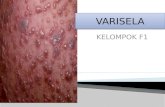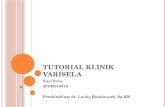PRESKES VARISELA
-
Upload
vita-pramatasari-harti -
Category
Documents
-
view
55 -
download
1
description
Transcript of PRESKES VARISELA
LAPORAN KASUS
SEORANG ANAK LAKI-LAKI UMUR 9 BULAN
DENGAN DIARE AKUT DEHIDRASI SEDANG
Oleh :
Pembimbing :
Yulidar Hafidh, dr., Sp.A(K)
KEPANITERAAN KLINIK ILMU KESEHATAN ANAK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS / RSUD Dr. MOEWARDI
SURAKARTA
2011
Khanifah Fitria Dewi G0007201/G-12-11
Ariesia Dewi Ciptorini G0007042/G-13-11
PRESENTASI KASUS
I. IDENTITAS PASIEN
Nama : An. M
Umur : 13 tahun 9 bulan
Berat badan : 49 kg
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Semanggi RT 01/18 Pasar Kliwon Surakarta
Tanggal masuk : 12 Oktober 2011 jam 17.44
No. CM : 01090634
II. ANAMNESIS
A. Keluhan Utama
Bintik-bintik berair di seluruh tubuh.
B. Riwayat Penyakit Sekarang
Alloanamnesis oleh ibu pasien.
Hari sebelum masuk rumah sakit, pasien panas tinggi mendadak terus
menerus, kemudian muncul bintik-bintik merah pada tangan yang menyebar
ke seluruh tubuh. Bintik-bintik tersebut berisi cairan bening. Terdapat batuk
dan nyeri telan. Buang air besar maupun kecil dalam batas normal. Tidak
didapatkan cairan keluar dari telinga. Nafsu makan dan minum menurun.
Sudah diperiksakan ke PKM namun keluhan tidak berkurang.
Hari sebelum masuk rumah sakit pasien merasa bintik – bintik semakin
banyak dan gatal, tenggorokan bertambah sakit, batuk bertambah ngekel
sampai dada terasa panas. Tidak terdapat sesak napas. Pasien masih mau
makan dan minum tapi nafsu makan berkurang.
Kurang lebih 30 menit yang lalu, BAB 1 x/hari, konsistensi padat<
warna kuning, mual tapi tidak muntah. BAK banyak tetapi tidak nyeri.
Tidak terdapat nyeri kepala. Tidak terdapat cairan keluar dari telinga.
1
C. Riwayat Penyakit Dahulu
- Riwayat sakit serupa : (-)
- Riwayat kejang : (-)
- Riwayat alergi obat dan makanan : (-)
D. Riwayat Nutrisi
- Asupan makan tiap hari cukup
E. Riwayat Penyakit Keluarga dan Lingkungan
- Keluarga yang menderita sakit serupa : (-)
- Lingkungan yang menderita sakit serupa : (+) banyak
F. Riwayat Kesehatan Keluarga
- Ayah : baik
- Ibu : baik
- Saudara : baik, tapi sebelumnya kakak dan adik menderita cacar air
G. Riwayat Penyakit yang Pernah Diderita
- Tonsilofaringitis:(+) - Enteritis : (-)
- Bronkitis : (-) - Disentri basiler : (-)
- Pneumonia : (-) - Disentri amuba : (-)
- Morbili : (-) - Thypus : (-)
- Pertusis : (-) - Cacing : (-)
- Difteri : (-) - Operasi : (-)
- Varicella : (-) - Gegar Otak : (-)
- Malaria : (-) - Fraktur : (-)
2
G. Pemeliharaan Kehamilan dan Kelahiran
- Pemeriksaan di bidan puskesmas, mendapat vitamin penambah darah.
- Frekuensi : trimester I : 1 x / bulan
trimester II : 1 x / bulan
trimester III : 2 x / bulan
- Keluhan selama kehamilan : (-)
Pasien adalah anak kedua dari dua bersaudara. Anak lahir dengan berat
badan lahir 2800 gram dan panjang badan lahir 50 cm, umur kehamilan 9
bulan 2 minggu, lahir secara sesar, menangis kuat, ditolong oleh dokter.
Riwayat keguguran tidak ada, anak lahir meninggal tidak ada. Ayah dan ibu
menikah satu kali.
H. Pohon Keluarga
An. M, 9 bulan
Kehamilan dan Kelahiran
1. Perempuan umur 3 tahun , BBL: 2700 gram, PBL: 48 cm, lahir spontan
dengan induksi. Saat ini keadaan sehat.
2. Laki-laki umur 9 bulan, BBL: 2800 gram, PBL: 50 cm, lahir sesar di
dokter. Saat ini keadaan sehat.
I. Riwayat Imunisasi
- Hepatitis B : 3x (usia 0,1,6 bln)
- BCG : 1x (usia 0 bln)
- DPT : 3x (usia 2, 4, 6 bln)
- Polio : 4x (usia 0, 2, 4, 6 bln)
3
- Campak : 9 bulan
Kesan : pada KMS dan ibu semua imunisasi .sudah merasa semua
lengkap
J. Perkembangan Anak
1. Personal Sosial
- Tersenyum : (+) mulai umur 2 bulan
- Makan roti sendiri : (+) mulai umur 6 bulan
2. Motorik Halus
- Memegang kerincing : (+) mulai umur 4 bulan
3. Bahasa
- Tertawa : (+) mulai umur 2 bulan
- Berpaling saat dipanggil : (+) mulai umur 5 bulan
- Mengeluarkan kata tanpa arti : (+) mulai umur 9 bulan
4. Motorik Kasar
- miring : (+) mulai umur 2 bulan
- mengangkat kepala : (+) mulai umur 3 bulan
- tengkurap : (+) mulai umur 3 bulan
- duduk : (+) mulai umur 7 bulan
Kesan : perkembangan anak sesuai dengan usia.
K. Riwayat Makan Minum Anak
1. ASI diberikan sejak lahir dan belum berhenti. Frekuensi pemberian
tiap kali anak menangis. Lamanya menyusui 10-15 menit, bergantian
payudara kanan dan kiri. Sesudah menyusu anak tidak menangis.
2. Susu formula diberikan sejak lahir. Frekuensi pemberian 3x per hari.
3. Makanan padat dan lauknya: bubur sumsum sejak umur 6 bulan
dengan frekuensi 3x per hari; bubur susu sejak umur 6 bulan dengan
frekuensi 3x per hari; dan nasi tim sejak umur 8 bulan dengan
frekuensi 3x per hari.
4
Kesimpulan: ASI dan susu formula sudah diberikan sejak lahir. Makanan
padat dan lauknya sudah diberikan sejak usia 6 bulan.
L. Keluarga Berencana
Ibu mengikuti program keluarga berencana suntik 3 bulan.
III. PEMERIKSAAN FISIK ( 15 Agustus 2011)
A. Keadaan Umum
- Keadaan umum : baik
- Derajat kesadaran : compos mentis
- Derajat gizi : gizi kesan baik
B. Tanda vital
- Laju Jantung : 94x/menit
- Laju Nadi : 94x/menit, regular, isi tegangan cukup
- Laju Pernafasan : 30x/ menit, kedalaman cukup, reguler,
tipe thorakoabdominal.
- Suhu : 390C peraksila
C. Status Gizi
1. Secara klinis
Intake minum : sedikit
Kepala : mesocephal (+), rambut jagung (-), susah dicabut (+)
Mata : edema palpebra(-/-), conjunctiva anemis (-/-), mata
cowong (/-), air mata (- berkurang/- berkurang),
injeksi conjungtiva (+/+)
Mulut : Mukosa basah (-), bibir pecah-pecah (-), faring
hiperemis (+/+), T1-T1 hiperemis (+/+). Tampak
vesikel di palatum, laring dan faring.
Leher : Kelenjar getah bening tidak membesar
Dada : Retraksi (-)
Cor : BJ I-II intensitas normal, regular, bising (-)
5
Pulmo : SDV (+/+), ST (-/-)
Abdomen : DP//DD, Nyeri tekan (-), bising usus (+) normal,
tympani, supel, hepar/lien tidak teraba NTE (+)
Ekstremitas : edema - - akral dingin - -
-- - -
Status gizi secara klinis : gizi baik
2. Secara antropometri
- Umur : 13 tahun 9 bulan
- Berat badan : 43 kg
- Tinggi badan : 165 cm
BBU =
45 x100 % = 73,08%
BBU < p3(WHO, 2005)
TBU =
6474 x 100 % = 86,48 %
TBU < p3 (WHO, 2005)
BBTB =
6,57 x 100 % = 92,85% p3<
BBTB < p15
z score -2<SD<-1 (WHO, 2005)
Interpretasi : gizi baik secara antropometri
Kebutuhan Kalori : 7 kg x 110 kal/hari = 770 kal/hari
Karbohidrat : 1/4 x 50 % x 770 kal = 96,25 gram/hari
Lemak : 1/9 x 35 % x 770 kal = 29,94 gram/hari
Protein : 1/4 x 15 % x 770 kal = 28,87 gram/hari
D. Kulit
Kulit sawo matang, kering, turgor kembali lambat, ujud kelainan kulit (-)
E. Kepala
Bentuk mesosefal, rambut warna hitam, sukar dicabut, ubun-ubun besar
cekung
F. Wajah
Odema (-), moon face (-)
6
G. Mata
Odema periorbita (-/-), konjungtiva anemis (-/-) , sklera ikterik (-/-), mata
cekung (+/+), air mata (+ berkurang/+ berkurang)
H. Hidung
Napas cuping hidung (-/-), sekret (-/-), darah (-/-)
I. Mulut
Mukosa basah (+), sianosis (-)
J. Telinga
Normotia, sekret (-/-) , mastoid pain(-/-), tragus pain(-/-)
K. Tenggorok
Uvula di tengah, mukosa pharing hiperemis (-)
L. Leher
Bentuk normocolli, limfonodi tidak membesar, glandula thyroid tidak
membesar, JVP tidak meningkat, kaku kuduk (-)
M. Toraks
Bentuk : normochest, retraksi (-)
Cor : Inspeksi : iktus kordis tidak tampak
Palpasi : iktus kordis kuat angkat
Perkusi : batas jantung kesan tidak melebar
batas kiri atas : SIC II LPSS
batas kiri bawah : SIC IV 2 jari medial LMCS
batas kanan atas : SIC II LPSD
batas kanan bawah : SIC IV LPSD
Auskultasi : BJ I-II intensitas normal, reguler, bising (-)
Pulmo : Inspeksi : pengembangan dada kanan = kiri
Palpasi : fremitus raba dada kanan = kiri
Perkusi : sonor /sonor di seluruh lapang paru
Auskultasi : suara dasar vesikuler (+/+)
suara tambahan (-/-)
N. Abdomen
Inspeksi : dinding perut sejajar dengan dinding dada
7
Auskultasi : bising usus (+) meningkat
Perkusi : timpani, undulasi (-), pekak beralih (-),
Palpasi : supel, turgor kembali lambat, hepar dan lien tidak teraba,
nyeri tekan (-).
O. Ekstremitas
Akral dingin Oedem Sianosis
Capillary refill time <2 detik
Arteri dorsalis pedis teraba kuat
P. Pemeriksaan Neurologi
1. koordinasi : baik
2. sensorium : baik
3. reflek fisiologis :
a. bisep +2
b. trisep +2
c. patela +2
d. achiles +2
4. reflek patologis :
a. babinsky (-)
b. chadock (-)
c. oppenheim (-)
d. gordon (-)
e. meningeal sign :
1. kernig (-)
2. kernig sign (-)
3. kaku kuduk (-)
4. brudzinsky I (-)
5. brudzinsky II (-)
6. Hoffman tromer (-)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8
IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG
Laboratorium darah tanggal 16 Agustus 2011
- Hemoglobin : 9,8 g/dl (11,5-15,5 g/dl)
- Hematokrit : 31 % ( 35-45 %)
- Eritrosit : 4,36.106 µL ( 4- 5,2 . 106 µL)
- Leukosit : 7,9.103 µL ( 4,5- 14,5.103 µL)
- Trombosit : 340.000 µL (150.000- 450.000 µL)
- GDS : -
- MCV: 70,2 / µm (80,0-96,0)
- MCHC : 32,1 g/dl (33,0-36,0)
- MCH: 22,5 pg (28,0-33,0)
- RDW : 16,8 % (11,6 – 14,6)
- HDW : 3,3 g/dl (2,3 – 3,2)
- MPV : 6,1 fl (7,2 -11,1)
- PDW : 52 % (25 - 65)
HITUNG JENIS :
- Eosinofil : 1,40 % (1,0-2,0)
- Basofil : 0,70 % (0,0 – 1,0)
- Netrofil : 14,00 % (18,0 – 74,0)
- Limposit : 79,50 % (60,0 – 66,0)
- Monosit : 4,30 % (0,0 – 6,0)
- LUC : 8,80 %
- Retikulosit : -
KIMIA KLINIK :
- Besi (SI) : 14 µg/dl (27 - 109)
- TiBC : 243 µg/dl (228 - 428)
- Saturasi transferrin : 6% (15-45%)
- Na+ : 140 mmol/L ( 136-146 mmol/L )
- K+ : 4,1 mmol/L ( 3,5- 5,1 mmol/L )
- Ca- : 1,10 mmol/L ( 1,17 – 1,29 mmol/L )
9
MCH = Hb x 10 = (9,8 / 4,36 ) x 10
AE
= 22,5 (Hipokromik)
MCHC = Hb x100 = (8,5 / 31) x 100
Hct
= 32,1 (Hipokromik)
MCV = Ht x 10 = (31/ 4,36) x 10
AE = 70,2 (Mikrositik Hipokromik)
IM = MCV = 70,2 / 4,36
AE
= 16,1 (Anemia Defisiensi Besi)
Kesimpulan : Anemia Mikrositik Hipokromik e/c Defisiensi Besi
a. Urinalisis tanggal 16 Agustus 2011
Sedimen eritrosit : 0 /LPB
leukosit : 0 /LPB
silinder : 0 /LPK
kristal : (-)
epitel : 0 /LPK
Lain-lain bakteri : (+)
Warna : Kuning
Kejernihan : Jernih
Berat Jenis : 1,015
pH : 9,0
Leukosit : (-)
Nitrit : (-)
Protein : (-)
Glukosa : (-)
Keton : (-)
Urobilinogen : Normal
Bilirubin : (-)
10
Eritrosit : (-)
b. Feses Rutin tanggal 9 Maret 2010
Makros : Warna : Coklat
Konsistensi : Lunak
Lendir : (-)
Darah : (-)
Pus : (-)
Makanan tak tercerna : (-)
Mikros : Sel Epitel : (-)
Eritrosit : (-)
Leukosit : (-)
Protozoa : (-)
Telur Cacing : (-)
Lain-lain : Kuman (+)
Catatan : Tinja lunak warna coklat
Tidak ditemukan adanya parasit atau jamur patogen
V. RESUME
Sejak 5 hari SMRS pasien mencret, awalnya sebanyak kurang lebih 5-
10 kali tiap hari, kurang lebih @ ¼ - ½ gelas aqua, berbau amis, dengan
cairan lebih banyak daripada ampas, warna kuning, lendir (+), darah (-),
nyeri perut saat diare (-). Pasien tampak kehausan setelah diare beberapa
hari. Pasien mengalami muntah tiap 2 jam yang berisi lebih banyak cairan.
Diare juga disertai panas tinggi diseluruh tubuh terus menerus, sudah
diberikan obat penurun panas, namun hanya bertahan selama 3 jam, setelah
itu panas kembali tinggi.
Pasien masih mau makan, tetapi setelah makan dimuntahkan lagi, dan
tidak terlalu lahap. Keinginan untuk minum bertambah ketika pasien sedang
panas (demam).
11
Pemeriksaan fisik didapatkan: KU baik, compos mentis, gizi kesan baik;
VS : Laju Jantung : 90x/menit; Laju Nadi = 90x/ menit, reguler, isi dan
tegangan cukup, ; Laju pernafasan = 30 x/menit, reguler, tipe
thorakoabdominal, kedalaman cukup ; suhu = 36,7 0C. Kulit : turgor
menurun; Kepala: mata cekung (+/+), air mata( + berkurang/ + berkurang) ;
Mulut : Mukosa basah (+) ↓ , Thorax, Cor dan Pulmo dalam batas normal;
Abdomen : inspeksi :dinding perut sejajar dinding dada, auskultasi : bising
usus meningkat, perkusi : timpani, palpasi: supel, turgor kembali lambat,
hepar tidak teraba, lien tidak teraba, nyeri tekan tidak ada. Pada
pemeriksaan laboratorium didapatkan : Hemoglobin: 9,8 g/dl; Hematokrit :
31,0 %; Eritrosit : 4,36 106 µL; Leukosit :7.900 µL; Trombosit : 340.000 µ;
Na : 140 mmol/L; K : 4.1 mmol/L; Ca: 1,10 mmol/L
VI. DAFTAR MASALAH
1. Diare
2. Muntah
3. Dehidrasi sedang
4. Panas
5. Anemia
VII. DIAGNOSIS BANDING
Diare akut dengan dehidrasi sedang e/c DD:
- Virus
- Bakteri
Anemia mikrositik hipokromik DD Defisiensi besi
Penyakit infeksi
Gizi Kurang
VIII. DIAGNOSIS KERJA
Diare akut rotavirus dengan dehidrasi sedang
Anemia hipokromik mikrositik e/c Defisiensi besi
12
Gizi Kurang
IX. PENATALAKSANAAN
1. Rawat inap bangsal Gastroenterologi Anak
2. Diet nasi bubur 770 kalori/hari
3. Terapi rehidrasi : Oralit 75 cc/kgBB dalam 3 jam pertama
4. Drug :
- Probiotik 2 x 1.10 7-9 (p.o)
- Zinc 1 x 20 mg (p.o)
- Oralit 50 cc tiap muntah dan 100 cc tiap diare ( setelah terehidrasi)
X. PLANNING
Monitoring
- KU dan VS/ 4 jam
- Balance cairan/ diuresis / 8 jam
- Status Hidrasi/ jam selama rehidrasi → Status Hidrasi / 8 jam setelah
terehidrasi
-
XI. PROGNOSIS
Ad vitam : baik
Ad sanam : baik
Ad fungsionam : baik
XII. PROGRESS REPORT
DPH Tanggal Keluhan/KU/VS Pemeriksaan / Diagnosis Terapi
I 15/8/11 Keluhan : muntah (+)/2 jam, 5x mual (-) panas(+)
Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata
cekung (+/+), air mata (+/+)Hidung : NCH (-/-), secret (-/-)Telinga : secret (-/-)
1.Diet nasi bubur 770 kalori/hari2. Terapi rehidrasi : Oralit 75 cc/kgBB dalam 3 jam
13
makan(+) kurang lahapminum (+) kehausanBAB(+) 5-10 kali air>ampas, warna kuning,lendir (+), amis (+)BAK (+)
KU : baik, compos mentis.Gizi kesan baik.VS : HR=90x, RR=30x, S=36,70C
Mulut : MB (+) sianosis (-)KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)
meningkat, turgor kembali lambat
Ext : a.d - - oedem - - - - - -
CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat
Dx : 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang teratasi
2. Anemia hipokrom mikrositik
3. Gizi baik
pertama3. Drug :
- Probiotik 2 x 1.10 7-9
(p.o)- Zinc 1 x 20 mg (p.o)- Oralit 50 cc tiap
muntah dan 100 cc tiap diare ( setelah terehidrasi)
Dx : DL 2, Urin dan feces rutin
Mx : KU VS / 4 jam BC+SH+D / 8 jam
II 16/08/11 Keluhan : muntah (-) mual (-) panas(-) makan(+) baikminum (+) baikBAB(+) 2kali konsistensi mulai mengental (lembek), warna kuning, lendir (-), amis (-)BAK (+) sedikitKU : baik, cm, gizi kesan baik.VS : HR=92x, RR=30x, S=36,40C
Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata
cekung (-/-), air mata (+/+)Telinga : secret (-/-)Hidung : NCH (-/-) secret (-/-)Mulut : MB (+) sianosis (-)KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)
meningkat, turgor kembali cepat
Ext : a.d - - oedem - - - - - -
CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat
Dx 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang terehidrasi
2. Anemia defisiensi besi 3. Gizi baik
1. Diet nasi bubur 770 kal/hari
2. Probiotik 2x1sachet (p.o)3. Zinc 1 x 20 mg (p.o)4. Oralit 70 cc jika diare 30 cc jika muntah
Mx : KU VS / 4 jam BC+SH+D / 8 jam
III 17/08/11 Keluhan : muntah (-) mual (-) panas(-) batuk (+) pilek (+) ingus bening makan(+) baikminum (+) baik mau banyakBAB(+) 1 kali (lembek), warna kuning, lendir (-), amis (-), ampas
Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata
cekung (-/-), air mata (+/+)Telinga : secret (-/-)Hidung : NCH (-/-) secret (+/+)Mulut : MB (+) sianosis (-)Faring : hiperemis (+) T1-T1KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)
meningkat, turgor kembali cepat
Ext : a.d - - oedem - - - - - -
1. Diet nasi bubur 770 kal/hari
2. Probiotik 2x1sachet (p.o)3. Zinc 1 x 20 mg (p.o)4. Oralit 70 cc jika diare 30 cc jika muntah5. Cetirizine 1x 25 mg p.o
Mx : KU VS / 8 jam BC+SH+D / 8 jam
14
lebih banyak BAK (+) KU : baik, cm, gizi kesan baik.VS : HR=92x, RR=32x, S=36,80C
CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat
Dx 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang terehidrasi
2. Anemia defisiensi besi 3. Gizi baik
IV 18/8/11 Keluhan : muntah (-) mual (-) panas(-) batuk (+) dahak (+) pilek (-) makan(+) baikminum (+) baik mau banyakBAB(+) sudah tidak ada mencret (lembek), warna kuning, BAK (+) banyak, warna kuning jernih.KU : baik, cm, gizi kesan baik.VS : HR=114x, RR=32x, S=36,90C
Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata
cekung (-/-), air mata (+/+)Telinga : secret (-/-)Hidung : NCH (-/-) secret (+/+)Mulut : MB (+) sianosis (-)Faring : hiperemis (-)KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)
meningkat, turgor kembali cepat
Ext : a.d - - oedem - - - - - -
CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat
Dx 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang terehidrasi
2. Anemia defisiensi besi 3. Gizi baik
1. Diet nasi bubur 770 kal/hari
2. Probiotik 2x1sachet (p.o)3. Zinc 1 x 20 mg (p.o)4. Oralit 70 cc jika diare 30 cc jika muntah5. Cetirizine 1x 25 mg p.o
Mx : KU VS / 8 jam BC+SH+D / 8 jam
ANALISA KASUS
Diagnosis diare akut dehidrasi sedang ditegakkan berdasarkan :
Anamnesis :
1. Pasien mengalami diare sebanyak 10 kali kurang lebih @ 1/4 gelas
belimbing dengan cairan lebih banyak daripada ampas, warna kuning,
lendir (+), darah (-), nyeri perut saat diare (-) sejak 5 hari SMRS.
15
2. Pasien juga muntah setiap 2 jam sekali, minum masih mau, makan tidak
selahap biasanya.
Pemeriksaan Fisik :
1. Keadaan Umum : baik, tampak kehausan
2. Tanda vital penderita didapatkan Laju Jantung 90x/menit, Laju nadi
90x/menit, reguler, simetris, isi dan tegangan cukup, Laju Pernapasan
30x/menit, kedalaman cukup, tipe thorakoabdominal, suhu 36,7C
peraxila.
3. Mata cekung (+/+), air mata (+/+) berkurang, mukosa bibir dan mulut
basah(+), bising usus (+) meningkat,turgor kulit kembali lambat, akral
hangat, CRT<2 detik, a. dorsalis pedis teraba kuat.
Penentuan Dehidrasi ringan sedang (kehilangan cairan 5-10% berat badan)
(IDAI 2004)
1. Apabila didapatkan dua tanda utama ditambah dua atau lebih
tanda tambahan
2. Keadaan umum gelisah dan cengeng
3. Ubun-ubun besar sedikit cekung, mata sedikit cekung, air mata
kurang, mukosa mulut dan bibir kering
4. Turgor kurang
5. Akral hangat
6. Pasien harus rawat inap
Pemeriksaan Penunjang :
Hasil laboratorium pasien masih menunjukkan angka dalam batas normal.
Tidak didapatkan hemokonsentrasi, penurunan elektrolit dan trombositosis. Hal
ini kemungkinan dapat disebabkan karena pasien sudah terehidrasi.
Pembahasan :
16
Penyebab diare pada kasus ini diduga karena dua hal yaitu infeksi virus,
infeksi bakteri.
Perbandingan gejala klinis diare akut oleh virus dan bakteri (Soebagyo, 2008)
Gejala klinis Virus Rota ETECMasa Tunas 17-72 jam 6-72 jamPanas + -Mual dan muntah Sering -Nyeri perut Tenesmus +Nyeri Kepala - -Lamanya sakit 5-7 hari 2-3 hariSifat tinja
Volume Sedang BanyakFrekuensi 5-10 x / hr SeringKonsistensi Cair CairLendir/darah - -Bau - +Warna Kuning-Hijau Tak berwarnaLeukosit - -Lain-lain Anorexia Meteorismus
Penatalaksanaan :
Prinsip pengobatan diare ialah atasi dehidrasi dulu dengan menggantikan
cairan yang hilang lewat tinja dengan atau tanpa muntah, dengan cairan yang
mengandung elektrolit dan glukosa, Pada kasus ini tatalaksana yang utama
adalah terapi cairan yang menurut WHO adalah dengan memberikan cairan
oralit per oral sebanyak 75 cc/KgBB dan bila oralit per oral tidak dapat diberikan
maka dimasukkan melalui nasogastrik dengan volume sama dengan kecepatan
20ml/KgBB/jam, namun pada pasien ini tidak dilakukan karena upaya rehidrasi
oral masih dapat dilakukan. Pemberian zink untuk membantu regenerasi sel bila
terjadi kerusakan mukosa usus dan probiotik guna dalam pengaturan
keseimbangan flora usus.
Pada pasien ini tidak diberikan antibiotik karena tidak ada indikasi yang
mengarah ke diare e/c Shigella, Cholera, Amoeba baik dari anamnesa maupun
pemeriksaan fisik. Pada pasien diare ini tidak boleh dipuasakan, dianjurkan
untuk banyak minum. Prognosis pasien ini baik.
17
A. Definisi
Varisela merupakan infeksi akut primer oleh virus varisela-zooster
yang menyerang kulit dan mukosa, klinis terdapat gejala konstitusi, kelainan
kulit polimorf, terutama berlokasi di bagian sentral tubuh (Handoko, 2007).
B. Epidemiologi
Varisela merupakan penyakit yang sangat menular, tetapi sangat
bergantung pada kekebalan seseorang. Varisela terutama menyerang individu
yang belum mempunyai antibodi (Rampengan, 2008).
Varisela dapat menyerang semua umur termasuk bayi baru lahir dan
dewasa. Sembilan puluh persen penderita adalah anak berumur kurang dari 10
tahun dengan insiden tertinggi pada kelompok umur 2-6 tahun, sedangkan
sebagian kecil (+5%) pada golongan umur di atas 15 tahun (Rampengan,
2008).
Transmisi atau penularan penyakit varisela dilaporkan melalui banyak
cara. Penularan dapat dengan:
1. Kontak langsung
2. Percikan ludah/melalui udara sehingga menyebabkan penyakit ini
sangat menular walaupun sebelum rash timbul.
3. Papul dan vesikel tetapi bukan krusta, mengandung populasi virus
cukup tinggi.
4. Transplasental.
(Rampengan, 2008)
Delapan puluh sampai sembilan puluh persen penularan terjadi dalam
keluarga karena kontak kedua dalam keluarga umumnya lebih berat
(Rampengan, 2008).
Masa penularan varisela terutama mulai pada 2 hari sebelum timbul
lesi kulit dan berakhir bila telah terjadi krusta, biasanya 5 hari kemudian.
Sedang pada neonatus tertular selama terjadi viremia pada tubuh ibu hamil.
Tidak terdapat perbedaan jenis kelamin maupun ras (Rampengan, 2008).
Faktor risiko terjadinya varisela berat dapat terjadi pada:
19
1. Neonatus umur 1 bulan, terutama lahir dari ibu dengan seronegatif.
Persalinan sebelum masa gestasi 28 minggu juga dengan risiko tinggi
terjadi varisela berat karena imunoglobulin G baru dapat masuk
transplasental ke bayi setelah umur 28 minggu.
2. Dewasa muda atau dewasa.
3. Terapi steroid dosis tinggi (prednisolon 1-2 mg/kg/hari) selama 2
minggu. Walaupun dengan dosis sama dalam jangka waktu pendek
terutama saat memasuki atau selama masa inkubasi.
4. Keganasan, terutama pada penderita leukemia. Hampir 30% penderita
leukemia terdapat varisela menyerang meluas ke dalam alat dalam
dengan angka kematian 7%.
5. Gangguan imunitas (obat kanker, HIV), gangguan pada imunitas
seluler lebih mudah menyebabkan varisela berat.
6. Kehamilan.
(Rampengan, 2008)
C. Etiologi
Virus varisela-zoster (VVZ). Penamaan virus ini memberi pengertian
bahwa infeksi primer virus ini menyebabkan penyakir varisela, sedangkan
reaktivasi menyebabkan herpes zoster (Rampengan, 2008).
VVZ adalah herpesvirus manusia, diklasifikasikan sebagai herpesvirus
alfa karena kesamaannya dengan prototipe kelompok ini, yang adalah virus
herpes simpleks (HSV). VVZ adalah virus DNA helai ganda, terselubung;
genom virus mengkode lebih dari 70 protein, termasuk protein yang
merupakan sasaran imunitas dan timidin kinase virus, yang membuat virus
sensitif terhadap hambatan oleh asiklovir dan dihubungkan dengan agen
antivirus (Arvin, 2000).
D. Imunitas
Antibodi terhadap varisela zoster diperoleh dari ibu, bertahan selama 6
bulan, sehingga bayi di bawah umur 6 bulan pada umunnya bebas dari
penyakit varisela. Bayi yang lahir dari ibu dengan varisela kurang atau sama
20
dengan 5 hari sebelum partus virus dapat ditransfer ke janin melalui plasenta
sehingga dapat menimbulkan varisela kongenital (Rampengan, 2008).
Pada penderita yang rentan terhadap varisela dan mempunyai faktor
risiko tinggi terutama pada neonatus, bayi yang dirawat intensif,
imunodefisiensi, dan penderita keganasan, varisela sering menyebabkan
kematian (Rampengan, 2008).
Virus merangsang imunitas seluler dan humoral, sehingga penderita
akan memperoleh imunitas yang lama (long lasting imunity). Terbentuk 4
subklas Imunoglobulin G, yaitu IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Pada anak dengan
infeksi alamiah, setelah 2 minggu akan terdapat peningkatan IgG1 dan
meningkat setelah 1 bulan, sedangkan IgG2 dan IgG3 terbentuk dalam kadar
yang sedikit dan akan menurun secara bertahap, setelah 10 tahun antibodi
sudah tidak terdeteksi dengan ELISA. Antibodi IgG1 dan IgG4 yang terbentuk
masih dapat dideteksi setelah 10 tahun (Rampengan, 2008).
E. Patogenesis
Virus varisela masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh melalui saluran
pernapasan atas dan orofaring. Pada mulanya virus bereplikasi dalam kelenjar
limfe regional, 4-6 hari kemudian terjadi penyebaran dari sejumlah kecil virus
melalui darah dan limfe (viremia primer). Selanjutnya virus masuk ke sistem
retikuloendotelial, tempat utama replikasi virus selama sisa masa inkubasi
(Straus et al, 2008; Rampengan, 2008).
Pada masa inkubasi dari infeksi ini terjadi respon imun pejamu baik
humoral maupun seluler. Pada kebanyakan individu, replikasi virus dapat
mengalahkan pertahanan pejamu. Akibatnya, setelah hampir 2 minggu setelah
infeksi terjadi viremia yang lebih besar (viremia sekunder) dan timbul gejala
dan lesi kulit. Virus bersirkulasi di dalam leukosit mononuklear terutama
limfosit. Bahkan pada varisela tanpa komplikasi, viremia sekunder
menyebabkan infeksi subklinis pada beberapa organ selain pada kulit.
Respon imun yang efektif dari pejamu menghilangkan viremia dan
membatasi progresifitas dari lesi varisela pada kulit dan organ lain. Imunitas
humoral terhadap VVZ melindungi dari varisela. Orang dengan antibodi
21
serum yang dapat terdeteksi biasanya tidak menjadi sakit setelah paparan
eksogen. Imunitas seluler terhadap VVZ juga berkembang dan bertahan
selama beberapa tahun, melindungi dari infeksi yang parah (Straus et al,
2008; Rampengan, 2008).
Lesi pada kulit terjadi akibat infeksi kapiler endotelial pada papil
lapisan dermis kemudian menyebar ke sel-sel epitel lapisan epidermis, folikel
kulit, dan glandula sebasea sehingga terjadi pembengkakan. Pada mulanya
ditandai dengan adanya makula dan berkembang dengan cepat menjadi
papula, vesikel, dan akhirnya menjadi krusta. Lesi ini jarang menetap dalam
bentuk makula dan papula saja. Vesikel ini akan berada pada lapisan sel
sedangkan dasarnya adalah lapisan yang lebih dalam (Rampengan, 2008).
Degenerasi sel akan diikuti dengan terbentuknya sel raksasa berinti
banyak, dan kebanyakan dari sel tersebut mengandung badan inklusi tipe A.
Dengan berkembangnya lesi yang cepat, lekosit polimorfonuklear akan
masuk ke dalam korium dan cairan vesikel sehingga mengubah cairan yang
jelas dan terang menjadi berwarna keruh, kemudian terjadi absorbsi dari
cairan ini, akhirnya terbentuk krusta (Rampengan, 2008).
Terbentuknya lesi-lesi pada membran mukosa juga dengan cara yang
sama tetapi tidak langsung membentuk krusta. Vesikel-vesikel biasanya akan
pecah membentuk luka yang terbuka, namun akan sembuh dengan cepat
(Rampengan, 2008).
F. Manifestasi Klinis
Masa inkubasi varisela bervariasi antara 10-21 hari, rata-rata 10-14 hari.
Penyebaran varisela terutama secara langsung melalui udara dengan
perantaraan percikan liur. Pada umumnya tertular dalam keluarga, daycare
center atau sekolah (Rampengan, 2008).
Setelah masa inkubasi, mulai timbul gejala prodromal berupa panas yang
tidak terlalu tinggi, malaise, sakit kepala, anoreksia, rasa berat pada punggung
dan kadang-kadang disertai batuk kering, diikuti eritema pada kulit dapat
berbentuk skarlatinaform atau morbiliform (Rampengan, 2008).
22
Panas biasanya menghilang dalam 4 hari, bilamana panas tubuh menetap
perlu dicurigai adanya komplikasi atau gangguan imunitas. Eritema akan
berkembang dengan cepat (dalam beberapa jam) berubah menjadi makula
kecil, kemudian papula yang kemerahan lalu menjadi vesikel. Vesikel ini
biasanya kecil, berisi cairan jernih, tidak umbilicated dengan dasar
eritematous, mudah pecah serta mengering membentuk krusta, bentuk ini
sangat khas dan lebih dikenal sebagai ”tetesan embun/air mata” (tears drop)
(Rampengan, 2008).
Lesi kulit mulai nampak di daerah badan dan kemudian menyebar secara
sentrifugal ke bagian perifer seperti muka dan ekstremitas. Dalam perjalanan
penyakit ini akan didapatkan tanda yang khas yaiu terlihat adanya bentuk
papula, vesikel, krusta dalam waktu yang bersamaan, dimana keadaan ini
disebut polimorf. Jumlah lesi pada kulit dapat 250-500, namun kadang-kadang
dapat hanya 10 bahkan lebih sampai 1500. Lesi baru tetap timbul selama 3-5
hari, lesi sering menjadi bentuk krusta pada hari ke-6 (hari ke-2 sampai ke-12)
dan sembuh lengkap pada hari ke-16 (hari ke-7 sampai ke-34). Erupsi
kelamaan atau terlambatnya berubah menjadi krusta dan penyembuhan,
biasanya dijumpai pada penderita dengan gangguan immunitas seluler
(Rampengan, 2008).
Bila terjadi infeksi sekunder, sekitar lesi akan tampak kemerahan dan
bengkak serta cairan vesikel yang jernih berubah menjadi pus disertai
limfadenopati umum. Vesikel tidak hanya terdapat pada kulit melainkan juga
terdapat pada mukosa mulut, mata, dan faring (Rampengan, 2008).
Pada penderita varisela yang disertai dengan defisiensi imunitas sering
menimbulkan gambaran klinik yang khas berupa perdarahan, bersifat
progresif dan menyebar menjadi infeksi sistemik. Demikian pula pada
penderita yang sedang mendapat imunosupresif. Hal ini disebabkan oleh
terajdinya limfopenia (Rampengan, 2008).
Pada ibu hamil yang menderita varisela dapat menimbulkan beberapa
masalah pada bayi yang akan dilahirkan dan bergantung pada masa kehamilan
ibu, antara lain:
23
1. Varisela neonatal
Varisela neonatal dapat merupakan penyakit serius, hal ini bergantung
pada saat ibu kena varisela dan persalinan (Rampengan, 2008).
a. Bila ibu hamil terinfeksi varisela 5 hari sebelum partus atau 2 hari
setelah partus, berarti bayi tersebut terinfeksi saat viremia kedua
dari ibu, bayi terinfeksi transplasental, tetapi tidak memperoleh
kekebalan dari ibu karena belum cukupnya waktu ibu memproduksi
antibodi. Pada keadaan ini, bayi yang dilahirkan akan mengalami
varisela berat dan menyebar. Perlu diberikan profilaksis atau
pengobatan dengan varicella-zoster immune globulin (VZIG) dan
asiklovir. Bila tidak diobati dengan adekuat, angka kematian
sebesar 30%. Penyebab kematian utama akibat pneumonia berat
dan hepatitis fulminan (Rampengan, 2008).
b. Bila ibu terinfeksi varisela lebih dari 5 hari antepartum, sehingga si
ibu mempunyai waktu yang cukup untuk memproduksi antibodi
dan dapat diteruskan kepada bayi. Bayi cukup bulan akan
menderita varisela ringan karena pelemahan oleh antibodi
transplasental dari ibu. Pengobatan dengan VZIG tidak perlu, tetapi
asiklovir dapat dipertimbangkan pemakaiannya, bergantung pada
keadaan bayi (Rampengan, 2008).
2. Sindrom varisela kongenital
Varisela kongenital dijumpai pada bayi dengan ibu yang menderita
varisela pada umur kehamilan trimester I atau II dengan insidens 2%.
Manifestasi klinik dapat berupa retardasi pertumbuhan intrauterin,
mikrosefali, atrofi kortikalis, hipoplasia ekstremitas, mikroftalmia,
katarak, korioretinnitis, dan scarring pada kulit. Beratnya gejala pada
bayi tidak berhubungan dengan beratnya penyakit pada ibu. Ibu hamil
dengan zoster tidak berhubungan dengan kelainan pada bayi
(Rampengan, 2008).
3. Zoster infantil
24
Penyakit ini sering muncul dalam umur bayi 1 tahun pertama, hal ini
disebabkan karena infeksi varisela maternal setelah masa gestasi ke-20.
Penyakit ini sering menyerang pada saraf dermatom thoracis
(Rampengan, 2008).
G. Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan laboratorium tidak perlu dilakukan untuk menegakkan
diagnosis varisela karena gambaran klinis telah jelas. Untuk pemeriksaan
varisela, bahan diambil dari dasar vesikel dengan cara kerokan atau apusan
dan dicat dengan Giemsa, Hematoksilin Eosin (HE) atau apusan Tzanck. Dari
bahan ini akan terlihat sel-sel raksasa (giant cell) yang multi-nukleus dan
epitel sel berisi acidophilic inclusion bodies. Akan tetapi, pemeriksaan ini
tidak cukup spesifik untuk menentukan varisela dan untuk lebih memastikan
dapat dilakukan pemeriksaan imunofluoresen sehingga terlihat antigen virus
intrasel (Rampengan, 2008).
H. Diagnosis
Diagnosis biasanya sudah dapat ditegakkan dengan anamnesis dan
gambaran klinisyang khas berupa:
1. Timbulnya erupsi papulo-vesikuler yang bersamaan dengan demam yang
tidak terlalu tinggi.
2. Perubahan-perubahan yang cepat dari makula menjadi papula kemudian
menjadi vesikel dan akhirnya menjadi krusta.
3. Gambaran lesi berkelompok dengan distribusi paling banyak pada tubuh
lalu menyebar ke perifer, yaitu muka, kepala, dan ekstremitas.
4. Membentuk ulkus putih keruh pada mukosa mulut.
5. Terdapat gambaran yang polimorf.
(Rampengan, 2008)
I. Diagnosis Banding
1. Variola
Varisela Variola
Stadium prodromal Singkat (1-2 hari) Panjang (3-4 hari) +
demam tinggi
25
Rash Sentral-perifer Perifer-sentral
Lesi Terutama badan
Lebih superfisial
Umbilikasi (-)
Polimorf
Muka+ekstremitas
dalam
Umbilikasi (+)
Monomorf
(Rampengan, 2008)
2. Impetigo
Lesi impetigo pertama adalah vesikel yang cepat menjadi pustula
dan krusta.
Distribusi lesi impetigo terletak dimana saja.
Impetigo tidak menyerang mukosa mulut.
(Rampengan, 2008)
3. Skabies
Pada skabies terdapat papula yang sangat gatal.
Lokasi biasanya antara jari-jari kaki.
Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan Sarcoptes scabiei.
(Rampengan, 2008)
4. Dermatitis herpetiformis
Biasanya simetris terdiri atas papula vesikuler yang eritematosus,
serta ada riwayat penyakit kronik dan sembuh dengan
meninggalkan pigmentasi.
(Rampengan, 2008)
J. Komplikasi
Komplikasi varisela jarang pada anak, lebih sering pada dewasa.
1. Infeksi sekunder
2. Otak: ensefalitis, acute postinfections cerebellar ataxia
3. Pneumonitis
4. Sindrom Reye, dengan gejala: nausea dan vomitus, hepatomegali, dan
pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan SGPT dan
SGOT serta amonia.
5. Hepatitis
26
6. Komplikasi lain seperti artritis, trombositopenia purpura, miokarditis,
keratitis.
(Rampengan, 2008)
K. Penatalaksanaan
Pengobatan varisela adalah simtomatik dengan:
1. Obat topikal dengan kalamin lotion atau bedak salisil 1%.
2. Antipiretik/analgetik, biasanya dipakai aspirin, parasetamol, ibuprofen.
3. Antihistamin, dapat digunakan diphenhydramine dosis 5mg/kg/hari yang
dibagi dalam 3 kali pemberian.
4. Obat antivirus, seperti:
Vidarabin (adenosine arabinoside): menghambat polymerase
DNA virus. Dosis 10-20 mg/kgBB/hari, diberikan sehari dalam
infuse selama 12 jam, lama pemberian 5-7 hari.
Asiklovir: menghambat polymerase DNA virus dan mengakhiri
replikasi virus. Asiklovir lebih baik dibandingkan vidarabin. Obat
ini dapat mengurangi bertambahnya lesi pada kulit dan lamanya
panas, bila diberikan dalam 24 jam mulai timbulnya rash.
Asiklovir lebih banyak digunakan pada penderita dengan
komplikasi atau gangguan imunitas. Obat ini tidak mengurangi
rasa gatal pada kulit, komplikasi atau penularan sekunder.
Dosis 5-10 mg/kgBB dibagi dalam 4-5 dosis per hari, dapat
diberikan secara oral atau iv/drip tiap 8 jam selama 5-7 hari, tidak
melebihi 3200 mg/hari.
5. Diet yang adekuat
Berikan makanan penuh dan jangan dibatasi. Kadang-kadang penderita
mengalami anoreksia, sebaiknya dimotivasi banyak minum untuk
mempertahankan status hidrasi. Cairan yang cukup sangat diperlukan bila
penderita diberikan asiklovir, karena obat ini dapat berkristalisasi dalam
tubulus renalis bila penderita dalam keadaan dehidrasi.
L. Pencegahan
1. Atasi dehidrasi
27
a. Tanpa dehidrasi
Cairan rumah tangga dan ASI diberikan semaunya, oralit diberikan
sesuai usia setiap kali buang air besar atau muntah dengan dosis :
1. <1 tahun : 50-100 cc
2. 1-5 tahun : 100-200 cc
3. 5 tahun : semaunya
b. Dehidrasi ringan sedang
Rehidrasi dengan oralit 75 cc/kgBB dalam 3 jam pertama dilanjutkan
pemberian kehilangan cairan yang sedang berlangsung sesuai umur
sepeti yang di atas setiap kali buang air besar.
Bisa juga dengan kriteria :
1. Dehidrasi Ringan (Perkiraan defisit cairan 30-50 ml/kgBB)
Rehidrasi dengan CRT/ORALIT 30-50 ml/kgBB/3-4 jam jika
ada perbaikan lalu maintenance 100 ml/kgBB/20-21 jam
2. Dehidrasi Sedang (Perkiraan defisit cairan 30-50 ml/kgBB)
Rehidrasi dengan ORALIT/RL iv 70 ml/kgBB/3 jam jika ada
perbaikan maintenance 100 ml/kgBB/20-21 jam.
c. Dehidrasi Berat
Rehidrasi parenteral dengan cairan Ringer Laktat atau Ringer Asetat
100 cc/kgBB. Cara pemberian :
1. < 1 tahun 30 cc/kgBB dalam 1 jam pertama dilanjutkan 70
cc/kgBB dalam 5 jam berikutnya.
2. 1 tahun : 30 cc/kgBB dalam ½ jam pertama dilanjutkan 70
cc/kgBB dalam 2 ½ jam berikutnya.
Minum diberikan jika pasien sudah mau minum 5 cc/kgBB selama
proses rehidrasi.
2. Pemakaian antibiotik
Bila ada indikasi seperti pada Shigella dan Cholera. Antibiotik sesuai
dengan hasil pemeriksaan penunjang. Sebagai pilihan adalah
kotrimoksazol, amoksisilin dan atau sesuai hasil uji sensitivitas.
3. Diet
28
Anak tidak boleh dipuasakan, makanan diberikan sedikit-sedikit tapi
sering, rendah serat, buah-buahan diberikan terutama pisang.
4. Jangan menggunakan spasmolitika
5. Koreksi elektrolit : koreksi bila terjadi hipernatremia, hiponatremia,
hiperkalemia atau hipokalemia.
6. Probiotik
7. Vitamin A
a. 6 bulan- 1 tahun : 100.000 IU
b. > 1 tahun : 200.000 IU
8. Pendidikan orangtua : penyuluhan tentang penanganan diare dan cara-
cara pencegahan diare (IDAI, 2004).
Indikasi rawat inap :
1. Diare akut dengan dehidrasi berat
2. Diare akut dehidrasi ringan sedang dengan komplikasi
3. Usia < 6 bulan (usia yang mempunyai resiko tinggi mengalami
dehidrasi), buang air besar cair > 8 kali dalam 24 jam dan muntah > dari
4 kali sehari (Armon, 2001).
M. Pemantauan
1. Terapi
2. Setelah pemberian cairan rehidrasi harus dinilai ulang derajat dehidrasi,
barat badan, gejala dan tanda dehidrasi. Jika masih dehidrasi maka
dilakukan rehidrasi ulang sesuai dengan dehidrasinya. Jika setelah 3
hari pemberian antibiotik klinis dan laboratorium tidak ada perubahan
maka dipikirkan penggantian antibiotik sesuai hasil uji sensitivitas.
3. Tumbuh Kembang
4. Timbang berat badan sebelum dan sesudah rehidrasi, 2 minggu setelah
sembuh dan seterusnya secara periodik sesuai umur. Jika anak
mengalami gizi buruk maka dikelola sesuai dengan SPM gizi buruk.
Penderita dapat dipulangkan bila penderita tidak dehidrasi, keadaan umum
dan tanda vital baik, sudah bisa makan dan minum (IDAI, 2004).
29
ANEMIA DEFISIENSI BESI
A. Definisi
Anemia yang disebabkan kurangnya zat besi untuk sintesis hemoglobin.
B. Patofisiologi
Zat besi (Fe) diperlukan untuk pembuatan heme dan hemoglobin (Hb).
Kekurangan Fe mengakibatkan kekurangan Hb. Walaupun pembuatan eritrosit
juga menurun, tiap eritrosit mengandung Hb lebih sedikit dari pada biasa
sehingga timbul anemia hipokromik mikrositik.
C. Etiologi
Kekurangan Fe dapat terjadi bila :
Makanan tidak cukup mengandung Fe
Komposisi makanan tidak baik untuk penyerapan Fe (banyak sayuran,
kurang daging)
Gangguan penyerapan Fe (penyakit usus, reseksi usus)
Kebutuhan Fe meningkat (pertumbuhan yang cepat, pada bayi dan
adolesensi, kehamilan)
Perdarahan kronik atau berulang (epistaksis, hematemesis,
ankilostomiasis).
D. Epidemiologi
Diperkirakan 30% penduduk dunia menderita anemia dan lebih dari 50%
penderita ini adalah ADB dan terutama mengenai bayi,anak sekolah, ibu hamil
dan menyusui. Di Indonesia masih merupakan masalah gizi utama selain
kekurangaan kalori protein, vitamin A dan yodium. Penelitian di Indonesia
mendapatkan prevalensi ADB pada anak balita sekita 30-40%, pada anak
30
sekolah 25-35% sedangkan hasil SKRT 1992 prevalensi ADB pada balita
sebesar 55,5%. ADB mempunyai dampak yang merugikan bagi kesehatan
anak berupa gangguan tumbuh kembang, penurunan daya tahan tubuh dan
daya konsentrasi serta kemampuan belajar sehingga menurunkan prestasi
belajar di sekolah.
E. Diagnosis
1. Anamnesis
a. Riwayat faktor predisposisi dan etiologi :
Kebutuhan meningkat secara fisiologis
- masa pertumbuhan yang cepat
- menstruasi
- infeksi kronis
Kurangnya besi yang diserap
- asupan besi dari makanan tidak adekuat
- malabsorpsi besi
Perdarahan
- Perdarahan saluran cerna (tukak lambung, penyakit Crohn, colitis
userativa)
b. Pucat, lemah, lesu, gejala pika
2. Pemeriksaan fisis
a. Anemis, tidak disertai ikterus, organomegali
b. Limphadenopati, stomatitis angularis, atrofi papil lidah
c. Ditemukan takikardi, murmur sistolik dengan atau tanpa pembesaran
jantung
3. Pemeriksaan penunjang
a. Hemoglobin, Hct dan indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC) menurun
b. Hapus darah tepi menunjukkan hipokromik mikrositik
31
c. Kadar besi serum (SI) menurun dan TIBC meningkat , saturasi
menurun
d. Kadar feritin menurun dan kadar Free Erythrocyte Porphyrin (FEP)
meningkat
e. sumsum tulang : aktifitas eritropoitik meningkat
F. Diagnosis Banding
Anemia hipokromik mikrositik:
1. Thalasemia (khususnya thallasemia minor) :
‐ Hb A2 meningkat
‐ Feritin serum dan timbunan Fe tidak turun
2. Anemia karena infeksi menahun:
‐ Biasanya anemia normokromik normositik. Kadang-kadang terjadi
anemia hipokromik mikrositik
‐ Feritin serum dan timbunan Fe tidak turun
3. Keracunan timah hitam (Pb):
‐ Terdapat gejala lain keracunan Pb
4. Anemia sideroblastik:
‐ Terdapat ring sideroblastik pada pemeriksaan sumsum tulang
G. Penyulit
Bila Hb sangat rendah dan keadaan ini berlangsung lama dapat terjadi
payah jantung.
H. Penatalaksanaan
1. Medikamentosa
- Pemberian preparat besi (ferosulfat/ferofumarat/feroglukonat) dosis 4-6
mg besi elemental/kgBB/hari dibagi dalam 3 dosis, diberikan di antara
waktu makan. Preparat besi ini diberikan sampai 2-3 bulan setelah kadar
hemoglobin normal.
32
- Asam askorbat 100 mg/15 mg besi elemental (untuk meningkatkan
absorbsi besi).
2. Bedah
- Untuk penyebab yang memerlukan intervensi bedah seperti perdarahan
karena diverticulum Meckel.
3. Suportif
- Makanan gizi seimbang terutama yang mengandung kadar besi tinggi
yang bersumber dari hewani (limfa, hati, daging) dan nabati (bayam,
kacang-kacangan).
4. Lain-lain (rujukan sub spesialis, rujukan spesialisasi lainnya)
- Ke sub bagian terkait dengan etiologi dan komplikasi (Gizi, Infeksi,
Pulmonologi, Gastro-Hepatologi, Kardiologi).
I. Langkah Promotif/Preventif
Upaya penanggulangan AKB diprioritaskan pada kelompok rawan yaitu
BALITA, anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, wanita usia subur
termasuk remaja putri dan pekerja wanita. Upaya pencegahan efektif untuk
menanggulangi AKB adalah dengan pola hidup sehat dan upaya-upaya
pengendalian faktor penyebab dan predisposisi terjadinya AKB yaitu berupa
penyuluhan kesehatan, memenuhi kebutuhan zat besi pada masa pertumbuhan
cepat, infeksi kronis/berulang pemberantasan penyakit cacing dan fortifikasi
besi.
33
DAFTAR PUSTAKA
1. Armon, 2001. An evidence and consensus based guidline for acute
diarrhoea management. [email protected]
2. Aswitha, dkk, 2000. Kapita Selekta Kedokteran. Gastroenterologi Anak.
Media Aesculapius. Jakarta. Hal 470-471.
3. Ditjen PPM & PLP. 1999. Buku Ajar Diare. Jakarta. Hal: 8-10
4. IDAI, 2004. Standar Pelayanan Medis. Badan Penerbit IDAI. Jakarta. Hal:
49-52
5. Irwanto, 2002. Ilmu Penyakit Anak. Diagnosa dan Penatalaksanaan.
Salemba Medika. Jakarta. Hal : 73-79.
6. Randy P Prescilla, MD, FAAP, 2006. Gastroenteritis
www. emedicinehealth.com
7. Subagyo, 2004. Standar Pelayanan Medis Kelompok Staf Medis
Fungsional Anak RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Surakarta. Hal : 58-63.
8. WHO, 2004. Diarrhoea : Water, Sanitation and Hygiene Links to Health
www.wikipedia.com
9. Hillman RS, Ault KA. 1995. Iron Deficiency Anemia. Hematology in
Clinical Practice. A Guide to Diagnosis and Management. New York;
McGraw Hill, pp: 72-85
10. Lanzkowsky P. 1995. Iron Deficiency Anemia. Pediatric Hematology and
Oncology. Edisi ke-2. New York; Churchill Livingstone Inc, 1995 : 35-50.
11. Recht M, Pearson HA. 1999. Iron Deficiency Anemia. Dalam : McMillan
JA, DeAngelis CD, Feigin RD, Warshaw JB, penyunting. Oski’s
Pediatrics: Principles and Practice. Edisi ke-3. Philadelphia; Lippincott
William & Wilkins, pp: 1447-8
34