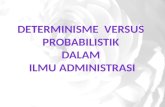Politik Roma Versus Politik Yesus
-
Upload
chandra-hartanto -
Category
Documents
-
view
54 -
download
3
description
Transcript of Politik Roma Versus Politik Yesus
Politik Roma Versus Politik Yesus
Pada kesempatan ini akan dikemukakan dengan singkat hal-hal historis apa yang menjadi penyebab Yesus dihukum mati melalui penyaliban dirinya. Tulisan ini, dengan demikian, adalah tulisan kelima dari rangkaian tulisan di blog ini yang menyoroti tema masalah-masalah dalam soteriologi salib.
Jauh sebagai suatu peristiwa adikodrati satu-satunya yang bersignifikansi soteriologis universal dan abadi, kematian Yesus di kayu salib faktual historisnya adalah suatu peristiwa kodrati, insani dan politis biasa dalam suatu ruang dan waktu terbatas yang tidak berdimensi soteriologis universal dan abadi apapun.
Melalui banyak perumpamaannya dan banyak ucapannya yang lain, Yesus memberitakan bahwa Kerajaan Allah sedang ada di tengah rakyat Yahudi yang sedang dijajah Roma (antara lain, Lukas 17:21b), bahwa Allah Yahudi kini sedang langsung memerintah sebagai Raja, dan murid-muridnya diajarnya untuk meminta supaya Kerajaan Allah ini terus-menerus berada di tengah mereka (Lukas 11:2; Matius 6:10). Akta-akta Yesus mendemonstrasikan bahwa bersama Yesus benar Allah sedang berkarya di tengah bangsa Yahudi. Kata Yesus, “Jikalau aku mengusir setan dengan jari Allah, sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu!” (Lukas 11:20; Matius 12:28) Hanya Allah yang menjadi Raja mereka. Inilah teokratisme Yesus. Sementara itu, pada pihak lain, bagi orang Romawi, hanya sang Kaisar yang bertakhta di Roma yang merupakan raja baik bagi bangsa Romawi sendiri maupun bagi semua bangsa jajahan. Bagi Yesus, dalam teokratisme Yahudi tidak bisa ada dua raja, melainkan hanya satu; dan raja ini bukan sang Kaisar tetapi Allah Yahudi. Dengan demikian, Yesus atas nama Allah dan atas nama rakyat menolak dan melawan Kaisar.
Perlawanan Yesus dari Nazaret terhadap Roma yang sedang menjajah bangsa Yahudi dengan jelas diungkap secara simbolik, antara lain, dalam tuturan sastra injil tentang seorang Gerasa yang kerasukan roh jahat (Markus 5:1-20). Ketika Yesus bertanya kepada roh jahat itu siapa namanya, roh itu menjawab, “Namaku legion, karena kami banyak.” (ayat 9). Kata Latin “legion” dikenakan untuk satuan prajurit pejalan kaki Roma ditambah pasukan berkuda, dengan jumlah besar antara 3.000 sampai 6.000 orang. Nama ini, dengan demikian, adalah kiasan untuk penjajahan Roma atas Tanah Israel. Dus, Yesus mendemonisasi lawannya, Kekaisaran Romawi. Permusuhan dan perlawanan terhadap Roma yang menduduki tanah Israel diungkap dengan jelas ketika Yesus berseru kepada setan-setan itu, “Keluar dari orang ini!” Tetapi setan-setan itu meminta untuk diizinkan tetap tinggal di daerah itu (ayat 10)―inilah persisnya yang dikehendaki Roma, yakni tetap mengontrol seluruh Tanah Israel. Sebaliknya, rakyat Israel menginginkan mereka diusir dan dibenamkan ke dalam danau seperti babi-babi. Yesus tampil sebagai seorang pengusir setan yang digdaya; dan kehadirannya sebagai orang yang dipenuhi Roh dan kuasa Allah (Markus 1:10b, 12; Matius 12:28; Lukas 11:20; lebih jauh tentang ini, klik http://www.ioanesrakhmat.com/2008/10/spiritualitas-yesus-dari-nazaret.html) sungguh merupakan suatu ancaman nyata bagi kedamaian dan stabilitas masyarakat Israel di bawah rekayasa politis kolonial Roma (Pax Romana): saat Roma mati terbenam dalam air danau hanya menunggu waktunya saja, pembebasan tidak lama lagi tiba.
Bagi Yesus, Tanah Israel, Eretz Israel, adalah milik Allah Yahudi, Tanah Perjanjian yang oleh Allah Yahudi dulu diberikan kepada Abraham, dan yang kemudian diwariskan kepada keturunannya yang membentuk satu bangsa Israel. Bagi Yesus, Allah Abraham adalah Allah Ishak dan Allah Yakub
(Markus 12:26), Allah bangsa Israel. Ikatan perjanjian dengan Abraham ini, dalam pandangan Yesus, tidak pernah dibatalkan: Israel, menurutnya, adalah “satu keluarga” yang tidak boleh dipecah-belah (Markus 3:25), dan “anak-anak” dalam satu keluarga harus diperhatikan lebih dulu (Markus 7:27). Untuk menunjukkan bahwa Yesus ingin mempertahankan dan mengembalikan keutuhan 12 suku Israel, dia membentuk komunitas kecil lingkaran dalam para murid yang terdiri atas 12 orang (Markus 3:14). Jelas, Yesus memperjuangkan kepentingan Israel sebagai satu bangsa. Maka, kalau dikaitkan dengan Tanah Israel, ketika Yesus berkata, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah” (Markus 12:17), dia bermaksud menyatakan bahwa Kaisar tidak memiliki Tanah Israel, tetapi Allah pemiliknya, karena itu tanah ini harus Kaisar kembalikan kepada Allah, pemilik sah tanah ini, dan kepada bangsa Israel, umat Allah, yang mewarisi tanah itu dari Abraham. Dan bangsa Roma harus menyingkir dari tanah yang bukan milik mereka, kembali ke negeri asal mereka sendiri. Doktrin sekular tentang pemisahan agama/gereja dan negara tidak termuat dalam ucapan politis Yesus ini, Yesus yang berwawasan teokratis.
Berita yang terus-menerus di banyak lokasi di Galilea disampaikan Yesus bahwa kini Allah Yahudi sedang memerintah sebagai Raja Israel ditafsir lawan-lawannya sebagai suatu proklamasi bahwa dia sendiri adalah raja Yahudi, dan dengan demikian dia menolak dan melawan Kaisar Roma. Penafsiran semacam ini bisa dibenarkan mengingat bahwa dalam kepercayaan mesianik Israel orang yang berbicara dan bertindak atas nama Allah, seperti Yesus dari Nazaret, adalah wakil langsung dari Allah, representasi Allah sendiri, dan tangan Allah sendiri. Wakil, representasi, juru bicara dan tangan Allah dalam kehidupan riil bangsa Israel tidak lain adalah raja atau mesias Israel sendiri. Adalah suatu ketentuan hukum Romawi, barangsiapa menolak dan melawan Kaisar, orang itu harus dihukum mati.
Persis ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem pada perayaan Paskah Yahudi, perayaan untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, orang banyak memproklamasikan Yesus sebagai Raja Israel; kata mereka, dalam tuturan Markus, “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi” (Markus 11:9; par.). Tetapi ada persoalan di sini. Apa yang dicatat dalam injil-injil sinoptik (Markus, Matius dan Lukas) tentang masuknya Yesus dengan jaya dan aman-aman saja ke kota Yerusalem pada perayaan Paskah setelah orang banyak mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus adalah sang Raja Yahudi, keturunan Raja Daud, sukar dipercaya sebagai kejadian historis. Jika arak-arakan gegap gempita yang kuat diwarnai pesan-pesan mesianik dan pemulihan kerajaan Daud ini sungguh terjadi, pasti peristiwa ini akan diberi reaksi represif cepat oleh Gubernur Pontius Pilatus (yang sedang berada di Yerusalem) untuk mencegah timbulnya pemberontakan sekaligus untuk “mengamankan” figur yang diproklamasikan rakyat banyak sebagai mesias Yahudi. Tuturan tentang peristiwa yang sama dalam Injil Yohanes (12:12-16) lebih dapat dipercaya, karena, dituturkan, setelah orang banyak memproklamasikan Yesus sebagai “Raja Israel” (ayat 13), Yesus “pergi bersembunyi” (ayat 36b), menghindari para penguasa yang pasti sedang mencarinya untuk menangkapnya.
Bagaimana pun juga, tuturan dalam keempat injil tentang kejadian di pintu gerbang Yerusalem ini bermaksud untuk menyampaikan sebuah fakta bahwa rakyat Yahudi memang menantikan kedatangan seorang mesias pembebas dan pemenuhan penantian ini tampaknya, oleh orang
banyak, dikaitkan dengan kehadiran Yesus di tengah mereka. Hal ini bisa terjadi karena mereka menyamakan Yesus yang memberitakan kedatangan Kerajaan Allah dan memperagakan kehadiran kuasa Allah dalam tindakan-tindakan penyembuhan dan eksorsismenya dengan Kerajaan Allah itu sendiri. Yesus menunjuk pada Kerajaan Allah dan mengajak orang banyak untuk melihat kepada Kerajaan ini, tetapi rakyat menunjuk pada Yesus sebagai sang mesias yang bertakhta dalam Kerajaan itu sendiri, dan para penguasa Bait Allah menuduh Yesus sebagai orang yang mengklaim posisi mesianik. Mereka mengganti Allah yang diwartakan dan diejawantahkan Yesus dengan diri Yesus sendiri! Bagi Yesus, Allah adalah sang Pembebas Israel, tetapi bagi rakyat Yahudi Yesuslah sang Pembebas mereka!
Ketika Yesus sudah berada di Yerusalem, dia memasuki Bait Allah lalu melakukan unjuk rasa di sana dan berkata keras mengenai Bait ini (Markus 11:15-18; Injil Thomas # 71; Yohanes 2:14-16a). Demonstrasi Yesus di Bait Allah, meskipun berskala kecil, dan ucapan kerasnya, adalah simbol, tanda, isyarat dan pesan bahwa dia menolak otoritas Yahudi dan otoritas Roma yang menguasai Bait Allah. Sebab kedua otoritas ini menghalangi keterlibatan langsung Allah Yahudi dalam kehidupan bangsa Yahudi. Bait Allah, melalui ritual kurban serta pemungutan pajak yang dilakukan di dalamnya, di tangan kedua otoritas ini telah menjadi sebuah institusi religio-politis yang menekan rakyat, yang menghalangi perjumpaan langsung rakyat dengan Allah Yahudi, karena kedua otoritas ini berfungsi sebagai broker (yang dalam pandangan Yesus) tidak sah antara Allah Yahudi dan rakyat. Keselamatan dari Allah dan kasih karunia-Nya, bagi Yesus, tidak boleh diperantarai oleh siapapun dan oleh otoritas kelembagaan apapun, melainkan harus langsung diterima rakyat Yahudi, sebab Kerajaan Allah ada di tengah rakyat.
Celakanya, menyerang Bait Allah, menentang otoritas yang menguasainya, dan menolak ritual dan pemungutan pajak resmi yang dilakukan di dalamnya, apalagi kalau perlawanan, penentangan dan penolakan ini dilakukan pada perayaan Paskah, akan berakibat kematian bagi si pelawan. Barangsiapa menyerang Bait Allah, orang itu dipandang menyerang Roma sebagai penguasa yang ada di belakang Bait Allah, yang memerintah Tanah Israel melalui wakil Kaisar (gubernur provinsi Yudea) dan kaki tangan Yahudinya (keluarga Herodes, kaum bangsawan Yahudi, Imam Besar Kayafas, Sanhedrin, imam-imam kepala, para ahli Taurat dan para tua-tua)! Hukuman mati adalah ganjaran sah bagi setiap orang yang menyerang Bait Allah. Tentu, di balik ini, ada suatu kesepakatan tidak tertulis antara otoritas Romawi dan otoritas Yahudi yang menetapkan bahwa barangsiapa membuat suatu kerusuhan di Bait Allah dan di kota Yerusalem pada perayaan Paskah, yang potensial menimbulkan keributan besar, orang itu dapat langsung ditangkap, diperiksa singkat lalu dieksekusi, sebagai suatu gertak dan teror terhadap rakyat Yahudi supaya mereka tidak bertindak macam-macam (bdk. Markus 14:2; Yohanes 11:48).
Melalui suatu kerjasama otoritas Yahudi dan otoritas Romawi, dan dengan melibatkan seseorang dari “lingkaran dalam” komunitas kecil yang Yesus bangun, Yesus kemudian dapat ditangkap, lalu diperiksa, dan akhirnya dihukum mati menurut cara penghukuman mati Romawi bagi para pemberontak: Yesus mati disalibkan dengan sebuah tuduhan politis bahwa dia mengklaim diri sebagai Raja Orang Yahudi di suatu tanah yang sedang dijajah Roma. Tuduhan ini ditulis pada titulus yang dipasang pada kayu salib Yesus. Tuduhan semacam ini (yang mendakwa Yesus sebagai Raja Orang Yahudi, dan bukan Raja Orang Israel) hanya mungkin dikeluarkan oleh pihak Roma. Di awal pemeriksaannya terhadap Yesus yang sedang diadili, Pontius Pilatus bertanya, “Engkau inikah raja
orang Yahudi?” (Markus 15:2; Matius 27:11; Lukas 23:3; Yohanes 18:33).
Jadi, kematian Yesus adalah suatu konsekwensi politis wajar dan insani dari keyakinan dan kiprah politis Yesus sendiri. Yesus, dengan gerakannya menghadirkan Kerajaan Allah di tengah rakyat yang membuatnya dipandang sebagai sang mesias atau raja Yahudi, terlalu kecil dan lemah ketika dia berhadapan dengan raksasa Imperium Romanum yang sedang menjajah negeri dan bangsanya. Dia adalah seorang teokratis dan mesianis yang gagal. Tidak ada keselamatan, kemerdekaan dan penyucian yang timbul dari kematiannya di kayu salib bagi bangsa Israel, berbeda dari keyakinan para pejuang Makkabe dalam sejarah Israel (abad 2 SM) bahwa curahan darah suci setiap mukmin Yahudi akan memberi kemerdekaan dan penyucian bagi Tanah Israel! (lebih jauh tentang ini, klik http://ioanesrakhmat2009.blogspot.com/2009/05/betulkah-yesus-dengan-sengaja-mau-mati.html). Roma masih berkuasa atas Tanah Israel beberapa ratus tahun ke depan setelah kegagalan pergerakan yang Yesus lancarkan; bahkan sejak berakhirnya Perang Yahudi II melawan Roma (132-135 M) yang dipimpin Mesias Simon Bar Kokhba Israel tidak pernah lagi berdiri sebagai suatu bangsa dan negara merdeka sampai pada terbentuknya Negara Israel modern yang sekular di tahun 1948.
Kematian Yesus di kayu salib pada saat terjadinya tidak memberi efek soteriologis bagi Tanah Israel dan bangsa Yahudi, apalagi efek soteriologis universal dan abadi apapun, tidak seperti belakangan diklaim orang Kristen perdana, dua sampai sepuluh dasawarsa setelah Yesus wafat. Orang Kristen perdana, ketika mereka merenungi makna kematian Yesus yang sia-sia dan berupaya keluar dari keadaan gagal dan memalukan yang sangat kuat menekan mental mereka melalui rasionalisasi-rasionalisasi teologis yang mereka buat (tentang ini, klik http://ioanesrakhmat2009.blogspot.com/2009/04/jalan-jalan-keselamatan-alternatif.html), mengklaim bahwa kematian Yesus menyelamatkan umat manusia dan jagat raya. Ini sungguh suatu klaim yang terlalu tinggi, jauh dari kenyataan yang sebenarnya.
Soteriologi Salib Meremehkan Kemampuan Manusia
Merengek-rengek, meminta belas kasihan dan keselamatan?
Menurut soteriologi salib, azab dan kematian Yesus di kayu salib pasti tidak sia-sia, sebab azab dan kematian Yesus ini adalah jalan keselamatan yang Allah haruskan dan sediakan satu-satunya, dan dengan demikian merupakan jalan yang pasti efektif dan mujarab mendamaikan Allah dengan manusia dan berkhasiat secara magis untuk menjadikan manusia, memakai ungkapan Rasul Paulus, “ciptaan baru” (2 Korintus 5:17). Namun, seperti sudah saya tekankan sebelumnya (klik di sini), soteriologi salib faktanya tidak mujarab dan tidak berkhasiat apa-apa. Kesengsaraan dan kematian Yesus hanya tinggal sebagai suatu fakta sejarah yang mengerikan di masa lampau, tidak berdampak riil dan signifikan bagi perubahan watak dan moralitas manusia dan peradaban dunia pada masa kini.
Nah, pada kesempatan ini saya ingin menggugat soteriologi salib dari suatu sudut pandang lainnya. Dalam penilaian saya, soteriologi ini merendahkan sampai ke titik nol kemampuan manusia pada dirinya sendiri untuk meraih dan mengerjakan keselamatannya sendiri.
Yang saya maksud dengan “keselamatan” di sini bukanlah keselamatan di akhirat yang diterima orang ketika dia masuk surga sesudah kematiannya. Sebagaimana sudah saya argumentasikan
sebelumnya (klik di sini), di alam baka surga dan neraka itu, jangan kaget, tidak ada. Bagi saya, dan bagi sangat banyak orang lainnya, Kristen maupun bukan, kehidupan yang terpenting bagi manusia adalah kehidupannya sekarang ini di dalam dunia ini, sementara manusia masih memiliki tubuh dan menjalani kehidupan berbudaya.
Keselamatan yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah perubahan watak, karakter dan moralitas manusia sementara dia masih hidup dalam dunia ini sekarang ini. Doktrin tentang keselamatan yang ditawarkan suatu agama manapun yang tidak mengubah watak, karakter dan moralitas manusia sekarang ini di dalam dunia ini adalah doktrin yang kosong melompong dan tidak signifikan, karena hanya menghanyutkan orang masuk ke dalam angan-angan tentang suatu surga di luar dunia dan di luar sejarah―suatu eskapisme dangkal dari orang-orang yang lemah jiwanya, yang hanya mau beragama karena diiming-imingi hadiah surga sesudah kematian, seperti kanak-kanak yang baru mau belajar hanya kalau diiming-imingi sebuah permen atau sebuah boneka baru.
Soteriologi salib harus digugat, karena, seperti sudah dikatakan di atas, soteriologi ini dibangun di atas sebuah asumsi etis antropologis negatif bahwa manusia pada dirinya sendiri, secara moral, adalah makhluk yang pada kodratnya serba bobrok dan bejat, yang sama sekali tidak bisa berbuat baik, yang telah sepenuhnya kehilangan kemuliaan Allah (teks suci yang sering dikutip gereja adalah Roma 3:10-23). Kebobrokan dan kebejatan moralitas manusia ini pertama-tama adalah, kata gereja dengan mengutip teks suci, akibat dari dosa Adam dan Hawa dulu di Taman Eden (Kejadian 3:1-19), yang terus menjalar ke seluruh manusia di seantero planet bumi dan di segala zaman sampai dunia ini kiamat (Roma 5:12-19).
Gereja dengan ekstrim lebih jauh mengajarkan bahwa pemberontakan Adam dan Hawa terhadap Allah yang mengakibatkan mereka menerima penghukuman ilahi menyebabkan setiap bayi yang baru dilahirkan pada masa sesudahnya dilahirkan sebagai manusia berdosa yang bermoral bejat, kendatipun sang bayi masih belum tahu membedakan tangan kanannya dari tangan kirinya. Dosa “asal” atau dosa “warisan” ini menyebabkan setiap orang sejak dilahirkan sudah bobrok secara moral, dan untuk seterusnya tidak akan mampu berbuat baik dan benar secara moral, sampai mereka, demikian gereja mengajarkan, diselamatkan oleh azab dan kematian Yesus dan menerima baptisan Kristen sebagai suatu tahap inisiasi masuk ke dalam kehidupan yang diselamatkan di dalam persekutuan gereja.
Saya mau menegaskan bahwa asumsi etis antropologis negatif yang menjadi landasan soteriologi salib ini keliru, berdasarkan alasan berikut.
Sejarah evolusi manusia, fisikal maupun sosio-kultural, yang sudah berlangsung dalam kurun yang sangat panjang di muka bumi menunjukkan bahwa manusia pada dirinya sendiri memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan kebudayaan serta peradaban mereka ke arah yang makin baik, makin cemerlang dan makin bertahan ke depan. Seleksi alam (natural selection) memang menentukan dan kerap tidak terhindarkan, tetapi manusia, secara individual maupun secara kolektif, juga memiliki kemampuan yang membuat mereka umumnya selalu bisa bertahan dan menang (survival of the fittest) dalam menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan serta tantangan berat alamiah dan kultural yang menghadang kehidupan dan kebudayaan mereka. Kemampuan ini juga mencakup kemampuan untuk manusia makin dapat hidup dengan lebih baik
secara moral pada diri mereka sendiri.
Memang banyak kejadian di dalam dunia ini dan sejarah manusia yang juga menunjukkan bahwa manusia kerap gagal pada diri mereka sendiri untuk hidup baik dan benar secara moral, misalnya manusia masih dikuasai dorongan primordial untuk berperang satu sama lain sehingga akhirnya membinasakan kehidupan dan menghancurkan peradaban mereka sendiri. Tetapi, fakta bahwa manusia dan peradabannya masih bisa bertahan dan bahkan lebih dikembangkan lagi hingga ke zaman modern ini dan ke zaman-zaman seterusnya memperlihatkan bahwa naluri dan kesadaran mereka mengenai kebajikan, kebenaran dan tanggungjawab masih lebih kuat ketimbang naluri kejahatan yang bisa menghancurkan mereka.
Dari manakah kemampuan mengembangkan moralitas positif dalam diri manusia ini berasal? Jelas, bukan dari intervensi ilahi apapun, melainkan dari gen manusia (nature) dan pendidikan (nurture) yang mereka terima.
Gen yang baik, pendidikan moral yang benar dan kehidupan masyarakat yang sehat, akan menghasilkan manusia-manusia bermoral yang tangguh di dalam masyarakat. Bila aspek genetik yang baik dan aspek genetik yang altruis diberi tempat utama untuk berperan, berhadapan dengan aspek genetik yang buruk dan aspek genetik yang egois dan serakah, masa depan manusia akan lebih baik di tangan mereka sendiri. Sains dan teknologi modern di bidang biologi molekuler sudah bisa merekayasa gen manusia; prestasi di bidang sains genetik ini, bila dengan hati-hati dan dengan penuh tanggungjawab etis dikembangkan, bisa lebih membuka harapan dalam usaha manusia untuk mengembangkan dan memapankan segi-segi kebaikan dan kebajikan moral manusia.
Nah, harus diakui bahwa manusia pada dirinya sendiri memiliki kemampuan untuk hidup bermoral tinggi, karena kodrat genetiknya dan karena hasil pendidikannya. Soteriologi salib bisa berjalan, fungsional, hanya kalau kemampuan positif manusia ini disangkal total, dan kalau perasaan sangat berdosa dan tidak memiliki kemampuan moral apapun untuk berbuat baik dibesar-besarkan sedemikian rupa sampai membuat manusia tidak bisa lagi melihat bahwa dirinya sebenarnya mampu berbuat baik secara moral.
Soteriologi salib sangat menghina dan merendahkan kapasitas manusia individual dan kolektif untuk berbuat kebajikan, dan harus memaksa manusia melihat dirinya sangat hina dan tidak berharga secara moral apapun, melainkan hanya bisa menangis dan meratap di hadapan suatu Allah Kristen yang dari-Nya diharapkan belas kasihan kepada dirinya yang tidak berharga apapun diberikan.
Singkat kata, soteriologi salib tidak membantu manusia mengembangkan dirinya untuk makin baik secara moral, malah mendemoralisasi manusia. Soteriologi salib menuntut kita merangkak dengan terluka dan meratap di bawah kaki Yesus, bukan berjalan sebagai sahabat bersamanya! Dan ajaran tentang dosa warisan tidak memberi dampak positif secara psikologis kepada manusia masa kini karena memperlakukan manusia taken for granted sebagai manusia yang bermoral bobrok, dan juga tidak etis karena menjatuhkan penghukuman atas dosa dua orang nenek moyang manusia kepada keturunan mereka yang hidup di zaman-zaman lain.
Soteriologi Salib Tidak Mujarab
Orang Kristen sedunia sering membanggakan soteriologi salib sebagai satu-satunya soteriologi atau jalan keselamatan yang paling menjamin manusia. Betapa tidak? Dalam soteriologi salib, kata orang Kristen, jalan keselamatan manusia diberikan atau diprakarsai oleh Allah sendiri, yakni dengan Allah menyediakan sendiri jalannya, yakni jalan sengsara (via dolorosa) Yesus Kristus dan kematiannya yang mengerikan di kayu salib. Manusia tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk keselamatan diri mereka, melainkan hanya tinggal menerima saja jalan yang Allah berikan ini.
Kata gereja, soteriologi salib ini berbeda dari soteriologi Islam, misalnya, yang mengharuskan manusia melakukan kebajikan lebih banyak dari kejahatan jika manusia ini ingin mengalami keselamatan, masuk surga. Dalam penilaian keliru orang Kristen (tentang ini, lihat di sini), soteriologi Islami yang menempatkan perbuatan manusia pada tempat utama ini menyebabkan kaum Muslim terus-menerus merasa tidak pasti mengenai masa depan mereka di akhirat.
Menurut soteriologi salib, ketika Yesus memikul salib, menanggung azab, kesengsaraan dan aniaya, dan akhirnya mati dibunuh melalui penyaliban dirinya oleh musuh-musuhnya, Yesus mengalami ini semua karena dia diharuskan (Yunani: dei) Allah untuk menanggung di atas pundaknya sendiri semua penghukuman ilahi yang seharusnya ditanggung manusia karena dosa-dosa mereka terhadap Allah, baik dosa warisan Adam dan Hawa maupun dosa pribadi. Karena Yesus, demi manusia, sudah menanggung hukuman berat ini di dalam azab, kesengsaraan dan kematiannya sendiri, manusia tidak perlu lagi menerima penghukuman Allah, tapi tinggal menerima keselamatan saja, tanpa harus membayar apapun, sebab semuanya diberikan betul-betul gratis oleh Allah (sola gratia).
Untuk manusia menerima keselamatan dari Allah, dibebaskan dari penghukuman ilahi, manusia, demikian gereja mengajarkan, hanya perlu menerima dengan patuh dan dengan iman (sola fide) jalan keselamatan yang Allah telah sediakan ini.
"Menerima dengan patuh" berarti menyatakan ya dan persetujuan total, tanpa protes apapun, terhadap kekerasan yang Allah telah lakukan di dalam azab, kesengsaraan dan kematian Yesus (tentang kekerasan ilahi ini, lihat di sini) sebagai jalan pengganti yang seharusnya ditempuh manusia berdosa, sebagai jalan untuk membebaskan manusia dari penghukuman ilahi, sebagai jalan untuk menebus manusia dari hutang nyawa yang ditimbulkan oleh dosa yang telah diperbuat nenek moyang manusia maupun oleh diri mereka sendiri, sebagai jalan yang melaluinya Allah mendamaikan diri-Nya dengan manusia, sebagai jalan manusia mengalami pemulihan hubungan dengan Allah dan dengan sesamanya.
"Menerima dengan iman" berarti mempercayai dengan sungguh-sungguh dalam hati dan menerima dalam pikiran sebagai kebenaran bahwa jalan salib Yesus dan kematiannya yang mengerikan telah dengan mujarab menghapus semua dosa manusia, telah dengan cespleng menyembuhkan manusia dari luka-luka yang ditimbulkan oleh kehidupan yang berat dan melelahkan sebagai akibat dosa-dosa manusia, telah dengan berkhasiat mendatangkan suatu kehidupan baru melalui kelahiran kembali (rebirth) manusia yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga manusia mampu menjalani kehidupan moral yang benar dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesama. Pendek kata, jalan salib Yesus dan kematiannya, kalau benar jalan ini adalah jalan satu-satunya yang Allah berikan dengan gratis kepada dunia ini, haruslah jalan yang mujarab satu-satunya untuk melahirkan suatu kemanusiaan yang pada masa kini dalam dunia ini secara menyeluruh mengalami pembaruan, dan
yang akan pasti menerima kehidupan surgawi di alam baka ketika sejarah manusia berakhir total.
Nah, pada kesempatan ini saya mau menyoroti dengan singkat poin terakhir yang baru dikemukakan di atas, yakni bahwa jalan kesengsaraan Yesus dan kematiannya di kayu salib, atau soteriologi salib, pasti mujarab untuk menghasilkan suatu kemanusiaan yang secara total dibarui, a totally new humanity, kalau memang benar bahwa jalan ini adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia yang disediakan Allah sendiri dan azab serta kematian Yesus tidak sia-sia. Sedangkan ihwal bahwa kepercayaan pada azab dan kematian Yesus akan membebaskan orang dari ancaman api neraka, dan menjamin orang masuk surga, tidak perlu saya soroti lagi karena saya sudah mengulas dengan kritis pokok tentang surga dan neraka di blog ini.
Soteriologi salib sangat kuat menekankan dampak dari via dolorosa dan kematian Yesus terhadap moralitas manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus [maksudnya: percaya kepada azab dan kematian Yesus di kayu salib sebagai jalan jitu penebusan manusia dari hutang-hutang dosa mereka, sebagai jalan jitu Allah mendamaikan diri-Nya dengan dunia ini] adalah, menurut suatu teks suci, "ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang" (2 Korintus 5:17; Galatia 6:15).
Pertanyaannya: Apakah betul soteriologi salib Yesus Kristus mujarab menghasilkan orang Kristen yang diciptakan baru, yang kehidupan moralnya luhur, tinggi, dan menjadi teladan suatu kehidupan baru, yang dimungkinkan terjadi karena peristiwa salib Yesus satu-satunya dan pekerjaan Roh Kudus?
Jawabannya: Tidak!
Dalam hal moralitas, kebanyakan orang Kristen pada masa kini, meskipun mengklaim diri sudah bertobat dan sudah lahir baru, dalam kenyataannya hidup tidak berbeda dari kebanyakan orang lainnya dalam dunia ini. Mereka sama-sama melakukan banyak kekerasan dan pelanggaran moral lainnya dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetap bermasalah dengan Allah dan dengan sesamanya, dan tetap tidak tangguh dalam menghadapi masalah berat! Kalaupun ada sejumlah orang Kristen yang dapat hidup dengan bermoral tinggi, tangguh, dan menjadi figur-figur teladan dalam masyarakat, hal yang sama pun dapat ditemukan dalam diri banyak orang yang beragama lain, yang tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan.
Para pengajar misiologi Kristen sering memakai contoh para martir Kristen di abad kedua dan ketiga di wilayah kekaisaran Romawi sebagai bukti bahwa kuasa pembaruan dan pembebasan yang diyakini memancar dari kematian Yesus di kayu salib telah dengan mujarab menjadikan mereka, para martir itu, orang-orang yang bermoral tangguh, yang memakai "kebebasan Kristiani" mereka untuk dengan tidak takut dan dengan konsisten melawan penguasa-penguasa lalim Romawi yang sedang memaksa mereka untuk meninggalkan kepercayaan Kristen mereka dengan ancaman hukuman mati jika mereka menolak. Tetapi persoalan dengan argumentasi ini adalah bahwa umat beragama lain pun memiliki sejumlah syuhadah mereka sendiri, yang dipandang sebagai figur-figur yang bermoralitas agung meskipun orang-orang yang menjadi teladan moralitas ini tidak percaya pada Yesus. Selain itu, jika kesyahidan dijadikan tolok ukur keluhuran dan ketangguhan moralitas, apakah kita juga harus menyimpulkan bahwa sekian juta orang Jerman yang mau mati syahid demi membela Hitler dan
Nazisme pada era Perang Dunia II adalah juga orang-orang yang bermoral luhur dan tangguh sementara kita tahu enam juta orang Yahudi telah dibunuh oleh rezim jahat ini? Begitu juga, apakah para ekstrimis religius dewasa ini yang melakukan tindak terorisme "bom bunuh diri" atas nama Allah dan agama mereka adalah orang-orang yang bermoral agung?
Kepada jemaat Kristen di Galatia, Rasul Paulus di pertengahan abad pertama menyatakan bahwa mereka adalah orang yang "sungguh-sungguh sudah merdeka" karena Yesus Kristus "telah memerdekakan" mereka dari semua "kuk perhambaan" (misalnya hukum Taurat) (Galatia 5:1). Dan ciri kemerdekaan kristiani ini, tulis sang Rasul, adalah kesanggupan setiap orang Kristen untuk hidup bermoral tinggi, hidup menghasilkan "buah Roh" (Galatia 5:22-23). Tetapi, di dalam jemaat yang sama ini, orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan ini, tulis Rasul Paulus, adalah juga orang-orang yang masih "hidup dalam dosa", masih "saling menggigit dan saling menelan" dan "saling membinasakan" (Galatia 5:13-15). Ya, inilah orang Kristen dalam pandangan sang Rasul: sudah dimerdekakan, tapi juga terus berbuat dosa.
Kalau orang Kristen berargumen dengan menunjuk pada kebudayaan Barat Kristen sebagai kebudayaan unggul yang dimungkinkan tercipta karena dibangun oleh orang-orang Kristen yang sudah menjadi ciptaan baru, mereka harus melihat juga banyak kebobrokan kebudayaan Barat yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Malah agama Kristen karena dogmatisme beku, skripturalisme dan ajaran etisnya yang ketinggalan zaman kerap menghambat perkembangan sains dan teknologi. Mantan Presiden George W. Bush, ketika masih memerintah, mengklaim diri sebagai the war President yang melihat tangan Allah bekerja dalam penyerbuan Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak. Apakah sang mantan Presiden ini manusia ciptaan baru bentukan Roh Yesus Kristus? Hemat saya, sama sekali bukan, meskipun dia diklaim sebagai a reborn Christian oleh banyak kalangan Kristen injili USA yang mendukungnya!
Orang Kristen boleh berkilah, bahwa kehidupan baru yang diterima orang Kristen adalah suatu proses, tidak sekaligus tercapai; lalu mereka akan mengutip teks suci yang bunyinya demikian, "Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui..." (Kolose 3:9-10). Tetapi, orang yang bukan-Kristen pun, yang tidak diselamatkan oleh Yesus Kristus, dapat mendisiplinkan kehidupan mereka setiap hari untuk tahap demi tahap, dengan mengerahkan potensi dan bakat yang ada dalam diri setiap manusia, melalui suatu proses pembelajaran yang panjang dan makan waktu, akhirnya menjadi suatu ciptaan baru, seorang manusia sempurna, manusia contoh, insan kamil. Dan, patut diketahui, banyak orang ateis berhasil menjalani kehidupan bermoral yang sangat tinggi peringkatnya. Peradaban umat manusia yang terus maju, ketika agama Kristen tidak lagi mengendalikannya, menunjukkan bahwa manusia dalam dirinya memiliki potensi dan bakat untuk terus maju, berevolusi ke tingkat kehidupan yang makin tinggi (tentang ini, klik di sini), tanpa perlu percaya pada pengurbanan Yesus.
Jadi, harus disimpulkan, soteriologi salib, yang diklaim orang Kristen sebagai satu-satunya soteriologi yang paling menjamin pembaruan dan keselamatan manusia karena menawarkan jalan keselamatan satu-satunya yang disediakan Allah untuk dunia, tidak mujarab untuk menyelamatkan manusia. Orang yang percaya dan menganut soteriologi salib untuk dirinya sendiri, dalam kenyataannya tidak otomatis menjadi manusia tangguh yang dibarui. Seharusnya, demi manfaat azab dan kematian Yesus di kayu salib, soteriologi ini bekerja secara magis, langsung mujarab dan manjur membarui dan
menyelamatkan manusia yang mempercayai dan menganutnya; tetapi, dalam kenyataannya, tidak demikian! Karena itu, kegagalan soteriologi salib untuk dengan mujarab membentuk moralitas luhur manusia menambah lagi satu alasan untuk menyatakan bahwa soteriologi ini tidak valid, atau bahwa soteriologi ini tidak powerful. Meskipun mereka percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa mereka dan membenarkan mereka di hadapan Allah, namun nyatanya orang Kristen tetap terus berbuat dosa! Simul iustus et peccator. Jadi, apa yang harus saya katakan selain bahwa iklan soteriologi salib terlalu jauh dari kenyataan! Soteriologi ini bukan saja tidak realistik (karena menjanjikan pembaruan moralitas manusia secara otomatis dan mujarab!), tetapi juga tidak ideal untuk manusia (karena soteriologi ini memerlukan perlakuan keras dan biadab terhadap manusia Yesus). Salib Yesus akhirnya menjadi sebuah salib yang bengkok. Dan soteriologi salib yang magis ini, tentunya, perlu diganti dengan jalan-jalan keselamatan alternatif (seperti sudah dibahas sebelumnya).
Jalan-jalan Keselamatan Alternatif
Ketika jalan besar buntu dan macet, jalan-jalan alternatif perlu ditempuh!
Narasi-narasi jalan salib (via dolorosa) Yesus menyakralisasi kejahatan dan kekerasan, bukan melawan atau meniadakannya. Ini adalah kenyataan tekstual Perjanjian Baru.
Kalau dilihat secara historis, sebelum Paulus menulis surat-suratnya dan sebelum injil-injil muncul, para murid perdana Yesus (orang Yahudi) menghadapi suatu fakta sejarah yang sangat pahit dan memalukan: Yesus telah disengsarakan dan dibunuh oleh suatu koalisi Yahudi-Romawi. Sang Mesias yang mereka harapkan akan mendatangkan suatu permulaan baru bagi bangsa Yahudi yang sedang dijajah ternyata dikalahkan dan berhasil dibunuh oleh lawan-lawannya. Ini adalah suatu peristiwa yang menggoncang keyakinan-keyakinan teologis mereka (bagaimana mungkin sang Mesias utusan Allah bisa dengan mudah dikalahkan dan Allah tidak menolongnya?) dan sangat memalukan mereka (bagaimana bisa sang Mesias mati dengan cara, dalam pandangan Yahudi, begitu memalukan dengan dibunuh melalui suatu cara penghukuman mati Romawi yang biadab: penyaliban?).
Untuk mengatasi kegoncangan dan rasa malu yang besar ini, mereka harus melakukan rasionalisasi-rasionalisasi atas berbagai hal buruk yang telah dialami Yesus. Dalam rangka merasionalisasi inilah, sakralisasi terhadap jalan salib dan kematian Yesus dilakukan: Ya, memang Yesus harus disengsarakan dan dizalimi dan dibunuh karena semua ini sudah dikehendaki (Yunani: dei) Allah untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka (dosa warisan maupun dosa masa kini) dengan jalan mengurbankan Yesus! Darah hewan dalam Yom Kippur yang diyakini efektif untuk menghapus dosa Israel dalam keyakinan Yahudi (PL) diganti dengan darah Yesus dalam keyakinan Kristen (PB)!
Jadi, jalan keselamatan melalui kesengsaraan dan kematian Yesus memang lahir dari suatu latarbelakang religius-kultural (Yahudi) yang memandang bahwa Allah Yahudi memerlukan darah tercurah untuk menenangkan hati-Nya yang panas dan bergolak karena dosa-dosa umat (manusia). Ketika darah hewan diganti dengan darah manusia, Yesus, bahasa kekerasan pun muncul, tanpa dapat dihindari lagi. Kekerasan yang seharusnya dihindari (ingat salah satu perintah dalam Dasa Titah: Jangan membunuh!), dalam peristiwa kematian Yesus justru disakralisasi sebagai suatu peristiwa ilahi yang suci untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang pemurka.
Dalam azab Yesus dan pembunuhan atas dirinya, kekerasan yang dilakukan manusia (para pemimpin agama Yahudi dan Gubernur Pontius Pilatus) diubah menjadi "sacred violence", kekerasan yang kudus, karena kekerasan aktual yang tidak suci, yang dialami Yesus, diubah menjadi suatu kekerasan yang dikehendaki dan dipakai Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia.
Nah, rasionalisasi dan sakralisasi terhadap via dolorosa yang semacam ini berhasil meredakan ketegangan dan tekanan mental berat yang dialami para murid perdana Yesus yang sudah ditinggalkan Yesus, sang Master mereka, yang sudah dibunuh dengan cara yang memalukan. Bagi kalangan Yahudi, ingat, orang yang disalibkan adalah orang yang dikutuk Allah, orang yang durhaka! Tetapi, celakanya, perspektif berteologi semacam ini yang diajukan para penulis Perjanjian Baru telah melegitimasi secara teologis dan menyakralisasi kekerasan yang telah menimpa Yesus, seorang yang tidak bersalah. Allah sendiri (bisa anda bayangkan, jika Dia memang maha pengasih dan maha penyayang) saya yakin tidak mau menerima perspektif berteologi para murid perdana Yesus semacam ini!
Nah, berbagai usaha untuk menyingkirkan dimensi kekerasan dari soteriologi Kristen tradisional akan sia-sia, karena soteriologi Kristen ini memang memakai bahasa kekerasan.
Nah, saya sudah perlihatkan di posting terdahulu (berjudul "Menggugat The Passion of the Christ di Hari Paskah 12 April 2009"; klik di sini), soteriologi Kristen tradisional yang memuja kekerasan dan pertumpahan darah semacam ini tidak valid, dan sudah berisi unsur-unsur demonik sejak pertama kali dirumuskan oleh kekristenan perdana.
Adakah alternatifnya? Jawabnya: Alternatifnya tersedia.
Soteriologi melalui kematian Yesus bersifat kristosentris, berpusat pada diri Yesus Kristus, khususnya pada azab, kesengsaraan dan kematian Yesus. Kristologi semacam ini jelas memuja dan menyakralisasi penderitaan Yesus. Ini disebut dolorisme, pemujaan pada azab dan sengsara Yesus (dolores = azab, kesengsaraan). Film Mel Gibson, The Passion of the Christ, jelas menjadikan dolorisme sebagai tulang punggung skenarionya. Dan dolorisme ini, terus terang saja, juga menjadi teologi kekristenan evangelikal/injili. Mereka, kalangan Kristen ini, berkontradiksi dalam diri dan teologi mereka: mereka menkhotbahkan cinta ilahi yang begitu besar bagi dunia ini (Yoh. 3:16), tetapi juga memuja-muja kekerasan yang dialami manusia Yesus. Karena itu tidak heran, mereka pun sering bisa tanpa ragu mempraktikkan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan kekristenan mereka, karena mereka memang dikondisikan oleh soteriologi mereka untuk memuja kekerasan. Seorang teman saya menyatakan bahwa film The Passion of the Christ tidak ada bedanya dengan film tentang pemberantasan G30S/PKI yang dibuat atas perintah rezim jahat Soeharto dalam era Orba. Kedua film ini penuh lumuran darah, dan di dalamnya kekerasan terhadap sesama manusia menjadi suatu cara hidup (way of life) dan pandangan dunia (world view) produser dan sutradara film-film ini.
Nah, alternatifnya adalah soteriologi yang teosentris: keselamatan manusia hanya berpusat dan bergantung pada Allah yang maha rakhmani dan rahimi, maka pengasih dan maha penyayang, yang tidak memerlukan mediator insani apapun untuk diri-Nya berhubungan dengan semua insan dalam dunia ini. Allah yang semacam ini didatangi langsung oleh manusia, tanpa melalui perantara insani manapun (Musa, Buddha Gautama, Khrisna, Yesus, Mohammad, Gulam Ahmad, ataupun Lia Eden,
dsb.).
Yesus dari Nazaret mengajarkan dan mendemonstrasikan Allah yang semacam ini. Sebagai seorang yang teosentris (= berpusat pada diri Allah, yang dipanggillnya Abba/Bapa), Yesus meminta para muridnya untuk berdoa langsung kepada Allah dengan memanggil-Nya "Bapa" (dalam Doa Bapa Kami, bagian yang berisi panggilan "Bapa" kepada Allah adalah bagian otentik dari ajaran Yesus sendiri).
Dalam salah satu perumpamaannya, yakni perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menggambarkan sang anak bungsu yang berdosa, ketika balik kembali dalam rasa sesal dan pertobatannya kepada ayahnya, sang ayah, dengan hatinya yang tergerak oleh kerahiman, segera berlari, langsung mendatangi dan merangkul anaknya yang semula sudah terhilang ini. Sang ayah tidak mengirim seorang utusan atau wakil atau perantara untuk bertemu dan menerima anak bungsunya ini; tetapi dia langsung menemuinya sendiri dan langsung memaafkan si anak tanpa perlu ada seseorang lain yang diutus dan dikurbankan. Nah, soteriologi otentik Yesus adalah soteriologi teosentris, bukan kristosentris. Gereja perdanalah yang mengubah soteriologi teosentris Yesus menjadi soteriologi kristosentris gereja!
Alternatif berikutnya adalah soteriologi logosentris (= berpusat pada logos, ucapan atau pengajaran, yang Yesus sampaikan, bukan pada dirinya sendiri yang, dalam dolorisme, digambarkan dikurbankan dengan kejam dan berdarah-darah). Dengan menghayati ucapan-ucapan Yesus, dengan masuk ke dalam dunia perumpamaan-perumpamaannya, orang akan mengalami pencerahan budi dan pembaruan etika kehidupan. Pencerahan budi dan pembaruan etika inilah pengalaman keselamatan.
Nah, soteriologi logosentris dihayati antara lain dalam komunitas Kristen yang melahirkan Injil Thomas (berisi 114 ucapan Yesus; lihat posting Injil Thomas dalam The Freethinker Blog saya). Injil Thomas aslinya ditulis dalam bahasa Yunani pada pertengahan abad kedua Masehi, yang memuat banyak ucapan tua dan asli Yesus dari Nazaret, bahkan lebih tua dan lebih asli dari yang terdapat dalam Injil-injil kanonik PB. Pada logion #1 Injil Thomas ini dimuat pernyataan, "Barangsiapa dapat menemukan maksud dari ucapan-ucapan [Yesus] ini, dia tidak akan mengalami kematian." Jelas, bagi komunitas Thomas ini, bukan azab dan sengsara serta kematian Yesus yang menyelamatkan, melainkan ucapan-ucapannya. Saved by Jesus' words, not by his death! Injil Thomas bahkan sama sekali tidak menyinggung azab, kesengsaraan dan kematian Yesus! Soteriologi logosentris juga dihayati oleh komunitas "Q" (existed tahun 50-an abad pertama Masehi di Galilea) yang dokumen sucinya terdapat dalam Injil Lukas dan Injil Matius, dan sudah dipadukan dengan bahan-bahan sumber lain membentuk Injil Lukas dan Injil Matius.
Alternatif lainnya yang juga alkitabiah adalah soteriologi yang egosentris atau humanosentris (atau antroposentris), yang menegaskan bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri (ego) atau sang manusianya sendiri (human/anthropos) melalui kehidupannya sendiri, melalui perbuatan-perbuatannya sendiri (tentang ini, klik di sini), bukan bergantung pada suatu figur perantara atau penebus manapun. Dengan mendisiplinkan diri untuk menempuh suatu kehidupan yang penuh kebajikan bagi semua orang, seseorang akan terus bertumbuh, semakin ekspansif, dari waktu ke waktu, menuju pada suatu kemanusiaan yang diperluas, yang bisa dan sanggup merangkul semua jenis kehidupan lainnya, suatu kemanusiaan yang sama dengan keilahian. Dalam bahasa PB,
suatu kehidupan "dengan kepenuhan Kristus." Kehidupan yang ekspansif semacam ini adalah kehidupan dalam keselamatan, kehidupan ilahi sendiri. Yang ilahi dialami di dalam yang insani, kini dan di dunia ini. Dan setiap manusia memiliki potensi dan bakat untuk menjadi ilahi dalam kehidupannya di dunia ini. Soteriologi semacam ini dihayati banyak truth seekers independen dan juga kalangan mistikus. Kekristenan perdana juga memiliki sekian jenis kekristenan semacam ini, misalnya beberapa kalangan Kristen gnostik.
Nah, sekian soteriologi alternatif di atas juga dihayati banyak orang Kristen dewasa ini, di zaman modern, di zaman ketika kekerasan semakin disadari untuk dijauhi demi keselamatan global, di zaman ketika bahasa "darah Yesus" dalam soteriologi Kristen tradisional dipandang obsolete, usang, superstitious, takhayul, dan tidak bermakna, meaningless, serta tidak etis, unethical.
Bagaimana semua ini bisa terjadi? Karena kitalah, manusia, tuhan atas dogma gereja, dan bukan sebaliknya! Kuasai dan kendalikan dogma, dan jangan dikuasai dan dikendalikan olehnya. Ikutilah ke mana nalar membawamu. Hanya dengan cara inilah kamu tidak mengkhianati kemanusiaanmu. Take this as your destiny!
Menggugat The Passion of the Christ di Hari Paskah 12 April 2009
Semalam, 11 April 2009, mulai pukul 21.30 sampai pukul 24.00, TV RCTI menayangkan sebuah film religius lama Mel Gibson (produksi tahun 2003), The Passion of the Christ, persis pada malam sebelum hari Paskah keesokan harinya (12 April 2009). Waktu penayangan ini bukan kebetulan, dan hanya bisa terjadi kalau waktu tayang ini sudah dibeli sebelumnya oleh kalangan Kristen tertentu. Waktu tayang yang sudah dibeli memungkinkan tidak adanya selingan-selingan iklan selama pemutaran film ini. Kalau saya tak salah ingat, tahun lalu film Mel Gibson yang sama juga ditayangkan oleh sebuah stasiun TV, dengan tanpa selingan iklan sama sekali. Rupanya akan menjadi suatu kebiasaan untuk menayangkan The Passion of the Christ setiap tahun lewat sebuah stasiun TV, untuk merayakan hari Jumat Agung (hari peringatan kematian Yesus di kayu salib) dan untuk menyambut hari Paskah (hari kebangkitan Yesus).
Apa tujuan penayangan film ini pada malam sebelum hari Paskah? Bisa diduga, film ini ditayangkan pertama-tama untuk kepentingan internal umat Kristen, supaya mereka makin bisa menghayati makna pengurbanan Yesus Kristus di kayu salib sehingga iman mereka makin dimantapkan. Inti iman Kristen berisi ajaran ini: Atas kehendak dan perintah Allah, Yesus didera, disiksa dan dibunuh di kayu salib dengan sangat biadab untuk menanggung penghukuman yang seharusnya ditimpakan pada manusia karena dosa-dosa mereka. Bagi keyakinan Kristen, ini adalah tindakan dan jalan normatif satu-satunya yang Allah sendiri adakan, sekali untuk selamanya dan untuk semua orang, dan karena itu harus hanya diterima dan dipercaya manusia jika manusia ingin mengalami pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah.
Selain untuk kepentingan devosional internal ini, film ini ditayangkan orang Kristen juga sebagai bagian dari kegiatan kristenisasi, kegiatan pekabaran injil Kristen kepada dunia non-Kristen: supaya orang non-Kristen yang menyaksikan film ini, dan melihat bagaimana Yesus disengsarakan, dizalimi dan dibunuh oleh para penguasa dunia ini, tergerak hati untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka sehingga mereka mengalami pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Tuhan lewat jalan Yesus Kristus.
Namun faktanya apa? Setahu saya, orang-orang non-Kristen, antara lain teman-teman saya yang beragama Islam, jauh dari tergerak hati ketika menyaksikan film Mel Gibson yang sarat dengan adegan kekerasan dan kebiadaban ini, mereka malah merasa muak dan jijik dengan film ini dan tidak bisa mengerti mengapa orang Kristen bisa sangat menyukai bahkan memuja film ini, dan juga tidak bisa mengerti dan tidak dapat menerima pesan teologis Kristen bahwa Allah memakai suatu jalan kekerasan yang harus dijalani Yesus Kristus hanya supaya hubungan manusia dengan diri Allah ini dipulihkan.
Hemat saya, soteriologi salib atau jalan keselamatan melalui azab, kesengsaraan dan kematian Yesus di kayu salib memang memuat permasalahan-permasalahan teologis berat yang sangat sulit diatasi, atau bahkan tidak dapat diatasi sehingga merongrong validitas inti iman Kristen.
Pertama, kalau dosa manusia itu (dosa warisan ataupun dosa pribadi) dipandang Allah sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya dan terhadap diri Allah sendiri, maka apakah tindak kekerasan yang Allah sendiri telah lakukan terhadap Yesus (dengan mengharuskannya menempuh jalan penderitaan dan kematian mengenaskan di kayu salib) akan bisa menghapus kekerasan dosa-dosa manusia? Apakah suatu tindak kekerasan bisa meniadakan suatu tindak kekerasan lainnya? Apakah tindak kekerasan Allah terhadap Yesus bisa mengeliminasi tindak kekerasan yang manusia lakukan terhadap sesamanya dan terhadap Allah? Bukankah pendapat kita adalah bahwa kekerasan akan menimbulkan kekerasan baru, bukan menghapuskannya? Bukankah dosa manusia tidak bisa dihapuskan oleh kekerasan ilahi? Bukankah dosa Allah tidak bisa menghapus dosa manusia? Bukankah dosa hanya menumpuk dosa, bukan melenyapkannya?
Kedua, bukankah teologi tentang penebusan dosa melalui penderitaan dan kematian biadab Yesus di kayu salib telah melegitimasi dan malah telah melakukan sakralisasi terhadap perbuatan biadab para pemimpin Yahudi dan gubernur Romawi Pontius Pilatus terhadap Yesus dari Nazaret yang sebetulnya tidak bersalah? Dengan kata lain, bukankah ketika gereja sedunia merayakan Jumat Agung, mereka sebenarnya sedang melegitimasi dan menyakralisasi kekejaman dan kekerasan serta kebiadaban sekelompok penguasa keagamaan dan politis kepada Yesus dari Nazaret? Bukankah tidak ada kekerasan yang sakral sehingga kekerasan ini boleh dilakukan?
Demikian juga, bukankah ketika gereja merayakan Paskah, tanpa mereka sadari mereka sebenarnya juga memberi legitimasi teologis terhadap serangkaian tindak kekerasan yang ditimpakan pada Yesus sejak dia diadili, lalu diseret ke Golgota dan akhirnya disalibkan di situ? Bukankah Paskah berarti pembenaran terhadap serentetan tindakan biadab terhadap Yesus yang berakhir di hari Jumat Agung, hari kematian Yesus di kayu salib? Legitimasi teologisnya berbunyi demikian: Ya, benar, Yesus memang harus disengsarakan, dizalimi, lalu dibunuh dengan kejam, supaya semua tindakan kejam ini bisa memuncak pada tindakan Allah membangkitkan Yesus di hari Paskah. Jika demikian, bukankah Paskah itu bukan suatu warta gembira, bukan suatu warta kemenangan, melainkan suatu legitimasi teologis yang kejam dan tidak berhati atas serangkaian tindak kekerasan yang sebelumnya dialami Yesus? Bukankah tanpa jalan kesengsaraan (via dolorosa) Yesus, tidak akan ada kebangkitannya? Dengan demikian, bukankah kebangkitan Yesus membenarkan jalan kesengsaraannya? Ya, supaya Yesus dibangkitkan, supaya ada kemenangan atas maut, Yesus harus dizalimi dan disengsarakan! Bukankah, dengan demikian, merayakan Paskah berarti membenarkan
Pontius Pilatus dan para penguasa Yahudi dalam berlaku keras dan biadab terhadap Yesus?
Teologi Paskah, dengan demikian, mengunci kekristenan dalam suatu dilema dan kontradiksi pelik: pada satu pihak, Paskah dapat berarti Allah, dengan membangkitkan Yesus, menolak semua kekerasan yang telah dialami Yesus sebelumnya; namun di lain pihak, Allah memerlukan jalan kekerasan dijalani Yesus supaya Yesus menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia, dan dengan membangkitkan Yesus, Allah membenarkan semua perlakuan keras yang telah dialami Yesus ketika dia diharuskan Allah menempuh via dolorosa.
Ketiga, kisah-kisah injil Kristen tentang masa-masa kesengsaraan Yesus, yang dijalaninya sejak dia diadili, lalu dibawa ke Kalvari, dan kemudian disalibkan di sana, secara bertahap menggeser kesalahan yang sebetulnya ada pada pihak Roma (gubernur Pontius Pilatus) ke pihak Yahudi yang direpresentasikan para penguasa Bait Allah. Penggeseran tanggungjawab ini akhirnya menjadikan orang Yahudi sebagai pihak yang satu-satunya bersalah terhadap Yesus, sebagai pihak yang telah melakukan pembunuhan terhadap Tuhan (deicide). Inilah motif anti-Yahudi yang terdapat paling kuat dalam kisah-kisah pengadilan Yesus dalam injil-injil Kristen. Motif ini kemudian, di zaman modern, melahirkan anti-semitisme yang menimbulkan antara lain pembunuhan jutaan orang Yahudi (Holokaus) oleh rezim Hitler di Eropa pada abad XX.
Anti-semitisme ini sering tanpa disadari dibela gereja Kristen ketika mereka, misalnya, mempersalahkan orang Yahudi sebagai pembunuh Tuhan, dan karena itu mereka (orang Yahudi), dalam pandangan gereja, telah kehilangan anugerah ilahi yang semula diberikan kepada mereka. Dengan merayakan masa-masa kesengsaraan Yesus (dalam minggu-minggu Pra-Paskah) dalam ibadah gereja, gereja Kristen sebenarnya terus-menerus memelihara dan mewariskan ideologi anti-Semitisme, tanpa mau tahu atau tanpa menyadari bahwa anti-Semitisme ini telah menghilangkan begitu banyak nyawa orang Yahudi dalam zaman modern ini.
Begitulah, di dalam inti terpenting dogma Kristen tentang jalan keselamatan manusia lewat Yesus Kristus yang disalibkan terkandung unsur-unsur demonik yang harus diwaspadai. Karena itu, sudah sepatutnya film Mel Gibson The Passion of The Christ tidak usah lagi ditayangkan untuk umum via TV di tahun-tahun yang akan datang.
Aku Guyur Api Neraka, Aku Bakar Surga!
Soteriologi dalam semua agama menawarkan selain keselamatan di dunia ini juga dan terutama keselamatan di akhirat: barangsiapa memercayai suatu dogma atau suatu figur insani yang suci sebagai juruselamat, orang itu akan masuk surga dan terluput dari neraka. Begitu juga, dengan memegang soteriologi salib, gereja menjanjikan: Barangsiapa percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, orang itu akan pasti masuk surga dan terhindar dari neraka. Nah, dalam bab ini, saya mau mengargumentasikan bahwa surga dan neraka itu tidak ada, sehingga soteriologi salib atau soteriologi apapun sebetulnya menjanjikan sesuatu yang kosong bagi akhir kehidupan manusia.
Masalahnya, ajaran tentang adanya surga dan neraka sudah begitu dalam tertanam dalam kesadaran setiap orang beragama. Orang beragama apapun senantiasa diajarkan, sejak kecil, untuk percaya pada adanya surga dan neraka. Mereka sejak kanak-kanak sudah diiming-imingi surga dan
ditakut-takuti neraka. Jadi, sangat susah atau bahkan mustahil untuk melepaskan orang beragama dari kepercayaan mereka pada adanya surga dan neraka.
Kata orangtua atau guru agama kita, kalau kita berbuat banyak kebajikan, lebih banyak dari kejahatan kita, dalam dunia sekarang ini, maka nanti dalam kehidupan di akhirat kita akan masuk surga, hidup dalam kebahagiaan abadi. Tetapi, mereka juga wanti-wanti mengingatkan, kalau kita berbuat kejahatan lebih banyak dalam dunia ini ketimbang kebajikan, kita nantinya akan masuk neraka, hidup dalam penderitaan abadi, dibakar api dan belerang sangat panas yang tak pernah padam.
Orang Kristen, seperti baru dikatakan, sejak di sekolah minggu juga diindoktrinasi dengan ajaran bahwa hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus akan masuk surga sesudah kematian, dan orang yang tidak percaya pada Yesus nantinya akan masuk neraka. Bagi mereka, Yesus adalah tiket eksklusif satu-satunya untuk orang masuk surga.
Orang beragama yang memegang orientasi waktu siklikal pun percaya pada hal yang sama: setelah perbuatan bajik mencukupi, mereka akan terlepas dari siklus kematian dan kelahiran kembali dan masuk ke dalam nirvana, keadaan bahagia yang kekal abadi, dan hidup sebagai dewa-dewi. Jika dharma dan kebajikan belum mencukupi, mereka terlempar kembali, masuk ke dalam siklus kematian dan kelahiran kembali ke dalam dunia yang maya dan fana.
Kalangan Muslim ekstrimis bahkan percaya bahwa jika mereka mati di jalan Allah, mati sebagai syahid ketika berjihad dengan melakukan terorisme, mereka, setelah kematian, akan langsung dihadiahi kehidupan surgawi yang sangat menyenangkan, dengan dilayani puluhan bidadari yang cantik tak terbayangkan.
Tetapi, saya bertanya kepada mereka semua yang percaya pada adanya surga dan neraka: Bukankah untuk bisa merasakan sesuatu yang sangat menyenangkan (= surga) perlu ada tubuh, anggota tubuh, organ, indra, syaraf dan sel-sel otak? Bukankah untuk bisa merasakan sesuatu yang sangat menyiksa (= neraka) juga diperlukan tubuh, anggota tubuh, organ, indra, syaraf dan sel-sel otak? Tanpa tubuh, anggota tubuh, organ, indra, syaraf dan otak, tidak akan ada perasaan dan pengalaman positif atau negatif apapun.
Jika kehidupan sesudah kematian adalah suatu kehidupan tanpa tubuh, tanpa raga, tanpa organ, tanpa indra, tanpa syaraf, tanpa otak, maka kehidupan rohani yang transparan dan tanpa bentuk, yang bak angin atau asap belaka ini, adalah kehidupan yang tidak bisa merasakan apapun dan tidak bisa masuk ke dalam pengalaman apapun. Perasaan dan pengalaman, jika kedua hal ini ingin nyata dirasakan dan dialami, memerlukan media jasmaniah: tubuh, anggota tubuh, organ tubuh, indra, syaraf dan otak. Dengan demikian, kehidupan rohani setelah kematian, jika kehidupan semacam ini ada, adalah kehidupan tanpa rasa dan tanpa pengalaman apapun. Kehidupan yang tanpa rasa dan tanpa pengalaman apapun tidak akan bisa merasakan dan mengalami surga, juga tidak akan bisa merasakan dan mengalami neraka. Dengan kata lain, kehidupan rohaniah sesudah kematian ragawi tidak memungkinkan orang yang sudah mati mengalami baik surga maupun neraka. Surga atau neraka tidak bisa dirasakan dan dialami oleh orang yang sudah mati. Surga dan neraka hanya ada dalam ajaran agama, tetapi tidak bisa sungguh-sungguh dialami dan dirasakan orang yang sudah
mati tetapi hidup lagi dengan tidak memakai raga apapun lagi.
Begitu juga, dalam suatu kehidupan rohaniah sesudah kematian, api yang terus bernyala dalam neraka pastilah bukan api sungguhan seperti api dalam oven pembakar dan pelumer baja yang kita kenal dalam dunia ini. Api rohaniah, api yang bukan api riil sungguhan, jika ada, tidak bisa menimbulkan rasa sakit, rasa panas, dan rasa tersiksa apapun. Neraka rohaniah, dengan demikian, tidak akan menyiksa apapun, dan neraka yang tidak bisa menyiksa adalah neraka yang tidak pernah ada. Neraka panas di alam baka hanya ada dalam khayalan orang yang masih hidup di bumi dengan memakai pengalaman di bumi. Jelas, neraka adalah suatu pelipatgandaan pengalaman buruk dan penderitaan manusia di bumi yang diproyeksikan ke alam keabadian.
Demikian juga, surga sesudah kematian, surga dalam kehidupan rohaniah sepenuhnya di alam baka, pastilah juga bukan rasa nikmat tertinggi jasmaniah sungguhan seperti orang rasakan dengan indra, syaraf dan otak ketika, misalnya, mencapai orgasme atau ejakulasi dalam suatu hubungan seksual badaniah yang dialami dalam dunia material sekarang ini. Surga rohaniah, dengan demikian, jika ada, adalah surga yang tidak bisa menimbulkan rasa nikmat apapun; dan rasa nikmat yang tidak bisa dirasakan secara jasmaniah, melalui organ, indra, syaraf dan otak, adalah rasa nikmat yang tidak pernah ada. Dengan begitu, surga rohaniah juga tidak pernah ada. Surga di alam baka hanya ada dalam khayalan manusia yang masih hidup di bumi dengan memakai pengalaman di bumi. Jelas jadinya, surga di alam baka adalah suatu pelipatgandaaan pengalaman bahagia yang dialami di muka bumi yang diproyeksikan ke alam keabadian.
Surga rohaniah dan neraka rohaniah dengan demikian tidak pernah akan menjadi tempat kenikmatan abadi dan tempat siksaan abadi. Dengan kata lain, keduanya tidak ada. Orang beragama yang memandang surga dan neraka di alam baka sebagai kenyataan-kenyataan material dan jasmaniah adalah orang yang gagal mengakui dan melihat adanya diskontinuitas antara alam fana jasmaniah dan alam baka rohaniah, antara tubuh manusia yang hidup dan mayat orang yang sudah mati yang harus dikuburkan atau dibakar dan yang, sesudah beberapa waktu lamanya, akhirnya lenyap menyatu dengan bumi. Tidak ada raga yang dilanjutkan keberadaannya sebagai raga di alam baka.
Kalaupun jiwa dipahami sebagai “energi” yang kekal, dan sebagai energi akan terus ada kendatipun orangnya sudah mati, energi ini, jika tidak terintegrasi dalam suatu media jasmaniah material, yakni tubuh, tidak akan menjadi suatu makhluk hidup yang dapat mencerap dan merasakan hal apapun. Orang beragama percaya, orang mati yang masuk ke dalam surga atau dibuang ke neraka akan terus hidup sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran personal dan jati diri. Nah, kalau jiwa hidup lagi setelah kematian ragawi sebagai suatu energi kekal, energi selamanya adalah sesuatu yang a-personal atau non-personal, sesuatu yang tidak memiliki kesadaran personal dan jati diri. Jadi, dari sudut perspektif fisika molekuler material, keberadaan surga dan neraka tidak bisa dihipotesiskan, kendatipun jiwa dapat dipandang berubah menjadi atau bertahan sebagai energi.
Tetapi, orang beragama bisa membantah dengan menyatakan bahwa kehidupan sesudah kematian adalah juga kehidupan ragawi, sehingga bisa tetap merasakan dan mengalami sesuatu seperti ketika orang masih hidup di dunia. Orang Kristen adalah kalangan yang bisa diantisipasi akan berargumen semacam ini, dengan mereka menunjuk pada tubuh kebangkitan Yesus yang diklaim bersifat ragawi.
Tetapi kontra-argumennya juga ada: Jika Yesus yang bangkit dari kematian adalah Yesus yang sungguh-sungguh masih memiliki raga sungguhan, maka dia, sesudah kebangkitannya, akan harus tunduk pada keterbatasan-keterbatasan ragawi, bahwa dia akan, misalnya, lapar, sakit dan terkurung, terikat pada tempat, tidak bebas, termasuk juga bahwa dia akan tetap menjadi semakin tua, lisut lalu mati lagi. Raga yang hidup abadi dan tidak pernah akan binasa hanya ada dalam mitos, dalam dongeng, dalam fiksi, tidak ada dalam kenyataan, di dunia ini maupun di akhirat. Jika setelah kematian dan kebangkitannya Yesus masuk surga, di surga, karena dia masih memiliki raga, umurnya akan tetap bertambah lalu dia pasti menua dan akan mati lagi. Surga macam apakah yang di dalamnya orang mati yang dibangkitkan bisa mati lagi?
Jika demikian halnya, kehidupan Yesus sesudah kebangkitannya tidaklah berbeda dari kehidupannya sebelum kematian dan kebangkitannya. Dengan kata lain, Yesus yang semacam ini adalah Yesus yang belum pernah terbebas dari kehidupan ragawi, dan tidak pernah mengalami kehidupan lain sesudah kematiannya. Sungguh malang Yesus jika keadaannya semacam ini! Doktrin tentang kebangkitan ragawi Yesus yang tujuan semulanya mau mengunggulkan dia di atas semua orang suci lainnya akhirnya malah memenjarakannya dalam serba kedagingannya dan menjadikannya makhluk paling malang di dunia ini dan di akhirat!
Di samping itu, kehidupan setelah kematian yang masih terkurung oleh raga dan semua sifat fananya, bukanlah kehidupan setelah kematian, melainkan masih sebatas kehidupan ragawi dalam dunia ini, kehidupan yang masih belum terbebaskan. Kehidupan setelah kematian yang semacam ini tidaklah pernah ada di akhirat.
Nah, dengan penasaran Anda mungkin akan bertanya: Kalau surga dan neraka tidak bisa dirasakan dan dialami oleh orang yang sudah mati, atau kalau surga dan neraka tidak pernah ada di alam baka, lalu apa yang akan dialami orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati, jika masih harus hidup lagi di alam baka, tidak akan mengalami hal apapun: mereka berada dalam kekosongan; tanpa surga dan tanpa neraka, tanpa upah dan tanpa ganjaran, tanpa rupa dan tanpa bentuk, tanpa pekerjaan dan tanpa rehat.
Jika demikian, apakah masih perlu mengajarkan orang beragama tentang surga dan neraka?
Dalam tradisi Yahudi-Kristen, ajaran tentang surga dan neraka lahir dari dalam suatu pandangan dunia apokaliptik yang menuntut semua musuh umat dan musuh Allah dalam dunia fana ini, yang telah menyengsarakan umat Allah, dibalas dan dihukum habis-habisan dalam api neraka setelah kematian mereka; sedang umat yang disengsarakan, sebagai pahala untuk ketaatan dan kesetiaan mereka pada Allah dan agama Allah, dihadiahi surga selamanya. Jadi, dapat dikatakan, ajaran tentang ancaman api neraka sesudah kematian sebenarnya menunjukkan kebencian umat pada musuh-musuh Allah, kebencian yang terus dirawat, dipertahankan, dihidupkan dan dipelihara sampai pada kematian dan sesudahnya. Ajaran tentang api neraka, dengan demikian, mengajarkan kebencian kekal pada musuh-musuh umat. Jelas, ajaran yang terus menebar kebencian sudah seharusnya ditolak.
Rabiah Al-Adawiyah menyatakan akan mengguyur api neraka dengan air sampai padam, dan
membakar surga dengan suluh sampai lenyap terbakar, supaya orang mau beragama bukan karena iming-iming surga atau karena ketakutan akan api neraka, melainkan karena cinta saja. Ya, ajaran yang menebar kebencian sudah seharusnya diganti dengan ajaran tentang cinta, cinta kepada sesama bahkan cinta kepada musuh! Yesus Kristus sangat menekankan keharusan para pengikutnya untuk mengasihi musuh mereka sekalipun! Para Boddhisatva yang seharusnya sudah lepas dari siklus kematian dan kelahiran kembali, lalu masuk ke dalam nirvana, bersumpah tidak akan mau masuk ke dalam nirvana sampai seluruh rumput di padang mendapat penerangan budi melalui dharma yang mereka terus-menerus sebarkan! Artinya, mereka memilih untuk selamanya berada dalam dunia ini untuk menebar cinta. Mereka melakukan pengurbanan diri yang begitu besar karena cinta mereka kepada semua makhluk dalam dunia ini.
Cinta juga akan membuat kita merasa lebih bertanggungjawab untuk memadamkan api neraka kemiskinan dan penderitaan riil dalam dunia ini sekarang ini ketimbang membiarkan diri dilanda ketakutan pada neraka yang tidak pernah ada dalam dunia baka! Cinta juga akan mendorong kita untuk terus-menerus memperjuangkan tegaknya surga dalam dunia ini sekarang ini di antara orang yang miskin dan sengsara, ketimbang membiarkan diri terpincut oleh iming-iming surga yang tidak pernah ada dalam dunia baka!
Betulkah Yesus dengan Sengaja Mau Mati demi Dunia?
Apakah Yesus dari Nazaret menginginkan dirinya sendiri menjadi juruselamat dunia dengan mati secara mengenaskan di kayu salib, sebagai suatu kematian pengganti demi keselamatan umat manusia sedunia di segala zaman dan tempat? Ini adalah sebuah pertanyaan berat dan sangat sensitif bagi perasaan banyak orang Kristen; meskipun demikian, akan diupayakan jawabannya dalam tulisan ini, tulisan keenam dari rangkaian tulisan mengenai masalah-masalah dalam soteriologi salib yang digali dalam blog ini.
Teks skriptural Perjanjian Lama yang pasti dirujuk orang Kristen untuk mendukung soteriologi salib adalah teks tentang hamba Tuhan yang menderita, antara lain (Deutero) Yesaya 52:13-53:12. Film Mel Gibson, The Passion of The Christ (tentang gugatan saya terhadap film ini, klik di sini), untuk mendukung dolorisme, dibuka dengan sebuah kutipan teks Yesaya 53:5b, "Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kalimat-kalimat sebelumnya dalam teks Yesaya ini berbunyi demikian, "Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita" (Yesaya 53:4-5a). Sosok yang kena tulah dan menanggung azab demi kepentingan orang lain (vicarious sufferings) ini disebut sebagai "hamba" Tuhan, ebed Yahweh (Yesaya 52:13; 53:11b).
Dalam konteks historisnya, figur hamba Tuhan dalam Deutero Yesaya ini tentu saja tidak mengacu pada suatu figur mesianik di masa depan yang jauh, yang belum lahir, yang akan, melalui azab dan kematiannya, menyelamatkan dan menebus umat manusia di segala zaman dan tempat, tetapi pada suatu figur historis tertentu pada zaman ketika Deutero Yesaya ditulis (pada masa Pembuangan di Babel, abad VI SM), entah seorang imam, seorang nabi, atau seorang raja, Yahudi atau non-Yahudi, yang azabnya akan mendatangkan kebaikan, kesembuhan dan kesejahteraan untuk bangsa Israel sendiri, bukan untuk dunia secara universal dalam segala zaman. Tetapi jauh kemudian, pada
permulaan abad kedua Masehi, oleh umat Kristen Perjanjian Baru, teks Deutero Yesaya ini dikenakan kepada Yesus, seperti kita baca dalam 1 Petrus 2:22-25; perhatikan khususnya ayat 24 yang memuat kutipan langsung dari teks Deutero Yesaya: "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh."
Selain dalam teks PL ini, dokumen Yahudi ekstrakanonik yang ditulis dengan mengambil Pemberontakan Makkabe (167-142 SM) sebagai latar historisnya, yakni 2 Makkabe (ditulis sekitar tahun 125 atau 124 SM) dan 4 Makkabe (bergantung pada 2 Makkabe; ditulis sekitar tahun 50 M), juga memuat gagasan soteriologis Yahudi serupa: kematian seorang Yahudi yang saleh dan benar sebagai syuhadah dalam perlawanan habis-habisan terhadap raja lalim (raja Siria, Antiokhus IV Epifanes), mendatangkan pendamaian dan penebusan untuk bangsa Israel dan menyucikan tanah mereka (2 Makkabe 6:18-17:41; 4 Makkabe 1:11; 5:1-6:27-28; 17:21; 18:4 ), dan yang bersangkutan akan dibangkitkan dan menerima kehidupan kekal (2 Makkabe 7:9; bdk. ayat 11, 14, 23, 29, 36; 4 Makkabe 16:25; bdk. 7:18-19; 13:17). Dalam 4 Makkabe 5:1-6:28 terdapat kisah tentang Eleazar, seorang tua dari keluarga imam. Dikisahkan dengan imajinatif, menjelang ajal sebagai seorang martir di perapian yang panas bernyala-nyala Eleazar berkata, "Ya, Tuhan, Engkau mengetahui bahwa aku dapat luput. Tetapi kini aku sekarat di dalam perapian ini demi Taurat. Berilah rakhmat-Mu pada umat-Mu; semoga kekejaman yang aku alami ini melunasi semua yang harus mereka tanggung. Biarlah darahku menyucikan mereka, ambillah nyawaku sebagai suatu pengganti bagi mereka" (6:27-28).
Kita dapat bertanya, apakah Yesus dari Nazaret, karena suatu ilham, mengambil teks-teks Yahudi ini lalu menerapkannya kepada dirinya sendiri, dan dengan demikian dia memandang dirinya entah sebagai hamba Tuhan yang menderita, sebagai sang mesias yang harus (Yunani: dei) mati tanpa perlawanan, atau pun sebagai seorang syuhadah yang mati dalam perlawanan keras terhadap penguasa lalim demi menyucikan Tanah Israel dan memerdekakan serta menebus bangsanya? Ataukah, gereja perdana (Yahudi dan non-Yahudi), tersirat ataupun tersurat, mengenakan teks-teks Deutero Yesaya (seperti dalam 1 Petrus 2:22-25), 2 dan 4 Makkabe dan teks-teks profetis lainnya kepada Yesus setelah kematiannya di kayu salib untuk menjadi landasan skriptural bagi soteriologi salib yang mereka konstruksi demi mengatasi tekanan jiwa yang begitu besar, yang mereka alami karena sang mesias mereka mati disalibkan di tangan bangsa Romawi, mati sebagai seorang yang (dari kaca mata Yahudi) terkutuk, terkena tulah, tanpa perlawanan apapun dari pihaknya? Pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimanapun juga, mengandung masalah-masalah berat yang harus diatasi.
Masalahnya, pertama, pada era kegiatan Yesus di muka umum, era pra-Kristen, era sebelum dokumen-dokumen tertua Perjanjian Baru yang memuat soteriologi penebusan lewat salib Yesus ditulis, dalam tradisi Yahudi pasca-biblis teks-teks skriptural Deutero Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita tidak ditafsir secara mesianik, maksudnya: tidak diterapkan pada suatu figur mesias manapun.
Dalam kepercayaan dan pemikiran religio-politis mesianik Yahudi zaman Yesus, tidak terbuka kemungkinan untuk memandang seorang mesias Yahudi manapun akan menderita, mengalami azab, apalagi menderita dan tewas dengan memalukan, tanpa perlawanan fisik dan militer ketika
berhadapan dengan musuh bangsa, negara dan agama. Dalam pandangan Yahudi, sebutan "mesias yang menderita" atau sebutan "mesias yang menempuh jalan sengsara" adalah suatu contradictio in terminis: penderitaan atau jalan sengsara tidak bisa disandingkan dengan gelar agung mesias. Bagi orang Yahudi yang terus-menerus hidup dalam penjajahan bangsa asing silih berganti, jika betul seseorang itu seorang mesias yang diutus Allah, orang itu, sang mesias Yahudi ini, keturunan Raja Daud ini, memikul tugas besar dan agung untuk memerdekakan bangsa Yahudi dari para penindas mereka dengan mengangkat senjata, berperang melawan penjajah-penjajah mereka, dan menyucikan kota Yerusalem dan seluruh Tanah Israel (lihat teks ekstrakanonik Mazmur-mazmur Salomo 17:22). Sang mesias sejati Yahudi didukung rakyat sepenuhnya, duduk di takhta kerajaan Yahudi dengan segala kemuliaannya, dan, melalui gerakan militer, mengalahkan setiap musuh bangsa yang merenggut kemerdekaan mereka. Inilah "teologi kemuliaan" (theologia gloria) dan "teologi perang" (theologia bellum) yang menjadi teologi mesianik zaman Yesus, yang juga dipertahankan para murid perdana Yesus (lihat Markus 10:37; 14:31, 47).
Jadi, kalau Yesus dari Nazaret mengambil teks tentang hamba Tuhan yang menderita dalam Kitab Deutero Yesaya dan menjadikan teks ini sebagai landasan skriptural untuk, karena suatu dorongan dan ilham, membenarkan tindakannya menempuh via dolorosa dengan rela, penuh rasa sakit namun tanpa perlawanan sampai dia mati mengenaskan di kayu salib, jelas Yesus, dengan menghayati "teologi salib" (theologia crucis) ini, bergerak di luar bingkai mesianisme Yahudi yang lazim pada masanya, dan tentu saja dia, karenanya, tidak akan dimengerti dan diterima rakyat Yahudi meskipun dia bisa jadi, langsung atau tak langsung, mengklaim dirinya raja Yahudi. Bahkan seorang murid utama yang dekat dengan Yesus, yakni Petrus, kita tahu, tidak bisa mengerti pandangan, kemauan dan langkah Yesus yang eksentrik, di luar kelaziman, ini: menjadi mesias rajani yang menderita (lihat Markus 8:31-32). Jadi, kalau diukur dari teologi kemuliaan dan teologi perang yang lazim dalam mesianisme Yahudi pada zamannya, jelas tidak akan ada seorang yang seperti Yesus, yang, dengan teologi salibnya, melangkah ke luar jauh dari dunia simbolik Yahudi zamannya!
Tetapi, bukankah Yesus, kita bertanya, bisa saja memang dengan sengaja mau berbeda dari pandangan mesianik umum Yahudi zamannya? Tentu, bisa saja pandangan mesianik Yesus begitu berbeda dari mesianisme Yahudi zamannya. Kalau memang benar demikian, ini memenuhi kriterion "dissimilarity" atau "distinctiveness" yang dipakai para peneliti Yesus sejarah. Menurut kriterion ini, sesuatu itu asli atau orisinil dari Yesus kalau sesuatu yang dikatakan dari Yesus ini (ucapannya atau tindakannya) begitu khas, distinctive atau dissimilar, sehingga berkontras atau berbeda tajam dengan kelaziman dalam dunia Yahudi pada umumnya di zamannya. Jadi, OK-lah, kita bisa saja percaya bahwa Yesus sendiri memang menghayati teologi salib, bukan teologi kemuliaan atau teologi perang, seperti dilaporkan dalam Injil-injil PB (lihat Markus 8:31; 9:31; 10:33-34; dan par.). OK-lah Yesus menghayati teks tentang hamba Tuhan yang menderita dalam Kitab Deutero Yesaya.
Tetapi, persoalannya adalah via dolorosa yang ditempuh Yesus, dan kematiannya di kayu salib, tidak berakibat soteriologis apapun bagi bangsa Yahudi yang dibelanya di hadapan kekuasaan Romawi. Sedangkan, teks dalam Deutero Yesaya yang sebagian sudah dikutip di atas menyatakan bahwa hamba Tuhan yang menderita itu, menderita demi mendatangkan kesembuhan, kesehatan, keselamatan, pembenaran dan penebusan bagi bangsa Israel. Setelah Yesus mati disalibkan, bahkan sampai berabad-abad sesudahnya, Tanah Israel nyatanya tetap terjajah, tetap tidak merdeka, dan bangsa Israel tetap terluka, sakit, tidak selamat, tidak sejahtera, tidak dibenarkan dan tidak tertebus.
Dilihat dari sudut ini, kita harus menyatakan bahwa azab dan kematian Yesus sia-sia saja. Visi kehambaan yang membawanya pada kematian tidak efektif, kosong, dan dia menjadi seorang hamba Tuhan, ebed Yahweh, yang gagal total. Tidak ada keselamatan dari diri Yesus dan kematiannya bagi bangsanya.
Orang Kristen, demi iman mereka, mungkin akan masih mau bertahan dengan menyatakan bahwa jalan sengsara Yesus dan kematiannya memang tidak dimaksudkan Allah untuk manjur secara politis faktual bagi bangsa dan negerinya pada zamannya, melainkan untuk umat manusia secara universal di segala zaman dan tempat. Tetapi posisi iman Kristen semacam ini berpijak pada suatu logika yang salah: Bagaimana mungkin Yesus (atau Allah) memandang azab dan kematiannya (azab dan kematian Yesus) berefek soteriologis global, universal dan abadi, sementara efek soteriologis lokal, nasional dan temporernya bagi Tanah Israel dan bangsa Yahudi dalam zamannya yang sedang terjajah sama sekali tidak ada? Lagi pula, sebagaimana sudah diargumentasikan sebelumnya di blog ini (klik di sini), azab dan kematian Yesus nyatanya juga tidak manjur untuk secara magis menyelamatkan dan mengubah manusia kapanpun dan di manapun sesudah zaman Yesus, apalagi untuk orang yang hidup dan sudah mati sebelum dia mati disalibkan, misalnya untuk Adam dan Hawa (tentang ini dibahas dalam tulisan ketujuh sesudah tulisan ini, klik di sini).
Masalah keduanya adalah bahwa kalau Yesus memang benar memakai dan menerapkan teks-teks martir Yahudi dalam 2 dan 4 Makkabe (seperti sebagian sudah dikutip di atas) kepada dirinya sendiri, dia dalam kenyataannya tidak mengalami hal-hal dahsyat yang telah dialami oleh orang-orang yang dikisahkan dalam teks-teks Yahudi ekstrakanonik ini, dan kemartirannya juga sia-sia.
Berbeda dari orang Yahudi pada masa perjuangan dan pemberontakan Makkabe (167-142 SM) yang frontal terbuka dan bersenjata melawan helenisasi yang dilancarkan dengan gencar oleh Raja Antiokhus IV Epifanes terhadap bangsa dan agama Yahudi, Yesus tidak frontal menghadapi Roma dalam suatu perlawanan terbuka bersenjata. Berbeda dari apa yang dilukiskan dialami para pejuang Makkabe yang harus menghadapi siksaan sangat mengerikan bertubi-tubi sampai mereka mati dengan tubuh tidak utuh lagi, dalam Injil-injil PB tidak ada gambaran tentang penyiksaan amat dahsyat dan mengerikan yang dialami Yesus. Tentu Injil-injil PB menuturkan penyiksaan atas Yesus ketika dia diadili dan ketika dia digiring ke Golgota, sampai pada puncaknya dia mati dengan sangat mengenaskan di kayu salib. Tetapi, gambaran azab dan kematian Yesus ini sangat jauh kalah dahsyat dan kalah mengerikan jika dibandingkan dengan gambaran azab dan kesengsaraan serta kematian Eleazar dan tujuh pria bersaudara bersama ibu mereka yang sudah tua dalam 2 Makkabe (5:1-6:28 dan 7:1-42).
Dan, hal yang terpenting adalah kenyataan sejarah bahwa pada akhirnya para pejuang Makkabe melalui pengurbanan diri mereka sampai mati syahid secara mengerikan membuahkan kemerdekaan dan penyucian bagi bangsa Yahudi untuk jangka waktu yang cukup panjang (142-63 SM); hal ini kontras dengan gerakan Yesus yang, seperti sudah dikatakan di atas, tidak menghasilkan kemerdekaan dan penyucian kembali tanah dan bangsa Yahudi. Jadi, menerapkan teks-teks martir dalam 2 dan 4 Makkabe pada Yesus tidak pas. Kalaupun betul Yesus pribadi menghayati teks-teks martir dalam 2 dan 4 Makkabe ini, jalan hidup atau nasibnya membawanya ke arah lain: dia mati dengan sia-sia, dan bangsa Israel tetap terjajah untuk jangka waktu yang panjang berabad-abad ke depan, sesudah perjuangannya yang singkat kandas total. Jadi, kalaupun pemuda Yahudi idealis
Yesus dari Nazaret ingin mati syahid demi menyucikan Tanah Israel dan menjadi tebusan bagi bangsanya (menurut Markus 10:45, bagi "banyak orang"), dalam kenyataannya dia, di akhir perjuangannya, gagal telak.
Menurut tiga catatan dalam Injil Markus, Yesus sudah tahu sebelumnya dan meramalkan bahwa dia akan menderita dan pada akhirnya akan mati dibunuh (Markus 8:31; 9:31; 10:33-34). Ini berbeda dari sekian mesias Yahudi lainnya, yang tampil sebelum maupun sesudah Yesus, yang tidak menubuatkan sebelumnya bahwa mereka pada akhirnya akan mati dibunuh oleh penguasa asing yang menjajah tanah mereka. Semua mesias Yahudi lainnya ini, misalnya Simon Bar Kokhba, mengharapkan dan memperjuangkan kemenangan melalui pemberontakan dan perang, bukan mengharapkan kekalahan dan kematian.
Nah, apa yang akan kita katakan tentang seseorang yang sudah tahu akan mati tetapi terus saja maju sampai akhirnya orang ini benar-benar mati dibunuh lawan-lawannya? Apakah tindakan ini bukan suatu kenekatan, atau bukankah ini suatu tindakan bunuh diri yang sudah direncanakan sebelumnya? Mungkin sekali Yesus memang nekat karena impiannya atau karena wangsit yang diterimanya bahwa dia akan mati untuk menebus dosa bangsa Israel dan memerdekakan dan menyucikan Tanah Israel. Yesus mengalami keadaan ini mungkin karena dia mengidentikkan dirinya total dengan hamba Tuhan yang menderita seperti dituturkan Deutero Yesaya atau dengan para martir Makkabe. Jika memang demikian keadaannya, dunia patut bersedih sebab, seperti sudah ditulis di atas, sejarah membuktikan bahwa impian atau wangsitnya itu keliru dan tidak terpenuhi.
Pada sisi lain, ya dunia patut beriba hati karena Yesus sendiri sangat frustrasi pada akhirnya ketika dia menemukan Allah tidak berintervensi dalam bentuk apapun, jika penulis Injil Markus memang melaporkan suatu ingatan historis bahwa di kayu salib Yesus berteriak-teriak sangat kecewa (dengan mengutip Mazmur 22:2a) karena dia melihat dan merasakan Allah telah meninggalkannya: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", "Allahku, Allahku, mengapa dikau menelantarkanku?" (Markus 15:34). Jika memang teriakan ini faktual diucapkan Yesus yang sedang kesakitan tersalib, kita harus katakan bahwa akhirnya, meskipun sudah terlambat, Yesus menemukan dirinya tidak bisa tahan menanggung azab, tidak seperti yang digambarkan dalam Deutero Yesaya tentang seorang hamba Tuhan yang kuat menanggung azab dan tidak seperti para martir Makkabe yang tangguh dan heroik. Rasa frustrasi Yesus ini berbeda tajam dengan kedigdayaan Eleazar di perapian panas yang bernyala-nyala, juga dengan kedigdayaan Sokrates yang dengan tenang meminum racun yang diharuskan Negara Atena atas dirinya (tahun 399 SM).
Tetapi, adakah rekonstruksi alternatif daripada mengargumentasikan bahwa Yesus mati bunuh diri dengan direncanakan, dengan memakai tangan-tangan otoritas Yahudi dan otoritas Romawi, karena dia mau mengikuti jejak sang hamba Tuhan dalam Deutero Yesaya atau jejak para martir Makkabe? Saya kira masih ada alternatif untuk menjelaskan persoalan yang kompleks ini.
Hemat saya, Yesus adalah seorang yang optimis, bukan seorang yang fatalistis, yang menyerah pada nasib yang dibayang-bayangkannya sendiri. Dia percaya bahwa apa yang diperjuangkannya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang luhur, bagi bangsa Israel, yaitu memberitakan dan merayakan kehadiran Allah Yahudi di tengah rakyat, Allah yang datang kepada mereka sebagai Raja dan Bapa mereka untuk memberikan kemurahan dan kerahiman-Nya. Ketika Allah Yahudi ini datang melawat
umat-Nya, Israel, maka Allah ini, kata Yesus, akan mencari domba-domba yang hilang dari kawanannya, dari antara umat Israel; bahwa Allah ini akan menerima kembali dengan penuh kemurahan dan belas kasih orang-orang yang berpaling kembali kepada-Nya bak seorang ayah yang tulus menerima kembali anaknya yang bungsu yang balik kembali kepadanya setelah menempuh kehidupan yang tidak patut di luar negeri; bahwa Allah ini akan, karena kemurahan-Nya, membebaskan orang-orang yang berhutang karena kemiskinan mereka yang parah dan kepasrahan mereka; bahwa Allah ini akan mendengarkan dan mengabulkan doa dan permintaan rakyat Yahudi yang terus-menerus mengharapkan pertolongan ilahi; bahwa Allah ini akan memelihara dengan setia umat-Nya seperti Dia memelihara dengan telaten bunga bakung di padang dan burung di udara. Ketika Allah ini datang dengan bela rasa-Nya, dengan compassion-Nya, maka, seperti didemonstrasikan Yesus dengan nyata, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dibuat berjalan, orang buta dicelikkan, orang yang kerasukan setan dipulihkan, orang yang terkapar hampir mati di jalan karena luka-lukanya didatangi, ditolong, dirawat dan disembuhkan, orang yang mau dirajam diampuni dan diselamatkan. Yesus yang semacam ini adalah Yesus pencinta dan pemelihara kehidupan. Yesus yang semacam ini yakin betul bahwa Allah, Bapanya, terus menyertainya dan memeliharanya seperti Allah ini terus memelihara bunga bakung di padang dan burung pipit di udara.
Nah, orang yang optimis, ceria, mencintai kehidupan, dekat dengan burung-burung di udara dan dengan bunga bakung di padang, dan dengan anak-anak, suka menolong, giat membangun semangat, memberi pengharapan, mengampuni, menyembuhkan dan penuh dengan bela rasa seperti Yesus ini tidak mungkin membayangkan dirinya akan berumur singkat, akan disiksa oleh orang lain, lalu mati dibunuh dengan penyaliban. Yesus yang semacam ini tentu berharap dirinya akan berumur panjang, akan bisa lama berada di tengah rakyat Yahudi yang sedang menderita karena penjajahan dan kemiskinan untuk memberdaya mereka, dan akan dengan bersemangat terus menghadirkan dan memperagakan kuasa dan bela rasa Allah bagi bangsa Yahudi. Dia tentu, dari sejarah Israel dan dari kenyataan yang dilihatnya setiap hari, dapat kita bayangkan mengetahui kekejaman otoritas Yahudi dan otoritas Romawi yang kerap menyalibkan orang Yahudi. Dia, karena itu, tentu sangat tidak menyukai pembunuhan orang di kayu salib. Dia tentu berusaha keras untuk menghindari benturan dengan para penguasa de jure dan de facto Tanah Israel selama dia masih berkarya di kampung-kampung Galilea.
Jika gambaran positif dan optimis tentang Yesus ini secara historis tepat, dan, seperti baru dikatakan, ada alasan yang cukup untuk kita percaya bahwa gambaran ini memang tepat (minimal 70% tepat!), maka sangat tidak mungkin jika Yesus sendiri menubuatkan berulang-ulang (seperti ditulis Markus) bahwa dirinya akan menempuh via dolorosa yang akan, dalam waktu singkat, bermuara pada pembunuhan dirinya di kayu salib. Bila rekonstruksi historis alternatif ini benar, maka semua ucapan Yesus dalam Injil-injil PB yang menubuatkan kesengsaraan dan kematian dirinya di tangan penguasa Yahudi dan penguasa Romawi bukanlah ucapan asli Yesus, melainkan ucapan dan teologi orang Kristen perdana sesudah Yesus wafat yang harus merasionalisasi fakta sejarah berat bahwa Yesus mati dibunuh dengan cara memalukan dan kejam, di luar perkiraan mereka sebelumnya, seperti sudah diuraikan pada waktu yang lalu (klik di sini). Dengan rasionalisasi inilah mereka akhirnya dapat menerima azab dan kematian Yesus yang mereka tidak sangka-sangka itu sebagai sesuatu yang sudah harus terjadi, bertujuan dan bermakna karena, menurut mereka, Yesus sudah meramalkannya sebelumnya.
Begitu juga, ucapan-ucapan Yesus dalam injil-injil PB yang menyatakan dirinya akan mati untuk menjadi penyelamat dan penebus bangsa Israel bukanlah ucapan-ucapan asli Yesus, melainkan ajaran gereja perdana yang ditempelkan pada mulut dan lidah Yesus, yang disusun oleh gereja perdana berdasarkan, langsung atau tak langsung, teks-teks Deutero Yesaya, 2 dan 4 Makkabe dan teks-teks profetis lainnya. Dengan mengonstruksi soteriologi semacam ini, gereja perdana berhasil mengubah kematian Yesus yang faktualnya sia-sia menjadi kematian yang bertujuan, setidaknya dalam keyakinan mereka. Sedangkan, bagi Yesus yang teosentris keselamatan dan penebusan hanya diberikan oleh Allah, Bapanya, yang rakhmani dan rahimi, kepada bangsa Israel, bukan oleh dirinya sebagai anak sang Bapa, yang menundukkan dirinya pada kerahiman ilahi sang Bapa.
Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa Yesus tidak mau dengan sengaja mati untuk menebus dosa dunia. Soteriologi salib tidak berasal dari Yesus, tetapi sepenuhnya ciptaan gereja perdana sesudah masa kehidupan Yesus.
Pertanyaan yang dengan membandel timbul tentu adalah mengapa atau karena hal apa Yesus pada akhirnya memang mati disalibkan dalam usia muda? Pertanyaan ini sudah dijawab dalam tulisan yang lalu (klik di sini). Pada kesempatan ini, cukup dengan singkat diulang kembali. Yesus dihukum mati karena beritanya tentang Kerajaan Allah yang sedang datang di tengah rakyat Yahudi ditafsirkan oleh lawan-lawannya sebagai klaim pribadinya bahwa dia adalah raja Yahudi, dan dengan demikian dia dinilai telah melanggar suatu hukum Romawi yang mewajibkan rakyat jajahan untuk tunduk hanya kepada Kaisar Roma sebagai raja Israel. Yesus ditangkap di Yerusalem dan akhirnya dihukum mati karena dia telah melakukan suatu kesalahan fatal berdemonstrasi di Bait Allah pada waktu perayaan Paskah, perayaan untuk memperingati kemerdekaan bangsa Yahudi dari tangan Mesir dalam sejarah nenek moyang Israel. Teologi Yesus yang memandang Allah tanpa perantara apapun memberikan kemurahan-Nya kepada umat Yahudi membuatnya berang dan marah ketika menyaksikan Bait Allah telah difungsikan sebagai lembaga perantara untuk mempertemukan Allah Yahudi dengan umat-Nya. Kemarahannya ini mendorongnya untuk berunjuk rasa di Bait Allah. Seandainya Yesus tidak berdemonstrasi di Bait Allah, mungkin umurnya masih akan panjang dan tidak mati disalibkan sebagai suatu bentuk penghukuman mati Romawi.
Dengan demikian kematian Yesus di kayu salib terjadi bukan karena Allah mengharuskannya demikian, bukan juga karena dia ingin bunuh diri, tetapi karena kebencian lawan-lawannya dan kesalahannya berunjuk rasa di dalam Bait Allah. Kematian ini, jika diketahui lebih dulu oleh Yesus, tentu akan dia hindari sebisa mungkin. Dengan demikian jelaslah bahwa Yesus tidak mau mati dengan sengaja untuk menyelamatkan dunia. Azabnya yang akan segera membawanya kepada kematian dilihat Yesus, ketika dia kesakitan terpaku di kayu salib, sebagai sesuatu yang tidak dia sangka-sangka; karena itu dia, dalam segala sifat kemanusiaannya, sangat kecewa dan merasa Allah telah meninggalkannya. Akhir kehidupan Yesus benar-benar sebuah tragedi, sebuah kecelakaan sejarah.Politik Roma Versus Politik Yesus
Pada kesempatan ini akan dikemukakan dengan singkat hal-hal historis apa yang menjadi penyebab Yesus dihukum mati melalui penyaliban dirinya. Tulisan ini, dengan demikian, adalah tulisan kelima dari rangkaian tulisan di blog ini yang menyoroti tema masalah-masalah dalam soteriologi salib.
Jauh sebagai suatu peristiwa adikodrati satu-satunya yang bersignifikansi soteriologis universal dan abadi, kematian Yesus di kayu salib faktual historisnya adalah suatu peristiwa kodrati, insani dan politis biasa dalam suatu ruang dan waktu terbatas yang tidak berdimensi soteriologis universal dan abadi apapun.
Melalui banyak perumpamaannya dan banyak ucapannya yang lain, Yesus memberitakan bahwa Kerajaan Allah sedang ada di tengah rakyat Yahudi yang sedang dijajah Roma (antara lain, Lukas 17:21b), bahwa Allah Yahudi kini sedang langsung memerintah sebagai Raja, dan murid-muridnya diajarnya untuk meminta supaya Kerajaan Allah ini terus-menerus berada di tengah mereka (Lukas 11:2; Matius 6:10). Akta-akta Yesus mendemonstrasikan bahwa bersama Yesus benar Allah sedang berkarya di tengah bangsa Yahudi. Kata Yesus, “Jikalau aku mengusir setan dengan jari Allah, sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu!” (Lukas 11:20; Matius 12:28) Hanya Allah yang menjadi Raja mereka. Inilah teokratisme Yesus. Sementara itu, pada pihak lain, bagi orang Romawi, hanya sang Kaisar yang bertakhta di Roma yang merupakan raja baik bagi bangsa Romawi sendiri maupun bagi semua bangsa jajahan. Bagi Yesus, dalam teokratisme Yahudi tidak bisa ada dua raja, melainkan hanya satu; dan raja ini bukan sang Kaisar tetapi Allah Yahudi. Dengan demikian, Yesus atas nama Allah dan atas nama rakyat menolak dan melawan Kaisar.
Perlawanan Yesus dari Nazaret terhadap Roma yang sedang menjajah bangsa Yahudi dengan jelas diungkap secara simbolik, antara lain, dalam tuturan sastra injil tentang seorang Gerasa yang kerasukan roh jahat (Markus 5:1-20). Ketika Yesus bertanya kepada roh jahat itu siapa namanya, roh itu menjawab, “Namaku legion, karena kami banyak.” (ayat 9). Kata Latin “legion” dikenakan untuk satuan prajurit pejalan kaki Roma ditambah pasukan berkuda, dengan jumlah besar antara 3.000 sampai 6.000 orang. Nama ini, dengan demikian, adalah kiasan untuk penjajahan Roma atas Tanah Israel. Dus, Yesus mendemonisasi lawannya, Kekaisaran Romawi. Permusuhan dan perlawanan terhadap Roma yang menduduki tanah Israel diungkap dengan jelas ketika Yesus berseru kepada setan-setan itu, “Keluar dari orang ini!” Tetapi setan-setan itu meminta untuk diizinkan tetap tinggal di daerah itu (ayat 10)―inilah persisnya yang dikehendaki Roma, yakni tetap mengontrol seluruh Tanah Israel. Sebaliknya, rakyat Israel menginginkan mereka diusir dan dibenamkan ke dalam danau seperti babi-babi. Yesus tampil sebagai seorang pengusir setan yang digdaya; dan kehadirannya sebagai orang yang dipenuhi Roh dan kuasa Allah (Markus 1:10b, 12; Matius 12:28; Lukas 11:20; lebih jauh tentang ini, klik http://www.ioanesrakhmat.com/2008/10/spiritualitas-yesus-dari-nazaret.html) sungguh merupakan suatu ancaman nyata bagi kedamaian dan stabilitas masyarakat Israel di bawah rekayasa politis kolonial Roma (Pax Romana): saat Roma mati terbenam dalam air danau hanya menunggu waktunya saja, pembebasan tidak lama lagi tiba.
Bagi Yesus, Tanah Israel, Eretz Israel, adalah milik Allah Yahudi, Tanah Perjanjian yang oleh Allah Yahudi dulu diberikan kepada Abraham, dan yang kemudian diwariskan kepada keturunannya yang membentuk satu bangsa Israel. Bagi Yesus, Allah Abraham adalah Allah Ishak dan Allah Yakub (Markus 12:26), Allah bangsa Israel. Ikatan perjanjian dengan Abraham ini, dalam pandangan Yesus, tidak pernah dibatalkan: Israel, menurutnya, adalah “satu keluarga” yang tidak boleh dipecah-belah (Markus 3:25), dan “anak-anak” dalam satu keluarga harus diperhatikan lebih dulu (Markus 7:27). Untuk menunjukkan bahwa Yesus ingin mempertahankan dan mengembalikan keutuhan 12 suku Israel, dia membentuk komunitas kecil lingkaran dalam para murid yang terdiri atas 12 orang
(Markus 3:14). Jelas, Yesus memperjuangkan kepentingan Israel sebagai satu bangsa. Maka, kalau dikaitkan dengan Tanah Israel, ketika Yesus berkata, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah” (Markus 12:17), dia bermaksud menyatakan bahwa Kaisar tidak memiliki Tanah Israel, tetapi Allah pemiliknya, karena itu tanah ini harus Kaisar kembalikan kepada Allah, pemilik sah tanah ini, dan kepada bangsa Israel, umat Allah, yang mewarisi tanah itu dari Abraham. Dan bangsa Roma harus menyingkir dari tanah yang bukan milik mereka, kembali ke negeri asal mereka sendiri. Doktrin sekular tentang pemisahan agama/gereja dan negara tidak termuat dalam ucapan politis Yesus ini, Yesus yang berwawasan teokratis.
Berita yang terus-menerus di banyak lokasi di Galilea disampaikan Yesus bahwa kini Allah Yahudi sedang memerintah sebagai Raja Israel ditafsir lawan-lawannya sebagai suatu proklamasi bahwa dia sendiri adalah raja Yahudi, dan dengan demikian dia menolak dan melawan Kaisar Roma. Penafsiran semacam ini bisa dibenarkan mengingat bahwa dalam kepercayaan mesianik Israel orang yang berbicara dan bertindak atas nama Allah, seperti Yesus dari Nazaret, adalah wakil langsung dari Allah, representasi Allah sendiri, dan tangan Allah sendiri. Wakil, representasi, juru bicara dan tangan Allah dalam kehidupan riil bangsa Israel tidak lain adalah raja atau mesias Israel sendiri. Adalah suatu ketentuan hukum Romawi, barangsiapa menolak dan melawan Kaisar, orang itu harus dihukum mati.
Persis ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem pada perayaan Paskah Yahudi, perayaan untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, orang banyak memproklamasikan Yesus sebagai Raja Israel; kata mereka, dalam tuturan Markus, “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi” (Markus 11:9; par.). Tetapi ada persoalan di sini. Apa yang dicatat dalam injil-injil sinoptik (Markus, Matius dan Lukas) tentang masuknya Yesus dengan jaya dan aman-aman saja ke kota Yerusalem pada perayaan Paskah setelah orang banyak mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus adalah sang Raja Yahudi, keturunan Raja Daud, sukar dipercaya sebagai kejadian historis. Jika arak-arakan gegap gempita yang kuat diwarnai pesan-pesan mesianik dan pemulihan kerajaan Daud ini sungguh terjadi, pasti peristiwa ini akan diberi reaksi represif cepat oleh Gubernur Pontius Pilatus (yang sedang berada di Yerusalem) untuk mencegah timbulnya pemberontakan sekaligus untuk “mengamankan” figur yang diproklamasikan rakyat banyak sebagai mesias Yahudi. Tuturan tentang peristiwa yang sama dalam Injil Yohanes (12:12-16) lebih dapat dipercaya, karena, dituturkan, setelah orang banyak memproklamasikan Yesus sebagai “Raja Israel” (ayat 13), Yesus “pergi bersembunyi” (ayat 36b), menghindari para penguasa yang pasti sedang mencarinya untuk menangkapnya.
Bagaimana pun juga, tuturan dalam keempat injil tentang kejadian di pintu gerbang Yerusalem ini bermaksud untuk menyampaikan sebuah fakta bahwa rakyat Yahudi memang menantikan kedatangan seorang mesias pembebas dan pemenuhan penantian ini tampaknya, oleh orang banyak, dikaitkan dengan kehadiran Yesus di tengah mereka. Hal ini bisa terjadi karena mereka menyamakan Yesus yang memberitakan kedatangan Kerajaan Allah dan memperagakan kehadiran kuasa Allah dalam tindakan-tindakan penyembuhan dan eksorsismenya dengan Kerajaan Allah itu sendiri. Yesus menunjuk pada Kerajaan Allah dan mengajak orang banyak untuk melihat kepada Kerajaan ini, tetapi rakyat menunjuk pada Yesus sebagai sang mesias yang bertakhta dalam Kerajaan
itu sendiri, dan para penguasa Bait Allah menuduh Yesus sebagai orang yang mengklaim posisi mesianik. Mereka mengganti Allah yang diwartakan dan diejawantahkan Yesus dengan diri Yesus sendiri! Bagi Yesus, Allah adalah sang Pembebas Israel, tetapi bagi rakyat Yahudi Yesuslah sang Pembebas mereka!
Ketika Yesus sudah berada di Yerusalem, dia memasuki Bait Allah lalu melakukan unjuk rasa di sana dan berkata keras mengenai Bait ini (Markus 11:15-18; Injil Thomas # 71; Yohanes 2:14-16a). Demonstrasi Yesus di Bait Allah, meskipun berskala kecil, dan ucapan kerasnya, adalah simbol, tanda, isyarat dan pesan bahwa dia menolak otoritas Yahudi dan otoritas Roma yang menguasai Bait Allah. Sebab kedua otoritas ini menghalangi keterlibatan langsung Allah Yahudi dalam kehidupan bangsa Yahudi. Bait Allah, melalui ritual kurban serta pemungutan pajak yang dilakukan di dalamnya, di tangan kedua otoritas ini telah menjadi sebuah institusi religio-politis yang menekan rakyat, yang menghalangi perjumpaan langsung rakyat dengan Allah Yahudi, karena kedua otoritas ini berfungsi sebagai broker (yang dalam pandangan Yesus) tidak sah antara Allah Yahudi dan rakyat. Keselamatan dari Allah dan kasih karunia-Nya, bagi Yesus, tidak boleh diperantarai oleh siapapun dan oleh otoritas kelembagaan apapun, melainkan harus langsung diterima rakyat Yahudi, sebab Kerajaan Allah ada di tengah rakyat.
Celakanya, menyerang Bait Allah, menentang otoritas yang menguasainya, dan menolak ritual dan pemungutan pajak resmi yang dilakukan di dalamnya, apalagi kalau perlawanan, penentangan dan penolakan ini dilakukan pada perayaan Paskah, akan berakibat kematian bagi si pelawan. Barangsiapa menyerang Bait Allah, orang itu dipandang menyerang Roma sebagai penguasa yang ada di belakang Bait Allah, yang memerintah Tanah Israel melalui wakil Kaisar (gubernur provinsi Yudea) dan kaki tangan Yahudinya (keluarga Herodes, kaum bangsawan Yahudi, Imam Besar Kayafas, Sanhedrin, imam-imam kepala, para ahli Taurat dan para tua-tua)! Hukuman mati adalah ganjaran sah bagi setiap orang yang menyerang Bait Allah. Tentu, di balik ini, ada suatu kesepakatan tidak tertulis antara otoritas Romawi dan otoritas Yahudi yang menetapkan bahwa barangsiapa membuat suatu kerusuhan di Bait Allah dan di kota Yerusalem pada perayaan Paskah, yang potensial menimbulkan keributan besar, orang itu dapat langsung ditangkap, diperiksa singkat lalu dieksekusi, sebagai suatu gertak dan teror terhadap rakyat Yahudi supaya mereka tidak bertindak macam-macam (bdk. Markus 14:2; Yohanes 11:48).
Melalui suatu kerjasama otoritas Yahudi dan otoritas Romawi, dan dengan melibatkan seseorang dari “lingkaran dalam” komunitas kecil yang Yesus bangun, Yesus kemudian dapat ditangkap, lalu diperiksa, dan akhirnya dihukum mati menurut cara penghukuman mati Romawi bagi para pemberontak: Yesus mati disalibkan dengan sebuah tuduhan politis bahwa dia mengklaim diri sebagai Raja Orang Yahudi di suatu tanah yang sedang dijajah Roma. Tuduhan ini ditulis pada titulus yang dipasang pada kayu salib Yesus. Tuduhan semacam ini (yang mendakwa Yesus sebagai Raja Orang Yahudi, dan bukan Raja Orang Israel) hanya mungkin dikeluarkan oleh pihak Roma. Di awal pemeriksaannya terhadap Yesus yang sedang diadili, Pontius Pilatus bertanya, “Engkau inikah raja orang Yahudi?” (Markus 15:2; Matius 27:11; Lukas 23:3; Yohanes 18:33).
Jadi, kematian Yesus adalah suatu konsekwensi politis wajar dan insani dari keyakinan dan kiprah politis Yesus sendiri. Yesus, dengan gerakannya menghadirkan Kerajaan Allah di tengah rakyat yang membuatnya dipandang sebagai sang mesias atau raja Yahudi, terlalu kecil dan lemah ketika dia
berhadapan dengan raksasa Imperium Romanum yang sedang menjajah negeri dan bangsanya. Dia adalah seorang teokratis dan mesianis yang gagal. Tidak ada keselamatan, kemerdekaan dan penyucian yang timbul dari kematiannya di kayu salib bagi bangsa Israel, berbeda dari keyakinan para pejuang Makkabe dalam sejarah Israel (abad 2 SM) bahwa curahan darah suci setiap mukmin Yahudi akan memberi kemerdekaan dan penyucian bagi Tanah Israel! (lebih jauh tentang ini, klik http://ioanesrakhmat2009.blogspot.com/2009/05/betulkah-yesus-dengan-sengaja-mau-mati.html). Roma masih berkuasa atas Tanah Israel beberapa ratus tahun ke depan setelah kegagalan pergerakan yang Yesus lancarkan; bahkan sejak berakhirnya Perang Yahudi II melawan Roma (132-135 M) yang dipimpin Mesias Simon Bar Kokhba Israel tidak pernah lagi berdiri sebagai suatu bangsa dan negara merdeka sampai pada terbentuknya Negara Israel modern yang sekular di tahun 1948.
Kematian Yesus di kayu salib pada saat terjadinya tidak memberi efek soteriologis bagi Tanah Israel dan bangsa Yahudi, apalagi efek soteriologis universal dan abadi apapun, tidak seperti belakangan diklaim orang Kristen perdana, dua sampai sepuluh dasawarsa setelah Yesus wafat. Orang Kristen perdana, ketika mereka merenungi makna kematian Yesus yang sia-sia dan berupaya keluar dari keadaan gagal dan memalukan yang sangat kuat menekan mental mereka melalui rasionalisasi-rasionalisasi teologis yang mereka buat (tentang ini, klik http://ioanesrakhmat2009.blogspot.com/2009/04/jalan-jalan-keselamatan-alternatif.html), mengklaim bahwa kematian Yesus menyelamatkan umat manusia dan jagat raya. Ini sungguh suatu klaim yang terlalu tinggi, jauh dari kenyataan yang sebenarnya.
Mitos Iman Ortodoks
ada jalan lurus, ada jalan menyimpang,keduanya berfungsi
Di kalangan setiap umat beragama, selalu ada kelompok yang dengan bangga dan takabur menyebut diri ortodoks. Kata “ortodoks” berarti ajaran atau pandangan (doksa) yang benar atau lurus (orthos). Kelompok ortodoks ini memandang setiap kelompok keagamaan lain yang menganut ajaran atau pandangan berbeda atau bertentangan dengan ajaran atau pandangan mereka sebagai bidaah atau kelompok sesat dan menyesatkan yang sudah menyimpang dari ortodoksi. Bagi kelompok ortodoks, kelompok heterodoks atau kelompok yang menganut ajaran atau pandangan lain (heteros) atau kelompok non-ortodoks tidak bisa berdiam bersama mereka dalam satu masyarakat. Bagi mereka, bagaimana mungkin yang sesat atau yang bengkok atau yang salah bisa bersanding bersama dengan yang benar dan yang lurus; bagaimana mungkin gelap bisa hidup bersama dengan terang. Memakai kosmologi dualistik, kelompok ortodoks memandang diri mereka berada di pihak Allah, dan sedang melawan kelompok non-ortodoks yang mereka pandang berada di pihak setan. Kehidupan dilihat oleh kelompok ortodoks sebagai suatu arena peperangan abadi melawan kelompok yang tidak ortodoks, peperangan antara Allah melawan setan, antara “kami yang benar” dan “kalian yang salah”.
Setiap agama memiliki sejarah panjang pertikaian antara kelompok ortodoks dan kelompok heterodoks atau kelompok non-ortodoks. Pertikaian ini semula bertitik-tolak dari pertikaian di bidang ajaran, ketika kelompok heterodoks atau non-ortodoks juga berpengaruh di dalam masyarakat yang dengan serakah ingin dikuasai secara sepihak oleh kelompok ortodoks. Tetapi, pertikaian atau polemik di bidang ajaran dilihat oleh kelompok ortodoks tidak bisa mereka
menangkan dengan mudah, khususnya ketika masyarakat di mana mereka hidup sangat plural dan toleransi atas keanekaragaman pandangan menjadi gaya hidup bersama. Karena itu, untuk dengan telak memenangkan pertikaian doktrinal, mereka melihat perlu memakai kekuatan politik dan kekuatan militer sebagai kekuatan-kekuatan ampuh untuk membinasakan lawan-lawan ideologis mereka. Mereka pun dengan segala cara yang lihai berusaha keras untuk dapat dirangkul oleh, atau merangkul, kekuatan politik dan kekuatan militer yang sedang berkuasa dalam masyarakat sebagai kekuatan-kekuatan penentu, pengendali dan perancang kehidupan masyarakat dan negara.
Tidak cukup hanya dengan merangkul kekuatan politik dan kekuatan militer, mereka, kelompok ortodoks, berupaya juga untuk merangkul atau dirangkul oleh kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang diyakini akan dapat mematikan gerak dan nafas kehidupan kelompok heterodoks atau non-ortodoks. Maka, ketika terbentuk aliansi kuat yang tidak suci antara kekuatan agama ortodoks, kekuatan politik, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, kelompok ortodoks dengan mudah menggilas dan melumat kelompok-kelompok heterodoks atau non-ortodoks dalam masyarakat. Inilah yang sesungguhnya terjadi ketika kekristenan perdana pada abad keempat merangkul sekaligus dirangkul oleh kekaisaran Romawi yang pada waktu itu diperintah oleh Kaisar Konstantinus Agung. Keberhasilan politis kelompok ortodoks ini, ketika mereka berhadapan dengan kelompok-kelompok yang mereka pandang sebagai bidaah, nyata dengan sangat jelas ketika Kaisar Theodosius pada tahun 381 secara resmi menyatakan bahwa bidaah (dalam hal ini: Arianisme, Manikheisme, gnostisisme, Ebionisme dan paganisme) adalah suatu tindak kejahatan melawan negara! Pada waktu itu, beragama berbeda dari agama mayoritas yang didukung kekaisaran adalah suatu tindakan subversif! Pasukan Inkwisisi yang dibentuk gereja Roma Katolik pada Abad Pertengahan yang bertugas mengejar, menangkap, mengadili dan melumatkan para bidaah hanyalah melanjutkan kebijakan negara dan gereja yang sudah dibangun pada abad keempat ini.
Hal penting yang patut ditanyakan adalah apa tolok ukur yang dipakai kelompok ortodoks untuk menentukan bahwa merekalah pemilik satu-satunya ajaran atau akidah atau ideologi religius yang lurus dan benar, sementara yang berbeda atau bertentangan dari yang mereka pegang dicap tidak lurus, sesat dan tidak benar. Ortodoksi, di manapun dan kapanpun juga, sama sekali tidak mendasarkan kebenaran atau kelurusan pandangan dan doktrin mereka pada ilmu pengetahuan. Mereka melandaskan klaim kebenaran dan kelurusan doktrinal mereka pada sejumlah otoritas yang diklaim tidak bisa digugat: otoritas insani, otoritas Kitab Suci, otoritas dogma keagamaan yang diterima dan diabadikan, dan otoritas iman. Otoritas insani di sini adalah orang-orang suci atau para pemimpin suci zaman lampau yang dipercaya telah menyampaikan dan merawat ajaran yang lurus dan benar, yang telah dicatat dan direkam dan diabadikan tanpa kesalahan apapun di dalam Kitab Suci sebagai sabda dan wahyu ilahi sepenuhnya yang tidak bisa bercacat, dan yang dipelihara dan dilestarikan dalam dogma keagamaan yang sudah ditetapkan sekali untuk selamanya pada awal-awal kelahiran suatu agama. Otoritas insani di sini tentu saja juga mencakup otoritas pemegang kekuasaan politik, militer dan ekonomi dalam masyarakat yang melindungi dan memelihara kelompok ortodoks. Otoritas insani dan otoritas Kitab Suci yang melindungi kelompok ortodoks, dan otoritas dogma yang menopang kelompok ini, diklaim dan dipertahankan oleh kelompok ini sebagai otoritas yang tidak bisa salah dalam hal apapun dan kapanpun.
Hal “tidak bisa bercacat” dan “tidak bisa salah” ini bukan ditemukan dan dipertahankan dengan berlandaskan pada suatu penyelidikan dan pengujian secara ilmiah menurut kaidah-kaidah
mendapatkan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai hal-hal yang diimani begitu saja. Iman tidak dihasilkan dari suatu penyelidikan saintifik untuk mendapatkan secara objektif kebenaran sesuatu, melainkan sebagai sesuatu yang diimpi-impikan, diharap-harapkan, diangan-angankan, dibayang-bayangkan dan diyakini begitu saja. Iman berdasar pada keyakinan subjektif; sedang ilmu pengetahuan didapatkan berdasarkan penyelidikan objektif atas sesuatu. Iman dan sains adalah dua hal yang bertentangan secara epistemologis: pengetahuan imaniah didapat dari keyakinan dan harapan subjektif partikular pada suatu Tuhan sebagai objek di luar sejarah dan di luar pengalaman riil dan empiris manusia; sedangkan ilmu pengetahuan diperoleh dari penalaran logis, pengujian dan pembuktian menurut prosedur dan metodologi yang objektif, ketat, repeatable, dapat diulang, baku dan universal. “Demi Allah, mudah-mudahan esok tidak hujan”, adalah ungkapan iman; sedangkan ungkapan ilmu pengetahuan berbunyi lain: “Menurut data objektif yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan serta dianalisis oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, dipastikan besok Jakarta akan diterpa hujan lebat yang berlangsung lama.” Iman berada dalam wilayah mitos; sedangkan sains berada dalam wilayah logos. Logos menentang mitos, dan mengunggulinya dalam pencapaian kebenaran. Sebagai mitos, iman berbicara mengenai mimpi-mimpi, angan-angan, harapan-harapan, yang tidak berpijak pada nalar dan fakta empiris; sedangkan sains sebagai logos berpijak pada landasan penalaran logis yang ditopang bukti empiris objektif.
Nah, di Jakarta, saya perhatikan, belakangan ini kelompok Kristen ortodoks dilanda histeria keagamaan untuk mempertahankan, membela dan melindungi ketuhanan Yesus Kristus, dari pandangan-pandangan kalangan sejarawan kritis yang menyelidiki Yesus dari sudut pandang ilmu sejarah, ilmu kajian kritis teks Kitab Suci, ilmu arkeologi dan ilmu antropologi lintas budaya. Kalangan Kristen ortodoks Jakarta yang minder, histeris dan kelabakan ini membangun suatu aliansi dengan kekuatan ekonomi di Jakarta untuk mendapatkan sumber-sumber dana untuk menyelenggarakan seminar-seminar yang membela dan mempertahankan serta memenjarakan ketuhanan Yesus, dengan mengundang apologet-apologet gnostik Kristen mancanegara yang harus dibiayai dan dibayar mahal hanya untuk melontarkan pandangan-pandangan gnostik mereka yang tidak menerima fakta keberdagingan dan kebersejarahan Yesus dari Nazaret. Proyek seminar-seminar ortodoks ini adalah proyek iman, bukan proyek ilmu pengetahuan, sementara kebenaran objektif tentang Yesus dari Nazaret bisa diperoleh hanya dengan jalur penyelidikan ilmiah seperti yang sudah dan sedang digelar baik oleh the Jesus Seminar serta the Jesus Project, dan banyak pakar kritis lainnya di dunia ini, maupun yang juga saya lakukan di Indonesia. Ilmu pengetahuan tentang Yesus tidak didapat dari otoritas insani, otoritas Kitab Suci, otoritas dogma, atau otoritas iman, melainkan hanya dari penyelidikan ilmiah, yang memakai nalar, sains dan bukti untuk mendapatkannya. Kitab Suci, dalam hal ini, adalah suatu sumber, bukan sumber satu-satunya, bagi penemuan siapa Yesus dari Nazaret itu.