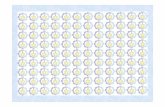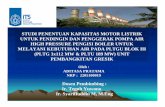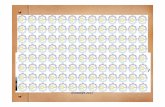PLTGU Pemaron awal
-
Upload
thuguzzmahadiputra -
Category
Documents
-
view
382 -
download
4
Transcript of PLTGU Pemaron awal

PLTGU PemaronPengertian Mesin Uap
Mesin uap (steam engine) masuk dalam kategori pesawat kalor, yaitu
peralatan yang digunakan untuk merubah tenaga termis dari bahan bakar menjadi
tenaga mekanis melalui proses pembakaran. Ada dua jenis pesawat kalor yaitu
Internal Combustion Engines/ICE (motor pembakaran dalam) dan External
Combustion Engines/ECE (motor pembakaran luar). Pada pesawat kalor jenis
ICE, proses pembakaran bahan bakar untuk mengasilkan tenaga mekanis
dilakukan didalam peralatan itu sendiri; sedangkan pada ECE, peralatan ini hanya
merubah tenaga termis menjadi tenaga mekanis adapun proses pembakaran
dilakukan diluar peralatan tersebut.
Contoh dari pesawat kalor jenis ICE adalah motor bensin dan motor disel
yang sangat populer sebagai prime mover baik untuk otomotif maupun untuk
industri. Pada motor bensin dan motor disel proses pembakaran bahan bakar
(bensin/solar) dilakukan didalam silinder motor itu sendiri dan perubahan tenaga
termis hasil pembakaran menjadi tenaga mekanis juga dilakukan didalam pesawat
itu sendiri melalui gerakan kian kemari dari piston menjadi gerakan putaran dari
crank shaft.
Contoh dari pesawat kalor jenis ECE adalah mesin uap dan turbin uap.
Pada peralatan ini, mesin uap hanya merubah tenaga potensial dari uap menjadi
tenaga mekanis berupa gerakan kian kemari dari piston dan selanjutnya diubah
menjadi gerakan putaran dari crank shaft; sedangkan turbine uap merubah tenaga
potensial dari uap menjadi tenaga mekanis yang langsung merupakan gerakan
putaran dari as turbin. Adapun proses pembakaran bahan bakar dilakukan diluar
mesin uap dan turbin uap, yaitu didalam ketel uap (boiler). Didalam ketel uap
(boiler) tenaga termis hasil pembakaran bahan bakar digunakan untuk
memanaskan air sehingga berubah menjadi uap dengan temperatur dan tekanan
tinggi, untuk selanjutnya uap dengan temperatur dan tekanan tinggi tersebut
dialirkan ke-mesin uap atau turbin uap untuk diubah menjadi tenaga mekanis.
Adapun cara kerja mesin uap adalah sebagai berikut :
1

Lihat gambar dibawah ini,
Gambar 2. Cara kerja mesin uap
Didalam cylinder mesin uap terdapat piston yang mempunyai piston rod
yang dihubungkan dengan cross head yang berada diluar cylinder. Cross head
dihubungkan oleh connecting rod dengan crank shaft (tidak tampak pada gambar),
sehingga apabila piston bergerak kian kemari maka crank shaft dapat berputar.
Slide valve yang mempunyai valve rod digerakkan oleh crank shaft melalui
eksentrik, sehingga slide valve dapat bergerak kian kemari sambil membuka dan
menutup dua buah lubang uap yang berhubungan dengan cylinder. Valve box
dimana slide valve berada mempunyai dua saluran, saluran pemasukan yang
dihubungkan dengan boiler untuk menyalurkan uap dengan tekanan tinggi (warna
merah), dan saluran pembuangan yang dihubungkan dengan cerobong untuk
membuang uap bekas (warna biru).
Pada waktu piston mencapai posisi paling kiri, maka slide valve akan
membuka lubang uap cylinder bagian kiri sehingga uap dari boiler dapat masuk
kedalam cylinder pada bagian kiri dari piston dan mendorong piston kekanan,
sementara itu lubang uap sebelah kanan dihubungkan dengan saluran pembuangan
sehingga uap bekas dapat terbuang keluar melalui cerobong. Sebelum akhir
langkah piston, lubang uap tersebut sudah ditutup oleh slide valve sehingga
2

pasokan uap terhenti namun piston tetap bergerak kekanan karena ekpansi dari
uap.
Pada waktu piston mencapai posisi paling kanan, maka slide valve akan
membuka lubang uap cylinder bagian kanan sehingga uap dari boiler dapat masuk
kedalam cylinder pada bagian kanan piston dan mendorong piston kekiri,
sementara itu lubang uap sebelah kiri dihubungkan dengan saluran pembuangan
sehingga uap bekas dapat terbuang melalui cerobong. Sebelum akhir langkah
piston, lubang uap tersebut sudah ditutup oleh slide valve sehingga pasokan uap
terhenti namun piston tetap bergerak kekanan karena ekpansi dari uap.
Karena cross head dengan crank shaft dihubungkan oleh connecting rod, maka
gerakan kian kemari dari piston tersebut akan diubah menjadi gerakan putaran
dari crank shaft. Demikian selama ada pasokan uap dari boiler maka mesin uap
akan merubah menjadi tenaga mekanis dengan gerakan putaran dari crank shaft.
Gambar 3. Cara kerja mesin uap saat mulai bekerja
Pada pembangunan konstruksi awal suatu pembangkit, banyak hal yang
harus diperhitungkan. Letak yang strategis, jalur atau rute saluran yang akan
dipilih dan yang paling efisien, dan perhitungan perkiraan beban yang akan
datang. Peramalan beban ini mencakup penentuan jumlah beban yang lalu dan
yang akan datang sesuai dengan pertumbuhan beban yang akan diperkirakan.
Dengan begitu, akan dapat ditentukan kapasitas G.I dan yang lainnya. Sehingga
keandalan sistem akan tercipta.
3

Pada kenyataannya, pertambahan beban tiap tahunnya kadangkala tidak
sesuai dengan perkiraan sebelumnya, kadangkala terjadi pertumbuhan yang
terlampau tinggi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada turunnya tingkat
keandalan sistem. Sehingga perlulah di bangun suatu saluran baru. Pembangunan
suatu saluran baru juga akan mengakibatkan suatu masalah baru seperti terjadi
pembebanan mekanis pada saluran yang lama, adanya andongan yang berlebih,
robohnya tiang-tiang jaringan dan lain-lain. Maka dari itu pada saat pembangunan
suatu saluran baru hendaknya mempertimbangkan segala faktor yang ada.
Energi listrik merupakan kebutuhan primer yang terus berkembang seiring
dengan perkembangan teknologi. eningkatan ini perlu diimbangi dengan
pemenuhan kebutuhan akan energi listrik dengan cara pembangunan pembangkit
yang baru dari pihak produsen. Kebutuhan listrik di Bali juga mengalami
peningkatan yang cukup tajam diperkirakan sekitar 8- 12 % pertahun. Jika
PLTGU Pemaron beroperasi maka akan terjadi perubahan di dalam sistem
kelistrikan di Bali, baik itu perubahan tegangan maupun rugi daya. Diharapkan
perubahan yang lebih baik yaitu tegangan dapat lebih stabil dan rugi-rugi dapat
menurun. Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka dalam penelitian ini
dibahas sejauh mana pengaruh pembangunan PLTGU Pemaron terhadap rugi
daya pada sistem di Bali.
Prinsip pokok dari semua pembangkit listrik bertenaga gas dan uap adalah
Brayton Bycle. Apabila kita hanya bicara tentang PLTG maka kita harus berpikir
tentang open cycle tetapi apabila ingin mengetahui siklus kerja PLTGU maka kita
harus mengetahui tentang combined cycle.
Gambar 4 Brayton Bycle
4

Pada open cycle dimulai dari pemompaan bahan bakar dan pemasukan
udara dari intake air filter menuju combuster. Di combuster campuran bahan
bakar dan udara disemprotkan oleh nozzle sehingga di ruang bakar terjadi
pembakaran. Pembakaran tadi akan memutar turbin gas yang selanjutnya akan
memutar generator yang akan menghasilkan energi listrik. Gas buang dari turbin
gas akan langsung dibuang melalui bypass stack. Sedangkan untuk PLTGU
menggunakan combined cycle dimana gas buang dari turbin gas akan dimanfaatkan
kembali untuk mengoperasikan turbin uap. Dibutuhkan HRSG (Heat Recovery Steam
Generator) yang prinsip kerjanya sama dengan boiler. Gas buang dari turbin gas tidak
langsung dibuang melalui bypass stack akan tetapi masuk ke HRSG. Setelah masuk ke
HRSG maka gas tadi akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian
digunakan untuk memutar High Pressure Steam Turbine (HPST), kemudian HPST
memutar Low Pressure Steam Turbine (LPST) yng akhirnya akan membangkitkan
generator. Hasil pembuangan LPST akan dikondensasi dan dialirkan ke pompa. Dari
pompa kemudian dilairkan kembali ke HRSG. Begitu seterusnya sehingga terbentuk
siklus tertutup.
Konsep perencanaan
Perencanaan sistem ketenagalistrikan modern di negara berbudaya sesuai
dilakukan berlandaskan teknik riset operasional melalui beberapa tahapan.
Tahap pertama, penyusunan prakiraan kebutuhan beban [kilo Watt/kW] dan
energi listrik [kilo Watt per jam/kWh] dalam kurun waktu perencanaan (misalnya
20 tahun mendatang). Untuk Bali misalnya, perkiraan tingkat pertumbuhan beban
8-9 persen per tahun dengan memperhatikan struktur bebannya.
Tahap 2, penyusunan sistem tetap (fixed system) ketenagalistrikan yang terdiri
atas sistem yang sudah ada dan sistem yang sudah ditetapkan rencana
pembangunannya. Sistem tetap Bali melalui dua saluran kabel laut Jawa-Bali 2x
100 MW, PLTGU Gilimanuk daya mampu 133 MW, PLTG Pesanggaran 71 MW,
PLTD Pesanggaran 42 MW. Jumlah pasokan 446 MW.
5

Tahap 3, penyusunan sistem variablel (variable system), yakni komponen sistem
yang patut dipertimbangkan sebagai kandidat pembangunan. Untuk Bali misalnya,
dapat dipertimbangkan pembangunan jaringan transmisi dari Jawa ke Bali, PLTU
Batubara 50-100 MW di Bali, PLTP Bedugul, PLTGU 150 MW Pemaron, PLTG
100 MW Pesanggaran, Gianyar, Amlapura.
Tahap 4, proses optimasi perencanaan sistem, berdasarkan teknik dynamic
programming untuk mencari solusi optimal pasokan guna memenuhi kebutuhan.
Proses optimasi bertujuan selama kurun waktu perencanaan memilih kandidat/
alternatif perencanaan yang memberi fungsi sasaran (jumlah biaya) yang terendah
tanpa melanggar syarat batas.
Dari uraian di atas, terlihat perencanaan sistem ketenagalistrikan perlu
pertimbangan luas/mendalam. Dalam pembangunan sistem ketenagalistrikan
merupakan upaya padat modal dan memerlukan bahan bakar yang relatif mahal
harganya serta berdampak pada pola hidup masyarakat dan lingkungan hidup.
Oleh karena itu, optimasi sistem ketenagalistrikan penting untuk
dipertanggungjawabkan dampaknya (seperti akibat kenaikan tarif listrik, bila
pilihan proyek tak optimal) kepada masyarakat, kini tersedia berbagai program
komputer perencanaan sistem ketenagalistrikan, seperti WASP dari International
Atomic Energy Agency di Wina, Austria.
Peneliti telah melakukan perencanaan jangka pendek berkaitan dengan
pembangunan PLTGU Pemaron yang dipermasalahkan. Dengan melakukan
beberapa penyederhanaan seperti beban listrik Pulau Bali disederhanakan atas
waktu beban puncak (WBP) dan luar waktu beban puncak (LWBP).
Besaran beban pembangkitan LWBP 246 MW dan WBP 340 MW.
Distribusi beban diperhatikan. Sebesar 242 MW atau 81 persen pada WBP berada
di pusat beban di Gardu Induk (GI) Kapal, Sanur, Pesanggaran, Nusa Dua,
Gianyar, dan hanya 21 MW (7 persen) di GI Pemaron dan di 35 MW (12 persen)
GI lain, Baturiti, Gilimanuk, Negara dan Amplapura. Pembangkit Listrik di Jawa
6

tergolong murah dikarenakan pembangkit-pembangkit listrik di Jawa berkapasitas
besar dan menggunakan bahan bakar batubara. Listrik dari batubara memang jauh
lebih murah. Dengan tambahan 180 MW dari Jawa, maka ketersediaan pasokan
listrik di Bali menjadi 241 MW + 180 MW = 421 MW.
Selain daya listrik yang dimiliki oleh PLN tersebut, di Bali tersedia juga
pasokan listrik yang berasal bukan dari PLN. Pembangkit listrik non-PLN ini
dimiliki oleh Hotel-hotel besar maupun Industri dan disebut sebagai 'captive
power'. Sejauh data yang penulis miliki, 'captive power' yang tersedia di Bali
sebesar 549 MW.
Kesalahan lokasi
Dari jumlah pasokan mampu Bali sebesar 446 MW, jumlah pasokan
efektif terbatas hanya menjadi 358 MW, disebabkan kesalahan pemilihan lokasi
PLTG Gilimanuk yang di sebelah barat pusat beban.
Jumlah pasokan dari barat 333 MW (200 MW melalui dua kabel laut 150
kV Jawa-Bali dan 133 MW dari PLTG Gilimanuk) menjadi hanya sampai 245
MW, dibatasi oleh kemampuan daya penyaluran transmisi 150 kV dari barat,
melalui dua saluran 150 kV Gilimanuk-Kapal dan satu saluran 150 kV Gilimanuk
-Pemaron.
Dengan demikian jumlah pasokan daya efektif Bali menjadi hanya 358
MW (245 MW dari barat dan 113 MW dari Pesanggaran). Gangguan pada satu
saluran kabel laut 150 kV (pasokan berkurang 100 MW), berakibat jumlah
pasokan menjadi 346 MW (100 MW dari Jawa, 133 MW dari PLTG Gilimanuk,
dan 113 MW dari PLTD/PLTG Pesanggaran), masih lebih besar dari beban WBP
340 MW.
Oleh karena itu tidak terjadi pemadaman. Tetapi gangguan sebesar 50 MW
di PLTD/PLTG Pesanggaran, jumlah pasokan jadi hanya 308 MW (dari barat 245
MW+ (113-50) MW dari Pesanggaran) sudah menyebabkan pemadaman 32 MW
7

(340 MW-308 MW). Rupanya pembangunan PLTG Gilimanuk hanya
dimaksudkan untuk mengantisipasi gangguan kabel laut 150 kV Jawa-Bali dan
bukan mengacu pada pengamanan pasokan sistem Bali.
Sehingga untuk pemilihan lokasi penempatan PLTG Gilimanuk di sebelah
timur, misalnya di GI Pesanggaran, Gianyar, Amlapura, jumlah pasokan akan
tetap sesuai dengan daya mampu pembangkitan sebesar 446 MW, tak menghadapi
kendala batasan penyaluran.
Dengan demikian pasokan Bali berkurang 88 MW (446 MW-358 MW).
Dihitung dengan biaya spesifik pembangunan PLTG 400 dollar per kW, nilai
ekonomi pemborosan pasokan sistem pembangkitan akibat salah pilih lokasi ialah
35,2 juta dollar. Ini contoh pertama kesalahan pemilihan lokasi pembangunan
pusat listrik di Bali.
Rencana jangka pendek
Dengan daya 150 MW, rencana pembangunan PLTGU Pemaron dapat
digolongkan perencanaan jangka pendek. Alternatif kandidat pasokan/
pembangkit baru yang pantas dipertimbangkan untuk Bali adalah: (1).
Pembangunan jaringan transmisi 500 kV Paiton, Banyuwangi, Gilimanuk, Kapal,
(2). PLTGU Pemaron 150 MW, (3). PLTG Pemaron 100 MW, (4). PLTG
Pesanggaran 100 MW, (5). PLTG Amlapura 100 MW dan (6). Pemanfaatan
captive power (milik industri) 549 MW yang ada di Bali.
Mengacu pada UU No 20/ 2002 Ketenagalistrikan, konsep perencanaan
sistem dan kemungkinan kandidat alternatif perluasan di atas dan dalam kaitannya
dengan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), apakah
telah dilakukan perencanaan jangka panjang Sistem Ketenagalistrikan Bali dan
dijelaskan kepada masyarakat Bali? Sehingga, dengan demikian mekanisme
checks and balance dapat ditegakkan.
8

Sementara itu, dari hasil perhitungan penulis, dapat disimpulkan telah
terjadi kesalahan pilihan teknologi, pilihan lokasi dan pelanggaran tata ruang
pembangunan PLTGU Pemaron. Kesalahan pertama, pilihan teknologi
membangun PLTGU, padahal yang diperlukan PLTG. Struktur beban listrik Bali
lebih membutuhkan pemenuhan beban WBP.
Tidak tersedianya gas alam (yang relatif murah harganya dibandingkan
dengan pemakaian minyak HSD sebagai bahan bakar) di Bali, tidak membuka
kemungkinan untuk mengoperasikan PLTGU sebagai penanggung beban dasar.
Kalau PLTGU Pemaron dioperasikan sebagai penanggung beban dasar, maka
impor energi murah dari Jawa perlu dikurangi.
Ini akan meningkatkan fungsi sasaran. Mengurangi pembangunan PLTGU
menjadi PLTG akan menghemat biaya pembangunan sekitar 30 juta dollar AS.
Karena itu, unsur PLTU dari PLTGU yang tak diperlukan Bali, dapat dialihkan ke
wilayah lain yang lebih mendesak kebutuhannya, tapi juga ada gas alamnya, di
Sumatera Selatan misalnya.
Kesalahan kedua, pilihan lokasi yang jauh dari pusat beban mengakibatkan
adanya tambahan biaya angkutan (minyak diangkut dari selatan terminal BBM
Manggis ke utara/Pemaron) dan susut jaringan listrik akibat penyaluran energi
listrik, dibangkitkan di utara/ Pemaron untuk kemudian dikirim ke pusat beban di
selatan Bali.
Seringnya terjadi Pemadaman Listrik bergilir berdampak pada
terganggunya kegiatan produksi bagi para pemilik usaha kecil dan menengah.
Kebutuhan listrik yang tinggi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tak seimbang
dengan jumlah pasokan listrik yang tersedia. Sehingga dapat diprediksi sejumlah
wilayah di Indonesia, masih akan mengalami pemadaman listrik bergilir hingga
tahun 2010 mendatang. Ini terjadi karena Perusahaan Listrik Negara PLN
mengalami defisit akibat tidak seimbangnya pasokan yang dimiliki PLN dengan
permintaan masyarakat. Untuk di Provinsi Bali pemadaman listrik kerap terjadi
9

dan untuk meminimalisir krisis listrik tersebut khususnya di Bali, PLN melalui
PT. Indonesia Power akan mendatangkan mesin diesel untuk menambah pasokan
listrik sebesar 45 megawatt yang nantinya akan mencover seluruh Kabupaten di
Bali dan dipusatkan di PT. Indonesia Power di Desa Pemaron, Kabupaten
Buleleng. Lebih jauh antonius mengungkapkan untuk di Bali ada tiga lokasi
pembangkit listrik yaitu di Denpasar, Gilimanuk, dan Buleleng dan untuk
penambahan kapasitas dipusatkan di Pembangkit Listrik di Desa
Pemaron,Buleleng. Dengan akan bertambahnya kapasitas listrik di Bali,
diharapkan kebutuhan-kebutuhan listrik di Bali termasuk antrian dari masyarakat
untuk mendapatkan listrik yang mencapai 56 ribu daftar tunggu di seluruh Bali
akan bisa segera terealisasi secara bertahap di tahun 2010 dan target
pengoperasiannya akan mulai dilaksanakan di bulan Agustus 2010. Untuk
mendukung power dari kapasitas pasokan listrik, PLN akan merencanakan
mendatangkan gas yang juga akan dipusatkan di Desa Pemaron, Buleleng
sehingga nantinya pembangkit listrik akan ramah lingkungan dan yang terpenting
adalah akan mampu menghemat biaya pengeluaran karena tidak lagi
menggunakan BBM melainkan menggunakan gas dan menekan biaya produksi.
Pihak pengelola PLTGU Pemaron, PT Indonesia Power belum
mendapatkan kesepakatan dengan PT PLN mengenai harga beli listrik yang nanti
dihasilkan pembangkit listrik tersebut. Akibatnya sejak dibangun 2003 hingga saat
ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pemaron belum bisa
dioperasionalisasikan.
Kepala Unit PLTGU Pemaron Gede Nurija di sela-sela penyerahan
bantuan community development tahap II tahun 2005 sebesar Rp 75 juta di kantor
Desa Pemaron mengatakan Indonesian Power dan PLN saat ini tengah berupaya
melakukan kesepakatan mengenai harga listrik itu. Menurutnya belum sepakatnya
harga listrik itu tidak ada hubungannya dengan kenaikan harga BBM. Pengelola
PLTGU Pemaron, sebutnya, berencana mengganti bahan bakar pembangkit listrik
yang selama ini menggunakan solar. "Saat ini baru dalam tahap survai untuk
mempergunakan bahan bakar gas yang akan diambil dari Sulawesi," jelasnya.
10

Ditambahkan, selama ini pihaknya hanya mengoperasionalisasikan dua
unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang menghasilkan listrik 96
megawatt. Listrik yang dihasilkan itu didistribusikan ke seluruh Bali bersama
pembangkit listrik dari Jawa dan Gilimanuk. Bila PLTU telah
dioperasionalisasikan, kapasitas listrik yang dihasilkan akan bertambah 50
megawatt.
Sementara, penyerahan bantuan community development dilakukan
Manager Humas PT Indonesia Power Unit Pembangkit Listrik Bali, I Gusti Arya
Dirawan, yang diterima secara simbolis oleh Kepala Desa Pemaron Putu Ariana.
Bantuan itu diberikan secara rutin setiap tahun di beberapa wilayah di Buleleng.
Penyerahannya dilakukan dua tahap sekitar Juni dan November-Desember. Pada
tahap I sudah diserahkan bantuan Rp 50 juta.
Berbagai Kemungkinan Ganguan Pasokan Listrik Bali
Ada 5 kemungkinan gangguan pembangkit listrik di Bali atau gangguan
pasokan dari Jawa, yaitu:
1. Terputusnya 2 (dua) Kabel bawah laut di Gilimanuk,
Jika gangguan ini terjadi oleh satu dan lain hal, maka pasokan
listrik Bali akan menjadi sebesar 241 MW ( 421 MW - 180 MW). Dan
karenanya akan terjadi pemadaman sebesar 84 MW khusus pada malam
hari saja ( 325 - 241 MW). Sementara pada siang hari pasokan listrik
masih aman, karena beban puncak siang hari hanya sebesar 210 MW.
2. Terputusnya 1 (satu) Kabel Bawah laut di Gilimanuk,
Dengan gangguan hanya 1 Kabel bawah laut, maka dampaknya
lebih ringan. Pasokan listrik Bali menjadi sebesar 331 MW (421 MW - 90
MW). Dengan beban puncak malam hari masih sebesar 325 MW, maka
pasokan listrik Bali di malam hari masih aman 6 MW, walaupun sangat
kritis.
11

3. PLTG Gilimanuk (120 MW) terganggu,
Terganggunya PLTG Gilimanuk atau tidak beroperasi karena
'overhaul' menyebabkan pasokan listrik Bali berkurang sebesar 120 MW.
Jumlah listrik yang bisa dipasok PLN akan menjadi 301 MW (421 MW -
120 MW ). Keadaan ini menyebabkan layanan listrik Bali khusus untuk
malam hari harus dikurangi sebanyak 24 MW (325 MW - 301 MW).
4. PLTG Pesanggaran (80 MW) terganggu,
Gangguan di PLTG Pesanggaran mengakibatkan Bali kehilangan
pasokan listrik sebesar 80 MW. Kemampuan PLN Distribusi Bali
melayani beban malam hari menjadi 341 MW (421 MW - 80 MW). Jika
dibandingkan dengan beban puncak malam hari, maka jumlah ini masih
mencukupi dan sedikit lebih sebesar 16 MW.
Kemungkinan pemadaman tetap ada mengingat terbatasnya saluran
transmisi dari GI Gilimanuk ke GI Kapal. Transmisi melalui Gardu Induk
(GI) Gilimanuk ke GI Kapal hanya terbatas sampai 200 MW, sehingga
daya sebesar 300 MW dari Bali Barat harus disalurkan melalui GI
Pemaron- GI Baturiti-GI Kapal sebesar 100 MW.
Kondisi seperti ini menunjukkan, bahwa perencanaan lokasi PLTG
di Gilimanuk ternyata salah, yaitu kurang memperhatikan kemungkinan
gangguan di PLTG Pesanggaran dan terbatasnya saluran transmisi GI
Gilimanuk-GI Kapal. Pasokan listrik untuk Bali terlalu mengandalkan Bali
Barat, dimana semestinya sebagian pasokan diperlukan dari Bali Timur.
5. PLTD Pesanggaran (41 MW) terganggu,
Terganggunya PLTD Pesanggaran hanya menyebabkan kehilangan
pasokan sebesar 41 MW. Jumlah ini belum signifikan mengganggu
pasokan listrik di Bali.
12

Dari 5 kemungkinan gangguan terhadap sistem pasokan listrik Bali,
nampak bahwa yang paling berat adalah bila serentak/sekaligus 2 buah Kabel
bawah laut terganggu (lihat Tabel).
Tabel Kemungkinan jenis gangguan dan besarnya pemadaman pada tingkat beban
325 MW.
Jenis Gangguan Dampak
2 (dua) Kabel bawah laut Pemadaman 84 MW
1 (satu) Kabel bawah lau Hanya tersisa 6 MW
PLTGU Gilimanuk Pemadaman 24 MW
PLTGU Pesanggaran
PLTD Pesanggaran
Tersisa 16 MW
Masih aman
Alternatif Penambahan Pasokan Listrik Bali
Melalui analisa yang telah dikemukakan tersebut, beberapa alternatif solusi
pengamanan pasokan listrik Bali dapat disampaikan sebagai berikut:
1. PLN menawarkan PLTGU Pemaron, tetapi ternyata selama 2 tahun ini
rencana lokasi penempatan PLTGU di Pemaron telah menuai perlawanan
yang keras dari masyarakat setempat sebagaimana telah dijelaskan di awal
tulisan ini. Melihat, bahwa PLN hanya merelokasi PLTG Tanjung Priok
yang berkapasitas 100 MW tersebut dengan tambahan Turbin Uap 50
MW, maka solusi yang ditawarkan oleh PLN adalah solusi sementara, dan
bukan solusi jangka panjang. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik Bali
adalah 13 % setahun, maka praktis 3 tahun lagi tambahan pasokan 150
MW ini akan terlampaui. Berarti Bali harus lagi memikirkan pembangkit
listrik yang baru, dan itu berarti Bali siap-siap memulai babak baru pro-
kontra pembangunan pembangkit listrik. Dengan demikian, solusi relokasi
PLTG Tanjung Priok ini adalah solusi jangka pendek (2-3 tahun).
Ketika merencanakan PLTGU di Pemaron, PLN hanya
memikirkan kepentingan sektoral tanpa berempati kepada masyarakat
yang sudah menolak lokasi tersebut. Rencana pembangunan PLTGU
13

Pemaron jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan perundangan
(PERDA No.4/1999 dan UU Ketenagalistrikan no.20/2002, Pasal 5,9,10
dan 11), karena itu ditolak oleh sebagian masyarakat dan izin
pembangunan dan izin operasinya berpotensi dibatalkan.
Rencana pembangunan PLTGU dengan pilihan lokasi di Pemaron
bukan merupakan solusi yang memecahkan sebuah masalah, tapi justru
menyebabkan timbulnya masalah baru.
2. Dengan menerapkan semangat 'win-win solution' atau dalam istilah bahasa
Bali 'apang pade payu',solusi jangka pendek berupa pemindahan PLTG
Tanjung Priok tersebut masih bisa diterima, mengingat PLN maupun
negara Indonesia sedang dalam kesulitan keuangan. Tetapi LOKASI
jangan di Pemaron. Pemasangan 2 buah Turbin Gas General Electric dari
Tanjung Priok sebesar 2 x 50 MW = 100 MW sebenarnya sudah dapat
mengamankan pasokan listrik di Bali, sekalipun 2 saluran Kabel bawah
laut di Gilimanuk terganggu. Dalam Tabel diatas telah dikemukakan,
bahwa akibat terganggunya 2 saluran kabel bawah laut hanya
menyebabkan pemadaman sebesar 84 MW. PLTG ini dapat dipasang di GI
Amlapura, yang jaraknya hanya 15 km dari Depo Minyak Pertamina di
Manggis. PLTG ini juga bisa dipasang di GI Gianyar atau bahkan di GI
Pesanggaran.
Alternatif ini juga bisa digolongkan sebagai rencana jangka pendek
(1-2 tahun).
3. UU Ketenagalistrikan no. 20/2002, Pasal 5 berbunyi: (1) Pemerintah
Daerah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Pasal ini
membuka peluang pemerintah daerah memanfaatkan 'captive power'
(sebagai asset regional) untuk ikut berperan serta memenuhi kebutuhan
listrik Bali secara terintegrasi dengan pasokan PLN.
Masalahnya barangkali adalah bagaimana mengatur mengenai
kesepakatan harga jual beli listrik antara PLN dan pemilik captive power.
14

PLN selama ini yang berkewajiban memberi pasokan listrik/menjual
listriknya ke masyarakat, dapat saling tukar menukar energi dengan
pemilik captive power. Pada saat PLN kekurangan pasokan, captive power
memasok listrik ke PLN, dan kemudian ketika pasokan PLN mencukupi,
PLN membayar kembali dalam jumlah KHW yang telah dipakainya.
Untuk keperluan tukar menukar energi ini perlu pemasangan 'relais' dan
KWH Meter di kedua sisi serta penyusunan PERDA tentang hal ini.
Alternatif ini dapat digolongkan sebagai rencana jangka pendek (1-2
tahun).
4. Alternatif berikutnya adalah pembangunan saluran udara transmisi 500 kV
Jawa-Bali melintasi Selat Bali dengan panjang bentangan 3,7 km dan
tinggi menara sekitar 300 meter. Proyek ini sebenarnya sudah ada studi
serta desainnya, sudah siap hendak mulai dibangun pada akhir 1990-an.
Proyek ini merupakan solusi jangka panjang yang termurah, karena Bali
akan dapat memanfaatkan sumberdaya energi berskala besar dari PLTU
Batubara di Jawa. Untuk proyek ini hanya diperlukan waktu sekitar 5
tahun. Alternatif ini bisa dikelompokkan sebagai rencana jangka
menengah (5-6 tahun).
5. Alternatif jangka panjang adalah menciptakan budaya hemat energi,
dengan menggunakan lampu hemat energi. Pengawasan penggunaan
peralatan listrik lainnya yang hemat energi akan dapat mengurangi
pemakaian listrik. Selain itu listrik merupakan teknologi yang mudah
diatur: dimatikan pada saat tidak diperlukan (switch off) dan dinyalakan
hanya bila benar-benar diperlukan (switch on), juga akan berdampak pada
pengurangan pemakaian listrik. Budaya switch off/switch on yang
digalakkan secara gencar melalui kampanye seperti Keluarga Berencana,
bukan saja menghemat pemakaian bahan bakar, tetapi juga mengurangi
susutnya mesin pembangkit, dan memperlama umur produktif mesin.
Selain penghematan yang bisa dicapai, upaya tersebut juga dapat
15

mengurangi tingkat polusi dan besarnya dana investasi untuk membiayai
pembangkitan baru. Upaya meningkatkan disiplin serta budaya hemat
energi harus segera dimulai dari sektor rumah tangga, komersiil dan
pemerintahan.
16