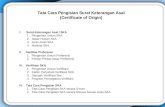Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
Transcript of Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
1/66
PERBEDAAN KADAR SGOT PADA SINDROM KLINIS
PENYAKIT SINDROM KORONER AKUT
DI RSD. DR. SOEBANDI JEMBER
OlehIzzatul Mufidah Mahayyun
NIM 122010101015
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
2/66
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
3/66
iii
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, skripsi ini saya persembahkan untuk:
1. Allah SWT atas sifat rahman dan rahim serta hidayah-Nya dalam setiap
perjalanan hidup yang saya lalui;
2. Umik dan abi tercinta, Dra. Gumul Isnaningsih dan Drs. Sumadi, serta adik
saya Kafi Hannan Al Hadi.
3. Guru-guru saya yang telah memberikan ilmu dan pendidikan sejak dari taman
kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Kedokteran Universitas Jember.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
4/66
iv
MOTO
“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan
petunjuk.”
(Terjemahan Q.S. Ad Duha 7)
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Terjemahan Q.S. Al Insyirah 5-7)
“Untuk siapa diriku saat ini dan harapanku di masa depan, aku berhutang pada ibu,
malaikatku.”
(Abraham Lincoln)
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
5/66
v
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
nama : Izzatul Mufidah Mahayyun
NIM : 122010101015
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Perbedaan Kadar
SGOT pada Sindrom Klinis Penyakit Sindrom Koroner Akut di RSD. dr. Soebandi
Jember” adalah benar -benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan
substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada institusi manapun, serta
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya
sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.
Jember, Desember 2015
Yang menyatakan,
Izzatul Mufidah Mahayyun
NIM 122010101015
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
6/66
vi
SKRIPSI
PERBEDAAN KADAR SGOT PADA SINDROM KLINIS
PENYAKIT SINDROM KORONER AKUT
DI RSD. DR. SOEBANDI JEMBER
Oleh:
Izzatul Mufidah Mahayyun
NIM 122010101015
Pembimbing
Dosen Pembimbing Utama : dr. Hairrudin, M. Kes
Dosen Pembimbing Anggota : dr. Rini Riyanti, Sp. PK.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
7/66
vii
PENGESAHAN
Karya ilmiah skripsi berjudul “Perbedaan Kadar SGOT pada Spektrum Klinis
Penyakit Sindrom Koroner Akut di RSD. dr. Soebandi Jember” telah diuji dan
disahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Jember pada :
Hari : Senin
Tanggal : 28 Desember 2015
Tempat : Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Tim Penguji:Penguji I, Penguji II,
dr. Suryono, Sp. JP. FIHA dr . Ika Rahmawati Sutejo, M. Biotech NIP 19691011 200003 1 001 NIP 19711019 199903 1 001
Penguji III, Penguji IV
dr. Hairrudin, M.Kes dr. Rini Riyanti, Sp. PK
NIP 19751011 200312 1 008 NIP 19720328 199903 2 001
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember
dr. Enny Suswati, M.Kes
NIP 19700214 199903 2 001
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
8/66
viii
RINGKASAN
Perbedaan Kadar SGOT pada Spektrum Klinis Penyakit Sindrom Koroner
Akut di RSD. dr. Soebandi Jember; Izzatul Mufidah Mahayyun, 122010101015;
2015; Fakultas Kedokteran Universitas Jember.
Sindrom Koroner Akut (SKA) adalah sebuah kondisi yang melibatkan
ketidaknyamanan dada, nyeri dada (chest pain), atau gejala lain yang disebabkan oleh
kurangnya oksigen ke otot jantung (miokardium). Sindrom Koroner Akut (SKA)
merupakan salah satu manifestasi klinis Penyakit Jantung Koroner (PJK) selainStable Angina (Angina Pektoris Stabil). Namun SKA memiliki prognosis yang lebih
buruk dibanding Angina Pektoris Stabil karena bersifat progresif dan pada perjalanan
penyakitnya sering terjadi perubahan secara tiba-tiba dari keadaan stabil menjadi
keadaan tidak stabil atau akut serta paling sering mengakibatkan kematian. Sindrom
klinis SKA terdiri dari angina pektoris tidak stabil (APTS) atau unstable angina
(UA), Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI), dan ST elevation
myocardial infarction (STEMI).
Mekanisme terjadinya SKA disebabkan oleh proses pengurangan pasokan
oksigen akut atau subakut dari miokard, yang dipicu oleh adanya robekan plak
aterosklerotik dan berkaitan dengan adanya proses inflamasi, trombosis,
vasokonstriksi, dan mikroembolisasi yang berujung pada infark miokard. Infark pada
miokard menyebabkan dikeluarkannya enzim-enzim yang menjadi penanda
biokimiawi jantung, salah satunya adalah enzim transaminase SGOT. Enzim ini tidak
spesifik jantung tetapi meningkat kadarnya pada infark miokard sehingga dapat
terdeteksi dalam sirkulasi. Oleh karena itu, perlu diketahui berapakah kadar SGOT
pada sindrom klinis SKA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar SGOT
yang terjadi pada masing-masing sindrom klinis SKA tersebut. Hasil penelitian
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi
masyarakat, sehingga dapat mengatur pola hidup untuk menghindari serangan jantung
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
9/66
ix
yang merupakan manifestasi SKA dan menjadi pedoman untuk sarana diagnostik
biomarker SKA dalam melaksanakan tindakan prevensi yang tepat sehingga insidensi
kematian karena SKA dapat diturunkan.
Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan desain
studi cross sectional . Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari rekam
medis pasien SKA yang terdapat pada RSD. dr. Soebandi Jember pada bulan
Agustus-Oktober 2015. Data diambil dari Ruang Rekam Medis Rawat Inap RSD. dr.
Soebandi Jember dan menghasilkan 16 sampel untuk masing-masing kelompok (UA,
NSTEMI, dan STEMI). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
komparatif non parametrik Kruskal-Wallis dengan analisis Post Hoc menggunakan
uji Mann-Whitney.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok UA, kadar SGOT masih
berada pada rentang nilai normal dengan rata-rata sebesar 27,50 ±9,675 U/L. Berbeda
dengan rata-rata kadar SGOT pada kelompok NSTEMI dan STEMI yang
menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 65,88 ±39,007 U/L dan 162,38
±95,759 U/L. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan nilai signifikansi
p=0,000
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
10/66
x
PRAKATA
Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya tercurahkan kepada Allah
SWT yang telah memberikan kasih sayang dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbedaan Kadar SGOT pada Spektrum Klinis
Penyakit Sindrom Koroner Akut di RSD dr. Soebandi Jember ”. Skripsi ini disusun
untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada
Fakultas Kedokteran Universitas Jember.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena
itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. dr. Enny Suswati, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember;
2. dr. Hairrudin, M.Kes selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan
kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam penelitian beliau, serta dr. Rini
Riyanti, Sp. PK selaku Dosen Pembimbing Anggota yang keduanya telah
meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan perhatiannya dalam penulisan tugas
akhir ini;
3. dr. Suryono, Sp. JP. FIHA dan dr. Ika Rahmawati Sutejo, M. Biotech sebagai
dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam
penulisan tugas akhir ini;
4. Umik dan abi tercinta Dra. Gumul Isnaningsih dan Drs. Sumadi yang senantiasa
memberikan dukungan berupa ilmu, doa, dan curahan kasih sayang kepada saya
untuk tetap semangat melanjutkan apa yang sudah saya jalani;
5. Adik lelaki saya satu-satunya, Kafi Hannan Al Hadi yang selalu setia
mengobarkan semangat lewat tindakan dalam diamnya;
6. Kelompok penelitian besar, yaitu dr. Suryono, Sp. JP. FIHA.; dr. Hairrudin,
M.Kes; Dr. drg. IDA Susilawati, M. Kes; Della, Rizki, Rediana, dan Galih,
terima kasih atas kesempatan, kerjasama, bantuan, doa, serta semangat yang
diberikan selama penyelesaian penelitian dan skripsi ini;
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
11/66
xi
7. Keluarga besar IMSAC FK UJ, terima kasih untuk telah menjadi wadah
menimba ilmu dan ukhuwah deretan saudara sesurga;
8. Angkatan 2012 FK UJ Panacea, saudara-saudara saya yang keberadaannya selalu
dapat mencairkan suasana;
9. Kelompok KKN PPM 01 saya di Desa Ngampelrejo, yang telah menemani,
berbagi ilmu, dan kekompakan selama dua bulan lebih lamanya. Terima kasih
telah memberi arti akan sebuah keluarga;
10. Kepengurusan BEM Kabinet PHP yang kompaknya tiada duanya, terima kasih
untuk momen-momen dalam waktu yang berharga;
11. Analis Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Mbak
Nuris, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian tugas akhir ini;
12. Perawat-perawat ICCU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih
atas kesabaran dan bantuannya dalam proses penelitian selama ini;
13. Bagian ruang rekam medis rawat inap RSD. dr. Soebandi Jember atas
bantuannya dalam pengambilan data rekam medis pasien;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak
demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.
Jember, Desember 2015
Penulis
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
12/66
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL ..................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... iii
HALAMAN MOTO ......................................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................... v
HALAMAN PEMBIMBINGAN ..................................................................... vi
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... vii
RINGKASAN ................................................................................................... viii
PRAKATA ........................................................................................................ x
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xvi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii
BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 3
1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................. 4
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................ 4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 5
2.1 Sindrom Koroner Akut .................................................................... 5
2.1.1 Definisi ........................................................................................ 5
2.1.2 Faktor Risiko ............................................................................... 5
2.1.3 Patofisiologi ................................................................................. 6
2.1.4 Unstable Angina (UA) ................................................................. 11
2.1.5 Non-ST Elevation Myocard Infark (NSTEMI) ............................ 13
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
13/66
xiii
2.1.6 ST Elevation Myocard Infark (STEMI) ....................................... 14
2.2 Serum Glutamic Oxaloacetic Tr ansaminase (SGOT) ...................... 15
2.2.1 Definisi ........................................................................................ 15
2.2.2 Peningkatan SGOT ...................................................................... 16
2.2.3 Metode Pemeriksaan SGOT ........................................................ 16
2.3 Kerangka Konsep Penelitian ............................................................ 20
2.4 Hipotesis ............................................................................................. 20
BAB 3. METODE PENELITIAN ................................................................... 21
3.1 Jenis Penelitian .................................................................................. 21
3.2 Rancangan Penelitian ....................................................................... 21
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ....................................................... 22
3.3.1 Populasi Penelitian ...................................................................... 22
3.3.2 Sampel Penelitian ........................................................................ 22
3.3.3 Besar Sampel ............................................................................... 23
3.3.4 Teknik Pengambilan Sampel ....................................................... 23
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................... 23
3.5 Variabel Penelitian ............................................................................ 24 3.5.1 Variabel Dependen ...................................................................... 24
3.5.2 Variabel Independen .................................................................... 24
3.6 Definisi Operasional .......................................................................... 24
3.6.1 SGOT ........................................................................................... 24
3.6.2 Pasien Sindrom Koroner Akut ..................................................... 24
3.6.3 Data Rekam Medis Pasien ........................................................... 24
3.7 Instrumen Penelitian ......................................................................... 25
3.8 Prosedur Kerja Penelitian ................................................................ 25
3.8.1 Mendapatkan Sampel Pasien SKA.. ............................................ 25
3.8.2 Teknik Perolehan Data Sampel SKA .......................................... 25
3.9 Pengambilan dan Analisis Data ....................................................... 25
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
14/66
xiv
3.9.1 Pengambilan Data.. ...................................................................... 25
3.9.2 Analisis Data................................................................................ 26
3.10 Alur Penelitian ................................................................................. 27
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................... 28
4.1 Hasil Penelitian ............................................................................. 28
4.1.1 Distribusi Pasien Sindrom Koroner Akut .............................. 28
4.1.2 Distribusi Jenis Kelamin Pasien Sindrom Koroner Akut ...... 29
4.1.3 Distribusi Usia Pasien Sindrom Koroner Akut...................... 30
4.1.4 Rata-Rata Kadar SGOT pada Spektrum Klinis SKA ............ 31
4.2 Analisis Hasil Penelitian ............................................................... 32
4.2.1 Uji Normalitas Data ............................................................... 32
4.2.2 Uji Kruskall-Wallis................................................................ 33
4.3 Pembahasan .................................................................................. 34
4.4 Keterbatasan Penelitian ............................................................... 38
BAB 5. PENUTUP ............................................................................................ 39
5.1 Kesimpulan.................................................................................... 39
5.2 Saran .............................................................................................. 39DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 40
LAMPIRAN ...................................................................................................... 44
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
15/66
xv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1 Stratifikasi kelompok sampel ............................................................. 26
Tabel 3.2 Check list penelitian ........................................................................... 24
Tabel 4.3 Hasil uji Kruskal-Wallis kadar SGOT pasien SKA ........................... 33
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
16/66
xvi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Proses aterosklerosis ...................................................................... 7
Gambar 2.2 Pembentukan plak hingga fatty streak .......................................... 9
Gambar 2.3 Kompleks inflamasi dalam aterosklerosis ...................................... 10
Gambar 2.4 Kerangka konsep penelitian ........................................................... 20
Gambar 3.1 Rancangan penelitian ..................................................................... 21
Gambar 3.2 Skema alur penelitian ..................................................................... 27Gambar 4.3 Penghitungan waktu peningkatan enzim jantung pada infark miokard
............................................................................................................................ 37
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
17/66
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sindrom Koroner Akut (SKA) adalah sebuah kondisi yang melibatkan
ketidaknyamanan dada, nyeri dada (chest pain), atau gejala lain yang disebabkan oleh
kurangnya oksigen ke otot jantung (miokardium). Lebih dari delapan juta pasien per
tahun datang dengan keluhan nyeri dada atau gejala penyerta lainnya yang
berhubungan dengan iskemik miokardial di departemen emergensi yang ada di
Amerika Serikat (Amsterdam et al., 2014). Mekanisme terjadinya SKA disebabkan
oleh proses pengurangan pasokan oksigen akut atau subakut dari miokard, yang
dipicu oleh adanya robekan plak aterosklerotik dan berkaitan dengan adanya proses
inflamasi, trombosis, vasokonstriksi, dan mikroembolisasi dengan manifestasi dapat
berupa angina pektoris tidak stabil (APTS) atau unstable angina (UA), Non-ST
elevation myocardial infarction (NSTEMI), dan ST elevation myocardial infarction
(STEMI) (Depkes, 2008). Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan salah satu
manifestasi klinis Penyakit Jantung Koroner (PJK) selain Angina Pektoris Stabil
(Stable Angina). Namun SKA memiliki prognosis yang lebih buruk dibanding
Angina Pektoris Stabil karena bersifat progresif dan pada perjalanan penyakitnya
sering terjadi perubahan secara tiba-tiba dari keadaan stabil menjadi keadaan tidak
stabil atau akut serta paling sering mengakibatkan kematian (Morrow, 2010).
Penyakit Jantung Koroner (PJK) atau penyakit kardiovaskular saat ini
merupakan salah satu penyebab utama dan pertama kematian di negara maju dan
berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit jantung koroner menyumbang 47,7% dari
seluruh kematian akibat penyakit kardiovaskular di Amerika pada tahun 2011 ( Heart
Disease and Stroke Statistics, 2015). Mackay dan Mensah (2004) menyatakan bahwa
beban PJK secara global diproyeksikan akan meningkat dari sekitar 47 juta kejadian
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
18/66
2
pada tahun 1990 hingga menjadi 82 juta pada tahun 2020 dan lebih dari 60% beban
global PJK terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Diperkirakan
bahwa diseluruh dunia, PJK pada tahun 2020 menjadi pembunuh pertama tersering
yakni sebesar 36% dari seluruh kematian. Angka ini dua kali lebih tinggi dari angka
kematian akibat kanker. Di Indonesia dilaporkan PJK (yang dikelompokkan menjadi
penyakit sistem sirkulasi) merupakan penyebab utama dan pertama dari seluruh
kematian, yakni sebesar 26,4%, angka ini empat kali lebih tinggi dari angka kematian
yang disebabkan oleh kanker (6%). Dengan kata lain, lebih kurang satu diantara
empat orang yang meninggal di Indonesia adalah akibat PJK. Berdasarkan diagnosis
dokter atau gejala, penderita PJK pada tahun 2013 di Indonesia sebesar 1,5% atau
diperkirakan sekitar 2.650.340 orang, dengan jumlah terbanyak berada pada Provinsi
Jawa Timur sebesar 375.127 orang (Riset Kesehatan Dasar, 2013)
Penyakit jantung yang melibatkan pembuluh koroner akan menghasilkan
penanda biokimiawi. Penanda biokimiawi jantung tersebut akan dilepaskan dari otot
jantung ketika terjadi kerusakan akibat infark miokard. Infark miokard ditandai
dengan pelepasan enzim-enzim maupun petanda-petanda spesifik jantung lain yang
terdapat pada sel otot jantung yang mengalami nekrosis. Enzim-enzim yang
dilepaskan termasuk juga enzim transaminase yaitu SGOT.
Serum Glutamate Oxaloacetate Transaminase (SGOT) merupakan enzim
yang terutama ditemukan pada otot jantung dan hati. Enzim ini didefinisikan sebagai
penanda biokimia untuk diagnosis infark miokard akut pada tahun 1954. Enzim ini
tidak spesifik jantung tetapi meningkat kadarnya pada infark miokard sehingga dapat
terdeteksi dalam sirkulasi. Kadar SGOT dapat meningkat secara signifikan pada gagal
jantung kongestif akut dan/atau infark miokard, dimana peningkatannya berkisar
antara tiga sampai sepuluh kali dari nilai normal. Kadar SGOT dapat kembali normal
tetapi biasanya tidak akan kembali normal secepat SGPT (Ronald dan Grisanti,
2001).
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
19/66
3
Berdasarkan fakta bahwa SKA terkait dengan peningkatan kadar SGOT dalam
darah, maka penulis tertarik untuk meneliti “Perbedaan Kadar SGOT pada Spektrum
Klinis Penyakit SKA di RSD dr. Soebandi Jember ”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar SGOT pada masing-masing spektrum
klinis SKA yaitu UA, NSTEMI, dan STEMI. Sehingga harapannya di akhir seluruh
penelitian, SGOT dapat dijadikan sebagai salah satu acuan diagnostik biomarker
selain troponin pada penderita SKA agar tidak jatuh pada kondisi yang semakin parah
sehingga insidensi kematian karena SKA dapat diturunkan. Sebab pemeriksaan
SGOT sudah tercakup dalam pemeriksaan darah lengkap yang hampir selalu
diperiksa pada pasien-pasien dengan penyakit dalam. Selain itu pula dari segi biaya,
pemeriksaan SGOT lebih murah dibandingkan dengan pemeriksaan troponin yang
masih merupakan pemeriksaan tersendiri karena bukan termasuk dalam pemeriksaan
darah lengkap. Sehingga dari segi biaya pemeriksaan, SGOT memiliki keunggulan
tersendiri dibandingkan dengan pemeriksaan troponin. Adapun alasan mengambil
RSD. dr. Soebandi Jember sebagai tempat penelitian karena rumah sakit ini
merupakan rumah sakit pendidikan tipe B dari Fakultas Kedokteran Universitas
Jember yang lokasinya mudah dijangkau untuk mengadakan survei pada penderita
SKA. Rumah sakit ini juga menjadi pusat rujukan medis untuk wilayah Jember.Selain
itu, saat ini juga merupakan era BPJS dimana pasien-pasien banyak dirujuk ke rumah
sakit daerah agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah
apakah ada perbedaan kadar SGOT pada spektrum klinis penyakit Sindrom Koroner
Akut di RSD. dr. Soebandi Jember?
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
20/66
4
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui adanya perbedaan kadar SGOT pada spektrum klinis penyakit Sindrom
Koroner Akut di RSD. dr. Soebandi Jember.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk dinas kesehatan dan institusi
kesehatan terutama RSD. dr. Soebandi Jember dalam mendukung pengambilan
kebijaksanaan bidang kesehatan.
2. Sebagai pedoman untuk sarana diagnostik biomarker SKA dan melaksanakan
tindakan prevensi yang tepat sehingga insidensi kematian karena SKA dapat
diturunkan.
3. Menjadi dasar bagi institusi untuk pengembangan penelitian selanjutnya,
khususnya pada bidang kardiovaskular;
4. Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, sehingga
dapat mengatur pola hidup untuk menghindari serangan jantung yang merupakan
manifestasi SKA;
5. Memberikan sumbangan informasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran (IPTEKDOK) khususnya tentang perbandingan peningkatan SGOT
pada kejadian SKA.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
21/66
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sindrom Koroner Akut (SKA)
2.1.1 Definisi
Sindrom Koroner Akut (SKA) adalah sebuah kondisi yang melibatkan
ketidaknyamanan dada, nyeri dada (chest pain), atau gejala lain yang disebabkan oleh
kurangnya oksigen ke otot jantung (miokardium). Sindrom ini merupakan kumpulan
gejala yang mengacu pada spektrum presentasi klinis mulai dari penderita angina
tidak stabil atau unstable angina (UA), penderita infark miokard tanpa elevasi
segmen ST atau Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI), hingga penderita
infark miokard dengan gambaran elevasi segmen ST atau ST elevation myocardial
infarction (STEMI). Hal ini hampir selalu dikaitkan dengan ruptur plak aterosklerotik
dan trombosis parsial atau lengkap dari arteri yang mengalami infark.
Sindrom Koroner Akut merupakan salah satu manifestasi klinis dari Penyakit
Jantung Koroner selain stable angina (angina stabil). Proses aterosklerosis dianggap
menjadi penyebab utama munculnya sindroma ini, dengan sebagian besar kasus
terjadi karena adanya gangguan dari lesi sebelumnya yang bersifat tidak parah.
Namun apabila lesi ini sudah menyebabkan aterosklerosis dan menyumbat arteri
koroner yang memasok darah dan oksigen ke sel-sel otot jantung maka dapat
menghasilkan manifestasi klinis Sindrom Koroner Akut (SKA), yang ditandai dengan
angina pectoris (nyeri dada), Infark Miokard Akut (IMA), atau bahkan kematian
mendadak (Price, 2002; Shah, 2003).
2.1.2 Faktor Risiko
Framingham Heart Study membagi faktor risiko terjadinya PJK menjadi tiga
macam, yaitu faktor risiko konvensional, faktor risiko yang dapat dimodifikasi, dan
faktor risiko non-tradisional. Faktor risiko konvensional terdiri atas: usia lebih dari 45
tahun pada pria dan lebih dari 55 tahun pada wanita, riwayat sakit jantung dini pada
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
22/66
6
keluarga dimana ayah atau saudara laki-laki didiagnosis mengalami sakit jantung
sebelum usia 55 tahun dan ibu atau saudara perempuan didiagnosis mengalami sakit
jantung sebelum usia 65 tahun, dan perbedaan ras. Faktor risiko yang dapat
dimodifikasi terdiri atas: kadar kolesterol darah tinggi, hipertensi, merokok, Diabetes
Mellitus, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, sindrom metabolik, stress, dan depresi.
Sedang faktor risiko non-tradisional terdiri atas: peningkatan kadar CRP di darah,
peningkatan lipoprotein-a, peningkatan homosistein, aktivator plasminogen jaringan,
fibrinogen, dan berbagai faktor lain seperti end-stage renal disease (ESRD), penyakit
inflamasi kronik yang mempengaruhi jaringan ikat seperti lupus, rheumatoid arthritis,
infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency
Syndrome (AIDS), dan Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART). Sebagian
faktor risiko konvensional dan modifikasi disebut juga faktor risiko mayor. Referensi
lain mengatakan bahwa faktor risiko PJK diantaranya adalah tekanan darah, merokok,
lipid, diabetes mellitus, obesitas, dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung
(Supriyono, 2008).
2.1.3 Patofisiologi
Beberapa bukti menunjukan bahwa aterosklerosis adalah proses inflamasi
kronik yang menjadi penyebab utama terjadinya kelainan pembuluh darah pada
penyakit ini. Aterosklerosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti penebalan tunika
intima arteri ( sclerosis, penebalan) dan penimbunan lipid (athere, pasta) yang
mencirikan lesi yang khas. Penyakit aterosklerotik yang mempengaruhi arteri koroner
merupakan penyebab terpenting morbiditas dan mortalitas (Price dan Lorrain, 2006).
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
23/66
7
Gambar 2.1.Proses aterosklerosis (Sumber: Amsterdam et al., 2014)
Lesi aterosklerotik pada manusia biasanya terbentuk selama bertahun-tahun
dan tanpa gejala. Meskipun aterosklerosis ini bersifat kronis, namun adanya
komplikasi trombotik yang menjadi konsekuensi klinis dari penyakit ini dapat terjadi
tiba-tiba tanpa didahului keluhan secara klinis. Proses aterosklerosis meliputi
beberapa tahap:
1. Endothelial Dysfunction (tidak berfungsinya endotel)
Banyak penelitian mengatakan bahwa perlukaan pada endotel arteri
merupakan awal permulaan terbetuknya aterosklerosis. Pada keadaan normal sel
endotel akan menghasilkan enzim NO (nitric oxide) yang berguna sebagai
endogen vasodilator, mencegah agregasi trombosit, dan antiinflamasi. Selain itu
sel endotel juga menghasilkan enzim antioksidan.
Endotel dapat mengalami disfungsi diakibatkan oleh paparan agen toksik
dari bahan kimia lingkungan. Contoh: asap rokok, kadar lipd yang abnormal di
dalam sirkulasi, atau karena penyakit diabetes. Semua itu diketahui sebagai
faktor resiko aterosklerosis.
Beberapa faktor fisik dan kimia akan mempengaruhi fungsi dari endotel
dengan manifestasi:
1. Melemahnya barier pertahanan endotel.
2. Keluarnya sitokin inflamasi
3. Meningkatnya perlengkatan molekul
4. Berubahnya substansi vasoaktif (prostasiklin dan NO)
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
24/66
8
2. Lipoprotein Entry and Modification (masuknya lipoprotein dan terjadinya
perubahan)
Lipoprotein adalah suatu lemak pengangkut di aliran yang tidak larut air
dan di sekelilingnya terdapat banyak hidrophilic phospolipid , kolesterol bebas,
dan lipoprotein. Ada 5 kelas dari lipoprotein:
1. Kilomikron
2. VLDL (Very-Low Density Lipoprotein)
3. IDL (Intermediate Density Lipoprotein)
4. LDL (Low-Density Lipoptein)
5. HDL (High-Density Lipoprotein)
Ketika sel endotel mengalami disfungsi, hal ini menyebabkan
ketidakefektifan yang dapat menyebabkan lipoprotein lebih lama dalam aliran
darah. Oksidasi adalah tipe yang pertama dari perubahan dari LDL di ruang
subendotel. Perubahan efek biokimia tersebut menyebabkan perubahan LDL
menjadi mLDL. Perubahan ini akan menarik sel monosit kedalam dinding sel
sikulasi dan kemudian mLDL akan memacu endotel untuk menghasilkan
mediator inflamasi.
3. Recruitment of Leukocytes (Penarikan Leukosit)
Proses masuknya dan perubahan biokimia LDL adalah kunci dari proses
aterogenesis yang mencakup melekatnya leukosit, terutama adalah monosit dan
limfosit T di dalam dinding sel pembuluh darah. Setelah monosit melekat dan
masuk ke ruang subendotel, monosit berubah menjadi makrofag, agar mampu
memfagosit dan memakan dari modifikasi LDL (mLDL). Namun hal ini akan
merubah LDL menjadi foam cell dan hal ini merupakan awal terbentuknya
komponen aterosklerosis yang disebut fatty streak .
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
25/66
9
Gambar 2.2. Pembentukan plak hingga fatty streak (Sumber: Willerson, 2007)
4. Migration of Smooth Muscle Cells (Migasi Sel Otot Polos)
Makrofag yang teraktivasi melepaskan zat-zat kemoatraktan dan sitokin
(misalnya monocyte chemoattractant protein-1, tumor necrosis factor a, IL-1,
IL-6, CD40, dan c-reactive protein) yang makin mengaktifkan proses ini dengan
merekrut lebih banyak makrofag, sel T, dan sel otot polos pembuluh darah (yangmensintesis komponen matriks ekstraseluler) pada tempat terjadinya plak. Sel
otot polos pembuluh darah bermigrasi dari tunika media menuju tunika intima,
lalu mensintesis kolagen, membentuk kapsul fibrosis yang menstabilisasi plak
dengan cara membungkus inti lipid dari aliran pembuluh darah. Makrofag juga
menghasilkan matriks metalloproteinase (MMPs), enzim yang mencerna matriks
ekstraseluler dan menyebabkan terjadinya disrupsi plak.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
26/66
10
Gambar 2.3. Kompleks inflamasi sitokin yang berasal dari berbagai komponen
seluler (makrofag, sel otot polos, trombosit, sel endotel, sel dendritik,
limfosit T, dan sel mast) memainkan peran dalam inisiasi dan
perkembangan aterosklerosis (Sumber: Willerson, 2007).
Stabilitas plak aterosklerosis bervariasi. Perbandingan antara sel otot polos
dan makrofag memegang peranan penting dalam stabilitas plak dan
kecenderungan untuk mengalami ruptur. LDL yang termodifikasi meningkatkan
respons inflamasi oleh makrofag. Respons inflamasi ini memberikan umpan
balik, menyebabkan lebih banyak migrasi LDL menuju tunika intima. Makrofag
yang terstimulasi akan memproduksi matriks metaloproteinase yang
mendegradasi kolagen. Di sisi lain, sel otot pembuluh darah pada tunika intima
yang membentuk kapsul fibrosis, merupakan subjek apoptosis. Jika kapsul
fibrosis menipis, ruptur plak mudah terjadi, menyebabkan paparan aliran darah
terhadap zat-zat trombogenik pada plak. Hal ini menyebabkan terbentuknya
bekuan (Myrtha, 2012).
Ruptur plak aterosklerotik merupakan tahapan kritis yang menentukan
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
27/66
11
timbulnya manifestasi SKA, seperti angina pektoris, IMA, infark serebral dan
sudden death (Shah, 2003; Gough dkk., 2006). Tahap kritis terjadinya IMA
adalah terjadinya ruptur plak aterosklerotik yang disusul dengan pembentukan
trombus. Kombinasi dari kedua kejadian tersebut dapat menghasilkan oklusi
total atau subtotal dari sirkulasi koroner, perluasan dan durasi oklusi menentukan
derajad iskemia miokard dan ini menentukan gejala klinisnya. Jadi tidak semua
ruptur dan pembentukan trombus mengakibatkan manifestasi klinis IMA. Ruptur
plak aterosklerotik menjadi penyebab SKA karena memicu trombosis. Bila
trombosis menyebabkan oklusi pembuluh darah dan terjadi pada pembuluh yang
memasok organ-organ vital seperti otak dan jantung, akan menyebabkan
iskhemia, stroke, infark serebral, IMA, bahkan kematian mendadak.
Sindrom Koroner Akut (SKA) sering terjadi berkaitan dengan
aterosklerosis. Bagian inti ateroma mengandung material timbunan lemak
terutama kolesterol, sedangkan bagian permukaannya diselubungi oleh lapisan
pelindung yang terutama tersusun oleh kolagen disebut fibrous caps. Apabila
terjadi injuri yang menyebabkan kerusakan fibrous cap, maka platelet akan
beragregasi diikuti aktivasi kaskade pembekuan darah sehingga terbentuk
trombus. Apabila trombus menyebabkan sumbatan pada pembuluh koroner,
dapat menimbulkan gangguan fungsi pompa dan irama jantung yang berakibat
fatal meskipun hanya terjadi dalam sekejap. Sehingga, manifestasi klinis akut
aterosklerosis terjadi apabila terdapat trombus oklusif sebagai akibat dari ruptur
plak.
2.1.4 Unstable Angina (Angina Pektoris Tidak Stabil)
Sindroma Angina Pektoris Tidak Stabil (APTS) telah lama dikenal sebagai
gejala awal dari Infark Miokard Akut (IMA). Banyak penelitian melaporkan bahwa
Unstable Angina merupakan risiko untuk terjadinya IMA dan kematian.Unstable
Angina memiliki istilah lain yang sering digunakan antara lain angina preinfark,
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
28/66
12
angina dekubitus, dan angina kresendo (angina dengan frekuensi dan durasi yang
semakin meningkat). Angina tipe ini merupakan spektrum dari sindrom iskemik
miokard akut yang berada di antara angina pektoris stabil ( stable angina) dan infark
miokard akut.
Terminologi Unstable Angina harus tercakup dalam kriteria penampilan klinis
sebagai berikut:
1. Angina pertama kali
Angina timbul pada saat aktifitas fisik. Baru pertama kali dialami oleh penderita
dalam priode satu bulan terakhir.
2. Angina progresif
Angina timbul saat aktifitas fisik dan pola timbulnya berubah dalam periode satu
bulan terkahir, yaitu menjadi lebih sering, lebih berat, lebih lama, timbul dengan
pencetus yang lebih ringan dari biasanya, dan tidak hilang dengan cara yang biasa
dilakukan. Penderita sebelumnya menderita angina pektoris stabil.
3. Angina waktu istirahat
Angina timbul tanpa didahului aktifitas fisik ataupun hal-hal yang dapat
menimbulkan peningkatan kebutuhan O2 miokard. Lama angina sedikitnya 15
menit.
4. Angina sesudah IMA
Angina yang timbul dalam periode dini (1 bulan) setelah IMA.
Kriteria penampilan klinis tersebut dapat terjadi per kriteria itu sendiri atau
bersamaan, dengan tanpa adanya gejala IMA. Nekrosis miokard yang terjadi pada
IMA harus disingkirkan dengan pemeriksaan enzim serial dan pencatatan EKG.
Gejala angina pektoris pada dasarnya timbul karena iskemik akut yang tidak menetap
akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai O2 miokard (Bahri, 2004).
Pada UA dan NSTEMI, pembuluh darah terlibat tidak mengalami oklusi total
sehingga dibutuhkan stabilisasi plak untuk mencegah progresi, trombosis, dan
vasokonstriksi. Angina pektoris tidak stabil dan NSTEMI mempunyai patogenesis
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
29/66
13
dan presentasi klinik yang sama, hanya berbeda dalam derajatnya. Bila ditemui
penanda biokimia nekrosis miokard (peningkatan troponin I, troponin T, atau
creatinin kinase CK-MB) maka diagnosis adalah NSTEMI. Sedangkan bila penanda
biokimia ini tidak meninggi atau meningkat namun tidak lebih dari 50% diatas nilai
normal, maka diagnosis adalah UA.
Untuk menyingkirkan adanya IMA, pada pasien terdiagnosis perlu dilakukan
pencatatan EKG saat serangan angina. Bila dilakukan pencatatan EKG saat istirahat
didapatkan hasil normal, harus dilakukan stress test dengan treadmill ataupun sepeda
ergometer. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah nyeri dada berasal dari jantung
atau tidak serta menilai beratnya penyakit. Gambaran EKG penderita UA dapat
berupa depresi segmen ST, depresi segmen ST disertai inversi gelombang T, elevasi
segmen ST, hambatan cabang ikatan His dan tanpa perubahan segmen ST, dan
gelombang T. Perubahan EKG pada UA bersifat sementara dan masing-masing dapat
terjadi sendiri-sendiri ataupun bersamaan. Perubahan tersebut timbul di saat serangan
angina dan kembali ke gambaran normal atau awal setelah keluhan angina hilang
dalam waktu 24 jam. Bila perubahan tersebut menetap setelah 24 jam atau terjadi
evolusi gelombang Q, maka disebut sebagai IMA.
2.1.5 Infark Miokard tanpa ST Elevasi (NSTEMI)
Non ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) secara umum
dibedakan dengan STEMI melalui refleksi gambaran infark miokard dan nekrosis
berdasarkan hasil EKG. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan luas
area yang mengalami infark dan juga perbedaan lokasi terjadinya obstruksi (Bode dan
Zirlik, 2007). Kerusakan area yang terjadi pada NSTEMI tidak seluas yang terjadi
pada STEMI karena gangguan suplai darah hanya bersifat parsial dan sementara.
NSTEMI didefinisikan berdasarkan ketinggian biomarker jantung tanpa adanya
elevasi segmen ST (Daga dkk, 2011). Biomarker yang sering dijadikan acuan adalah
troponin T dan troponin I karena lebih spesifik daripada enzim jantung yang lain.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
30/66
14
Peningkatan troponin pada daerah perifer terjadi setelah 3-4 jam dan dapat menetap
sampai 2 minggu.
NSTEMI dapat di sebabkan oleh penurunan suplai oksigen dan atau
peningkatan kebutuhan oksigen miokard yang diperberat oleh obstruksi koroner.
NSTEMI terjadi karena trombosis akut atau proses vasokonstriksi koroner.
Trombosis akut pada arteri koroner di awali dengan adanya ruptur plak yang tak
stabil. Plak yang tidak stabil ini biasanya mempunyai inti lipid yang besar, densitas
otot polos yang rendah, fibrous cap yang tipis, dan konsentrasi faktor jaringan yang
tinggi. Selain itu, terdapat faktor patofisiologi lain yang terjadi pada NSTEMI yaitu
adanya infalamasi vaskuler dan kerusakan pada ventrikel kiri (Harun dan Alwi,
2009).
NSTEMI sering terjadi pada orang tua yang telah memiliki penyakit jantung
dan non-jantung sebelumnya. Gambaran klinis yang tampak yaitu nyeri dada dengan
lokasi khas substernal atau kadangkala di epigastrium dengan ciri seperti diikat,
perasaan terbakar, nyeri tumpul, rasa penuh, berat atau tertekan. Selain itu juga
terdapat gejala tidak khas yang sering terjadi pada pasien yang berusia diatas 65 tahun
seperti dispneu, mual, diaforesis, sinkop, nyeri di lengan, bahu atas atau pun di leher.
2.1.6 Infark Miokard dengan ST-Elevasi (STEMI)
Infark miokard akut dengan elevasi ST (STEMI) merupakan merupakan salah
satu spektrum SKA yang paling berat (Kumar dan Cannon, 2009). Infark miokard
pada STEMI umumnya terjadi jika aliran darah koroner menurun secara mendadak
setelah oklusi trombus pada plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya. Oklusi
ini akan mengakibatkan berhentinya aliran darah (perfusi) ke jaringan miokard
(Firdaus, 2011). Diagnosis STEMI ditegakkan jika terdapat keluhan angina pektoris
akut disertai elevasi segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan.
Penilaian ST elevasi dilakukan pada J point dan ditemukan pada 2 sadapan yang
bersebelahan. Nilai ambang elevasi segmen ST untuk diagnosis STEMI untuk pria
dan perempuan pada sebagian besar sadapan adalah 0,1 mV. (PERKI, 2015).
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
31/66
15
Selain itu pemeriksaan enzim jantung berupa peningkatan cardiac spesific
troponin (cTn) dan CK-MB dapat memperkuat diagnosis meskipun tidak perlu
menunggu hasil pemeriksaan enzim untuk melakukan terapi. Peningkatan nilai enzim
diatas 2 kali nilai batas atas normal menunjukkan adanya nekrosis jantung (infark
miokard) cTn harus digunakan sebagai pertanda optimal untuk pasien STEMI yang
disertai kerusakan otot skeletal, karena pada keadaan ini juga akan terjadi
peningkatan CK-MB. Selain itu CK-MB juga dapat meningkat pada operasi jantung,
miokarditis, dan kardioversi elektrik.
2.2 SGOT
2.2.1 Definisi
SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) atau juga dinamakan
AST ( Aspartat Aminotransferase) merupakan enzim katalitik yang memiliki aktivitas
metabolisme yang tinggi. Enzim ini ditemukan dalam dua bentuk isoenzim yaitu c-
AST yang terdapat di sitoplasma dan m-AST yang terdapat di mitokondria. Enzim ini
ditemukan terutama di otot jantung dan hati, sementara dalam konsentrasi sedang
dijumpai pada otot rangka, ginjal, dan pankreas (Kurniawan, Bahrun, & Darmawaty,
2012). Penyakit yang menyebabkan perubahan, kerusakan, atau kematian sel pada
jaringan tersebut akan mengakibatkan terlepasnya enzim ini ke sirkulasi. Konsentrasi
SGOT yang rendah dijumpai dalam darah, kecuali jika terjadi cedera seluler akan
dillepaskan dalam jumlah banyak ke dalam sirkulasi.
Berdasarkan nilai yang dianut pada laboratorium patologi klinik di RSD dr.
Soebandi Jember, kadar SGOT normal dalam serum sebesar 10-31 U/L untuk
perempuan dan 10-35 U/L untuk laki-laki. Menurut (Halfman, 2000), pada infarkmiokard, kadar SGOT akan meningkat 12 jam setelah onset nyeri dada, kemudian
akan mencapai puncaknya antara 1-2 hari, dan kembali normal pada hari ke-3 hingga
hari ke-5. Selain itu terdapat pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kadar SGOT
akan normal kembali setelah 3-6 hari jika tidak terjadi infark tambahan (Bhagwat &
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
32/66
16
Padmini, 2014). Kadar SGOT biasanya dibandingkan dengan kadar enzim jantung
lainnya, seperti CK (creatin kinase), LDH (lactat dehydrogenase). Pada penyakit
hati, kadarnya akan meningkat 10 kali lebih dan akan tetap demikian dalam waktu
yang lama. Kadar SGOT serum umumnya diperiksa secara fotometri atau
spektrofotometri, semi otomatis menggunakan fotometer atau spektrofotometer, atau
secara otomatis menggunakan chemistry analyzer .
2.2.2 Peningkatan SGOT
Menurut Pedoman Interpretasi Data Klinik Kemenkes 2011, kondisi yang
meningkatkan kadar SGOT adalah:
1. Peningkatan SGOT lebih dari 20 kali normal: hepatitis viral akut, nekrosis hati
(toksisitas obat atau kimia)
2. Peningkatan 3-10 kali normal : infeksi mononuklear, hepatitis kronis aktif,
sumbatan empedu ekstra hepatik, sindrom Reye, dan infark miokard
(SGOT>SGPT)
3. Peningkatan 1-3 kali normal : pankreatitis, perlemakan hati, sirosis Laennec,
sirosis biliaris.
2.2.3 Metode Pemeriksaan SGOT
Metode pemeriksaan SGOT merujuk pada rekomendasi menurut IFCC
( International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) yang
dimodifikasi. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kadar SGOT
dalam darah seseorang secara fotometris dengan prinsip NADH dioksidasi menjadi
NAD+, menghasilkan penurunan absorbansi pada 340 nm yang secara langsung
sebanding dengan aktivitas SGOT pada sampel. Prinsip dari metode ini sebagai
berikut:
L-Aspartate + 2-OxoglutarateAST
Oxaloacetate + L-Glutamate
Oxaloacetate + NADH + H+
MDH L-Malate + NAD
+
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
33/66
17
Keterangan:
AST = Aspartate Aminotransferase
MDH = Malat Dehidrogenase
NAD+ = Nicotinamide Adenin Dinucleotide
NADH = NAD tereduksi
Menurut (Sardini, 2007), metode yang digunakan sesuai dengan modifikasi
IFCC terdiri dari 2 macam. Pertama disebut juga metode IFCC dengan penambahan
reagen pyridoxal-5-phosphate (P-5-P) yang biasa disebut metode " IFCC with P-5-P "
atau " substrate start ", yang kedua adalah metode IFCC tanpa penambahan reagen
pyridoxal-5-phosphate (P-5-P) yang biasa disebut metode " IFCC without P-5-P " atau
" sample start ". Penambahan P-5-P berfungsi untuk menstabilkan aktivitas
transaminase dan menghindari nilai-nilai palsu yang rendah dalam sampel yang tidak
mengandung cukup endogen P-5-P.
a. Alat dan bahan
Dalam pengukuran kadar SGOT, diperlukan serum atau plasma dengan
antikoagulan heparin atau EDTA. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan SGOT
dengan modifikasi metode IFCC adalah sebagai berikut:
- Rak tabung reaksi ukuran 12 × 75 mm
- Mikropipet 200 μl, 100 μl
- Yellow tip
- Sentrifuge
- Spektrofotometer
b. Reagen
Terdapat dua macam reagen yang digunakan pada pemeriksaan SGOT yaitu:
- Reagen 1 (R1): TRIS (pH 7,65): 110 mmol/L
L-Aspartate: 320 mmol/L
MDH (Malate Dehydrogenase): ≥ 800 U/L
LDH (Lactate Dehydrogenase): ≥ 1200 U/L
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
34/66
18
- Reagen 2 (R2): 2-Oxoglutarate: 65 mmol/L
NaOH: 1 mmol/L
c. Pyridoxal-5-Phosphate FS
Good’s buffer (pH 9,6): 100 mmol/L
Pyridoxal-5-Phosphate: 13 mmol/L
d. Prosedur Pengukuran SGOT
Panjang gelombang : 340 nm, Hg 365 nm, Hg 334 nm
Jalur optik : 1 cm
Suhu : 37oC
Pengukuran : terhadap udara
1. Substrate Start atau IFCC with P-5-P
- Reagen sudah siap untuk digunakan
- Campur 1 bagian P-5-P + 100 bagian R1 (contoh: 100 μl P-5-P + 10 ml
R1) = monoreagen
- Stabilitas setelah pencampuran: 6 hari pada suhu 2-8 oC
24 jam pada suhu 15-28oC
Monoreagen harus terhindar dari cahaya.
- Inkubasi R1 selama 5 menit, kemudian masukkan R2 dan campurkan.
Baca absorbansi setelah 1 menit dan mulai stopwatch. Setelah itu, baca
kembali absorbansi pada menit ke-1, ke-2, dan ke-3 setelah stopwatch
dihidupkan.
2. Sample Start atau IFCC without P-5-P
- Campur 4 bagian R1 + 1 bagian R2 (contoh: 20 ml R1 + 5 ml R2) =
monoreagen.
- Stabilitas setelah pencampuran: 4 minggu pada suhu 2-8 oC
5 hari pada suhu 15-28oC
Monoreagen harus terhindar dari cahaya.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
35/66
19
- Campurkan monoreagen, baca absorbansi setelah 1 menit dan mulai
stopwatch. Baca kembali absorbansi pada menit ke-1, ke-2, dan ke-3
setelah stopwatch dihidupkan.
e. Penghitungan
Dari pembacaan absorbansi, hitung:
∆A/min × faktor = Aktivitas AST (U/L)
- Faktor Substrate Start
340 nm: 2143
334 nm: 2184
365 nm: 3971
- Faktor Sample Start
340 nm: 1745
334 nm: 1780
365 nm: 3235
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
36/66
20
2.3 Kerangka Konsep Penelitian
Gambar 2.3 Kerangka Konsep
2.4 Hipotesis Penelitian
Dari rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang ada, maka dapat ditarik
hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan kadar SGOT pada spektrum
klinis penyakit Sindrom Koroner Akut di RSD. dr. Soebandi Jember.
Sindrom Koroner Akut
Aterosklerosis
Biomarker :
Peningkatan SGOT
Infark Miokard
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
37/66
21
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik observasional dengan
menggunakan desain studi cross sectional (Pratiknya, 2008). Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk menganalisis kadar SGOT dalam darah (variabel independent)
terhadap kejadian Sindrom Koroner Akut (variabel dependent) di Rumah Sakit
Umum Daerah (RSD) dr. Soebandi Kabupaten Jember.
3.2 Rancangan Penelitian
Secara skematis rancangan penelitian ditunjukan pada Gambar 3.1 berikut ini.
Gambar 3.1 Rancangan penelitian
Keterangan :
P : Populasi
RM : Rekam Medik
UA : Unstable Angina
NSTEMI : Non ST-segment Elevation Myocardial Infarction
STEMI : ST-segment Elevation Myocardial Infarction
P S NSTEMI
UA
STEMI
RM
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
38/66
22
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien dengan diagnosis Sindrom
Koroner Akut di RSD. dr. Soebandi Jember pada bulan Agustus-Oktober 2015.
3.3.2 Sampel
Sampel pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pasien
Unstable Angina (UA), Non ST-segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI),
dan ST-segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI), dengan menggunakan
data rekam medis sebagai sumber penelitian. Sampel yang akan diambil, didasarkan
pada kriteria-kriteria sebagai berikut :
a. Kriteria Inklusi
1) Pasien yang dirawat di ICCU pada bulan Agustus-Oktober 2015 dengan
diagnosis UA, NSTEMI, dan STEMI di RSD. dr. Soebandi Kabupaten
Jember.
2) Pasien yang diperiksa kadar SGOT dalam rentang waktu 8-48 jam setelah
serangan angina.
b. Kriteria Eksklusi
Pasien SKA dengan penyakit pada hepar
3.3.3 Besar Sampel
Berdasarkan Lameshow (1997), besar sampel ditentukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
n = Z1-a/2 P (1-P)
d
= 1,96 . 0,50. 0.50
0,05
= 9,8 (dibulatkan menjadi 10)
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
39/66
23
Keterangan
n = Besar sampel
Z1-a/2 = Nilai Z pada derajat kemaknaan (biasanya 95%= 1,96)
P = Proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi, bila tidak
diketahui proporsinya, ditetapkan 50% (0,50)
d = Derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan: 10%
(0,10), 5% (0,05), atau 1% (0,01)
Maka didapatkan besar sampel untuk setiap kelompok adalah 10 sampel.
Sehingga terdapat 30 total sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria
Roscow yaitu besar sampel dalam penelitian adalah 30-500 sampel (Notoatmodjo,
2010).
3.3.4 Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan stratified random sampling (pengambilan sampel secara acak
stratifikasi), yaitu dengan cara mengidentifikasi karakteristik dari populasi yang
berbeda-beda (heterogen), kemudian menentukan strata atau lapisan dari jenis
karakteristik kelompok-kelompok tersebut. Penentuan strata ini didasarkan pada
perbedaan EKG dan pemeriksaan laboratoris pada kelompok UA, NSTEMI, dan
STEMI. Setelah strata ditentukan, baru kemudian dari masing-masing kelompok
strata diambil sampel yang mewakili strata tersebut secara random dengan
menggunakan teknik undian (Notoatmodjo, 2010).
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian
Pengambilan data dilakukan di ruang ICCU RSD. dr.Soebandi Jember pada
Agustus -Oktober 2015
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
40/66
24
3.5 Variabel Penelitian
3.5.1 Variabel Dependen
Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah peningkatan
kadar SGOT.
3.5.2 Variabel Independen
Variabel Independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah sindrom
klinis penyakit SKA di RSD. dr. Soebandi Jember.
3.6 Definisi Operasional
3.6.1 SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) / AST ( Aspartat
Aminotransferase) adalah enzim yang memiliki aktivitas metabolisme yang
tinggi, ditemukan di jantung, dan didapatkan dari hasil pemeriksaan
laboratorium pasien yang didiagnosis munderita UA, NSTEMI, dan STEMI
saat pertama kali datang di ICCU RSD.dr. Soebandi Jember.
3.6.2 Pasien Sindrom Koroner Akut adalah:
1) Pasien UA adalah pasien yang datang di ICCU RSD. dr. Soebandi Jember
dan didiagnosis sebagai penderita UA berdasarkan diagnosis dokter pada
rekam medis.
2) Pasien NSTEMI adalah pasien yang datang di ICCU RSD. dr. Soebandi
Jember dan didiagnosis sebagai penderita NSTEMI berdasarkan diagnosis
dokter pada rekam medis.
3) Pasien STEMI adalah pasien yang datang di ICCU RSD. dr. Soebandi
Jember dan didiagnosis sebagai penderita STEMI berdasarkan diagnosis
dokter pada rekam medis.
3.6.3 Data rekam medis pasien adalah:
Data rekam medis pasien SKA yang mencakup kadar SGOT yang diperiksa
dalam waktu 8-48 jam setelah onset nyeri dada.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
41/66
25
3.7 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan berupa:a. Rekam medis dari pasien SKA yang mencakup hasil tes laboratorium berupa
nilai SGOT di ICCU RSD. dr. Soebandi Jember
b. Check list untuk mendata pasien-pasien SKA yang berasal dari ICCU RSD.
dr. Soebandi Jember
3.8 Prosedur Kerja Penelitian
3.8.1 Mendapatkan Sampel Pasien SKA
Sampel pasien SKA yang merupakan kelompok uji didapatkan dari rekam
medis pasien ICCU RSD dr. Soebandi Jember.
3.8.2 Teknik Perolehan Data Sampel SKA
Langkah I : Permohonan etik penelitian dan surat keterangan persetujuan
etik kepada Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas
Jember.
Langkah II : Permohonan ijin penelitian kepada RSD. dr.Soebandi Jember.
Langkah III : Pengambilan data rekam medis di Bagian Rekam Medis
RSD dr.Soebandi Jember.
Langkah IV : Mencatat nilai SGOT dari rekam medis
Langkah V :Pengolahan data yang telah diperoleh dengan analisa
statistik.
3.9 Pengambilan dan Analisis Data
3.9.1 Pengambilan Data
Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :
a. Menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan.
b. Membuat stratifikasi data berdasarkan karakteristik kelompok Unstable
Angina, NSTEMI, dan STEMI seperti pada Tabel 3.1.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
42/66
26
Tabel 3.1. Stratifikasi kelompok sampel
UA NSTEMI STEMI
Angina tipikal + + +
EKG:
1. ST Elevasi
2. ST inversi/T depresi
-
+
-
+
+
-
Biomarker Troponin / Normal
c. Mencatat data hasil tes laboratorium pasien di Laboratorium RSD dr.
Soebandi Jember melalui rekam medis.
d. Data yang telah didapatkan dengan jumlah sampel sesuai rumus, dapat
dimasukkan dalam Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Check List Penelitian
3.9.2 Analisis Data
Data dianalisis dengan uji normalitas Saphiro Wilk dengan p>0,05. Kemudian
secara statistik data kadar SGOT akan dianalisis dengan One Way Anova dan
dilakukan uji Post Hoc (Dahlan, 2009).
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
43/66
27
3.10 Alur Penelitian
Gambar 3.2 Alur Penelitian
Pencatatan
Data
Pengolahan
Data
Analisis
Data
Perijinan dan
Persetujuan Etik
Kelompok SKA
Pengumpulan data sampel dari
Rekam Medis RSD dr.Soebandi
Jember
Sesuai kriteria
inklusi
Sesuai kriteria
eksklusi
Tidak diteliti
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
44/66
28
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2015, di Ruang Rekam
Medis Rawat Inap RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember. Data penelitian
dikumpulkan dari dokumen rekam medis atau catatan kesehatan pasien SKA yang
terdiri atas Unstable Angina (UA), Non-ST Elevation Myocard Infark (NSTEMI), ST
Elevation Myocard Infark (STEMI). Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik
distribusi frekwensi serta dijelaskan secara naratif yang meliputi persentase setiap
kategori dari variabel penelitian.
4.1.1 Distribusi Pasien Sindrom Koroner Akut
Penelitian ini menggunakan populasi pasien SKA di RSD dr. Soebandi. Data
didapatkan dari Ruang Rekam Medis Rawat Inap RSD dr. Soebandi, pasien yang
mengalami SKA sebanyak 88 pasien dari bulan Agustus-Oktober 2015. Dari populasi
tersebut terdapat 25 sampel pasien UA, 24 sampel pasien NSTEMI, dan 19 sampel
pasien STEMI yang memenuhi kriteria sampel. Kemudian sampel diacak dan diambil
16 sampel dari masing-masing kelompok. Distribusi sampel pasien SKA per
bulannya disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Distribusi sampel pasien SKA per bulan
Bulan Jumlah Sampel (Orang)
UA NSTEMI STEMI
Agustus 10 8 7September 6 10 8
Oktober 9 6 4
Jumlah 25 24 19
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
45/66
29
Berdasarkan Tabel 4.1 tertera jumlah pasien SKA selama bulan Agustus-
Oktober 2015. Penderita UA terbanyak berada pada bulan Agustus yaitu sebesar 10
orang dan penderita NSTEMI dan STEMI terbanyak berada pada bulan September
yaitu sebesar 10 dan 8 orang.
4.1.2 Distribusi Jenis Kelamin Pasien Sindrom Koroner Akut
Distribusi jenis kelamin penderita SKA dalam penelitian ini disajikan pada
Gambar 4.1.
Gambar 4.1 Distribusi jenis kelamin pasien SKA
Berdasarkan Gambar 4.1 dari 48 sampel diperoleh hasil distribusi jenis kelamin
pasien SKA yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terkena SKA dengan jumlah pasien sebanyak 40 orang (83,3%) dibandingkan perempuan yang berjumlah
hanya 8 orang (16,7%). Distribusi jenis kelamin ini sesuai dengan hasil Riset
Kesehatan Dasar 2013 yang mencantumkan bahwa penderita penyakit jantung
koroner terbanyak ditemukan pada laki-laki.
83,3%
16,7%
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
46/66
30
4.1.3 Distribusi Usia Pasien Sindrom Koroner Akut
Distribusi usia pasien SKA dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2 Distribusi Usia Pasien SKA
Berdasarkan Gambar 4.2, dari 48 sampel diperoleh hasil distribusi usia pasien
SKA yang menunjukkan bahwa kelompok usia < 45 tahun berjumlah 5 orang
(10,4%), kelompok usia 45-54 tahun berjumlah 9 orang (18,8%), kelompok usia 55-
64 tahun berjumlah 19 orang (39,6%), kelompok usia 65-74 tahun berjumlah 13
orang (27%), dan kelompok usia > 74 tahun berjumlah 2 orang (4,2%). Kelompok
usia ini dibagi berdasarkan hasil dari Riset Kesehatan Dasar 2013 yang
mencantumkan bahwa penderita penyakit jantung koroner banyak ditemukan pada
kelompok usia 45-54 tahun, 55-64 tahun, dan 65-74 tahun dengan hasil tertinggi
terletak pada kelompok usia 55-64 tahun seperti yang ada pada penelitian ini.
10,4%
18,8%
39,6%
27%
4,2%
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
47/66
31
4.1.4 Rata-Rata Kadar SGOT pada Spektrum Klinis SKA
Rata-Rata Kadar SGOT pada masing-masing kelompok SKA disajikan pada
Tabel 4.2
Tabel 4.2 Rata-rata kadar SGOT masing-masing kelompok SKA
Kelompok
SKA n Mean (U/L) ± SD
UA 16 27,50 ±9,675
NSTEMI 16 65,88 ±39,007
STEMI 16 162,38 ±95,759
Rata-rata kadar SGOT kelompok UA pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa
hasil yang diperoleh merupakan hasil terendah (27,50 (U/L) ±9,675) apabila
dibandingkan dengan dua kelompok lainnya yaitu NSTEMI dan STEMI, sedangkan
rata-rata kadar SGOT pada kelompok STEMI menunjukkan hasil paling tinggi
(162,38 (U/L) ±95,759) diantara ketiga kelompok tersebut.
Gambar 4.3 Histogram Rata-Rata Kadar SGOT
27,50 U/L
65,88 U/L
162,38 U/L
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
48/66
32
4.2 Analisis Hasil Penelitian
4.2.1 Uji Normalitas Data
Syarat yang harus dimiliki oleh data penelitian agar dapat melakukan analisis
data dengan uji parametrik One-Way ANOVA ialah sampel harus berasal dari
kelompok yang independen, data masing-masing kelompok terdistribusi normal, dan
varian data harus homogen. Sampel dalam penelitian ini berasal dari kelompok yang
independen sebab kadar SGOT pada satu kelompok tidak tergantung pada kadar
SGOT pada kelompok lain. Perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas
sebelum melakukan analisis terhadap data untuk dapat memenuhi syarat uji One-Way
ANOVA. Rincian hasil uji normalitas dan uji homogenitas dapat dilihat pada
lampiran C. Uji Saphiro-Wilk (n= 0,05) lebih dari nilai α.Sedangkan data pada kelompok UA dan NSTEMI memiliki distribusi tidak normal
karena nilai signifikansi ( p
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
49/66
33
karena p
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
50/66
34
Berdasarkan Tabel 4.3 uji Kruskal-Wallis kadar SGOT pasien SKA di RSD. dr.Soebandi Kabupaten Jember diperoleh nilai p=0,000
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
51/66
35
rentang nilai normal sedangkan dua pasien lainnya (12,5%) memiliki kadar SGOT
yang meningkat. Didapatkan hasil bahwa rata-rata kadar SGOT pada UA adalah
27,50 U/L. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Srikrishna et al.
(2015) dan Sideris et al. (2005) yang menemukan kadar SGOT pada UA sebesar
21.29 U/L dan 25 U/L. Kadar SGOT pada UA yang masih berada pada rentang
normal dikarenakan belum terjadinya infark miokard sehingga kadar SGOT belum
meningkat pada pasien dalam kelompok ini. Nyeri dada yang terjadi pada UA
merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan oksigen
pada miokard karena adanya sumbatan yang berasal dari plak aterosklerosis yang
lepas, sehingga dapat menyebabkan hipoksia pada sel miokard. Hipoksia pada sel
miokar menyebabkan terjadinya metabolisme sel anaerob, yang akan menghasilkan
produk samping berupa asam laktat. Menurut Hernawati (Tanpa Tahun), apabila
produksi asam laktat tersebut terakumulasi, dapat menghambat kontraksi otot dan
menyebabkan rasa nyeri pada otot sehingga hal inilah yang mendasari terjadinya
nyeri dada atau angina pada UA. Selain itu, cedera pada sel tergantung pada berat
atau ringannya stress yang dialami oleh sel tersebut. Menurut Rahmani (Tanpa
Tahun), urutan perubahan struktur sel pada iskemia atau hipoksia yaitu: 1) Reversible
cell injury dan 2) Irreversible cell injury. Kemungkinan stress yang terjadi pada sel
miokard UA masih tergolong stress yang ringan sehingga sel miokard masih berada
pada tahapan reversible cell injury dan hal ini mengakibatkan kadar SGOT pada UA
masih normal.
Kadar SGOT kelompok NSTEMI mengalami peningkatan pada 14 pasien
(87,5%) dengan dua pasien lainnya memiliki kadar SGOT yang normal dan pada
kelompok STEMI, kadar SGOT meningkat pada 13 pasien (81,2%) dengan tiga
pasien lainnya memiliki kadar SGOT normal. Hal ini dikarenakan pada spektrum
klinis SKA dengan NSTEMI dan STEMI sudah terdapat infark pada miokard.
sehingga menyebabkan sel otot jantung mengeluarkan enzim yang berfungsi sebagai
penanda kerusakan miokard, salah satunya adalah SGOT yang meningkat. Rata-rata
kadar SGOT pada kelompok NSTEMI dan STEMI sebesar 65,88 U/L dan 162,38
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
52/66
36
U/L. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Srikrisnha et al .
(2015) yang menyatakan bahwa rata-rata kadar SGOT pada kelompok pasien
NSTEMI dan STEMI yang masih berada dalam rentang normal yaitu sebesar 26,91
±11,64 U/L dan 30,60 ±10,04 U/L. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa dari
keseluruhan kelompok, rata-rata kadar SGOT pada kelompok STEMI memiliki nilai
tertinggi. Sebab oklusi pembuluh darah koroner yang terjadi pada pasien STEMI
merupakan oklusi total sedangkan oklusi yang terjadi pada pasien NSTEMI
merupakan oklusi parsial, sehingga menyebabkan keluasan infark miokard pada
STEMI lebih luas dibandingkan dengan NSTEMI.
Menurut Pedoman Interpretasi Data Klinik Kemenkes 2011, kenaikan SGOT
pada infark miokard berkisar antara 3-10 kali dari rentang nilai normal SGOT. Hasil
yang didapat pada penelitian ini adalah bahwa kadar SGOT pada pasien STEMI
meningkat lebih besar (hampir mendekati sepuluh kali lipat dari nilai normal)
dibandingkan dengan peningkatan kadar SGOT pada pasien NSTEMI (tercantum
dalam lampiran). Hal ini sebanding dengan rata-rata kadar SGOT pada kelompok
STEMI yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok NSTEMI. Namun dalam
penelitian ini, peneliti tidak dapat menentukan berapa kali peningkatan kadar SGOT
yang dialami oleh pasien SKA sebab peneliti tidak mengetahui baseline kadar SGOT
pasien sebelum terjadinya SKA.
Persentase kenaikan kadar SGOT pada 16 pasien STEMI lebih sedikit
dibandingkan dengan pada 16 pasien NSTEMI. Hal ini kemungkinan berhubungan
dengan jam pemeriksaan SGOT pada pasien setelah onset nyeri dada berlangsung.
Menurut Sobel dan Shell (1972), kadar SGOT pada infark miokard akut meningkat
sejak 8-12 jam setelah serangan nyeri dada, kemudian mencapai puncak tertinggi
yaitu antara 2-10 kali dari nilai normal pada 18-36 jam setelah nyeri dada, dan akan
menurun menuju nilai normal pada hari ke-3 sampai hari ke-4. Sedangkan menurut
Halfman (2000), kadar SGOT pada infark miokard akan meningkat sekitar 12 jam
setelah onset nyeri dada, dengan kadar puncak antara 1-2 hari, dan kembali normal
pada hari ke 3-5. Gambar 4.3 mengilustrasikan waktu kenaikan enzim jantung pada
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
53/66
37
infark miokard (salah satunya SGOT), yang dihubungkan dengan waktu setelah
terjadinya onset nyeri dada menurut Halfman (2000).
Gambar 4.3 Penghitungan waktu peningkatan enzim jantung pada infark miokard
Sumber: Halfman (2000)
Berdasarkan Gambar 4.3, penyebab dari normalnya kadar SGOT pada sampel
pasien NSTEMI dan STEMI kemungkinan terletak pada faktor waktu pemeriksaan.
Kemungkinan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien tersebut setelah terjadinya
onset nyeri dada masih dalam rentang waktu awal kenaikan kadar SGOT, sehingga
hasil yang didapatkan adalah kadar SGOT yang masih dalam rentangan nilai normal
meskipun sebenarnya SGOT sudah meningkat dari kadar awal sebelum terjadinya
SKA.
Seperti yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka bahwa serum
transaminase SGOT ini terdapat tidak hanya pada sel miokard melainkan juga pada
sel hepar. Dalam penelitian ini, pasien yang memiliki riwayat penyakit hepatitis atau
penyakit hati lainnya tidak dimasukkan ke dalam sampel penelitian. Peneliti melihat
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
54/66
38
dari riwayat penyakit dahulu pada rekam medis pasien, yang mencantumkan bahwa
tidak adanya keterkaitan penyakit yang diderita pasien dengan penyakit hati. Selain
itu, peneliti juga melihat kadar SGPT pada hasil laboratorium pasien (tercantum
dalam lampiran B) dan memilih kadar SGPT pasien yang berada pada rentang nilai
normal untuk menghindari kenaikan SGOT yang berasal dari sel hepar. Karena
menurut penelitian Sobel dan Shell (1972), meskipun SGOT juga terdapat pada sel
hepar selain di sel jantung, tetapi untuk diagnosis penyakit hepar lebih spesifik
menggunakan SGPT. Kurniawan (2012) juga menjelaskan dalam penelitiannya
bahwa peningkatan kadar SGPT pada pasien infark miokard tidak menunjukkana
perbedaan yang bermakna. Hal ini dikarenakan aktivitas SGOT pada otot jantung
jauh lebih tinggi (lebih cardiac specific) daripada SGPT.
4.4 Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini yaitu
tidak adanya data yang menyebutkan kadar SGOT pasien SKA sebelum terjadinya
penyakit SKA tersebut sehingga peneliti tidak mengetahui seberapa besar kenaikan
SGOT yang terjadi pada setiap pasien SKA. Selain itu, SGOT yang sudah
ditinggalkan sebagai biomarker SKA dan digantikan oleh troponin menyebabkan
beberapa sumber rujukan yang digunakan sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu.
Kelemahan yang terakhir adalah jumlah sampel yang masih memungkinkan adanya
bias sebab waktu penelitian yang singkat sehingga perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut dengan penambahan waktu penelitian dan jumlah sampel.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
55/66
39
BAB 5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data komparasi dan pembahasan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar SGOT dengan
masing-masing sindrom klinis penyakit SKA di RSD. dr. Soebandi Jember.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat
diberikan antara lain:
1. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan dengan jumlah sampel yang lebih banyak
agar nilai-nilai kesalahan dalam penelitian bisa dikurangi, sehingga bisa
memperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat
menggunakan lebih dari satu macam rumah sakit agar dapat memberikan
gambaran yang lebih luas dan yang terakhir, kadar SGOT sebelum terjadinya
penyakit SKA perlu dicatat supaya peneliti dapat mengetahui berapa kenaikan
SGOT yang terjadi pada pasien tersebut.
2. Pihak rumah sakit disarankan agar pencatatan status pasien pada rekam medis
dilakukan dengan lebih teratur dan lengkap untuk memudahkan peneliti yang akan
melakukan penelitian berdasarkan rekam medis.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
56/66
40
DAFTAR PUSTAKA
AHA. 2014. Guideline for the Management of Patients With Non – ST-Elevation
Acute Coronary Syndromes. JACC. content.onlinejacc.org. [23 September
2015].
Amsterdam Ezra, et al. 2014. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of
Patients With Non – ST-Elevation Acute Coronary Syndromes. Jurnal
American Heart Association, Inc., 9 (10.1161/CIR.0000000000000134): 9.
Anwar Bahri. 2004. Angina Pektoris Tak Stabil . Sumatera Utara : Repository
Universitas Sumatera Utara
Bhagwat, K. dan Padmini, H.. 2014. Co-Relation Between Lactate Dehydrogenase
and Creatine Kinase-Mb in Acute Myocardial Infarction. International
Journal of Advanced Research in Pharmaceutical and Bio Sciences, 3: 6-12.
Bode, Christop dan Zirlik, Andreas. 2007. STEMI and NSTEMI: the dangerous
brothers. Freiburg: European Heart Jurnal , 5: 2-4
Boudi FB. Risk factors for coronary artery disease. Medscape [serial online] 2014.
URL: http://emedicine.medscape.com/article/164163-overview. [27
September 2015].
Daga, Lal C. dkk. 2011. Approach to STEMI and NSTEMI. Journal of JAPI , 59: 2.
Dahlan, M. Sopiyudin. 2013. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta:
Salemba Medika.
Depkes RI. 2008. Riset Kesehatan Dasar 2007 . Jakarta: Departemen
Kesehatan Republik Indonesia.
Erhardt, L. R., Sjogren, A., dan Sawe, U.. 1974. Late Rise in SGPT After Acute
Myocardial Infarction. Journal of Internal Medicine, 196 (6): 245-251.
Firdaus, Isman. 2011. Strategi Farmako-invasif pada STEMI Akut . Jurnal Kardiologi
Indonesia, 32 (4): 7-8.
Gough PJ; Gomez IG; Wille PT and Raines EW. 2006 Macrophage expression of
http://emedicine.medscape.com/article/164163-overviewhttp://emedicine.medscape.com/article/164163-overview
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
57/66
41
active MMP-9 induces acute plaque disruption in apoE-deficient mice J. Clin.
Invest, 13 (116): 59-69.
Halfman, C. J. (2000). Serum Markers for the Diagnosis of Myocardial Infarction.
Laboratory Medicine and Pathophysiology , 6.
Harun, Sjaharuddin dan Alwi, Idrus. 2009. Infark Miokard Akut Tanpa Elevasi ST .
Jakarta: Interna Publishing.
Hernawati. (Tanpa Tahun). Produksi Asam Laktat pada Exercise Aerobik dan
Anaerobik . Bandung: Fakultas MIPA Jurusan Biologi UPI.
Kumar C, dan Cannon. 2009. Acute Coronary Syndromes: Diagnosis and
Management. Mayo Clin Proc, 84 (53).
Kurniawan, L. B., Bahrun, U., & Darmawaty. 2012. Hubungan Kadar Transaminase
terhadap Mortalitas dan Lama Perawatan Pasien Infark Miokard . Jurnal
Kedokteran Yarsi, 20 (1): 30.
Lameshow, Stanley. 1997. Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan. Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada.
Mackay G. dan Mensah J..2004.The Atlas of Heart Disease and Stroke. Switzerland:
WHO, Marketing & Dissemination.
Morrow. 2010. Cardiovascular Risk Prediction in Patients With Stable and Unstable
Coronary Heart Disease. Circulation AHA Journal , 121 (75): 2682-2684.
Myrtha, Risalina. 2012. Patofisiologi Sindrom Koroner Akut. Jurnal Kalbe Indonesia,
39 (4): 6-8.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka
Cipta.
Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. 2015. Pedoman
Tatalaksana Sindrom Koroner Akut. Jakarta: Centra Communications.
Price MJ., Shah PK. 2002. Feature: Biology of the Vulnerable Plaque: Part I. Cath
Lab Diges, 10 (4).
Price, Sylvia A. dan Wilson, Lorraine M.. 2006. Patofisiologi Konsep Klinis dan
Proses-Proses Penyakit Edisi 6. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
58/66
42
Rahmani. (Tanpa Tahun). Sebab Sebab Jejas, Kematian, dan Adaptasi Sel. Jakarta:
Universitas Jakarta.
Rathish R., Gayatri Gunalan, Sumanthi. 2013. Current Biomarkers for Myocardial
Infarction.International Journal of Pharma and Bio Sciences 2013 Jan, 4(1):
(B) 434 - 442
Riset Kesehatan Dasar. 2013. Situasi Kesehatan Jantung. Jakarta: Badan Litbangkes
Kementerian Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran.
Sardini, S. (2007). Penentuan Aktivitas Enzim GOT dan GPT dalam Serum dengan
Metode Reaksi Kinetik Enzimatik sesuai IFCC (International Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Pusal Teknologi Keselamalan
dan Metrologi Rildiasi - Badan Tenaga Nuklir Nasional: 93-96.
Satoto, Hari Hendriarto. 2014. Patofisiologi Penyakit Jantung Koroner . Jurnal
Anestesiologi Indonesia, 6 (3).
Shah PK., Galis ZS. 2001. Matrix Metalloproteinase Hypothesis of Plaque Rupture.
Circulation,104: 1878
Sideris, Bonios, Eftihiadis, Melexopoulou, Mousiama, Diplaris, dan Ogias. 2005.
Severe Thrombocytopenia After Heparin Therapy in a Patient with Unstable
Angina and Recent Stent Implantation. Hellenic Journal of Cardiology, 45:
242-243.
Sobel, Burton E. dan Shell, William E.. 1972. Serum Enzyme Determinations the
Diagnosis and Assessment of Myocardial Infarction. Circulation AHA
Journal , 45 (2): 471.
Srikrishna R., Ramesh S., dan Girishbabu R.. 2015. Study of High Sensitive-CRP and
Cardiac Marker Enzymes in Acute Coronary Syndrome. Journal of Krishna
Institute of Medical Sciences University, 4 (2): 107-110.
Supriyono M. 2008. Faktor-Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian
Penyakit Jantung Koroner pada Kelompok Usia< 45 Tahun (Studi Kasus di
RSUP Dr. Kariadi dan RS Telogorejo Semarang). Semarang: Undip.
The American Association for Clinical Chemistry. 2007. Laboratory Medicine
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
59/66
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
60/66
44
Lampiran A. Ethical Clearance
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
61/66
45
Lampiran B. Analisis Data Sekunder
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
62/66
46
Lampiran C. Hasil Penelitian
1. Frekuensi Kadar SGOT pada Masing-Masing Spektrum Klinis SKA
Statistics
UA NSTEMI STEMI
N Valid 16 16 16
Missing 32 32 32
Mean 27.50 65.88 162.38
Median 25.50 52.00 162.50
Mode 28 55 21a
Std. Deviation 9.675 39.007 95.759
Variance 93.600 1521.583 9169.850
Skewness 1.943 1.481 .309
Std. Error of Skewness .564 .564 .564
Kurtosis 4.227 2.038 -.661
Std. Error of Kurtosis 1.091 1.091 1.091
Minimum 15 20 21
Maximum 55 167 333
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
2. Uji Normalitas Data
Tests of Normality
Klasifikasi SKA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
KadarSGOT
dimension1
UA .313 16 .000 .772 16 .001
NSTEMI .235 16 .019 .854 16 .016
STEMI .102 16 .200* .960 16 .659
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
63/66
47
Tests of Normality
Klasifikasi SKA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
TRANS_SGOT
dimension1
UA .246 16 .011 .890 16 .055
NSTEMI .152 16 .200* .974 16 .902
STEMI .173 16 .200* .879 16 .037
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
3. Uji Homogenisitas Data
Test of Homogeneity of Variances
KadarSGOT
Levene Statistic df1 df2 Sig.
16.650 2 45 .000
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
64/66
48
Lampiran D. Analisis Hasil Penelitian
1. Uji Non Parametrik Kruskal-Wallis
Ranks
Klasifikasi SKA N Mean Rank
KadarSGOT
dimension1
UA 16 11.81
NSTEMI 16 25.66
STEMI 16 36.03
Total 48
Test Statisticsa,b
KadarSGOT
Chi-square 24.124
df 2
Asymp. Sig. .000
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Klasifikasi
SKA
2. Uji Post-Hoc Mann-Whitney
a. UA dan NSTEMI
Ranks
Klasifikasi SKA N Mean Rank Sum of Ranks
KadarSGOT
dimension1
UA 16 10.22 163.50
NSTEMI 16 22.78 364.50
Total 32
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
65/66
49
Test Statisticsb
KadarSGOT
Mann-Whitney U 27.500
Wilcoxon W 163.500
Z -3.792
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000a
a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Klasifikasi SKA
b. UA dan STEMI
Ranks
Klasifikasi SKA N Mean Rank Sum of Ranks
KadarSGOT
dimension1
UA 16 10.09 161.50
STEMI 16 22.91 366.50
Total 32
Test Statisticsb
KadarSGOT
Mann-Whitney U 25.500
Wilcoxon W 161.500
Z -3.866
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000a
a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Klasifikasi SKA
c. NSTEMI dan STEMI
Ranks
Klasifikasi SKA N Mean Rank Sum of Ranks
KadarSGOT
dimension1
NSTEMI 16 11.38 182.00
STEMI 16 21.63 346.00
Total 32
-
8/18/2019 Perbedaan Kadar Sgot Pada Sindrom Klinis Ska Iya
66/66
50
Test Statisticsb
KadarSGOT
Mann-Whitney U 46.000
Wilcoxon W 182.000
Z -3.091
Asymp. Sig. (2-tailed) .002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a
a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Klasifikasi SKA