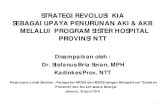Pengaruh Status Imunisasi dan Status Gizi terhadap Penyakit Menular
description
Transcript of Pengaruh Status Imunisasi dan Status Gizi terhadap Penyakit Menular

Pengaruh Status Imunisasi dan Status Gizi terhadap Penyakit Menular
Ivan Laurentius S
102011265 / D3
Mahasiswa FK UKRIDA Semester 6
FK UKRIDA 2011
Jalan Arjuna Utara No. 6, Jakarta 11510
E-mail: [email protected]
Pendahuluan
Penyakit-penyakit menular merupakan masalah kesehatan yang dapat menyerang
berbagai kelompok usia, khususnya pada anak-anak. Kondisi gizi buruk dan cakupan
imunisasi yang rendah mendukung timbulnya penyakit-penyakit menular di Indonesia. Salah
satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi keadaan-keadaan ini adalah melalui fasilitas
Puskesmas. Program-program yang dilaksanakan puskesmas untuk meningkatkan gizi dan
cakupan imunisasi masyarakat tercantum sebagai program utama dari puskesmas dalam
kegiatan KIA dan upaya peningkatan gizi masyarakat.
Tingkatan Pencegahan Penyakit
Dalam kesehatan masyarakat ada lima tingkatan pencegahan penyakit. Kelima tingkat
pencegahan tersebut antara lain adalah: peningkatan kesehatan (health promotion),
perlindungan khusus (specific protection), diagnosis dini dan pengobatan cepat dan tepat
(early diagnosis and prompt treatment), pembatasan kecacatan (disability of limitation), dan
pemulihan kesehatan (rehabilitation).1
Lebih spesifik lagi, kelima tingkatan pencegahan penyakit tersebut digolongkan
kedalam tiga hal, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier.
Peningkatan kesehatan dan perlindungan khusus merupakan pencegahan primer, sementara
diagnosis dini dan pengobatan cepat dan tepat serta pembatasan kecacatan adalah bagian dari
pencegahan sekunder, dan pencegahan tersiernya adalah dan pemulihan kesehatan.
Pencegahan primer sasarannya adalah kelompok risiko tinggi (ibu hamil dan
menyusui, perokok, obesitas, dan pekerja seks), dengan tujuan untuk menghindarkan mereka
agar tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. Pencegahan sekunder sasarannya adalah
penderita penyakit kronis dengan tujuan untuk memberikan penderita kemampuan untuk
mencegah penyakit bertambah parah. Sementara, pencegahan tersier sasarannya adalah
1

kelompok pasien yang baru sembuh dengan tujuan agar penderita segera pulih dengan
mengurangi kecacatan seminimal mungkin.2 Pencegahan primer masuk keadalam kategori
fase pencegahan prepatogenesa (belum sakit), sementara pencegahan sekunder dan tersier
masuk kedalam kategori fase pencegahan patogenesa (kondisi sakit).
1. Peningkatan Kesehatan (Health Promotion)
Peningkatan kesehatan merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan pada saat
masih sehat sehingga tidak menjadi sakit dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan
perilaku yang baik. Peningkatan kesehatan dapat membantu masyarakat dalam
mengembangkan sumber untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan
mereka.3
Peningkatan kesehatan (health promotion) misalnya dapat dilakukan dalam bentuk:
pendidikan kesehatan, meningkatkan gizi yang baik, pengembangan kepribadian, perusahaan
yang sehat dan memadai, rekreasi, penyuluhan perkawinan dan pendidikan seksual, serta
pemeriksaan kesehatan periodik.5 Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, peningkatan
kesehatan juga dapat berbentuk: melakukan penyuluhan dan pendidikan kesehatan,
memberikan nutrisi yang sesuai dengan standar, dan meningkatkan kesehatan mental.1
2. Perlindungan Khusus (Specific Protection)
Specific protection adalah upaya spesifik untuk mencegah terjadinya penularan
penyakit tertentu, misalnya dengan melakukan serangkaian kegiatan imunisasi dan
peningkatkan keterampilan remaja untuk menolak menggunakan narkoba.2 Selain kedua hal
tersebut, perlindungan khusus juga dilakukan melalui upaya higiene personal, sanitasi
lingkungan, perlindungan bahaya penyakit kerja, avoidment allergic, dan nutrisi khusus
(nutrisi untuk ibu hamil dan bayi), dsb.1,4,5
3. Diagnosis Dini dan Pengobatan Cepat dan Tepat (Early Diagnosis and Prompt
Treatment)
Early diagnosis and prompt tratment ini ditujukan pada individu yang telah jatuh
sakit. Tujuan utama dari diagnosis dini dan pengobatan cepat dan tepat adalah untuk
mencegah penyebaran penyakit menular, mengobati dan menghantikan proses penyakit,
menyembuhkan orang sakit dan mencegah terjadinya komplikasi dan cacat.2 Hal-hal yang
terkait dengan hal ini adalah diagnosis dini setiap keluhan dan pengobatan segera serta
2

pemberantasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi.1 Diagnosis dini
sangat penting untuk penyakit kanker dan penyakit-penyakit menular.
4. Pembatasan Kecacatan (Disability of Limitation)
Pada tahap ini, kecacatan yang terjadi diupayakan untik diatasi, agar tidak mengarah
pada cacat yang lebih buruk.2 Misalnya adalah dengan penyempurnaan pengobatan lanjutan
agar tidak menimbulkan komlikasi, pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan, serta
perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk pengobatan.1
5. Pemulihan Kesehatan (Rehabilitation)
Untuk tahap rehabilitasi ini, upaya yang dapat dilakukan antara lain pendidikan
khusus yang disesuaikan dengan kondisi klien yang direhabilitasi, penempatan klien seseuai
dengan keadaannya (selective place), terapi kerja, dan pembentukan kelompok paguyuban
khusus bagi klien yang memiliki kondisi yang sama.4
Epidemiologi Penyakit-penyakit Menular
Epidemiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari distribusi kejadian kesakitan dan
kematian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kejadiannya pada kelompok dan
masyarakat.6 Penyelidikan epidemiologi (PE) adalah rangkaian kegiatan untuk mengetahui
suatu kejadian baik sedang berlangsung maupun yang telah terjadi, sifatnya penelitian,
melalui pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan analisa data, membuat
kesimpulan dan rekomendasi dalam bentuk laporan. Pengertian istilah-istilah dalam
penyelidikan epidemiologi KLB/wabah, antara lain:
Infektifitas adalah kemampuan unsur penyebab masuk dan berkembang biak, dapat
dianggap dengan menghitung jumlah minimal dari unsur penyebab untuk
menimbulkan infeksi terhadap 50% pejamu spesies sama. Dipengaruhi oleh sifat
penyebab, cara penularan, sumber penularan, serta faktor pejamu seperti umur, sex
dll.
Patogenesitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh bibit penyakit untuk membuat
orang menjadi sakit, atau untuk membuat sekelompok penduduk yang terinfeksi
menjadi sakit. Patogenesitas sangat dipengaruhi oleh infektivitas, sehingga
penghitungannya mengunakan formulasi yang sama dengan infektifitas (patogenesitas
= infektifitas).
3

Dengan tingkatan penyakit berdasarkan gejala dibagi menjadi: A = tanpa gejala, B =
penyakit ringan, C = penyakit sedang, D = Penyakit Berat, dan E = Mati. Maka,
infektifitas = patogenesitas dapat dihitung yaitu (B+C+D+E / A+B+C+D+E) artinya
kasus infeksi dibagi dengan jumlah yang terkena infeksi. Pengertian patogenestias =
infektifitas adalah 50% pejamu spesies yang sama. Misalnya, dalam suatu kelompok
penyelidikan (individu-individu dalam suatu kelompok) telah memiliki gejala yang
sama diatas 50 % dari jumlah individu dalam suatu kelompok) maka dapat dipastikan
bahwa kelompok masyarakat dalam suatu penyelidikan epidemiologi sudah dapat
diketahui unsur penyebabnya alias sudah dapat ditetap diagnosa epidemiologi
komunitasnya.
Virulensi adalah nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang berat (D+E)
terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis yang jelas (B+C+D+E). Virulensi
dipengaruhi oleh dosis, cara masuk/penularan, faktor pejamu.
Reservoir adalah organisme hidup atau mati (misalnya tanah) dimana penyebab
infeksi biasanya hidup dan berkembang biak. Reservoir dapat berupa manusia,
binatang, tumbuhan serta lingkungan lainnya. Reservoir merupakan pusat penyakit
menular, karena merupakan komponen utama dari lingkaran penularan dan sekaligus
sebagai sumber penularan.
Bentuk KLB/Wabah didasarkan pada cara penularan dalam kelompok masyarakat.
Gambar 1. Betuk KLB/Wabah yang didasarkan pada cara penularan dalam kelompok masyarakat
Kasus adalah mereka dimana suatu agen infektif telah masuk dan tinggal dalam tubuh
mereka dan telah ada gejala infeksi.
4

Karier adalah mereka yang menyimpan agen infektif di dalam tubuhnya. Menurut
jenis dibagi menjadi: tanpa gejala (misalnya polio, hepatitis), karier dalam
penyembuhan (contoh: diphteriae), dan karier kronik (contoh: tifus).
Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan
dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu.7 Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang
jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada
waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.7
Kriteria tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) mengacu pada Keputusan Dirjen
PPM&PLP No. 451-I/PD.03.04/1999 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan
Penanggulangan KLB. Menurut aturan itu, suatu kejadian dinyatakan luar biasa bila terdapat
unsur:8
Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal.
Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu
berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu).
Peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan
angka rata-rata per bulan tahun sebelumnya.
Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih
bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.
Angka rata-rata perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan > 2 kali
dibandingkan angka rata-rata per bulan tahun sebelumnya.
CFR suatu penyakit dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50 %
atau lebih dibanding CFR periode sebelumnya.
Proporsional Rate penderita baru dari suatu periode tertentu menunjukkan kenaikan >
2 kali dibandingkan periode yang sama dan kurun waktu/tahun sebelumnya.
Beberapa penyakit khusus, seperti kolera dan DHF/DSS: 1) Setiap peningkatan kasus
dari periode sebelumnya (pada daerah endemis); 2) Terdapat satu atau lebih penderita
baru dimana pada periode 4 minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas
dari penyakit yang bersangkutan.
Beberapa penyakit yang dialami 1 atau lebih penderita, seperti keracunan makanan
dan keracunan pestisida.
5

KLB penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat
menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar sehingga perlu diantisipasi
dan dicegah penyebarannya dengan tepat dan cepat. Kejadian-kejadian KLB perlu dideteksi
secara dini dan diikuti tindakan yang cepat dan tepat, perlu diidentifikasi adanya ancaman
KLB beserta kondisi rentan yang memperbesar risiko terjadinya KLB agar dapat dilakukan
peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB, dan oleh
karena itu perlu diatur dalam pedoman Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
(SKD-KLB).
Surveilans Epidemiologi Kesehatan
Sistem surveilans epidemiologi merupakan tatanan prosedur penyelenggaraan
surveilans epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveilans dengan
laboratorium, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian dan penyelenggara program
kesehatan, meliputi tata hubungan surveilans epidemiologi antar wilayah Kabupaten/Kota,
Propinsi dan Pusat9.
Kegiatan-kegiatan dalam surveilans adalah sebagai berikut:
pengumpulan data secara sistematis dan terus menerus
pengolahan, analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi
penyebarluasan informasi yang dihasilkan kepada orang-orang atau institusi yang
dianggap berkepentingan, dan
menggunakan informasi yang dihasilkan dalam manajemen yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian.10
Masalah kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai sebab, oleh karena itu secara
operasional masalah-masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan
sendiri, diperlukan tatalaksana terintegrasi dan komprehensif dengan kerjasama yang
harmonis antar sektor dan antar program, sehingga perlu dikembangkan subsistem survailans
epidemiologi kesehatan yang terdiri dari Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular,
Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Surveilans Epidemiologi Kesehatan
Lingkungan Dan Perilaku, Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan, dan Surveilans
Epidemiologi Kesehatan Matra.
Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan
faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular.
6

Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan
faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular.
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko
untuk mendukung program penyehatan lingkungnan.
Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan
faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu.
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan
faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan matra.9
Program Puskesmas
Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu organisasi fungsional yang
menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat
diterima dan terjangkau oleh masyarakat, serta biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan
masyarakat. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah
untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan
kesadaran serta kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujudnya derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan ‘Indonesia Sehat 2010’. Upaya kesehatan
tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas
bagi mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada
perorangan.11
Program pokok Puskesmas merupakan program pelayanan kesehatan yang wajib di
laksanakan karena mempunyai daya ungkit yang besar terhadap peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ada 6 Program Pokok pelayanan kesehatan
di Puskesmas yaitu :
7

1. Program pengobatan (kuratif dan rehabilitatif) yaitu bentuk pelayanan kesehatan
untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan pada seseorang pasien dilakukan
oleh seorang dokter secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh
selama anamnesis dan pemeriksaan
2. Promosi Kesehatan yaitu program pelayanan kesehatan puskesmas yang diarahkan
untuk membantu masyarakat agar hidup sehat secara optimal melalui kegiatan
penyuluhan (induvidu, kelompok maupun masyarakat).
3. Pelayanan KIA dan KB yaitu program pelayanan kesehatan KIA dan KB di
Puskesmas yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada PUS (Pasangan Usia
Subur) untuk ber KB, pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas serta pelayanan bayi
dan balita.
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu program
pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penular
penyakit menular/infeksi (misalnya TB, DBD, Kusta dll).
5. Kesehatan Lingkungan yaitu program pelayanan kesehatan lingkungan di
puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya
sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk
pengendalian pencemaran lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat,
6. Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu program kegiatan pelayanan kesehatan, perbaikan
gizi masyarakat di Puskesmas yang meliputi peningkatan pendidikan gizi,
penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kekurangan Yaodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Keadaan zat gizi lebih,
Peningkatan Survailans Gizi, dan Perberdayaan Usaha Perbaikan Gizi
Keluarga/Masyarakat.12
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh
pelayanan kesehatan profesional oleh petugas sektor, maupun non-profesional oleh kader.
8

Posyandu sendiri dikembangkan dari pos pengembangan balita, pos imunisasi, pos KB, dan
pos kesehatan. Adapun pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh posyantu meliputi: KB,
KIA, gizi imunisasi, penanggulangan diare, dsb. Sasaran dari pelayanan posyandu adalah
sebuah anggota masyarakkat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pasangan usia
subur.
Seperti telah disebutkan diatas, di posyandu terdapat pelayan kesehatan profesional
dan non-profesional. Fungsi dari para perawat kesehatan profesional anataralain adalah:
memberikan bimbingan teknis saat pelaksaaan penimbangan, membantu menyuluh,
memberikan pelayanan imunisasi dan pengobatan sederhana, memberikan penyuluhan,
merujuk pasien ke puskesmas, dan pelayanan kontrasepsi. Sementara peran kader yang
merupakan masyarakat meliputi: mencatat pendaftaran, membantu menimbang, memberikan
penyuluhan, mengirim masyarakat ke petugas kesehatan, menemukan penderita diare
kemudian melakukan penyuluhan dan oralit, serta merujuk bayi yang belum diimunisasi agar
dibawa ke posyandu.13
Kesehatan Ibu dan Anak
1. Ibu Hamil
Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:
a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah,
pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkar lengan atas), pemberian tablet besi,
pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi fundus uteri, temu wicara
(konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
serta KB pasca pesalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader.
Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.
b. Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelas Ibu
Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan.
Kegiatan Kelas Ibu Hamil antara lain sebagai berikut:
Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui,
KB dan gizi
Perawatan payudara dan pemberian ASI
Peragaan pola makan ibu hamil
Peragaan perawatan bayi baru lahir
2. Ibu Nifas dan Menyusui
9

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup:
Penyuluhan/konseling kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
dan ASI eksklusif dan gizi.
Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah 200.000 SI (1 kapsul segera setelah
melahirkan dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama).
Perawatan payudara.
Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi
fundus uteri (rahim). Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.
3. Bayi dan Anak balita
Pelayanan Posyandu untuk bayi dan anak balita harus dilaksanakan secara
menyenangkan dan memacu kreativitas tumbuh kembangnya. Jika ruang pelayanan memadai,
pada waktu menunggu giliran pelayanan anak balita sebaiknya tidak digendong melainkan
dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan orangtua di bawah bimbingan kader.
Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur balita. Adapun jenis
pelayanan yang diselenggarakan
Posyandu untuk balita mencakup:
Penimbangan berat badan
Penentuan status pertumbuhan
Penyuluhan dan konseling
Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi
dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke
Puskesmas.14
Imunisasi
1 Pengertian dan Tujuan Imunisasi
Imunisasi merupakan usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan
memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tumbuh membuat zat anti untuk mencegah
penyakit. Sedangkan vaksin sendiri diartikan sebagai bahan yang dipakai untuk merangsang
pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan (misalnya vaksin
BCG, DPT, dan campak) dan memlalui mulut (vaksin polio). Tujuan dari imunisasi ini tidak
lain bertujuan untuk menciptakan kekebalan anak agar dapat menurunkan angka mortalitas
serta mengurangi kecatatan akibat penyakit.15
10

2. Sasaran Imunisasi
Yang perlu diimunisasi adalah orang-orang yang rentan terkena penyakit tertentu pada
suatu saat karena profesinya, misalnya: ibu hamil, bayi dan anak balita, anak sekolah, remaja,
orang tua, manula, profesional (dokter, para medis), calon jemaah haji, dan orang-orang yang
akan berpergiaan ke luar negeri.
3. Imunisasi Wajib (Imunisasi Dasar) dan Imunisasi Pelengkap
Di Indonesia, terdapat dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi yang diwajibkan oleh
pemerintah (imunisasi dasar) dan imunisasi yang hanya dianjurkan atau hanya sebagai
pelengkap saja. Biasanya imunisasi yang merupakan imunisasi pelangkap dapat digunakan
untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) atau penyakit endemik dan hanya untuk
kepentingan tertentu (berpergian).15
Imunisasi yang diwajibkan merupakan sebuah Program Pengembangan Imunisasi
(PPI) yang wajib diberikan kepada bayi usia satu tahun ke bawah. Imunisasi yang diwajibkan
adalah program yang resmi dari pemerintah terutama dari Departemen Kesehatan). Setiap
anak dibawah usia 1 tahun, wajib memperoleh lima jenis imunisasi. Kelima jenis imunisasi
ini disebut dengan LIL (Lima Imunisasi Dasar Lengkap). Lima imunisasi dasar yang
diwajibkan antara lain BCG (Bacille Calmette Guerin), hepatitis B, polio, DPT (Difteri,
Pertusis, Tetanus), dan campak.16
Sementara itu, imunisasi yang hanya dianjurkan (imunisasi pelengkap) merupakan
program imunisasi non-PPI. Meskipun hanya sebagai pelengkap, sebenarnya jenis imunisasi
ini juga sangat penting bagi anak. Karena bertujuan agar sistem kekebalan tubuh anak
menjadi lebih baik lagi. Imunisasi pelengkap biasanya dilakukan oleh dokter praktik swasta
yang biayanya relatif lebih mahal. Beberapa jenis imunisasi pelengkap adalah: Hib
(Haemophilus influenzae type B), Penumokokus (PVC), Influenza, MMR (Measless/campak,
Mumps/gondong, Rubella/campak jerman), dsb.16
4. Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL)Adapun jenis Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) beserta jadwalnya sebagai
berikut:
Jenis Imunisasi Penyakit yang Berusaha Dicegah Cara pemberian VaksinBCG (Bacille Calmette Guerin)
TBC (tuberkulosis), yaitu penyakit yang menyerang paru-paru, selaput otak, tulang, kelenjar getah bening, dan usus.
Disuntikkan(biasanya dilengan atas)
Hepatitis B Hepatitis B, yakni penyakit yang Disuntikkan
11

menyerang hati, dapat juga menyebabkan sirosis (hari mengkerut) dan kanker hati.
(biasnaya di daerah paha)
Polio Polio, yaitu penyakit yang mengakibatkan kelumpuhan, baik lumpu satu kaki saja atau kedua kakinya.
Diteteskan di mulut
DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus)
Difteri adalah salah satu penyakakit yang disebabkan bakteri. Tetanus adalah penykit akibat bakteri yang masuk melalui luka kulit, dapat menyebabkan kontraksi hebat pada otot. Pertusis adalah batuk rejan atau batuk seratus hari.
Disuntikan
Campak Campaak adalah penyakit yang menyebabkan kulit kemerahan dan demam.
Disuntikan
Tabel 1. Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL)16
Tabel 2. Jadwal Imunisasi Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tahun 2006.15
Secara lebih lengkap, pemberian imunisasi BCG diberikan sejak lahir, dan apabila
usia >3 bulan harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dahulu. BCG baru dapat diberikan
apabila uji tuberkulin negatif. Sementara imunisasi Hepatitis B diberikan dalam waktu 12 jam
setelah lahir, dilanjutkan pada usia 1bulan dan kemudian pada rentan waktu 3-6 bulan. Untuk
polio diberikan pada saat kunjungan pertama dan secara berkala dilakukan pada 2, 4, 6, 18
bulan, lalu pada usia 5 tahun. Imunisasi DPT dapat diberikan pada usia >= 6 minggu, secara
terpisah atau dikombinasi dengan Hepatitis B (Hepatitis-combo/DPT-HB). Untuk campak-1
diberikan pada usia 9 bulan, sedangkan campak-2 diberikan pada usia 6 tahun.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukkan bahwa cakupan
imunisasi dasar di seluruh provinsi di Indonesia rata-rata untuk tiap jenis imunisasi adalah:
BCG 77,9%, polio 66,7%, DPT-HB 61,9%, dan campak 74,4%; sedangkan berdasarkan
kelengkapannya, hanya 53,8% anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar
lengkap.
12

5. Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI)
Reaksi yang timbul setelah pemberian vaksinasi disebut sebagai kejadian ikutan
pasca-imunisasi (KIPI) atau adverse events following immunization (AEFI). Secara khusus
KIPI dapat didefinisikan sebagai kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi, baik
karena efek aksin, efek samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, efek farmakologis, dsb.
Walaupun saat ini reaksi KIPI dapat diminimalkan, tetap saja petugas imunisasi maupun
dokter mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kemungkinan reaksi KIPI apa saja yang
dapat terjadi.17 Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan reaksi KIPI terhadap beberapa
jenis imunisasi:
Imunisasi Efek Samping
DPT Difteri: umumnya demam dalam 24-48 jam, sakit, kemerahan dan
bengkak pada daerah injeksi, rewel, mengantuk, serta anoreksia.
Tetanus: sama seperti difteri ditambah urtikaria dan malaise, adanya
benjolan pada daerah injeksi.
Pertusis: sama seperti tetanus, namun dapat terjadi kehilangan
kesadaran, kejang demam, dan reaksi alergi sistemik.
Haemophilus
influenzae tipe b
Reaksi lokal ringan seperti eritema, nyeri, dan demam ringan
Polio Paralisis karena vaksinasi jarang terjadi dalam 2 bulan imunisasi
MMR Mumps (gondong): secara esensial tidak ada efek samping.
Rubella (campak jerman): anoreksia, malaise, ruam, dan demam
sampai 10 hari.
Meassles (campak): Anoreksia, malaise, ruam, dan demam sampai 10
hari
Tabel 4. Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI)15
6. Rantai Vaksin (Cold Chain)
Rantai Vaksin atau Cold Chain adalah pengelolaan vaksin sesuai dengan prosedur
untuk menjaga vaksin tersimpan pada suhu dan kondisi yang telah ditetapkan. Peralatan
rantai vaksin adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam pengelolaan vaksin sesuai
dengan prosedur untuk menjaga vaksin pada suhu yang telah ditetapkan.
13

Sarana rantai vaksin atau cold chain dibuat secara khusus untuk menjaga potensi
vaksin dan setiap jenis sarana cold chain mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-
masing.
Lemari Es
Setiap puskesmas harus mempunyai 1 lemari es sesuai standar program (buka atas).
Posko potensial secara bertahap juga dilengkapi dengan lemari es.
Mini Freezer
Sebagai sarana untuk membekukan cold pack di setiap puskesmas diperlukan 1 buah
freezer.
Vaccine Carrier
Vaccine carrier biasanya di tingkat puskesmas digunakan untuk pengambilan vaksin
ke kabupaten/kota. Untuk daerah yang sulit vaccine carrier sangat cocok digunakan ke
lapangan, mengingat jarak tempuh maupun sarana jalan, sehingga diperlukan vaccine carrier
yang dapat mempertahankan suhu relatif lebih lama.
Thermos
Thermos digunakan untuk membawa vaksin ke lapangan/posyandu. Setiap thermos
dilengkapi dengan cool pack minimal 4 buah @ 0,1 liter. Mengingat daya tahan untuk
mempertahankan suhu hanya kurang lebih 10 jam, maka thermos sangat cocok digunakan
untuk daerah yang transportasinya mudah dijangkau.
Cold Box
Cold Box di tingkat puskesmas digunakan apabila dalam keadaan darurat seperti
listrik padam untuk waktu cukup lama, atau lemari es sedang mengalami kerusakan yang bila
diperbaiki memakan waktu lama.
Freeze Tag/Freeze Watch
Freeze Tag untuk memantau suhu dari kabupaten ke puskesmas pada waktu
membawa vaksin, serta dari puskesmas sampai lapangan / posyandu dalam upaya
peningkatan kualitas rantai vaksin.
Kotak dingin cair (Cool Pack)
Kotak dingin cair (Cool Pack) adalah wadah plastik berbentuk segi empat, besar
ataupun kecil yang diisi dengan air yang kemudian didinginkan pada suhu +2ºC dalam lemari
es selama 24 jam. Bila kotak dingin tidak ada, dibuat dalam kantong plastik bening.
Kotak dingin beku (Cold Pack)
14

Kotak dingin beku (Cold pack) adalah wadah plastik berbentuk segi empat, besar
ataupun kecil yang diisi dengan air yang kemudian pada suhu -5ºC − 15ºC dalam freezer
selama 24 jam. Bila kotak dingin tidak ada, dibuat dalam kantong plastik bening.15,18
Status Gizi Buruk
Secara umum diterima bahwa gizi merupakan salah satu determinan penting respons
imunitas. Penelitian epidemiologis dan klinis menunjukkan bahwa kekurangan gizi
menghambat respons imunitas dan meningkatkan risiko penyakit infeksi. Sanitasi dan higiene
perorangan yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, kontaminasi pangan dan air, dan
pengetahuan gizi yang tidak memadai berkontribusi terhadap kerentanan terhadap penyakit
infeksi. Berbagai penelitian yang dilakukan selama kurun waktu 35 tahun yang lalu
membuktikan bahwa gangguan imunitas adalah suatu faktor antara (intermediate factor)
kaitan gizi dengan penyakit infeksi
Sebagai contoh, kekurangan energi-protein (KEP) berkaitan dengan gangguan
imunitas berperantara sel (cell-mediated immunity), fungsi fagosit, sistem komplemen,
sekresi antibodi imunoglobulin A, dan produksi sitokin (cytokines). Kekurangan zat gizi
tunggal, seperti seng, selenium, besi, tembaga, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6,
dan asam folat juga dapat memperburuk respons imunitas. Selain itu, kelebihan zat gizi atau
obesitas juga menurunkan imunitas.
Gangguan pada berbagai aspek imunitas, termasuk fagositosis, respons proliferasi sel
ke mitogen, serta produksi T-lymphocyte dan sitokin telah ditemukan pada kondisi
kekurangan gizi. Sampai saat ini, mekanisme yang melaluinya kekurangan gizi
mengakibatkan gangguan fungsi imunitas masih terus mendapat perhatian serius para ahli
gizi, imunolog, ahli biologi, dan ahli di bidang lain yang terkait.
Fungsi imunitas yang dinilai adalah komponen, komplemen, delayed-hypersensitivity,
thymus-dependent lymphocytes, secretory IgA, microbicidal capacity of neutrophils, dan
leukocyte terminal transferase. Beberapa penelitian baik pada tikus maupun manusia telah
menghasilkan informasi penting berkenan hubungan antara susu terfermentasi dengan
imunitas. Pemberian susu terfermentasi dapat mendorong pembentukan antiobodi dan
respons imunitas seluler pada orang sehat. Fungsi imunitas yang paling dipengaruhi adalah
imunitas erperantara sel dan aktivitas sitokin.
Walaupun ada bukti bahwa kekurangan gizi dapat mempengaruhi patogen akan tetapi,
pada umumnya dampak kekurangan gizi pada penyakit infeksi dikaitkan dengan menurunnya
15

fungsi imunitas tubuh. Kekurangan energi-protein, misalnya, antara lain, menyebabkan
penurunan pada proliferasi limposit, produksi sitokin, dan respons antibodi terhadap vaksin.19
Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
UPGK adalah kegiatan masyarakat untuk melembagakan upaya peningkatan gizi
dalam tiap keluarga di Indonesia. Usaha ini dibimbing pemerintah melalui departemen terkait
yaitu kesehatan, pertanian, BKKBM, Agama , dan lain-lain.
Pengertian secara lebih rinci bahwa UPGK :
merupakan usaha keluarga untuk mempergaiki gizi seluruh anggota keluarga
dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat dengan kader sebagai penggerak
masyarakat and petugas berbagai sektor sebagai pembimbing dan Pembina.
merupakan bagian dari kehidupan keluarga sehari-hari dan juga merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
secara operasional adalah rangkaian kegiatan yang saling mendukung untuk
melaksanakan alih teknologi sederhana kepada keluarga/masyarakat.
Langkah-langkah kegiatan UPGK meliputi 3 komponen besar yaitu :
Penyuluhan Gizi Masyarakat
Tujuan kegiatan ini adalah terjadinya proses perubahan, pengertian, sikap dan
perilaku yang lebih sehat mengenai kegunaan dan pemanfaatan pelayanan gizi yang tersedia
dimasyarakat.
Pelayanan Gizi Melalui Posyandu
Tujuan pelayanan ini adalah menurunnya angka kurang kalori protein (KKP) dan
kebutaan karena kekurangan vitamin A pada balita serta anemia gizi pada bayi hamil.
Peningkatan Pemanfaatan Tanaman Perkarangan
Keadaan gizi buruk pada anak akan berpengaruh pada kesehatan anak. Hal ini daapt
menyebabkan menurunnya system
Salah satu kegiatan pelayanan gizi di posyandu adalah pemberian makanan tambahan
( PMT ) kepada anak balita yang dilaksanakan oleh kader-kader PKK atau kaderdesa lainnya
dengan bimbingan teknis oleh petugas gizi puskesmas.15,18
Kartu Menuju Sehat (KMS)
16

Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal
anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Dengan KMS gangguan
pertumbuhan atau risiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, sehingga dapat dilakukan
tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat KMS di
Indonesia digunakan sebagai sarana utama kegiatan pemantauan pertumbuhan. Pemantauan
pertumbuhan adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari (1) penilaian pertumbuhan anak
secara teratur melalui penimbangan berat badan setiap bulan, pengisian KMS, menentukan
status pertumbuhan berdasarkan hasil penimbangan berat badan; dan (2) menindaklanjuti
setiap kasus gangguan pertumbuhan. Tindak lanjut hasil pemantauan pertumbuhan biasanya
berupa konseling, pemberian makanan tambahan, pemberian suplementasi gizi dan rujukan.15
Fungsi utama KMS ada tiga, yaitu;
Sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak. Pada KMS dicantumkan grafik
pertumbuhan normal anak, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang
anak tumbuh normal, atau mengalami gangguan pertumbuhan. Bila grafik berat badan
anak mengikuti grafik pertumbuhan pada KMS, artinya anak tumbuh normal, kecil
risiko anak untuk mengalami gangguan pertumbuhan. Sebaliknya bila grafik berat
badan tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan, anak kemungkinan berisiko
mengalami gangguan pertumbuhan.
Sebagai catatan pelayanan kesehatan anak. Di dalam KMS dicatat riwayat pelayanan
kesehatan dasar anak terutama berat badan anak, pemberian kapsul vitamin A,
pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan dan imunisasi.
Sebagai alat edukasi. Di dalam KMS dicantumkan pesan-pesan dasar perawatan anak
pemberian makanan anak, perawatan anak bila menderita diare.
Langkah-langkah pengisian Kartu Menuju Sehat
1. Memilih KMS sesuai jenis kelamin
2. Mengisi identitas anak dan orang tua pada halaman muka KMS
3. Mangisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak
4. Meletakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan anak
5. Mencatat setiap kejadian yang dialami anak
6. Menentukan status pertumbuhan anak
7. Mengisi catatan pemberian imunisasi bayi
8. Mengisi catatan pemberian kapsul vitamin A
9. Isi kolom pemberian ASI eksklusif
17

Gambar 2. Kartu Menuju Sehat (KMS)
Kesimpulan
Status imunisasi dan status gizi memengaruhi kesehatan anak terhadap infeksi
penyakit menular. Keadaan gizi berpengaruh pada sistem imunitas anak; bila gizi buruk
sistem imunitas menurun dan demikian sebaliknya. Imunisasi memberikan kekebalan pada
penyakit menular yang bersangkutan. Maka dari itu, seorang anak perlu memiliki status gizi
yang baik serta imunisasi yang lengkap untuk mengurangi risiko terhadap penyakit menular.
Daftar Pustaka
1. Rajab, Wahyudin. Buku Ajar Epidemiologi Untuk Mahasiswa Kebidanan. Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2009.
2. Maulana DJH. Promosi Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2009.
3. Kusnanto. Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta: Penerbit
Buku Kedokteran EGC; 2004.h.96.
4. Asmadi. Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2008.
5. Efendi F, Makhfudli. Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik Dalam
Keperawatan. Jakarta: Penerbit Salemba Medika; 2009.
6. Muninjaya AAG. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC;
1999. h. 115 – 38.
7. Departemen Kesehatan RI. Peraturan Menteri Republik Indonesia No.
949/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelengaraan Sistem Kewaspadaan
Dini Kejadian Luar Biasa. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2004.
18

8. Departemen Kesehatan RI. Keputusan Dirjen PPM&PLP No. 451-I/PD.03.04/1999
tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB. Jakarta:
Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 1999.
9. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik
Indonesia; 2003.
10. Buchari, Lapau. Prinsip dan Metode Epidemiologi. Jakarta: Balai Penerbit FK UI;
2009.
11. Depkes. Kebijakan Dasar Puskesmas. Dalam Kepmenkes no 128 tahun 2004.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. 2010.
12. Ali A. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.Dinas Kesehatan Kabupaten
Polewali Mandar.Sulawesi Barat. 2012.
13. Suryanah. Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran
EGC; 1996.h.109-11.
14. Gunawan S. Kepala Direktorat Epim Depkes RI. Pertemuan Nasional Program
Imunisasi. Jakarta; 1989.
15. Hidayat, AAA. Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan.
Jakarta: Penerbit Salemba Medika; 2008.h.54-60.
16. Eveline, Djamaludin N. Panduan pintar merawat bayi dan balita. Jakarta: KAWAH
media; 2010.h.72-5.
17. Cahyono JBSB, Lusi RA. Verawati, Sitorus R, Utami RCB, Dameria K. Vaksinasi,
cara ampuh cegah penyakit infeksi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI);
2010.h.37.
18. Suparmanto SAS. Petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan posyandu.
Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009.h.30-62.
19. Siagian A. Gizi, Imunitas, dan Penyakit Infeksi [disertasi]. Medan: Universitas
Sumatera Utara; 2004.
19