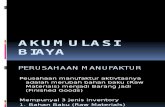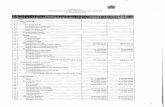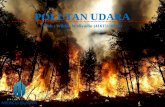PENENTUAN TITIK AKUMULASI POLUTAN SAMPAH DI …
Transcript of PENENTUAN TITIK AKUMULASI POLUTAN SAMPAH DI …

i
PENENTUAN TITIK AKUMULASI POLUTAN SAMPAH DI TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR
Oleh:
I Ketut Sukarasa
JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA
2016

ii
ABSTRAK
Penelitian untuk letak terkumpulnya sisa cairan hasil timbunan sampah. telah dilakukan. .
Hasil pengukuran nilai hambatan jenis lapisan tanah di area TPA Temesi Gianyar
menunjukkan adanya cairan sampah dengan nilai berkisar 1,84 - 9,87 Ωm, Polutan
tersebut rata-rata berada pada kedalaman 1,55 - 6,91 m. Titik akumulasi polutan sampah
terdapat pada lintasan 1, dengan titik koordinat 80 33'75” - 8
0 33’76’’ LS dan 115
0
21'019’’ - 1150
21’016’’ BT dan pada kedalaman 2,70 - 5,37 m. pada lintasan 2
terakumulasi pada dua tempat. Daerah pertama terletak pada koordinat 8 033'743’’ -
8033'745" LS dan 115
0 21’012’’ - 115
021,013’’ BT dan daerah keduaterletak pada titik
koordinat 80 33'750"- 8
0 33’754’’LS dan 115
0 21'015"- 115
021'016" BT
Kata kunci : Geolistrik, konfigurasi schlumberger, polutan sampah

iii
ABSTRACT
This research determine the and location of accumulation of pollutant in Garbage Dump
(GD) at Temesi Gianyar regency through resistivity geoelectric method typed
schlumberger configuration. The result of study, the soil resistivity values in landfill
dump area and some areas showed the existence of pollutant garbage by resistivity values
ranged from 1.84 - 9.87 Ωm. Pollutant values is 1.55 - 6.91 m. this research was divided
at accumulation point of garbage at first track showed the point coordinates 8 033'75’’ -
8033'76’’ S and 115
021’019’’ - 115
021'016’’ E in depth of 2.70 - 5.37 meters. Second
track was accumulated two areas. first area showed at coordinates 8 033'743’’ - 8
033'745"
S and 115 021'012" - 115
021'013’’ E and second areas showed at coordinate 8
0 33'750" -
80 33'754" S and 115
0 21’015’’ - 115
021’016’’ E.
Key Words: Geoelectric, schlumberger configuration, garbage dump, pollutanst

iv
KATA PENGANTAR
Syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa penulis panjatkan, atas
segala jalan, rahmat, dan karunia-Nya atas terlesaikannya makalah ini.
Penyusunan makala dibantu oleh banyak pihak. Sebab itu, penulis sampaikan
terima kasih kepada:
1. Ir. S. Poniman, M.Si. adalah Ketua Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Unud.
2. Istri, anak-anak yang dengan rela waktunya tersita untuk menyelesaikan
makalah ini.
3. Para pengajar di Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Udayana yang
mendorong terselesainya, tulisan ini.
Kritik, saran penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tulisan. Akhirnya
kata tulisan ini bermanfaat.
Bukit Jimbaran, Juli 2016
Penyusun

v
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ........................................................................................ i
ABSTAK ...................................................................................................... ii
ABSTRACT ................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR .................................................................................. iv
DAFTAR ISI ............................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 LatarBelakang ............................................................................ 3
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 3
1.3 Batasan Masalah ......................................................................... 3
1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................ 3
1.5 Manfaat Penelitian ...................................................................... 3
BAB II DASAR TEORI ............................................................................... 5
2.1 Sampah .................................................................................... 5
2.2 Jenis-jenis Sampatr Menurut Bentuknya ................................... 5
2.3 Sistem Pengolahan Sampah di TPA. ......................................... 5
2.4 Geolistrik ................................................................................. 7
2.5 Resistivitas Batuan ................................................................... 8
2.6 Potensial Listrik dalam Medium Homogen ............................... 9
2.7 Potensial untuk Titik Arus di dalam Bumi.. .............................. 11
2.8 Dua Elektroda Arus di Permukaan Bumi .................................. 12
2.9 Konfrgurasi Elektroda Schlumberger ........................................ 13
BAB III METODE PENELITIAN.......... ...................................................... 16
3.1 Waktu dan Tempat ..................................................................... 16
3.2 Spesifikasi Alat Geolistrik Hambatan Jenis ........................ ......... 16
3.3 Penentuan Lintasan ..................................................................... 18
3.4 Prosedur Akuisi Data .................................................................. 19
3.5 Pengolahan Data ........................................................................ 21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................. ......... 22
4.1 Analisa Hasil Pengolahan Data dengan Software Res2Dinv ........ 22
BAB V KESIMPULAN ................................................................................ 24

vi
5.1 Kesimpulan ................................................................................ 24
DAFTAR PUSTAKA

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan manusia di dunia selalu meninggalkan sisa, yaitu
barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Benda sisa tersebut karena
sudah tidak berguna lagi sehingga diperlakukan sebagai barang buangan, yang
berupa sampah dan limbah. Barang sisa dibuang berupa padatan akan
menhasilkan polutan menjadi penyebab turunnya kualitas lingkungan, mampu
membawa jenis-jenis penyakit. Bisa juga turunnya kegunaan sumberdaya alam,
yang dibabkan pencemaran lingkungan, tersuumbatnya irigasi dan berbagai
kejadian lainnya(Bahar, 1985).
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 menyatakan bahwa
rakyat di Indonesia, menghasilkan sampah perhari kira-kira 1 kg per orang atau
sekitar 220.000 ton dalam sehari. Setiap tahunnya jumlah sampah yang dihasilkan
penduduk Indonesia semakin bertambah. Semua kegiatan manusia tersebut,
akhirnya akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Secara umum ada tiga jenis TPA, yaitu tipe Open Dumping, Sanitary
Landfill dan Control Landfill. Pada tipe pertama, yaitu sampah dibuang,
meumpuk seperti gunung tanpa dibuakan saluran polutan sampah. Ini berkibat
terjadi pencemaran lingkungan di sekitar TPA. Tipe yang kedua adalah sistem
pengelolaan dengan membuang sampah di daerah lembah dengansyarat
mempunyai berporositas besar, dimana pada alasnya geotekstil untuk menghindari
masuknya lindi ke dalam batuan. Selanjutnya tipe terakhir adalah sistem
pengelolaan dengan cara sampah ditampung pada lokasi cekungan, lalu ditutupi
tanah, diratakan dengan ketebalan tertentu dan dilakukan secara periodik. Metode
ini dilengkapi dengan saluran pengeluaran gas di lahan tumpukan sampah.
Di Indonesia secara awalnya TPA banyak menggunakan sistem Sanitary
Landfill, namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar TPA di Indonesia
beralih menggunakan sistem open dumping(Kementerian Lingkungan Hidup,
2010). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sistem Sanitary
Landfill ke sistem open dumping, diantaranya diakibatkan faktor biaya yang
sangat mahal untuk mengelola TPA dengan sistem Sanitary Landfill. Dampak

2
negatif dari perubahan sistem ini adalah dapat merusak lingkungan hidup,
menimbulkan bau busuk, dan dapat mencemari air yang terkandung dalam lapisan
tanah.
Pembuangan akhir adalah salah satu contoh tempat menaruh sampah yang
dilakukan masyarakat Indonesia dengan menggunakan sistem terbuka. Tempat ini
hampir menerima semua sampah yang diproduksi di daerah perkotaan utamanya
dan sekelilingnya(DKP Kabupaten Gianyar, 2010). Jenis sampah hasil buangan di
daerah ini terbanyak dari jenis organik yang berasal dari pusat-pusat perbelanjaan
seprti pasar. Sistem pembuangan dengan cara seperti ini, sampahnya lebih cepat
mengalami pembusukan dibandingkan yang lain. Ketika busuk ada air yang
dihasilkan dan merambat ke dalam tanah.
Limbah berupa cairan yang dihasilkan merupakan efek samping
pembusukan, pada dsarnya berisi kandungan kimia, kotor, virus dan lainnya
mampu meresap ke dalam tanah. Jika terjadi hujan, maka lingkungan akan
tercemar oleh polutan tersebut. Rembesan hujan maupun oleh sampah itu sendiri
akan mencemari air tanah.
Air adalah kebutuhan vital bagi kelangsungan hidupmanusia. Dulu,
manusia hidup di tempat yang dekat sumber airnya, yaitu sungai, ataupun danau.
Hal ini memudahkan memperoleh air untuk kehidupan. Akibat menumpuknya
jumlah penduduk dan kemajuan teknologi berakibat keperluan akan air sangat
bertambah. Oleh sebab itu kebanyakkan manusia menggunakan air tanah dalam
kehidupannya. Air tanah yang rasanya tawar digunakan untuk pertanian,
perkebunan, minum, mandi, hewan dan tanaman. Menipisnya lahan pemukiman,
akibat dipakai prumahan, banyak orang-orang menetap di kota-kota besar dan
tinggal di daerah sekitar pembuangan samph. Masyarakat yang tidak mampu
membeli air dari PDAM akan menggunakan air sumur untuk kebutuhan vitalnya.
Bahkan tidak jarang masyarakat membuat sumur di daerah dekat pembuangan
samph. Hal ini akan berakibat seringnya masyarakat terjangkit penyakit menular,
muntaber, kolera dan penyakit lainnya. Untuk itu perlu ada antisifasi dalam upaya
kesehatan penduduk terjamin.
Konduktivitas dari cairan bekas sampah sampah diketahui mempunyai
nilai brbeda dengan airtanah lainnya. Dari penelitian sebelumnya yang telah

3
dilaksanakan, menunjukan bahwa limbah cair mempunyai konduktivitas yang
lebih gede daripada air lainnya. Harga hambatan jenis limbahcair lebih rendah
dari tanah air. Untuk air bersih adalah berharga diantara 10 -100 Ωm, sedangkan
menurut Handayani (2004) yang telah melakukan pengamatan lapangan
memonitor rembesan cairanlimbah di laboratorium, berhasil menentukan besar
resistivitas polutan sampah di bawah 10 Ωm. Dari nilai hambatan jenis ini akan
dicari tempat cairan berkumpul, merembes di sekitar pembuangan,
dimanfaatkannya beda nilai hambatan jenis.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan diatas, maka dalam penelitian
ini permasalahannya dapat dirumuskan dengan: dimana letak akumulasi sampah
tersebut terkumpul dan ke arah mana bergeraknya?
1.3 Batasan Masalah
Perlu ada batasan permasalah penelitian agar tidak melebar jauh, yaitu:
1. Metodenya adalah alat geolistrik resistivitas dengan konfigurasi
Schlumberger dan software interpretasi yang dipakai Res2dinv.
2. Dalam menentukan letak akumulasi polutan sampah, tidak menguraikan
secara spesifik polutan yang terindentifikasi.
1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk: mengidentifikasi letak titik akumulasi polutan
sampah yang dihasilkan dari pembusukan sampah (Studi kasus di TPA Temesi)
1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian bermanfaat untuk:
1. Mampu menyampaikan pola pikir penulis ke masyarakat, agar
permasalahan pencemaran lingkungan akibat sampah lebih dimengerti.
2. Di daerah manakah perkiraan cairan sampah terkumpul.

4
3. Berguna untuk antisipasi dini dalam usaha mengetahui tingkat pencemaran
lingkungan dan dipakai sebagai pedoman mengolah sampah dikemudian
hari.
4. Dapat memberikan referensi daerah yang tepat unfuk digunakan sebagai
tempat pemukiman masyarakat di sekitar TPA Temesi Gianyar

5
BAB II
DASAR TEORI
2.1 Sampah
Pengertian sampah dikemukakan oleh Achmad (2004), yaitu bagian dari
bahan tidak terpakai atau benda yang dibuang. Pada dasarnya asalnya dari
kegiatan manusia dan bersifat padat. Pengertian lain adalah limbah atau buangan
mempunya berfase padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan manusia
atau barang bekas tidak terpakai lagi, bisa juga kotoran hewan dan tumbuhann.
2.2 Jenis-jenis Sampah
Sampah menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi bagian padat dan cair.
Fase padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan
sampah cair. Dapat berasal dari sampah rumah tangga, dapur, kebun, plastik,
metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya dikelompokkan menjadi sampah
organik dan anorganik.
Jika berdasar tanah berkemampuan menguraikan, dibagi menjadi(Achmad,
2004):
1. Biodegradable adalah sampah yang gampang diuraikan oleh bakteri aeron
maupuan unaerob, sepeti bekas kotoran dari dapur, hewan peliharaan, dan
lain-lain.
2. Non-biodegradable adalah sisa yang suh diuraikan secara proses biologi.
Sampah jenis ini terbagi menjadi:
a. Recyclable: jenis sisa yang banyak diolah dan dimanfaatkan kembali
oleh manusia karena masih punya niali ekonomi tinggi. Ada yang
dipakai sebagai pas bunga, sapu bulu. Bahan-bahan yang dimanfaatkan
ini biasanya berjenis plastik, kertas atau kain.
b. Non-recycloble adalah barang bekas yang susah diolah atau didaur
ualng. Benda jenis ini misalnya rongsokan alat-alat elektronik paling
banyak.
Sampah cair adalah sisa yang tidak diperlukan kembali dan
dibuang ke tempat pembuangan, misalnya

6
1. Cairan berwarna hitam adalah sampahcair yang dihasilkan dari wc.
Sampah ini mengandung bakteri patogen yang berbahaya.
2. Hasil fluida dari masyarakat, yaitu sampah cair yang dihasilkan dari dapur,
kamar mandi dan tempat cuci pakaian. Sampah ini juga berbahaya.
Fase sampah dapat berupa padatan, cairan dan bisa juga menghasilkan gas.
Dalam kondisi fase kedua yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat
dikatakan sebagai emisi. Polusi gas buang emisi sangat berbahaya bagi
kelangsungan hidup manusia. Dengan kemajuan teknologi, aktivitas industri
menghasilkan limbah, terbanyak misalnya pertambangan.
2.3 Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap barang sisa dengan tujuan
mempersedikit bahkan kalau bisa mampu menghilangkan permasalahan yang ada
kaitannya dengan kerusakanlingkungan. Sesuai ilmu lingkung, suatu pengolahan
sampah dianggap baik jika yang diolah tidak menjadi tempat berkembang biaknya
bibit penyakit serta menjadi perantara penyebarluasan suatu bakteri berbahaya.
Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tidak mencemari udara, air, atau tanah.
Bahkan tidak menimbulkan bau, serta kebakaran.
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan kegiatan dalam mengelola
sampah dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Terjangkau
b. Batuan susah ditembus air,
c. Tanahnya tidak lagi dipakai pertanian,
d. Jangka waktu lama, minimal 5-10 tahun,
e. Jauh dari sumber air bersih.
f. Daerahnya bebas banjir
Jenis sistem pembuangan akhir sampah antara lain(Arifin,F.2001) :
1. Sistem pembuangan terbuka. Cara ini dilakukakn ketika manusia muali
ada. Sampah dibuang begitu saja, tanpa perlauan apa-apa. Biasanya model
ini menjadi tempat berkembang biak beberapa penyakit. Lingkungan akan

7
tercemari oleh sampah, diterbangkan angin, bahkan hewan-hewanpun ikut
membawa ke sekitarnya. Metode ini menjadikan:
a. Tercemarnya udara
b. Tanah juga tercemar
c. Menimbulkan kebakaran
d. Terbentuk asap akibat pembakaran
e. Menjadi sarang penyakit
f. Lingkungan nyaman dilihat,
g. Munculnya binatang-binatang seperti tikus, kecoak dan lain-lain
h. Bekas area pembuangan sussa dijadikan funsgi lain, apalagi
pertanian.
2. Pembuangan sampah dengan pengurugan yang dikendalikan. Sampah
dibuang di daerah lembah dan setelah tinggi diatasnya ditumpuk dengan
tanah. Metode ini dilengkapi dengan saluran pengeluaran gas di lahan
tumpukan sampah.
.
Pengeloaan sampah di Indonesia rata-rata kurang begitu baik. Sebagai
contoh, masih banyak tempat pembuangan yang menghasilkan bau yang
menyengat. Tidak ada saluran air, bahkan dibeberapa kota di Indonesia sampah
berminggu-minggu tidak diangkut.
2.4 Geolistrik
Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika yang mempelajari sifat
aliran listrik di dalam bumiPendekteksian di atas permukaan bumi meliputi
pengukuran medan potensial, arus dan elektromagnetik yang terjadi baik secara
alamiah maupun terhadap penginjeksian arus ke dalam batuan. Metode yang
terkenal adalah(PT Gada Energi, 2015).:
1. Potensial diri
2. Arus telurik
3. Magnetotelurik
4. Elektromagnetik
5. Induced Polarization

8
6. Tahanan Jenis
Ada beberapa konfigurasi dalam pengambilan data, diantaranya Wenner,
Schrumberger, Wenner-Schlumberger, Dipol-dipor, Rectangle Line source dan
sistem gradien 3 titik(Hendrajaya dan Idam (1990).
Hambatan listrik di antara 2 titik dapat diketahui dengan menggunakan Hukum
Ohm(Azhar, Handayani, 2004)
.
R= 𝑣
𝑙…………………………………………..(2.1)
Dengan:
R = hambatan
V = perbedaan tegangan
i = aruslistrik (ampere)
Peralatan yang menghitung nilai resistivitas paling efektif jika dipakai
untuk exploitasi dan explorasi yangtidak dalam. Kemampuan alat mendeteksi
paling efektif kurang dari 300 meter. Oleh karenanya peralatan ini tidak baik
untuk mencari minyak. Sering sekali alat ini digunakan untuk mencari sumber-
sumber air, lapisan lempung tanah atau geotermal(Telford, W. M., dkk., 1990)
2.5 Resistivitas Batuan
Dari semua sifat fisika batuan dan mineral, resistivitas memperlihatkan
variasi harga yang sangat banyak, pada logam nilainya berkisar pada 10-8
Ωm
hingga 107Ωm. Begitu juga batuan-batuan lain, dengan komposisi berbeda akan
menghasilkan rentang resistivitas yang bervariasi pula, sehingga nilai
maksimumnya mungkin dari 1.6 x 10-8
Ωm (perak) hingga 1016
Ωm pada belerang
mumi(Telford, W. M., dkk., 1990).
Konduktor didefinisikan sebagai bahan yang memiliki resistivitas kurang dari
10-6
Ωm, sedangkan isolator bernilai lebih dari 107 Ωm. Secara umum, berdasarkan
nilai resistivitas listriknya, batuan dan mineral dapat dikelompokan menjadi tiga
(Telford, W.M., dkk 1990), yaitu:
a. Konduktor baik : 10-8
< p <1 Ωm
b. Semikonduktor : 1 < p < 107Ωm
c. Isolator : p > 107Ωm

9
Tabel 2.1. Variasi Nilai Resistivitas Material Bumi
2.6 Potensial Listrik dalam Medium Homogen(Telford, W.M., dkk 1990),
Dalam menginterpretasikan pengukuran pada metode georistrik, biasanya
bumi dianggap homogen isotropis, yaitu setiap lapisan memiliki resistivitas yang
sama. Prinsip dasar dari metode geolistrik resistivitas adalah mengukur respon
berupa potensial pada suatu elektroda akibat arus yang diinjeksikan ke dalam
bumi.
Gambar 2.1 Aliran arus listrik dan bidang ekuipotensial oleh satu titik sumber
pada suatu kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi(Telfod,
1990)

10
Perumusan teoritis metode geolistrik resistivitas didasarkan pada prinsip
perhitungan potensial listrik pada suatu medium tertentu akibat suatu sumber arus
listrik di permukaan bumi. Bidang eqipotensial dari arus listrik akan menyebar ke
segala arah dan permukaan-permukaan dalam bumi berupa permukaan
bola(Telfod, 1990)
Jika lapisan homogenisotropis dialiri aruslistrik searah I (diberi
medanlistrik E) maka elemen δI yang melalui luasan δA rapatnya J, maka:
δI= 𝐽 δ𝐴 ……………………………………….(2.2)
Berdasarkan hukum Ohm hubungan antara rapat arus 𝐽 dengan medan listrik
𝐸 diperoleh:
𝐽 = σ𝐸 ………………………………………..(2.3)
Di mana:
σ = Konduktivitas bahan (l/Ωm)
E = kuat medan listrik (volt/meter)
Medan listrik (𝐸 ) merupakan gradien dari potensial skalar, sehingga
𝐸 = ∇ V……………………………………...(2.4)
maka persamaan (2.3) menjadi :
𝐽 = -σ∇ V………………………….. .... ........(2.5)
Arus listrik mengalir pada medium homogen memenuhi persamaan:
∇ .𝐽 = 0……………………………………....(2.6)
Substitusi persamaan (2.5) ke persamaan (2.6), maka :
∇ .(- σ ∇ 𝑉 )=0. ............................................(2.7)
Pada medium homogen isotropis, o adalah konstanta sehingga menjadi :
∇2 V = 0............................................ ..........(2.8)
Persamaan (2.8) merupakan persamaan Laplace.

11
2.7 Potensial untuk Titik Arus di dalam Bumi
Jika arus yang masuk ke dalam medium homogen isotropis sumbernya
adalah tunggal, maka garis potensial akan berbentuk bola. Dalam koordinat bola
operator Laplacian dapat dituliskan sebagai berikut :
Karena lapisan homogen isotropis maka medium mempunyai simetri bola dan
karena arus yang melintas sebidang dengan arah θ serta Ø, jadinya V hanya
sebagai fungsi dari jarak:
Kalikan persamaan (2.12) dengan r2, maka didapat :
Dengan mengintegrasi dari persamaan (2.13) maka didapat :
Integrasi dari persamaarr (2.14), akanmenghasilkan persamaan berikut :
V = - 𝐴
𝑟 + B……………………………………….........(2.15)
Catatan:
A, B = konstanta
Pada saat V = 0, maka B = 0. Dengan mesubstiusi ini didapat
V = -𝐴
𝑟 ……………...............................……………………..(2.16)
Arus keluar secara radial melewati permukaan bola dengan jari-jari r adalah :

12
Karena σ = 1
𝜌 maka persamaan di atas menjadi :
A = 𝑙𝜌
4𝜋 …………………………………………………….(2.19)
Maka:
V = 𝑙𝜌
4𝜋
1
𝑟 atau 𝜌 =
4𝜋𝑟𝑉
𝐼…………………………………...(2.20)
2.8 Elektroda Arus
Seandainya kita memasang dua buah elektroda dan padanya dialirkan arus,
maka potensialnya dapat diukur seperti gambar (2.2). Besarnya tegangan di titik
P1 oleh sebab arus elektroda C1 adalah (Hendrajaya, Idam, 1990)
V11 = 1𝜌
2𝜋
1
𝑟1 …………………………………………(2.21)
Besarnya tegangan di titik P1 akibat C2 dapat ditulis:
V12 = - 1𝜌
2𝜋
1
𝑟2 ………………………………………(2.22)
Sehingga potensial total pada titik P1 oleh C1 dan C2 dapat dinyatakan dengan:
V11 + V12 = 1𝜌
2𝜋
1
𝑟1−
1
𝑟2 …………………………….(2.23)
Sama seperti di atas untuk titik P2 oleh Cr serta C2 adalah:
V21 + V22 = 1𝜌
2𝜋
1
𝑟3−
1
𝑟4 ……………………………………..(2.24)
Akan ada beda tegangan diantara P1 dengan P2 ialah

13
:
∆𝐹 = 1𝜌
2𝜋
1
𝑟1−
1
𝑟2 −
1
𝑟3−
1
𝑟4 ……………………………..(2.25)
Gambar 2.2. Bidang ekipotensial (Telfod, 1990)
Konfigurasi dengan 4 elektroda inilah yang biasanya digunakan dalam
pengambilan data di lapangan
2.9 Konfigurasi Elektroda Schlumberger
Pada dasarnya tujuan survei geolistrik tahanan jenis adalah untuk
mengetahui resistivitas lapisan batuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan
pengukuran di permukaan bumi. Resistivitas bumi berhubungan dengan jenis
mineral, kandungan fluida dan derajat saturasi air dalam batuan.
Pengaturan letak probe atau elektrode bisa bervariasi sesuai dengan
kebutuhan dan keadaan permukaan. Konfigurasi yang ada diantaranya
(Handayani, Idam, 1990)
a. Schlumberger.
b. b. Wenner
c. c. Diple-Dipole
d. Pole-pole
e. Pole-dipole

14
Prinsip konfigurasi Schlumberger idealnya jarak antara MN dibuat
sekecil-kecilnya dan secara teoritis tidak berubah. Tetapi karena keterbatasan
kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB sudah dirubah relatif lebih besar maka
MN hendaknya dirubah pula. Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar
dari 1/5 AB seperti gambar 2.3.
Gambar 2.3 Skema Konfigurasi Schlumberger (Hendrajaya, Idam, 1990)
Dua elektroda arus dipermukaan bersumber dari +1 di titik C1, dan - 1
dititik C2 pada (Gambar 2.3) memungkinkan jumlah distribusi potensial
kombinasi ditemukan disetiap tempat.
Potensial di titik P1:
V1 = 1𝜌
2𝜋
1
𝑟1−
1
𝑟2 …………………………………(2.26)
Gambar 2.4 Skema peralatan resistivitas model Schlumberger(Handayani, Idam, 1990)
Potensial di titik P2 :
V1 = 1𝜌
2𝜋
1
𝑟3−
1
𝑟4 …………………………………………(2.27)

15
Potensial diantara P1, dan P2 kemudian menjadi :
∆𝑉 = 𝑉1 – V2
∆𝑉 = 1𝜌
2𝜋
1
𝑟1−
1
𝑟2−
1
𝑟3+
1
𝑟4 ………………………………………..(2.28)
Diperoleh resistivitas rho (𝜌)
𝜌 = ∆𝐹
1 2𝜋
1
𝑟1−
1
𝑟2−
1
𝑟3+
1
𝑟4 -1
………..........................................(2.29)
K = 2𝜋 1
𝑟1−
1
𝑟2−
1
𝑟3+
1
𝑟4 -1
………….............................…………(2.30)
𝜌 = ∆𝑉
𝐼 x K ………………………….............................……………(2.31)
Dimana:
𝜌 = Resistivitas (Om)
r1= Jarak antata C1dan P1 (m)
r2 = Jarakantara P1 dan C2(m)
r3 = Jarakantara C1dan P3(m)
r4 = Jarakantara P2 dan C3(m)
K = Faktor geometri (m)
Persamaan ∆𝑉
𝐼 adalah hambatan diantara P1 dan P2, dan dalam kurung sebagai
faktor geometri (K) bergantung pada posisi tempat titik elektroda.

16
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Tempat
Lokasi penelitian adalah di tempat pembuangan akhir yang ada di
Kabupaten Gianyar. Koordinatnya adalah pada titik 8033'124"- 8
033'256" LS dan
115 021’012’’ – 115
021’013’’ BT. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 70 dan
luas areanya kurang lebih 4 hektar(DKP Kabupaten Gianyar, 2010). Daerahnya
dikelilingi sawah, hanya disebelah utara ada pemukiman penduduk.
Gambar 3.1. Lokasi Penelitian TPA Temesi Gianyar(DKP Kabupaten Gianyar, 2010).
3.2. Spesifikasi Alat Geolistrik Hambatan Jenis
Alat yang digunakan adalah geolistrik (resistivity meter) adalah jenis
Naniura NRD 300 HF (Anggraeni,F, 2004) dengan spesifikasi sebagai berikut :

17
1. Pemancar
Adapun spesifikasi pemancar dari alat geolistrik (resistivity meter)
Naniura NRD 300 HF yang digunakan adalah seperti pada tabel.
Tabel 3.1. Spesifikasi pemancar alat geolistik hambatan jenis
Pemancar Spesifikasi
d. Catu daya
e. Daya
f. Tegangan keluaran
g. Arus keluar
h. Ketelitian
i. Sistim pembacaan
j. Catu daya digitalmeter
k. Fasilitas
12 volt
300 Watt (>20 A)
500 Volt
Maksimum 2000 mA
1 mA
Digital
9 volt, baterai kosong
Current loop indicator
2. Penerima
Adapun spesifikasi pemancar dari alat geolistrik (resistivity meter)
Naniura NRD 300 HF yang digunakan adalah seperti pada Tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.2. Spesifikasi penerima pada alat geolistik hambatan jenis(Anggraeni,F, 2004)
Penerima Spesifikasi
l. Impedansi masukan
m. Batas pengukuran
n. Kepekaan potensial
o. Kompensator
a. Kasar
b. Halus
p. System pembacaan
q. Catu daya digital meter
r. Fasilitas pembacaan alat
s. Berat alat
10 M-Ohm
10-1
mV s/d 500 V
0,1 mV
10 x putaran
1 x putaran
Digital
3 volt
Hold (data disimpan
di memory)
5 kg

18
Gambar 3.2 Peralatan yang digunakan.
Keterangan Gambar 3.2 :
1. Geolistriktipe Naniura NDR 300 HF.
2. Dua gulung kabel elektroda arus.
3. Dua buah kabel elektroda potensial.
4. Accu 24 volt.
5. Empat buah elektroda arus dan potensial
6. Empat buah palu untuk menanam elktroda.
3.3. Penentuan Lintasan
Hampir seluruh areal yang mengelilingi TPA merupakan persawahan dan
beberapa pemukiman penduduk. Di utara TPA merupan areal persawahan dan
pemukiman penduduk. Hamparan sawah yang sangat luas juga terdapat di timur
dan selatan TPA, pemukiman penduduk yang berada di timur TPA merupakan
penduduk yang berprofesi sebagai pemulung yang mencari barang bekas di TPA.
Di sebelah selatan terdapat beberapa rumah penduduk yang berprofesi sebagai
petani. Daerah penumpukan sampah secara open dumping paling banyak terdapat
di bagian selatan TPA.
Sampah yang ditampung akan mengalami proses pembusukan akibat tidak
ada ozon yang masuk. Hal ini mengakibatkan terbentuknya polutan sampah yang
semakin lama jumlah polutan ini akan semakin meningkat seiring dengan

19
peningkatan volume sampah. Letak pusat pembuangan sampah yang letaknya
relatif tinggi dari pada daerah sekitamya, akan mengakibatkan polutan tersebut
mengalir dan merembes ke daerah yang lebih rendah di sekitarnya.Hasil dari
observasi ini digunakan untuk menentukan letak lintasan. Lintasan diambil
berdasarkan bentuk topografi lokasi penelitian dan letak sampah lama atau
sampah baru. Lintasan yang diambil tidak sejajar karena kondisi lokasi penelitian
mempunyai relief yang tidak rata. Letak lintasan dapat dilihat pada Gambar 3.3
berikut ini.
Gambar 3.3. Letak lintasan pengukuran TPA Temesi Gianyar
3.4. Prosedur Akusisi Data
Tahap pengambilan data yang dimaksudkan adalah primer yang didapat
melalui suatu pengukuran. Besaran yang diukur adalah arus listrik (I), tegangan
(V) dan faktor geometri K (m). Data yang tercatat adalah nilai semu dari
resistivity. Adapun tahapan pada saat penelitian adalah:
a. Ukur panjanglintasan.

20
b. Berikan spasi awal yaitu a = 2 m (n=: l) dan ditandai dengan pasak.
Jangkauan ini disesuaikan dengan aturan konfigurasi
Schlumberger.
c. Pasang keempat elektroda sebagai arus dua dan sisanya untuk
potensial ditempat yang sudah ditandai dengan pasak.
d. Hubungkan keempat elektroda tersebut dengan resistivity meter
dengan menggunakan kabel.
e. Aktifkan resistivity meter, kemudian lakukan injeksi arus listrik ke
dalam tanah.
f. Catat nilai tegangan (mv) dan arus (mA) sebagai data akhir dari
alat resistivity meter.
g. Pindahkan posisi elektroda sesuai dengan aturan konfigurasi
Sclumberger, kemudian injeksikan arus dan catat hasilnya.
Pemindahan dilakukan sampai seluruh panjang lintasan yang telah
ditetapkan terlingkupi.
h. Pada pengukuran kedua (n = 2), spasi antara elektroda potensial
tidak berubah yaitu a = 2 m. Kemudian lakukan serupa seperti
langkah di atas. Pemasangan elektroda untuk 1-D dan 2-D dapat
dilihat pada gambar (3.4) dan (3.5)(Hendrajaya, Idam, 1990)
Gambar (3.4) Pemasangan elektroda 1-D(Gada Energi, 2015)

21
Gambar 3.5 . Pengaturan elektroda 2-D (Hendrajaya, Idam, 1990)
Pengukuran geolistrik 1-D dilakukan untuk menentukan distribusi nilai tahanan
jenis batuan terhadap kedalaman pada suatu titik. Semakin panjang lintasan, maka
pendugaan akan lebih dalam.
3.5. Pengolahan Data
Hasil pencatatan data yang telah diperoleh berupa besar arus listik (I),
potensial listrik (v) digunakan untuk menghitung resistivitas semu, dengan
mengalikan nilai faktor geometri yang telah dihitung berdasarkan jarak keempat
elekhoda y'ang diletakan pada lintasan pengukuran tersebut. Pengamatan akan
menghasilkan nilai semu dari hambatan batuan. Data yang diperoleh berupa
resistivitas semu dari perhitungan, spasi elekrroda potensial, nilai n, dan datum
point (dp\ diketik pada notepad dan disimpan dalam bentuk format dat kemudian
diinterpretasikan ke dalam sofiware Res2Dinv.
Software Res2Dinv berfungsi untuk menentukan nilai resistivitas
sebenarnya dan kedalaman lapisan sekaligus menggambarkan pola rembesan
polutan dalam tanah. Proses pengolahan data dengan komputer dapat dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut(Bahri, 2005): Data-data yang telah tersimpan
dalam format dat, dibuka melalui software Res2Dinv.

22
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisa Data dengan Sofware Res2Dinv(PT Gada Energi, 2015)
Setelah dilakukan perhitungan menggunakan sofware Res2dinv yang
tersedia, maka diperoleh hasil seperti di bawah ini.
Gambar 4.1 Penampang resistivitas hasil inversi pada lintasan 1
Gambar 4.1 di atas adalah hasil setelah data-data lapangan pada lintasan 1
dengan panjang lintasan 36 m diiterpretasikan ke dalam Software Res2Dinv . Dari
Gambar 4.1 tersebut dapat dinyatakan bahwa polutan sampah tersebar dari titik 10
m sampai pada titik 32 m dari lintasan pengukuran dengan titik koordinat 8033'75"
- 8033'761" LS dan 115
021’024’’ - 115
0 21’014’’ BT, pada kedalaman 1,55 - 5,37
m. Pada lintasan 1 polutan sampah digambarkan oleh warna biru ketuaan dan
birumuda dengan nilai resistivitas 5,30 - 7,78 Ωm. polutan sampah tersebut
terakumulasi pada titik 22 - 30 m dengan titik koordinat 8 0 33'75’’ - 8
013'76" LS
dan 115 021'019" -

23
Gambar 4.2 Penampang resistivitas hasil inversi pada lintasan 2
Gambar 4.2 di atas adalah gambar yang dihasilkan setelah data-data lapangan
pada lintasan 2 dengan panjang lintasan 52 m diiterpretasikan ke dalam Software
Res2Dinv . Dari Gambar 4.2 tersebut dapat dinyatakan bahwa polutan sampah
merembes pada dua daerah yaitu daerah pertama dari titik 12 - 24 m dengan titik
koordinat 8033'740" - 8
033'746" LS dan 115
021’011’’ - 115
021’013’’. BT
dandaerah kedua dari titik 30 - 40 m pada koordinat B 033'749’’ - 8
033'755" LS
dan 1 15021'014’' - 115
021'016" BT dengan resistivitas rendah, yang dicitrakan
dengan warnabiru tua dan biru mudah dengan nilai resistivitas 1,84 - 4,68 Ωm
dengan kedalaman 2,70 - 8,68 m. Untuk daerah pertama, polutan tersebut
terakumulasi dari titik 18 – 22m dengan koordinat 8033'743’' - 8
033'745" LS dan
115 0
21’012’’ - 115 021’013’’ BT dari lintasan tersebut. Sedangkan untuk daerah
kedua, polutan sampah tersebut terakumulasi dari titik 32 m sampai pada titik 38
m dari lintasan pengukuran tersebut dengan titik koordinat 80 33'750"- 8
033'754’’
LS dan 115 021’015’’- 115
0 21’016’’ BT.

24
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Hasil pengukuran nilai resistivitas semu pada lapisan tanah di area TPA
Temesi Gianyar menunjukan adanya polutan sampah dengan kisaran 1,84
-9,87 Ωm, yang sebagian besar merembes ke arah selatan sejauh lebih dari
400 m. Polutan tersebut rata rata berada pada kedalaman 1,55 - 6,91 m.
2. Titik akumulasi polutan sampah terdapat pada lintasan 1, dengan
titikkoordinat 8 0 33'75" - 8
0 33'76" LS dan 115
021'019’’ - 115
021'016"
BT dan pada kedalaman 2,70 - 5,37 m. Pada lintasan 2 terakumulasi pada
dua tempat. Daerah pertama terletak pada koordinat 8 0'33'743’’ - 8
033'745" LSdan 115
021'O12’’ - 115
021'013" BT dan daerah kedua
terletak pada titik koordinat 80 33'750"- 8
0 33'754" LS dan 115
0 21'015"-
115 0 21'016"BT. Kemudian pada lintasan 3 terletak pada koordinat 8
033'715" – 8
033'719" LS dan 115
021'019" - 115
021'018" BT, dan lintasan
7 terletak pada titik koordinat 8 033'755" - 8
033'756" LS dan
115021’017’’– 115
021'015" BT.

25
DAFTAR PUSTAKA
Achmad,R.2004. Kimia Lingkungan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Anggraeni,F 2004. Aplikasi Metoda Geolistrik Resistivity untuk Mendeteksi Air
Tanah..Jember
Apparao, A. 1997. Development in Geoelectrical Methods. National Geophysics
Reasearce Institute Hyderabad. India
Arifin,F.2001. Tinjauan Geohidrologi Sebagai Salah Satu Pertimbangan Dalam
Pemilihan Lokasi TPA Sampah (Studi Kasus TPA Sampah Tamangapa
Makassar), Makassar.
Azhar dan Handayani Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger untuk
Penentuan Tahanan Jenis Batubara, Bandung
Broto, S. dan Afifah,R.S.2008. Pengolahan Data Geolistrik dengan Metode
Schlumberger. Teknih Vol.29, No. 2, ISSN 0852-1697..
Daftar Isian Adipura Kabupaten Gianyar, 2009-2010.
DKP Kabupaten Gianyar.2010.
Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelola Sumber Daya dan
LingkunganPerairan. Kanisius. Yogyakarta.
Hendrajaya, L., Arif Idam, 1990. Geolistrik Tahanan Jenis
Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP
85/1999
PT Gada Energi, 2015, Hydrogeophysich Dan Explorasi Mineral: Aplikasi
Metode Geolistrik 1D dan 2D, ITB
Telford, W. M., Geldart, L. P., and SherifT R. E., (1990). Applied Geophysics,
2nd
edition, Cambridge University Press, USA.