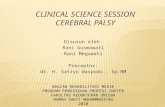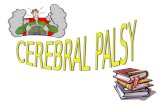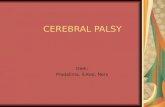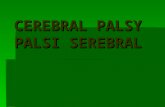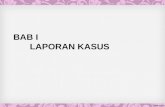Penatalaksanaan fisioterapi pada kasus cerebral palsy spastic quadriplegic
-
Upload
vertilia-desy -
Category
Health & Medicine
-
view
27.233 -
download
7
description
Transcript of Penatalaksanaan fisioterapi pada kasus cerebral palsy spastic quadriplegic

PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS
CEREBRAL PALSY SPASTIC QUADRIPLEGIC
DISUSUN OLEH :
Ade Fitri (1006719652)
AsmallahPutriWandasari (1006778011)
IrmanGalihPrihantoro (1006778213)
Nabila Fatana (1006720181)
VertiliaDesi (1006720420)
PROGRAM VOKASI KEDOKTERAN
BIDANG STUDI FIFIOTERAPI 2010
UNIVERSITAS INDONESIA

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena akan
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan makalah konferensi kasus Fisioterapi Pediatri (FT A) dengan tepat
waktu.
Pembuatan makalah ini bertujuan untuk melengkapi tugas dalam Praktek
Klinik I Semester V.
Dalam penyusunan makalah ini kami telah banyak memperoleh bimbingan
dan dukungan dari berbagai pihak baik dokter, instruktur atau fisioterapis, senior
fisioterapis angkatan 2009, dan teman-teman seperjuangan.Oleh sebab itu pada
kesempatan kali ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah banyak membantu penyusunan makalah ini.
Kami menyadari tanpa bimbingan dan pengarahan dari semua pihak, maka
laporan ini tidak akan tersusun dengan baik. Pada kesempatan kali ini kami
mengucapkan terima kasih kepada dokter, dosen mata ajar fisioterapi pediatri,
seluruh pembimbing praktek klinik fisioterapi di Rumah Sakit Umum Pusat
Nasional Dr Cipto Mangunkusumo dan teman-teman mahasiswa fisioterapi
Universitas Indonesia.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
makalah konferensi ini. Oleh sebab itu penulis mengaharapkan saran-saran dan
kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga
makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan rekan-
rekan fisioterapis pada khususnya.
Makalah ini belum atau tidak bisa dijadikan acuan sebelum disetujui dosen
pembimbing dan dikonferensikan atau dipresentasikan.
Jakarta, 23 November 2012
Penulis
i

LEMBAR PENGESAHAN
Makalah konferensi kasus telah dikoreksi, disetujui, dan diterima Pembimbing
Praktek Klinik Program Studi Fisioterapi Pediatri (FTA) RSCM untuk
melengkapi tugas Praktek Klinik dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti
Ujian Akhir Semester (UAS) 2012.
Pada hari : Selasa
Tanggal : 27 November 2012
Pembimbing,
…………………..………
Sri Novia Fauza, S. ST. FT
ii

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................i
LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................................................ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Masalah ...............................................................................1
b. Identifikasi Masalah .....................................................................................2
c. Rumusan Masalah.........................................................................................2
d. Tujuan Penulisan ..........................................................................................3
e. Metode Penulisan .........................................................................................3
BAB II KAJIAN TEORI
1. Definisi Cerebral Palsy.................................................................................5
2. Anatomi dan Fisiologi Otak.........................................................................6
3. Patofisiologi Cerebral Palsy.......................................................................10
4. Etiologi Cerebral Palsy...............................................................................11
5. Manifestasi KlinisCerebral Palsy...............................................................14
6. PrognosisCerebral Palsy.............................................................................15
7. Klasifikasi Cerebral Palsy..........................................................................17
8. Cerebral PalsySpastik Quadriplegi.............................................................23
9. Penatalaksanaan Fisioterapi pada Cerebral PalsySpastik Quadriplegi
26
BAB III ISI
1. Formulir fisioterapi ....................................................................................51
BAN IV PENUTUP
1. Kesimpulan .................................................................................................69
2. Saran ...........................................................................................................69
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................70
iii

LAMPIRAN..................................................................................................................72
iii

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2003 memperkirakan
jumlah anak penyandang cacat di Indonesia sekitar 7-10% dari jumlah
penduduk Indonesia. Sebagian besar anak penyandang cacat atau sekitar
295.250 anak berada di masyarakt dalam pembinaan dan pengawasan orang
tua dan keluarga. Pada umumnya mereka belum mendapatkan pelayanan
kesehatan sebagaimana mestinya (Depkes, 2011). Kecacatan ini timbul
karena bawaan lahir ataupun didapat setelah lahir. Adapun faktor – faktor
yang mempengaruhi yaitu natal, prenatal, postnatal, dan social ekonomi.
Banyak jenis kecacatan yang terjadi pada anak, diantanranya adalah
Cerebral Palsy. Cerebral Palsy sendiri merupakansekelompok gangguan
gerak atau postur yang disebabkan oleh lesi yang tidak progresif yang
menyerang otak yang sedang berkembang atau immatur. Lesi yang terjadi
sifatnya menetap selama hidup, tetapi perubahan gejala bisa terjadi sebagai
akibat proses pertumbuhan dan maturasi otak. Kerusakan jaringan saraf yang
tidak progresif pada saat prenatal dan sampai 2 tahun post natal termasuk
dalam kelompok Cerebral Palsy.
Di Indonesia 1 - 5 dari setiap 1.000 anak yang lahir hidup di Indonesia
memiliki kondisi tersebut. Sedangkan di USA ada kecenderungan
peningkatan prevalensi pada dua dekade terakhir. Hal ini disebabkan
kemajuan penanganan obstetri dan perinatal, sehingga terdapat peningkatan
bayi immatur, berat lahir rendah dan bayi prematur dengan komplikasi yang
bertahan hidup. Insiden bervariasi antara 2-2,5/1000 bayi lahir hidup. Di USA
perkiraan prevalensi pada yang sedang atau berat antara 1,5-2,5/1000
kelahiran, kurang lebih mengenai 1.000.000 orang (Elita Mardiani, 2006).
Cerebral Palsy bukanlah termasuk penyakit secara tersendiri, tetapi
istilah yang diberikan untuk sekelompok gejala motorik yang bervariasi
akibat lesi otak yang tidak progresif. Akibat lesi otak yang bevariasi maka
muncul berbagai macam klasifikasi Cerebral Palsy, diantaranya berdasarkan
1

bagian tubuh yang terkena atau topografinya pada tubuh; hemiplegic,diplegic,
atau quadriplegic; gangguan motorik yang dominan; apakah itu spastic,
floopy, atau athetose. Nantinya dalam makalah ini akan dibahas secara
mendalam tentang Cerebral Palsy Spastic Quadriplegic.
2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
kami sebagai penulis dapat mengidentifikasikan masalah untuk kasus tersebut
sebagai berikut:
a. Gangguan ambulasi dan transfer
b. Gangguan gerak
c. Gangguan Postur
2.1 Pembatasan Masalah
Banyaknya jenis dan masalah yang timbul pada kasus
Cerebral Palsy, maka kami akan membatasi permasalahan yang
akan dibahas dalam makalah ini. Adapun masalah yang dibahas
akan dibatasi pada Penatalaksanaan fisioterapi pada penderita
Cerebral Palsy Spastic Quadriplegic.
2.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah:
1. Apa definisi dari Cerebral Palsy?
2. Bagaimana anatomi dan fisiologi otak?
3. Bagaimana epidemiologi dari Cerebral Palsy?
4. Bagaimana Patofisiologi dari Cerebral Palsy?
5. Apa etiologi dari Cerebral Palsy?
6. Apa saja manifestasi klinis dari Cerebral Palsy?
7. Bagaimana prognosa dari Cerebral Palsy?
8. Apa definisi dari Cerebral Palsy Spastic Quadriplegic?
2

9. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Cerebral
Palsy Spastic Quadriplegic?
3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi dua,
yakni:
3.1 Tujuan Umum
3.1.1 Karya tulis ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kami
sebelum kami pindah stase pada peminantan lain.
3.1.2 Untuk mengaplikasikan pengetahuan kami dalam mengatasi
masalah pada kasus Cerebral Palsy Spastic Quadriplegic
3.2 Tujuan Khusus
3.2.1 Mengetahui definisi dari Cerebral Palsy
3.2.2 Mengetahui anatomi dan fisiologi otak
3.2.3 Mengetahui patofisiologi dari Cerebral Palsy
3.2.4 Mengetahui etilogi dari Cerebral Palsy
3.2.5 Mengetahui manifestasi klinis dari Cerebral Palsy
3.2.6 Mengetahui prognosa dari Cerebral Palsy
3.2.7 Mengetahui klasifikasi dari Cerebral Palsy
3.2.8 Mengetahui definisi dari Cerebral Palsy Spastic
Quadriplegic
3.2.9 Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kasus
Cerebral palsy
3

4. Metode Penulisan
Dalam Penyusunan makalah ini, metode yang kami gunakan adalah
metode kepustakaan yaitu dengan membaca buku – buku yang bersangkutan
dengan kasus ini. Selain itu kami juga mencari literatur dari internet untuk
menambah informasi yang bersangkutan, dan observasi langsung pada pasien.
Dalam sistematika penulisan, BAB I merupakan pendahuluan yang
meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika
penulisan.BAB II merupakan kajian teori yang meliputi definisi, anatomi
fisiologi otak, epidemiologi, patofisiologi, etiologi, manifestasi klinis,
prognosis, dan penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Cerebral Palsy Spastic
Quadriplegic. BAB III merupakan pembahasan status, serta BAB IV yang
merupakan penutupan berupa kesimpulan dan saran.
4

BAB II
KAJIAN TEORI
1. Definisi Cerebral Palsy
Cerebral Palsy adalah kondisi neurologis yang terjadi permanen tapi tidak
mempengaruhi kerusakan perkembangan saraf karena itu bersifat non progresif
pada lesi satu atau banyak lokasi pada otak yang immatur (Campbell SK et al,
2001 dalam Jan S, 2008).
Cerebral palsy adalah masalah-masalah pada sistem saraf pusat yang
berakibat tidak berkembangnya sistem saraf pusat atau mempengaruhi otak
atau tulang belakang (Pamela, 1993).
Cerebral palsy mencakup kelompok dari kondisi yang mempengaruhi
anak sehingga memiliki kekurangan dalam kontrol pergerakan. Cerebral palsy
adalah sebuah gangguan dari perkembangan dan postur dikarenakan sebuah
kerusakan atau lesi dari otak yang belum berkembang (Bax, 1964). Biasanya
yang dijadikan acuan onset kejadiannya sebelum 3 tahun. Lesi saraf pada
cerebral palsy tidak progresif, walaupun menjadi perubahan dan variasi dalam
perjalanannya tergantung kelainan yang terlihat dan perkembangan pada tiap
anak. Perubahan ini terjadi tergantung dari beberapa faktor yakni maturasi
otak, pertumbuhan tubuh, keseimbangan otot, dan gerakan anak dan
kecenderungan postur (Pamela, 1993).
5

2. Anatomi Fisiologi Otak
Brain anatomy. The brain is presented in three views: lateral, coronal, and midsaggital (Lane R. et al, 2009).
2.1. Bagian – bagian Otak
Otak mengatur dan mengkordinir sebagian besar gerakan, perilaku
dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah,
keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung
jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia.
Otak dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena
infeksi maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Ketiga lapisan
membran meninges dari luar ke dalam adalah sebagai berikut.
6

a. Duramater atau Lapisan Luar
Duramater kadangkala disebut pachimeningen atau meningen fibrosa
karena tebal, kuat, dan mengandung serabut kolagen. Pada duramater
dapat diamati adanya serabut elastis, fibrosit, saraf, pembuluh darah,
dan limfe. Lapisan dalam duramater terdiri dari beberapa lapis fibrosit
pipih dan sel-sel luar dari lapisan arachnoid.
b. Araknoid atau Lapisan Tengah
Arachnoid merupakan selaput halus yang memisahkan duramater
dengan piamater. Lapisan arachnoid terdiri atas fibrosit berbentuk
pipih dan serabut kolagen. Arachnoid berbentuk seperti jaring laba-
laba. Antara arachnoid dan piamater terdapat ruangan berisi cairan
yang berfungsi untuk melindungi otak bila terjadi benturan.
c. Piamater atau Lapisan Dalam
Piamater merupakan membran yang sangat lembut dan tipis penuh
dengan pembuluh darah dan sangat dekat dengan permukaan otak.
Lapisan ini berfungsi untuk memberi oksigen dan nutrisi serta
mengangkut bahan sisa metabolisme.
Otak terdiri dari empat bagian besar yaitu cerebrum atau otak besar,
cerebellum atau otak kecil, brainstem atau batang otak, dan
dienchepahalons (Satyanegara, 1998).
2.1.1.Cerebrum atau Otak Besar
Bagian terbesar dari otak manusia disebut cerebrum disebut juga
sebagai cortex cerebri. Cerebrum membuat manusia memiliki
kemampuan berpikir atau intelektual, analisa, logika, bahasa, kesadaran,
persepsi, memori, aktifitas motorik yang kompleks, dan kemampuan
visual.
Cerebrum dibagi menjadi dua belahan, yaitu hemisfer kanan dan
hemisfer kiri. Kedua belahan tersebut terhubung oleh saraf. Secara
umum, hemisfer kanan berfungsi mengontrol sisi kiri tubuh dan terlibat
dalam kreativitas serta kemampuan artistik. Sedangkan hemisfer kiri
7

berfungsi mengontrol sisi kanan tubuh dan untuk logika serta berpikir
rasional.
Cerebrum dibagi menjadi empat lobus. Bagian lobus yang
menonjol disebut gyrus dan bagian lekukan disebut sulcus. Keempat
lobus tersebut masing-masing adalah:
a. Lobus Frontal merupakan bagian lobus yang ada dipaling depan dari
cerebrum. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat
alasan, kemampuan gerak, kognisi, perencanaan, penyelesaian
masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, kontrol
perilaku seksual dan kemampuan bahasa secara umum.
b. Lobus Parietal berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor
perasaan seperti tekanan, sentuhan dan rasa sakit.
c. Lobus Temporal berada di bagian bawah berhubungan dengan
kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi dan bahasa dalam
bentuk suara.
d. Lobus Occipital ada di bagian paling belakang, berhubungan dengan
rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan
interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.
2.2. Cerebellum atau Otak Kecil
Cerebellum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung
leher bagian atas. Cerebellum berfungsi dalam pengaturan koordinasi
perencanaan gerak, pengaturan tonus, kontrol postur dan keserasian
gerak, pengaturan keseimbangan. Cerebrum juga berfungsi sebagai
pengatur sistem saraf otonom, seperti pernafasan, mengatur ukuran
pupil, dan ain-lain.
Jika terjadi cedera atau terdapat kerusakan pada area ini, dapat
mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot.
Gerakan menjadi tidak terkoordinasi, misalnya orang tersebut tidak
mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya atau tidak mampu
mengancingkan baju.
8

2.3. Brainstem atau Batang Otak
Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala
bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum
tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia
termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur
proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia yaitu
fight or flight saat datangnya bahaya.
Brainstem terdiri dari tiga bagian, yaitu:
a. Mesencephalon disebut juga mid brain adalah bagian teratas dari
batang otak yang menghubungkan cerebrum dan cerebellum. Mid
brain berfungsi dalam mengontrol respon penglihatan, gerakan mata,
pembesaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh dan pendengaran.
b. Medulla oblongata adalah titik awal saraf tulang belakang dari
sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan, begitu juga
sebaliknya. Medulla oblongata bertugas mengontrol fungsi otomatis
otak seperti: detak jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dan
pencernaan.
c. Pons merupakan stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat
otak bersama dengan formasi reticular. Pons yang menentukan
apakah kita terjaga atau tertidur.
2.4. Dienchephalons
Terdiri dari thalamus, hypothalamus, subthalamus, dan
epithalamus.
a. Thalamus berfungsi sebagai station relay dari sensoris, berperan
dalam perilaku dan emosi sejalan dengan hubungannya dengan
system limbic, serta mempertahankan kesadaran.
b. Hypothalamus terletak dibawah thalamus yang berfungsi mengatur
emosi, hormon, temperatur tubuh, kondisi tidur dan bangun,
keseimbangan kimia tubuh, serta makan dan minum.
9

c. Subthalamus merupakan nukleus motorik ekstrapiramida yang
penting. Fungsinya belum dapat dimengerti sepenuhnya, tetapi lesi
pada subtalamus dapat menimbulkan diskinesia.
d. Epithalamusberhubungan dengan sistem limbik dan berperan pada
beberapa dorongan emosi dasar dan integrasi informasi olfaktorius.
3. Patofisiologi
Karena kompleksitas dan kerentanan otak selama masa perkembangannya,
menyebabkan otak sebagai subyek cedera dalam beberapa waktu. Cerebral
ischemia yang terjadi sebelum minggu ke–20 kehamilan dapat menyebabkan
defisit migrasi neuronal, antara minggu ke–24 sampai ke–34 menyebabkan
periventricular leucomalaciaatau PVL dan antara minggu ke–34 sampai ke-40
menyebabkan focal atau multifocal cerebral injury.
Cedera otak akibat vascular insufficiency tergantung pada berbagai faktor
saat terjadinya cedera, antara lain distribusi vaskular ke otak, efisiensi aliran
darah ke otak dan sistem peredaran darah, serta respon biokimia jaringan otak
terhadap penurunan oksigenasi. Kelainan tergantung pada berat ringannya
asfiksia yang terjadi pada otak. Pada keadaan yang berat tampak
ensefalomalasia kistik multipel atau iskemik yang menyeluruh. Pada keadaan
yang lebih ringan terjadi patchy necrosis di daerah paraventrikular substansia
alba dan dapat terjadi atrofi yang difus pada substansia grisea korteks serebri.
Kelainan dapat lokal atau menyeluruh tergantung tempat yang terkena.
Stres fisik yang dialami oleh bayi yang mengalami kelahiran prematur
seperti imaturitas pada otak dan vaskularisasi cerebral merupakan suatu bukti
yang menjelaskan mengapa prematuritas merupakan faktor risiko yang
signifikan terhadap kejadian cerebral palsy. Sebelum dilahirkan, distribusi
sirkulasi darah janin ke otak dapat menyebabkan tendensi terjadinya
hipoperfusi sampai dengan periventrikular white matter. Hipoperfusi dapat
menyebabkan haemorrhage pada matrik germinal atau periventricular
leucomalacia, yang berhubungan dengan kejadian diplegia spastik.
10

Pada saat dimana sirkulasi darah ke otak telah menyerupai sirkulasi otak
dewasa, hipoperfusi kebanyakan merusak area batas dari arterycerebral mayor,
yang selanjutnya menyebabkan fenotip spastik quadriplegia. Ganglia basal
juga dapat terpengaruh dengan keadaan ini, yang selanjutnya menyebabkan
terjadinya koreoathetoid atau distonik. Kerusakan vaskular yang terjadi pada
saat perawatan seringkali terjadi dalam distribusi artery cerebral bagian
tengah, yang menyebabkan terjadinya fenotip spastik hemiplegia.
Tidak ada hal–hal yang mengatur dimana kerusakan vaskular akan terjadi,
dan kerusakan ini dapat terjadi lebih dari satu tahap dalam perkembangan otak
janin. Autoregulasi peredaran darah cerebral pada neonatal sangat sensitif
terhadap asfiksia perinatal, yang dapat menyebabkan vasoparalysis dan
cerebral hyperemia. Terjadinya kerusakan yang meluas diduga berhubungan
dengan vaskular regional dan faktor metabolik, serta distribusi regional dari
rangsangan pembentukkan synaps.
Pada waktu antara minggu ke-26 sampai dengan minggu ke-34 masa
kehamilan, area periventricular white matter yang dekat dengan lateral
ventricles sangat rentan terhadap cedera. Apabila area ini membawa fiber yang
bertanggungjawab terhadap kontrol motorik dan tonus otot pada kaki, cedera
dapat menyebabkan spastik diplegia.Saat lesi yang lebih besar menyebar
sebelum area fiber berkurang dari korteks motorik, hal ini dapat melibatkan
centrum semiovale dan corona radiata, yang dapat menyebabkan spastisitas
pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah.
4. Etiologi Cerebral Palsy
Cerebral palsy dapat disebabkan faktor genetik maupun faktor lainnya.
Apabila ditemukan lebih dari satu anak yang menderita kelainan ini, maka
kemungkinan besar disebabkan oleh faktor genetik. (Soetjiningsih, 1995).
Menurut Soetjiningsih, kerusakan pada otak dapat terjadi pada masa prenatal,
natal dan postnatal.
11

4.1. Riwayat Prenatal
a. Kelainan perkembangan dalam kandungan, faktor genetik, kelainan
kromosom.
b. Usia ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 40 tahun.
c. Infeksi intrauterin : TORCH (Toxoplasma, Rubella atau campak
Jerman, Cytomegalovirus, Herpes simplexvirus) dan sifilis
d. Radiasi saat masih dalam kandungan
e. Asfiksia intrauterin (abrubsio plasenta, plasenta previa, anoksia
maternal, kelainan umbilikus, perdarahan plasenta, ibu hipertensi, dan
lain – lain).
f. Keracunan saat kehamilan, kontaminasi air raksa pada makanan, rokok
dan alkohol.
g. Induksi konsepsi.
h. Riwayat obstetrik (riwayat keguguran, riwayat lahir mati, riwayat
melahirkan anak dengan berat badan < 2000 gram atau lahir dengan
kelainan morotik, retardasi mental atau sensory deficit).
i. Toksemia gravidarum, yaitu kumpulan gejala–gejala dalam kehamilan
yang merupakan trias HPE (Hipertensi, Proteinuria dan Edema), yang
kadang–kadang bila keadaan lebih parah diikuti oleh KK (kejang–
kejangataukonvulsi dan koma). Patogenetik hubungan antara toksemia
pada kehamilan dengan kejadian cerebral palsy masih belum jelas.
Namun, hal ini mungkin terjadi karena toksemia menyebabkan
kerusakan otak pada janin.
j. Disseminated Intravascular Coagulation oleh karena kematian prenatal
pada salah satu bayi kembar
4.2. Riwayat Natal
a. Anoksia/hipoksia
Penyebab terbanyak ditemukan dalam masa natal ialah cidera otak.
Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya anoksia. Hal demikian
terdapat pada keadaan presentasi bayi abnormal, partus lama, plasenta
12

previa, infeksi plasenta, partus menggunakan bantuan alat tertentu dan
lahir dengan seksio sesar.
b. Perdarahan otak
Perdarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama, sehingga sukar
membedakannya, misalnya perdarahan yang mengelilingi batang otak,
mengganggu pusat pernapasan dan peredaran darah sehingga terjadi
anoksia. Perdarahan dapat terjadi di ruang subaraknoid dan
menyebabkan penyumbatan CSS atau cairan serebrospinalis sehingga
mangakibatkan hidrosefalus. Perdarahan di ruang subdural dapat
menekan korteks serebri sehingga timbul kelumpuhan spastis.
c. Prematuritas
Bayi kurang bulan mempunyai kemungkinan menderita pendarahan
otak lebih banyak dibandingkan dengan bayi cukup bulan, karena
pembuluh darah, enzim, factor pembekuan darah dan lain-lain masih
belum sempurna.Bayi kurang bulan mempunyai kemungkinan
menderita pendarahan otak lebih banyak dibandingkan dengan bayi
cukup bulan, karena pembuluh darah, enzim, faktor pembekuan darah
dan lain-lain masih belum sempurna.
d. Postmaturitas
e. Ikterus neonatorum
Ikterus adalah warna kuning pada kulit, konjungtiva, dan mukosa akibat
penumpukan bilirubin, sedangkan hiperbilirubinemia adalah ikterus
dengan konsentrasi bilirubin serum yang menjurus kearah terjadinya
kernikterus atau ensefalopati bilirubin bila kadar bilirubin tidak
dikendalikan (Tjipta, 1994 dalam Arif Mansjoer, 2008). Ikterus pada
masa neonatus dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang kekal
akibat masuknya bilirubin ke ganglia basal, misalnya pada kelainan
inkompatibilitas golongan darah.
f. Kelahiran sungsang
g. Bayi kembar
13

Ternyata bahwa makin canggih unit perawatan infeksi neonatal, makin
tinggi angka kejadian cerebral palsy. Sehingga dikatakan bahwa cerebral palsy
adalah produk sampah dari suatu kemajuan unit perawatan intensif neonatal.
(Soetjiningsih, 1995)
4.3. Riwayat Postnatal
a. Trauma kepala
b. Meningitis / ensefalitis yang terjadi 6 bulan pertama kehidupan
c. Racun berupa logam berat, CO.
d. Luka parut pada otak paska bedah.
5. Maniferstasi Klinis
5.1. Terdapat spastisitas , terdapat gerakan-gerakan involunter seperti atetosis,
khoreoatetosis, tremor dengan tonus yang dapat bersifat flaksid, rigiditas,
atau campuran.
5.2. Terdapat ataksia, gangguan koordinasi ini timbul karena kerusakan
serebelum. Penderita biasanya memperlihatkan tonus yang menurun atau
hipotonus, dan menunjukkan perkembangan motorik yang terlambat.
Mulai berjalan sangat lambat, dan semua pergerakan serba canggung.
5.3. Menetapnya refleks primitif dan tidak timbulnya refleks-refleks yang lebih
tinggi, seperti refleks landau atau parasut.
5.4. Penglihatan
Masalah penglihatan yang biasanya muncul pada anak cerebral palsy
adalah juling. Bila terjadi hal tersebut harus segera diperiksakan ke dokter
karena dapat menyebabkan hanya dapt menggunakan satu matanya saja.
5.5. Pendengaran
Kehilangan pendengaran berhubungan dengan mikrosefali,
mikroftalmia dan penyakit jantung bawaan, dimana disarankan untuk
memeriksa ada tidaknya infeksi TORCH (toksoplasma, rubella,
sitomegalovirus dan herpes simpleks). Pada sebagian penderita diskinesia,
kernikterus dapat menyebabkan ketulian sensorineural frekuensi tinggi.
14

Gangguan pendengan dapat menyebabkan terjadinya gangguan bahasa
atau komunikasi.
5.6. Kesulitan makan dan komunikasi
Kesulitan makan dan komunikasi ini kemungkinan disebabkan karena
adanya air liur yang berlebihan akibat fungsi bulbar yang buruk, aspirasi
pneumonia yang berulang dan terdapat kegagalan pertumbuhan paru-paru.
Masalah kesulitan makan yang menetap dapat menjadi gejala awal
dari kesulitan untuk mengekspresikan bahasa di masa yang akan datang.
Penilaian awal kemampuan berkomunikasi dilakukan dengan bantuan ahli
terapi bicara dan bahasa adalah penting dilakukan untuk mengetahui alat
yang sesuai sebagai alternatif untuk membantu berkomunikasi. Hal ini
penting dilakukan untuk memantau perkembangan kognitif anak.
5.7. Pertumbuhan
Kesulitan makan dapat menyebabkan anak tidak tumbuh dengan
semestinya. Anak tersebut dapat kekurangan berat badan.
5.8. Kesulitan belajar
Anak dengan gangguan komunikasi akan sulit dalam menerima suatu
pemahan, walau tidak semua anak dengan cerebral palsy mengalami hal
tersebut.
5.9. Gangguan tingkah laku
Anak cerebral palsy mengalami kesulitan dalam komunikasi dan
gerak, sehingga anak akan lebih mudah marah jika dia diajarkan sesuatu
pelajaran atau hal baru akan mengalami kesulitan. Sehingga harus lebih
sabar dalam menghadapinya.
6. Prognosis
Beberapa faktor berpengaruh terhadap prognosis penderita cerebral palsy
seperti tipe klinis, keterlambatan dicapainya milestones, adanya reflek
patologik dan adanya defisit intelegensi, sensoris dan gangguan emosional.
Anak dengan hemiplegi sebagian besar dapat berjalan sekitar umur 2 tahun,
kadang diperlukan short leg brace, yang sifatnya sementara. Didapatkannya
tangan dengan ukuran lebih kecil pada bagian yang hemiplegi, bisa disebabkan
15

adanya disfungsi sensoris di parietal dan bisa menyebabkan gangguan motorik
halus pada tangan tersebut. Lebih dari 50% anak tipe diplegi belajar berjalan
pada usia sekitar 3 tahun, tetapi cara berjalan sering tidak normal dan sebagian
anak memerlukan alat bantu. Aktifitas tangan biasanya ikut terganggu,
meskipun tidak tampak nyata. Anak dengan tipe kuadriplegi, 25% memerlukan
perawatan total, sekitar 33% dapat berjalan, biasanya setelah umur 3 tahun.
Gangguan fungsi intelegensi paling sering didapatkan dan menyertai terjadinya
keterbatasan dalam aktifitas. Keterlibatan otot-otot bulber, akan menambah
gangguan yang terjadi pada tipe ini (Steven et all, 2004).
Sebagian besar anak yang dapat duduk pada umur 2 tahun dapat belajar
berjalan, sebaliknya anak yang tetap didapatkan reflek moro, asimetri tonic
neck reflex, extensor thrust dan tidak munculnya reflek parasut biasanya tidak
dapat belajar berjalan. Hanya sedikit anak yang tidak dapat duduk pada umur 4
tahun akan belajar berjalan (Steven et all, 2004).
Pada penderita Cerebral Palsy didapatkan memendeknya harapan hidup.
Pada umur 10 tahun angka kematian sekitar 10% dan pada umur 30 tahun
angka kematian sekitar 13%. Penelitian didapatkan harapan hidup 30 tahun
pada gangguan motorik berat 42%, gangguan kognitif berat 62% dan gangguan
penglihatan berat 38%. Hasil tersebut lebih buruk dibanding gangguan yang
ringan atau sedang.
Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penderita Cerebral Palsy
bervariasi seperti sheltered whorkshops, home based program, pekerjaan
tradisional, pekerja pendukung. Hasil penelitian menunjukkan adanya prediktor
sukses atau tidak suksesnya bekerja pada penderita Cerebral Palsy. Dimana
yang dapat bekeja secara kompetitif bila mempunyai IQ>80, dapat melakukan
aktifitas dengan atau tanpa alat bantu, berbicara susah sampai normal dan dapat
menggunakan tangan secara normal sampai membutuhkan bantuan
(Rosenbaum et all, 2002).
16

7. Klasifikasi Cerebral Palsy
(Laurie Glazener, 2009)
7.1. Klasifikasi Cerebral Palsy berdasarkan Berdasarkan gejala dan tanda
neurologis:
7.1.1. Tipe Spastik
Spastik berarti kekakuan pada otot. Hal ini terjadi ketika
kerusakan otak terjadi pada bagian cortex cerebri atau pada traktus
piramidalis. Tipe ini merupakan tipe cerebral palsy yang paling sering
ditemukan yaitu sekitar 70 – 80 % dari penderita.
Pada penderita tipe spastik terjadi peningkatan tonus otot
(hipertonus), hiperefleks dan keterbatasan ROM sendi akibat adanya
kekakuan. Selain itu juga dapat mempengaruhi lidah, mulut dan faring
sehingga menyebabkan gangguan berbicara, makan, bernapas dan
menelan. Jika terus dibiarkan pederita cerebral palsy dapat mengalami
dislokasi hip, skoliosis dan deformitas anggota badan.
Tipe spastik dapat diklasifikasikan berdasarkan topografinya,
yaitu:
a. Monoplegi
Pada monoplegi, hanya satu ekstremitas saja yang mengalami
spastik. Umumnya hal ini terjadi pada lengan atau anggota gerak
atas.
17

b. Diplegi
Disebabkan oleh spastik yang menyerang traktus
corticospinalbillateral. Kekakuan terjadi pada dua anggota gerak,
sedangkan sistem–sistem lain normal. Anggota gerak bawah
biasanya lebih berat dibanding dengan anggota gerak atas.
c. Triplegi
Spastik pada triplegi menyerang tiga anggota gerak. Umumnya
menyerang pada kedua anggota gerak atas dan satu anggota gerak
bawah.
d. Tetraplegi atau quadriplegi
Ditandai dengan kekakuan pada keempat anggota gerak dan juga
terjadi keterbatasan pada tungkai.
7.1.2. Tipe Diskinetik
Merupakan tipe cerebral palsy dengan otot lengan, tungkai dan
badan secara spontan bergerak perlahan, menggeliat dan tak
terkendali, tetapi bisa juga timbul gerakan yang kasar dan mengejang.
Luapan emosi menyebabkan keadaan semakin memburuk. Gerakan
akan menghilang jika anak tidur. Tipe ini dapat ditemukan pada 10 –
15 % kasus cerebral palsy.
Terdiri atas 2 tipe, yaitu :
a. Distonik
Gerakan yang dihasilkan lambat dan berulang–ulang sehingga
menyebabkan gerakan melilit atau meliuk-liuk dan postur yang
abnormal.
b. Athetosis
Menghasilkan gerakan tambahan yang tidak dapat dikontrol,
khususnya pada lengan, tangan dan kaki serta disekitar mulut.
18

7.1.3. Tipe Ataxsia
Pada tipe ini terjadi kerusakan pada cerebellum, sehingga
mempengaruhi koordinasi gerakan, keseimbangan dan gangguan
postur. Tipe ini merupakan tipe cerebral palsy yang paling sedikit
ditemukan yaitu sekitar 5 – 10 % dari penderita. Pada penderita tipe
ataxia terjadi penurunan tonus otot atau hipotonus, tremor, cara
berjalan yang lebar akibat gangguan keseimbangan serta kontrol gerak
motorik halus yang buruk karena lemahnya koordinasi.
7.1.4. Tipe Campuran
Merupakan tipe cerebral palsy yang merupakan gabungan dari
dua tipe cerebral palsy. Gabungan yang paling sering terjadi adalah
antara spastic dan athetoid.
7.2. Klasifikasi cerebral palsy berdasarkan derajat keparahan fungsional:
7.2.1. Cerebral Palsy ringan (10%), masih bisa melakukan pekerjaan atau
aktifitas sehari hari sehingga tidak atau hanya sedikit sekali
membutuhkan bantuan khusus.
7.2.2. Cerebral Palsy sedang (30%), aktifitas sangat terbatas sekali sehingga
membutuhkan bermacam bentuk bantuan pendidikan, fisioterapi, alat
brace dan lain lain.
7.2.3. Cerebral Palsy berat (60%), penderita sama sekali tidak bisa
melakukan aktifitas fisik. Pada penderita ini sedikit sekali menunjukan
kegunaan fisioterapi ataupun pendidikan yang diberikan. Sebaiknya
penderita seperti ini ditampung dalam rumah perawatan khusus.
7.3. Derajat keparahan cerebral palsy berdasarkan Gross Motor Function
Classification Systemm atau GMFCS :
Berdasarkan faktor dapat tidaknya beraktifitas atau ambulation, Gross
Motor Functional Classification Systematau GMFCS secara luas
digunakan untuk menentukan derajat fungsional penderita cerebral palsy.
19

Pembagian derajat fungsional cerebral palsy menurut Motor
Functional Classification System, dibagi menjadi 5 level dan berdasarkan
kategori umur dibagi menjadi 4 kelompok (Peter Rosenbaum et al, 2002)
yaitu:
7.3.1. Kelompok sebelum usia 2 tahun
a. Level 1: Bayi bergerak dari terlentang ke duduk di lantai dengan
kedua tangan bebas untuk memainkan objek. Bayi merangkak
menggunakan tangan dan lutut, menarik untuk berdiri dan mengambil
langkah-langkah berpegangan pada benda. Bayi berjalan antara 18
bulan dan 2 tahun tanpa memerlukanalat bantu atau walker.
b. Level 2: Bayi mempertahankan posisi duduk di lantai namun perlu
menggunakan tangan menjaga keseimbangan. Bayi merayap pada
perut atau merangkak pada tangan dan lutut. Bayi mungkin menarik
untuk berdiri dan mengambil langkah berpegangan pada benda.
c. Level 3: Bayi duduk di lantai dengan tegak ketika trunk control baik.
Bayi merayap maju dengan perut.
d. Level 4: Bayi memiliki head control tetapi memerlukan trunk control
untuk duduk di lantai. Bayi dapat berguling untuk terlentang dan
mungkin berguling untuk telungkup.
e. Level 5: Gangguan fisik membatasi kontrol gerakan. Bayi tidak dapat
mempertahankan kepala dan trunk untuk melawan gravitasisaat
telungkup dan duduk. Bayi memerlukan bantuan orang dewasa untuk
berguling.
7.3.2. Kelompok 2 – 4 tahun
a. Level 1: Anak-anak duduk di lantai dengan kedua tangan bebas untuk
memainkan objek. Bergerak dari duduk ke berdiri dilakukan tanpa
bantuan orang dewasa. Anak-anak berjalan untuk berpindah
tempattanpa memerlukan alat bantu atau walker.
b. Level 2: Anak-anak duduk di lantai, tetapi mungkin memiliki
kesulitan dengan keseimbangan ketika kedua tangan bebas untuk
memainkan objek. Anak-anak menarik benda yang tidak bergerak
20

untuk berdiri. Anak-anak merangkak dengan tangan dan lutut
bergerak bergantian, berpindah tempat dengan berjalan berpegangan
pada benda dan berjalan menggunakan alat bantu atau walker.
c. Level 3: Anak-anak duduk di lantai dengan posisi duduk W dan
mungkin memerlukan bantuan orang dewasa untuk mengasumsikan
duduk. Anak-anak merayap atau merangkak dengan tangan dan lutut
(sering dengan gerakan tangan dan lutut yang tidak bergantian) untuk
berpindah tempat. Anak-anak mungkin menarik pada benda yang
stabil untuk berdiri. Anak-anak mungkin berjalan dalam ruangan
dengan jarak dekat dengan menggunakan alat bantu atau walkerdan
memerlukan bantuan orang dewasa untuk mengarahkan langkahnya.
d. Level 4: Anak-anak duduk di lantai ketika ditempatkan, tetapi tidak
dapat menjaga keseimbangan tanpa menggunakan tangan untuk
mendukung. Anak-anak sering membutuhkan alat bantu untuk duduk
dan berdiri. Mobilisasi diri untuk jarak pendek atau dalam ruangan
tercapai melalui berguling, merayap, atau merangkak pada tangan dan
lutut tanpa gerakan bergantian atau simultan.
e. Level 5: Gangguan fisik membatasi gerakan dan kemampuan untuk
menjaga kepala dan trunk dalam melawan gravitasi. Semua bidang
fungsi motorik terbatas. Beberapa anak mobilisasi menggunakan kursi
roda.
7.3.3. Kelompok 4 – 6 tahun
a. Level 1: Anak dapat duduk dan bangkit dari duduk pada kursi, tanpa
membutuhkan bantuan tangan. Anak bergerak dari lantai dan dari
kursi untuk berdiri tanpa bantuan obyek. Anak berjalan baik dalam
ruangan maupun diluar ruangan, dan dapat naik tangga. Terdapat
kemampuan untuk berlari atau melompat.
b. Level 2: Anak duduk di kursi dengan kedua tangan bebas
memanipulasi obyek. Anak dapat bergerak dari lantai untuk berdiri,
tetapi seringkali membutuhkan obyek yang stabil untuk menarik atau
mendorong dengan tangannya. Anak berjalan tanpa alat bantu
21

didalam ruangan dan dengan jarak pendek pada permukaan yang rata
diluar ruangan. Anak dapat berjalan naik tangga dengan berpegangan
pada tepi tangga., tetapi tidak dapat berlari atau melompat.
c. Level 3: Anak dapat duduk pada kursi, tetapi membutuhkan alat bantu
untuk pelvis atau badan untuk memaksimalkan fungsi tangan. Anak
dapat duduk dan bangkit dari duduk menggunakan permukaan yang
stabil untuk menarik atau mendorong dengan tangannya. Anak
seringkali dibantu untuk mobilitas pada jarak yang jauh atau diluar
ruangan dan untuk jalan yang tak rata.
d. Level 4: Anak duduk di kursi tapi butuh alat bantu untuk kontrol
badan untuk memaksimalkan fungsi tangan. Anak duduk dan bangkit
dari duduk membutuhkan bantuan orang dewasa atau obyek yang
stabil untuk dapat menarik atau mendorong dengan tangannya. Anak
dapat berjalan pada jarak pendek dengan bantuan walker dan dengan
pengawasan orang dewasa, tetapi kesulitan untuk jalan berputar dan
menjaga keseimbangan pada permukaan yang rata. Anak dibantu
untuk mobilitas ditempat umum. Anak bisa melakukan mobilitas
dengan kursi roda bertenaga listrik.
e. Level 5: Kelainan fisik membatasi kemampuan kontrol gerakan,
gerakan kepala dan postur tubuh. Semua area fungsi motorik terbatas.
Keterbatasan untuk duduk dan berdiri yang tidak dapat dikompensasi
dengan alat bantu, termasuk yang menggunakan teknologi. Anak
tidak dapat melakukan aktifitas mandiri dan dibantu untuk mobilisasi.
Sebagian anak dapat melakukan mobilitas sendiri menggunakan kursi
roda bertenaga listrik dengan sangat membutuhkan adaptasi.
7.3.4. Kelompok 6 – 12 Tahun
a. Level 1: Anak berjalan didalam dan diluar ruangan, naik tangga tanpa
keterbatasan. Anak menunjukkan performa fungsi motorik kasar
termasuk lari dan lompat, tetapi kecepatan, keseimbangan dan
koordinasi berkurang.
22

b. Level 2: Anak berjalan didalam dan diluar ruangan dan naik tangga
dengan berpegangan di tepi tangga, tetapi terdapat keterbatasan
berjalan pada permukaan yang rata dan mendaki, dan berjalan
ditempat ramai atau tempat yang sempit. Anak dapat melakukan
kemampuan motorik kasar, seperti berlari atau melompat yang
minimal.
c. Level 3: Anak berjalan didalam dan diluar ruangan pada permukaan
yang rata dengan bantuan alat bantu gerak. Anak masih mungkin
dapat naik tangga dengan pegangan pada tepi tangga. Tergantung
fungsi dari tangan, anak menggerakan kursi roda secara manual atau
dibantu bila melakukan aktifitas jarak jauh atau diluar ruangan pada
jalan yang tidak rata.
d. Level 4: Anak bisa dengan level fungsi yang sudah menetap dicapai
sebelum usia 6 tahun atau lebih mengandalkan mobilitas
menggunakan kursi roda dirumah, disekolah dan ditempat umum.
Anak dapat melakukan mobilitas sendiri dengan kursi roda bertenaga
listrik.
e. Level 5: Kelainan fisik membatasi kemampuan kontrol gerakan,
gerakan kepala dan postur tubuh. Semua area fungsi motorik terbatas.
Keterbatasan untuk duduk dan berdiri yang tidak dapat dikompensasi
dengan alat bantu, termasuk yang menggunakan teknologi. Anak
tidak dapat melakukan aktifitas mandiri dan dibantu untuk mobilitas.
Sebagian anak dapat melakukan mobilitas sendiri menggunakan kursi
roda bertenaga listrik dengan sangat membutuhkan adaptasi.
8. Cerebral Palsy Spastic Quadriplegi
Dalam makalah ini, kelompok kami kami mengambil kasus mengenai
Cerebral Palsy Spastis Quadriplegi.
8.1. Pengertian Cerebral Palsy Spastis Quadriplegi
Cerebral Palsy Spastis Quadriplegi yaitu kerusakan pada sistem saraf
pusat yang berdampak tidak berkembangnya sistem saraf tersebut ditandai
23

tonus otot yang meninggi serta semua badan terasa kaku terutama pada
lengan sehingga mengalami gangguan pada bagian motorik dan
terlambatnya perkembangan anak. Quadriplegi dibeberapa klinik disebut
juga sebagai double hemiplegi yaitu dua sisi tubuh terutama dilengan
lebih kaku dibanding kaki. (Pamela, 1993)
8.2. Manifestasi klinis Cerebral Palsy Spastis Quadriplegi
Menurut Sherrill, 1984, ciri fisik yang sering ditemui adalah sebagai
berikut:
1.) Pada kasus ini Assymetrical Tonic Neck Reflex dan Moro Reflex atau
ATNR yang harusnya sudah hilang pada usia 6 bulan, masih ada.
2.) Kepala dan leher cenderung ke arah fleksi, hal ini dapat disebabkan
oleh gangguan visual.
3.) Persendian bahu atau shoulder cederung ke arah abduksi disebabkan
adanya hipertonus.
4.) Lengan bawah atau forearm akan cendurung ke arah pronasi.
5.) Pergelangan tangan atau wrist seringkali dalam posisi fleksi,
sedangkan jari-jari tangan dalam posisi mengepal.
6.) Sendi panggul atau hip cenderung dalam posisi adduksi, yang
menyebabkan tungkai dan kaki dalam posisi menggunting dan
menyebabkan terjadinya dislokasi hip. Dislokasi ini terjadi karena
adanya gaya yang berlebih yang menyebabkan sendi melampaui
batas normal anatominya.
7.) Sendi lutut atau knee akan cenderung dalam posisi semifleksi.
8.) Ankle joint akan cenderung dalam posisi plantar fleksi, karena
terjadi ketengan dari tendong achilles.
9.) Masalah keseimbangan, terjadi karenan adanya kerusakan pada
cerebellum. Anak dengan pola jalan menggunting akan rawan untuk
jatuh ke depan.
10.) Spastik sering berpengaruh pada otot-otot pernafasan.
11.) Keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan.
24

12.) Pada kebanyakan kasusCerebral Plasy Spastic Quadriplegia, anak
berguling dan keduduk denganflexipatrondan tanpa rotasi trunk.
8.3. Prognosis Cerebral Palsy Spastis Quadriplegi
Prognosis pasien Cerebral Palsy Spastic Quadriplegi dipengaruhi
beberapa faktor antara lain:
8.3.1. Berat ringannya kerusakan yang dialami pasien.
Menurut tingkatannya Cerebral Palsy Spastic Quadriplegisecara
umum diklasifikasikan dalam tiga tingkat yaitu:
a. Mild
Pasien dengan Mild Quadriplegi dapat berjalan tanpa
menggunakan alat bantu seperti billateral crutches atau walker, dan
dapat bersosialisasi dengan baik dengan anak-anak normal
seusianya pasien.
b. Moderate
Pasien dengan Moderate Quadriplegi mampu untuk berjalan
saat melakukan aktifitas sehari-hari tetapi terkadang masih
membutuhkan alat bantu seperti billateral crutches atau walker.
Namun demikian untuk perjalanan jauh atau berjalan dalam waktu
yang relatif lama dan jarak tempuh yang relatif jauh, pasien masih
memerkulan bantuan kursi roda.
c. Severe
Sedangkan pasien dengan Severe Quadriplegi sangat
tergantung pada alat bantu atau bantuan dari orang lain untuk
berjalan meskipun hanya untuk mencapai jarak yang dekat,
misalnya untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain
dalam satu rumah. Pasien sangat tergantung pada kursi roda atau
orang lain untuk melakukan aktifitas.
25

8.3.2. Pemberian terapi pada pasien Cerebral Palsy Spastic Quadriplegi
Pemberian terapi dengan dosis yang tepat dan adekuat juga
berpengaruh terhadap prognosis pasien. Semakin tepat dan adekuat
terapi yang diberikan semakin baik prognosisnya.
8.3.3. Kondisi tubuh pasien.
Dengan kondisi tubuh yang baik akan mempermudah pasien
untuk mengembangkan kemampuannya pada saat latihan sehingga
pasien dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara mandiri.
8.3.4. Lingkungan tempat pasien tinggal dan bersosialisasi.
Peran lingkungan terutama keluarga sangat mempengaruhi
perkembangan pasien, dukungan mental yang diberikan keluarga
kepada pasien sangat dibutuhkan pasien tidak hanya pada saat
menjalani terapi sehingga pasien bersemangat setiap kali menjalani
sesi latihan tetapi juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri pasien
untuk bersosialisasi dengan dunia luar.
9. Penatalaksanaan Fisioterapi pada Cerebral PalsySpastik Quadriplegi
Asesmen merupakan proses pengumpulan data baik data pribadi maupun
data pemeriksaan pasien. Asesmen dilakukan bertujuan untuk
mengidentifikasikan urutan masalah yang timbul pada kasus Cerebral Palsy
Spastic Quadriplegic kemudian menjadi dasar dari penyusunan program terapi
dan tujuan terapi yang disesuaikan dengan kondisi pasien serta lingkungan
sekitar pasien. Dalam asesmen meliputi:
9.1. Anamnesis
Anamnesis merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya
jawab antara sterapis dengan sumber data. Dilihat dari segi
pelaksanaannya anamnesis dibedakan atas dua yaitu: Autoanamnesis,
merupakan anamnesis yang langsung ditujukan kepada pasien yang
bersangkutan dan Alloanamnesis, merupakan anamnesis yang dilakukan
26

terhadap orang lain yaitu keluarga, teman, ataupun orang terdekat dengan
pasien yang mengetahui keadaan pasien tersebut. Anamnesis yang akan
dilakukan berupa :
9.1.1. Identitas Penderita atau Anamnesis Umum
Anamnesis ini berisi tentang : nama, umur, jenis kelamin, alamat,
pekerjaan, hobi dan agama. Identitas pasien harus diisi selengkap
mungkin, ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pemberian
tindakan.
Dari data identitas pasien, kita juga mendapatkan kesan mengenai
keadaan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan dari pendidikan
terakhir dan pekerjaan pasien. Sehingga kita dapat memberikan
tindakan dan edukasi yang sesuai bagi pasien.
9.1.2. Keluhan Utama
Keluhan utama merupakan keluhan yang paling mengganggu
pasien pada saat itu. Keluhan utama pasien dijadikan sebagai
acuan dalam menggali informasi lebih dalam, melakukan
pemeriksaan dan pemberian tindakan. Pada anak, keluhan utama
yang ditanyakan anak belum bisa apa dan sudah bisa apa.
9.1.3. Riwayat Penyakit Sekarang
Riwayat penyakit sekarang merupakan rincian dari keluhan
utama, yang berisi riwayat perjalanan penyakit secara kronologis
dengan jelas dan lengkap serta keterangan tentang riwayat
pengobatan yang pernah dilakukan sebelumnya dan hasil yang
diperoleh. Riwayat penyakit sekarang harus meliputi: lokasi dan
penjalaran, intensitas atau keparahan, disabilitas, durasi,
frekuensi, kondisi atau keadaan saat munculnya gejala, faktor
pencetus, faktor yang memperberat, faktor yang memperingan,
kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Hal ini bertujuan sebagai
acuan dalam melakukan pemeriksaan serta pemberian tindakan.
27

9.1.4. Riwayat Prenatal
Mencakup usia ibu saat hamil, kehamilan direncanakan atau
tidak, rutin kontrol ke dokter atau dokter atau tidak, selama hamil
ibu mengalami trauma, perdarahan, dan menderita penyakit
lainnya atau tidak, mengkonsumsi obat-obatan atau jamu-jamuan
tidak.
9.1.5. Riwayat Natal
Mencakup usia kehamilan, lahir normal atau caesar, ditolong
oleh siapa, dimana, langsung menangis atau tidak, berat badan
lahir, panjang badan lahir, saat lahir apakah anak berwana biru
atau kuning tidak.
9.1.6. Riwayat Post Natal
Mencakup penah kejang atau tidak, berwana biru atau kuning
tidak, anak minum ASI sampai usia berapa tahun.
9.1.7. Riwayat Penyakit Dahulu
Riwayat penyakit dahulu merupakan riwayat penyakit fisik
maupun psikiatrik yang pernah diderita sebelumnya. Meliputi,
anak pernah deman, kejang, diare, atau penyakit lainnya yang
tidak berhubungan secara langsung dengan keluhan utama anak
atau tidak, pernah dirawat di rumah sakit atau tidak, dimana,
kapan atau saat usia berapa tahun, dan berapa lama. Hal ini perlu
diketahui karena ada beberapa penyakit yang sekarang dialami
ada hubungannya dengan penyakit yang pernah dialami
sebelumnya serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan
tindakan yang akan dilakukan.
28

9.1.8. Riwayat Penyakit Keluarga
Sejarah keluarga memegang peranan penting dalam kondisi
kesehatan seseorang. Penyakit yang muncul pada lebih dari satu
orang keluarga terdekat dapat meningkatkan resiko untuk
menderita penyakit tersebut. Penyakit yang muncul bersamaan
pada keluarga juga mengindikasikan resiko yang lebih besar,
misalnya diabetes dan penyakit jantung.
9.1.9. Riwayat Psikososial
Riwayat psikososial pada kasus anak berisikan anak tersebut
anak ke berapa dari berapa bersaudara, usia, pendidikan, dan
pekerjaan orang tua, sehari-hari anak diasuh oleh siapa.
Pentingnya mengetahui riwayat psikososial adalah untuk
merancang terapi dan home program yang tepat bagi pasien.
9.1.10. Riwayat Imunisasi
Berisikan imunisasi apa saja yang pernah diberikan kepada
anak tersebut.
(Depkes dalam Lunar 2012)
29

Keterangan gambar:
a. Imunisasi BCG: Ditujukan untuk memberikan kekebalan bayi
terhadap bakteri tuberkolosis atau TBC.
b. Imunisasi DPT: Memberikan kekebalan bagi bayi terhadapat
penyakit Dipteri, Pertusis atau batuk rejan dan tetanus.
c. Imunisasi Polio: Memberikan kekebalan bagi bayi terhadap
penyakit polio atau kelumpuhan
d. Imunisasi Hib: Mencegah bayi terkena infeksi Haemophils
influenza tipe b yang dapat menyebabkan penyakit meningitis,
infeksi tenggorokan dan pnemonia. Imunisasi Hib ini sangat
mahal, maka belum di wajibkan.
e. Imunisasi Pneumokokus: melindung bayi dari bakteri penyebab
infeksi pada telinga. Selain itu bakteri ini bisa menimbulkan
permasalah serius seperti meningits dan infeksi pada darah.
9.1.11. Riwayat Tumbuh Kembang
Riwayat tumbuh kembang normal anak meliputi: fase-fase
perkembangan dan pertumbuhan anak dapat dilalui pada saat usia
anak berapa tahun, senyum pada orang untuk pertama kali;
berbicara pertama kali, pemberian ASI sampai dengan usia berapa
tahun, pemberian susu formula sejak usia berapa, alasan
pemberian susu formula, cara minumnya, jenis makanan yang
dapat dimakan oleh anak pada saat ini, cara makannya, bahasa
yang dapat anak ucapkan saat itu.
30

Normal Development Child menurut WHO, 1993:
31

Normal Development and Cerebral Palsy Development
menurut WHO, 1993
9.2. Pemeriksaan
Pemeriksaan terdiri dari:
9.2.1. Pemeriksaan Umum mencakup cara datang, normal, digendong,
atau menggunakan alat bantu, kesadaran,koperatif atau tidak, tensi,
pemeriksaan lingkar kepala, nadi,respirasi rate, status gizi, suhu
tubuh.
a. Kesadaran
Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon
seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan, tingkat
kesadaran dibedakan menjadi :
32

1. Compos Mentis atau conscious, yaitu kesadaran normal,
sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan
tentang keadaan sekelilingnya.
2. Apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk
berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh.
3. Delirium, yaitu gelisah, disorientasi berupa orang, tempat,
waktu, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi,
kadang berhayal.
4. Somnolen atau Obtundasi, Letargi, yaitu kesadaran
menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur,
namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah
dibangunkan tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi
jawaban verbal.
5. Stupor atau soporo koma, yaitu keadaan seperti tertidur
lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri.
6. Coma atau comatos, yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada
respon terhadap rangsangan apapun atau tidak ada respon
kornea maupun reflek muntah, mungkin juga tidak ada
respon pupil terhadap cahaya.
b. Tensi atau Tekanan Darah
Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada
dinding arteri. Tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat
terjadi kontraksi otot jantung. Sedangkan, tekanan diastolik
adalah tekanan darah yang digambarkan pada rentang di antara
grafik denyut jantung. Tekanan darah biasanya digambarkan
sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik.
Pengukuran tekanan darah pada anak-anak dilakukan pada
kasus-kasus tertentu.
33

Jumlah tekanan darah yang normal berdasarkan usia
seseorangadalah:
- Bayi usia di bawah 1 bulan : 85/15 mmHg
- Usia 1 – 6 bulan : 90/60 mmHg
- Usia 6 – 12 bulan : 96/65 mmHg
- Usia 1 – 4 tahun : 99/65 mmHg
- Usia 4 – 6 tahun : 160/60 mmHg
- Usia 6 – 8 tahun : 185/60 mmHg
- Usia 8 – 10 tahun : 110/60 mmHg
(Pamela, 1993)
c. Lingkar Kepala
Mengukur lingkar kepala berfungsi untuk mengetahui
perkembangan otaknya. Meskipun ukuran lingkar kepala anak
tidak berpengaruh pada tingkat kecerdasannya, namun ukuran
lingkar kepala berkaitan dengan volume otaknya. Lingkar
kepala anak akan bertambah sesuai dengan usia dan juga
diepngaruhi oleh jenis kelamin.
Lingkar kepala pada anak laki-laki
Grafik lingkaran kepala anak laki-laki (berdasarkan Nelhaus
G. Pediatr. 41: 106; 1986) dalam Arif Mansjoer 2000.
34

Lingkar kepala pada anak perempuan
Grafik lingkaran kepala anak perempuan (berdasarkan
Nelhaus G. Pediatr. 41: 106; 1986) dalam Arif Mansjoer
2000.
d. Nadi
Mengetahui denyut nadi merupakan dasar untuk melakukan
latihan fisik yang benar dan terukur atau mengetahui seberapa
keras jantung bekerja. Pengukuran nadi dilakukan dengan durasi
1 menit.
Frekuensi denyut nadi normal:
Usia Denyut Nadi
1 minggu 100 – 140 kali/menit
2 – 8 minggu 90 – 130 kali/menit
3 – 12 bulan 90 – 130 kali/menit
1 – 6 tahun 75 – 115 kali/menit
7 – 12 tahun 70 – 80 kali/menit
(Pamela, 1993)
35

Pola nadi yang normal adalah detaknya berirama.
Pola nadi Deskripsi
Bradikardia Frekuensi nadi lambat.
Takikardia Frekuensi nadi meningkat, dalam keadaan tidak pada
ketakutan, menangis, aktivitas meningkat, atau demam
yang menunjukan penyakit jantung.
Aritmia Frekuensi nadi meningkat selama inspirasi, menurun
selama ekspirasi. Sinus Aritmia merupakan variasi
normal pada anak, khususnya selama tidur.
e. Respirasi Rate
Respirasi rate adalah jumlah seseorang mengambil napas per
menit. Tingkat respirasi biasanya diukur ketika seseorang dalam
posisi diam dan hanya melibatkan menghitung jumlah napas
selama satu menit dengan menghitung berapa kali dada
meningkat.
Tabel respirasi rate normal pada anak
Usia Pernapasan
1 minggu 30 – 60 kali/menit
2 – 8 minggu 30 – 40 kali/menit
3 – 12 bulan 20 – 30 kali/menit
1 – 6 tahun 19 – 29 kali/menit
7 – 12 tahun 15 – 20 kali/menit
(Pamela, 1993)
f. Suhu Badan
Nilai hasil pemeriksaan suhu merupakan indikator untuk
menilai keseimbangan antara pembentukan dan pengeluaran
panas. Nilai ini akan menunjukkan peningkatan bila pengeluaran
panas meningkat. Kondisi demikian dapat juga disebabkan oleh
vasodilatasi, berkeringat, hiperventilasi dan lain-lain. Demikian
sebaliknya, bila pembentukan panas meningkat maka nilai suhu
36

tubuh akan menurun. Memeriksa suhu badan bias menggunakan
punggung tangan. Afebris berarti dalam batas normal, subfebris
berarti demam yang tidak tinggi atau saat dipalpasi terasa
hangat, febris berarti demam.
g. Status Gizi
Status gizi anak dapat dilihat dari pemeriksaan turgor kulit,
konjungtiva mata, dan proporsi tubuh. Namun, untuk lebih
meyakinkannya lagi, dapat dihitung dari rumus:
Panjang badan = 80 + 5n
Berat badan = 8 + 2n
Dimana n adalah umur dalam tahun.
(Arif Mansjoer, 2000)
9.2.2.Pemeriksaan khusus
Pemeriksaan khusus terdiri dari:
1. Pengamatan Posisi
Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai ada tidaknya
gerakan ekstremitas abnormal, asimetris, posisi dan gerakan
yang abnormal. Pengamatan posisi dilakukan pada saat
terlentang, berguling, telungkup, merayap, ke duduk, duduk,
merangkak, ke berdiri, berdiri, dan berjalan. Pengamatan posisi
anak dilakukan sesuai dengan kemampuan anak. Setiap posisi
memiliki komponennya masing – masing.
a. Terlentang
Komponen yang dilihat:
1.) Gerakannya (aktif, simultan, kecenderungan posisi)
2.) Posisi kepala
3.) Posisi trunk (simetris atau tidak simetris)
4.) Posisi shoulder
37

5.) Posisi elbow
6.) Posisi wrist
7.) Posisi jari
8.) Posisi hip
9.) Posisi knee
10.) Posisi ankle
b. Berguling
Komponen yang dilihat:
1.) Via (hip atau shoulder)
2.) Rotasi trunk (ada atau tidak)
c. Telungkup
Komponen yang dilihat:
1.) Head lifting
2.) Head control
3.) Forearm support
4.) Hand support
5.) Posisi trunk
6.) Posisi hip
7.) Posisi knee
8.) Posisi ankle
d. Merayap
Komponen yang dilihat:
1.) Head control
2.) Forearm support
3.) Rotasi trunk
4.) Gerakannya simultan
5.) Trnsfer weight bearing
e. Duduk
38

Komponen yang dilihat:
1.) Head control
2.) Trunk control
3.) Hand support
4.) Weight bearing
5.) Sitting balance
6.) Protective reaction
f. Ke duduk
Komponen yang dilihat:
1.) Posisi awal
2.) Proses
3.) Head control
4.) Forearm support
5.) Hand suppport
6.) Fiksasi gerakan
7.) Transfer weight bearing
g. Merangkak
Komponen yang dilihat:
1.) Head control
2.) Weight bearing
3.) Rotasi trunk
4.) Transfer wieght bearing
5.) Gerakannya simultan atau tidak
h. Berdiri
Komponen yang dilihat
1.) Head control
2.) Posisi shoulder
3.) Posisi elbow
4.) Posisi wrist
39

5.) Posisi jari-jari
6.) Posisi trunk
7.) Trunk control
8.) Posisi hip
9.) Posisi knee
10.) Posisi ankle
11.) Weight bearing
12.) Standing balance
i. Ke berdiri
Komponen yang dilihat:
1.) Posisi awal
2.) Proses
3.) Head control
4.) Trunk control
5.) Weight bearing
6.) Transfer weight bearing
7.) Pola ke berdiri
j. Berjalan
Komponen yang dilihat:
1.) Head control
2.) Trunk control
3.) Rotasi trunk
4.) Transfer weight bearing
2. Spastisitas
Spastisitas merupakan fungsi tonus yang meningkat
tergantung pada kecepatan gerakan. Merupakan gambaran lesi
pada Upper Motor Neuron. Membentuk ekstrimitas pada posisi
ekstensi.Pengukuran spastisitas dilakukan apabila ada
40

kecurigaan kecenderungan posisi. Skala pengukuran dapat
menggunakan ashworth.
Skala Klinis Spastisitas (ASHWORTH)
0 : Tidak terdapat peningkatan tonus postural.
1 : Sedikit peningkatan tonus, terdapat tahanan minimal
di akhir Lingkup Gerak Sendi.
1+ : Sedikit peningkatan tonus, tahanan sedikit kurang dari
½ Lingkup Gerak Sendi.
2 : Peningkatan tonus lebih nyata hampir seluruh
Lingkup Gerak Sendi, namun masih bisa digerakkan
3 : Peningkatan tonus bermakna, sehingga gerakan pasif
sulit dilakuakan.
4 : Sendi dalam posisi fleksi atau ekstensi atau dalam
satu posisi.
(Malene Wesselhoff, 2012)
3. Ankle Clonus
Bila terjadi rileks yang sangat hiperaktif, maka keadaaan ini
disebut klonus. Jika kaki dibuat dorsi fleksi dengan tiba-tiba,
dapat mengakibatkan dua atau tiga kali gerakan sebelum
selesai pada posisi istirahat. Kadang-kadang pada penyakit
Sistem Saraf Pusat terdapat aktivitas ini dan kaki tidak mampu
istirahat di mana tendon menjadi longgar tetapi aktivitas
menjadi berulang-ulang.
4. Tightness
a. Pemeriksaan tightness pada m. hamstringPosisi os : terlentangTatalaksana : fleksikan salah satu hip. Positif jika hip
pada sisi kontralateral terangkat.
b. Pemeriksaan tightness pada m. illiopsoasPosisi os : telungkupTatalaksana : fleksikan kedua knee. Positif jika hip fleksi.
41

c. Pemeriksaan tightness tendon achillesPosisi os : terlentangTatalaksana : dorsi fleksikan ankle. Positif jika ankle sulit
didosi fleksikan.
5. Pemeriksaan 7 Refleks
Merupakan salah satu komponen penentu prognosis
berjalan. Pemeriksaan 7 refleks dilakukan mulai usia 1 tahun
hingga usia kurang dari 7 tahun. Pemeriksaan 7 refleks
meliputi (Pamela, 1993):
a. ATNR atau Asymetrical Tonic ReflexLokasi :brainstem
Muncul saat usia : 2 bulan
Hilang saat usia : 4 bulan
Cara pemeriksaaan : anak terlentang dengan posisi kepala
pada midline, kemudian kepala dirotasikan ke salah satu
sisi. Positif jika elbow dan knee pada ipsilateral fleksi, dan
pada sisi kontralateral: shoulder abduksi, elbow ekstensi.
b. STNR atau Symetrical Tonic Neck ReflexLokasi : brainstem
Muncul saat usia : 4 sampai 6 bulan
Hilang saat usia : 10 bulan
Cara pemeriksaaan : anak telungkup dipangkuan
pemeriksa. Kemudian kepala anak difleksikan atau
diekstensikan. Positif jika saat kepala difleksikan, maka
kedua lengan fleksi dan tungkai ekstensi. Positif jika saat
kepala ekstensikan, maka kedua lengan ekstensi dan tungkai
fleksi.
42

c. Neck RightingLokasi : Midbrain
Muncul saat usia : Baru lahir
Hilang saat usia : 4 sampai 6 bulan
Cara pemeriksaaan : anak dalam posisi terlentang.
Kemudian kepala dirotasikan ke salah satu sisi. Positif jika
tubuh berputar mengikuti kepala, mulai dari shoulder,
trunk, dan pelvis, serta anggota gerak bawah.
d. Extensor ThrustLokasi : Spinal
Muncul saat usia : Baru lahir
Hilang saat usia : 1 sampai 2 bulan
Cara pemeriksaaan : knee anak dalam posisi fleksi.
Kemudian telpak kaki digores atau disentuh. Positif jika
knee menjadi lurus.
e. MoroLokasi : Spinal
Muncul saat usia : Baru lahir
Hilang saat usia : 1 sampai 2 bulan
Cara pemeriksaaan : anak dalam posisi terlentang, kepala
dan punggung anak disangga tangan pemeriksa. Kemudian
secara tiba-tiba jatuhkan pegangan kepala anak tanpa
ditekan. Positif jika ada reaksi seperti terkejut, yaitu kedua
elbow fleksi dengan forearm supinasi.
f. Parachute Lokasi : Cortical
Muncul saat usia : 6 sampai 9 bulan
Hilang saat usia : tidak hilang atau sepanjang usia
Cara pemeriksaaan : anak diposisikan seperti akan
terjun, handling pemeriksa pada bagian torakal, posisi
43

kepala lebih rendah dari kaki. Positif jika kedua lengan anak
lurus, jari-jari tangan diekstensikan seolah hendak
mendarat, atau sering disebut handsupport.
g. Foot placement
Lokasi : Cortical
Muncul saat usia : Baru lahir
Cara pemeriksaaan : anak diposisikan berdiri, handling
pada axilla anak. Kemudian punggung tungkai anak digoreskan
pada meja. Positif jika kaki anak naik ke atas meja.
Penilaian 7 refleks:
ATNR ( - ) : 0
STNR ( - ) : 0
Neck righting ( - ) : 0
Extensor thrust ( - ) : 0
Moro ( - ) : 0
Paracute ( + ) : 0
Foot placement ( + ) : 0
Keterangan:
Jika skor 0, maka anak bisa berjalan.
Jika skor 1, maka anak bisa berjalan tanpa atau dengan alat
bantu.
Jika skor 2 atau lebih dari 2, maka prognosa berjalan jelek.
6. Pemeriksaan Fungsi Bermain
Anak kecil mempunyai organ memori yang belum banyak
terisi. Melalui bermain anak akan mengeksplorasi dan
memanipulasi benda-benda di sekitarnya. Setelah mengenali
dan mempelajari, selanjutnya anak akan menyimpannya di
dalam sel-sel memori atau otak. Semakin banyak sel
44

memorinya terisi oleh data-data tertentu yang diperolehnya
melalui permainan, maka akan semakin meningkatkan
kemampuan kognitifnya. Fungsi bermain anak berbeda-beda
sesuai dengan usianya.
Pemeriksaan denver II adalah suatu pemeriksaan yang
digunakan untuk screening perkembangan anak dari lahir
sampai usia 6 tahun, yang meliputi 4 aspek penilaian yaitu
personal sosial, motorik kasar, bahasa, dan motorik halus.
9.3. Pengumpulan Data Tertulis Pemeriksaan Penunjang
Merupakan data-data yang dijadikan sebagai referensi. Dalam kasus
ini, data penunjang yang dipakai adalah BERA, pemeriksaan mata, dan
radiografi panggul.
a. BERA atau Brain Evoked Response Audiometry merupakan tes
neurologik untuk fungsi pendengaran batang otak terhadap
rangsangansuara. BERA dapat digunakan untuk mendeteksi dini
adanya gangguan pendengaran, bahkan sejak bayi baru saja
dilahirkan. Tes BERA ini dapat menilai fungsi pendengaran bayi
atau anak yang tidak kooperatif.
9.4. 1. Urutan Masalah Fisioterapi Berdasarkan Prioritas
Urutan masalah didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik baik
pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus dan juga keluhan
dari pasien itu sendiri. Masalah yang timbul meliputi:
2. Diagnosa Fisioterapi
Disusun berdasarkan dari urutan masalah yang ada. Diagnosa
Fisioterapi terdiri dari impairment, keterbatasan gerak, keterbatasan
fungsional yang berhubungan dengan diagnosa medik.
45

9.5. Program Pemeriksaan Fisioterapi
1. Pengumpulan data program Fisioterapi dari dokter Rehabilitasi
Medik
Merupakan program yang disusun oleh dokter Rehabilitasi Medik
yang bersangkutan.
2. Tujuan
a. Tujuan Jangka Pendek
Tujuan jangka pendek biasanya dibuat berdasarkan prioritas
masalah yang utama. Dalam membuat tujuan jangka pendek ini
harus disertai dengan bagaimana tujuan atau rencana tersebut
akan dicapai, alokasi waktu pencapaian, dan kondisi-kondisi
seputar pasien dan lingkungan yang memungkinkan tujuan
tersebut dapat dicapai.
b. Jangka Panjang
Tujuan jangka panjang juga dibuat berdasarkan prioritas
masalah, tetapi bukan masalah yang utama atau segera. Tujuan
jangka panjang harus realistis sesuai dengan perkiraan pemulihan
yang maksimal sesuai patologi dan keadaan pasien juga harapan
dari pasien dan keluarga. Pada kasus anak dengan masalah
Cerebral Palsy Spastic Quadriplegic menentukan prognosis
berjalan berdasarkan penilain 7 refleks dan komponen prognosis
berjalan yang lain adalah kognisi, distribusi spastis, level spastis
berdasarkan nilai Skala Ashworht, penganan atau intervensi dini,
lingkungan atau persepsi, setelah usia 2 tahun belum bisa duduk
maka prognosis berjalan buruk.
3. Metode Pemberian Fisioterapi
Fisioterapis memilih intervensi berdasarkan pada kompleksitas
dan tingkat keparahan dari problem. Fisioterapis memilih,
mengaplikasikan atau memodifikasi satu atau lebih prosedur
46

intervensi berdasarkan pada tujuan akhir dan hasil yang diharapkan
yang telah dikembangkan terhadap pasien.
Metode tersebut meliputi:
1.)Metode Bobath atau Neuro Development Treatment(NDT)
a. Konsep Neuro Development Treatment
Neuro Development Treatment (NDT) menekankan pada
hubungan antara normal postural reflex mechanism
(mekanisme refleks postural normal), yang merupakan suatu
mekanisme refleks untuk menjaga postural normal sebagai
dasar untuk melakukan gerak. Mekanisme refleks postural
normal memiliki kemampuan yang terdiri dari: (1) normal
postural tone, (2) normal reciprocal innervations, dan (3)
variasi gerakan yang mengarah pada fungsional. Syarat agar
mekanisme refleks postural normal dapat terjadi dengan baik:
(1) righting reaction yang meliputi labyrinthine righting
reaction, neck righting reaction, body on body righting
reaction, body on head righting reaction, dan optical righting
reaction, (2) equilibrium reaction, yang mempersiapkan dan
mempertahankan keseimbangan selama beraktivitas, (3)
protective reaction, yang merupakan gabungan antara righting
reaction dengan equilibrium reaction (The Bobath Centre of
London, 1994).
b. Prinsip Teknik Neuro Development Treatmentatau NDT
Prinsip dasar teknik metode Neuro Development
Treatment atau NDTmeliputi 3 hal:
1. Patterns of movement
Gerakan yang terjadi pada manusia saat bekerja adalah
pada pola tertentu dan pola tersebut merupakan representasi
dari kontrol level kortikal bukan kelompok otot tertentu.
Pada anak dengan kelainan sistem saraf pusat, pola gerak
yang terjadi sangat terbatas, yang mana dapat berupa
47

dominasi refleks primitif, berkembangnya pola gerak
abnormal karena terbatasnya kemampuan bergerak, dan
adanya kompensasi atau adaptasi gerak abnormal. Akibat
lebih lanjut anak atau penderita akan menggunakan pola
gerak yang abnormal dengan pergerakan yang minim.
2. Use of handling
Handling bersifat spesifik dan bertujuan untuk
normalisasi tonus, membangkitkan koordinasi gerak dan
postur, pengembangan ketrampilan, dan adaptasi respon.
Dengan demikian anak atau penderita dibantu dan dituntun
untuk memperbaiki kualitas gerak dan tidak dibiarkan
bergerak pada pola abnormal yang dimilikinya.
3. Prerequisites for movement
Agar gerak yang terjadi lebih efisien, terdapat 3 faktor
yang mendasari atau prerequisites yaitu (1) normal postural
tone mutlak diperlukan agar dapat digunakan untuk
melawan gravitasi, (2) normal reciprocal innervations pada
kelompok otot memungkinkan terjadinya aksi kelompok
agonis, antagonis, dan sinergis yang terkoordinir dan
seimbang, dan (3) postural fixation mutlak diperlukan
sehingga kelompok otot mampu menstabilkan badan atau
anggota gerak saat terjadi gerakan/aktivitas dinamis dari
sisa anggota gerak.
c. Teknik-Teknik Dalam Neuro Development Treatment (NDT)
Metode Neuro Development Treatment (NDT) memiliki
teknik-teknik khusus untuk mengatasi pola abnormal aktivitas
tonus refleks (Wahyono, 2008). Teknik-teknik tersebut
meliputi:
48

1. Inhibisi
Inhibisi disini menggunakan Reflex Inhibiting Pattern
(RIP) yang bertujuan untuk menurunkan dan menghambat
aktivitas refleks yang abnormal dan reaksi asosiasi serta
timbulnya tonus otot yang abnormal. Sekuensis dalam
terapi ini meliputi bagian tubuh dengan tingkat affected
terkecil didahulukan dan handling dimulai dari proksimal.
2. Fasilitasi
Fasilitasi bertujuan untuk memperbaiki tonus postural,
memelihara dan mengembalikan kualitas tonus normal,
serta untuk memudahkan gerakan-gerakan yang disengaja
(aktivitas sehari-hari).
3. Propioceptive Stimulation
Merupakan upaya untuk memperkuat dan
meningkatkan tonus otot melalui propioseptive dan taktil.
Berguna untuk meningkatkan reaksi pada anak, memelihara
posisi dan pola gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi
secara otomatis.
4. Key Points of Control (KPoC)
Key Points of Control (KPoC) adalah bagian tubuh
(biasanya terletak di proksimal) yang digunakan untuk
handling normalisasi tonus maupun menuntun gerak aktif
yang normal. Letak Key Points of Control (KPoC) yang
utama adalah kepala, gelang bahu, dan gelang panggul.
5. Movement Sequences and Functional Skill
Teknik inhibisi dan fasilitasi pada dasarnya digunakan
untuk menumbuhkan kemampuan sekuensis motorik dan
keterampilan fungsional anak
49

d. Tujuan Pelaksanaan Neuro Development Treatment(NDT)
Tujuan pelaksanaan metode Neuro Development
Treatment (NDT) adalah menghambat pola gerak abnormal,
normalisasi tonus dan fasilitasi gerakan yang normal, serta
meningkatkan kemampuan aktivitas pasien.
50

BAB III
ISI
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM VOKASI
BIDANG STUDI KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI FISIOTERAPI
FORMULIR FISIOTERAPI
Nama fisioterapi : Ibu Sri Novia, SST FT Peminatan : FT A – Pediatric
Nama dokter : dr. Amendi, SpKFR Ruangan : Pelayanan URM FT lt 2
Nomer Registrasi: 312 – 11 - 81 TanggalPemeriksaan: 20
N
ovember201
2
I. PENGUMPULAN DATA IDENTITAS PASIEN : (S)
Nama Inisial : An A N
Tempat & tgl lahir : Bogor, 17 Oktober 2008 (4 tahun 1 bulan)
Alamat : Cilebut, Bogor
Pendidikan Terakhir : -
Pekerjaan : -
Hobi : -.
Diagnosa Medik : Cerebral Palsy Quadriplegic
51

II. PENGUMPULAN DATA RIWAYAT PENYAKIT (S)
KU : Belum bisa berguling.
RPS : Saat ini anak hanya bisa miring kanan dan miring kiri itu pun
hanya sesekali dan tidak bisa mempertahankannya terlalu
lama.
Sejak lahir jari – jari anak kaku dan cenderung menggenggam.
Saat usia 6 bulan, ibu menyadari bahwa perkembangan anak
terlambat karena anak hanya terlentang saja, kemudian anak
dibawa berobat ke RSCM bagian tumbuh kembang anak lalu
anak di rujuk ke fisioterapi anak terkait keterlambatan anak
saat usia anak 1 tahun. Anak mempunyai dan menggunakan
back slap sejak usia1 tahun dan menggunakan AFO sejak usia
3 tahun 8 bulan.
R. Prenatal : - Usia ibu saat hamil 24 tahun
- Kehamilan diinginkan
- Rajin kontrol di bidan secara rutin setiap satu
bulan sekali dan diberikan vitamin untuk
menambah kalsium.
- Pernah USG saat usia kehamilan 4 bulan dan
dikatakan tidak ada masalah.
- Rutin minum susu untuk ibu hamil.
- Trauma tidak pernah
- Pendarahan tidak pernah
52

R. Natal : - Lahir secara normal dan spontan di tolong
dokter di Rumah Sakit Sunda Kelapa dan anak
langsung menangis.
- Usia kehamilan cukup bulan : 9 bulan 6 hari
- BBL : 2300 gr
- PBL : 44 cm
- Kuning tidak ada
- Biru tidak ada
R. Postnatal: - Kuning tidak ada
- Biru tidak ada
- Kejang tidak
- ASI sampai usia anak 2 tahun
RPD : Tidak ada
RPK : Tidak ada
RPSi : - Anak ke 2 dari 2 bersaudara.
- Anak pertama laki-laki, normal, dan sudah meninggal saat
usia 4 bulan karena sakit dan gagal nafas.
- Usia ayah 30 tahun, pendidikan terakhir ayah SMK, pekerjaan
ayah sebagai tukang parkir.
- Usia ibu 28 tahun, pendidikan terakhir ibu SMK, pekerjaan
ibu rumah tangga.
R. Imunisasi : Imunisasi dasar lengkap.
R. Tumbang : Gross Motor :
- Miring kanan dan kiri : usia 3 tahun
Fine Motor :
53

- Senyum sosial : usia 1 tahun
Bahasa dan Bicara :
- Mengeluarkan kata-kata “hmm” dan tidak
bermakna : usia 3 tahun
Nutrisi :
- Makan bubur susu kental, disuapin dan tidak
langsung telan : usia 2 tahun
- Minum susu formula dan air putih, dengan botol dot
dan di pegangin atau di suapin dengan sendok : usia
2 tahun
III. PEMERIKSAAN (O)
a. Pemeriksaan Umum
1) Cara Datang : Di gendong
2) Kesadaran : Compos Mentis
3) Koperatif
4) Tensi tidak dilakukan
5) Lingkar kepala 39 cm (nn : 47-53 cm)
6) Nadi 100 x/menit
7) RR 20 x/menit
8) Status Gizi : kesan kurang
9) Suhu : Afebris
b. Pemeriksaan Khusus
1. Pengamatan Posisi
1) Terlentang bisa
- Kepala bergerak bebas dan cenderung menoleh
kesatu sisi
- Posisi trunk : Asimetris
- Ekstremitas atas bergerak aktif dan di dominasi pola
ATNR
Dengan kecenderungan posisi :
54

Upper Extremity Dextra
o Shoulder : Retraksi, semifleksi, abduksi,
eksorotasi
o Elbow : Semifleksi
o Forearm : Supinasi
o Wrist : Semifleksi
o Finger : Fleksi, menggenggam dengan
thumb in
Upper Extremity Sinistra
o Shoulder : Retraksi, fleksi, abduksi,
eksorotasi
o Elbow : semifleksi
o Forearm : Pronasi
o Wrist : Fleksi
o Fingers : Fleksi, menggenggam dengan
thumb out
- Ekstremitas bawah : menggunting
Dengan kecenderungan posisi :
Lower Extermity billateral
o Hip : Semifleksi, adduksi, endorotasi
o Knee : Semifleksi
o Ankle : Plantar fleksi, eversi
o Toes : Fleksi
2) Berguling tidak bisa
3) Diposisikan telungkup bisa
- Head liftingbisa
- Head control inadekuat
- Forearm supporttidak bisa
- Hand supporttidak bisa
- Posisi trunk : Asimetris
- Ekstremitas atas : Keduanya tertindih oleh badan
55

Dengan kecenderungan posisi :
Upper Extremity Billateral
o Shoulder : Retraksi, fleksi, adduksi,
endorotasi
o Elbow : Fleksi
o Forearm :Pronasi
o Wrist : Fleksi
o Fingers : Fleksi dan menggenggam
- Ekstremitas bawah : menggunting
Dengan kecenderungan posisi :
Lower Extremity Billateral
o Hip : Semifleksi, adduksi, endorotasi
o Knee : Semifleksi
o Ankle : Plantar fleksi, eversi
o Toes : Fleksi
4) Merayap tidak bisa
5) Diposisikan duduk bisa dengan fiksasi di pelvic :
- Head lifting bisa
- Headcontrol inadekuat
- Hand supporttidak bisa
- Trunk controltidak bisa
- Posisi trunk round back
- Weight bearing di sacrum
- Sitting balancetidak ada
- Protective reactiontidak ada
- Ekstremitas atas di dominasi pola ATNR
Dengan kecenderungan posisi :
Upper Extremity Dextra
o Shoulder : Retraksi, adduksi, endorotasi
o Elbow : Semifleksi
o Forearm : Supinasi
56

o Wrist : Semifleksi
o Finger : Fleksi, menggenggam dengan
thumb in
Upper Extremity Sinistra
o Shoulder : Retraksi, adduksi, endorotasi
o Elbow : Semifleksi
o Forearm : Pronasi
o Wrist : Fleksi
o Fingers : Fleksi, menggenggam dengan
thumb out
- Ekstremitas bawah : menggunting
Dengan kecenderungan posisi :
Lower Extremity Billateral
o Hip : Semifleksi, adduksi, endorotasi
o Knee : Semifleksi
o Ankle : Plantar fleksi, eversi
o Toes : Fleksi
6) Ke duduk tidak bisa
7) Merangkak tidak bisa
8) Di posisikan berdiri dengan fiksasi di axilla
- Head liftingbisa
- Head control inadekuat
- Trunk control tidak bisa dilihat
- Weight bearingtidak ada, menapak tetapi tidak
menumpu
- Ekstremitas atas bergerak aktif dan di dominasi pola
ATNR
Dengan kecenderungan posisi :
Upper Extremity Dextra
o Shoulder : Retraksi, adduksi, endorotasi
o Elbow : Semifleksi
57

o Forearm : Supinasi
o Wrist : Netral
o Finger : Fleksi, menggenggam dengan
thumb in
Upper Extremity Sinistra
o Shoulder : Retraksi, adduksi, endorotasi
o Elbow : Semifleksi
o Forearm : Pronasi
o Wrist : Fleksi
o Fingers : Fleksi, mengenggam dengan thumb
out
- Ekstremitas bawah : menggunting
Dengan kecenderungan posisi :
Lower Extremity Billateral
o Hip : Semifleksi, adduksi, endorotasi
o Knee : Semifleksi
o Ankle : Plantar fleksi, eversi
o Toes : Fleksi
9) Ke berdiri tidak bisa
2. Spastisitas ada
Skala Ashworth :
1) Upper Extremity :
- Dextra : 1+
- Sinistra : 1+
2) Lower Extremity :
- Dextra : 2
- Sinistra : 2
3. Tonus postural : Tinggi
58

4. Ankle Clonustidak ada
5. Tightnessada, pada :
1) m. Illiopsoas billateral
2) m. Achilles billateral
6. Pemeriksaan 7 refleks :
1) ATNR (+) : 1
2) Neck righting (-) : 0
3) Ekstensor Thrust (-) : 0
4) Moro (+) : 1
5) STNR (-) : 0
6) Parachute (-) : 1
7) Foot Pacement (-) : 1 +
Skor : 4 (nn : 0)
Kesimpulan : Prognosis berjalan buruk.
7. Fungsi bermain :
Jenis permainan : Puzzle bentuk ember, kerincingan
- Mengikuti sumber bunyi bisa
- Mengikuti objek bisa
- Meraih mainan tidak bisa
- Menggenggam tidak bisa
- Mengikuti perintah sederhana tidak bisa
- Mengenal bentuk dan warna tidak bisa
- Berhitung tidak bisa
- Memainkan mainan sesuai fungsi tidak bisa
Kesimpulan : Level bermain sesuai anak 4 bulan
IV. PENGUMPULAN DATA TERTULIS PEMERIKSAAN
PENUNJANG
1. BERA, Tanggal pemeriksaan 12 mei 2009
59

Kesimpulan : Ambang dengar AS : 30 dB (normal)
Ambang dengar AD : 40dB (abnormal)
2. MATA, Tanggal pemeriksaan 11 juni 2011
Kesimpulan : Konjungtiuitas OS
Observasi cortical visual impairment
3. Radiografi tanpa kontras, Tanggal pemeriksaan 28
september 2011
Kesimpulan : Gambaran DDH kiri dengan dislokasi kaput
femur bilateral ke superolateral
V. 1. URUTAN MASALAH FISIOTERAPI BERDASARKAN
PRIORITAS
1) Tonus postural tinggi
2) Pola ATNR mendominasi setiap gerakan
3) Kecenderungan posisi trunk asimetris dan hyperekstensi
4) Kecenderungan posisi shoulder retraksi dan hip semifleksi,
adduksi dan endorotasi
5) Head control inadekuat
6) Tidak bisa forearm support
7) Tidak bisa hand support
8) Tidak bisa rotasi trunk
9) Belum bisa berguling
10) Tidak ada trunk control
11) Tidak ada sitting balance
12) Tidak ada protektif reaction
13) Tightness pada m. Illiopsoas billateral, m. Hamstring
billateral, dan m. Achilles billateral
14) Fungsi bermain tidak sesuai usia, selevel usia 4 bulan
2. DIAGNOSA FISIOTERAPI
Belum bisa berguling karena adanya head control inadekuat,
shoulder retraksi, trunk asimetri hiperekstensi,tidak bisa rotasi
60

trunk, dan kecenderungan posisi hip semifleksi, adduksi,
endorotasi terkait dengan tonus postural tinggi dan pola ATNR
di setiap gerakan.
61

VI. PROGRAM PELAKSANAAN FISIOTERAPI (P)
1. Pengumpulan data program fisioterapi dari dokter Rehabilitasi
Medik
1) Inhibisi spastis
2) Stimulasi propioseptif
3) Latihan ROM dan streching
4) Latihan rolling untuk sitting
2. Tujuan :
a. Tujuan Jangka Pendek
1) Berguling
2) Persiapan duduk di kursi roda
3) Maintenance : - Memelihara lingkup gerak sendi
- Memelihara fleksibelitas otot
- Memelihara kapasitas fungsional
paru
- Memelihara kepadatan tulang dan
mencegah osteoporosis
b. Tujuan Jangka Panjang
1) Duduk di kursi roda dengan fiksasi di badan
2) Maintenance : - Memelihara lingkup gerak sendi
- Memelihara fleksibelitas otot
- Memelihara kapasitas fungsional
paru
- Memelihara kepadatan tulang dan
mencegah osteoporosis
62

3. Metoda Pemberian Fisioterapi
NO JENIS METODA DOSIS KETERANGAN
1. Terapi
Latihan
NDT atau
BOBATH Anak
1 kali
seminggu
- Inhibisi spastik
- Fasilitasi berguling
- Mengembangkan head
control, trunk contol, fore
arm support, hand support
- Memelihara fleksibelitas
otot dan lingkup gerak
sendi
4. Uraian Tindakan Fisioterapi
a. Stimulasi taktil:
Posisi anak : terlentang di atas wedge
Posisi terapis : di depan anak
Tatalaksana : Terapis memposisikan anak terlentang di
atas wedge. Terapis memberikan sentuhan
awal secara gantle pada wajah anak, arah
mulai dari dahi sampai dagu. Kemudian
lanjutkan usapan pada badan, tangan, dan
tungkai.Ulangi beberapa kali.
b. Inhibisi spastisitas
1) Untuk menurunkan tonus postural dan
mengembangkan rotasi trunk.
Posisi anak : miring ke salah satu sisi di atas
matras
Posisi terapis : di samping anak
Tatalaksana : Handling tangan terapis di pelvic
anak dan tangan lainnyamemfiksasi
pada bahu anak pada posisi shoulder
protraksi. Gerakkan pelvic ke arah
posterior dan anterior secara
63

bergantian dengan gentle sehingga
terjadi gerakan rotasi pada trunk,
ulangi beberapa kali sampai mulai
terasa tonus anak menurun.
Kemudian fasilitasikan anak ke arah
telungkup atau berguling via
shoulder, ulangi beberapa kali.
Untuk mengajarkan anak cara
berguling.
2) Inhibisi dan mengembangkan head control,
Posisi anak : telungkup di pangkuan terapis
Posisi terapis : duduk bersila
Tatalaksana : Posisikan anak telungkup di atas
paha terapis. Handling tangan
terapis pada bahu dan tangan
lainnya pada pelvic anak. Gerakkan
bahu anak ke arah elevasi anterior
dan pelvic ke arah depresi posterior
secara bersama-sama dengan gentle
sehingga terjadi gerakan elongasi
pada trunk dan tunggu sampai anak
mengangkat kepala.
3) Inhibisi spastis
Posisi anak : terlentang di atas matras
Posisi terapis : di depan anak
Tatalaksana : Terapis memposisikan anak
terlentang di atas matras. Lalu
terapis memasangkan back slap
pada ke dua lengan anak untuk
menginhibisi pola spastis pada
64

lengan. Kemudian posisikan kaki
anak didepan badan terapis selebar
bahu anak. Terapis menggerakkan
ke 2 lengan anak dengan handling
dan fiksasi pada tangan anak dengan
posisi pronasi dan ekstensi wrist
gerakkan shoulder ke arah fleksi dan
abduksi.
4) Mengembangkan head control, trunk control, dan
hand support
Posisi anak : duduk di pangkuan terapis
Posisi terapis : duduk bersila
Tatalaksana : Anak memakai back slap pada ke
dua lengan. Terapis memposisikan
anak duduk di pangkuannya. Terapis
meletakkan tangan anak dalam
posisi pronasi dan ekstensi wrist
kemudian letakkan ke dua tangan
anak di samping tubuhnya dan
diatas paha terapis. Fiksasi terapis
pada pelvic. Biarkan dalam beberapa
menit.
5) Inhibisi, aproksimasi, dan mengembangkan head
control, trunk control, dan hand support.
Posisi anak : di posisikan duduk bersila
Posisi terapis : di belakang os
Tatalaksana : Anak memakai back slap pada ke
dua lengan. Terapis memposisikan
anak duduk di depannya. Terapis
meletakkan ke dua tangan anak di
65

samping tubuhnya dengan posisi
shoulder abduksi, forearm pronasi
dan ekstensi wrist. Setelah beberapa
menit, terapis menggerakkan pelvic
ke arah samping kanan, samping
kiri, depan dan belakang dengan
handling ke dua tangan terapis di
pelvic anak. Setelah tonus postural
anak menurun dan bahu netral,
letakkan ke dua tangan anak di
belakang tubuhnya dan di atas paha
terapis dengan posisi tangan masih
sama. Biarkan beberapa menit, lalu
terapis merotasikan bahu anak
secara bersamaan dengan handling
pada kedua tangan anak. Ulangi
beberapa kali.
c. fasilitasi berguling
Untuk mengembangkan head control, rotasi trunk,
forearm support, dan hand support
Di Bola
1) Posisi anak : terlentang di atas bola
Posisi terapis : di depan anak
Tatalaksana : Lepaskanback slap pada ke dua
lengan anak. Terapis memposisikan
anak terlentang di atas bola.
Handling terapis pada hip dan bahu
anak, terapis fasilitasikan anak ke
telungkup atau berguling via hip lalu
kembalikan anak ke terlentang dan
lakukan secara berulang-ulang.
Sesekali saat anak berguling ke arah
66

terlentang anak di posisikan duduk
agar anak secara tidak langsung
mengangkat dan mempertahankan
kepalanya tegak beberapa saat.
2) Posisi anak : telungkup di atas bola
Posisi terapis : dibelakang anak
Tatalaksana : Salah satu tangan terapis memfiksasi
hip agar kaki terbuka selebar bahu
dan mencegah gerakan fleksi,
adduksi, dan endorotasi. Sedangkan
Tangan yang lainnya memposisikan
ke dua tangan anak untuk fore arm
support. Kemudian terapis
mendorong bola secara perlahan ke
samping kanan, kiri, depan, dan
belakang. Secara tidak langsung
anak mengangkat kepalanya
beberapa saat. Ulangi beberapa kali.
Sesekali saat dorongan bola
kebelakang, dorong bola sampai ke
dua kaki anak menyentuh lantai dan
seolah-olah anak berdiri dengan
pegangan pada bola. Diamkan anak
dalam posisi berdiri seperti ini
beberapa saat.
5. Program untuk dirumah
1) ALL DAY MANAJEMENT maksudnya lakukan hal di bawah
ini sepanjang daur kehidupannya.
2) Sering menyentuh wajah anak dan seluruh tubuh dengan
tangan atau kain kasar
67

3) Cara menggendong dengan benar yaitu
1. Posisi ke dua tungkai lurus dan ke dua lengan di depan
2. Menggendong anak menghadap depan, tangan kanan
ibu memegang paha anak dari bawah dan tangan kiri
ibu di dada anak, usahakan agar punggung anak tidak
terlalu bersandar.
4) Cara mengangkat anak yang benar yaitu dengan cara tangan
ibu pada bahu belakang anak, miringkin anak terlebih
dahulu lalu angkat bahu anak kemudian bokongnya.
5) Bermain dengan posisi anak telungkup dan di ganjal bantal
pada area dada sesering mungkin. Biarkan kepala anak
terangkat dan tegak.
6) Bermain atau makan diposisikan duduk bersila atau
dipangkuan orang tua. Pasang back slap pada kedua lengan
anak dan arahkan ke dua tangan anak untuk menumpu di
depan atau di samping badannya. Pastikan anak aman dan
dalam pengawasan orang tua.
VII. EVALUASI
1. Evaluasi Hasil Terapi
1) Selasa, 20 November 2012
S : Mood anak sedang tidak baik, resah, dan sering
menangis saat intervensi fisioterapi karena bibirnya
sedang sariawan dan sering tergigit.
O : - Nadi : 108 x/menit
- RR : 24 x/menit
- Saat anak di posisikan telungkup dengan forearm
support anak bisa mempertahankan posisi
kepalanya terangkat dan tegak dalam beberapa
saat.
- Anak lebih mudah miring kanan atau miring kiri
via shoulder walau belum sampai berguling.
68

A : Belum bisa berguling karena adanya head control
inadekuat, tidak bisa rotasi trunk, dan
kecenderungan posisi trunk asimetri hyperekstensi,
shoulder retraksi, dan hip semifleksi, adduksi,
endorotasi pola menggunting terkait dengan tonus
postural tinggi dan pola ATNR di setiap gerakan.
P : BOBATH anak : Inhibisi pola spastis dan fasilitasi
berguling
69

BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Kerusakan central pada otak yang imatur atau kerusakaan saat pre natal,
natal, dan post natal sampai usia 2 tahun dapat menyebabkan kelumpuhan ke 4
anggota gerak, sebagian, atau satu sisi tubuh yang biasa dikenal dengan
cerebral palsy.
Cerebral Palsy adalah kumpulan gejala neuromuskular atau pada otot-otot
saraf dengan berbagai macam etiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis,
yang disebabkan lesi non progresif pada otak imatur.
Pada kasus ini termasuk cerebral palsy spastic quadriplegic atau total
body involvement. Dengan ciri-ciri tonus postural meningkat, spastis pada total
ekstensi head, neck, and trunk, kontraksi otot yang berlebih, sehingga
menyebabkan kecenderungan posisi pada keempat anggota gerak, refleks
primitif yang masih menetap yang menjadi refleks patologis.
Penatalaksanaan fisioterapi pada cerebral palsy adalah Neuro
Development Treatment atau Bobath anak. Yang meliputi, stimulasi, inhibisi
dan fasilitasi. Pada kasus ini, tindakan fisioterapi yang dilakukan yaitu
stimulasi taktil dan propioseptif, inhibisi spastis, fasilitasi berguling dan
maintenance sepanjang daur kehidupan anak.
2. Saran
Jika mempunyai anak dengan kasus seperti yang telah diuraikan diatas,
lakukan penanganan sedini mungkin, jangan biarkan kecacatan anak berlanjut.
Intervensi sedini mungkin dengan dokter spesialis anak dan tindakan
fisioterapi. Hindari mengangkat anak dengan cara menarik, ada baiknya
miringkan anak terlebih dahulu lalu angkat. Kemudian cara menggendong anak
dengan posisi tangan, tungkai dan lengan anak lurus didepan. Hindari
pemakaian baby walker pada anak.
70

DAFTAR PUSTAKA
Arif Mansjoer. Kapita Selekta Kedokteran Jilid 2. Edisi ke-3. Jakarta: Media Aesculalpius FKUI; 2000.
Elita Mardiani. Tesis Faktor – Faktor Risiko Prenatal Dan Perinatal Kejadian Cerebral Palsy. Semarang: Universitas Diponegoro; 2006.
Jan S. Tecklin. Pediatric Physical Therapy. 4th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Walkins; 2008.
Kuban KCK, Leviton A. Cerebral palsy. The New England Journal of Medicine 1992.
Lane R. et al. Psychosom Med. Philadelphia: Lippincott Williams & Walkins; 2009.
Laurie Glazener. Texbook: Sensory Development. 2009.
Lunar. Jadwal Imunisasi IDAI dan Dep. Kesehatan RI. Post on 1 Mei 2012. Available in: http://forensik093.blogspot.com/2012/05/jadwal-imunisasi-idai-dan-dep-kesehatan.html
Malene Wesselhoff. The Modified Ashworth Scale. Post on Juni 2012. Available in: http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Ashworth-Scale/
Pamela M. Eckersley. Elements of Paediatric Physiotherapy. Singapore: Longman Singapore Publishers; 1993.
Peter L. Rosenbaum L P, Walter D S et al. Prognosis for Gross Motor Function in Cerebral Palsy : Creation of Motor Development Curves. JAMA. 2002.
Paul D. Anderson. Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Alih bahasa oleh Yasmin Asih. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 1996.
Peter L. Rosenbaum, Walter SD, et al. Prognosis for gross motor function in cerebral palsy: creation of motor developmental curve. JAMA 2002.
Satyanegara. Ilmu Bedah Saraf. Edisi ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1998.
71

Soetjiningsih. Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 1995.
Steven M, Strauss J D, et all. Prognosis for ambulation in cerebral palsy : A population-based study. Pediatrics 2004.
Williem. Penyandang Cacat di Indonesia. Post on 29 Oktober 2012. Available in: www.depkes.go.id
World Health Organization1993. Promoting the Development of Young Children With Cerebral Palsy: World Health Organization, Geneva.
72

LAMPIRAN
73