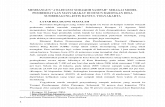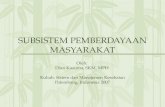Pemberdayaan Masyarakat Di TPA
-
Upload
iqbal-rhizaldi -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
Transcript of Pemberdayaan Masyarakat Di TPA

7
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pemberdayaan Masyarakat
Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk
menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan
hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya (Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat
selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.
Menurut McArdle (1989), pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh
orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan, orang-orang yang telah
mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan
keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi
pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka
tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun, bukan hanya untuk
mencapai tujuannya yang penting, akan tetapi lebih pada makna pentingnya proses dalam
pengambilan keputusan. Friedmann (1992), menyatakan bahwa proses pemberdayaan
adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap menjadi semakin
efektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional,
internasional maupun bidang politik, ekonomi dan lain- lain. Proses pemberdayaan
mengandung dua kecenderungan:
a. Menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan
atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya;
b. Kemampuan individu untuk mengendalikan lingkungannya, adalah suatu proses
pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan politik, ekonomi dan
sosial yang tidak dapat dipaksakan dari luar.
Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor sosial, politik dan
psikologi. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mencerminkan paradigma baru
pembangunan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat
dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya sekarang tidak mampu untuk
melepaskan diri dari perangkap ketidak mampuan dan keterbelakangan.

8
Menurut Hikmat (2001), pemberdayaan masyarakat merupakan strategi
pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang mempunyai
arah pada kemandirian masyarakat. Oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat
pada dasarnya masyarakat perlu mengembangkan kesadaran atas potensi, masalah dan
kebutuhannya sehingga akan terwujud rasa tanggungjawab dan kesadaran untuk memiliki
dan memelihara program pengembangan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat
tentang keberdayaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan masyarakat untuk
menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat
meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik
mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Konsep pemberdayaan
dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri,
partisipasi, jaringan kerja dan keadilan Hikmat (2001). Pemberdayaan dan partisipasi
merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial
dan transformasi budaya, proses ini akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih
berpusat pada rakyat.
Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sangat penting, menurut Uphoff (Sumardjo
dan Saharudin, 2003) ada tiga alasan utama yaitu (1) sebagai langkah awal
mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan suatu cara untuk
menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap program
pembangunan yang dilaksanakan (2) sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai
kebutuhan potensi dan sikap masyarakat setempat (3) masyarakat mempunyai hak untuk
memberikan pemikir annya dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan
di wilayah mereka. Sedangkan menurut Oppenheum (Sumardjo dan Saharudin, 2003) ada
dua hal yang mendukung terjadinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan
dan pembangunan, yaitu: (1) adanya unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu
pada diri seseorang dan (2) iklim dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pelaku
tersebut.
Menurut Syaukani (1999), pemberdayaan tidak hanya terpusat pada individu-
individu masyarakat, tetapi juga pendukungnya misalnya peraturan, nilai-nilai modern,

9
kerja keras, hemat, keterbukaan, rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Pemberdayaan
masyarakat adalah kemampuan setiap individu untuk terlibat dan berperan dalam
pembangunan, dengan demikian masyarakat berhak dan wajib menyumbangkan
potensinya dalam pembangunan, sekecil dan selemah apapun kualitas sumberdaya
seseorang bisa diberdayakan dalam pembangunan di daerahnya.
Menurut Departemen Dalam Negeri (1996), Pembangunan Masyarakat Desa
adalah seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dan kelurahan dan
mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu
dengan mengembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong. Dalam memperdayakan
masyarakat, pemerintah mengarahkan program-program yang diperuntukkan dan
langsung akan dinikmati masyarakat, rencana dan pelaksanaannya dilakukan oleh
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas
sumberdaya manusia dan masyarakat agar mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan tujuan dan sasarannya,
meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat; pencapaian tujuan pembangunan
masyarakat; semangat membangun pada seluruh masyarakat; dan menempatkan manusia
sebagai subyek pembangunan. Sasarannya adalah pimpinan lembaga kemasyarakatan;
tokoh masyarakat dan warga masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin.
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membekali
keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu memberikan kontribusi
dan dukungan terhadap proses pembangunan yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat
akan ikut menangani limbah domestik apabila mereka memiliki "keberdayaan", sehingga
pemberdayaan masyarakat menjadi penting dan mendesak (Ditjen Bina Bangda, 2002).
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, menempatkan otonomi daerah secara utuh
pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan tujuan untuk memberdayakan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Atas dasar ini, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai kewenangan
dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan
aspirasi masyarakat (Elfian, 2001).

10
Prinsip dasar otonomi daerah adalah memberdayakan daerah dan pemberdayaan
masyarakat. Agar Pemerintah Daerah mampu mengelola sumberdaya secara optimal,
keputusan publik harus mampu menjawab permasalahan dengan memanfaatkan
sumberdaya secara optimal di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna sejauh mana masyarakat terlibat dalam
pengambilan keputusan, melaksanakannya dan mengawasi keputusan tersebut, termasuk
peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan menuju kemandirian, sehingga
berperan sebagai penjinak bencana bukan menjadi korban bencana (Jurnal Otonomi
Daerah, 2001).
Selanjutnya menurut Bangda (2002), strategi pemberdayaan masyarakat antara
lain adalah:
a. Keterbukaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah domestik, yang segala
sesuatunya dibicarakan dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi faham dan
mengerti.
b. Responsif dan aspiratif, menampung dan menindaklanjuti keinginan masyarakat dan
tidak membiarkan masalah menjadi berlarut-larut.
c. Jemput bola, tidak menunggu timbul masalah baru bekerja, tetapi aktif untuk
membantu masyarakat dalam keadaan apapun.
d. Dengan membentuk kelompok (1 kelompok = 10 orang) untuk mengelola dan
menangani limbah domestik, kelompok ini menjadi ujung tombaknya.
e. Mengembangkan semangat “perang terhadap limbah domestik” dalam diri
masyarakat melalui media elektronik, cetak, spanduk dan brosur.
f. Mengembangkan budaya bersih dan sehat dalam lingkungan RT, RW dan Desa atau
Kelurahan.
Pelaksanaannya dapat berbentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat antara lain: kursus, pelatihan, orientasi, lokakarya, seminar, studi banding,
diseminasi dan sosialisasi. Setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan
diharapkan mampu dan ikut serta dalam pengelolaan limbah domestik. Menurut Stewart
(1994) pemberdayaan merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan
tanggung jawab secara penuh. Pemberdayaan bukan berarti melepaskan pengendalian,
tapi menyerahkan pengendalian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah masalah

11
hilangnya pengendalian atau hilangnya hal-hal lain, yang paling penting pemberdayaan
memungkinkan pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan masyarakat seoptimal mungkin
untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
Pemberdayaan menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat
yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang
menaruh kepedulian sebagai pihak memberdayakan, Sumodiningrat (1997). Dalam kaitan
dengan upaya memberdayakan masyarakat guna mencapai kehidupan yang lebih baik.
Payne (1997) suatu proses pemberdayaan bertujuan membantu masyarakat memperoleh
daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan melalui
peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki
masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. MAcArdle (1989)
mengemukakan bahwa hal terpenting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam
setiap proses pengambilan keputusan.
Menurut Hikmat (2001), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan;
Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses
memberikan keleluasaa n, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu
yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya
membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui
organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan
atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Seringkali
kecendrungan primer terwujud melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.
Selanjutnya disebutkan bahwa proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan
masyarakat yang berdasarkan prinsif bekerja bersama masyarakat mempunyai hak-hak
yang harus dihargai, sehingga masyarakat lebih mampu mengenali kebutuhannya dan
dilatih untuk dapat merumuskan rencana serta melaksanakan pembangunan secara
memadai dan swadaya. Dalam hal ini, praktisi pembangunan berperan dalam
memfasilitasi proses dialog, diskusi, curah pendapat dan mensosialisasikan temuan
masyarakat.
Menurut Moebyarto (1995), pemberdayaan masyarakat mengacu kepada
kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas

12
sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial
yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu "senasib"
untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk
pemberdayaan yang paling efektif. Dalam rangka mewujudkan kesamaan derajat yang
lebih besar antara perempuan dan laki- laki, pemberdayaan perempuan merupakan proses
kesadaran pembentukan kapasitas terhadap partisipasi perempuan yang lebih besar dan
tindakaan transformasi. Dalam rangka peningkatan partisipasi aktif laki- laki dan
perempuan, maka perempuan harus terlibat secara proporsional, sehingga dapat
menciptakan kemitraan yang adil, IRC, UNICEF dan Yayasan Dian Desa (1999).
Strategi pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki- laki menggunakan
pendekatan dua arah, yaitu saling menghormati, saling mendengar dan menghargai
keinginan serta pendapat orang lain. Dalam proses pemberdayaan ini, terjadi pembagian
kekuasaan secara demokratis atas dasar kebersamaan, keutamaan dan tenggang rasa.
Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki adalah kondisi dimana laki- laki
dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan,
kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku yang saling membantu dan
mengisi disemua bidang kehidupan (Priyono, 1996).
Praktek proyek pembangunan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tidak
secara otomatis diterapkan dengan cara yang sensitif gender. Bila tidak ada kaitan
tertentu yang dilakukan untuk melibatkan semua segmen dalam komunitas dalam aksi
partisipatif dari proyek, yang biasanya terjadi adalah laki-laki yang berpendidikan dan elit
yang terlibat seperti yang ada dalam struktur kekuasaan dimana suara perempuan anggota
masyarakat yang tidak beruntung dan miskin tidak didengar, Hemelrijk, et al (2001).
Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses
pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan
keputusan merupakan hal penting dalam pemberdayaan. Faktor- faktor determinin yang
mempengaruhi proses pemberdayaan, antara lain, perubahan sistem sosial yang
diperlukan sebelum pembangunan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu
perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam
melaksanakan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan
politik (Rojek, 1986).

13
Di dalam kerangka pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, maka haruslah
terjadi pergeseran fungsi birokrasi sebagai fasilitator. Selayaknya birokrasi harus kembali
ke hakikat fungsi yang sebenarnya ialah sebaga i pelayan masyarakat, bukan
mencampuradukan dengan pembangunan maupun pemberdayaan. Rakyat memegang hak
dan wewenang yang tinggi untuk menentukan kebutuhan pembangunan, ikut terlibat
secara aktif dalam pembangunan dan mengontrolnya serta memperoleh fasilitas dari
pemerintah (Santoso, 2002).
Jadi pemberdayaan masyarakat adalah memberi daya atau kekuatan dan
kemampuan serta meningkatkan harkat dan martabat untuk dapat berdiri sendiri diatas
kakinya sendiri melalui penyuluhan dan pendampingan pada suatu kegiatan yang
bertujuan membekali keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu
memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pembangunan di lingkungannya.
2.2. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "participation" yang berarti ambil bagian
atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Sedangkan dalam kamus
Webster, arti partisipasi "mengambil bagian atau ikut menanggung bersama orang lain"
Natsir (1986). Apabila dihubungkan dengan masalah sosial, maka arti partisipasi adalah
suatu keadaan dimana seseorang ikut merasakan sesuatu bersama -sama dengan orang lain
sebagai akibat adanya interaksi sosial, Fairchild (1977). Secara harfiah, partisipasi berarti
"turut berperanserta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu
kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat
didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat
secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari da lam dirinya maupun dari luar
dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan" (Moeliono, 2004).
Dari sudut terminologi partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara
melakukan interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak
diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan kelompok yang melakukan
pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan insentif moral untuk
mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-
keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.

14
Tjokroamidjojo (1990), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah
keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijaksanaan kegiatan,
memikul beban dan pelaksanaan kegiatan, memetik hasil dan manfaat kegiatan secara
adil. Partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan
pembangunan, yang ditekankan adalah hak dan kewajiban setiap orang. Koentjaraningrat
(1974) berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut menentukan
arah atau tujuan pembangunan, dimana ditekankan bahwa partisipasi itu adalah hak dan
kewajiban bagi setiap masyarakat.
Jadi partisipasi dapat diartikan sebagai sesuatu keterlibatan seseorang atau
masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan
pembangunan untuk menciptakan, melaksanakan serta memelihara lingkungan yang
bersih dan sehat. Peranserta masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan
menyertai pemerintah dalam memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar,
mempercepat dan menjamin keberhasilan usaha pembangunan Santoso dan Iskandar
(1974). Masyarakat diharapkan ikut serta, karena hasil pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat
sendiri, dalam hal ini pemerintah memberi bantuan dan masyarakat mempunyai
tanggapan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan tersebut. Agar
masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan tiga syarat sebagai
berikut: 1). adanya kesempatan untuk membangun; 2). adanya kemauan untuk
memanfaatkan kesempatan; dan 3). adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
Secara teoritis, partisipasi merupakan alat dan sekaligus tujuan pembangunan
masyarakat. Sebagai alat pembangunan, partisipasi berperan sebagai penggerak dan
pengarah proses perubahan sosial yang dikehendaki, demokratisasi kehidupan sosial
ekonomi serta yang berasaskan kepada pemerataan dan keadilan sosial, pemerataan hasil
pembangunan yang bertumpu pada kepercayaan kemampuan masyarakat sendiri,
selanjutnya sebagai tujuan pembangunan, partisipasi merupakan bentuk nyata kehidupan
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, Cary (1970). untuk menjamin
kesinambungan pembangunan, maka partisipasi masyarakat harus tetap diperhatikan dan
dikembangkan. Menurut Cary (1970), agar partisipasi dalam pembangunan dapat terus

15
berkembang perlu diperhatikan prasyarat sebagai berikut: 1). aspek partisipasi yang
mendasar adalah luasnya pengetahuan dan latar belakang kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menentukan prioritas pemecahan masalah; 2). adanya kemampuan
untuk belajar terhadap berbagai masalah sosial dan cara mengambil keputusan
pemecahannya; dan 3). kemampuan untuk mengambil tindakan secara cepat dan tepat.
Menurut Cressey (1987), partisipasi menjadi fokus utama dalam usaha
peningkatan tarap hidup masyarakat, dan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan-
pertanyaan tentang kewenangan, otoritas, legitimasi serta pengendalian dan tampak
terkait dengan aspek-aspek politik. Dalam prakteknya, partisipasi tidak dapat
didefinisikan secara terbatas, tergantung pada aktor yang terlibat. Terdapat beberapa
model partisipasi pada saat ini yang didasarkan pada pemikiran dan pendekatan terhadap
persoalan, beberapa tipe partisipasi itu ialah:
a. Partisipasi dilihat sebagai kesatuan organik dari kepentingan perusahaan (organic
unity of interest) partisipasi mengambil tempat melalui kerja kelompok dan struktur
untuk mengusahakan aspek-aspek peningkatan dan pengembangan sesuai dengan
sasaran dan tujuan perusahaan.
b. Partisipasi berdasarkan lembaga yang ada (statutory), biasanya dijumpai pada
masyarakat yang memiliki konsensus politik yang stabil, umumnya bersifat formal,
biasanya dimulai dari legalitas, berkembang ke lembaga-lembaga seperti perwakilan
atau pengaturan tripartit.
c. Partisipasi sukarela (voluntary), tidak diprogram, muncul berdasarkan kebutuhan
kelompok dan kebutuhan perusahaan dan bersifat positif kadang-kadang kepada
pengambil keputusan bersama perusahaan.
d. Partisipasi manajeman sendiri (self management) yang mengembangkan demokrasi
dan formalitas kontitusi seperti diskusi investasi dan pengembangan.
Menurut Hassan (1973), partisipasi dalam pembangunan berarti masyarakat ikut
ambil bagian dalam suatu kegiatan, ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan hanya dapat
diharapkan bila yang bersangkutan merasa dirinya berkepentingan dan diberi kesempatan
untuk ambil bagian. Dengan kata lain, partisipasi tidak mungkin optimal jika diharapkan
dari mereka yang merasa tidak berkepentingan terhadap suatu kegiatan, dan juga tidak
optimal jika mereka yang berkepentingan tidak diberi keleluasaan untuk ambil bagian.

16
Sedangkan Poerwadarminta (1986), berpendapat bahwa masyarakat adalah pergaulan
hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatan-
ikatan aturan yang tertentu). Selanjutnya Soekanto (1986) berpendapat bahwa masyarakat
adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja secara cukup lama sehingga
mereka dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial
dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Masyarakat adalah sekelompok
orang yang mempunyai identitas sendiri, yang membedakan dengan kelompok lain dan
hidup diam dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini, baik
sempit maupun luas mempunyai peranan akan adanya persatuan di antara anggota
kelompok dan menganggap dirinya berbeda dengan kelompok lain. Mereka memiliki
norma-norma, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dipatuhi bersama
sebagai suatu ikatan. Perangkat dan pranata tersebut dijadikan pedoman untuk memenuhi
kebutuhan kelompok dalam arti seluas- luasnya (Widjaja, 1986).
Jenssen (1992) berpendapat, berbagai kelompok pada hakekatnya terlibat dalam
pembangunan di daerah seperti administratur pembangunan, politisi, spesialis, teknisi,
kelompok tani, pedagang, pelaku bisnis, manajer perorangan, guru, anggota lembaga
keuangan dan organisasi-organisasi lainnya. Untuk itu, kontribusi mereka dalam
mempersiapkan perencanaan yang direfleksikan dalam kepentingan gagasan, usulan dan
harapan merupakan hal yang sangat diperlukan. Selanjutnya Departemen Dalam Negeri
(1982), menyatakan bahwa partisipasi dilakukan dalam berbagai refleksi di antaranya
dalam pengambilan keputusan, baik secara individu maupun secara institusional misalnya
melalui kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga
Masyarakat Desa (LMD). Upaya meningkatkan peranserta masyarakat dibutuhkan dalam
pembangunan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Partisipasi masyarakat dalam
perencanaan secara teknis berlangsung berdasarkan pertimbangan sasaran dan tujuan.
Sasaran yang dimaksud meliputi pembenahan administratif dan kepentingan umum.
Selanjutnya Cressey (1987), menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh konteks
sosial ekonomi atau pemasaran, teknologi dan produktivitas, serta organisasi sosial dan
kelembagaan. Selanjutnya menurut Cressey (1987) dan FAO (1991), bahwa komponen
penting dalam partisipasi meliputi: waktu dan tahapan, isi kegiatan dan konstruksi proses
termasuk didalamnya aktor yang terlibat.

17
Hamidjojo (1993) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat yang berintikan
gotong-royong yang diangkat dari tradisi khas bangsa Indonesia dengan diberi
persyaratan atau kualifikasi baru, yaitu rasionalitas, otoaktivitas (swadaya, individualitas
atau kepribadian yang otonom, masyarakat yang dewasa dan harus bisa menolong diri
sendiri. Keberhasilan partisipasi masyarakat haruslah didasari kewajaran, kesukarelaan,
sikap, dan prilaku aktif yang langgeng. Dalam partisipasi masyarakat terkandung dua
makna dwitunggal, yaitu bahwa swadaya dan gotong-royong, dan merupakan suatu
prinsif kerjasama dan bentuk kerja yang spontan, di antara warga desa dan antara warga
desa dan Kepala Desa beserta Pamong Desa, yang mengandung unsur: kekuatan atau
prakarsa sendiri, berupa pengarahan kemampuan pikiran, tenaga, sosial dan hartabenda
(daya), melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan lingkungan tetangga, masyarakat dan
pemerintah (rumah tangga) desa, dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan
rasa keterikatan timbal balik dalam meraih dan menikmati hasil karya.
Partisipasi diartikan mengambil bagian atau ikut serta menanggung bersama orang
lain. Jika dihubungkan dengan masalah sosial, maka arti pe rtisipasi adalah suatu keadaan
yang seseorang ikut merasakan sesuatu bersama-sama dengan orang lain sebagai akibat
adanya interaksi sosial (Fairchild, 1977). Hasil studi Uphoff dalam Cernea (1988)
terhadap tiga proyek pembangunan pedesaan di Gana, Meksiko, dan Nepal
menyimpulkan bahwa kegagalan suatu proyek disebabkan oleh ketergantungan yang luar
biasa pada perencanaan yang tersentralisasi, tidak mendorong partisipasi. Bahkan
sekalipun perencanaan mulai memperhatikan partisipasi, analisis lebih lanjut
menunjukkan bahwa organisasi sosial dalam partisipasi tergolong lemah atau malahan
tidak ada. Selanjutnya Uphoff (1988) lebih lanjut mendefinisikan lima cara untuk
menjamin partisipasi pemanfaat dalam rancangan proyek dan pelaksanaan. Pertama, taraf
partisipas i yang dikehendaki meski diperjelas sejak semula dan dengan cara yang dapat
diterima untuk semua pihak. Kedua, harus ada tujuan yang realistis untuk partisipasi dan
kelonggaran meski diberikan untuk kenyataan bahwa beberapa tahap perencanaan relatif
berlarut, sedangkan fase lainnya akan lebih singkat. Ketiga, dikebanyakan bagian dunia
perlengkapan khusus untuk memperkenalkan dan mendukung partisipasi memang
diperlukan. Keempat, meski ada komitmen rencana untuk bersama-sama memikul
tanggung jawab di semua tahap siklus proyek. Pada akhirnya disimpulkan bahwa tidak

18
semata dalam pembuatan keputusan proyek, tetapi juga menggali pengetahuan penduduk,
mencatat bidang keahlian lokal yang dapat memberikan kontribusi sesungguhnya bagi
rancangan proyek: mengumpulkan data sosial ekonomi, memantau dan mengevaluasi
proyek yang dikumpulkan oleh orang luar; memberikan pemahaman teknis; dan
memberikan kontribusi informasi ruang dan sejarah tentang proyek terdahulu yang
mungkin sejenis dan penyebab keberhasilan dan kegagalan.
Menurut Davis dalam Sastropoetro (1988), ada beberapa syarat agar terdapat
pertisipasi yang efektif, diantaranya adalah kemampuan. Seseorang dengan kemampuan
ekonomi yang tinggi mampu berpartisipasi dalam berbagai bentuk, misalnya tenaga,
uang, ide atau pemikiran dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasinya
juga lebih tinggi dibanding seseorang yang kemampuan ekonominya lebih rendah. Di
samping itu partisipasinya juga lebih bersifat "murni" tanpa pamrih, tanpa motif ekonomi.
Sebaliknya, seseorang yang kemampuan ekonominya rendah akan berpartisipasi atas
dasar pamrih, yakni untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ini bisa
terpenuhi dengan berpartisipasi sebagai tenaga kerja, untuk memperoleh upah. Sedangkan
menurut Arianta (1995) dalam penelitiannya mengenai partisipasi anggota lembaga
perkeriditan desa menemukan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor
penyebab utama partisipasi dari anggota lembaga tersebut. Anggota masyarakat
terdorong untuk berpartisipasi terhadap lembaga tersebut karena faktor ekonomi berupa
keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Menurut GTZ (1997), pendekatan partisipatif diperlukan untuk melibatkan semua
pihak sejak langkah awal, mulai tahapan analisis masalah, penetapan rencana kerja
sampai pelaksanaan dan evaluasinya. Kegiatan partisipatif dapat dikelompokkan pada
dua kelompok sasaran yaitu: partisipasi para pengambil keputusan, dan partisipasi
kelompok setempat yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
apabila berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan setiap masyarakat menjalankannya
secara obyektif tidak hanya mengutamakan kepentingan dirinya atau kelompoknya saja,
maka kerugian yang akan timbul tidak akan berarti dibandingkan manfaatnya (Suratmo,
1977). Selanjutnya menurut Suratmo (1999), manfaat partisipasi adalah:

19
a. Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, dan mengetahui
dampak yang akan terjadi, serta dapat menanggulangi.
b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai masalah lingkungan.
c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada
pemerintah.
d. Pemerintah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ada dalam Amdal.
e. Dapat dihindarinya kesalah pahaman dan terjadinya konflik.
f. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat proyek.
g. Meningkatnya perhatian dari pemerintah dan pemrakarsa proyek pada masyarakat.
Kerugian partisipasi masyarakat yang sering terjadi berdasarkan pengalaman di Amerika
Serikat menurut Canter (1977), adalah:
a. Informasi yang masuk dari masyarakat bermacam-macam bentuknya, mempersulit
untuk mengambil keputusan.
b. Informasi dan pendapat dari masyarakat yang tidak banyak tahu atau tidak memahami
mengenai proyek pembangunan, dampak dan pengelolaan lingkungan.
c. Masyarakat terkadang tidak berminat lagi dalam dengar pendapat, karena penjelasan
yang diberikan pada masyarakat sering terlalu teknis.
d. Penyimpulan pendapat masyarakat tidak selalu berpegang pada pendapat terbanyak
(mayoritas), tetapi berdasarkan pendapat-pendapat dan informasi yang logis dan dapat
diterima secara ilmiah oleh pemerintah.
e. Kalau ada perbedaan pendapat diantara kelompok masyarakat, maka rumusan atau
keputusan yang akan diambil menyebabkan selalu ada kelompok yang tidak puas.
f. Dimanipulasikan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok yang tidak baik.
Partisipasi ini dikatagorikan sebagai partisipasi langsung. Sebaliknya ada
partisipasi tidak langsung, yaitu apabila warga dikerahkan karena adanya gagasan dari
atas dimana warga dimobilisasi, dikerahkan secara paksa untuk aktif dalam kegiatan
lingkungan (Huntington and Nilson (1977). Menurut Adimihardja (2001), proses
partisipasi sesungguhnya adalah keterlibatan masyarakat secara menyeluruh mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, antara lain adalah:
a. Tahap perencanaan, dilakukan jika praktek pembangunan tidak berjalan sebagai
perencana untuk masyarakat, tetapi sebagai pendapat dalam proses perencanaan yang

20
dilakukan oleh masyarakat, dengan melakukan diskusi kelompok terarah untuk
membahas persoalan-persoalan yang terjadi diantara kelompok-kelompok atas
organisasi sosial masyarakat dan mempraktekan analisa pola keputuasan yang
dilakukan masyarakat dalam proses perencanaan.
b. Tahap pelaksanaan perencanaan partisipatif merupakan konsekwensi logis dari
implementasi pemberdayaan masyarakat, masyarakat mempunyai peran utama,
sebagai pengelola perencanaan mulai identifikasi potensi dan pendayagunaan sumber-
sumber lokal sehingga penyusunan usulan rencana serta evaluasi mekanisme
perencanaan. Tahap pengawasan dan evaluasi kegiatan pengawasan dan evaluasi
partisipatif, teknik dan prosedur, instrumentasi, pengumpulan, pengelolaan dan
analisis data, serta pelaporan harus diberikan kewenangan kepada masyarakat untuk
melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi internal, seperti Tabel 1.
Tabel 1. Evaluasi Partisipatif
Aspek Evaluasi Partisipatif
Siapa
Apa
Bagaimana
Kapan
Mengapa
Anggota masyarakat, staf proyek, fasilitator masyarakat mengidentifikasi sendiri indikator keberhasilan termasuk hasil produk yang akan dicapai.
Evaluasi sendiri, produk sederhana yang diadaptasi dengan budaya lokal, ada diskusi hasil dengan melibatkan partisipan dalam proses evaluasi.
Evaluasi sendiri, metode sederhana yang diadaptasi dengan budaya lokal, ada diskusi hasil yang melibatkan persyaratan dalam proses evaluasi.
Tergantung atas proses perkembangan masyarakat dan intensitas relatif sering.
Pemberdayaan masyarakat lokal untuk intensitas, mengontrol, melakukan tindakan koreksi.
Sumber: Narayama (1993).
Sedangkan Angell dalam Murray and Lappin (1967), menyatakan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam mengikuti kegiatan di
lingkungannya, antara lain: umur, pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan lama tinggal.
Individu yang berusia menengah keatas cendrung untuk aktif berpartisipasi dalam
kegiatan yang ada dilingkungannya. Individu yang mempunyai pekerjaan tetap cenderung
untuk berpartisipasi. Begitupula dengan penghasilan, makin tinggi penghasilan makin
banyak partisipasi yang dib erikan, sebab jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dirinya dan keluarganya cenderung untuk tidak berpartisipasi.

21
Inkeles (1969) menyatakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi
seseorang dalam mengikuti kegiatan di lingkungannya, antara lain: umur, penghasilan,
pekerjaan, pendidikan dan lama tinggal. Individu yang mempunyai tingkat pendidikan
dan penghasilan yang tinggi cenderung untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang
ada di lingkungannya. Ia juga mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
individu, semakin luas pengetahuannya dan kesadarannya terhadap lingkungan yang
akhirnya akan diikuti dengan keterlibatannya pada masalah-masalah kemasyarakatan.
Faktor lama tinggal juga merupakan salah satu faktor yang tidak kecil perannya dalam
mempengaruhi partisipasi seseorang dalam kegiatan yang ada di lingkungannya. Semakin
lama tinggal di suatu tempat, semakin besar rasa memiliki dan perasaan dirinya sebagai
bagian dari lingkungannya, sehingga timbul keinginan untuk selalu menjaga dan
memelihara lingkungan dimana dia menetap. Partisipasi dapat bersifat individual atau
kolektif, terorganisasi atau tidak terorganisasi yaitu secara spontan dan sukarela.
Pada hakekatnya, strategi dan pendekatan pembangunan manusia adalah
menumbuhkan otonomi perilaku pribadi dan sosial yang terintegrasi. Interaksi tersebut
merupakan kristalisasi dan faktor- faktor situasional dan beserta kognisi, keinginan, sikap,
motivasi dan responnya. Latar belakang sosial kultural, status sosial dan tingkat
kehidupan menentukan kesempatan dan kemampuan untuk turut berproses dalam
pembangunan. Faktor internal manusia dan lingkungan sosial, terutama lembaga sosial
untuk menumbuhkan self sustain capacity masyarakat, bekerjasama dengan lembaga
pemerintahan mempunyai makna penting dalam pembangunan sumberdaya manusia yang
berkelanjutan (Supriatna, 1997). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan
terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang
mendukungnya, yaitu: (1) adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi
lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi,
(2) adanya kemauan; adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan sikap
mereka untuk termotivasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas
partisipasinya tersebut, (3) adanya kemauan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada
dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, baik pikiran, tenaga,
waktu atau sarana dan material lainnya (Slamet, 1994).

22
Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan,
manusia yang paling berinteraksi atau dengan lainnya, seperti psikologis individu (needs,
harapan, motif, reward) pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi,
kelembagaan yang mendukung, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal serta
peraturan dan pelayanan pemerintah. Sedangkan menurut Oppenheim (1973) dalam
Sumardjo dan Saharudin (2003), ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu
pada diri seseorang dan terdapat iklim atau lingkungan yang memungkinkan terjadinya
perilaku tertentu.
Menurut Sahidu (1998) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan
masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif harapan, dan penguatan informasi. Faktor
yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan
pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan,
sarana dan prasarana. Faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman
yang dimiliki. Terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat
desa agar ikut serta dalam pembangunan, yaitu: (1) Learning process (learning by doing) :
Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas kegiatan pelaksanaan program dan sekaligus
mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat; (2). Institusional
development. Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada
dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya
tampung dan daya dukung sosial; (3) Participatory. merupakan suatu pendekatan yang
umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat (Marzali, 2003).
Menurut Hikmat (2001), pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang
sangat potensial dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial dan transformasi budaya,
proses ini pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada
rakyat. Secara sederhana partisipasi mengandung makna peran serta seseorang untuk
sekelompok orang atau sesuatu pihak dalam suatu kegiatan atau upaya mencapai sesuatu
secara sadar diinginkan oleh pihak yang berperan serta tersebut. Bila menyangkut
partisipasi dalam pembangunan masyarakat, maka menyangkut keterlibatan secara aktif
dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu
usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan
masyarakat (Sumardjo dan Saharudin (2003). Sedangkan menurut Bumberger dan Shams

23
(1989), terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi
merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari
masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumberdaya dan kapasitas yang
dimilikinya. Dalam proses ini tidak ada campur tangan dan prakarsa pemerintah. Kedua,
partisipasi harus mempertimbangkan adanya investasi dari pemerintah dan LSM, di
samping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang
lebih efisien, mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai,
jadi, masyarakat miskin tidak leluasa sebebas-bebasnya bergerak sendiri berpartisipasi
dalam pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan.
Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya
dapat dibedakan menjadi yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam
partisipasi masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil
keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota
masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu,
dimana keputusan terakhir tetap berada ditangan pejabat pembuat keputusan tersebut.
Dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat
keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar
kedudukkannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif
pemecahan masalah dan membahas keputusan. Kenyataan menunjukan bahwa masih
banyak yang memandang partisipasi masyarakat semata-mata hanya sebagai
penyampaian informasi, penyuluhan bahkan sekedar alat public relation agar proyek
tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karena nya partisipasi masyarakat tidak saja
digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan.
Partisipasi dalam pemanfaatan TPA berarti masyarakat ikut ambil bagian dalam
suatu kegiatan, hanya dapat dirasakan bila masyarakat berkepentingan dan diberi
kesempatan untuk ambil bagian. Partisipasi tidak mungkin optimal jika masyarakat yang
berkepentingan tidak diberi keleluasaan untuk ambil bagian. Pendekatan partisipatif
diperlukan untuk melibatkan semua pihak sejak langkah awal, mulai analisis masalah,
penetapan rencana kerja sampai pelaksanaan dan evaluasinya. Lebih lanjut disebutkan
bahwa seseorang akan berpartisipasi apabila terpenuhi prasyarat untuk berpartisipasi,
yaitu adanya: 1). kesempatan, suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang

24
tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi, 2). kemauan, sesuatu yang
mendorong atau menumbuhkan minat dan resiko, mereka untuk termotivasi
berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut,
dan 3). kemampuan, adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia
mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu atau
sarana dan material lainnya.
Dengan demikian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan
seseorang atau masyarakat untuk berperanserta melakukan kegiatan bersama-sama
dengan orang lain secara aktif dan sukarela dalam menentukan arah, strategi dan tujuan
pembangunan. 2.3. Pencemaran Lingkungan
Menurut Saeni (1989), pencemaran adalah peristiwa adanya penambahan
bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke dalam lingkungan yang
biasanya memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan itu. Zat pencemar adalah
zat yang mempunyai pengaruh menurunkan kualitas lingkungan, atau menurunkan nilai
lingkungan itu. Kontaminan adalah zat yang menyebabkan perubahan dari susunan
normal dari suatu lingkungan. Kontaminan tidak digolongkan sebagi zat pencemar bila
tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya menurut Saeni (1997),
salah satu jenis bahan pencemar yang dapat membahayakan kesehatan manusia adalah
logam berat. Zat yang bersifat racun dan yang sering mencemari lingkungan misalnya
merkuri (Hg), timbal (Pb), kadmium (Cd), dan tembaga (Cu). Perusakan lingkungan
hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi
lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (UU No.23 Tahun 1997).
Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 23 Tahun 1997, baku mutu lingkungan hidup
adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau
harus ada zat pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya
tertentu. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa setiap usaha kegiatan dilarang melanggar
baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Pencemaran lingkungan merupakan bermacam-macam mahluk hidup, bahan, zat-
zat pada suatu lingkungan, yang menyebabkan timbulnya pengaruh yang berbahaya

25
terhadap lingkungan, karena adanya perubahan yang bersifat fisik, kimiawi, maupun
biologis (Supardi, 1994). Pencemaran lingkungan mempunyai derajat pencemaran atau
tahap pencemaran yang berbeda, didasarkan pada konsentrasi zat pencemar, waktu
tercemarnya, lamanya kontak antara bahan pencemaran dengan lingkungan.
Menurut Tchobanoglous, et.al (1977), perolehan gas nitrogen (N2), karbon
dioksida (CO2) dan metana (CH4), pada landfill tergantung banyaknya komponen
organik pada landfill, hara yang tersedia, kadar air pada sampah, tingkat kepadatan
sampah pada kondisi awal, waktu penimbunan dan lain- lain. Secara umum perolehan gas
N2, CO2, CH4 pada landfill dapat dihitung dengan melakukan perkalian antara volume
sampah pada landfill dengan nilai persen masing-masing gas, menurut jangka waktu
penimbunan sampah.
Sampah merupakan sumber beberapa jenis penyakit menular, keracunan dan lain-
lain (Slamet, 1994). Bahan beracun, bakteri, virus, jamur dan lain- lain yang ada dalam
timbunan sampah, dapat berpindah tempat ke tempat lain melalui proses lindi. Apabila
cairan dari sampah yang mengandung bibit penyakit masuk kedalam air permukaan,
maka air permukaan tersebut akan berperan sebagai penyebar mikroba patogen atau
penyakit menular di dalam air.
Ada empat hal penyebab pencemaran air tanah yaitu:
a. Bila jarak antara sumur dan jamban kurang dari 10 m untuk tanah biasa dan paling
dekat 15 m untuk tanah porus atau gembur.
b. Lokasi sumur tersebut sebelumnya merupakan lokasi sumber limbah rumahtangga
atau dekat industri atau bekas lokasi sampah (TPA).
c. Merembesnya air permukaan yang telah tercemar, WC dan air cucian ke dalam sumur.
d. Masuknya debu yang sudah tercemar ke dalam sumur terbuka.
Dari keempat sumber pencemaran air tanah yang berasal dari TPA merupakan
rembesan dari timbunan limbah di TPA sampah, dan merupakan sumber kontaminan
potensial bagi air permukaan, air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Selanjutnya
Eugene (1987) mengemukakan bahwa lindi akan mencemari tanah, air tanah dan sungai.
Jadi tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh lindi tergantung dari sifat lindi, jarak
aliran dengan air tanah dan sifat-sifat tanah yang dilaluinya. Oleh sebab itu untuk

26
menghindari pencemaran oleh lindi, sumber air sumur dangkal yang umumnya masih
digunakan oleh penduduk sebagai air minum harus terletak jauh dari sanitary landfill.
Pencemaran air dapat mengganggu tujuan penggunaan air dan akan menyebabkan
bahaya bagi manus ia melalui keracunan atau sumber dan penyebab penyakit. Daerah
perkotaan dengan tingkat aktivitas masyarakat dan industri yang demikian tinggi secara
bersamaan akan menghasilkan sampah sehingga membutuhkan tempat pembungan akhir
sampah kota yang perlu dikelola dengan baik agar dampak pencemarannya tidak
mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Nitrat dalam hal ini merupakan pencemar utama
yang dapat mencapai air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang diakibatkan oleh
aktivitas manusia termasuk dari penempatan sampah, Vasu at.al. (1998). Di samping itu
pergerakan air sangat mudah dipengaruhi oleh pengambilan air atau pemompaan air tanah
dangkal melalui sumur-sumur bor yang umumnya disiapkan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhannya.
Secara umum sumber pencemaran air tanah berasal dari tempat-tempat
pembuangan sampah, mudah meresap ke dalam tanah, sehingga sampah organik
merupakan sumber primer pencemaran bakteriologik (Bitton, 1984 dalam Wuryadi,
1990). Menurut Bouwer (1987) menambahkan, jarak aman dari bidang resapan adalah
30 meter untuk daerah di atas muka air tanah, dan 60 meter di bawah muka air tanah.
Bakteri patogen yang biasanya disebarkan melalui air adalah bakteri amuba
disentri, kolera dan tipus. Jumlah bakteri patogen dalam air umumnya sedikit
dibandingkan dengan bakteri coli (coliform), sehingga bakteri ini dipakai sebagai bakteri
indikator terhadap kualitas perairan karena jumlahnya banyak dan mudah diukur (Diana,
1992). Jenis bakteri coliform sebagai indikator adalah Escherichia coli dan Aerobacter
coli. Dari kedua jenis tersebut, yang lebih umum dan lebih banyak terdapat di perairan
atau tanah adalah jenis E. coli, yaitu sebagai indikator pencemar fecal (tinja), dihitung
berdasarkan MPN (most probabel number) (Saeni, 1991).
2.4. Pengertian-pengertian
A. Pengertian Sampah
Pengertian sampah dapat lebih jelas diketahui dengan mempelajari beberapa
pengertian. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan
limbah padat. Sedangkan limbah itu sendiri pada dasarnya adalah suatu bahan yang

27
terbuang atau dibuang dari suatu hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan
tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi
yang negatif. Sampah mempunyai nilai negatif karena penanganan untuk membuang atau
membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, disamping juga dapat mencemari
lingkungan (Sa’id, 1998).
Sampah (solid waste) adalah semua jenis bahan padat yang dibuang sebagai bahan
buangan, tidak bermanfaat atau barang-barang yang dibuang karena kelebihan
(Tchobanoglous et al., 1977). Pavoni menyatakan bahwa, sampah adalah semua bahan
buangan yang umumnya dalam bentuk padat, berasal dari manusia dan binatang yang
dibuang sebagai barang yang tidak berguna atau tidak dibutuhkan lagi. Sampah
merupakan segala bentuk buangan padat yang sebagian besar berasal dari aktivitas
manusia (domestik). menurut Hadiwijoto (1983), sampah domestik lebih banyak
didominasi oleh bahan organik, meskipun tipe dan komponennya berpartisipasi dari satu
kota ke kota lainnya, bahkan dari hari-kehari.
B. Sumber dan Jenis Sampah
Menurut Sa’id (1987) penggolongan atau pembagian sampah dapat dilakukan
berbagai cara, tergantung kebijakan negara setempat, dua cara pembagian yang sering
digunakan, berdasarkan teknis dan berdasarkan sumbernya sebagai berikut:
a. Berdasarkan teknis, sampah dibagi atas:
1). Sampah bersifat semi basah, golongan bahan organik, misalnya sampah dapur,
sampah restoran berupa sisa buangan sayuran dan buah-buahan, mudah terurai,
karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang rendah.
2). Sampah anorganik sukar terurai karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang
panjang, misalnya kaca, plastik dan selulosa.
3). Sampah berupa abu hasil pembakaran, secara kuantitatif sampah jenis ini sedikit,
tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup besar.
4). Sampah berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, ayam, ikan dan
burung.
5). Sampah jalanan, semua sampah yang dikumpulkan di jalan-jalan, misalnya daun-
daunan, kantong plastik, kertas dan lain- lain.

28
6). Sampah industri, dari kegiatan produksi, secara kuantitatif limbah ini banyak,
tetapi ragamnya tergantung jenis industri tersebut.
b. Berdasarkan sumbernya, sampah digolongkan dalam:
1). Sampah domestik (domestic waste).
Berasal dari lingkungan perumahan, baik di perkotaan maupun pedesaan, ragam
sampah perkotaan lebih banyak, serta jenis sampah organiknya secara kuantitatif
dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pedesaan umumnya bahan-bahan organik
sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.
2). Sampah komersial (commercial waste)
Tidak berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi, tetapi lebih merujuk
kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial dari kegiatan
perdagangan, seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan.
Tabel 2: Sumber dan Jenis Sampah Sumber Jenis, Fasilitas, Aktivitas, Lokasi
Timbulnya Sampah Jenis Sampah
Perumahan Komersial Fasilitas kesehatan Perkotaan Industri Lapangan terbuka Industri pengolahan Pertanian
Rumah tinggal, apartemen atau rumah susun. Toko, restoran, pasar, bangunan kantor, hotel, percetakan, toko onderdil, perusahaan. Rumah sakit, puskesmas, poliklinik, apotik. Rumah sakit, puskesmas, poliklenik, apotik. Bangunan, pabrik, penyulingan, instalasi, kimia, pertambangan, pembangkit tenaga. Jalan, taman, tanah kosong, lapangan bermain, pantai, jalan tol, tempat rekriasi. PDAM, IPAL, proses pengolahan industri. Hasil semua atau ladang, kebun, peternakan.
Sisa makan, rubbish, abu, sampah khusus. Sisa makan, rubbish, abu, sisa bangunan, sampah khusus. Sisa makan, rubbish, sampah khusus. Sisa makan, rubbish, sampah khusus. Sisa makanan, rubbish , sisa atau bekas buangan, sampah khusus, sampah berbahaya. Sampah khusus rubbish. Sampah dan instalasi lumpur residu. Sisa makanan membusuk, sampah perkotaan, rubbish , sampah berbahaya.
Sumber: Tehobauoglous (1997).
Pengertian sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan adalah benda yang
dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sehingga
tidak mengganggu kelangsungan hidup (Azwar, 1983). Sampah digolongkan dalam ilmu
kesehatan lingkungan adalah:

29
a. Garbage, sisa pengolahan makanan yang mudah membusuk, misalnya koto ran dapur
rumah tangga, restoran, hotel dan lain- lain.
b. Rubbish, bahan atau sisa pengelolaan yang tidak mudah membusuk (mudah terbakar:
kayu, kertas, dan yang tidak mudah terbakar: kaleng dan kaca).
c. Ashes, ialah segala jenis abu hasil pembakaran kayu, batubara.
d. Segala jenis bangkai yang besar seperti kuda, sapi, kucing, tikus.
Street sweeping, ialah segala benda padat sisa sampah hasil industri, misal industri
kaleng dengan potongan-potongan sisa kaleng.
Menurut Sumirat (1994), jenis sampah dibagi atas dasar sifat-sifat biologi dan
kimianya, yaitu:
a. Sampah yang membusuk (garbage), yang mudah membusuk karena aktivitas
mikroorganisme.
b. Sampah yang tidak membusuk (refure), jenis ini terdiri dari kertas-kertas, logam,
karet, plastik dan lainnya yang tidak dapat membusuk.
c. Sampah yang berbentuk debu atau abu hasil dari pembakaran, baik pembakaran bahan
bakar, sampah jenis ini tidak membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan untuk
mendapatkan tanah atau penimbunan.
d. Sampah berbahaya, adalah sampah karena jumlah, konsentrasi atau sifat kimiawi,
fisika dan mikrobiologinya dapat menimbulkan bahaya.
Jadi pada dasarnya sumber sampah dapat diklarifikasi beberapa kategori yang
berhubungan dengan tata guna tanah: permukiman penduduk, tempat-tempat umum,
tempat pardagangan, sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah maupun swasta,
daerah industri, pertanian dan rumah sakit.
C. Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah bertujuan mengubah sampah menjadi bentuk yang tidak
mengganggu dan menekan volume, sehingga mudah diatur. Cara pengelolaan sampah
yang dianggap terbaik saat ini adalah penimbunan dan pemadatan secara berlapis- lapis
(sanitary landfills), sampah tidak terbuka selama 24 jam karena apabila air hujan yang
terserap ke lapisan tanah dan melalui lapisan sampah akan membentuk cairan lindi, yang
mengandung padatan terlarut dan zat- zat lain hasil perombakan bahan organik oleh
mikroba. Lindi tersebut dapat mengalir bersama air hujan atau air permukaan dan

30
meresap kedalam lapisan- lapisan tanah dan masuk ke dalam air tanah (Clark, 1977).
Hasil analisis lindi oleh Department of Public Health, USA (1972) terdapat pada Tabel 3.
Pada Tabel 3 dijelaskan semakin lama umur lindi, konsentrasi zat pencemar
semakin berkurang, karena zat-zat tersebut telah mengalami penguraian oleh tanah. Ion
klorida (Cl̄ ) sebagai ion anorganik sulit teruraikan, baik melalui pertukaran ion, adsorbsi,
filtrasi, dan biodegradasi. Dalam hal ini ion Cl̄ dapat dipakai sebagai indikator terhadap
aliran lindi, secara tidak langsung dapat menimbulkan pencemaran terhadap air tanah,
khususnya air sumur gali (Slamet, 1994).
Tabel 3. Hasil Analisis Lindi Sistem Sanitary Landfill (ppm) Umur Lindi Parameter Satuan 2 Tahun 6 Tahun 17 Tahun
BOD5 COD Jumlah Padatan Klorida (C1¯) Natrium (Na?) Besi (Fe) Sulfat (SO4²¯) Kesadahan Logam-logam berat
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
39 68.0 54 610.0 9 144.0 1 697.0
900.0 5 500.0
680.0 7830.0
15.8
8 000.0 14 080.0 6 795.0 1 330.0
810.0 6.3 2.0
2 200.0 1.5
40.0 225.0
1 198.0 135.0 74.0 0.6 2.0
540.0 5.4
Sumber: Department of Public Health USA (1972).
Tinggi rendahnya curah hujan, jarak aliran dengan air tanah, dan sifat-sifat tanah
yang dilalui akan mempengaruhi sifat lindi, dan sifat lindi akan mempengaruhi tingkat
pencemaran yang ditimbulkannya, sedangkan komposisi lindi dipengaruhi oleh asal dan
umurnya. Dengan demikian, untuk menghindari kontaminasi terhadap lingkungan, lindi
yang terjadi harus aman dari pencemaran sebelum disalurkan ke saluran pembuangan.
Menurut Suratmo (2002), pengelolaan sampah di TPA terdiri dari open dumping,
landfill, insinerator, pembuatan kompos dan teknologi baru (reduce, recycle dan reuse).
Sedangkan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah harus diperhatikan
ketersediaan tempat sampah di rumah, ketersediaan TPS, ketaatan membayar iuran dan
ketaatan membuang sampah di tempat yang telah ditentukan.

31
Gambar 2: Diagram Kerangka Dasar Pemikiran Pengelolaan Sampah
Menurut Sa’id (1988), pengelolaan sampah adalah perlakuan atau tindakan yang
dilakukan terhadap sampah yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan
dan pengolahan serta pemusnahan. Sedangkan menurut Soewedo (1983), pengelolaan
sampah adalah perlakuan terhadap sampah guna menghilangkan masalah yang berkaitan
dengan lingkungan.
Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan
dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan
pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan cara yang sesuai dengan
prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam,
keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap
masyarakat. Pengelolaan sampah adalah suatu proses mulai dari sumber sampai dengan
di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan, mengganggu kelestarian dan sumberdaya alam.
Secara umum syarat pokok pengelolaan sampah, yaitu: penyimpanan atau
pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan dan pembuangan akhir. Dari
beberapa syarat pokok tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan dan
pembuangan akhir sampah. Pengolahan sampah merupakan proses antara sebelum
dilakukan pembuangan sampah di TPA yang bersifat optimal. Teknik dan cara
pengolahan sampah dapat dilakukan dengan metode daur ulang, biologis (pembuatan
kompos), pemadatan dan insinerator.
UU & PERDA
Penyuluhan
Dinas Kebersihan (Petugas Kebersihan)
Sarana & Prasarana Angkutan
Penghasil Sampah (masyarakat)
Pengumpul Sampah
Sampah Terkumpul
Disiplin
Pengetahuan
Kesadaran
Prilaku atau Kebiasaan
Membuang Sampah
Sampah Terangkut
Lingkungan Bersih Sehat dan Nyaman

32
Azwar (1983) menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat tiga
aktivitas meliputi:
a. Penyimpanan atau pengumpulan
Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar hasil pengumpulan sampah tidak terjadi
perubahan yang dikehendaki, seperti pembusukan, atau kadar air yang meningkat.
Penyimpanan ini dilakukan pada tempat pengumpulan sementara sebelum sampah
diangkut, dibuang, dimanfaatkan serta dimusnahkan. Tempat-tempat ini sering
dijumpai di toko-toko, warung, hotel, restoran, kantor dan rumah.
b. Pengangkutan
Pengangkutan sampah dari pemukiman penduduk yang terletak di pinggir jalan raya
diangkut dengan gerobak. Dari hasil pengumpulan dari rumah ke rumah dipindahkan
ke tempat pembuangan sementara (TPS), selanjutnya diangkut dengan truk ke tempat
pembuangan akhir (TPA) sampah.
c. Pemusnahan.
Menurut Partoatmodjo (1993), menyatakan pemusnahan dan pemanfaatan tersebut
sebagai berikut:
1) Sanitary landfill, membuang dalam lembah dan ditutup dengan selapis tanah,
yang dilakukan lapis demi lapis, sehingga sampah tidak berada di alam secara
terbuka.
2) Landfill, sampah dibuang dalam lembah tanpa ditimbun oleh lapisan tanah.
3) Open Dumping, membuang sampah di atas permukaan tanah.
4) Dumping in water, membuang sampah di perairan misalnya di sungai atau di laut.
5) Insinerasi, pembakaran sampah secara besar-besaran dan tertutup dengan
menggunakan insenerator.
6) Individual insenerator, pembakaran sampah dengan insenerator yang dilakukan
oleh perorangan dalam rumahtangga.
7) Hog feeding, sampah sayuran dijadikan untuk pakan babi.
8) Composting, pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, yang bermanfaat
untuk menyuburkan tanah.
9) Discharge to sewers, sampah dihaluskan kemudian dibuang ke dalam saluran
air.

33
10) Pendaur ulangan sampah dengan cara memanfaatkan kembali barang- barang
yang masih bisa dipakai.
11) Reduksi, menghancurkan sampah menjadi bagian kecil-kecil dan hasilnya
dimanfaatkan.
Pembuangan akhir sampah adalah upaya untuk memusnahkan sampah di tempat
tertentu yang disebut tempat pembuangan akhir sampah (TPA), dan dalam pembuangan
akhir ada beberapa metode yaitu:
a. Open Dumping
Metode open dumping adalah cara pembuangan akhir dengan hanya menumpuk
sampah begitu saja tanpa ada perlakuan khusus, sehingga dapat menimbulkan
gangguan terhadap lingkungan.
b. Controlled Landfill
Adalah sistem open dumping yang diperbaiki atau ditingkatkan, merupakan peralihan
antara teknik open dumping dan sanitary landfill. Pada cara ini penutupan sampah
dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbunan sampah yang
dipadatkan setelah mencapai tahap tertentu.
c. Sanitary Landfill
Pada sistem ini sampah ditimbun dalam tanah yang luas kemudian dipadatkan dan
ditutup dengan tanah penutup harian pada setiap hari dan akhir operasi (Suryanto,
1988).
Menurut Sumitro et al., (1991) dalam usaha penanggulangan masalah sampah
melalui pemanfaatan sampah tersebut, perlu diperhatikan kandungan zat kimia, seperti
keberadaan karbon dan kobalt yang dapat menimbulkan gangguan pada tanaman. Hal ini
dapat berkembang menjadi masalah yang serius, karena selain dapat merusak hasil
tanaman, misalnya meracuni tanaman tomat, unsur-unsur tersebut juga berbahaya bagi
manusia yang mengkonsumsi produk pertanian tersebut. Resiko yang tidak dapat
dihindarkan dari pembuangan sampah di landfill adalah terbentuknya gas dan lindi yang
dipengaruhi oleh dekomposisi dari mikroba dan iklim, sifat dari sampah dan iklim
pengoperasian sampah di landfill. Perpindahan gas dan lindi dari lendfill ke lingkungan
sekitarnya menyebabkan dampak yang serius pada lingkungan, selain berdampak buruk
terhadap kesehatan juga menyebabkan kebakaran dan peledakan, kerusakan pada

34
tanaman, bau yang tidak sedap, masalah setelah penutupan landfill, pencemaran air tanah,
udara dan pencemaran global, El-fadil (1997).
Menurut El- fadil et al., (1997), dan Samom et al., (2002) hendaknya TPA
dioperasikan dengan sistem sanitary landfill yang dilengkapi dengan pemasangan
instalasi recovery gas, sistem pengolahan dan pengumpulan gas yang mencegah
pemindahan gas dari TPA atau emisi gas melalui permukaan landfill, penghalang hid rolik
seperti ekstraksi dan sumur pantauan, sumur relief dan parit perlindungan dan sistim
pengumpulan untuk masalah pengontrolan lindi. Selain itu untuk meminimisasi dampak
lingkungan jika mungkin diusulkan kepada pemerintah untuk mengadopsi sistem
pengubahan sampah menjadi energi karena tidak mungkin hanya dengan sanitary landfill
dapat menghilangkan semua pengaruh negatif sampah dan lingkungan.
D. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Pada era saat ini tempat pembuangan sampah akhir yang umum dipergunakan di
beberapa negara adalah dengan tanah urugan atau dikenal dengan landfill yang berfungsi
sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Menurut Tchobanoglous 1999, TPA adalah
suatu fasilitas fisik yang digunakan untuk pembuangan sisa limbah padat atau sampah
diatas permukaan tanah dari bumi. Akan tetapi saat ini istilah TPA mengacu pada
rekayasa fasilitas untuk pemusnahan limbah padat kota yang dirancang dan dioperasikan
untuk meminimumkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikenal dengan sanitary landfill adalah
sistem pembuangan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutupi serta dilapisi tanah
setiap hari. Di dalam sistem TPA akan terjadi proses dekomposisi sampah secara kimia,
biologi, dan fisik yang menghasilkan gas-gas dan bahan organik lainnya. Air hujan yang
jatuh pada lokasi TPA akan berinfiltrasi ke dalam sistem sampah dan melarutkan hasil
dekomposisi ini berupa cairan yang disebut air lindi, komposisi air lindi bervariasi antara
satu lokasi dengan lokasi lainnya, Widyatmoko dan Sintorini (2002).
Menurut Novotny dan Olem (1994) saat ini Tempat Pembuangan Akhir termasuk
sumber pencemaran air tanah utama di dunia setelah tanki septik dengan perhitungan saat
itu di Amerika Serikat hanya 6 % dari seluruh sanitary landfill yang tidak menyebabkan
masalah lingkungan dan beroperasi secara baik. Hal ini didukung oleh Freeze and Cherry
(1979) yang menyatakan bahwa kontaminasi air tanah oleh bahan organik yang dapat

35
bergerak akan menjadi masalah yang sangat serius. TPA Bantar Gebang, pada prinsipnya
merupakana suatu landfill yang dirancang dan dikonstruksikan secara modern,
pengumpulan lindi dan pengolahannya pada 4 kolam aerasi. E. Lindi
Masalah yang timbul dalam pengurugan atau penimbunan sampah ke dalam tanah
adalah kemungkinan pencemaran sumber air oleh lindi. Tchobanoglous (1977)
menyatakan lindi merupakan limbah cair atau cairan yang melalui timbunan sampah yang
mengekstrak bahan yang terlarut atau tersuspensi di dalamnya. Cairan tersebut berasal
dari dekomposisi sampah dan dapat juga berasal dari sumber luar, seperti aliran air
permukaan, air hujan, air tanah dan air yang berasal dari mata air bawah tanah.
Pengertian lain lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke
dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas zat-zat terlarut, termasuk juga zat
organik hasil proses dekomposisi biologis (Damanhuri, 1995). Jadi dapat disimpulkan
bahwa lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan
sampah, melarutkan dan membilas zat- zat terlarut. Cairan tersebut mengandung bahan
organik yang tinggi sebagai hasil dekomposisi sampah dan juga berasal dari proses
infiltrasi dari air limpasan.
Air lindi merupakan bahan cair yang timbul pada bagian bawah sanitary landfill,
yang jumlahnya tergantung pada berbagai faktor seperti: curah hujan, kemiringan dan
jenis lapisan tanah penutup, kepadatan sampah, kelembaban sampah dan kondisi
lingkungan sanitary landfill. Debit air lindi berhubungan positif dengan besarnya curah
hujan, air lindi yang akan timbul diperkirakan sebesar 50 persen, pada proses
penimbunan dan 20 persen setelah penimbunan. Fasilitas air lindi diharapkan dapat
menampung jumlah air lindi pada bulan-bulan basah, yakni bulan Januari dan Februari
(Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2002). Menurut Chen (1975), komposisi lindi bervariasi
karena proses pembentukan lindi dipengaruhi oleh macam buangan (zat organik atau
anorganik), mudah tidaknya peruraian (larut atau tidak larut), kondisi landfill (suhu, pH,
potensial redoks, kelembaban, umur); karakteristik sumber air (kuantitas dan kualitas);
komposisi tanah penutup.

36
Pengaruh sanitary landfill adalah pencemaran air tanah dan air permukaan, terjadi
bila sanitary landfill berdampingan dengan badan air, jika air hujan jatuh di atas
permukaan landfill, meresap dan turun melalui lapisan kedap air ke badan air yang lebih
rendah. Pembentukan lindi akibat air hujan tidak dapat dihindari pada awal pengisian
sampah. Setelah lindi melalui tanah pada kedalaman beberapa meter kontaminasi
bakteriologis tidak ditemui lagi. Suspensi yang terdapat di dalam lindi dapat terbawa
sampai ke dalam tanah yang lebih jauh, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah
(Thank, 1985).
Air lindi akibat proses degradasi sampah dari TPA merupakan sumber utama yang
mempengaruhi perubahan sifat fisik air, suhu air, rasa, bau dan kekeruhan. Suhu limbah
yang berasal dari lindi umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan air penerima. Hal ini
dapat mempercepat reaksi kimia dalam air, mengurangi kelarutan gas dalam air,
mempercepat pengaruh rasa dan bau (Husin dan Kustaman, 1992). Sedangkan Menurut
Schmeider (1970), untuk menghindari pencemaran oleh lindi, maka tempat pembuangan
akhir sampah, harus terletak jauh dari kantong air dan memiliki lapisan kedap air,
sekurang-kurangnya 3 meter di atas permukaan air tanah tertinggi. Selanjutnya
Environmental Protection Agency (1977), menyarankan lokasi pengelolaan sampah harus
menjauhi jaringan drainase, terletak di garis pantai terluar (batas pasang 10 tahun) dan
jauh dari badan air, minimal 300 meter dari air permukaan.
Permasalahan TPA yang memerlukan penanganan khusus dari operasi sistem
TPA ini adalah mengusahakan agar air lindi tidak meresap ke dalam sistem air tanah
dangkal supaya tidak mencemari lingkungan. Pada prinsipnya pada TPA telah disiapkan
unit pengolah air lindi yang dikumpulkan sebelum dibuang ke sistem air permukaan.
Pada kondisi normal air lindi ditemukan pada dasar TPA dan bergerak melewati lapisan
dasar yang juga tergantung pada sifat-sifat bahan sekitarnya. Pengelolaan lindi dapat
dilakukan dalam beberapa metode secara umum yaitu: pengurangan secara alami oleh
tanah, menghambat pembentukan lindi, pengumpulan dan pengolahan, perlakuan
pendahuluan untuk mengurangi volume dan kelarutan, dan detoksifikasi limbah
berbahaya sebelum dibuang ke saluran.