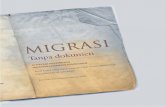Paper Migrasi Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia
description
Transcript of Paper Migrasi Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia

Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia?
Indonesia terhadap pekerja migran pada prinsipnya sejalan dengan kerangka HAM. Kebebasan setiap orang memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E Ayat 1, UUD 1945 Amandemen); dan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Amandemen), merupakan alasan seseorang memutuskan menjadi pekerja migran. Secara bersamaan, perlindungan pekerja migran Indonesia (atau yang disebut Tenaga Kerja Indonesia/ TKI) menjadi kewajiban negara. Ironisnya, dalam konteks Indonesia, perlindungan pekerja migran masih merupakan tanda tanya besar.
Berbagai data menunjukkan peningkatan jumlah berbanding terbalik dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Berbagai studi menyebutkan push and pull factors dari migrasi, termasuk faktor kemiskinan yang berkorelasi dengan migrasi. Kemiskinan, atau menurut sebagian kalangan, lebih tepat disebut pemiskinan sebagai dampak pembangunan yang tidak berkeadilan, selalu menjadi faktor utama seseorang bermigrasi. Tidak salah jika model migrasi seperti ini dikategorikan sebagai forced migration, migrasi yang dilakukan secara terpaksa (Hidayah, 2010). Menjadi pekerja migran adalah strategi terakhir untuk mempertahankan hidup.
Berbagai data menunjukkan peningkatan jumlah berbanding terbalik dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Berbagai studi menyebutkan push and pull factors dari migrasi, termasuk faktor kemiskinan yang berkorelasi dengan migrasi. Kemiskinan, atau menurut sebagian kalangan, lebih tepat disebut pemiskinan sebagai dampak pembangunan yang tidak berkeadilan, selalu menjadi faktor utama seseorang bermigrasi. Tidak salah jika model migrasi seperti ini dikategorikan sebagai forced migration, migrasi yang dilakukan secara terpaksa (Hidayah, 2010). Menjadi pekerja migran adalah strategi terakhir untuk mempertahankan hidup.
Dari besaran pekerja migran, penting pula dicermati bahwa tingginya jumlah perempuan pekerja migran, sejalan dengan menguatnya feminisasi kemiskinan dan migrasi khususnya negara-negara berkembang. Feminisasi migrasi didorong oleh terbatasnya akses yang dimiliki perempuan terhadap kesempatan kerja di negara asal, akibat keterbatasan pendidikan yang diterima, selain juga akibat stereotip sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan domestik keluarga.
Diperkirakan pekerja migran Indonesia di luar negeri berjumlah lebih dari 6 juta jiwa. Sebagian besar mereka atau sekitar 79% adalah perempuan yang mayoritas bekerja di sektor domestik atau pekerja rumah tangga (PRT) migran. Ada tiga hal yang menggambarkan kondisi dan situasi kerja PRT migran saat ini, yaitu dark, dirty, and dangerous. Secara khusus, persoalan seksualitas dan reproduksi sangat lekat dengan berbagai pengalaman buruk PRT migran Indonesia. Situasi PRT migran berada dalam area “privat” yang bersifat “hidden”, sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran
Studi juga menunjukkan fenomena pekerja migran Indonesia yang dideportasi karena mereka tidak berdokumen. Sebagian besar mereka adalah perempuan, yang menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi dimulai dari tempat mereka bekerja hingga kepulangan. Saat pemulangan misalnya, keberadaan Terminal TKI adalah praktik terlembaga dan sistematis dalam bentuk pemerasan, diskriminasi, pungutan liar, dan praktik-praktik lainnya yang merugikan pekerja migran Indonesia. Namun nyatanya hak yang seharusnya mereka dapatkan kenyataannya malah terjadi pelanggaran disana-sini seperti Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan, pelanggaran yangsering terjadi migrant tidak boleh mengambil cuti, gaji tidak dibayar, terjerat hutang dan pekerja bekerja melebihi masa kontrak; Hak atas kesehatan Reproduksi pelanggaran yang sering terjadi adalah pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi; Hak atas hidup Kemerdekaan Kesehatan Integritas diri, dan bebas dari kekerasan; Berikut hak para migrant yang sering di langgar;

Kategori hak yang di lindungi Pelanggaran yang mungkin terjadiHak atas Pekerjaan dan SumberPenghidupan
Terjerat hutang; Mengalami penipuan, tidak jadi berangkat ke
negara tujuan; Menunggu keberangkatan terlalu lama; Diselundupkan tanpa dokumen yang sah; Dipalsukan identitas diri untuk kepentingan
kerja; Gaji tidak dibayar; Gaji dibayar setengah/tidak sesuai perjanjian;
Pemotongan gaji di luar prosedur; Over charging; Bekerja melebihi masa kontrak; Tempat bekerja tidak seperti dalam perjanjian; Bekerja melebihi jam kerja; Pelarangan berkumpul dan mendirikan serikat
pekerja; Penolakan untuk ijin cuti, istirahat mingguan
pembayaran biaya lembur; Kondisi kerja yang tidak layak, buruk, atau
berbahaya; Tidak ada upaya hukum terhadap pelanggaran
hak pekerja; Pemberian paspor, visa, dan dokumen lain yang
bukan merupakan dokumen untuk menjadi pekerja migrant;
Paspor dan dokumen lain dihilangkan/ diambil/dipegang pihak lain;
Pembatasan kebebasan untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain
Hak atas Kesehatan Reproduksi Pemeriksaan kesehatan tanpa izin yang bersangkutan;
Pemaksaan penggunaan kontrasepsi; Pemaksaan aborsi; Dipaksa bekerja dalam keadaan sakit; Tidak mendapatkan layanan kesehatan ketika
sakit; Tidak ada jaminan keselamatan kerja
Hak atas Hidup, Kemerdekaan, Kesetaraan, Integritas Diri, dan Bebas dari Kekerasan
Dijual ke perusahaan penyalur tenaga kerja yang lain
Perkosaan Pelecehan seksual Penyiksaan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi,
dan merendahkan martabat Pembunuhan Perbudakan/tindakan setara perbudakan Penyekapan Perdagangan perempuan Dijual/dipekerjakan ke beberapa majikan Mendapat ancaman/intimidasi
Hak atas Kesetaraan di depan Hukum Penolakan atas asas praduga tak bersalah Tidak mendapat waktu dan fasilitas yang
memadai selama proses peradilan dan di penjara
Peradilan yang tidak bebas dan berpihak Penangkapan dan penahanan yang sewenang-
wenang Tidak memperoleh pengadilan yang
secepatnya

Tidak mendapat akses ke pengadilan Tidak mendapat bantuan pembela Pelanggaran hak-hak narapidana
Hak atas Standar Hidup dan Jaminan Sosial Asuransi tidak dibayarkan, tidak bisa diklaim
Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan Tindakan yang melanggar hak-hak atas
makanan yang sehat Pembatasan akses terhadap lingkungan yang
sehatHak Sipil Politik Keluarga tidak mendapat informasi memadai
tentang keberadaan perempuan pekerja migran Larangan berkomunikasi dengan
keluarga/teman Hilang kontak Pembatasan terhadap akses mendapatkan
informasi Pembatasan/larangan hak untuk berkumpul, berserikat, atau berorganisasi
Larangan/pembatasan untuk mengenakan pakaian tertentu
Larangan/pembatasan hak untuk kembali/pulang ke tempat/negara asal
Deportasi Larangan beribadah
Hak atas Budaya Pembatasan penggunaan bahasa tertentu Pembatasan praktik budaya tertentu
Sumber: Komnas Perempuan dan Komnas HAM, 2009
Terdapat beberapa permasalahan seputar perlindungan pekerja migran Indonesia. Pertama, di tingkat peraturan perundang- undangan mengenai pekerja migran, pada tahun 2004, Indonesia memberlakukan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Ironisnya, UU yang sempat menjadi tumpuan harapan adanya perlindunganbagipekerjamigran ini justru meninggalkan banyak celah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran, karena tidak banyak menyentuh agenda “perlindungan” ketimbang aspek “penempatan” dan komoditisasi pekerja migran. UU ini juga cenderung menegasikan keberadaan pekerja migran tidak berdokumen, padahal pada kenyataannya jumlah pekerja migran tidak berdokumen diperkirakan jauh lebih banyak daripada pekerja migran berdokumen.
Sejak diundangkan, UU ini banyak menuai protes dari berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Pada 27 Februari 2006, Presiden telah menginstruksikan agar UU ini diamandemen. Namun, ironisnya, instruksi tersebut tidak mengarah kepada perbaikan perlindungan, namun agar migrasi tenaga kerja ke luar negeri dipermudah. Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 mengenai paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Dalam Bab IV huruf b, Presiden memandatkan Menakertras untuk mengajukan draft revisi UU PPTKILN kepada DPR, dengan menghapus persyaratan bahwa Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib memiliki unit pelatihan kerja untuk mendapatkan izin atau SIUP. Kemudahan tersebut merupakan skema untuk memenuhi target pengiriman pekerja migran.
Terkait dengan anak, UU PPTKILN mengatur mengenai ketentuan usia minimum menjadi TKI di luar negeri, yaitu dalam Pasal 35 (lihat Sagala, 2010), yang menyatakan:
Perekrutan calon TKl oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:
a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKl yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang- kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun:

b. sehat jasmani dan rohani;
c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
d. berpendidikan sekurang- kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertarna (SLTP) atau yang sederajat.
Artinya, selain menekankan bahwa anak dan yang belum berpendidikan sekurang- kurangnya lulus SLTP atau sederajat, tidak boleh menjadi TKI, UU PPTKILN juga mengatur bahwa khusus bagi calon TKl yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan harus sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. “Pengguna perseorangan” dalam hal ini dapat dimaknai sebagai pemberi kerja perorangan yang tidak bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa bernilai ekonomis. Dengan kata lain, dipekerjakan pada Pengguna perseorangan dapat diartikan bekerja dalam lingkup domestik atau “pekerjaan kerumahtanggaan” atau sebagai “pekerja rumah tangga” (atau masih biasa disebut dengan istilah: pembantu rumah tangga). Penjelasan Pasal 35 huruf a UU PPTKILN menjelaskan:
Dalam praktiknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian risiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi.
Pasal ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan (12 April 2007) yang menyatakan dengan tegas bahwa pasal mengenai pembatasan umur minimal 21 tahun bagi seseorang untuk menjadi TKI ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan dengan demikian Pasal ini tetap berlaku. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini bukanlah penghapusan hak terhadap suatu pekerjaan, tetapi merupakan persyaratan yang dapat dibenarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang bekerja diluar negeri.
UU PPTKILN, dengan demikian, secara eksplisit mengakui realitas pekerja yang yang dipekerjakan pada “Pengguna perseorangan” (dapat dimaknai sebagai pemberi kerja perorangan yang tidak bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa bernilai ekonomis, atau dengan kata lain, dipekerjakan pada Pengguna perseorangan dapat diartikan bekerja dalam lingkup domestik atau “pekerjaan kerumahtanggaan” atau sebagai “pekerja rumah tangga” atau masih biasa disebut “pembantu rumah tangga”), dan untuk itu menentukan usia minimum 21 tahun untuk jenis pekerjaan ini.
Pertimbangan utama mengenai penetapan usia minimum ini dengan memperhatikan unsur “dalam praktiknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna”, “yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual”, dan “pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi”, sehingga “dengan demikian risiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi.”
Sayangnya, cuplikan kecil ini tenggelam dengan buruknya sistem perlindungan secara keseluruhan. Sebagai contoh, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem perlindungan PRT. Meski Program Legislasi Nasional telah mencantumkan RUU Perlindungan PRT sebagai salah satu RUU yang harus dibahas oleh pemerintah dan DPR tahun ini, komitmen politik pemerintah maupun sebagian besar kepentingan di DPR memperlambat proses penggodokan RUU ini menjadi UU. Sejalan dengan itu, mengenai “kesetaraan gender” sebagaimana dimuat di Bagian Penjelasan UU PPTKILN, nampaknya tak lebih hanya untaian huruf yang tak bermakna. Bagian Penjelasan UU PPTKILN menyatakan:
“... Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara

Migrasi Internasional: Realita dan Perubahan Kesejahteraan
dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi....”
Kedua, selain UU PPTKILN peraturan lainnya antara lain: (a) Inpres No 6 Tahun 2006 (2 Agustus 2006) tentang Kebijaksanaan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran; (b) Permenakertrans No: PER19/ MENV/2006tentangPelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (12 Mei 2006); dan (c) Peraturan Presiden No 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (8 September 2006).
Kelahiran BNP2TKI pada kenyataannya telah menciptakan konflik berkepanjangan antara Depnakertrans dan BNP2TKI, yang berakibat terabaikannya perlindungan pekerja migran. Berbagai ketentuan perundang- undangan lebih banyak mendelegasikan kewajiban negara dalam melindungi pekerja migran, kepada para pebisnis yang selalu berorientasi pada profit. Dengan peran PPTKIS yang sangat dominan, mulai dari pendidikan calon pekerja migran, pengurusan dokumen, hingga penempatan pekerja migran, perlindungan pekerja migran menjadi jauh dari kerangka penegakan HAM.
Ketiga, belum diratifikasinya Konvensi Migran 1990 dan tidak efektifnya implementasi instrumen ASEAN: ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2008). Pada tanggal 22 September 2004, Menteri Luar Negeri, atas nama Pemerintah Indonesia, telah menandatangani Konvensi Migran 1990. Meskipun peratifikasiandanpengundangan Konvensi menurut Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009, seharusnya diratifikasi pada tahun 2005, hingga kini Konvensi ini belum diratifikasi. Padahal peratifikasian Konvensi ini sangat penting dan telah memenuhi alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan (Komnas Perempuan, 2009). Sebagai tambahan, dengan fakta tingginya jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia, ditambah banyaknya pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan dan meninggal dunia di Malaysia, pemerintah juga belum efektif menggunakan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai instrumen untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Keempat, lemahnya diplomasi. Salah satu upaya dalam melindungi pekerja migran yang juga wajib dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan kerja sama antar-negara (baik bilateral maupun multilateral) sebagaimana diamanatkan dalam UU PPTKILN (Pasal 7):
Dalam melaksanakan tugas pemerintah dan tanggung jawab, berkewajiban:
a. menjamin terpenuhinya hak- hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
b. m e n g a w a s i p e l a k s a n a a n penemp at an calon TKI; c. membentuk dan mengembang- k a n s i s t e m i n f o r m a s i penempatan calon
TKI di luar negeri;d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI
secara optimal di negara tujuan; dane. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa
penempatan, dan masa purna penempatan
Sebagai bagian dari upaya diplomatik, dikenal adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan. Sepanjang pengalaman Pemerintah Indonesia, terdapat MOU antara Pemerintah Indonesia dengan 9 (sembilan) negara yaitu: Malaysia (2 MoU), Korea Selatan (G to G), Taiwan, Jepang (G to G), Australia, Jordania, Kuwait, Uni Arab Emirat, dan Qatar (Roostiawati, 2010).
MoU adalah salah satu bentuk perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional utama. Oleh karena itu, sudah semestinya antara Indonesia dengan negara-negara

tujuan penempatan lain di luar yang telah memiliki MoU dengan Indonesia, perlu diupayakan pembuatan MoU guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
Bagian lain dari diplomasi adalah upaya pembelaan sebagai bagian dari perlindungan pekerja migran Indonesia yang menghadapi persoalan hukum di negara tujuan dan penegakan hukum pada kasus-kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia. Dalam hal pekerja migran yang terancam hukuman mati, misalnya, upaya diplomasi Pemerintah Indonesia masih sangat lemah dan kurang efektif

Analisis Film Perjuangan TKI Hongkong “Perempuan-Perempuan Perkasa”
Banyak masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan, sebagian besar adalah perempuan. Dalam film ini menceritakan bagaimana kehidupan BMP (Buruh Migran Perempuan) yang mencerai peruntungan di Hongkong, salah satu wilayah administratif di Republik Rakyat Cina. Mereka menganggap di hongkong memiliki kondisi yang mendukung dalam berbagai aspek dengan segala kemampanan yang dimiliki oleh Negara tersebut. Sehingga banyak (Tenaga Kerja Indonesia) TKI yang berbondong-bondong pergi ke Hongkong dengan berbagai motif dan beberapa diantaranya sangat terinspirasi dengan TKI yang sebelumnya bekerja menjadi TKI terlebih dahulu. Pada film ini menceritakan tiga BMP yan mengadu nasib di Hongkong. Mereka menceritakan hak-hak mereka sebagai buruh migran yang telah di atur dalam pasal serta di sepakati oleh Negara-negara yang menjadi anggota PBB. Banyak diantara mereka yang sukses ada juga yang tidak, dengan dibumbui cerita sedih dan menggenaskan.
1. Nurhidayatun, migran asal kebumen, datang ke hongkong pada bulan 9 maret 2010, langsung ke majikan hari itu juga. Alasannya untuk membantu perekonomian keluarga, orangtua tidak bekerja untuk membiayai adik-adiknya. Ia menganggap hongkong adalah Negara yang mapan, serta anggapannya ketika ia bekerja di hongkong impian dan cita-citanya bisa tercapai. Ketika menjadi BMP tidak ada majikan perempuan, setelah tiga bulan majikan memotong gaji, dengan alasan pekerjaan Nurhidayatun selalu tidak beres. Ia di tampar pakai tangan hingga berdarah, dilempar dengan sandal mengakibatkan telinga Nurhidayatun mengalami cacat, ia juga dibawa majikannya ke kamar mandi, telinganya dipukul hingga berdarah. Setelah kejadian kekerasan tersebut majikan tidak membawanya ke rumah sakit. Ia juga tidak diberi libur sama sekali, ia juga tidak bisa mengabari keluarganya selama satu tahun bekerja. Ia tidak diberi makan, bahkan ia pernah selama 24jam tidak diperbolehkan tidur, tangannya di injak. Dalam keadaan tidak sadar,ia dibawa ke rumah sakit Princess Margaret Hospital. Ketika sadar ia melihat tangan dan kakinya terbungkus dengan kondisi menggenaskan dengan berat badan hanya 23kg. akibat penganiayaan yang di alami Nurhidayatun ia di rawat di Princess Margaret Hospital selama empat bulan. Nurhidayatun berpesan menjadi seorang BMP di Hongkong aspek kebahasaan sangatlah penting dan harus berhati-hati. Kemudian Nurhidayatun menuntut majikannya atas pelanggaran hokum berupa penganiayaan, pelanggaran undang-undang perburuhan, dan tuntutan asuransi.
2. Heni Sri Sundani, ia terinspirasi dari gurunya yang sebelumnya juga sebagai BMP. Ketika bekerja sebagai migrant di Hongkong dijadikan jalan alternative untuk kuliah. Ketika di hongkong ia melihat peluang dan dapat berkuliah di Hongkong. Ia aktif ikut organisasi Indonesian Migrant Union, belajar bersama advokasi, hokum perburuhan, manajemen, mengelola organisasi perburuhan lingkar pena membahas buletin, berdiskusi. Ia juga memiliki majikan yang baik, dengan fasilitas dan hak-hak diberikan oleh majikan dengan libur di hari sabtu dan minggu. Hari libur tersebut dimanfaatkan oleh Heni untuk menempuh diploma IT komputer di tempuh dengan tiga tahun, kemudian melanjutkan di salah satu universitas di Hongkong. Bagi Heni hal ini adalah kesempatan dan merupakan peluang untuk berbagi, dan mereka memotivasi untuk meningkatkan kualitas hidup bukan hanya dari segi materi. Heni berkeinginan menjadi seorang penulis sejak kecil, dan dapat ia wujudkan mengikuti acara internasional sastra yang karyanya lolos seleksi dan dilaksanakan di Ubud, Bali. Ia ingin menjadi inspirasi bagi orang-orang di daerah asalnya terutama perempuan bahwa kehidupan ini tidak sebatas dusun, dimana kebanyakan siklus perempuan di daerah asalnya sangat lah sedikit, terbatas pendidikan sekolah dasar kemudian mereka menikah dengan laki-laki dari dusun sebelah. Karya-karya heni diakui internasional, dan heni ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata 2.
3. Bertha Eliana Siagian, seorang buruh migrant perempuan dengan latar belakang bapak dari batak dan ibu dari jawa. Ia datang ke hongkong pada tahun 2000-an. Awalnya ia memiliki jaringan dalam Netowork theory seorang yang memperkenalkan bahwa di hongkong banyak buruh migrant. Kemudian Bertha tertarik juga untuk menjadi migrant di Hongkong. Bekal pengetahuan dan aspek kebahasaan memudahkan bertha menjadi BMP di Hongkong yang terbilang sulit. Ia sebagai asisten rumah tangga, membantu mengurus 6 orang anak majikan

dengan majikan sebagai seorang pengajar yang baik serta Fasilitas yang layak. Ada sekolah lembaga TKW yang dikelola oleh orang Filiphina. Bertha terisnpirasi untuk melibatkan diri dalam sekolah kesetaraan sekitar tahun 2005 bagi TKI hongkong. Dengan ini harapan Bertha para TKI di Indonesia ketika kembali, dapat melanjutkan pendidikannya di Indonesia atau membawa remitansi ke Negara asal. Ia tidak merasa malu dan merendah menjadi seorang TKW, sebaliknya ia merasa bangga. Mungkin kesempatan yang dia dapatkan saat ini tidak akan ia dapatkan jika ia tidak menjadi seorang TKW. Bertha aktif bekerja di sektor rumah tangga dan tetap aktif sebagai sukarelawan, mengajar dikelas kesetaraan bagi TKI
Hongkong menjadi salah satu Negara tujuan migrant asal Indonesia dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Hongkong juga mampu mefasilitasi para migrant asal Indonesia dengan baik salah satunya Hongkong memberikan keleluasaan bagi TKI kebebasan dalam melakukan organisasi, baik di Victoria park, atau di bagian wilayah Hongkong lainnya. Hal ini terkadung dalam kerangka hokum HAM yang wajib dipenuhi oleh Negara-negara yang bertanggung jawab terhadap warga negaranya tak terkecuali migrant asal Indonesia termasuk para TKI maupun BMP. Dan sudah merupakan kewajiban Negara dalam memenuhi hak-hak para migrant tersebut. Tertera dalam International Convenant Pasal 2 (1) Kovenan menegaskan kewajiban negara: Setiap Negara secara sendiri atau pun dengan bantuan internasional dan kerja kooperatif dengan negara lain, mengusahakan sumber-sumber untuk pemenuhan hak-hak yang telah diakui dalam konvensi, termasuk mengusahakan adanya peraturan hukum formal. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang diatur mecakup: hak untuk bekerja (pasal 6); hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7); hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi perpekerjaan (pasal 8).
Akan tetapi terjadi kelalaian hokum dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan para migrant, meskipun dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang menyatakan bahwa “setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Seperti yang di alami oleh Nurhidayatun yang mungkin menjadi salah satu BMP yang tidak bernasib mujur, ia mengalami kekerasan hingga kondisinya menggenaskan karena tidak diperlakukan manusiawi oleh majikannya. Hak-hak Nurhidayatun tidak diberikan oleh majikannya.
Perempuan menjadi fokus objek dalam permasalahan buruh migrant karena seringnya terjadi ketimpangan gender. Dominan perempuan dalam melakukan aktivitas domestik rumah tangga yang mendapatkan sterotype social-budaya hingga rentannya perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang berbasis gender. Perempuan dianggap lemah dan tidak memiliki power yang sering mengalami diskriminasi. Berkaitan pula dengan feminisasi migrant, yang mana buruh migrant lebih banyak berjenis kelamin perempuan. Lebih dari separuh penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan (Whitehead,2003). Fenomena lebih miskinnya perempuan dibanding laki-laki dalam kelompok miskin bukanlah sesuatu hal yang baru. Fakta yang terbaru—atau lebih tepatnya baru disadari-- adalah bahwa jumlah perempuan selalu lebih besar dalam kelompok miskin, dan kenaikan persentase kemiskinan senantiasa berkorelasi positif dengan persentase perempuan miskin. Kemiskinan ini berefek pada tindakan migrasi, melihat perempuan miskin lebih banyak, maka yang melakukan migrasi lebih banyak dilakukan oleh perempuan sehingga terjadilah feminisasi migran. Hal ini terdapat pada Landasan Aksi dan deklarasi Beijing. Hak-hak para BMP ini sangat jelas, berlaku bagi BMP yang beruntung seperti Heni Sri Sundani dan Bertha Eliana Siagian. Mereka dapat mengembangkan potensi-potensi mereka, sehingga ia mengalami kemajuan dalam kualitas diri mereka, tidak hanya sebagai buruh domestik di negeri orang, karena fasilitas-fasilitas yang ia dapatkan serta majikan yang menerapkan hukum HAM serta memberikan hak-hak mereka sebagai BMP. Tidak sebanding dengan perlakuan yang diterima Nurhidayatun dari majikannya. Hak-haknya yang telah tersepakati dengan jelas tidak didapatkannya. Menjadi permasalahan dan momok bagi migrant sendiri ketika berada di negeri orang. Nurhidayatun tentunya mengalami trauma, akan tetapi keterpaksaan untuk bisa bertahan hidup mengingat kondisi keluarganya di daerah asal.