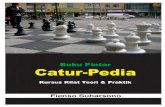Paper Lingkungan Hayati Catur
-
Upload
mipa048284 -
Category
Documents
-
view
253 -
download
0
Transcript of Paper Lingkungan Hayati Catur
DEGRADASI LINGKUNGAN MELALUI DEGRADASI HUTAN DAN DEFORESTASI, PENYEBAB, AKIBAT SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA Oleh : I Ketut Catur Marbawa I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejarah memberi petunjuk kepada kita bahwa alam memiliki batasbatas kemampuannya untuk pulih. Ketika ambang batas itu terlewati degradasi alam dengan segala konsekuensinya akan ditanggung oleh generasi yang akan datang. Manusia berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Dengan akal budi manusia mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun demikian seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup telah terjadi dimana-mana, termasuk di Indonesia. Yang menonjol adalah gangguan atau kerusakan pada berbagai ekosistem yang menyebabkan komponen komponen yang menyusun ekosistem, yaitu keanekaragaman varietas (genetic, variety, atau subspecies diversity), keanekaragaman jenis (species diversity) juga ikut terganggu. Akibatnya, terjadilah kepunahan varietas atau jenis hayati yang hidup di dalam ekosistem. Pada akhirnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, manusia yang sangat tergantung pada kelestarian ekosistem tapi berlaku kurang bijaksana terhadap lingkungannya, akan merasakan berbagai akibatnya. Kerusakan lingkungan, khususnya di Indonesia, telah terjadi pada berbagai tempat dan berbagai tipe ekosistem. Misalnya, pada ekosistem pertanian, pesisir dan lautan, juga ekosistem hutan. Bukti sejarah lenyapnya hutan alam di Benua Eropa seiiring dengan perubahan sosial masyarakatnya yang ditandai dengan revolusi industri adalah pelajaran yang sangat berharga. Kerusakan sumberdaya alam di Indonesia adalah karena melupakan dan gagal belajar dari fenomena kerusakan sejarah di benua Eropa. Hutan alam dataran rendah di Pulau Jawa telah habis dalam tempo 100 tahun pada periode 1800 1900. Prediksi para ahli bahwa hutan-hutan alam dataran rendah di Sumatra dan sebagian Kalimantan lenyap hanya dalam hitungan 30 tahun. Deforestasi dan degradasi hutan masih tetap menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Indonesia memiliki 10 persen hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12 persen dari jumlah spesies binatang menyusui/ mamalia, pemilik 16 persen spesies binatang reptil dan ampibi. 1.519 spesies burung dan 25 persen dari spesies ikan dunia. Sebagian diantaranya adalah endemik (hanya dapat ditemui di daerah tersebut). Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Laju kerusakan hutan Indonesia pada saat ini masih tinggi, mencapai 1,08 juta hektare per tahun. Meski menurut data Direktorat Jendral Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( Ditjen RHL) Dephut, laju kerusakan hutan saat ini turun dari kisaran 1,87 juta hektare
per tahun pada kurun 1985-1998 dan 2,83 juta hektare per tahun pada 1987-2000, namun luas hutan kritis sampai akhir 2009 diperkirakan mencapai 69,9 juta hektare (Arif Pujianto, 2009) Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta hektar, sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (hak penguasaan hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 persen atau setara dengan 43 juta hektar saja yang masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer. B. Tujuan Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan paper ini bertujuan untuk mengulas tentang degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, faktor penyebab, akibat yang ditimbulkannya serta upaya penanggulangannya. II. PENGERTIAN Hutan Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) Deforestasi Deforestasi adalah pengalihan hutan menjadi lahan dengan tujuan lain atau pengurangan tajuk pohon di bawah ambang batas minimum 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 m (in situ) dan areal minimum 0,5 ha (FAO, dalam Draft 1 Strategi Nasional REDD+ BAPPENAS). Degradasi Perubahan di dalam hutan yang berdampak negatif terhadap struktur atau fungsi tegakan atau lahan hutan sehingga menurunkan kemampuan hutan dalam menyediakan jasa/produk hutan, atau dapat diartikan sebagai penurunan stok carbon (carbon stock degradation) hutan (FAO dan submisi Indonesia ke Sekretariat UNFCCC Maret 2008, dalam Draft 1 Strategi Nasional REDD+, BAPPENAS). Degradasi hutan merupakan perubahan luas tutupan hutan yang lebih banyak untuk tujuan ekonomi, non ekologis dimana penggunaan dan pemanfaatan lahan (land use) tidak berubah, tetapi sebagai kawasan hutan, yang berubah adalah kuantitas dan kualitas penutupan hutannya (Siaran Pers Departemen Kehutanan, 20 April 2007).
III. METODOLOGI Penulisan paper ini menggunakan metodologi studi literatur yang bersumber dari website-website yang ada. IV. PEMBAHASAN A. Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia Secara umum deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam dan luar sektor kehutanan. Dari dalam sektor kehutanan, pemicu tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kegiatan, yaitu Penebangan ilegal dan dari pengelolaan hutan yang tidak lestari, Kebakaran hutan, Perubahan hutan alam (tanah mineral dan gambut) untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan konsesi hutan. Sedangkan dari luar sektor kehutanan, pemicu deforestasi dan degradasi hutan antara lain adalah Perambahan hutan oleh masyarakat, Kebakaran lahan (non-kawasan hutan), Perluasan permukiman, Pemekaran wilayah, Ekstensifikasi perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, kopi), Ekstensifikasi lahan pertanian, Pembukaan tambak di hutan mangrove, Peningkatan lahan penggembalaan (pasture land), Pertambangan, dan Pembangunan infrastruktur. Secara lebih sederhana, seluruh hal di atas dapat dikelompokan menjadi penyebab deforestasi akibat adanya konversi hutan menjadi kawasan non hutan baik secara terencana maupun tidak terencana, serta degradasi hutan akibat adanya penabangan liar dan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis fishbone, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama penyebab deforestasi dan degradasi seperti lemahnya tata tuang, tidak efektifnya unit manajemen hutan, lemahnya tata kelola, permasalahan tenurial, dan lemahnya dasar hukum serta penegakan hukum (Draft 1 Strategi Nasional REDD+, BAPPENAS).
Tata Ruang yang lemah
Tenurial Bermasalah
Unit Manajemen Hutan Tidak Efektif Tata Kelola Lemah
Dasar dan Penegakan Hukum Lemah
Komponen Masalah Lemahnya Data dan Informasi yang sahih dan akurat lemah Partispasi dalam perencanaan tata ruang dan tata guna lahan Perencanaan sektorat tidak terpadu Konflik lahan tidak pernah tuntas Status dan batas kawasan hutan tidak jelas Terbatasnya alternatif sumber pendapatan Budaya dan pola mata pencaharian berbasis lahan Masyrakat adat tidak memiliki hak formal Hutan produksi kolap, hutan lindung terancam, hutan konservasi rentan Kinerja organisasi pengelolaan hutan rendah Integritas dan kapasitas pengelola hutan rendah Ketidakadilan distrubusi manfaat dari sektor hutan Koordinasi antar sektor dan antara pusat dan daerah lemah Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas rendah Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan dan anggaran rendah Korupsi dan kolusi Isi dasar hukum kontraproduktif dan tidak jelas Tumpang tindih dasar hukum Penegakan hukum lemah, termasuk adanya mafia hukum
Gambaran analisis fishbone terhadap timbulnya degradasi hutan di Indonesia tergambar dibawah ini.TATA RUANG LEMAH MASALAH TENURIAL Masyrakat adat tidak memiliki hak formal Lemahnya Data dan Informasi yang sahih dan akurat lemah Budaya dan pola mata pencaharian berbasis lahan Terbatasnya alternatif sumber pendapatan Partispasi dalam perencanaan tata ruang dan tata guna lahan Perencanaan sektorat tidak terpadu Paradigma Pembangunan belum patuh pada prinsip berkelanjutan Lack of leadership Target pertumbuhan ekonomi Kesenjangan Supply dan demand Kayu Status dan batas kawasan hutan tidak jelas Konflik lahan tidak pernah tuntas UNIT MANAJEMEN HUTAN TIDAK EFEKTIF Hutan produksi kolap, hutan lindung terancam, hutan konservasi rentan
deforestasi
dan
Kinerja organisasi pengelolaan hutan rendah Integritas dan kapasitas pengelola hutan rendah Deforestasi dan Degradasi Hutan Isi dasar hukum kontraproduktif dan tidak jelas Tumpang tindih dasar hukum
Ketidakadilan distrubusi manfaat dari sektor hutan Koordinasi antar sektor dan antara pusat dan daerah lemah Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas rendah Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan dan anggaran rendah Korupsi dan kolusi
Penegakan hukum lemah, termasuk adanya mafia hukum
LINGKUNGAN
TATA KELOLA LEMAH
DASAR DAN PENEGAKAN HUKUM LEMAH
FAKTOR PENYEBAB
AKIBAT/HASIL
Gambar 1.
Identifikasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan dengan Analisis Fishbone
1. Perencanaan Tata Ruang yang Lemah Rencana Tata Ruang disusun sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang sekaligus sebagai wadah kepentingan para pihak di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta maupun masyarakat dan bertujuan untuk mengoptimalkan ruang dengan tetap menjaga keseimbangan antara tujuan menaikkan tingkat pertumbuhan daerah, kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan (Siagian dan Komarudin, 2009). Namun demikian, dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan instrumen RTRW tidak dapat secara memadai mewadahi berbagai kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan. Di beberapa daerah, dokumen RTRW bahkan menjadi dokumen yang menyebabkan deforestasi melalui konversi yang terencana. Persoalan ini muncul karena berbagai hal, terutama hal-hal berikut : a. Perencanaan Pembangunan Sektoral Tidak Terpadu Perencanaan pembangunan yang masih bersifat sektoral dan belum mampu menjadi dokumen yang secara independen mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral. Saat ini masing-masing lembaga pada umumnya membuat rencana tahunan sendiri-sendiri dengan membuat alokasi sumber daya lahan terpisah. Perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang kurang terpadu sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian ruang dan deforestasi pada areal-areal berhutan yang masih dalam kondisi baik. b. Ketersediaan dan Akses Data dan Informasi Lemah Ketersediaan dan akses pada data dan informasi spasial biofisik, maupun sosial ekonomi yang sahih dan akurat, masih terbatas. Umumnya perencana juga tidak menggunakan metodologi yang memberikan informasi kepada pengambil keputusan dengan pilihanpilihan prioritas, termasuk isu karbon. Salah satu contoh akibat pengambilan keputusan tersebut adalah RTRW (baik kabupaten maupun provinsi) yang menetapkan kawasankawasan hutan yang telah terdegradasi tetap menjadi kawasan hutan, sedangkan kawasan hutan yang masih mempunyai hutan dengan kondisi sedang sampai bagus dimasukkan dalam rancangan dikonversi. Konversi hutan dengan kondisi demikian akan memberikan emisi yang sangat besar. c. Partisipasi Dalam Perencanaan Lemah Proses partisipasi dalam proses pembuatan rencana tata ruang wilayah tidak berjalan. Penyusunan RTRW masih bersifat top down dan belum secara utuh menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi yang hakiki sehingga masyarakat yang mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan tidak dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap dokumen tersebut. Ketiadaan partisipasi dan transparansi ini memudahkan terjadinya aktivitas penggunanaan lahan yang tidak direncanakan dalam RTRW namun terjadi di lapangan, misalnya perambahan oleh masyarakat
untuk pembukaan perkebunan, pertanian, pemukiman, pertambangan tanpa izin dan lain-lain. Hal ini merupakan cerminan umum dari tingkat kecakapan sosial (sociability) masyarakat, yang seringkali menyalurkan ketidakpuasan dengan cara-cara yang justru merugikan sumber daya hutan atau lingkungan. 2. Tenurial
a. Penyelesaian Konflik Lahan Tidak Tuntas Hutan dengan keragaman atas hak, status dan fungsinya telah menjadi suatu medan perebutan kepentingan yang pelik dan hingga saat ini masih belum terselesaikan. Konflik dan ketidaksepakatan tentang siapa yang seharusnya mengontrol dan mengelola hutan dan Kawasan Hutan negara merupakan sumber dari berbagai ketegangan, dan tidak jarang justru menyebabkan tindakan-tindakan yang merusak. Asal-usul ketegangan ini terletak pada tafsir dari definisi dan lokasi hutan di Indonesia serta kewenangannya. Tafsir-tafsir yang berbeda menyebabkan perbedaan-perbedaan mendasar tentang peran kontrol terhadap sumber daya hutan oleh pelaku dan lembaga yang berbeda. Konflik atas peran kontrol terhadap lahan dan sumber daya alam yang disebabkan oleh ketidakjelasan hakhak tenurial harus diselesaikan dengan usaha serius melalui strategi tindakan yang jelas. b. Masyarakat Adat Tidak Memiliki Hak Formal Dualisme hukum atas pengakuan hak ulayat masyarakat adat di kawasan hutan serta non-kawasan hutan menjadi salah satu permasalahan tenurial ini. Ketiadaan hak formal masyarakat adat menyebabkan mereka tidak bisa mengambil keputusan terkait sumber daya alam di wilayah adatnya yang menjadikan potensi mereka dalam mengawasi kawasan hutan menjadi semakin lemah. Sementara prosedur yang memungkinkan mereka memiliki pengakuan sebagai masyarakat hukum terkesan sangat sulit dan panjang. Pemicu lain terhadap meningkatnya konflik tenurial adalah batas kawasan hutan yang tidak jelas di lapangan, akibat dari proses pengukuhan kawasan hutan yang tidak kunjung selesai. c. Mata Pencaharian dan Kelangkaan Alternatif Sumber Pendapatan Keberadaan hutan biasanya memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan. Banyak konsep yang menjelaskan mengenai masyarakat dan hutan, seperti sistem pengetahuan lokal, kearifan lokal, dan masyarakat adat. Konsep-konsep tersebut pada dasarnya menjelaskan keterikatan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dengan lahan dan sumber daya alam yang ada serta dihasilkan dari hutan tersebut. Dalam dua dekade terakhir, ketika kerusakan hutan sedang menjadi perhatian banyak pihak, keberadaan masyarakat sekitar hutan juga tidak terlepas di dalamnya. Keterkaitan masyarakat dengan deforestasi dan degradasi hutan sering menjadi pokok pembahasan. Hal ini dipicu oleh kenyataan bahwa budaya produksi atau mata pencaharian masyarakat di pedesaan biasanya berbasis pada pengelolaan lahan dan pemungutan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.
3. Unit Manajemen Hutan Tidak Efektif Luas kawasan hutan Indonesia mencapai 132,399 juta ha (BAPLAN, 2008), sekitar 15% merupakan hutan konservasi (HK), 22% hutan lindung (HL), 46% hutan produksi (HP) dan 17% hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Berdasarkan data satelit 2007, kawasan hutan yang masih berhutan hanya sekitar 92,328 juta ha (40%) dan yang sudah tidak berhutan sekitar 40,071 juta ha (21%). Luas hutan yang dapat dikonversi (HPK) mencapai 22,7 juta ha, dan hanya 10,7 juta ha yang masih berhutan. Pengelolaan hutan di hampir seluruh fungsi hutan dalam keadaan yang rentan. Kelemahan unit manajemen hutan terjadi di seluruh tingkatan, baik pada sistem pengelolaan hutan, organisasi pengelola hutan, maupun pada tingkat individu yang bekerja di sektor kehutanan pada berbagai fungsi hutan. Berbagai permasalahan unit manajemen hutan berdasarkan tingkatannya, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sistem Pengelolaan Hutan Lemah Permasalahan pada tingkat sistem pengelolaan meliputi kerangka peraturan, kebijakan, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau menghambat pencapaian tujuan pengelolaan lestari. Diawali dari lemahnya data dan informasi dalam penyusunan perencanaan telah menyebabkan pengelolaan hutan pada semua fungsi hutan menjadi tidak valid dan sulit mencapai predikat berkelanjutan. Proses penataan batas kawasan hutan, yang mampu menunjukkan di mana dan berapa luas kawasan hutan yang pasti secara legal maupun aktual diakui dan dihormati semua pihak, sampai saat ini belum mampu dilakukan. Kemudian, hampir seluruh hutan produksi dan hutan lindung di luar Jawa tidak jelas siapa penanggung jawabnya yang menyebabkan kawasan hutan menjadi open access dan memicu deforestasi dan degradasi, baik yang direncanakan maupun tidak. Pengelolaan Hutan Produksi yang Lemah Di bidang pengusahaan hutan ini, dari jumlah 486 unit HPH di tahun 1992, yang masih bertahan sampai tahun 2007 sebanyak 115 unit atau hanya 24%, dengan berbagai sebab, baik kendala internal maupun eksternal. Pengelolaan hutan alam produksi masih jauh dari kaidah dan prinsip-prinsip Sustainable Forest Management (SFM). Para pelaku usaha di sektor kehutanan lebih memikirkan aspek bisnis daripada kelestarian produksi. Teknik pemanenan tidak lagi memperhatikan kaidah penurunan dampak penebangan, pemanenan dilakukan melebihi jatah tebangan (over cutting), limbah dan derajat kerusakan hutan pada kawasan bekas tebangan sangat tinggi. Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi yang Rentan Upaya pelindungan hutan yang dilakukan pada hutan lindung dan hutan konservasi juga masih mendapat kendala. Pada hutan lindung, kewenangan antara pusat dan daerah tidak jelas sehingga hutan terkesan tidak bertuan dan open access. Dalam kondisi seperti ini, peluang deforestasi tidak terencana semakin terbuka lebar. Pada pengelolaan hutan konservasi, hingga saat ini telah dibentuk 527 unit kawasan konservasi daratan dan laut, meliputi 50 unit Taman Nasional (TN), 118 unit Taman Wisata Alam (TWA), 22 unit Taman
Hutan Raya (Tahura), 14 unit Taman Buru (TB), 248 unit Cagar Alam (CA) dan 75 unit Suaka Margasatwa (SM). Untuk kawasan konservasi laut telah ditetapkan sebanyak 7 unit Taman Nasional, 5 unit Cagar Alam, 2 unit Suaka Margasatwa, dan 14 unit Taman Wisata Alam. Masih lemahnya kapasitas pengelolaan menjadi tantangan utama saat ini. Sebagai gambaran, dari seluruh unit kawasan konservasi, baru 34,4 % yang telah memiliki Rencana Pengelolaan, pada umumnya TN dan TWA. Sedangkan penyusunan zonasi/blok pengelolaan, baru tercapai 8,4%. Untuk 21 Taman Nasional Model, semuanya telah memiliki Rencana Pengelolaan, namun demikian 19% di antaranya belum disahkan. Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi serta Reward dan Punishment tidak jelas Belum terdapat peraturan-perundangan yang secara efektif dan efisien mampu menjadi landasan pemecahan masalah kehutanan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Penetapan peraturanperundangan lebih memenuhi kebutuhan birokrasi dalam menjalankan tugas administrasinya daripada memecahkan persoalan yang dihadapi pengelola hutan di lapangan. Di samping itu juga ditemukan kurangnya alternatif pemecahan masalah di lapangan, karena sebagian besar isi peraturan mengandung larangan sebagai bentuk pengendalian kerusakan hutan. Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan juga sering terjadi. Programprogram unggulan yang dipayungi oleh keputusan pejabat teknis sering berubahubah, tergantung pejabat yang berwenang saat itu. Misalnya, program pembentukan Taman Nasional Model yang saat ini terlantar dan tidak terukur keberhasilannya. Kemudian pada hutan produksi, pemberian izin RKT yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan dalam volume yang besar bertentangan dengan semangat pembatasan ekploitasi hutan alam atau bahkan menafikan informasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon izin tersebut. Di sisi lain, pelanggaran dalam proses pemberian izin baik yang dilakukan oleh pengaju izin maupun pemberi izin sangat sedikit yang dikenakan sanksi yang menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran-pelanggaran terus terjadi. b. Kelembagaan yang Lemah Belum terwujudnya kinerja kelembagaan seperti yang diharapkan, sehingga menjadi penyebab lemahnya pelayanan publik terkait perizinan dan penyelenggaraan ekonomi kehutanan, serta belum adanya prioritas nyata bagi penguatan organisasi pengelola hutan di tingkat lapangan/tapak. Kondisi demikian ini menjadi penyebab rendahnya informasi mengenai kekayaan sumber daya hutan sebagai dasar penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan. Selain itu masalah kelembagaan yang lemah ini juga timbul dari ketidakjelasan penerapan otonomi daerah yang dipayungi oleh Undang-undang No 32/2004 dan turunannya dihubungkan dengan aturan sektoral maupun ketidaktepatan pembagian kewenangan itu sendiri, hal mana menyebabkan timbulnya ketidakjelasan penanggungjawab sektor kehutanan pada level tapak.
Pada tingkat organisasi pengelola, sebagian besar waktu dan tenaga habis untuk masalah administratif daripada substantif. Hal ini didorong oleh sistem penilaian kinerja organisasi yang hanya diukur dari penyerapan anggaran dan dokumen-dokumen laporan, tidak sampai pada efektivitas dan efisisensi anggaran, penilaian keluaran, hasil, dampak dan manfaat yang secara nyata terjadi di lapangan. Kondisi seperti ini mendorong cara kerja organisasi yang ekslusif dari pada inklusif sehingga upaya-upaya kerja sama, baik di internal organisasi maupun kerja sama strategis dengan pihak-pihak lain yang berpotensi mendukung pengelolaan selalu terhambat. c. Permasalahan Kapasitas Individu yang Lemah Permasalahan kapasitas pada tingkat individu mancakup kompetensi (kemampuan, kualifikasi, dan pengetahuan), sikap dan prilaku (attitude), dan integritas (etos kerja dan motivasi), maupun jiwa kepemimpinan yang kuat dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di lapangan. Permasalahan di tingkat individu pada kondisi yang relatif normal biasanya disebabkan oleh situasi dalam organisasi yang tidak mendukung berkembangnya kapasitas individu. Bahkan terdapat kondisi dimana orang-orang di dalam organisasi cenderung pragmatis dan selalu mencari peluang untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan pribadinya. 4. Dasar dan Penegakan Hukum Lemah a. Dasar hukum Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilahirkan dengan semangat reformasi, berusaha mengembalikan tatanan kehutanan kepada sistem pengurusan hutan yang lebih baik. Namun demikian, undang-undang ini masih perlu penguatan, salah satunya dalam hal pengaturan kewenangan pusat dan daerah dalam semangat desentralisasi yang bertanggung jawab. Beberapa fenomena yang mendasari perlunya penguatan ini dapat dilihat dari kerancuan kewenangan beberapa perizinan pengusahaan hutan, dan tumpang tindih kawasan hutan dengan rencana tata ruang wilayah. Secara langsung atau tidak langsung, masih kurang kuatnya Undang-undang Kehutanan ini membuka peluang terjadinya deforestasi yang terencana (planned deforestation) masih terbuka. Masalah mengenai kurang kuatnya Undangundang kehutanan dapat dilihat dari kategori berikut : Peluang ekploitasi hutan alam masih sangat terbuka Permintaan terhadap hasil hutan kayu masih tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat. Berbagai industri hilir di dalam dan luar negeri sangat bergantung pada kayu yang berasal dari hutan alam Indonesia sebagai bahan bakunya. Pada dasarnya keberadaan industri berbasis kayu dan siklus produksinya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan perlu difasilitasi dan dijamin keberlangsungannya oleh Undang-undang kehutanan. Karenanya, pembatasan pembatasan perlu dilakukan secara tegas agar kelestarian produksi pada industri hilir juga diikuti oleh kelestarian hutan sebagai sumber bahan bakunya. Merujuk pada sejarah pengusahaan hutan produksi dan kondisi terkini hutan alam di Indonesia maka sudah saatnya diberlakukan
penghentian terhadap ekploitasi hutan alam sekaligus mengintensifkan pembangunan hutan tanaman di areal areal yang telah terdeforestasi. Dalam konteks ini, Undang-undang Kehutanan memiliki kelemahan karena masih memberikan ruang yang cukup leluasa untuk ekploitasi hutan alam yang masih dalam kondisi baik. Sebagai contoh, ketidaktegasan pembatasan HTI pada hutan yang sudah tidak produktif dalam UU 41/1999 menyebabkan lahirnya peraturan pelaksana yang sangat berbeda dari waktu ke waktu. Pasal 30:3 PP No. 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan misalnya secara tegas menyatakan bahwa izin Hutan Tanaman hanya dapat diberikan pada lahan kosong, padang alang-alang atau semak belukar pada hutan produksi. Namun ketentuan ini kemudian berubah secara signifikan pada aturan kemudian yaitu PP No. 3/2008 yang mengubah PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang hanya menyatakan bahwa hutan tanaman diprioritaskan pada hutan produksi yang tidak produktif yang berarti membuka kemungkinan dilaksanakan pada seluruh kawasan hutan lainnya. Selain peluang ekploitasi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan kayu, ekploitasi hutan alam juga masih terbuka untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan atau pertanian. UU 41/1999 membuka peluang dilakukannya konversi tanpa memberi batasan dasar yang jelas dan tegas. Akibatnya aturan pelaksana dari ketentuan ini juga dapat diartikan berbeda-beda dari satu waktu ke waktu lain yang tidak terlalu lama. Sebagai contoh, Kepmenhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan mengatur bahwa untuk melepas kawasan hutan konservasi, maka status kawasan tersebut harus diubah secara bertahap menjadi hutan lindung dan hutan produksi sebelum bisa diubah menjadi APL. Tetapi kemudian, Pasal 4 jo Pasal 29 PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan bahwa Kawasan Hutan Konservasi dapat diubah menjadi APL melalui persetujuan DPR. Ketidakjelasan batasan pada UU 41/1999 sendiri telah menimbulkan perbedaan penfasiran atas kehendak UU dalam mengelola hutan sehingga memudahkan terjadinya pembentukan aturan berdasarkan kepentingan sesaat. Padahal apabila penentuan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan serta PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam), maka seharusnya perubahan peruntukan dan fungsi tidak mudah untuk dilakukan. Pada tataran implementasi, perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Modus yang tidak langsung misalnya dengan menelantarkan hutan, izin konsesi yang telah diperoleh hanya dipergunakan untuk memanen kayu dan setelah itu hutan ditelantarkan sampai akhirnya diusulkan untuk areal perkebunan atau peruntukan lainnya dengan alasan bahwa hutan tersebut telah rusak, tidak produktif, atau terdegradasi. Benturan atau ketidakharmonisan peraturan
Benturan atau ketidakharmonisan peraturan perundangundangan dapat terjadi secara horinzontal (antar sektor) atau vertikal (antara pusat dan daerah). Dengan terbitnya undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah menjadi sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam undangundang ini disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebutkan pula bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, antara pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewenangan masing-masing. Sayangnya pengalaman dalam memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengeluarkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada daerah telah memicu laju deforestasi pada kurun wktu 2000 2003. Benturan antara pusat dan daerah biasanya tampak kasat mata dalam tata ruang wilayah yang dipayungi oleh Peraturan Daerah. Tumpang tindih atau usulan perubahan fungsi hutan untuk penggunaan lain selalu saja terjadi dalam tata ruang wilayah. Pada kasus tumpang tindih kawasan yang telah terlanjur terjadi, misalnya pembukaan pertambangan atau perkebunan yang terlanjur ada karena lemahnya koordinasi, proses penegakan hukumnya seringkali mendapat hambatan dari aspek lemahnya kemantapan kawasan hutan sebagai akibat dari proses pengukuhan kawasan yang tidak selesai. Dalam ketentuan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah melalui proses : 1) penunjukkan kawasan hutan; 2) penataan batas kawasan hutan; 3) pemetaan kawasan hutan; dan 4) penetapan kawasan hutan. Syarat tersebut sangat mutlak untuk masing-masing kegiatannya, jadi untuk dapat menentukan suatu kawasan adalah hutan atau tidak, maka prosesnya harus memenuhi 4 unsur tersebut. Bila tidak maka penentuan kawasan hutan tersebut menjadi batal demi hukum, dan deforestasi atau degradasi yang terjadi akibat penggunaan untuk sektor penggunaan lahan lainnya tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Ketidaklengkapan Peraturan Aturan yang tidak lengkap akan memudahkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan khususnya terkait dengan pemberian perizinan usaha kehutanan maupun izin kegiatan lain di kawasan hutan. Undang-undang pertanian misalnya, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk memberikan izin perkebunan di daerahnya. Walaupun Undang-undang Kehutanan mengatur bahwa seharusnya untuk perkebunan dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan terlebih dahulu, namun pada kenyataannya hal ini tidak berjalan di lapangan.
Ketidaklengkapan di tataran aturan ini juga terjadi karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada pihak yang tepat atau tidak disertai oleh insentif yang tepat. Sebagai contoh adalah pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan penataan tata batas kawasan hutan. Ketentuan ini menyebabkan kendala di tingkat implementasi karena sumber daya berada di Pemerintah Pusat dan Kabupaten. Di lain pihak, sumber daya pendukung tidak diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur untuk melaksanakan hal tersebut. Terkait aturan yang tidak lengkap, maka Undang-undang Kehutanan juga masih belum memberikan sanksi yang memadai bagi pelaku utama pembalakan liar, melainkan hanya terbatas pada pelaku di lapangan (physical perpetrator). Di sisi lain, penerapan UU Lain seperti UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, maupun UU Lingkungan Hidup yang lebih siap untuk menangkap pelaku utama kejahatan kehutanan masih sangat minim. b. Penegakan hukum tidak tegas Kondisi penegakan hukum di Indonesia sedang berada di dalam ambang yang kritis. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sangat rendah karena maraknya praktek mafia hukum (Satgas PMH, 2010). Praktek mafia hukum juga terjadi di sektor kehutanan. Dalam hal ini, ditengarai bahwa modus operansi mafia hukum di sektor kehutanan terdapat sebelum dan setelah ada perkara. Pada saat sebelum ada perkara, modus yang terjadi mulai dari proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, perizinan sampai dengan pada saat eksploitasi sumber daya hutan (pemberian dan pelaksanaan izin). Pada dasarnya dalam seluruh proses tersebut ditemui banyak kasus di mana aparat penegak hukum terlibat dengan cara melindungi para pelaku kejahatan. Hal ini menyebabkan terjadinya pembiaran yang tinggi yang berakibat pada kerusakan hutan yang sangat luas. Pada saat setelah ada perkara, kerap terjadi dalam seluruh proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pengambilan putusan yang rentan terhadap mafia hukum. Hal ini menyebabkan angka tindak pidana kehutanan yang dihukum sangat sedikit dan mayoritas adalah pelaku di lapangan. 5. Tata Kelola (governance) Dalam menilai tata kelola hutan, terdapat empat isu penting yang perlu dinilai yaitu, tenurial, tata ruang, manajemen hutan serta distribusi manfaat dari sektor kehutanan. Seperti telah terlihat dalam pembahasan sebelumnya, dalam konteks Indonesia, ke-empat isu tersebut menjadi penyebab utama (underlying causes) dari terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Pada bagian ini, fokus analisis permasalahan adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang pada dokumen ini akan difokuskan pada (a) koordinasi, (b) transparansi, partisipasi, (c) akuntabilitas, (d) efektivitas dan efisiensi, (e) aspek keadilan (fairness), dan (f ) ketidakhadiran pengelola di lapangan. a. Koordinasi
Terdapat beberapa isu dalam koordinasi, pertama adalah ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah yang juga dipengaruhi oleh penerapan rezim otonomi daerah yang masih pada tahap awal. Gambaran dari ketidakjelasan ini juga terlihat pada tingkat sektoral. Data DitjenPlanologi Kehutanan menyebutkan bahwa luas total APL kurang lebih 55 juta ha, sementara data BPS tentang luas lahan pertanian saat ini kurang lebih 69 juta ha. Dengan demikian, terdapat sekitar 14 juta ha kawasan hutan yang telah berubah menjadi lahan pertanian tanpa diketahui oleh Kementerian Kehutanan. Ketidakjelasan data dan informasi ini telah menjadi setting situasi dalam setiap pengambilan keputusan selama ini sehingga kualitas keputusanya akan sangat rendah. Di kawasan hutan konservasi, menurut data Ditjen Planologi Kehutanan (2008) selama periode 8 tahun (19972005), terdapat pengurangan penutupan kawasan hutan menjadi non-hutan seluas 480.000 ha atau 1,7% dari total luas kawasan konservasi. Walaupun masih terdapat permasalahan sebagaimana tersebut diatas, kawasan konservasi relatif masih utuh dibanding kawasan hutan produksi dan hutan lindung karena memiliki unit manajemen yang jelas dan mandiri. b. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas Absennya transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan juga menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan hutan, untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam proses perizinan serta melakukan pengawasan atas pelanggaran izin yang terjadi. Hal ini mengakibatkan tidak saja data yang lebih akurat tidak tersedia dalam proses pengambilan keputusan, juga penyalahgunaan wewenang para pengambil kebijakan para pejabat yang berwenang dalam suatu proses perizinan tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari masyarakat. Tentang minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat, paling tidak disebabkan oleh dua faktor, yaitu ketidakjelasan di tingkat aturan dan lemahnya kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. c. Aspek Keadilan (Fairness) Ketidakadilan distribusi pendapatan dari sektor kehutanan, baik antara pusat dan daerah maupun terhadap masyarakat di sekitar hutan, memunculkan rasa ketidakadilan antar pihak yang berkepentingan (stakeholders). Rasa ketidakadilan tersebut juga berpengaruh terhadap laju deforestasi dan degradasi hutan karena mereka yang merasa memiliki hak dan belum mendapatkan distribusi manfaat kemudian mengambil manfaat dari hutan. Keadaan tersebut ditambah dengan absennya sistem penegakan hukum yang kuat sehingga berdampak pada meluasnya deforestasi dan degradasi. d. Efektivitas dan efisiensi rendah Secara umum, efektivitas dan efisiensi pengurusan hutan termasuk rendah yang ditandai dengan tidak efektifnya pengawasan sehingga telah terjadi konversi tidak terencana secara besar-besaran di berbagai kawasan hutan yang tidak ditindak ataupun ketidaktepatan dan ketidakefektifan pelaksanaan berbagai program yang direncanakan seperti program GERHAN. Hal ini bersumber dari berbagai faktor lain seperti peraturan perundang-undangan yang menyebabkan proses
pengeluaran izin bersifat rumit dan panjang namun tanpa disertai oleh proses pengawasan yang jelas sehingga menimbulkan birokrasi yang tidak efektif dan berbiaya tinggi. Faktor lain adalah pemanfaatan anggaran yang tidak tepat sasaran serta sumber daya manusia yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif. Hal terakhir juga terkait dengan sistem renumerasi, rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai yang tidak didasarkan atas penilaian kinerja. 6. Faktor Lingkungan yang mendorong Kekuatan pendorong (driving force) merupakan kondisi makro yang mendorong terjadinya kegiatan langsung pada kejadian deforestasi dan degradasi hutan. Termasuk dalam kategori ini adalah: a. belum patuhnya pengambil kebijakan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; b. permintaan (supply) akan kebutuhan yang harus didukung oleh sumber daya hutan, seperti kayu dan sawit pada tingkat global dan nasional melebihi kemampuan produksi dari pengelolaan hutan lestari; c. target pertumbuhan ekonomi; d. Lemahnya leadership. B. Akibat Degradasi Hutan Kerusakan hutan ini telah menimbulkan beberapa dampak negatif yang besar di bumi: 1. Efek Rumah Kaca (Green house effect). Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi mengabsorsi gas Co2. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dan lain-lain) akan menyebabkan kenaikan gas Co2 di atmosfer yang menyelebungi bumi. Gas ini makin lama akan semakin banyak, yang akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, tetapi tidak dapat dilewati oleh pancaran energi panas dari permukaan bumi. Akibatnya energi panas akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh lapisan Co2 tersebut, sehingga terjadi pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Kenaikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah terjadi sejak abad ke 19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemanasan global (global warming). Peningkatan emisi yang tinggi menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang sangat drastis dan membawa dampak berupa kemarau yang berkepanjangan, banjir, badai dan peningkatan permukaan air laut. Hal itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi penduduk dunia yang tinggal di daerah sekitar pantai sampai pegunungan, penurunan kualitas lingkungan global dan ancaman ketersediaan sumber daya alam di masa mendatang. Sesuai dengan Stern Review (2006) deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisi global, dari jumlah tersebut 75% nya berasal dari negara-negara berkembang. Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi sumber penghidupan
masyarakat lokal, fungsi daerah-daerah aliran sungai serta keberadaan keanekaragaman hayati. Hutan berperan penting dalam siklus karbon global dan dapat berfungsi sebagai penghasil emisi (emitter) maupun penyerap emisi (removal). Hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional dengan berbasis (base-year) tahun 2000 menunjukkan bahwa sektor kehutanan merupakan pengemisi GRK (net emitter) tertinggi (Gambar 1). Emisi ini pada umumnya berasal dari deforestasi, degradasi, dan kebakaran hutan termasuk gambut (2nd National Communication, 2009). Berdasarkan base-year 2000, sektor kehutanan menyumbang 48% emisi GRK nasional, paling tinggi dibandingkan sektor lain.
2. Kerusakan Lapisan Ozon Lapisan Ozon (O3) yang menyelimuti bumi berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Di tengah-tengah kerusakan hutan, meningkatnya zat-zat kimia di bumi akan dapat menimbulkan rusaknya lapisan ozon. Kerusakan itu akan menimbulkan lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi, sehingga dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi. 3. Kepunahan Species Hutan di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan rusaknya hutan sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan bahkan akan mengalami kepunahan. Dalam peringatan Hari Keragaman Hayati Sedunia 2007 Departemen Kehutanan mengumumkan bahwa setiap harinya Indonesia kehilangan satu species (punah) dan kehilangan hampir 70% habitat alami pada sepuluh tahun terakhir ini.(http://laurentius.blog.uns.ac.id/2009/08/25/) 4. Merugikan Keuangan Negara. Sebenarnya bila pemerintah mau mengelola hutan dengan lebih baik, jujur dan adil, pendapatan dari sektor kehutanan sangat besar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya tahun 2003 jumlah produksi kayu bulat yang legal (ada ijinnya) adalah sebesar 12 juta
m3/tahun. Padahal kebutuhan konsumsi kayu keseluruhan sebanyak 98 juta m3/tahun. Data ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara pasokan dan permintaan kayu bulat sebesar 86 juta m3. Kesenjangan teramat besar ini dipenuhi dari pencurian kayu (illegal loging). Dari praktek tersebut diperkirakan kerugian yang dialami Indonesia mencapai Rp.30 trilyun/tahun. Hal inilah yang menyebabkan pendapatan sektor kehutanan dianggap masih kecil yang akhirnya mempengaruhi pengembangan program pemerintah untuk masyarakat Indonesia (Laurentius, 2009) Peristiwa banjir yang sering melanda Indonesia akhir-akhir ini, disebutkan bahwa salah satu akar penyebabnya adalah karena rusaknya hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air (catchment area). Hutan yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di waktu musim hujan dan menjamin ketersediaan air di waktu musim kemarau, akibat kerusakan hutan makin hari makin berkurang luasnya. Tempat-tempat untuk meresapnya air hujan (infiltrasi) sangat berkurang, sehingga air hujan yang mengalir di permukaan tanah jumlahnya semakin besar dan mengerosi daerah yang dilaluinya. Limpahannya akan menuju ke tempat yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir. Bencana banjir dapat akan semakin bertambah dan akan berulang apabila hutan semakin mengalami kerusakan yang parah. Tidak hanya akan menimbulkan kerugian materi, tetapi nyawa manusia akan menjadi taruhannya. C. Upaya Penanggulangan Rusaknya hutan di Indonesia telah mendorong berbagai pihak untuk turut serta menyelamatkannya. Namun penyelamatan itu tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama semua pihak dalam rangka menjamin kelangsungan hutan dengan kehidupan liarnya untuk tetap bertahan di kehidupan masa depan. Kondisi hutan yang terus menurun luasannya, tak boleh menjadikan kita terus menyalahkan masa lalu, juga tak boleh menuding-nuding berbagai pihak yang pada akhirnya hanya akan memperpanjang perdebatan, bukan melahirkan tindakan yang konkret untuk menyelamatkan hutan. Butler, 2007 dalam Mahmuddin, 2009, mengemukaan beberapa langkah untuk menyelamatkan hutan hujan dan termasuk ekosistem di seluruh dunia dengan fokus pada 4 hal yaitu: Pendidikan masyarakat, Rehabilitasi hutan hujan tropis, hidup dengan tidak merusak lingkungan, taman perlindungan. 1. Pendidikan masyarakat Di negara-negara hutan hujan termasuk Indonesia, penduduk lokal kadang kala tidak mengerti apa pentingnya hutan hujan. Dengan program pendidikan, mereka dapat belajar bahwa hutan memberikan sumber kunci (seperti air bersih) dan adalah rumah bagi hewan dan tumbuhan yang tak akan ditemukan di bagian lain manapun di dunia. 2. Rehabilitasi Hutan Hujan Walaupun tidak mungkin untuk menanam kembali sebuah hutan hujan, beberapa hutan hujan dapat memulihkan diri setelah ditebangi,
terutama jika mereka mendapat bantuan melalui penanaman pohon kembali. 3. Hidup dengan tidak merusak Lingkungan Di negara-negara hutan hujan, banyak ilmuwan dan organisasi yang bekerja untuk menolong penduduk lokal hidup dengan cara yang tak terlalu merusak lingkungan. Beberapa orang menyebut ide ini dengan sustainable development (perkembangan yang berkepanjangan). Sustainable development memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan dari masyarakat yang pada saat bersamaan juga melindungi lingkungan. Tanpa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di dan di sekitar hutan hujan, akan sangat sulit untuk melindungi taman dan alam liar. Agar taman-taman tersebut bisa berguna, masyarakat lokal harus tertarik pada konservasi. Saat ini Indonesia juga telah berupaya menggunakan sistem kredit karbon melalui penghindaran penggundulan hutan. 4. Taman Perlindungan Cara efektif untuk melindungi hutan hujan adalah melibatkan penduduk asli di manajemen taman. Para penduduk asli ini lebih tahu mengenai hutan dibandingkan dengan siapapun dan memiliki ketertarikan untuk menjaganya dengan aman sebagai ekosistem yang telah memberinya makanan, tempat berlindung, dan air bersih. Taman-taman ini juga dapat membantu perekonomian di negara-negara hutan hujan dengan cara ekoturism. Pada Draft 1 Strategi Nasional REDD+ menyebutkan di tingkat nasional perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang sangat tinggi telah menjadi salah satu isu penting dalam hal perencanaan pembangunan Indonesia. Dampak perubahan iklim yang merusak telah dirasakan dan diperkirakan akan semakin buruk dan akan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan apabila tidak dilakukan antisipasi. Selain adaptasi untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, Indonesia juga menetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk melakukan berbagai mitigasi sebagai upaya yang tidak terpisahkan. Komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sebesar 26% dari business as usual (BAU) dengan upaya sendiri pada tahun 2020 telah disampaikan oleh Kepala Negara dalam dua pertemuan internasional yang strategis, yaitu Sidang G20 di Pittsburgh September 2009 dan COP 15 UNFCCC di Kopenhagen Desember 2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 memuat upaya berbagai bidang dalam menghadapi perubahan iklim ini dengan mengarusutamakan pada kegiatan pembangunan. Namun, khusus pada pencapaian target 26%, telah pula dilakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang khusus terkait dengan mitigasi. Pada bidang kehutanan dan lahan gambut, mitigasi dapat dilakukan melalui penurunan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, serta melalui penyerapan GRK dari peningkatan fungsi hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Di dalam pembahasan internasional hal-hal tersebut masuk ke dalam isu Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus (REDD+) yang dimulai sejak COP 13 di Bali Desember 2007 yang direncanakan akan mulai berjalan setelah tahun 2012.
REDD sendiri pada dasarnya adalah sebuah mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, merupakan salah satu opsi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Stratetegi Nasional REDD+ Indonesia ini dirancang sebagai sebuah arahan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan pragmatis. Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut maka pengurangan emisi akan dilaksanakan melalui strategi pembangunan rendah karbon yang terpadu (hulu sampai hilir) dan komprehensif (multi aspek). Prinsip yang mendasari perumusan strategi ini merupakan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada desentralisasi bertanggung jawab. Pemeliharaan keseimbangan fungsi ekologis. Keadilan antar generasi. Kerangka pelaksanaan pengurangan emisi melalui REDD+ meliputi : 1. Penurunan emisi dari deforestasi, 2. Penurunan emisi dari degradasi hutan, 3. Penguatan peran konservasi, 4. Penguatan peran pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya hutan, dan 5. Peningkatan simpanan karbon melalui restorasi dan rehabilitasi. Kelima tema penting tersebut akan didekati dengan pendekatan pengurangan sumber emisi (source) dan meningkatkan simpanan (sink) karbon. Dengan mengacu kepada berbagai permasalahan yang ada maka strategi nasional REDD+ Indonesia terbagi secara garis besar terdiri dari : 1. Strategi pemenuhan prasyarat dan kondisi pemungkin Strategi pemenuhan prasyarat terdiri dari program pembuatan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan REDD+, program pembentukan metodologi REDD+, dan program pembangunan pembagian manfaat dan tanggung jawab. Strategi pemenuhan kondisi pemungkin terdiri dari program reformasi perencanaan pembangunan sektor penggunaan lahan, program reformasi dasar dan penegakan hukum, program penguatan pemberdayaan ekonomi lokal, program pelibatan pemangku kepentingan, dan program penguatan tata kelola. Penjabaran strategi reformasi pembangunan sektor terdiri dari program reformasi pembangunan sektor kehutanan, pertanian, pertambangan, dan sektor penggunaan lahan lainnya yang berkelanjutan. 2. Strategi reformasi pembangunan beberapa sektor terkait Strategi Pembangunan sektor kehutanan bertumpu pada aspek penurunan sumber emisi GRK dan peningkatan dan perlindungan stok karbon. Beberapa aspek yang dicakup dalam upaya penurunan emisi GRK adalah : Penguatan konservasi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan sektor kehutanan, Penguatan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya hutan, Peningkatan efektivitas penegakan hukum di wilayah KPH, dan Penyempurnaan pengelolaan gambut di kawasan hutan.
Peningkatan dan perlindungan stok karbon (sink) mencakup delapan kegiatan utama, yaitu : Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung (kawasan konservasi,hutan lindung dan kawasan lindung lainnya yang akan ditetapkan kemudian dalam tata ruang wilayah) dalam rangka pemeliharaan simpanan karbon, Peningkatan upaya reboisasi hutan di kawasan hutan terdeforestasi, Pengembangan insentif untuk meningkatkan stok karbon di daerah yang terdegradasi dan lahan bekas kebakaran, Pelaksanaan pengkayaan (enrichment planting) pada kawasan terdegradasi, Pelaksanaan restorasi hutan pada hutan lindung, kawasan konservasi, dan pada kawasan IUPHHK-Restorasi, Peningkatan upaya restorasi lahan gambut yang terdeforestasi dan terdegradasi, Peningkatan upaya rehabilitasi hutan mangrove, dan Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. Strategi pembangunan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim difokuskan pada upaya meminimalisasi dampak negatif dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan itu, strategi pembangunan pertanian juga diarahkan pada upaya intensifikasi dan penerapan teknologi tepat guna yang menghindari pembukaan lahan baru pada kawasan-kawasan yang masih memiliki tutupan hutan sedang sampai baik. Penguatan sektor pertanian dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD+ ini antara lain : Penyempurnaan perencanaan pertanian yang menghindari perluasan pada kawasan yang memiliki tutupan hutan sedang sampai baik serta perlindungan terhadap kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi di kawasan perkebunan; Penerapan intensifikasi pertanian untuk tanaman pangan, varietas unggul dan perkebunan rakyat serta untuk peternakan; (3) pemanfaatan lahan tidur/ bongkor atau lahan terlantar; Penerapan kebijakan land swap pada kawasan APL di tanah mineral dari lahan dengan stock C tinggi (>100 t C/ha) ke lahan dengan stock C rendah (