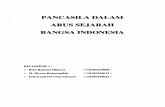Pancasila.docx
-
Upload
yunittamuassassari -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Pancasila.docx
Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, karena Pancasila merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Karena itu, bangsa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
Saat ini kita merasakan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sudah tidak terlihat lagi. Terlebih lagi dikalangan generasi muda saat ini yang tidak lagi akrab dengan istilah Pancasila. Pada masa Orba, Pancasila dijadikan mata pelajaran yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Di luar dunia pendidikan pun ada penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dilaksanakan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).
Pada era Orba, Pancasila selalu menjadi buah bibir, hingga muncul istilah tiada hari tanpa Pancasila dalam kehidupan era Orde Baru itu. Namun, saat ini Pancasila meredup seiring masuknya kita ke era reformasi. Pancasila beserta berbagai perangkat sosialisasinya dipinggirkan karena dinilai telah dijadikan sebagai alat propaganda politik atau bahkan dituding telah diselewengkan menjadi alat legitimasi kekuasaan Orde Baru.
Memang, kita tidak perlu mensakralkan kata Pancasila, tetapi bukan berarti pula kita ingin menghilangkannya. Pada masa Orde Baru, penolakan terhadap Pancasila memang banyak dikaitkan dengan masalah pensakralan ini sehingga dituding nilainya lebih tinggi daripada agama. Padahal, upaya mensosialisasikan Pancasila pada masa Orde Baru tidak lebih dalam rangka bagaimana istilah ini melekat dalam hati dan pikiran kita.
Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, karena Pancasila merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Karena itu, bangsa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
Jika Pancasila tidak segera kembali menjadi roh bangsa Indonesia, dikhawatirkan akan muncul ideologi alternatif yang akan djadikan landasan perjuangan dan pembenaran bagi gerakan-gerakan radikal. Karena itu, bagi bangsa Indonesia tidak ada pilihan lain selain mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar keragaman bangsa dapat dijabarkan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal I
Pertama, kita masih ingat kasus eksekusi makam di Koja, Tanjung Priok Jakarta. Dalam kasus tersebut para Satpol PP DKI Jakarta melakukan kekerasan terhadap masyarakat setempat. Korban berjatuhan dan masyarakat membalas dengan kekerasan pula. Dua Satpol PP tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Puluhan mobil polisi dan Satpol PP dibakar. Kantor Pelindo dirusak dan barang-barangnya dijarah. Kemudian kita masih ingat pula bagaimana polisi menyerbu Kampus Unas di Makasar dengan brutal dan dibalas oleh mahasiswa dengan mengeroyok polisi yang sedang bertugas dan perusakan fasilitas umum kota. Kasus kekerasan ini masih dapat diperpanjang, seperti kasus penganiayaan terhadap aksi damai di Monas-Jakarta yang terdiri atas perempuan, anak-anak, konflik kekerasan di Poso, konflik antar etnis di Kalimantan dan masih banyak yang lain. Kasus di atas menggambarkan sikap yang arogan, anarkhis, memaksakan kehendak, mengabaikan dialog dan musyawarah. Padahal nilai-nilai yang kita anut dalam Pancasila mengajarkan bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.Kedua, kasus korupsi yang pada era reformasi ini justru semakin marak melibatkan banyak pihak baik eksekutif, legislatif dan iudikatif. Dalam kasus Gayus Tambunan misalnya polisi terlibat dalam memanipulasi data di BAP, jaksa terlibat dengan meringankan tuntutan dan hakim terlibat dengan membebaskan Gayus Tambunan (kemudian ditangkap lagi di Singapura). Kita tercengang dengan kasus ini, Gayus Tambunan yang PNS golongan III/a usia 30 tahun mampu memiliki rumah seharga Rp 3 milyar. Mobilnya 3, salah satunya mobil mewah Toyota Alphard. Kemudian tabungannya di Bank Rp 25 milyar. Pertanyaan kita adalah di Dirjen Pajak itu apa hanya Gayus yang korupsi. Kasus korupsi pasa era reformasi ini begitu banyak. Sebut saja beberapa contoh (yang sudah divonis pengadilan) seperti kasus pembelian helikopter yang melibatkan Abdullah Pateh, kasus korupsi di KPU yang melibatkan Mulyana W. Kusuma, Rusandi Kanta Prawira, Achmad Rojali dan Nazaruddin Sjamsudin, kasus suap terhadap Hakim Agung di MA oleh Harini Wiyoso (mantan hakim), kasus Said Agil Husin Al Munawar berkaitan dengan Dana Abadi Umat (DAU), kasus Bulog yang melibatkan Rahardi Ramelan, kasus Theodorus Fransiscus Toemion-Ketua BKPM, kasus pungli dokumen keimigrasian yang melibatkan mantan Kapolri yang menjadi Dubes RI di Malaysia. Kemudian kasus suap yang diterima para anggota DPR RI seperti Al Amin Nasution, Hamka Yandu, Anthony Zeibra Abidin, dan terakhir (masih dalam proses) belasan anggota DPR RI yang menerimatravellers chequedari Miranda Gultom. Dan jangan lupa kasus korupsi BLBI pada awal reformasi (1998) meliputi dana Rp 150 trilyun sebagai extraordinary crime yang tidak pernah tuntas sampai sekarang.. Kasus-kasus korupsi di atas melibatkan beragam profesi dari pejabat jaksa, hakim, polisi, pengusaha, wakil rakyat, aktivis LSM, bahkan professor dari perguruan tinggi. Kasus-kasus korupsi ini memperlihatkan perilaku manusia Indonesia yang tidak bermoral, tidak tahu malu, tidak bertanggung jawab, kepengin cepat kaya dan memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Korupsi telah mendorong pembusukan kultural dan hancurnya mental spiritual bangsa. Padahal nilai-nilai Pancasila mengajarkan tentang perbuatan luhur, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka bekerja keras dan tidak merugikan kepentingan umum (masalah kasus korupsi lebih lanjut baca Deni Setya Wati, 2008)Ketiga, dalam kehidupan berdemokrasi Pilkada masih diwarnai dengan konflik horizontal antar pendukung,money politic, sementara tingkat partisipasi politik yang rendah menunjukkan proses pendidikan politik lewat Pilkada tidak berhasil. Rakyat apatis pada proses atau manfaat Pilkada atau mungkin mereka hanya mau mencoblos kalau dibayar. Rekrutmen politik calon yang marak dipenuhi artis juga memperlihatkan popularitas lebih penting dari kapabilitas. Hal ini menunjukkan semangat reformasi yang ingin mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis telah gagal. Kemudian biaya perseorangan bagi para calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang sangat tinggi, membuat banyak orang curiga bagaimana mereka dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Godaan korupsi terbentang di masa mendatang. Kehidupan berdemokrasi kita masih jauh dari harapan, manusia Indonesia belum siap berbeda pendapat, belum siap dinyatakan kalah, suara atau dukungan diperjual-belikan dan berbiaya mahal yang mengarah kepada tindakan korupsi. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada (sekitar 60 %) memperlihatkan bahwa manusia Indonesia belum memiliki kesadaran berdemokrasi. Mereka hanya berpartisipasi setelah dibayar. Ini berarti mereka bukan merupakancivilized society sebagai bagian penting darigood governance.Keempat, potret diri manusia Indonesia yang buram juga tampak pada dunia pendidikan kita. Kasus di Jakarta, beberapa Kepala Sekolah sepakat untuk melonggarkan pengawasan pada para murid yang mengikuti Ujian Nasional. Mereka mengetahui para muridnya menerima bocoran kunci jawaban lewat SMS. Tetapi mereka membiarkan kecurangan tersebut berlangsung. Untuk apa? Tentu saja agar sekolah mereka meraih prestasi dengan prosentase kelulusan yang tinggi dan ini menyangkut reputasi. Sementara itu di perguruan tinggi para mahasiswa yang ingin cepat menyelesaikan kuliahnya, membuatkan atau membeli skripsi, tesis bahkan disertasi dengan harga Rp 5 juta Rp 15 juta. Anehnya pembuat karya tulis ilmiah ini memasang iklan di surat kabar, di toko buku atau di pinggir-pinggir jalan kampus. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural juga beramai-ramai mengambil S2, bukan untuk menambah ilmu tapi untuk kemudahan promosi jabatan atau sekedar menambah gengsi sosial mereka. Kadang-kadang tidak jelas mereka kuliah dimana atau berapa kali mereka ikut kuliah. Dalam kasus di atas, sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi mencerminkan semangat perubahan sebagai agent of change. Padahal pelaku pendidikan harus melakukan transfer of knowledge dalam rangka perubahan pengetahuan, transfer of culture untuk perubahan budaya dan transfer of attitude untuk perubahan perilaku. (A. Kadarmanta, 2008) Dari kasus di atas, tampak bahwa manusia Indonesia itu mengejar prestise bukan prestasi dan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan (the end of justifies the mean). Keempat hal tersebut di atas, mengingatkan kita kepada pidato kebudayaan budayawan Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki Jakarta tanggal 6 April 1977. Dalam pidatonya Mochtar Lubis menyatakan bahwa manusia Indonesia itu berciri munafik, berpura-pura, lain di muka lain di belakang. Ciri yang lain tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan atau keputusan yang telah diambil. Ciri berikutnya bermental feodal, yang di atas mengedepankan pangkat jabatan dan kekuasaan; yang di bawah bersikap rendah diri . Kemudian manusia Indonesia itu suka sesuatu yang berbau takhayul, menyimpan jimat dan suka mendatangi tempat yang dianggap keramat. Ciri yang lain adalah memiliki karakter yang kurang kuat, mudah goyah dan tidak optimis melihat masa depan. Manusia Indonesia juga tidak suka bekerja keras, cenderung boros dan kepengin cepat kaya. Tentu saja kita tidak bisa membenarkan stereotipe atau prototipe di atas. Kita tidak bisa melakukan generalisasi ciri manusia Indoneia seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa menolak kenyataan cukup banyak orang Indonesia berciri seperti dikemukakan Mochtar Lubis. Bagi kita yang penting bisa mengambil manfaat dari pemikiran atau penilaian kritis tersebut. Kita perlu melakukan intropeksi diri. Seperti apakah wajah kita itu sebenarnya? Dengan demikian kita bisa membenahi diri kita dan melakukan nation and character building. Proses nation and character building adalah proses pendidikan. Bagaimana kita mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang berkarakter atau berkepribadian berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat. Manusia yang berkarakter adalah manusia yang berkeutamaan yang tampak dalam perbuatan atau tindakannya. (Doni Koesoema.A, 2007)
SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Sosok manusia ideal Indonesia tentunya berperilaku seperti tertuang dalam 45 butir nilai luhur Pancasila yang kita yakini sebagai nilai-nilai yang pernah tumbuh dan berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.Pancasila adalah suatu filsafat yang merupakan fundamen pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. (Prof. Drs. Sunaryo Wreksosuhardjo, 2008). Tidak pernah ada suatu bangsa hidup terpisah dari akar tradisinya sebagaimana tidak ada pula suatu bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal yang dimiliki. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar acap kali menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kekeringan atau kekerdilan identitas. Namun demikian, terlalu terobsesi dengan budaya luar dan pada saat yang sama mencampakkan tradisi dan nilai-nilai baik lokal berpeluang menjadikan bangsa tersebut kehilangan identitas. Akibatnya bangsa tersebut tidak pernah menjadi dirinya sendiri. (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008) Sebagai sebuah konsensus nasional, Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai keindonesiaan yang majemuk dan nilai-nilai yang bersifat universal. Universalitas Pancasila dapat dilihat pada semangat ketuhanan (sila pertama); kemanusiaan, keadilan, dan keadaban (sila kedua); dan keadilan sosial (sila kelima) dan sekaligus keindonesiaan (persatuan Indonesia) dan semangat gotong-royong (sila keempat). Sayangnya, nilai-nilai ideal Pancasila telah tereduksi dan dikebiri oleh penguasa Orde Baru. Sepanjang sejarah Orde Baru, Pancasila telah dijadikan alat untuk membungkam suara kedaulatan rakyat dengan atas nama pembangunan nasional. Orde baru juga telah melakukan penyeragaman tafsir atas Pancasila yang dibakukan dan disebarluaskan melalui penataran dan pendidikan di sekolah dan peguruan tinggi. Ironisnya, pada saat yang sama Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam Eka Prasetya Pancakarsa. Tindakan represif, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan hukum di kalangan pejabat pemerintahan adalah bukti telanjang dari penyalahgunaan Pancasila yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Dampak langsung dari manipulasi atas dasar negara Pancasila adalah sikap antipati (fobia) atas Pancasila ketika rezim otoriter Orde Baru tumbang. Dewasa ini kita tengah berada pada era reformasi tetapi reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Sebagai sebuah karya luhur anak bangsa, Pancasila selayaknya ditempatkan secara terhormat dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Posisinya sebagai panduan nilai dan pedoman bersama (common platform) untuk mewujudkan tujuan atau kesejahteraan bersama bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa digantikan oleh pandangan-pandangan sektarian mana pun, yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.REVITALISASI PANCASILAGelombang demokrasi dalam bentuk tuntutan reformasi di negara-negara tidak demokrasi, termasuk Indonesia pada era Orde Baru, menjadi ancaman bagi eksistensi ideologi nasional seperti Pancasila. Namun demikian, globalisasi juga melahirkan paradoksnya sendiri: di satu sisi globalisasi demokrasi mengakibatkan kebangkrutan banyak paham ideologi, di sisi yang lain juga mendorong bangkitnya nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dangkal dan sempit semacamethnonationalism, atau bahkantribalism. Gejala ini yang terus mengancam integrasi negara-negara majemuk dari sudut etnis, sosiokultural, dan agama seperti Indonesia. Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia bersamaan dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik membuat Pancasila seolah kehilangan relevansinya. Sementara itu proses desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Apabila tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin menumbuhkan sentimenlocal-nationalismyang dapat tumpang tindih denganethnonationalism. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun akibat langsung dari proses desentralisasi akan makin kehilangan posisi sentralnya ( Azyumardi Azra, 2008 ). Mempertimbangkan posisi krusial Pancasila di atas, maka perlu dilakukan revitalisasi makna, peran, dan posisi Pancasila bagi masa depan Indonesia sebagai negara modern. Perlunya revitalisasi Pancasila karena didasari keyakinan bahwa Pancasila merupakan simpul nasional yang paling tepat bagi Indonesia yang majemuk. Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional. Empat pemimpin nasional pasca Soeharto sejak dari Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum berhasil membawa Pancasila ke dalam wacana dan kesadaran publik. Ada kesan traumatik untuk kembali membicarakan Pancasila. Kini, sudah waktunya para elite dan pemimpin nasional memberikan perhatian khusus kepada ideologi pemersatu ini jika kita betul-betul peduli padanation and character buildingdan integrasi bangsa Indonesia. Sementara itu Prof. Dr. Muladi, SH, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI menyatakan bahwa salah satuside effectruntuhnya Orde Baru yang sangat menyedihkan adalah berkembangnya sikapskeptisterhadap ideologi bangsa Kegamangan terhadap ideologi Pancasila tersebut menyurutkan makna ideologi, baik sebagai perekat persatuan bangsa maupun sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan bangsa lain yang akan berhubungan dengan bangsa Indonesia (the predictability function of ideology).Sebagai bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita dan tujuan seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni adanya kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kebhinnekaan budaya masyarakat Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus diterima sebagai kekayaan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Nusantara ini, dengan keanekaragaman budayanya masing-masing, sejak dahulu telah saling berhubungan dan berinteraksi. Berdasarkan kesamaan visi mengenai masa depan, maka para pemuda dari suku-suku bangsa tersebut pada tahun 1928 telah mengikrarkan sumpah untuk menjadi satu bangsa dengan menggunakan bahasa persatuan dan bersama-sama hidup di satu tanah air. Dari peristiwa ini terlihat bahwa kebhinnekaan budaya bukan menjadi halangan untuk mewujudkan persatuan bangsa.Justru budaya yang beraneka ragam tersebut mampu berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya secara selaras dan serasi. Oleh sebab itulah perlu selalu disadari dan dipahami bersama bahwa bangsa Indonesia ini memang dibentuk dari suku-suku bangsa yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Maka langkah utama yang perlu ditempuh dalam rangka membangun kehidupan baru bagi bangsa Indonesia di masa depan adalah menggunakan salah satu asas dalam konsepsi kemandirian lokal, yaitu pendekatan kebudayaan, sebagai bagian utama dari strategi pembangunan masyarakat dan bangsa. Implementasi pendekatan kebudayaan dalam pembangunan bangsa diyakini akan dapat menumbuhkan kebanggaan pada setiap anak bangsa terhadap diri dan budayanya dan pada gilirannya akan menumbuhkan pula toleransi dan pengertian akan keberadaan budaya lainnya. Hal ini merupakan faktor utama perekat persatuan bangsa.Pada proses reformasi, penyaluran aspirasi politik masyarakat telah dapat diakomodasikan dalam sistem multi partai. Pada satu sisi, hal ini dapat mencerminkan perwujudan demokrasi, akan tetapi pada sisi lain dapat mengarah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut pada akhirnya dapat diselewengkan dengan pembentukan kekuatan-kekuatan dengan memobilisasi kekuatan berdasarkan asas masing-masing. Hal ini dapat bermuara pada berkembangnya primordialisme sempit berdasarkan agama, etnis ataupun ras dan aspek kedaerahan lainnya.Revitalisasi Pancasila semakin terasa penting kalau diingat kita tengah gigih menerapkan prinsip-prinsipgood governance,dimana tiga aktor yaitu pemerintah (state), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) harus bersinergi secara konstruktif mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Antara lain terwujud dalam bentuk pelayanan publik (public services) yang optimal. Dalam kaitannya dengan ancaman atau pengaruh globalisasi harus dihadapi dengan sikap mental dan karakter yang kuat sebagai jatidiri bangsa Indonesia. Akhirnya revitalisasi Pancasila menjadi penting karena kita masih menghadapi ancaman disintegrasi nasional dengan semangat separatisme dari Daerah yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah Pusat.Kita jangan sampai tidak mengenal diri kita sendiri dan tidak mengenal nilai-nilai hakiki dan luhur yang telah merupakan konsensus nasional menjadi falsafah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu Pancasila. Seperti kata Socrates (470-399 SM)kenalilah dirimu sendiri.