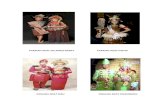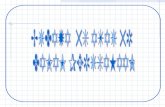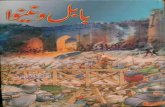OMSK.doc
-
Upload
siti-muawanah -
Category
Documents
-
view
10 -
download
4
Transcript of OMSK.doc
BAB IPENDAHULUAN1. 1 Latar Belakang
Otitis media supuratif kronis (OMSK) ialah infeksi kronik di telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan sekret yang keluar dari telinga tengah terus-menerus atau hilang timbul. Sekret mungkin encer atau kental, bening atau berupa nanah. OMSK didalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah congek, teleran atau telinga berair. Kebanyakan penderita OMSK menganggap penyakit ini merupakan penyakit yang biasa yang nantinya akan sembuh sendiri. Penyakit ini umumnya tidak memberikan rasa sakit kecuali apabila sudah terjadi komplikasi.1Otitis media supuratif kronik merupakan penyakit infeksi telinga yang memiliki prevalensi tinggi dan menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Dinegara berkembang dan negara maju prevalensi OMSK berkisar antara 1 46% , dengan prevalensi tertinggi terjadi pada populasi di Eskimo (12 46%) dan prevalensi terendah pada populasi di Amerika dan Inggris (kurang dari 1%). Di Indonesia menurut Survei Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran Depkes 1993 1996 prevalensi OMSK sekitar 3,1% populasi. OMSK hingga saat ini masih sering dijumpai di Indonesia.2
Penyakit ini sangat menggangu dan sering menyulitkan dokter maupun pasiennya sendiri. Perjalanan penyakit yang panjang, terputusnya terapi, terlambatnya pengobatan ke spesialis THT dan sosioekonomi yang rendah membuat penatalaksanaan penyakit ini tetap menjadi problem di bidang THT.31.2 TujuanAdapun tujuan penulisan laporan kasus ini adalah :
1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan tinjauan kepustakaan mengenai hubungan perjalanan penyakit OMSK terhadap terjadinya kolesteatoma
2. Untuk memenuhi tugas kepaniteraan klinik senior di Laboratorium Ilmu Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Anatomi Telinga Tengah
Telinga tengah terdiri dari:
1. Membran timpani
2. Kavum timpani
3. Prosesus mastoideus
4. Tuba eustachius.
2.1.1. Membran Timpani4,5
Membran timpani dibentuk dari dinding lateral kavum timpani dan memisahkan liang telinga luar dari kavum timpani. Membran ini panjang vertikal rata-rata 9-10 mm dan diameter antero-posterior kira-kira 8-9 mm, ketebalannya rata-rata 0,1 mm. letak membran timpani tidak tegak lurus terhadap liang telinga akan tetapi miring yang arahnya dari belakang luar ke muka dalam dan membuat sudut 450 dari dataran sagital dan horizontal. Membran timpani merupakan kerucut, dimana bagian puncak dari kerucut menonjol ke arah kavum timpani, puncak ini dinamakan umbo. Dari umbo ke muka bawah tampak refleks cahaya (cone of light).
Membran timpani mempunyai tiga lapisan yaitu:
1. Stratum kutanem (lapisan epitel) berasal dari liang telinga
2. Stratum mukosum (lapisan mukosa) berasal dari kavum timpani
3. Stratum fibrosum (lamina propria) yang letaknya antara stratumkutaneum dan mukosum.
Lamina propria yang terdiri dari dua lapisan anyaman penyambung elastic yaitu:
1. Bagian dalam sirkuler
2. Bagian luar radier.
Secara anatomi membran timpani dibagi dalam dua bagian:
1. Pars Tensa
Merupakan bagian terbesar dari membran timpani suatu permukaan yang tegang dan bergetar sekeliling menebal dan melekat pada anulus fibrosus pada sulkus timpanikus bagian tulang dari tulang temporal.
2. Pars Flasida atau membran Sharpnell, letaknya dibagian atas muka dan lebih tipis dari pars tensa dan pars flasida dibatasi oleh 2 lipatan yaitu:
1. Plika maleolaris anterior (lipatan muka)
2. Plika maleolaris posterior ( lipatan belakang).
Membran timpani terletak dalam saluran yang dibentuk oleh tulang dinamakan sulkus timpanikus. Akan tetapi bagian atas muka tidak terdapat sulkus ini dan bagian ini disebut insisura timpanika (Rivini). Permukaan luar dari membran timpani disarafi oleh cabang n. aurikulo temporalis dari nervus mandibula dan nervus vagus. Permukaan dalam disarafi oleh n. timpani cabang dari nervus glosofaringeal.
Aliran darah membran timpani berasal dari permukaan luar dan dalam. Pembuluh-pembuluh epidermal berasal dari aurikula yang dalam cabang dari arteri maksilaris interna. Permukaan mukosa telinga tengah didarahi oleh timpani anterior cabang dari arteri maksilaris interna dan oleh stylomastoid cabang dari arteri aurikula posterior.
2.1.2. Kavum Timpani6
Kavum timpani terletak di dalam pars petrosa dari tulang temporal, bentuknya bikonkaf, atau seperti kotak korek api. Diameter anteroposterior atau vertikal 15mm, sedangkan diameter tranversal 2 6 mm. kavum timpani mempunyai 6 dinding yaitu:
Atap kavum timpani
Dibentuk oleh lempengan tulang yang tipis disebut tegmen timpani. Tegmen timpani memisahkan telinga tengah dari fosa kranial dan lobus temporalis dari otak.
Lantai kavum timpani
Dibentuk oleh tulang tipis memisahkan lantai kavum timpani dari bulbus jugularis, atau tidak ada tulang sama sekali hingga infeksi dari kavum timpani mudah merembet ke bulbus vena jugularis.
Dinding medial
Berturut-turut dari atas ke bawah kanalis semisirkularis horizontal, kanalis fasialis, tingkap lonjong (oval window), tingkap bundar (round window) dan promontorium. Dinding posterior
Dinding posterior dekat keatap mempunyai satu saluran disebut aditus ad antrum, yang menghubungkan kavum timpani dengan antrum mastoid melalui epitimpanum. Di bawah aditus terdapat lekukan kecil yang disebut fosa inkudis yang merupakan suatu tempat prosesusbrevis dari inkus dan melekat pada serat-serat ligamen. Dibawah fosainkudia dan di medial dari korda timpani adalah piramid, tempat terdapatnya tendon muskulus stapedius, tendon yang berjalan keatas dan masuk kedalam stapes. Diantara piramid dan anulus timpanikus adalah resesus fasialis.
Dinding anterior
Dinding anterior ini terutama berperan sebagai muara tuba eustachius. Tuba ini berhubungan dengan nasofaring dan mempunyai dua fungsi. Pertama, menyeimbangkan tekanan membrane timpani pada sisi sebelah dalam, kedua sebagai drainase sekresi dari telinga tengah, termasuk sel-sel udara mastoid. Diatas tuba terdapat sebuah saluran yang berisi otot tensor timpani. Di bawah tuba, dinding anterior biasanya tipis dimana ini merupakan dinding posterior dari saluran karotis.
Dinding lateral
Dinding lateral kavum timpani adalah bagian tulang dan membran. Bagian tulang berada diatas dan bawah membran timpani.
2.1.3 Prosesus Mastoideus6Antrum mastoid adalah sinus yang berisi udara didalam pars petrosa tulang temporal. Berhubungan dengan telinga tengah melalui aditus dan mempunyai sel-sel udara mastoid yang berasal dari dinding-dindingnya.
Proses mastoid sangat penting untuk sistem pneumatisasi telinga. Pneumatisasi didefinisikan sebagai suatu proses pembentukan atau perkembangan rongga-rongga udara di dalam tulang temporal, dan sel-sel udara yang terdapat di dalam mastoid adalah sebagian dari sistem pneumatisasi yang meliputi banyak bagian dari tulang temporal. Sel-sel prosesus mastoid yang mengandung udara berhubungan dengan udara didalam telinga tengah.
Sellulae mastoideus seluruhnya berhubungan dengan kavum timpani. Dekat antrum sel-selnya kecil semakin ke perifer sel-selnya bertambah besar. Oleh karena itu bila ada radang pada sel-sel mastoid, drainase tidak begitu baik sehingga mudah terjadi radang pada mastoid (mastoiditis).2.1.4 Tuba Eustachius4
Tuba eustachius disebut juga tuba auditory atau tuba faringotimpani bentuknya seperti huruf S. Tuba ini merupakan saluran yang menghubungkan kavum timpani dengan nasofaring. Pada orang dewasa panjang tuba sekitar 36 mm berjalan kebawah, depan dan medial dari telinga tengah 13 mm dan pada anak dibawah 9 bulan adalah 17,5 mm.
Tuba terdiri dari 2 bagian yaitu:
1. Bagian tulang terdapat pada bagian belakang dan pendek (1/3 bagian)
2. bagian tulang rawan terdapat pada bagian depan dan panjang (2/3 bagian)
Bagian tulang sebelah lateral dari dinding depan kavum timpani dan bagian tulang rawan medial masuk ke nasofaring. Bagian tulang rawan ini berjalan ke arah posterior, superior dan medial sepanjang 2/3 bagian keseluruhanpanjang tuba (4 cm), kemudian bersatu dengan bagian tulang atau timpani. Tempat pertemuan itu merupakan bagian yang sempit yang disebut ismus. Bagian tulang tetap terbuka, sedangkan bagian tulang rawan selalu tertutup dan berakhir pada dinding lateral nasofaring. Pada orang dewasa muara tuba pada bagian timpani terletak kira-kira 2 2,5 cm, lebih tinggi dibanding dengan ujungnya nasofaring. Pada anak-anak, tuba pendek, lebar dan letaknya mendatar maka infeksi mudah menjalar dari nasofaring ke telinga tengah. Tuba dilapisi oleh mukosa saluran nafas yang berisi sel-sel goblet dan kelenjar mucus dan memiliki lapisan epitel bersilia didasarnya. Epitel tuba terdiri dari epitel silinder berlapis dengan sel selinder. Disini terdapat silia dengan pergerakannya ke arah faring. Sekitar ostium tuba terdapat jaringan limfosit yang dinamakan tonsil tuba. Otot yang berhubungan dengan tuba eustachius yaitu:
1. M. Tensor veli palatini2. M Levator veli Paltini3. M. salphingo faringeus4. M. tensor timpani
Fungsi tuba eustachius sebagai ventilasi telinga yaitu mempertahankan keseimbangan tekanan udara di dalam kavum timpani dengan tekanan udara luar, drainase sekret dari kavum timpani ke nasofaring dan menghalangi masuknya sekret dari nasofaring ke kavum timpani.
2.2 OTITIS MEDIA SUPURATIF FRONIK
2.2.1 Definisi
Gambaran dasar yang sering pada semua kasus OMSK adalah dijumpainya membran timpani yang tidak intak. OMSK adalah peradangan kronis dari telinga tengah dimana ditemukan membran timpani tidak intak (perforasi) dan adanya sekret (otorea) purulen yang hilang timbul dan berlangsung lebih dari 2 bulan.62.2.2 Etiologi
Terjadinya OMSK hampir selalu dimulai dengan otitis berulang pada anak, jarang dimulai setelah dewasa. Faktor infeksi biasanya berasal dari nasofaring (adenoiditis, tonsilitis, rinitis dan sinusitis), mencapai telinga tengah melalui tuba Eustachius.6
Penyebab OMSK antara lain:61. Lingkungan
Hubungan penderita OMSK dan faktor sosial ekonomi belum jelas, tetapi mempunyai hubungan erat antara penderita OMSK dan sosioekonomi, dimana kelompok sosioekonomi rendah memiliki insiden yang lebih tinggi. Tetapi sudah hampir dipastiakn hal ini berhubungan dengan kesehatan secara umum, diet, tempat tinggal yang padat.
2. Genetik
Faktor genetik masih diperdebatkan sampai saat ini, terutama apakah insiden OMSK berhubungan dengan luasnya sel mastoid yang dikaitkan sebagai faktor genetik. Sistem sel-sel udara mastoid lebih kecil pada penderita otitis media, tetapi belum diketahui apakah hal ini primer atau sekunder.
3. Otitis Media sebelumnya
Secara umum dikatakan otitis media kronis merupakan kelanjutan dari otitis media akut atau otitis media dengan efusi, tetapi tidak diketahui faktor apa yang menyebabkan satu telinga dan bukan yang lainnya berkembang menjadi keadaan kronis
4. Infeksi
Organisme yang terutama dijumpai adalah Gram- negatif, flora tipe- usus, dan beberapa organisme lainnya. Bakteri aerob yang sering ditemukan yaitu Pseudomonas aeruginosa, Stafilokokus aureus dan proteus.
5. Infeksi saluran nafas atas
Banyak penderita mengeluh sekret telinga sesudah terjadi infeksi saluran nafas atas. Infeksi virus dapat mempengaruhi mukosa telinga tengah menyebabkanmenurunya daya tahan tubuh terhadap organisme yang secara normal berada dalam telinga tengah sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri.
6. Autoimun
Penderita dengan penyakit autoimun akan memiliki insiden lebih besar terhadap otitis media kronis.
7. Alergi
Penderita alergi mempunyai insiden otitis media kronis yang lebih tinggi dibanding yang bukan alergi. Yang menarik adalah dijumpainya sebagian penderita yang alergi terhadap antibiotik tetes telinga atau bakteria atau toksin-toksinnya, namun hal ini belum terbukti kemungkinannya.
8. Gangguan fungsi tuba eustachius
Pada telinga yang inaktif berbagai metode telah digunakan untuk mengevaluasi fungsi tuba eustachius dan umumnya menyatakan bahwa tuba tidak mungkin mengembalikan tekanan negatif menjadi normal.
Beberapa faktor yang menyebabkan perforasi membran timpani menetap pada OMSK:6 Infeksi yang menetap pada telinga tengah mastoid yang mengakibatkan produksi sekret telingan purulen berlanjut.
Berlanjutnya obstruksi tuba eustachius yang mengurangi penutupan spontan pada perforasi
Beberapa perforasi yang besar mengalami penutupan spontan melalui mekanisme migrasi epitel.
Pada pinggir perforasi dari epitel skuamosa dapat mengalami pertumbuhan yang cepat diatas sisi medial dari membran timpani. Proses ini juga mencegah penutupan spontan dari perforasi.
Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit infeksi telinga tengah purulenta menjadi kronik majemuk, antara lain:61. Gangguan fungsi tuba eustachius yang kronik atau berulang.
a. infeksi hidung dan tenggorokan yang kronis atau berulang
b. obstruksi anatomik tuba Eustachius parsial atau total
2. Perforasi membran timpani yang menetap
3. Terjadinya metaplasia skuamosa atau perubahan patologik menetap lainnya pada telinga tengah
4. Obstruksi menetap terhadap aerasi telinga atau rongga mastoid. Hal ini dapat disebabkan oleh jaringan parut, penebalan mukosa, polip, jaringan granulasi atau timpanisklerosis
5. Terdapat daerah-daerah dengan sekuester atau osteomilitis persisten di mastoid.
6. Faktor-faktor konstitusi dasar seperti alergi, kelemahan umum atau perubahan mekanisme pertahanan tubuh.
Faktor predisposisi pada OMSK:6 Infeksi saluran nafas atas yang berulang, alergi hidung, rhinosinusitis kronis.
Pembesaran adenoid pada anak, tonsilitis kronik
Mandi dan berenang di kolam renang atau sungai
Mengkorek telinga dengan alat yang terkontaminasi
Malnutrisi, diabetes melitus dan Koch pulmonal
Otitis media purulenta akut yang berulang
2.2.3 Klasifikasi
Letak perforasi di membran timpani penting untuk menentukan tipe atau jenis OMSK. Perforasi membran timpani dapat ditemukan di daerah sentral, marginal atau atik. Oleh karena itu disebut perforasi sentral, marginal atau atik.1
Pada perforasi sentral, perforasi terdapat di pars tensa, sedangkan di seluruh tepi perforasi masih ada sisa membran timpani. Pada perforasi marginal sebagian tepi perforasi langsung berhubungan dengan anulus atau sulkus timpanikum. Perforasi atik ialah perforasi yang terletak di pars flaksida.1OMSK dapat dibagi atas dua jenis, yaitu :
OMSK tipe aman (tipe mukosa atau tipe benign)
Proses peradangan pada OMSK tipe aman terbatas pada mukosa saja, dan biasanya tidak mengenai tulang. Perforasi terletak di sentral. Umumnya OMSK tipe aman jarang menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Pada OMSK tipe aman tidak terdapat kolesteatoma.1 OMSK tipe bahaya (tipe tulang atau tipe maligna).
Yang dimaksud dengan OMSK tipe maligna ialah OMSK yang disertai dengan kolesteatoma. OMSK ini dikenal juga dengan OMSK tipe bahaya atau tipe tulang. Perforasi pada OMSK tipe bahaya letaknya marginal atau atik, kadang-kadang terdapat juga kolesteatoma pada OMSK dengan perforasi subtotal. Sebagian besar komplikasi yang berbahaya atau fatal timbul pada OMSK tipe maligna.1Berdasarkan sekret yang keluar dari kavum timpani dikenal juga OMSK aktif dan OMSK tenang.11. OMSK aktif
Pada jenis ini terdapat sekret pada telinga dan tuli. Biasanya didahului oleh perluasan infeksi saluran nafas atas melalui tuba eustachius atau setelah berenang dimana kuman masuk melalui liang telinga luar. Sekret bervariasi dari mukoid sampai purulen. Jarang ditemukan polip yang besar pada liang telinga luas. Perluasan infeksi ke sel-sel mastoid mengakibatkan penyebaran yang luas dan penyakit mukosa yang menetap harus dicurigai bila tindakan konservatif gagal untuk mengontrol infeksi atau jika granulasi pada mesotimpanum dengan atau tanpa migrasi sekunder kulit, dimana kadang-kadang adanya sekret yang berpulsasi diatas kuadran posterosuperior.1,62. OMSK tenang
Pada pemeriksaan telinga dijumpai perforasi total yang kering dengan mukosa telinga tengah yang pucat. Gejala ini dijumpai berupa tuli konduktif ringan. Gejala lain yang dijumpai seperti vertigo, tinitus atau suatu rasa penuh dalam telinga.1,6 Kolesteatoma1Kolesteatoma adalah suatu kista epiterial yang berisi deskuamasi epitel (keratin). Deskuamasi terbentuk terus lalu menumpuk sehingga kolesteatoma bertambah besar.
Istilah kolesteatoma mulai diperkenalkan oleh Johanes Muller pada tahun 1838 karena disangka kolesteatoma merupakan suatu tumor, yang ternyata bukan. Beberapa istilah lain yang diperkenalkan oleh para ahli antara lain adalah keratoma (Schucknecht), squamous epiteliosis (Birrel, 1958), kolesteatosis (Birrel, 1958), epidermoid kolesteatoma (Friedman, 1959), kista epidermoid (Ferlito, 1970), epidermosis (Sumarkin, 1988).
Kolesteatoma Patogenesis kolesteatom1Banyak teori dikemukakan oleh para ahli tentang patogenesis kolesteatoma, antara lain adalah teori invaginasi, teori migrasi, teori metaplasi dan teori implantasi.
Teori tersebut akan lebih mudah dipahami bila diperhatikan definisi kolesteatoma menurut Gray (1964) yang mengatakan; kolesteatoma adalah epitel kulit yang berada pada tempat yang salah, atau menurut pemahaman penulis, kolesteatoma dapat terjadi oleh karena adanya epitel kulit terperangkap.
Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh epitel kulit (keratinizing stratified squamosa epitelium) pada tubuh kita berada pada lokasi yang terbuka / terpapar ke dunia luar. Epitel kulit di liang telinga merupakan suatu daerah Cul-de-sac sehingga apabila terdapat serumen padat di liang telinga dalam waktu yang lama maka dari epitel kulit yang berada medial dari serumen tersebut seakan terperangkap sehingga membentuk kolesteatoma.
Klasifikasi Kolesteatom1Kolesteatoma dapat dibagi atas dua jenis:
1. Kolesteatoma kongenital yang terbentuk pada masa embrionik dan ditemukan pada telinga dengan membran timpani utuh tanpa tanda-tanda infeksi. Lokasi kolesteatoma biasanya dikavum timpani, daerah petrosus mastoid atau di cerebellopontin angle. Kolesteatoma di cerebellopontin angel sering ditemukan secara tidak sengaja oleh ahli bedah saraf.
2. Kolesteatoma akuisital yang terbentuk setelah anak lahir, jenis ini terbagi atas dua:
a. Kolesteatoma akuisital primer
Kolesteatoma yang terbentuk tanpa didahului oleh perforasi membran timpani. Kolesteatoma timbul akibat terjadi proses invaginasi dari membran timpani pars flaksida karena adanya tekanan negatif ditelinga tengah akibat gangguan tuba. (Teori invaginasi)
b. Kolesteatoma akuisital sekunder
Kolesteatoma terbentuk setelah adanya perforasi membran timpani. Kolesteatoma terbentuk sebagai akibat dari masuknya epitel kulit dari liang telinga atau dari pinggir perforasi membran timpani ke telinga tengah (teori migrasi) atau terjadi akibat metaplasi mukosa kavum timpani karena iritasi infeksi yang berlangsung lama (teori metaplasi).
Pada teori implantasi dikatakan bahwa kolesteatoma terjadi akibat implantasi epitel kulit secara iatrogenik kedalam telinga tengah sewaktu operasi, setelah blust injury, pemasangan pipa ventilasi atau setelah miringotomi.
2.2.4 Patologi
Otitis media supuratif kronis lebih sering merupakan penyakit kambuhan daripada menetap. Keadaan kronis ini lebih berdasarkan keseragaman waktu dan stadium dari pada keseragaman gambaran patologis. Ketidakseragaman ini disebabkan karena proses peradangan yang menetap atau kekambuhan ini ditambah dengan efek kerusakan jaringan, penyembuhan dan pembentukan jaringan parut.6Secara umum gambaran yang ditemukan adalah:6 Terdapat perforasi membran timpani di bagian sentral. Ukurannya dapat bervariasi mulai kurang dari 20% luas membran timpani sampai seluruh membrana dan terkenanya bagian-bagian anulus.
Mukosa bervariasi sesuai stadium penyakit. Selama infeksi aktif, mukosa menjadi tebal dan hiperemis serta menghasilkan sekret mukoid atau mukopurulen. Setelah pengobatan, penebalan mukosa dan sekret mukoid menetap akibat disfungsi kronik tuba Eustachius. Faktor alergi dapat juga merupakan penyebab terjadinya perubahan mukosa menetap.
Tulang-tulang pendengaran dapat rusak atau tidak, tergantung pada beratnya infeksi sebelumnya.
Bila infeksi kronik terus berlanjut, mastoid mengalami proses sklerotik, sehingga ukuran prosesus mastoid berkurang. Antrum menjadi lebih kecil dan pneumatisasi terbatas, hanya ada sedikit sel udara saja sekitar antrum.
2.2.5 Gejala Klinis3,61. Telinga Berair (otorrohoe)
Sekret bersifat purulen ( kental, putih ) atau mukoid ( seperti air dan encer ) tergantung stadium peradangan. Sekret yang mukus dihasilkan oleh aktivitas kelenjar sekretorik telinga tengah dan mastoid. Pada OMSK tipe jinak, cairan yang keluar mukopus yang tidak berbau busuk yang sering kali sebagai reaksi iritasi mukosa telinga tengah oleh perforasi membram tipani dan infeksi. Keluarnya secret biasanya hilang timbul. Meningkatnya jumlah secret dapat disebabkan infeksi saluran nafas atau kontaminasi dari liang telinga luar setelah mandi atau berenang. Pada OMSK stadium inakatif dijumpai adanya secret telinga. Sekret yang sangat bau, berwarna kuning abu-abu kotor memberi kesan kolesteatoma dan produk degenerasinya. Dapat terlihat keeping-keping kecil, berwarna putih, mengkilap. Pada OMSK tipe ganas unsur mukoid dan secret telinga tengah berkurang atau hilang karena rusaknya lapisan mukosa secara luas. secret yang bercampur darah berhubungan dengan adanya jaringan granulasi dan polip telinga dan merupakan tanda adanya kolesteatom yang mendasarinya. Suatu secret yang encer berair tanpa nyeri mengarah kemungkinan tuberkolosis.
2. Gangguan pendengaran
Ini tergantung dari derajat kerusakan tulang-tulang pendengaran. Biasanya dijumpai tuli konduktif namun dapat pula bersifat campuran. Gangguan pendengaran mungkin ringan sekalipun proses patologi sangat hebat, karena daerah yang sakit ataupun kolesteatom, dapat menghambat bunyi dengan efektif ke fenestra ovalis. Bila kurang dari 20 db ini ditandai bahwa rantai tulang pendengaran masih baik. Kerusakan dan fiksasi dari rantai tulang pendengaran menghasilkan penurunan pendengaran lebih dari 30 db. Beratnya ketulian tergantung dari besar dan letak perforasi membrane timpani serta keutuhan dan mobilitas system pengantaran suara ke telinga tengah pada OMSK tipe maligna biasanya didapat tuli konduktif berat karena putusnya rantai tulang pendengaran, tetapi seringkali juga kolesteatom bertindak sebagai penghantar suara sehingga ambang pendengaran yang didapat harus diinterpretasikan secara hati-hati. Penurunan fungsi kohlea biasanya terjadi perlahan-lahan dengan berulangnya infeksi karena penetrasi toksin melaui jendela bulat (foramen rotundum) atau fistel labirin tanpa terjadinya labirinitis supuratif. Bila terjadinya labirinitis akan terjadi tuli saraf berat, hantaran tulang dapat menggambarkan sisa fungsi kohlea.3. Otolagia (nyeri telinga)
Nyeri tidak lazim dikeluhkan penderita OMSK, dan bila ada merupakan suatu tanda yang serius. Pada OMSK keluhan nyeri dapat karena terbendungnya drainase pus. Nyeri dapat berarti adanya ancaman komplikasi akibat hambatan pengaliran secret, terpaparnya durameter atau dinding sinus lateralis, atau ancaman pembentukan abses otak. Nyeri telinga mungkin ada tetapi mungkin oleh adanya otitis eksterna sekunder. Nyeri merupakan tanda berkembang komplikasi OMSK seperti petrositis, subperiosteal abses atau thrombosis sinus lateralis.4. Vertigo
Vertigo pada penderita OMSK merupakan gejala serius lainnya. Keluhan vertigo seringkali merupakan tanda telah terjadinya fistel labirin akibat erosi dinding labiarin oleh kolestotum. Vertigo yang timbul biasanya akibat perubahan tekanan udara yang mendadak atau pada penderita yang sensitif keluhan vertigo dapat terjadi hanya karena perforasi besar membrane timpani yang akan menyebabkan labirin lebih mudah terangsang oleh perbedaan suhu. Penyebaran infeksi ke dalam labirin juga akan menyebabkan keluhan vertigo. Vertigo juga bisa terjadi akibat komplikasi serebelum. Fistula merupakan temuan yang serius, karena infeksi kemudian dapat berlanjut dari telinga tengah dan mastoid ke telinga dalam sehingga timbul labirinitis dan dari sana mungkin berlanjut menjadi meningitis. Uji fistula perlu dilakukan pada kasus OMSK dengan riwayat vertigo. Uji ini memerlukan pemberian tekanan positif dan negatif pada membrane timpani, dengan demikian dapat diteruskan melalui rongga telinga tengah.
Tanda Klinis
Tanda-tanda klisis OMSK tipe maligna :8,91. Adanya Abses atau fistel retroaurikular
2. Jaringan granulasi atau polip diliang telinga yang berasal dari kavum timpani.
3. Pus yang selalu aktif atau berbau busuk (aroma kolesteatom)
4. Foto rontgen mastoid adanya gambaran kolesteatom. 2.2.6 Pemeriksaan Klinis
Untuk melengkapi pemeriksaan, dapat dilakukan pemeriksaan klinis sebagai berikut:
Pemeriksaan Audiometri6
Pada pemeriksaan audiometri penderita OMSK biasanya didapati tuli konduktif. Tapi dapat pula dijumpai adanya tuli sensorineural, beratnya ketulian tergantung besar dan letak perforasi membran timpani serta keutuhan dan mobilitas sistem penghantaran suara di telinga tengah.
Evaluasi audiometri penting untuk menentukan fungsi konduktif dan fungsi koklea. Dengan menggunakan audiometri nada murni pada hantaran udara dan tulang serta penilaian tutur, biasanya kerusakan tulang-tulang pendengaran dapat diperkirakan, dan bisa ditentukan manfaat operasi rekonstruksi telinga tengah untuk perbaikan pendengaran.
Pemeriksaan Radiologi
Pemeriksaan Radiologi daerah mastoid pada penyakit telinga tengah kronis nilai diagnostiknya terbatas dibandingkan dengan manfaat otoskopi dan audiometri. Pemeriksaan radiologi biasanya mengungkapkan mastoid yang tampak sklerotik, lebih kecil dengan pneumatisasi lebih sedikit dibandingkan mastoid yang satunya atau yang normal. Erosi tulang, terutama pada daerah atik memberi kesan kolesteatoma.6,72.2.7 Penatalaksanaan
Prinsip terapi OMSK tipe maligna ialah pembedahan, yaitu mastoidektomi. Terapi konservatif dengan medika mentosa hanyalah terapi sementara sebelum dilakukan pembedahan.8
Ada beberapa jenis teknik operasi pada OMSK dengan mastoiditis kronis yaitu : mastoidektomi sederhana, mastoidektomi radikal, mastoidektomi radikal dengan modifikasi, miringoplasti, timpanoplasti dan timpanoplasti dengan pendekatan ganda.9
Untuk OMSK tipe maligna pembedahan yang dilakukan yaitu mastoidektomi radikal atua mastoidektomi radikal dengan modifikasi.
Mastoidektomi radikal
Operasi ini dilakukan pada OMSK maligna dengan infeksi atau kolesteatom yang sudah meluas. Pada operasi ini rongga mastoid dan kavum timpani dibersihkan dari semua jaringan patologik. Maleus, inkus dan krus anterior posterior stapes diangkat kecuali basis stapes. Dinding batas antara liang telinga luar dan telinga tengah dengan rongga mastoid diruntuhkan, sehingga ketiga daerah anatomi tersebut menjadi satu ruangan. Tujuan operasi ini ialah untuk membuang semua jaringan patologik dan mencegah komplikasi ke intrakranial. Fungsi pendengaran tidak diperbaiki.3 Mastoidektomi radikal dengan modifikasi
Operasi ini dilakukan pada OMSK maligna dengan kolesteatoma di daerah atik, tetapi belum merusak kavum timpani. Seluruh ronggamastoid dibersihkan dan dinding posterior liang telinga direndahkan. Dinding posterior MAE diangkat sebagian, dipertahankan dinding MAE tempat anulus timpanikus. Tujuan operasi ini ialah untuk membuang semua jaringan patologik dan mempertahankan pendengaran yang masih ada.32.2.8 Komplikasi
Adam dkk (1989) mengemukakan kalsifikasi sebagai berikut:1A. Komplikasi di telinga tengah:
1. Perforasi persisten
2. Erosi tulang pendengaran
3. Paralisis nervus fasialis
B. Komplikasi telinga dalam
1. Fistel labirin
2. Labirinitis purulenta
3. Tuli saraf (Sensorineural)
C. Komplikasi Ekstradural
1. Abses ekstradural
2. Trombosis sinus lateralis
3. Petrositis
D. Komplikasi ke susunan saraf pusat
1. Meningitis
2. Abses otak
3. Hidrosefalus otits
Shambough (2003) membagi atas komplikasi sebagai berikut:1A. Komplikasi intratemporal
Perforasi membran timpani
Mastoiditis akut
Paresis N. Fasialis
Labirinitis
Petrositis
B. Komplikasi ekstratemporal
Abses subperiosteal
C. Komplikasi intrakranial
Abses otak
Tromboflebitis
Hidrosefalus otikus
Empiema subdura
Abses subdura / ekstradura
2.2.8 Prognosis
Frekuensi komplikasi yang mengancam jiwa pada OMSK telah menurun drastis dengan ditemukannya antibiotik. Komplikasi ke kranial merupakan penyebab utama kematian pada OMSK di negara sedang berkembang, yang sebagian besar kasus terjadi karena penderita mengabaikan keluhan telinga berair. Meningitis adalah komplikasi intrakranial yang sering ditemukan di seluruh dunia. Kematian terjadi pada 18,6% kasus OMSK dengan komplikasi intrakranial.3BAB III
LAPORAN KASUS
I. Identitas Pasien
MRS tanggal 26 Oktober 2010
Nama
: Tn. P
Umur
: 33 tahun
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Pekerjaan
: Buruh TambangAlamat
: Tanjung Selor, Kabupaten BulunganPendidikan terakhir
: SMA
II. Anamnese
Keluhan Utama
: Keluar Cairan dari telinga sebelah kananRiwayat Penyakit Sekarang:
Keluhan tersebut dialami pasien sejak kecil sejak usia sekolah dasar. Telinga sering terasa nyut-nyut dan diikuti oleh keluarnya cairan bening namun pasien tidak berobat ke dokter dan hanya berobat ke orang pintar dikampungnya. Sejak saat itu dibelakang daun telinga pasien juga timbul benjolan seperti bisul (bernanah) dan sekitar 4 tahun yang lalu benjolan tersebut sempat dioperasi namun timbul kembali. Selanjutnya sakit telinga tersebut bersifat hilang timbul hingga pasien dewasa. Namun sejak setahun terakhir sakit telinga kanan dirasakan hampir terus-menerus disertai keluarnya cairan seperti nanah dan berbau busuk, pasien juga merasakan nyeri kepala sebelah kanan dan juga bisul dibelakang telinga yang bernanah.
Riwayat penyakit dahulu:
Tidak ada riwayat sakit gigi berulang, pilek dan batuk berulang
Tidak ada riwayat penyakit kencing manis
Tidak ada riwayat penyakit TB.
Riwayat penyakit keluarga:
Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama dengan pasien
Tidak ada keluarga yang menderita penyakit kencing manis
Tidak ada keluarga yang menderita penyakit TB
Riwayat kebiasaan:
Sewaktu kecil pasien sering mandi di sungai / kali
Pasien sering mengkorek-korek telinga
III. Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan dilakukan tanggal 26 Oktober 2010 jam 13.00 wita
Kesadaran: Composmentis
Vital Sign: Nadi: 72x/menit, Pernafasan : 20x/menit,
Tekanan Darah : 110/70mmHg, Suhu : 36,80C
Status Generalis:
Kepala: Conjungtiva anemis (-), sklera ikterik (-), sianosis (-), pupil isokor 3mm/3mm, refleks cahaya (-), pembesaran KGB (-)
Thorax: pergerakan simetris, Rhonki (-), Wheezing (-), sonor, vesikuler, S1S2 tunggal reguler
Abdomen: flat, soefel, hepar lien tidak teraba, bising usus (+) normal
Ekstremitas: akral hangat, edema (-)/(-)
Status Lokalis (THT)
StrukturKananKiri
TELINGA
AurikulaRadang (-), sikatrik (-), nyeri tarik (-), nyeri tekan tragus (-)Radang (-), sikatrik (-), nyeri tarik (-), nyeri tekan tragus (-)
RetroaurikulaRadang (+), sikatrik (-), nyeri tekan (+)Fistel (+)Radang (-), sikatrik (-), nyeri tekan (-)
MAEHiperemis (+), , sekret (+), sempit (+)Hiperemis (-), sekret (-)
Membran timpaniSulit dievaluasiJernih, tipis, retraksi (-), edema (-), refleks cahaya (+)
HIDUNG
FetorTidak adaTidak ada
Septum nasiTidak ada deviasi
Vestibulum nasiHiperemis (-)Hiperemis (-)
Mukosa cavum nasiHiperemis (-), discharge (-), tumor (-)Hiperemis (-), discharge (-), tumor (-)
Konka nasiPermukaan halus, hiperemis (-), edema (-)Permukaan halus, hiperemis (-), edema (-)
TENGGOROKAN
Fetor(+)
TonsilMembesar (-), hiperemis (-), debris (-)Membesar (-), hiperemis (-), debris (-)
UvulaSimetris, hiperemis (-), edema (-)
Palatum moleSimetris, hiperemis (-), edema (-)
Dinding faringPermukaan halus, hiperemis (-), granula (-), refleks muntah (+)
Pemeriksaan Pendengaran
Tes GarputalaKananKiri
RinneNegatifPositif
WeberLateralisasi ke telinga kanan
SchwabachMemanjangSama dengan pemeriksa
Pemeriksaan Penunjang (26 Oktober 2010)
Laboratorium
Lekosit13.500 /mm3
Hemoglobin17,1 gr/dL
Hematokrit50.6 %
Trombosit317.000 /mm3
BT3
CT7
Radiologi foto Schullers dextra et sinistra
Diagnosa : OMSK Maligna dekstra+ Fistel Retroaurikuler deksta + Paralise Saraf Fasialis
Penatalaksanaan:
Perbaiki Keadaan Umum
Berikan Antibiotik
Operasi Mastoidektomi Radikal
Saran higiene yang baik dan tidak boleh berenang
Terapi
IVFD RL : D5% = 1: 2 (14 tpm)
Inj. Cefotaxim 2 x 1 gr
Laporan Operasi
Laporan Operasi Mastoidektomi Radikal tanggal 29 Oktober 2010 :
1. Pasien dilakukan general anastesi, ETT terpasang
2. Desinfeksi lapangan operasi, pasang duk steril
3. Insisi retroaurikuler dekstra, tampak fistel + jaringan granulasi di retroaurikula
4. Insisi diperdalam sampai tulang tampak jaringan granulasi + jaringan fibrosa, tulang tereskpose, tampak hole di daerah antrum mastoid
5.Tampak massa kolesteatoma memenuhi rongga mastoid dengan dinding posterior MAE sudah runtuh, tegmen dura masih intak, sinus dura sudah menipis.
6. Kuret kolesteatoma
7. Buat meatoplasty, pasang tampon pada daerah mastoid.
8. Tutup luka operasi dan jahit luka operasi. Operasi selesai.
Proses Operasi Mastoidektomi RadikalLEMBAR FOLLOW UP
Tanggal/JamHasil ObservasiPenatalaksanan
27 Oktober 2010S : Keluar cairan dari telinga, warna kuning, bau (+),
O : KU baik
Vital Sign : T:36.6, N : 98x/menit, R : 26 x/menit, TD : 130/80
Sekret mukopurulent (+), otore fetor (+), otalgia (-),
A : OMSK Maligna (D) + Fistel Retroaurikula (D) + paralise saraf fasialisIVFD RL : D5% = 1: 2 (14 tpm)
Inj. Cefotaxim 2 x 1 grHasil laboratorium
Hb : 14.7
Hct : 45%
Leukosit : 9.400
Plt : 246.000
Sgot/Sgpt : 18/16
28 Oktober 2010S : keluhan tidak bisa tidur malam,
O : KU baik
Vital Sign : T:36, N : 98x/menit, R : 25x/menit, TD : 130/80
Luka operasi sedikit basah,
A : Post Op hari 1 Mastoidektomi Radikal (D) a/i OMSK Maligna (D) + Fistel Retroaurikula (D) + paralise saraf fasialisCefotaxim 2x1 gr iv
Antrain 3x1 amp iv
Dexamethason 3x1 amp iv
Cimetidin 3x1 amp iv
Metronidazol 3x500 mg tab
Longgarkan head verban
29 Oktober 2010S : keluhan tidak bisa tidur malam, nyeri kepala (+)
O : KU baik
Vital Sign : T:36, N : 80x/menit, R : 20x/menit, TD : 120/80
Luka operasi ,
A : Post Op hari 2 Mastoidektomi Radikal (D) a/i OMSK Maligna (D) + Fistel Retroaurikula (D) + paralise saraf fasialisTerapi lanjut
Diazepam 5 mg malam hari
30 Oktober 2010S : keluhan tidak bisa tidur malam, nyeri kepala (-)
O : KU baik
Vital Sign : T:36, N : 80x/menit, R : 20x/menit, TD : 140/80
Luka operasi ,
A : Post Op hari 3 Mastoidektomi Radikal (D) a/i OMSK Maligna (D) + paralise saraf fasialis + Fistel Retroaurikula (D)Terapi lanjut
Tanggal/JamHasil ObservasiPenatalaksanan
1 November 2010S : Nyeri Kepala (-)
O : KU baik
Vital Sign : T:36.6, N : 98x/menit, R : 26 x/menit, TD : 130/80
Luka operasi sedikit basah
A : Post op hari 5 OMSK Maligna (D) + Fistel Retroaurikula (D) + paralise saraf fasialisAff Infus (vemplon)
Terapi lain lanjut
2 November 2010S : keluhan tidak bisa tidur malam,
O : KU baik
Vital Sign : T:36, N : 98x/menit, R : 25x/menit, TD : 130/80
Luka operasi kering,
A : Post Op hari 6 Mastoidektomi Radikal (D) a/i OMSK Maligna (D) + Fistel Retroaurikula (D) + paralise saraf fasialisTerapi lanjut
3 November 2010S : keluhan tidak bisa tidur malam, nyeri kepala (+)
O : KU baik
Vital Sign : T:36, N : 80x/menit, R : 20x/menit, TD : 120/80
Luka operasi kering
A : Post Op hari 7 Mastoidektomi Radikal (D) a/i OMSK Maligna (D) + Fistel Retroaurikula (D) + paralise saraf fasialisAff Hecting
Pulang
Foto foto Post op hari ke 7 (tanggal 3 November 2010)
Dilakukan Aff hecting dan pasien dibolehkan pulang
BAB IV
DISKUSI
Otitis media purulenta kronik (OMSK) dengan kolesteatoma merupakan keradangan atau infeksi kronik yang mengenai mukosa dan struktur tulang di dalam kavum timpani dan dengan terbentuknya kolesteatoma (deskuamasi epitel liang telinga) ditandai dengan perforasi membran timpani, sekret yang keluar terus menerus atau hilang timbul.
Berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosa menderita OMSK Maligna + Fistel Retroaurikuler. Berdasarkan anamnesa, pasien mengeluhkan keluarnya cairan dari telinga kanan dalam satu tahun terakhir, dimana sekret seperti nanah, berbau busuk dan pasien juga mengeluhkan pendengaran menurun dan sering mengalami nyeri kepala sebelah kanan.
Pada pemeriksaan otoskopi sulit untuk mengevaluasi keadaan membrane timpani dikarenakan MAE menyempit dikarenakan adanya pendesakan dari bagian posterior.. Sedangkan pada pemeriksaan tes pendengaran dengan garpu tala didapatkan tes Rinne negatif pada telinga kanan, Weber lateralisasi ke sebelah kanan, dan Schwabah mmemanjang pada telinga sebelah kanan dengan kesimpulan adanya tuli konduksi pada telinga kanan. Penurunan pendengaran pada pasien OMSK tergantung dari derajat kerusakan tulang-tulang pendengaran yang terjadi. Biasanya dijumpai tuli konduktif, namun dapat pula terjadi tuli persepsi yaitu bila telah terjadi invasi ke labirin atau tuli campuran. Beratnya ketulian tergantung dari besar dan letak perforasi membran timpani serta keutuhan dan mobilitas sistem penghantaran suara ke telinga tengah. Tuli konduktif merupakan tuli yang disebabkan oleh kelainan di telinga luar dan tengah. Pada kasus otitis media supuratif kronik dengan kolesteatoma pada pasien, tuli konduktif yang terjadi dimungkinkan disebabkan oleh perforasi membran timpani yang hampir total dan kerusakan tulang pendengaran yang terdestruksi akibat kolesteatoma oleh rena berbagai enzim kolagenase, asam fospatase dan enzim proteolitik yang dilepaskan oleh osteoklast dan sel inflamasi mononuclear terkait kolesteatoma.
Dari pemeriksaan penunjang X-ray yaitu foto mastoid posisi Schuller didapatkan gambaran kolesteatoma. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kolesteatoma yang terdapat pada penderita telah menyebabkan kerusakan di sekitar kolesteatoma tersebut yang menyebabkan kerusakan tulang disekitarnya sehingga pada operasi mastoidektomi radikal didapatkan dinding posterior MAE yang sudah runtuh, tegmen dura intak, dan sinus dura yang sudah menipis.
Mekanisme pengrusakan tulang oleh kolesteatoma dikatakan mungkin oleh reaksi imunologik yang timbul, juga karena penekanan debris yang menumpuk bersama dengan reaksi asam yang timbul karena dekomposisi bakteri. Proses tersebut menyebabkan erosi yang perlahan-lahan pada tulang disekitarnya. Erosi tulang ini akhirnya akan merusak sel-sel mastoid, bahkan dapat terus merusak ke arah mastoid menyebabkan abses retroaurikuler.
Pasien diketahui menderita Paralisis Saraf Fasialis, ini ditandai dengan kelumpuhan pada otot-otot wajah, dimana pasien tidak atau kurang dapat menggerakkan otot-otot wajah seperti ketika menggembungkan pipi dan mengerutkan dahi tampak sekali wajah pasien tidak simetris.
Salah satu komplikasi OMPK yang dijumpai pada telinga tengah adalah paralisis saraf fasialis perifer yang menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot wajah, komplikasi paralisis saraf fasialis perifer setelah pasien mengalami otitis media terjadi sekitar 1 2,3% pada era preantibiotik. Dilaporkan oleh beberapa penelitian insiden terjadinya paralisis saraf fasialis bervariasi dari 0,16 5,1% pada era antibiotik, namun telah banyak diterima bahwa insiden tersebut cenderung menurun pada era antibiotik.
Mekanisme efek dari OMPK terhadap fungsi saraf fasialis dapat disebabkan oleh : Proses inflamasi secara langsung yang meluas di sepanjang saraf fasialis.
Penekanan saraf fasialis oleh kolesteatoma ataupun jaringan granulasi.
Proses neuropatologi saraf fasialis itu sendiri.
Patogenesis terjadinya paralisis fasialis pada OMPK belum diketahui pasti karena keterbatasan biopsi pada saraf yang rusak dan belum banyak diteliti.Sebuah penelitian menyatakan terjadinya gangguan pada saraf fasialis disebabkan oleh adanya infiltrasi sel-sel inflamasi yang berasal dari kolesteatoma pada selubung saraf epineural (epineural nerve sheath) yang menyebabkan neuritis dan degenerasi akson. Paralisis fasialis tidak hanya tergantung dari besarnya destruksi tulang di kanalis fasialis akan tetapi juga oleh perluasan proses inflamasi disepanjang saraf fasialis. Pada banyak kasus, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, segmen timpani merupakan tempat tersering dari kanalis fasialis yang mengalami destruksi dan sebagian kasus terdapat pada segmen atas mastoid, sedangkan destruksi tulang pada segmen labirin sangat jarang
Prinsip pengobatan pasien OMSK maligna adalah operasi. Pada pasien ini dilakukan mastoidektomi radikal pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan maksud menghentikan infeksi secara permanen dan mencegah terjadinya komplikasi. Saat operasi dilakukan didapatkan kumpulan kolesteatoma yang memenuhi rongga mastoid. Pada pasien ini fungsi pendengaran tidak dapat dipertahankan oleh karena telah terjadi destruksi tulang pendengaran oleh kolesteatoma. Selain itu didapatkan rongga pembatas antara telinga luar dan tengah telah hancur yang dimungkinkan disebabkan destruksi oleh kolesteatoma. Setelah operasi dilakukan pasien diberikan antibiotik Cefotaxime sebagai antibiotik sefalosforin generasi III yang memiliki kelebihan lebih mudah menembus blood brain barier sehingga dapat menekan aktivitas bakteri apabila menginfeksi otak dan sekitarnya, Metronidazol untuk mematikan mikroba anaerob, Antrain yang mengandung Metamizole diberikan karena kemampuannya sebagai analgetik, dan deksamethason sebagai antiinflamasi untuk menekan peradangan yang terjadi.
Setelah beberapa hari perawatan pasca operasi dan luka operasi telah kering, pasien diijinkan pulang pada tanggal 3 November 2010 atau tepatnya 7 hari pasca operasi Mastoidektomi Radikal (D). Edukasi yang diberikan kepada pasien agar penyakit tidak berulang kembali yaitu pasien diingatkan untuk tidak mengorek telinga, menjaga agar air tidak masuk ke telinga sewaktu mandi, menghindari berenang. 9