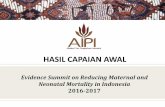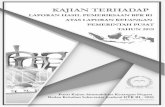Modul-AKN
-
Upload
abdul-rohman -
Category
Documents
-
view
101 -
download
7
description
Transcript of Modul-AKN

Kata Pengantar
Administrasi Keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap nasib suatu bangsa, sehingga kebijakan yang ditempuh pemerintah akan menjurus pada kegiatan yang dapat mengakibatkan kemiskinan atau kemakmuran, keterpurukan atau kejayaan suatu bangsa/Negara tersebut.
Kepandaian dalam mengendalikan Negara saja belumlah cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan, perlu system dan cara pengelolaan serta pengendalian keuangan Negara yang baik, dibutuhkan pula kemampuan untuk melihat ke depan dengan penuh kebijaksanaan yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar kekayaan Negara untuk kepentingan dan kasejahteraan masyarakat.Jadi betapa pentingnya peranan Administrasi Keuangan Negara dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah didalam menjalankan fungsinya, tercapai atau tidaknya tujuan Negara tergantung juga pada proses pengelolaan keuangan Negara.
Dalam buku modul Administrasi Keuangan Negara penyusun kelompokkan sesuai Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kedalam empat modul yaitu modul pertama: mengidentifikasi dan mengkaji tentang pengertian serta lingkup Administrasi Keuangan Negara, modul kedua membahas tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran Negara, modul ketiga membahas tentang mencatat realisasi anggaran kedalam akuntansi pemerintahan, modul keempet membahas tentang pemeriksaan keuangan ( auditing ).
Semoga dengan adanya buku yang berbentuk modul ini dapat membantu dan mempermudah mahasiswa didalam mempelajari masalah administrasi keuangan Negara sehingga mahasiswa mampu untuk dapat menganalisis isu-isu administrasi keuangan Negara yang sedang berkembang saat ini.
Dalam penyusunan buku modol yang sangat sederhana ini tentu saja terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu, penyusun mengharap adanya kritik dan saran dari semua pihak guna untuk memperbaiki serta menyempurnakan buku modul Administrasi Keuangan Negara, juga tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku modul ini.
Surakarta, September 2010
Penyusun,

PENDAHULUAN
Modul Administrasi Keuangan Negara
A. Latar Belakang
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operasional pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah di bidang administrasi keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang administrasi keuangan negara.
Reformasi administrasi keuangan ini antara lain dilatarbelakangi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang masih berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting dalam melakukan reformasi adalah perubahan sistem pemerintahan. Era otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 berdampak pada perubahan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jika sebelumnya pengelolaan keuangan negara didominasi oleh peran pusat, sistem otonomi daerah dengan prinsip money follows function mengharuskan peran daerah yang lebih besar. Sebagian besar urusan fungsi pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar diserahkan penanganannya kepada pemerintah daerah. Sebagai akibatnya, anggaran yang digunakan untuk belanja pada pelayanan-pelayanan dasar wajib diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, makin besar belanja negara yang dikelola oleh pemerintah daerah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat/stakeholder.
Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi pajak dalam mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang selama ini besar porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin berkurang oleh karena jumlah sumber yang terbatas. Pada satu pihak, biaya penyelenggaraan pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber adalah pajak dari masyarakat. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat oleh pemerintah dengan transparan.
Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan good governance dan otonomi daerah. Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara:
Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum; Penataan kelembagaan; Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.
Dengan demikian reformasi administrasi dan manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi Pemerintah Daerah.

B. Tujuan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran UmumSetelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu mengenai administrasi keuangan negara, termasuk keuangan daerah secara umum sehingga mahasiwa dapat mengkonstruksikan administrasi keuangan negara..
Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa dapat:
a. Mengidentifikasi pengertian dan lingkup administrasi keuangan negara/daerah; b. Menganalisis mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara/daerah
(budgeting ) c. Menganalisis tentang realisasi anggaran yang dimasukkan kedalam akuntansi
pemerintahan ( accounting ) dan d. Menganalisis mengenai pemeriksaan keuangan negara/daerah ( auditing )
C. Deskripsi Ringkas
Materi Modul Administrasi Keuangan Negara ini disusun dalam rangka memberikan perkuliahan untuk membahas atau menganalisa materi mengenai aministrasi keuangan negara. Materi dimulai dengan mengidentifikasi pengertian serta lingkup pola perbuatan atau kegiatan administrasi keuangan negara, dilanjutkan dengan pembahasan materi mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara/daerah sehingga mahasiswa mampu menganalisis isu tentang anggaran Negara/daerah (budgeting), kemudian dilanjutkan dengan pambahasan materi mengenai realisasi anggaran yang dituangkan kedalam akuntansi pemerintahan, sehingga mahasiwa dapat menyusun akuntansi pemerintahahan serta mampu menganalisa isu tentang pelaksanaan akuntansi pemerintahan (accounting), selanjutnya pada modul terakhir membahas materi tentang pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan Negara/daerah sehingga mahasiswa dapat menganalisis isu tentang pemeriksaan keuangan (auditing).
D. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini dilakukan dengan cara ceramah atau pemaparan materi Administrasi Keuangan Negara dengan menggunakan buku-buku literature yang berkaitan dengan materi perkuliahan administrasi keuangan negara termasuk undang-undang di bidang keuangan negara (UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004) sebagaimana diatur pula untuk keuangan daerah dalam UU 32/2004 dan UU 33/2004. Keberhasilan pembelajaran ini juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para mahasiswa di dalam aktivitas perkuliahan maupun diskusi atau tanya jawab serta seminar untuk mempresentasikan tugas mahasiswa secara kelompok.

MODUL: 1
PENGERTIAN DAN LINGKUP ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
A.Pengertian Administrasi Keuangan Negara.
Administrasi sebagai ilmu pengetahuan termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan social,oleh sebab itu administrasi juga mempunyai kaitan erat dengan ilmu-ilmu social lainnya seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sosiologi dan lain-lain.
Adiministrasi oleh Sondang P Siagian (1973:13) didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.Apabila kita lihat definisi tersebut, maka terdapat beberapa hal yang terkandung didalamnya yaitu pertama, administrasi sebagai seni artinya suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak dapat diketahui.Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu yaitu: adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut. Didalam golongan peralatan dan perlengkapan disini termasuk juga keuangan, waktu, tempat, peralatan materi serta perlengkapan lainnya. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena administrasi timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.
Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan berbagai faktor terutama keuangan, yang digambarkan oleh Leonard D White bahwa hubungan administrasi dengan faktor uang bagai manusia dengan bayangannya sendiri, jadi tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada sesuatu yang dapat diselenggarakan tanpa pengeluaran uang.Sedang Frank P Sherwood menyimpulkan bahwa darah hidup ( the life blood) dari setiap organisasi adalah uang. (Subakdi Soesilowidagdo 1980: 2). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan usaha untuk mencapai tujuan akan mempunyai akibat kebutuhan dan penggunaan uang, ini berarti bahwa proses administrasi itu tentu ada serangkaian perbuatan yang berhubungan dengan faktor penggunaan uang, misalnya perbuatan: memikir, meneliti sumber –

sumber keuangan, kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai, mencatat transaksi-transaksi keuangan, mengawasi supaya penggunaan uang dapat cukup untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
Jadi segenap perbuatan yang bertalian dengan penggunaan faktor uang dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan, maka disebut administrasi keuangan. Administrasi Keuangan tersebut telah dipelajari oleh suatu ilmu yang disebut ilmu administrasi keuangan. Ilmu administrasi keuangan bertujuan memberikan pengetahuan kepada manusia tentang bagaimana menyediaan uang yang dapat digunakan untuk membiayai suatu proses penyelenggaraan tujuan ( atau proses administrasi ) dan menjamin penggunaan-penggunaannya secara sah dan efisien. Seorang pakar dari Perancis bernama D’audiffret berpendapat mengenai kegunaan Ilmu Administrasi Keuangan adalah: pengelolaan kekayaan atau keuangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nasib rakyat suatu Negara, tergantung kepada cara mengatur dan kebijaksanaan pengurusan kekayaan atau keuangan tersebut yang dapat mengakibatkan kaya raya atau kelemahan/kemiskinan, keagungan atau keruntuhan Negara tersebut. Pakar tata Negara atau tata pemerintahan yang bagaimanapun ulungnya, tidak akan dapat memberikan hasil yang baik dan memuaskan bagi bangsa dan negaranya, kecuali dengan menyelenggarakan pengurusan keuangan dengan baik, terutama kecakapan juga pengertian yang mendalam dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang harus diarahkan pada tujuan yang dapat melindungi serta menumbuhkan kekayaan dan perekonomian yang erat hubungannya dengan kesejahteraan juga kemakmuran rakyat ( Subakdi Soesilowidagdo, 1980: 9-10 ).
Demikian halnya dengan negara dan pemerintahannya, dalam setiap proses penyelenggaraan usaha untuk mencapai tujuan Negara tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan masalah faktor penggunaan sumber dana ( faktor uang ). Oleh sebab itu segenap perbuatan yang berhubungan dengan faktor penggunaan uang dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Negara, maka disebut Administrasi Keuangan Negara. Sedangkan yang menjadi masalah utama Administrasi Keuangan Negara adalah pengambilan keputusan kebijaksanaan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, laporan realisasi anggaran dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak serta penggunaan dana dilain pihak. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Administrasi Keuangan Negara adalah pertanggung jawaban, efesiensi dan efektivitas dalam pengadaan dana serta dalam penggunaan dana.
B.Pendekatan-Pendekatan Dalam Studi Administrasi Keuangan Negara
Masalah – masalah Administrasi Keuangan Negara dapat dianalisis atau dibahas dengan melalui lima kelompok pendekatan yang berbeda sebagai berikut:
1. Pembahasan ditinjau dari sudut pendekatan manajemen.2. Pembahasan atau analisa yang ditinjau dari sudut pendekatan keuangan Negara.

3. Analisa atau pembahasan ditinjau dari segi administrasi Negara termasuk didalamnya administrasi pembangunan’
4. Pembahasan yang ditinjau dari sudut sejarah perkembangan system anggaran.5. Analisa atau pembahasan ditinjau dari segi organisasi sebagai system terbuka dan terpadu
( Abdullah, 1982:1 )
Pembahasan administrasi keuangan Negara apabila ditinjau dari sudut pendekatan manajemen, yaitu administrasi keuangan Negara sebagai alat pimpinan eksekutif untuk melaksanakan fungsi – fungsi manajemennya, artinya administrasi keuangan Negara dapat dianalisa dengan beberapa segi yaitu :
1. Planning – penyusunan anggaran2. Organizing – penyusunan perbendaharaan, organisasi kementrian keuangan3. Directing – peraturan-peraturan sebagai pedoman kerja4. Coordinating – koordinasi dalam pelaksanaan/ merealisasikan anggaran5. Controling – pengawasan dan pemeriksaan keuangan Negara6. Reporting – perhitungan anggaran ( Sofwan Badri, 1977: 5-6).
Selain pendapat Sofwan Badri, ada juga pendapat lain dari Abdullah yaitu bahwa administrasi keuangan Negara apabila ditinjau dari sudut pendekatan manajemen, maka pembahasannya mencakup fungsi perencanaan keuangan, ketatalaksanaan penggunaan dana, penyediaan dana dan atau mengadakan dana yang diperlukan serta mengatasi masalah-masalah khusus (1982:2).
Menurut pendapat Robert W Johnson dalam bukunya yang berjudul Financial Management adalah bahwa financial management meliputi; financial planning, managing assets, raising funds dan meeting special problem ( 1971: 13). Disamping pendapat-pendapat tersebut ada juga yang berpendapat bahwa kegiatan administrasi keuangan Negara dapat digolongkan ke dalam beberapa kegiatan yang meliputi perencanaan keuangan, pembelanjaan dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan keuangan serta masalah keuangan lainnya.
Pembahasan administrasi keuangan Negara apabila ditinjau dari segi pendekatan keuangan Negara, bahwa administrasi keuangan Negara merupakan salah satu lingkup dari keuangan Negara yang pembahasannya mencakup badan hukum public baik keuangan Negara maupun keuangan badan hokum yang lebih rendah, pembahasan biasanya ditekankan pada segi-segi yang berhubungan dengan pengeluaran Negara, penerimaan Negara termasuk perpajakan dan hutang Negara, serta anggaran Negara ( Soetrisno PH 1981: 15 )
Pembahasan administrasi keuangan Negara jika dilihat dari sudut pendekatan administrasi negara
yang mengemukakan pendapat dari Dimock & Dimock, bahwa ada dua segi yang berkaitan dengan administrasi keuangan negara yaitu pertama, merupakan bidang keuangan negara yang luas meliputi fungsi pemungutan dan perhitungan pajak, pemeliharaan dana, hutang negara dan

administrasi hutang negara, kedua, merupakan bagian administrasi negara, sebagaimana ditinjau dari sudut pandang pimpinan administrasi dan mereka yang menaruh perhatian terhadap apa yang dilakukannya ( Dimock & Dimock terjemahan Husni Thamrin Pane,1980 : 202) Menurut mereka administrasi keuangan negara terdiri dari serangkaian langkah dimana dana –dana disediakan untuk pejabat – pejabat tertentu menurut metode dan prosedur yang dapat menjamin pertanggung jawaban yang sah serta daya guna dari penggunaan dana tersebut.
Administrasi keuangan negara dapat dianalisa atau dibahas dengan melihat dari segi pendekatan sejarah perkembangan system anggaran. Apabila ditinjau dari sudut pendekatan ini maka administrasi keangan negara telah berkembang dari administrasi keuangan negara tradisional yang kira- kira dikembangkan di Amerika Serikat sejak tahun 1789 ke arah administrasi keuangan negara Hasil Karya (Performance Financial Administration) pada tahun 1949. Sedang perkembangan selanjutnya terjadi dari performance financial administration menuju kea rah system Administrasi Keuangan Negara Terpadu (Integreted Financial Administration), administrasi keuangan negara tradisional berorientasi pada pengawasan, sedangkan administrasi keuangan negara hasil karya berorientasi pada ketatalaksanaan, adapun administrasi keuangan negara terpadu lebih berorientasi pada perencanaan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. (Abdullah, 1982 : 10).
Ruang lingkup pembahasan administrasi keuangan negara selanjutnya jika ditinjau dari sudut pendekatan organisasi sebagai system terbuka dan terpadu, sudut pandang pendekatan ini pembahasannya diarahkan pada organisasi keuangan, yang mana ada dalam batas - batas dan kendala –kendala lingkungan-lingkungan luar, mencakup lima unsur pokok yang saling terkait dan pengruh mempengaruhi. Kelima unsure tersebut terdiri dari; unsur tujuan dan nilai, unsur tehnis, unsur psikhososial, unsur structural dan unsur administrasi keuangan, disamping itu organisasi keuangan sebagai kesatuan yang menyeluruh mempunyai hubungan dengan lingkungan luar. Dari pendekatan organisasi sebagai suatu system terbuka dan terpadu, administrasi keuangan negara hanya merupakan salah satu bagian saja dari organisasi keuangan, sedangkan organisasi keuangan itu sendiri termasuk sebagai salah satu unsur dalam lingkungan umum yang mencakup lingkungan budaya, tehnologi, pendidikan, politik, demografi, hukum, peraturan dan perundang-undangan, ekonomi dan lingkungan social.(Abdullah,1982:17) Demikian penjelasan mengenai beberapa pendekatan yang digunakan untuk membahas atau menganalisa permasalahan-permasalahan administrasi keuangan negara.
C.Ruang Lingkup Administrasi Keuangan Negara.
Dalam membahas Administrasi keuangan negara selain ditinjau dari sudut pedekatan-pendekatan juga dapat dibahas dengan melihat ruang lingkup dari administrasi keuangan negara apabila dilihat dari pola perbuatan atau kegiatannya yaitu seperti yang dikemukakan oleh Prof. I Gondo Wardoyo bahwa bahwa taraf hidup seseorang tergantung kepada tiga faktor yaitu besarnya

penghasilan uang, kecakapan penggunaan uang dan nilai uangnya, begitu pula dengan negara dan pemerintahannya tergantung dari penyelenggaraan administrasi keuangan negara, supaya dalam penggunaan uang dapat efisien dan efektif maka dilakukan tiga pola perbuatan/kegiatan administrasi keuangan negara ( Subakdi Soesilowidagdo 1980:11 ) yaitu:
1. Pembuatan anggaran ( budgeting)2. Pembukuan (accounting )3. Pemeriksaan keuangan ( auditing )
Tiga pola perbuatan atau kegiatan administrasi keuangan negara tersebut yang menjadi pokok bahasan dalam modul ini, yaitu pada modul dua mengenai anggaran, modul tiga tentang accounting dan modul empat mengenai pemeriksaan keuangan (auditing)

MODUL 2
ANGGARAN NEGARA
A.Pengertian Anggaran dan Penganggaran.
Anggaran merupakan suatu instrument penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen, sedangkan di dalam dunia bisnis maupun organisasi sektor public termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan keuangan negara/daerah, adapun dalam akuntansi bisnis, anggaran tidak menjadi bagian dari proses akuntansi karena anggaran bukan merupakan bukti transaksi-transaksi tetapi anggaran merupakan suatu rencana keuangan. Sementara, anggaran dalam akuntansi pemerintahan dicatat atau dibukukan mengingat anggaran menjadi dasar aktivitas pemerintah. Pencatatan anggaran meliputi pencatatan anggaran yang disetujui oleh legislatif, pengalokasian pendapatan dan belanja pada unit-unit pemerintahan dan penutupan (closing entries) pencatatan anggaran tersebut.
Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan didalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasinya secara sistematis. Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun anggaran tertentu, pada hakekatnya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh aparat-aparat pemerintah bersama-sama rakyat.(Imam Ghozali & Arifin Sabeni, 1991:41)
John F Due secara terinci memberikan pengertian anggaran negara sebagai berikut: “Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa kini dan di masa yang lalu” Jadi dengan pengertian anggaran negara sebagaimana dikemukakan John F Due tersebut bahwa melalui anggaran negara tidak hanya dapat disaksikan besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan, tetapi juga data mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Sehingga secara lebih terinci dapat dinyatakan bahwa:

1. Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode dimasa depan maupun kebijaksanaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut
2. Selain mengungkap kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode di masa depan, dari anggaran negara dapat diketahui pula realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa lalu
3. Sehingga melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah di masa lalu serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah di masa yang akan dating.( Revrisond Baswir,1999:24)
The National Committe on Governmental Accounting atau Komite Nasional Akuntansi Pemerintahan di Amerika Serikat memberikan definisi: anggaran adalah satu rencana kegiatan yang diukur dalam satuan uang yang berisikan perkiraan belanja dalam satu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Selain itu Wildavsky (1975), memberikan definisi bahwa anggaran merupakan suatu catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan-aspirasi-strategi organisasi, satu bentuk kekuatan control dan alat atau jaringan komunikasi(Bachtiar Arief, Muchlis&Iskandar,2009:123) Berdasarkan definisi anggaran tersebut dapat diringkas menjadi:
a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja, b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, c. Alat pengendalian, d. Instrument politik, e. Disusun dalam periode tertentu.
Pengertian anggaran menurut UU No. 17 tahun 2003 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara/daerah (pusat/daerah) yang disetujui oleh DPR/DPRD. Anggaran setiap tahun diajukan pemerintah pusat dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada dewan perkilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan. Untuk anggaran daerah, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda ) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk mendapat persetujuan.Definisi anggaran menerut PP No.25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang lain dengan menekankan rincian dari struktur anggaran yaitu pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja Negara yang cenderung tanpa batas, sedangkan Wildavsky(1975) menyatakan “budgeting is translating financial resources into human purposes” atau

penganggaran adalah penjabaran sumber daya keuangan untuk berbagai tujuan manusia. (Bahtiar Arif,Muchlis dan Iskandar, 2009:124). Penganggaran merupakan aktivitas yang terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (budget cycle), siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan, ketika anggaran masih dilaksanakan dan belum dibuat pelaporan, proses perencanaan dan penyusunan telah dimulai. Di sinilah terjadi kesulitan untuk memanfaatkan pelaporan dan hasil pemeriksaan untuk dipakainsebagai masukan dalam proses penyusunan anggaran.
Dalam penganggaran perlu diperhatikan beberapa factor sebagai berikut:
1. Kondisi perekonomian (economic wealth) negara, apakah memungkinkan untuk mencapai proyeksi pendapatan dan belanja tahun depan. Ekonomi yang tidak stabil seperti laju inflasi yang tidak terkendali, suku bunga yang tinggi dan nilai tukar mata uang yang bergejolak tidak menentu merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam penganggaran.
2. Struktur politik seperti system politik, tingkat korupsi, penggantian struktur pemerintahan juga karakter pemerintahan dan kabinet dan jumlah serta kekuatan dari kelompok penekan (pressure groups) menentukan dalam penganggaran karena anggaran dikenal sebagai alat politik.
3. Ketidak seimbangan antara belanja dan pendapatan yang sangat besar merupakan factor penentu dalam penganggaran. Langkah sumber pendapatan dan besarnya anggaran belanja yang diajukan mengharuskan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan untuk menyusun prioritas dan memangkas usulan anggaran belanja, di sinilah memungkinkan “moral hazard and adverse selection” yang dilakukan pejabat dan pelaksana di Kementrian Keuangan. Wildavsky (1975) mengidentifikasi adanya perendahan (underestimating) anggaran pendapatan dan melakukan negosiasi yang tidak wajar dengan pemerintahan lain dan sering kali pertimbangan persetujuan anggaran belanja tidak didasarkan pada kebutuhan serta ekonomi, tetapi tergantung pada hasil negosiasi. (Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, 2009: 125)

B.Klasifikasi Anggaran
Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan atau pembagian dari anggaran supaya dapat memberikan gambaran yang lebih rinci. Klasifikasi anggaran terutama ditujukan untuk keperluan sebagai berikut:
a. Untuk memudahkan proses perumusan sasaran program-program yang hendak dilakukan b. Untuk memudahkan proses formulasi penerimaan dan pengeluaran secara kuantitatif c. Untuk memudahkan pelaksanaan anggaran d. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan
anggaran e. Untuk memudahkan pelaksanaan analisa ekonomi f. Untuk memudahkan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran g. Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah
digariskan.
Sedangkan bentuk pengklasifikasiannya dalam garis besarnya dapat dibedakan berdasarkan beberpa pendekatan sebagai berikut:
1. Klasifikasi berdasarkan obyek
Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja. Pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan lain adalah pendapatan hibah dan sebagainya. Belanja diklasifikasikan dalam belanja operasional dan modal. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pembayaran bunga dan sebagainya, klasifikasi ini sering digunakan karena relative sangat mudah, tetapi di dalam klasifikasi ini tidak dapat diketahui pertanggungjawaban setiap unit dan tingkat prioritas belanja di dalam keterbatasan sumber keuangan.
2. Klasifikasi organic atau berdasarkan organisasi.
Anggaran diklasifikasikan berdasarkan unit pemerintah seperti anggaran kementrian kesehata, anggaran kementrian pendidikan nasional dan seterusnya, termasuk unit organisasi vertical di

bawahnya. Klasifikasi ini memungkinkan untuk melihat besar anggaran setiap unit, pencapaian serta efisiensi dan efektifitasnya, akan tetapi klasifikasi ini tidak memungkinkan untuk melihat pengalokasian anggaran kepada sasaran-sasaran pembangunan pembangunan secara nasional.
Klasifikasi organik dan obyek sebenarnya merupakan dua bentuk pengklasifikasian yang berbeda, namun dalam praktek kedua bentuk klasifikasi ini hampir selalu dipakai secara bersamaan, dalam klasifikasi organic, anggaran dikelompokkan berdasarkan kementrian atau lembaga Negara.
3. Klasifikasi berdasarkan fungsi atau fungsional.
Klasifikasi fungsional biasanya digunakan untuk menunjukkan tujuan umum yang akan dicapai oleh pengeluaran pemerintah, dengan klasifikasi fungsional ini cakrawala pengalokasian dan pengkajian keputusan yang berkaitan dengan anggaran diharapkan dapat diperluas. Sering menjadi masalah dalam klasifikasi fungsional ini adalah : walaupun sebagian besar pengeluaran pemerintah dapat dibagi kedalam berbagai kegiatan fungsional, tetapi kadang-kadang diperlukan pertimbangan khusus dalam mengevaluasi berbagai kegiatan fungsional tersebut.
4. Klasifikasi berdasarkan kehematan atau ekonomis.
Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomisnya sedangkan prioritas belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan kebijakan nasional mengingat terbatasnya pendapatan negara, oleh karena itu didahulukan pendapatan dalam negeri dan belanja operasional kemudian pembiayaan dan belanja modal sesuai dengan tingkat prioritas. Dengan kata lain dalam klasifikasi ekonomis ini, anggaran diklasifikasi sedemikian rupa sehingga menyajikan informasi yang berguna bagi proses pengambilan keputusan ekonomi, hal-hal yang perlu diketahui oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian misalnya perbandingan alokasi anggaran untuk belanja konsumsi dan untuk pengadaan sarana yang bersifat meningkatkan produksi, dampak anggaran terhadap pendapatan, dampak anggaran terhadap penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya.
5. Klasifikasi berdasarkan program.
Yang dimaksud program disini adalah serangkaian kegiatan yang dimulai sejak penyiapan barang dan jasa secara intern sampai dengan penyerahannya kepada pihak ekstern, dengan demikian program pada dasarnya merupakan kumpulan dari beberapa jenis kegiatan atau proyek, oleh sebab itu penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam klasifikasi program lebih ditekankan pada pengelompokan kegiatan dan program. Agar proses pengambilan keputusan manajemen dan analisa kinerja dapat dilakukan secara efektif, maka pelasanaan anggaran dengan klasifikasi program ini perlu dilengkapi dengan standar biaya dan kinerja untuk setiap kegiatan atau proyek, dengan demikian klasifikasi program akan memberikan dasar yang kokoh untuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sumber daya.

6. Klasifikasi terpadu.
Klasifikasi anggaran Indonesia secara berangsur-angsur dilengkapi dengan klasifikasi fungsional atau berdasarkan fungsi dan berdasarkan karakteristik ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia menganut klasifikasi anggaran terpadu.
C. Penyusunan Anggaran.
Berbicara masalah anggaran, APBN/APBD tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman terhadap anggaran negara/daerah yang sering dirumuskan sebagai rencana kerja yang dituangkan dalam rencana keuangan. Dalam hal ini disatu pihak berisikan kebijakan dan program kerja pemerintah dalam bentuk pengeluaran, sedangkan di pihak lain berisikan rencana penerimaan yang diharapkan dapat menutup pengeluaran tersebut. Anggaran merupakan hasil dari perencanaan berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu (Ibnu Syamsi, 1993:90)
Agar dapat menghasilkan anggaran yang baik, dalam penyusunan anggaran harus meperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Keseimbangan, yaitu adanya asumsi yang rasional terjadi keseimbangan antara rencana penerimaan dan pengeluaran.
2. Komprehensif, adalah seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dan mempunyai akibat keuangan harus dicantumkan dalam anggaran.
3. Kemandirian, yaitu adanya usaha-usaha dari daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan.
4. Terperinci, adalah secara detail memuat rincian mengenai penerimaan maupun pengeluaran melalui kode setiap mata anggaran.
5. Disiplin, yaitu rencana APBN/APBD harus sudah diajukan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan sehingga perlu diperhatikan saat penyusunan dan pengesahannya.
6. Fleksibel, karena disadari bahwa anggaran pada dasarnya masih merupakan rencana sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan.
7. Prioritas, yaitu penyusunan anggaran diupayakan dapat mempertajam keutamaan penggunaan dana yang tersedia untuk pembiayaan program dan kegiatan.
8. Keterbukaan, yaitu apabila rancangan anggaran (APBN/APBD) telah disetujui untuk dilaksanakan, maka anggaran tersebut harus dipublikasikan untuk diketahui oleh semua pihak.( Suhadak dan T Nugroho, 2007:44)
Anggaran disusun dengan berbagai system yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan yang pada dasarnya dalam konsep penyusunan anggaran dikenal beberapa system yaitu:

1. Sistem anggaran tradisional (traditional budget) dikenal dengan line-item budgeting system yang menitikberatkan pada pelaksanaan anggaran serta pengawasannya. Dalam pelaksanaan anggaran yang dipentingkan adalah berapa besarnya jatah pada masing-masing lembaga serta sejauh mana lembaga tersebut melaksanakan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Cara penyusunan anggaran dilakukan dengan merinci jenis pendapatan dan belanja, jenis pendapatan disusun seperti pendapatan pajak, non pajak, hibah dan sebagainya, sedangkan belanja disusun berdasarkan jenis belanja seperti belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembayaran bunga dan belanja perimbangan keuangan pusat dan daerah, transfer lain dan belanja modal.
2. Sistem anggaran inkremental (incremental budgeting), dalam sistem ini besarnya dana yang diberikan pada unit-unit atau lembaga diusahakan jumlahnya ditingkatkan secara bertahap karena kebutuhan baik untuk kegiatan pemerintah, pelayanan public dan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Penganggaran dengan metode incremental budgeting pada dasarnya menggunakan line-item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai anggarannya dari tahun sebelumnya.Jones dan Pendlebury (1996) dalam bukunya Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar ( 2009:129) menyatakan tiga alasan mengapa metode ini banyak digunakan yaitu pertama, banyak kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintah yang telah dilakukan tahun lalu dan perlu dilanjutkan untuk tahun ini, kedua, metode ini mudah dilakukan dan menghindari konflik antar unit pemerintah, ketiga, metode ini sangat konsertatif dengan adanya perubahan yang relative kecil atau dengan batas tertentu berdasarkan pertimbangan yang memadai.
3. Revenue budgeting, dalam system anggaran ini dilakukan dengan dasar kemampuan suatu Negara untuk memperoleh pendapatan, selajutnya disusun belanja sesuai dengan kemampuan tersebut. Apabila disusun anggaran belanja sesuai dengan kemampuan memperoleh pendapatan negara, anggaran tersebut berimbang (balance budget), selain itu apabila melebihi pendapatan negara anggaran belanja itu disebut anggaran pengeluaran (spending budget) Sistem anggaran ini akan efektif digunakan oleh suatu Negara yang sangat terbatas terbatas pendapatannya, tetapi situasi ekonomi dan politik relative stabil, adapun system anggaran ini pernah digunakan oleh beberapa Negara bagian di Amerika Serikat.
4. Repetitive budgeting, merupakan penganggaran dengan mengulang anggaran dari tahun –tahun sebelumnya karena adanya kondisi yang tidak stabil di bidang ekonomi dan politik. Dasar pertimbangan menggunakan system anggaran ini karena tidak memungkinkannya menyusun dengan system anggaran lain, hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tidak stabil, dari pada membuat anggaran yang tidak memadai lebih baik menggunakan anggaran tahun lalu yang kemungkinan juga tidak sesuai. Anggaran yang disusun dengan system ini umumnya dilakukan oleh negara kaya maupun negara miskin yang situasi ekonomi dan politiknya tidak stabil.
5. Supplemental budgeting, sistem anggaran ini digunakan dengan cara membuat anggaran yang membuka kesempatan untuk melakukan revisi secara luas, sedangkan cara ini

dilakukan apabila kondisi negara tidak dalam kesulitan pendapatan negara, tetapi memiliki kendala administrasi. Dengan kondisi keuangan yang tidak ada kendala, maka sistem anggaran ini sangat memungkinkan dilakukan, sebaliknya untuk negara yang memiliki kendala pendapatan, maka sistem anggaran ini tidak sesuai untuk diterapkan. Kelebihan pada system anggaran ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata (real) yang sedang berlangsung, tetapi kelemahannya system anggaran ini adalah ketidak jelasan dalam anggaran yang sering berubah, selain itu juga ketidakjelasan arah prioritas dari belanja Negara, meskipun pendapatan tidak ada masalah, namun jika belanja Negara menjadi tidak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan maka hal ini sama dengan pemborosan.
6. Zero-base budgeting, sesuai dengan namanya, anggaran disusun dari nol ( () ) meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari system anggaran incremental yang sering kali ditemukan adanya program yang sudah tidak effektif, tetapi anggarannya justru meningkat, padahal dalam praktek dimungkinkan adanya incremental atas “paket keputusan” atau decision packages yang digunakan dalam penyusunan system anggaran ini. Sistem penyusunan anggaran basis nol ini adalah dengan paket-paket keputusan, adapun paket keputusan (decision package) adalah suatu dokumen yang menggambarkan informasi terkait dengan efek dari berbagai alternatif kegiatan. Secara ringkas proses penganggaran meliputi tiga kegiatan pokok: (1) pengidentifikasian unit keputusan (decision units), yaitu unit organisasi yang akan melaksanakan program, (2) pengembangan paket keputusan (decision packages) yang berisi program yang direncanakan dan alternative lain yang terpisah dari program tersebut (mutually inclusive) atau berupa kelanjutan (incremental) sebagai perbaikan dari program sebelumnya, dan (3) penentuan peringkat decision packages, dengan susunan dari program yang membutuhkan dana yang rendah sampai dengan yang membutuhkan dana yang besar.
7. Planning Programing Budgeting System (PPBS), system anggaran ini dikembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan (decision makers) dapat mengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model-model manajemen keuangan yang ada, dalam system anggaran ini menggunakan analisa biaya-manfaat atau cost and benefit analysis. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan pendapatan dan besarnya belanja merupakan pertimbangan dilakukannya analysis cost and benefits, untuk itu pilihan yang menghasilkan benefits besar yang akan diambil lebih dulu. Dengan kata lain akan dilakukan penyusunan daftar prioritas berdasarkan program yang memiliki manfaat yang besar. Penyusunan anggaran berdasarkan PPBS meliputi lima kegiatan pokok: (1) perumusan tujuan organisasi dan unit-unit dibawahnya, (2) penyusunan program berdasarkan tujuan-tujuan yang sama dari setiap unit, (3) program yang telah tersusun dirinci lagi menjadi aktivitas-aktivitas program (program elements), (4) setiap elemen dibuat analisis biaya dan manfaat, dan ( 5 ) perhitungan biaya dan manfaat dalam

setiap tingkatan program. Program-program yang memiliki manfaat lebih besar dari pada biayanya akan dimasukkan dalam anggaran, sedangkan yang sebaliknya akan ditolak, dengan demikian adanya standar ini yang disampaikan secara transparan kepada legislatif akan memudahkan fungsi pengendaliannya dan memudahkan juga aparat pengawasan dan pemeriksa. Selain itu penganggaran ini dilakukan dengan pendekatan fungsi sehingga program yang sama antar unit dapat dijadikan satu supaya tidak ada tumpang tindih antar unit pemerintahan. Sistem anggaran ini juga mengukur biaya dan manfaat dalam jangka panjang sehingga alokasi sumber daya untuk jangka waktu tersebut dapat dimanfaatkan, serta anggaran selama beberapa tahun bias disusun berdasarkan analisis tersebut.
8. Sistem anggaran kinerja ( performance budgeting), system anggaran ini disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur dari berbagai kegiatan, dan system anggaran ini juga menggunakan klasifikasi berdasarkan obyek seperti line-item budgeting. Dalam system ini yang menitikberatkan pada berbagai segi yang akan dicapai (output), seperti pembangunan social ekonomi dan aspek fisik yang terukur dengan jelas, ditekankan pula segi-segi fungsional dari masing-masing lembaga, pengelompokan setiap kegiatan proyek yang berorientasi dan menekankan pada pengendalian anggaran juga menekankan pada efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan dengan menetapkan standar biaya (cost standard), dengan standar biaya tersebut, disusun anggaran tahun berikutnya dan bisa disesuaikan dengan pertimbangan yang logis.
Keunggulan system anggaran kinerja dari system anggaran lainnya, adalah bahwa system anggaran ini mengubah paradigma dari penilaian kinerja lembaga berdasarkan besarnya dana yang terserap dari suatu program atau kegiatan, selanjutnya pemahaman tentang anggaran dapat diklasifikasikan menurut fungsinya yaitu sebagai fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.
Anggaran berfungsi alokasi menjelaskan tentang peranan pemerintah dalam menjaga kesinambungan penyediaan barang-barang publik serta mengatur alokasi sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat, dalam kaitan dengan kebijakan fiskal, fungsi alokasi ini terkait dengan pangalokasian anggaran pembangunan secara tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, dalam kaitannya dengan hubungan pusat-daerah, fungsi alokasi dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk daerah dalam desentralisasi fiskal seperti pemberian bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang harus dialokasikan secara tepat, misalnya alokasi DAU, dimaksudkan sebagai pengganti transfer dana dari pusat ke daerah selama ini dalam bentuk subsidi daerah otonom (SDO) dan dana inpres yang ditentukan jumlahnya sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri.
Anggaran berfungsi distribusi dimaksudkan sebagai aplikasi dari fungsi distribusi, pemerintah harus berupaya untuk mewujudkan keadilan secara merata, terjadinya disparitas dan ketidak merataan kepemilikan faktor-faktor produksi akan senantiasa berbeda antar kelompok masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu peran pemerintah untuk melakukan intervensi dalam meminimalisasi disparitas tersebut. Salah satu kebijakannya adalah tax and subsidy policy di mana terjadi redistribusi pendapatan masyarakat yang tinggi kepada mereka yang miskin.

Dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal dapat dilihat pula dalam kerangka otonomi daerah bahwa pemerintah pusat mengelola keuangan dan mendistribusikan dana peimbangan secara adil kepada seluruh daerah.
Kemudian dilanjutkan dengan anggaran berfungsi stabilisasi yang bertujuan untuk mencapai stabilisasi pada perekonomian secara umum dan tercermin dari stabilnya indicator-indikator makro ekonomi, perangkat kebijakan fiskal yang dilakukan harus diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makro ekonomi, misalnya mengatasi defisit anggaran. Dari berbagai alternatif pembiayaan yang tersedia (utang dalam negeri, utang luar negeri, penjualan aset, privatisasi atau mencetak uang) harus diperhitungkan mana kombinasi yang dapat diperhitungkan memberikan gejolak terkecil dalam perekonomian, sedangkan dari sisi moneter pemerintah dapat mencapai stabilitas makro (suku bunga, inflasi, nilai tukar dan lain-lain) dengan instrument kebijakan moneter seperti discount rate dan open market operation.
D. Masa Daur Anggaran Negara.
Kadang-kadang pengertian anggaran negara dibedakan dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran, jadi anggaran negara dalam arti luas meliputi suatu daur anggaran negara. Sedangkan arti sempit , anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu satu tahun.
Anggaran negara memiliki beberapa fungsi yaitu :
a. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang. b. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih
pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebuh dahulu.
c. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggung jawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR
Seperti dijelaskan diatas bahwa anggaran negara memiliki suatu masa daur/siklus anggaran, sedangkan daur anggaran adalah proses penganggaran secara terus menerus, dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh pihak yang berwenang. Daur/siklus anggaran negara Republik Indonesia secara umum terdiri atas lima tahap yaitu :
1.Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU-APBN) oleh pemerintah kepada DPR.
a. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23, setiap tahunnya APBN ditetapkan melalui undang-undang.
b. Pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran adalah badan eksekutif.
c. Proses penyusunan dan pengajuan RUU-APBN meliputi :

c.1. Penerbitan Surat Edaran Menteri Keuangan yang berisi permintaan sumbangan anggaran dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan untuk belanja rutin dan Daftar Usulan Proyek untuk belanja pembangunan.
c.2. DUK dan DUP masing-masing Kementerian/lembaga disampaikan pada Direktorat Jendral Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sedangkan untuk DUP juga disampaikan pada Badan Prencana Pembangunan Nasional (Bappenas).
c.3. DUK dibahas di DJA sedangkan DUP dibahas di DJA dan Bappenas.
c.4. Pembuatan rancangan anggaran oleh menteri keuangan dengan melibatkan gubernur bank sentral dan menteri-menteri yang lain dalam tingkat dewan moneter.
c.5. Penyusunan nota keuangan oleh Kemenkeu yang berisi antara lain :
* Kebijakan fiskal dan moneter
* Perkembangan harga, gaji dan upah
* Taksiran penerimaan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang
* Jumlah uang yang beredar.
2. Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-APBN dan penetapan UU APBN.
a. Sebelum tahun anggaran dimulai, pemerintah menyampaikan RUU-APBN, Nota Keuangan dan Perincian Lebih Lanjut kepada DPR , jika DPR menyetujui RUU-APBN tersebut, maka RUU tersebut disahkan menjadi UU, sebaliknya apabila tidak disetujui, maka UU-APBN tahun sebelumnya digunakan kembali (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945).
b. UU-APBN mewajibkan pemerintah menyusun laporan realisasi pada pertengahan tahun anggaran berikut Prognosa enam bulan berikutnya. Laporan realisasi berikut Prognosa dibahas pemerintah dengan DPR. Demikian pula dengan penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, maka pemerintah mengajukan RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN (RUU-TPAPBN).
c. Penyusunan perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan APBN dan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selanjutnya disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun.
3. Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan oleh pemerintah.
a. Pemerintah mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) mengenai Perincian Lebih Lanjut yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pemerintah.

b. Daftar Isian Kegiatan, Daftar Isian Proyek dan Surat Keputusan Otorisasi (DIK, DIP dan SKO) merupakan dokumen dasar pelaksanaan anggaran, ketiganya merupakan kredit anggaran, yaitu batas pengeluaran yang didapat digunakan untuk mengelola kegiatan rutin atau kegiatan pembangunan pemerintah.
c. Setelah DIK diterima oleh Kepala Kantor dan DIP oleh Pemimpin Proyek/ Bendaharawan Proyek, maka telah dapat diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik SPPR (Rutin) dan SPPP (Pembangunan) ke Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN).
d. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dapat berupa SPM-DU (Penyediaan Dana UYHD), SPM-TU (Tambahan UYHD), SPM-GU (Pengganti Dana UYHD), atau SPM-LS (SPM Langsung). SPM-DU digunakan untuk kas kecil dana awal, sedangkan SPM-GU untuk pengisian kembali kas kecil. SPM-LS digunakan untuk pengeluaran di atas Rp. 10.000.000,-. SPM ini kemudian diuangkan pada KPKN.
e. DIK sebagai dasar pelaksanaan amggaran rutin disetujui oleh Menkeu (dilimpahkan ke DJA), sedangkan DIP sebagai dasar pelaksanaan anggaran pembangunan disetujui oleh Menkeu (dilimpahkan ke DJA dan ketua Bappenas). DIK dan DIP ini disebut sebagai otorisasi kredit anggaran (dana anggaran) dan dalam akuntansi disebut allotment.
f. DIK diterbitkan per bagian anggaran (kementerian/lembaga), per unit organisasi (eselon I ) dan per lokasi (propinsi). DIP diterbitkan per proyek/bagian proyek. Dirjen atau Pejabat setingkat yang membawahi proyek segera menyusun Petunjuk Operasional (PO) yang memuat :
f.1 Uraian dan rincian lebih lanjut dari DIP.
f.2. Petunjuk khusus dari pimpinan kementerian/lembaga yang perlu diperhatikan oleh pemimpin proyek dalam pelaksanaan pembangunan proyek.
4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawas fungsional;
a. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan fungsional dalam lingkup pemerintah dan pengawasan oleh atasan langsung.
b. Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh :
b.1. Inspektorat jendral kementerian/lembaga
b.2. Inspektorat wilayah propinsi
b.3. Inspektorat wilayah kabupaten/kota yang bersifat sektoral.
b.4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bersifat lintas sektoral.
c. Pengawasan atasan langsung disebut pengawasan melekat

d. Kepala kantor/pemimpin peoyek dan bendaharawan harus menyampaikan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) dan laporan keadaan kas (LKK)
5. Pembahasan dan persetujuan DPR atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan penetapan UU PAN ;
a. Perhitungan anggaran (pelaksanaan anggaran) dibuat oleh pemerintah untuk diperiksa oleh BPK, kemudian perhitungan anggaran disampaikan ke DPR selambat-lambatnya 18 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir (Pasal 6 UU-APBN).
b. Pertanggung jawaban pemerintah tersebut disebut sebagai PAN, sedangkan PAN disusun berdasarkan Perhitungan Anggaran (PA) dari bagian anggaran (kementerian/lembaga) dan pembukuan Kemenkeu sendiri.
c. Isi PAN mencakup ;
c.1 Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran
c.2. Sisa Anggaran Lebih (SAL) / Sisa Anggaran Kurang (SAK), yaitu realisasi penerimaan dikurangi realisasi pengeluaran
c.3. Perincian SAL/SAK.
d. Selain UU-PAN, disertakan juga nota PAN yang antara lain memuat sebab-sebab perbedaan yang terdapat antara anggaran dan realisasinya serta penetapan surplus (SAL) dan deficit (SAK). Nota PAN juga memuat hasil pemeriksaan BPK atas PAN.
Sejak dulu pembukuan APBN pada dasarnya menggunakan basis kas, sedangkan basis kas ini digunakan untuk pendapatan dan pengeluaran anggaran, namun seiring dengan aplikasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis kas berangsur ditinggalkan dan seterusnya menggunakan basis akrual.
Istilah dan prosedur tersebut dapat saja berubah/bervariasi, tergantung pada peraturan perundang –undangan yang sedang berlaku, peraturan perundangan yang berlaku saat ini pada prinsipnya memuat isi yang sama, tetapi istilah dan nama seperti formulir dan kelembagaan mengalami perubahan, misalnya istilah DUK dan DUP sudah tidak dikenal, namun diganti dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), bendahara proyek diganti istilahnya dengan bendahara pengeluaran dan sebagainya.
Pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, proses seperti yang dikemukakan dalam daur anggaran di atas dikemukakan sebagai berikut :
1. Penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah.

2. Pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh DPR dan pemerintah 3. Penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman bagi
kementerian/lembaga.4. Menteri/pemimpin lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran tahun berikut
berdasarkan target prestasi yang hendak dicapai 5.
Menteri/pemimpin lembaga melakukan pembahasan dengan komisi DPR mengenai rancangan anggaran, sesuai dengan pedoman dari menteri keuangan, dan hasilnya juga disampaikan kepada menteri keuangan
6. Presiden menyampaikan RAPBN pada pertengahan Agustus.7. Penetapan APBN dilakukan dua bulan sebelum awal tahun anggaran yang bersangkutan
agar dokumen pelaksanaan anggaran dapat diterbitkan tepat waktu dan pemerintah daerah mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun dan menetapkan APBD
8. Dalam membahas dan menetapkan anggaran, UU Susunan dan Kedudukan mengatur kewenangan panitia anggaran dan komisi-komisi sektoral pada lembaga legislative.
Dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangan negara diberlakukan aturan sebagai berikut :
1. Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Laporan keuangan (setidak-tidaknya) terdiri atas : a. Laporan Realisasi APBN b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan
badan lain).
E.Anggaran Pemerintah Di Indonesia.

Anggaran di Indonesia telah mengalami perkembangan-perkembangan seperti anggaran yang mengedepankan belanja (spending/deficit budget) dan anggaran pendapatan dan belanja yang seimbang (balance budget). Sejak tahun 1999, struktur anggaran pendapatan dan belanja yang realistis, sebagai contoh, penerimaan pinjaman luar negeri yang sebelumnya merupakan anggaran pendapatan pembangunan berubah menjadi anggaran penerimaan pembiayaan luar negeri, sedangkan pinjaman tersebut bukan merupakan pendapatan negara melainkan merupakan penerimaan yang harus dibayar pada saat jatuh tempo pinjaman tersebut atau merupakan suatu utang pemerintah.
Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis, fungsi, organisasi dan kegiatan.
1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
Struktur APBN berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja yang terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan, sedangkan pendapatan dikelompokkan menjadi : pendapatan negara dan pendapatan hibah.
a. Pendapatan Negara, terdiri dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah.
a.1. Pendapatan dalam negeri dikelompokkan dalam kelompok besar yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan perpajakan yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat berasal dari berbagai jenis pajak
Pajak dalam negeri diperoleh dari :
Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas dan sebagainya. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) di dalam APBN dikelompokkan menjadi dua, yaitu penerimaan PPh dari sector migas dan penerimaan PPh dari sector non migas.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun PPN dipungut 10% dari harga barang dan jasa.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Biaya Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan, sedangkan biaya yang dikenakan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cukai merupakan penerimaan yang dipungut dari cukai tembakau dan rokok, alcohol serta minuman yang mengandung etil alcohol.
Pajak lainnya diperoleh dari penerimaan seperti biaya materai.
Pajak perdagangan internasional.

Pajak perdagangan internasional berasal dari penerimaan bea masuk dari kegiatan impor barang dan pajak ekspor barang. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (SDA), bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. Penerimaan dari SDA yaitu penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Penerimaan dari bagian laba BUMN merupakan penerimaan yang berasal dari keuntungan BUMN yang dibagikan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang saham tersebut. Penerimaan PNBP lainnya diperoleh dari sewa fasilitas negara, jasa-jasa tertentu yang diberikan seperti pernikahan, pengadilan dan sebagainya.
a.2. Pendapatan hibah.
Pendapatan hibah merupakan pendapatan yang diberikan oleh pihak lain baik dari negara lain maupun lembaga atau perseorangan kepada pemerintah tanpa menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali dengan mengeluarkan sumber daya ekonomi.
b. Belanja Negara.
Belanja dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
b.1. Belanja Pemerintah Pusat.
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja social dan belanja modal. Selain klasifikasi berdasarkan jenis belanja tersebut, belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi yaitu belanja (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) kependudukan dan perlindungan social.
b.2. Belanja untuk Daerah.
Belanja untuk daerah merupakan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Dana otonomi khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang mendapatkan otonomi khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh Propinsi Papua mendapatkan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Dana penyesuaian merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai kebijakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
c. Pembiayaan Negara.
Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan yang digunakan untuk menutup defisit atau menggunakan surplus.

Pembiayaan negara tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri, sedangkan pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Struktur APBD berdasarkan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Pendapatan daerah.
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain
lain pendapatan yang sah.
a.1. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pajak dan retribusi daerah.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah berasal dari bagian laba dari penyertaan pemerintah daerah. Penyertaan pemerintah daerah tersebut terdiri dari penyertaan pada badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
Lain-lain PAD yang sah berupa hasil penjualan kekayaan daerah seperti asset tetap daerah, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, penerimaan komisi, selisih keuntungan kurs, pendapatan denda, pendapatan hasil eksekusi jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social umum, pendapatan dari jasa pendidikan dan pelatihan serta pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
a.2. Dana Perimbangan.
Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah dari transfer dana dari pemerintah pusat berupa belanja untuk daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
a.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan propinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan dari pemerintah lain.
b. Belanja Daerah.
Belanja daerah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar yaitu : (1) belanja tidak langsung dan (2) belanja langsung.

b.1 Belanja tidak langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja pegawai dalam hal ini merupakan belanja untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pejabat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk di dalamnya pimpinan dan anggota DPRD.
b.2. Belanja langsung.
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Klasifikasi belanja sesuai fungsi sama dengan klasifikasi belanja sesuai fungsi dalam APBN, hal ini untuk memudahkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan / manajemen keuangan negara.
c. Pembiayaan.
Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan yang digunakan untuk menutup deficit atau menggunakan surplus. Pembiayaan negara tersebut terdiri dari pembiayaan dalam begeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dan pembiayaan non perbankan, sedangkan pembiayaan dalam negeri tersebut juga diperoleh dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penggunaan dana cadangan.

F.Proses Penganggaran.
Reformasi bidang keuangan negara dimulai dengan penyempurnaan proses penganggaran. Sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan berikut ini.
1. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran
Dalam penyusunan anggaran dewasa ini digunakan pendekatan budget is a plan, a plan is budget, oleh karena itu antara rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan, disusun secara terintegrasi. Untuk melaksanakan konsep ini Pemerintah Daerah harus memiliki rencana kerja dengan indikator kinerja yang terukur sebagai prasyarat.
2. Penyatuan anggaran (unified budget)
Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran ini adalah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai satu dokumen anggaran. Kepala satuan kerja perangkat daerah bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan anggaran di kantornya. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. Dengan pendekatan ini

diharapkan tidak terjadi duplikasi anggaran, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif.
3. Penganggaran Berbasis Kinerja
Konsep yang digunakan dalam anggaran ini adalah alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu untuk keperluan ini diperlukan adanya program/kegiatan yang jelas, yang akan dilaksanakan pada suatu tahun anggaran. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini diperlukan adanya: indikator kinerja, khususnya output (keluaran) dan outcome (hasil), standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, standar analisa biaya, dan biaya standar keluaran yang dihasilkan.
4. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Pemerintah dituntut untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah/Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD Pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya sehubungan dengan adanya program/kegiatan tersebut.
5. Klasifikasi anggaran
Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan, Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan mengacu pada Government Finance Statistic (GFS) sebagaimana yang dudah diterapkan di berbagai negara. Klasifikasi anggaran dimaksud terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja.
Dalam rangka penyusunan anggaran, proses dipilah menjadi dua tahapan, yaitu tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Tahap perencanaan pada pemerintah pusat dikoordinir oleh Bappenas sedang pada pemerintah daerah dikoordinir oleh satuan kerja perencanaan daerah. Tahap penganggaran dipimpin oleh Kementerian Keuangan pada Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah.
Penyusunan rencana kerja dimulai pada bulan Januari dengan menyiapkan rancangan kebijakan umum, program indikatif, dan pagu indikatif, yang diperlukan oleh Kementrian/Lembaga/SKPD untuk menyusun RKA-KL/RKA-SKPD. Rancangan RKP/RKPD ini selesai bulan Juni untuk selanjutnya disampaikan ke DPR/DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. Setelah disepakati bersama dengan DPR/DPRD, maka kebijakan umum, program prioritas, dan plafon anggaran sementara, akan menjadi dasar bagi Kementrian/Lembaga/SKPD untuk menyusun RKA. RKA ini selanjutnya digunakan untuk menyusun RAPBN/RAPBD yang wajib disampaikan ke legislatif untuk dibahas dan diperbaiki sebelum disetujui untuk ditetapkan menjadi APBN/APBD.

Proses pengesahan RAPBN dilakukan setelah ada persetujuan oleh DPR, pada RAPBD ada tambahan proses evaluasi. Evaluasi atas RAPBD yang telah disetujui oleh DPRD dilakukan oleh gubernur untuk RAPBD kabupaten/kota dan Mendagri untuk RAPBD provinsi. Proses evaluasi yang diatur dalam UU 32/2004 dan diatur lebih lanjut dalam PP 58/2005 bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
G. Pelaksanaan Anggaran/Perbendaharaan
Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA. Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementrian/lembaga. Setelah masa transisi pada TA 2005, maka pada TA 2006, DIPA sudah dapat serentak dibagikan pada awal sekali TA 2006 dimulai, tepatnya tanggal 2 Januari 2006 yang lalu. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah pun ditempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur.
Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA. Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Dokumen ini disertai dengan rencana penarikan dana untuk mendanai kegiatan dan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan maka rencana penerimaan kas juga dilampirkan. DPA disampaikan kepada kepala SKPKD untuk dimintakan pengesahan.
Jika DIPA bagi kementerian/lembaga sudah dapat dijadikan dokumen untuk segera melaksanakan anggaran Pemerintah Pusat, pada pemerintah daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD merupakan suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. SPD ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan melaksanakan kegiatan sudah tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, ada dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
1. Sistem Penerimaan
Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (Azas Bruto). Pendapatan diakui setelah uang disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh karena itu penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2. Sistem Pembayaran
Belanja membebani anggaran daerah setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Umum Daerah.
Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem LS. Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah tertentu. Cara lainnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan melalui Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran.
MODUL 3AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
A. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Kerangka konseptual akuntansi menjelaskan antara lain asumsi dasar, karakteristik kualitatif laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan pokok, prinsip-prinsip akuntansi dan kendala informasi yang relevan dan andal. Mengingat akuntansi tidak seperti ilmu eksakta, pengembangan prinsip akuntansi yang diatur dalam suatu kerangka konseptual harus mendapatkan akseptabilitas atau pengakuan dari para pengguna dan institusi atau pihak yang relevan lainnya.Pengembangan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh komite independen yang dibentuk oleh pemerintah, sebelum menjadi suatu ketetapan, kerangka konseptual tersebut didiskusikan dengan banyak pihak dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal tersebut dilakukan selain untuk memenuhi akseptabilitas, juga memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerangka konseptual merupakan konsep yang mendasari pengembangan standar akuntansi, penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas dan penyelesaian masalah yang belum diatur

dalam standar akuntansi, dengan demikian tujuan dari kerangka konseptual adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan lainnya. Didalam akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual telah diatur dan ditetapkan sebelum standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan tersebut digunakan sebagai acuan bagi pengguna laporan keuangan terhadap permasalahan yang belum diatur dalam suatu standar akuntansi pemerintahan tertentu, namun demikian apabila terdapat pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi pemerintahan maka standar akuntansi pemerintahan yang diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual.Kerangka konseptual tersebut merupakan pedoman dasar akuntansi pemerintahan untuk memenuhi tujuan yang dijelas sebagai berikut :
a. Bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual merupakan acuan dalam menyusun standar tersebut.
b. Bagi penyusun laporan keuangan, kerangka konseptual merupakan acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang ditemui dalam praktek yang belum diatur dalam suatu standar akuntansi pemerintahan tertentu.
c. Bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat atau opini atas kewajaran laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
d. Bagi para pengguna laporan keuangan, kerangka konseptual merupakan acuan dalam menafsirkan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. .
B. Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan.
Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tujuan tiga hal. Pertama adalah untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka. Kedua adalah untuk terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Terakhir adalah untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana jenis dan isi diatur oleh PP 24/2005 tentang SAP. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, secara umum tata cara dan tanggung jawab pelaporan diatur dalam PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan PP 8/2006, tanggung jawab atas pelaksanaan APBN/APBD ada pada entitas pelaporan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu sebagai bendahara umum dan sebagai pengguna annggaran. Terkait dengan hal itu, sistem akuntansi pemerintah pun terdiri

dari dua bagian bagian utama, baik itu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama adalah sistem yang berlaku untuk instansi yang bertindak sebagai pengguna anggaran yang diterapkan pada satuan kerja. Sesuai dengan perannya sebagai pengguna anggaran, bagian sistem ini terutama untuk mencatat pendapatan, belanja dan aset yang menjadi kewenangannya. Pendapatan yang dikelola oleh pengguna anggaran adalah bukan pajak atau retribusi untuk daerah. Pendapatan jenis ini pada umumnya terkait dengan jasa yang diberikan oleh instansi yang mengelola. Selanjutnya adalah proses akuntansi yang terkait dengan belanja, baik itu yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan maupun dengan sistem langsung yang pembayarannya langsung dari kas umum. Akuntansi atas belanja akan merupakan kegiatan yang paling banyak dan rumit dibanding akuntansi atas transaksi-transaksi lainnya karena itu merupakan bagian utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sebagai pengguna anggaran, satuan kerja juga wajib melakukan pencatatan atas aset yang dikelola dan digunakan. Hal ini penting dilakukan karena satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan aset yang digunakan. Dari kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran, pada akhir periode akan menghasilkan tiga laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Bagian kedua adalah sistem yang berlaku untuk bendahara umum. Bagian ini terutama mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaannya kepada satuan kerja pengguna anggaran, misalnya pendapatan bunga dan hasil investasi. Dalam pencatatan atas belanja pun ada belanja-belanja yang tidak diserahkan kepada satuan kerja pengguna anggaran, misalnya belanja bunga, hibah dan dana perimbangan. Selain itu, transaksi pembiayaan juga dilaksanakan oleh bendahara umum. Termasuk dalam jenis transaksi ini antara lain investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi dan pemberian pinjaman jangka kepada pihak lain. Dari pelaksanaan akuntansi ini oleh bendahara umum ini, ada 4 jenis laporan yang dihasilkan, yaitu LRA, Neraca, LAK dan CaLK.
Gambar-1
SKPD LRA
Neraca
CaLK
LRA
Neraca
CaLK
LAK
LRA
Neraca
CaLK
LAKPPKD
SistemAkuntansiSatker
SistemAkuntansi
BUD
BUD/ SKPKD
diserahkan
Kep
ala
Daera
h

Dari dua bagian sistem tadi, pada akhir periode laporan-laporan yang dihasilkan akan digabungkan untuk menjadi laporan entitas yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK. Empat laporan itu akan menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan kepada lembaga legislatif mewakili rakyat. Hubungan dua bagian sistem itu dapat digambarkan dalam Gambar-1 di atas.
Secara umum dapat digambarkan bahwa empat jenis laporan keuangan tersebut merupakan satu kesatuan laporan. LRA, Neraca dan LAK merupakan lembar muka dari laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian pada bagian berikutnya disajikan penjelasan atas tiga laporan tersebut dalam bentuk CaLK.
C. Laporan Realisasi Anggaran
1. Pengertian
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.
2. Ruang Lingkup
APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

Pendapatan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu jenis pendapatan yang dipungut dan/atau diterima oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan Undang-Undang. Belanja mencakup seluruh jenis belanja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembiayaan mencakup seluruh transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Disamping itu terdapat transfer antar pemerintahan sehubungan dengan adanya desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan. Bagi yang menerima dikelompokkan dalam pendapatan transfer, sedangkan bagi yang memberikan ditampung dalam belanja transfer.
Anggaran pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk APBD, yang merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama suatu periode terntentu. Anggaran diukur dengan satuan rupiah. Anggaran diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja yang dituangkan dalam Perda APBD disebut sebagai apropriasi, yaitu merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan anggaran pendapatan dalam Perda APBD disebut Estimasi Pendapatan.
Berdasarkan APBD selanjutnya disiapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD. Anggaran yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran pendapatan SKPD pada DPA disebut Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan. Anggaran belanja pada DPA disebut Allotment. Dengan demikian, LRA SKPD membandingkan antara realisasi terhadap alokasi anggaran dalam DPA SKPD yang bersangkutan, sedangkan untuk LRA di tingkat pemerintah daerah realisasi anggaran dibandingkan dengan estimasi pendapatan dan apropriasi yang tertuang dalam APBD.

D. Basis Akuntansi
1. Basis Anggaran dan Basis Akuntansi
Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya.
Apabila ada pemerintah daerah yang menerapkan basis akrual penuh dalam sistem akuntansinya, termasuk untuk pendapatan dan belanja, maka dalam penyusunan LRA, laporan yang dihasilkan dari basis akrual tersebut harus dikonversi ke LRA berbasis kas. Konversi dari LRA berbasis akrual ke LRA wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengakuan Pendapatan
Sistem penerimaan pendapatan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan:
Wajib bayar/masyarakat langsung menyetor ke rekening Kas Umum Daerah.
Wajib bayar/masyarakat menyetor ke juru pungut/Bendahara Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan tersebut menyetor ke rekening Kas Umum Daerah.
Dengan menggunakan basis kas, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, pada saat uang diterima juru pungut/Bendahara Penerimaan, jumlah tersebut belum diakui sebagai pendapatan daerah, pengakuannya baru dilakukan setelah uang tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
3. Pengakuan Belanja
Sistem pembayaran dalam pelaksanaan anggaran ada dua, yaitu:
Pembayaran langsung kepada yang berhak
Pembayaran dengan dana kas kecil melalui Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan Basis Kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 2, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (SKPKD).
Dengan demikian, untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga/vendor pengakuan belanjanya dilakukan pada saat uang dikeluarkan, yaitu pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Sedangkan untuk pembayaran dengan dana kas kecil, pada saat diterbitkannya SP2D untuk pemberian uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran (SP2D UP) ataupun untuk penambahan uang persediaan (SP2D TU) belum diakui sebagai belanja. Pengeluaran tersebut merupakan transaksi transito yang belum membebani anggaran. Pengakuan belanja baru dilakukan setelah pengeluaran yang dilakukan dipertanggungjawabkan olah Bendahara Pengeluaran dan telah diverifikasi serta disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditandai dengan diberikannya pengganti uang persediaan dengan diterbitkannya SP2D GU.
4. Pengakuan Pembiayaan
Pelaksanaan anggaran pembiayaan merupakan kewenangan Bendahara Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum

Daerah. Dengan demikian, perlakuan pengakuan penerimaan pembiayaan ini sama dengan pengakuan pendapatan sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan antara lain untuk pemberian pinjaman, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan. Pembayarannya dapat dilakukan melalui pembayaran langsung atau melalui Bendahara Pengeluaran dengan uang persediaan. Pengakuannya sama dengan pengakuan belanja, yaitu untuk pembayaran langsung diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS sedangkan untuk pembayaran melalui uang persediaan dilakukan setelah pertanggungjawaban atas pengeluaran ini diverifikasi dan disetujui oleh SKPKD.

E.
1. Struktur Anggaran
Anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Struktur anggaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan .....................
b. Belanja .....................
c. Surplus/Defisit (a – b) .....................
d. Pembiayaan: .....................
Penerimaan Pembiayaan (d1) .....................
Pengeluaran Pembiayaan (d2) .....................
Pembiayaan Neto (d1 – d2) .....................
e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (c – d) .....................
2. Pendapatan
Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang Sah.
a. Pendapatan Asli daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pajak yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri dari:
- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD
b. Pendapatan transfer
Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sesuai dengan UU No. 33/2004 dan transfer lainnya sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam, atau dalam UU APBN. Transfer dari Daerah Otonom lainnya antara lain seperti Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Pajak Bahan Bakar, Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di atas, yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya hibah dan dana darurat.

3. . Belanja
Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi. Klasifikasi belanja menurut organisasi artinya anggaran dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Klasifikasi menurut organisasi ini tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan, melainkan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan.
a. Klasifikasi Fungsi
Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut:
- Pelayanan Umum
- Pertahanan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi
- Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Fasilitas Umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya
- Agama
- Pendidikan
- Perlindungan Sosial
Klasifikasi fungsi ini diisi sesuai dengan urusan (affair) pemerintahan. Dengan demikian, klasifikasi fungsi ini perlu dilihat hubungannya dengan program dan kegiatan suatu entitas atau satuan kerja. Klasifikasi fungsi ini disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan UU No. 17/2003 fungsi Pertahanan hanya berlaku untuk Pemerintah Pusat.
b. Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga
Berdasarkan karakternya belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.
Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
c. Klasifikasi Ekonomi
Klasifikasi ekonomi adalah klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanjanya, terdiri dari:
Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai xxx
- Belanja Barang xxx
- Bunga xxx
- Subsidi xxx
- Hibah xxx
- Bantuan Sosial xxx
- Belanja Operasi-lainnya xxx
Belanja Modal:
- Belanja Modal - Tanah xxx
- Belanja Modal – Peralatan dan mesin xxx
- Belanja Modal – Gedung dan Bangunan xxx
- Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx
- Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya xxx
- Belanja Modal - Aset Lainnya xxx
Belanja Tak Terduga xxx
4. Transfer
Transfer yang dimaksud di sini adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil. Contoh: bagi pemerintah provinsi terdapat bagi hasil ke kabupaten/kota, bagi pemerintah kabupaten terdapat bagi hasil ke desa.
5. Surplus/Defisit
Surplus/Defisit timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, di mana jumlah pendapatan tidak sama dengan jumlah belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
7. Pembiayaan Neto
Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila manajemen keuangan pemerintah dilakukan dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini seharusnya mendekati jumlah surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.
8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan neto.
LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan keuangan, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

F. AKUNTANSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
1. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran dialokasikan, dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran ditandai dengan terbitnya Perda APBD. Akuntansi diselenggarakan di SKPD dan di BUD. Akuntansi di SKPD dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Akuntansi di tingkat BUD terutama dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas.
Akuntansi anggaran untuk Perda APBD dilakukan di BUD. Ilustrasi akuntansi untuk anggaran yang disahkan dengan Perda APBD adalah:
Tanggal Uraian Ref Debet KreditEstimasi Pendapatan xxx Apropriasi Belanja xxx Surplus/Defisit xxxEstimasi Penerimaan Pembiayaan xxxPembiayaan Neto xxx Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Xxx
Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD), berarti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai hak untuk menggunakan dana maksimal sebesar anggaran belanja yang dialokasikan dan SKPD mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pendapatan ke BUD sebesar alokasi estimasi pendapatan yang dituangkan di DPA SKPD. Jurnal pengalokasian dana berupa DPA-SKPD dicatat seperti berikut:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditEstimasi Pendapatan yg Dialokasikan xxx Utang kepada BUD xxx
Piutang kepada BUD xxx Allotment Belanja xxx
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditAlokasi Estimasi Pendapatan xxx Alokasi Apropriasi Belanja xxx

Apabila pemerintah belum siap melaksanakan akuntansi anggaran maka, anggaran yang disahkan dan anggaran yang dialokasikan dapat dicatat secara tata buku tunggal (single entry accounting).
2. Akuntansi Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Seperti diuraikan di atas bahwa penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Apabila pendapatan lansung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan Utang kepada BUD. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat dengan mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Apabila pendapatan disetor melalui bendahara penerimaan, maka SKPD akan mendebet Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit Pendapatan yang Ditangguhkan. Pendapatan yang Ditangguhkan mencerminkan adanya kewajiban bagi SKPD untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan utang SKPD kepada BUD. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Selanjutnya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akun Pendapatan yang Ditangguhkan. Jurnal balik dilakukan dengan mendebet Pendapatan yang Ditangguhkan dan mengkredit Kas di Bendahara Penerimaan.
BUD tidak melakukan pencatatan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan. BUD melakukan pencatatan pada saat kas telah disetorkan dan diterima pada rekening Kas Umum Daerah, dengan mendebet Kas di Kas Daerah dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan BUD.
Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah.
Berikut ini ilustrasi akuntansi untuk penerimaan pendapatan pajak:
Pendapatan yang disetor ke BUD
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD xxx Pendapatan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah xxx Pendapatan .... xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)
Pendapatan melalui Kas Bendahara Penerimaan
SKPD
Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit

Kas Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan yang Ditangguhkan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)
Penyetoran kas oleh SKPD kepada BUD
Jurnal 1
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD xxx Pendapatan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)
Jurnal 2
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPendapatan yang Ditangguhkan xxx Kas Bendahara Penerimaan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)
BUD
Penerimaan Kas pada SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditTidak ada Jurnal
Penerimaan Setoran Kas dari SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah xxx Pendapatan.... xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Contoh:
Pemerintah Provinsi X memberikan kuasa kepada PT Y untuk melakukan pemungutan Pajak Bahan Bakar dengan memberikan upah pungut sebesar 2% dari jumlah penerimaan. Dalam bulan Mei 2006 jumlah penerimaan Pajak Bahan Bakar Rp100 juta, dengan upah pungut yang dipotong langsung Rp2 juta.
Jurnal untuk contoh tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUtang Kepada BUD 100 juta Pendapatan Pajak 100 juta

(Buku Pembantu: Pajak Bahan Bakar)
Belanja Barang 2 juta Piutang dari BUD 2 juta(Untuk mencatat upah pungut)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah 100 juta Pendapatan Pajak 100 juta(Buku Pembantu: Pajak Bahan Bakar)
Belanja Barang 2 juta Kas di Kas Daerah 2 juta(Untuk mencatat upah pungut)
Terhadap pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap/lainnya perlu ada jurnal pendamping untuk mengakui penurunan aset yang bersangkutan pada SKPD. Jurnal pendamping ini sering disebut Jurnal Korolari.
Sebagai contoh:
Diterima hasil penjualan kendaraan bermotor sebesar Rp10 juta. Harga perolehan kendaraan tersebut Rp20 juta.
Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD 10 juta Pendapatan Lain-lain PAD 10 juta(Untuk mencatat hasil penjualan kendaraan)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 20 juta Peralatan dan Mesin 20 juta(Untuk mencatat mesin yang dijual)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah 10 juta Pendapatan Lain-lain PAD 10 juta(Untuk mencatat hasil penjualan kendaraan)
Apabila terdapat pengembalian pendapatan maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang

pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Contoh:
Berdasarkan peraturan perundang-undangan pembayaran Pajak X dibayar secara cicilan setiap bulan berdasarkan jumlah pajak yang dibayar pada tahun sebelumnya. Dalam tahun 2005 jumlah pajak yang sudah dibayar setap bulan sebesar Rp1.200.000,00. Ternyata setelah diperhitungkan pada akhir tahun, pajak yang menjadi beban perusahaan tersebut pada tahun 2005 hanya Rp1.000.000,00. Pengembalian kelebihan pajak Rp200.000,00 ini dibayarkan pada bulan Maret 2006.
Jurnal untuk pengembalian pendapatan pada tahun 2006 tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPendapatan Pajak 200 juta Utang kepada BUD 200 juta
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPendapatan Pajak 200 juta Kas di Kas Daerah 200 juta
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Contoh:
Pada periode Januari sampai dengan November 2005 terdapat penerimaan pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar Rp100 juta. Pada bulan Desember 2005 diketemukan adanya kesalahan dan kelebihan penerimaan sebesar Rp5 juta. Kelebihan ini dikembalikan kepada yang berhak pada bulan Desember 2005.
Jurnal untuk pengembalian pendapatan pada tahun 2005 tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPendapatan Retribusi 5 juta Utang kepada BUD 5 juta
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPendapatan Retribusi 5 juta Kas di Kas Daerah 5 juta
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Contoh:
Pada tahun 2005 terdapat penjualan tanah pemda seluas 1.050 m2 dengan harga Rp1.000,00 per m2. Pada tahun 2005 telah diterima seluruhnya. Pada tahun 2006 oleh pembeli dilakukan pengukuran
ulang, ternyata luasnya hanya 1.000 m2, sehingga Pemerintah daerah harus mengembalikan 50 x Rp1.000,00 = Rp50.000,00. Pada tahun 2006 tidak terjadi lagi penjualan tanah oleh pemda.
Pengembalian pendapatan yang diterima tahun lalu pada umumnya dibayar oleh BUD maka transaksi ini tidak dibukukan oleh SKPD. Transaksi tersebut mengurangi ekuitas dana. Pengembalian tersebut dicatat oleh BUD dengan mendebet SILPA dan mengkredit Kas di Kas Daerah.
Jurnal untuk pengembalian pendapatan pada tahun 2006 tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditTidak ada Jurnal
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditSILPA (Pengembalian Pendapatan) 50.000 Kas di Kas Daerah 50.000
3. Akuntansi Belanja
Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang/jasa yang dibeli diterima Pemerintah. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran.
a. Pembayaran langsung
Pembayaran diberikan secara langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).
Contoh:
pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2006 dengan SP2D LS sebesar Rp50 juta. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Askes, Taspen, dan Taperum sebesar Rp3 juta.
Jurnal untuk pembayaran gaji pegawai tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Pegawai 50 juta Piutang dari BUD 50 juta(Untuk mencatat belanja pegawai)

BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Pegawai 50 juta Kas di Kas Daerah 50 juta(Untuk mencatat belanja pegawai)
Kas di Kas Daerah 3 juta Penerimaan PFK 3 juta
Potongan atas pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pihak lain dicatat sebagai penerimaan PFK, sebaliknya pada saat disetorkan kepada pihak lain yang berhak dicatat sebagai Penyetoran PFK. Penerimaan dan penyetoran PFK ini bukan transaksi anggaran tetapi dalam istilah keuangan dikenal sebagai transaksi transito. Oleh karena itu penerimaan/pengeluaran PFK tidak disajikan dalam LRA tetapi disajikan dalam Laporan Arus Kas.
Contoh:
Apabila potongan sebesar Rp3 juta di atas disetor ke Kas Negara akan dijurnal:
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPengeluaran PFK 3 juta Kas di Kas Daerah 3 juta(Untuk mencatat penyetoran PFK)
Apabila terdapat belanja untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya, maka pada saat terjadi pembayaran tidak hanya dilakukan pencatatan belanja tetapi sekaligus perolehan asetnya. Pencatatan aset tetap yang diperoleh dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pendamping yang seringkali dikenal sebagai jurnal korolari.
Contoh:
Dibeli mesin fotocopy seharga Rp60 juta dari PT Tritanu dan sudah dibayar secara langsung dengan SP2D LS pada tanggal 30 Mei 2006.
Jurnal untuk pembelian mesin fotocopy tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Modal – Peralatan dan Mesin 60 juta Piutang dari BUD 60 juta(Untuk mencatat realisasi belanja modal)
Peralatan dan Mesin 60 juta Diinvestasikan dalam Aset Tetap 60 juta(Untuk mencatat perolehan mesin fotocopy)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin 60 juta Kas di Kas Daerah 60 juta(Untuk mencatat realisasi belanja modal)
b. Pembayaran melalui Dana Kas Kecil
Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari perkantoran. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap. Dana kas kecil ini disebut Uang Persediaan (UP). Pada saat uang persediaan diberikan kepada para Bendahara Pengeluaran belum membebani belanja. Belanja baru diakui setelah pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit perbendaharaan, dalam hal ini Kuasa BUD, ditandai dengan terbitnya SPM GU atau SPM GU Nihil.
Contoh:
Diberikan uang persediaan sebesar Rp10 juta kepada Sdr. Zulfikar, Bendahara pengeluaran di Dinas Perindustrian.
Jurnal untuk pemberian uang persediaan tersebut adalah:
SKPD
No. Uraian Ref Debet KreditKas di Bendahara Pengeluaran 10 juta Uang Muka dari BUD 10 juta(Untuk mencatat pemberian uang muka kerja)
BUD
No. Uraian Ref Debet KreditUang Muka Kepada SKPD 10 juta Kas di Kas Daerah 10 juta(Untuk mencatat pemberian uang muka kerja)
Pada saat dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan barulah diakui sebagai belanja. Dengan sistem dana tetap, maka dalam tahun berjalan kepada SKPD akan diberikan SP2D GU sebagai pengganti uang yang telah dibelanjakan sehingga UP di Bendahara Pengeluaran kembali ke jumlah UP semula.
Contoh:
Dari UP telah dibelanjakan Rp8 juta untuk biaya perjalanan dinas. Pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan ke SKPKD dan setelah diverifikasi pengeluaran tersebut disetujui. Selanjutnya diberikan pengganti dengan menerbitkan SP2D-GU sebesar Rp8 juta.
Jurnal untuk pertanggungjawaban UP serta penggantian tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Barang 8 juta Piutang dari BUD 8 juta

(Untuk mencatat belanja perjalanan dinas)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Barang 8 juta Kas di Kas Daerah 8 juta
Dalam hal terdapat kebutuhan pengeluaran kas yang besar, melebihi UP yang tersedia, SKPD dapat mengajukan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) kepada BUD. Perlakuan akuntansi TUP ini adalah seperti dana kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi. TUP ini harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan. Terhadap TUP yang telah dipertanggungjawabkan tidak diberikan penggantian. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP diterbitkan SP2D GU Nihil.
Contoh:
Diberikan TUP Rp 25 juta kepada Bendahara Pengeluaan Dinas Perdagangan.
Jurnal untuk pemberian TUP adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Bendahara Pengeluaran 25 juta Uang Muka dari BUD 25 juta(Untuk mencatat TUP)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUang Muka ke SKPD 25 juta Kas di Kas Daerah 25 juta(Untuk mencatat TUP)
Dari TUP tersebut telah dikeluarkan untuk belanja perjalanan dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp20 juta dan telah diterbitkan SP2D GU Nihil.
SKPD
Jurnal 1: untuk mengakui realisasi belanja
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Barang 20 juta Piutang dari BUD 20 juta(Untuk mencatat belanja perjalanan dinas)
Jurnal 2: untuk mengurangi uang muka
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUang muka dari BUD 20 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran 20 juta(Untuk mencatat belanja perjalanan dinas)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Barang 20 juta Uang Muka ke SKPD 20 juta
Pemerintah pada umumnya mengeluarkan ketentuan tentang batas akhir penerbitan SP2D GU sebagai pengganti UP yang telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pertanggungjawaban atas pengeluaran UP yang telah melewati batas akhir penerbitan SP2D GU tidak diberikan penggantian kas. Pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran akan diterbitkan SP2D GU Nihil. Sisa UP pada akhir tahun anggaran disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah. Sebagai bukti penyetoran akan diperoleh Surat Tanda Setoran (STS). Demikian pula sisa TUP, apabila kegiatan sudah selesai maka sisa TUP harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah.
Contoh:
Dari UP sejumlah Rp10 juta telah dibelanjakan Rp9 juta untuk belanja barang dan jasa. Pengeluaran ini dipertanggungjawabkan pada tanggal 27 Desember 2005. Terhadap pengeluaran ini tidak diberikan penggantian UP, tetapi diterbitkan SPM dan SP2D GU Nihil.
Jurnal SPM dan SP2D GU Nihil, adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Barang 9 juta
Piutang dari BUD 9 juta
Uang Muka dari BUD 9 jutaKas di Bendahara Pengeluaran 9 juta
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Barang 9 juta
Uang muka ke SKPD 9 juta
Terhadap sisa UP akan disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah.
Contoh:
Sisa UP untuk contoh di atas adalah Rp1 juta. Jumlah tersebut disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2006.
Jurnal untuk setoran sisa UP adalah:

SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUang Muka dari BUD 1 juta Kas di Bendahara Pengeluaran 1 juta
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah 1 juta Uang Muka ke SKPD 1 juta
c. Penerimaan Kembali Belanja
Walaupun pembayaran belanja telah dilakukan secara hati-hati, namun kadang-kadang terjadi kesalahan/kelebihan sehingga ada koreksi atau penerimaan kembali belanja di kemudian hari. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan lain-lain PAD.
Contoh:
Pada bulan Juni 2006 diterima kembali belanja pegawai bulan Maret 2006 sejumlah Rp2 juta.
Jurnal untuk penerimaan kembali belanja tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPiutang dari BUD 2 juta Belanja Pegawai 2 juta(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah 2 juta Belanja Pegawai 2 juta(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)
Contoh:
Pada bulan Juni 2006 diterima pengembalian belanja perjalanan dinas sejumlah Rp5 juta dari seorang pegawai yang dibayarkan pada tahun 2005.

Jurnal untuk penerimaan kembali belanja tersebut adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD 5 juta Pendapatan lain-lain PAD 5 juta(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja perjalanan dinas tahun lalu)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah 5 juta Pendapatan Lain-lain PAD 5 juta(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja perjalanan dinas tahun lalu)
4. Akuntansi Surplus/Defisit
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Surplus/defisit diperoleh melalui jurnal penutup pendapatan dan belanja. Perhitungan Surplus/defisit dilakukan di tingkat pemerintah daerah (BUD) melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses penggabungan di BUD. Di SKPD tidak dilakukan penandingan antara pendapatan dan belanja sehingga tidak ada surplus/defisit.
Dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan penutupan akun secara berjenjang. Di SKPD, akun realisasi anggaran ditutup ke akun alokasi anggaran dalam DPA SKPD.
Contoh:
Estimasi pendapatan di DPA SKPD Rp10 juta dan realisasi pendapatan Rp9 juta. Allotment Belanja sebesar Rp20 juta dan realisasi belanja Rp18 juta.
Jurnal penutup di SKPD adalah:
STanggal Uraian Ref Debet KreditPendapatan 9 jutaUtang kepada BUD 1 juta Estimasi Pendapatan yang dialokasikan 10 juta
Allotment Belanja 20 juta Piutang dari BUD 2 juta Belanja ... 18 juta
Selanjutnya penutupan akun pendapatan dan belanja serta anggarannya di BUD dapat diilustrasikan berikut ini.
Contoh:

Estimasi Pendapatan Rp1.000 miliar dan realisasi Pendapatan Rp950 miliar. Sementara Apropriasi Belanja Rp1.250 miliar dan Realisasi Belanja Rp1.100 miliar.
Jurnal Penutup
(Rp miliar)
Tanggal Uraian Ref Debet KreditDes 31 Apropriasi Belanja 1.250
Alokasi Apropriasi Belanja 1.250
Des 31 Alokasi Estimasi Pendapatan 1.000 Estimasi Pendapatan 1.000
Des 31 Pendapatan 950Surplus/Defisit 150 Belanja 1.100
5. Akuntansi Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
a. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah.
Terhadap setiap penerimaan pembiayaan dibuat 2 (dua) jurnal. Pertama, untuk mengakui realisasi penerimaan anggaran, kedua, jurnal korolari untuk mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi transaksi tersebut.
Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf i, k, l, dan m UU 1/2004, bahwa Bendahara Umum Daerah berwenang untuk:
menempatkan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
Berdasarkan kewenangan tersebut, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Contoh:
Pada tahun 2006 diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp500 juta. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang, yang akan diangsur selama 5 tahun mulai tahun 2008.
Jurnal untuk penerimaan pinjaman tersebut adalah:
Tanggal Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah 500 juta Penerimaan Pinjaman 500 juta
Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jk panjang
500 juta
Utang kepada Pemerintah Pusat 500 juta
b. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Kas Daerah.
Contoh:
Dikeluarkan uang sejumlah Rp100 juta sebagai penyertaan modal pada PDAM.
Jurnal untuk pengeluaran penyertaan modal pada PDAM tersebut adalah:
Tanggal Uraian Ref Debet KreditPengeluaran Penyertaan Modal Pemda 100 juta Kas di Kas Daerah 100 juta(Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)
Penyertaan Modal Pemda 100 juta Diinvestasikan dalam Investasi Jk
Panjang100 juta
(Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)
c. Akuntansi Pembiayaan Neto
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
Contoh:
Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman sejumlah Rp200 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp250 juta.
Jurnal penutupnya adalah:
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit

Penerimaan Pinjaman 200 jutaPembiayaan Neto 50 juta Pengeluaran Penyertaan Modal 250 juta(Untuk menutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan)
6. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.
SILPA/SIKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan Pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran.
Contoh:Surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp100 juta sedangkan Pembiayaan Neto bersaldo debet Rp50 juta.
Jurnal penutupnya adalah:
Tanggal Uraian Ref Debet KreditSurplus/Defisit 100 juta Pembiayaan Neto 50 juta SILPA 50 juta(Untuk menutup Surplus/defisit dan Pembiayaan neto)
7. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang
Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang/aset harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai aset tersebut pada tanggal transaksi. Berhubung transaksi ini harus dicatat sebagai pendapatan dan belanja atau pembiayaan, maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai pendapatan, belanja, atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran. Berdasarkan dokumen pengesahan inilah dibuat jurnal untuk mencatat transaksi ini. Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas maka transaksi ini tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.
Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang dan barang rampasan.
Contoh:
Diterima hibah dari UNICEF sebuah mobil ambulance seharga Rp200 juta.
Jurnal penerimaan hibah berupa barang ini adalah:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD 200 juta
Pendapatan Hibah 200 juta

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin 200 jutaPiutang dari BUD 200 juta
Peralatan dan Mesin 200 jutaDiinvestasikan dalam Aset Tetap 200 juta
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Modal – Peralatan dan Mesin 200 juta
Pendapatan Hibah 200 juta
MODUL 4.
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.
A. PENGERTIAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN
1. Konsep Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah.
Terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu pengawasan,
pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun

aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar
eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah.
Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah)
untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat
dicapai.(Basuki, 2008 :230)
Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang
memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja
pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ditentukan sesuai peraturan
perundang-undang yang berlaku.(Mardiasmo, 2008 : 213)
Pada tataran teknis aplikatif juga berbeda, monitoring oleh DPRD dilakukan pada tahap awal.
Pengendalian dilakukan terutama pada tahap menengah (operasional), yaitu level pengendalian
manajemen (management control) dan pengendalian tugas (task control). Sedangkan pemeriksaan
dilakukan pada tahap akhir, obyek yang diperiksa adalah kinerja anggaran (anggaran policy), anggaran
kinerja dan laporan pertanggung jawaban yang terdiri atas nota perhitungan APBD, neraca, laporan
aliran kas dan laporan surplus ataupun defisit anggaran.
Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan
(diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar
supaya tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberi wewenang dan keleluasaan yang luas
tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat
Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai
kekuatan penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (social
control). Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang
memadai dan pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah (misalnya inspektorat).
2. Konsep Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.(Pasal 1 butir 5 PP No. 58 tahun 2005).
Pengertian keuangan daerah tersebut lebih luas dari pada pengertian keuangan daerah menurut PP No.
105 tahun 2000 yang hanya mempunyai arti pada lingkup APBD,sedangkan pengertian keuangan daerah
menurut PP No. 58 tahun 2005 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi:
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan
pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan / atau kepentingan umum.
Menurut Mamesah (1995) dalam bukunya Abdul Halim (2008) Keuangan Daerah dapat
diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai
oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan yaitu:
1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan
daerah, seperti pajak daerah retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain, dan
atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum (DAU)
dan dana alokasi khusus (DAK) sesuai peraturan yang telah ditetapkan, hak tersebut dapat
menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk
membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah,
infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi sedangkan kewajiban tersebut
dapat menurunkan kekayaan daerah.

Seperti halnya keuangan negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri
atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk
dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah,
sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah yang dikelola BUMD. Disamping itu pengurusan
akuntansi keuangan daerah juga dibagi dua yaitu pengurusan umum dan pengurusan khusus (berkaitan
dengan kewajiban perbendaharaan ), seperti halnya pada keuangan negara, pengurusan umum dibagi
menjadi dua yaitu otorisator dan ordonator.Menurut UU No.5 tahun 1974, wewenang otorisator,
ordonator dan bendaharawan dipegang oleh kepala daerah (gubernur, walikota dan bupati), akan tetapi
dalam pelaksanaannya wewenang tersebut dilimpahkan kepada sekwilda, kepala biro keuangan dan
kepala bagian perbendaharaan, serta Bank Pembangunan Daerah dan pegawai negeri sipil, sedangkan
keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah.
Definisi manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-
sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah
tersebut.Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah.
(Abdul Halim,2008: 27). Menurut Mamesah (1995), tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi dua
golongan yaitu tata usaha umum dan tatausaha keuangan. Tata usaha umum menyangkut kegiatanan
seperti surat menyurat, meng-agenda, meng-ekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau meng-
arsipkan dan kegiatan dokumentasi lainnya. Sedangkan tata usaha keuangan pada intinya adalah tata
buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan
berdasarkan prinsip, standardisasi dan prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual
di bidang keuangan.Tata usaha keuangan atau tata buku inilah yang sering disebut dengan akuntansi
keuangan daerah, meskipun tidak tepat benar karena tata buku hanya merupakan sebagian kecil dari
akuntansi.
Di era reformasi keuangan daerah, tata buku atau tata usaha keuangan daerah tidak lagi
memadai untuk dijadikan sebagai penghasil informasi yang dikehendaki oleh PP No.105 tahun 2000 dan
Kepmendagri No.29 tahun 2002 yang telah diperbarui dengan PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri
No.13 tahun 2006, yang didasari oleh UU No. 17 tahun 2003. Menurut peraturan perundang-undangan
terbaru yang dimaksud tersebut, tugas pengelola keuangan daerah adalah:
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
2. Menyusun rancangan dan perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pengertian tentang manajemen keuangan daerah tersebut diatas merupakan sebagian dari
beberapa pengertian manajemen keuangan daerah yang ada. Salah satu pengertian manajemen
keuangan daerah, selain pengertian diatas adalah definisi manajemen keuangan daerah sebagai usaha
yang dilakukan manajer, yakni pemerintah daerah, dalam membelanjakan dana yang dimiliki daerah
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebit serta dalam mendapatkan dana yang
dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut.
Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian manajemen keuangan pemerintah daerah
menurut Coe (1989) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi hal-hal seperti berikut:
1. Rencana hasil anggaran belanja dan biaya.
2. Laporan mengenai kuitansi dan pembayaran dari dana yang dianggarkan.
3. Pembelian barang dan pelayanan.
4. Penanaman modal.
5. Utang jangka pendek dan jangka panjang yang dibayar jatuh tempo sesuai perjanjian.
6. Pengawasan.
7. Kehilangan dan pertanggungjawaban yang benar tentang keuangan pada akhir tahun.
8. Pemeriksaan transaksi keuangan secara resmi
9. Laporan yang diterima sesuai dengan kondisinya.
Dalam kaitan ini, bidang akuntansi yang membantu pemerintah daerah dalam melakukan
usaha-usaha tersebut adalah akuntansi manajemen daerah, yaitu bidang akuntansi yang menghasilkan
informasi untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak internal entitas pemerintah daerah
(kabupaten, kota. atau propinsi).
3. Reposisi Lembaga Pemeriksa.

Otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam
melakukan pengelolaan keuangan daerah, salah satu hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan
terjadinya perpindahan penyelewengan dan KKN dari pemerintah pusat menuju ke daerah.
Kasus di negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi di
daerah, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi
pengawasan oleh DPRD.
Harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit
pemerintahan di Indonesia antara lain adalah:
1. Kelemahan yang bersifat inherent.
2. Kelemahan yang lebih bersifat stuktural.(Mardiasmo, 2008:216)
Kelemahan pertama yang bersifat inherent adalah tidak tersedianya indikator kinerja
(performance indicaror) yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, hal
demikian umum dialami organisasi sektor publik karena out put yang dihasilkan oeh organisasi publik
adalah berupa pelayanan publik yang tidak mudah diukur.
Pengauditan terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah dilaksenakan apabila telah
ditetapkam kriteria kinerja yang harus dicapai pemerintah daerah. Selain itu tidak adanya kriteria kinerja
yang jelas dan memadai, permasalahan lainnyaadalah belum adanya Standar Akuntansi Keuangan
Pemerintah yang baku. Pada dasarnya pengauditan terhadap pemerintah daerah adalah
membandingkan hasil yang dicapai (output result) dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah daerah akan menghadapi masalah dalam melakukan pengukuran kinerja apabila
DPRD tidak menetapakan kriteria kinerja yang memadai, hal tersebut tidak hanya menyebabkan
kesulitan bagi eksekutif daerah, akan tetapi juga kesulitan bagi auditor yang telah ditunjuk oleh DPRD
untuk menetapkan performance indicator yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi eksekutif daerah
dalam menjalankan tugas.
Kelemahan kedua yang bersifat struktural yaitu terkait dengan masalah struktur lembaga audit
terhadap pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, permasalahan yang ada adalah banyaknya lembaga

pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya dan menyebabkan pelaksanaan
pengauditan tidak efisien serta tidak efektif.
Saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional terhadap pembiayaan
desentralisasi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspektur Jendral Pembangunan (Irjenbang), Inspektorat Jendral Dalam Negeri,
Inspektorat Wilayah Propinsi dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Lembaga pemeriksa fungsional
tersebut terkadang overlapping dan kurang terkoordinasi dengan baik.
Untuk menciptakan lembaga audit yang efisien dan efektif, maka diperlukan reposisi terhadap
lembaga audit yang ada, sedangkan reposisi yang dimaksud berupa pemisahan tugas dan fungsi yang
jelas dari lembaga-lembaga pemeriksa pemerintah tersebutt, apakah sebagai auditor internal atau
auditor eksternal.
Auditor internal adalah auditor yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian
dari organisasi yang diawasi. Sedangkan yang termasuk audit internal adalah audit yang dilakukan oleh
Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan
BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi(Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota
(Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang berada di luar
organisasi yang diperiksa. Lembaga pemeriksa eksternal tersebut merupakan lembaga pemeriksa yang
independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor eksternal pemerintah adalah BPK, karena BPK
merupakan lembaga yang independen dan merupakan supreme auditor.
Reposisi lembaga pemeriksa tersebut akan efektif apabila semua lembaga pemeriksa yang ada
melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara baik. Reposisi lembaga pemeriksa merupakan salah
satu cara untuk memberdayakan lembaga pemeriksa negara yang beberapa waktu yang lalu mengalami
distorsi, apabila lembaga pemeriksa telah ditata ulang, maka diharapkan dapat diikuti dengan dihasilkan
standar akuntansi keuangan sektor publik dan standar auditing pemerintah secara lebih baik.
4. Memperkuat Value For Money Audit.

Good governance akan dapat tercapai apabila lembaga pengawas dan pemeriksa berfungsi
secara baik. Jika lembaga pengawas dan pemeriksa telah tertata dengan baik maka yang perlu dilakukan
adalah dengan memperbaiki teknik pengawasan dan pemeriksaan.
Salah satunya adalah dengan memperkuat pelaksanaan audit kinerja (value for money audit
atau performance audit), sebagaimana diatur dalam Standar Audit Pemerintah (SAP) tahun 1995, value
for money audit atau audit kinerja adalah pengauditan yang dilakukan untuk memeriksa tingkat
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program atau kegiatan dan unit kerja tertentu.
Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit bertujuan untuk menentukan apakah:
a. Suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya seperti
karyawan/pegawai, gedung, ruang dan peralatan kantor secara hemat dan efisien.
b. Penyebab ketidak hematan dan ketidak efisienan.
c. Entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kehematan dan efisiensi. (Mardiasmo, 2008:218)
Audit efektivitas disebut juga program audit bertujuan untuk menentukan:
a. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh
undang-undang atau badan lain yang berwenang.
b. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang
bersangkutan.
c. Apakah entitas yang diaudit telah mentaati peraturan perundang-undangan yang ada dan
berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan.(Mardiasmo,2008:220)
Tujuan untuk memerkuat pelaksanaan value for money (VFM) audit tersebut adalah dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Hal tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan
otonomi derah dan desentralisasi karena nantinya DPR/DPRD, menteri-menteri dan lembaga-lembaga
pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah harus memberikan pertanggung jawaban publik kepada
masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas publik juga merupakan bagian penting dari sistem politik
dan demokrasi.
5. Penentuan Indikator Kinerja Sebagai Dasar Penilaian Kinerja.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau
Program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan
sebagai indikator kinerja yaitu kinerja anggaran atau kebijakan anggaran (policy budget) dan anggaran
kinerja (performance budget).
Kinerja anggaran adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi
kinerja kepala daerah. Alat tersebut berupa strategi makro dan kebijakan yang tertuang dalam Propeda
dan Renstrada, Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta Strategi dan Prioritas APBD.
Anggaran kinerja adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk
mengevaluasi unit-unit kerja yang ada dibawah kendali kepala daerah selaku manajer
eksekutif.Anggaran kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya
pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Untuk
mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dikembangkan Standar Analisa Belanja (SAB),
tolok ukur kinerja dan standar biaya. Standar Analisa Belanja (SAB) terdiri dari dua jenis yaitu SAB Makro
dan SAB Mikro.
SAB Mikro merupakan perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap kegiatan atau proyek dalam
unit kerja pemerintah daerah. Latar belakang diperlukannya Standar Analisa Belanja adalah untuk
menghasilkan alikasi dana yang akurat, adil dan mampu memberi insentif bagi setiap unit kerja untuk
melaksanakan prinsip 3 E yaitu Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas secara berkesinambungan. Dalam SAB
Mikro ditentukan standar plafon atau batas atas belanja masing-masing kategori pengeluaran baik rutin
maupun modal sehingga tercapai nilai yang wajar.
Dalam suatu siklus atau proses anggaran SAB berada dalam tahap perencanaan dan persiapan
anggaran. Perencanaan anggaran merupakan arahan kebijaksanaan di bidang anggaran yang
diterjemahkan melalui serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada suatu periode tertentu
dengan menggunakan sejumlah tertentu sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang.
Perencanaan anggaran juga harus mampu melakukan penilaian kebutuhan, menentukan skala
prioritas, memperkirakan penerimaan dan pengeluaran, serta indikator kinerja yang akan dicapai.
Dengan demikian SAB Mikro merupakan pendukung bagi pelaksanaan anggaran daerah yang disusun

berdasarkan pendekatan kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah, maka perlu
diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.
Mekanisme untuk menentukan indikator-indikator tersebut kinerja tersebut memerlukan hal-
hal sebagai berikut:
1. Sistem perencanaan dan pemgendalian.
Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi
jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi
dengan menggunakan rantai komando yang jelas berdasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan
fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi.
Kinerja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara
detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dapat dijadikan sebagai standar
penilaian.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme.
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standadisasi yang telah maka
diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja (profesioalisme
kerja).
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar.
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward & punishment)
yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan fungsi serta penggunaan sumber
daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk
memberikan penghargaan dan hukuman.
5. Mekanisme Sumber Daya Manusia.
Pemerintah daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk
memperbaiki kinerja personel dan organisasi.
Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak
internal dalam hal ini adalah pemerintah daerah harus dapat menggunakannya dalam rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya atau dengan kata lain indikator
kinerja berperan untuk menunjukkan memberikan indikasi atau menitik beratkan/memfokuskan
perhatian pada bidang yang relevan untuk dilakukan perbaikan.
Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol sekaligus sebagai
informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator
kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pembelanjaan publik. Indikator kinerja
akan dapat membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi
masalah yang penting.
Disamping itu indikator kinerja juga akan membantu pemerintah daerah dalam proses
pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Indikator kinerja
memudahkan bagi DPR/DPRD dalam mengkaji dan mengawasi alokasi dan penggunaan dana anggaran,
khususnya melalui proses pembahasan pada sidang dewan.