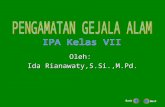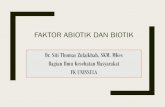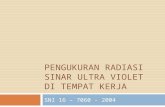MODUL 1 Pengukuran Faktor Abiotik Lingkungan
-
Upload
ilham-saiful-rizal -
Category
Documents
-
view
122 -
download
29
description
Transcript of MODUL 1 Pengukuran Faktor Abiotik Lingkungan
-
MODUL 1
Pengukuran Faktor Abiotik Lingkungan
1.1 Tujuan
1. Mengetaui komponen abiotik lingkungan
2. Mengetaui prinsip, cara kerja, dan cara menggunakan alat-alat pengukur faktor abiotik
lingkungan
3. Menjelaskan pengaruh komponen abiotik teradap lingkungan
1.2 Faktor Abiotik Lingkungan
Kata abiotik secara harfiah berarti tidak hidup. Faktor abiotik adalah setiap
parameter tidak hidup, komponen, aspek atau faktor yang mengontrol distribusi
(persebaran geografis) dan kelimpaan (jumlah individu) dari organisme biologi di bumi
(Magguran, 1988). Faktor abiotik terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya fisik
(physical resources) dan faktor fisik (physical factors) (Magurran, 1988).
1. Sumber Daya Fisik (Physical Resources)
Sumber daya fisik adalah faktor abiotik yang dibutuhkan oleh organisme
untuk bertahan hidup. Sumber daya fisik untuk tumbuhan adalah cahaya, air, karbon
dioksida, dan nutrisi. Sumber daya fisik untuk hewan adalah oksigen, air, dan nutrisi.
Bila salah satu sumber daya fisik tidak terpenuhi maka organisme tersebut tidak
mampu bertahan hidup (akan mati), karena sumber daya fisik tersebut merupakan
faktor utama (absolute factors) (Magurran, 1988).
2. Faktor Fisik (Physical Factors)
Faktor fisik adalah faktor abiotik yang membatasi derajat (kualitas hidup)
organisme untuk bertahan hidup. Tidak ada perbedaan faktor fisik yang dibutuhkan
oleh hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup seperti pH, salinitas, dan suhu tanah.
Ketika faktor-faktor tersebut menentukan ada atau tidaknya organisme di suatu
lingkungan, makan faktor-faktor tersebut disebut faktor pembatas (Magurran, 1988).
1.2.1 Cahaya
Cahaya matahari merupakan sumber energi utama suatu ekosistem. Seluruh
rantai makanan diawali dengan organisme fotosintetik (produsen primer), tanpa caaya
matahari maka semua kehidupan akan mati. Cahaya merupakan bentuk energi yang
memiliki spektrum yang luas yang disebut Spektrum elektro magnetik (EMS). Cahaya
berasal dari matahari yang menghasilkan spektrum cahaya terutama dalam bentuk
-
yang terlihat cahaya dan panas (infra merah), ultraviolet, dan energi radiasi yang lebih
rendah (gelombang mikro, gelombang radio) (Krohne, 2001).
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa cahaya matahari yang turun ke
bumi digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan proses tersebut
merupakan hal terpenting dari semua faktor abiotik karena tanpa fotosintesis tidak ada
oksigen yang dihasilkan dan semua organisme yang bernapas tidak bisa hidup
(meskipun banyak mikro-organisme bisa hidup tanpa oksigen). Energi cahaya juga
mempengaruhi faktor-faktor lain seperti suhu melalui interaksi dengan air, tanah dan
udara. Faktor-faktor seperti kualitas cahaya, intensitas cahaya, dan periode cahaya
memainkan peranan penting dalam ekosistem. Alat yang digunakan untuk mengukur
intensitas cahaya adalah lux meter.
a. Lux meter
Lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas
cahaya di suatu tempat. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini maka
diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya. Sehingga
cahaya yang diterima oleh sensor dapat diukur dan ditanpilkan pada sebuah tampilan
digital ataupun non digital. Pengkalibrasian alat ukur ini dilakukan dengan jarak
antara sumber cahaya ke sensor sebesar 100 cm atau 1meter dan dalam posisi tegak
lurus. Untuk mendapatkan sumber cahaya digunakan sebuah lampu dan
pengkalibrasian ini dilakukan dalam sebuah ruangan dengan kondisi ruangan gelap
(Magurran, 1988).
Cara penggunaan lux meter
1. Tekan tombol on
2. Lakukan kalibrasi
3. Arahkan sensor ke sumber cahaya
4. Catat hasil pengukuran intensitas cahaya
5. Lakukan pengukuran sebanyak tiga kali
Gambar 1. Lux meter
1.2.2 Temperatur
Distribusi hewan dan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh suhu. Misalnya,
perbedaan musim di suatu wilayah menyebabkan perbedaan jenis satwa atau
tumbuhan di antara wilayah tersebut. Beberapa contoh pengaruh suhu terhadap
ekosistem adalah waktu mekarnya bunga, waktu perkecambahan biji, hewan berdarah
panas dan dingin (homoioterm dan polikioterm), waktu hibernasi reptil dan mamalia,
-
migrasi beberapa hewan, dll. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara adalah
termometer udara (termometer air raksa) (Magurran, 1988).
a. Termometer raksa
Termometer yang di dalamnya terdapat air raksa yang bisa memuai dan menyusut.
Termometer ini bisa digunakan untuk mengukur suhu udara maupun tanah.
Cara menggunakan termometer
1. Letakan termometer pada objek yang akan diukur suhunya
2. Tunggu selama 15 menit (hingga suhu stabil)
3. Catat hasil pengukuran
Temperatur erat hubungannya dengan kelembaban dan kecepatan angin.
Kelembaban udara merupakan perbandingan jumlah uap air di udara. Alat yang
digunakan untuk mengukur kelembaban udara relatif adalah sling psychrometer.
Kecepatan angin adalah kecepatan udara yang bergerak secara horizontal pada
ketinggian dua meter diatas tanah. Perbedaan tekanan udara antara asal dan tujuan
angin merupakan faktor yang menentukan kecepatan angin. Kecepatan angin akan
berbeda pada permukaan yang tertutup oleh vegetasi dengan ketinggian tertentu,
misalnya tanaman padi, jagung, dan kedelai. Oleh karena itu, kecepatan angin
dipengaruhi oleh karakteristik permukaan yang dilaluinya. Kecepatan angin dapat
diukur dengan menggunakan alat yang disebut anemometer. Jenis anemometer yang
paling banyak digunakan adalah anemometer manual.
b. Sling psychrometer
Sling psychrometer terdiri atas dua termometer yaitu termometer kering dan
basah. Kelembaban udara relatif diketahui dengan melihat suhu kering dan selisih
antara suhu kering dan suhu basah (yang tertera di termometer) pada tabel
kelembaban udara relatif.
Cara menggunakan sling psychrometer
1. Basahi kasa pada termometer basah dengan aquadest
2. Sling diputar satu arah (menjauhi badan) selama tiga menit
3. Baca suhu yang tertera di masing-masing termometer
4. Lihat kelembaban udara relatif pada tabel
c. Anemometer
Sensornya terdiri dari tiga sampai empat buah baling-baling yang dipasang
pada jari-jari yang berpusat pada suatu sumbu vertikal. Seluruh baling-baling
menghadap ke satu arah melingkar sehingga bila angin bertiup maka rotor akan
berputar pada arah tetap. Kecepatan putar rotor tergantung pada kecepatan tiupan
angin. Perputaran rotor mengatur sistem akumulasi angka penunjuk jarak tiupan
angin. Dengan alat ini penambahan nilai yang dapat dibaca dari satu pengamatan
ke pengamatan berikutnya, menyatakan akumulasi jarak tempuh angin selama
-
waktu pengamatan sehingga, kecepatan angin adalah akumulasi jarak tempuh
dibagi dengan waktu pengamatan.
Cara menggunakan anemometer
1. Kalibrasi anemometer
2. Arahkan anemometer ke sumber angin
3. Lakukan selama tiga menit
4. Kunci termometer
5. Catat hasil pengukuran kecepatan angin
Gambar 3. Termometer, anemometer, sling psychrometer
1.2.3 Faktor abiotik geografi dan geologi
Ada beberapa faktor yang termasuk dalam faktor abiotik geografi dan geologi di
antaranya adalah ketinggian, garis lintang, bujur, kapasitas resapan air, dan kondisi
tanah. Dari beberapa faktor tersebut kita hanya akan membahas kondisi tanah.
1.2.3.1 Tanah
Faktor abiotik tanah terdiri dari tekstur, suhu, pH, kadar air, bobot isi (bulk density)
dan kandungan organik serta anorganik tanah. Berikut penjelasan masing-masing
parameter.
a. Tekstur tanah
Ukuran partikel tanah bervariasi dari partikel mikroskopis (tanah liat) hingga
partikel terbesar (pasir). Tanah lempung adalah campuran pasir dan partikel tanah
liat pasir tanah cocok untuk tanaman yang tumbuh karena aerasi yang baik
kelebihan air mengalir dengan cepat, hangat dengan cepat pada siang hari dan
mudah untuk dibudidayakan. Tanah liat cocok untuk pertumbuhan tanaman
karena mengandung sejumlah besar air dan kaya nutrisi mineral (Undang, dkk.,
2006).
b. Suhu tanah
Suhu tanah merupakan faktor ekologi yang penting. Diketahui bahwa suhu tanah
di bawah kedalaman sekitar 30cm hampir konstan sepanjang hari namun suhu
musiman berbeda. Suhu yang rendah menyebabkan pembusukan yang dilakukan
-
oleh dekomposer. Alat yang digunakan untung mengukur suhu tanah adalah
termometer tanah.
Cara menggunakan termometer tanah
1. Buat lubang pada tanah untuk menancapkan termometer
2. Tancapkan termometer pada lubang tersebut selama tiga menit
3. Cabut termometer dari lubang, catat suhu yang tertera
4. Bersihkan termometer dengan aquadest
c. pH, kadar air, kadar organik dan anorganik tanah
pH tanah berpengaruh terhadap aktivitas biologi tanah dan tersedianya
mineralt tanah. Oleh karena itu, pH tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan. Kelembaban tanah adalah jumlah air yang ditahan di
dalam tanah setelah kelebihan air dialirkan, apabila tanah memiliki kadar air yang
tinggi maka kelebihan air tanah dikurangi melalui evaporasi, transpirasi, dan
transport air bawah tanah. Alat yang digunakan untuk mengukur pH dan
kelembaban tanah adalah soil moisture tester.
Cara menggunakan soil moisture tester
1. Buat lubang pada tanah sedalam 10 cm
2. Tancapkan sensor soil moisture tester pada lubang tersebut selama 3 menit
3. Tekan tombol pada soil moisture tester
4. Catat hasil pengukuran pH dan kelembaban tanah
5. Bersihkan sensor dengan aquadest
Pengukuran kelembaban tanah (kadar air tanah) juga bisa dengan
menggunakan metode gravimetri. Metode gravimetri adalah teknik pemisahan air
dari matriks tanah melalui pemanasan, metode ini merupakan pengukuran secara
langsung. Umumnya dalam skala lab digunakan oven untuk mengeringkan tanah.
Pengukuran kadar air di laboratorium dengan menggunakan oven (Undang, dkk.,
2006).
Alat dan bahan
1. Cawan porselen
2. Neraca analitik
3. Oven
4. Desikator
Cara kerja
1. Timbang tanah pada cawan sebanyak 10 g sebagai berat basah tanah
-
2. Masukan cawan berisi 10 g tanah ke dalam oven pada suhu 105 - 110 C
selama 24 jam.
3. Setelah 24 jam, biarkan/dinginkan tanah di dalam desikator selama 1 jam
4. Timbang cawan berisi tanah, sebagai berat kering tanah.
Kandungan Organik Tanah
Cara kerja:
1. Cawan yang akan digunakan dioven 30 menit pada suhu 100 - 105C
2. Dinginkan cawan di dalam desikator, timbang cawan (A)
3. Sampel ditimbang sebanyak 2 g ke dalam cawan yang sudah dikeringkan (B)
4. Sampel dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 550 - 600C sampai
pengabuan sempurna
5. Setelah pengabuan selesai, sampel dimasukkan ke dalam desikator, ditimbang
(C)
6. Kadar abu dihitung dengan rumus:
Dari hasil perhitungan kadar abu, maka bisa dihitung kandungan organik tanah
dan kandungan mineral tanah dengan rumus sebagai berikut:
d. Bobot isi (Bulk density)
Bobot isi tanah (Bulk density) adalah perbandingan antara massa tanah dengan
volume partikel ditambah dengan ruang pori diantaranya. Massa tanah ditentukan
setelah kering oven 105 C dan volumenya merupakan volume dari contoh tanah
yang di ambil di lapangan, sehingga dinyatakan dalam g.cm-3. Bobot isi dapat
diukur dengan metode : (1) silinder, (2) clod, (3) boring, (4) radioaktif (sinar
Kadar air tanah (%) = Berat Basah Berat Kering
Berat Kering
X 100%
Kadar Abu = C A
B - A
X 100 %
Kandungan organik = Berat kering Berat abu
Berat abu X 100 %
Kandungan Mineral = Berat abu
Berat kering
X 100 %
-
gama) dan ring blok. Praktikum kali ini, kita menggunakan metode silinder,
karena mudah diaplikasikan dalam skala lab dengan alat yang sederhana (Undang,
dkk., 2006).
Pengukuran bobot isi tanah dengan metode silinder
Alat dan Bahan
1. Pipa silinder
2. Neraca
3. Mistar/jangka sorong
Cara kerja
1. Ukur tinggi tabung dan jari-jari tabung silinder
2. Timbang pipa silinder kosong sebagai Y gram
3. Tancapkan pipa silinder pada tanah (sampai terambil tanah yang padat di pipa)
4. Timbang pipa silinder dan tanah tersebut sebagai X gram
5. Hitung kadar air tanah sebagai Z gram
6. Hitung volume tanah pada silinder
7. Hitung bobot isi (bulk density) dengan rumus:
e. Porositas Tanah
Porositas atau ruang pori tanah adalah volume seluruh pori-pori dalam suatu
volume tanah utuh, yang dinyatakan dalam persen. Porositas terdiri dari ruang
diantara partikel pasir, debu dan liat serta ruang diantara agregat-agregat tanah.
Menurut ukuranya porositas tanah dikelompokkan ke dalam : ruang pori kapiler yang
dapat menghambat pergerakan air menjadi pergerakan kapiler, dan ruang pori
nonkapiler yang dapat memberi kesempatan pergerakan udara dan perkolasi secara
cepat sehingga sering disebut pori drainase. Berat jenis partikel tanah 1,3 -1,5 g/cm
(Undang, dkk., 2006).
Bulk density = 100 (X Y ) / (100 + Z) g
Volume tanah cm
Porositas tanah = (1- Voume tanah )
Berat jenis partikel
X 100%
-
DAFTAR PUSTAKA
Krohne.D.T. 2001. General Ecology 2nd Ed. Brooks Cole Publishing. Pacific Grove CA
USA.
Magurran, A.E. 1988. Ecological Diversity and Its Measurments. Princeton University Press.
New Jersey
Undang, K., F. Agus., A. Dariah & A. Adimihardja. 2006. Sifat Fisik Tanah Dan Metode
Analisisnya. Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian Departemen
Pertanian. Jakarta