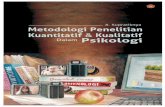Metodologi Penelitian
-
Upload
campur-aduk -
Category
Documents
-
view
262 -
download
4
Transcript of Metodologi Penelitian

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, maka tuntutan akan
kesejahteraan manusia dari waktu ke waktu juga berubah menjadi semakin
meningkat. Tuntutan tersebut menimbulkan konsekuensi peningkatan ketersediaan
untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan yang menjadi semakin beragam dan
kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mengembangkan
teknologi dan upaya-upaya yang antara lain berupa penggalian sumber daya alam
dan industrialisasi.
Industri merupakan suatu rangkaian usaha mengolah dan memanfaatkan
sumber daya alam secara masal sehingga menghasilkan suatu produk dengan efektif
dan efisien terbukti telah mampu memenuhi kebutuhan dan meringankan kehidupan
bagi sebagian penduduk bumi ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan
industri juga menghasilkan implikasi negatif antara lain berupa terjadinya perubahan
kualitas lingkungan akibat pencemaran baik pencemaran udara, air, tanah, maupun
air tanah dan merosotnya cadangan sumber daya alam baik yang terbaharukan,
maupun tidak terbaharukan. Walau juga tidak dapat di-generalisasi bahwa setiap
kegiatan industri atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam pasti akan
mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Ada sebagian kegiatan
pemanfaatan sumber daya alam dan industri yang sejak awal dijalankan dengan
bijaksana dan komitmen yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan ternyata dapat
beraktifitas dengan lingkungan.
Limbah industri dapat berupa gas seperti CO2, SO2, dan NO, maupun
limbah cair seperti logam-logam berat kadmium, kromium, besi, mangan, timbal dan
senyawa organic, dan padatan. Timbulnya pencemaran oleh limbah iindustri
biasanya disebabkan karena adanya daya dukung badan penerima terlampaui.
Industri pengolahan pada umumnya memerlukan bahan baku yang dikonversikan
melalui langkah-langkah proses menjadi produk yang dikehendaki. Seringkali
diperlukan pula penambahan bahan penolong yang macam dan jumlahnya
tergantung pada jenis industri yang bersangkutan.
Pabrik kertas banyak menghasilkan limbah dari hasil samping proses
produksi berupa zat warna, bahan organik dan logam berat seperti raksa (Hg), khrom
(Cr), kadmium (Cd), seng (Zn), yang dapat meracuni makhluk hidup di perairan,
sehingga kandungan ion-ion ini dibatasi kehadirannya. Dari hasil pemeriksaan
laboratorium, kadar khrom dan zeng pada limbah cair industri kertas Blabak masing-
masing sebesar 0,1 mg/l dan 0,1 mg/l. Limbah cair ini sudah diatas ambang batas
(NAB) baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,
bahwa untuk parameter khrom dan zeng maksimal diperbolehkan adalah 0,05 mg/l
1

dan 0,05 mg/l. Agar pencemaran terhadap lingkungan tidak terjadi, maka diperlukan
pengelolaan dampak terhadap lingkungan (positif maupun negatif). Pendekatan
pengelolaan dampak negatif terhadap lingkungan dilakukan dengan metode yang
berdasarkan pada cara end of pipe. Dimana metode ini membiarkan limbah tetap
terbentuk, kemudian dilakukan penanganan pada akhir dari suatu proses. Alternatif
pengolahan limbah cair yang mengandung logam berat terutama logam khrom dan
seng sehingga tidak merusak ekosistem sekitar adalah dengan proses kimia
menggunakan natrium bisulsit sebagai presipitan. Prinsip kerja proses ini adalah
terjadinya pencampuran antara lain limbah dan presipitan, dimana air limbah dari
pabrik kertas dicampur dengan bahan presipitan, kemudian diaduk hingga homogen
yang dilanjutkan dengan pengendapan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Apakah proses presipitasi kimia dengan menggunakan natrium bisulfit dapat
menurunkan kadar khrom dan seng pada limbah cair industri kertas ?
2. Berapa dosis natrium bisulfit yang paling tepat untuk penurunan kadar khrom
dan seng pada limbah cair industri kertas ?
3. Berapakah efisiensi penurunan kadar khrom dan seng dengan menggunakan
natrium bisulfit pada limbah cair industri kertas ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui apakah proses presipitasi kimia dengan menggunakan natrium bisulfit
dapat menurunkan kadar khrom dan seng ?
2. Mengetahui dosis natrium bisulfit yang paling tepat terhadap penurunan kadar
khrom dan seng pada limbah cair industri kertas.
3. Mengetahui efisiensi penurunan kadar khrom dan seng dengan menggunakan
natrium bisulfit pada limbah cair industri kertas.
1.4 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Pengolahan menggunakan natrium bisulfit dalam skala laboratorium.
2. Parameter yang diteliti adalah seng (Zn) dan khrom (Cr).
2

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Masukan bagi industri kertas yang mengolah dengan menggunakan logam berat
khususnya parameter pencemar seng dan khrom pada limbah cairnya untuk
dipakai sebagai bahan pertimbangan di dalam pengolahan limbah cair.
2. Bagi peneliti lain, sebagai acuan atau masukan dalam menindaklanjuti pengolahan
limbah cair yang mengandung pencemar seng dan khrom.
3

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Air Buangan
Menurut Tjokrokusumo (1995), air buangan diartikan sebagai kejadian
masuknya atau dimasukkannya benda padat, cair, dan gas ke dalam air dengannya
berupa endapan atau padat, padat tersuspensi, terlarut, sebagai koloid, emulsi yang
menyebabkan air dimaksud harus dipisahkan atau dibuang dengan sebutan air
buangan. Air buangan kemudian disebut sebagai air buangan tercemar secara fisik,
kimia, biologi bahkan mungkin radioaktif.
Menurut jenisnya air buangan terbagi atas, (1) jenis buangan domestik
dan (2) buangan industri, sedangkan menurut macam buangannya adalah bersifat
fisis, kimia, biologi, radoaktif (Tjokrokusumo, 1995). Limbah adalah buangan yang
kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tdak dikehendaki lingkungannya
karena tidak mempunyai nilai ekonomis serta mengandung bahan pencemar yang
bersifat racun dan berbahaya (Perdana Ginting,1995). Limbah ini dikenal dengan
limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya), yang dirumuskan sebagai bahan dalam
jumlah relatif sedikit tetapi mempunyai potensi untuk merusak lingkungan hidup
dan sumber daya. Bahan beracun dan berbahaya banyak dijumpai sehari-harinya,
baik yang tersimpan, diproses, diperdagangkan, diangkut dan lain-lain.
Beberapa kriteria bahan berbahaya dan beracun telah ditetapkan antara
lain : mudah terbakar, mudah meledak, korosif, oksidator reduktor, iritasi,
mutagenik, patogenik, toksik, mudah membusuk dan lain-lain dalam jumlah tertentu
dengan kadar tertentu pula kehadirannya dapat mengganggu kesehatan bahkan
mematikan manusia atau kehidupan lainnya sehingga perlu ditetapkan batas-batas
yang diperkenankan dalam lingkungan (Perdana Ginting, 1995).
2.2 Karakteristik Air Buangan
Pengertian mengenai air limbah perlu dipahami untuk menentukan jenis
bahan peralatan, teknologi pengolahan dan satuan unit pengolahan air limbah.
Menurut (Tjokrokusumo, 1995) karakteristik air limbah dibedakan menjadi 3
golongan yaitu :
1. Karakteristik Fisik
Karakteristik fisik air limbah ditentukan dari parameter-parameter
a. Padatan tersuspensi
b. Suhu
c. Warna
d. Bau
4

2. Karakteristik Kimia
Karakteristik kimia air limbah dapat ditentukan dari parameter-parameter
a. Zat organic
b. Zat anorganik
c. Gas-gas
3. Karakteristik Biologi
Karakteristik biologi pada umumnya ditentukan dari parameter-parameter :
a. Kelompok mikroorganisme yang terdapat dalam air limbah
b. Organisme patogen yang ada
Karakteristik biologi pada umumnya ditentukan oleh banyaknya mikrorganisme
per milliliter dalam air limbah yang belum diolah dan banyaknya organisme
patogen. Organisme patogen ini dapat menimbulkan penyakit seperti thypus,
disentri, kolera. Kebanyakan mikroorganisme yang terdapat dalam air limbah
merupakan bantuan yang penting bagi proses pembusukan (Linsley dan
Franzins, 1991).
2.3 Logam Berat
Logam berat merupakan unsur-unsur logam seperti besi, nikel, seng, kobalt,
merkuri, kadmium, arsen, khrom, dan timbal yang memiliki berat atom yang besar.
Logam berat termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan
logam-logam lainnya. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila
logam berat ini berikatan dan atau masuk ke dalam tubuh suatu organisme, dan tetap
tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi.
Adapun karakteristik logam berat, meliputi (Fuji M, 1973) :
a. Memiliki spesifikasi grafit yang sangat besar (lebih dari 4)
b. Memiliki nomor atom 22-24 dan 40-50 serta unsur lantanida dan aktanida
c. Memiliki respon biokimia spesifik (khas) pada organisme hidup.
Pencemaran yang ditimbulkan oleh logam berat pada tingkat tertentu dapat
mengganggu kesehatan manusia, karena masalah yang ditimbulkan oleh logam berat
yang mempunyai sifat-sifat berikut :
a. Beracun.
b. Tidak dapat dihancurkan atau dirombak oleh mikroorganisme.
c. Langsung atau tidak dapat diakumulasi oleh mikroorganisme atau manusia (Fuji
M, 1973).
Berdasarkan sifat racun pada logam berat dikelompokkan menjadi :
a. Tidak beracun, yaitu tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan, contohnya :
aluminium (Al), natrium (Na), kalsium (ca).
b. Kurang beracun, yaitu dalam jumlah konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan, contohnya : magnesium (Mg), seng (Zn), kobalt (Co).
5

c. Moderat, yatu dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang dapat pulih
maupun tidak dapat pulih dalam waktu yang lama, contoh : barium (Ba), mangan
(Mn).
d. Sangat beracun, yaitu dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang tidak pulih
pada waktu yang singkat bahkan dapat menyebabkan kematian, contoh : merkuri
(Hg), plumbun (Pb), khrom (Cr). (Fujii M, 1973).
2.4 Khromium (Cr)
Khromium banyak digunakan dengan besi membentuk baja yang tak
berkarat dan berkekuatan tinggi. Logam Cr dengan Ni membentuk lapisan khrom
nikel untuk pelapis senjata dan kawat-kawat tahanan pada alat-alat listrik dan lain-
lainnya. Senyawa khrom banyak dipakai dalam penyamakan kulit, pembuatan zat
warna, industri kimia, pelapisan logam dan lainnya. Logam khrom tidak
menimbulkan resiko medis, tetapi senyawa Cr dapat menimbulkan pengisapan kabut
asam dan kontak langsung dengan kulit serta mata yang menyebabkan iritasi bisul
bernanah pada hidung dan tenggorokan yang kemudian terjadinya kanker paru-paru
(Tyoso, 1995).
2.5 Pencemaran Air
Pencemaran air adalah suatu peristiwa masuknya zat-zat ke dalam air
yang mengakibatkan kualitas air tersebut menurun, sehingga dapat mengganggu dan
membahayakan kesehatan masyarakat. Badan air dikatakan tercemar apabila
ditandai adanya perubahan fisik atau tanda yang dapat diamati melalui (Whardana,
1996 :
a) Adanya perubahan suhu air
Oksigen yang terlarut dalam air akan turun bersamaan dengan kenaikan suhu.
Makin tinggi kenaikan suhu air makin sedikit oksigen yang terlarut di dalamnya.
b) Adanya perubahan pH (konsentrasi ion hydrogen)
Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke sungai
akan mengubah pH air yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan
organisme di dalam air.
c) Adanya perubahan warna, bau dan rasa air
Bahan buangan dan air limbah dari kegiatan industri yang berupa bahan organik
dan anorganik seringkali larut dalam air. Degradasi bahan buangan industri
dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan warna air. Bau yang keluar dapat
langsung dari bahan buangan atau air limbah kegiatan industri, dapat pula
berasal dari hasil degradasi bahan buangan oleh mikroba yang hidup di dalam
air, sedangkan rasa berasal dari pelarut sejenis garam-garaman.
6

d) Timbulnya endapan, koloidal dan bahan terlarut
Endapan dan koloidal serta bahan terlarut berasal dari adanya bahan buangan
industri yang berbentuk padat. Endapan dan koloidal yang melayang di dalam air
akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam lapisan air sehingga proses
fotosintesis tidak dapat berlangsung, akibatnya kehidupan air dapat terganggu.
e) Adanya mikroorganisme
Bahan buangan degradasi cukup banyak maka berarti mikroorganisme akan ikut
berkembang biak, tidak tertutup kemungkinan mikroba patogen ikut berkembang
pula, terutama buangan dari industri pengolahan bahan makanan.
f) Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan
Zat radioaktif dapat menyebabkan bermacam-macam kerusakan biologis melalui
efek langsung atau tertunda. Komponen pencemar air ternyata ikut menentukan
bagaimana indikator tersebut terjadi. Komponen air tersebut dikelompokkan
sebagai berikut :
a. Bahan buangan padat
Adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar maupun
yang halus, sehingga kemungkinan yang dapat terjadi adalah pelarutan
bahan buangan padat oleh air dan juga pengendapan bahan buangan padat
di dasar air.
b. Bahan buangan organik
Bahan buangan organik yang dapat membusuk dan terdegradasi oleh
mikrorganisme sehingga keberadaannya dapat menaikkan populasi
mikroorganisme di dalam air termasuk mikroba patogen di dalamnya.
c. Bahan buangan anorganik
Bahan ini berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi
oleh mikroorganisme. Biasanya berasal dari industri yang melibatkan
penggunaan unsur logam seperti : Pb, As, Cd, Hg, Cr, Ni, Ca, Mg, Zn dan
Co, sehingga dapat terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Air
yang mengandung ion logam seperti Pb, As dan Hg sangat berbahaya bagi
tubuh manusia karena sifat racun, sehingga tidak dapat digunakan sebagai
air minum.
d. Bahan buangan zat kimia
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bahan pencemar air berupa :
sabun, bahan pemberantas hama, zat warna kimia, larutan penyamak kulit
dan zat radioaktif.
e. Bahan buangan cairan berminyak
Bahan buangan cairan berminyak yang dibuang ke air akan mengapung
menutupi permukaan air sehingga menghalangi difusi oksigen dari udara
ke dalam air. Akibatnya jumlah O2 terlarut ke dalam air menjadi
berkurang. Selain itu juga menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam
air.
7

2.6. Industri Pulp dan Kertas
Industri pulp dan kertas secara umum adalah proses produksi untuk
pembuatan kertas, dimana dalam pembuatan kertas ini dapat dibagi menjadi dua
kelompok kerja yaitu unit pulp (pembuatan bubur kertas) dan unit kertas (pembuatan
lembaran kertas). (Billings dan DeHaas,1971).
Seluruh kegiatan pada proses produksi kertas terbagi empat bagian yaitu
(Anonim, 2000) :
1. Bagian Persiapan Pulp
Pulp yang merupakan bahan utama untuk pembuatan disiapkan di bagian
hidrapulper. Bahan yang digunakan adalah kertas bekas (afval), apabila
diperlukan juga menggunakan wood pulp. Bahan tersebut dimasukkan
kedalam hidrapulper dan kemudian ditambahkan air sesuai dengan
perbandingan tertentu untuk mendapatkan konsentrasi 4 – 5 %. Bubur ini
sebelum masuk ke penampung melewati High Density (Hd) Cleaner Dan
Fiber Sorter. Hd Cleaner berfungsi untuk memisahkan bubur kertas dari
kotoran-kotorannya berdasarkan perbedaan berat jenis, sedangkan fiber sorter
menyaring bubur kertas dari Hd Cleaner. Bubur kertas yangt halus dialirkan
ke bak penampung yang selanjutnya dikirimkan ke cycling chest. Bubur kertas
yang kasar dikembalikan ke hidrapulper dan kotoran-kotorannya dibuang oleh
fiber sorter.
2. Bagian Persiapan Bahan Kimia (Stock Preparation)
a. Bagian Persiapan Bahan Kimia
Di bagian persiapan bahan kimia, terdapat penyiapan bahan pembantu
yang dipakai sebagai campuran dalam pembuatan kertas meliputi :
1). Pembuatan larutan kaolin
Larutan kaolin dibuat dengan melarutkan 400 kg kaolin
(Al2O3.SiO212H2O) dalam 1,5 m3 air dalam tangki berpengaduk.
Setelah larut dipompa dan disaring serta dipindahkan ke bak
penampung.
2). Pembuatan larutan size
Pabrik kertas menggunakan size yang sudah jadi dalam konsentrasi
tinggi. Untuk keperluan produksi kertas maka size tersebut tinggal
dilarutkan dalam air sampai diproleh konsentrasi 50 g/l, selanjutnya
siap dikirim ke mixing chest.
3). Pembuatan larutqn alum
Alum sebanyak 350 kg dilarutkan dalam 1,5 m3 air, kemudian dipanasi
sampai mendidih menggunakan uap langsung selama 1,5 jam. Larutan
alum kemudian dipompa ke tangki penampung dan siap dipompa ke
mixing chest.
8

4). Pembuatan larutan tapioka
Dalam tangki pemanas dimasukkan 100 kg tapioka dan air kira-kira
1,5 m3, kemudian dipanaskan dalam jaket uap sambil diaduk sampai
masak kurang lebih 1/2 jam. Larutan alum yang terbentuk dipompa dan
disaring masuk ke bak penampung.
b. Bagian stock preparation
Pada bagian stock prearation, pulp mengalami berbagai perlakuan proses :
1). Proses penghalusan
Pulp dan hidrapulper setelah melewati HD cleaner dan fiber sorter
ditampung disalah satu dari 3 buah cycling chest. Cycling chest berupa
silinder vertikal yang bagian tengahnya disekat berlubang-lubang dan
dilengkapi dengan pengaduk. Sekat ini berfungsi sebagai penyempurna
sirkulasi aliran. Untuk mendapatkan kehalusan serat yang diinginkan
maka pulp dihalusakn menggunakan refiner sambil disirkulasikan dari
cycling chest yang satu ke cycling chest yang lain. Disini digunakan 2
macam refiner dan conical refiner yaitu double disk refiner dan
conical refiner. Setelah kehalusan tertentu didapat, selanjutnya pulp
tersebut dipompa ke mixing chest.
2). Proses pencampuran
Mixing chest merupakan tempat untuk mencampur antara pulp dengan
bahan-bahan pembantu (kaolin, alum, size, dan tapioca). Mixing chest
berupa silinder vertikal yang dilengkapi dengan pengaduk berguna
untuk meratakan pencampuran dan bahan pembantu. Penambahan
alum dilakukan setelah bahan pembantu yang lain ditambahkan, sebab
jika alum ditambahkan bersama-sama, maka serat akan mengumpul
kecil-kecil. Pulp keluar dari mixing chest dengan pH diharapkan
sekitar 4,5 – 5,5 karena jika terlalu basa akan mengalami kesulitan
dalam pembuatan kertas nantinya dan kualitas kertas yang didapat
jelek.
3. Bagian Operasi Mesin Kertas
Alat-alat ataupun proses yang terjadi dibagaian operasi mesin pabrik kertas
meliputi :
a). Machine chest
Merupakan wadah berbentuk silinder yanga dilengkapi dengan pengaduk.
Di dalam chest ini stock disirkulasikan seperti pada mixing chest. Dalam
machine chest pulp ditambah air sehingga konsentrasinya 3 %. Machine
chest berjumlah 2 buah dan keduanya saling berhubungan. Pulp dari
machine chest dipompa conical box 1.
b). Conical box 1
Conical box berbentuk seperti kerucut dan berfungsi untuk meninggalkan
level dari pulp sehingga tekanannya konstan dan pengaliran pulp ke
9

refiner dan mixing tank tidak perlu pemompaan. Pulp di conical box harus
selalu terisi penuh sehingga terjadi over flow. Conical box ada 2 buah
yaitu conical box 1 yang berfungsi sebagai pengatur aliran pulp ke refiner,
conical box 2yang berfungsi sebagai pengatur aliran pulp ke mixing tank.
Sedang over flow conical box 2 disirkulasikan ke conical box 1. Conical
box menampung white water dari chest untuk diumpankan ke mixing tank
sebagai pengencer. Refiner berfungsi untuk menguraikan pulp yang
menggumpal akibat penambahan bahan kimia di mixing chest.
c). Mixing tank
Pulp yang masuk ke mixing tank oleh white water diencerkan sehingga
konsentrasinya tertentu. Konsentrasi yang dikehendaki tergantung pada
jenis kertas yang akan dibuat. Dari mixing tank, pulp dibersihkan dalam
centry cleaner 1. Pulp yang bersih masuk ke vertical screen sedang yang
kotor masuk ke centry cleaner 2 kembali ke mixing tank dan yang kotor
masuk ke centry cleaner 3. Pulp yang bersih dari centry cleaner 3
dikembalikan ke centry claner 2 sedang yang kotor dibuang.
d). Vertical screen dan Johnson Screen
Vertical screen berupa silinder vertical yang dilengkapi ayakan yang
berdiameter 1 mm. Alat ini berfungsi untuk menangkap kotoran-kotoran
yang terbawa oleh pulp sebelaum dialirkan ke flow head box, sedangkan
pulp yang jelek dari vertical screen disaring lagi ke johnson screen, pulp
yang baik disirkulasikan ke mixing tank, sedang yang kasar dibuang.
e). Flow Head Box
Dari vertical screen, pulp masuk ke flow head box yang berfungsi untuk
mengatur pulp ke wire part. Ketebalan sheet diatur dengan slice. Disini
tidak ditambahkan air untuk pengenceran tetap air disemprotkan dengan
water spray nozzle untuk menghilangkan buih. Tinggi pulp dan flow head
box disesuaikan dengan kecepatan wire part.
f). Wire part
Wire part berupa anyaman kawat, dibawah wire part terdapat table rool
yang berputar supaya air keluar. Di antara wire dan flow head box terdapat
forming board yang berfungsi menahan air supaya sheet terbentuk terlebih
dahulu. Setelah itu baru sheet tersebut berjalan ke wire part. Sambil
berjalan kandungan air berkurang sedikit demi sedikit. Sheet kemudian
terbawa melalui suction box. Dengan hisapan pompa vacuum maka air
akan terhisap sehingga kandungan air dalam sheet akan berkurang. Air
yang keluar akan dirampung dalam white water chest. Supaya ukuran
kertas tertentu maka sheet tersebut dipotong pada sisi-sisinya dengan
water sprayer. Sisa potongan tersebut dijatuhkan ke broken chest.
Demikian juga sheet yang sobek-sobek dimasukkan ke broken chest.
Sheet tersebut kemudian diencerkan dengan air sehingga konsentrasiya
menjadi 0,1 %. Wire part kemudian membawa sheet melalui suction couch
10

rool. Disini air dihisap sehingga kandungan airnya berkurang lagi.
Kemudian sheet bergerak ke press part. Air yang terhisap oleh suction
couch rool masuk ke white water chest.
g). Decker machine
Pulp yang encer sekali dari broken chest oleh decker machine dipekatkan
sehingga konsentarasinya menjadi 3 – 4 %. Decker machine ini terletak da
atas machine chest, sedangka airnya dialirkan ke white water chest.
Decker machine berbentuk silinder horizontal yang dindingnya merupakan
saringan 50 mesh.
h). Press part
Press part berfungsi untuk menghasilkan permukaan kertas dan
mengurangi kandungan air yang terbawa oleh sheet. Pengepresan
dilakukan secara mekanik dengan melewatkan sheet di antara 2 rool
silinder yang berputar berlawanan. Di sini da 3 pasang press part. Press 1
tekanannya paling rendah kemudian berturut-turut makin tinggi. Sheet
yang masuk ke unit press kemudian dibawa oleh felt suction box untuk
menghisap air, juga dilengkapi water shower untuk membersihkan feltnya.
i). Drying part
Sheet dari proses kemudian dikeringkan di drying part. Drying part
merupakan silinder-silinder berongga yang diisi uap air sebagai pemanas.
Kondensat kemudian melalui steam trap jenis bimetal, jika kondensat
cukup banyak akan membuka kondensat keluar. Dari tiap-tiap silinder
kondensat mengumpul menjadi satu untuk dikirim ke seksi boiler. Drying
part terdiri dari 6 silinder yang dirangkaikan dengan felt. Dari 6 silinder
dalam group tersebut, satu silinder terletak paling atas dan satyu silinder
paling bawah berfungsi sebagai pengering felt, sedangkan 4 silinderyang
tletak di tengah berfungsi untuk mengeringkan sheet. Pemanasan dari
drying part secar bertingkat mulai 5 0C bertingkat naik sampai 110 0C
kemudian turun secara berangsur-angsur sampai ke 70 0C pada group
terakhir. Di tengah drying part ini terdapat smooth rool untuk melicinkan
sheet.
j). Cooling part
Cooling part terdiri dari 2 silinder berongga yang diisi air untuk
mendinginkan sheet. Silinder tersebut dilapisi dengan tembaga, sheet yang
masih dari drying part didinginkan di cooling part sampai suhu 300 C.
k). Calender
Calender berfungsi untuk menghaluskan permukaan sheet dari cooling
part. Calender berupa 6 silinder horizontal yang disusun vertical. Antara
silinder yang di bawah dengan yang di atasnya berputar berlawanan.
Tekanan total calender 300 – 400 kg / cm2. Setelah dihaluskan, sheet
diperciki air untuk mengurangi kerapuhan kertas. Kandungan air pada
11

sheet di pope rel sekitar 8 %. Dari pope reel kertas dicek gramaturenya
dan dicocokkan dengan standar spesifikasinya.
4. Bagian Penutup
Alat-alat digunakan pada bagian ini meliputi :
a. Double cutter
Gulungan kertas dari pope reel dibawa ke double cutter. Double cutter
merupakan rangkaian alat untuk memotong kertas dalam 2 arah yaitu arah
vertical dan horizontal, sehingga kertas dari pope rool yang berupa
gulungan setelah dipotong di double cutter akan menjadi lembaran
berbentuk persegi dengan ukuran tertentu. Sisa kertas (potongan tepi)
dimanfaatkan untuk dibuat pulp lagi di hidrapulper.
b. Super calendar
Super calendar berupa silinder-silinder horizontal yang disusun vertical.
Jumlah yang disusun ada 11 dan silinder yang ke 2, 6, 8, 10 dari bawah
berdiameter lebih kecil dan dialirkan uap air. Masing-masing silinder yang
dibawah dan yang diatasnya berputar berlawanan. Kertas yang keluar dari
super calendar sudah halus dan siap untuk dipotong di mesin pemotong.
c. Mesin emboss
Mesin emboss dipergunakan untuk membuat kertas line. Untuk membuat
kertas, sebelumnya kertas diuapi kemudian dilewatkan diantara 2 silinder
yang pressnya berpola, sehingga bila kertas melewatinya tersebut akan
menjadi ikut berpola seperti roll silinder yang menekannya. Kapasitas
mesin emboss adalah 5 ton/hari.
d. Mesin cutter
Di bagian finishing terdapat 2 buah mesin cutter. Pemotongan hanya dapat
memotong dalam 1 arah (beda dengan double cutter). Daya potong mesin
ini 500 gr/m. pemotong ini dilengkapi dengan pisau pemotong berputar
dengan kecepatan tertentu, dan dapat memotong kertas dengan ukuran
tertentu sesuai dengan yang dinginkan.
e. Penyortiran
Kertas yang telah dipotong-potong diserahkan ke bagian sortir. Adapun
maksud penyortiran ini adalah untuk memilih kertas yang utuh, tidak
berlipat, ukuran dan warna yang sama. Setelah disortir, dihitung,
dibungkus, dipak kemudian dibal. Untuk mengetahui skema proses
produksi pabrik kertas dapat ditunjukan pada gambar 2.1.
12

Gambar 2.1. Skema Unit Proses Produksi Pabrik Kertas
(Anonim, 2000)
13
Conveyor Hydra Pulper Hd Cleaner Cycling Chest Refiner
Limbah Padat
Former
Machine ChestConical BoxMixing TankPressure Mixing Chest
Making Felt Press Size Press Dryer Cooling
Chemical
Limbah Cair
Calender CoatingCalender IIGloss CalenderPope Reel
Limbah Cair Belt Filter Press
SludgeCustomerGudang Hasil
Wraping (Finishing)
Sheeter

2.7. Karakteristik Air Buangan
Kualitas air buangan industri kertas dikelompokkan menjadi :
1. Karakter fisis, dengan parameter :
a. Temperatur
Temperatur air limbah perlu diperhatikan dengan adanya kenaikkan
temperatur air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar
oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menyebabkan timbulnya bau
tidak sedap akibat terjadinya degradasi anaerobic yang mungkin terjadi.
b. Kekeruhan
Kekeruhan yang dimliki oleh limbah cair diakibatkan oleh kandungan
padatan baik senyawa organic, anoraganik dan mikroorganisme.
Kekeruhan akan menghambat penembusan cahaya matahari yang
dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk reaksi fotosintetis yang
menghasilkan O2. Jika reaksi fotosintetis terhambat, maka penambahan
oksigen terlarut akan tidak berlangsung secara maksimal dan jumlah
mikroorganisme per-m2 akan menurun. Hal ini akan menyebabkan
makanan alami ikan dan perairan menyusut dan ikan tidak dapat bersaing
akan menyisih dari perairan tersebut. Usaha pengurangan kekeruhan perlu
dilakukan agar proses alami yang berlangsung dapat dipertahankan
(Billings and DeHass, 1971).
c. Warna
Limbah cair yang berwarna akan meningkatkan warna badan air yang
menerima limbah cair tersebut, jika limbah itu dibuang ke lingkungan
tanpa pengolahan. Badan air yang berwarna dapat menyerap berbagai
panjang gelombang cahaya matahari., sehingga intensitas cahaya yang
diperlukan untuk reaksi fotosintesis akan menurun. Warna dalam limbah
cair industri pulp dan kertas terutama berasal dari proses pulp yang timbul
disebabkan oleh terlarutnya lignin. Sedangkan yang berasal dari proses
pembuatan kertas disebabkan oleh zat warna yang digunakan (Billings and
deHass, 1971).
d. Bau
Bau dalam air umumnya disebabkan oleh gas-gas terlarut seperti H2S dan
senyawa organic yang menguap. Kualitas air yang baik adalah yang tidak
berbau (Billings an DeHass, 1971).
e. Padatan
Konsentrasi dalam limbah cair dibagi menjadi padatan total (total solid),
padatan tersuspensi (suspended solid), dan padatan terlarut (dissolved
soid). Dalam air limbah industri kertas umumnya berupa zat padat
tersuspensi terdiri dari serat, pigmen, dan bahan aditif. Adanya zat padat
tersuspensi mempengaruhi keseimbangan dalam badan air penerima
(Billings and DeHass, 1971).
2. Karakteristik kimia, dengan parameter :
14

a. pH
pH adalah suatu parameter yang berkaitan dengan konsentasi ion hydrogen.
Kehadiran ion hydrogen ini disebabkan oleh penguraian asam dengan
elektrolit kuat. Jika air memiliki nilai pH yang trendah, air ini mengandung
ion hydrogen yang tinggi dan keadaan ini mendorong korosi pada pipa atau
saluran dan dapat mematikan kehidupan makhluk air. Jika pH air itu tinggi
maka makhluk air tidak dapat bertahan utuk hidup (Billlings and DeHass,
1971).
b. Biological Oxygen Demand (BOD)
Parameter BOD adalah parameter yang digunakan untuk tolak ukur
kandungan senyawa organic yang dapat dirombak oleh mikroorganisme.
Semula mikroorganisme yang aerobik berperan dalam perombakan pada
keadaan perairan masih mengandung O2 kemudian mikroorganisme
anaerobic mengambil alih dalam perombakan pada keadaan perairan
kekurangan atau tanpa O2.
c. Chemical Oxygen Demand (COD)
Senyawa organic dan anorganik masih banyak yang tidak dapat dirombak
oleh mikroorganisme. Senyawa ini dinyatakan sebagai tolak ukur yang lain
untuk menyatakan kebutuhan oksigen yang diperlukan pada reaksi oksidasi
secara kimiawi. Kebutuhan oksigen untuk reaksi ini dinyatakan sebagai COD
(Billings dan DeHaas, 1971).
d. Senyawa Beracun dan Logam Berat
Senyawa ini berada dalam air dalam bentuk padatan terlarut. Konsentrasi
ion-ion logam berat antara lain raksa (Hg), khrom (Cr), kadmium (Cd), seng
(Zn), yang dapat meracuni makhluk hidup perairan, sehingga kandungan ion-
ion ini dibatasi kehadirannya (Billings And DeHaas, 1971).
e. Dissolved Oxygen (DO)
Oksigen terlarut merupakan salah satu parameter yang penting, Karena
parameter ini memiliki dua pengaruh yang berlawanan. Sisi yang
menguntungkan adalah oksigen yang digunakan untuk mendukung
kelangsungan hidup makhluk air. Sisi yang merugikan kehadiran O2
menyebabkan korosi peralatan kalau air itu digunakan untuk air industri
secara langsung.
2.8. Pengendapan Kimia (Presipitasi Kimia)
2.8.1. Pengertian
Pengendapan secara kimia atau basa disebut presipitasi kimawi, merupakan
suatu proses yang mengubah senyawa terlarut menjadi bentuk tak larut,
dengan reaksi kimia atau perubahan komposit pelarut untuk memperkecil
kelarutan senyawa di dalamnya (anonim, 1995).
2.8.2 Penggunaan Presipitasi Kimia
15

Presipitasi kimia dapat dipakai untuk mengolah limbah encer yang
mengandung bahan beracun, yang dapat diubah menjadi bentuk tak larut,
misalnya : limbah yang mengandung arsen, cadmium, kromium, copper,
lead, merkuri, nikel, selenium, perak, thalium, dan zeng. Industri utama
merupakan sumber limbah yang mengandung logam adalah pelapisan logam
dan industri elektronik (anonim, 1995).
2.9. Landasan Teori
Industri kertas memiliki kandungan warna, bahan organic dengan indicator
BOD dan COD, temperatur, bahan tersuspensi, dan logam berat yang cukup tinggi.
Keberadaan logam berat dalam limbah cair akan mempengaruhi lingkungan di
sekitarnya baik tanah, air sungai maupun air tanah yang menyebabkan
terkontaminasinya lingkungan tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap
kesehatan manusia yang menggunakan air tercemar atau dengan memakai dalam
kehidupan yang berasal dari perairan tersebut. Untuk itu perlu adanya alternatif
pangolahan agar limbah yang dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang
disyaratkan. Untuk meminimalisasi limbah cair yang mengandung logam berat,
terutama logam khrom (Cr) dan seng (Zn) adalah dengan pengolahan kimia proses
presipitasi dengan menggunakan larutan natrium bisulfit (Anonim, 2001).
Presipitasi sulfit mempunyai beberapa keuntungan , yaitu logam sulfit tidak
amphoterik. Khrom dan seng dapat dipresipitasi dalam proses tanpa suatu langkah
reduklsi secara terpisah. Reaksi untuk logam divalent dengan presipitan natrium
bisulfit mengikuti persamaan berikut :
L++ + Na2 S2O LS2O + 2Na+
Penghilangan logam khrom dan seng dengan presipitan natrium bisulfat akan
berlangsung reduksi dan presipitasi khrom hidroksid dalam satu langkah berikut :
Cr + Na2 S2O + 5H2O 2Na(OH)3 + Cr(OH)3 + 2S
+ 4H+
Zn + Na2 S2O + 5H2O 2Na(OH)3 + Zn(OH)3 + 2S
+ 4H+
Sumber sulfit yang sudah pernah dipakai meliputi sodium sulfit (Na2S),
sodium hidrosulfit (NaHS), dan fero sulfit. Dua yang pertama mempunyai kelarutan
tinggi, sedangkan fero sulfit sedikit larut. (Anonim, 2001).
Proses presipitasi kimia untuk menghilangkan logam berat dapat
digambarkan pada Gambar 2.2 :
16

Chemical
kopresitatant
Pengaduk Paddle
Inlet
Outlet
Bak Presipitator
Bak Pengendap Sludge
(Sumber : Anonim, 1995)
Gambar 2.2. Skema Proses presipitasi Kimia
2.10. Hipotesis
Dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori
diatas dapat dikemukakan hipotesis bahwa :
1. Proses presipitasi kimia dengan menggunakan ntrium bisulfit dapat menurunkan
kadar khrom dan seng pada limbah cair industri kertas.
2. Dosis natrium bisulfit yang paling baik adalah 12 ml.
3. Efisiensi proses presipitasi kimia dengan menggunakan natrium bisulfit sebesar
12 ml.
17
Chemical Presipitatant

Bab III
Metode Penelitian
3.1. Obyek Penelitian
Outlet limbah cair pabrik kertas PN. Blabak. Magelang.
3.2. Alat Dan Bahan Penelitian
Alat yang digunakan :
Beaker glass volume 1000 ml
Pipet ukur
Pengaduk dengan alat jar-test
Stop watch
pH meter
Karet hisap
Kalori meter
Bahan yang digunakan :
Larutan sodium bisulfat
Limbah cair (sample) industri kertas
3.3. Variabel Penelitian
Variabel-variabel penelitian terdiri dari :
1. Variabel terikat
Variabel terikat yaitu variabel yang diduga nilainya akan berubah karena
pengaruh dari variable bebas, dalam hal ini adalah Khrom dan Seng.
2. Variabel Bebas
Variabel bebas yaitu variabel yang berpengaruh atau yang menyebabkan
berubahnya variabel terikat. Variable yang berpengaruh yaitu dosis sodium
bisulfat 5 % dengan variasi 0 (kontrol), 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ml dan pH dengan
variasi 8, 9, dan 10.
3.4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dan analisis laboratorium dilakukan di kampus II Sekolah
Tinggi Teknik Lingkungan “YLH” Yogyakarta.
3.5. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan mulai bulan Mei sampai Agustus 2004.
3.6. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data diperoleh dengan pengukuran dan pemeriksaan air
buangan limbah industri kertas sebelum dan sesudah dilaksanakan perlakuan.
18

3.7. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan ada dua kegiatan yaitu :
a). Kegiatan di lapangan
Pengambilan sampel dilakukan pada bak penampung air limbah
b). Kegiatan di laboratorium
Perlakuan dan pemeriksaan sampel di laboratorium.
3.8. Cara Kerja
a). Disiapkan beaker glass volume 1000 ml dan diberi kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
b). Dimasukkan air limbah masing-masing 1000 ml ke dalam beaker glass.
c). Masing-masing ditambahkan sodium bisulfit 5 % dengan dosis 0 ml
(kontrol), 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml, dan 12 ml.
d). Diperiksa pH sesuai dengan kebutuhan perlakuan yaitu 8.
e). Pengadukkan dengan jar test sampai terjadi larutan homogen dengan
kecepatan 80 rpm dengan waktu 60 detik.
f).Setelah selesai pengadukkan bahan didiamkan selama 30 menit.
g). Ulangi perlakuan a sampai f untuk pH 9 dan 10.
h). Diperiksa kandungan parameter Zn da Cr.
3.9. Analisis Data
19
Natrium Bisulfit
( 0 (Kontrol), 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 )
Tangki berpengaduk @ = 1000 ml
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 )
Pengecekkan pH = 8
Pengadukkan 80 rpm selama 60
detik
Diamkan selama 30 menit
Pengadukkan 80 rpm selama 60 detik
Ulangi untuk pH 9dan 10
Analisis laboratorium

3.9.1. Analisis Regresi
Untuk pengujian hipotesa dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh
dianalisa dalam analisa regresi linear untuk mengestimasi seberapa dekatnya
hubungan antara variabel. Variabel yang saling berhubungan tersebut adalah
variabel terikat dalam hal ini adalah kadar Zn dan Cr, sedang variabel bebas
adalah konsentrasi sodium bisulfit. Persamaan garis regresi linear adalah :
Y = a + bx
Untuk mendapatkan harga a dan b menggunakan rumus :
3.9.2. Perhitungan Efisiensi Penurunuan
Kandungan Hg total dapat diketahui dari hasil analisa laboratorium.
Sehingga dapat diketahui besarnya penurunan Hg total pada setiap perlakuan.
Besarnya efisiensi penurunan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:
keterangan :
E = Efisiensi penurunan (%)
Co = Konsentrasi awal (mg/l)
Ce = konsentrasi akhir (mg/l
3.10. Spesifikasi Perancangan Alat Presipitasi
6
20

3 4
5
6666666
1
2
Keterangan : 1. Ruang Pencampuran
2. Ruang Pengendapan
3. Penambahan Presipitan
4. Pengadukkan
5. Input
6. Output
Keterangan Design Alat :
1. waktu tinggal bak flokulasi 20 – 60 menit
2. gradient kecepatan 40 – 6 /detik
3. power input (P) = G2 . V . μ
4. power input menggunakan pedal
Keterangan :
P = Power input
G = Gradient kecepatan (det-1)
V = Volume kolam pengaduk (m3)
μ = Koefisien kekentalan dinamis (N.det/m2)
Cd = Koefisiien drag = 1,8
ρ = Rapat massa air (kg/m3)
A = Luas penampung pedal (m2)
v = Kecepatan relatif pedal dalam air (m/s)
21

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2000, Laporan Kerja Praktek di PN Blabak, Magelang.
Anonim, 1995, Pengolahan Limbah Secara Kimia, Kursus Perancangan Air Limbah
Industri, UGM, Yogyakarta.
Billings R.N. and De Haas G.G., 1971, Pollution Control in Pulp and Paper Industry
dalam Industrial Pollution Control hand Book, H.F. Lund (ed). Mc Graw-Hill Inc. New
York.
Fujii, 1973, Pengaruh Logam Berat terhadap Lingkugnan, Perwata Oceana Vol. 2,
Jakarta.
Ginting, P., 1995, Pengendalian Pencemaran Industri, Rajawali Pers, Jakarta.
Tjokrokusumo, 1995, Pengantar Enjinering Lingkungan, STTL, Yogyakarta.
Tyoso, 1995, Strategi Umum Minimasi Limbah Industri, Jurusan Teknik Kimia, UGM,
Yogyakarta.
Wardhana W.A., 1996, Teknik Analisis Radioaktifitas Lingkungan, Andi Offset,
Yogyakarta.
22