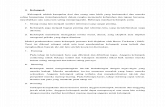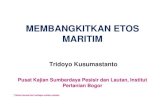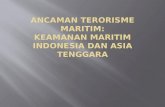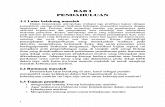maritim makalah
-
Upload
kartika-mahardhika -
Category
Documents
-
view
1.166 -
download
28
description
Transcript of maritim makalah

1
KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum .wr .wb
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNyalah
makalah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Makalah mengenai Hukum Pengangkutan (Maritim) : Penerapan Asas
Cabotage dalam Industri Migas ini disusun atas dasar untuk memenuhi nilai
tugas makalah yang diberikan oleh dosen mata kuliah Hukum Maritim.
Pembahasan mengenai penerapan asas cabotage dalam industri
pengangkutan dan migas sangatlah penting maka dari itu, penulis berharap
semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembacanya yang ingin
mengetahui mengenai penerapan asas cabotage dalam industri migas.
Semoga makalah ini dapat menambah informasi bagi para pembacanya.
Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah
ini.
Wassalammu’alaikum .wr .wb
Jakarta, 28 Mei 2012
Penulis

2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................. 1
Daftar Isi ............................................................................................................ 2
Bab I : Pendahuluan
1. Latar Belakang ....................................................................................... 3
2. Pokok Permasalahan ............................................................................. 4
Bab II : ISI
2.1 Hukum Pengangkutan di Indonesia
2.1.1 Pengaturan di Indonesia............................................................ 5
2.1.2 Tentang Pengangkutan dengan Kapal ...................................... 6
2.2 Asas Cabotage ...................................................................................... 8
2.3 BP Migas.............................................................................................. 12
2.4 Penerapan asas Cabotage bagi Industri Migas
2.4.1 Kasus Posisi ............................................................................ 16
2.4.2 Penerapan asas cabbotage terhadap kapal-kapal dalam
industri migas di Indonesia ........................................................................ 17
Bab III : Penutup.............................................................................................. 21
Daftar Pustaka................................................................................................. 23

3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah suatu negara, dengan kekayaan alam yang
melimpah, seperti bahan-bahan tambang emas, nikel, perak, minyak dan gas,
juga di bagian perkebunan, seperti kopi, kelapa sawit dan karet. Sebuah
Negara yang terdiri dari pulau-pulau, yang dihubungkan dengan laut yang
begitu luas, maka dalam hal menyalurkan seluruh kekayaan alam tersebut,
diperlukan suatu sistem pengangkutan laut yang memadai.
Sekitar tahun 2009 lalu, dunia hukum mengenai pengangkutan laut
dihebohkan dengan masalah penerapan asas Cabbotage, dengan
dikeluarkannya Inpres No 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri
Perkapalan. Asas cabbotage adalah bahwa, setiap kapal yang melintas
dikawasan Indonesia harus berbenderakan bendera Indonesia. Menurut PP
tersebut, bahwa dengan menerapkan asas cabbotage maka kapal yang ada
haruslah berbendera Indonesia dengan konsekuensi bahwa kepemilikan atas
saham kapal tersebut, sebanyak 51% dipegang oleh Indonesia, badan hukum
Indonesia atau warga negara Indonesia.
Pada makalah ini akan dibahas mengenai peran BP Migas dalam
hukum pengankutan laut di bidang minyak dan gas bumi. BP Migas berperan
sebagai Badan Pelaksana bagian Hulu dalam Penambangan Minyak dan Gas
Bumi. BP Migas mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
bagian hulu dalam pertambangan Minyak dan Gas Bumi baik di darat maupun
di laut.
Mengenai isu asas cabbotage, BP Migas juga mengalami masalah.
Masalah terdapat pada kapal-kapal yang digunakan untuk melakukan
kegiatan hulu pertambangan minyak. Pada kegiatan hulu tersebut,
sebenarnya sebanyak 90% kapal adalah berbendera Indonesia, jadi tidak
terdapat masalah. Masalah timbul pada kapal jenis jack up rig dan 3D seismic
vessel. Sebanyak 10% kapal adalah berbendera asing, termasuk jenis kapal
tersebut, sedangkan jika diganti dengan bendera Indonesia, banyak dari
pihak Indonesia, seperti badan hukum Indonesia atau warga negara
Indonesia, mereka tidak mau mengambil resiko menanamkan modal pada
jeniskapal tersebut, padahal jenis kapal itu adalah hal yang penting dalam
pertambangan. Dikarenakan para pengusaha Indonesia tidak ingin
mengambil resiko, kedua jenis kappa tersebut adalah digunakan hanya dalam

4
jangka waktu yang relatif pendek, sekitar 20 hari sampai dengan 3 bulan saja,
dan hanya pada lokasi tertentu saja. Kemudian, tidak banyak industri
galangan kapal di Indonesia yang mampu memproduksinya karena biaya
yang mahal.
Hal ini berakibat kepada berhentinya operasi drilling rig, maka produksi
minyak pun terhenti. Ini berdampak pada berkurangnya produksi minyak
mentah siap jual atau lifting pada tahun 2011. Pada APBN 2011, pemerintah
mengasumsikan lifting pada tahun 2011 akan ada di posisi 970.000 barrel per
hari. Namun, akibat akumulasi masalah, antara lain masalah drilling rig, maka
target lifting diperkirakan akan berkurang menjadi 940.000 barrel per hari.
Tetapi kemudian pemeriintah mengeluarkan PP No 22 tahun 2011
tentang Angkutan Perairan Laut yang memiliki ketentuan pengecualian asas
cabotage terhadap industri migas. Lalu mentri perhubungan memberikan
jangka waktu kepada industri migas untuk segera melengkapi kapalnya
dengan bendera Indonesia, sampai dengan tahun 2015, pada Peraturan
Menteri Perhubungan No 48 tahun 2011.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan hukum pengangkutan di Indonesia?
2. Bagaimakah pengaturan asas cabbotage di Indonesia?
3. Apa peran BP Migas dalam proses pertambangan Minyak dan Gas,
termasuk hal pengangkutan hasil tambang?
4. Apa keuntungan diterapkannya asas cabbotage bagi BP Migas, terkait
dengan masalah Rig kapal?

5
BAB II ISI
2.1 Hukum Pengangkutan di Indonesia 2.1.1 Pengaturannya di Indonesia. Pengangkut, berdasar pasal 466 KUHD, dalam arti menurut title adalah
orang yang baik karena penggunaan penyediaan kapal menurut waktu atau
penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan, maupun karena
perjanjian lainnya, mengikatkan diri untuk melaksanakan pengenkutan
barang-barang seluruhnya atau sebagian menyebrang laut.
Menurut The Hague Rules 1924, pengangkut adalah baik pemilik kapal
atau pihak pengguna penyediaan kapal, dalam hal kapal di carter,
berdasarkan perjanjian pengangkutan.
Sedangkan menurut The Hamburg Rules 1978, pengangkut dibedakan
menjadi carriers dan actual carriers. Carriers adalah setiap orang untuk siapa
atau untuk atas nama siapa perjanjian pengangkutan barang di laut diadakan
dengan pihak yang berkepentingan dengan barang muatan. Sedang, actual
carriers adalah mereka melaksanakan pengakutan barang atau
melaksanakan sebagian pengangkitan dan termasuk didalamnya orang lalin
terhadap siapa pelaksanaannya telah dipercayakan padanya.
Pengaturan mengenai hukum pengangkutan laut di Indonesia, dahulu
diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Buku V mengenai
Pengangkutan, pada KUHD mengatur tidak hanya mengenai pengangkutan
barang tetapi juga pengengkutan orang. KUHD hanya mengetur mengenai
pengangkutan melalui laut saja.
1. Bagian III, title 5 buku I, pasal 91 – 98 mengenai tugas pengangkut
serta juragan kapal yang berlayar di sungai dan perairan pedalaman.
2. Bagian II title 5 buku I pasal 86 – 90 mengenai kedudukan para
ekspeditur sebagai pengusaha kapal.
Kemudian pengaturan mengenai pengangkutan kapal ini berubah
sejak diundangkannya, UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, yang
kemudian diganti dengan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Mengenai peraturan pelaksanannya, Indonesia memiliki diantaranya
PP No 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta Inpres No. 5 tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

6
2.1.2 Tentang Pengangkutan dengan Kapal Kapal digunakan untuk berbagai perjanjian, antara lain adlaah sewa-
menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lainn
Jasa-jasa angkutan laut biasanya mengenai barang-barang besar atau
bulk comoditi dan juga dapat menempuh jarak jauh, lebih jauh jarak yang
ditempuh relatif akan lebih murah freightnya, ruang angkutan laut
dibandingkan dengan angkutan darat memang lebih besar dan luas. Kapal
dapat menampung sampai ribuan ratus ton.
Menurut KUHD pasal 309, kapal adalah semua bahtera papun
namanya dan papun sifatnya, yang ditujukan untuk berlayar. Menurut
Memiore van Toelechting, bahwa kapal adalah benda-benda yang dapat
berlayar dan bergerak di air, meliputi juga kapal keruk dan rakit yang tidak
ditujukan untuk berlayar di laut.
Pasal 309 ayat (2) bahwa kapal juga meliputi segala alat
perlengkapan, yaitu segala benda yang bukan suatu bagian dari kapal itu
sendiri namun diperuntukan untuk selamanya dipakai tetap dnegan kapal itu
Kapal laut ialah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di lautan
atau sementara di pakai disungai-sungai untuk dipakai mengarungi lautan
atau sementara mengarungi sunga-sungai.
Kapal laut Indonesia adalah kapal laut yang dimiliki oleh seorang atau
lebih warga negara Indonesia atau dimiliki untuk 2/3 bagian oleh seorang atau
lebih negara Indonesia dan untuk 1/3 bagian oleh seorang atau lebih
penduduk Indonesia, dengan syarat pemegang buku dari kapal tersebut
harus seorang waraga negara Indonesia (Pasal 311 KUHD RI pasal 2 ayat
(1)).
Sedangkan menurut UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal
adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan
dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah
permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
Berdasar pasal 8 UU No 17 Tahun 2008, bahwa pengangkutan dalam
negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak berkewarganegaraan
Indonesia. Disebutkan pula bahwa, kapal asing dilarang mengangkut
penumpang dan/atau barang antarpulau atau pelabuhan di wilayah perairan
Indonesia.

7
Bagi kapal laut yang diakui secara sah, dulu, menuru KUHD adahal
harus dapat memiliki paling tidak 1 dari 4 surat kapal, yaitu :
1. Surat Laut yang diberikan oleh Menteri Perhubungan Laut untuk
sesutau waktu tertentu kepada kapal laut Indonesia yang besarnya
dibagi dalam (inhoud) 500meter kubik briuto atau lebih yang bukan
suatu kapal laut nelayan dan bukan suatu kapal pesiar.
2. Surat - pas – kapal, yang menurut UU dibagi menjadi dua, yaitu :
o Pas Tahunan yang diberikan setahun sekali kepada kapal laut
Indonesia yang besarnya dibagian dalam adalah 20 meter kubik
bruto atau lebih tetapi kurang dari 50 meter kubik bruto dan
bukan suatu kapal nelayan atau kapal pesiar.
o Pas kecil diberikan kepada kapal laut Indonesia yang besarnya
kurang dari 20 M kubik dan bukan suatu kapal nelayan atau
kapal pesiar
3. Surat laut sementara : Diberikan kepada kapal laut Indonesia yang
memenuhi persyaratan perundang-undangan (ayat 2, pasal 1, 2, 3
pasal 311 KUHD) yang dibeli dan dibikin diluar wilayah Negara
Republik Indonesia yang dipesan oleh melalui menteri perhubungan
laut selama dalam pelayarannya ke Wilayah Indonesia oleh konsulat
RI setempat dapat diberi surat ijin berlayar (surat laut sementara, yang
apabila sudah sampai di wilayah Indonesoa, harus secepatnya ditukar
dengan surat laut.
Mengenai Kebangsaan Kapal, pasal 311 dan 312 KUHD mengatur
mengenai kebangsaan kapal Indonesia, kebangsaan kapal dinyatakan oleh
pemberian surat laut dan pas kapal.
Berdasarkan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa Tata
Cara pendaftaran kapal adalah sebagai berikut :
1. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Pegawai Balik Nama
(pejabat pendaftar kapal)dengan disertai dokumen :
o Surat Ukur yang diberikan menurut ketentuan hukum yang
berlaku.
o Akta penyerahan pembuatan kapal/surat pembelian kapal/surat
tanda bukti kepemilikan lainnya␣ o Pendaftaran kapal untuk penggunaan kapal sebagai kapal
laut/kapal penangkap ikan laut atau kapal sungai␣ 2. Jika pendaftaran sebagai kapal laut/kapal penangkap ikan laut, maka
perlu tambahan dokumen berupa:

8
o Keterangan dari pemohon bahwa kapal tersebut adalah kapal
Indonesia menurut ketentuan 311 KUH Dagang, yaitu kapal yang
dapat dibuktikan sebagai kapal Indonesia berdasarkan surat-surat
laut dan pas-pas kapal (baik pas tahunan maupun pas kecil).
o Surat-surat lainnya yang diperlukan untuk penetapan kebangsaan
kapal.
3. Berdasarkan permohonan tersebut Syahbandar (pejabat pendaftar
kapal) akan membuat akta pendaftarannya dan kepada pemilik kapal
diberikan salinan pertama pendaftaran /grosse akta pendaftaran (de
grosse van de acte can teboekstelling), apabila pemeriksaan data surat
dan pihak membuktikan kebenaran kepemilikannya, dan telah
memenuhi semua persyaratan.
4. Pendaftaran dapat dilakukan ditempat yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan, namun setelah didaftarkan dan tercatat di suatu
tempat, maka pendaftaran tersebut tidak dapat dipindahkan ke tempat
lain.
5. Pendaftaran tersebut dapat dicoret apabila:
o Kapal karam atau dibajak oleh pihak tertentu
o Kapal dibongkar
o Kapal laut/ kapal penangkap ikan laut kehilangan sifat sebagai
kapal Indonesia
Pendaftaran ini menganut stelsel negatif jadi nama yang tercantum dalam
daftar belum tentu menunjukkan sebagai pemilik kapal yang bersangkutan.
Jadi pemilik yang sebenarnya sewaktu-waktu dapat mengajukan haknya
kepada yang berwenang.
2.2 Asas Cabbotage
Istilah cabotage berasalh dari abad ke 19 di Prancis, dari kata caboter
“sail along a coast”, kemungkinan dari Spanyol cabo “cape, headland”.
Cabotage dalam kamus Oxford adalah the right ti operate sea, air, or
other transport services within a particular territory. Restriction of the
operation of sea, air or other transport services within or into a particular
country to that country’s own transport services.
Cabotage berarti prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara
komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari
negara itu sendiri secara eksklusif. Asas cabotage adalah kegiatan angkutan
laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan

9
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU 17 Tahun 2008 Penggunaan kapal
berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan
dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan
negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta
memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan
angkutan laut nasional. Pada 2009, pelayaran nasional telah memenuhi
kebutuhan armada untuk angkutan laut batu bara dalam negeri dan angkutan
migas dalam negeri.
Lahirnya Asas Cabotage menjadi harapan baru bagi industri angkutan
laut nasional. Usaha mereka terjaga dan kedaulatan negara terlindungi dari
gangguan pihak asing. Ironisnya, setelah lahir peraturan mengenai kewajiban
kapal angkutan laut di dalam negeri berbendera Indonesia, industri angkutan
laut nasional masih belum dapat bangkit. Sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia, Indonesia masih di bawah bayang-bayang negara lain. Sebelum
adanya Asas Cabotage, sebagian besar angkutan laut domestik dilayani
kapal-kapal berbendera asing. Hal ini menjadikan kepentingan usaha
angkutan laut nasional terpuruk. Atas dasar itu pada 7 Mei 2011, lahir Asas
Cabotage.
Asas ini memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran
dalam negeri sepenuhnya hak negara pantai. Artinya, negara pantai berhak
melarang kapal-kapal asing berlayar dan berdagang di sepanjang perairan
negara tersebut. Penerapan Asas Cabotage didukung ketentuan Hukum Laut
Intenasional, berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas
wilayah lautnya. Karena itu, kapal asing tidak boleh berada atau memasuki
wilayah perairan tanpa izin dan alasan yang jelas. Kecuali untuk jalur kapal
bantuan dan memiliki izin atau alasan yang sah tanpa mengganggu stabilitas
keamanan dan ketertiban negara.
Mengenai asas cabotage sebenarnya telah diatur dalam Instruksi
Presiden No 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Laut,
diinstruksikan Presiden kepada 13 Menteri dan para
Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk menerapkan asas
cabotage dengan konsekuen, dengan merumuskan kebijakan serta
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan jabatan masing-
masing.
Kemudian keluar Keputusan menteri Perhubungan No 71 tahun 2005
tentang pengangkutan muatan /barang antar pulau di dalam negeri,

10
menetapkan road map penerapan asas cabotage berdasarkan komoditi yang
akan optimal terlaksana selambat-lambatnya 1 januari 2011.
Keluarnya UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, memberikan
keberpihakan kepada asas cabotage ini, tertuang dalam pasal 8 ayat 1,
bahwa Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera merah putih
dan pada ayat 2 diyatakan bahwa, Kapal asing dilarang mengangkut
penumpang dan atau barang antar pelabuhan di Indonesia.
Untuk menunjang penerapan asas cabotage, pemerintah kemudian
mengeluarkan PP No 20 tahun 2012, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa,
Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan
laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. PP No 20 tahun
2010, kemudian diubah dengan PP No 22 tahun 2011.
Secara ekonomi, tujuan diberlakukannya Asas Cabotage adalah untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, dengan memberikan
kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut
nasional dan lokal. Diyakini peraturan ini dapat meningkatkan produksi kapal
dalam negeri, karena seluruh kapal yang berlayar di perairan tanah air harus
berbendera Indonesia. Selain itu, Asas Cabotage difungsikan untuk
melindungi kedaulatan negara, khususnya di bidang industri maritim.
Melihat potensi bisnis angkutan kapal di Indonesia, khususnya migas
yang mencapai 4-5 miliar dolar AS per tahun, menjadi peluang besar bagi
industri maritim nasional. Ironisnya, berdasarkan laporan INSA pada 2009,
selama ini angkutan oil dan gas di Indonesia dilayani 54 unit kapal yang
seluruhnya berbendera asing. Atas lahirnya Asas Cabotage diharapkan
industri galangan kapal dalam negeri yang selama ini mati suri kembali hidup.
Sementara itu, dari data Kementerian Perhubungan, hingga September 2010,
jumlah kapal berbendera Indonesia tercatat sebanyak 9.835 unit. Rata-rata
kapasitas angkutan kapal-kapal tersebut 13,03 juta Gross Ton (GT) atau
meningkat dari 6.041 unit dengan kapasitas angkut 5,67 juta GT pada Maret
2005. Yaitu, terdiri dari 8.205 unit kapal berkapasitas angkut 12,4 juta GT
milik Perusahaan Angkutan Laut Nasional Pemegang Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan 1.630 unit sisanya berkapasitas
angkut 591.337 GT milik perusahaan angkutan laut pemegang Surat Izin
Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).
Kendala yang dihadapi dalam menerapkan Asas Cabotage adalah
perusahaan pelayaran nasional tidak sepenuhnya memiliki kapal. Mereka

11
hanya menggantungkan usahanya pada kegiatan keagenan kapal. Kualitas
dan perusahaan pelayaran membengkak tanpa kontrol. Sebagai contoh, pada
September 1993 terdapat 1045 perusahaan pelayaran dan 389 perusahaan
non pelayaran. Pertambahan jumlah perusahaan pelayaran yang demikian
cepat tidak seimbang dengan pertambahan jumlah tonase kapal-kapal niaga.
Sampai 2001, tercatat ada 1.762 perusahaan pelayaran.
Terungkap, kondisi ini terjadi karena beban biaya yang harus dipikul
perusahaan pelayaran nasional sangat besar. Beban pajak yang berlapis-
lapis dan tinggi menghambat pertubuhan usaha angkutan kapal dalam negeri.
Masalah ini tidak dialami perusahaan kapal asing di negaranya. Mereka justru
banyak diberikan kemudahan baik dari segi permodalan maupun regulasinya.
Walhasil, persaingan antara kapal Indonesia dengan kapal asing menjadi
tidak fair.
Pada 19 November 2010, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 73 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Permenhub No 22 Tahun 2010 yang mengatur pengangkutan barang antarpelabuhan dalam negeri. Dalam revisi ini, batas waktu penggunaan kapal asing untuk angkutan barang antarpelabuhan di
dalam negeri diperpanjang hingga 7 Mei 2011. Padahal, mestinya asas cabotage yang ditetapkan pada 2005 itu harus dipatuhi paling lambat Januari 2011.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono beralasan hal itu dilakukan lantaran pemerintah menilai Indonesia belum memiliki perusahaan kapal penunjang kegiatan lepas pantai yang memadai.
Sebelumnya, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyatakan khawatir akan potensi penurunan produksi minyak mentah 200 ribu barel per hari atau US$2,6 miliar akibat penerapan
asas cabotage. Sebagai responsnya, selain merevisi permenhub, pemerintah bahkan juga akan segera mengajukan revisi terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kepada DPR.
Menurut Menteri Perhubungan Freddy Numberi, setidaknya ada lima pasal dalam UU Pelayaran yang akan diamendemen untuk menghindari mandeknya produksi minyak nasional. Dalam amendemen itu, kapal
pendukung kegiatan lepas pantai akan dikeluarkan dari klasifikasi penerapan asas cabotage. Setengah hati Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Indonesian National Shipowners Association (INSA) Paulis Djohan menilai
keputusan pemerintah itu tidak konsisten. Menurut Paulis, keputusan itu menunjukkan pemerintah tidak serius ingin menjaga kedaulatan ekonomi bangsa di laut dengan mengoptimalkan potensi kapal offshore berbendera

12
Merah Putih.
2.3 BP Migas Penguasaan pertambangan Minyak dan Gas bumi dikuasai oleh
negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar hasil dari kekayaan
alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sebesar-besarnya bagi
rakyat banyak. Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemegang kuasa
pertambangan, yang diberikan dari negara, untuk melakukan kegiatan
eksploitasi dan ekplorasi.
Eksplorasi adalah kegiatan dengan tujuan utnuk memperoleh informasi
mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan
minyak dan gas bumi serta menentukan tempat wilayah kerja. Sedangkan
ekploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan
gas bumi dan menentukan mengenai tempat wilayah kerja.
Berdasarkan pasal 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu
hulu dan hilir.
Kegiatan Hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada
kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi. Kegiatan
eksploitasi adalah bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari
wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas :
1. Pengeboran dan penyelesaian sumur;
2. Pembangunan sarana pengankutan;
3. Penyimpanan;
4. Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di
lapangan;
5. Kegiatan lain yang mendukungnya.
Kegiatan usaha hulu dikendalikan melalui kontrak kerja sama (KKS),
kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya
dipergunakan utnuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan kegiatan usaha hilir, yang diatur dalam pasal 1 angka 10,
pasal 5, pasal 23 – 25 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
adalah kegiatan yang bertumpukan pada kegiatan usaha :
1. Pengolahan;
2. Pengangkutan;
3. Penyimpanan;
4. Niaga.

13
Agar peranan minyak dan gas bumi terlaksana dengan baik, dalam UU
No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka diatur mengenai
tugas dan wewenang kelembagaan dalam bidang Minyak dan Gas Bumi :
1. Pemerintah (Departemen ESDM, direktorat jendral minyak dan gas
bumi), melaksanakan tugas-tugas kebijakan, pengaturan, pembinaan
dan pengawasan dalam penyelenggaraan penguasaan minyak dan
gas bumi.
2. Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), melaksanakan
tugas pengendalian ketentuan dalam kontrak kerja sama pada
kegiatan usaha hulu migas.
3. Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengalokasikan
persediaan dan pendistribusian BBM serta menetapkan tariff
pengangkutan gas bumi melalui pipa.
Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengendalian kegiatan
usaha hulu adalah badan pelaksana, sedangkan dalam usaha hilir adalah
badan pengatur. Mengenai badan pelaksana diatur dalam pasal 1 angka 23,
pasal 44 – 45 uu No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Kedudukan badan pelaksana merupakan badan hukum milik negara.
Fungsi dari badan pelaksana adalah melakukan pengawasan terhadap
kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas
bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang
maksimal bagi negara dan rakyat.
Pengaturan mengenai badan pelaksana adalah PP No 42 tahun 2002
tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP
Migas), yaitu pada pasal 11 mengenai tugas dari BP Migas :
1. Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya
dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja
sama;
2. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama;
3. Mengkaji dan menyempaikan rencana pengembangan lapangan yang
pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja kepada
menteri untuk emndapatkan persetujuan;
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan;
5. MEmberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
6. Melaksanakan pengawasan dan melaporkan kepada menteri
mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama;
7. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang
dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada negara.

14
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP
Migas) dalam melakukan kegiata hulunya, tentunya membutuhkan sarana
pengangkutan yang memadai agar hasil dari pertambangan Minyak dan Gas
Bumi dapat memberikan manfaat dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi
rakyat banyak.
Industri hulu migas, setiap tahun mengoperasikan lebih dari 600 buah
kapal, 90% dari kapal-kapal tersebut adalah berbendera Indonesia, sisanya
adalah berbendera asing, sekitar 60 kapal. Dilihat dari jenis kapalnya yang
masih berbedera asing adalah, kapal jenis Jack Up Rig dan 3D Seismic
Vessel, yang keduanya adalah kapal besar penunjang kegiatan eksploitasi
minyak dan gas.
Kapal 3D Seismic Vessel adalah kapal survey untuk menunjang
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di laut.
Jack Up Rig adalah salah satu jenis Rig. Rig adalah serangkaian
peralatan khusus yang digunakan untuk membor sumur atau mengakses
sumur. Ciri utama rig adalah adanya menara yang terbuat dari baja yang
digunakan untuk menaik-turunkan pipa-pipa tubular sumur.
Rig pengeboran adalah suatu bangunan dengan peralatan untuk
melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh
air, minyak, atau gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah. Rig
pengeboran bisa berada di atas tanah (on shore) atau di atas laut/lepas
pantai (off shore) tergantung kebutuhan pemakaianya. Walaupun rig lepas
pantai dapat melakukan pengeboran hingga ke dasar laut untuk mencari
mineral-mineral, teknologi dan keekonomian tambang bawah laut belum
dapat dilakukan secara komersial. Oleh karena itu, istilah "rig" mengacu pada
kumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran pada
permukaan kerak Bumi untuk mengambil contoh minyak, air, atau mineral.
Rig pengeboran minyak dan gas bumi dapat digunakan tidak hanya
untuk mengidentifikasi sifat geologis dari reservoir tetapi juga untuk membuat
lubang yang memungkinkan pengambilan kandungan minyak atau gas bumi
dari reservoir tersebut.
Umumnya, rig dikategorikan menjadi dua macam menurut tempat
beroperasinya:
1. Rig darat (land-rig): beroperasi di darat.
2. Rig laut (offshore-rig): beroperasi di atas permukaan air (laut, sungai,
rawa-rawa, danau atau delta sungai).
Ada bermacam-macam offshore-rig yang digolongkan berdasarkan
kedalaman air:

15
1. Swamp barge: kedalaman air maksimal 7m saja. Sangat umum dipakai
di daerah rawa-rawa atau delta sungai.
2. Tender barge: mirip swamp barge tetapi di pakai di perairan yang lebih
dalam.
3. Jackup rig: platform yang dapat mengapung dan mempunyai tiga atau
empat “kaki” yang dapat dinaik-turunkan. Untuk dapat dioperasikan,
semua kakinya harus diturunkan sampai menginjak dasar laut. Terus
badan rig akan diangkat sampai di atas permukaan air sehingga
bentuknya menjadi semacam platform tetap. Untuk berpindah dari satu
tempat ke tempat lain, semua kakinya haruslah dinaikan terlebih
dahulu sehingga badan rig mengapung di atas permukaan air. Lalu rig
ini ditarik menggunakan beberapa kapal tarik ke lokasi yang dituju.
Kedalaman operasi rig jackup adalah dari 5m sampai 200m.
4. Drilling jacket: platform struktur baja, umumnya berukuran kecil dan
cocok dipakai di laut tenang dan dangkal. Sering dikombinasikan
dengan rig jackup atau tender barge.
5. Semi-submersible rig: sering hanya disebut “semis” merupakan rig
jenis mengapung. Rig ini “diikat” ke dasar laut menggunakan tali
mooring dan jangkar agar posisinya tetap di permukaan. Dengan
menggunakan thruster, yaitu semacam baling-baling di sekelilingnya,
rig semis mampu mengatur posisinya secara dinamis. Rig semis sering
digunakan jika lautnya terlalu dalam untuk rig jackup. Karena
karakternya yang sangat stabil, rig ini juga popular dipakai di daerah
laut berombak besar dan bercuaca buruk.
6. Drill ship: prinsipnya menaruh rig di atas sebuah kapal laut. Sangat
cocok dipakai di daerah laut dalam. Posisi kapal dikontrol oleh sistem
thrusterberpengendali komputer. Dapat bergerak sendiri dan daya
muatnya yang paling banyak membuatnya sering dipakai di daerah
terpencil atau jauh dari darat.
Dari fungsinya, rig dapat digolongkan menjadi dua macam:
1. Drilling rig: rig yang dipakai untuk membor sumur, baik sumur baru,
cabang sumur baru maupun memperdalam sumur lama.
2. Workover rig: fungsinya untuk melakukan sesuatu terhadap sumur
yang telah ada, misalnya untuk perawatan, perbaikan, penutupan, dsb.

16
2.4 Penerapan asas cabotage bagi Indutri Migas. 2.4.1 Kasus Posisi
Pada tahun 2005 lalu, presiden mengeluarkan sebuah Inpres yaitu,
Inpres No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional,
dalam Inpres tersebut ditekankan mengenai penerapan asas cabotage,
bahwa setiap kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia, yang
digunakan untuk kegiatan pengangkutan adalah harus berbendera Indonesia.
Implikasi dari diterapkannya hal ini, tidak hanya persoalan mengenai
penggantian bendera tetapi juga menyangkut kepemilikan saham, bahwa
perusahaan kapal tersebut haru dimiliki sahamnya oleh orang Indonesia,
sebanyak 51% saham.
Industri hulu Migas, menyangkut BP Migas sebagai badan pelaksana
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, melaksanakan tugas
pengendalian ketentuan dalam kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu
migas, ikut merasakan penerapan asas cabotage ini.
Sebenarnya, BP Migas tidak begitu memikirkannya, karena sebanyak
90% dari kapal yang dipergunakan oleh BP Migas untuk kegiatan usaha hulu
adalah telah berbendera Indonesia, dan hanya sekitar 10% saja yang
berbendera asing.
Masalah timbul karena 10% dari kapal tersebut yang berbendera
asing, adalah termasuk jenis kapal Jack Up Rig dan 3D seismic vessel, kapal
besar yang sangat menunjang kegiatan hulu pertambangan minyak dan gas
bumi.
Jack Up Rig dan 3D Seismic Vessel masuk ke dalam katagori kapal
menurut UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, karena termasuk dalam
pengertian kapal pada pasal 1 angka 36, Kapal adalah kendaraan air dengan
bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat
apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Jack Up rig dan 3D Seismic Vessel adalah alat apung atau bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah, maka dari itu masuk dalam katagori
kapal menurut UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Masalah ini menjadi serius karena dengan berhentinya operasi drilling
rig, maka produksi minyak pun terhenti. Ini berdampak pada berkurangnya
produksi minyak mentah siap jual atau lifting pada tahun 2011. Pada APBN
2011, pemerintah mengasums ikan lifting pada tahun 2011 akan ada di posisi

17
970.000 barrel per hari. Namun, akibat akumulasi masalah, antara lain
masalah drilling rig, maka target lifting diperkirakan akan berkurang menjadi
940.000 barrel per hari.
Sebelumnya, untuk mencegah penghentian operasi pengeboran
minyak lepas pantai akibat masalah azas cabotage, pemerintah akan
membuat sebuah aturan yang berfungsi sebagai penjembatan antara undang-
undang pelayaran dengan kebutuhan pelaku usaha di bidang pengeboran
minyak. Aturan ini akan ditetapkan dalam sebuah peraturan pemerintah yang
memberikan pengecualian pada drilling rig atau fasilitas eksploitasi minyak
lepas pantai sebagai alat yang tidak terkena azas cabotage .
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)
mewujudkan semangat Nasionalisme melalui penandatanganan perjanjian
komitmen penggunaan armada kapal berbendera Indonesia untuk operasi
hulu minyak dan gas bumi dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKS) yang beroperasi di Indonesia.
Kontraktor KKS yang menandatangani komitmen penggunaan kapal
Nasional untuk operasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia adalah
Santos, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, JOB Pertamina –
Petrochina East Java, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java,
CNOOC SES Ltd, Star Energy, Sele Raya dan Kangean Energi Indonesia.
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(BPMIGAS) memperkirakan hingga tahun 2015, industri hulu minyak dan gas
bumi membutuhkan tambahan armada baru sebanyak 235 kapal berbendera
Indonesia dari berbagai jenis, kapasitas dan ukuran untuk memenuhi azas
cabotage yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan No 48 tahun 2011 yang
menetapkan batas waktu untuk pemenuhan kapal-kapal tersebut adalah
tahun 2015.
2.4.2 Penerapan asas cabbotage terhadap kapal-kapal dalam industri migas di Indonesia Cabotage berarti prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara
komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari
negara itu sendiri secara eksklusif. Asas cabotage adalah kegiatan angkutan
laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

18
Pasal 8 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kemudian Inpres No
5 Tahun 2005, lalu PP No 22 Tahun 2011, telah memberikan kejelasan
bahwa asas cabotage harus diterapkan dalam sistem pengangkutan laut di
Indonesia.
Dikarenakan Jack Up Rig dan 3D Seismic Vessel adalah termasuk
dalam katagori kapal menurut UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka
kedua jenis kapal tersebut masuk ke dalam penerapan asas cabotage.
Bahwa mereka haruslah berbendera Indonesia dalam melaksanakan
kegiatannya di wilayah perairan Indonesia.
Masalah timbul dalam penerapan asas cabotage ini, karena kedua
jenis kapal tersebut tidak dimiliki oleh banyak perusahaan Indonesia, karena
jangka waktunya yang relatif sebentar, tidak ada pengusaha Indonesia yang
berminat untuk melakukan investasi dalam hal Jack Up Rig dan 3D Seismic
Vessel. Jack Up rig akan selesai digunakan ketika pengeboran selesai,
kemudian 3D seismic vessel hanya digunakan untuk survey pada lokasi
tertentu saja, selama 20 hari – 3bulan, jadi kontraknya tidak bisa dibuat
tahunan. Di Indonesia tidak terdapat galangan kapal yang mampu membuat
kapal jenis tersebut, akrena itu termasuk kapal mahal dan butuh biaya besar
untuk membuatnya.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, agar industri Migas masih
dapat tetap berjalan, maka pemerintah mengeluarkan PP No 22 Tahun 2011
tentang Perubahan terhadap PP No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan Laut. Dalam PP tersebut, ada pengecualian terhadap penerapan
asas cabotage.
Pengecualian tersebut adalah bahwa kapal asing dapat melakukan
kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengengkut penumpang dan/atau
barang dalam negeri di wilayah perairan di Indonesia sepanjang kapal
berbedera Indonesia belum tersedia atau cukup tersedia. Kapal asing
tersebut wajib memiliki izin dari mentri Perhubungan. Kegiatan lain tersebut
adalah meliputi kegiatan:
1. Survey Minyak dan Gas Bumi;
2. Pengeboran;
3. Kontruski lepas pantai;
4. Penunjang operas lepas pantai;
5. Pengerukan;
6. Salvage dan pekerjaan bawah air.
Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 206a PP No 22 tahun 2011.

19
Ketentuan tersebut dibuat dengan maksud untuk menjaga
kelangsungan industri Migas di Indonesia. Karena dengan pemberlakuan asa
cabotage produksi minyak pun terhenti. Berdampak pada berkurangnya
produksi minyak mentah siap jual atau lifting pada tahun 2011. Pada APBN
2011, pemerintah mengasumsikan lifting pada tahun 2011 akan ada di posisi
970.000 barrel per hari. Namun, akibat akumulasi masalah, antara lain
masalah drilling rig, maka target lifting diperkirakan akan berkurang menjadi
940.000 barrel per hari.
Untuk membantu agar perhatian industri galangan kapal nasional
terpusat pada peningkatan standar, BP MIGAS telah menetapkan ada tiga
prinsip dalam pengadaan kapal, yakni kualitas mutakhir, harga yang cukup
kompetitif, dan ketepatan waktu pengiriman. Syarat ini juga diberlakukan
pada barang-barang penunjang operasi lainnya yang dikerjakan di Indonesia.
Pengusaha dan galangan kapal harus dipaksa memenuhinya, jika pengguna
tidak memacu perkembangan industri dalam negeri, niscaya kemandirian
hanya angan-angan.
Jadi pada dasarnya penerapan asas cabotage ini adalah suatu pijakan
awal aga Indonesia menjadi negara yang lebih maju, agar Indonesia dapat
membuat sendiri kapal-kapal yang akan digunakan untuk melakukan
pengangkutan di Indonesia, termasuk kapal-kapal kelas berat sekelas jack up
Rig dan 3D seismic vessel.
Tetapi terdapat pro dan kontra terhadap ketentuan pasal 206a PP No
22 tahun 2011, karena pemerintah dianggap tidak konsekuen dengan apa
yang telah ditentukan di awal. Pemerintah tidak berusaha dengan sungguh-
sungguh dalam melakukan asas cabotage.
Dengan diberlakukannya PP tersebut, memang Industri migas di
Indonesia akan kembali bergerak, tetapi indsutri perkapalan dan
pengangkutan di Indonesia akan sulit berkembang, pengusaha galangan
kappa yang tadinya dituntut untuk membuat kapal-kapal kelas berat seperti
Rig dan 3D Seismic Vessel menjadi tidak bersemangat kembali karena
dikeluarkannya peraturan ini, mereka harus bersaing dengan para kapal asing
yang memproduksi kapal-kapal tersebut.
Walaupun begitu, Mentri perhubungan melalui Peraturan Menteri
Perhubungan No 48 tahun 2011 menetapkan jangka waktu agar industri
migas cepat melakukan pemenuhan atas kapal-kapalnya, sehingga harus
berbendera Indonesia, yaitu hingga tahun 2015. Padahal industri perkapalan dalam bidang Minyak dan Gas adalah
sangat besar dan dapat dibilang dapat menghasilkan untung yang tidak

20
sedikit, juga dapat memajukan teknologi perkapalan Indonesia, serta
memajukan sistem pengangkutan di Indonesia. Walaupun pada awalnya
dibutuhkan biaya yang tidak sedikit bahkan relatif besar untuk membuat
kapal-kapal tersebut, tetapi jika asas cabotage dapat benar-benar diterapkan
maka mau tidak mau para pengusaha galangan kapal akan membuatnya dan
mau tidak mau indutri migas akan menyewa atau membeli kapal-kapal kelas
berat tersebut untuk keperluan survey atau pengeboran atau hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan hulu dalam minyak dan gas bumi.
BP Migas berkeinginan untuk menjunjung tinggi nasionalisme dan
mendukung penerapan asas cabotage, sehingga Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) mewujudkan semangat
Nasionalisme melalui penandatanganan perjanjian komitmen penggunaan
armada kapal berbendera Indonesia untuk operasi hulu minyak dan gas bumi
dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang beroperasi di
Indonesia. Kontraktor KKS yang menandatangani komitmen penggunaan
kapal Nasional untuk operasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia adalah
Santos, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, JOB Pertamina –
Petrochina East Java, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java,
CNOOC SES Ltd, Star Energy, Sele Raya dan Kangean Energi Indonesia.

21
BAB III KESIMPULAN
1. Pengaturan mengenai Hukum Pengangkutan di Indonesia adalah : o Kitab undang-undang Hukum Perdata, buku III tentang perikatan
o Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Buku V tentang pengangkutan
o UU No 21 tahun 1992 yang kemudian diganti dengan UU No 17 tahun
2008 tentang Pelayaran
o PP No 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
o PP No 20 Tahun 2010 yang diubah dengan PP No 22 tahun 2011
tentang Angkutan Perairan Laut
o Inpres No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran
Nasional
o Peraturan Menteri Perhubungan No 48 tahun 2011
2. Asas Cabotage dalam Hukum Pengangkutan di Indonesia.
o Asas Cabotage berarti prinsip yang memberi hak untuk beroperasi
secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan
angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif. Asas cabotage adalah
kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan
laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta
diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
o Pengaturan mengenai penerapan asas cabotage terdapat dalam UU No
17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kemudian PP No 20 tahun 2010 yang
diubah dengan PP No 22 tahun 2011 tentang Angkitan perairan laut.
Serta Inpres No 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Indsutri Pelayaran
Nasional.
3. Peran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. o Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), melaksanakan
tugas pengendalian ketentuan dalam kontrak kerja sama pada kegiatan
usaha hulu migas. Kedudukan badan pelaksana merupakan badan
hukum milik negara. Fungsi dari badan pelaksana adalah melakukan
pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber
daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan
manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara dan rakyat.
o Pengaturan mengenai BP Migas terdapat dalam UU No 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, serta PP No 42 tahun 2002 tentang

22
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP
Migas)
o Industri hulu migas, setiap tahun mengoperasikan lebih dari 600 buah
kapal, 90% dari kapal-kapal tersebut adalah berbendera Indonesia,
sisanya adalah berbendera asing, sekitar 60 kapal. Dilihat dari jenis
kapalnya yang masih berbedera asing adalah, kapal jenis Jack Up Rig
dan 3D Seismic Vessel, yang keduanya adalah kapal besar penunjang
kegiatan eksploitasi minyak dan gas.
4. Keuntungan penerapan asas cabotage dalam industri migas dan pengangkutan di Indonesia.
o Ketentuan mengenai pengecualian penerapan asas cabotage dalam
sistem pengankutan laut di Indonesia pada bidang industri Migas dibuat
dengan maksud untuk menjaga kelangsungan industri Migas di
Indonesia. Karena dengan pemberlakuan asa cabotage produksi minyak
pun terhenti. Berdampak pada berkurangnya produksi minyak mentah
siap jual atau lifting pada tahun 2011.
o Untuk membantu agar perhatian industri galangan kapal nasional
terpusat pada peningkatan standar, BP MIGAS telah menetapkan ada
tiga prinsip dalam pengadaan kapal, yakni kualitas mutakhir, harga yang
cukup kompetitif, dan ketepatan waktu pengiriman. Syarat ini juga
diberlakukan pada barang-barang penunjang operasi lainnya yang
dikerjakan di Indonesia.
o Pengusaha dan galangan kapal harus dipaksa memenuhinya, jika
pengguna tidak memacu perkembangan industri dalam negeri, niscaya
kemandirian hanya angan-angan.
o Jadi pada dasarnya penerapan asas cabotage ini adalah suatu pijakan
awal agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju, agar Indonesia
dapat membuat sendiri kapal-kapal yang akan digunakan untuk
melakukan pengangkutan di Indonesia, termasuk kapal-kapal kelas
berat sekelas jack up Rig dan 3D seismic vessel.
o Pada dasarnya penerapan asas cabotage dalam indutri migas di
Indonesia tidak akan memberikan kerugian pada pemasukan negara
melalui migas, jika diterapkan dengan benar. Jutru akan lebih
menghemat pengeluaran karena memakai kapal buatan dalam negeri,
serta memberikan keuntungan juga bagi industri perkapalan dan
pengangkutan Indonesia.

23
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan
The Hague Rules, 1924
The Hamburg Rules, 1978
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan
oleh Subekti. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2009
Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan UU Kepailitan (Wetboek van
Koophandel en Faillissements-verordening). Diterjemahkan oleh
Subekti. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2006.
Indonesia. Undang-undang Pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008. TLN. No.
4849
Indonesia. Peraturan Pemerintah Perkapalan. PP No. 51 tahun 2002. TLN.
No. 4227
Indonesia. Peraturan Pemerintah Angkutan Peraturan Laut. PP No. 20 Tahun
2010. TLN. No. 5108
Indonesia. Peraturan Pemerintah mengubah PP No 20 tahun 2010 Angkutan
Perairan Laut. PP No. 22 Tahun 2011. TLN. No. 5268 Indonesia. Instruksi Presiden Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.
Inpres No. 5 tahun 2005.
Indonesia. Peraturan menteri Perhubungan Tata Cara Pemberian Izin
Penggunaan Kapal Asing untuk kegiatan Lain yang tida Termasuk
kegiatan mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan
Angkutan Laut dalam Negeri. Peraturan Menteri Perhubungan No 48
tahun 2011.
Indonesia. Undang-undang Minyak dan Gas Bumi. UU No 22 Tahun 2011.
TLN. No. 4152
Indonesia. Peraturan pemerintah BP Migas. PP No 42 Tahun 2002. TLN. No.
4216
Buku
Adji, Sution Usman, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono. Hukum
Pengangkutan di Indonesia. Cet. 2. Jakarta: PT Rinka Cipta, 1991.
Motik, Chandra. Serba Serbi Konsultasi Hukum Maritim. Cet. 1. Jakarta:Ind-
Hill-Co, 2003.
Salim, H. Hukum Pertambangan di Indonesia. Cet. 5. Jakarta: PT
RajaFrafindo Persada, 2010.

24
Soedjono, Wiwoho. Seri Hukum Dagang : Hukum Pengangkutan Laut di
Indonesia dan perkembangannya. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1987.
Soempena, S. Buku Tentang Hukum Laut. Jakarta, 1997
Sutedi, Adrian. Hukum Pertambangan. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Tjakranegara, Soegijatna. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang.
Cet. 1. Jakarta: PT Rinka Cipta, 1995.
Artikel Buletin. BP Migas. “Asas Cabotage, Musibah atau Anugerah?.” Buletin BP Migas.
(September 2009). Hlm. 2
BP Migas. “Mendorong Penerapan Asas Cabotage yang Komprehensif.”
Buletin BP Migas. (September 2009). Hlm. 3 – 5
BP Migas. “Dukung Asas Cabotage: BP Migas Haruskah KKKS Gunakan
Kapal Berbendera Indonesia?.” Buletin BP Migas. (September 2009).
Hlm. 6-7
BP Migas. “Wawancara dengan Budi Indianto, Deputi Pengendalian Operasi
BP Migas, Saya yakin Asas Cabotage Teralisasi.” Buletin BP Migas.
(September 2009). Hlm. 9 – 11.
Artikel Internet
Akbar, Raden Jihad. “Efisienkah Azas Cabotage Bagi Sektor Migas?.”
http://today.co.id/read/2011/02/26/13116/efisienkah_azas_cabotage_b
agi_sektor_migas. Diunduh pada 28 Mei 2012.
Basuki, Orin. “Drilling Rig Bisa Beroperasi Lagi”.
http://tekno.kompas.com/read/2011/04/12/11342885/.Drilling.Rig.Bisa.
Beroperasi.Lagi. Dinduh pada 28 Mei 2012.
Dabu. “PENGATURAN CABOTAGE : PP pengaturan cabotage terbit, kapal
asing dimungkinkan beroperasi di Indonesia”
http://nasional.kontan.co.id/news/pp-pengaturan-cabotage-terbit-kapal-
asing-dimungkinkan-beroperasi-di-indonesia-1. Diunduh pada 28 Mei
2012
Media Indonesia. “Inkonsistensi tunda Cabotage”.
http://www.migas.esdm.go.id/tracking/beritakemigasan/detil/253776/Ink
onsistensi-Tunda-Cabotage. Diunduh pada 28 mei 2012.

25
Migasnet08_fajar. “Rig dan Jenisnya”.
http://migasnet08fajarramadhan8071.blogspot.com/2010/01/pengertian
-rig-dan-jenisnya.html. Diunduh pada 28 Mei 2012.
Sikumbang, Idris Hadi. “Incafo Overview”. http://www.iluni.org/ikhtisar-incafo.
Diunduh pada 28 Mei 2012.
Redaksi. “ASAS CAbotage : Pelayaran Nasional Tersenyum.”
http://indomaritimeinstitute.org/?p=1525. Diunduh pada 28 Mei 2012.

26
HUKUM MARITIM
BP MIGAS DAN PERMASALAHANNYA
PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM INDUSTRI MIGAS DI INDONESIA
DISUSUN OLEH :
KARTIKA MAHARDHIKA PUTRI
0906558243
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK, 29 MEI 2012