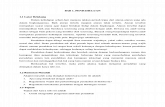makalah isbd
-
Upload
krishna-sahputra -
Category
Documents
-
view
68 -
download
4
description
Transcript of makalah isbd

BAB 1
Latar Belakang
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya
masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk
minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka
tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan
lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara
yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika
Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era
kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris
berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan
upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di
permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi,
kriminalitas, pengangguran.
Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada
masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat
tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup
dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-
negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam
dari jumlah penduduknya tergolong miskin.
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa
penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah
penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di
perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996
(sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta
jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin
diperkirakan makin bertambah.

Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan pengangguran?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia ?
3. Apa saja dampak-dampak dari kemiskinan ?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di NKRI ?
5. Bagaimana cara meminimalisir kemiskinan di Indonesia?
Tujuan
1. Mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi
masalah kemiskinan di Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menganalisa sebab dan akibat dari kemiskinan yang menjadi
problema masyarakat Indonesia saat kini.
3. Mahasiswa mampu untuk ikut berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang
ada seminimal mungkin ikut membantu dalam mencari solusi kemiskinan di daerah
mereka sendiri.

BAB 2
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinian dan Pengangguran
Kemiskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,pendidikan dan kesehatan.
Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang
tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian
mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat
pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan
tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah
pokok makro ekonomi yang paling utama.
Kemiskinan saat ini menjadi permasalahan yang serius khususnya di Indonesia,
ketimpangan ekonomi, lapangan kerja yang tidak mencukupi, tingkat pendidikan
yang rendah, penguasaan aset ekonomi seperti sumber daya alam yang dikuasai
oleh individu tertentu menjadi beberapa faktor yang mengakibatkan membesarnya
masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.
Ini semua menjadi tanggung jawab bukan hanya dari pemerintah saja tetapi juga
setiap makhluk pemangku kepentingan sosial yang ada dengan melakukan
koordinasi yang baik dari setiap elemen yang ada untuk memberantas kemiskinan.
B. Faktor-faktor Penyebabnya Kemiskinan
Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalahsebagai berikut:
Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkatdi setiap 10 tahun menurut hasil sensus
penduduk. Menurut data Badan PusatStatistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih
penduduk.Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27
juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia
persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170

ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang
permenit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawaIndonesia menjadi negara ke-4 terbanyak
penduduknya setelah China, India dan Amerika.Meningkatnya jumlah penduduk membuat
Indonesia semakin terpuruk dengankeadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang
bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah
dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di
bawah garis kemiskinan.
Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagianhasil
pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteriaketidakmerataan versi Bank Dunia
didasarkan atas porsi pendapatan nasional yangdinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40%
penduduk berpendapatan rendah(penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah
serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan
ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan
rendahmenikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggapsedang
atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12hingga 17 persen
pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskinmenikmati lebih dari 17 persen
pendapatan nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan
nasional dikatakan cukupmerata. Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang
mereka lakukanrelatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada
sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut jugasebagai
ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkaninefisiensi ekonomi.
Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata - rata bearapa pun, ketimpangan yang
semakin tinggi akan menyebabkan semakinkecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk
mendapatkan pinjaman atausumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset
yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi
pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dankemudian
menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. Ketimpangan pembangunan di
Indonesia selama ini berlangsung dan berwujuddalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi.
Bukan saja berupa ketimpanganhasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga
ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata
berupaketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan
regional. Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain dengan
menelaah perbedaan mencolok dalam aspek -aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana

perbankan, investasi dan pertumbuhan.Sepanjang era PJP I (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian
rata - rata hanyatumbuh 3, 54 persen per tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan
tumbuhdengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat ituditargetkan
tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-ratatahunan sektor industri
pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak sepertimasa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita
tertentu terdapat sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan
sektor industry pengolahaan,selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang
tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor industry pengolahan diharapka dapatmenjadi
pemimpin sepanjang sektor Repelita VI.Ketimpangan pertumbuhan antarsektor, khususnya antara
sektor pertanian dansektor industry pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan
pertumbuhansektoral ini bukanlah kecelakaan atau ekses pembangunan. Ketimpangan ini
lebihkepada suatu hal yang terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan menjadikan
Indonesia sebagai negara industry. Akan tetapi sampai sejauh manakahketimpangan ini apat
ditolerir? Pemerintah perlu memikirkan kembali perihalketepatan keputusan menggunakan
industrialisasi sebgai jalur pembangunan karenaakan sangat berdampak bagi pendapatan penduduk
dan selanjutnya kemiskinan.
Tingkat pendidikan yang rendah
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakansalah satu penyebab kemiskinan di suatu negara
Ini disebabkan karena rendahnyatingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk
adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibuthkan lebih banyak teanga kerja
yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.Menurut Schumaker
pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnyadibandingkan faktor-faktor produksi
lain.
Kurangnya perhatian dari pemerintah.
Pemerintah yang kurang peka terhadaplaju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah
satu faktor kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu
mengendalikan tingkatkemiskinan di negaranya.
C. Dampak-dampak dari Kemiskinan
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dankompleks. Pertama,
pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguranterbuka tahun 2007 saja sebanyak
12,7 juta orang. Jumlah yang cukup fantastis mengingat krisis multidimensional yang sedang
dihadapi bangsa saat ini.Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak
memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah
menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akanmemberikan dampak secara langsung
terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dantingkat pengeluaran rata-rata.Dalam konteks daya saing
secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan
kekuatan daya saing bangsa.Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan
suatu bangsadalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di
tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensimeningkatkan
angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itudidasarkan atas kontribusi pangan yang
cukup dominan terhadap penentuan gariskemiskinan yakni hampir tiga perempatnya (74,99
persen).Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnyatingkat pendidikan
seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yangterlalu memprioritaskan ekonomi
makro atau pertumbuhan ( growth).
Ketika terjadikrisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan
yangmelakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gajikaryawan
akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harusdirumahkan atau dengan
kata lain meraka terpaksa di-PHK (Putus Hubungan Kerja).Kedua, kekerasan. Sesungguhnya
kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang
tidak mampu lagi mencarinafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan
bagiseseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun
dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu (dengan caramengintimidasi
orang lain) di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit
dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga denganmudah ia mendapatkan uang dari
memalak.Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomenayang terjadi
dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskintidak dapat lagi menjangkau
dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapatmenjangkau dunia pendidikan yang sangat
mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin.Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah
kesulitan.Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam.Tingginya tingkat putus
sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikanseseorang. Dengan begitu akan mengurangi
kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan
bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut
keterampilan di segala bidang.Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang
sangatmahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif
atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan
miskin.Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat

ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut.Hal ini menjadi bukti lain dari
kemiskinan yang kita alami.semuanya ini adalahekspresi berontakan identitas diri setiap individu.
Terlebih lagi fenomena bencanaalam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung
terhadapmeningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang
daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di
perdesaan maupun perkotaan.
D. Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi
kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008
pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain
pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan
memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat
meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima
membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang
ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang
digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan
menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan
pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang
berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini
bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang
lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang
berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola
bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan
Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro

• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan
ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan
berusaha bagi masyarakat miskin.
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi
pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat
penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.
Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan
perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program
ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan
pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan
dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah
Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III
rumah sakit;
e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan
ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang

di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak
(PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban
bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang
memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan
rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan
penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga
miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi
persyaratan).
E. Upaya Meminimalisir Kemiskinan
Pada Hari Kemiskinan Internasional lalu berbagai pihak menyatakan perang
melawan kemiskinan.Ditargetkan pada tahun 2015 Indonesia bebas dari kemiskinan.
Ini tekad yang bagus.
Namun selain tekad, harus didukung dengan niat yang ikhlas, perencanaan,
pelaksanaan dan juga pengawasan yang baik. Tanpa itu semua hanya omong belaka.
Menghilangkan kemiskinan boleh dikata mimpi atau hanya janji surga. Tapi
mengurangi kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan. Ada beberapa program yang
perlu dilakukan agar kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi.
Pertama, meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa mungkin pendidikan harus
terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah yang rusak
menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan hanya fisik, bisa jadi
gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi.
Dulu pada tahun 1970-an, sekolah dasar dibagi dua. Ada sekolah pagi dan ada
sekolah siang sehingga 1 bangunan sekolah bisa dipakai untuk 2 sekolah dan
melayani murid dengan jumlah 2 kali lipat. Sebagai contoh di sekolah saya ada SDN
Bidaracina 01 Pagi (Sekarang berubah jadi Cipinang Cempedak 01 Pagi) dan SDN
Bidaracina 02 Petang. Sekolah pagi mulai dari jam 7.00 hingga 12.00 sedang yang

siang dari jam 12:30 hingga 17:30. Satu bangunan sekolah bisa menampung total
960 murid!
Ini tentu lebih efektif dan efisien. Biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung
sekolah bisa dihemat hingga separuhnya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa hal
itu bisa mengurangi jumlah pelajaran karena jam belajar berkurang. Padahal tidak.
Sebaliknya jam pelajaran di sekolah terlalu lama justru membuat siswa jenuh dan
tidak mandiri karena dicekoki oleh gurunya. Guru bisa memberi mereka PR atau
tugas yang dikerjakan baik sendiri, bersama orang tua, atau teman-teman mereka.
Ini melatih kemandirian serta kerjasama antara anak dengan orang tua dan juga
dengan teman mereka.
Selain itu biaya untuk beli buku cukup tinggi, yaitu per semester atau caturwulan
bisa mencapai Rp 200 ribu lebih. Setahun paling tidak Rp 400 ribu hanya untuk beli
buku. Jika punya 3 anak, berarti harus mengeluarkan uang Rp 1,2 juta per tahun.
Hanya untuk uang buku orang tua harus mengeluarkan 130% lebih dari Upah
Minimum Regional (UMR) para buruh yang hanya sekitar 900 ribuan.
Untuk mengurangi beban orang tua dalam hal uang buku, pemerintah bisa
menyediakan Perpustakaan Sekolah. Dulu perpustakaan sekolah meminjamkan
buku-buku Pedoman (waktu itu terbitan Balai Pustaka) kepada seluruh siswa secara
gratis. Untuk soal bisa didikte atau ditulis di papan tulis.
Ini beda dengan sekarang di mana buku harus ditulis dengan pulpen sehingga begitu
selesai dipakai harus dibuang. Tak bisa diturunkan ke adik-adiknya.
Saat ini biaya SPP sekolah gratis hanya mencakup SD dan SMP (Meski sebetulnya
tetap bayar yang lain dengan istilah Ekskul atau Les) sedang untuk Perguruan Tinggi
Negeri biayanya justru jauh lebih tinggi dari Universitas Swasta yang memang
bertujuan komersial. Untuk masuk UI misalnya orang tahun 2005 saja harus bayar
uang masuk antara Rp 25 hingga 75 juta. Padahal tahun 1998 orang cukup bayar
sekitar Rp 300 ribu sehingga orang miskin dulu tidak takut untuk menyekolahkan
anaknya di PTN seperti UI, IPB, UGM, ITS, dan sebagainya. Meski ada surat edaran
Rektor bahwa orang tua tidak perlu takut akan bayaran karena bisa minta
keringanan, namun teori beda dengan praktek.
Boleh dikata orang-orang miskin saat ini mimpi untuk bisa masuk ke PTN. Jika pun
ada paling cuma segelintir saja yang mau bersusah payah mengurus surat
keterangan tidak mampu dan merendahkan diri mereka di depan birokrat kampus
sebagai Keluarga Miskin (Gakin) untuk minta keringanan biaya.

Tanpa pendidikan, sulit bagi rakyat Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan
menjadi bangsa yang maju.
Kedua, pembagian tanah/lahan pertanian untuk petani. Paling tidak separuh rakyat
(sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih hidup di bidang pertanian. Menurut
Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar.
Bahkan ada yang tidak punya tanah dan sekedar jadi buruh tani. Kadang terjadi
tawuran antar desa hingga jatuh korban jiwa hanya karena memperebutkan lahan
beberapa hektar!
Artinya jika 1 hektar bisa menghasilkan 6 ton gabah dan panen 2 kali dalam setahun
serta harga gabah hanya Rp 2.000/kg, pendapatan kotor petani hanya Rp 9,6 juta
per tahun atau Rp 800 ribu/bulan. Jika dikurangi dengan biaya benih, pestisida, dan
pupuk dengan asumsi 50% dari pendapatan mereka, maka penghasilan petani hanya
Rp 400 ribu/bulan saja.
Pada saat yang sama 69,4 juta hektar tanah dikuasai oleh 652 pengusaha. Ini
menunjukkan belum adanya keadilan di bidang pertanahan. Dulu pada zaman Orba
(Orde Baru) ada proyek Transmigrasi di mana para petani mendapat tanah 1-2
hektar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Transportasi, rumah, dan
biaya hidup selama setahun ditanggung oleh pemerintah.
Program itu sebenarnya cukup baik untuk diteruskan mengingat saat ini Indonesia
kekurangan pangan seperti beras, kedelai, daging sapi, dsb sehingga harus impor
puluhan trilyun rupiah setiap tahunnya.
Jika petani dapat tanah 2 hektar, maka penghasilan mereka meningkat jadi Rp 48
juta per tahun atau bersih bisa Rp 2 juta/bulan per keluarga.
Memang biaya transmigrasi cukup besar. Untuk kebutuhan hidup selama setahun,
rumah, lahan, dan transportasi paling tidak perlu Rp 40 juta per keluarga. Dengan
anggaran Rp 10 trilyun per tahun ada 250.000 keluarga yang dapat diberangkatkan
per tahunnya.
Seandainya tiap keluarga mendapat 2 hektar dan tiap hektar menghasilkan 12 ton
beras per tahun, maka akan ada tambahan produksi sebesar 6 juta ton per tahun. Ini
sudah cukup untuk menutupi kekurangan beras di dalam negeri.
Saat ini dari 2 juta ton kebutuhan kedelai di Indonesia (sebagian untuk tahu dan
tempe), 60% diimpor dari luar negeri. Karena harga kedelai luar negeri naik dari Rp
3.500/kg menjadi Rp 7.500/kg, para pembuat tahu dan tempe banyak yang bangkrut
dan karyawannya banyak yang menganggur.

Jika program transmigrasi dilakukan tiap tahun dan produk yang ditanam adalah
produk di mana kita harus impor seperti kedelai, niscaya kekurangan kedelai bisa
diatasi dan Indonesia tidak tergantung dari impor kedelai yang nilainya lebih dari Rp
8 trilyun per tahunnya. Ini akan menghemat devisa.
Ketiga, tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha besar.
Para petani/pekebun kecil sulit untuk mengekspor produk mereka. Sebaliknya para
pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk mereka (para pengusaha bisa
menekan/melobi pemerintah) sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau
harus membayar tinggi sama dengan harga Internasional. Ini sudah terbukti dengan
melonjaknya harga minyak kelapa hingga 2 kali lipat lebih dalam jangka waktu
kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga Internasional. Pemerintah tidak bisa
berbuat apa-apa.
Jika produk utama seperti beras, kedelai, terigu dikuasai oleh pengusaha, rakyat
akan menderita akibat permainan harga.
Selain itu dengan dikuasainya industri pertanian oleh pengusaha besar, para petani
yang merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia akan semakin tersingkir dan
termiskinkan.
Keempat, lakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu dikaji apakah pertanian kita
efisien atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan berbahaya bagi kesehatan,
pertimbangkan predator alami seperti burung hantu untuk memakan tikus, dsb.
Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan berbahaya, coba pupuk organik seperti
pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya pestisida dan pupuk, para petani akan
semakin terbantu karena ongkos tani semakin rendah.
Jika membajak sawah bisa dilakukan dengan sapi/kerbau, kenapa harus memakai
traktor? Dengan sapi/kerbau para petani bisa menternaknya sehingga jadi banyak
untuk kemudian dijual. Daging dan susunya juga bisa dimakan. Sementara traktor
bisa rusak dan butuh bensin/solar yang selain mahal juga mencemari lingkungan.
Kelima, data produk-produk yang masih kita impor. Kemudian teliti produk mana
yang bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga kita tidak tergantung dengan
impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai contoh jika mobil bisa kita
produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat devisa dan membuka lapangan
kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor terjual di Indonesia dengan nilai
lebih dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN
yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk membuat/mendukung BUMN yang menciptakan

kendaraan nasional, maka akan terbuka lapangan kerja dan penghematan devisa
milyaran dollar setiap tahunnya.
Keenam, stop eksploitasi/pengurasan kekayaan alam oleh perusahaan asing. Kelola
sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh asing dengan alasan kita tidak
mampu dan sedang transfer teknologi. Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini
ketika minyak hampir habis kita masih ”transfer teknologi”.
Padahal 95% pekerja dan insinyur di perusahaan-perusahaan asing adalah orang
Indonesia. Expat paling hanya untuk level managerial. Bahkan perusahaan migas
Qatar pun di Kompas sering pasang lowongan untuk merekrut ahli migas kita.Saat ini
1.500 ahli perminyakan Indonesia bekerja di Timur Tengah seperti Arab Saudi,
Kuwait, dan Qatar. Bahkan ada Doktor Perminyakan yang bekerja di negara Eropa
seperti Noewegia.
Sekilas kita untung dengan pembagian 85% sedang kontraktor asing hanya 15%.
Padahal kontraktor asing tersebut memotong terlebih dulu pendapatan yang ada
dengan cost recovery yang besarnya mereka tentukan sendiri. Bahkan ongkos
bermain golf dan biaya rumah sakit di luar negeri ex-patriat dimasukkan ke dalam
cost recovery, begitu satu media memberitakan. Akibatnya di Natuna sebagai
contoh, Indonesia tidak dapat apa-apa. Kontraktor asing sendiri, seperti Exxon
sendiri mengantongi keuntungan hingga Rp 360 trilyun setiap tahun dari
pengelolaan minyak dan gas di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut PENA,
pada tahun 2008 saja sekitar Rp 2.000 trilyun/tahun dari hasil kekayaan alam
Indonesia justru masuk ke kantong asing. Padahal jitu bisa dipakai untuk melunasi
hutang luar negeri dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Bahkan untuk royalti emas dan perak di Papua, Freeport yang cuma “tukang
cangkul” dapat 99% sementara bangsa Indonesia sebagai pemilik emas cuma dibagi
1%! Bagaimana bisa kaya? Jadi kalau didapat emas dan perak sebesar Rp 100 trilyun,
Indonesia cuma dapat Rp 1 trilyun saja!
Banyak perusahaan asing beroperasi menguras kekayaan alam Indonesia. Tetangga
saya yang menambang emas bekerjasama dengan penduduk lokal dengan memakai
alat pahat dan martil saja bisa mendapat Rp 240 juta per bulan, bagaimana dengan
Freeport yang memakai banyak excavator dan truk-truk raksasa yang meratakan
gunung-gunung di Papua?
Agar Indonesia bisa makmur, maka Indonesia harus mengelola sendiri kekayaan
alamnya.

Jika beberapa langkah sederhana bisa dilakukan, niscaya Indonesia akan menjadi
lebih baik.

BAB 3
PENUTUP
Kemiskinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pola pembangunan yang
dicanangkan oleh pemerintah. Ia akan hadir dengan kuantitas yang luar biasa besarnya
seiring dengan tidak meratanya pembangunan. Kemiskinan juga tidak lagi dipahami hanya
sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak/kebutuhan
dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sarana aktualisasi diri.
Dua variabel pokok yang sangat menentukan dalam menentukan besar kecilnya jumlah
kemiskinan atau yang lazim dikenal dengan Garis Kemiskinan (GK) adalah Garis kemiskinan
Makanan (GKM) yang berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100
kkal/hari per kapita dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) yang berbasis pada
pemenuhan hak pokok seperti pendidikan dan kesehatan.
Sector UMKM yang telah teruji dalam sejarah Indonesia dimasa krisis ekonomi 1997, dewasa
ini makin menampakkan peran vitalnya dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, adalah wajar manakala pemerintah menyadari peran vital tersebut yang
ditandai dengan regulasi kebijakan yang berbasis rakyat yang dalam hal ini bersinergi dengan
sector UMKM.
Dari hal tersebut, ditujuklah sector UMKM sebagai instrument yang kompetitif dalam
menanggulangi kemiskinan. Beberapa kebijakan yang menyangkut pemberdayaan sector
UMKM ini seperti pengguliran program KUR dan PNPM. Melalui dua program tersebut,
beberapa persoalan yang menghadang UMKM selama ini seperti minimnya akses
perkreditan dan pola pendampingan usaha, sedikit demi sedikit dapat teratasi.