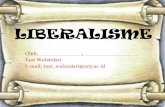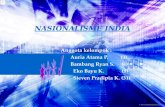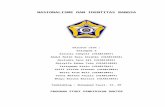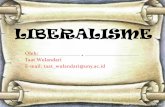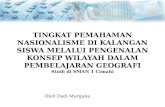Liberalisme dan nasionalisme
-
Upload
novi-hendra -
Category
Education
-
view
7.912 -
download
4
description
Transcript of Liberalisme dan nasionalisme

LIBERALISME DAN NASIONALISME
A. Liberalisme
Liberalisme atau liberal merupakan sebuah paham, ideology, pandangan filsafat dan
tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai-nilai
poitik yang utama. Kebebasan adalah tujuan tersendiri oleh kaum liberalis,karena
diasumsikan tanpa kebesan manusia tidak dapat hidup dan masyarakat tidak akan dapat
berfungsi arena itu gagasan kebebaan di setiap masa dan tempat selalu memainkan peran.
Tradisi-tradisi hukum alam di jaman kuno dan abad pertengahan pun telah menuntut
ruang kebebasan yang terjamin dari cengkeraman kekuasaan yang masih mengutamakan
masyarakat di atas individu.
Baru di era Aufklärung (jaman pencerahan), kebebasan individu menjadi premis
yang dapat melegitimasi tatanan hukum dengan sebenarnya. Dalam bukunya “Two
Treatises on Government” (1690) John Locke pernahmerumuskan bahwa manusia adalah
miliknya sendiri. Negara didasari pada suatu perjanjian yang dijalani manusia dalam
rangka melindungi hak-hak mereka atas kebebasan.
Menurut Karl Popper 1956 bahwa asas liberalsime menuntut agar pembatasan-
pembatasan terhadap kebesan individu yang tak terhindari adanya pergaulan social
sedapat mungkin.. dikurangi. Gagasan ini memiliki intisasi yang melahirkan teori-teori
politik diataranya poin intisari tersebut adalah :
Pertama tidakan pemerintah yang aktifitas dan wewenang kekuasannya harus
terikat akan terjaminnya hak-hak kebebasan yang menciptakan Negara hukum yang
menjadi cirri khas liberalism politis seperti yang dicanangkan oleh John Locke. Kedua,
tentang ekonomi pasar, dengan asumsi bahwa kebebasan adalah jalan terbaik menuju
kesejahteraan bagi semua pihak yang disokong oleh ahli ekonomi iberal seperti Adam
Smith.
Ketiga, perdamaian. Kaum liberalism memandang perdamaian tidak hanya untuk
kedaimain batin melainkan juga perdamaian lahir yang menciptakan asumsi bahwa
penkatan terhadap perdamain merupakan suatu pelanggaran besar seperti pererangan dan

untuk mengatasi dan melawannya adalah dengan merumuskan dan menjalankan kembali
arti dar kebebasan. Dan oleh karena kebebasan beraksi, batas-batas yang terbuka dan
perdagangan bebas merupakan bagian dari tuntutan dasar liberal.
Melihat pada perkembangan bangsa Indonesia yang terpengaruh oleh paham
liberal dengan berbagai kebijakan deregulasi perbankan dan keuangan di awal tahun
1980-an adalah awal dari liberalisme ekonomi dan dominasi paham neo-liberal di antara
para ekonom. Sejak itu berbagai kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah adalah
untuk melayani kepentingan korporasi, yang pada masa itu adalah para konglomerat Orde
Baru, keluarga Suharto dan TNC yang digandengnya.
Dengan liberalisme itu, mereka menjarah berbagai asset dan sumberdaya nasional
untuk memenuhi kepentingan keserakahan modal dan kehidupan serba mewah mereka.
Globalisasi melestarikan kompradorisme (kaki tangan dan kepanjangan tangan
kapitalisme internasional), tetapi sekaligus juga hendak menancapkan kukunya lebih
dalam lagi guna menguasai secara total perekonomian nasional suatu negara.
Pada intinya adalah menghancurkan kedaulatan nasional. Kaum komprador yang
terlalu berkuasa secara nasional juga tidak mereka sukai, seperti kerajaan bisnis Suharto
serta kroni-kroni konglomeratnya, karena seringkali mampu menghalang-halangi
kepentingan kapital global untuk kepentingan mereka sendiri yang mengganggu
mekanisme pasar. Yang mereka inginkan sekarang adalah dominasi sepenuhnya,
mekanisme pasar sepenuhnya, dan kontrol hukum sepenuhnya.
Kita bisa mencatat banyak kejadian kasus globalisasi yang kemudiannya telah
menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional,
kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia memasuki masa depan yang
gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia
merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia
dan para ekonom neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara
bersangkutan, baik dari segi KKN, korupsi, bad-governance dan lainnya; karena hendak
menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya.
Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar.
Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung

oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai
sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun di bantu, baru sebatas bantuan
uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep
dan visi yang jelas.
Bahkan kini terdapat kecenderungan, pemerintah semakin enggan terlibat
mengurusi permasalahan sosial. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme,
pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-
tingginya, termasuk menarik pajak dari rakyat sebesar-besarnya. Sedangkan
tanggungjawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan
sepenuhnya kepada masyarakat.
Bila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi
yang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari
negara-negara maju ketika mereka memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan
kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan sosial yang benar-benar
dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah.
Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak
ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya,
pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga
memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN
dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam policy pengelolaan nation-state-nya
pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga
menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi
mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.
B. Nasionalisme
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan
kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu
konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.Para nasionalis menganggap negara
adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari

teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran
politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.
Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai
merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah
tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan
dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan
menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah
dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman
pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila
suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah
kekuatan ini.
Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan
ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang
dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka
kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan
sebagainya
Sedangkan arti Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran
nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk
merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk
membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.
Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai
bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara
tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain.
Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi
kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama
dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Nasionalisme dapat diartikan:
Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya
sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap

seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.
Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme.
Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta
yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain
HUBUNGAN LIBERALISME DENGAN NASIONALISME
Sulit tentunya untuk menciptakan Negara yang memiliki nilai luhur, yakni
menciptakan perdamaian, keadilan serta merealisasikan good governence. Dalam upaya
meningkatkan terciptanya perdamaian (peace building) dan pencegahan terjadinya
konflik (conflict prevention), adalah tugas semua elemen baik pemerintah ataupun
masyarakat sipil.
Ahir – akhir ini banyak terjadi ketegangan social yang lama terpendam kemudian
dimunculkan diberbagai tempat atau daerah, melihat fenomena yang terjadi masyarakat
Indonesia yang seharusnya berdampingan malah melahirkan pertengkaran antar suku,
agama, supporter dan banyak lagi. Perlu di ingat bahwa salah satu yang menyebabkan
kekerasan di nusantara terjadi semenjak rezim Orde Baru. Akibat kurang stabilnya
pemerintah, yang terdesak oleh hutang Negara yang semakin membengkak dan tuntutan
reformasi akibat krisis multidimensi pada saat itu.
Karena bagaimanapun juga liberalisme merupakan factor keutamaan dalam
religius, artinya dengan menentang klaim kebenaran eklusif akan menyempitkan pola
fikir manusia itu sendiri melalui kebenaran mutlaknya, sebab manusia secara otonom
harus menentukan sikap dan tindakannya sesuai dengan tuntutan akal budi. Dan
liberalisme menjunjung tinggi toleransi serta memperjuangkan ruang seluas – luasnya
bagi kebebasan individu baik itu menyangkut HAM, kebebasan PERS dan menyatakan
pendapat, serta berserikat.
Dalam kancah politik liberalisme memiliki tujuan mulia, seperti ikut serta
mewujudkan Negara hukum, yang berdasarkan konstitusi, dan menyamakan semua
individu dihadapan hukum tanpa ada “frivilese feudal” dan prinsip legalitas administrasi
Negara, serta mengutuk hukuman yang kejam.

Seperti halnya sebuah sistem pemerintahan dan politik, sebuah sistem ekonomi
pastilah didasarkan atas pemikiran atau aliran filsafat tertentu. Demikian pula halnya
dengan dua sistem ekonomi yang sedang diperdebatkan dengan hangatnya sekarang ini di
negeri kita, yaitu liberalisme dan ekonomi kerakyatan (nasionalisme). Karena itu
keduanya tidak saja dapat diperdebatkan dari perspektif ilmu ekonomi, tetapi juga dari
perspektif sejarah pemikiran atau filsafat sebagaimana akan saya coba lakukan sejauh
kemampuan saya.
Aliran pertama lazim disamakan dengan sistem ekonomi pasar bebas liberal dan
berakar dari perpaduan pemikiran sosial, politik dan ekonomi, serta anthropologi falsafah
seperti liberalisme, utilitarianisme, individualisme, materialisme, kapitalisme, hedonisme,
dan lain sebagainya. Yang kedua lahir dari paham seperti altruisme, kolektivisme, dan
sosialisme, baik sosialisme bercorak secular maupun keagamaan.
Ekonomi kerakyatan dipandang sebagai sistem yang sesuai dengan semangat
UUD 45, baik sebelum maupun sesudah diamandemen. Karena itu sering dihubungkan
apa yang disebut sebagai Ekonomi Konstitusi. Mohamad Hatta (1959) menyebutnya
sebagai Ekonomi Terpimpin. Dalam perkataan ‘kerakyatan’ itu tersimpul dasar keadilan
sosial atau demokratis, yaitu satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk
semua (Hadori Junus, dalam Mubyarto 1980). Dalam sistem ini dikehendaki produksi
dikerjakan untuk kepentingan bersama dan secara bersama-sama pula, melalui koperasi,
dengan pengawasan masyarakat secara terpimpin.
Tetapi malang, sistem yang dipandang berpihak kepada rakyat ini tidak
dilaksanakan dengan baik sebagaimana terbukti dengan mandegnya perkembangan
koperasi. Sarjana-sarjana ekonomi mencari sumber kegagalannya pada strategi
pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat liberal-materialistis, terutama yang
dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru. Menurut Mubyarto (1980) sistem yang
tersimpul dalam kebijakan pembangunan Orde Baru tidak sesuai dengan GBHN, sebab
dalam GBHN jelas sekali ciri-ciri negatif dari sistem ekonomi liberal ditolak seperti
misalnya free-fight liberalism, etatisme dan kecenderungan monopoli serta oligopoli. Di
bawah strategi pembangunan seperti itu, yang kelak memberi jalan lempang bagi neo-

liberalisme, bangsa Indonesia menderita dan lumpuh, serta akhirnya jatuh ke tangan
eksploitasi asing. Dampak dahsyatnya pula tidak kalah sangat dirasakan secara cultural,
berupa suburnya pola dan gaya hidup konsumtif dan hedonis.
Bersumber dari pemikiran Adam Smith, pada akhir abad ke-18 bersamaan dengan
berkobarnya Revolusi Perancis dan lahirnya Revolusi Industri di Inggeris, lahir pula dua
aliran pemikiran yang dominan. Yaitu individualisme di bidang hukum dan anthropologi
filsafat, dan ide pasar terbuka yang berkaitan dengan perkembangan industri. Menurut
paham inidividualisme, manusia yang lahir dengan bawaan bebas dan hidup bebas, tidak
boleh dikekang kebebasannya. Paham ini sangat dominant pada abad ke-20 dalam
kehidupan politik, ekoomi, dan seni.
Ekonomi Kerakyatan dan Terpimpin
Semangat UUD 45 cenderung ke sosialisme religius. Ini dapat dilihat pada pasal 33 dasar
konstitusi negara kita tersebut. Sistem ekonomi kerakyatan atau terpimpin adalah
pengejawantahannya. Ia juga sejalan dengan cita-cita nasionalisme Indonesia
sebagaimana diyakini para pendiri negara ini. Ia, nasionalisme kita, lahir pada awal abad
ke-20 sebagai bentuk perlawanan atau penentangan terhadap kolonialisme dan
imperialisme yang dilakukan negara kapitalis.
Dalam kolonialisme terkandung tiga hal:
1. Politik dominasi dan hegemoni;
2. Eksploitasi ekonomi;
3. Penetrasi budaya.
Karena itu nasionalisme Indonesia mengandung juga tiga aspek penting yang
berlawanan:
1. Aspek politik. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghilangkan dominasi politik
bangsa asing dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang
berkedaulatan rakyat

2. Aspek sosial ekonomi. Nasionalisme Indonesia muncul untuk menghentikan
eksploitasi ekonomi asing dan membangun masyarakat baru yang mandiri dan
kreatif;
3. Aspek budaya. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali
kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan perubahan zaman.
Sistem ekonomi yang sesuai dengan jiwa nasionalisme Indonesia ialah ekonomi
kerakyatan yang oleh Bung Hatta disebut ekonomi terpimpin. Ada pula yang
menyebutnya sebagai Ekonomi Kesejahtaraan yang merupakan percampuran kapitalisme
dan sosialisme. Menurut Bung Hatta, ekonomi terpimpin merupakan konsekwensi dari
nasionalisme Indonesia yang timbul sebagai perlawanan menentang kolonialisme dan
imperialisme. Dalam menancapkan kekuasaannya pemerintah kolonial menggunakan
sistem kapitalisme perdagangan yang eksploitatif dan menjadikan negeri ini sebagai
perkebunan raksasa. Dengan itu rakyat Indonesia dieksplotasi sebagai buruh perkebunan
dengan gaji rendah, sedangkan pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang besar.
Ekonomi terpimpin adalah juga lawan dari ekonomi liberal yang melahirkan
sistem kapitalisme. Ekonomi liberal menghendaki pemerintah tidak campur tanganm
dalam perekonomian rakyat dengan membuat peraturan-peraturan ketat (regulasi) yang
membatasi gerak bebas pasar. Ekonomi terpimpin adalah sebaliknya. Pemerintah harus
aktif bertindak dan memberlakukan peraturan terhadap perkembanan ekonomi dalam
masyarakat agar rakyat tidak dieksploitasi, harga tidak dipermainkan dan dengan
demikian tercapai keadilan sosial.
Alasan mengapa ekonomi terpimpin dipandang sesuai dengan cita-cita
nasionalisme Indonesia ialah: Karena membiarkan perekonomian berjalan menurut
permainan bebas dari tenaga-tenaga masyarakat berarti membiarkan yang lemah menjadi
makanan yang kuat. Ekonomi liberal bercita-cita memberikan kemakmuran dan
kemerdekaan bagi semua orang, tetapi hasilnya menimbulkan pertentangan dan
kesengsaraan. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah melarat. Sebab
kebebasan atau liberalisme yang disandang oleh sistem itu dalam kenyataan hanya
dimiliki ioleh segolongan kecil orang (yaitu pemilik modal atau kapital) dan kepada

mereka yang segelintir itu sajalah keuntungan dan kemakmuran berpihak, bukan kepada
rakyat banyak.
Tetapi dalam sistem ekonomi terpimpin itu tedapat banyak aliran. Antara lain:
1. Ekonomi terpimpin menurut ideologi komunisme;
2. Ekonomi terpimpin menurut pandangan sosialisme demokrasi;
3. Ekonomi terpimpin menurut solidaroisme;
4. Ekonomi Terpimpin menurut paham Kristen Sosialis;
5. Ekonomi Terpimpin berdasar ajaran Islam;
6. Ekonomi Terpimpin berdasarkan pandangan demokrasi sosial.
Semua aliran ekonomi terpimpin ini menentang dasar-dasar individualisme, yang
meletakkan buruk baik nasib masyarakat di tangan orang-orang yang mengemudikan
kehidupan dan tindakan ekonomi. Ekonomi liberal berdasarkan pada individualisme.
Individu (baca kepentingan individu) didahulukan dari masyarakat. Tetapi ekonomi
terpimpin mendahulukan masyarakat dari individu. Sekalipun demikian di antara paham-
paham ekonomi terpimpin itu ada yang menolak kolektivisme, karena bagi mereka
kolektivisme sebenarnya hanya berlaku dalam ideologi komunisme dan sosialisme.
Tetapi terdapat persamaan pula dari sistem ekonomi terpimpin yang berbeda-beda
itu, yaitu dalam hal menentang individualism an dalam hal pemberian tempat yang
istimewa kepada pemerintah untuk mengatur dan memimpin perekonomian negara.
Perbedaan antara sistem-sistem itu berkenaan dengan seberapa besar campur tangan
kekuasaan publik dan bagaimana coraknya campur tangan itu dalam perekonomian
individu dan masyarakat. Ideologi komunisme menghendaki campur tangan besar dan
menyeluruh dari pemerintah atau negara, sehingga individu ditindas. Sistem ekonomi
kpmunis bersifat totaliter, dikuasai oleh negara.
Tetapi ekonomi terpimpin yang lebih sesuai dalam konteks nasionalisme
Indonesia ialah ekonomi bercorak sosialis, yang berkehendak melaksanakan cita-cita
demokrasi ekonomi. Dengan diimbangi demokrasi ekonomi, maka sifat individualistis
dari demokrasi liberal dapat dikurangi. Di dalamnya campur tangan negara terbatas dan

peranan individu tidak sepenuhnya dimusnahkan, hanya saja gerak mereka dibatasi dan
diatur demi melindungi kepentingan masyarakat. Bung Hatta bertolak dari pemikiran
Lerner, penulis buku The Economics of Control (1919). Unsur-unsur ekonomi kapitalis
dan kolektif digabungkan ke dalamnya, menjadi sistem yang disebut “Welfare
economics” atau ekonomi kemakmuran
Dalam sistem tersebut tiga hal yang harus dilaksanakan: Pertama, segala sumber
perekonomian yang ada harus dikerjakan supaya semua orang memperoleh pekerjaan;
kedua, melaksanakan pembagian pendapatan yang adil, agar perbedaan atau jurang besar
dalam pendapatan dan kekayaan antara yang kaya dan yang miskin dikurangi; ketiga,
menghapuskan monopoli dan oligapoli dalam perekonomian, sebab keduanya melahirkan
eksploitasi yang melampaui batas dan pemborosan ekonomi yang besar pula.
kedua paham ini sering betentangan dikarenakan tidak adanya keseimbangan
pemikiran dalam tujuannya . nasionalsime yang lebih mngarah kebebasan dalam rasa
persatuan dikekangai leh liberalism yang merujuk pada kebebsan indivudu dengan
mengindahkan kepentingan yang lain termasuk mengindahkan nasionalisme yang ada.
Kaum liberalism memandang perdamaian tidak hanya untuk kedaimain batin
melainkan juga perdamaian lahir yang menciptakan asumsi bahwa penkatan terhadap
perdamain merupakan suatu pelanggaran besar seperti pererangan dan untuk mengatasi
dan melawannya adalah dengan merumuskan dan menjalankan kembali arti dar
kebebasan. Dan oleh karena kebebasan beraksi, batas-batas yang terbuka dan
perdagangan bebas merupakan bagian dari tuntutan dasar liberal. Begitupun dengan
nasionalisme yang tidak menginginkan dany peperangan dan dengan naionalsimelah
pererangan dan ketegangan dapat dihentikan.
Oleh karena itu muncul ketegangan antara nasionalsime denan liberalism dalam
hal apapun termasuk dalam pemerintahan. Dimana penganruh liberalism dalam
pemerintahan akn mengahamcurkan rasa nasionalsime. Dan kedua paham ini tidak dapat
dijalankan dalam suatu pemerintahan baik itu dalam penyelenggaran ataupun penyaluran
dala sebuah kebijakan public Indonesia.

Dan ketegangan hubungan ini dapt dilihat dengan tidak adanya jalan yang diambil
pemerintah dalam penyelesaiannya, baik itu pada masa orde lama, orde abru, dan
reformasi. Baik nasionalsimeyang sedang berkuasa ataupun liberalism yang edang
dijlankan yang merasuk didalam pemrintahan.
KEBIJAKAN PUBLIK MASA 1987-1992
Masa ini dapat disebut dengan masa orde lama dimana Kebijakan public pada
masa orde lama mengarah pada rasa nasionalis. Hal ini dikarenakan bahwa rasa
kebersamaan setelah kemerdekaan masih membaur dalam kehidupan berkebangsaaan dan
program serta kebijakan yang dikeluarkan pada masa itu cenderung menuntut untuk
menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep liberalism dan kolonialisme serta
hadirnya komunisme dihapuskan disetiap tatanan pemerintahan, agar dalam
mengeluarkan suatu kebijakan tidak berbau cara yang merujuk pada hilangnya rasa
nasionalsime.
Adanya kebijakan public yang berdasarkan pada nasiolasime akan akan
menciptakan politik kebangsaan yang lahir sebagai senjata dari pemerintah untuk
memastikan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Nasionalisme politik adalah visi dan
kemakmuran rakyat sebagai misi yang harus diwujudkan. Pemerintah perlu menguatkan
kembali komitmen untuk menata kebijakan ekonomi demi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat Indonesia.
Wujud dari nasionalisme politik pemerintah butuh keberpihakan yang konkret
terhadap pengurangan kemiskinan, memberantas hangus proses pemiskinan yang
berlangsung sistemik, membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta membangun kembali
ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia.
Meminjam istilah Bung Karno membangun bangsa dengan memikul natuur dan
terpikul natuur. Pembangunan dan pertumbuhan haruslah sepadan dengan ketersediaan
sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia sendiri. Pemerintah harus
dipercaya rakyat dan memiliki wibawa di tengah pergaulan internasional.
Kepercayaan rakyat adalah realita obyektif untuk memperoleh elektabiltas yang
substansial. Kewibawaan pemerintah di mata internasional pun sesuatu yang obyektif

untuk ber-interaksi dan membangun pakta-pakta kerja sama bilateral maupun
multilateral. Karena tak kan bisa lagi suatu bangsa bisa bangga dengan eksklusivisme dan
politik isolasi. Tapi, juga jangan pernah menjadi bangsa pembebek, epigon. Bangsa yang
hanya bisa jadi muntahan pasar tanpa memiliki daya saing dan produk unggulan untuk
berkompetis
Kegiatan perekonomian lebih berbasis pada ekonomi kerakyatan sehingga
campurtangan liberalis tidak mampu mempengaruhi pemerintah. Konsep dasar
pemerintahan adalah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan
rakyat. Upaya-upaya tersebut berkaitan dengan manajemen dan politik yang diterapkan
oleh kepala pemerintahan. Pendekatan manajemen dijalankan agar implementasi itu
berlangsung secara sistematis. Pendekatan politik digunakan untuk menciptakan
dukungan yang lebih banyak dari wakil-wakil rakyat terhadap suatu kebijakan yang
diperuntukan bagi rakyat. Perpaduan keduanya merupakan sebuah “seni” dalam
memimpin suatu organisasi.
Apabila kita cermati kebijakan publik merupakan keniscayaan pemerintahan yang
dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemerintah menghipun sumber daya finansial dari
pajak yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas rakyat. Oleh karena rakyat
memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk memamaj pemerintahan maka ia
harus menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat.
Persoalannya, formasi dan implementasi kebijakan publik itu kerap kurang
dipahami secara utuh oleh rakyatnya. Pemerintahan yang dijalankan oleh orang yang
tidak amanah cenderung membohongi rakyat karena dianggapnya rakyat tidak tahu. Oleh
karena itu, tampaknya diperlukan serangkaian strategi untuk mengawal formulasi dan
implementasi kebijakan publik tersebut, terutama di era trasfaransi seperti sekarang ini.
Pembohongan terhadap rakyat sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Untuk
itulah, rakyat harus cerdas dalam mencermati persoalan pemerintahan dengan menata dan
mendorong penerapan strategi untuk mengawal formaulasi dan implementasi kebijakan
publik.
Kebijakan publik di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan.
Dari kebijakan yang dilakukan secara sentralistik berubah menjadi desentralistik, dari
kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah otonom, dari semula masyarakat hanya

dianggap sebagai pengguna berubah menjadi pengontrol dan pengawas. Dari
penyeragaman berubah menjadi keberagaman berdasarkan kerangka dasar yang
ditetapkan.
Kebijakan sentralistik dialami dalam tiga periode, yaitu pada masa Orde Lama,
Masa Orde Baru, dan Masa Transisi. Kebijakan pada masa Orde Lama masih berorientasi
politik. Salah satu contoh kebijakan publik saat itu dilakukan secara sentralistik dalam
bidang pendidikan, bahwa kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada proses
indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Dengan
demikian pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, bukan untuk
kebutuhan pasar melainkan untuk orientasi politik. Indroktrinasi pendidikan mulai dari
jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap
militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan di suasana perang dingin pada
saat itu.
KEBIJAKAN PUBLIK MASA 1992-1997
Pada masa ini atau dikenal dengan masa orde baru kebijakan public lebih
cenderung kepada arah liberalis, dimana adanya ketergantungan akan kehidupan pada
pihak asing dan liberalism barat juga telah masuk ke setiap tatanan kehidupan yang
berujung pada kebebsan untuk bertindak dalam perubaha. Ekomoni pasar dikuasai oleh
elit-elit dan pemerintahan juga dikuasi elit-elit dalam tujuan memperoleh kekuasaan
seutuhnya.
Konfigurasi politik orde baru secara umum bersifat tunggal (homogen) dan
monolitik. Menurut teori pembagian entitas dalam bentuk-bentuk negara modern
sebagaimana diungkapakan Alfred Stepan, karakter yang menunggal dan monolitik
tersebut terjadi pada level negara (state) dan masyarakat (society). Pada level negara
terlihat dari relatif solidnya semua unsur yang ada di dalam entitas negara, baik eksekutif,
legislatif ataupun yudikatif. Sedangkan pada level masyarakat dengan karakter negara
yang monolitik dan menunggal dapat dipastikan negara menjadi pengendali dan
masyarakat dapat ditundukkan, diarahkan dan dikendalikan secara sistemik. Sehingga
kondisi politik ini pada tahap berikutnya mendorong atas bentuk dan format ketunggalan
dan monolitik dalam masyarakat, baik dalam kerangka hubungan masyarakat (society)

dengan masyarakat (society), ataupun hubungan masyarakat (society) dengan negara
(state).
Konfigurasi politik orde baru yang menunggal dan monolitik itu terbangun lewat
soliditas elemen-elemen negara baik vertikal ataupun horizontal. Secara horizontal negara
terkonsolidasi dengan kuat oleh dukungan militer, birokrasi dan partai Golkar. Sedangkan
secara vertikal, negara melakukan perekayasaan secara sistemik dengan membangun
sentralisasi dan dominasi pemerintah pusat dalam kerangka hubungan pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah. Konteks ini mempertegas bahwa negara di era rezim orde
baru merupakan personifikasi dari militer (angkatan darat), birokrasi, Golkar dan
pemerintahan pusat (sentralistik).
Pertama, walaupun friksi dan kesenjangan antar perwira sudah muncul di era orde
baru, namun selama orde baru keberadaan militer telah menjadi sentrum dari kekuasaan
orde baru. dimotori oleh angkatan darat, dominasi militer dalam wilayah politik
menyandarkan pada konsep dwifungsi ABRI. Hal ini merupakaan penjelmaan dari
dominasi militer diwujudkan dengan hadirnya struktur militer yang paralel dengan
struktur pemerintahan sipil, kerangka ini merupakan perekayasaan untuk pengendalian
dan penundukan kepada masyarakat. Selain itu, dalam kancah percaturan politik,
personel militer mendapatkan tempat dengan melakukan penyebaran di semua institusi
kekuasaan yang ada seperti lembaga perwakilan rakyat (legislatif), birokrasi dan partai
politik. Mikanisme pengangkatan militer untuk lembaga perwakilan rakyat telah terjamin
keberadaannya, sedangkan dalam birokrasi nampak personel militer dalam jabatan-
jabatan strategis seperti Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri dan lainnya, hal yang sama
juga terjadi dalam tubuh partai Golkar.
Kedua, Politisasi juga terjadi dalam tubuh birokrasi. Birokrasi dijadikan istrumen
penting kekuasaan Soeharto sehingga melegitimasi hegemoni rezim Seoharto dan tak
terkalahkan selama pemerintahannya. Kerangka kerjanya minimal dapat dilihat dalam
dua hal, pertama, kebijaksanaan sentralisasi manajemen birokrasi seperti jenjang karir,
gaji, pengangkatan, pemberhentian dan lain sebagainya. Pada akhirnya kebijakan ini
mengantarkan pada homogennya struktur birokrasi baik dari pusat sampai daerah, dari
Sabang sampai Merauke. Kedua, kebijaksanaan monoloyalitas tunggal, dimana semua
birokrat harus berafiliasi dengan partai Golkar dan tidak boleh berafiliasi dengan partai

lainnya. Hal ini menyebabkan menyatunya suara birokrasi untuk Golkar, dan pastinya
Soeharto pasti menang dalam pemilihan umum.
Ketiga, kekuatan politik orde baru juga disokong oleh partai Golkar, dan
merupakan satu-satunya partai politik yang hegemonik ketimbang partai yang lain PPP
dan PDI setelah pemfusian. Keberadaan Golkar dengan kekuatan militer yang penuh dan
birokrasi yang taat, tidak pernah terkalahkan oleh partai-partai yang lain, bahkan Yusril
Ihza Mahendra pernah mengungkapkan dalam sebuah tulisannya bahwa yang namanya
Golkar tidak akan pernah terkalahkan seumur hidup selama sistem kepartaian masih
seperti orde baru. Hal ini menyebabkan kemandulan suara-suara kritis dari legislatif
terhadap eksekutif, bahkan lembaga yudikatif-pun menjadi lembaga yang tidak
independen karena keputusannya mengabdi dan membenarkan prilaku orde baru.
Dipastikan mereka semua mendukung semua kebijakan-kebijakan orde baru walaupun
tidak bersesuaian dengan keadilan, kemanusiaan dan kebenaran.
Keempat, Hegemoni orde baru juga telihat jelas dari sentralisasi kebijakan di
Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1950-an dan 1960-an membulatkan
tekad orde baru untuk menggunakan asas sentralisasi dalam negara. Konsepsi ini pada
dasarnya disandarkan pada pengamanan dan ketertiban sehingga di daerah-daerah
kerapkali terjadi pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, semisal di Aceh, Papua dan
daerah-daerah lainnya.
Untuk menunjukkan hegemoni rezim Soeharto baik vertikal ataupun horisontal
dapat dilihat dari perwujudan lembaga Muspida yang anggotanya terdiri dari pemerintah
Propinsi dan Kabupaten/Kota, Muspika yang anggotanya terdiri dari Camat, Koramil dan
Komando Sektor, sedangkan di Desa terdiri dari LMD, LKMD dan Babinsa dari militer.
Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sangat berfungsi pada politik pengendalian,
penundukan, serta rekayasa politik dan kebijakan selama rezim orde baru. Secara
horisontal lembaga-lembaga tersebut diisi oleh militer, kepolisian dan kejaksaan.
Sendangkan secara vertikal lembaga-lembaga itu diisi oleh personal Gubernur dan
Walikota/Bupati.
Dalam konteks masyarakat sipil fenomena sentralistik, tunggal dan monolitik
sangat berpengaruh pada tertib, ketundukan dan kekerasan sosial, baik hubungannya
masyarakat (society) dengan masyarakat (society) ataupun hubungannya masyarakat

(society) dengan negara (state). Hal ini merupakan akibat dari telah bekerjanya
perekayasaan politik Soeharto dalam pengendalian dan penundukan negara kepada
masyarakat, baik lewat institusi-institusi tersebut ataupun pada level wacana (discourse).
Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Mas`oed bahwa pada dataran institusi
mikanisme pengendalian dan penundukan oleh negara kepada masyarakat diwujudkan
dengan mikanisme korporatisme. Dimana negara pada rezim orde baru menggambarkan
hubungan masyarakat dengan masyarakat yang termobilisasi, terkontrol, tertib dan sikap
politik yang menunggal. Sedangkan pada wilayah wacana juga terjadi pengendalian,
kontroling dan pengarahan pada wacana tunggal dengan alasan-alasan SARA, harmoni
sosial, integrasi bangsa, ketertiban, pembangunan dan lain sebagainya, bahkan seringkali
menurut Anderson memanfaatkan instrumen budaya
Sementara itu, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada
penyeragaman menjelaskan pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformalitas atau
keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal
dari organisasi sosial masyarakat, semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat
yang homogen. Pada masa ini tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga
melahirkan disiplin semu dan melahirkan masyarakat peniru.
Pada masa ini pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima. Pembangunan
tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung
pada utang luar negeri sehingga melahirkan sistem yang tidak peka terhadap daya saing
dan tidak produktif. Berbagai layanan publik tidak mempunyai akuntabilitas sosial oleh
karena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya. Bentuk pembangunan
pada saat itu mengingkari kebhinekaan serta semakin mempertajam bentuk
primordialisme. Penerapan pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan kualitas
melainkan pada target kuantitas.
Pemerintah Orde Baru juga harus bertanggungjawab atasa keterkaitan kepada
IMF karena kehadiran hutang luar negeri membawa kita menghadapi dua masalah besar
yang harus segera diselesaikan. Pertama, adalah system KKN (Korupsi, Kolusi,
Nepotisme) yang parah. Indonesia menjadi bangsa yang celaka dan merugi karena selama
32 tahun hanya membangun KKN. KKN ini terjadi karena pemerintahnya sejak awal
memang berorientasi untuk Korupsi, sehingga kekayaan nasional yang luar biasa

besarnya hanya dibagi di kalangan elite saja (keluarga Presiden dan kroni-kroni
konglomerat serta elit kekuasaan). Dan yang menyedihkan nampaknya system KKN
masih terus berlanjut hingga kini.
Kedua, adalah sistem Pasar Bebas yang kapitalistik yang memanfaatkan KKN
untuk keuntungan pemodal asing (TNC/MNC) dari negara-negara maju. Contoh paling
jelas adalah Freeport di Papua dan Exxon di Aceh. Sistem pasar bebas dan globalisasi ini
mengekalkan hubungan neokolonialisme-imperialisme, sehingga Indonesia sukar sekali
keluar dari ketergantungannya pada negara-negara maju dan badan-badan dunia tersebut.
KEBIJAKAN PUBLIK MASA 1997-SEKARANG
Pada masa inidikenal dengan masa reformasi dimana kebijakan merupakan masa
refleksi terhadap arah pembangunan nasional dalam bentuk terberdayanya liberalisme.
Dalam bidang pendidikan, menjelaskan bahwa pada masa krisis pembangunan telah
membawa masyarakat dan bangsa kepada keterpurukan. Dari krisis moneter berlanjut
pada krisis ekonomi dan berakhir pada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan telah
menjadi warna yang dominan di dalam kehidupan dan budaya bangsa saat itu. Oleh
karena pendidikan merupakan proses pembudayaan, maka krisis kebudayaan yang
dialami merupakan refleksi dari krisis nasional. Pada masa ini direfleksi berbagai
pemikiran dalam memajukan sistem pemerintahan kita, sehingga berbagai perubahan
dirasakan sangat drastis dan mencengangkan.
Kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah merupakan konsekuensi dari
keinginan era reformasi untuk menggelorakan kehidupan demokrasi. Salah satu kebijakan
publik dalam bidang pendidikan adalah menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi
sekolah. Namun, kebijakan ini kerap kali mendapat tantangan dari dalam, khususnya para
pelaksana yang tidak terbiasa dengan kebijakan di era terbaru. Banyak di antara
pelaksana pemerintahan hanya mengandalkan kegiatan copy-paste terhadap
pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian, para pelaksana pembangunan
cenderung berlaku konvensional dalam memanaj pemerintahan bagi kepentingan rakyat.
Kini saatnya memformulasikan kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial yang
memutus keterikatan dan ketergantungan kepada agenda globalisasi yang mulai merebak
dari masa reformasi sampai sekarang. WTO dan IMF telah membatasi pilihan-pilihan

kebijakan yang ada dan memaksakan kebijakan yang hanya sesuai dengan agenda
mereka. Pada masa lalu mereka memakai pendekatan pertumbuhan ekonomi sebagai
doktrin, dan sekarang mereka menambahkan “Kompetisi Bebas” sebagai doktrin. Ini
harus ditentang dan dicarikan alternatifnya. Ada banyak alternatif yang tersedia
sebenarnya, asalkan kita tidak “turut dan manut” saja terhadap pasar bebas / globalisasi.
Oleh karena itu berbagai kelompok nasional harus berembuk dan berdialog
bersama guna menetapkan pokok-pokok pandangan dan visi nasional yang non-Pasar
Bebas. Banyak alternatif yang mungkin yaitu:
1. Sistem ekonomi jangan berprinsip pasar bebas (liberalisme ekonomi). Haruslah
mencontoh berbagai pengalaman negara lain, termasuk AS, Jerman dan Jepang, yang
dalam sejarahnyajuga memakai ekonomi merkantilis dan proteksionis ketimbang
pasar bebas di masa awal pembangunannya. Indonesia masih dalam tahap-tahap awal
perkembangannya, dan karenanya perlu menerapkan ekonomi yang proteksionis dan
kerakyatan.
2. Sistem ekonomi haruslah mendahulukan pasar domestik dan menaruh di belakang
orientasi pada pasar ekspor. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat
produksi domestic untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian
rakyat; dan bukan untuk melayani kepentingan TNC dan konglomerat atas pasar
eksport.
3. Pertanian dijadikan prioritas utama perekonomian, karena di sinilah hidup mayoritas
rakyat. Karena itu alokasi untuk sektor pertanian (termasuk kelautan dan perikanan)
harus lebih besar dari yang lain-lainnya. Pertanian harus dirubah melalui agrarian
reform, sehingga terjadi distribusi tanah dan sumberdaya yang merata. Selain itu
diadakan berbagai kemudahan dan fasilitas serta perlindungan bagi petani untuk
memperkuat sektor pertanian.
4. Industrialisasi berdasarkan pada bahan baku setempat, sehingga tidak tergantung
impor dari luar. Ini berarti di satu pihak memperkuat sektor pertanian, sektor kelautan
dan lain-lainnya; serta memperkuat sektor industri itu sendiri serta industri-industri
kecil yang terkait dengannya.

5. Diadakan perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan, yaitu negara
menjalankan berbagai peran penyelenggaraan barang publik (public goods) dan
prasarana publik (public facilities), seperti air, listrik, transportasi, kesehatan,
pendidikan dan lainnya. Segala sesuatu yang bersifat publik haruslah bersifat gratis.
6. Tidak tergantung kepada badan-badan multilateral, dan ikut serta merubah badan-
badan tersebut agar menjadi badan yang terutama melayani kepentingan negara-
negara Dunia Ketiga
7. Penghapusan sebagian besar hutang karena alasan-alasan etika, moral, dan ekonomi
yang layak.
8. Melepaskan diri dari rejim devisa bebas dan rejim nilai tukar mengambang bebas
(free-float exchange rate); dan sebagai gantinya menetapkan kontrol modal (capital
control) dan nilai tukar tetap (fixed exchange).
9. Menyokong diadakannya Tobin Tax terhadap arus keluar masuk modal swasta yang
saat ini merupakan ‘hot money’ dan volatilitasnya sangat tinggi.
10. Menolak paham Neo-liberal dan mencari alternatif ilmu ekonomi yang lebih
mencerminkan kepentingan rakyat dan nasional, seperti dengan neo-protectionism,
neo-keynesianism, welfare state, ekonomi kerakyatan dan lain-lainnya.
11. Demokrasi yang diarahkan bagi penguatan aspirasi rakyat dan organisasi rakyat;
kebebasan berpikir, berbicara, berorganisasi; dan pemenuhan HAM sepenuhnya
12. Kerjasama Dunia Ketiga untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-
negara maju (G-7, OECD), untuk di dapat resolusi yang layak bagi Dunia Ketiga,
seperti memperkuat kembali hasil yang telah dicapai UNCTAD lewat GSP
(Generalized System of Preference) dan pengurangan hutang

KESIMPULAN
Liberalisme dan nasionalsime merupakan paham yang betujuan memperoleh
kebesan tertuntu menurut konsepnya masing-maing. Namun kedua paham ini sering
betentangan dikarenakan tidak adanya keseimbangan pemikiran dalam tujuannya .
nasionalsime yang lebih mngarah kebebasan dalam rasa persatuan dikekangai leh
liberalism yang merujuk pada kebebsan indivudu dengan mengindahkan kepentingan
yang lain termasuk mengindahkan nasionalisme yang ada.
Kaum liberalism memandang perdamaian tidak hanya untuk kedaimain batin
melainkan juga perdamaian lahir yang menciptakan asumsi bahwa penkatan terhadap
perdamain merupakan suatu pelanggaran besar seperti pererangan dan untuk mengatasi
dan melawannya adalah dengan merumuskan dan menjalankan kembali arti dar
kebebasan. Dan oleh karena kebebasan beraksi, batas-batas yang terbuka dan
perdagangan bebas merupakan bagian dari tuntutan dasar liberal. Begitupun dengan
nasionalisme yang tidak menginginkan dany peperangan dan dengan naionalsimelah
pererangan dan ketegangan dapat dihentikan.
Oleh karena itu muncul ketegangan antara nasionalsime denan liberalism dalam
hal apapun termasuk dalam pemerintahan. Dimana penganruh liberalism dalam
pemerintahan akn mengahamcurkan rasa nasionalsime. Dan kedua paham ini tidak dapat
dijalankan dalam suatu pemerintahan baik itu dalam penyelenggaran ataupun penyaluran
dala sebuah kebijakan public.

DAFTAR PUSTAKA
Miriam Budiardjo, PENGANTAR ILMU POLITIK. Liberaslime.
Sistem Ekonomi Indonesia. 2005. Liberalime ekonomi indnesia.
Abdul Hadi, 2009. Liberalisme dan nasionalisme kita. Jakarta
(www.ahmadsumantho.com)
Erick Fitra. Skripsi 2006. Liberalism dalam kebijakan ekonomi pemerintah kota Padang.
Mahasiswa Ekonomi Pebangunan 2002.
Google.com. nasionalisme dalam pemerintahan (shikumbang.blogspot.com)

Tugas Ekonomi Politik
HUBUNGAN LIBERALISME DAN NASIONALISME INDONESIA
DAN KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK
DALAM TIGA ERA DI INDONESIA
Oleh
Novi Hendra
BP 06193058
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010