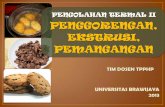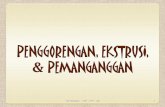laporan praktikum penggorengan keripik buah
-
Upload
eva-mayasari -
Category
Documents
-
view
1.441 -
download
128
description
Transcript of laporan praktikum penggorengan keripik buah

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Produksi buah-buahan di Indonesia seperti nenas, salak, pisang, dan
pepaya cukup tinggi. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2009), produksi
buah-buahan Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Produksi buahbuahan
tahun 2007 mencapai 17.116.662 ton, meningkat dibandingkan produksi tahun
2006 sekitar 16.171.130 ton dan tahun 2005 sebesar 14.786.599 ton.
Produksi buah yang melimpah kadang juga belum dimanfaatkan
(Antarlina dan Rina 2005). Petani tidak dapat menyimpan buah-buahan lebih lama
karena umur simpannya pendek. Penanganan buah yang kurang hati-hati pada saat
panen, termasuk pengemasan dan transportasi, akan menyebabkan kerusakan
10−60%. Oleh karena itu, perlu upaya meningkatkan umur simpan dan nilai
tambah buah-buahan (Sofyan 2004).
Nangka memiliki aroma yang kuat dan rasa yang manis. Pengolahan nangka
menjadi keripik nangka telah adalah salah satu cara untuk memperpanjang umur
simpan buah. Pengolahan buah segar menjadi kripik buah sangat sederhana,
karena pada dasarnya hanya merupakan proses penguapan air dan bagian buah
yang dapat dimakan. Pengolahan nangka menjadi keripik nangka dengan
menggunakan deep frying dan vacuum frying merupakan salah satu upaya untuk
memperpanjang daya guna produk pangan tersebut.
Nenas termasuk komoditas yang mudah rusak, susut, dan cepat busuk. Buah
ini memiliki kadar air yang sangat tinggi, yaitu sekitar 90 %. Hal inilah yang
menyebabkan nenas mudah rusak sehingga harus disimpan dan ditangani dengan
baik Namun demikian setiap menjaga agar rasa dan aroma khas buah tidak
berubah dan kripik menjadi renyah maka proses penguapan air harus di lakukan
dengan cara menggoreng buah menggunakan penggorengan deep frying atau
penggorengan dengan tekanan rendah / vakum / hampa.
Terdapat 2 (dua) cara proses menggoreng, yaitu deep frying dan vacuum
frying. Menggoreng cara deep frying membutuhkan minyak dalam jumlah banyak

sehingga bahan makanan dapat terendam seluruhnya di dalam minyak. Deep
frying dapat digunakan untuk menggoreng semua bahan makanan, seperti
kentang, salak, apel, papaya, wortel, dan lain sebagainya. Deep frying merupakan
sistem penggorengan dengan menggunakan titik asap yang lebih tinggi karena
suhu pemanasan yang lebih tinggi, biasanya mencapai 200-205oC dan bahan
pangan yang digoreng terendam dalam minyak (Ketaren, 1986). Sedangkan
vacuum frying, mesin ini menggoreng produk buah dan sayur dengan sistim
vakum. Artinya buah dan sayur tetap digoreng dengan minyak goreng, hanya saja
disertai dengan proses penyedotan uap air dengan pompa. Pada ruang
penggorengan tekanan vakum disetting otomatis pada kisaran 70 cmhg. Jika pada
penggorengan biasa suhu bisa tak terkendali, maka dengan mesin vacuum frying
ini suhu justru dikendalikan pada kisaran 800C – 900C.
Nangka dan nenas merupakan produk pangan yang dapat diolah menjadi
produk baru, seperti keripik, tepung, nangka goreng dan lain-lain. Produk olahan
ini yang dapat meningkatkan nilai jual dan umur simpan lebih lama.
1.2 Tujuan
Tujuan dari praktikum ini adalah :
1. Mengetahui proses pengolahan pangan dengan metode deep frying
dan vacuum frying.
2. Mengtahui efek suhu dan lama pemanasan terhadap kadar air,
tekstur, kadar minyak, warna, dan tingkat kesukaan panelis pada
produk yang digoreng dengan deep frying dan vacuum frying.
3. Membandingkan kualitas produk akhir yang digoreng dengan deep
frying dan vacuum frying.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Nanas (Ananas comosus (L) Merr)
Nanas merupakan salah satu tanaman buah yang banyak dibudidayakan di
daerah tropis dan subtropis. Industri pengolahan buah nanas di Indonesia menjadi
prioritas tanaman yang dikembangkan, karena memiliki potensi ekspor. Volume
ekspor terbesar untuk komoditas hortikultura berupa nanas olahan yaitu 49,32 %
dari total ekspor hortikultura Indonesia tahun 2004 (Biro Pusat Statistik, 2005).
Nanas yang kerap dikonsumsi sebagai buah segar dapat tumbuh dan
berbuah di dataran tinggi hingga 1.000 meter dpl. Tanaman buah yang tidak
menyukai air yang menggenang ini, kini ditanam luas di Indonesia. Sentra
produksinya terdapat di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera
Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Nanas memiliki berbagai varietas yaitu Cayenne, Queen, Spanyol, dan
Abacacy. Nanas yang dibudidayakan di Sumatera Selatan adalah varietas Queen,
dengan beberapa ciri antara lain mempunyai daun sangat keras, berukuran lebih
pendek dari ukuran daun jenis lainnya yaitu berkisar antara 35 cm hingga 60 cm
dan berduri tajam, buah lonjong dan berbentuk kerucut dengan rasa yang manis
serta mempunyai warna kuning kemerahan (Sunaryono, 1989).
Tanaman ini mempunyai banyak manfaat terutama pada buahnya. Riset
terkini menunjukkan nanas sarat dengan antioksidan dan fitokimia yang
berkhasiat mengatasi penuaan dini, wasir, kanker, serangan jantung, dan
penghalau stres. Sebagai salah satu famili Bromeliaceae, buah nanas mengandung
vitamin C dan vitamin A (retinol) masing-masing sebesar 24,0 miligram dan 39
miligram dalam setiap 100 gram bahan (Tabel 1). Kedua vitamin sudah lama
dikenal memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang mampu melindungi tubuh
dari berbagai serangan penyakit, termasuk kanker, jantung koroner dan penuaan
diri. (Posman Sibuea Peserta Program Doktor Ilmu Pangan UGM, Lektor Kepala
Jurusan THP Unika Santo Thomas SU Medan).

Kandungan gizi buah nanas segar (100 gram bahan)
N0 Kandungan gizi Jumlah
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
KaloriProteinLemakKarbohidratFosforZat BesiVitamin AVitamin B1 Vitamin C Air Bagian dapat dimakan
52,00 kal 0,40 g 0,20 g 16,00 g 11,00 mg 0,30 mg 130,00 SI 0,08 mg24,00 mg85,30 g53,00 %
(Sumber : Buletin Teknopro Hortikultura Edisi 71 Juli 2004. Manfaat Nanas Bagi
Kesehatan)
Tingkat kematangan buah nanas yang baik untuk dikonsumsi dapat dilihat
dari warna buahnya yaitu bila warna kuning telah mencapai 25 % (dari total
permukaan buah). Pada tingkat ini buah mempunyai total padatan terlarut yang
tinggi dan keasamannya rendah. Demikian pula tingkat kematangan buah dapat
dilihat dari warna pada mata dan kulit buah yaitu tidak kurang dari 20 % tetapi
tidak lebih dari 40 % mata mempunyai bercak kuning (Muchtadi D, 1992).
Umur simpan buah-buahan segar antara 1 sampai 7 hari pada 21,11oC,
sedangkan buah-buahan kering umur simpannya dapat mencapai 1 tahun atau
lebih (Desrosier, N.W 1970 dalam Muchtadi, 1997). Sedangkan kadar air buah
kering antara 18 sampai 25 % (Winarno dan Laksmi, 1974 dalam Muchtadi R,
1997).
2.2 Nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk)
Buah nangka (Artocarpus heterophyllus), adalah salah satu jenis buah
yang paling banyak ditanam di daerah tropis. Rasanya manis, aromanya pun
harum segar.

Buah nangka mengandung vitamin A, B, dan C dalam bentuk senyawa
thiamin, riboflavin, dan niacin. Juga mengandung mineral seperti calcium,
potassium, ferrum (zat besi), magnesium, dalam jumlah yang cukup banyak bila
dibandingkan dengan berbagai buah lainnya. Buah nangka mempunyai kandungan
gizi yang tinggi, 100 gram buah nangka memiliki 106 kalori, 27,6 gram
karbohidrat dan 1,2 gram protein.
Ada berbagai manfaat kesehatan pada buah nangka. Nangka merupakan
sumber vitamin C dan antioksidan yang bisa meningkatkan sistem daya tahan
tubuh. Dapat juga membantu melancarkan pencernaan dan mengatasi konstipasi
(sembelit) karena mengandung serat tinggi. Mengandung saponin, isoflavon, dan
lignan yang membantu menangkal radikal bebas penyebab kanker. Selain
buahnya, bagian dari pohon nangka yang lain juga dapat dimanfaatkan. Biji
nangka diketahui banyak mengandung karbohidrat, protein, energi, mineral ,
kalsium, dan fosfor.
Nangka tumbuh dengan baik di iklim tropis sampai dengan lintang 25˚
utara maupun selatan, walaupun diketahui pula masih dapat berbuah hingga
lintang 30˚. Tanaman ini menyukai wilayah dengan curah hujan lebih dari 1500
mm pertahun di mana musim keringnya tidak terlalu keras. Nangka kurang toleran
terhadap udara dingin, kekeringan dan penggenangan.
2.2 Deep frying
Deep frying merupakan sistem penggorengan dengan menggunakan titik
asap yang lebih tinggi karena suhu pemanasan yang lebih tinggi, biasanya
mencapai 200-205oC dan bahan pangan yang digoreng terendam dalam minyak.

Lemak atau minyak yang digunakan dengan sistem menggoreng deep frying
adalah yang tidak berbentuk emulsi dan mempunyai titik asap (smooking point) di
atas suhu penggorengan, sehingga asap tidak terbentuk selama proses
penggorengan. Jika pada proses penggorengan terbentuk asap atau smook, maka
ini berarti lemak tersebut mengalami dekomposisi sehingga mengakibatkan bau
dan rasa tidak enak pada bahan yang digoreng. Suhu menggoreng optimum adalah
161-190oC.
Produk penggorengan mempunyai warna, aroma, serta rasa yang khas
sehingga disukai oleh setiap orang. Produk penggorengan mengandung minyak
dan akrilamida yang merugikan kesehatan. Waktu penggorengan adalah salah satu
faktor yang sangat mempengaruhi kandungan minyak, kandungan akrilamida
dalam produk dan tingkat konsumsi energi.
Waktu penggorengan tergantung pada proses pindah panas dari minyak
goreng ke produk. Pindah panas dari minyak ke produk tergantung pada suhu
minyak di sekitar produk. Suhu minyak disekitar produk dipengaruhi oleh desain
penggoreng yaitu tinggi minyak dalam penggoreng dan desain elemen pemanas.
Penempatan sebagian elemen pemanas di bagian atas penggoreng akan
mempengaruhi pergerakan minyak dalam penggoreng (Tandilittin, 2008).
Proses pemasakan berlangsung oleh penetrasi panas dari minyak yang
masuk ke dalam bahan pangan. Proses pemasakan ini dapat mengubah atau tidak
merubah karakter bahan pangan, tergantung dari bahan pangan yang diperoleh.
Hasil gorengan yang berukuran tipis seperti kripik merupakan pengecualian.
Permukaan lapisan luar (outer zone surface) akan berwarna coklat keemasan
akibat penggorengan atau yang disebabkan oleh reaksi browning. Tingkat
intensitas warna browning (pencoklatan) ini tergantung dari lama dan suhu
menggoreng dan juga komposisi kimia pada permukaan luar dari bahan pangan.
Jika bahan segar digoreng, makan bagian luar kulit akan mengkerut akibat proses
dehidrasi bagian luar bahan pangan pada waktu menggoreng. Pembentukannya
terjadi akibat panas dari lemak panas sehingga menguapkan air yang terdapat pada
bagian luar bahan pangan. Selama proses menggoreng dengan sistem deep frying
berlangsung, sebagian minyak masuk ke bagian kerak dan bagian luar sehingga

outer zone dan mengisi ruang kosong yang pada mulanya diisi air
(Ketaren, 1986).
Minyak yang diserap untuk mengempukkan bahan makanan, sesuai dengan
jumlah air yang menguap pada saat menggoreng. Lapisan permukaan merupakan
hasil reaksi Maillard (browning non enzimatic) yang terdiri dari polimer yang
larut, dan tidak larut dalam air serta berwarna coklat kekuningan. Biasanya
senyawa polimer ini terbentuk bila makanan jenis gula dan asam amino, protein
dan atau senyawa yang mengandung nitrogen digoreng secara bersamaan. Pada
beberapa makanan seperti kentang dan kulit ayam memiliki natural coating,
sehingga tidak membutuhkan breading dan battering dahulu sebelum dilakukan
penggorengan (Sartika, 2009). Gambar deep fryer ditunjukkan pada gambar 4.
Gambar 4. Deep fryer
2.3 Vacuum frying
Salah satu usaha untuk memperpanjang masa simpan sayuran atau buah
adalah dengan metode pengeringan atau pemasakan untuk mendapatkan produk
sayuran atau buah kering siap santap. Pengeringan merupakan suatu proses
penghilangan atau pengeluaran sebagian air dari bahan pangan dengan cara
menguapkan air dan menggunakan energi panas, sampai batas mikroba tidak
dapat hidup (Winarno, 1997). Keuntungan dari pengeringan adalah bahan pangan
dapat menjadi lebih awet, volume bahan menjadi lebih kecil dan ringan serta
mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan penyimpanan, sehingga
pada akhirnya dapat memperkecil biaya produksi terutama apabila dilakukan
dalam jumlah besar.

Penggorengan vakum adalah salah satu teknologi pengeringan yang dapat
diterapkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk tetap dapat
mempertahankan gizinya, banyak jenis buah-buahan dan sayuran yang dapat
diproses dengan penggorengan vakum, seperti buncis muda, brokoli, kembang
kol, wortel, nenas, mangga, apel, dan sebagainya. Beberapa negara di Asia
(Jepang, Thailand, Taiwan) telah menggunakan teknologi penggorengan vakum
ini untuk memproduksi snack bergizi dan menyehatkan dari sayur-sayuran
(Widaningrum, 2008).
Penggorengan vakum merupakan cara pengolahan yang tepat untuk
menghasilkan kripik buah-buahan dengan mutu tinggi. Dengan teknologi ini
buah-buahan yang melimpah dan terbuang pada saat musim buah, dapat
dimanfaatkan sehingga tetap memiliki harga jual tinggi. Cara menggoreng dengan
menggunakan penggoreng vakum (hampa udara), akan menghasilkan kripik
dengan warna dan aroma buah asli serta rasa lebih renyah. Kerenyahan tersebut
diperoleh karena proses penurunan kadar air dalam buah terjadi secara berangsur-
angsur.
Untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus dalam artian
warna, aroma, nilai nutrisi dan rasa buah-sayur tidak berubah dan renyah maka
pengaturan suhu yang digunakaan tidak boleh melebihi 85 oC dan tekanan vakum
antara 65 – 76 cmHg. Proses penggorengannya dapat berlangsung pada suhu
rendah, disamping kedap udara sehingga tidak bersinggungan dengan udara yang
dapat menimbulkan pencoklatan pada produk yang dihasilkan karena proses
oksidasi (Anonim, 2007). Gambar vacuum fryer ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Vacuum fryer
Keterangan gambar :

1. Pompa Vakum Water jet, berfungsi untuk menghisap udara di dalam ruang
penggoreng sehingga tekanan menjadi rendah, serta untuk menghisap uap air
bahan.
2. Tabung Penggoreng, berfungsi untuk mengkondisikan bahan sesuai tekanan
yang diinginkan. Di dalam tabung dilengkapi keranjang buah setengah
lingkaran.
3. Kondensor, berfungsi untuk mengembunkan uap air yang dikeluarkan selama
penggorengan. Kondensor ini menggunakan air sebagai pendingin.
4. Unit Pemanas, menggunakan kompor gas LPG.
5. Unit Pengendali Operasi (Boks Kontrol), berfungsi untuk mengaktifkan alat
vakum dan unit pemanas.
6. Bagian Pengaduk Penggorengan, berfungsi untuk mengaduk buah yang berada
dalam tabung penggorengan. Bagian ini perlu sil yang kuat untuk menjaga
kevakuman tabung.
7. Mesin pengering (spinner), berfungsi untuk meniriskan keripik.
Sejauh ini beberapa jenis buah yang sudah umum dibuat keripik dengan
menggunakan penggorengan vakum adalah pisang, apel, kentang, kentang,
pepaya, melon, mangga, nanas, dan sebagainya. Untuk produk buah dan sayuran
lainnya masih perlu dilakukan penelitian. Keuntungan penggorengan vakum
dibandingkan dengan penggorengan konvensional adalah warna buah atau sayur
relatif tidak berubah, lebih renyah, tampil lebih menarik dan rasa lebih enak.
Produk inilah yang disukai konsumen (Widaningrum, 2008).

Gambar 3. Skema susunan sistem peralatan penggorengan vakum
Keterangan : 1. Tabung/tangki penggorengan 6. Drum air
2. Kotak panel kontrol 7. Tabung gas elpiji
3. Kondensor 8. Pompa air
4. Penampung kondensat 9. Keranjang bahan
5. Pompa vakum
(Siregar, Halomoan P, Dadang D. Hidayat dan Sudirman, 2004).
Spesifikasi mesin penggoreng vakum (vacuum frying):
Merk : Reksa
Type : RK-07 VF
Ruang penggoreng : 0,185 M3
System penggoreng : Diskontinyu
Bahan : Plat stainless steel
Kapasitas : 7,5 kg bahan masuk
Sistem pemanas : Elemen heater 3000 W
Wadah bahan : Plat stainless steel berlubang
Volume minyak : 105 L
Penerangan : lampu 50 Watt/12 Volt
Pengadukan : manual
Sensor suhu : Thermocontrol
Sistem vakum

Pompa : 1000 Watt/220 Volt
Jumlah injector : 15 buah
Sistem sirkulasi : kontinyu
Sistem pendinginan
Dimensi bak : 600 x 1200 x 1800 mm
Pendinginan : kondensor dengan air sebagai medium pendingin
Pengatusan minyak (Spiner)
Dimensi centrifuge : 500 x 600 x 600 mm
Motor : 0,25 PK
Putaran : 400 rpm
Cara kerja mesin penggorengan vakum:
1. Mengatur control suhu sesuai dengan suhu penggorengan yang digunakan
2. Menekan tombol power untuk menghidupkan mesin penggoreng vakum
3. Memasukkan sampel yang telah dikupas ke dalam keranjang yang ada pada
ruang penggorengan dan menutup rapat ruang penggoreng
4. Setelah mencapai suhu yang dikehendaki, pompa vakum mulai dihidupkan
5. Pada tekanan 70-76 cmHg, mulai dilakukan penggorengan dengan
menggerakkan tuas keranjang sehingga bahan terendam minyak goring
6. Setelah mencapai waktu yang dikehendaki keranjang yang ada dalam ruang
penggoreng diangkat dengan menggerakkan tuas. Tutup ruang penggoreng
dibuka dan bahan diambil selanjutnya dimasukkan dalam centrifuge untuk
meniriskan minyak
2.4 Air Dalam Bahan Pangan
Air dalam bahan pangan memiliki peranan yang sangat penting karena air
merupakan sumber nutrient seperti bahan makanan lainnya dan keberadaan air
sanagt penting untuk keberlangsungan proses biokimiawi organism hidup. Air
yang terdapat dalam bahan pangan sangat berperan penting yaitu berfungsi untuk
membentuk tekstur bahan pangan, cita rasa dan kesegaran bahan pangan. Air
dalam bahan pangan terdapat dalam :

a. Air bebas, terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan interglanular dan pori-pori
yang terdapat pada larutan
b. Air yang terikat secara lemah karena terserap (teradsorpsi) pada permukaan
koloid makromolekular seperti protein, pectin pati dan sellulosa, selain itu juga
terdispersi diantara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat-zat yang ada
dal;am sel. Air merupakan pelarut zat-zat yang ada dalam sel. Air yang ada
dalam bentuk ini masih mempunyai sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada
proses pembekuan. Ikatan antara air dengan koloid tersebut merupakan ikatan
hydrogen.
c. Air dalan keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat, ikatan bersifat
ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan.
Fungsi air dalam bahan pangan adalah sebagai :
a. Air dapat mempengaruhi penampakan tekstur serta cita rasa makanan
b. Air dalam bahan makanan menentukan kesegaran dan daya bahan makanan
c. Kerusakan bahan makanan dapat ditentukan oleh kandungan air yang ada
dalam bahan makanan, seperti pembusukan bahan pangan oleh mikroba.
d. Air dalam bahan makanan menentukan komposisi yang dapat menentukan
kualitas bahan makanan tersebut.
Faktor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan mutu produk pangan
adalah perubahan kadar air dalam produk. Aktivitas air (aw) berkaitan erat dengan
kadar air, yang umumnya digambarkan sebagai kurva isotermis, serat
pertumbuhan bakteri, jamur dan mikroba lainnya. Makin tinggi aw pada umumnya
makin banyak bakteri yang dapat tumbuh, sementara jamur tidak menyukai aw
yang tinggi (Christian 1980 dalam Herawati 2008). Mikroorganisme menghendaki
aw minimum agar dapat tumbuh dengan baik, yaitu untuk bakteri 0,90, khamir
0,80-0,90 dan kapang 0,60-0,70 (Winarno, 1992 ).
Prabhakar dan Amia (1978) dalam Herawati (2008) menyatakan bahwa
pada aw yang tinggi, oksidasi lemak berlangsung lebih cepat dibanding pada aw
rendah. Kandungan air dalam bahan pangan selain mempengaruhi perubahan
kimia juga ikut menentukan kandungan mikroba pada pangan, begitu pula dengan
penghilangan (pengeringan) dan pembekuan air (deMan, 1997). Penghilangan

kandungan air dari dalam bahan pangan merupakan salah satu prinsip dasar
pengawetan bahan pangan dengan cara pengeringan yang dapat dilakukan secara
sederhana melalui penjemuran sinar matahari atau menggunakan alat bantu seperti
vacuum frying atau dengan sistem penggorengan deep frying, yang pada intinya
adalah penghilangan kadar air untuk proses pengawetan sehingga menghambat
pertumbuhan mikroba pembusuk dan memperpanjang umur simpang bahan
pangan tersebut.
Kadar air merupakan persentase kandungan air dalam suatu bahan, dapat
dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) dan berat kering (dry basis). Kadar
air dalam berat basah batas maksimum teoritis adalah < 100% sedang kadar air
berat kering batas maksimumnya > 100%. Kadar air setimbang adalah kadar air
bahan pada kondisi tekanan uap bahan sama dengan tekanan uap air pada
lingkungannya pada suhu dan kelembaban konstan.
Analogi dengan hokum pendinginan Newton dengan analisis pengering.
Dengan asumsi bahwa laju kehilangan lengas dari bijian yang dikelilingi udara
pengering sebanding dengan perbedaan antara kadar air bijian dan kadar air
setimbang, maka dapat dinyatakan:
dM/dt = K (M-Me)
dengan menggunakan kondisi awal dan kondisi batas Mo untuk t = 0 dan Mt
untuk t > 0 maka persamaannya menjadi:
M t−Me
M o−Me = e−k xt
nilai (Mt - Me)/(Mo – Me) disebut nisbah lengas atau moisture ratio (MR) dimana
Mt adalah kadar air bahan pada penggorengan selama t menit, Mo adalah kadar
air awal bahan, Me adalah kadar air setimbang Kx adalah konstanta laju
penurunan kadar air bahan dan t adalah waktu penggorengan (menit).
Kadar air setimbang adalah kadar air bahan pada kondisi tekanan uap
bahan sama dengan tekanan uap air pada lingkungannya pada suhu dan
kelembaban konstan. Pada kasus ini kadar air setimbang (Me) = 0, maka:
lnM t
M o
=−K x t

2.5 Penggorengan Bahan Pangan
Penggorengan merupakan salah satu metode preparasi bahan pangan yang
penting. Penggorengan adalah proses pemberian panas terhadap suatu bahan
dengan media pengantar berupa minyak. Penggorengan merupakan operasi yang
digunakan untuk mengubah mutu bahan pangan agar layak dikonsumsi. Selain itu
penggorengan mempunyai efek pengawetan yang disebabkan oleh terjadinya
perusakan mikrobia dan enzim karena pengaruh pemanasan serta penurunan
aktivitas air (aw) pada bahan.
Penggorengan dengan system gangsa dilakukan dengan menggunakan pan
yang berbentuk datar atau sedikit cekung dan hanya sedikit minyak goreng yang
dibutuhkan, sehingga tidak sampai merendam bahan pangan yang digoreng. Suhu
pemanasan yang dipakai system deep frying (Ketaren, 1986).
Penetrasi panas dari minyak goring ke dalam bahan pangan menyebabkan
bahan pangan menjad masak. Selama penggorengan akan terjadi penguapan air
dalam bahan panga, pembentukan kerak serta dekomposisi minyak akibat
berserap dan mengisi ruang komposisi ruang kosong dalam bahan pangan yang
berisi air (Weiss, 1970).
Selama penggorengan air yang ada dalam bahan akan diuapkan. Uap yang
keluar dari bahan naik ke permukaan minyak dan tampak mendidih. Jika suhu
internal lebih dari 100oC penguapan menjadi intensif dan mampu mengeringkan
bahan. Setelah bahan menjadi kering kenaikan suhu pada permukaan bahan akan
menyebabkan warna coklat dan efek renyah sampai batas tertentu tergantung pada
lama penggorengan.
Jaringan dinding sel dalam kentang mentah tetap merupakan structural
pada produk akhir. Disolusi lamella tengah yang terjadi selama proses
penggorengan akan menyebabkan kenaikan angka keretakan dan terjdai rongga
yang dapat terjadi juga di bawah permukaan untuk kemudian membentuk suatu
pembengkakan vesikuler atau terjadi pelepuhan dan menyebabkan bahan menjadi
renyah.

Heid (1967) menyatakan bahwa perubahan spesifik yang terjadi selama
penggorengan adalah:
1. Evaporasi air
2. Kenaikan suhu produk pada tingkat yang diinginkan
3. Kenaikan suhu permukaan untuk mendapatkan warna kuning keemasan dan
efek yang dihasilkan
4. Perubahan dimensional produk yang dihasilkan.
Pindah panas adalah perpindahan energy kalor dari suatu zat ke zat yang
lain untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan sewaktu
proses berlangsung. Pada saat proses berlangsung terjadi dua jenis kondisi yaitu,
(1) mencapai kedaan yang dibutuhkan untuk pengerjaan pada suhu tertentu
dengan jalan pemasukan dan pengeluaran kalor, (2) mempertahankan keadaan
yang dibutuhkan untuk operasi proses, misalnya pada pengerjaan eksoterm dan
endoterm. Kalor atau panas mengalir dengan sendirinya dari suhu yang tinggi ke
suhu yang rendah. Secara umum pindah panas dapat terjadi secara konduksi,
konveksi dan radiasi. Pindah panas secara konveksi ialah pergerakan energy kalor
dari zat yang mempunyai suhu yang tinggi menuju ke zat yang suhunya rendah
pada medium zat cair. Konduksi ialah perpindahan energy kalor yang sering
terjadi pada benda padat sebagai media penghantar panas yang baik misalnya
terjadi pada logam yang dipanaskan,; Radiasi adalah perpindahan energy kalor
atau panas melalui gelombang dari suatu zat ke zat lainnya.
2.6 Minyak
Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada
golongan lipid , yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut
dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar,misalnya dietil eter
(C2H5OC2H5), Kloroform (CHCl3), benzena dan hidrokarbon lainnya, lemak dan
minyak dapat larut dalam pelarut yang disebutkan di atas karena lemak dan
minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut.

Pada bidang pengolahan pangan lemak dan minyak merupakan media
penghantar panas yang baik, seperti minyak goreng dan margarine. Bahan-bahan
dan senyawa kimia akan mudah larut dalam pelarut yang sama polaritasnya
dengan zat terlarut . Tetapi polaritas bahan dapat berubah karena adanya proses
kimiawi. Misalnya asam lemak dalam larutan KOH berada dalam keadaan
terionisasi dan menjadi lebih polar dari aslinya sehingga mudah larut serta dapat
diekstraksi dengan air. Ekstraksi asam lemak yang terionisasi ini dapat dinetralkan
kembali dengan menambahkan asam sulfat encer (10 N) sehingga kembali
menjadi tidak terionisasi dan kembali mudah diekstraksi dengan pelarut non-
polar. Lemak dan minyak merupakan senyawa trigliserida atau triasgliserol, yang
berarti “triester dari gliserol” . Jadi lemak dan minyak juga merupakan senyawaan
ester. Hasil hidrolisis lemak dan minyak adalah asam karboksilat dan gliserol .
Asam karboksilat ini juga disebut asam lemak yang mempunyai rantai
hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang.
Minyak goreng
Minyak goreng selain berfungsi sebagai penghantar panas juga berfungsi
sebagai penambah cita rasa dan kalori bahan pangan. Mutu minyak goreng
ditentukan oleh titik asapnya yaitu suhu pemanasan minyak sampai ternbentuk
akrolein yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada
tenggorokan. Makin tinggi titik asap, makin baik mutu minyak goreng tersebut.
Titik asap suatu minyak goreng tergantung dari kadar gliserol bebas.
2.7 Penggaraman dan penambahan kapur
Penggaraman merupakan salah satu cara pengawetan yang sudah lama
dilakukan orang. Garam dapat bertindak sebagi pengawet karena garam akan
menarik air dari bahan sehingga mikroorganisme pembusuk tidak dapat
berkembang biak karena menurunnya aktivitas air (aw). Selain itu proses
penggaraman dapat menghindari reaksi pencoklatan. Pada proses penggaram
digunakan serbuk garam kira-kira 10% dari berat bahan dan larutan garam

berkonsentrasi 10%. Bahan dan serbuk garam disusun dalam wadah khusus
seperti stoples secara berlapis-lapis.
Buah setelah dikupas akan berubah warna menjadi coklat atau kehitaman.
Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia dari asam pada buah dengan udara yang
dikenal dengan reaksi pencoklatan (browning enzimatis). Untuk menghindari hal
tersebut, buah yang sudah dikupas sesegera mungkin direndam dengan air garam
yang dapat melindungi buah dari reaksinya dengan udara. Reaksi pencoklatan
lebih lanjut dari buah yang sudah direndam dalam larutan gula biasanya dilakukan
proses sulfuring. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan warna dan cita rasa,
asam askorbat (vitamin C) dan vitamin A. Selain itu sebagai bahan pengawet
kimia untuk menurunkan atau menghindari kerusakan oleh jasad renik sehingga
dapat mempertahankan mutu manisan selama penyimpanan. Perendaman dalam
larutan garam bertujuan untuk membentuk daging buah yang kompak karena
garam dapat menarik air dari bahan sehingga kadar air berkurang dalam bahan.
Perendaman dalam larutan kapur beberapa saat dilakukan untuk membuat
bahan pangan seperti buah tetap renyah. Hal ini disebabkan oleh kalsium yang
masuk ke dalam jaringan buah.

3 METODE PRAKTIKUM
3.1 Bahan Praktikum
Bahan praktikum yang digunakan dibagi menjadi bahan baku yang terdiri
atas nangka dan nenas yang diperoleh dari pasar tradisional di Yogyakarta. Bahan
lain yang digunakan dalam praktikum ini adalah garam, kapur, minyak goreng,
dan air mineral.
3.2 Alat Praktikum
Alat yang digunakan pada praktikum ini meliputi Neraca Analitis (G
1500-DO Ohaus Scale Type HR 300 Florham Park, USA), seperangkat Vacuum
frying, seperangkat Deep frying, seperangkat universal testing machine merk
Zwick/Z0.5, baskom, pisau, oven, Lovibond Tintometer model F, Infra Red
Moisture Tester.
3.3 Jalannya Praktikum
Praktikum dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap penggorengan dan
tahap analisis mutu produk hasil penggorengan. Parameter analisis yang dilakukan
terhadap produk keripik nangka dan nenas yang diolah dengan menggunakan
metode vacuum frying dan deep frying meliputi kadar air dengan metode
thermogravimetri, analisis tekstur dengan Zwick/Z0.5, analisis kadar minyak
menggunakan metode Soxhlet, analisis warna dengan Lovibond Tintometer, dan
uji sensoris berdasarkan tingkat kesukaan.
3.4. Pengumpulan Data
Perlakuan yang digunakan pada praktikum Deep Frying ini ada 8
kombinasi yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Praktikum Deep Frying dan Pembagian Tugas Kelompok
Sampel Temperatur Waktu Kelompok PelaksanaanNangka 140oC 10 menit 1 1 November 2011Nangka 150oC 10 menit 2 1 November 2011Nangka 140oC 15 menit 3 1 November 2011Nangka 150oC 15 menit 4 1 November 2011Nanas 150oC 15 menit 5 27 Oktober 2011Nanas 140oC 15 menit 6 27 Oktober 2011Nanas 150oC 10 menit 7 27 Oktober 2011Nanas 140oC 10 menit 8 27 Oktober 2011
Perlakuan yang digunakan pada praktikum Vacuum Frying ini ada 8
kombinasi yang disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Kombinasi Perlakuan Praktikum Vacuum Frying dan Pembagian Tugas Kelompok
Sampel Temperatur Pressure Kelompok PelaksanaanNangka 80oC -60 cmHg 1 1 November 2011Nangka 90oC -60 cmHg 2 1 November 2011Nangka 80oC -70 cmHg 3 1 November 2011Nangka 90oC -70 cmHg 4 1 November 2011Nanas 90oC -70 cmHg 5 27 Oktober 2011Nanas 80oC -70 cmHg 6 27 Oktober 2011Nanas 90oC -60 cmHg 7 27 Oktober 2011Nanas 80oC -60 cmHg 8 27 Oktober 2011
3.5. Prosedur Pratikum
Penggorengan dengan deep fryer
- Buah Nanas yang akan digoreng sebelumnya dikupas, dibersihkan,
dibuang empulurnya, dicuci dengan air mengalir, ditiriskan, kemudian
diiris dengan ketebalan 2-3 mm. Irisan buah nanas tadi, kemudian
direndam dengan larutan kapur 1% dan larutan garam 1%, kemudian
ditiriskan.
- Buah Nangka yang akan digoreng sebelumnya dikupas dari kulit
luarnya, dibuang bijinya, dicuci dengan air mengalir, kemudian
dipotong menjadi dua bagian dengan potongan secara vertikal. Irisan

buah nangka tadi, kemudian direndam dalam larutan kapur 1% dan
larutan garam 1%, kemudian ditiriskan.
- Minyak goreng sebanyak 5 liter yang akan digunakan telah
dipanaskan sampai dengan suhu yang akan dicobakan dalam bejana
deep fryer. Apabila minyak goreng tersebut telah mencapai suhu yang
diinginkan maka potongan Nanas dan Nangka tersebut dimasukkan
dalam keranjang penggorengan untuk selanjutnya dicelupkan dalam
minyak panas perlahan-lahan. Kemudian mulai dihitung waktu
pemanasan dengan variasi waktu penggorengan selama menit, menit
dan menit dan variasi suhu 150˚C, 160˚C, 170˚C.
Penggorengan dengan vacuum fryer
- Buah Nanas yang akan digoreng sebelumnya dikupas, dibersihkan,
dibuang empulurnya, dicuci dengan air mengalir, ditiriskan, kemudian
diiris dengan ketebalan 2-3 mm. Irisan buah nanas tadi, kemudian
direndam dengan larutan kapur 1% dan larutan garam 1%, kemudian
ditiriskan.
- Buah Nangka yang akan digoreng sebelumnya dikupas dari kulit
luarnya, dibuang bijinya, dicuci dengan air mengalir, kemudian
dipotong menjadi dua bagian dengan potongan secara vertikal. Irisan
buah Nangka tadi, kemudian direndam dalam larutan kapur 1%,
kemudian ditiriskan.
- Tahapan penggorengan meliputi penyiapan alat penggoreng sistem
hampa/vakum dengan menuangkan minyak ke dalam tabung
penggoreng hingga 16 liter dan mengisi bak hingga sekitar 2 cm dari
permukaan. Kemudian tutup tangki dibuka dan keranjang
penggorengan diangkat dengan memutar engkol ke bawah dan dislot
sehingga posisi keranjang berada di atas minyak. Minyak goreng tidak
dapat digunakan untuk Nanas dan Nangka secara bersamaan, hal ini
untuk menghindari perubahan rasa dari keripik yang digoreng.

- Semua valve dicek dan dipastikan dalam keadaan posisi tertutup serta
selang gas sudah terpasang sempurna. Selanjutnya pengontrol suhu
dinyalakan dengan memencet tombol power kemudian ditunggu
sampai di display suhu muncul angka sekitar 29oC hingga 30oC (suhu
ruang) lalu pengontrol suhu disetel pada suhu yang diinginkan yaitu
70˚C, 80˚C, 90˚C dengan memencet tanda atau .
- Setelah itu menghidupkan kompor dan membiarkannya hingga suhu
pada pengontrol stabil menunjukkan suhu 70oC. Lalu irisan buah segar
dimasukkan keranjang bahan yang berada dalam tabung penggoreng
kemudian tabung ditutup rapat. Pada posisi keranjang masih di atas
(engkol di bawah), pompa dihidupkan sampai tekanan mencapai -72
cm Hg dan suhu menunjukkan angka yang diinginkan. Slot ditarik dan
engkol diputar ke atas sehingga posisi keranjang terendam minyak.
Kran pembuangan dari tangki pendingin dibuka.
- Untuk memastikan bahan sudah berada dalam minyak, dapat dilihat
dari kaca pada tutup tabung maka terlihat gelembung air dalam minyak
yang masih banyak dan bergejolak hebat, keadaan demikian
menandakan bahwa Nanas/Nangka belum kering. Setiap 10 menit
engkol diputar ke depan dan ke belakang dengan arah ½ lingkaran
sebanyak ± 4 kali dengan tujuan untuk mengaduk bahan selama
penggorengan. Berakhirnya penggorengan dapat ditandai oleh tidak
adanya gelembung dalam minyak sehingga minyak tidak bergejolak
lagi dengan dilihat melalui kaca. Pada umumnya setiap satu kali proses
penggorengan membutuhkan waktu 30-45 menit, pada praktikum ini
akan digunakan variasi waktu dan menit.
- Sesudah penggorengan dianggap selesai, pompa dimatikan, tekanan
dikembalikan pada kondisi normal yaitu tekanan 1 atmosfir kemudian
tutup dibuka, keranjang bahan dinaikkan ke atas minyak dan keranjang
dibuka kemudian keripik dikeluarkan.

3.2 Tempat Praktikum
Praktikum ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan
Desember 2010 di laboratorium KBP dan laboratorium Rekayasa Fakultas
Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
IV.1Kadar Air
Perlakuan Berat botol
Berat sampel
B + S
(B + S)'
KA (wb)
KA (wb)
(B) (S)
Deep Frying
140oC, 10 menit
9.77 2.11911.9 10.876 47.7
46.69475
8.64 2.02610.7 9.7412 45.7
140oC, 15 menit
8.61 2.00510.6 9.7372 43.8 43.36555
8.52 2.03310.6 9.6793 42.9
150oC, 10 menit
9.01 2.17311.2 10.302 40.5 40.7819
8.65 2.08310.7 9.8788 41.1
150oC, 15 menit
9.89 2.26912.2 11.287 38.3 38.92295
9.88 2.18612.1 11.202 39.6
Vacuum Frying
800C, -60 mmHg
9.76 2.04911.8 11.415 19.1
18.8426
9.84 2.0411.9 11.503 18.6
800C,-70 mmHg
8.15 2.00610.2 9.8003 17.6
17.69195
8.88 2.00810.9 10.533 17.8

900C, -60 mmHg
9.13 2.03211.2 10.907 12.5
12.2877
9.79 2.11811.9 11.652 12.1
900C, - 70 mmHg
9.58 2.03111.6 11.402 10.1
10.40095
10 2.03612.1 11.833 10.7
Untuk menentukan kadar air bahan dilakukan dengan metode gravimetric.
Dalam hal ini kadar air ditentukan tiap rentang waktu tertentu. Kadar air yang
digunakan adalah kadar air basis basah (wet basah/wb) dengan rumus:
Ka (wb )=berat awal−berat ak h irberat awal
x100 %
Berdasarkan penghitungan kadar air basis basah didapatkan nilai rata-rata
kadar air kadar kentang pada Tabel 7.
Tabel 7. Kadar air rata-rata keripik kentang
Penggorengan Ketebalan irisan (mm) Lama perendaman (menit) Kadar air (%wb)
Vacuum
1 20 17,8799d1 30 15,5260c1 40 16,6351c2 20 9,3186a2 30 9,0821a2 40 9,3934a3 20 18,4957e3 30 13,5402b3 40 12,9984b
Deep 1 20 20,1048g1 30 20,0322g1 40 19,6501fg2 20 18,7439e2 30 19,7652fg2 40 19,9836g

3 20 19,2931f3 30 22,5277h3 40 22,3119h
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata pada α 5%
Berdasarkan hasil pengujian kadar air keripik kentang diperoleh bahwa
parameter kadar air memberikan hasil yang berbeda nyata pada keripik kentang
dengan perlakuan ketebalan irisan dan lama perendaman. Akan tetapi, perlakuan
deep frying dengan lama perendaman 30 menit dan 40 menit dengan masing-
masing ketebalan irisan 3 mm tidak berbeda nyata. Perlakuan dengan kode 493
dengan 794 dapat dilihat perbedaan yang sangat nyata. Hal ini disebabkan karena
luas permukaan atau tingkat ketabalan irisan kentang 493 adalah 1 mm,
sedangkan 794 memiliki tingkat ketebalan irisan 3 mm.
Berdasarkan hasil pengamatan kadar air selama proses penggorengan salak
dengan metode vacuum frying dan deep frying diperoleh Tabel 8. Secara umum,
bentuk irisan memberikan perbedaan kandungan kadar air pada keripik salak.
Tabel 8. Kadar air rata-rata keripik salak
Penggorengan Bentuk irisan Lama perendaman (menit) Kadar air (% wb)
Vacuum
vertikal 20 20,1048jvertikal 30 19,9877jvertikal 40 18,7833i
horisontal 20 18,4876hhorisontal 30 17,8799ghorisontal 40 16,8880f
belah samping 20 9,0133dbelah samping 30 7,9631bbelah samping 40 7,5303a
Deep
vertikal 20 27,1695pvertikal 30 26,9575overtikal 40 26,6122n
horisontal 20 26,0127mhorisontal 30 25,8726lhorisontal 40 25,4764k
belah samping 20 9,2096ebelah samping 30 9,0821debelah samping 40 8,6030c
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata pada α 5%

Tabel 7 dan Tabel 8 menyatakan bahwa selama proses penggorengan
kentang dan salak terjadi perubahan kadar air. Hal ini terjadi karena kandungan air
bahan menguap. Semakin lama penggorengan jumlah air yang diuapkan semakin
banyak, sehingga kadar air semakin kecil. Pada penggorengan kentang kadar air
menurun dengan stabil. Selain itu, luas permukaan atau ketebalan bahan yang
digoreng mempengaruhi tingkat kecepatan air yang menguap.
Kandungan air dalam bahan pangan selain mempengaruhi perubahan
kimia juga ikut menentukan kandungan mikroba pada pangan, begitu pula dengan
penghilangan (pengeringan) dan pembekuan air (deMan, 1997). Penghilangan
kandungan air dari dalam bahan pangan merupakan salah satu prinsip dasar
pengawetan bahan pangan dengan cara pengeringan yang dapat dilakukan secara
sederhana melalui penjemuran sinar matahari atau menggunakan alat bantu seperti
vacuum frying atau dengan sistem penggorengan deep frying, yang pada intinya
adalah penghilangan kadar air untuk proses pengawetan sehingga menghambat
pertumbuhan mikroba pembusuk dan memperpanjang umur simpang bahan
pangan tersebut.
IV.2Tekstur
Pembuatan keripik salak dan keripik kentang dilakukan dengan beberapa
perlakuan dan kondisi. Pada pembuatan keripik salak, perlakuan yang divariasikan
adalah meliputi cara pemotongan (vertikal, horisontal dan belah samping) dan
lama perendaman salak dengan menggunakan larutan kapur (20, 30 dan 40 menit).
Sedangkan pada pembuatan keripik kentrang, perlakuan yang divariasikan adalah
meliputi ketebalan pengirisan (1, 2 dan 3 mm) dan lana perendaman kentang
menggunakan larutan kapur (20, 30 dan 40 menit).
Pembuatan keripik salak dan kentang diawali dengan perendaman salak
dan kentang pada larutan kapur pada lama waktu perendaman yang berbeda, yaitu
20, 30 dan 40 menit. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap
tekstur keripik salak dan kentang (Tabel 9 dan Tabel 10). Berdasartkan hasil yang
didapatkan (Tabel 9), terlihat bahwa semakin lama perendaman salak pada larutan

kapur akan meningkatkan gaya tekan terhadap salak yang telah direndam. Hal
tersebut terjadi pula pada salak yang telah menjadi keripik baik melalui proses
vacuum frying maupun deep frying dimana gaya tekan pada keripik salak menjadi
lebih besar seiring lama perendaman salak pada larutan kapur (berkisar antara
(4,90 sampai 63,30 N untuk vacuum frying dan 0,46 sampai 17,51 N untuk deep
frying). Semakin besarnya gaya tekan yang diberikan pada salak setelah direndam
maupun pada keripik salak menandakan bahwa semakin lama perendaman maka
tekstur keripik makin keras.
Tabel 9. Data pengukuran dengan menggunakan UTM keripik kentang
Ketebalan(mm)
Lama perendaman
(menit)
I II
Sebelum vacuum frying
Setelah vacuum frying
Sebelum deep frying
Setelah deep frying
Tinggi (mm)
Gaya (N)
Tinggi (mm)
Gaya (N)
Tinggi (mm)
Gaya (N)
Tinggi (mm)
Gaya (N)
120 4,24 2,49 7,54 1,63 4,24 2,49 7,48 2,9630 13,23 2,89 9,08 2,23 13,23 2,89 11,96 3,9440 13,09 19,08 23,76 6,97 13,09 19,08 17,41 4,99
220 5,78 192,08 8,60 10,71 5,78 192,08 9,36 4,6930 5,88 194.75 9,26 13,15 5,88 194.75 10,84 9,4740 5,94 218,81 15,47 14,65 5,94 218,81 17,72 20,98
320 6,27 123,10 11,42 18,08 6,27 123,10 13,56 12,2430 6,81 277,42 15,85 13,54 6,81 277,42 14,89 14,2540 6,92 267,33 16,99 27,32 6,92 267,33 16,38 23,07
Pemotongan Lama perendaman
(menit)
I IISebelum vacuum
fryingSetelah vacuum
fryingSebelum deep
fryingSetelah deep
fryingTinggi (mm)
Gaya (N)
Tinggi (mm)
Gaya (N)
Tinggi (mm)
Gaya (N)
Tinggi (mm)
Gaya (N)
Vertikal203040
4,2410,7711,92
19,0834,8769,22
8,429,4814,86
22,5827,6334,98
4,2410,7711,92
19,0834,8769,22
7,0411,9311,43
0,957,4917,51
Horizontal203040
13,3716,2418,92
93,92112,08180,60
9,8010,8213,73
4,9040,4263,30
13,3716,2418,92
93,92112,08180,60
12,7010,369,98
16,729,800,46
Belah samping
203040
12,6712,9514,37
57,7374,29107,00
6,3812,8719,7
17,1718,2829,00
12,6714,3714,37
57,73107,00107,00
9,1516,6819,88
7,798,5315,02

Tabel 10. Data pengukuran dengan menggunakan UTM keripik salak
Hasil yang sama juga terjadi pada keripik kentang (Tabel 10) dimana
gaya tekan pada keripik kentang berkisar antara 1,63 sampai 27,32 N untuk
vacuum frying dan 2,96 dan 23,07 N untuk deep frying. Penanganan dengan
pemberian larutan kapur dapat mempertahankan rasa dan tekstur. Tekstur buah
menjadi lebih keras, sehingga terjadinya transpirasi maupun respirasi dapat
ditekan (Soritua, 2010).
Metode pembuatan keripik salak maupuk kentang dengan menggunakan
metode vacuum frying dan deep frying ternyata juga menghasilkan tekstur yang
berbeda. Keripik salak maupun kentang hasil vacuum frying memiliki tekstur
yang lebih keras dibandingkan dengan menggunakan metode deep frying. Hal
tersebut terjadi karena pada proses vacuum frying selain menggoreng dengan
minyak, terjadi suatu proses penyedotan uap air dengan pompa sehingga produk
keripik yang dihasilkan lebih kering dengan tekstur yang lebih keras (Anonim,
2008).
Perbedaan arah pemotongan salak pada pembuatan keripik salak pun
menghasilkan efek tekstur keripik salak yang berbeda (Tabel 9). Pada keripik
salak hasil vacuum frying, tingkat tekstur yang paling keras (dengan rerata gaya
tekan yang paling tinggi sebesar 36,20 N) terjadi pada keripik salak yang dipotong
secara horisontal. Sedangkan tekstur yang paling keras pada keripik salak hasil
deep frying adalah pada arah pemotongan secara belah samping dengan rerata
gaya tekan sebesar 10,45 N.
Pada keripik kentang yang dihasilkan dengan perbedaan ketebalan
kentang menghasilkan tekstur yang berbeda. Berdasarkan hasil yang didapat,
terlihat bahwa keripik kentang dengan metode vacuum frying maupun deep frying
yang memiliki tekstur paling keras adalah pada keripik kentang dengan ketebalan
pemotongan 3 mm (rerata gaya tekan 19,65 N untuk vacuum frying dan 16,52 N
untuk deep frying). Proses pengirisan harus menghasilkan potongan yang bersih
dan rata. Potongan yang bersih menyerap minyak lebih sedikit saat digoreng dan

hasil gorengan tidak terlihat oily (berminyak) (Adicahyadi, 2008). Hasil yang ada
menunjukkan dengan metode vacuum frying dimana penyerapan minyaknya lebih
sedikit dibandingkan deep frying menghasilkan tekstur keripik yang lebih keras
dan tidak terlalu berminyak.
Secara keseluruhan, pemotongan keripik salak horisontal dengan lama
perendaman pada larutan kapur selama 40 menit untuk metode vacuum frying dan
pemotongan keripik salak vertikal dengan lama perendaman pada larutan kapur
selama 40 menit untuk metode deep frying memiliki tekstur yang lebih keras
dibandingkan perlakuan lainnya. Sefdangkan pada keripik kentang, tekstur yang
paling keras diantara perlakuan yang ada ialah keripik dengan ketebalan
pemotongan 3 mm direndam pada larutan kapur selama 40 menit untuk metode
vacuum frying maupun deep frying.
Pembuatan kerpik kentang dengan metode vacuum frying dan deep frying
menghasilkan produk keripik kentang yang berbeda dilihat dari segi teksturnya
secara sensoris. Parameter yang diuji berupa tekstur dengan bantuan 15 panelis
untuk menilai teksur dari keripik kentang yang dihasilkan. Berdasarkan hasil
analisis statistiknya, terlihat bahwa tekstur dari keripik kentang yang diolah secara
vacuum frying berbeda dengan keripik kentang yang diolah dengan deep frying.
Faktor yang mempengaruhi perbedaan tekstur tersebut dikarenakan suhu
penggorengan pada kedua metode tersebut berbeda. Selain itu, perlakuan vakum
(kedap udara) akan lebih membuat keripik kentang menjadi lebih keras karena
kadar airnya lebih banyak dikurangi dibandingkan dengan keripik kentang dengan
deep frying.
Perbedaan ketebalan irisan kentang pada pembuatan keripik kentang
mempengaruhi tingkat kesukaan pada keripik kentang yang dihasilkan. Hal
tersebut terlihat dengan hasil analisis statistik yang memperlihatkan ketebalan
keripik 1 mm berbeda secara signifikan terhadap keripik kentang yang memiliki
ketebalan 2 dan 3 mm. Semakin banyak perbedaan ketebalan irisan keripik
kentang akan mempengaruhi produk keripik kentang yang dihasilkan.
Lama perendaman pada keripik kentang yang menggunakan larutan kapur
tidak memiliki pengaruh yang berbeda nyata secara signifikan terhadap tekstur

produk keripik kentang yang dihasilkan secara statistik dari tingkat kesukaan
panelis. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan lama waktu perendaman
keripik dengan larutan kapur tidak akan mempengaruhi tingkat kesukaan sensoris
terhadap tekstur keripik kentang yang dihasilkan.
Secara keseluruhan uji sensoris pada keripik salak yang dihasilkan dengan
metode vacuum maupun deep frying menghasilkan tingkat kesukaan yang berbeda
pada tekstur keripik salak. Hal ini dapat disebabkan dengan adanya perbedaan
suhu penggorengan dan ada tidaknya perlakuan vakum pada proses pengolahan
keripik salak.
Perbedaan cara pemotongan atau irisan pada keripik salak secara sensoris
tidak berpengaruh signifikan terhadap tekstur keripik salak yang dihasilkan. Hal
tersebut terlihat pada hasil uji statistik dimana hasil uji sensoris yang dihasilkan
hampir sama antara pemotongan vertikal, horisontal maupun belah samping.
Perbedaan lama perendaman keripik salak secara vacuum maupun deep
frying terlihat berpengaruh terhadap tekstur keripik salak secara statistik.
Perbedaan signifikan terjadi antara lama perendaman 40 menit dengan dua
perlakuan lainnya yaitu 20 dan 30 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
lama perendaman bahan keripik salak di dalam larutan kapur, maka akan
mempengaruhi tingkat kesukaan terhadap tekstur keripik salak yang dihasilkan.
IV.3 Warna
Warna merupakan faktor penting dalam proses penerimaan makanan,
karena warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam
makanan, seperti pencoklatan dan pengkaramelan. Warna merupakan nama umum
untuk semua pengindraan yang berasal dari aktivitas retina mata, jika cahaya
mencapai retina, mekanisme saraf mata menanggapi, salah satunya memberi
sinyal warna, menurut definisi tersebut warna tidak dapat dipelajari tanpa sistem
pengindraan manusia (deMan, 1997). Pada umumnya perubahan warna yang
terjadi yang disebabkan oleh adanya pemanasan suhu (baik pada vacuum ataupun
deep frying), pada proses pemanasan produk menjadi kecoklatan, hal tersebut
disebut sebagai pencoklatan nonenzim.

Pencoklatan nonenzim (reaksi maillard) sangat penting pada
pemanufakturan makanan, hasilnya mungkin dikehendaki ataupun tidak. Untuk
produk yang reaksi pencoklatan menguntungkan, ciri warna yang terbentuk
biasanya menyenangkan. Reaksi pencoklatan dapat didefinisikan sebagai urutan
peristiwa yang dimulai dengan reaksi gugus amino pada asam amino, peptide atau
protein dengan gugus hidroksil glikosidik pada gula, urutan diakhiri dengan
pembentukan polimer nitrogen berwarna coklat atau melanoidin (Ellis, 1959
dalam deMan 1997). Menurut Boskou dan Elmadfa (1999) reaksi utama pada
maillard (non-enzymic browing) adalah reaksi gula dengan asam amino bebas.
Produk yang terbentuk seperti produk amadori yang disebut sebagai
premelanoidin, yang merupakan polimerisasi pada saat penggorengan menjadi
makromolekular melanoid yang kecoklatan. Kecoklatan ini makin bertambah
seiring meningkatnya suhu diatas 1500C.
Faktor yang mempengaruhi reaksi pencoklatan yaitu suhu, pH, kandungan
air, oksigen, logam, fosfat, sulfur dioksida, dan inhibitor lainnya. Adanya
peningkatan suhu juga mengakibatkan peningkatan laju pencoklatan secara cepat.
Laju pencoklatan meningkat 2 sampai 3 kali untuk setiap kenaikan suhu 100, jika
kandungan gula pada makanan tinggi maka laju dapat lebih tinggi lagi
(deMan, 1997). Suhu mempengaruhi juga susunan pigmen yang terbentuk. Pada
suhu yang lebih tinggi, kandungan karbon pigmen meningkat dan lebih banyak
pigmen yang terbentuk per mol karbon dioksida yang dibebaskan. Intensitas
warna pigmen meningkat dengan meningkatnya suhu. Pengaruh pH terhadap
reaksi pencoklatan sangat bergantung pada kandungan air. Jika produk banyak
mengandung air, sebagian besar pencoklatan terjadi karena pengkaramelan, tetapi
pada keadaan kandungan air rendah dan pH lebih besar dari 6, reaksi maillard
mendominasi (deMan, 1997). Pencoklatan yang disebabkan oleh reaksi maillard
juga menyebabkan terjadinya pigmen coklat atau melanoidin yang dapat
mengakibatkan terbentuknya banyak senyawa baurasa dan senyawa bau. Uji
warna pada produk kentang dan salak diuji menggunakan uji warna lovibond dan
uji sensoris. Dibawah ini merupakan hasil tabel uji warna lovibond, sebagai
berikut :

Tabel 11. Hasil uji analisis warna (Lovibond)
BahanKetebalan
(mm)Bentuk irisan
Lama perendaman larutan kapur tohor 10%, larutan garam
1% (menit)
Sebelum perendaman larutan kapur
tohor 10%
Sesudah perendaman larutan kapur tohor 10%,
larutan garam 1%
Vakum Frying
Deep frying
Vacum Frying
Deep frying
Kentang 1 − 40 40kuning 9.0; biru 1.1
merah 1.0; kuning 12.2; biru 1.0
merah 1.0; kuning 11.0; biru 2.0
merah 1.0; kuning 2.0; biru 2.0
Salak − vertikal 20 20kuning 11.0; biru 1.0
merah 1.0; biru 1.0
merah 2.0; kuning 14.0; biru 3.0
merah 1.0; kuning 11.0; biru 1.0
Kentang 2 − 40 40kuning 3.3; merah 1.0
kuning 3.3; merah 2.3
merah 0.7; kuning 2.0
merah 1.0; kuning 1.1
Salak − vertikal 30 30kuning 2.0; merah 1.6
kuning 1.3' merah 1.0
merah 1.8; kuning 6.0
merah 1.8; luning 2.2
Kentang 3 − 40 40kuning 4.4; merah 1.0
merah 1.0; biru 1.0; kuning 12.8
kuning 4.0; biru 1.0; merah 2.3
biru 0.2; kuning 10.0; merah 2.0
Salak − vertikal 40 40merah 1.0; kuning 1.0; biru 0.2
merah 1.0; kuning 1.8
biru 0.3; kuning 2.0; merah 1.0
biru 0.3; kuning 5.2; merah 2.2

Kentang 1 − 20 20kuning 8.8; merah 1.4
kuning 6.0; merah 1.0
biru 1.1; kuning 23.2; merah 2.3
biru 1.3; kuning 13.4; merah 4.1
Salak − 30 30kuning 2.0; merah 1.0
kuning 1.6; merah 1.0
biru 0.1; kuning 4.4; merah 2.5
biru 0.1; merah 2.1; kuning 10.0
Kentang 2 − 20 20kuning 7.8; merah 1.4
kuning 5.9; merah 1.0
merah 2.0; kuning 3.4
merah 2.0; kuning 3.2
Kentang 3 − 20 20kuning 10.0; biru 1.0
merah 2.0; biru 1.3
merah 2.0; kuning 4.4
merah 2.0; kuning 3.3
Salak −horizontal
40 40merah 1.2; kuning 1.0
merah 1.4; kuning 1.7
merah 2.4; kuning 1.5
merah 2.0; kuning 2.4
Kentang 1 − 30 30kuning 2.3; merah 1.4
kuning 1.5; merah 1.0
biru 0.3; kuning 4.3; merah 2.3
biru 0.3; merah 2.3; kuning 9.8
Salak −belah samping
20 20kuning 7.2; merah 1.3
kuning 4.9; merah 0.8
merah 2.3; kuning 3.4
merah 2.3; kuning 2.4
Salak −belah samping
− 40 −kuning 5.3; merah 1.3
−
merah 2.1; kuning 2.3
Kentang 2 − 30 30kuning 1.8; merah 1.4
kuning 2.3; merah 0.3
biru 0.5; kuning 4.8; merah
kuning 10.03; merah 2.3

2.3
Salak −belah samping
30 30kuning 3.2, merah 1.3
merah 1.1; kuning 11.1
merah 2.4; kuning 20.3
merah 2.2; kuning 72.2
Salak −belah samping
40 −merah 1.3; kuning 1.7
merah 2.1; kuning 82.2
merah 4.1; kuning 72.2
−
Kentang 3 30 30kuning 2.2, merah 1.1
kuning 2.0; merah 1.1
merah 2.5; kuning 18.8
merah 2.4; kuning 71.2
Salak −belah samping
30 30merah 0.2; kuning3.9
merah 1.3; kuning 10.2
merah 1.4; kuning 2.3
kuning 9.3; merah 1.2
Salak −belah samping
40 −merah 1.4; kuning 1.9
merah 1.8; kuning 23.8
merah 3.2; kuning 20.2
−
Hasil uji warna Lovibond menggambarkan bahwa warna yellowness
(kuning) dan blueness (biru) menyatakan warna semakin kecoklatan, akibat dari
proses pemanasan suhu tinggi yang dominan disebabkan oleh reaksi maillard
(pencoklatan non enzim).
Adanya perbedaan perlakuan pada kentang memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap perubahan warna, hal ini dinyatakan dengan huruf yang
berbeda dibelakang angka menandakan adanya pengaruh atau perbedaan yang
nyata antar perlakuan terhadap kategori warna, sedangkan huruf yang sama
menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan antar perlakuan. Adanya
faktor perbedaan perlakuan berupa sistem pemasakan yang berbeda (vacuum dan
deep frying), perendaman dengan larutan kapur tohor, tipe pemotongan yang
berbeda, semua faktor tersebut pada beberapa antar sampel memberikan pengaruh
yang signifikan. Hal ini disebabkan secara dominan oleh faktor sistem pemasakan
(vacuum dan deep frying) yang berbeda, karena vacum menggunakan suhu yang
rendah (dibawah 1000C) dalam proses pemasakannya menghasilkan warna

kecoklatan yang tidak terlalu coklat, sedangkan sistem pemasakan dengan deep
frying menghasilkan warna produk yang lebih coklat karena pada proses nya
menggunakan suhu yang lebih tinggi (diatas 1600C). Hal tersebut sangat
mempengaruhi perubahan warna pada kentang.
Perbedaan ketebalan irisan pada kentang mempengaruhi warna, hal ini
disebabkan karena ketebalan mempengaruhi kecepatan dalam pemasakan.
Pemasakan yang lebih lama menghasilkan warna yang lebih coklat, apalagi
menggunkan pemanasan dengan suhu tinggi (deep frying). Faktor perendaman
tidak berpengaruh terhadap perubahan warna pada produk kentang. Sama seperti
pada produk kentang pengaruh perbedaan warna antar perlakuan disebabkan
secara dominan karena pemanasan, dimana terjadinya proses maillard
(pencoklatan non enzimatik). Bentuk irisan tidak berpengaruh terhadap
perubahan warna pada produk salak. Perbedaan lamanya perendaman dengan
larutan kapur tohor terhadap salak mempengaruhi terhadap perbedaan warna antar
produk.
IV.4 Keseluruhan
Parameter yang diamati dalam praktikum ini meliputi warna, aroma,
tekstur, rasa dan keseluruhan dari keripik yang dihasilkan. Pengujian sensoris
dilakukan dengan metode uji kesukaan secara scoring menggunakan 16 panelis
tidak terlatih. Nilai skor untuk tiap-tiap parameter antara 1-5, semakin besar nilai
skor sensoris berarti semakin tinggi pula nilai kesukaan panelis terhadap keripik
yang diamati. Hasil dari pengujian sifat sensoris keripik kentang dapat dilihat
pada Tabel 12 dan keripik salak pada Tabel 13.
Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa parameter aroma memberikan hasil
yang berbeda nyata pada keripik kentang dengan perlakuan ketebalan irisan dan
lama perendaman. Keripik kentang dengan perlakuan ketebalan pengirisan 2 mm
dan lama perendaman dalam larutan kapur tohor 10% selama 30 menit yang
digoreng secara vacuum frying merupakan produk yang paling disukai oleh
panelis.
Tabel 12 Uji sensoris keripik kentang

PenggorenganKetebalan
Irisan (mm)
Lama Perendaman
(menit)
Parameter
Warna Aroma Tekstur Rasa Keseluruhan
Vacuum
1 20 3,69fgh 2,87cd 3,38efg 3,06fgh 3,19de
1 30 3,81gh 3,13cd 3,19defg 2,81efg 2,88bcd
1 40 3,00cdef 2,94cd 3,06def 2,62defg 2,81bcd
2 20 4,06h 3,25d 3,69fg 3,63h 3,81f
2 30 3,44efgh 3,31d 3,00def 2,88fg 3,19de
2 40 2,87cde 2,81cd 2,94de 2,69defg 2,75bcd
3 20 3,38defgh 3,25d 3,81g 3,56h 3,69ef
3 30 3,19cdefg 3,06cd 3,44efg 3,19gh 3,31def
3 40 2,50bc 2,44bc 2,94de 2,56defg 2,44bc
Deep
1 20 3,31defg 3,06cd 3,06def 2,81efg 3,06cde
1 30 3,81gh 3,00cd 3,38efg 2,44cdef 2,88bcd
1 40 3,87gh 3,06cd 3,44efg 2,75defg 3,06cde
2 20 2,69bcd 2,63bcd 2,13bc 2,19cde 2,50bc
2 30 2,06ab 2,06ab 1,62ab 1,88bc 1,75a
2 40 3,00cdef 2,75bcd 2,50cd 2,13cd 2,38b
3 20 1,50a 1,75a 1,50ab 1,44a 1,50a
3 30 1,63a 1,69a 1,44a 1,44a 1,44a
3 40 1,69a 1,38a 1,19a 1,25a 1,44a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata pada α 5%
Keripik kentang perlakuan tersebut secara umum tidak berbeda nyata
dengan keripik kentang perlakuan lainnnya untuk parameter aroma pada taraf α
5% atau tingkat kepercayaan 95%. Akan tetapi berbeda nyata dengan keripik
kentang dengan perlakuan ketebalan pengirisan 3 mm dan lama perendaman
dalam larutan kapur tohor 10% selama 20 menit, 30 menit dan 40 menit yang
digoreng secara deep frying. Selain itu juga berbeda nyata dengan keripik kentang
dengan perlakuan ketebalan pengirisan 2 mm dan lama perendaman dalam larutan
kapur tohor 10% selama 30 menit yang digoreng secara deep frying dan ketebalan
pengirisan 3 mm dan lama perendaman dalam larutan kapur tohor 10% selama 40
menit yang digoreng secara vacuum frying.
Berdasarkan analisis SPSS, aroma keripik kentang dengan perlakuan
penggorengan dan ketebalan irisan memberikan pengaruh beda nyata sedangkan
lama perendaman memberikan pengaruh beda nyata pada keripik kentang yang
dihasilkan. Aroma keripik kentang dengan penggorengan secara vacuum frying

lebih disukai dibanding deep frying. Semakin tipis pengirisan juga memberikan
pengaruh lebih disukai oleh panelis.
Parameter rasa memberikan hasil yang berbeda nyata pada keripik kentang
dengan perlakuan ketebalan irisan dan lama perendaman. Keripik kentang dengan
perlakuan ketebalan pengirisan 2 mm dan lama perendaman dalam larutan kapur
tohor 10% selama 20 menit yang digoreng secara vacuum frying merupakan
produk yang paling disukai oleh panelis. Keripik kentang perlakuan tersebut
secara umum berbeda nyata dengan keripik kentang perlakuan lainnnya untuk
parameter rasa pada taraf α 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Akan tetapi tidak
berbeda nyata dengan keripik kentang dengan perlakuan ketebalan pengirisan 3
mm dan lama perendaman dalam larutan kapur tohor 10% selama 20 menit dan 30
menit yang digoreng secara vacuum frying. Selain itu juga tidak berbeda nyata
dengan keripik kentang dengan perlakuan ketebalan pengirisan 1 mm dan lama
perendaman dalam larutan kapur tohor 10% selama 20 menit yang digoreng
secara vacuum frying.
Berdasarkan analisis SPSS, rasa keripik kentang dengan perlakuan
penggorengan, ketebalan irisan dan lama perendaman memberikan pengaruh beda
nyata pada keripik kentang yang dihasilkan. Rasa keripik kentang dengan
penggorengan secara vacuum frying lebih disukai dibanding deep frying. Semakin
tebal pengirisan dan semakin lama perendaman menyebabkan penurunan tingkat
kesukaan panelis terhadap rasa keripik kentang yang dihasilkan.
Secara keseluruhan keripik kentang dengan perlakuan ketebalan pengirisan
2 mm dan lama perendaman dalam larutan kapur tohor 10% selama 20 menit yang
digoreng secara vacuum frying merupakan produk yang paling disukai oleh
panelis. Secara umum berbeda nyata dengan keripik kentang perlakuan lainnnya.
Akan tetapi tidak berbeda nyata dengan keripik kentang dengan perlakuan
ketebalan pengirisan 3 mm dan lama perendaman dalam larutan kapur tohor 10%
selama 20 menit dan 30 menit yang digoreng secara vacuum frying. Perlakuan
penggorengan, ketebalan irisan dan lama perendaman memberikan pengaruh beda
nyata pada keripik kentang yang dihasilkan. Keripik kentang dengan vacuum
frying secara keseluruhan lebih disukai oleh panelis dibanding deep frying. Akan

tetapi dilihat dari segi biaya, vacuum frying lebih mahal dibanding deep frying
sehingga perlu dipertimbangkan jenis penggorengan yang akan digunakan.
Tabel 13 Uji sensoris keripik salak
Penggorengan Bentuk Irisan Lama
Perendaman (menit)
ParameterWarn
aArom
aTekstur Rasa Keseluruhan
Vacuum
vertikal 20 1,87ab 2,38abcde 1,69a 2,13abc 1,94a
vertikal 30 2,94d 3,19fg 2,63b 3,31ef 3,13bc
vertikal 40 3,62ef 3,44g 3,13b 3,31ef 3,37cd
horisontal 20 2,56cd 2,88cdefg 2,50b 2,88de 2,75b
horisontal 30 2,06bc 2,63bcdef 1,75a 2,63cde 2,00a
horisontal 40 3,13de 3,06efg 2,50b 3,06de 3,00bc
belah samping 20 3,00d 2,94defg 2,50b 3,13de 2,94bc
belah samping30 2,88d 2,6
3bcdef 2,50b 2,94de 2,62b
belah samping 40 3,75f 3,56g 3,69c 3,81f 3,81d
Deep
vertikal 20 1,87ab 2,56bcdef 1,44a 2,13abc 1,88a
vertikal 30 1,75ab 2,19abc 1,44a 1,75ab 1,56a
vertikal 40 1,75ab 1,81a 1,62a 1,81ab 1,62a
horisontal 20 1,88ab 2,13ab 1,50a 1,88abc 1,88a
horisontal 30 1,69ab 2,31abcd 1,69a 2,06abc 1,81a
horisontal 40 1,88ab 2,13ab 1,81a 2,38bcd 2,06a
belah samping 20 1,50ab 2,06ab 1,38a 1,69ab 1,50a
belah samping 30 1.38a 2,19abc 1,25a 1,50a 1,56a
belah samping 40 1,94ab 2,06ab 1,44a 2,06abc 1,87a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata pada α 5%
Penggorengan secara vacuum lebih baik untuk menghasilkan produk
dengan bahan yang mengandung kadar gula tinggi. Hal ini disebabkan suhu
penggorengan vacuum yang rendah sehingga produk dengan kadar gula tinggi
yang digoreng tidak mengalami browning atau reaksi maillard sehingga
mempunyai kenampakan fisik yang lebih baik dibanding deep frying.
Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa parameter aroma memberikan hasil
yang berbeda nyata pada keripik salak dengan perlakuan bentuk irisan dan lama
perendaman. Keripik salak dengan irisan belah samping dan lama perendaman

dalam larutan kapur tohor 10% selama 40 menit yang digoreng secara vacuum
frying merupakan produk yang paling disukai oleh panelis.
Aroma keripik salak dengan perlakuan penggorengan memberikan
pengaruh beda nyata sedangkan bentuk irisan dan lama perendaman tidak
memberikan pengaruh beda nyata pada keripik salak yang dihasilkan. Aroma
keripik salak dengan penggorengan secara vacuum frying lebih disukai dibanding
deep frying.
Parameter rasa memberikan hasil yang berbeda nyata pada keripik salak
dengan perlakuan bentuk irisan dan lama perendaman. Keripik salak dengan
perlakuan bentuk pengirisan belah samping dan lama perendaman dalam larutan
kapur tohor 10% selama 40 menit yang digoreng secara vacuum frying merupakan
produk yang paling disukai oleh panelis. Keripik salak perlakuan tersebut secara
umum berbeda nyata dengan keripik salak perlakuan lainnnya untuk parameter
rasa pada taraf α 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Akan tetapi tidak berbeda
nyata dengan keripik salak dengan perlakuan bentuk pengirisan vertikal dan lama
perendaman dalam larutan kapur tohor 10% selama 30 menit dan 40 menit yang
digoreng secara vacuum frying.
Rasa keripik salak dengan perlakuan penggorengan dan lama perendaman
memberikan pengaruh beda nyata sedangkan bentuk irisan tidak memberikan
pengaruh beda nyata pada keripik salak yang dihasilkan. Rasa keripik salak
dengan penggorengan secara vacuum frying lebih disukai dibanding deep frying.
Semakin lama perendaman, rasa keripik salak semakin disukai panelis.
Secara keseluruhan keripik salak dengan perlakuan bentuk pengirisan
belah samping dan lama perendaman dalam larutan kapur tohor 10% selama 40
menit yang digoreng secara vacuum frying merupakan produk yang paling disukai
oleh panelis. Secara umum berbeda nyata dengan keripik kentang perlakuan
lainnnya. Akan tetapi tidak berbeda nyata dengan keripik salak dengan perlakuan
bentuk pengirisan vertikal dan lama perendaman dalam larutan kapur tohor 10%
selama 40 menit yang digoreng secara vacuum frying.
Perlakuan penggorengan dan lama perendaman memberikan pengaruh
beda nyata sedangkan bentuk irisan pada keripik salak yang dihasilkan. Keripik

salak dengan vacuum frying secara keseluruhan lebih disukai oleh panelis
dibanding deep frying. Hal ini dikarenakan salak mempunyai kandungan gula
yang tinggi. Penggorengan vacuum lebih baik untuk menghasilkan produk dengan
bahan yang mengandung kadar gula tinggi. Hal ini disebabkan suhu
penggorengan vacuum yang rendah sehingga produk dengan kadar gula tinggi
yang digoreng tidak mengalami browning atau reaksi maillard sehingga
mempunyai kenampakan fisik yang lebih baik dibanding deep frying.
V. KESIMPULAN
V.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Keripik salak dan keripik kentang lebih disukai dengan metode vacuum frying
dibandingkan dengan deep frying.
2. Ketebalan bahan dan lama perendaman mempengaruhi karakteristik keripik
kentang dan keripik salak
3. Metode penggorengan vacuum frying lebih baik untuk menghasilkan produk
dengan bahan yang mengandung kadar gula tinggi.
4. Lama perendaman dapat mempengaruhi rasa keripik yang disukai panelis.
5. Panelis lebih menyukai keripik yang digoreng dengan metode vacuum frying.
V.2 Saran
Pemilihan proses penggorengan (metode penggorengan) juga harus
diperhatikan produk pangan yang sesuai untuk digoreng dengan metode
penggorengan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Adicahyadi, Lisa. 2008. Renyahnya Bisnis Keripik Kentang. http://www.foodreview.biz/login/preview.php?view&id=55806. 10 Desember 2010.

Anonim. 2003. Industri Pangan Butuh Uji Sensoris. http://www.pelita.or.id/baca.php?id=35545. (Diakses tanggal 14 Desember 2010).
Anonim. 2008. Sifat-sifat Sensoris. http://tekhnologi-hasil-pertanian.blogspot.com/ 2008/ 08/ sifat - sifat - sensoris_8614.html. (Diakses tanggal 17 Mei 2009).
Anonim. 2008. Menggoreng Buah dan Sayur Menggunakan Mesin Vacuum frying. http://keripikbuah.com/menggoreng-buah-dan-sayur-dengan-mesin-vacuum-frying.htm . 3 November 2010 .
Anonim. 2010. Kandungan air dalam bahan pangan. http://www.rajman.co.cc/2010/07/kandungan-air-dalam-bahan-pangan.html, akses tanggal 31 Agustus 2010.
Anonim. 2010. http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/13/dar21.htm, akses tanggal 31 Agustus 2010
Anonim. 2010. Penggorengan Vakum Untuk Pembuatan Kripik Buah-buahan. http://www.pustaka-deptan.go.id/agritek/dkij0122.pdf. (Diakses pada tanggal 1 September 2010).
De Mand, John M. 1997. Kimia Makanan. Penerbit ITB, Bandung.
Dimitrios Boskou dan Ibrahim Elmadfa, 1997, Frying of Food, Technomic Publishing CO.INC, Lancaster-Basel.
Herawati, Heny. 2008. Penentuan Umur Simpan Pada Produk Pangan. Jurnal Litbang Pertanian.
Kartika, Bambang, Pudji Astuti dan Wahyu Supartono. 1988. Pedoman Uji Inderawi Bahan Pangan. PAU Pangan dan Gizi UGM. Yogyakarta.
Ketaren, S. Minyak dan Lemak Pangan, 1986, UI Press.
Rahayu, Kapti. 1988. Penyedap. dalam Bahan Tambahan Makanan (Food Additives). Trenggono, dkk. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi UGM. Yogyakarta.
Sartika, R.A.D., Pengaruh suhu dan lama proses menggoreng (Deep frying) terhadap pembentukan asam lemak trans. Makara, sains, vol. 13, no. 1, April 2009 : 23 – 28. CV Yasaguna. Jakarta.
Setiyo, Yohanes. 2003. Aplikasi Sistem Kontrol Suhu dan Pola Aliran Udara pada Alat Pengering Tipe Kotak. [email protected]. (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2010).
Setyarso, Nur Asidik. 2004. Skripsi. Perpindahan Panas dan Massa pada Kentang Berbentuk Silinder Selama Penggorengan Tekanan Hampa. Jurusan Teknik Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Gadjah Mada.

Siregar, Halomoan P, Dadang D. Hidayat dan Sudirman. 2004. Evaluasi Unit Proses “Vacum Frying” Skala Industri Kecil Menengah. http://203.190.188.132/download//e-book/makalah/Vakum%20frying.pdf. (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2010).
Soritua, Parulian. 2010. Pembuatan Keripik Kentang. http://kamiitp08.blogspot.com/2010/10/pembuatan-keripik-kentang.html. 3 November 2010.
Tandilittin, H. Desain dan Uji Penggoreng Open Deep frying dengan perubahan posisi elemen pemanas. Tesis IPB. 2008.
Tobias, Pedro, Ricardo del Rosario, Manuel Palomar, Romeo Obordo, Marianto R. Villanueva, Amelia Gerpacio, Federico G. Villamayor, E. Magboo, Dely P. Gapasin dan Madeline B. Quiamco. 1983. The Philippines Recommends for Cassavaa. Philippine Council for Agriculture and Resources Research and Development. Los Banos. Laguna.
Widaningrum, N. Setyawan dan D.A. Setyabudi. 2008. Pengaruh Cara Pembumbuan dan Suhu Penggorengan Vakum Terhadap Sifat Kimia dan Sensori Keripik Buncis (Phaseolus radiatus) Muda. http://pascapanen.litbang.deptan.go.id/media/ publikasi /jurnal/j.Pascapanen.2008_2_6.pdf. (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2010).
Wijaya, C. Hanny. 2009. The Science of Taste . Sensasi Rasa. Food Review. Vol.IV, No.10, Oktober 2009, hal. 10. PT Media Pangan Indonesia. Bogor.
Winarno, FG. 1997. Kimia Pangan dan Gizi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

LAMPIRAN
Lampiran 1. Pengujian Sensoris dengan Metode Scale Hedonic Test
(Larmond, 1977)
1. Sampel keripik, kemudian ditempatkan di dalam cawan porselin. Masing-
masing cawan diberi label secara acak dan ditata secara acak juga.

2. Panelis dipersilahkan mencicipi sampel satu per satu dengan diselingi
berkumur air hangat dan memakan roti tawar pada tiap sampel untuk
menghindari adanya bias.
3. Panelis menuliskan penilaian masing-masing sampel pada boring yang
disediakan. Penilaian meliputi warna, bau atau flavor, tekstur, rasa dan
keseluruhan.
Pengujian Sensoris
Nama : ………………….. Tanggal : …………….. 2010
Jenis kelamin : ………………….. Tanda Tangan : ……………..
Umur : ………………….. Sampel : Keripik

Dihadapan saudara disajikan suatu produk makanan, yaitu keripik yang
terbuat dari kentang dan salak. Saudara diminta untuk memberikan penilaian
terhadap masing-masing parameter dengan memberikan nilai pada kolom sesuai
dengan penilaian saudara:
Tahap 1. Penilaian produk keripik dengan menggunakan skala penilaian:
1 = sangat tidak suka 4 = agak suka
2 = tidak suka 5 = sangat suka
3 = suka
Parameter KentangWarnaBau/flavorTeksturRasaKeseluruhan
Parameter SalakWarnaBau/flavorTeksturRasaKeseluruhan
Atas partisipasi Anda kami ucapkan banyak terima kasih
Lampiran 2. Analisis tekstur dengan Zwick/ Z 0.5
1. Siapkan sampel sesuaikan dengan perlakuan

2. Aktifkan Program Universal Testing Machine
3. Power mesin dalam posisi ON
4. Panel mesin dalam posisi ON
5. Tunggu sampai proses download selesai
6. Sesuaikan Test Standar (Compression, Tensile Strength, Penetration)
7. Setiap melakukan pengujian perhatikan parameter, sesuaikan dengan
pengujian yang akan dilakukan
8. Isi data sampel sesuai dengan specimen
9. Lakukan pengujian, tunggu sampai proses pengujian selesai
10. Sesuaikan grafik dengan data yang ada
11. Tulis kode sampel
12. Cetak hasil pengujian
Lampiran 3. Analisis kadar air metode Gravimetri (AOAC, 1984).

1. Ditimbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 gram dalam botol
timbang yang telah dikeringkan dalam oven pada suhu 105oC dan diketahui
beratnya (berat konstan).
2. Dikeringkan pada suhu 100-105oC selama 3-5 jam, didinginkan dalam
desikator lalu timbang. Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit,
kemudian dinginkan dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai tercapai
berat konstan.
3. Pengurangan berat ini merupakan banyaknya air dalam sampel yang dihitung
dengan rumus:
Kadar air (%)=a−ba
×100 %
Keterangan:
a = berat sampel mula-mula (gram)
b = berat sampel setelah dikeringkan (gram)
Lampiran 4. Analisis warna dengan Lovibond Tintometer model F.

Cara Kerja:
1. Masukkan bahan ke dalam cuvet
2. Diletakkan dalam chamber lid (alat tintometer) dan kemudian ditutup
3. Hidupkan alat atau tekan power
4. Diamati warna sampel dengan eyepiece dan mengatur warna sampai sama
menggunakan parameter warna (panel)
5. Dilihat angka panel