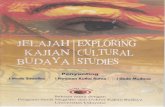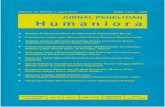LAPORAN PENELITIAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT …
Transcript of LAPORAN PENELITIAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT …

LAPORAN PENELITIAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JATILUWIH : POTENSIWARISAN BUDAYA DUNIA
TIM PENELITI :
Dr. I Nyoman Dhana, M.AProf. Dr. A.A Bagus wirawan, S.U.
Dr. Putu sukardja, M.Si.Dr. Ni Made Wiasti, M.Hum.
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas UdayanaNomor : DIPA A-023.04.2.415253/2014 sesuai SPK Nomor : 276/UN
14.4.5/KU/2014 Tanggal 11 Juni 2014
PROGRAM STUDI DOKTOR KAJIAN BUDAYAPROGRAM PASCASARJANA
UNIVERDITAS UDAYANA2014

HALAMAN PENGESAHAN
Judul : Kearifan Lokal Masyarakat Desa Jatiluwih :Potensi Warisan Budaya Dunia
Peneliti :a. Nama Lengkap : Dr. I Nyoman Dhana, M.Ab. NIDN : 0016095702c. Jabatan Fungsional : Lektord. Program Studi : Antropologie. Nomor HP : 08124600481f. Alamat Surel (e-mail) : [email protected] Peneliti (1)a. Nama Lengkap : Prof. Dr. A.A Bagus Wirawan, S.U.b.NIDN : 0020074804c. Perguruan Tinggi : Universitas UdayanaAnggota Peneliti (2)a. Nama Lengkap : Dr. Putu Sukardja, M.Si.b. NIDN : 0022065205c. Perguruan Tinggi : Universitas UdayanaAnggota Peneliti 3a. Nama Lengkap : Dr. Dra. Ni Made Wiasti, M.Humb.NIDN : 0008125913c. Perguruan Tinggi : Universitas UdayanaTahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari Rencana 1 TahunBiaya Tahun Berjalan : Rp 10.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)Biaya Keseluruhan : Rp 10.000.000,00
-Denpasar, 29 Oktober 2014
Mengetahui,Ketua Program Doktor Kajian BudayaUniversitas Udayana
Ketua Peneliti,
(Prof. Dr. A.A Bagus Wirawan, S.U)NIP 19480720197803 1 001
Dr. I Nyoman Dhana, M.ANIP 19570916198403 1 002

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JATILUWIH : POTENSIWARISAN BUDAYA DUNIA
ABSTRAK
Masyarakat Desa Jatiluwih merupakan masyarakat yang hidup dikawasan Warisan Budaya Dunia Jatiluwih yang juga merupakan Daerahtujuan wisata. Untuk mengelola kawasan ini tentu saja kelestarian danimplementasi kearifan lokal menjadi penting adanya. Terkait dengan halitu, penelitian ini berttujuan untuk mengidentifikasi dan memahamikearifan lokal masyarakart desa Jatiluwih, sehibngga hasilnya diharapkanberguna untuk mendukung pengelolaan kawasan warisan budaya dubiadan daerah tujuan wisata Jatiluwih.
Hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan bahwa kearifanlokal yang dimiliki masyarakat Desa Jatiluwih memang berkaitan denganupaya pelestarian budaya dan lingkungan setempat. Olreh karena itukearifan lokal tersebut berpotensi untuk membangun manajemen baikuntuk melestarikan kawasan warisan budaya dunia Jatiluwih maupundaerah tujuan wisata jatiluwih.
Kata Kunci : Kearifan lokal, warisan budaya dunia, daerah tujuan wisata

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Desa Jatiluwih dan Subak Jatiluwih di Kabupaten Tabanan, Bali
sejak beberapa tahun yang lalu memiliki status ganda, yaitu sebagai daerah tujuan
wisata (DTW) dan sebagai warisan budaya dunia (WBD). Terkait dengan hal ini,
maka dua lembaga ini perlu dikelola dengan dengan strategi yang relavan dengan
statusnya itu. Sebagaimana diketahui, pariwisata di Bali diatur dalam peraturan
khusus, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataan Budaya Bali. Pasal 1 angka 14 peraturan tersebut menyatakan
bahwa :
“Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yangberlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran AgamaHindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama denganmenggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehinggaterwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataandan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis,harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraankepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan”.
Berdasarkan gagasan ini maka pengembangan pariwisata di Bali, termasuk
pengembangan DTW Jatiluwih perlu dilakukan dengan tetap berorientasi pada
pelestarian budaya dan lingkungan alam setempat. Begitu juga halnya dengan
gagasan di balik WBD menekankan pada pentingnya pelestarian dan lingkungan
alam setempat. Dengan demikian, pengelolaan Desa Jatiluwih dan Subak
jatiluwih, baik sebagai DTW maupun sebagai WBD, diorientasikan untuk
melestarikan budaya dan lingkungan alam setempat.

Mengingat masyarakat Desa Jatiluwih merupakan ujung tombak dalam
pengelolaan DTW dan WBD Jatiluwih, maka pengelolaannya yang berorientasi
pada pelestarian budaya dan lingkungan alam setempat perlu disesuaikan dengan
kearifan lokal masyarakat Desa Jatiluwih. Dengan demikian masyarakat Desa
Jatiluwih dapat diharapkan mau dan mampu berpatisipasi secara optimal dalam
proses pengelolaan DTW dan WBD itu. Dalam rangka mewujudkan gagasan
inilah diperlukan penelitian tentang kearifan lokal masyarakat Desa Jatiluwih.
Terkait dengan kearifan lokal, Chambers (1983 : 106-118) menegaskan bahwa
setiap masyarakat memiliki pengetahuan dan teknologi tradisional yang disebut
”pengetahuan rakyat pedesaan”. Pengetahuan dan teknologi tradisional, jika
diwariskan secara turun temurun menjadi tradisi (Giddens, 2003). Suatu tradisi
sangatlah luas cakupannya, salah sartu di antaranya adalah kearifan tradisional.
Keraf (2002 : 289) mengemukakan bahwa kearifan tradisional bukan hanya
menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam
dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut
pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan
bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis. Dengan
demikian, kearifan tradisional ada yang berbentuk kearifan sosial, yaitu
pengetahuan, keyakinan, dan adat kebiasaan yang memedomani hubungan
manusia dengan sesamanya, dan ada pula yang berbentuk kearifan lingkungan,
yaitu pengetahuan, keyakinan, dan adat kebiasaan yang memedomani hubungan
manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Jika kearifan sosial dan kearifan

lingkungan itu dimiliki oleh masyarakat pada lokasi tertentu maka disebut
kearifan lokal.
Bertolak dari paparan di atas, maka dalam rangka menyusun strategi
pengelolaan DTW dan WBD Jatiluwih yang berorientasi pada pelestarian budaya
dan lingkungan alam setempat diperlukan penelitian tentang kearifan lokal
masyarakat Desa Jatiluwih. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan
memfokuskan perhatian pada kearifan lokal masyarakat desa Jatiluwih, baik yang
berbentuk kearifan sosial maupun kearifan lingkungan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan di atas tampaklah masalah yang perlu dikaji dalam
penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.
1) Bagaimana kearifan sosial masyarakat Desa Jatiluwih?
2) Bagaimana kearifan lingkungan masyarakat Desa Jatiluwih
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
mengindentifikasi, memahami, dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.
1) Mengindentifikasi, memahami, dan menjelaskan kearifan sosial
masyarakat Desa Jatiluwih, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan adat
kebiasaan yang memedomani hubungan manusia dengan sesamanya.
2) Mengindentifikasi, memahami, dan menjelaskan kearifan lingkungan
masyarakat Desa Jatiluwih, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan adat

kebiasaan yang memedomani hubungan manusia dengan lingkungan
alam sekitarnya.
1.3.2 Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoretis maupun
praktis, yakni sebagai berikut.
1) Manfaat teoretis, yaitu menambah pengetahuan tentang kearifan sosial dan
kearifan lingkungan masyarakat Desa Jatiluwih dalam konteks strategi
pengelolaan Desa Jatiluwih dan Subak Jatiluwih, baik sebagai DTW
maupun WBD.
2) Manfaat praktis, yaitu untuk menyusun strategi pengelolaan Desa
Jatiluwih dan Subak Jatiluwih, baik sebagai DTW maupun WBD.
1.4 Kerangka Pemikiran
1.4.1 Pandangan Manusia terhadap Lingkungannya
Tujuan penelitian ini sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya tidak
lepas dari telaah tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam
menelaah hubungan manusia dengan lingkungannya, maka pandangan manusia
terhadap lingkungan tidak dapat diabaikan karena berdasarkan pandangannya
itulah manusia berusaha memanfaatkan potensi lingkungan dengan melakukan
berbagai kegiatan. Sehubungan dengan hal ini, Soemarwoto dalam tulisannya
berjudul Lingkungan Hidup dan Pembangunan (1989) menunjukkan bahwa
perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan sangat ditentukan oleh citra

lingkungan yang mereka miliki. Menurut Soemarwoto (1989 : 94) citra
lingkungan adalah sebagai berikut.
“Citra lingkungan menggambarkan anggapan orang tentang strukturlingkungan, bagaimana lingkungan itu berfungsi, reaksinya terhadaptindakan orang serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Citralingkungan itu memberi petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan danapa yang tidak boleh dilakukan demi kebaikan orang itu”.
Berdasarkan pengertian tentang citra lingkungan ini, maka dapat
dikatakan bahwa sikap dan perilaku manusia dalam mengelola lingkungannya
tidak lepas dari pandangannya atau anggapannya tentang lingkungan yang
bersangkutan. Jika lingkungannya dianggap mengandung potensi yang bermanfaat
baginya, maka mereka akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut untuk
memenuhi kebutuhannya. Menurut Soemarwoto (1989 : 94), citra lingkungan
yang dimiliki suatu masyarakat bisa bersumber pada pengetahuan yang mereka
dapatkan dari hubungan mereka dengan lingkungan dan/atau bisa pula bersumber
pada agama, kepercayaan ataupun mistik. Dengan mengacu kepada pendapat
Sanderson (1993), agama, kepercayaan ataupun mistik sebagai sumber citra
lingkungan dapat dikatakan sebagai sub dari salah satu unsur sistem sosiokultural
masyarakat yang bersangkutan, yaitu unsur sistem sosiokultural berupa
superstruktur ideologis. Superstruktur ideologis meliputi cara-cara yang telah
terpolakan yang dengan cara tersebut para anggota masyarakat berpikir serta
melakukan konseptualisasi, menilai, dan merasa (Sanderson, 1993 : 62).
Sebagaimana diketahui, citra lingkungan masyarakat Bali dalam arti
demikian dapat dilihat dari ideologi yang mereka anut, yakni ideologi Tri Hita
Karana. Ideologi ini menekankan pada pentingnya keharmonisan hubungan

antara manusia dengan manusia (pawongan), hubungan manusia dengan
lingkungan alam nyata atau sekala (palemahan) dan hubungan manusia dengan
lingkungan alam tidak nyata atau niskala (parhyangan). Dengan demikian, citra
lingkungan masyarakat Bali terlihat bersifat ekosentrisme.
1.4.2 Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat dalam Lingkungan
Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai hutan menunjukkan bahwa
dalam pemanfaatan potensi sumberdaya hutan bisa terjadi kompetisi dan konflik
antarkelompok pemanfaat. Salah satu contohnya adalah kompetisi yang berlanjut
dengan konflik antara masyarakat setempat dan pengusaha hutan di Irian jaya
sebagaimana ditunjukkan oleh Soehendra dan Aninung (1993). Selain itu bisa
pula terjadi kerjasama warga masyarakat dalam mengelola hutan sehingga
menghasilkan masukan finansial bagi mereka sekaligus menghasilkan kelestarian
hutan yang bersangkutan. Contohnya adalah kasus pengelolaan hutan yang
dilakukan oleh orang Badui sebagaimana ditelaah oleh Iskandar (1992).
Beberapa hasil penelitian tentang hutan di Bali khususnya menunjukkan
bahwa ada ada masyarakat-masyarakat yang mampu memanfaatkan sumberdaya
hutan untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap melestarikan hutan yang
bersangkutan. Di antaranya adalah hasil penelitian Astika, dkk (1984)
menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah
mampu memanfaatkan sekaligus melestarikan hutan setempat dengan
memberlakukan peraturan (awig-awig) dan sanksinya secara ketat. Begitu juga
hasil penelitian Atmadja (1992; 1993, 1993a) mengenai Hutan Wisata Kera
Sangeh (1992; 1993a) dan Hutan Wisata Kera Kedaton (1993) menunjukkan

peran masyarakat setempat dalam mengelola hutan tersebut sehingga tetap lestari
dan mampu memberikan masukan finansial, baik terhadap rumah tangga maupun
komunitas setempat.
Mencermati hasil penelitian yang menunjukkan pemanfaatan hutan yang
menghasilkan masukan finansial bagi masyarakat yang bersangkutan sekaligus
menghasilkan kelestarian hutan, maka segera dapat dipahami bahwa partisipasi
masyarakat dalam melestarikan hutan tidak lepas dari kepentingannya untuk
meraih masukan finansial melalui pengelolaan hutan yang bersangkutan. Hal ini
dapat dilakukan tanpa dan dan/atau dengan menjadikan hutan sebagai objek
wisata, tergantung dengan konteks ekologis serta kemauan dan kemampuan
masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian seperti itu, termasuk
penelitian yang hendak dilakukan ini tetap perlu dilakukan untuk
mengembangkan model pengelolaan hutan yang berpoptensi untuk menghasilkan
masukan finansial bagi para partisipannya sekaligus untuk melestarikan hutan
yang bersangkutan. Dikatakan demikian bukan hanya kerena keberhasilannya
telah terbukti dari hasil penelitian terdahulu, melainkan juga karena masing-
masing hutan tentu memiliki kondisi ekologis yang tidak selalu sama, begitu pula
masyarakat di sekitarnya tidak selalu memiliki kemauan dan kemampuan yang
sama dalam konteks pemanfaatan hutan.
Menurut teori rasionalitas, manusia diasumsikan sebagai makhluk yang
rasional. Artinya, manusia selalu berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
dalam melakukan setiap tindakan (Basrowi dan Sukidin, 2003; Mustain, 2007).
Sehubungan dengan itu, setiap individu manusia dalam kehidupan masyarakat

memiliki kesadaran akan keuntungan yang dapat diperoleh melalui tindakan-
tindakannya (Yunita, 1986 : 68-69). Demikian juga teori insentif selektif
mengasumsikan bahwa keikutsertaan seseorang yang rasional dalam melakukan
suatu kegiatan dipengaruhi oleh jenis, bentuk, dan isi harapan-harapan yang bakal
menguntungkan.
Berdasarkan asumsi teori rasionalitas di atas, maka daoat diduga bahwa
warga masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan
jika mereka memandang kegiatan tersebut memberi keuntungan bagi mereka, dan
sebaliknya. Berpegang pada dugaan ini maka tidak mengherankan jika masyarakat
setempat telah berperan dalam melestarikan Hutan Wisata Kera di Bali
sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Atmadja (1992 dan
1993). Sebab dalam kenyataannya, hutan tersebut merupakan objek wisata yang
setiap hari dikunjungi banyak wisatawan, sehingga menghasilkan keuntungan
finansial bagi masyarakat yang bersangkutan.
1.4.3 Refleksi tentang Model Pelestarian Hutan Berbasis Masyarakat
Berdasarkan pemikiran mengenai partisipasi masyarakat dalam program
pelestarian lingkungan sebagaimana dipaparkan di atas, maka program pelestarian
hutan perlu disusun dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.
Dengan demikian dapat diharapkan semua pihak akan berpartisipasi dengan
penuh semangat dan berkelanjutan. Secara lebih konkret, model pelestarian hutan
yang disusun dan dilaksanakan adalah model yang benar-benar didasarkan pada
kepentingan, kemauan, dan kemampuan para pihak terkait sehingga meyakinkan

akan memberi kuntungan finansial bagi para partisipannya. Salah satu model
strategis dalam hal ini adalah model pelestarian hutan yang memberikan akses
kepada masyarakat untuk mengembangkan tanaman pangan di kawasan hutan
lindung, namun tanpa merusak tanaman hutan. Selain itu mereka juga diberi
kewajiban untuk memelihara kayu yang tumbuh di hutan dengan catatan mereka
juga diberi hak atas hasil kayu itu yang pengaturannya didasarkan pada system
pembangian hasil sesuai dengan semua pihak terkait. Dengan demikian dapat
diharapkan bahwa masyarakat akan mengembangkan rasa memiliki dan
tanggungjawab terhadap kelestarian hutan.
Sebaliknya, jika program pelestarian hutan dilakukan hanya dengan
melarang orang untuk memanfaatkan sumberdaya hutan sebagaimana sering
dilakukan selama ini, maka orang akan selalu cenderung berusaha
memanfaatkannya secara maksimal bahkan secara illegal selama mereka
memandang hutan itu berpotensi besar untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Apalagi jika hutan dipandangnya sebagai sumberdaya milik bersama (common
proverty), maka dengan mengacu kepada tesis Hardin sebagaimana dibahas oleh
Soemarwoto (2001 :94), kemungkinan besar pandangannya itu akan mendorong
mereka untuk memanfaatkan sumberdaya hutan untuk memperoleh keuntungan
sebesar-besarnya hanya untuk diri mereka sendiri sehingga pada gilirannya
terjadi kerusakan hutan yang berdampak negatif terhadap masyarakat setempat.

1.5 Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan motode penelitian kualitatif
yang mengandalkan teknik pengamatan dan wawancara mendalam dalam proses
pengumpulan data; dan mengandalkan teknik interpretatif dalam proses analisis
data kualitatif. Proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini
berorientasi pada paradigma kritis, yaitu mengacu teori-teori sosial kritis, dan
metode dekonstruksi. Secara lebih konkret, penerapan metode dan teknik
penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.
1.5.1 Penentuan Lokasi Penelitian
Berkenaan dengan kawasan Subak Jatiluwih ada Peta Desa Jatiluwih.
Dalam peta desa ini ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sawah yang
merupakan bagian dari Subak Jatiluwih ternyata berada di dalam wilayah Desa
Jatiluwih. Berdasarkan informasi yang diperoleh, para petani subak ini merupakan
warga atau penduduk Desa Jatiluwih. Oleh karena itu, lokasi pelaksanaan
penelitian ini adalah di Desa Jatiluwih.
1.5.2 Penentuan Informan
Mengingat penelitian ini menggunakana pendekatan penelitian kualitatif,
maka data dan informasi yang dibutuhkan akan digali melalaui pengamatan dan
wawancara mendalam. Oleh karena itu, informan (bukan responden) merupakan
narasumber yang amat penting dalam penelitian ini, sebab tanpa informan akan
sulit memperoleh data dan keterangan untuk mencapai tujuan penelitian. Sudah

dapat dipastikan informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Desa dan
Subak Jatiluwih. Namun untuk menentukan orangnya memerlukan petunjuk dari
informan pangkal. Sehubungan dengan itu, kepala Desa Dinas dan Kepala Desa
Adat setempat serta Kepala Subak Jatiluwih dijadikan informan pangkal dalam
penelitian ini Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1989 : 130),
informan pangkal adalah orang-orang yang dapat memeberikan petunjuk kepada
peneliti tentang adanya individu lain yang paham tentang berbagai sektor
kehidupan masyarakat yang ingin dikaji oleh peneliti. Individu-individu lain ini
disebut informan pokok atau informan kunci (key informant).
Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk informan pangkal itu dikembangkan
jumlah informan, baik informan pangkal yang lainnya maupun informan kunci
dan informan selanjutnya. Dengan demikian, pengembangan informan dalam
penelitian ini bersifat snowboll, yakni dari informan ke informana lain.
Penambahan informan akan diakhiri apabila terdapat indikasi bahwa tidak ada
lagi variasi informasi dan kategorisasi data dan informasi telah jenuh.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Informasi : Pengamatan dan
Wawancara Mendalam
1.5.3.1 Pengamatan
Metode pengamatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara mencermati hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
Namun perlu dikemukakan di sini, bahwa dalam pengamatan juga dilakukan

wawancara dengan menanyakan sesuatu yang telah dilihat dan didengar terkait
dengan masalah yang dikaji guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang
lebih jauh. Hal ini biasa dilakukan dalam pengamatan terlibat, sehingga para akhli
mengatakan pengamatan terlibat sebagai pengamatan langsung bersama metode
lainnya dalam pengumpulan informasi (Mulyana, 2006 : 162), atau sebagai
pengamatan yang bercirikan interaksi peneliti dengan subjek (Satori dan
Komariah, 2009 : 117). Aspek-aspek yang akan dicermati dalam pengamatan
adalah (1) keadaan/situasi di rumah informan; (2) orang-orang yang ikut serta
dalam situasi tersebut, termasuk jenis kelamin, usia, profesi, tempat asal, dan
lain-lain; (3) kegiatan yang dilakukan orang dalam situasi tersebut; (4) benda-
benda yang ada di tempat itu serta letak dan penggunaannya; (5) perbuatan, yaitu
tindakan para pelaku dalam proses berlangsungnya kegiatan dalam situasi yang
diamati; ekspresi wajah yang dapat dilihat sebagai cerminan perasan dan emosi.
1.5.3.2 Wawancara Mendalam
Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini terutama
untuk menggali informasi mengenai pengalaman individu yang biasanya disebut
sebagai metode penggunaan data pengalaman individu (individual life history)
atau dokumen manusia (human document) (Koentjaraningrat, 1989 : 158). Dalam
hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan leluasa tanpa
terikat pada suatu daftar pertanyaan rinci yang disiapkan sebelumnya. Dengan
cara ini memungkinkan wawancara berlangsung luwes, arahnya bisa lebih terbuka
sehingga diperoleh informasi yang lebih kaya, pembicaraan tidak terlampau

terpaku atau tidak menjenuhkan/membosankan baik bagi peneliti maupun bagi
informan.
1.5.3.4 Teknik Analisis Data
Analisis data/informasi akan dilakukan dengan teknik analisis interpretatif,
terutama secara emik tetapi juga secara etik, sehingga dapat dihindari
kemungkinan adanya masalah dengan informan yang telah melakukan sesuatu
tindakan tetapi tidak mampu menginfoprmasikan maknanya sebagaimana
dikatakan oleh Brian Vay (2004). Proses analisis ini bisa sejalan dengan proses
wawancara dan pengamatan, artinya analisis dilakukan secara bergantian dengan
wawancara dan pengamatan dalam satu paket waktu. Secara konkret
mekanismenya bahwa setiap informasi penting yang diperoleh dari informan
langsung dianalisis untuk membuat hipotesis-hipotesis kecil yang kemudian
digunakan untuk membuat pertanyaan yang diajukan berikutnya. Dengan
demikian teknik analisis dan wawancara tersebut mengacu kepada apa yang oleh
Taylor dan Bogdan (1984 : 128)disebut dengan istilah go hand-in-hand. Data
yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar berwujud data
kualitatif. Data ini akan dianalisis dengan mengikuti prosedur analisis data
kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu
reduksi data, menyajikan data, menafsirkan data, dan menarik simpulan. Kegiatan
pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan
rangkaian kegiatan yang terkait dan bisa berlangsung secara ulang-alik, sampai
mendapatkan hasil penelitian akhir, yakni etnografi yang bersifat holistik dan

sarat makna, dalam konteks pemberian jawaban terhadap masalah yang dikaji
dalam penelitian ini.

BAB IIHASIL PENELITIAN :
SISTEM SOSIOKULTURAL DALAM KONTEKS SUBAKJATILUWIH
Kawasan Subak Jatiluwih pada dasarnya merupakan wilayah yang di
dalamnya terdapat sawah dan para petani pemilik dan/atau penggagarap sawah
tersebut. Dilihat dari perspektif teori sistem sosiokultural Sanderson sebagaimana
telah dipaparkan di atas, tampaklah bahwa di dalam kawasan tersebut terdapat
beberapa unsur sistem sosiokultural yang berpotensi untuk membangun
manajemen kawasan subak yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.
Beberapa unsur sistem sosiokultural tersebut meliputi infrastruktur, struktur
sosial, dan superstruktur ideologis yang dapat digambarkan sebagai berikut.
2.1 Infrastruktur : Ekologi, Demografi, Ekonomi, dan Teknologi
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, infrastruktur merupakan
salah satu komponen pokok sistem sisiokultural yang terdiri dari empat
subkomponennya : ekologi, demografi, ekonomi, dan teknologi. Berkenaan
dengan hal ini, melalui penelitian di kawasan Subak Jatiluwih Kecamatan
Penebel Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali diperoleh data yang menunjukkan
adanya potensi sosiokultural untuk membangun manajemen WBD berbasis
masyarakat dan budaya di kawasan subak tersebut. Adapun data yang dimaksud
dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Arti istilah ekologi dalam hal mengacu kepada pendapat Sanbderson (2011
: 59-61), yaitu meliputi seluruh lingkungan fisik yang terhadapnya manusia harus
beradaptasi. Ia meliouti sifat-sifat tanah, sifat iklim, pola hujan, sifat kehidupan
tanaman dan binatang, serta ketersediaan sumber daya alam. Sesuai dengan
pengertian ini, kawasan Subak Jatiluwih dilihat sebagai ekologi yang secara fisik
berbatasan dengan kawasan atau wilayah di sekitarnya. Di sebelah utara
berbatasan dengan kawasan hutan, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah
Desa Babahan, di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Wangaya Gede,
dan di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Senganan. Jarak antara
kawasan ini dengan Kota Kecamatan Penebel (13 km.), Kota Kabupaten Tabanan
(26 km.), dan Kota Propinsi Bali (47 km.).
Peta Desa Jatiluwih menunjukkan bahwa sawah Subak Jatiluwih
merupakan bagian dari wilayah Desa Jatiluwih. Luas keseluruhan desa ini adalah
2.233 ha., yang secara garis besar terbagi ke dalam 4 peruntukan : 1) tanah sawah
(303 ha), 2) ladang/kebun (814 ha), pekarangan (24 ha) dan lain-lain (jurang)
seluas 1.092 ha. Peruntukan lahan ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi
masyarakat terhadap kondisi lingkungan alam setempat dalam rangka memenuhi
berbagai macam kebutuhan hidup mereka. Kondisi lingkungan alam tersebut
dapat diketahui antara lain dari kondisi geografisnya, terutama ketinggian
letaknya tidak merata, yaitu antara 500-1500 meter di atas permukaan laut.
Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa kemiringan kawasan ini cukup
tajam. Secara topografis, kemiringan kawasan ini, memang cukup tajam dan tidak
merata, yakni antara 26-29 derajat.

Berkenaan dengan bidang pertanian dalam arti luas, Petugas Penyuluhan
Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Jatiluwih, yaitu
Tama (2009 : 11), menunjukkan data mengenai potensi wilayah ini di bidang
pertanian.
”Pada umumnya WKPP Jatiluwih sangat potensial untuk pengembanganPeternakan dan Perikanan, terutama ternak sapi karena tersedianya pakanternak terutama rumput lapangan yang tersedia sepanjang tahun.terkecoalipada bulan-bulan tertentu misalnya bulan Juli sampai dengan Septemberpakan rumput agak berkurang. tetapi petani bisa menyiasati dengantanaman pengganti seperti batang pisang, pelepah kelapa, pelepah pakis,dllnya.tetapi juga banyak kendala yang dihadapi petani seperti modal yangmasih kecil serta menganggap ternak sapi merupakan usahasampingandiluar usaha pokok bertani padi. Adapun kelemahan petanipeternak sapi di WKPP Jatiluwih adalah sbb :
1. kandang terlalu sempit.
2. Kandang tidak berdinding pada umumnya sapi kedinginan.
3. Petani pada umumnya menengok sapinya sekali sehari”.
Jika disimak tampaklah bahwa pada dasarnya masalah yang terjadi di bidang
peternakan sapi di Desa Jatiluwih berupa apa yang disebut oleh Tama sebagai
kendala, yakni kurang memadainya modal dan kurang layaknya kondisi kandang
untuk beternak sapi secara efektif. Tampaknya masalah tersebut dapat ditangani
dengan memahami dan menggunakan teknologi tepat guna di bidang peternakan
sapi sehingga dapat diharapkan sapi yang dipelihara bisa sehat dan gemuk
sehingga harga jualnya bisa tinggi. Dengan harga jual sapi yang tinggi tentu saja
memungkinkan bagi peternak yang bersangkutan untuk memperbesar modalnya
untuk meningkatkan usaha peternakan sapinya. Sapi, selain bernilai ekonomis
juga dapat digunakan untuk melestarikan budaya lokal. Budaya lokal yang
dimaksud seperti membajak, sehingga bisa menghemat biaya produksi pertabian

ketimbang menggunakan traktor yang memerlukan biaya ekonomi lebih tinggi,
baik untuk membeli traktor maupun bahan bakar dan kemungkinan biaya untuk
perawatannya. Selain itu kotoran sapi pun bisa digunakan sebagai bahan pupuk
organik untuk pertanian sehingga kelestarian tanah dapat dipertahankan sesuai
dengan gagasan terkait dengan WBD.
Selain beternak sapi, masyarakat Desa Jatiluwih juga memelihara berbagai
macam ternak : kerbau, kuda, kambing, babi, ayam buras, petelur, itik, entok,
angsa, merpati, burung puyuh, kelinci, bekisar, dan burung berkicau. Populasi
masing-masing jenis ternak ini adalah sebagaimana tampak pada tabel 1 di bawah
ini.
Tabel 1
Populasi Ternak di Desa Jatiluwih
No. Jenis Ternak Ternak Besar Unggas
Jantan Betina
1 Sapi 462 802
2 Kerbau 12 22
3 Kuda 1 -
4 Kambing 4 10
5 Babi 528 388
6 Ayam buras - - 4055
7 Ayam petelur - - 303.400
8 Ayam pedaging - - 0

9 Itik - - 930
10 Entok - - 12
11 Angsa - - 4
12 Merpati - - 22
13 Burung Puyuh - - 4
14 Kelinci - - 25
15 Bekisar - - 5
16 Burung berkicau - - 32
Sumber data : Tama (2009 : 12).
Data pada tabel 1 di atas secara jelas menunjukkan bahwa ada 15 jenis
ternak yang dipelihara oleh masyarakat di Desa Jatiluwih. Populasinya beragam,
dari yang terkecil (1 ekor kuda) sampai yang terbesar (303.400 ekor ayam
petelur). Tentu saja semua jenis ternak tersebut bernilai jual, namun ada beberapa
di antaranya yang populasinya sangatlah minim, seperti kambing hanya 14 ekor,
entok 12 ekor padahal sebagaimana diketahui, harga kambing dan entok relatif
mahal. Pasar pun tampaknya membutuhkan jenis ternak ini. Misalnya kambing,
selain dibutuhkan untuk bahan sate dan gule kambing yang banyak penggemarnya
juga untuk keperluan upacara agama Hindu di Bali. Jika peternakan di Desa
Jatiluwih dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna, kiranya
bermacam-macam jenis ternak tersebut di atas dapat ditingkatkan, baik kuantitas
maupun kualitasnya, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan
peternak yang bersangkutan. Seperti halnya ternak sapi, jenis ternak sebagaimana

tercantum dalam tabel di atas juga dapat dilihat sebagai potensi untuk mendukung
gagasan WBD, yakni melestarikan lingkungan alam, terutama dengan
menggunakan kotoran ternak tersebut sebagai bahan pupuk organik.
Seiring dengan perkembangan bidang peternakan, ternyata data tahun 2011
mengenai ternak tertentu di Jatiluwih menunjukkan penurunan populasinya
dibandingkan dengan populsinya pada tahun 2009 sebagaimana tampak pada tabel
1 di atas. Data mengenai perbandingan populasinya itu dapat dilihat pada tabel 2
di bawah ini.
Tabel 2Perbandingan Pupulasi Ternak (2009 dan 2011) di Jatiluwih
No. Jenis Ternak Ternak Besar Unggas
2009 2011 2009 2011
1 Sapi 1.264 500 - -
2 Kerbau 34 6 - -
3 Kuda 1 - - -
4 Kambing 14 - - -
5 Babi 916 900 - -
6 Ayam buras - - 4055 -
7 Ayam petelur - - 303.400 150.000
8 Ayam pedaging - - 0 -
9 Itik - - 930 30
10 Entok - - 12 -

11 Angsa - - 4 -
12 Merpati - - 22 -
13 Burung Puyuh - - 4 -
14 Kelinci - - 25 -
15 Bekisar - - 5 -
16 Burung berkicau - - 32 -
Sumber data : Diolah dari Tama (2009 : 12), dan Data Monografi
Desa Jatiluwih (2011)
Khusus berkenaan dengan budidaya perikanan di Desa Jatiluwih menurut
Tama (2009 : 12-13) tidak berkembang, karena terbatasnya air, terutama di musim
kemarau sering terjadi kekeringan karena letaknya tinggi, dan masyarakat belum
biasa memelihara ikan bersama tanaman padi (mina padi). Akan tetapi masih ada
warga masyarakat di desa ini yang memelihara ikan di kolam, seperti ikan mujair,
ikan mas, ikan nila. Jika masyarakat diberi pengetahuan dan keterampilan
mengenai teknologi tepat guna di bidang perikanan, maka tidak tertutup
kemungkinannya mereka bisa berhasil dalam usaha memelihara ikan.
Keberhasilan memelihara ikan bisa mendorong masyarakat untuk menambah
populasi ikan peliharaannya melalui berbagai cara termasuk dengan cara
mengembangkan budidaya ikan dengan sistem mina padi. Sistem ini bisa
berfungsi ganda, tidak saja untuk menambah pendapatan masyarakat juga bisa
berfungsi ekologis, bahwa secara alamiah ikan menjadi predotor atau pemangsa
serangga yang merupakan hama tanaman padi seperti wereng.

Dilihat dari sudut demografi, ekonomi, dan teknologinya, masyarakat
Desa Jatiluwih tampak mempunyai kondisi tertentu. Menurut buku Data
Monografi Desa Jatiluwih (2011 : 3), penduduknya yang tergolong sebagai tenaga
kerja berjumlah 2389 orang. Dari segi usia, mereka dapat dikelompokkan menjadi
6 kelompok usia dengan jumlah setiap kelompoknya sebagaimana tampak pada
tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4Jumlah Angkatan Kerja di Jatiluwih Menurut Kelompok Umur
No. Kelompok Usia (Tahun) Jumlah Persentase
1 10-14 203 8,50
2 15-19 416 17,40
3 20-26 389 16,29
4 27-40 311 13,02
5 41-56 462 19,36
6 57- ke atas 607 25,43
Total 2388 100
Sumber Data : Diolah dari Buku Data Monografi Desa Jatiluwih (2011 : 3)
2.2 Struktur Sosial : Perilaku Aktual
Struktur sosial mengacu kepada perilaku aktual yang berkaitan dengan
kepolitikan, keluarga, kerabat, dan pendidikan. Dalam konteks ini ada beberapa
organisasi selain subak tersebut yang justru sudah berperan aktif dalam
pengelolaan Subak Jatiluwih. Organisasi tersebut adalah desa Dinas Jatiluwih dan
desa Adat Jatiluwih. Perannya itu tampak antar lain dalam surat pernyataan
bersama para tokoh beberapa organisasi tertanggal 14 Mei 2003, tentang
kiesediaan dan persetujuan mereka atas dimasukkannya Subak Jatiluwih dalam

daftar usulan WBD. Para tokoh tersebut adalah Ketua BPD Jatiluwih, Kepala
Desa Jatiluwih, Kepala Subak Jatiluwih, Bendesa Adat Jatiluwih, Bendesa Adat
Guning Sari, dan Camat Penebel. Surat pernyataan tersebut jelas menunjukkan
adanya potensi untuk mendukung gagasan WBD, yakni melestarikan alam dan
budaya setempat. Potensi tersebut jelas pula merupakan potensi sosiokultural,
karena masing-masing tokoh itu atas nama organisasi yang dipimpinnya yang
tentu saja memiliki aturan.
Nama Subak Jatiluwih sesungguhnya adalah Subak Gede Jatiluwih. Subak
ini merupakan gabungan dari beberapa subak yang merupakan bagiannya. Adapun
beberapa subak yang menjadi bagian dari Subak Gede Jatiluwih dan jumlah
anggotanya adalah sebagasimana tampak pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3Jumlah Anggota Subak-Subak yang Menjadi Bagian dari Subak Gede
JatiluwihNo. Nama Subak Jumlah Anggota
(orang)
1 Subak jatiluwih 70
2 Subak Besi Kalung 79
3 Subak kedamaian 55
4 Subak Medui (Kedamaian Selatan) 51
5 Subak Gunung Sari Desa 35
6 Subak Gunung Sari Mekayu 25
Total Anggota 315
Sumber Data : Laporan Tim Penyusun Master Plan Subak Jatiluwih (2003)

Jumlah anggota subak ini jelas merupakan sumber daya manusia yang jika dapat
dikelola secara efektif memungkinkan untuk mengembangkan manajemen Subak
Jartiluwih sebagai WBD berbasis masyarakat dan budaya lokal.
Selain potensi tersebut, para petani Subak Jatiluwih juga telah terhimpun
ke dalam beberapa kelompok yang secara khusus bergerak dalam bidang
peternakan. Dengan adanya kelompok-kelompok tersebut maka ada peluang
untuk mewujudkan gagasan WBD menjadi kegiatan nyata. Adapun kelompok-
kelompok tersebut meliputi 3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dua dari 3
kelompok ini berusaha di bidang peternakan, yang satu bernama Gabungan
Kelompok Tani Merta Jati berusaha di bidang peternakan sapi dan yang lainnya
bernama Gabungan kelompok Tani Dukuh Sari berusaha di bidang peternakan
babi. Unsur kepolitikan dalam struktur sosial seperti ini berpotensi untuk
mengembangkan cara-cara terorganisasi suatu masyarakat dalam memelihara
hukum, aturan internal dan hubungan individu-individu, termasuk mengendalikan
konflik-konflik sosial terkait dengan pengelolaan kawasan Subak Jatiluwih
sebagai WBD.
2.3 Superstruktur Ideologis : Ideologi Umum, Agama, Ilmu Pengetahuan
Sebagaimana dikemukakan, salah satu unsur superstruktur ideologis
adalah ideologi umum. Ideologi umum mengacu kepada kepercayaan dan norma
yang menonjol dalam masyarakat dalam konteks apa yang baik dan tidak baik,
apa yang benar dan tidak benar, dan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
Dalam konteks ini, subak dan desa pakraman di Bali, termasuk di Jatiluwih
mempunyai peraturan yang disebut awig-awig yang terdiri atas sejumlah bab dan

pasal. Landasan dasarnya adalah filsafat Tri Hita Karana yang menekankan
pentingnya keharmonisan hubungan manusia-Tuhan, manusia-manusia, dan
manusia-lingkungan alam. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam konteks ini,
maka ditentukan hal-hal yang boleh dan/atau tidak boleh dilakukan, yang patut
dan tidak patut dilakukan dalam hubungan manusia dengan lingkungan
sosiokultural dan lingkungan alam. Dengan dermikin, awig-awig subak dan awig-
awig desa pakraman merupakan dua peraturan yang mengandung potensi penting
untuk dijadikan acuan dalam membangun manajemen kawasan WBD berbasis
masyarakat dan budaya lokal.
Selain filsafat Tri Hita Karana, dalam agama Hindu yang dianut oleh
masyarakat di Jatiluwih juga ada beberapa konsep yang berpotensi penting untuk
dijadikasn acuan dalam membangun manajemen WBD berbasis masyarakat dan
budaya lokal. Dikatakan demikian karena dalam ajaran agama Hindu dikenal
berbagai macam konsep yang merupakan kearifan lokal yang memungkinkan
untuk membangun keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan dengan
sesamanya. Adapun konsep-konsep tersebut, antara lain konsep desa-kala-patra;
dharma, artha, kama, moksa; tatwamasi; dan konsep Sagilik Saguluk, Paras
Paros Sarpanaya, Salunglung Subayantaka. Konsep-konsep ini memungkinkan
untuk dipakai pedoman yang efektif dalam mencegah masalah konflik sosial
karena mengandung makna-makna tersendiri yang telah membudaya. Konsep
desa-kala-patra yang mengandung makna yang menekankan pentingnya
pleksibilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diketahui dari
pendapat Mantra (1993 : 14) tentang konsep desa, kala, patra sebagai berikut.

”Konsep ini menunjukkan penerimaan terhadap kenyataan hidupbahwa dalam keseragaman ada keragaman, dalam kesatuan pastiada perbedaan. Hal ini memberi gambaran tentang bentukkomunikasi kebudayaan Bali, baik ke luar maupun ke dalam.Menerima perbedaan dan variasi yang timbul sesuai desa, kala,patra (waktu, tempat, dan keadaan)”.
Petikan ini tampak mencerminkan bahwa konsep desa, kala, patra pada intinya
menekankan pentingnya upaya penyesuaian sikap dan perilaku dalam
menjalankan kehidupan sosial di tengah fenomena keberagaman dan perbedaan,
baik dalam konteks keruangan/tempat (desa) maupun waktu (kala), dan situasi
(patra). Ini berarti konsep desa, kala, patra, mencerminkan ideologi
fleksibilitasisme, yakni kelenturan sikap dan perilaku sosial sesuai dengan
keadaan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Jika konsep ini diterapkan
oleh masyarakat di kawasan Subak Jatiluwih, maka semestinya mereka mampu
mengatur langkah mereka sesuai dengan aturan yang berlaku guna memperoleh
masukan finansial dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam dan
keharmonisan hubungan dengan sesama warga masyarakat.
Konsep dharma, artha, kama, moksa sebagaimana diketahui menekankan
bahwa kebenaran (dharma) perlu dipedomani dalam rangka mencari nafkah
(artha) untuk memenuhi nafsu, keinginan, dan kebutuhan (kama) agar mencapai
kebahagiaan (moksa). Jika hal ini dipadukan dengan konsep desa, kala, patra
sebagaimana dipaparkan di atas, maka secara idealnya upaya mencari nafkah
(artha) untuk memenuhi kebutuhan (kama), selain disesuaikan dengan kebenaran
(dharma) juga dengan situasi dalam konteks ruang/tempat (desa), waktu (kala),
dan keadaan masyarakat setempat (patra). Dengan cara demikian memungkinkan

diperoleh hasil tanpa menimbulkan masalah, dan memungkinkan pula untuk
menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan nyaman.
Serupa dengan itu, konsep Tat Tawam Asi dapat dimaknai sebagai
larangan terhadap kekerasan guna mencapai kedamaian. Hal ini dapat dijadikan
sebagai kode etik karena mengandung arti ”Aku adalah Engkau” sehingga
relevan untuk membangun sikap saling menyayangi antarsesama demi
terwujudnya kedamaian. Pandangan ini mencerminkan kesadaran bahwa dalam
rangka mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat yang satatus dan identitas
warganya berbeda-beda, maka diri sendiri (aku) dan orang lain (engkau) perlu
diposisikan secara dialektis, bukan secara oposisi biner, sehingga bisa hidup
berdampingan secara damai. Jika disimak dengan mengacu gagasan G.W.F Hegel
sebagaimana dikuitip oleh Sitorus (2004 : 167-168), Tat Twam Asi yang diartikan
sebagaimana dipaparkan di atas juga mengandung gagasan bahwa orang lain
(engkau) sebenarnya tidak pernah hadir secara absolut sebagai orang lain. Orang
lain juga berperan dalam keberadaan diri sendiri (aku), tanpa orang lain (engkau)
maka diri sendiri (aku) pun tidak ada. Selain itu, diri sendiri (aku) dan orang lain
(engkau) saling membutuhkan dan dengan demikian saling tergantung. Oleh
karena itu sikap saling menolak antara diri sendiri (aku) dan orang lain (engkau)
sesungguhnya adalah sebuah kekeliruan. Jika pemaknaan terhadap istilah Tat
Twam Asi di atas dikaji dengan mengacu gagasan Durkheim tentang solidaritas
ssosial sebagaimana dikutip oleh Laeyendecker (1983 : 291), istilah Tat Twam Asi
juga mencerminkan adanya ideologi solidaritasisme yang bersifat organis, yakni
ideologi yang menekankan pada pentingnya kerjasama atas dasar rasa saling

membutuhkan dan saling tergantung antarawarga masyarakat yang memiliki ciri-
cirinya masing-masing. Dengan demikian ideologi yang terkandung dalam istilah
Tat Twam Asi itu memang sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam
membangun manajemen berbasis masyarakat dan budaya lokal di kawasan Subak
Jatiluwih.
Terkait dengan konsep Sagilik Saguluk, Paras Paros Sarpanaya,
Salunglung Subayantaka menekankan pentingnya komitmen (janji kepada
sesama), kesadaran kolektif (senasib dan sepenanggungan), dan rasa hormat-
menghormati dan seterusnya. Oleh karena itu, dikaji dengan mengacu gagasan
Durkheim tentang solidaritas sosial sebagaimana dikutip oleh Laeyendecker (1983
: 290) tampaklah konsep ini mencerminkan adanya ideologi solidaritasisme yang
bersifat mekanis. Solidaritas sosial seperti ini tentu saja merupakan potensi yang
penting untuk membangun keharmonisan sosial dalam berbagai bidang
kerhidupan, termasuk dalam pengelolaan WBD. Mempunyai berbagai sarana fisik
yang dapat dimaknai dan difungsikan sebagai pengikat masyarakat agar mereka
Subak Jatiluwih dan Desa Pakraman Jatiluwih mempunyai berbagai sarana
fisik yang dapat dimaknai dan difungsikan sebagai pengikat masyarakat agar
mereka secara bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk melestarikan
budaya dan lingkungan alam setempat. Sarana fisik yang dimaksudkan dalam hal
ini adalah pura subak, bendungan, dan pura desa. Terkait dengan sarana fisik ini,
masyarakat memiliki kepercayaan akan adanya kekuatan supernatural diyakini
dapat mengadili manusia jika melakukan hal-hal yang tidak patut dilaksanakan.

BAB III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN :PERSPEKTIF MANAJEMEN WARISAN BUDAYA DUNIA
BERBASIS MASYARAKAT DAN BUDAYA LOKALDALAM PENGELOLAAN KAWASAN SUBAK JATILUWIH
Sebagaimana diketahui, manajemen kelembagaan berproses secara
dinamis melalui tahapan-tahapannya yang secara garis besar meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Oleh karena itu, dalam rangka
membangun manajemen warisan budaya dunia berbasis masyarakat dan budaya
lokal berdasarkan potensi sistem sosiokultural dalam pengelolaan Subak
Jatiluwih, maka langkah yang patut dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sosial budaya
dan lingkungan alam setempat. Untuk itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah
dipaparkan pada bab II di atas, model manajemen warisan budaya dunia yang
memungkinkan untuk dikembangkan dalam pengelolaan Subak Jatiluwih dapat
digambarkan sebagai berikut.

Perencanaan merupakan satu tahapan yang paling awal dalam
membangun suatu manajemen. Definisi perencanaan dalam hal ini mengacu
kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan perencanaan pembangunan adalah
suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sejalan dengan itu, Dror
sebagaimana dikutip oleh Schoorl (1980 : 294), mendefinisikan perencanaan
sebagai proses dalam penyiapan seperangkat keputusan mengenai tindakan di
kemudian hari yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan
menggunakan cara-cara yang optimal.
Jika perencanaan dalam arti seperti itu disusun dalam rangka pengelolaan
Subak Jatiluwih sebagai WBD berdasarkan potensi sistem sosiokultural
sebagaimana dipaparkan pada bab II di atas, maka model perencanaan yang
memungkinkan untuk itu adalah perencanaan yang sesuai dengan filsafat Tri Hita
Karana. Artinya, bahwa keharmonisan hubungan antara manusia-Tuhan,
manusia-alam (lahan sawah, air, dan binatang), hubungan antara warga
masyarakat setempat (warga subak, desa pakraman, dan deasa dinas) tetap
dijadikan sebagai pegangan utama dalam proses perencanaan tersebut. Filsafat
yang demikian itu tentu saja dapat dijadikan acuan penting dalam membangun
manajemen warisan budaya dunia berbasis masyarakat dan budaya lokal.
Dikatakan sebgai acuan penting, karena dengan filsafat tersebut dapat diharapkan
terjadi sinergi antara para pihak terkait, meskipun masing-masing pihak
mempunyai status yang berbeda-beda. Berdasarkan sinergi yang memadai dapat

diharapkan mereka membangun konerja sesuai dengan tujuan penetapan Subak
Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia.
Selain itu, konsep-konsep yang sejalan dengan itu yang ada dalam ajaran
agama Hindu di Bali pun tidak kalah pentingnya untuk dijadikan acuan utama
dalam perencanaan pembangunan Subak Jatiluwih. Ada beberapa konsep
merupakan kearifan lokal masyarakat dan kebudayaan Bali, antara lain berupa
konsep-konsep yang mengandung nilai budaya yang patut dijadikan pedoman
dalam rangka menciptakan keharmonisan sosial. Konsep-konsep tersebut antara
lain desa-kala-patra; dharma, artha, kama, moksa; tatwamasi; dan konsep Sagilik
Saguluk, Paras Paros Sarpanaya, Salunglung Subayantaka. Konsep-konsep ini
memungkinkan untuk dipakai pedoman yang efektif dalam mencegah masalah
konflik sosial karena mengandung makna-makna tersendiri yang telah
membudaya. Konsep desa-kala-patra yang mengandung makna yang
menekankan pentingnya pleksibilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini
dapat diketahui dengan mencermati pendapat Mantra (1993 : 14) tentang konsep
desa, kala, patra sebagai berikut.
”Konsep ini menunjukkan penerimaan terhadap kenyataan hidupbahwa dalam keseragaman ada keragaman, dalam kesatuan pastiada perbedaan. Hal ini memberi gambaran tentang bentukkomunikasi kebudayaan Bali, baik ke luar maupun ke dalam.Menerima perbedaan dan variasi yang timbul sesuai desa, kala,patra (waktu, tempat, dan keadaan)”.
Petikan ini tampak mencerminkan bahwa konsep desa, kala, patra pada intinya
menekankan pentingnya upaya penyesuaian sikap dan perilaku dalam
menjalankan kehidupan sosial di tengah fenomena keberagaman dan perbedaan,
baik dalam konteks keruangan/tempat (desa) maupun waktu (kala), dan situasi

(patra). Ini berarti konsep desa, kala, patra, mencerminkan ideologi
fleksibilitasisme, yakni kelenturan sikap dan perilaku sosial sesuai dengan
keadaan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Jika konsep ini diterapkan
dalam rangka membangun manajemen Subak Jatiluwih, maka apat diharapkan
bahwa para pihak terkait akan mampu mengatur langkah mereka sesuai dengan
aturan yang berlaku guna mencapai tujuan pembangunan Subak Jatiluwih.
Konsep dharma, artha, kama, moksa sebagaimana diketahui menekankan
bahwa kebenaran (dharma) perlu dipedomani dalam rangka mencari nafkah
(artha) untuk memenuhi nafsu, keinginan, dan kebutuhan (kama) agar mencapai
kebahagiaan (moksa). Jika hal ini dipadukan dengan konsep desa, kala, patra
sebagaimana dipaparkan di atas, maka secara idealnya upaya mencari nafkah
(artha) untuk memenuhi kebutuhan (kama), selain disesuaikan dengan kebenaran
(dharma) juga dengan situasi dalam konteks ruang/tempat (desa), waktu (kala),
dan keadaan masyarakat setempat (patra). Dengan cara demikian memungkinkan
diperoleh hasil tanpa menimbulkan masalah, dan memungkinkan pula untuk
menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan nyaman.
Serupa dengan itu, konsep Tat Tawam Asi dapat dimaknai sebagai
larangan terhadap kekerasan guna mencapai kedamaian. Hal ini dapat dijadikan
sebagai kode etik karena mengandung arti ”Aku adalah Engkau” sehingga
relevan untuk membangun sikap saling menyayangi antarsesama demi
terwujudnya kedamaian. Pandangan ini mencerminkan kesadaran bahwa dalam
rangka mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat yang satatus dan identitas
warganya berbeda-beda, maka diri sendiri (aku) dan orang lain (engkau) perlu

diposisikan secara dialektis, bukan secara oposisi biner, sehingga bisa hidup
berdampingan secara damai. Jika disimak dengan mengacu gagasan G.W.F Hegel
sebagaimana dikuitip oleh Sitorus (2004 : 167-168), Tat Twam Asi yang diartikan
sebagaimana dipaparkan di atas juga mengandung gagasan bahwa orang lain
(engkau) sebenarnya tidak pernah hadir secara absolut sebagai orang lain. Orang
lain juga berperan dalam keberadaan diri sendiri (aku), tanpa orang lain (engkau)
maka diri sendiri (aku) pun tidak ada. Selain itu, diri sendiri (aku) dan orang lain
(engkau) saling membutuhkan dan dengan demikian saling tergantung. Oleh
karena itu sikap saling menolak antara diri sendiri (aku) dan orang lain (engkau)
sesungguhnya adalah sebuah kekeliruan. Jika pemaknaan terhadap istilah Tat
Twam Asi di atas dikaji dengan mengacu gagasan Durkheim tentang solidaritas
ssosial sebagaimana dikutip oleh Laeyendecker (1983 : 291), istilah Tat Twam Asi
juga mencerminkan adanya ideologi solidaritasisme yang bersifat organis, yakni
ideologi yang menekankan pada pentingnya kerjasama atas dasar rasa saling
membutuhkan dan saling tergantung antarawarga masyarakat yang memiliki ciri-
cirinya masing-masing. Dengan demikian ideologi yang terkandung dalam istilah
Tat Twam Asi itu memang sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam
membangun kerjasama (bukan perseteruan) antara kelompok sosial yang berbeda
seperti antara para pihak terkait dalam pengelolaan Subak Jatiluwih sebagai
warisan budaya dunia dan/atau sebagai daerah tujuan wisata.
Terkait dengan konsep Sagilik Saguluk, Paras Paros Sarpanaya,
Salunglung Subayantaka menekankan pentingnya komitmen (janji kepada
sesama), kesadaran kolektif (senasib dan sepenanggungan), dan rasa hormat-

menghormati dan seterusnya. Oleh karena itu, dikaji dengan mengacu gagasan
Durkheim tentang solidaritas sosial sebagaimana dikutip oleh Laeyendecker (1983
: 290) tampaklah konsep ini mencerminkan adanya ideologi solidaritasisme yang
bersifat mekanis. Ideologi solidaritasisme yang bersifat mekanis ini memang
tampak penting dan relevan dalam rangka mencegah perseteruan antara para pihak
yang terlibat dalam suatu kegiatan bersama, seperti halnya dalam pengelolaan
Subak Jatiluwih.
Agar dapat menyusun perencanaan seperti itu serta melaksanakan, maka
konsep Tri Hita Karana dan konsep-konsep lain yang sejalan dengan itu perlu
dipahami dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Tanpa demikian bukan
tidak mungkin akan timbul berbagai masalah yang mengganggu langkah
pencapaian tujuan pengelolaan Subak Jatiluwih sebagai WBD, yakni melestarikan
lingkungan alam dan budaya setempat. Dikatakan demikian karena sebagaimana
dikemukakan oleh Basrowi dan Sukidin (2003), Mustain (2007), dan Yunita
(1986), bahwa setiap manusia yang bersifat rasional akan memiliki motivasi kuat
untuk melakukan suatu kegiatan yang menjanjikan keuntungan bagi dirinya
sendiri. Dilihat dari perspektif teori pertukaran, maka keuntungan dalam konteks
teori rasionalitas itu lebih mengarah kepada keuntungan finansial berupa uang
tunai sebagai hasil dari pertukaran. Dalam konteks ini pendapat Damsar (2006 :
33), penting untuk dicermati, yakni sebagai berikut.
“Teori pertukaran melihat bahwa uang sebagai salah satu rujukan utamaorang untuk terus menerus terlibat dalam memilih di antara perilaku-perilaku alternatif. Suatu tindakan sosial dipandang ekuivalen dengantindakan ekonomis. Suatu tindakan dipandang rasional apabila seseorangmenghasilkan uang. Oleh sebab itu, makin tinggi uang yang diperolehmakin besar kemungkinan suatu tingkah laku akan diulang”.

Dengan mengacu teori rasionalitas dan teori pertukaran ini, maka pengelolaan
Subak Jatiluwih berpeluang menimbulkan upaya para pihak terkait untuk
memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri melalui
cara-cara yang membuat pihak tertentu merasa diperlakukan secara kurang adil.
Masalah seperti ini berpotensi menjadi penghambat para pihak yang merasakan
ketidakadilan dalam ikut serta melestarikan alam dan budaya setempat. Dengan
demikian tujuan penetapan Subak Jatiluwih sebagai WBD sulit dicapai.
Untuk mengantisipasi timbulnya masalah seperti itu, maka suatu langkah
yang penting untuk dilaksanakan adalah menempatkan wakil dari kelompok-
kelompok masyarakat (subak, desa pakraman, desa dinas) secara proporsional
dalam personel badan pengelola Subak Jatiluwih, baik sebagai WBD maupun
sebagai daerah wisata. Penempatan wakil kelompok-kelompok masyarakat
tersebut hendaknya sesuai dengan kemauan, kompetensi, dan kemampuannya
pada bidang-bidang tugas yang ada dalam pengelolaan Subak Jatiluwih. Hal ini
penting agar mereka dapat bersinergi dan berkinerja kinerja secara optimal.
Selain itu, pembagian hasil pengelolaan Subak Jatiluwih pun perlu dilakukan
dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan. Dengan demikian
dapat diharapkan semua pihak merasa puas atas tata cara pengelolaan subak
tersebut, dan dengan demikian pula semua pihak dapat diharapkan akan ikut
berperan aktif dan sungguh-sungguh dalam upaya melestarikan lingkungan alam
dan budaya setempat secara bersama-sama dan berkelanjutan sesuai dengan
tugasnya masing-masing.

Agar terwujud keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan alam,
maka teknologi yang mesti digunakan dalam pengelolaan Subak Jatiluwih adalah
teknologi pertanian dalam arti luas yang tetapt guna dan ramah lingkungan. Hal
ini perlu dilakukan dalam bidang bercocok tanam di sawah dan diladang, bidang
peternakan, dan bidang perikanan. Dengan mengimplementasikan nulai-nilai Tri
Hita Karana, usaha di bidang pertanian dalam arti luas ini dapat diharapkan dapat
berjalan secara lancar, tertib dan aman.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasannya dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1) Sistem sosiokultural : infrastruktur material, struktur sosial, dan
superstruktur ideologis yang berkaitan dengan Subak Jatiluwih terlihat
mempunyai potensi yang memungkinkan untuk mendukung
pengembangan manajemen berbasis masyarakat dan budaya setempat
dalam pengelolaan subak tersebut.
2) Model manajemen berbasis masyarakat dan budaya lokal yang
memungkinkan untuk dikembangkan dalam pengelolaan Subak Jatiluwih
adalah yang manajemen yang berlandaskan para filsafat Tri Hita Karana
serta konsep-konsep yang sejalan dengan filsafat tersebut dan merupakan
kearifan lokal masyarakat Bali. Pada intinya konsep-konsep tersebut
menekankan betapa pentingnya keharmonisan dalam hubungan manusia –
Tuhan, manusia-manusia, dan manusia-lingkungan alam. Selain itu
konsep-konsep tersebut menekankan pentingnya kebenaran (dharma)
untuk menuntun langkah mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan,
namun tetap dengan sikap yang luwes sesuai dengan konteks waktu dan
ruang. Hal ini perlu dijadikan acuan utama dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan Subak Jatiluwih guna
mencapai tujuan penetapan subak tersebut sebagai warisan budaya dunia.
4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diajukan dalam hal ini
adalah sebagai berikut.
1) Agar kelestarian alam dan budaya lokal yang terkait dengan Subak
Jatiluwih dapat dicapai, maka para pihak terkait (petani subak, masyarakat
Desa Pakraman Jatiluwih, Masyarakat Desa Dinas Jatiluwih, Pemerintah
Daerah Kabupaten Tabanan, dan Pemerintah Provinsi Bali), mesti benar-
benar menjadikan filsafat Tri Hita Karana sebagai pedoman dalam
pengelolaan Subak Jatiluwih.
2) Untuk itu, semua pihak tersebut perlu memahami dan
mengimplementasikan filsafat Tri Hita Karana secara sungguh-sungguh
dan dinamis, yakni menyesuaikan pelaksanaannya dengan situasi yang
aktual dalam konteks waktu dan tempat pelaksanaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Amal, I. 1998. “Perspektif Pembangunan Jangka Panjang : Globalisasi,Demokrasi, dan Wawasan Nusantara”. Dalam Y.M.A. Aziz (ed.) VisiGlobal Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke-21. Yogyakarta : PustakaPelajar. Halalam 44-52.
Basrowi dan Sukidin. 2003. Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif.Surabaya : Penerbit Insan Cendekia.
Barker, Chris. 2005. Cultural Studies : Teori dan Praktik. Yogyakarta : PTBentang Pustaka.
Brian Fay. 2002. Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer. Yogyakarta, Penerbit Jendela.Dhana, I Nyoman. 2010 Penguatan Strategi Pembangunan Ekonomi yang
Berwawasan Nusantara Guna Menjaga Ketahanan Nasional dalam Rangka

Memperkokoh NKRI : Perspektif Sosial Budaya. Makalah dalam RangkaFGD, diselenggarakan oleh MPR RI Bekerjasama dengan UniversitasUdayana, Denpasar, 27 Nopember 2010.
Deperindag. 2008. Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025. Makalah dalamCreative Converence, di Bali.
Depbudpar. 2009. Kegiatan Tahun Indonesia Kreatif 2005. Makalah dalamSeminar Indonesia Kreatif, di Bogor.
Fashri, Fauzi. 2007. Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif PemikiranPierre Bordieu. Yogyakarta : Juxtapose.Geriya, I Wayan dkk.2009. Kebudayaan Unggul Inventori Unsur Unggulan
sebagai Basis Kota Denpasar Kreatif. Denpasar Bappeda Kota denpasar.Geriya, I Wayan dkk. 2010. Inovasi Budaya Pengembangan Kewirausahaan dan
Partisipasi Masyarakat untuk Penguatan Industri dan Kota KreatifDenpasar. Laporan Penelitian. Denpasar : Bappeda Kota Denpasar.
Geertz, C. 1971. The Interpretation of Cultures. New York : Basic Book.Geertz, C. 1984. ”Tihingan : Sebuah Desa di Bali”. Dalam Koentjaraningrat (ed),
Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta : Lembaga Penerbit FakultasEkonomi Universitas Indonesia. Halalam 246-277.
Geertz, C. 1989. Penjaja dan Raja. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.Harris, Marvin. 1979 Cultural Materialism The Struggle for a Science of Culture.
New York : Random House.Koentjaraningrat. 1980. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta : PT Dian
Rakyat.Koentjaraningrat. 1989. “Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu”,
dalam Metode-Metode Penelitianm Masyarakat (Koentjaraningrat,red.). Jakarta, Penerbit PT Gramedia. Halaman 158-172.
Koentjaraningrat. 1980. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta : PT DianRakyat.
Koentjaraningrat. 1989. “Metode Wawancara”. Dalam Metode-Metode PenelitianMasyarakat (Koentjaraningrat, red.). Jakarta, Penerbit PT Gramedia.Halaman 129-157.
Laeyendecker, Leonardus. 1983. Tata, Perubahan, dan Ketimpangan. Jakarta :Penerbit PT Gramedia.
Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumbertentang Metode-Metode Baru (Tjetjep Rohindi, penerjemah). Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia.
Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi Kualitatif : Paradigma baru Ilmu Komunikasidan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Mustain. 2007. Petani VS Negara Gerakan Sosial Petani Melawan HegemoniNegara. Yogyakarta : AR-Ruzz Media.
Nash, Dennison. 1987. “Tourism as a Form of Imperialism”. Dalam Valeme L.Smith (ed) Hosts and Guests The Anthropology of Tourism. Oxford : BasilBlackwell. Halaman 33-47.
Nugroho, H. 2006. “Kata Pengantar”. Dalam G. Ritzer, The Globalization of

Nothing Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi (I.Lucianda,penerjemah). Yogyakarta : Universitas Atmadjaja. Halamanxxiii-xxx.
Piliang, Y.A. 2005. “Antara Minimalisme dan Pluralisme”. Dalam. A. Adlin (ed.).Menggeledah Sebuah Hasrat Sebuah Pendekatan Pulti Perspektif.Yogyakarta : Jalasutra. Halaman 1-24.
Pronk. J.P. 1993. Sedunia Perbedaan Sebuah Acuan dalam KerjasamaPembangunan Tahun 1990-an (S. Maimoen, penerjemah. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
Ramanthra, I Wayan, 2010. Alam dan Budaya Bali Sebagai Basis PembangunanEkonomi Kreatif. Makalah dalam Seminar Nasional Kebudayaan Balidalam Rangka Dies Natalis Ke-48 Universitas Udayana. Denpasar, 17September 2010.
Richard, G. 1997. Cultural Tourism in Europe. Wallingford: CAB International.Ritzer, G. 2006. The Globalization of Nothing Mengkonsumsi Kehampaan di Era
Globalisasi (I. Lucianda,penerjemah). Yogyakarta : UniversitasAtmadjaja.
Ryan, Chris and Micelle Aiken (eds). 2005. Indigenous Tourism: TheCommodification and Management of Culture. Amsterdam: Elsevier.
Sanderson, Stephen K. 1993. Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan TerhadapRealitas Sosial(Farid Widjidi dan S.Menno, penerjemah). Jakarta :Rajawali Press.
Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung : Alfabeta.
Shiva, Vandana. 1993. “Kata pengantar”. Dalam Perspektif Sosial dan EkologiKeragaman Hayati (Hira Jamtani, ed.). Jakarta : Kophalindo. Halalam 7-13.
Sitorus, F.K. 2004. “Identitas Dekonstruksi Permanen”, dalam Mudji Sutrisno danHendar Putranto (ed.). Hermeneutika Pascakolonial . Yogyakarta :Kanisius. Halaman 155-171.
Soemardjan, Selo. 1993 “Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan”, dalamMasyarakat dan Manusia dalam Pembangunan : Pokok-PokokPikiranSelo Soemardjan (Desiree Zuraida dan Jufrina Rizal, penyunting). Jakarta :Pustaka Sinar Harapan. Halaman 25-230.
Steger, Manfred B. Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar. Yogyakarta :Lafadl.Suparlan, Parsudi. 1986. “Masalah-Masalah Sosial dan IlmuSosialDasar”. Dalam Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat(A.W. Widjaja, penyunting). Jakarta : Akademika Pressindo. Halaman 61-74.
Taylor, Steven dan Bogdan Robet, 1984.Introduction to Qualitative ResearchMethods. New York, John Wiley & Sons.
Yunita, T Winarto. 1986. “Perberdaan Antara Interpretasi Neofungsionalisme danTindakan Individu yang Rasional”, dalam Berita Antropologi. JurusanAntropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.Jakarta. Halaman 66-80

LAMPIRAN : DAFTAR INFORMAN
1) I Wayan Diasa, mantan Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Tabanan.
2) I Nengah Wirata, ST, mantan Kepala Desa Jatiluwih.
3) I Nengah Kartika, Kepala Desa Jatiluwih.
4) I Nyoman Sutama, B Sc. Pekaseh Subak Jatiluwih.