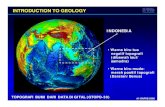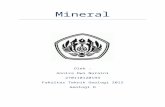Laporan Fieldtrip Geologi Dasar
-
Upload
diva-alfiansyah -
Category
Documents
-
view
461 -
download
6
Transcript of Laporan Fieldtrip Geologi Dasar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM STUDI GEOFISIKA JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
LAPORAN FIELDTRIP GEOLOGI DASAR
(BAYAT, KLATEN)
DISUSUN OLEH:
DIVA ALFIANSYAH
12/330930/PA/14410
ASISTEN LAPANGAN:
FITRUL ISLAM
YOGYAKARTA
2013
1

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Fieldtrip Geologi Dasar
(Kabupaten Klaten)
Oleh :
Diva Alfiansyah
(12/330930/PA/14410)
Diterima dan disahkan oleh :
Program Studi Geofisika Jurusan Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Juni 2013
Asisten Lapangan,
Fitrul Islam
2

KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahiim
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat
menyelesaikan Laporan Fieldtrip Geologi Dasar ini. Adapun laporan ini disusun
guna menjelaskan secara detail mengenai kegiatan Fieldtrip Geologi Dasar yang
dilaksanakan pada Minggu, 26 Mei 2013 di Kabupaten Klaten.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Shalahuddin Husein, S.T,
M.Sc., Ph.D., Fitrul Islam selaku asisten lapangan dan seluruh kakak-kakak
asisten yang telah memberikan bimbingan selama jalannya kegiatan Fieldtrip
Geologi Dasar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada orang tua atas doa dan
dukungannya serta teman-teman dan semua pihak yang telah membantu hingga
terselesaikannya laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan
ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat
kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini.
Akhirnya sekian dari kami, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di
hati para pembaca, kami mohon maaf. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat
bagi semua pihak, baik secara praktis maupun manfaat keilmuan.
Yogyakarta, 29 Mei 2013
Penyusun,
Diva Alfiansyah
12/330930/PA/14410
3

DAFTAR ISI
Halaman Judul.......................................................................................................i
Lembar Pengesahan...............................................................................................ii
Kata Pengantar.......................................................................................................iii
Daftar Isi................................................................................................................iv
Daftar Gambar.......................................................................................................vi
Daftar Tabel...........................................................................................................vii
I. Pendahuluan...................................................................................................1
A. Latar Belakang.........................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan..................................................................................1
C. Waktu, Letak, dan Kesampaian Daerah...................................................1
D. Peralatan...................................................................................................2
II. Geologi Regional............................................................................................4
A. Fisiografi Pulau Jawa...............................................................................4
B. Stratigrafi Regional..................................................................................6
C. Struktur Geologi Regional........................................................................8
III. Isi....................................................................................................................11
A. Stasiun Pengamatan 1 (STA 1).................................................................11
1. Lokasi STA.........................................................................................11
1.1 Lokasi STA...................................................................................11
1.2 Waktu Pengamatan.......................................................................11
1.3 Cuaca............................................................................................11
1.4 Lokasi Pengamatan.......................................................................12
2. Geomorfologi STA.............................................................................12
3. Litologi dan Mineralogi......................................................................13
a. Litologi dan Mineralogi Lokasi Pengamatan 1............................13
b. Litologi dan Mineralogi Lokasi Pengamatan 2............................15
4. Struktur Geologi.................................................................................16
5. Potensi................................................................................................17
a. Potensi Lokasi Pengamatan 1.......................................................17
b. Potensi Lokasi Pengamatan 2.......................................................17
4

6. Geokronologi......................................................................................18
B. Stasiun Pengamatan 2 (STA 1).................................................................18
1. Lokasi STA.........................................................................................18
1.1 Lokasi STA..................................................................................18
1.2 Waktu Pengamatan......................................................................20
1.3 Cuaca...........................................................................................20
1.4 Lokasi Pengamatan......................................................................20
2. Geomorfologi STA.............................................................................20
3. Litologi dan Mineralogi......................................................................23
a. Litologi dan Mineralogi Lokasi Pengamatan 1...........................23
b. Litologi dan Mineralogi Lokasi Pengamatan 2...........................24
c. Litologi dan Mineralogi Lokasi Pengamatan 3...........................25
4. Struktur Geologi.................................................................................27
5. Potensi................................................................................................29
a. Potensi Lokasi Pengamatan 1......................................................29
b. Potensi Lokasi Pengamatan 2......................................................29
c. Potensi Lokasi Pengamatan 3......................................................29
6. Geokronologi......................................................................................29
IV. Kesimpulan.....................................................................................................32
V. Daftar Pustaka................................................................................................33
VI. Lampiran........................................................................................................34
5

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Citra Satelit STA 1...............................................................................11
Gambar 2. Batas Morfologi STA 1 LP 1...............................................................12
Gambar 3. Batas Morfologi STA 1 LP 2...............................................................13
Gambar 4. Batugamping Kalsilutit dan Kalsit pada STA 1 LP 1..........................14
Gambar 5. Urat Dolomit pada STA 1 LP 1............................................................14
Gambar 6. Batugamping Kalsilutit dan Kalsit pada STA 1 LP 2..........................15
Gambar 7. Kedudukan Bidang Sesar STA 1 LP 1.................................................16
Gambar 8. Persilangan Urat Dolomit pada STA 1 LP 1........................................17
Gambar 9. Citra Satelit STA 2 LP 1......................................................................19
Gambar 10. Citra Satelit STA 2 LP 2....................................................................19
Gambar 11. Citra Satelit STA 2 LP 3.....................................................................20
Gambar 12. Batas Morfologi STA 2 LP 1.............................................................21
Gambar 13. Batas Morfologi STA 2 LP 2.............................................................22
Gambar 14. Batas Morfologi STA 2 LP 3.............................................................22
Gambar 15. Batu Diabas pada STA 2 LP 1...........................................................23
Gambar 16. Pelapukan Membola pada Batu Diabas.............................................24
Gambar 17. Batugamping Numulites pada STA 2 LP 2........................................25
Gambar 18. Batu Sekis-Filit – Batu Marmer pada STA 2 LP 3 A.........................26
Gambar 19. Batu Sekis-Filit – Batu Kuarsit pada STA 2 LP 3 B..........................27
Gambar 20. Kemiringan pada Watuprau STA 2 LP 2............................................27
Gambar 21. Strike Dip pada Batu Sekis-Filit dan Batu Kuarsit STA2LP3B(1)....28
Gambar 22. Strike Dip pada Batu Sekis-Filit dan Batu Kuarsit STA2LP3B(2)....28
6

DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tatanan Stratigrafi Pegunungan Selatan Menurut Beberapa Peneliti......8
7

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berbagai macam ilmu yang kita pelajari tidak hanya dibutuhkan
teori saja, namun juga diperlukan praktik ke lapangan untuk
memperjelas ilmu yang kita pelajari tersebut. Salah satu ilmu tersebut
adalah ilmu geologi, terlebih ilmu geologi tersebut adalah geologi
dasar yang sejatinya menjadi dasar ilmu bagi geofisikawan. Untuk itu
dilakukanlah kegiatan Fieldtrip Geologi Dasar di Kecamatan Bayat,
Kabupaten Klaten. Dalam kegiatan ini dapat dijumpai secara langsung
fenomena yang berhubungan secara langsung dengan mata kuliah
geologi dasar itu sendiri. Kegiatan ini sangat berguna ketika teori yang
kita pelajari langsung dipraktikan di lapangan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari kegiatan Fieldtrip Geologi Dasar ini
adalah,
1. Memperkenalkan berbagai fenomena yang berhubungan dengan
aplikasi mata kuliah praktikum geologi dasar yang telah dipelajari
selama praktikum di kampus.
2. Mengetahui berbagai jenis mineral penyusun litologi yang ada di
alam
3. Mengetahui berbagai jenis bentang alam yang telah dipelajari di
lapangan
4. Mengetahui penerapan pengukuran struktur geologi secara nyata
di lapangan
5. Menginterpretasikan kemampuan membaca peta topografi di
lapangan
C. Waktu, Letak, dan Kesampaian Daerah
Fieldtrip Geologi Dasar Program Studi Geofisika Universitas
Gadjah Mada tahun ini dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Mei 2013
di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada dua Stasiun Pengamatan dan
lima Lokasi Pengamatan yang dikunjungi, yaitu
8

1. STA 1 berada di Jimbung Lor, Dukuh Koplak, Desa Krakitan,
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Pemberangkatan dilakukan
pukul 07.42 WIB dari Kampus Fakultas MIPA Utara dan sampai
pukul 08.55 WIB di STA 1 LP 1. Lalu dilakukan pengamatan dan
akhirnya pada pukul 09.20 WIB pengamatan berpindah ke LP 2
yang lokasinya berdekatan. Pengamatan selesai dilakukan pada
pukul 10.45 WIB.
2. STA 2 berada di lereng timur Gunung Pendul, Desa Gunung
Gajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Pemberangkatan
dilakukan pada pukul 10.45 WIB dari lokasi STA 1 dan sampai
pada pukul 11.20 WIB tepatnya di STA 2 LP 1. Setelah itu
dilanjutkan ke LP 2 kemudian pengamatan berakhir di LP 3 pada
pukul 15.53 WIB. Jarak antar lokasi pengamatan pada STA 2 ini
juga cukup berdekatan, hampir serupa dengan STA 1.
D. Peralatan
Adapun beberapa perlengkapan lapangan beserta kegunaannya
yang digunakan untuk menunjang kegiatan Fieldtrip Geologi Dasar,
yaitu :
1. Palu Geologi, digunakan untuk memecah batuan agar diketahui
bagian dalam batuan yang masih segar atau untuk memisahkan
urat mineral dari batu asalnya.
2. Kompas Geologi, digunakan untuk mengukur strike dip pada urat
mineral dan mengetahui arah mata angin pada lokasi pengamatan
3. Lup, digunakan untuk memperbesar dan mengidentifikasi
komposisi yang terkandung dalam batuan agar diketahui sifat
fisik dari mineral yang menyusun batuan tersebut
4. Peta Dasar (Peta Topografi), digunakan untuk penentuan lokasi
5. Kamera, digunakan untuk mendokumentasi lokasi pengamatan,
batuan, mineral ataupun lainnya yang terdapat di lokasi fieldtrip
6. Plastik Sampel, digunakan untuk menyimpan sampel-sampel
batuan atau mineral yang ditemukan di lokasi pengamatan
9

7. Kertas HVS atau Buku Catatan Geologi, digunakan untuk
mencatat materi dan hasil pengamatan yang didapatkan di lokasi
pengamatan
8. Alat tulis lapangan, terdiri atas pensil (HB atau 2B), penggaris,
busur derajat, penghapus, OHP marker, dan Clipboard
9. Larutan HCl 0,1 M, digunakan untuk menguji kereaktifan mineral
10

II. GEOLOGI REGIONAL
A. Fisiografi Pulau Jawa
Pengamatan kondisi geologi Pulau Jawa dapat dilakukan mulai
Kala Miosen. Sebelum Miosen sejarah hanya didapat beberapa
singkapan batuan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yaitu pada zaman
Eosen dan akhir kala Kapur. Pada zaman itu situasi Pulau Jawa
mungkin mirip dengan situasi Kepulauan Banda dan Maluku
Tenggara. Di Kepulauan Maluku terdapat 2 sistem busur yaitu, busur
dalam atau busur volkanis dan busur luar atau busur non volkanis.
Pada Kala Kapur hingga Oligosen Tengah diperkirakan busur volkanis
terbentuk di Laut Jawa dan satu busur non volkanis terbentuk di
daratan Pulau Jawa. Singkapan batuan pada busur non volkanis
diperkirakan berumur Eosen. Batuan pada busur non volkanis ini
tersusun oleh fragmen kerak bumi yang tertimbun pada jalur subduksi,
dan mengandung banyak kuarsa. Mineral ini sangat dominan dalam
batuan berumur Eosen dan berasal dari gunung api asam, baik yang
terdapat di daratan maupun lingkungan marin. Antara busur volkanis
dan busur non volkanis terdapat cekungan busur luar yang relatif
dalam, terletak di sekitar pantai utara Pulau Jawa.
Pada akhir Oligosen dan awal Miosen terjadi perubahan yang
nyata, yaitu jalur subduksi bergeser ke selatan. Busur volkanis
diperkirakan berada di pantai selatan Pulau Jawa sekarang. Gunung
api tersebut muncul dari dasar laut membentuk deretan pulau gunung
api. Aktivitas vulkanik ini adalah tahap pertama dalam pembentukan
Pulau Jawa. Pada dasarnya Pulau Jawa ini satu busur gunung api
dengan laut dangkal yang luas sampai Kalimantan, kondisi ini ada
sampai Pliosen Tengah. Selama periode ini, busur dalam menggeser
ke utara hingga Pantai Utara Jawa. Di samping itu, laut dangkal
mengalami pengangkatan membentuk daratan, sehingga sedimen
marin muncul ke atas permukaan laut. Pengangkatan maupun
penenggelaman serta aktivitas volkanis merupakan proses geologi
11

yang pernah terjadi di Pulau Jawa, sehingga memberikan keunikan
pada sejarah geologi. Pada batas Kala Pliosen dan Kuarter bentuk
Pulau Jawa secara garis besar sudah muncul. Pada akhir Pliosen
diperkirakan Pulau Jawa sering tenggelam, yang muncul di
permukaan hanya perbukitan di bagian selatan Jawa. Keadaan waktu
itu mungkin mirip dengan keadaan di Sumatera sekarang dengan suatu
dataran aluvial pantai yang sangat luas. Bagian berbukit mulai
terangkat pada awal Kuarter di Jawa Tengah. Pada Kala Kuarter Pulau
Jawa terbentuk oleh subduksi, membentuk jalur volkanik regional.
Pada Pleistosen Tengah, kegiatan volkanik mencapai puncaknya dan
mengakibatkan pembentukan jalur gunung api di bagian tengah Jawa.
Pada zaman Kuarter terjadi perubahan iklim di bumi secara
ekstrim. Sebelumnya pada zaman Tersier iklim di wilayah Indonesia
merupakan iklim tropis lembab dengan suhu rata-rata per tahun lebih
tinggi dari pada sekarang. Berdasarkan data geologi, pernah terjadi
jaman es, yaitu sebagian besar air laut menjadi es, sehingga
permukaan air laut menurun dan daratan bertambah luas. Peristiwa
yang lain adalah jaman pencairan es, sehingga muka air laut naik.
Akibat peristiwa tersebut adalah terbentuknya teras marin,
pembentukan sedimen pada lingkungan marin di darat dan
pembentukan sedimen darat pada lingkungan marin. Sedimen dan
teras tersebut sekarang dapat ditemukan pada beberapa lokasi di Jawa.
Pada jaman es terjadi penurunan air laut antara 50 meter sampai 100
meter, sehingga Laut Jawa menjadi daratan yang sangat luas. Pulau
Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa menjadi satu daratan.
Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap tumbuhan, proses
pelapukan dan erosi yang sangat menentukan bentukan bentang alam
dan pembentukan tanah.
12

B. Stratigrafi Regional
Batuan tertua yang tersingkap di daerah Bayat terdiri dari batuan
metamorf berupa filit, sekis, batu sabak dan marmer. Penentuan umur
yang tepat untuk batuan metamorf hingga saat ini masih belum ada.
Satu-satunya data tidak langsung untuk perkiraan umurnya adalah
didasarkan fosil tunggal Orbitolina yang ditemukan oleh Bothe
(1927). Karena umur batuan sedimen tertua yang menutup batuan
malihan tersebut berumur awal Tersier, maka umur batuan malihan
tersebut disebut batuan Pre-Tertiary Rocks.
Batupasir yang tidak gampingan secara tidak selaras menumpang
di atas batuan malihan yang sedikit gampingan dan batulempung,
kemudian di atasnya tertutup oleh batugamping yang mengandung
fosil nummulites yang melimpah dan bagian atasnya diakhiri oleh
batugamping Discocyc1ina. Peristiwa itu menunjukkan lingkungan
laut dalam. Keberadaan forminifera besar ini bersama dengan
foraminifera plangtonik yang sangat jarang ditemukan di dalam batu
lempung gampingan, menunjukkan umur Eosen Tengah hingga Eosen
Atas. Batuan berumur Eosen ini disebut Formasi Wungkal-Gamping.
Diorit di daerah Jiwo merupakan penyusun utama Gunung Pendu,
yang terletak di bagian timur Perbukitan Jiwo. Diorit ini kemungkinan
bertipe dike. Singkapan batuan beku di Watuprahu di atas batuan
Eosen miring ke arah selatan. Batuan beku ini terletak di bawah
batupasir dan batugamping yang masih mempunyai kemiringan
lapisan ke arah selatan. Penentuan umur pada dike intrusi pendul oleh
Soeria Atmadja dan kawan-kawan (1991) menghasilkan sekitar 34
juta tahun, dimana hasil ini kurang lebih sesuai dengan teori
Bemmelen (1949), yang menafsirkan bahwa batuan beku tersebut
adalah merupakan leher dari gunung api Oligosen.
Sebelum kala Eosen tangah, daerah Jiwo mulai tererosi. Erosi
tersebut disebabkan oleh pengangkatan atau penurunan muka air laut
selama periode akhir oligosen. Proses erosi tersebut telah menurunkan
13

permukaan daratan yang ada, kemudian disusul oleh periode
transgresi dan menghasilkan pengendapan batugamping dimulai pada
kala Miosen Tengah. Di daerah Perbukitan Jiwo tersebut mempunyai
ciri litologi yang sama dengan Formasi Oyo yang tersingkap lebih
banyak di Pegunungan Selatan.
Di daerah Bayat tidak ada sedimen laut yang tersingkap di antara
Formasi Wungkal-Gamping dan Formasi Oyo. Selama zaman Kuarter,
pengendapan batugamping telah berakhir. Pengangkatan yang diikuti
dengan proses erosi menyebabkan daerah Perbukitan Jiwo berubah
menjadi daerah lingkungan darat. Pasir vulkanik yang berasal dari
gunung api Merapi yang masih aktif mempengaruhi proses
sedimentasi endapan aluvial terutama di sebelah utara dan barat laut
dari Perbukitan Jiwo.
Keadaan stratigrafi Pegunugan Selatan, dari tua ke muda yaitu :
1. Formasi Wungkal-Gamping
2. Formasi Kebo Butak
3. Formasi Semilir
4. Formasi Nglanggran
5. Formasi Sambipitu
6. Formasi Oyo
7. Formasi Wonosari
8. Formasi Kepek.
14

Tabel 1. Tatanan Stratigrafi Pegunungan Selatan Menurut Beberapa Peneliti
C. Struktur Geologi Regional
Pada bagian selatan Bayat, terdapat dataran rendah yang berarah
memanjang barat-timur, sejajar dengan kaki Pegunungan Selatan.
Dataran Bukit ini terpotong oleh sesar dan singkapan batuan metamorf
tergeser ke arah timur laut di daerah Padasan, G. Semangu dan
berbelok ke utara hingga daerah Jokotuo, dijumpai marmer yang
merupakan kantong diantara filit. Pada bagian utara dari Jiwo Barat
yaitu di G. Tugu, G. Kampak dan daerah Ngembel serta bagian utara,
timur dan tenggara dari Jiwo Timur, msing-masing di G. Jeto, G.
Bawak, G. Temas dan di G. Lanang, tersingkap batugamping yang
menumpang secara tidak selaras di atas batuan yang lebih tua. Di
bagian tenggara G. Kampak dan di G. Jeto, batugamping ini
15

menumpang di atas batuan metamorf, sedang di Temas menumpang di
atas batuan beku.
Batugamping ini terdiri dari dua fasies yang berbeda. Fasies yang
pertama terdiri dari batugamping algae, kenampakan perlapisan tidak
begitu jelas. Algae membentuk struktur onkoid dalam bentuk bola-
bola berukuran 2 hingga 5 cm. Fasies seperti ini dijumpai di
G.Kampak, bagian selatan G.Tugu, G. Jeto, G. Bawak dan di bagian
barat G.Temas. Fasies yang kedua berupa batugamping berlapis, yang
merupakan perselingan antara kalkarenit dengan kalsilutit. Fasies
batugamping berlapis ini dijumpai di Ngembel, utara G. Tugu, bagian
timur G. Temas dan di G. Lanang. Di beberapa tempat kalsilutitnya
menebal kearah lateral dan berubah menjadi napal, seperti yang
terdapat di utara G. Tugu. Fasies ini tidak menunjukkan struktur alga
dan kaya akan kandungan foraminifera plangon, kemungkinan
diendapkan di dangkalan karbonat yang lebih dalam ditandai dengan
adanya struktur nendatan (slump structures) seperti yang terlihat di
bagian timur Temas dan di G. Lanang.
Pada bagian selatan di G. Temas dijumpai kontak antara batuan
beku dengan batugamping. Batuan bekunya sudah sangat lapuk,
menunjukkan tanda-tanda retakan yang kebanyakan telah terisi oleh
oksida besi dan sebagian terisi oleh kalsit. Retakan pada batuan beku
tersebut tidak menerus pada batugamping. Hal ini menunjukkan
bahwa sebelum pengendapan batugamping, batuan bekunya telah
mengalami retakan, terisi oleh hasil pelapukannya sendiri yang berupa
oksida besi. Setelah terjadi pengendapan batugamping, sebagian dari
karbonatnya mengisi celah akibat retakan tersebut membentuk urat
kalsit. Belakangan setelah batugamping terangkat dan tererosi,
sebagian dari urat kalsit pada batuan beku ini bersama batuan bekunya
tersingkap dan mengalami pelapukan membentuk tanah. Urat kalsit
yang ada mengalami pelarutan dan pengendapan kembali dalam
16

bentuk caliche, seperti yang banyak dijumpaidi barat G. Temas dan
lereng timur dan selatan G. Pendul.
Berdasarkan kandungan fosilnya, batugamping neogen di
Perbukitan Jiwo ini menunjukkan umur N12 atau Miosen Berdasarkan
atas umur ini maka batugamping tersebut dapat dihubungkan dengan
Formasi Wonosari untuk fasies batugamping algae , sedangkan fasies
batugamping berlapis adalah sepadan dengan formasi Oyo. Setelah
pengendapan batugamping, di Perbukitan Jiwo tidak ditemukan lagi
batuan lain yang berumur Tersier. Zaman Kuarter terwakili oleh breksi
lahar, endapan pasir fluvio-vulkanik Merapi serta endapan lempung
hitam dari lingkungan rawa.
Breksi lahar dijumpai pada bagian utara dari perbukitan Ngembel,
berupa breksi dengan fragmen andesit yang berukuran aneka ragam,
mulai dari kerikil hingga bongkah. Fragmen tersebut tersebar
umumnya mengapung pada matriks yang berukuran lanau sampai
pasir halus, bersifat tufan. Gejala perlapisan dan fosil tidak ditemukan
pada breksi ini. Breksi ini diduga berasal dari aktivitas aliran lahar
dari G. Merapi dari arah barat laut, yang berhenti karena membentur
bukit batugamping Ngembel, dan terjadi pada kala Pleistosen.
17

III. ISI
A. Stasiun Pengamatan 1 (STA 1)
1. Lokasi STA
1.1 Lokasi STA
Lokasi STA 1 berada di Jimbung Lor, Dukuh Koplak, Desa
Krakitan, Kecamatan Bayar, Kabupaten Klaten.
Gambar 1. Citra Satelit STA 1
1.2 Waktu Pengamatan
a. Lokasi Pengamatan 1 (LP 1) : 08.55 WIB – 09.20 WIB
b. Lokasi Pengamatan 2 (LP 2) : 09.20 WIB – 09.50 WIB
1.3 Cuaca
Cuaca ketika pengamatan pada STA 1 ini adalah dalam
kondisi cerah.
18

1.4 Lokasi Pengamatan
Pada STA 1 ini terdapat dua lokasi pengamatan yang letaknya
saling berdekatan.
2. Geomorfologi STA
STA 1 ini termasuk dalam formasi wonosari dimana ditemukan
batuan sedimen dari batugamping klastik sampai nonklastik dan
batugamping kalkarenit sampai batugamping kalsilutit. Hal
tersebut dapat dilihat dari kenampakan singkapan batugamping
sebelah selatan. Terlihat pula secara jelas kemiringan lapisan
karena proses tektonik yang cukup berpengaruh sehingga
termasuk dalam bentang alam struktural. Daerah ini dulunya
merupakan wilayah laut dangkal yang terangkat karena subduksi.
Batas Morfologi :
Utara : Vegetasi
Selatan : Pemukiman
Timur : Pegunungan atau Gunung Kampak
Barat : Vegetasi
Gambar 2. Batas Morfologi STA 1 LP 1
19

Gambar 3. Batas Morfologi STA 1 LP 2
3. Litologi dan Mineralogi
a. Litologi dan Mineralogi pada Lokasi Pengamatan 1
Batuan yang ditemukan pada lokasi ini adalah batugamping
kalsilutit. Batu ini berjenis sedimen klastik dengan warna
putih kekuningan dan struktur masif. Teksturnya klastik
berukuran lempung dengan sortasi baik dan kemas tertutup.
Bentuk butirannya rounded dan sphericity.
Mineral yang ditemukan dalam batugamping adalah kalsit,
ada pula urat mineral yang terdapat pada sesar yaitu berupa
urat dolomit.
Kalsit memiliki warna colourless dan cerat putih. Kilap yang
dimiliki adalah kilap kaca dengan kekerasan sesuai skala
mohs adalah 3. Sifat kemagnetannya diamagnetik, diafenitas
transparan dengan belahan 3 arah dan pecahan even serta
sistem kristal yang orthorombik.
20

Gambar 4. Batugamping Kalsilutit dan Kalsit pada STA 1 LP 1
Dolomit memiliki warna colourless dan cerat putih. Kilap
yang dimiliki adalah kilap kaca. Sifat kemagnetannya
diamagnetik, diafenitas transparan dengan belahan 3 arah dan
pecahan even serta sistem kristal yang heksagonal.
Gambar 5. Urat Dolomit pada STA 1 LP 1
21

b. Litologi dan Mineralogi pada Lokasi Pengamatan 2
Batuan yang ditemukan di lokasi ini adalah batugamping
kalsilutit. Batu ini berjenis sedimen klastik dengan warna
putih kekuningan dan struktur masif. Teksturnya berukuran
lempung dan memiliki komposisi mineral berupa kalsit.
Kalsit memiliki warna colourless dan cerat putih. Kilap yang
dimiliki adalah kilap kaca dengan kekerasan sesuai skala
mohs adalah 3. Sifat kemagnetannya diamagnetik, diafenitas
transparan dengan belahan 3 arah dan pecahan even serta
sistem kristal yang trigonal.
Gambar 6. Batugamping Kalsilutit dan Kalsit pada STA 1 LP 2
22

4. Struktur Geologi
Pada STA 1 LP 1 dilakukan pengukuran strike dip terhadap
bidang sesar yang ada dan hasilnya adalah N233oE/13o.
Gambar 7. Kedudukan Bidang Sesar STA 1 LP 1
Pada STA 1 LP 1 ini juga dilakukan pengukuran pada urat
dolomit dan hasilnya adalah N23oE/84o dan N293oE/82o.
23

Gambar 8. Persilangan Urat Dolomit pada STA 1 LP 1
5. Potensi
a. Potensi pada Lokasi Pengamatan 1
Lokasi pengamatan 1 ini dapat digunakan sebagai objek
geologi dan dapat pula dilakukan pengamatan untuk
pengembangan wilayah. Sedangkan potensi negatifnya adalah
tingkat erosi dan pelapukan yang tinggi pada daerah ini
menyebabkan penurunan tanah. Daerah ini juga tidak cocok
untuk ditambang karena batugamping yang ada telah
tercampur dengan mineral lain yang tidak dibutuhkan dalam
pertambangan.
b. Potensi pada Lokasi Pengamatan 2
Lokasi pengamatan 2 ini dapat digunakan sebagai lahan
pertambangan batugamping karena batugamping yang masih
segar, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian
penduduk sekitar. Namun, apabila terlalu sering dilakukan
pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi untuk
longsor.
24

6. Geokronologi
Lokasi STA 1 ini awal mulanya adalah wilayah laut dangkal.
Kemudian dalam waktu yang sangat lama terjadilah subduksi
yang mengakibatkan wilayah ini terangkat. Diperkirakan lokasi
pengamatan 1 letaknya lebih dalam dibanding lokasi pengamatan
2. Pada lokasi pengamatan 1 terjadi sesar turun yang sekarang
hanya terlihat footwallnya saja, diperkirakan hangingwallnya
telah tertutup vegetasi sehingga tidak terlihat. Akibat sesar turun
dan gesekan kedua bidang tersebut memunculkan adanya batu
breksi. Gesekan kedua bidang tersebut juga membuat material-
material dari kedua bidang saling berpindah sehingga tercampur.
Sementara itu di lokasi pengamatan 2 terlihat bidang perlapisan
batugamping bagian bawah tidak teratur, hal tersebut diakibatkan
oleh arus turbulensi air yang sangat kuat ketika masih berupa laut
dangkal sehingga menimbulkan lingkungan cheotik atau
lingkungan yang tidak beraturan. Kemudian pada perlapisan
batugamping bagian atas terlihat berjajar dengan teratur, hal
tersebut terjadi karena arus air pada bagian ini lebih tenang
dibanding bagian bawah tadi. Sehingga batugamping memiliki
kesempatan untuk mengendap secara teratur dan berlapis-lapis.
B. Stasiun Pengamatan 2 (STA 2)
1. Lokasi STA
1.1 Lokasi STA
Lokasi STA 2 ini berada di Desa Gunung Gajah, Kecamatan
Bayat, Kabupaten Klaten. Terdapat tiga Lokasi Pengamatan
yaitu, Lereng Timur Gunung Pendul, Watuprahu, dan
Singkapan Batu Metamorf.
25

Gambar 9. Citra Satelit STA 2 LP 1
Gambar 10. Citra Satelit STA 2 LP 2
26

Gambar 11. Citra Satelit STA 2 LP 3
1.2 Waktu Pengamatan
a. Lokasi Pengamatan 1 (LP 1) : 11.22 WIB – 12.12 WIB
b. Lokasi Pengamatan 2 (LP 2) : 13.26 WIB – 14.27 WIB
c. Lokasi Pengamatan 3 (LP 3) : 14.44 WIB – 15.53 WIB
1.3 Cuaca
Cuaca ketika pengamatan pada STA 1 ini adalah dalam kondisi
cerah.
1.4 Lokasi Pengamatan
Pada STA 2 ini terdapat tiga lokasi pengamatan yaitu, Lereng
Timur Gunung Pendul, Watuprahu, dan Singkapan Batu
Metamorf.
2. Geomorfologi STA
Pada LP 1 terdapat intrusi gunung pendul, sehingga sekelilingnya
mempunyai kemungkinan terbentuk batuan intrusi. Terdapat pula
pelapukan membola di daerah ini yang mengikis batuan sekitarnya.
Pada LP 2 terdapat watuprau yang termasuk dalam formasi
27

wungkal-gamping yang terdiri dari batuan berumur sekitar eosen
tengah sampai eosen akhir. Batuan ini termasuk dalam kategori
mudstone dimana lumpur yang mendominasi. Pada LP 3 terdapat
singkapan batu metamorf yang termasuk dalam formasi malihan
atau kompleks batuan metamorf. Secara keseluruhan daerah LP 1
sampai LP 3 termasuk dalam bentang alam vulkanik, dimana
terlihat adanya sisa-sisa batuan beku hasil intrusi dan terletak pada
zona subduksi yang memiliki pengaruh tektonik sangat kuat.
Batas Morfologi Lokasi Pengamatan 1 (LP 1) :
Utara : Vegetasi
Selatan : Vegetasi
Barat : Singkapan Batuan Beku
Timur : Perumahan dan kebun warga
Gambar 12. Batas Morfologi STA 2 LP 1
Batas Morfologi Lokasi Pengamatan 2 (LP 2) :
Utara : Perkebunan
Selatan : Jalan raya
Barat : Rumah warga
28

Timur : Gunung atau perkebunan
Gambar 13. Batas Morfologi STA 2 LP 2
Batas Morfologi Lokasi Pengamatan 3 (LP 3) :
Utara : Singkapan Batuan Metamorf
Selatan : Vegetasi
Barat : Jalan raya, vegetasi
Timur : Jalan raya, rumah warga
Gambar 14. Batas Morfologi STA 2 LP 3
29

3. Litologi dan Mineralogi
a. Litologi dan Mineralogi pada Lokasi Pengamatan 1 (LP 1)
Batuan yang ditemukan pada lokasi ini adalah diabas. Diabas
memiliki struktur masif dan warna abu-abu sehingga sifatnya
intermediet. Komposisi mineral yang terdapat di dalamnya
adalah mika muskovit dan feldspar plagioklas. Hubungan antar
mineralnya anhedral dan memiliki ciri khusus yaitu
plagioklasnya saling silang.
Gambar 15. Batu Diabas pada STA 2 LP 1
Pada batuan beku tersebut terjadi pelapukan membola atau
yang biasa disebut speroidal dengan diameter batuan yang
masih segar sebesar 14 cm dan batuan beku yang terlapukkan
berdiameter 22 cm. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa
awalnya batu tersebut berdiameter 22 cm kemudian mengalami
pelapukan sehingga diameternya berkurang 8 cm menjadi 14
cm.
30

Gambar 16. Pelapukan Membola pada Batu Diabas
b. Litologi dan Mineralogi pada Lokasi Pengamatan 2 (LP 2)
Batuan yang ditemukan pada lokasi ini adalah batu sedimen
yang bersifat semi metamorf atau metasedimen. Batu ini
bernama batugamping numulites. Warnanya putih kecoklatan,
bentuk butirnya angular dan strukturnya masif. Struktur
kimianya organik, karena terdapat organisme mati yaitu
numulites yang melekat di batuan. Termasuk jenis batuan
sedimen non klastik.
31

Gambar 17. Batugamping Numulites pada STA 2 LP 2
c. Litologi dan Mineralogi pada Lokasi Pengamatan 3 (LP 3)
Batuan yang ditemukan pada lokasi ini adalah batu sekis-filit
dan batu marmer. Batu sekis-filit memiliki warna coklat
mengkilap dan tekstur lepidoblastik. Strukturnya foliasi
(sekistose) dengan komposisi mineral adalah muskovit, biotit,
dan feldspar. Terdapat marmer yang termetamorfisme diantara
batu sekis-filit itu pada lokasi pengamatan 3 A.
32

Gambar 18. Batu Sekis-Filit – Batu Marmer pada STA 2 LP 3 A
Kemudian pada lokasi pengamatan 3 B ditemukan batu sekis-
filit dan batu kuarsit. Batu sekis-filit memiliki warna coklat
mengkilap dan tekstur lepidoblastik. Strukturnya foliasi
(sekistose) dengan komposisi mineral adalah muskovit, biotit,
dan feldspar. Terdapat batu kuarsit yang termetamorfisme
diantara batu sekis-filit. Batu kuarsit memiliki warna putih dan
tekstur granoblastik dengan struktur non foliasi.
33

Gambar 19. Batu Sekis-Filit – Batu Kuarsit pada STA 2 LP 3 B
4. Struktur Geologi
Pada STA 2 LP 2 dilakukan pengukuran strike dip terhadap
kemiringan watuprau dan hasilnya adalah N91oE/41o.
Gambar 20. Kemiringan pada watuprau STA 2 LP 2
34

Pada STA 2 LP 3 dilakukan pengukuran strike dip terhadap
kemiringan lapisan sekis-filit – kuarsit – sekis-filit dan hasilnya
adalah N128oE/4o dan N116oE/8o.
Gambar 21. Strike Dip pada Batu Sekis-Filit dan Batu Kuarsit STA 2 LP 3 B (1)
Gambar 22. Strike Dip pada Batu Sekis-Filit dan Batu Kuarsit STA 2 LP 3 B (2)
35

5. Potensi
a. Potensi Lokasi Pengamatan 1
Lokasi ini dapat dimanfaatkan untuk objek geologi dan juga
batuan yang terdapat di sekitarnya dapat digunakan untuk
bahan bangunan.
b. Potensi Lokasi Pengamatan 2
Daerah ini termasuk cagar budaya sehingga dapat menarik
perhatian wisatawan untuk meningkatkan pendapatan warga
sekitar. Selain itu, daerah ini dapat dijadikan objek penelitian
geologi.
c. Potensi Lokasi Pengamatan 3
Lokasi ini dapat dijadikan sebagai objek geologi atau objek
pengamatan. Namun, karena struktur foliasi atau lembaran dari
batu sekis-filit ini bersifat rapuh maka daerah ini rawan
longsor.
6. Geokronologi
Secara keseluruhan keadaan awal pada STA 2 dari ketiga lokasi
pengamatan yang ada ini berbeda. Pada LP 1 awalnya merupakan
daerah dike pada gunung pendul yang tererosi. Gunung pendul
dibentuk karena proses intruai, daerah sekelilingnya kemungkinan
terbentuk batuan intrusi. Dulunya bagian batuan yang tampak pada
permukaan sekarang ini merupakan bagian dalam dari gunung
berapi, namun gunung berapi tersebut tererosi hingga bagian dalam
gunung berapi tampak ke permukaan. Kemudian batuan beku yang
ada tersebut mengalami pelapukan karena adanya air hujan yang
memasuki celah batuan tersebut. Karena pergerakan air dinamis
atau menyesuaikan permukaan maka feldspar plagioklas terkikis
dan membentuk pelapukan membola.
Pada LP 2 awalnya merupakan wilayah laut dangkal, organisme
laut banyak yang tinggal di daerah ini kemudian organisme yang
didominasi oleh kerang atau numulites ini mati dan terendapkan
36

disini. Setelah itu, daerah ini mengalami subduksi sehingga laut
dangkal yang ada tadinya menjadi terangkat atau uplifting. Dalam
proses pengangkatan endapan terjadi proses metamorfisme pada
batu sedimen yang berupa batugamping numulites, namun tak
seluruhnya termetamorfisme. Sehingga batuan sedimen mengalami
metamorfisme sebagian atau dikatakan batu metasedimen. Karena
tidak termetamorfisme seutuhnya maka termasuk dalam
metamorfisme derajat rendah. Kemudian dalam waktu yang sangat
lama, batuan ini menjadi sangat kompak karena pengaruh suhu dan
tekanan. Bukti batu ini adalah batu metasedimen dapat terlihat dari
dalam batugamping numulites ini terdapat batu marmer yang
sedang tumbuh namun belum sempurna.
Pada LP 3 terdapat dua sub lokasi yaitu LP 3 A dan LP 3 B. LP 3 A
masih merupakan bagian dari LP 2 yaitu awalnya berupa laut
dangkal yang terangkat karena subduksi. Namun bedanya
batugamping yang ada di LP 3 A telah berubah menjadi batu
metamorf yaitu batu sabak. Kemudian secara berkala menjadi batu
filit, lalu berlanjut menjadi batu sekis. Namun proses
metamorfisme dari batu filit ke sekis tidak terjadi secara sempurna,
maka jadilah batu sekis-filit. Pada daerah ini juga ditemukan batu
marmer yang tersingkap diantara batu sekis-filit. Kemungkinan
batu marmer ini merupakan pertumbuhan lanjutan dari batu
marmer pada LP 2 yang termasuk formasi wungkal-gamping. Jadi
protolith dari batu marmer ini adalah batugamping numulites yang
berada di LP 2.
Sedangkan LP 3 B sudah berbeda dengan LP 3 A, daerah ini
merupakan daerah transisi, perbatasan laut dan daratan. Awalnya
terdapat batulempung yang kemudian termetamorfisme menjadi
batuan sekis-filit sama prosesnya seperti LP 3 A, namun dari sekian
banyak batulempung yang ada terjadi kelebihan silika. Sehingga
silika yang berlebih itu berkumpul menjadi satu yang kemudian
37

bereaksi dengan oksigen membentuk kuarsa. Sementara mineral-
mineral lain yang sama resistennya dengan kuarsa telah hilang.
Dalam kurun waktu yang sangat lama kuarsa yang berkumpul
diantara batulempung itu juga ikut termetamorfismekan sehingga
menjadikan kuarsa tadi batu kuarsit. Batu kuarsit tersebut tumbuh
diantara batu sekis-filit dan mengikuti pergerakan batu sekis-filit
hingga sekarang. Batu kuarsit tersebut tidak hancur karena
memiliki resistensi yang tinggi dimana hubungan antar kuarsa tidak
dihubungkan oleh semen sehingga sangat kuat.
38

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan teori dan data yang diperoleh dari kegiatan Fieldtrip
Geologi Dasar ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu :
1. Secara keseluruhan lokasi Dukuh Koplak, Desa Krakitan, Kecamatan
Bayat, Kabupaten Klaten dapat digunakan sebagai tempat
pertambangan batugamping karena memiliki kandungan batugamping
yang melimpah
2. Batuan Beku pada lereng gunung pendul, Desa Gunung Gajah,
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dapat digunakan sebagai bahan
bangunan dan objek penelitian geologi
3. Batuan tertua yaitu batugamping numulites pada watuprau, Desa
Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dapat digunakan
sebagai cagar budaya dan objek penelitian geologi
4. Singkapan batu sekis-filit, batu marmer, dan batu kuarsit pada formasi
kompleks malihan dekat rumah warga dapat dijadikan sebagai objek
penelitian geologi
39

V. DAFTAR PUSTAKA
Antonio.”Laporan Fieldtrip Geologi
Struktur”.http://geologistruktur.blogspot.com/2011/02/indonesia.html
(diakses pada 28 Mei 2013 pukul 07.20)
Munawaroh.”Physisograpy Zonation of Java Islands”.http://earthy-
moony.blogspot.com/2010/04/physiograpy-zonation-of-java-
islands.html (diakses pada 30 Mei 2013 pukul 08.50)
Munawaroh.”Satuan Batuan Paleogen Eosen”.http://earthy-
moony.blogspot.com/2011/02/satuan-batuan-paleogen-eosen.html
(diakses pada 30 Mei 2013 pukul 16.30)
Tim Asisten Geologi Dasar.2013.Panduan Praktikum Geologi
Dasar.Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
Wibandono, Ibnu. “Geologi Regional Bayat
Klaten”.http://ibnudwibandono.wordpress.com/2010/07/12/geologi-
regional-bayat-klaten/ (diakses pada 30 Mei 2013 pukul 09.00)
40