Laporan Asam Sitrat p0
-
Upload
hanif-farhan -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
description
Transcript of Laporan Asam Sitrat p0

BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangAsam sitrat (2-dihidroxypane-1,2,3-tricarboxylic acid) adalah asam organik yang
secara alami terdapat pada buah-buahan seperti jeruk, nenas dan pear. Asam sitrat pertama kali diekstraksi dan dikristalisasi dari buah jeruk, sehingga asam sitrat hasil ektraksi dari buah-buahan ini dikenal sebagai asam sitrat alami. Asam sitrat dapat dibuat melalui fermentasi dengan menggunakan Aspergilus niger yang mampu mensintesa asam sitrat dalam medium fermentasi ekstraseluler dengan konsentrasi yang cukup tinggi, jika dibiakan dalam media yang kadar garamnya rendah mengandung gula sebgai sumber karbon.
Asam sitrat (C6H8O7) banyak digunakan dalam industri terutama industri makanan, minuman, dan obat-obatan. Kurang lebih 60% dari total produksi asam sitrat digunakan dalam industri makanan, dan 30% digunakan dalam industri farmasi, sedangkan sisanya digunakan dalam industri pemacu rasa, pengawet, pencegah rusaknya rasa dan aroma, sebagai antioksidan, pengatur pH dan sebagai pemberi kesan rasa dingin. Dalam industri makanan dan kembang gula, asam sitrat digunakan sebgai pemacu rasa, penginversi sukrosa, penghasil warna gelap dan penghelat ion logam. Dalam industri farmasi asam sitrat digunakan sebgai pelarut dan pembangkit aroma, sedangkan pada industri kosmetik digunakan sebagai antioksidan (Bizri & Wahem, 1994).
1.2 Tujuan Percobaan1. Membuat asam sitrat dari ampas buah nanas dengan cara fermentasi.2. Untuk mengetahui bagaimana fermentasi asam sitrat terhadap penyediaan
KH2PO4 dan pH yang berbeda.
1.3 Manfaat Percobaan1. Mahasiswa mampu membuat asam sitrat dari ampas buah nanas dengan cara
fermentasi.2. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana fermentasi asam sitrat terhadap
penyediaan KH2PO4 dan pH yang berbeda.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Asam Sitrat Asam sitrat merupakan senyawa intermediet dari asam organik yang
berbentuk kristal atau serbuk. Asam ini merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus Citrus (jeruk-jerukan). Rumus kimia asam sitrat adalah C6H8O7 (strukturnya ditunjukkan pada tabel informasi di sebelah kanan). Struktur asam ini tercermin pada nama IUPAC-nya, asam 2-hidroksi-1,2,3-propanatrikarboksilat. Asam sitrat dikenal sebagai senyawa antara dalam siklus asam sitrat yang terjadi di dalam mitokondria, yang penting dalam metabolisme makhluk hidup. Asam sitrat dapat diproduksi secara kimiawi atau secara fermentasi menggunakan mikroorganisme. Pemecahan karbohidrat dengan cara fermentasi dapat menghasilkan berbagai macam senyawa organik diantaranya adalah asam sitrat. Dengan enzim amylase, glukoamilase, atau amiloglukosidase, senyawa karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, dan melalui jalur EMP glukosa akan diubah menjadi asam piruvat. Asam piruvat melalui siklus krebs atau siklus TCA akan diubah menjadi menjadi asam sitrat. Kapang (mold) Aspergillus niger adalah kapang yang dapat menghasilkan enzim yang dapat mengubah karbohidrat menjadi asam sitrat. Penggunaan asam sitrat untuk industri misalnya makanan, minuman, dan farmasi. Asam sitrat juga merupakan suatu asam trikarboksilat, yang digunakan dalam industri farmasi, makanan dan minuman sebagai “acidifying and flavour agent”. Asam sitrat diproduksi dari beet dan molase dengan cara fermentasi menggunakan Aspergillus niger L – 51. (Arif Rachman, 2014)
2.2 Landasan Teori
Teori Aspergillus niger
Aspergilus niger merupakan fungi dari filum ascomycetes yang berfilamen,mempunyai hifa berseptat, dan dapat ditemukan melimpah di alam. Fungi ini biasanya diisolasi dari tanah, sisa tumbuhan, dan udara di dalam ruangan. Koloninya berwarna putih pada Agar Dekstrosa Kentang (PDA) 25°C dan berubah menjadi hitam ketika konidia dibentuk. Kepala konidia dari Aspergillus niger berwarna hitam, bulat, cenderung memisah menjadi bagian-bagian yang lebih longgar seiring dengan bertambahnya umur. (Pazza, 2013)
Banyak jenis mikroba yang dapat digunakan dalam pembuatan asam sitrat, diantaranya A. niger, A. wentii, A. ciavatus, Penicillum luteum. Diantara semuanya, A. niger merupakan galur yang paling produktif. A. niger termasuk salah satu jenis kapang. Berbeda dengan bakteri dan khamir, kapang adalah multiseluler, terdiri dari banyak sel yang bergabung menjadi satu. Melalui mikroskop dapat dilihat bahwa kapang terdiri dari benang yang disebut hifa. Kumpulan dari hifa disebut miselium. Kapang tumbuh dengan cara memperpanjang hifa pada ujungnya. Kapang dapat berwarna hitam, putih atau lainnya. Secara biokimia kapang bersifat aktif karena merupakan organisme saprofit. Organisme ini dapat menguraikan bahan-bahan organik kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana. (Damayanti, 2010)

2.3 Reaksi Pembuatan Asam Sitrat dan Permuniannya.
a) Reaksi Pembentukan
(C6 H 10 O5¿n(5) + n(H 2 O¿(l)→ (C12 H 22O11¿(5)
Karbohidrat sukrosa
¿ (H 2 O¿(l) → (C6 H 12 O6¿(s) + C6 H 12 O5¿(s)
Glukosa Fruktosa
(C6 H 12 O6¿(s)+ O2( gr) → (C6 H 8 O7 ¿(s)+ 2 (H 2 O¿(l)
Asam sitrat b) Reaksi Permunian
2(C6 H 8 O7 ¿(s) +3(Ca(OH )2→ ( Ca3 ¿+ 6 (H 2 O¿(l)
Ca. Sitrat
( Ca3 ¿+ 3(H 2 SO4 ¿(l)→ 3(Ca(SO)4 .+ 2 (C6 H 8 O7 ¿(s)
Ca. Sulfat As. Sitrat
(C6 H 8 O7 ¿(s) + 3 ( NaOH¿(l)→ (Na3 C6 H 8 O7 ¿(s) +3 (H 2 O¿(l)
Na. Sitrat
2.4 Hal-Hal yang Berpengaruh
A. Waktu 7 hari adalah optimum, bila kurang dari 7 hari, bahan baku belum terfermentasi semua. Bila lebih mungkin asam sitrat berubah menjadi asam oksalat.
B. Mikroba Pada percobaan ini digunakan jamur Aspergillus niger. Keuntungan dari penggunaan jamur ini adalah penanganannya mudah, dapat digunakan bahan baku yang murah, yield tinggi dan konsisten, serta ekonomis.
C. Jangan menaruh petri dalam keadaan keadaan terbalik, karena percobaan dalam surface culture.
D. Konsentrasi gula awal Konsentrasi gula awal menentukan yield asam sitrat dan asam organik lain. Untuk Aspergillus niger adalah 15-18%, jika lebih dari 18% tidak ekonomis dan jika kurang dari 15% terbentuk asam oksalat.
E. pH Pengaturan pH sangat penting dalam fermentasi. Ini disebabkan pada pH tertentu, strerilisasi mudah dilakukan. Sterilisasi mula-mula dilakukan pada pH 2,2 atau lebih rendah. Sebagai pengatur digunakan asam klorida. Sedang pH yang baik 3,4 - 4,5. Pada pH tinggi dihasilkan asam oksalat. Untuk kondisi tertentu (misal percobaan) kadang akan menghasilkan enzim yang hanya berfungsi mengubah karbohidrat menjadi asam sitrat. Untuk kondisi lain akan dihasilkan enzim yang lain pula.
F. Pemberian OksigenPemberian oksigen yang terlalu banyak menimbulkan efek merugikan bagi hasil asam sitrat. Sebaliknya, bila pemberian oksigen terlalu sedikit akan kurang menguntungkan.

G. Suhu Suhu yang baik adalah 26 oC – 28oC. Jika lebih dari 30 oC, keasaman naik dan akibatnya ada asam oksalat.
H. Komposisi Media Fermentasi
KOMPONEN KUANTITASSukrosaAmmonium NitratPotassium Dihidrogen PhospatMagnesium SulfatHCl
125 – 1502,0 – 2,50,75 – 1,00,20 – 0,25(untuk pengaturan pH)
2. 5 Aplikasi Asam Sitrat
Zat asam sitrat banyak digunakan dalam kehidupan manusia, terutama pada proses industri sebagai berikut :
1. Industri KimiawiDalam industri kimiawi asam sitrat digunakan sebagai bahan tambahan dalam
antifoam agent, pelembut pakaian, campuran warna tekstil, campuran detergent (sabun cuci). Hal ini dikarenakan sifat sitrat sebagai pengendali pH dalam cairan pembersih rumah tangga. Selain itu, kemampuan asam sitrat dalam mengikat ion-ion logam, menjadikannya berguna sebagai bahan sabun dan detergent. Dengan mengikat ion-ion logam pada air sadah, asam sitrat akan memungkinkan sabun untuk membentuk busa dan berfungsi dengan baik tanpa penambahan zat penghilang kesadahan.
2. Industri FarmasiDalam industri farmasi (10% dari total produksi), digunakan sebagai bahan
pengawet dalam penyimpanan darah atau sebagai sumber zat besi dalam bentuk feri-sitrat.
3. Industri MakananHampir 60% dari total pembuatan asam sitrat digunakan sebagai bahan makanan
dan minuman, antara lain digunakan sebagai pemberi rasa asam, antioksidan dan pengemulsi. Rasa sari buah, es krim, marmalde diperkuat dan diawetkan dengan menggunakan asam sitrat.
(Maria Inggrid dan Suarto, 2012)
2.6 Kelebihan dan Kekurangan Media Semi Padat
Medium padat atau semi padat dalam fermentasi permukaan menggunakan partikel substrat padat, seperti jagung giling, bekatul gandum dengan atau tanpa penambahan larutan nutrien yang diserap oleh permukaan substrat padat tersebut.
Fermentasi media padat merupakan proses fermentasi yang berlangsung dalam substrat tidak larut, namun mengandung air yang cukup sekalipun tidak mengalir bebas. Solid State Fermentation mempunyai kandungan nutrisi per volume jauh lebih pekat sehingga hasil per volum dapat lebih besar. Keuntungan fermentasi media padat diantaranya adalah medium yang digunakan relatif

sederhana, ruang yang diperlukan untuk peralatan fermentasi relatif kecil karena air yang digunakan sedikit, inokulum dapat disiapkan secara sederhana, kondisi medium tempat pertumbuhan mikroba mendekati kondisi habitat alaminya, aerasi dihasilkan dengan mudah karena ada ruang diatara tiap partikel substratnya, produk yang dihasilkan dapat dipanen dengan mudah (Fajar, 2012)
Salah satu kelemahan medium padat atau semi padat adalah pemakaian substrat yang tidak efisien karena itu pada fermentasi aerobik sifat porositas medium padat atau semi padat dengan sifat porositas yang baik memungkinkan penetrasi udara ke bagian dalam medium sehingga pertumbuhan dapat. Pada fermentasi ini, kelemahannya adalah mikroba kurang sensitife terhadap tingginya konsentrasi mineral mikro. (Iqbal, 2010)
2.7 Kelebihan dan Kekurangan Media Cair
Fermentasi media cair diartikan sebagai fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinyu dari sistem pertumbuhan sel yang bersangkutan atau substrat baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Fermentasi cair meliputi minuman anggur dan alkohol, fermentasi asam cuka, yogurt dan kefir (Dharma, 1992).
Fermentasi cair dengan teknik tradisional tidak dilakukan pengadukan, berbeda dengan fermentasi teknik fermentasi cair modern melibatkan fermentor yang dilengkapi dengan: pengaduk agar medium tetap homogen, aerasi, pengatur suhu (pendingin atau pemanasan) dan pengaturan pH. Proses fermentasi cair modern dapat dikontrol lebih baik dan hasil uniform dan dapat diprediksi. Juga tidak dilakukan sterilisasi, namun pemanasan, perebusan dan pengukusan mematikan banyak mikroba competitor (Dharma, 1992).
Keuntungan menggunakan fermentasi media cairadalah hampir disemua bagian tangki terjadi fermentasi dan kontak antar reaktan dan bakteri semakin besar. Sedangkan kelemahannyayaitu biaya operasi relatif mahal (Fajar, 2012)
2.8 Kandungan Gizi pada Nanas
Nanas segar adalah sumber antioksidan vitamin, terutama vitamin C. Seratus gram buah nanas mengandung 80 persen vitamin C. Vitamin C diperlukan untuk sintesis kolagen dalam tubuh. Kolagen sendiri adalah protein struktural utama dalam tubuh yang diperlukan untuk menjaga integritas pembuluh darah, kulit, organ, dan tulang. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C membantu tubuh dari penyakit kudis, mendongkrak imunitas, dan menghadang radikal bebas.
Nanas juga mengandung vitamin A dan beta karoten walaupun jumlahnya tidak banyak. Senyawa ini diketahui memiliki sifat antioksidan. Vitamin A juga diperlukan menjaga selaput lendir yang sehat, untuk kulit, dan penting bagi kesehatan mata. Studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah nanas yang kaya akan flavonoid membantu melindungi paru-paru dan kanker rongga mulut.
Selain itu, buah nanas juga kaya akan kandungan B-kompleks seperti folates¸thiamin, pyridoxine, riboflavin, dan mineral seperti tembaga, mangan, dan kalium. Sebagai catatan, kalium merupakan komponen penting dari sel dan cairan tubuh dan membantu mengendalikan denyut jantung dan tekanan darah. Tembaga

merupakan kofaktor yang bermanfaat untuk sintesis sel darah merah. (Yanti Puspita Sari, 2010)

BAB IIIMETODOLOGI PERCOBAAN
3.1 Bahan
1. Sumber karbohidrat: @ 20 gram ampas buah nanas
2. Bekatul @ 10 gr3. Sekam padi @ 5 gr4. Urea @ 2 gr5. KH 2 PO4 3 gr dan 7 gr
6. Mg SO4 .7 H 2 O @ 3 gr7. Aspergillus niger8. Ca(OH )25 gr
9. H 2 SO4 10. NaOH 11. Aquadest
3.2 Alat
1. Petridish2. Beaker glass3. Erlenmeyer 4. Gelas ukur5. Buret, statif, dan klem
6. Pipet7. Inkubator untuk fase semi
padat 8. Inkubator untuk fase cair9. Oven
3.3 Gambar Alat
Keterangan gambar
Gambar 3.1 : ovenGambar 3.2: petridish Gambar 3.3: erlemenyerGambar 3.4: incubator
Gambar 3.5: Buret, statif, dan klemGambar 3.6: gelas ukurGambar 3.7: pipet
3.4 Variabel Operasi
Table 3.1 Data Variabel Operasi
Gambar 3.1
Gambar 3.2Gambar 3.3
Gambar 3.4
Gambar 3.5
Gambar 3.7
Gambar 3.6

VariableMgSO4
(gr)KH2PO4
(gr)Urea (gr)
Sekam (gr)
Bekatul (gr)
pH Hari
1 3 3 2 5 10 2 72 3 3 2 5 10 5 73 3 7 2 5 10 5 7
a. Variable Tetap
MgSO4 (gr) 3Urea (gr) 2
Sekam (gr) 5Bekatul (gr) 10
b. Variable berubah
Variable KH2PO4 (gr) pH1 3 22 3 23 7 5
3.5 Cara kerja
Penyiapan Media
Pada percobaan ini dilakukan fermentasi media semi padat
Siapkan sumber karbohidrat yang akan digunakan. Bila sumber karbohidrat berupa buah, buah dikupas lalu dihaluskan dan airnya dibuang/dituang dengan cara diperas sampai sedikit kering.
Setelah agak kering, timbang sumber karbohidrat sesuai variabel dan kedalamnya ditambahkan nutrient – nutrient (urea, sekam padi, bekatul, Mg SO4.7H 2 O , KH 2 PO4 sesuai variabel. Aduk sampai homogen di dalam erlemenyer/beaker glass.
Tambahkan aquadest 50 ml hingga media menjadi lembab (sampai becek). Atur pH sesuai variabel.
Tutup beaker glass dengan alumunium foil dan bungkus dengan kertas koran, sterilkan dengan autoclave pada suhu 120oC -121 oC selama ± 15 menit.
Biarkan dingin pada suhu kamar. Setelah dingin tanami media dengan suspensi spora di dalam lemari. Aduk yang baik agar suspense spora dapat tersebar merata dalam media, lalu tutup kembali dengan alumunium foil.
Cara penanaman suspense spora:1. Menyiapkan kawat osse, bunsen, alkohol, dan HCl.2. Semprot ruang aseptic dengan menggunakan alkohol dan diamkan selama ± 1
menit. Lalu bisa dilakukan penanaman suspense spora.3. Penanaman suspense spora dilakukan dengan cara menstreilkan kawat osse:
panaskan kawat osse menggunakan Bunsen, kemudian masukan ke larutan HCl, kemudian panaskan kawat osse lagi.

Inkubasikan selama 7 hari pada 28 – 30 C (dalam incubator untuk media semi padat).
Setelah selesai inkubasi, tambahkan aquadest ke dalam beaker glass sedikit demi sedikit dan lumat semua isi beaker glass hingga tercampur merata. Volume aquadest yang ditambahkan maksimal 50 mL .
Saring dengan kertas saring atau pompa vakum dan filtratnya ditest untuk asam sitratnya
Analisa Hasil Panaskan filtrat yang diperoleh dari percobaan di atas sampai 70oC. Tambahkan
larutan Ca(OH )2 sebanyak 10 mL. Buat larutan Ca(OH )2 dengan melarutkan 5gr
Ca(OH )2 dengan aquadest sampai 50 mL (jaga temperatur konstan).
Endapan yang timbul cepat-cepat disaring (dalam keadaan panas 70 oC), kemudian dicuci dengan air panas 70 oC. Endapan tersebut adalah calcium citrat.
Keringkan endapan di oven kemudian timbang beratnya. Catat beratnya.
Endapan tersebut dilarutkan dengan H 2 SO4 encer, sesuai perhitungan, saring dengan kertas saring. Filtratnya merupakan asam sitrat dan endapannya adalah calcium sulfat.
Untuk mengetahui berat asam sitrat yang diperoleh pada percobaan, titrasi filtrat tersebut dengan NaOH 0,1N. Catat kebutuhan titran.
*Menghitung H 2 SO4 encer
¿¿(C6 H 5 O7 ¿2¿(s ) + 3( H 2 SO4 ¿(l) 3(Ca(OH )2 ¿(s) + 2 C6 H 8 O7 ¿2¿(s )
x grBM Ca sitrat
= Amol 3 A mol
Buat larutan H 2 SO4 dengan melarutkan 5 mL H 2 SO4 pekat menjadi 100 mL
gr = vol H 2 SO4 . ρ H 2 SO4 . kadar H 2 SO4
= 5 mL . 1,84 gr/cm3. 100/98 = 9,39 gr
Molar H 2 SO4 = mol/V = gr
BMV
= 9,39 gr /98 gr /mol
0,1 L
= 0,958 M Molar H 2 SO4 = mol/V
0,958 M = 3 A Mol
VV =……… L =……… mL

BAB IVHASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Percobaan
Tabel 4.1 Analisa Hasil Percobaan
Variabel
Parameter yang diukur
Hari-2 Hari-5 Hari-6Hari-7 (Panen
)
Var 1Volume titran (ml) 2,2 2,4 3,0 7,7
pH 3,345 3,325 3,276 3,072
Var IIVolume titran (ml) 3,4 4,4 3,0 10,1
pH 3,249 3,193 3,276 3,0131
Var IIIVolume titran (ml) 8,1 7,1 6,7 14,1
pH 3,060 3,094 3,1225 2,9487
Tabel 4.2 Berat Endapan Cu setelah di Oven dan Kebutuhan H2SO4
Variable Berat (gr) H2SO4 (ml)I 10,5 59,70II 6,0 31,441III 6,6 35,21
4.2 Pembahasan
4.2.1 Pengaruh Waktu terhadap pH
1 2 3 4 5 6 7 82,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
pH vs Waktu
Var 1 Var II Var III
hari
pH
Gambar 4.1 Grafik pH vs Waktu (Hari)
Pada variabel 1 terlihat bahwa grafik menunjukan kecenderungan semakin lama semakin menurun. Hal ini juga terjadi pada variabel 2 dan 3, namun pada variabel 2 terdapat adanya penyimpangan dari yang seharusnya. Semakin lama waktu yang fermentasi maka asam yang terbentuk semakin banyak, maka pH akan semakin

rendah. Pada variabel 2, adanya kenaikan pH pada hari ke 5 sampai hari ke-6. Begitu juga pada variabel 3, dari hari ke-2 sampai hari ke-6 terjadi kenaikan pH, setelah hari ke-6 baru terjadi penurunan pH. Penurunan pH disebabkan karena kurang cepatnya praktikan mengisolasi enzim sehingga enzim telah bereaksi pada suhu kamar dan akibatnya ada sedikit aktivitas enzim yang terjadi. Hal ini mempengaruhi aktivitas fermentasi yang tidak sesuai dengan pertumbuhan Aspergillus Niger pada pH. Akibatnya terjadi penyimpangan aktifvitas fermentasi asam sitrat karena adanya penambahan urea. Urea terurai menjadi NH3 dan CO2. NH3 bereaksi dengan air membentk NH4OH yang bersifat basa. Hal ini yang menyebabkan adanya penyimpangan dari pH yang dihasilkan dari percobaan. Selain itu, efek dari trace element dan makronutrient juga dapat mempengaruhi. Pada fase eksponensial, ketika terjadi pertumbuhan maksimal, laju pertumbuhan akan berjalan tetap dan komposisi kimia akan berubah karena adanya penggunaan oleh substrat dan dan sintesa produk. Ketika adanya akumulasi produk, dimana substrat dan nutrisi sudah menipis maka akan terjadi penurunan laju pertumbuhan. (Rintis Manfaati, 2011)
4.2.2 Penambahan KH2PO4
Asam sitrat merupakan asam organik yang memiliki pH 3-6 sedangkan pH yang diinginkan 2 dan 5. Maka perlu penambahan KH2PO4 guna menyangga asam dimana fungsinya sebagai pengencer yang tidak akan mempengaruhi pH yang sudah diatur , dimana pH yang diharapkan tetap asam serta fungsi KH2PO4yang lain sebagai sumber mineral bagi mikroorganisme yang akan tumbuh.
4.2.3 Komposisi Buah Nanas
Nanas merupakan buah yang kaya akan karbohidrat, terdiri atas beberapa gula sederhana misalnya sukrosa, fruktosa, dan glukosa, serta enzim gromelin yang dapat merombak protein menjadi asam amino agar mudah diserap tubuh (Rismunandar dalam Siahaan, 2010). Daging buah nanas juga mengandung mineral gula, vitamin A, vitamin C, dan mengandung mineral yang sangat diperlukan tubuh (Collins dalam Siahaan, 2010). Kandungan nanas secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kandungan zat gizi dalam 100 g buah nanas masak dan Tabel 2.2. Komposisi sari nanas dalam 100 g bahan.
Komponen Zat Gizi JumlahKalori 50 kalProtein 0,40 gLemak 0,20 g
Karbohidrat 13,0 gKalsium (Ca) 19,0 mg
Pospor (P) 9,0 mgSerat 0,4 g
Besi (Fe) 0,20 gVitamin A 20,00 REVitamin B1 0,08 mgVitamin B2 0,04 mgVitamain C 20,00 mg

Niacin 0,20 gTabel 2.1. Kandungan zat gizi dalam 100 g buah nanas masak
Sumber : Buah dan Sayuran untuk Terapi, 2000
Komponen JumlahAir 85,00 %
Protein 0,40 %Lemak 0,20 %
Abu 0,40 %Gula 12,00 %Asam 1,00 %
Vitamin A 130,00 IUVitamin B 0,08 mgVitamin C 24,00 mg
Tabel 2.2 Komposisi sari nanas dalam 100 g bahanSumber : Departemen Perindustrian, 1977
4.3.4 Fungsi Penambahan Sekam dan Bekatul
Pada percobaan, sampel ditambahkan sekam dan bekatul. Kemudian setelah diberi nutrisi, sampel ditutup rapat dengan aluminium foil dan setelah itu diinkubasikan selama 6 hari. Fermentasi asam sitrat pada percobaan ini menggunakan jamur Aspergilus niger dengan fermentasi yang bersifat aerob, fermentasi yang membutuhkan oksigen. Struktur sekam yang berongga memungkinkan menyimpan oksigen yang cukup untuk fermentasi selama inkubasi dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan fermentasi masih dapat berlanjut meski sistem diisolasi dengan aluminium foil. Dalam reaksi fermentasi, dibutuhkan suatu substrat yang mengandung nutrien dibutuhkan untuk difermentasikan dengan jamur. Dalam percobaan ini, yang bertindak sebagai substrat adalah bekatul. Kesimpulannya, fungsi sekam adalah penyimpan oksigen untuk kebutuhan fermentasi dan bekatul berfungsi sebagai substrat reaksi.
DAFTAR PUSTAKA

Anonym. 2012. Kandungan gizi Nanas dikutip http://www.sunpride.co.id/produk2/ . Diakses pada tanggal 19 September 2015
Dwi Atmaja, Giovanni, dkk. Maret 2013. “Produksi Asam Organik (Asam Sitrat) dengan Kultivasi Cair dan Substrat”. Laporan Praktikum Teknologi Bioindustri. https://www.scribd.com/doc/138680419/Laporan-Asam-Sitrat. 22 September 2015
Friedrich J., A. Cimerman, dan W. Steiner. 1994. Concomitant Biosynthesis of Aspergillus niger Pectolytic Enzymes and Citric Acid on Sucrosa. J. Enzym and Microbial Technology 16 : 703-710
Racman, arif. 2015 . asam sitrat dikutip http://resepkimiaindustri.blogspot.com/. Diakses tanggal 15 april 2015.
Sunarya.2007.Mudah dan Aktif Belajar Kimia. Bandung: Setia Purna Inves.
Wehner. 1893 dalam Rusmana I. 2005. Petunjuk Praktikum Bioteknologi Mikrobia. FMIPA IPB. Bogor.
Mangunwidjaja D. dan A. Suryani. 1994. Teknologi Bioproses. Penebar Swadaya. Jakarta
LEMBAR PERHITUNGAN

1. NaOH 0,1 N 500 mL
N= grMr
x1000v (ml)
0,1= gr40
x1000500
gr=2 gr NaOH
2. Berat endapan = 10,5 gr
3. A mol=(10,5−2,7)
498
3A mol = (0,0469 )H 2 SO 4
H 2 SO 4=0,049 L
¿49 ml

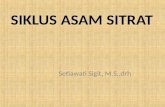









![SIKLUS ASAM SITRAT-14 [Compatibility Mode]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5571f96549795991698f7ae4/siklus-asam-sitrat-14-compatibility-mode.jpg)









