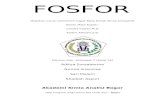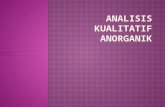Lap Anorganik Lengkap
-
Upload
sudiresahiyam -
Category
Documents
-
view
421 -
download
19
description
Transcript of Lap Anorganik Lengkap
ACARA I
PEMBUATAN KNO3
A. PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Tujuan : a). Memisahkan dua garam berdasarkan kelarutannya pada suhu
tertentu.
b). Membuat KNO3.
2. Hari, tanggal : Sabtu,7 Mei 2011.
3. Tempat : Laboratorium Kimia FKIP Universitas Mataram.
B. LANDASAN TEORI
KNO3 merupakan mineral terpenting dari nitrogen, dan disebut sebagai
sendawa. KNO3 pertama kali ditemukan di India dan Sendawa Chili (NaNO3) ditemukan
di Chili, Amerika. Kalium nitrat merupakan zat padat yang berbentuk kristal putih
dengan titik leleh sekitar 3400C, kalium nitrat memiliki sifat yang serupa dengan
natrium nitrat (NaNO3) yaitu tidak dapat menghisap air dari udara, oleh karena itu lebih
disukai dalam industry bahan penutup (Nitratmojo, 1983 : 58).
Pengaruh kenaikan suhu pada kelarutan zat berbeda satu dengan yang lain.
perbedaan ini dapat dipakai unyuk memisahkan campuran dua zat atau lebih dengan
cara rekristalisasi bertingkat. Contohnya memisahkan KNO3 dengan NaCl. Dari
percobaan terlihat bahwa kelarutan KNO3 sangat terpengaruh oleh kenaikan suhu.
Sedangkan NaCl tidak terpengaruh oleh suhu. Jika campuran ini dimasukkan dalam air
panas, maka kelarutan KNO3 lebih besar daripada natrium klorida, sehingga natrium
klorida lebih banyak mengkristal pada suhu tinggi, dan NaCl dapat dipisahkan dengan
menyaring dalam keadaan panas (Syukri, 1999 : 360).
Jika cairan didinginkan, KNO3 mengendap. Endapan ini dipisahkan kemudian
dimurnikan dengan rekristalisai. Nama umum untuk KNO3 adalah sendawa. Sedangkan
NaNO3 disebut sendawa Chili. Kalium nitrat mengkristal dalam bentuk prisma rombik,
tetapi jika larutannya diuapkan perlahan pada kaca arloji akan mengkristal dalam
bentuk rombohedral, isomorf dengan natrium nitrat dan kalsif (Purwoko, 2008 : 3).
1
C. PROSEDUR KERJA
1. Cara Kerja
No Cara Kerja Hasil Pengamatan1. Ditimbang 7,34 gr Al(NO3)3 dan
5,34 gr KCl.
Warna Al(NO3) = putih
Massa Al(NO3) = 7,34 gr
Warna KCl = putih
Massa KCl. = 5,34 gr
2. Dilarutkan kedua garam tersebut dengan aquades 10 ml.
Larutan A (Al(NO3)3)
Larutan B (KCl)
A = Setelah larut, terbenruk
larutan berwarna bening.
B = Setelah larut, terbenruk
larutan berwarna bening
Pada kedua larutan terdapat
pengotor yang tidak ikut
melarut yang berwarna abu
kehitaman.
3. Dicampurkan larutan A dan B Larutan A dan larutan B
mencampur sempurna.
2
A + B
Larutan C
4. Larutan C didinginkan dalam gelas beker berisi es batu pada suhu 0 C.
Setelah didinginkan, terbentuk endapan berwarna putih
5. Larutan C didekantasi.
Larutan C didekantasi, yaitu dengan mengalirkan larutan C pada batang pengaduk kaca sehingga akan terpisah antara sentrat (endapan putih) dan larutan.
3
A + B
6. Dimasukkan 1 mL air yang sudah dipanaskan ke dalam tabung C yg berisi sentrat.
yang bisa diamati endapan itu mencair dan berwarna putih. Penambahan air panas dilakukan untuk melarutkan pengotor yg masih terjebak dalam kristal yg terbentuk , dan selanjutnya untuk memurnikan kristal dilakukan dengan memanaskannya agar pengotor menguap
7. Larutan pada kegiatan no. 6 tersebut dipanaskan dengan pemanas spritus.
Endapan putih +pengotor ( karena masih belum murni Sehingga pemanasan (rekristalisasi) digunakan untuk mendapatkan kristal (endapan putih) yg lebih murni.
4
C D
+
C
pengotorpengotor pengotor
8. Kristal hasil pemanasan dikerok dengan spatula.
Warna kristal yang didapatkan adalah putih.
9. Ditimbang kristal yang dikerok tersebut dengan neraca analitik.
*gr kertas saring : 0,0002 gr *gr kertas saring + gr kristal : 3,2099 gr Jadi gr kristal = (gr kertas saring + gr kristal) - gr kertas saring = 3,2099 gr - 0,0002 gr = 3,2097 gr
2. Alat dan Bahan
Alat Bahan Gelas kimia Gelas ukur Neraca analitik Pemanas spritus Pengaduk Pipet tetes Segitiga Spatula Tabung reaksi besar termometer
Serbuk Al(NO3)3 Serbuk KCl Aquades Es batu
D. HASIL PENGAMATAN
(Terlampir)
E. ANALISIS DATA
1. Persamaan Reaksi
Reaksi pencampuran Al(NO3)3 dengan aquades
Reaksi pencampuran KCl dengan aquades
5
Reaksi pencampuran Al(NO3)3 dengan KCl
Reaksi pendinginan
2. Perhitungan
Diketahi :
Massa KCl = 3,34 gr
Massa Al(NO3)3 = 7,34 gr
Mr KCl = 74,5 gr/mol
Mr Al(NO3)3 = 213 gr/mol
Mr KNO3 = 101 gr/mol
Mr AlCl3 = 133,5 gr/mol
Dihitung :
Mol mula-mulaKCl
n = massa
Mr =
3,34 gr74,5 gr /mol
= 0,045 mol
Mol mula-mula Al(NO3)3
n = massa
Mr =
7,34 gr213 gr /mol
= 0,034 mol
Mula-mula : 0,034 mol 0,045 mol - -
Bereaksi : 0,015 mol 0,045 mol 0,045 mol 0.015 mol
Sisa :
0,023 mol 0 0,045 m0l 0,015 mol +
6
Berdasarkan keadaan sisa
Massa sisa KCl = 0 x 74,5 gr/mol =0
Massa sisa Al(NO3)3 = 0,023 mol x 213 gr/mol = 4,899 gr
Garam yang terbentuk
Massa KNO3 = 0,045 mol x 101 gr/mol= 4,545 gr
Masaa AlCl3 = 0,015 mol x 133,5 gr/mol = 2 gr
Kelarutan pada 0oC
Kelarutan KCl = 28,1 gr/100 ml = 5,62 gr/ 20 ml
Kelarutan Al(NO3)3 = 60,0 gr/100 ml = 12 gr/20 ml
Kelarutan KNO3 = 13,3 gr /100 ml = 2,669 gr/20 ml
Kelarutan AlCl3 = 43,9 gr/100 ml = 8,78 gr/100 ml
Berat teori yang mengendap
S (kelarutan) – berat sisa = … gr
S Al(NO3)3 – massa Al(NO3)3 sisa = 12 gr - 4,899 gr
S KCl – massa KCl sisa = 5,62 gr – 0 = 5,62 gr
S KNO3 - massa KNO3 sisa = 2,669 gr - 4,545 gr = - 1,885 gr
S AlCl3- massa AlCl3 sisa = 8,78 gr - 2 gr = 6,78 gr
Jika massa senyawa > massa kelarutan, maka terbentuk endapan
Jika massa senyawa < massa kelarutan, maka tidak terbentuk endapan
Maka dapat disimpulkan bahwa hanya KNO3 yang mengendap sedangkan
senyawa-senyawa lain dalam bentuk larutan.
Menghitung % rendemen
Dik : massa eksperimen = 3,2097 gr
: massa teori = 1,885 gr
Dit : % rendemen kristal KNO3…?
Dij :
% rendemen = massa eksperimen
massa teorix100 %
= 3,2097 gr1,885 gr
x100 %
7
= 170 %
F. PEMBAHASAN
Pada percobaan kali ini bertujuan untuk memisahkan dua garam berdasarkan
kelarutannya pada suhu tertentu dan membuat kalium nitrat (KNO3). Garam yang
dipisahkan dalam percobaan ini adalah garam KCl dan garam KNO3. Selanjutnya untuk
membuat KNO3 tersebut dengan cara mencampurkan/mereaksikan KCl dengan
Al(NO3)3. Suhu yang digunakan pada percobaan ini yaitu 0oC.
Untuk membuat KNO3 langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan cara
melarutkan masing-masing garam baik KCl maupun Al(NO3)3 dengan aquades 10 ml.
proses pelarutan ini bertujuan untuk agar setiap garam itu terionisasi menjadi ion-
ionnya, yaitu ion kalium, aluminium, ion nitrat dan ion klorin. Sehingga pada
pencampuran keua larutan akan terjadi pertukaran ion(ion exchange). Ion kalium dari
KCl akan berikatan dengan ion nitrat dari Al(NO3)3 membentuk KNO3.sedangkan ion
klorin akan berikatan dengan ion aluminium membentuk AlCl3. Kemudian campuran
larutan ini didinginkan hingga suhunya mencapai 0oC. Proses pendinginan campuran
kedua larutan bertujuan untuk mengendapakan salah satu garam yg terbentuk dari
pencanpuran tersebut.Berdasarkan teori, bahwa dalam pencampuran kedua larutan
terjadi pertukaran ion yg kembali menghasilkan dua garam baru yaitu KNO3 & Al(Cl)3,
dan berdasarkan teori kelarutan KNO3 pd suhu dingin < Al(Cl)3, shg KNO3 akan
mengendap. Dari uraikan di atas kita tarik hipotesa bahwa yang mengendap itu adalah
KNO3. Dan setelah dianalisis terbukti bahwa yang mengendap itu adalah KNO3.
Endapan yang terbentuk kemudian dipisahkan dengan cara dekantasi. Digunakan
proses dekantasi karena kedua zat tersebut sudah terpisah karena pendinginan
tersebut, dimana berbentuk padatan pada lapisan bawah dan cairan di bagian atas.
Cairan dituangkan dengan hati-hati melalui batang pengaduk, sehingga endapan yng
dihasilkan tertinggal di wadah . dalam kristal/endapan yang dihasilkan kemungkinan
8
masih terdapat pengotor-pengotor, untuk itu dilakukan rekristalisasi dengan tujuan
untuk memproleh kristal yang lebih murni. Prinsip dari kristalisai adalah perbedaan
kelarutan dari zat yang akan dipisahkan. Kristal yang dihasilkan tersebut Ditambahkan 1
mL air yang sudah dipanaskan ke dalam tabung yg berisi endapan, yang bisa diamati
endapan itu mencair dan berwarna putih. Penambahan air panas dilakukan untuk
melarutkan pengotor yg masih terjebak dalam kristal yg terbentuk , dan selanjutnya
untuk memurnikan kristal dilakukan dengan memanaskannya agar pengotor menguap.
Dalam hal ini dimungkinkan pengotornya adalah ion klorin. Setelah beberapa menit
terbentuk kristal yang berwarna putih, kemudian kristal dikerok menggunakan spatula.
Kristal yang didapatkan ditimbang dan didapatkan massa kristal adalah 3,2097gr dengan
persen kemurnian 170 %. Persen yang didapatkan lebih tinggi dari 100% hal ini
dimungkinkan masih adanya zat pengotor-pengotor.
G. KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Untuk memisahkan garam KCl dan Al(NO3)3 dilakukan dengan pendinginan hingga
suhu 0oC, hal ini didasarkan pada sifat kelarutan dari KNO3 yang memiliki kelarutan
lebih kecil pada suhu 0oC dari pada AlCl3.
2. Untuk membuat kalium nitrat, dapat digunakan garam KCl dan Al(NO3)3 yang
membentuk KNO3 melalui proses pelarutan, pendininan, dekantasi, dan pemanasan.
3. Persentase rendemen yang dihasilkan adalah 170%.
9
ACARA II
KIMIA MANGAN
A. PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Tujuan percobaan : Mempelajari senyawa mangan (VI), mangan (II), dan sifat-
sifatnya.
2. Hari, tanggal : Sabtu, 14 Mei 2011.
3. Tempat : Laboratorium Kimia FKIP Universitas Mataram.
B. LANDASAN TEORI
Mangan bersifat metalik dengan titik leleh kira-kira 124oC dan titik didih
1962oC. Dalam keadaan murni, logam mangan berwarna putih seperti perak, sangat
keras, tetapi mudah patah. Mangan mudah terisolasi oleh udara, bereaksi lambat
dengan air dan membentuk berbagai macam senyawa dengan tingkat oksidasi yang
paling bervariasi yaitu +2 hingga +7 (Sugiyarto, 2003: 34).
Oksida-oksida mangan dengan tingkat oksidasi lebih rendah besifat basa dan
bereaksi dengan asam membentuk garam katson Mn (II) dan Mn (III). Oksida-oksida
dengan tingkat oksidasi lebih tinggi sebaliknya bersifat asam dan bereaksi dengan
alkali menghasilkan garam-garam anion-okso. Jika MnO2 dilebur dengan hidroksida
logam alkali dan oksidator seperti KNO2 maka akan terbentuk garam manganat (VI)
yang berwarna hijau legam. Garam ini stabil dalam larutan alkali kuat, tetapi
terdisproporsionasi dalam larutan netral atau asam (Sugiyarto, 20003: 41).
Senyawa mangan (VI) kalium manganat, dapat dibuat dengan cara memanaskan
campuran KMnO4, MnO2, dan KOH padat. Suatu larutan yang mengandung mangan (III)
10
dapat diperoleh dengan cara mengoksidasi mangan (II) dengan KMnO4 dalam larutan
asam kuat. Garam mangan yang umum adalah MnSO4 dengan KMnO4. Garam KMnO4
biasanya digunakan dalam analisis volumetri. Namun karena larutan KMnO4 tidak dapat
digunakan sebagai larutan baku primer, maka diperlukan larutan standar untuk
menentukan konsentrasi larutan KMnO4. Untuk maksud ini dapat digunakan larutan
besi (II) ammonium sulfat yang rumusnya dinyatakan dengan (NH4)2SO4FeSO4.nH2O.
Harga n dapat ditentukan dengan mereaksikan larutan garam ini dengan larutan
standar KMnO4 sesuai dengan persamaan rekasi (Purwoko, 2007: 10 -11).
Mangan (III) di alam terdapat sebagai oksidanya yaitu Mn2O3 dan MnO(OH) tetapi
Mn3+ tidak stabil dalam air dan mudah tereduksi menjadi Mn2+ sebagaimana dinyatakan
oleh rendahnya nilai potensial reduksinya. Mineral Mn3O4 berwarna hitam, merupakan
campuran oksida Mn (II) dan Mn (III) yang terbentuk pada pemanasan semua jenis
mangan oksida hingga 100 0C diudara (Petrucci, 1987:153).
Kation mangan (II) diturunkan dari mangan (II) oksida. Ia membentuk garam-
garam tak berwarna, meskipun jika senyawa itu mengandung air kristal dan terdapat
dalam larutan, warnyanya agak merah jambu, ini disebabkan oleh adanya ion heksa
kuomanganat (II) (MnO(H2O)6)2+ ion mangan (III) tidak stabil, tetapi ada kompleks
yang mengandung mangan dalam keadaan oksidasi +3 dikenal orang. Mudah direduksi
menjadi ion mangan (II). Senyawa mangan (II) dengan kekecualian mangan (IV) oksida
adalah tidak stabil, karena ion mangan (IV) ini mudah direduksi menjadi mangan (II).
Senyawa mangan (VI) stabil dalam larutan basa dan berwarna hijau. Pada penetralannya
tejadi reaksi disproporsionasi, tebentuk endapan mangan dikosida dan ion manganat (VII)
atau permanganat. Jika mangan (VI) oksida diolah dengan asam, terbentuk ion-ion
mangan (II). Senyawa mangan (VII) mengandung ion manganat (VII) atau permangantat
MNO4-. Permanganat alkali adalah senyawa yang stabil yang menghasilkan larutan warna
lembayung. Semuanya merupakan zat pengoksidasi yang kuat (Shevla,1990).
11
C. PROSEDUR KERJA
1. Cara kerja
No Cara Kerja Hasil Pengamatan1 Mangan (VI)
Dimasukkan KMnO4 0,01 M sebanyak 5 ml, pada dua tabung berbeda.
Pada tabung A ditambahkan NaOH encer 5 ml dan MnO2, sedangkan pada tabung B ditambahkan H2SO4 encer 5ml, kemudian dikocok selama 2 menit.
Kemudian kedua larutan tersebut disaring, diamati warna hasil saringan pada kedua larutan tersebut.
Warna KMnO4 adalah ungu.
Pada tabung A KMnO4 + NaOH + MnO2 warna larutan ungu pekat, setelah pengocokan warna larutan semakin pekat dengan adanya bias kehijauan.
Sedangkan pada tabung B KMnO4 + H2SO4 + MnO2 warna larutan ungu , setelah pengocokan warna larutan menjadi ungu pekat.
Pada kedua larutan serbuk MnO2 tidak sepenuhnya larut.
Pada tabung A setelah penyaringan warna larutan yang dihasilkan adalah hiju tua.
12
Larutan yang menghasilkan warna hijau ditambahkan dengan H2SO4 encer 5 ml.
Pada tabung B setelah penyaringan warna larutan yang dihasilkan adalah tetap berwarna ungu namun lebih muda.
Hasil penyaringan yang berwarna hijau (yaitu pada tabung A) ditambahkan dengan H2SO4 menghasilkan larutan yang berwarna merah marun dengan adanya padatan coklat.
2 Mangan (III) Ditimbang 0,5 gr MnSO4
Dimasukkan MnSO4 yang sudah
Warna MnSO4 putih berbentuk serbuk halus
13
ditimbag tersebut pada tabung reaksi yang berisi 2ml H2SO4 encer.
Pada larutan tersebut ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 10ml
Larutan didinginkan
Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan KMnO4 0,1M pada larutan yang sudah didinginkan tersebut.
Ditambahkan aquades 50 ml.
Setelah MnSO4 dilarutkan dengan H2SO4 encer warna larutan putih keruh.
Larutan MnSO4 + H2SO4 pekat warna larutan tetap putih keruh mengeluarkan asap serta gelas kimia terasa panas.
Setelah pendinginan warna larutan tetap putih keruh, namun terdapat endapan pada larutan.
Larutan yang telah didinginkan tersebut ditambahkan dengan KMnO4 warna larutan berubah menjadi ungu keruh dengan masih terdapatnya endapan putih.
Pada penambahan
14
aquades warna larutan berubah menjadi merah marun muda, tanpa endapan, dan terdapat lapisan minyak di dalamnya, serta gelas kimia terasa panas.
2. Alat dan Bahan
Alat Bahan Tabung reaksi Gelas kimia Corong Pipet tetes Gelas ukur Kertas saring
KMnO4 0,01M KMnO4 0,1M NaOH encer H2SO4 encer H2SO4 pekat MnO2 MnSO4 Aquades
D. HASIL PENGAMATAN
(Terlampir)
E. ANALISIS DATA
Persamaan Reaksi :
Pembuatan Mangan (VI)
1. Dalam suasana Basa
KMnO4 + NaOH → MnO4- + Na+ + KOH
MnO4- + MnO2 → MnO4
2- + MnO2
2MnO4- + 3MnO2 + OH- → 3MnO4
2- + 4H2O
Dalam suasana asam
KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnO2 + H2O
4MnO4- + MnO2 + 2H2O → 5MnO4
2- + 4H+
3MnO42- + 4H+ → 2MnO4
- + MnO2 + 2H2O
Pembuatan Mangan (III)
MnSO4 + H2SO4 → MnSO4 + H2SO4
15
MnSO4 + KMnO4 → K2SO4 + MnO4- + Mn3+
Mn3+ + 5 MnO4- + 8H+ → 4 MnO4
- + 5 Mn3+ + 4 H2O
Perhitungan Eosel
1. Pembuatan Senyawa Mangan (VI)
a. Dalam suasana asam
MnO4- + e- → MnO4
2- x 2 Eo = + 0,56 V
MnO2 + 2H2O → MnO4 2- + 4H+ + 2e- x 1 Eo = - 2,26 V
2MnO4- + 2e- → 2MnO4
2- Eo = + 0,56 V
MnO2 + 2H2O → MnO4 2- + 4H+ + 2e- Eo = - 2,26 V
2MnO4 + MnO2 + 2H2O → 3MnO4 2- + 4H+ Eosell = +1,70V
b. Dalam suasana basa
MnO4 - + e- → MnO4
2- x 2 Eo = + 0,56 V
MnO2 + 4OH- → MnO4 2- + 4H2O + 2e- x 1 Eo = - 0,59 V
2MnO4- + 2e- → 2MnO4
2- Eo = + 0,56 V
MnO2 + 2OH+ → MnO4 2- + 2H2O + 2e- Eo = - 0,59 V
2MnO4 2- + MnO2 + 4OH- → 3MnO4 2- + 2H2O Eo
sell = +0.03 V
2. Pembuatan Senyawa Mangan (III)
Mn2+ → Mn3+ + e- x 5 Eo = - 1,51 V
MnO4 2- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O x 1 Eo = + 1,51 V
5Mn2+ → 5Mn3+ + 5e- Eo = - 1,51 V
MnO4 2- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O Eo = + 1,51 V
4Mn2+ + MnO4 - + 8H+ → 5Mn3+ + 4H2O Eo
sell = 0 V
F. PEMBAHASAN
Mangan merupakan unsure yang bereaksi lambat dengan air dan
membentuk senyawa dengan berbagai macam tingkat oksidasi. Mulai dari +2 hingga +7.
Dalam percobaan kali ini, dilakukan proses pembuatan mangan (VI) dan mangan (III)
serta diamati bagaimana sifat-sifatnya.
16
Pada pembuatan mangan (VI), reaksi dilakukan dalam dua suasana yaitu
suasana asam dan basa. Pada suasana asam KMnO4 direaksikan dengan H2SO4 dan
MnO2. KMnO4 yang merupakan mangan (VII) direduksi oleh MnO2 membentuk mangan
(VI). Akan tetapi reaksi ini menunjukkan uji negative terhadap keberadaan mangan (VI).
Hal ini terlihat dari hasil larutan yang masih berwarna ungu. Berdasarkan teori, mangan
(VI) yang terbentuk tersebut akan mengalami diproporsionasi dalam larutan asam dan
netral mempentuk permanganate dan MnO2. Pada suasana basa, KMnO4 0,01M
direaksikan dengan MnO2 tetapi dengan penambahan NaOH encer sebagai pemberi
suasana basa. Pada reaksi ini dihasilkan larutan yang berwarna hijau dan menunjukkan
bahwa mangan (VI) telah terbentuk dan stabil pada suasana tersebut. Meski demikian,
hasil ini baru akan dapat diperoleh bila pengocokan dilakukan dengan baik.
Pencampuran yang kurang sempurna akan menghasilkan filtrate yang masih tetap
berwarna ungu. Larutan hijau yang terbentuk ini kemudian direaksikan dengan H2SO4
yang membentuk larutan berwarna merah marun dan endapan-endapan coklat. Dari
hasil tersebut diketahi bahwa mangan (VI) tidak stabil pada kondisi asam. Hal ini juga
terlihat dari hasil Eo selnya, terlihat bahwa Eo sel reaksi untuk disproporsionasi dalam
suasana asam lebih besar dari dari suasana basa yang berarti bahwa disproporsionasi
lebih mudah terjadi pada suasana asam. Pada suasana asam Eo sel = +1,70 V dan pada
suasana basa hanya + 0.03 V.
Percobaan selanjutnya ialah pembuatan mangan (III). percobaan ini
dilakukan dalam suasana asam dengan mereaksikan MnSO4 sebagai sumber Mangan (II)
dengan H2SO4 sebagai pemberi suasana asam H2SO4 pekat yang memang diperlukan
untuk keberhasilan pembuatan mangan (III). Agar mangan (II) dapat membentuk
mangan (III), maka direaksikan dengan KMnO4 yang berperan sebagai oksidator.
Setelah direaksikan dengan KMnO4 yang berperan sebagai oksidator, terbentuk larutan
berwarna keunguan/merah jambu dengan masih terdapat endapan-endapan putih
MnSO4. Adanya warna merah jambu menunjukkan uji positif terhadap terbentuknya
mangan (III). Endapan putih yang terlihat masih cukup banyak. Hal ini karena mangan
(III) tidak stabil dan mengalami reduksi membentuk mangan (II) kembali.
Ketidakstabilan ini semakin meningkat dengan ditambahkannya aquades pada larutan
sebelumnya. Larutan ini menghasilkan larutan berwarna merah muda tanpaadanya
17
endapan. Endapan MnSO4 larut dengan adanya air sementara mangan (III) yang telah
terbentuk segera tereduksi menjadi mangan (II) yang ditunjukkan oleh larutan
berwarna merah muda tersebut. Berdasarkan Eo selnya yaitu 0, maka reaksi ini
merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi mangan (III) akan segera membentuk mangan
(II) ketika telah terbentuk.
G. KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Mangan (VI) dapat dibuat dengan mereaksikan KMnO4 dengan MnO2 yang bertindak
sebagai reduktor. Mangan (VI) yang terbentuk berwarna hijau dan hanya stabil bila
dibuat pada suasana basa.
2. Mangan (VI) yang dihasilkan pada suasana asam akan segera terdisproporsionasi
menjadi MnO2 berwarna hitam dan permanganate.
3. Mangan (III) dapat diperoleh dengan mengoksidasi Mangan (II) dalam garam MnSO4
dengan oksidator KMnO4.
4. uji positif mangan (III) ditunjukkan dengan adanya warna ungu kemerahan.
5. Mangan (III) bersifat tidak stabil terlebih pada air dan akan segera teroksidasi
membentuk mangan (II) berwarna merah muda dalam sebuah reaksi kesetimbagan
yang eksoterm.
ACARA III
GARAM MOHR
18
A. PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Tujuan : Membuat kristal besi (II) ammonium sulfat, (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O,
yang dikenal dengan nama garam mohr.
Menentukan jumlah air Kristal dalam garam mohr hasil sintesa.
2. Hari, tanggal : Sabtu, 23 Mei 2011.
3. Tempat : Laboratorium Kimia FKIP Universitas Mataram.
B. LANDASAN TEORI
Besi adalah logam yang menempati urutan kedua dari logam-logam yang umum
terdapat di kerak bumi. Besi (II) dengan garam sulfat dari logam alkali dapat
membentuk garam rangkap dengan rumus umum M2Fe(SO4)2.6H2O (M adalah K, Rb,Cs
atau NH4). jika jumlah mol sama, masing-masing dari besi (II) sulfat dan ammonium
sulfat dilarutkan sampai jenuh dalam air panas, dan dalam larutan besi (II) sulfat
ditambahkan sedikit asam sulfat,kemudian kedua larutan dicampur, maka pada
pendinginan akan mengkristal berbentuk monoklin berwarna hijau kebiru-biruan.
Garam ini, besi (II) amonium sulfat dengan rumus (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O, biasanya
disebut garam mohr. Dibandingkan dengan besi (II) sulfat atau besi (II) klorida, Kristal
garam mohr stabil di udara dan larutannya tidak mudah dioksidasi oleh oksigen oleh
oksigen di atmosfer (Purwoko, 2007:15)
Semua garam besi (II) terhidrat mengandung ion [Fe(H2O)6]2+ yang berwarna pucat
kehijauan. Jika sebagian teroksidasi menjadi besi (III) warna menjadi kuning kecoklatan.
Kristal garam besi (II) sulfat heptahedrat, FeSO4.7H2O, cendrung kehilangan beberapa
molekul air. Dalam fase padat, garam rangkap ammonium besi (II) sulfat heksahidrat
atau lebih tepatnya ammonium heksa akuo besi (II) sulfat atau disebut garam mohr,
menunjukkan stabilitas kisi yang paling tinggi. Garam ini di udara terbukatidak
mengalami eflourenense dan juga tak teroksidasi, sehingga sering dipakai sebagai
larutan standar khususnya pada titrasi redoks, misalnya untuk standarisasi larutan
kalium permanganate (Sugiyarto,2003:5.50-5.51).
Garam mohr (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O cukup stabil terhadap udara dan terhadap
hilangnya air, dan umumnya dipakai untuk membuat larutan beku Fe2+ bagi analisis
volumetric, dan sebagai zat pengkalibrasi dalam pengukuran magnetic. Sebaliknya
19
FeSO4.7H2O secara lambat melapuk dan berubah menjadi kuning cokelat bila dibiarkan
dalam udara (Cotton, 2009:462-464).
C. PROSEDUR KERJA
1. Cara kerja
NO CARA KERJA HASIL PENGAMATANLarutan A
1 Ditimbang 0,35 gr Fe menggunakan neraca analitik
.
Berat Fe = 0,35 gram yang berwarna hitam.
2. Dicampurkan Fe yang sudah ditimbang tersebut dengan H2SO4 10%.
Setelah dicampur Fe dengan H2SO4 yang berwarna bening, terbentuk larutan berwarna abu kehitaman.
3 Larutan A tersebut dipanaskan hingga semuanya melarut.
Pada saat pemanasan berlangsung terdapat bau.
4. Larutan A disaring. Filtrate hasil penyaringan bening dan tersisa endapan berwarna hitam pada kertas saring.
20
5. Ditambahkan H2SO4 10% sedikit pada filtrate.
Stelah penambahan dengan sedikit H2SO4 10% larutan tetap berwarna bening.
6. Larutan pada no 5 tersebut diuapkan Terbentuk Kristal dipermukaan larutan.
7. Dibuat larutan B dengan mencampurkan 1,4 ml NH3 dan 5ml H2SO4 10%.
LarutanH2SO4 (bening) + NH3 (bening), menghasilkan larutan berwarna bening.
8. Larutan B tersebut diuapkan hingga jenuh Yang menandakan larutan sudah jenuh yaitu adanya letupan, setelah terjadi letupan pemanasan
21
dihentikan.
9. Dicampurkan larutan A dan B selagi keduanya masih panas.
Larutan hasil pencampuran yaitu berwarna sedikit kuning dan terdapat butiran-butiran putih (endapan putih).
10. Larutan hasil pencampuran didinginkan hingga terbentuk Kristal berwarna hijau muda.
Larutan hasil pendinginan hijau muda.
11 Rekristalisasi Ditambahkan air panas pada gelas
kimia yang terdapat kristal hijau.
terlihat endapan sedikit melarut.
22
Disaring
Endapan dioven
setelah disaring endapan yang tersisa pada kertas saring dioven.
tujuan dioven yaitu untuk menghilangkan kadar air dalam endapan(Kristal).
12. Ditimbang endapan yang telah di oven. Berat kertas saring = 1,026 gr
Berat kertas saring + berat kristal = 2,5 gr
Berat kristal = 1,474 gr
2. Alat dan bahan
Alat Bahan Gelas kimia Gelas ukur Pipet tetes Neraca analitik Pembakar spritus Kaki tiga dan kawat
kasa Oven corong
larutam H2SO4 10% air panas besi larutan NH3 kertas saring
23
D. HASIL PENGAMATAN
(Terlampir)
E. ANALSIS DATA
1. Persamaan Reaksi
Fe(s) + H2SO4(aq) FeSO4(aq) + H2(g)
2NH4OH(aq) + H2SO4(aq) (NH4)2SO4(aq) + 2H2O
FeSO4(aq) + (NH4)2SO4(aq) (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O(s)/garam mohr
2. Perhitungan
Mencari mol garam mohr
Mol Fe = Mol (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
Gram Fe = 0,35 gr
Ar Fe = 56
Mol Fe =gr FeAr Fe
= 0,35 gr
56 gr /mol
= 0,00625 mol
Mol garam mohr = 0,00625 mol
Mencari massa garam mohr
Massa = mol x Mr
= 0,00625 mol x 390 gram/mol
= 2,4375 gram
Kemurnian Kristal (garam mohr)
Kemurnian garam mohr = massa garam mo h r percobaan
massa garam moh r teorix 100 %
= 1,4742,4375
x100 %
24
= 60,47 %
F. PEMBAHASAN
Praktikum kali ini bertujuan untuk membuat kristal besi (II) ammonium sulfat,
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O yang dikenal dengan nama garam mohr. Garam mohr
merupakan garam rangkap dari besi sulfat dan ammonium sulfat dengan rumus molekul
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O. Pembuatan garam mohr dilakukan dengan pemcampuran
larutan A (FeSO4), besi (II) sulfat dan larutan B [(NH4)2SO4], ammonium sulfat. Namun
sebelum mencampurkan, kedua larutan tersebut dibuat terlebih dahulu.
Pembuatan larutan A yang merupakan besi (II) sulfat dibuat dengan asam sulfat
10% dan besi. Besi yang direaksikan tersebut dalam bentuk serbuk, hal ini bertujuan
agar reaksi cepat berlangsung. Kemudian larutan tersebut dipanaskan untuk
mempercepat reaksi dan menghilangkan gas hidrogen hasil reaksi, berdasarkan
persamaan :
Fe(s) + H2SO4(aq) FeSO4(aq) + H2(g)
Sedangkan untuk membuat larutan B yang merupakan larutan ammonium
sulfat, (NH4)2SO4 dilakukan dengan mereaksikan H2SO4 dengan NH3 yang kemudian
diuapkan hingga jenuh. Tujuan larutan dijenuhkan yaitu agar endapan (kristal) cepat
terbentuk.
Pencampuran kedua larutan (A) dan larutan (B) dilakukan dalam keadaan
larutan masih panas, alasannya untuk mempercepat reaksi sehingga akan lebih mudah
terbentuknya kristal (endapan). Pada pencampuran, larutan B dimasukkan ke dalam
gelas kimia larutan A hal ini disebabkan karena larutan B tidak memiliki endapan pada
pemanasan, karena pada larutan B itu merupakan campuran H2SO4 dan NH3 yang
merupakan reaksi penetralan untuk membuat (NH4)2SO4. Jika dilakukan sebaliknya
dimana larutan A yang dituangkan ke dalam gelas kimia larutan B maka akan
dikhawatirkan kemungkinan tersisanya kristal besi pada dinding gelas kimia, sehingga
dapat mengurangi jumlah FeSO4, dan hal ini tentu akan mengurangi jumlah garam mohr
yang terbentuk nantinya. Setelah pencampuran, campuran kedua garam ini didiamkan
hingga terbentuk kristal yang berwarna hijau, dimana kristal hijau inilah yang disebut
garam mohr.
25
Untuk mendapatkan garam mohr yang lebih murni dilakukan rekristalisasi
pada kristal garam, dengan cara menambahkan sedikit air panas pada kristal. Tujuannya
untuk melarutkan pengotor-pengotor yang masih ada pada kristal, sehingga didapatkan
kristal garam yang lebih murni. Kemudian disaring dan hasil saringan kemudian dioven.
Didapatkan kristal garam yang berwarna hijau muda yang hampir berwarna putih yang
berbentuk monoklin, dan berdasarkan literature bahwa kristal garam yang berwarna
hijau dan berbentuk monoklin ini hasil pencampuran garam FeSO4 dan (NH4)2SO4
adalah garam mohr dengan rumus molekul (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O. Berdasarkan analisi
data pada perhitungan didapatkan berat garam mohr yaitu 1,474 gr dengan kemurnian
60,47 %. Kemurnian rendemen yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa pada
kristal masih terperangkap pengotor-pengotor yang tidak larut pada proses
pengkristalan (pemurnian kristal).
G. KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan dan pembahasan dapat disimpulkan sbb:
1. Garam mohr ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O) dapat dibuat dengan mencampurkan dua
garam yaitu garam besi (II) sulfat dan garam ammonium sulfat.
2. Cirri fisik dari garam mohr adalah kristal berwarna hijau muada dengan bentuk
monoklin.
3. Persen kemurnian garam yang dihasilkan adalah 60,47%.
26
ACARA IV
PEMBUTAN KRISTAL TEMBAGA ( II ) SULFAT
A. PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1 Tujuan Praktikum : a. membuat dan mengenal sifat kristal tembaga (II) sulfat.
b. memahami proses pembuatan kristal.
2. Waktu Praktikum : Sabtu, 28 Mei 2011.
Sabtu,04 Juni 2011.
3. Tempat Praktikum : Laboratorium kimia FKIP Universitas Mataram.
B. LANDASAN TEORI
Kebanyakan senyawa Cu ( I ) cukup mudah teroksidasi menjadi Cu ( II ), namun
oksidasi selanjutnya menjadi Cu ( III ) adalah sulit. Terdapat kimiawi larutan Cu2+ yang
dikenal baik, dan sejumlah besar garam berbagai anion didapatkan, banyak diantaranya
larut dalam air, menambah perbendaharaab kompleks. Cu ( II ) cenderung mengalami
distorsi bila diletakkan dalam lingkungan simetri kubus ( yaitu oktahedral atau tetrahedral
biasa ). Akibatnya Cu ( II ) hampir selalu ditemukan dalam lingkungan yang memungkinkan
distorsi dari simetri yang biasa ini. Kekhasan distorsi oktahedron adalah bahwa terdapat
empat iktan Cu – L pendek dalam bidang dan dua ikatan trans yang panjang. Dalam batas
tertentu, pemanjangan tertentu menyebabkan situasi yang tidak dapat dibedakan dari
koordinasi segi empat seperti ditemukan dalam CuO dan banyak kompleks diskret Cu ( II )
( Cotton dan Wilkinson, 2007: 479 – 480 ).
Garam – gram tembaga ( II ) umumnya berwarna biru, baik dalam bentuk hidrat,
padat, maupun dalm bentuk larutan air, warna ini benar – benar khas hanya untuk ion
tetraakuokuprat ( II ) [Cu(H2O)4]2+ saja. Garam – garam tembaga ( II ) anhidrat, seperti
tembaga ( II ) sulfat anhidrat CuSO4, berwarna putih ( atau sedikit kuning ). Dalam larutan
air selalu terdapat ion kompleks tetraakuo ( Vogel, 1990: 229 – 230 ).
27
Tenbaga tidak larut dalam asam yang bukan pengoksidasi namun larut dalam asam
nitrat ( HNO3 ). Bentuk pentahidrat yang terhidrat dengan kehilangan empat molekul
airnya pada 1100 C dan lima molekul air pada 1500 C. pada 6500 C tembaga ( II ) sulfat
terurai menjadi tembaga ( II ) oksida ( CuO ), SO2 dan O2 ( Keenan, 1992: 194 ).
Tembaga adalah logam berdaya hantar listrik tinggi, maka dipakai sebagai kabel
listrik. Tembaga tidak larut dalam asam yang bukan pengoksidasi tetapi tembaga
teroksidasi oleh HNO3 sehingga tembaga larut dalam HNO3 ( Syukri, 1990: 626 ).
3 Cu + 8 H+ + 2 NO3- → 3 Cu2+ + 2 NO + 4 H2O
C. PROSEDUR KERJA
CARA KERJA
NO CARA KERJA HASIL PENGAMATAN
1. Diisi 10 mL H2SO4 pekat dan 25 mL air ke
dalam gelas kimia.
H2SO4 + air larutan
tetap bening
2. Dimasukkan 2,5 gram keeping tembaga Massa keeping tembaga = 2,5057
gr
Warna keeping tembaga = cokelat
keemasan, setelah dilarutkan
dalam larutan H2SO4, keeping
tembaga tidak larut semua dan
warna larutan tetap bening dan
muncul gelembung disekitarnya.
3. Didalam lemari asam Setelah ditambahkan HNO3 pekat
larutan menjadi keruh, dan
dipanaskan, ketika dipanaskan
28
larutan ditambahkan dengan 5ml
H2SO4 pekat lagi sehingga warna
larutan menjadi biru muda bening
serta mengeluarkan uap dengan
bau yang menyengat. Setelah
ditambahkan 10 ml aquades, 2 ml
H2SO4 dan 5 ml HNO3 larutan
mengeluarkan uap yang berwarna
cokelat dan warna larutan biru tua
bening.
4. Larutan disaring ketika masih panas, dan
larutan disimpan hingga terbentuk Kristal.
Setelah disaring masih terdapat
sisa tembaga yang massanya
2,0224 gram. Setelah didiamkan
beberapa hari terbentuk Kristal
berwarna biru tua dengan larutan
berwarna biru muda.
5. Larutan didekantasi Kristal dan larutan terpisah
6. Kristal hasil dekantantasi dicuci dengan
sedikit air kemudian dilarutkan dalam air
29
sesedikit mungkin, kemudian didekantasi lagi.
7. Pada penambahan aquades yang ketiga
Kristal disaring.
8. Kristal dioven
30
9. Kristal yang sudah dioven ditimbang. Berat kertas saring = 0,94 gr
Berat kertas saring + Kristal = 1,52
gr
Berat Kristal = Berat kertas saring
+ Kristal - Berat kertas saring =
1,52 gr - 0,94 gr = 0,58 gram.
ALAT dan BAHAN
Alat Bahan
pengaduk
gelas kimia
pipet tetes
corong
cawan penguapan
timbangan analitik
kertas saring
oven
aquades
asam sulfat pekat
keping Cu
asam nitrat pekat
D. HASIL PENGAMATAN
(terlampir)
E. ANALISIS DATA
Persamaan Reaksi
Cu + 2 H2SO4 → Cu2+ + SO42- + SO2 + 2 H2O
3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu2+ + 6 NO3- + NO + 4 H2O
Reaksi lengkap
Cu + 3 H2O + H2SO4 + 2 HNO3 → CuSO4(aq) + 2 NO + 5 H2O
Perhitungan
Mencari mol Kristal tembaga (II) sulfat
31
Cu2+ + SO42- + 5 H2O → CuSO4.5H2O
Mol Cu = 2,505763 ,55
=0 , 039 mol
Mol CuSO4.5H2O = mol Cu = 0,039 mol
Mencari massa Kristal tembaga (II) sulfat
Massa CuSO4.5H2O = mol CuSO4.5H2O x Mr CuSO4.5H2O
= 0,039 x 249,55
= 9,73245 gram
Mencari kemurnian Kristal
Dik : massa Kristal percobaan = 0,58 gr
% rendemen = massa kristal percobaan x 100 %
Massa kristal teori
=
0,589 ,73245
x 100 %
= 5,95 %
F. PEMBAHASAN
Pada praktikum kali ini, percobaan yang dilakukan adalah pembuatan tembaga
( II ) sulfat. Tembaga ( II ) sulfat yang dibuat berbentuk kristal. Tembaga ( II ) sulfat yang
dibuat ini berbentuk hidrat dengan rumus molekul CuSO4.5H2O. hidrat ini merupakan
kristal berwarna biru. Kristal CuSO4.5H2O ini ada yang berbentuk rhombik dan ada juga
yang berbentuk monoklinik. Rhombik yaitu bentuk kristal bulat – bulat sedangkan
monoklinik berbentuk jarum.
Pada percobaan ini kristal CuSO4.5H2O dibuat dengan cara mereaksikan aquades,
asam sulfat pekat, logam tembaga ( Cu ), dan oksidator berupa asam nitrat pekat. Fungsi
penambahan aquades yaitu yaitu untuk menjadi hidrat pada kristal tersebut. Pada
pencampuran aquades dan H2SO4, terlebih dahulu aquades dimasukkan ke dalam gelas
kimia. Karena jika H2SO4 dimasukkan terlebih dahulu akan terjadi reaksi yang sangat
eksoterm dan membahayakan keselamatan praktikan. Penggunaan oksidator berupa
asam nitrat pekat karena logam Cu hanya larut ke dalam asam nitrat dan tidak larut
pada asam – asam yang lain. Asam nitrat pekat merupakan oksidator kuat. Asam nitrat
32
ini memiliki kemampuan mengoksidasi lebih tinggi dibandingkan dengan HCl. Hal ini
disebabkan karena pada asam nitrat memiliki oksidator tambahan berupa NO3-. NO3
- ini
merupakan oksidator yang lebih kuat dari H+. hal ini menyebabkan logam Cu terlalu
lemah sebagai reduktor untuk larut dalam HCl tetapi larut dalam asam nitrat pekat.
Setelah ditambahkan HNO3 pekat larutan menjadi keruh, dan dipanaskan, ketika
dipanaskan larutan ditambahkan dengan 5ml H2SO4 pekat lagi sehingga warna larutan
menjadi biru muda bening serta mengeluarkan uap dengan bau yang menyengat. Setelah
ditambahkan 10 ml aquades, 2 ml H2SO4 dan 5 ml HNO3 larutan mengeluarkan uap
yang berwarna cokelat dan warna larutan biru tua bening. Reaksi yang terjadi adalah :
Cu + 2 H2SO4 → Cu2+ + SO42- + SO2 + 2 H2O
Gas yang dihasilkan adalah NO. NO merupakan gas tak berwarna. Namun, pada
percobaan ini terbentuk gas berwarna coklat. Gas tersebut merupakan gas NO2. gas NO
sangat mudah sekali bereaksi dengan udara sehingga membentuk gas NO2 yang
berwarna coklat.
Pada percobaan ini, kristal yang terbentuk berbentuk monoklinik. Kristal yang
diperoleh terlebih dahulu dicuci dengan aquades. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan
kandungan nitrat yang masih ada pada kristal yang sudah terbentuk tersebut. Setelah
disaring, kristal yang diperoleh tersebut kemudian dikeringkan (dioven). Setelah kering,
kristal yang diperoleh tersebut kemudian ditimbang. Berat bersih kristal CuSO4.5H2O
yang diperoleh pada percobaan ini adalah 0,58 gram. Sedangkan berdasarkan teori,
berat kristal CuSO4.5H2O yang seharusnya diperoleh adalah 9,73245 gram. Dengan
demikian diperoleh % rendemen untuk kristal CuSO4.5H2O sebesar 5,95 %.
33
G. KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan percobaan, maka dapt disimpulkan sbb:
1. Kristal tembaga (II) sulfat dapat dibuat dengan mereaksikan keeping tembaga
dengan HNO3 pekat.
2. kristal CuSO4.5H2O berwana biru muda.
3. kristal CuSO4.5H2O ada yang berbentuk rhombik dan ada yang berbentuk
monoklinik.
4. fungsi penambahan aquades adalah untuk menjadi hidrat ada kristal.
5. logam Cu hanya larut pada asam oksidator asam nitrat pekat dan tidak larut pada
asam – asam yang lain.
6. % rendemen CuSO4.5H2O yang diperoleh adalah 5,95 %
34
SARAN
Terimakasih saya ucapkan kepada kakak-kakak co-Asst yang telah membimbing kami
selama praktikum berlangsung. Semoga yang kami dapat pada praktikum kimia anorganik
II ini bermanfaat bagi kami.
35
DAFTAR PUSTAKA
Cotton, F. Albert dan Geofrey Wilkinson. 2007. Kimia Anorganik Dasar. Jakarta: UI Press.
Idris, M, dkk. 2008. Kamus MIPA. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Keenan, Charles W, dkk. 1999. Kimia untuk Universitas. Jakarta: Erlangga.
Nitratmojo, Mahsun. 1983. Mengkaji Kimia Anorganik. Malang : IKIP Malang.
Purwoko, Agus Abhi. 2007. Petunjuk Praktikum Kimia Anorganik II. Mataram : Universitas
Mataram Press.
Shevla, G. 1990. Analisis Organik Kualitatif Makro dan Semimakro. Jakarta: PT. Kalman Media
Pustaka.
Sugiyarto, Kristian H. 2003. Dasar-dasar Kimia Organik Logam. Yogyakarta: UNY press.
Syukri, S. 1999. Kimia Dasar 2. Bandung : ITB Press.
Syukri, S. 1999. Kimia Dasar 3. Bandung: ITB Press.
Vogel. 1990. Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro. Jakarta: PT
Kalman Media Pusaka.
36