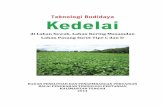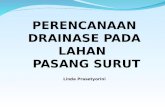Lahan Pasang Surut.docx
-
Upload
tarisaelen -
Category
Documents
-
view
120 -
download
43
Transcript of Lahan Pasang Surut.docx
Bab 3. Mengenal Lahan Gambut
Bab 1Pendahuluan
Lahan pasang surut merupakan lahan yang penyebarannya cukup luas. Di Indonesia terdapat sekitar 20,10 juta ha lahan pasang surut di tiga pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya (Widjaja Adhi et al., 1992). Sebagian besar dari luasan tersebut belum dimamfaatkan secara maksimal. Usaha pemanfaatan lahan pasang surut di kawasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dimulai sekitar 200 tahun yang lalu secara tradisional. Lahan pasang surut mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan pertanian dengan produk-tivitas tinggi bila dilakukan dengan menerap-kan teknologi spesifik lokasi dan didukung oleh kelembagaan yang konduktif. Pemanfaatan lahan pasang surut belum optimal karena berbagai kendala, hal ini terlihat dari tingkat produksi dan indeks pertanaman yang rendah.Lahan rawa pasang surut di Indonesia mulai memperoleh perhatian, kajian dan garapan secara serbacakup (comprehensive) sebagai suatu sumberdaya pada tahun 1968. Kepedulian ini dibangkitkan oleh persoalan yang sangat mendesak akan pemenuhan kebutuhan beras yang terus meningkat.Pada sekitar tahun 1920-an mulai dilakukan berbagai pembangunan di daerah lahan pasang surut antara lain pembuatan jalan, transmigrasi dan pembuatan saluran drainase. Program ini ternyata cukup berhasil sehingga mengilhami pemerintah untuk melakukan pembukaan lahan pasang surut secara besar-besaran dengan dibentuknya Tim Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S). Hal ini membuat wilayah ini mulai dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Indonesia. Bahkan ketika Indonesia menjadi negara swasembada beras ( tahun 1984) ternyata 59.1 % didukung dari hasil padi di lahan pasang surut (Isdijanto Ar-Riza et al., 1997).Pengelolaan tanah dan air merupakan kunci keberhasilan usaha tani di lahan pasang surut. Dengan upaya yang sungguh-sungguh lahan pasang surut ini dapat bermanfaat bagi petani dan masyarakat luas.Adapun tujuan dari pengelolaan lahan adalah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya lahan secara optimal, mendapatkan hasil maksimal dan mempertahankan kelestarian sumber daya lahan itu sendiri.
Bab 2Pembahasan
2.1 Pengertian dan KarakteristikLahan rawa pasang surut adalah suatu wilayah rawa yang dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air laut yang secara berkala mengalami luapan air pasang. Jadi lahan rawa pasang surut dapat dikatakan sebagai lahan yang memperoleh pengaruh pasang surut air laut atau sungai-sungai sekitarnya. Bila musim penghujan lahan-lahan ini tergenang air sampai satu meter di atas permukaan tanah, tetapi bila musim kering bahkan permukaan air tanah menjadi lebih besar 50 cm di bawah permukaan tanah.Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zone/wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut atau pun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Sebagian besar jenis tanah pada lahan rawa pasang surut terdiri dari tanah gambut dan tanah sulfat masam.
Gambar 2.1.1 Pembagian zona lahan rawa di sepanjang daerah aliran sungai bagian bawah dan tengah
Wilayah rawa pasang surut air asin/payau merupakan bagian dari wilayah rawa pasang surut terdepan, yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Biasanya, wilayah rawa ini menempati bagian terdepan dan pinggiran pulau-pulau delta serta bagian tepi estuari, yang dipengaruhi langsung oleh pasang surut air laut/salin. Pada zona wilayah rawa, terdapat kenampakan-kenampakan (features) bentang alam (landscape) spesifik yang mempunyai bentuk dan sifat-sifat yang khas disebut landform.Bagian terdepan terdapat dataran lumpur, atau mud-flats, yang terbenam sewaktu pasang dan muncul sebagai daratan lumpur tanpa vegetasi sewaktu air surut. Di belakang dataran lumpur, pada pantai yang ombaknya kuat dan pantainya berpasir, dapat terbentuk bukit-bukit rendah (beting) pasir pantai. Tanah yang terbentuk di sini merupakan tanah berpasir. Di belakangnya terdapat danau-danau kecil dan sempit yang disebut laguna (lagoons), biasanya ditempati tanah-tanah basah bertekstur liat. Lebih ke dalam ke arah daratan, dijumpai rawa pasang surut bergaram (tidal salt marsh) yang sebagian masih selalu digenangi pasang dan ditumbuhi hutan bakau/ mangove. Sebagian lagi, di wilayah belakangnya terdapat bagian lahan yang kadang masih dipengaruhi air pasang melalui sungai-sungai kecil (creeks), namun juga sudah ada pengaruh air tawar (fresh-water) yang kuat dari wilayah hutan rawa dan gambut air tawar yang menempati depresi/cekungan lebih ke darat. Bagian lahan yang dipengaruhi air payau ini ditumbuhi banyak spesies, tetapi yang terutama adalah nipah (Nipa fruticans), panggang (Sonneratia acida), dan pedada (Araliceae).Sifat tanah dan air yang perlu dipahami di lahan pasang surut ini berkaitan dengan:- tanah sulfat masam dengan senyawa piritnya tanah gambut- air pasang besar dan kecil kedalaman air tanah- kemasaman air yang menggenangi lahan.Berdasarkan pola genangannya (jangkauan air pasang), lahan pasang surut ini dibedakan menjadi 4 tipe luapan:1. Tipe A: Lahan yang selalu terluapi air pasang, baik pasang besar,maupun pasang kecil.2. Tipe B: Lahan yang hanya terluapi oleh pasang besar.3. Tipe C: Lahan yang tidak pernah terluapi walaupun pasang besar. Air pasang mempengaruhinya secara tidak langsung, kedalaman air tanah dari permukaan tanah pada waktu pasang kurang dari 50 Cm.4. Tipe D: Lahan yang tidak terluapi air pasang dan air tanahnya lebih dalam dari 50 Cm tetapi pasang surut air masih terasa tampak pada saluran tersier.
Bab 3. Mengenal Lahan Gambut
58Panduan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan13
Gambar 2.1.2 Empat tipe lahan pasang surut berdasarkan jangkauan air pasang
2.2 Luas Lahan dan PenyebarannyaDengan menggunakan peta satuan lahan skala 1 : 250.000, Nugroho et al. (1992) memperkirakan luas lahan rawa pasang surut di Indonesia, khususnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya mencapai 20,11 juta ha, yang terdiri dari 2,07 juta ha lahan potensial, 6,71 juta ha lahan sulfat masam, 10,89 juta ha lahan gambut dan 0,44 juta ha lahan salin. Sedangkan menurut wilayah dan statusnya, menunjukkan bahwa potensi lahan pasang surut terluas ada di Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya . Lahan tersebut tersebar terutama di pantai timur dan barat Sumatera, pantai selatan Kalimantan, pantai barat Sulawesi serta pantai utara dan selatan Irian Jaya sedangkan sebaran tipologi lahan berbeda menurut wilayah dalam arti bahwa tiap wilayah dapat mencakup beberapa tipologi lahan dan tipe luapan air.Dari luas lahan pasang surut tersebut, sekitar 9,53 juta hektar berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian, sedangkan yang berpotensi untuk areal tanaman pangan sekitar 6 juta hektar. Areal yang sudah direklamasi sekitar 4,186 juta hektar, sehingga masih tersedia lahan sekitar 5,344 juta hektar yang dapat dikembangkan sebagai areal pertanian. Dari lahan yang direklamasi, seluas 3.005.194 ha dilakukan oleh penduduk lokal dan seluas 1.180.876 ha dilakukan oleh pemerintah yang utamanya untuk daerah transmigrasi dan perkebunan Pemanfaatan lahan yang direklamasi oleh pemerintah adalah 688.741 ha sebagai sawah dan 231.044 ha sebagai tegalan atau kebun, sedangkan 261.091 ha untuk keperluan lainnya.2.3 Kendala di Lahan Pasang SurutKendala dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Pasang Surut Lahan pasang surut biasanya dicirikan oleh kombinasi beberapa kendala seperti (Anwarhan dan Sulaiman, 1985):1. Ph rendah2. Genangan yang dalam3. Akumulasi zatzat beracun ( besi dan aluminium)4. Salinitas tinggi, kekurangan unsur hara5. Serangan hama dan penyakit6. Tumbuhnya gulma yang dominan.Menurut Widjaja Adhi et al (1992), lahan pasang surut merupakan lahan marginal dan rapuh yang pemanfaatannya memerlukan perencanaan dan penanganan yang cermat. Kekeliruan di dalam membuka lahan ini akan membutuhkan investasi besar dan sulit untuk mengembalikannya seperti keadaan semula. Karena itu, pengembangan lahan pasang surut memerlukan perencanaan yang teliti, penerapan teknologi yang sesuai, dan pengelolaan yang tepat.Menurut Widjaja Adhi et.al (1992), faktor penting yang perlu dipertimbangkan di dalam pengembangan dan pengelolaan lahan pasang surut diantaranya adalah :1. Lama dan kedalaman air banjir atau air pasang serta kualitas airnya;2. Ketebalan, kandungan hara, dan kematangan gambut;3. Kedalaman lapisan pirit dan kemasaman total potensial dan aktual setiap lapisan tanahnya;4. Pengaruh luapan atau intrusi air asin/payau; dan5. Tinggi muka air tanah dan keadaan substratum lahan, apakah endapan sungai, laut, atau pasir kuarsa.Menurut Litbang Pertanian (1993) macam dan tingkat kendala yang diperkirakan dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor di atas digunakan dalam menyusun tipologi lahan pasang surut yang dikelompokkan kedalam 4 tipologi utama, yaitu:1. Lahan potensial; yaitu lahan nnnnnyang memiliki kendala teknis agronomis yang paling ringan, jika dibandingkan dengan lahan lainnya. Karakteristik lahan potensial adalah tekstur liat, lapisan pirit berada pada kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah, kandungan N dan P tersedia rendah, derajat keasaman (pH) 3,5 - 5,5 ; serta kandungan pasir kurang dari 5% dan debu 20%.2. Lahan sulfat masam; dicirikan oleh kandungan senyawa sulfida tinggi dan lapisan pirit terletak pada kedalaman kurang dari 50 cm. Di lapang terdapat dua macam lahan sulfat masam, yaitu :a. Lahan sulfat masam potensial; dicirikan oleh belum teroksidasinya lapisan pirit dan pH di atas 3,5;b. Lahan sulfat masam aktual; dicirikan oleh telah teroksidasinya lapisan pirit, dan pH kurang dari 3,5. Kemasan tanah yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan hara, sehingga tanaman dapat mengalami kekahatan dan keracunan hara.3. Lahan gambut; adalah lahan yang mempunyai lapisan gambut dengan berbagai ketebalan dan terbagi kedalam beberapa golongan yaitu : bergambut; ketebalannya kurang dari 50 cm, gambut dangkal; ketebalannya 50 - 100 cm, gambut sedang ; ketebalannya 100 - 200 cm, gambut dalam ; ketebalannya 200 - 300 cm, dan gambut sangat dalam, ketebalannya di atas 300 cm.4. Lahan salin; merupakan lahan yang dipengaruhi oleh intrusi air bergaram sehingga mempunyai daya hantar listrik lebih dari 4 MS / cm, tetapi mengandung unsur Na dapat dipertukarkan kurang dari 15%. Pendekatan yang ditempuh untuk mengatasi salinitas ini adalah dengan mengurangi terjadinya intrusi air bergaram dan mengusahakan komoditas serta varietas yang toleran terhadap salinitas.Genangan air menjadi kendala pengembangan terutama pada lahan bertipe luapan A yang sering mengalami kebanjiran karena keadaan topografinya menyulitkan pembuangan airnya. Kemasaman tanah yang tinggi mempengaruhi keseimbangan reaksi kimia dalam tanah dan ketersediaan unsur hara dalam tanah terutama fosfat. Rendahnya tingkat kesuburan alami tanah di lahan pasang surut berkaitan erat dengan karakteristik lahannya. Lahan gambut memiliki kekurangan unsur mikro turutama Zn, Cu, dan Bo, sedangkan lahan sulfat masam umumnya memiliki ketersedian P yang rendah karena besarnya fiksasi oleh Al dan Fe menjadi senyawa kompleks.Karakteristik lahan yang menjadi masalah dalam pengembangan pertanian di lahan pasang surut meliputi: fluktuasi rejim air, beragamnya kondisi fisiko-kimia tanahnya, tingginya kemasaman tanah dan asam organik pada lahan gambut, adanya zat beracun, intrusi air garam, dan rendahnya kesuburan alami tanahnya. Khusus untuk lahan sulfat masam meliputi : kemasaman tanah dan air sangat tinggi; kandungan aluminium (Al), besi (Fe) dan hidrogen sulfida (H2S) tinggi; dan ketersediaan unsur hara terutama P dan K rendah. Sedangkan untuk lahan gambut meliputi : kemasaman tanah dan air tinggi, ketersediaan unsur hara makro dan mikro terutama P, K, Zn, Cu dan Bo rendah, dan daya sangga tanah rendah.Zat beracun yang umum dijumpai di lahan pasang surut adalah aluminium, besi, hidrogen sulfida dan air garam atau natrium. Keracunan aluminium biasanya terjadi pada kondisi tanah kering dan disertai dengan kahat P, karena P diikat menjadi aluminium fosfat yang tidak larut. Besi ferro biasanya terdapat berlebihan pada lahan sulfat masam yang tergenang air. Hidrogen sulfida dapat terjadi pada tanah sulfat masam yang banyak mengandung bahan organik sebagai hasil reduksi sulfat dalam tanah yang tergenang. Kelarutan unsur beracun seperti Fe, Al, SO4 di dalam air mencapai puncaknya pada minggu minggu awal setelah hujan dengan pH yang sangat rendah dan berangur-angsur menurun sampai mendekati musim kemarau. Salinitas di lahan pasang surut disebabkan oleh adanya intrusi air laut yang biasanya terjadi pada bulan Juli-September. Salinitas yang tinggi pada zona perakaran akan menghambat penyerapan air dan unsur hara, bahkan pada konsentrasi tinggi dapat menyedot air dalam sel tanaman sehingga tanaman menjadi kering.Gulma merupakan salah satu kendala utama usahatani di lahan pasang surut. Gulma, yang merupakan pesaing tanaman dalam pemanfaatan unsur hara, air, dan ruang, ditaksir ada sekitar 120 jenis. Sebagian gulma juga menjadi tempat hidup dan tempat bernaung hama dan penyakit tanaman, serta menyumbat saluran air.Jenis gulma yang ditemukan di lahan pasang surut sangat dipengaruhi oleh tipe luapan. Pada lahan yang terus menerus tergenang, gulma yang paling banyak dijumpai adalah gulma air (eceng, semanggi, jajagoan, jujuluk), sedangkan pada lahan yang tidak tergenang, sebagian besar adalah gulma darat (alang-alang, gerintingan, babadotan, dll.). Pada lahan yang tergenang saat pasang besar saja, ditemukan baik gulma air maupun gulma darat.2.4 Pengembangan Lahan Pasang SurutPada tahun 1970an kebanyakan pakar tanah negara barat, khususnya dari Belanda, sangat menyangsikan potensi lahan rawa pasang surut untuk dikembangkan bagi tujuan pertanian. Pendapat ini mereka dasarkan atas sejumlah fakta yang mereka tafsirkan sebagai kendala berat berkenaan dengan hidrologi, gambut tebal, amblesan (subsidence), potensi membentuk tanah sulfat masam, konsistensi tanah rendah, pelindian hara oleh gerakan pasang surut air, penyusupan air laut, dan keterjangkauan (accessibility).Para pakar tanah Indonesia, dengan belajar dari pengalaman orang-orang Bugis dan dukungan kuat para pakar tanah Thailand dan Vietnam dengan pengalaman mereka di negara masing-masing, mengambil sikap tidak pesimistik namun juga tidak optimistik berlebihan. Sikap ini diambil karena tiga pertimbangan: (1) lahan rawa pasang surut mencakup luasan puluhan juta hektar di Indonesia dan karena itu merupakan kimah (asset) yang tidak boleh diabaikan, (2) untuk menyawahkan lahan rawa pasang surut tidak diperlukan pengadaan air yang biasanya memerlukan konstruksi-konstruksi mahal, karena air yang diperlukan sudah tersedia di tempat, tinggal ditata dengan biaya kurang mahal, dan (3) secara nasional pencukupan produksi beras merupakan tindakan strategis.Disamping tiga pertimbangan tadi, ada pertimbangan yang bersifat lebih pribadi. Kesediaan para pakar tanah Indonesia menerima tantangan berat, baik dari alam maupun dari sikap para rekan pakar dari negara maju, dihidupi oleh tanggungjanji (commitment) mereka kepada perbaikan kehidupan rakyat pedesaan pada umumnya dan rakyat petani pada khususnya, dan kebanggaan berlomba dengan para pakar negara maju dalam pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.Agar pelanjutan pengembangan rawa pasang surut dapat berlangsung pasti dan berlanjut secara sistematis, panggah (consistent) dengan maksud dan tujuan semula, dan berkesinambungan, diperlukan peletakan landasan kuat sebagai berikut:1. Keyakinan akan potensi lahan rawa pasang surut sebagai kimah nasional penting. Untuk membentuk keyakinan ini diperlukan inventarisasi andal yang menyangkut penetapan:a. Luas total lahan rawa pasang surut (angkanya sekarang masih simpang siur).b. Harkat untuk penggunaan pertanian menurut persebaran kelas-kelas harkat lahan yang dipilahkan berdasarkan suatu sistem klasifikasi terpilih (sekarang belum tuntas, baik klasifikasinya maupun pemetaannya)2. Keyakinan akan manfaat dan kelangsungan penelitian dan pengembangan lahan rawa pasang surut bagi pembangunan wilayah pada umumnya dan bagi pembangunan pertanian pada khususnya. Untuk menumbuhkan keyakinan ini diperlukan pembentukan organisasi mapan dan penyusunan rencana kerja pasti yang melibatkana. Perancangan metodologi yang menjamin perolehan hasil kerja yang memenuhi baku mutu IPTEK dan keterpaduan penelitian proaktif dan reaktif (sampai sekarang belum sepenuhnya tercapai)b. Pengadaan dukungan prasarana secara terus menerus (sampai sekarang tidak pernah pasti)c. Penyediaan sarana secara sinambung (sampai sekarang tidak pernah pasti)d. Jaminan penerapan hasil dalam program nasional (sampai sekarang jarang sekali terjadi)3. Jaminan bagi kemandirian penelitian yang berjalan atas cerapan (perception) dan anggitan (conception) IPTEK, kepentingan nasional, dan kemaslahatan rakyat umum,bukan atas kepentingan politik dan pandangan ad hoc (sampai sekarang tidak pernah terjamin).4. Inventarisasi dan kompilasi hasil-hasil penelitan dan pengembangan yang telah terkumpul selama ini, yang telah mencakup kurun waktu hampir 30 tahun sejak tahun 1968, untuk membentuk pangkal tolak kajian. Dari sini akan dapat dievaluasi telaah apa yang sudah dan belum dianggap memadai, dan telaah apa yang masih perlu diadakan (sampai sekarang belum pernah dilakukan).5. Insentif kepakaran berupa penyediaan wadah publikasi hasil-hasil tahapan penelitianndan pengembangan secara teratur dan berkualifikasi ilmiah (sekarang belum ada).Pengembangan lahan rawa pasang surut perlu diberi tujuan jelas, baik berjangka dekat maupun berjangka jauh. Tujuan berjangka dekat bersasaran menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah muncul. Untuk ini digunakan rancangan penelitian reaktif.Tujuan berjangka jauh bersasaran menyiapkan cara penyelesaian persoalan-persoalan yang diduga akan muncul kemudian sebagai konsekuensi penggunaan lahan rawa pasang surut selama masa panjang. Untuk ini digunakan rancangan penelitian proaktif.Tujuan akhir pengembangan lahan rawa pasang surut ialah merancang sistem pengelolaan bagi tujuan pertanian yang produktif dan berkelanjutan untuk kelas harkat lahan masing-masing. Produktivitas dan keterlanjutan ditetapkan menurut sudut pandang usahatani, terutama untuk pertanaman pangan dan hortikultura, dan menurut sudut pandang perusahaan, terutama untuk pertanaman industri. Sudut pandang usahatani sekaligus berguna merancang sistem pemukiman masyarakat pedesaan yang mapan.Tujuan jangka dekat melibatkan penelitian:a. Tata air makro (sekesatuan hidrologi) dan mikro (sekesatuan pengusahaan)b. Perubahan sifat fisik, kimia dan biologi substrat organik (gambut) dan substrat mineral dalam kaitannya dengan tata airc. Adaptasi berbagai jenis tanaman pada keadaan lahan dan kelenturan adaptasinya mengikuti perubahan sifat fisik, kimia dan biologi substratTujuan jangka jauh melibatkan penelitian:a. Reaksi fisik, kimia dan biologi yang berlangsung dalam substrat organik dan mineral berkenaan dengan penggunaan lahanb. Arah perubahan keadaan lahan yang disebabkan oleh reaksi fisik, kimia dan biologi, dan akibatnya atas harkat lahanc. Upaya konservasi produktivitas lahanTujuan akhir melibatkan penelitian menetapkan luasan ekonomi optimum lahanusaha, baik berskala usahatani maupun berskala perusahaan, berdasarkan saling nasabah (interrelationships) antara komponen-komponen :a. Kelas harkat lahanb. Macam dan sistem pertanamanc. Sistem pengelolaan lahan, baik makro maupun mikrod. Keterjangkauan lahan berkenaan dengan penyediaan sarana produksi dan pemasaran produksi.
2.5 Penataan Lahan Pasang Surut untuk Usaha TaniPenataan lahan yang dianjurkan selain tergantung dari tipologi lahan dan tipe luapan air juga tergantung dari sistem usaha tani yang akan dikelola, apakah hanya satu jenis tanaman, lebih dari satu jenis tanaman namun memiliki kebutuhan air dalam veolume yang sama atau meiliki kebutuhan air yang berbeda. Pada lahan yang tipe luapan air A pilihannya tidak banyak untuk lahan potensial sulfat masam dan gambut dangkal, dengan karekaterisitik ini pentaan lahan sebaiknya diarahkan sebagai sawah dan tanaman yang diusahakan hanya padi yang dapat ditanam 2 kali. Lahan yang bertipe luapan B-C penataaannya dapat diarahkan sebagai sawah/surjan, surjan bertahap atau tegalan, sedangkan lahan yang bertipe luapan B untuk lahan potensial, sulfat masam, dan gambut dangkal diarahkan sebagai tegalan dan untuk gambut sangat dalam tanaman yang disarankan adalah tanaman perkebunan (Alihamsyah, 2003). Lebih lanjut dikemukakan, penataan lahan sebagai surjan memiliki keuntungan: (1) intensitas penggunaan lahan meningkat; (2) beragam produksi pertanian dapat dihasilkan; (3) resiko kegagalan panen dapat dikurangi, dan (4) stabilitas produksi dan pendapatan usahatani meningkat.Menurut Widjaja Adhi (1995) dan Subagyo dan Widjaja Adhi (1998), lahan pasang surut dapat ditata sebagai sawah, tegalan dan surjan disesuaikan dengan tipe luapan air dan tipologi lahan serta tujuan pemanfaatannya .Secara umum terlihat bahwa lahan bertipe luapan A yang karena selalu terluapi air pasang dianjurkan ditata sebagai sawah, sedangkan lahan bertpe luapan B dapat ditata sebagai sawah atan surjan. Lahan bertipe luapan B/C dan C karena tidak terluapi air pasang tetapi air tanahnya dangkal dapat ditata sebagai sawah tadah hujan atau surjan bertahap dan tegalan, sedangkan untuk yang bertipe luapan D ditata sebagai sawah tadah hujan atau tegalan dan perkebunan. Lahan lahan sulfat masam akan lebih murah dan aman bila ditata sebagai sawah karena dalam keadaan anaerob atau tergenang, pirit tidak berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Bila disawahkan tanaman padi kemungkinan menderita keracunan besi dan/atau sulfida mungkin juga kahat fosfat. Sebaliknya bila ditanami palawija atau dimanfaatkan sebagai tegalan, tanaman menderita keracunan Al dan kemungkinan disertai kahat fosfat.Pemberian bahan amelioran atau bahan pembenah tanah dan pupuk merupakan faktor penting untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan. Amelioran tersebut dapat berupa kapur atau dolomit maupun bahan organik atau abu sekam dan serbuk kayu gergajian. Secara umum pemberian kapur antara 0,5 ton hingga 3,0 ton per hektar sudah cukup memadai (Sudarsono, 1992 dan Trip Alihamsyah 2003).Salah satu penciri yang spesifik dari lahan pasang surut adalah tingginya tingkat keragaman kesuburan lahan sekalipun dalam satu petakan sawah. Untuk itu kisaran dosis pupuk yang dibutuhkan batas antara kebutuhan minimal dengan kebutuhan maksimal cukup besar (Tabel 2) sedangkan pada lahan gambut terdapat dosis tunggal namun pada lahan yang bertipologi lahan ini perlu ditambahkan unsur hara mikro seperti Cu dan Zn, karena umumnya lahan gambut kahat akan unsur hara mikro (Suryadilaga, D.A., dkk.1992 dan Sudarsono 1992). Untuk mendapatkan dosis pupuk yang tepat pada tingkat keragaman yang tinggi merupakan suatu masalah tersendiri dalam mengelola lahan pasang surut untuk pertanian. Di tingkat petani, ini adalah hal yang sangat sulit dilakukannya, untuk itu peran petugas lapang mengarahkan petani dalam penentuan dan pemberian pupuk dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sangat dibutuhkan, di lain sisi petugas lapang itu sendiri perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai.Selain varietas unggul spesifik lahan pasang surut di atas, beberapa varietas padi unggul nasional juga dapat beradaptasi dengan baik di lahan pasang surut dengan hasil yang cukup tinggi. Variertas-vareitas tersebut antara lain adalah Cisanggarung, Cisadane, Cisokan, IR 42, dan IR66 (Sastraatmaja, S. dan Dadan Ridwan Ahmad. 2000).2.6 Pengelolaan Air pada Lahan Pasang SurutSistem tata air yang teruji baik di lahan pasang surut adalah sistem aliran satu arah (one way flow system) dan sistem tabat (dam overflow). Penerapan sistem tata air ini perlu disesuaikan dengan tipologi lahan dan tipe luapan air serta komoditas yang diusahakan.Pada lahan bertipe luapan air A diatur dalam sistem aliran satu arah, sedangkan pada lahan bertipe luapan B diatur dengan sistem aliran satu arah dan tabat, karena air pasang pada musim kemarau sering tidak masuk kepetakan lahan. Sistem tata air pada bertipe luapan C dan D ditujukan untuk menyelamatkan air, karena sumber air hanya berasal dari air hujan. Oleh karena itu, saluran air pada sistem tata air di lahan bertipe luapan C dan D perlu ditabat dengan pintu stoplog untuk menjaga permukaan air tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman serta memungkinkan air hujan tertampung dalam saluran tersebutPenerapan sistem tata air di petakan lahan dimaksudkan selain untuk memperlancar aliran air masuk dan keluar petakan lahan sehingga terjadi pencucian, juga untuk mendukung penerapan berbagai pola tanam.Sistem tata air di petakan lahan berupa pembuatan saluran cacing dan saluran keliling yang ukurannya 25-30 cm X 25-30 cm dan jaraknya antara 3 sampai 12 m, tergantung kepada sifat tanah atau tingkat masalah fisikokimia lahan dan tipe luapan air serta pola tanam yang akan dikembangkan. Untuk pola tanam padi-palawija atau palawija-palawija atau lahan yang masalah fisiko-kimianya berat, jarak antar saluran cacingnya makin pendek, sedangkan untuk pola tanam padi-padi atau lahan tipe luapan air A, jarak antar saluran cacingnya makin panjang. Pencucian lahan dilakukan setiap pasang kecil dan atau pasang besar.Penerapan sistem tata air tersebut selain dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan, juga dapat meningkatkan intensitas penggunaan lahan dengan beragam pola tanam serta pendapatan usahatani. Pada saat awal air pasang, air yang masuk kualitasnya jelek (pH 4,0) pada saat pasang maka harus ditunggu 7-8 jam.
Bab 3Penutup
3.1 KesimpulanLahan rawa pasang surut adalah suatu wilayah rawa yang dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air laut yang secara berkala mengalami luapan air pasang. Berdasarkan pola genangannya (jangkauan air pasang), lahan pasang surut ini dibedakan menjadi 4 tipe luapan:a. Tipe A: Lahan yang selalu terluapi air pasang, baik pasang besar,maupun pasang kecil.b. Tipe B: Lahan yang hanya terluapi oleh pasang besar.c. Tipe C: Lahan yang tidak pernah terluapi walaupun pasang besar. Air pasang mempengaruhinya secara tidak langsung, kedalaman air tanah dari permukaan tanah pada waktu pasang kurang dari 50 Cm.d. Tipe D: Lahan yang tidak terluapi air pasang dan air tanahnya lebih dalam dari 50 Cm tetapi pasang surut air masih terasa tampak pada saluran tersier.Lahan pasang surut mempunyai potensi besar untuk dikembangkan namun dalam pengembangannya mememiliki kekurangan. Kendala dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Pasang Surut Lahan pasang surut biasanya dicirikan oleh kombinasi beberapa kendala seperti (Anwarhan dan Sulaiman, 1985):a. Ph rendahb. Genangan yang dalamc. Akumulasi zatzat beracun ( besi dan aluminium)d. Salinitas tinggi, kekurangan unsur harae. Serangan hama dan penyakitf. Tumbuhnya gulma yang dominan.
3.2 SaranApabila dikelola dengan baik dan benar lahan gambut bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan yang tepat. Dalam pengelolaannya juga harus mementingkan kondisi lingkungan sehingga diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan.
Daftar Pustaka
Kenzhi. Pertanian Berkelanjutan di Tanah Pasang. kenzhi17.blogspot.com (Diakses 30 Maret 2014)
Dakhyar Nazemi, A. Hairani dan Nurita. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut Melalui Pengelolaan Lahan Dan Komodita. Banjarbaru: Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)
Tejoyuwono Notohadiprawiro. Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tujuan Pertanian Apa yang Sudah dan Belum Tercapai
Http://www.indo-peat.net
43Pand an Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan