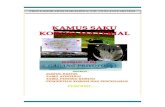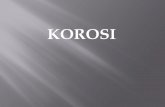Korosi Akbar
-
Upload
sucy-paramita -
Category
Documents
-
view
261 -
download
3
description
Transcript of Korosi Akbar

LAPORAN PRAKTIKUMKIMIA FISIKA
PERCOBAAN XIKOROSI
NAMA : ANDI AKBARNIM : H311 13 309KELOMPOK/REGU : III/5HARI/ TANGGAL PERCOBAAN : SENIN/ 17 MARET 2015ASISTEN : MARLINDA
LABORATORIUM KIMIA FISIKAJURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAMUNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara
suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan
senyawa-senyawa yang tidak dikendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut
perkaratan. Contoh korosi yang umum adalah perkaratan besi.
Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi dan oksigen (udara)
mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia
karat besi adalah Fe2O3.nH2O yaitu suatu zat berwarna coklat sampai merah. Korosi
merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku
sebagai anoda dimana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anoda
mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katoda dimana oksigen
tereduksi.
Ion besi (II) yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion
besi (III) yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi yaitu karat besi.
Proses perkaratan pada besi dapat berlanjut terus sampai seluruh bagian dari besi itu
hancur. Hal ini disebabkan oleh oksida-oksida besi yang terbentuk pada peristiwa awal
korosi akan menjadi katalis (otokatalis) pada peristiwa korosi selanjutnya.
Logam lain seperti Al tidak akan hancur karena korosi seperti pada logam besi
sehingga logam ini bersifat melindungi logam lain dari proses korosi selanjutnya
karena logam Al yang terbentuk melekat pada bagian dalam logam yang mengalami

korosi. Berdasarkan hal di atas, maka dilakukanlah percobaan ini untuk mengetahui
logam mana yang dapat mempercepat atau menghambat terjadinya korosi.
1.2 Maksud dan Tujuan Percobaan
1.2.1 Maksud Percobaan
Maksud dari percobaan ini adalah mengetahui dan mempelajari cara dalam
menentukan logam yang dapat meningkatkan dan menghambat korosi pada besi.
1.2.2 Tujuan Percobaan
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan logam yang dapat
meningkatkan dan menghambat korosi pada besi.
1.3 Prinsip Percobaan
Prinsip dari percobaan ini adalah menentukan logam yang dapat meningkatkan
dan menghambat terjadinya korosi pada besi dengan mengamati proses terjadinya
korosi pada besi dengan membandingkan besi yang tidak dilapisi dengan logam lain
dan besi yang dilapisi dengan logam Sn, Al dan Cu dengan bantuan larutan indikator
PP yang akan menghasilkan warna merah yang menunjukkan tempat terjadinya reaksi
reduksi dan K3Fe(CN)6 yang menghasilkan warna biru yang menunjukkan tempat
terjadinya reaksi oksidasi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Perisriwa korosi logam dapat dijelaskan dengan elektrokimia. Berbagai proses
elektroda memerlukan potensial elektroda yang lebih besar dari perhitungan. Potensail
tambahan itu disebut over voltage. Setengah reaksi yang kedua hanya terjadi pada
bagian yang tidak murni atau bagian yang cacat di permukaan besi. Besi berkarat
karena terbentuk Fe2O3.nH2O. Korosi besi berlangsung bila besi melarut pada bagian
anoda dan ion Fe2+ berdifusi melalui air ke bagian katoda dan mengendap sebagai
Fe(OH)2. Selanjutnya besi (II) hidroksida dioksidasi oleh O2 yang terdapat dalam air
membentuk FeO3.xH2O (Achmad, 1992).
Peringatan termodinamika tentang kemungkinan korosi, diberikan dengan
membandingkan potensial elektroda standar resduksi logam, seperti (Atkins, 1997):
Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s) Eo = -0,44 V
Dengan nilai untuk salah satu setengah reaksi dalam larutan asam berikut ini
(Atkins, 1997):
2H+(aq) + 2e- → 2H2(g) Eo = 0
4H+(aq) + O2(g) + 4e- → 2H2O(l) Eo = 1,23 V
Karena kedua pasangan redoks mempunyai potensial standar lebih posotif daripada Eo
(Fe2/Fe), maka keduanya dapat menyebabkan oksidasi besi. Potensial elektroda
tersebut adalah potensial standar dan nilainya berubah terhadap H medium
(Atkins, 1997):

E(a) = Eo(a) + RTF
ln α(H+) = -0,059 V x pH
E(b) = Eo(b) + + RTF
ln α(H+) = 1,23 V - 0,059 V x pH
Nilai ini menunjukkan, pada pH berapa besi mempunyai kecenderungan
teroksidasi. Akan tetapi, pembahasan termodinamika tentang korosi, hanya
menunjukkan ada tidaknya kecenderungan korosi. Jika terdapat kecenderungan
termodinamika, kita harus mempelajari kinetika proses yang bersengkutan untuk
melihat apakah proses itu cukup cepat (Atkins, 1997).
Laju korosi diukur dengan arus ion logam yang meninggalkan permukaan
logam dalam daerah anoda. Fluks ion ini menghasilkan arus korosi Ikor, yang dapat
diasamkan dengan arus anoda Ia. Karena setiap arus yang keluar dari daerah anoda
harus mencari jalan menuju ke daerah katoda, maka arus katoda Ic juga harus sama
dengan arus korosi (Atkins, 1997).
Terdapat beberapa teknik untuk mencegah korosi. Pelapisan permukaan
dengan suatu lapisan tidak tertembuskan, seperti cat, dapat mencegah masuknya udara
lembab. Sayangnya perlindungan ini gagal dan menimbulkan malapetaka jika cat
menjadi berpori, jika demikian maka oksigen dapat masuk ke dalam logam yang
tersingkap dan korosi terus berlanjut di bawah lapisan cat. Bentuk lain pelapisan
permukaan dilakuikan dengan galvanisasi, yaitu pelapisan benda besi dengan seng.
Karena potensial elektroda seng adalah (-0,76 V), yang lebih negatif dari pasangan
besi, maka korosi seng dipermudah secara termodinamika, sehingga besi itu bertahan
(seng itu bertahan karena dilindungi oleh lapisan oksida terhidrasi). Sebagai
perbandingan pelapisan dengan timah menyebabkan korosi besi yang sangat cepat,

begitu permukannnya tergores dan binya tersingkap. Hal ini disebabkan, pasangan
timah (Eo = -0,14) eV) mengoksidasi pasangan besi (Atkins, 1997).
Beberapa oksida bersifat lambat secara kinetika, dalam arti bahwa oksida itu
melekat pada permukaan logam dan membentuk lapisan tidak tertembuskan dengan
jarak pH yang cukup lebar. Pasifasi atau perlindungan kinetika ini, dapat dipandang
sebagai suatu cara untuk menurunkan arus pertukaran, dengan penutupan permukaan.
Jadi, aluminium lambat di udara, walaupun potensial reduksinya sangat negatif yakni
sebesar -0,66 V (Atkins, 1997).
Ketika reaksi kimia terjadi, ada peningkatan atau penurunan energi potensial.
Dalam kebanyakan kasus, perubahan energi potensial muncul sebagai panas yang
diserap dari lingkungan. Terkadang perubahan energi potensial berubah menjadi
energi listrik (Sienko, 1961).
Salah satu cara mencegah korosi besi adalah proteksi katodik. Misalnya,
batang seng atau magnesium ditanam dekat pipa besi kemudian dihubungkan dengan
pipa tersebut yang akan dilindungi dari korosi. Dalam hal ini pipa besi bertindak
sebagai katoda dan logam seng yang mempunyai potensial elektroda yang lebih
negatif akan mengalami oksidasi, sehingga pipa besi dapat terlindungi dari korosi
(Achmad, 1992).
Metode perlindungan lainnya adalah mengubah potensial objek dengan
memompakan elektron, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan reduksi oksidasi,
tanpa melibatkan oksida logam. Dalam perlindungan katoda, objek dihubungkan
dengan logam yang mempunyai potensial elektroda lebih negatif (seperti magnesium,
-2,36 V). Magnesium bertindak sebagai anoda korban, yang memberikan elektonnya
pada besi, dan dalam proses itu teroksidasi menjadi Mg2+ (Atkins, 1997).

Di antara beberapa metode pengendalian korosi dan pencegahan, penggunaan
inhibitor korosi sangat populer. Inhibitor korosi adalah zat yang bila ditambahkan
dalam konsentrasi rendah untuk berfungsi sebagai media atau mencegah reaksi logam
dengan media. Inhibitor seringkali ditambahkan pada beberapa sistem, yaitu sistem
pendingin, unit kilang, bahan kimia, unit produksi minyak dan gas, dan sebagainya
(Singh, 2012).
Tindakan inhibisi beberapa turunan benzimidazol yaitu
2-(2-furanil)-1H-benzimidazole (FB), 2-(2-piridil) benzimidazole (PB) dan
2(4-tiazolil) benzimidazole (TB), terhadap korosi besi dalam larutan asam nitrat telah
dipelajari dengan menggunakan perhitungan teori fungsi kepadatan (DFT), penurunan
bobot, polarisasi potensiodinamik dan spektroskopi impedansi elektrokimia (EIS).
Hasil yang diperoleh dari penurunan bobot, menunjukkan peningkatan efisiensi
inhibitor dengan meningkatnya konsentrasi inhibitor (Khaled, 2010).
Disamping besi ternyata aluminium juga dapat mengalami korosi dengan
larutan asam sitrat. Metode voltametri siklik digunakan untuk memperoleh
informasi mengenai reversibilitas reaksi, kestabilan produk korosi dan jumlah
tahap reaksi oksidasi maupun reduksi. Pada reaksi korosi aluminium dalam
larutan asam sitrat, reaksi dianggap reversibel jika Epa–Epc ≤ 0,118/n ≈ 0,039
volt. Kestabilan produk korosi diketahui dari rasio antara arus puncak anodik Ipa
dengan arus puncak katodik Ipc. Produk korosi yang terbentuk bersifat stabil jika
nilai Ipa/Ipc ≈ 1. Selain itu, jumlah tahap reaksi diketahui dari jumlah puncak
anodik maupun katodik (Prasetya, 2012).
Laju korosi dapat dihitung dengan metode kehilangan berat (weight loss), yang
biasa dinyatakan dengan mpy (mill per tahun), menggunakan rumus (Murabbi, 2012):

Laju Korosi = (K x W) / (D x A x T ) (2.1)
Semakin meningkatnya konsentrasi larutan NaCl maka semakin tinggi pula
laju korosi terjadi baik pada pengujian polarisasi ataupun imersi. Hasil pengujian
polarisasi didapatkan laju korosi terendah terdapat pada larutan NaCl 3% yaitu
Plat M sebesar 3,0671 mpy, dan yang tertinggi terdapat pada larutan NaCl 5% plat T
sebesar 10,39 mpy, sedangkan pada pengujian imersi didapatkan laju korosi terendah
pada larutan NaCl 3% yaitu plat M sebesar 0,9149 mpy untuk lama pencelupan
240 jam dan yang tertinggi terdapat pada larutan NaCl 5% plat T 3,4161 mpy untuk
lama pencelupan 80 jam (Murabbi, 2012).
Unsur logam yang memiliki karakteristik emas-merah adalah salah satu
konduktor panas dan listrik yang baik, logam yang dimaksud adalah logam tembaga,
logam tersebut sering digunakan dalam kabel listrik, khususnya tembaga yang sangat
murni dan berasal dari tembaga yang telah melalui proses elektrolisis sebagai langkah
pemurnian akhir logamnya, dan ternyata logam tembaga ini merupakan salah satu
logam yang dapat mempercepat terjadinya korosi (Kislaya, 2011).
Korosi logam tetap menjadi masalah besar dunia ilmiah karena mempengaruhi
bidang metalurgi, kimia dan minyak industri. Korosi merupakan fenomena permukaan
yang dikenal sebagai serangan dari logam atau paduan dengan lingkungan mereka
seperti udara, air atau tanah dalam reaksi kimia atau elektrokimia untuk membentuk
senyawa yang lebih stabil (Sultani, 2013).
Sangat jelas bahwa kedua proses yakni oksidasi dan reduksi saling melengkapi
satu sama lain, oksidasi dan reduksi merupakan dasar dalam reaksi kimia. Reaksi yang
melibatkan pertukaran elektron dikenal sebagai redoks (Malone, 1994).

Keadaan oksidasi atau bilangan oksidasi atom dalam suatu senyawa dapat
dimiliki oleh semua atom dalam suatu senyawa tersebut, apabila atom tersebut
terdapat dalam bentuk ion seperti ion monoatomik (Malone, 1994).
Penggantian balok magnesium sekali-kali, jauh lebih murah daripada
mengorbankan kapal, bangunan, atau pipa saluran, sebagai pengorbanan, artinya lebih
baik menggunakan sistem perlindungan dengan Mg daripada tidak melindungi
benda-benda yang telah disebutkan di atas sehingga dengan mudah berkarat dalam
perlindungan katoda arus terpasang, sel luar menyediakan elektron, sehingga
menghilangkan kebutuhan besi untuk mentransfer elektronnya sendiri (Atkins, 1997).
BAB III
METODE PERCOBAAN
3.1 Bahan Percobaan
Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah akuades, indikator
PP (fenolftalein), K3Fe(CN)6 0,1 M, serbuk NaCl, H2SO4 2 M, paku, agar, foil Sn, foil
Cu, foil Al, amplas, lap halus, kertas label, tissue roll dan sabun cair.
3.2 Alat Percobaan
Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah tabung reaksi, gelas piala
250 mL, gelas piala 100 mL, pembakar gas, kaki tiga, kasa, rak tabung, batang
pengaduk, tang, pinset, neraca toledo dan sikat tabung.
3.3 Prosedur Percobaan
Preparasi sampel paku dilakukan bersamaan dengan pembuatan larutan gel.
Pembuatan larutan gel dilakukan dengan akuades dipanaskan sebanyak 50 mL pada

gelas piala 250 mL. Setelah agak panas, maka ditambahkan 1 gram agar yang telah
ditimbang menggunakan neraca digital dan diaduk sampai larut kemudian
ditambahkan 5 gram NaCl lalu diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih,
ditambahkan 2 mL indikator PP dan 1,5 mL K3Fe(CN)6 0,1 M dan diaduk larutan
dengan baik kemudian pemanasan dihentikan. Preparasi sampel paku dimulai dengan
empat buah paku diamplas sampai bersih lalu dimasukkan ke dalam gelas piala
100 mL yang berisi sekitar 25 mL larutan H2SO4 2 M dan didiamkan selama 5 menit.
Setelah itu paku dipindahkan ke dalam gelas piala 100 mL yang berisi akuades yang
telah dipanaskan dan didiamkan selama 5 menit kemudian dikeringkan dengan tissue.
Tiga buah paku masing-masing dilapisi dengan foil Al, foil Sn dan foil Cu dan
direkatkan pada paku dengan menggunakan tang. Keempat paku tersebut kemudian
dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah diberi label. Setelah
pembuatan larutan gel dan preparasi sampel selesai, maka larutan gel tersebut dituang
ke dalam 4 tabung reaksi yang telah terisi paku. Didiamkan dan diamati warna yang
terbentuk disekitar ujung paku, tengah paku dan pangkal paku.
.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pengamatan
Tabel Hasil Pengamatan
Sistem
Keberadaan dan lokasi
warna merah muda
Keberadaan dan lokasi warna biru
Persamaan ion reaksi
Reaksi anoda Reaksi katoda
Fe - Kepala dan ujung paku
Fe(s) → Fe2+(aq)
+ 2e-O2(g) + 2H2O(l) + 4e- →
4OH-(aq)
Fe/Sn - Kepala dan ujung paku
Sn(s) → Sn2+(aq)
+ 2e-O2(g) + 2H2O(l) + 4e- →
4OH-(aq)
Fe/Al - - - -
Fe/Cu - Kepala dan ujung paku
Cu(s) → Cu2+(aq)
+ 2e-O2(g) + 2H2O(l) + 4e- →
4OH-(aq)
4.2 Reaksi
a. Fe
Anoda : 2Fe(s) → 2Fe2+(aq) + 4e-
Katoda : O2(g) + 2H2O(l) + 4e- → 4OH-(aq)

Reaksi : 2Fe(s) + O2(g) + 2H2O(l) → 2Fe2+(aq) + 4OH-
(aq)
Reaksi lengkap : 2Fe(s) + O2(g) + 2H2O(l) → 2Fe(OH)2(aq)
b. Fe/Sn
Anoda : 2Sn(s) → 2Sn2+(aq)
+ 4e-
Katoda : O2(g) + 2H2O(l) + 4e- → 4OH-(aq)
: 2Sn(s) + O2(g) + 2H2O(l) → 2Sn2+ + 4OH-
Reaksi lengkap : 2Sn(s) + O2(g) + 2H2O(l) → 2Sn(OH)2(aq)
c. Fe/Al
Tidak terjadi reaksi redoks.
d. Fe/Cu
Anoda : 2Cu(s) → 2Cu2+(aq) + 4e-
Katoda : O2(g) + 2H2O(l) + 4e- → 4OH-(aq)
Reaksi : 2Cu(s) + O2(g) + 2H2O(l) → 2Cu2+(aq) + 4OH-
(aq)
Reaksi lengkap : 2Cu(s) + O2(g) + 2H2O(l) → 2Cu(OH)2(aq)
e. Indikator PP dengan OH-
+ O2 + 2H2O + 4e
4.3 Pembahasan
Pada percobaan ini, paku-paku yang akan digunakan harus diamplas terlebih
dahulu sampai bersih sehingga karat dan kotoran-kotoran pada paku dapat
+ 4OH-→

dihilangkan. Setelah itu, paku-paku tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang
berisi asam sulfat dan didiamkan selama 5 menit. Hal ini dilakukan untuk
mengasamkan paku agar pori-porinya terbuka. Selanjutnya paku dimasukkan dalam
gelas kimia yang berisi akuades panas. Pemanasan akuades dilakukan agar terbentuk
uap air yang akan masuk ke dalam pori-pori paku sehingga dapat mempercepat reaksi.
Kemudian paku dikeringkan dengan tissue untuk membersihkan paku dari sisa-sisa
asam dan akuades yang mungkin masih melekat pada paku tersebut. Setelah itu, pada
paku dililitkan beberapa logam lain yaitu Al, Sn dan Cu yang berfungsi sebagai bahan
pelapis besi yang nantinya akan diamati apakah logam tersebut dapat menghambat
atau mempercepat terjadinya korosi.
Pada percobaan ini juga digunakan larutan gel yaitu larutan agar sebagai
medium indikator untuk memperjelas warna yang terjadi akibat adanya reaksi oksidasi
dan reduksi pada besi sehingga dapat diamati dengan jelas. Pada pembuatan larutan
gel ini, agar dilarutkan dalam air yang dipanaskan dan ditambahkan NaCl yang
berfungsi untuk menggaramkan atau sebagai jembatan garam yaitu tempat terjadi
peristiwa transfer elektron. Larutan agar ditambahkan dengan indikator PP dan
K3Fe(CN)6. Penambahan indikator PP berfungsi sebagai penunjuk tempat terjadinya
peristiwa reduksi dengan memberikan warna merah oleh adanya ion OH- yang berasal
dari reduksi yang melibatkan O2 dan H2O yang terjadi pada katoda. K3Fe(CN)6
digunakan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa oksidasi pada anoda dengan
memberikan warna biru oleh adanya KFe[Fe(CN)6] dari reaksi antara K3Fe(CN)6
dengan ion Fe2+. Campuran larutan kemudian dipanaskan sambil diaduk untuk
mencegah pemadatan dari agar.

Setelah proses pembuatan larutan gel dan preparasi sampel paku, maka
selanjutnya yaitu paku-paku tersebut dimasukkan ke dalam 4 buah tabung reaksi yang
berbeda. Kemudian ke dalam masing-masing tabung reaksi dituangkan larutan agar
dalam keadaan hangat yang berfungsi untuk menunjukkan tempat terjadinya reaksi
reduksi dan oksidasi pada peristiwa korosi yang terjadi pada paku.
Pada paku yang tidak terlapisi logam terdapat warna biru pada kepala dan
ujung paku dan tidak terdapat warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa paku yang
mengandung besi dengan mudah mengalami korosi dengan teroksidasinya logam besi
membentuk ion besi (II) oleh uap air disekitarnya. Pada paku yang dilapisi foil Al
tidak terdapat warna merah maupun warna biru disepanjang paku. Hal ini
menunjukkan bahwa logam Al dapat melindungi besi dari proses terjadinya korosi.
Pada paku yang dilapisi foil Sn terdapat warna biru pada bagian kepala dan ujung
paku. Hal ini menunjukkan bahwa logam Sn dapat mempercepat terjadinya korosi.
Pada paku yang dilapisi foil Cu terdapat warna biru pada ujung dan kepala paku. Hal
ini menunjukkan bahwa logam Cu dapat mempercepat terjadinya korosi pada besi.
Berdasarkan teori, logam Al dapat menghambat terjadinya korosi pada besi
sedangkan logam Sn dan Cu dapat mempercepat terjadinya korosi jika ditinjau dari
Eo-nya. Logam yang dapat melindungi besi dari korosi adalah logam yang Eo-nya lebih
kecil daripada Eo besi. Hal ini terbukti karena Eo logam Al lebih kecil dari pada Eo besi
sedangkan Eo Cu dan Sn lebih besar dari Eo besi. Al memiliki Eo yang paling rendah
yaitu (-1,66), Sn memiliki Eo (-0,136), Fe memiliki Eo (-0,440) dan Cu memiliki Eo
(+0,337). Berdasarkan harga Eo, logam Cu dan Sn lebih mudah tereduksi sehingga
tidak dapat melindungi paku besi dari korosi dan logam Al dapat melindungi paku dari
korosi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari percobaan ini adalah logam yang dapat menghambat korosi
pada besi adalah logam Al dan logam yang dapat mempercepat korosi adalah logam
Sn dan Cu.
5.2 Saran
5.2.1 Saran Untuk Praktikum
Saran untuk praktikum adalah sebaiknya digunakan lebih banyak logam lagi
untuk melapisi besi sehingga dapat dibandingkan hasilnya pada berbagai logam.

Kebersihan dalam laboratorium tetap dijaga agar praktikan dapat lebih nyaman
melakukan percobaan.
5.2.2 Saran Untuk Laboratorium
Saran untuk laboratorium adalah agar bahan-bahan yang akan digunakan lebih
diperbanyak dan juga fasilitas laboratorium yang sudah rusak diperbaiki.
5.2.3 Saran Untuk Asisten
Untuk asisten cukup di pertahankan cara membimbingnya karena sudah cukup
baik, namun tambahan sedikit, mungkin lebih diperjelas lagi penjelasan mengenai cara
hubungan praktikum dengan teori, sehingga praktikan bisa langsung membandingkan
hasil percobaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad, H., 1992, Elektro Kimia dan Kinetika Kimia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Al-Sultani, K. F. dan Shaymaa A. A., 2013, Improvement Corrosion Resistance of Low Carbon Steel by Using Natural Corrosion Inhibitor, International Journal of Advanced Research, 1 (4); 239-243.
Atkins, P. W., 1997, Kimia Fisika, Edisi keempat, Diterjemahkan oleh Kartohadiprodjo, Erlanga, Jakarta.
Khaled, K. F., 2010, Studies of Iron Corrosion Inhibition Using Chemical, Electrochemical and Computer Simulation Techniques, Elsevier, 1 (55); 6523-6532.
Kislaya, S., 2011, Basic Chemistry, Tilak Wasan, New Delhi.
Malone, L. J.,1994, Basic Concepts of Chemistry, Edisi keempat John Wiley & Sons, New York.

Murabbi, A. L. dan Sulistijono, 2012, Pengaruh Konsentrasi Larutan Garam terhadap Laju Korosi dengan Metode Polarisasi dan Uji Kekerasan serta Uji Tekuk Pada Plat Bodi Mobil, Jurnal Teknik Pomits, 1 (1); 1-5.
Sienko, M. dan Robert, P., 1961, Chemistry, Edisi kedua, McGraw-Hill Book Company, Tokyo.
Singh, A., Eno E. E., dan Quraishi, M. A., 2012, Corrosion Inhibition of Carbon Steel in HCl Solution by Some Plant Extracts, International Journal of Corrosion, 1 (10); 1-20.
Prasetya, A. Y. A. dan Isdiriayani, N., 2012, Korosi Aluminium dalam Larutan Asam Sitrat, Jurnal Teknik Kimia Inonesia, 11 (2); 116-123.
LEMBAR PENGESAHAN

Makassar, 18 Maret 2015 Asisten, Praktikan,
MARLINDA ANDI AKBARNIM: H311 11 259 NIM: H311 13 309