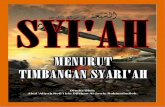KOHERENSI TERJEMAHAN AL-QURAN:...
Transcript of KOHERENSI TERJEMAHAN AL-QURAN:...

i
KOHERENSI TERJEMAHAN AL-QURAN:
Analisis Struktural Terjemahan al-Quran Depag RI Edisi Tahun 2002
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab
Oleh:
TARDI
NIM: 06.2.00.1.13.08.0052
Pembimbing:
Prof. Dr. H. Chatibul Umam, MA.
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2008

ii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Tesis ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar strata 2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia dicabut gelar
kesarjanaannya.
Ciputat, ..... Agustus 2008 Tardi

iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tesis dengan judul “KOHERENSI TERJEMAHAN AL-QURAN” : Analisis
Struktural Terjemahan al-Quran Depag RI Edisi 2002 yang ditulis oleh
N a m a : Tardi
NIM : 06.2.00.1.13.08.0052
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta telah diperbaiki sesuai dengan permintaan, saran dan masukan pembimbing
dan disetujui untuk dibawa ke sidang ujian tesis.
Jakarta, ...... Agustus 2008
Pembimbing,
Prof. Dr. H. Chatibul Umam, MA.

iv
PENGESAHAN
Tesis saudara Tardi (NIM. 06.2.00.1.13.08.0052) yang berjudul
KOHERENSI TERJEMAHAN AL-QURAN: Analisis Struktural Terjemahan
al-Quran Depag RI Edisi Tahun 2002 telah diujikan pada hari Kamis, 28
Agustus 2008 dan telah diperbaiki sesuai saran serta rekomendasi dari Tim
Penguji Tesis.
Jakarta, 04 September 2008
TIM PENGUJI:
1. Dr. Udjang Tholib, MA. (..................................)
Ketua/ Merangkap Penguji Tgl.
2. Prof. Dr. Chotibul Umam, MA. (...................................)
Pembimbing/ Merangkap Penguji Tgl.
3. Dr. Faizah Ali Sybromalisi (...................................)
Penguji Tgl.
4. Dr. Yusuf Rahman, MA. (...................................)
Penguji Tgl.

v
ABSTRAK
Penelitian ini membuktikan bahwa terjemahan al-Quran Departemen Agama
Republik Indonesia edisi 2002 menggunakan teori-teori terjemahan secara umum yang ditawarkan oleh Newmark. Teori tersebut dikembangkan melalui prosedur penerjemahan yang tidak hanya mengikuti satu langkah, tetapi tiga langkah, yakni analisis, transfer dan restrukturisasi. Ketiga langkah ini tidak dapat memecahkan kesulitan penerjemahan dalam tataran kata, frasa atau kalimat. Oleh karena itu, teknik atau strategi penerjemahan al-Quran tetap diperlukan. Penelitian ini menggambarkan strategi terjemahan al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, yang kemudian dibagi ke dalam dua bagian, yakni strategi struktural dan strategi semantis.
Strategi struktural digunakan untuk mencari padanan struktural antara bahasa al-Quran (Bsu) dan bahasa Indonesia (Bsa). Jika tidak ditemukan padanannya, maka pengalihan fungsi (transposisi) harus dilakukan. Sedangkan strategi semantis dilakukan atas dasar pertimbangan makna. Karena semua makna Bsu tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya ke dalam Bsa. Kedua strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat pernyataan Ahsin Sakho Muhammad, salah seorang anggota tim penerjemah al-Quran, bahwa kesulitan yang dapat dirasakan langsung oleh para anggota tim penerjemah al-Quran adalah mencari padanannya yang tepat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam tesis ini padanan kedua bahasa itu dianalisis menurut tingkat kebahasaaannya.
Selain itu, penelitian ini memperkuat pernyataan Suryawinata bahwa terjemahan al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia bersifat semantis. Kecenderungan terjemahan semantis dapat diketahui dari objektifitasnya, yakni tidak terikat dengan Bsu maupun Bsa secara penuh. Struktur Bsu, makna dan gaya bahasanya tetap dipertahankan dalam terjemahan Bsa, sehingga terjemahan al-Quran masih tetap terasa sedikit kaku tetapi tidak sekaku terjemahan harfiah.
Objek penelitian ini adalah terjemahan al-Quran yang berusaha menjelaskan materi melalui media yang berbeda, yakni bahasa al-Quran dengan bahasa Indonesia. Secara ideal, struktur bahasa al-Quran dan bahasa Indonesia merupakan struktur yang harus dipersamakan secara fungsional. Sehubungan kedua bahasa itu berbeda, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontrastif. Analisis ini mengandung dua langkah, yakni mendeskripsikan Bsu dan Bsa, dan membandingkan antara keduanya. Perbedaan antara keduanya merupakan variabel yang diperhatikan dalam penerjemahan.

vi
ABSTRACT
This research proves that Qur'an translation of Depag RI, Edition 2002 uses
common translation theory which was introduced by Newmark. That theory is developed through translation procedure that does not follow only one stage, but three stages, those are analyzing, transferring, and restructurisation. The three stages can not completely solve the translation difficulties in words, phrases, or sentences level. Therefore, techniques or strategies of Qur’an translation are still required. This research describes Qur’an translation strategy that is conducted by Depag RI, which is divided into two, namely structural strategy and semantical strategy.
Structural strategy is used to look for structural equivalent between the language of Qur' an (the source language) and Indonesian language (the target language). If its equivalent is undiscovered, the function shifting (transposition) will be performed. Whereas semantical strategy is performed based on meanings consideration. Since all meaning of the source language can not be translated utterly into the target language. Both strategies are meant to strengthen Ahsin Sakho Muhammad's statement, one of Qur'an translators of Depag RI, that the main difficulty felt by members of Qur’an translator team is how to get the equivalence of Qur’an language in Indonesian. So, the equivalence of the two languages is analyzed in this thesis in accordance of their terminological level.
This research also strengthens Suryawinata's statement that Qur’an translation of Depag RI gets semantical character. The preference of using semantical translation can be known from the objectivity, which is not tied up extremely either on source language or target language. The structure of source language, its meaning and style are maintained in target language translation. So that the Qur’an translation still looks textual but not as textual as literal translation.
The object of this research is Qur’an translation which tries to explain the material through different medium, those are the language of Qur' an and Indonesian language. Ideally, the structure of language of Qur’an should be functionally likened to Indonesian language. As both languages are different, the analysis technique used is contrastive analysis. This technique contains two steps, namely describing source language and target language, and comparing between both languages. The differences of two languages in translation are observed carefully.

vii
�� ا����
�� �ف إ�� إ���ت ا������ ب�ن ��� �2002)�'ن ا�&�درة "�� اه ا ا���� � ��وا��7 �65 ب�� وزارة ا�123ن ا������ ا0ن�ون�-�� �-���م +��)� ا��� �� ب�"����
�� @7 أآ=� ��>1ر و. ا�:�� ا��7 ا��6ح��ن�1�رك���A B �نDه C ا�>��)� B ,Dدة ا���آ��Aإ Dن� وه C ا��1انD ا�=�G� F . ه7 �نD ���7 و �نD ن)7 و
�-�>�M أن ��L آL ا��GK3ت ا�:�ئ)� أ�م A��� ا��� �� "1اء آ�ن5 @7 -�1ى � ا @�"���ام ا�>��)� أو ا0"��ا����� اPخ�ي ��)7 . ا�K�� أم ا���آ�D أم ا����وه ا ا���� �:>��� ص1رة ش�� 0"��ا����� �� �� . دوره� ا���م @7 �� �� ا�)�'ن
أو���� إ"��ا����� : �)�'ن ا��7 �65 ب�� وزارة ا�123ن ا������ وا��7 ���7 @7 نB�A1ا���Fد �و إ"��ا���� �آ����� .
�م ��-�Bا���آ��� B7 ا���ادف ب�A &1ل�� �ا���آ��� �ا0"��ا���� : Dآ����ف(آ�D ا�U� ا0ن�ون�-�� و��) �U� اPصL(�U� ا�)�'ن �وإذا � X�BK ه��ك ). �U� ا�
Bا���آ��� Bادف ب��� ,Z� �وأ� ا0"��ا����� ا����F� 1��@ .�L ا�1\�]� أ� F ب�ا�Aة ص�� ا��:�7 7A 7���@ .P BK�� F LصPا �U� 7@ 1د ن آL ا��:�7 ا��1
�ف�� رأي أح-B "��ء �)&� ���B ا0"��ا����@�"���ام آG. ن)Z إ�U� 7� ا�������� , �� �� أA[�ء ���� ��� A[1 ���� ا��� �� ا�)�ئL ب�ن ا��K3� ا��7 �1ا
L @7 ا�U� ا0ن�ون�-��ا�K7 ا���ادف ا�A ذ�^ . �)�'ن ه7 ا��&1ل L وB أ1�- D-7 حA 7 ه ا ا����@ B��Uا� Bرس ا���ادف ب�������� .
��6� �Z "1ر��و����� ب�ن �� �� ا�)�'ن ا��7 و@7 �نD 'خ� أن ه ا ا���� �`����Fد �� �65 ب�� وزارة ا�123ن ا������ ا0ن�ون�-�� �� . �� وه ا ا��1ع B ا���
�Uأو ب LصPا �Uو��)� ب ��م اb��Fام ا��bاA 7�:� ���:�ف B خGل �ه���ف�1 @7 وأ� @7 ا��� �� ا����F� c@ن ��آ�U� D� اPصL وأ"1ب�� ��)7 آ�� ه.ا�
�ف� �� ح�@�� �)�'ن�U� ا��� ���م ا���ون� و آ�نA 7دي إ�`� �� . B��� 7ا�)�'ن ا�� �� �ر ه ا ا���� ه1 ��&[�1ن ا�)�'ن ب��U ا�:�ب�� و
7 �� �� ا�)�'ن ب��U� ا0ن�ون�-���:� . �Uآ �ون�-��و��خ ه ا ا���� ا�U� ا0ن��آ�U� D� اPصL (أص��� ا���آ�D وا��� �� ا��= 7���A d@7 . ا��� �� �)�'ن
�ف�@�����L ا��-���م @7 , وب�� أن ا���آ���B ���]�ن @7 +��:����. و\�]��) و�U� ا�

viii
ه�� وصU� e� اPصL : وه ا ا���� L��A L�3��B. ه ا ا���� ه1 ا����L ا��)�ب7����ف وص]� دX� �(�6 ا��)�رن� ب���B و��Aص� ا�]�ق ب�B ا�B��U أ�. و�U� ا� � F ب
�� �اZ��A @7 ا��� .
PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) UIN syarif
Hidayatullah Jakarta yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan
Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
b be ب
t te ت
ts te dan es ث
j je ج
h h dengan garis di bawah ح
kh ka dan ha خ
d de د
dz de dan zet ذ
r er ر
z zet ز
s es س
sy es dan ye ش
s es dengan garis di bawah ص

ix
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan
d de dengan garis di bawah ض
t te dengan garis di bawah ط
z zet dengan garis di bawah ظ
koma terbalik di atas hadap kanan ‘ ع
gh ge dan ha غ
f ef ف
q ki ق
k ka ك
l el ل
m em م
n en ن
w we و
h ha هـ
F la el dan a
Apostrop ´ ء
y ye ي
2. Vokal
a. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
a fathah
i kasrah
u dammah
b. Vokal Rangkap

x
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
ai a dan i ى...
au a dan u و...
c. Vokal Panjang
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
â a dengan topi di atas ــــ�
î i dengan topi di atas ــــ�
û u dengan topi di atas ــــ

xi
3. Ta Marbûtah
Jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut
dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah
tersebut diikuti oleh kata sifat (na´t). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut
diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi /t/.
Contoh:
No Kata Arab Alih Aksara
1 �(��+ tarîqah
2 ��G"0ا �: al-jâmi’ah al-islâmiyyah ا���
wahdat al-wujud وح�ة ا�1 1د 3
4. Syaddah (Tasydîd)
Syaddah dalam alihaksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan
menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal itu tidak
berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah.
Contoh:
nazzala : نbل rabbanâ : ربـ�� al-darûrah : ا�[�ورة
5. Kata Sandang
Kata sandang “ا�ـ ” dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti dengan huruf
syamsiyyah maupun diikuti dengan huruf qamariyyah.
Contoh:
w�3ا� : al-syams X(ا� : al-qalam

xii
DAFTAR SINGKATAN
Bsa = Bahasa Sasaran
Bsu = Bahasa Sumber
F = Frasa
Fa = Fâ’il
FAdj = Frasa Adjektival
Fi = Fi’l
FN = Frasa Nominal
FV = Frasa Verbal
I = Ism
K = Klausa
Ket. = Keterangan
KS = Kata Sarana
M = Murakkab
N = Nomina
O = Objek
P = Predikat
Pel. = Pelengkap
R = Rabit
S = Subjek
V = Verba

xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perbandingan Fungsi Sintaksis Bsu dan Bsa hal. 60
Tabel 2 Perbandingan Kategori Bsu dan Bsa hal. 62
Tabel 3 Pronomina Persona Bsu dan Bsa hal. 102
Tabel 4 Pronomina Penunjuk Bsu hal. 105
Tabel 5 Pronomina Penghubung hal. 108
Tabel 6 Numeralia Bsu dan Bsa hal. 111
Tabel 7 Kata Sarana Bsu dan Bsa hal. 122

xiv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat
menyelesaikan tesis dengan judul KOHERENSI TERJEMAHAN AL-QURAN:
Analisis Struktural Terjemahan al-Quran Depag RI Edisi Tahun 2002. Karya
ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada
Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan
berbagai pihak. Karena itu, dengan penuh ketulusan hati penulis ingin menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA. sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Prof. Dr. H. Chatibul Umam, MA, selaku pembimbing tesis yang senantiasa
memberikan waktu kepada penulis dengan tulus untuk berkonsultasi, memberikan
bimbingan serta arahan hingga karya ilmiah ini selesai.
4. Departemen Agama, yang telah memberikan beasiswa kepada penulis selama 2
(dua) tahun untuk menyelesaikan program magister di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
5. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Sarip (alm.) dan Ibunda Kadisem
serta Ayahanda mertua, H. Muhyiddin (alm.) dan ibunda Hj. Muhdiyah yang telah
mengorbankan segalanya dan mendoakan untuk kebaikan hidup penulis di dunia
dan akhirat nanti.
6. Istri tercinta ’Aini Sa’adah yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis
dan sabar dalam kesendirian mengasuh dan mendidik ananda tersayang Anisah
Novie Musyarrofah, Abdullah Umar dan Wardah Shobahiyyah.

xv
7. Sahabat-sahabat penulis di SPs UIN Jakarta yang tinggal bersama penulis selama
dua tahun di Asrama Putra dan telah memberikan banyak bantuan dan dukungan
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
Penulis menyadari, dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis, tesis
ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran dari pihak manapun sangat
diharapkan.
Akhirnya, dengan senantiasa berharap rida dan rahmat Allah SWT, penulis
mempersembahkan karya ini kepada mereka yang berkeinginan kuat untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Semoga karya ini mempunyai nilai
manfaat. Amin.
Ciputat, 12 Agustus 2008
Penulis,
Tardi

xvi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i SURAT PERNYATAAN ........................................................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ iii PENGESAHAN ............................................................................................... iv ABSTRAK.................................................................................................... iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN......................................... vii DAFTAR SINGKATAN ............................................................................. xi DAFTAR TABEL ........................................................................................... xii KATA PENGANTAR ................................................................................. xiii DAFTAR ISI .............................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Permasalahan ......................................................................... 7
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan ....................................... 8
D. Tujuan Penelitian .................................................................. 11
E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian ............................................ 11
F. Metodologi Penelitian ........................................................... 12
G. Sistematika Penulisan ............................................................ 13
BAB II PARADIGMA TERJEMAHAN AL-QURAN ......................... 15
A. Hakikat Terjemahan .............................................................. 15
B. Ragam dan Prinsip Terjemahan ............................................. 20
C. Prosedur Terjemahan ............................................................. 36
D. Kualitas terjemahan dan Kelembagaannya ............................. 41
BAB III STRATEGI TERJEMAHAN AL-QURAN DEPAG RI .......... 47
A. Fungsi Sintaksis Bsu dan Bsa ................................................. 48
B. Strategi Struktural ................................................................. 63

xvii
C. Strategi Semantis .................................................................. 79
BAB IV PADANAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL SERTA
MAKNANYA DALAM TERJEMAHAN AL-QURAN ............ 95
A. Padanan Gramatikal ............................................................... 97
B. Padanan Leksikal ................................................................... 139
C. Jenis Makna dalam Terjemahan al-Quran .............................. 150
BAB V PENUTUP .................................................................................. 157
A. Kesimpulan ............................................................................ 157
B. Saran ..................................................................................... 158
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 160

xviii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Terjemahan, baik lisan maupun tulisan, sebagai bagian dari ilmu linguistik
relatif belum lama. Bahkan sampai sekarang mengenai masalah terjemahan belum
ada nama acuan yang diterima secara umum. Setiap pemerhati linguistik
terjemahan mempunyai istilah sendiri, seperti: “Ilmu Terjemahan”, “Teori
Terjemahan”, “Pengantar Teori Terjemahan” dan lain-lain.1 Menurut Wolfram
Wills dalam bukunya The Science of Translation, penerjemahan adalah suatu
proses transfer yang bertujuan untuk menyampaikan teks tertulis BSu (bahasa
sumber) ke dalam BSa (bahasa sasaran)2 yang optimal padan, dan memerlukan
pemahaman sintaksis, semantik, dan pragmatik, serta proses analisis terhadap
BSu.3
Islam memandang bahwa terjemahan menempati posisi strategis untuk
menjalankan misi-misi Islam dan keilmuan,4 di mana sasaran utamanya adalah
orang-orang non Arab yang tidak memahami teks-teks Arab sebagai bahasa
sumber ajaran-ajaran Islam, seperti al-Quran dan Hadits. Teks-teks tersebut harus
dipahami mereka sebagai bahasa yang komunikatif.
1 Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemahan (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), h. vii. 2 Istilah “bahasa sumber” merupakan terjemahan dari source language (SL), yakni bahasa yang
diterjemahkan. Sedangkan “bahasa sasaran” merupakan terjemahan dari target language (TL), yakni bahasa terjemahan. Istilah dalam terjemahan teks, bahasa sumber identik dengan “teks sumber” (Tsu), sedangkan bahasa sasaran identik dengan “teks sasaran” (Tsa). Kedua istilah tersebut juga merupakan terjemahan dari source text (ST) dan target text (TT).
3 Wolfram Wills, The Science of Translation (Stuttgart: Gunter Narr Verlag Tubingen, 1982), h. 3. Sebagaimana dikutip oleh Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translation: Bahasan Teori dan Penuntun Praktis Menerjemahkan (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 15-16.
4 Pada masa Bani Umayyah hanya dua orang khalifah yang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu, yaitu Khâlid bin Yazîd dan Khalifah Umar bin ‘Abd al-‘Azîz. Sedangkan Bani ‘Abbasiyah hampir sebagian besar memiliki kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sebut saja khalifah al-Mansûr, Hârûn al-Rasyîd, al-Ma’mûn, al-Mutawakkil. Lihat, Rasyîd al-Jamîli, Harakah al-Tarjamah fi al-Masyriq fi al-Qarnaini al-Tsâlits wa al-Râbi’ al-Hijri (Baghdad: Dâr al-Syu’ûn al-Tsaqâfiyah al-‘Âmmah, 1986), h. 76.

xix
Sebagai sebuah teks, al-Quran tidak pernah kering, apalagi habis. Teks al-
Quran bisa diterjemahkan dan ditafsirkan secara kaya, tergantung konteksnya,
baik konteks linguistik5 maupun non-linguistiknya.6 Dengan demikian,
persinggungan dan persentuhan antara penerjemah atau penafsir dengan al-Quran
merupakan pergulatan yang dinamis.
Bagi orang-orang asing, terjemahan al-Quran ke dalam bahasanya
mempunyai peran besar sebagai pengantar untuk mendekatkan pemahaman
pesan-pesan al-Quran. Dalam kaitannya dengan penerjemahan al-Quran, menurut
al-Zarqâni, penerjemahan al-Quran selama ini hendaknya mempunyai enam peran
penting di antaranya adalah memberi informasi yang jelas terhadap orang-orang
non Arab tentang substansi ajaran-ajaran Islam, dan menjalankan kewajiban
sebagai seorang muslim untuk menyampaikan lafal dan makna al-Quran.7
Manshûr Muhammad Hasb al-Nabi mengemukakan bahwa penerjemahan
dan penafsiran al-Quran yang akurat dan jelas adalah satu dakwah kepada non
muslim atau non Arab dengan cara yang obyektif dan ilmiah untuk memastikan
kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan untuk
menentang tuduhan-tuduhan dan pengingkaran mereka. Dengan terjemahan itu,
kiranya mampu membangkitkan kesadaran mereka dari keingkarannya.8
5 Mengingat objek kajian linguistik adalah bahasa, merupakan fenomena yang menyatu dengan
kehidupan manusia, maka objek kajiannya meliputi linguistik umum dan khusus (dilihat dari sisi berlakunya bahasa di suatu tempat), linguistik sinkronik dan diakronik (ditinjau dari sisi masa berlakunya), linguistik mikro dan makro (ditinjau dari segi faktor internal dan eksternal), linguistik teoritis dan terapan (berdasarkan tujuannya), linguistik tradisional, struktural, transformasional, generatif semantik, relasional dan linguistik sistemik (berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penelitian bahasa). Lihat, Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta Karya, cet. II, 2003), h. 14 - 17
6 Persoalan non linguistik adalah segala sesuatu yang menyertai teks di luar aspek kebahasaan teks, seperti hal-hal yang mencakup ideologi, budaya, sosial, politik, sejarah.
7 Disimpulkan dari Muhammad ‘Abd al-‘Adhîm al-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm al-Qurân (Mesir: ‘Isa al-Bab al-Halbi, t.t.) jilid II, h. 137-139.
8 Manshur Muhammad memberikan satu contoh ayat 33 surah Ibrahîm, pada kata Bدائ�� yang diartikannya dengan bekerja terus tanpa henti (menggambarkan aktivitas matahari dan bulan). Lihat, Manshûr Muhammad Hasb al-Nabiy, al-Qurân wa ‘Ilm al-Hadîts (Mesir: al-Hayyah al-Mishriyah al-‘Ammah li al-Kuttâb, 1991), h. 235-236.

xx
Al-Quran sebagai teks, satu-satunya pintu untuk memasukinya adalah
dengan menggunakan perangkat kebahasaan, mulai dari bahasa sebagai ilmu yang
sudah mapan dengan segala cabangnya (Fonologi, Morfologi, Sintaksis dan
Semantik), hingga temuan-temuan mutakhir dalam bidang ini, seperti pragmatika
bahasa, wacana, dan semua ilmu yang berbicara tentang hubungan bahasa dengan
konteks sosial-budaya. Semua ilmu ini harus didayagunakan untuk menguak teks.
Meski demikian, tidak hanya perangkat kebahasaan yang mampu untuk
mengeksplorasi makna al-Quran tersebut, namun masih banyak pendekatan yang
masih mungkin dilakukan untuk hal itu. Perangkat bahasa dipergunakan di sini
dalam kaitannya dengan fakta bahwa al-Quran adalah teks verbal.
Terjemahan al-Quran bagi orang yang asing, khususnya masyarakat muslim
Indonesia - sebagaimana yang dipahami selama ini - merupakan wacana yang
harus dibaca, dipahami dan diaplikasikan, sebagaimana orang yang paham dengan
bahasa al-Quran. Terjemahan al-Quran yang tidak tepat, sepadan dan adekuat
akan menimbulkan kontradiksi dan persepsi yang salah. Misalnya terjemahan al-
Quran yang dihasilkan oleh H.B. Jassin, seorang kritikus sastra pada akhir 1970-
an.9 Terjemahannya ini kemudian mendapatkan kecaman dan kritik serta
tanggapan dari berbagai komunitas masyarakat muslim di Indonesia, termasuk
dari Departemen Agama.10 Sebenarnya dalam hal penerjemahan, “betul-salah”
nya terjemahan hanya bersangkutan dengan aspek kebahasaan murni. Ini sifatnya
mutlak. Dan faktor bahasa itulah yang selalu membayangi proses penerjemahan,
karena antara Bsu dan Bsa berbeda. Jadi, istilah kesalahan dalam terjemahan
harus dibedakan antara “betul-salah” (correctness) dengan “baik-buruk” (good or
bad translation).11
9 Dia mendapatkan inspirasinya dari Dr. Yûsuf ‘Ali, seorang penerjemah al-Quran ke dalam
bahasa Inggris berasal dari India pada tahun 1930-an. Terjemahan H.B. Jassin ini bergaya puitis dengan kalimat-kalimat yang indah. Lihat, Phil M. Nur Kholis Setiawan, al-Quran Kitab Sastra Terbesar (Yogyakarta: elSAQ Press, 2005), h. 264.
10 Lihat, H. Oemar Bakry, Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B. Jassin tentang al-Quran al-Karim Bacaan Mulia (Jakarta: Mutiara, 1979).
11 Benny Hoedoro Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan (Bandung: Pustaka Jaya, 2006), h. 27.

xxi
Diakui bahwa terjemahan satu kalimat, tidaklah sepenuhnya sama dengan
bahasa sasaran yang dimaksud, karena adanya beberapa perbedaan antara kedua
bahasa tersebut. Lebih-lebih bahasa Arab mempunyai kosa kata yang sangat kaya.
Di sisi lain diakui pula, bahwa menerjemahkan al-Quran tidak akan pernah
berhasil,12 karena itu banyak ulama yang enggan menggunakan istilah terjemahan
al-Quran, tetapi “terjemahan makna-makna al-Quran”13 Namun demikian, istilah
terjemahan al-Quran di Indonesia lebih banyak digunakan dalam pengertian
“terjemahan makna-makna al-Quran”. Dan inilah yang membedakan terjemahan
kitab suci al-Quran dengan kitab Injil.
Menurut Suryawinata, praktek terjemahan al-Quran agaknya menggunakan
prinsip terjemahan semantis.14 Oleh karena itu, pada umumnya terjemahan
semantis terasa lebih kaku dengan struktur yang lebih kompleks karena ia
menggambarkan dan mempertahankan proses berpikir dan idiolek penulis aslinya.
Makna-makna al-Quran sering kali menguji ketelitian penerjemah, sehingga
penerjemah menerjemahkan makna baru di tingkat kata, frase dan kalimat yang
boleh jadi tidak dikehendaki al-Quran. Oleh karena itu, teks al-Quran –
sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Islam – adalah wacana otoritatif
(authoritative), sehingga penerjemahannya harus sedekat dan setepat mungkin
dengan teks aslinya baik gramatika, kosakata, konsep, makna, amanat maupun
stilistiknya.
Kehadiran Al-quran dan terjemahnya terbitan Departemen Agama RI Edisi
Tahun 2002 yang diakui telah mengalami beberapa penyempurnaan,15 sangatlah
12 Sambutan Menteri Agama, al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI (Surabaya:
Mekar Surabaya, 2004), h. iii. Lihat juga, M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi,( Jakarta: Lentera Hati, 2006) h. 323.
13 M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, h. 323. 14 Terjemahan semantis berusaha mempertahankan struktur semantis dan sintaktik serta makna
kontekstual dari teks BSu. Sehingga elemen budaya BSu harus tetap menjadi elemen budaya BSu meskipun ia hadir dalam teks terjemahan BSa. Lihat, Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translation (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h. 50.
15 Aspek-aspek penyempurnaan itu meliputi aspek bahasa, konsistensi, substansi dan transliterasi. Lihat, Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. vi.

xxii
penting bagi masyarakat Indonesia, karena al-Quran dengan menggunakan bahasa
aslinya tidak mudah dimengerti oleh kebanyakan umat Islam Indonesia.
Meskipun banyak bermunculan al-Quran berikut terjemahannya yang diterbitkan
oleh beberapa penerbit,16 namun tetap dalam pengawasan dan penelitian serta
pengesahan dari Lajnah Pentashih al-Quran.
Sebagai karya terjemahan teks suci al-Quran, al-Quran dan Terjemahnya
terbitan Departemen Agama perlu diuji dari segi kualitas hasil terjemahannya.
Menurut Suryawinata,17 di antara cara-cara yang dilakukan untuk menguji hasil
terjemahannya itu adalah (1) membandingkan teks Bsu dengan Teks Bsa, (2)
terjemahan balik, (3) prosedur Cloze, (4) pengujian pemahaman dan kesan oleh
pembaca teks Bsa, dan (5) membandingkan pemahaman dan kesan yang diperoleh
oleh pembaca teks Bsu dan pembaca teks Bsa.
Dalam banyak hal, penelitian dengan objek hasil terjemahan identik dengan
kritik terjemahan. Menurut Newmark,18 sebuah kritik terjemahan yang
komprehensif harus mencakup lima hal, yaitu (1) analisis singkat teks Bsu, (2)
interpretasi penerjemah, (3) perbandingan yang selektif bagian teks Bsu dan teks
Bsa, (4) evaluasi terjemahan, dan (5) peran karya tersebut dalam budaya atau
disiplin ilmu di dalam konteks Bsa.
Terjemahan al-Quran memiliki tingkat keterpahaman yang tinggi,
memenuhi seluruh makna dan maksud nas sumber dan bersifat otonom. Otonom
yang dimaksud adalah terjemahan itu dapat menggantikan nas sumbernya.19
16 Di antara penerbit yang menerbitkan al-Quran dan Terjemahnya serta telah mendapatkan Tanda
Tashih adalah C.V. Asy-Syifa, Semarang; C.V. Karya Utama, Surabaya; C.V. Mekar, Surabaya; C.V. Karindo, Jakarta; C.V. Ramsa Putra, Surabaya; C.V. Diponegoro, Bandung; C.V. Pustaka Amani, Jakarta; P.T. Al-Huda Pelita Insan Ind, Jakarta; P.T. Syamil Cipta Media, Bandung. Sedangkan untuk al-Quran dan Terjemahnya serta Transliterasinya adalah penerbit C.V. Sinar Baru Bandung. Lihat, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, Kegiatan Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, artikel diakses pada tanggal 17 April 2008 dari http/www.Depag.
17 Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translation, h. 176. 18 Peter Newmark, Approaches to Translation (Oxford: Pergamon Press, 1981), h. 186. 19 Muhammad ‘Abd al-‘Adhîm al-Zarqâni, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm al-Qurân, jilid II, h. 113.

xxiii
Singkatnya, kualifikasi itu ditetapkan supaya terjemahan yang dihasilkan
berkualitas.
Menilai kualitas terjemahan berarti menilai tingkat keterpahamannya.
Menurut Nida dan Taber, tingkat keterpahaman itu berkaitan sekali dengan ada
atau tidaknya dua hal, yaitu (a) ungkapan yang dapat menimbulkan salah paham
dan (b) ungkapan yang membuat pembaca sangat sulit memahami amanat yang
dikandungnya karena faktor kosa kata dan gramatika.20
Faktor kosa kata dan gramatika seringkali menjadi objek kritik terjemahan.
Moh. Mansyur, dalam studi kritisnya terhadap terjemahan al-Quran Departemen
Agama (1998) – sebagaimana penulis kemukakan pada bab penelitian terdahulu
yang relevan - menyatakan bahwa penyimpangan terjemahan dapat terjadi karena
pemilihan kata (diksi) yang kurang tepat dalam terjemahan gramatika BSu. Ismail
Lubis (2001) juga menyatakan bahwa penyimpangan terjemahan dapat
diakibatkan oleh ketidaksesuaiannya dengan gramatika Bsa. Ketidaksesuaiannya
itu antara lain: frasa preposisional daripada banyak digunakan di luar kalimat
perbandingan; dua kata syarat sekaligus digunakan untuk menyatakan satu
kalimat pengandaian, seperti kalau sekiranya, jika seandainya, jika sekiranya;
kata saling digunakan untuk menyatakan kooperatif (musyârakah) dengan
pengulangan kata verbal yang serupa, seperti saling dahulu mendahului dan
sebagainya.21
Namun dalam beberapa hal yang berkaitan dengan terjemahan al-Quran
Depag RI sendiri, misalnya ragam dan prinsip-prinsip terjemahan, strategi
terjemahan, padanan leksikal dan gramatikal serta kata-kata dan makna
terjemahan al-Quran, penelitiannya belum pernah dilakukan. Padahal menurut
Hoed,22 ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam terjemahan, yaitu
20 Nida, E.A. dan Taber C. The Theory and Practise of Translation (Leiden: The United Bible
Societies, 1982), h. 2. 21 Ismail Lubis, Falsifikasi Terjemahan al-Quran Depag RI Edisi 1990 (Yogyakarta: Tiara
Wacana Yogya, 2001), h. 215. 22 Benny Hoedoro Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 40.

xxiv
(a) perbedaan antara Bsu dan Bsa, (b) faktor konteks, dan (c) prosedur
terjemahan.
Faktor pertama, perbedaan antara Bsu dan Bsa jelas ada, sebab tidak ada dua
bahasa yang sama, karena masing-masing bahasa memiliki karakteristik masing-
masing, lebih-lebih kedua bahasa tersebut berbeda rumpun bahasanya. Kedua,
faktor konteks atau sebagai proses penerjemahan yang dapat membantu
memecahkan masalah, misalnya dalam konteks cerita suatu kegiatan dapat
dianggap “lampau”, meskipun tidak diungkapkan pemakaian kala lampau pada
bahasa terjemahannya. Ketiga, menentukan prosedur terjemahan atau teknik yang
cocok untuk memecahkan masalah perbedaan sistem dan struktur kedua bahasa
itu.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan
memang laik. Adapun penelitian yang dimaksudkan penulis adalah analisis
struktur wacana terjemahan al-Quran Departemen Agama Edisi Baru 2002.
Analisis struktural,23 dalam kajian penulis terfokus pada dua hal pokok, yaitu
analisis bentuk dan analisis makna. Dua model analisis itu meliputi satuan kata,
rangkaian kata (frasa), klausa dan kalimat. Sedangkan terjemahan al-Quran
dibangun oleh komponen-komponen yang terjalin di dalam suatu organisasi
kewacanaan. Menurut Mulyana, organisasi inilah yang disebut sebagai struktur
wacana. Beberapa aspek pengutuh wacana dapat dikelompokkan ke dalam dua
unsur, yaitu (a) unsur kohesi, seperti aspek leksikal dan gramatikal, dan (b) unsur
koherensi, seperti aspek makna (semantis).24
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
23 Istilah struktural pertama kali muncul dari pandangan seorang linguis struktural berkebangsaan
Swiss, Ferdinand de Saussure. Ia melahirkan aliran struktural dalam linguistik yang berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Lihat Jhon Lyons, Semantics (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), h. 231.
24 Mulyana, Kajian Wacana (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 25.

xxv
Adapun masalah yang mungkin muncul dari latar belakang di atas
adalah:
a. Ragam terjemahan al-Quran
b. Prinsip-prinsip terjemahan al-Quran
c. Strategi terjemahan al-Quran
d. Padanan Gramatikal dan Leksikal dalam terjemahan al-Quran
e. Kata-kata al-Quran dan terjemahannya
f. Makna dan terjemahan al-Quran
2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah penulis identifikasi, maka penulis
membatasinya sebagai berikut:
a. Strategi Terjemahan al-Quran.
b. Padanan Gramatikal dan Leksikal dalam terjemahan al-Quran.
c. Makna dalam terjemahan al-Quran
Adapun alasan penulis membatasi tiga masalah di atas, karena dalam
terjemahan al-Quran dituntut adanya tuntunan teknis untuk menerjemahkan
kata, frasa, klausa atau kalimat. Dan tuntunan ini disebut dengan teknik
terjemahan atau strategi terjemahan. Dalam literatur terjemahan, strategi ini
dikenal dengan prosedur terjemahan (translation procedures).
Sedangkan pembatasan masalah kedua, padanan gramatikal dan
leksikal, karena bahasa al-Quran sebagai Bsu dan bahasa Indonesia sebagai
Bsa memiliki karakteristik masing-masing, tentunya akan memiliki persamaan
dan perbedaan. Meminjam asumsi analisis kontrastif dalam bidang pengajaran
bahasa asing,25 bila struktur Bsu dan Bsa sama, maka terjemahan akan
cenderung lebih mudah. Akan tetapi bila Bsu dan Bsa berbeda, maka
25 Analisis kontrastif adalah komparasi sistem-sistem linguistik dua bahasa, misalnya sistem bunyi
atau sistem gramatikal. Analisis ini dikembangkan dan dipraktekan pada tahun 1950-an dan 1960-an, sebagai suatu aplikasi linguistik struktural pada pengajaran bahasa. Lihat, Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analsis Kontrastif Bahasa (Bandung: Angkasa, 1992), h. 4.

xxvi
penerjemah akan mengalami kesulitan dalam menemukan terjemahan yang
sesuai.
Kemudian pembatasan masalah ketiga, makna dan terjemahan, karena
keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Newmark,
menerjemahkan berarti memindahkan makna dari serangkaian atau satu unit
linguistik dari satu bahasa ke bahasa lain.26 Yang perlu dicermati bahwa
dalam sebuah wacana terdapat lebih dari satu macam makna.
3. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang penulis
rumuskan di sini adalah sebagai berikut:
a. Strategi apa yang dilakukan dalam terjemahan al-Quran Departemen
Agama RI.
b. Bagaimana padanan gramatikal dan leksikal terjemahan al-Quran dalam
perbandingan antara Bsu dan Bsa.
c. Jenis makna apa saja yang terkandung dalam terjemahan al-Quran.
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Berdasarkan penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan terjemahan
al-Quran Departemen Agama yang merupakan objek dari penelitian ini, penulis
temukan tiga buah penelitian, yaitu:
Moh. Mansyur (1998) dalam studi kritisnya terhadap terjemahan al-Quran
Depag RI, disimpulkan bahwa terjemahan al-Quran tersebut dianggap
menyimpang dari teori penerjemahan al-Quran yang semestinya. Di antara
penyimpangan itu antara lain karena penerjemahan yang dilakukan berdasarkan
pengalaman pribadi bukan dilandasi oleh teori linguistik dan tidak ditunjang oleh
pengetahuan lain yang membawa kepada kebenaran terjemahan.27 Sisi lainnya
26 Newmark, About Translation (Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1991) h. 27. 27 Moh. Mansyur, Studi Kritis Terhadap al-Quran dan Terjemahnya Depag RI (Disertasi S2
Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998), h. 91.

xxvii
mengenai diksi, diksi yang dimaksudkan adalah bukan saja dipergunakan untuk
mengatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau
gagasan, tetapi juga meliputi persoalan konteks, gaya bahasa dan ungkapan.
Mansyur sempat mengkritisi pemilihan kata (diksi) kata depan yang digunakan
dalam menerjemahkan beberapa huruf al-Jarr. Namun yang ia kritisi hanya pada
beberapa kasus dan beberapa huruf al-Jarr, misalnya B dalam beberapa pola.
Kemudian Ismail Lubis (2001) dalam studi penelitiannya juga mengkritisi
terjemahan al-Quran Depag RI Edisi tahun 1990. Hasil penelitiannya tidak jauh
berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Moh. Mansyur. Hanya
penekanannya pada sebab-sebab terjadinya kesalahan terjemahan dari aspek
ketidaksesuaiannya dengan gramatika Bahasa Indonesia, terutama dalam
pemilihan kata (diksi) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
M. Quraish Shihab dalam karyanya Menabur Pesan Ilahi (2006),
menemukan dalam al-Quran dan Terjemahnya terbitan Departemen Agama
beberapa makna yang dihilangkan dan muncul makna baru yang boleh jadi tidak
dikehendaki al-Quran. Dan menurutnya, hal-hal itu diakibatkan oleh
ketidaktelitian penerjemahan al-Quran. Di antaranya adalah bentuk muanntas
“baqarah” diterjemahkan dengan “sapi betina”, bentuk kata jamak (plural)
mawâzînuhu pada fa ammâ man tsaqulat mawâzînuhu diterjemahkan dengan
“timbangannya” dalam bentuk tunggal, juga wujûhakum pada fawallû wujûhakum
diterjemahkan dengan “wajahmu” dalam bentuk tunggal. Dalam setiap doa yang
ada dalam al-Quran, misalnya rabbanâ diterjemahkan seluruhnya dengan
menggunakan kata “ya” atau “wahai”.28
Ketiga penelitian di atas berkaitan sekali dengan terjemahan al-Quran
Depag RI. Perbedaan itu terletak pada edisi terjemahannya, yakni Moh. Mansyur
mengkritisi terjemahan al-Quran Depag RI edisi tahun 1970, sedangkan Ismail
Lubis terhadap edisi tahun 1990, demikian pula M. Quraish Shihab. Namun,
28 M. Quraish Shihab, Manabur Pesan Ilahi, h. 324-326.

xxviii
peneliti pertama menjadikan terjemahan al-Quran itu sebagai objek penelitiannya
dari sisi gramatika bahasa yang kemudian menyimpulkan bahwa terjemahan al-
Quran Depag RI edisi 1970 itu belum mengikuti teori terjemahan. Peneliti kedua
tidak jauh berbeda dengan peneliti pertama, hanya aspek yang ditekankan dalam
kritikannya adalah gramatika Bsa. Sedangkan peneliti terakhir menjadikan objek
penelitiannya dari sisi padanan makna Bsu ke dalam Bsa.
Sehubungan dengan hal itu, penulis hendak mengkritisi pendapat peneliti
pertama yang menyatakan terjemahan al-Quran Depag RI itu belum mengikuti
teori terjemahan. Teori yang dimaksudkan adalah semacam alat yang dipakai
untuk memudahkan proses penerjemahan dan harus diakui bahwa teori
penerjemahan memang diperlukan keberadaannya dalam penerjemahan teks
apapun.
Terjemahan al-Quran seperti terjemahan pada umumnya memiliki tujuan
dan jenis terjemahan yang diinginkan. Para pakar terjemahan sependapat bahwa
“betul-salah” (correctness) tergantung untuk siapa terjemahan itu dibuat.29
Misalnya terjemahan teks hukum dibuat untuk orang awam seharusnya dengan
menggunakan ungkapan atau istilah yang mudah dipahami mereka. Akan tetapi,
jika terjemahan itu dibuat untuk institusi pengadilan dan hukum, maka istilah atau
ungkapan yang digunakan adalah istilah-istilah yang baku. Dengan demikian,
pelaksanaan terjemahan harus mempelajari siapa pengguna terjemahan tersebut
(audience design). Atas dasar itu, kemudian hal yang dilakukan oleh penerjemah
adalah menentukan metode atau cara terjemahannya.
Prinsip dasar terjemahan - sebagaimana dijelaskan oleh Nida dan Taber –
hendaknya tidak mengikuti satu langkah saja, namun harus ditempuh dengan “tiga
langkah penerjemahan”, yaitu analisis Bsu, transfer atau mengalihbasakan dalam
pikiran dan restrukturisasi (menerjemahkan) .30 Namun, dengan mengikuti tiga
29 Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 66. 30 Nida dan Taber, The Theory and Practice of Translation (Leiden: The United Bible Societies,
1982), h. 82

xxix
langkah tersebut belum dapat memecahkan masalah terjemahan, terutama dalam
menanggulangi kesulitan terjemahan dalam tataran kata, , frase dan kalimat. Cara
penanggulangan ini dikenal dengan teknik atau strategi terjemahan.
Ada banyak teknik atau strategi terjemahan yang ditawarkan, misalnya
transposisi, modulasi, terjemahan deskriptif, penjelasan tambahan, catatan kaki,
terjemahan fonologis, terjemahan resmi/ baku, tidak diberikan padanan dan
padanan budaya.
Dalam bahasa tulisan, teks merupakan objek dari terjemahan. Karena itu,
terjemahannya dituntut bersifat terbuka. Keterbukaan ini yang menjadikan para
pengguna (audience) atau pembaca mudah memahami terjemahan sebagaimana
memahami teks sumbernya. Betul-salahnya terjemahan tergantung dari sisi aspek
kebahasaan murni. Maka banyak yang beranggapan bahwa terjemahan adalah
sekedar pengalihbahasaan. Lebih tepat dikatakan bahwa terjemahan adalah
pengalihan pesan (message) dari Tsu ke dalam Tsa. Berkaitan dengan pernyataan
tersebut, sebagaimana dikutip oleh Hanafi, Nida memberikan batasan
terjemahan yang berarti menciptakan padanan yang paling dekat dalam bahasa
penerima terhadap pesan bahasa sumber, pertama dalam hal makna dan kedua
pada gaya bahasanya.31 Padanan yang dimaksud di sini bisa berupa padanan
gramatikal, leksikal dan makna. Dengan demikian, padanan dan makna atau pesan
yang terkandung merupakan referensi dasar bagi terjemahan Tsu ke dalam Tsa.
Sehubungan dengan hal itu, maka penulis hendak memperkuat pernyataan
Suryawinata bahwa terjemahan al-Quran Depag RI bersifat semantis. Bsu
hendaknya dicarikan padanan makna atau pesannya di dalam Bsa. Apabila tidak
ditemukan padanannya, maka strategi semantis perlu dilakukan untuk
mendapatkan makna atau pesan yang diperoleh sebagaimana Bsu-nya.
31 Nurachman Hanafi, Teori dan Seni Menejemahkan, Flores: Nusa Indah, 1986, h. 25. Batasan ini
sama seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Burdah bahwa terjemah adalah usaha memindahkan pesan dari teks berbahasa Arab (teks sumber) dengan padanannya ke dalam bahasa Indonesia (bahasa sasaran). Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), h. 9.

xxx
Beberapa hal yang berkaitan dengan terjemahan al-Quran terbitan
Departemen Agama RI, terutama baik yang menyangkut strategi terjemahan,
padanan dan makna terjemahannya, menurut penulis belum dianalisis secara
mendalam oleh beberapa peneliti sebelumnya.
D. Tujuan Penelitian
Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk sejauh mana keutuhan
wacana terjemahan al-Quran Depag RI. Sedangkan secara khusus, penelitian ini
ditujukan untuk:
1. Memetakan strategi terjemahan al-Quran Depag RI edisi 2002.
2. Mencari unsur-unsur linguistik bahasa al-Quran yang dapat dipadankan
dengan bahasa Indonesia.
3. Membandingkan padanan formal dan makna terjemahan al-Quran Depag RI
dengan terjemahan edisi sebelumnya dan terjemahan lainnya.
E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna bagi pemikiran ilmiah
dalam memberikan gambaran dan memperluas pemahaman terhadap bahasa al-
Quran yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang lebih
penting adalah untuk:
1. Mendorong terhadap penelitian ayat-ayat al-Quran dan atau terjemahannya
yang lebih mendalam ditinjau dari aspek kebahasaannya.
2. Memberikan nilai tambah bagi pengajaran bahasa Arab dan aktivitas
penerjemahan dalam rangka mengatasi problem linguistik yang timbul
sebagai akibat perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia.
3. Memudahkan bagi para pelajar untuk memahami teks-teks berbahasa Arab
dan memilih padanan maknanya ke dalam bahasa Indonesia terutama yang
berkaitan dengan teks-teks keagamaan.
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

xxxi
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji dan
menganalisis data secara objektif sesuai dengan fakta nyata yang ditemukan,
kemudian memaparkannya secara deskriptif. Sementara model penelitiannya
adalah: (a) observasi terhadap data, (b) penyediaan data, (c) reduksi dan
pemaknaan secara deskriptif.
2. Data dan Sumber Data
Data ini berupa terjemahan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan
unsur-unsur teks terjemahan yang diawali dari tingkat kata, klausa, frase dan
kalimat. Sedangkan Sumber datanya adalah terjemahan al-Quran Depag RI
edisi tahun 2002 pada surah al-Baqarah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui metode baca, yaitu membaca secara cermat
terjemahan ayat-ayat al-Quran. Hasil baca dipindahkan ke dalam kartu data.
Selanjutnya data yang sudah ditranskripsi tersebut diklasifikasikan menurut
ketiga permasalahan, yaitu strategi terjemahannya, padanan gramatikal dan
leksikal serta makna dan terjemahannya.
4. Uji Keabsahan Data
Data diuji keabsahannya dengan validitas semantik-kontekstual, yaitu
mengklasifikasikan, memaknai dan mengkaji data dengan mempertimbangkan
konteks kalimat secara struktural. Reliabilitas data dilakukan dengan cara
pembacaan dan pengkajian berulang-ulang oleh peneliti agar memperoleh
keajegan yang memadai.
5. Analisis Data
Sehubungan dengan data yang hendak dianalisis adalah teks terjemahan
al-Quran, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis wacana untuk
mengungkap pertalian bentuk (kohesi) dan maknanya (koherensi). Menurut
Muhadjir, terjemah atau translation merupakan upaya mengemukakan materi
atau substansi yang sama melalui media yang berbeda; media tersebut

xxxii
mungkin bisa berupa bahasa yang satu ke bahasa yang lain, dari verbal ke
gambar dan sebagainya.32
Setiap wacana dalam tingkat kebahasaan memiliki struktur, dan struktur
yang dimaksud di sini adalah struktur mikro.33 Data seperti kata, kalimat dan
teks terjemahan semuanya dianalisis berdasarkan metode kualitatif.34
Beberapa prinsip analisis yang digunakan antara lain penghayatan dan
penafsiran oleh peneliti sendiri sebagai key instrument.
G. Sistematika Penulisan
Untuk menggambarkan isi tesis ini secara garis besar, penulis bagi ke
dalam lima bab, yaitu:
Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari subbab, yaitu latar belakang
masalah, permasalahan, perumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan,
tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian dan metodologi penelitian serta
sistematika penulisan.
Bab II merupakan kajian dasar untuk menganalisis permasalahan yang
telah dirumuskan sebelumnya dengan tema paradigma terjemahan yang terdiri
dari subbab hakikat terjemahan, ragam dan prinsip terjemahan, prosedur
terjemahan, kualitas terjemahan dan kelembagaannya.
32 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake, 1988), h. 138. 33 Menurut Teun A. Van Dijk, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto, wacana memiliki tiga
struktur, yaitu: (1) struktur makro, yaitu makna global yang dapat diamati lewat topik dari suatu tema; (2) superstruktur, yaitu kerangka struktur teks, bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh; dan (3) struktur mikro, yaitu makna yang diperoleh melalui analisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, frasa yang dipakai dan sebagainya. Lihat Eriyanto, Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 54.
34 Metode ini dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Lihat, Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2006 ), h. 81

xxxiii
Bab III merupakan bab analisis tentang strategi terjemahan al-Quran
Depag RI yang terdiri dari tiga subbab yaitu fungsi sintaksi Bsu dan Bsa, strategi
struktural, strategi semantis.
Bab IV juga masih dalam bab analisis yang berisi tentang padanan
gramatikal dan maknanya, padanan leksikal dan maknanya dan jenis makna
dalam terjemahan al-Quran.
Bab V sebagai penutup tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

xxxiv
BAB II
PARADIGMA TERJEMAHAN AL-QURAN
Kehidupan manusia tidak akan ada artinya bila tidak ada bahasa. Baik itu
bahasa yang dipergunakan oleh manusia yang mampu berbicara dan menulis atau
bahasa isyarat bagi yang tidak mampu berbahasa lisan. Melalui bahasa pula segala
informasi atau pesan dapat dipahami dan dilakukan. Bahasa yang besar hanya
dimiliki oleh bangsa yang mampu menyentuh segala aspek kehidupan dan
berhubungan dengan perasaan serta segala aktivitasnya.
Bahasa yang satu dengan lainnya tentunya tidak memiliki persamaan secara
keseluruhan. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab tidak ada persamaan
dari segi strukturnya, apalagi budayanya. Bahasa Arab yang dikenal sebagai bahasa
agama Islam yang dimaksudkan untuk mengenal dan memahami teks-teks keagamaan
telah lama diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Keterpahaman terhadap Islam pada awalnya dimulai dari keterpahaman terhadap
bahasa kitab sucinya, yakni al-Quran. Namun, bagi komunitas masyarakat yang
belum memahami bahasa itu secara optimal harus melewati satu cara yaitu membaca
terjemahan bahasanya. Dan dari bahasa itulah mereka akan memahami bahasa al-
Quran itu sendiri dan mengamalkan isi kandungannya.
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa bahasa
merupakan media terjemahan untuk mengungkapkan materi atau substansi yang
sama. Dalam bab ini, penulis perlu menjelaskan terjemahan Al-Quran yang
berkembang menurut masa dan ragam serta prosedur yang digunakan. Karena itu hal-
hal yang perlu dikemukakan dalam bab ini adalah hakikat terjemahan, ragam dan
prinsip terjemahan, prosedur terjemahan, kualitas terjemahan dan kelembagaannya.
A. Hakikat Terjemahan
Terjemahan dapat didefinisikan secara beragam oleh beberapa pakar atau
pemberi definisi. Pemberian definisi yang berbeda itu mungkin didasarkan pada
pengalihan bentuk-bentuk dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain, seperti yang

xxxv
ditulis oleh Larson dalam bukunya Meaning-based Translation: A Guide to
Cross-language equivalence:
“Translation is basically a change of form. When we speak of the form of a language, we are referring to the actual words, phrases, clauses, sentences, paragraphs, etc., which are spoken or written. ... In translation the form of the source language is replaced by the form of the receptor (target)
language.”35
Menurut definisi di atas, bentuk bahasa baik tertulis maupun lisan dalam
terjemahan dapat mengacu pada kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf.
Mungkin juga didasarkan pada penekanan terjemahan sebagai pengalihan
arti dan pesan dari suatu bahasa sumber (Bsu) ke dalam bahasa sasaran (Bsa),
seperti yang dinyatakan oleh Newmark sebagai berikut:
“Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message and/ or statement in one language by the same message and/ or statement in
another language.”36
Berdasarkan definisi yang dinyatakan Newmark, maka ada dua hal yang
diperbincangkan, yaitu: Pertama, Newmark memandang yang berkaitan dengan
terjemahan adalah teks tertulis. Kemungkinan yang muncul dari hal pertama ini
adalah dimaksudkan untuk membedakan terjemahan (translation) dengan
terjemahan lisan (interpretation).37 Kedua, Newmark tidak menggunakan istilah
equivalen atau padanan, tetapi ia lebih senang menggunakan istilah yang sama
dalam bahasa lain.
35 Mildred L. Larson (selanjutnya disebut Larson), Meaning-based Translation: A Guide to
Cross-language Equivalence (London: University Press of America, 1984), h. 3. 36 Peter Newmark (selanjutnya disebut Newmark), Aproaches to Translation (Oxford:
Pergamon Press, 1981), h. 7 37 Dua istilah translation dan interpretation mengandung perbedaan dalam bahasa Inggris.
Perbedaan itu terletak pada media yang digunakan, yaitu terjemahan menggunakan teks tulis sedangkan interpretasi menggunakan wacana lisan. Juga interperetasi tidak menggunakan sarana lainnya seperti kamus atau bahan referensi lain secara langsung serta tempatnya pun telah ditentukan, misalnya di ruang seminar atau konferensi. Lihat, Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translation: Bahasan Teori dan Penuntun Praktis Menerjemahkan (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 25-26.

xxxvi
Dengan demikian, dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
terjemahan adalah pengalihan yang sepadan atau sesuai dari suatu bahasa ke
bahasa lainnya baik berupa bentuk-bentuk bahasa maupun pesan-pesan yang
terkandung. Terjemahan yang diartikan pengalihan bentuk-bentuk akan
mempengaruhi penerjemah menjadi terikat, sedangkan terjemahan yang diartikan
pengalihan makna atau pesan-pesan yang terkandung dalam Bsu (the source
language) ke dalam Bsa (the target language) akan mendorong penerjemah lebih
bebas untuk menerjemahkan teks-teks Bsu. Oleh karena itu, al-Qattân
mengelompokkan terjemahan secara khusus ke dalam dua kategori, yaitu al-
38.a’nawiyyahM-alatau afsîriyyah T-arjamah alT-al dan arfiyyahH-arjamah alT
‘Abd , n tadiâQatt-h alSementara dua kategori terjemahan yang dikelompokkan ole
-pulkan bahwa terjemahan adalah mengalihkan pikiran dan idemenyim alîmH-al
ide serta kata-kata Bsu ke dalam Bsa tanpa mengubah isi teks Bsu-nya.39
Dari beberapa pendapat tentang terjemahan di atas, dapat diambil benang
merah bahwa terjemahan baik lisan maupun tulisan merupakan satu proses
kegiatan manusia di bidang bahasa, yaitu analisis teks Bsu, kemudian pengalihan
atau penggantian teks Bsu ke dalam Bsa. Menurut Larson, analisis teks Bsu
meliputi kata-kata, struktur gramatikal, situasi komunikasi dalam teks Bsu dan
konteks budayanya. Kemudian diungkapkan kembali dengan menggunakan
kosakata dan struktur gramatikal Bsa yang baik dan cocok dengan konteks budaya
Bsa.40 Di sinilah, kata merupakan salah satu dari enam hierarki bahasa dalam
38 Al-Tarjamah al-Harfiyyah ialah mengalihkan lafal-lafal Bsu ke dalam Bsa yang sesuai
menurut konstruksinya dan urutannya dalam kalimat itu. Al-Tarjamah al-Tafsîriyyah atau al-Ma’nawiyyah ialah mengalihkan makna atau pesan teks Bsu ke dalam Bsa tanpa terikat oleh urutan kata dalam teks itu atau konstruksinya. Lihat Mannâ’ al-Qattân, Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qurân (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), h. 307.
39 ‘Abd al-Halîm al-Sayyid Munsiy dan ‘Abd Allâh ‘Abd al-Râziq Ibrâhîm, al-Tarjamah: Usuluhâ wa Mabâdi`uhâ wa Tatbîquhâ (Riyad: Dâr al-Murîkh, t.t.), h. 11.
40 Larson, Meaning-based Translation: A Guide to Cross-language Equivalence, h. 4.

xxxvii
satuan terjemahan (unit of translation), yaitu fonem, morfem, kata, frasa, kalimat
dan teks.41
Setiap satuan bahasa dalam setiap bahasa mengandung dua level, yaitu level
pengungkapan (level of expression) dan level isi (level of content). Berbagai
bahasa mempunyai satuan-satuan yang berlainan tingkat pengungkapannya, tapi
sama dalam tingkat isinya. Misalnya kalimat bahasa Arab; Hâdzâ kitâb
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; Ini buku, yang berbeda tingkat
pengungkapannya (bentuknya), tapi sama pada tingkat isinya (maknanya).
Dengan demikian, terjemahan pada hakikatnya proses penggantian teks Bsu
dengan teks Bsa tanpa mengubah tingkat isi teks Bsu. Namun, perlu ditekankan di
sini bahwa pengertian “tingkat isi” harus dipahami secara maksimal dan luas,
yakni tidak hanya menyangkut arti dasar (material meaning) yang terkandung
dalam teks Bsu, tapi juga norma-norma Bsu, seperti makna leksikal, makna
gramatikal dan nuansa stilistis. Karena itu, Said melengkapi proses penggantian
menurut Larson di atas melalui skema berikut:42
Bsu Bsa
Pemahaman makna pentransferan makna
Makna
41 Ilmu linguistik kontemporer mencatat hierarki bahasa hingga lima tingkat, yaitu: tingkat
fonem, morfem, kata, rangkaian kata, kalimat dan teks. Lihat, Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemahan (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), h. 33.
42 Mashadi Said, Socio-Cultural Problems in the Translation of Indonesian Poems into English: A Case Study on “Foreign Shore” (Tesis Magister IKIP Malang, 1994), h. 20.
Teks Bsu
Leksikon (kata)
Struktur gramatikal
Konteks situasi
Konteks Budaya
Pengungkapan makna
Leksikon (kata)
Struktur gramatikal
Konteks budaya
Konteks situasi
Teks Bsa
Analisis makna

xxxviii
Kepatuhan pada norma-norma tersebut dalam terjemahan merupakan
kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh penerjemah, meskipun dia bebas
memilih sarana yang satu atau sarana lainnya dalam melakukan kegiatan
terjemahan asal saja tetap mempertahankan semua informasi yang terkandung
dalam teks Bsa. Misalnya, pengungkapan informasi dalam teks Bsu yang
menggunakan sarana gramatikal, tapi diungkapkan dalam teks Bsa dengan
bantuan sarana leksikal, seperti : dzahaba Khâlid ilâ al-madrasah; dipakai sarana
gramatikal, yaitu kala perfektif yang tidak ditemukan dalam Bsa, sehingga
terjemahannya menggunakan bantuan sarana leksikal: Khalid telah pergi ke
sekolah.
Penggunaan sarana leksikal maupun gramatikal dalam satu bahasa berbeda
dengan penggunaan sarana leksikal atau gramatikal dalam bahasa lain. Apalagi
bahasa al-Quran yang berbeda struktur dan sistemnya dengan bahasa Indonesia.43
Menurut Verhar – sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Chaer – bahwa struktur
dan sistem dalam bahasa lebih tepat digunakan, karena keduanya dapat diterapkan
dalam semua tataran bahasa yang meliputi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis,
juga dalam tataran leksikon.44
Karena itulah, sarana-sarana bahasa merupakan problematika dalam
terjemahan, seperti sarana leksikal, misalnya kata bahasa Arab: nomina ruz bisa
mempunyai aneka makna, yaitu: padi, gabah, beras atau juga nasi; verba ra`a
juga mempunyai medan makna semantis yang menyatakan persepsi, yaitu:
melihat, berpendapat, mengerti, menduga, bermimpi dan meminta nasehat.
Sedangkan sarana gramatikal, bahasa Arab memiliki bentuk tunggal, dual dan
jamak yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri yang tidak dimiliki bahasa
Indonesia, karena hanya dua bentuk yang dimiliki yaitu bentuk tunggal dan jamak
43 Struktur adalah susunan bagian-bagian kalimat atau konstituen kalimat secara linear. Contoh: Dia mengikut ibunya, maka kalimat itu dapat dianalisis atas bagian-bagian tertentu secara fonemis, morfemis, maupun sintaksis. Semua konstituen tadi dapat dibandingkan dengan bentuk bahasa yang lain. Sedangkan sistem adalah hubungan antara bagian-bagian kalimat. Misalnya, adanya bentuk kata kerja aktif dalam suatu bahasa itu merupakan fakta adanya sistem dalam bahasa tersebut.
44 Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 25.

xxxix
tanpa ciri-ciri khusus yang membedakannya. Pada kategori genus (maskulin dan
feminin), masing-masing memilikinya meskipun tidak sama ciri-cirinya. Lainnya
adalah aspek, karena bahasa Indonesia tidak memiliki bentuk aspek secara
gramatikal. 45
Dengan demikian, proses terjemahan harus ada dua teks yang harus
dipadankan, yaitu teks Bsu dan Bsa. Kemudian teks Bsa dapat diketahui
terjemahan atau bukan melalui ragam-ragam terjemahan yang berdasarkan prinsip
yang dianutnya.
B. Ragam Dan Prinsip Terjemahan
Menurut Nababan, munculnya beberapa terjemahan di Indonesia dengan
berbagai macam ragamnya disebabkan oleh empat faktor, yaitu: 1) adanya
perubahan sistem Bsu dengan sistem Bsa, 2) adanya perbedaan jenis materi teks
yang diterjemahkan, 3) adanya anggapan bahwa terjemahan adalah alat
komunikasi dan 4) adanya perbedaan tujuan dalam menerjemahkan suatu teks.46
Bahasa menurut beberapa pengertian bahasa dalam bahasa Indonesia
merupakan sebuah sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan
sehari-hari dengan makna ‘cara’ atau ‘aturan’, seperti dalam kalimat “Kalau tahu
sistemnya, tentu mudah mengerjakannya”. Tetapi dalam kaitan dengan keilmuan,
sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang
bermakna atau berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen
yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional.
Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis.
Dengan sistematis, artinya, bahasa tersusun menurut suatu pola; tidak tersusun
secara acak, secara sembarangan. Sedangkan sistemis, artinya, bahasa itu bukan
45 Aspek adalah keadaan peristiwa atau perbuatan. Meskipun bahasa Indonesia memiliki tiga
aspek, yakni telah, sedang dan akan, tetapi seluruhnya tidak menggunakan unsur-unsur morfologis sebagaimana bahasa fleksi. Ketiga aspek tersebut dalam bahasa Indonesia ditandai dengan kata-kata tertentu untuk menunjukkan perbedaan ketiga aspek itu. Samsuri, Analisis Bahasa (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 251.
46 M. Rudolf Nababan, Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) , h. 29.

xl
merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri dari sub-subsistem; atau sistem bawahan.
Di sini subsistem itu dapat disebutkan seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan
semantik. Ketiga subsistem, yaitu fonologi, morfologi dan sintaksis tersusun
secara hierarkial, artinya subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang
lain; lalu subsistem yang satu ini terletak di bawah subsistem lainnya lagi. Ketiga
subsistem tadi terkait dengan subsistem semantik. Sedangkan subsistem leksikon
yang juga diliput subsistem semantik, berada di luar ketiga subsistem struktural
itu.47
Di dalam literatur terjemahan, ada beberapa ragam terjemahan48 yang
pernah dikemukakan oleh para ahli, misalnya Nida dan Taber, Larson dan
Newmark sekaligus. Konsep-konsep mereka ini berimplikasi terhadap proses
penerjemahan. Ragam-ragam tersebut dapat digolongkan menurut jenis sistem
tanda yang terlibat, jenis naskah yang diterjemahkan dan menurut proses
penerjemahan.49
Sehubungan kajian yang dilakukan penulis ini terjemahan al-Quran, maka
ada beberapa contoh ayat yang terjemahannya dapat digolongkan menurut
beberapa ragam yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas. Di antara
ragam atau jenis terjemahan itu adalah sebagai berikut:
1. Terjemahan Harfiah (Literal Translation)
47 Abdul Chaer, Linguistik Umum, h. 35. 48 Ragam terjemahan dapat diistilahkan dengan metode terjemahan, yaitu cara terjemahan
yang digunakan para penerjemah dalam mengalihkan makna nas sumber (BSu) secara keseluruhan ke dalam bahasa penerima (BSa). Lihat, Syihabuddin, Penerjemahan Arab Indonesia (Bandung: Humaniora, 2005), h. 68 dan Benny Hoedoro Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2006), h. 55.
49 Proses ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja. Proses penerjemahan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang penerjemah pada saat dia mengalihkan amanat dari Bsu ke dalam Bsa. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu sistem kegiatan dalam aktivitas terjemahan. Suryawinata telah membagi proses penerjemahan melalui empat tahap, yaitu: 1) tahap analisis atau pemahaman, 2) tahap transfer, 3) tahap restrukturisasi dan 4) tahap evaluasi dan revisi. Lihat, Suryawinata, Translation, h. 19.

xli
Secara umum terjemahan harfiah adalah terjemahan yang
mengutamakan padanan kata atau ekspresi di dalam BSa yang mempunyai
rujukan atau makna yang sama dengan kata atau ekspresi dalam BSu.
atau iyyahztarjamah lafTerjemahan harfiah dapat juga dikatakan
â simH-al, Ibn Nâ’imah, rîqtBa-ânâ ibn alh yang diikuti oleh Yomusâwiyyah
dan sebagainya.50 Yang menjadi sasaran dalam terjemahan harfiah adalah
kata. Sehingga dalam menerjemahkan BSu ke dalam BSa, seorang penerjemah
pertama kali memahami teks, lalu menggantinya dengan BSa pada posisi dan
tempat kata BSu. Contoh:
= kuliah dosen Menyampaikan 7(� ا����ض�ة ا����ض�
1 2 3 3 2 1
Dengan menggunakan terjemahan harfiyah, penerjemah hanya mencari
padanan Bsu dengan Bsa-nya baik dari kata per kata maupun posisi kata itu
sendiri, sehingga susunan kata dalam kalimat terjemahan sama persis dengan
kalimat aslinya. Terjemahan harfiah semacam itu masih tetap
mempertahankan struktur BSu, meskipun struktur itu tidak berterima di dalam
BSa.
Terjemahan harfiah bisa saja dirubah sedikit agar berterima di dalam
BSa, sehingga terjemahan BSa: misalnya م ذ�^ ا���5 أ�� itu rumah di) ا��-�
depan masjid) menjadi terjemahan yang berterima: rumah itu di depan masjid.
Perubahan terjemahan harfiah ini disebut oleh Larson sebagai terjemahan
harfiah yang dimodifikasi (modified literal translation).51 Istilah terjemahan
harfiah menurut Nida, Taber dan Larson ini disebut dengan terjemahan kata-
demi-kata oleh Newmark, karena dalam terjemahan ini tatabahasa BSu dan
susunan katanya dipertahankan di dalam BSa.52 Sebagai contoh dalam bahasa
50 Syihabuddin, Penerjemahan Arab Indonesia (Bandung: Humaniora, 2005) h. 69. 51 Mildred L. Larson, Meaning-based Translation, h. 16 52 Newmark, Textbook of Translation (Oxford: Pergamon Press, 1988), h. 69.

xlii
Inggris: He works in the house bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
menjadi Dia bekerja di dalam itu rumah.
Sehubungan hal itu, menurut al-Zarqâniy, terjemahan harfiah terikat
dengan dua hal, yaitu: a) adanya kosa kata yang sama maknanya di dalam BSu
dan BSa dan b) adanya persamaan unit-unit linguistik antara BSu dan BSa.53
Dalam kaitannya dengan terjemahan Arab sebagai BSu ke dalam bahasa
Indonesia sebagai BSa, penggunaan terjemahan harfiah memiliki beberapa
kelemahan. Kelemahan itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama,
tidak seluruh kosa kata Arab ada terjemahannya yang sepadan dalam bahasa
Indonesia, sehingga banyak dijumpai kosa kata BSu yang digunakan atau kosa
kata asing. Istilah-istilah dalam al-Quran sulit ditemukan padanan katanya
dalam bahasa Indonesia, misalnya kata taqwa, iman, islam, shalat, zakat,
infaq, shadaqah, haji dan sebagainya. Sehingga istilah-istilah tersebut menjadi
istilah yang baku dalam bahasa Indonesia. Kedua, struktur dan hubungan
antara unit linguistik dalam bahasa Arab berbeda dengan struktur bahasa
Indonesia.
Terjemahan harfiah maupun terjemahan kata-demi-kata seringkali
dikritik dan dibela. Kalangan ulama berbeda pendapat tentang penerjemahan
al-Quran dengan menggunakan terjemahan harfiah. Sebagian menyatakan
tidak mungkin terjemahan al-Quran secara harfiah, dan sebagian lainnya
menyatakan dimungkinkan dalam beberapa kata, kalimat atau ayat al-Quran.54
Adapun alasan Ulama yang menyatakan terjemahan al-Quran secara
harfiah itu tidak mungkin atau mustahil55 adalah sebagai berikut:
53 Muhammad ‘Abd al-‘Azîm al-Zarqâniy, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm al-Qurân (T.tp, Dâr al-
Fikr, t.t.), jilid II, h. 113. 54 Al-Zarqâniy, Manâhil al-‘Irfân, h. 114. 55 Rasyîd Ridâ menyatakan bahwa terjemahan al-Quran secara harfiah sulit dilakukan dan
akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Lihat, Ahmad Syarbasiy, Yas’alûnaka fi al-Dîn wa al-Hayâh (Beirut: Dâr al-Jîl, 1980), jilid I, h. 328

xliii
a. Mencari atau melakukan sesuatu yang mustahil menurut istilah dihukumi
haram, karena termasuk kategori membinasakan diri. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 195:
�K�zإ�� ا�� XK�� وF �)1ا ب��
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan.”
b. Munculnya terjemahan semacam ini akan mendorong orang-orang
memahami al-Quran lewat terjemahan tanpa memperhatikan teksnya.
Sehingga lama kelamaan, teks al-Quran hilang dengan sendirinya.
c. Jika orang-orang sudah merasa cukup dengan terjemahan al-Quran dan
sudah tidak memerlukan teks al-Quran lagi, maka keaslian bahasa al-
Quran akan terancam kepunahan, sebagaimana bahasa Ibrani yang menjadi
bahasa Taurat dan bahasa Injil.
d. Jika peluang untuk menerjemahkan al-Quran secara bebas, maka orang-
orang akan berlomba menerjemahkan al-Quran dengan menggunakan
bahasa nasional atau daerah. Munculnya terjemahan dalam berbagai
bahasa akan memicu perbedaan dan perselisihan antara yang satu dengan
lainnya. Akhirnya muncul fitnah dalam bentuk kefanatikan terhadap
terjemahan al-Quran yang paling baik menurutnya.
e. Seluruh umat muslim mengakui bahwa al-Quran adalah kalam Ilahi yang
tidak bisa diterjemahkan secara sembarangan baik nama-nama maupun
istilah di dalam al-Quran.56
Sedangkan di antara ulama yang membolehkan al-Quran itu
diterjemahkan adalah Syaikh Mahmoud Syaltut. Dia menyatakan bahwa:
“Sesungguhnya menerjemahkan al-Quran, baik untuk belajar maupun
mengajar, untuk pemahaman sendiri maupun memberi pemahaman kepada
56 Ahmad Ibrâhim Mahnâ, Dirâsah haula Tarjamah al-Qurân (T.tp.: Matbû’ât al-Sya’b,
1978), h. 152-153.

xliv
orang lain, untuk ceramah atau menasehati orang lain, semuanya
diperbolehkan menurut pendapat Hanafi, Hanbali dan Syafi’i. Bahkan
pendapat ini diperkuat dengan dihukumi wajib Kifayah oleh Syaikh
Muhammad Bakhit, juru fatwa kawasan Mesir.57
Terjemahan harfiah banyak dilakukan oleh kalangan pondok pesantren
tradisional dalam pembelajaran teks-teks al-Quran, hadits dan naskah-naskah
keagamaan lainnya. Pembacaan teks tersebut disertai dengan terjemahannya
secara harfiah. Metode pengajaran ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu
metode sorogan dan bandongan.
Dengan kedua metode tersebut, para pelajar atau santri diharapkan
mampu menerapkan pengetahuan bahasa Arab secara langsung, terutama
struktur kata di dalam kalimat dan mampu memahami isi teks yang dimaksud.
Karena itu, menurut Nurachman Hanafi, ragam terjemahan ini memiliki
kelebihan, yaitu: a) segi bentuk dan struktur kalimatnya lebih sesuai dengan
bahasa aslinya. Penerjemah dalam hal ini bukan hanya sebagai penerjemah
melainkan juga sebagai transformer, dan b) gaya penulisan penerjemah lebih
sesuai dengan dan tepat menurut bahasa aslinya, sehingga penerjemah telah
berhasil menyentuh keinginan penulisnya.58
2. Terjemahan Dinamis
Ragam terjemahan ini seperti yang dianjurkan oleh Nida dan Taber di
dalam bukunya The Theory and Practice of Translation harus berpusat pada
konsep tentang padanan dinamis dan sama sekali berusaha menjauhi konsep
padanan formal dan bentuk.59 Namun secara eksplisit, mereka tidak
menjelaskan unsur-unsur terjemahan dinamis ini, kecuali Suryawinata yang
menjelaskan bahwa ragam terjemahan ini mengandung lima unsur, yaitu: 1)
57 Ahmad Ibrâhim Mahnâ, Dirâsah haula Tarjamah al-Qurân, h. 25. 58 Nurachman Hanafi, Teori dan Seni Menerjemahkan (Ende Flores: Nusa Indah, 1986), h. 57 59 Konsep padanan formal dan bentuk ini dekat sekali dengan konsep terjemahan harfiah.

xlv
reproduksi pesan, 2) ekuivalensi atau padanan, 3) padanan yang alami, 4)
padanan yang paling dekat dan 5) mengutamakan makna.60
Terjemahan yang baik tentu saja terjemahan yang memiliki tingkat
keterbacaan yang tinggi. Keterbacaan yang tinggi, menurut Nida dan Taber,
dapat dicapai apabila si penerjemah mampu melahirkan padanan alami dari
BSu yang sedekat mungkin di dalam BSa, sehingga terjemahan itu
mempunyai pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya pada pembaca BSa
sama dengan yang ditimbulkannya pada pembaca BSu.61
Seperti yang diuraikan di atas, terjemahan dinamis harus mengandung
padanan yang alami. Dilihat dari teori Semantik, hal ini sepertinya tidak
mungkin terwujud, karena pada dasarnya tidak ada dua kata yang mempunyai
makna yang persis sama, apalagi bila dua kata itu berasal dari bahasa dengan
latar sosial dan budaya yang benar-benar berbeda.
Dalam terjemahan ini, istilah sepadan sering menimbulkan kesulitan
bagi penerjemah. Jika keserupaan pesan di dalam BSu terhadap BSa itu tidak
menjadi masalah, maka bisa diterjemahkan sesuai dengan pesan yang
terkandung di dalam BSu tadi. Namun, masalahnya apakah pesan tersebut bisa
dipahami oleh pembaca BSa. Oleh karena itu, si penerjemah dalam terjemahan
dinamis ini jangan berpikir “Bagaimana kalimat ini diterjemahkan?”, tetapi
“Bagaimana pesan dalam teks ini terungkapkan dalam BSa?”
Sebagai contoh terjemahan dinamis dengan BSu Inggris adalah frasa
Lamb of God. Frasa ini terdapat di dalam kitab Injil yang tidak bisa
diterjemahkan dengan domba Allah dengan sasaran pembaca BSa yang
berbeda kultur sosial-budaya dan tidak pernah melihat domba. Lamb adalah
simbol kebersihan jiwa, apalagi jika dihubungkan dengan konteks
pengorbanan dalam kehidupan rohani. Oleh karena itu, padanan frasa alami
60 Suryawinata, Terjemahan: Pengantar Teori dan Praktek (Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, PPLPTK, 1989), h. 8.
61 Eugene A. Nida dan Charles R. Taber The Theory and Practice of Translation (Leiden: E.J. Brill, 1982), h. 22.

xlvi
yang paling dekat bagi orang-orang Eskimo adalah Anjing Laut Tuhan, karena
anjing laut melambangkan ketidakberdosaan di dalam budaya Eskimo.
Sedangkan contoh ayat al-Quran yang bisa dikategorikan terjemahan
dinamis seperti terjemahan ayat 268 surah al-Baqarah: “Setan menjanjikan
kemiskinan kepadamu...” Kata kemiskinan pada ayat tersebut merupakan
terjemahan dari kata al-faqr yang seharusnya diterjemahkan kefakiran. Tetapi
beberapa terjemahan al-Quran Indonesia seperti yang disusun oleh Mahmud
Junus, HB. Jassin dan Depag RI menerjemahkan al-Faqr dengan kemiskinan.
Padahal sebagaimana telah diketahui antara kemiskinan dan kefakiran
berbeda istilah dan makna menurut konteks golongan penerima zakat.
Kemudian, penggunaan kemiskinan dalam terjemahan ayat tersebut lebih
bermakna dan mudah diterima oleh pembaca Bsa daripada kefakiran, karena
istilah-istilah yang banyak digunakan dan diperdengarkan oleh masyarakat
Indonesia adalah kemiskinan, misalnya pengentasan kemiskinan, di bawah
garis kemiskinan, dan sebagainya.
3. Terjemahan Idiomatis
Terjemahan jenis ini tidak jauh berbeda dengan terjemahan harfiah.62 Si
penerjemah sangat berperan dalam menentukan apakah terjemahan itu harfiah
atau idiomatis. Jadi penerjemah berusaha menciptakan kembali makna dalam
BSu, yakni makna yang diinginkan penulis atau penutur asli, di dalam kata
atau kalimat yang luwes di dalam BSa. Terjemahan yang betul-betul idiomatis
62 Pembahasan terjemahan harfiah dan idiomatis merupakan lanjutan dari perdebatan antara terjemahan literal (harfiah) dan terjemahan bebas yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Hatim dan Mason mencatat bahwa pada abad XIV seorang penerjemah Arab, Sâlih al-Dîn al-Safadi mengkritik generasi-generasi penerjemah sebelumnya yang banyak mempraktekan terjemahan harfiah. Mereka mempelajari setiap kata dan makna bahasa Yunani, kemudian mencari padanan kata dan maknanya dalam bahasa Arab lalu meletakkannya dalam susunan yang sama. Al-Safadi menyalahkan pendapat yang menyatakan bahwa padanan satu-satu selalu ada untuk setiap kata BSu dan BSa. Lihat, Basil Hatim dan Ian Mason, Discourse and Translator (Longman: Longman Group Limited, 1990), h. 5. Namun demikian, terjemahan harfiah tetap dibela, seperti Newmark membela terjemahan harfiah dengan cara membedakannya dari terjemahan kata-demi-kata. Lihat, Peter Newmark, A Textbook of Translation (Oxford: Pergamon Press, 1988), h. 68-69. Larson sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksudkan terjemahan menurut Newmark adalah terjemahan harfiah yang telah dimodifikasi. Dan dalam hal ini, ia berpihak pada penerjemahan “bebas” yang disebutnya sebagai terjemahan idiomatis.

xlvii
tidak akan terasa seperti terjemahan, tetapi terasa seperti tulisan atau ungkapan
asli. Oleh karena itu, menurut Larson,63 tujuan akhir setiap terjemahan
hendaknya terjemahan idiomatis dan seorang penerjemah yang baik adalah
penerjemah yang selalu berusaha menciptakan terjemahan idiomatis.
Di dalam contoh berikut, dilihat dari struktur BSu maupun BSa sama
persis. Jadi terjemahan ini sudah memadai dalam ragam terjemahan harfiah
maupun idiomatis.
BSu: I love her atau أن� أح���
BSa: Aku mencintainya.
Karena kesamaan struktur dalam BSu dan BSa pada contoh di atas,
maka terjemahan tersebut dapat dikategorikan pada terjemahan kata-demi-kata
(word-for-word)
Akan tetapi dalam banyak kasus, struktur ini tidak bisa diterima di
dalam BSa. Misalnya:
Bsu : ا � ?atau what is your name ؟ "�^
Harfiah : Apa namamu?
Idiomatis : Siapa namamu?
Terjemahan harfiah di atas tidak bisa berterima bagi orang Indonesia,
karena pertanyaan tentang nama tidak diungkapkan dengan ungkapan Apa
namamu? Melainkan dengan ungkapan siapa namamu?
Masih banyak lagi contoh-contoh terjemahan idiomatis,64 seperti
ungkapan-ungkapan BSu yang disampaikan saat berjumpa atau berpisah
”,)atangdelamat s(ahlan wa sahlan” “: yaitu, dengan teman atau saudara
63 Larson, Meaning-based Translation, h. 16. 64 Terjemahan idiomatis menghasilkan makna leksikal yang terbentuk dari beberapa kata.
Kata-kata yang disusun dengan kombinasi kata lain akan menghasilkan makna yang berlainan. Sebagian idiom merupakan bentuk beku (tidak berubah), artinya bentuk tersebut tidak dapat diubah berdasarkan kaidah sintaksis yang berlaku bagi suatu bahasa. Karena itu makna idiomatik didapatkan dalam ungkapan-ungkapan dan peribahasa. T. Fatimah Djajasudarma, Semantik 2 Pemahaman Ilmu Makna (Bandung: Refika Aditama, 1999), h. 16.

xlviii
“kaifa , )ores elamats(khair” -al` “masâ, )agipelamat s(khair” - alhabâs
hâluk“ (bagaimana khabarmu?), “bi al-khair” (baik-baik saja), “syukran”
(terima kasih), “ma’a al-salâmah” (selamat jalan) dan sebagainya.
Ada beberapa ungkapan al-Quran yang identik dengan ungkapan di atas
yang dapat diterjemahkan menurut terjemahan idiomatis seperti ayat 54 surah
al-An’âm : XK�A مG" L(@ // maka katakanlah:” salam sejahtera untuk
kamu.” Ungkapan salâm ‘alaikum banyak ditemukan di dalam al-Quran
hingga 19 tempat. Kemudian, ungkapan ini dapat juga dialihkan makna Bsa
menjadi salam sejahtera. Pengalihan makna tersebut bisa saja terjadi dalam
terjemahan menurut ragam terjemahan idiomatis, karena ungkapan salam
sejahtera sudah menjadi ungkapan resmi dalam bahasa lisan maupun tulisan di
kalangan masyarakat Indonesia.
Dalam terjemahan, ragam terjemahan idiomatis jarang sekali terjadi
secara keseluruhan. Yang sering adalah campuran antara terjemah harfiah,
terjemah idiomatis; sebagian diterjemahkan secara harfiah karena memang
sudah cukup dan sebagian yang lain diterjemahkan secara idiomatis. Menurut
Larson, urutan terjemahan dapat digambarkan seperti dalam bagan berikut:65
very literal modified inconsistent near idiomatic unduly free literal literal mixture idiomatic
________+________+________+_________+________+________+_______
TRANSLATOR’S GOAL
Berdasarkan diagram di atas, maka ragam terjemahan bermula dari
ujung kiri, terjemahan sangat harfiah yang terikat dengan BSu dalam hal kata
dan struktur kalimat. Semakin ke kanan, terjemahan makin mencapai
tujuannya dengan mementingkan penyampaian makna dan pesan yang luwes
sesuai dengan BSu dan pembaca BSa.
65 Larson, Meaning-based Translation, h. 17.

xlix
4. Terjemahan Semantis dan Terjemahan Komunikatif
Terjemahan semantis dan terjemahan komunikatif merupakan konsep
yang diajukan oleh Peter Newmark, dan ia mengakuinya sebagai sumbangan
terpenting pada teori terjemahan. Dalam rangka memperkenalkan kedua
konsep itu, ia meletakkannya dalam satu bagan yang memuat beberapa jenis
terjemahan sebagai berikut:66
Berpihak pada Bsu Berpihak pada Bsa
harfiah (literal) bebas (free)
setia (faithful) idiomatik (idiomatic)
Di dalam bagan di atas, jenis atau ragam terjemahan suatu naskah dapat
ditentukan dari segi hasil terjemahan yang berpihak pada penulis asli atau teks
BSu dan pembaca BSa. Hasil terjemahan yang berpihak pada teks BSu, maka
ragam tersebut dapat dikategorikan pada terjemahan harfiah. Sedangkan hasil
terjemahan yang berpihak pada pembaca BSa, maka terjemahan tersebut
dinamakan terjemahan idiomatis.
Di antara terjemahan harfiah dan idiomatis ini ada terjemahan semantis
dan komunikatif. Keduanya saling bersinggungan. Terkadang keduanya tidak
bisa dibedakan untuk beberapa kasus, namun untuk kasus-kasus yang lain
keduanya bisa dibedakan.
Terjemahan semantis pada dasarnya terjemahan yang bersifat objektif.
Karena berusaha menerjemahkan apa yang ada, tidak menambah, mengurangi
atau mempercantik. Ragam terjemahan ini hanya ingin memindahkan makna
dan gaya bahasa teks BSu ke dalam teks BSa. Gaya bahasa BSu tidak bisa
dikorbankan selama bisa dimengerti di dalam BSa. Banyak ayat-ayat al-Quran
66 Peter Newmark, About Translation (Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1991), h. 41.
Semantis Komunikatif

l
yang mengandung gaya bahasa yang memang maknanya langsung bisa
dipahami, sehingga teks Indonesia tetap mencerminkan teks Bahasa al-Quran.
Di antara ayat yang dapat diterjemahkan secara semantis adalah ayat 223
surah al-Baqarah: X�2ش �zأن XK��1��ا ح@ XK� ح�ث Xن-�ؤآ // Isteri-isterimu
adalah ladang bagimu, Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan
cara yang kamu sukai.
Contoh ayat di atas terdapat kata nisa`ukum yang diterjemahkan dengan
makna istri-istrimu. Kata nisâ` merupakan bentuk jamak dari kata mar`ah atau
imra`ah yang berarti orang perempuan atau wanita. Meskipun kata wanita,
dan perempuan memiliki perbedaan, tetapi semuanya memiliki unsur
kesesuaian ciri-ciri semantik antara unsur leksikal yang satu dengan unsur
leksikal yang lain, sebagaimana yang akan penulis jelaskan di bab IV.
Kemudian ayat tersebut diterjemahkan sesuai dengan bunyi teks apa
adanya dengan tidak membubuhkan kata seperti yang mengandung arti
perumpamaan dan makna ayat tersebut dapat dipahami meskipun tanpa ada
penambahan atau pengurangan atau mempercantik gaya bahasa Indonesia.
Sedangkan terjemahan komunikatif lebih bersifat subjektif, karena
berusaha menciptakan efek pikiran dan tindakan pada pembaca BSa. Dengan
demikian, terjemahan ini mengakibatkan hilangnya sebagian makna BSu.
Menurut Newmark, kata mempunyai banyak makna yang luwes dan sekaligus
ruwet serta menimbulkan tafsiran yang beragam. Oleh karena itu, setiap
penyederhanaan dalam terjemahan komunikatif selalu mengakibatkan
hilangnya sebagian makna itu.67
Terjemahan komunikatif juga berlaku pada terjemahan al-Quran, seperti
ayat 47 surah al-Dzâriyât: � Dan langit itu Kami // ..وا�-z��ء ب����ه� ب��
bangun dengan tangan (kami).
67 Peter Newmark, Approaches to Translation (Oxford: Pergamon Press, 1981), h. 51

li
Menurut kajian stylistik, gaya bahasa al-Quran pada ayat tersebut
menggunakan majâz mursal atau sepadan dengan gaya bahasa sinekdoke
dalam bahasa Indonesia.68 Dengan munculnya arti tangan pada ayat tersebut,
berarti ada sebagian makna yang hilang. Karena itu, penyederhanaan makna
pada ayat-ayat seperti di atas menciptakan sikap, pemikiran dan penafsiran
para pembacanya. Oleh karena itu, terjemahan al-Quran Depag RI
mengartikan kata aidî (tangan) dengan kekuasaan.
Newmark menyatakan bahwa terjemahan semantis biasa digunakan
untuk menerjemahkan teks-teks otoritatif (authoritative) atau teks ekspresif,
yakni teks-teks yang isi dan gayanya, gagasan dan kata-kata serta strukturnya
sama-sama pentingnya. Jenis teks ini meliputi teks sastra, atau teks-teks lain
yang ditulis dengan indah dan bagus. Yang penting teks tersebut ditulis oleh
penulis yang mempunyai status yang tinggi.69 Karena itu, Suryawinata
menambahkan bahwa terjemahan al-Quran sebagai wacana otoritatif, termasuk
ke dalam ragam terjemahan semantis, karena penerjemahannya harus sedekat
dan setepat mungkin dengan teks aslinya baik gramatika, kosakata, konsep dan
makna, amanat maupun stilistiknya.70
Selanjutnya, meskipun banyak ragam terjemahan sebagai alternatif dan
model pengembangan dalam terjemahan, penerjemah tetap harus memiliki
prinsip-prinsip dasar yang harus dimilikinya. Yang dimaksud dengan prinsip-
prinsip terjemahan di sini adalah seperangkat acuan dasar yang seharusnya
dipertimbangkan oleh para penerjemah. Tentunya para penerjemah bisa
68 Sinekdoke adalah semacam bahasa figuratif yang menggunakan sebagian dari suatu hal
untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Misalnya: Setiap kepala dikenakan sumbangan sebesar Rp. 10.000,-. Dalam bahasa Arab disebut majâz mursal ‘alâqatuhu al-juz iyyah. .
69 Peter Newmark, Paraghrafs on Translation (Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1993), h. 1.
70 Suryawinata, Translation, h. 51.

lii
melakukan aktivitas terjemahan dengan berbagai macam ragam atau jenis
terjemahan yang telah dikemukakan sebelumnya, seperti terjemahan harfiah, kata-
demi-kata, dinamis, idiomatis, semantis hingga komunikatif.
Namun, semua ragam tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke
dalam dua prinsip terjemahan, yaitu prinsip yang setia pada teks Bsu dan yang
setia pada pembaca atau teks Bsa.
Menurut Suryawinata,71 ragam terjemahan yang berdasarkan prinsip
pertama dapat diketahui melalui hasil karya penerjemah, yakni antara lain: (a)
lebih banyak menggunakan kata-kata teks Bsu, (b) teks Bsa yang dibaca seperti
terjemahan teks Bsu, (c) gaya bahasa Bsu masih tercermin dalam teks
terjemahannya, (d) terjemahan Bsa masih mencerminkan waktu teks ditulis
(contemporary of the author), (e) tidak ditemukan penambahan dan pengurangan.
dalam teks Bsa, (f) genre sastra (literary genre) tertentu72 masih tetap
dipertahankan dalam terjemahan.
Sedangkan prinsip kedua, yakni setia pada pembaca atau teks Bsa juga
dapat diketahui melalui hasil karya penerjemah, antara lain: (a) dalam hal
keluwesannya, ketika dibaca seperti teks aslinya, (b) memiliki gaya sendiri dalam
terjemahannya, (c) terjemahan harus menggambarkan waktu saat teks Bsu itu
diterjemahkan, (d) penambahan dan pengurangan diperbolehkan dalam
terjemahan bahkan dianjurkan, (e) genre sastra tidak harus dipertahankanPrinsip-
prinsip terjemahan yang setia kepada teks Bsu
Dari beberapa prinsip di atas, maka dapat dipahami bahwa ragam
terjemahan yang digunakan adalah terjemahan harfiah atau terjemahan dari kata-
kata yang dipakai teks Bsu. Kemudian, yang perlu dipertahankan dari teks Bsu
adalah gaya bahasanya, sehingga jika dibaca akan terasa seperti terjemahannya.
Pengurangan dan penambahan dalam terjemahan yang setia dengan teks Bsu tidak
71 Suryawinata, Translation, h. 59. 72 Wacana yang mempunyai ciri-ciri struktural dan stilistis yang khusus; misalnya dongeng,
parabel, lirik dan sebagainya. Lihat, Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 64.

liii
berlaku sama sekali. Sedangkan dalam wacana sastra harus diterjemahkan dalam
bentuk sastra lagi, misalnya puisi harus diterjemahkan menjadi puisi, demikian
pula sebuah prosa diterjemahkan menjadi prosa.
Penerjemah yang mengikuti terjemahan setia pada teks Bsu, menurut
Rachmadie, akan mengalami beberapa kesulitan, karena pada kenyataannya
jarang sekali ada teks yang bisa diterjemahkan secara harfiah dengan ketepatan,
kejelasan, dan ketelitian yang sama dengan teks Bsu.73
Dengan mengikuti prinsip-prinsip terjemahan di atas, maka ragam
terjemahan yang setia mengikuti teks Bsa adalah terjemahan dinamis, idiomatik
dan komunikatif.
Pada kenyataannya, Terjemahan al-Quran Depag RI tetap menganut dua
prinsip di atas, karena ragam terjemahan yang diembannya tidak sebatas
terjemahan harfiyah, melainkan terjemahan semantis, idiomatis dan komunikatif
yang semuanya bisa dan mungkin terjadi. Hal itu disebabkan oleh teks al-Quran
sebagai teks keagamaan yang berbentuk prosa dengan bahasa yang puitis. Di
samping itu, teks al-Quran mengandung ajaran-ajaran teologis yang tentunya akan
berpengaruh dalam memahami teks aslinya dan bagaimana menetapkan
terjemahannya. Dalam al-Quran, terdapat beberapa kasus yang dinamakan iltifât
(alih pronomina), seperti: F 7� ��و�Aأ Z��ي @>�ن7 وإ z1ن ا�: ��. Ayat ini
terdapat dalam surah Yâsîn ayat 22 yang mengandung dua subjek dalam struktur
yang sama , yakni orang pertama tunggal (Aku) dan orang kedua jamak (kamu).
Selain itu, penggunaan kala dalam konteks hari kiamat yang belum atau
masih akan terjadi, seperti pada ayat 87 surah al-Naml berikut ini:
B @7 ا�-z��وات وB @7 ا��رض @]bع�1م ��]� @7 ا�&�1ر ...
Contoh ayat di atas menunjukkan adanya penggunaan kala lampau pada
verba fazi’a, sementara konteks peristiwa itu belum terjadi. Bahasa Indonesia
73 Sabrony Rachmadie, Zuchridin Suryawinata dan Achmad Efendi, Materi Pokok
Translation, Modul 1-6 (Jakarta: Karunika dan Universitas Terbuka, 1988), h. 124

liv
tidak mengenal kala seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian untuk
memberikan makna pada kata fazi’a, maka tidak perlu menyertakan kata telah
tetapi cukup menambahkan partikel –lah pada terjemahan verbanya sebagai
penekanan makna bahwa peristiwa tersebut benar-benar akan terjadi, sehingga
terjemahan verba fafazi’a menjadi maka terkejutlah.
Berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Suyawinata di
atas, secara khusus memang tidak ada aturan yang mengikat untuk memilih kedua
prinsip tersebut. Semua itu dikembalikan secara bebas kepada para penerjemah.
Secara historis, kegiatan terjemahan telah muncul sejak ratusan bahkan ribuan
tahun yang silam. Namun prinsip-prinsip terjemahan hingga kini masih
diperbincangkan dan diperdebatkan oleh kalangan penerjemah dan pakar
terjemahan. Sebagai contoh, sekitar tahun 834 M, Paus Damasus menugaskan
Jerome untuk menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru, karena terjemahan kitab
suci sebelumnya terikat dan setia dengan Bsu-nya. Kemudian, Jerome mencoba
untuk menerjemahkan kitab suci itu dengan prinsip terjemahan yang setia kepada
Bsa. Akhirnya, selama hidupnya Jerome mendapat tantangan dan kecaman dari
masyarakat pembaca.74 Contoh lainnya berkaitan erat dengan terjemahan kitab
suci al-Quran secara puitis oleh Hans Bague Jassin berjudul “Bacaan Mulia” dan
diterbitkan pada tahun 1978 oleh Penerbit Djambatan di Jakarta. Ternyata karya
terjemahannya menimbulkan polemik dan menjadi perhatian bagi umat Islam,
bahkan Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Islamiyah
Indonesia turut berbicara untuk upaya perbaikan terjemahan al-Quran itu. Di
antara alasan utamanya polemik itu muncul, karena HB. Jassin menerjemahkan al-
Quran terlalu setia pada Bsa pada ayat-ayat tertentu, misalnya kata “hudâ” tidak
diterjemahkan secara konsisten, sehingga muncul maknanya bermacam-macam
seperti petunjuk (ayat 2 surah al-Baqarah), pimpinan (ayat 16 surah al-Baqarah),
-surah al143 ayat (umat yang adil diterjemahkan dengan an”tummatan wasa“
74 Suhendra Yusuf, Teori Terjemah: Pengantar ke Arah Pendekatan Linguistik dan
Sosiolinguistik (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 63.

lv
, Selain itu 75. dan sebagainyaembun diterjemahkan dengan alltfa“, )Baqarah
terjemahan al-Quran yang dianggap melenceng dari makna kandungannya adalah
terjemahan oleh Nazwar Syamsu dalam bentuk buku sebagai koreksi terhadap
terjemahan Bacaan Mulia HB. Jassin. Penyimpangan terjemahan dalam buku
tersebut misalnya “al-Qarnain” diterjemahkan dua golongan (halaman 60), “din
al-Haqq” diterjemahkan agama logis (halaman 68), “wa al-mu`allafah
qulubuhum” diterjemahkan kekuatan penjagaan (halaman 74), “fa ummuhû
hâwiyah” diterjemahkan maka ibunya ialah yang menarik jatuh (halaman 152).76
C. Prosedur Terjemahan
Kata prosedur berarti urutan yang formal. Prosedur dalam suatu terjemahan
perlu diadakan untuk menghindari kesalahan dan memudahkan proses terjemahan,
karena penerjemahan tidak lepas dari berbagai persoalan. Pada umumnya dalam
penerjemahan, terdapat dua persoalan praktis yang dihadapi oleh para
penerjemah. Pertama, penerjemah tidak memahami makna satuan bahasa seperti
kata, kalimat atau paragraf sehingga tidak menangkap pesannya. Kedua,
penerjemah mengalami kesulitan untuk menerjemahkannya, meskipun sudah
memahami Bsu-nya.77
Untuk mengatasi hal itu, penerjemah perlu menempuh prosedur, yang
menurut Nida dan Taber, terdiri dari tiga langkah penerjemahan, yaitu: (1)
analisis (memahami Bsu); (2) transfer (menerjemahkan dalam pikiran); dan (3)
restrukturisasi (menerjemahkan).78
75 Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B. Jassin tentang al-Quranul Karim Bacaan Mulia
(Jakarta: Mutiara, 1979), h. 10-12. 76 Nazwar Syamsu, Koreksi Terjemahan Bacaan Mulia HB. Jassin (Padang Panjang: Pustaka
Saadiyah, 1916). 77 Benny Hoedoro Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan (Bandung: Pustaka Jaya, 2006), h.
11. 78 Nida dan Taber, The Theory and Practice of Translation, h. 22.

lvi
Analisis dilakukan dengan cara teks dibaca secara keseluruhan dan
pesannya dipahami secara garis besar. Teks yang dibaca itu meliputi struktur,
semantik dan gaya bahasa. Pada langkah pertama ini, sering ditemukan problem
pemahaman dan pemecahannya harus dicari di luar teks. Apalagi al-Quran
mengandung banyak makna dan pesan yang pemecahannya harus ditemukan dari
berbagai sumber, misalnya kamus, literatur tafsir baik klasik maupun
kontemporer, dan sebagainya. Langkah kedua, transfer dengan cara teks
diterjemahkan di dalam pikiran dan ditulis jika perlu sambil mencari pemecahan
problem yang harus dicari di luar teks. Pada langkah ini, menurut Hoed, adanya
“deverbalisasi”, yakni melepaskan diri dari ikatan bentuk teks atau kalimat-
kalimat Bsu untuk menangkap pesannya secara rinci.79 Namun untuk menjaga
agar makna dan pesan teks Bsu tidak hilang, teks sumber harus tetap dijadikan
acuan utama agar melahirkan satuan terjemahan terkecil yang dapat dicermati dan
dilakukan dan proses ini dinamakan close translation.80
Langkah ketiga, restrukturisasi yang dimulai dari cara mengatur susunan
kalimat secara teliti. Di sinilah, struktur gramatikal dan semantik Bsu mulai
diubah menjadi struktur gramatikal dan semantik Bsa.
Ketiga langkah dalam proses penerjemahan di atas dinilai belum
sepenuhnya dilakukan, oleh karena itu Newmark menambahkan satu langkah
sehingga jumlahnya empat langkah dan keempat langkah ini kemudian disebutnya
sebagai approach. Dengan demikian, prosedur terjemahan sepenuhnya harus
melewati empat tataran penerjemahan, yakni: (1) tataran teks (the textual level);
(2) tataran referensial; (3) tataran kohesi; (4) tataran kewajaran (the level of
naturalness).81
Perbedaan yang mencolok antara Nida dan Newmark mengenai prosedur
terjemahan itu terdapat pada langkah ketiga, yakni restrukturisasi menurut Nida
79 Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 11. 80 Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 11. 81 Peter Newmark, A Textbook of Translation (Oxford: Pergamon Press, 1988), h. 20-30.

lvii
dan tataran kohesi dan kewajaran menurut Newmark. Tataran kohesi dimaksudkan
sama dengan restrukturisasi, yakni keterpaduan antara gramatikal Bsa dan
maknanya terhadap gramatikal dan makna Bsu. Sedangkan tataran kewajaran
inilah yang kemudian sebagai langkah evaluasi dari langkah ketiga, apakah hasil
terjemahan itu berterima bagi pembaca atau tidak. Oleh karena itu, perlu
dilakukan pemeriksaan ulang dengan maksud apakah terjemahan ini sudah sesuai
dengan desain sasaran (audience design) dan analisis kepentingan (need analysis).
Kemudian, langkah-langkah tersebut di atas memunculkan berbagai macam
strategi terjemahan.82 Dalam prakteknya, penerjemah tidak mengambil seluruh
teknik yang digunakan sebagai strategi terjemahan, tetapi dia memilih beberapa
teknik yang sesuai dengan untuk siapa dan untuk tujuan apa penerjemahan itu
dilakukan. Ada banyak teknik yang ditawarkan, tetapi hanya beberapa yang
dianggap umum yang akan dikemukakan di sini.
1. Transposisi (Transposition)
Teknik ini dilakukan oleh penerjemah untuk mengubah struktur asli Bsu
di dalam Bsa agar mencapai efek yang padan. Pengubahan ini meliputi
pengubahan struktur kalimat secara keseluruhan, seperti bentuk jamak kepada
bentuk tunggal, bentuk kata kepada bentuk kata lainnya dan posisi kata.83
Misalnya dalam bahasa Inggris bentuk jamak musical instruments
diterjemahkan dengan bentuk tunggal alat musik. Di samping pengubahan,
termasuk juga pemisahan satu kalimat Bsu menjadi dua kalimat Bsa atau lebih,
atau penggabungan dua kalimat Bsu atau lebih menjadi satu kalimat Bsa juga
termasuk dalam teknik ini. Pemisahan atau penggabungan kalimat itu bisa
dilakukan karena pertimbangan gaya bahasa atau stilistika.84
2. Modulasi
82 Dalam literatur terjemahan, strategi terjemahan disebut prosedur terjemahan (translation
procedures). Suryawinata, Translation, h. 67. 83 Lihat, Newmark, A Textbook of Translation, h. 85 dan Rachmadie dkk., Materi Pokok
Translation (Jakarta: Karunika dan Universitas Terbuka, 1988), h. 136. 84 Newmark, A Textbook of Translation, h. 87.

lviii
Modulasi adalah strategi untuk menerjemahkan frasa, klausa atau
kalimat. Di sini penerjemah memandang pesan dalam kalimat Bsu dari sudut
yang berbeda atau cara berpikir yang berbeda.85 Teknik ini dilakukan karena
teks Bsu yang diterjemahkan tidak menghasilkan terjemahan Bsa yang wajar
atau luwes, seperti teks bahasa Inggris I broke my leg kemudian diterjemahkan
ke dalam Bsa menjadi kakiku patah. Contoh ini memberikan padanan yang
secara semantik berbeda sudut pandang atau cakupan maknanya, tetapi dalam
konteks yang bersangkutan memberikan pesan yang sama.
3. Padanan Deskriptif (Descriptive Equivalent)
Seperti yang tercermin dalam namanya, padanan ini berusaha
mendeskripsikan makna atau fungsi kata Bsu.86 Strategi ini dilakukan karena
kata Bsu tersebut sangat terkait dengan budaya khas Bsu dan penggunaan
padanan budaya dirasa tidak bisa memberikan derajat ketepatan yang
dikehendaki.
4. Penjelasan Tambahan (Contextual Conditioning)
Penjelasan tambahan dilakukan karena pertimbangan kejelasan makna.
Di sini penerjemah memasukkan informasi tambahan di dalam teks
terjemahannya karena ia berpendapat bahwa pembaca memerlukannya.
Informasi tambahan ini bisa diletakkan di dalam teks, di bagian bawah
halaman berupa catatan kaki atau di bagian akhir dari teks.87
5. Penerjemahan Fonologis
Penerjemah tidak menemukan padanan yang sesuai dalam Bsa sehingga
ia memutuskan untuk membuat kata baru yang diambil dari bunyi kata itu
dalam Bsu untuk disesuaikan dengan sistem bunyi (fonologi) dan ejaan
85 Newmark, A Textbook of Translation, h. 88. 86 Newmark, A Textbook of Translation, h. 83-84. 87 Newmark, A Textbook of Translation, h. 91-92.

lix
(grafologi) Bsa. Penerjemahan sejenis ini, Suryawinta menamakannya dengan
dengan transliterasi.88
6. Penerjemahan Resmi/ Baku
Ada sejumlan istilah, nama, dan ungkapan yang sudah baku atau resmi
dalam Bsa sehingga penerjemah langsung menggunakannya sebagai padanan.89
Untuk itu, penerjemah yang mengerjakan naskah dari bahasa asing ke dalam
bahasa Indonesia perlu memiliki “Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata
Asing” yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Depdikbud RI. Sisi lain kelebihan teknik ini adalah penerjemah bisa
memperoleh dua keuntungan: Pertama, ia bisa menyingkat waktu; dan kedua
ia bisa ikut serta memberi arah perkembangan bahasa Indonesia pada jalur
yang benar.90
7. Padanan Budaya (Cultural Equivalent)
Teknik ini berkaitan dengan budaya Bsu dan Bsa yang keduanya
memang berbeda. Kemudian dalam terjemahan, teknik ini digunakan untuk
memudahkan penerjemah agar bisa membuat kalimat Bsa yang mulus dan enak
dibaca, meskipun kemungkinan besar teknik ini tidak bisa menjaga ketepatan
makna. Hal yang terpenting dari teknik ini adalah mengganti kata yang khas
dalam Bsu dengan kata yang khas dalam Bsa. Untuk teks yang bersifat umum,
misalnya pengumuman atau propaganda, strategi ini bisa digunakan karena
pada umumnya pembaca Bsa tidak begitu peduli akan budaya Bsu.91
Selain tujuh teknik di atas, ada beberapa teknik yang ditawarkan oleh
beberapa pakar terjemahan, yang secara substansial merupakan hasil adaptasi dari
teknik-teknik di atas. Tim dosen terjemah di fakultas-fakultas dan lembaga-
lembaga khusus di Beirut mengemukakan bahwa terjemahan maknawiah (al-
yakni , hendaknya berdasarkan kepada enam teknik) arrufsTa-Tarjamah bi al
88 Suryawinata, Translation, h. 71. 89 Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 76. 90 Suryawinata, Translation, h. 74. 91 Newmark, A Textbook of Translation, h. 82-83.

lx
mendahulukan (al-taqdîm), mengganti (al-tabdîl), mengakhirkan (al-ta`khîr),
membuang (al-hadzf), mengutip (al-iqtibâs), dan menambahkan (al-ziyâdah).92
Sementara itu, al-Didâwî menyebutkan tujuh butir kunci penerjemahan, yaitu
adopsi (iqtibâs), metafora (isti’ârah), terjemah harfiah, alterasi (tabdîl), implikasi
(idkhâl), asimilasi (mu’âdalah), dan approximasi (taqrîb).93
Beberapa teknik penerjemahan, baik yang dikemukakan oleh lembaga
khusus di Beirut maupun oleh al-Didâwî, oleh Vinney Darbalini, secara garis
besar dikelompokkan ke dalam dua jenis terjemahan, yakni: (1) Terjemahan setia
(terikat) yang meliputi beberapa teknik antara lain: adopsi, metafora dan terjemah
harfiah; (2) terjemahan bebas yang meliputi beberapa teknik antara lain: aliterasi,
implikasi, asimilasi dan approximasi.94
Strategi atau teknik penerjemahan yang ditulis oleh beberapa pakar di atas
mendasarkan pemikirannya pada pengalaman mereka sebagai penerjemah. Karena
didasarkan pada pengalaman pribadi, pandangan-pandangan itu tidak bisa
dikatakan sebagai konstruk teoritis bagi penilaian yang sistematis terhadap teori
penerjemahan. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan-pandangan itu
berubah menjadi konsep umum sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas
penerjemahan.
Adapun yang terpenting menurut Lauven-Zwart, sebagaimana yang dikutip
oleh Nababan bahwa menghasilkan penerjemah dan terjemahan yang baik bukan
merupakan tujuan utama teori penerjemahan. Penerjemah dan terjemahan yang
lebih baik mungkin saja merupakan produk teori dan metode penerjemahan. Akan
tetapi, tugas itu pada umumnya diserahkan pada studi Penerjemahan Terapan.95
D. Kualitas Terjemahan Dan Kelembagaannya
92 Jamâ’ah Mudarris al-Tarjamah fî al-Ma’âhid, al-Uslûb al-Sahîh fî al-Tarjamah (Beirut:
Mansyûrât Maktabah al-Hayât, t.t.), h. 9. 93 Al-Dîdâwî, Muhammad. ‘Ilm al-Tarjamah baina al-Nazariyyah wa al-Tatbîqiyyah (Tunis:
Dâr al-Ma’ârif wa al-Nasyr, 1992), h. 171. 94 A. Widyamartaya, Seni Menerjemahkan (Jakarta: Kanisius, 1989), h. 30-36. 95 M. Rudolf Nababan. Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), h. 9.

lxi
Terjemahan dapat dibagi atas dua jenis, yakni: (1) terjemahan tertulis yang
dilakukan oleh orang yang disebut “penerjemah”, dan (2) terjemahan lisan yang
dilakukan oleh orang yang disebut “juru bahasa”.96 Dalam terjemahan tertulis
maupun lisan, penerjemah dituntut agar bertanggung jawab terhadap pesan yang
terkandung dalam teks sumber, sehingga mampu dialihkan secara betul dan
berterima bagi pembacanya. Tanggung jawab yang besar itu menyebabkan
penerjemah atau juru bahasa harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi.
Profesionalisme penerjemah, menurut Hoed dapat dilihat dari empat faktor
penting, yakni (1) pengetahuan umum, (2) keingintahuan dan berjiwa peneliti
(curiosity and research), (3) intelejensia, dan (4) retorika (kemampuan mengolah
bahasa).97 Dengan demikian, penerjemahan bukan pekerjaan asal-asalan. Dan
upaya untuk mengembangkan dan memajukan dunia terjemahan, harus dilakukan
peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah, serta upaya agar etik sebagai
moral profesional selalu dijaga dalam kegiatan penerjemahan.
Demikian pula kualitas terjemahan al-Quran secara umum dilihat dari
penerjemahnya. Misalnya terjemahan al-Quran di Indonesia kebanyakan
dilakukan oleh kalangan intelektual muslim baik yang berasal dari pendidikan
pesantren maupun akademis. Secara historis, sejak abad ke-17 M, di Indonesia
telah muncul upaya penerjemahan al-Quran yang pertama kali oleh ‘Abd al-Ra’ûf
al-Sinkiliy (1615-1693 M) dengan nama Tarjumân al-Mustafîd.98
96 Terjemahan tertulis (written translation) dan terjemahan lisan (oral translation) merupakan
jenis terjemahan yang sudah terkenal dan bisa berdiri sendiri serta telah menjadi jenis terjemahan profesional yang mencakup jenis terjemahan semua ragam bahasa. Kemudian terjemahan lisan dibagi lagi menjadi terjemahan lisan konsekutif (disampaikan secara berurutan-perkalimat atau peralinea) dan terjemahan lisan simultan. Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemahan, h. 31.
97 Benny Hoedoro Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 117. 98 ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkiliy hidup dalam enam periode kesultanan Aceh, yaitu periode Sultan
Iskandar Muda (1607-1636), Sultan Iskandar Tsani (1636-1640), Sultanah Taj al-‘Alam Safiyat al-Din Syah (1641-1675), Sri Sultan Nur al-‘Alam Nakiyat al-Din Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Syah Zakiyat al-Din Syah (1678-1688) dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699). Keempat penguasa yang terakhir ini adalah sultan perempuan yang di dalam kepemimpinan merekalah ‘Abd al-Ra’uf menjadi seorang mufti. Lihat, Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Idiologi (Jakarta: Teraju, 2003), h. 40.

lxii
Menyusul kemudian, pada akhir tahun 1920-an mulai muncul beberapa
literatur berbahasa Melayu yag mencoba untuk memberikan kemudahan dalam
berinteraksi dengan al-Quran. Di era ini, Mahmud Junus telah memulai
menerjemahkan al-Quran yang ditulis dalam tulisan Jawi (bahasa Indonesia atau
Melayu yang ditulis dengan tulisan Arab).99 Ahmad Hassan, pada tahun 1928,
juga telah memulai menerjemahkan al-Quran. Menjelang tahun 1940 ia telah
menyelesaikan terjemahannya hingga surah Maryam.100
Pada masa orde lama, bermunculan beberapa terjemahan al-Quran yang
disertai dengan penjelasannya yang kemudian masuk pada kelompok literatur
tafsir Indonesia. Misalnya tafsir al-Azhar karya Hamka atau Haji Abdul Malik bin
Abdul Karim Amirullah yang disusun sejak tahun 1962 dan diterbitkan pada
tahun 1967, tafsir An-Nur dan kedua adalah tafsir Al-Bayan oleh Teungku
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.101
Kemudian, muncul terjemahan al-Quran berikutnya pada masa orde baru,
yakni terjemahan al-Quran Depag RI. Terjemahan tersebut telah mengalami
terbitan kali ketiga, yaitu edisi 1970, 1989 dan 2002. Sebenarnya, Terjemahan al-
Quran edisi 1970 penerbitannya tidak dilakukan tepat pada tahun 1970, melainkan
terbitan perdananya pada tahun 1965, tepatnya tanggal 17 Agustus, mulai dari juz
1 hingga juz 10. Kemudian terbitan berikutnya mulai dari juz 11 hingga juz 20
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tahun yang berbeda, yaitu tahun 1967.
99 Pada tahun 1922, Junus telah menerbitkan tiga bab dari karyanya. Ketika itu pada
umumnya sarjana muslim di Indonesia menyatakan bahwa menerjemahkan al-Quran adalah haram. Beberapa tahun kemudian, ketika menjadi seorang mahasiswa di Universitas al-Azhar, Mesir, menurut salah seorang dosennya menyatakan bahwa menerjemahkan al-Quran hukumnya boleh, bahkan bisa fardlu kifayah. Atas dasar itu, Junus mendapat semangat baru untuk melanjutkan usahanya itu pada bulan Ramadan tahun 1354 H (1935 M) dan pada tahun 1938, tamatlah terjemahan al-Quran tiga puluh serta tafsirnya. Lihat, Mahmud Junus, Tafsir Quran Karim (Djakarta: Al-Hidajah, 1971), h. iii.
100 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, h. 49 101 Tafsir Al Bayan termasuk tafsir generasi ketiga yaitu mulai muncul pada tahun 1970-an,
dan merupakan penafsiran yang lengkap. Howard M. Federspiel, Kajian Al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1994), hal. 137. Sedangkan menurut Ishlah, tafsir ini masuk kategori generasi kedua karena dicetak pada tahun 1966 oleh PT Al-Ma'arif Bandung. Tafsir ini merupakan wujud ketidak puasannya terhadap karya tafsir yang pertama. Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Idiologi, hal. 60

lxiii
Dan pada tahun 1970, tepatnya tanggal 1 Januari, terbitan terakhir mulai dari juz
21 hingga 30 dapat diselesaikan.102 Penerjemahan dan penerbitan awal terjemahan
al-Quran Depag RI ini langsung ditangani oleh pemerintah sekaligus sebagai
fasilitator melalui Departemen Agama RI. Adapun tiga hal penting yang
melatarbelakangi terjemahan al-Quran itu dilakukan, yaitu: (1) Adanya keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan No. II/ MPRS/ 1960
tentang Garis-garis besar pola pembangunan semesta berencana tahapan pertama
1961-1969 lampiran A 4 Agama/ Kerohanian: Menerjemahkan kitab-kitab suci ke
dalam bahasa Indonesia; (2) Menghadirkan terjemahan al-Quran agar dipahami
kandungan al-Quran bagi masyarakat muslim yang belum mengerti bahasa Arab;
dan (3) Melalui terjemahan al-Quran ke dalam bahasa Indonesia tersebut bisa
memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim yang sudah memahami bahasa
Arab namun lemah dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan
susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar.103
Kemudian, untuk pengadaan aktivitas dan peningkatan efektifitas
terjemahan dibentuklah satu lembaga yang bernama Lembaga Penyelenggara
Penerjemah Kitab Suci Al-Quran yang berdasarkan Surat Keputusan No. 91 tahun
1962 dan No. 53 tahun 1963. Struktur lembaga tersebut diketuai oleh diketuai
oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H., mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan 10 anggota yang terdiri dari pakar tafsir, pakar terjemahan dan
intelektual pesantren serta akademikus.104
Dalam dekade 1980-an, terjemahan al-Quran juga telah dilakukan dengan
menggunakan bahasa non-Melayu dalam bentuk aksara Jawi (Arab pegon)
102 Ismail Lubis, Falsifikasi Terjemahan al-Quran Departemen Agama Edisi 1990
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 135. 103 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yamunu,
1965), h. 9. 104 Mereka itu adalah Prof. T.M. Hasbi Ashshiddiqi, Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. H.
Muchtar Jahya, Prof. H.M. Toha Jahya Omar, Dr. H.A. Mukti Ali, Drs. Kamal Muchtar, H. Gazali Thaib, K.H.A. Musaddad, K.H. Ali Maksum, Drs. Busjairi Madjidi. Khâdim al-Haramain al-Syarîfain, al-Qurân al-Karîm wa Tarjamah Ma’ânih bi al-Lughat al-Indûnisiyyah (al-Madînah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Tibâ’at al-Mushaf al-Syarîf, 1418 H), tanpa hal.

lxiv
sebagai media penulisannya.105 Karya-karya terjemahan itu antara lain al-Ibrîz
karya K.H. Bisyri Mushthofa.106
Kualitas terjemahan al-Quran harus tetap diupayakan agar pesan-pesan al-
Quran mudah dipahami dengan cepat dan tepat melalui bahasa terjemahannya.
Kekurangan dalam bahasa terjemahan al-Quran seringkali diakibatkan oleh
pemilihan kata (diksi) yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan maknanya.
Pendayagunaan kata dalam bahasa terjemahan pada dasarnya berkisar pada dua
persoalan pokok, yaitu: (1) ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan sebuah
gagasan, hal atau barang yang akan diamanatkan, (2) kesesuaian dalam
mempergunakan kata tadi.107 Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan
sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi
pembaca atau pendengar, seperti apa yang diamanatkan oleh al-Quran.
Setelah terjemahan al-Quran diterbitkan dan diedarkan, ternyata
membuahkan kritik dan saran dari pembaca terutama yang berhubungan dengan
bahasa terjemahannya. Sehubungan dengan hal itu, terjemahan al-Quran Depag
RI edisi pertama dilakukan perbaikan sebanyak dua kali, yakni: Pertama, pada
tahun 1989 yang diketuai oleh Drs. H. A. Hafizh Dasuki, MA dengan anggota
beberapa tim ahli. Satu tahun kemudian, tim itu menghasilkan terjemahan al-
Quran yang dicetak oleh Pemerintah Saudi Arabia pada tahun 1990; Kedua, pada
tahun 1998 yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga finalisasi baru
105 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, h. 62. 106 Al-Ibrîz (Kudus: Menara Kudus, t.th) diterbitkan dalam dua edisi, yaitu edisi per-juz
sebanyak 30 jilid dan edisi hard cover sebanyak 3 volume. Tafsir al-Ibrîz ini ditulis dengan huruf Arab pegon dan bahasa Jawa. Makna per-ayat menggunakan sistem makna gandul seperti yang lumrah dipakai oleh kebanyakan pondok pesantren di Jawa, sedangkan untuk tafsirnya ditulis di bagian pinggir (hâmisy).
107 Berkaitan dengan dua hal pokok di atas, maka ada beberapa syarat agar bisa mencapai ketepatan pilihann kata, antara lain: (1) membedakan secara cermat kata-kata yang bermakna denotasi dan konotasi, kata yang hampir bersinonim, kata yang mirip dalam ejaannya; (2) menghindari kata-kata ciptaan sendiri; (3) memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal dan sebagainya. Lihat Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 87.

lxv
terealisir pada tahun 2002 dan menghasilkan terjemahan al-Quran Depag RI edisi
2002.108
Dalam bidang terjemahan teks-teks keagamaan, termasuk teks al-Quran,
terdapat kendala kualitas yang disebabkan oleh tidak adanya dukungan dari segi
pembinaan dan dari segi standarisasi kualitas. Selain itu, kendala sosial juga
menghambat kualitas terjemahan al-Quran dan kendala itu bisa terjadi karena
profesi penerjemah memang belum disadari oleh masyarakat sebagai profesi yang
strategis dan yang harus didukung oleh profesionalisme yang tinggi berbeda
dengan profesi lainnya.
Upaya peningkatan kualitas terjemahan itu dapat diprioritaskan pada
lembaga-lembaga penerjemahan dengan melakukan berbagai penataran (kursus,
lokakarya, seminar, dan diskusi), atau ujian kualifikasi seperti yang dilakukan
oleh Pusat Penerjemahan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas
Indonesia (FIB UI). Bahkan mulai tahun 2005 FIB UI telah membuka program
Linguistik Terapan untuk bidang praktik Penerjemahan sehingga lulusannya akan
memperoleh gelar Magister.109 Berbeda dengan terjemahan teks-teks Arab dan
teks-teks keagamaan, pada umumnya para penerjemahnya memasuki profesinya
secara “tidak sengaja” atau “belajar sendiri” (otodidak). Di antara mereka banyak
yang tidak menempuh pendidikan formal sebagai penerjemah pada tingkat
perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang kualitas
terjemahannya sangat baik.
Kendala kualitas pada penerjemahan al-Quran memang berbeda dengan
penerjemahan teks Arab atau teks asing lainnya, karena penerjemahan al-Quran
108 Adapun penyelesaian edisi 2002 ini dilakukan, ketika Tim itu dipimpin oleh Drs.H.
Fadhal AR. Bafadal, M.Sc dan Tim Ahli yang terdiri dari Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, Prof. K. H. Ali Mustofa Ya’qub, MA., Dr. H. Ali Audah, Prof. Dr. H. Rif’at Syauqi Nawawi, MA., dan H. Junanda P. Syarfuan dengan anggota yang terdiri dari Drs. H. M. Shohib Tahar, Drs. H. Mazmur Sya’roni, Drs. H. M. Syatibi AH, H. Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag., dan Drs. H. Bunyamin Yusuf, M.Ag. Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. v.
109 FIB UI telah menyelenggarakan pendidikan spesialis 1 penerjemahan untuk bahasa Perancis dan Inggris. Lihat, Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 118.

lxvi
tidak hanya berkisar pada tataran teks (the textual level), tetapi pada tataran
berikutnya, yakni tataran referensial. Pada tataran ini membutuhkan penerjemah
yang berkualitas di bidang tafsir. Sebab terjemahan al-Quran acuan maknanya
tidak lepas dari para mufassir. Oleh karena itu, terjemahan al-Quran Depag RI
baik dalam penetapan tim pertama kali terjemahan al-Quran itu disusun hingga
perbaikan berikutnya, tim ahli di bidang tafsir masih tetap dilibatkan seperti Prof.
T.M. Hasbi Ashshiddiqi, Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, M.A., Prof. Dr. H. Said
Agil Husin Al Munawar, M.A., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, Prof. K.H. Ali
Mustofa Ya’qub, M.A., Dr. H. Ali Audah.110
Terjemahan al-Quran pada hakikatnya bukan menerjemahkan al-Quran itu
sendiri, karena itu terjemahan al-Quran bukan duplikat al-Quran. Tetapi
terjemahan al-Quran adalah menerjemahkan makna-maknanya, sehingga
sebagian besar ulama lebih setuju menggunakan istilah terjemahan makna-makna
al-Quran.111 Kemudian, upaya peningkatan kualitas terjemahan al-Quran
dikembalikan pada kualitas individual yang diserahi tugas untuk menerjemahkan
dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana syarat-syarat mufassir,
antara lain: harus memahami secara benar bahasa al-Quran dan bahasa
terjemahan, memahami benar gaya dan karakteristik bahasa al-Quran, versi
terjemahan harus otentik dan sedapat mungkin sesuai dengan bahasa aslinya,
menyempurnakan terjemahan dengan seluruh makna aslinya dan maksud-maksud
yang terkandung di dalamnya.112
Demikian selektifnya untuk menentukan makna yang sepadan dalam
penerjemahan al-Quran, sehingga penunjukkan tim penerjemah al-Quran versi
Departemen Agama juga sangat selektif, terutama penerjemah yang berkompeten
110 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya, h. v. 111 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya, h. iii. Lihat juga, M. Quraish Shihab,
Menabur Pesan Ilahi,( Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 323. 112 Muhammad ‘Ali al-Sâbûniy, al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qurân (Damsyiq: Maktabah al-
Ghazâliy, 1981), h. 207-208.

lxvii
dalam bidang tafsir. Sebab tafsir merupakan referensi utama bagi penetapan
makna-makna al-Quran di luar teks al-Quran itu sendiri.

lxviii
BAB III
STRATEGI TERJEMAHAN AL-QURAN DEPAG RI
Munculnya berbagai macam ragam dan prosedur terjemahan Arab-Indonesia
ditentukan oleh salah satunya adalah jenis teks yang akan diterjemahkan. Kemudian
untuk mengetahui adanya proses dan hasil terjemahan itu dapat diketahui melalui
penelitian. Penelitian mengenai hasil terjemahan sangat penting terutama untuk
menghubungkan teori terjemahan dan prakteknya.113 Kadangkala suatu konsep bisa
dan mudah dideskripsikan dalam uraian atau teori. Akan tetapi, bila sudah berada
dalam tataran praktek, mungkin sekali konsep-konsep ini sulit dibedakan atau bahkan
dikenali secara jelas.
Dalam praktiknya, penerjemah memilih beberapa metode yang sesuai dengan
untuk siapa dan untuk tujuan apa penerjemahan dilakukan. Sebenarnya terjemahan al-
Quran oleh Depag RI juga berorientasi kepada klien (client oriented) dan itu dapat
dibuktikan dengan adanya dua pihak dalam pelaksanaannya, yakni pemerintah selaku
pengambil kebijakan dan para pembaca terjemah yang telah memberikan masukan
dan saran untuk dilakukan perbaikan pada edisi penerbitan berikutnya.114 Sehingga
atas dasar itu, perbaikan-perbaikan pada beberapa penerbitan telah dilakukan,
meskipun sifatnya tidak menyeluruh.
113 Peter Newmark, Textbook of Translation (Oxford: Pergamon Press, 1988), h. 84. 114 Lihat, Sambutan Menteri Agama pada penerbitan al-Quran dan Terjemahnya Depag RI
edisi Tahun 2002, h. iii.

lxix
Berkaitan dengan itu, terjemahan al-Quran Depag RI edisi 2002 memiliki
strategi terjemahan yang mungkin sama atau berbeda dengan strategi terjemahan al-
Quran sebelumnya atau dengan penerjemah al-Quran lainnya, hanya kemudian
strategi terjemahan itu tidak diinventarisir secara terperinci, termasuk juga saran-
saran yang masuk guna perbaikan terjemahan al-Quran edisi baru itu.115
Oleh karena itu, pada bab ini strategi terjemahan al-Quran oleh Depag RI perlu
dilakukan analisis berdasarkan bahasa aslinya kemudian dibandingkan dengan bahasa
Indonesia sebagai Bsa. Sehubungan sistem yang digunakan dalam kedua bahasa
tersebut mengandung perbedaan, maka dalam bab ini, penulis menjelaskan analisis
strategi terjemahannya menurut analisis kontrastif pada strategi struktural. Oleh
karena itu bab ini dimulai dari perbandingan fungsi sintaksis Bsu dan Bsa, kemudian
analisis strategi struktural dan diakhiri dengan analisis strategi semantis.
A. Fungsi Sintaksis Bsu dan Bsa
Terjemahan al-Quran merupakan salah satu jenis teks yang harus
dilakukan suatu analisis. Karena secara ideal teks Bsu dan teks Bsa merupakan
teks-teks yang harus dipersamakan secara fungsional. Semakin mudah dua teks
itu dibandingkan, maka makin mudah pula dalam menentukan strategi
menerjemahkan teks Bsu. Karena itu, analisis yang digunakan adalah analisis
kontrastif (anakon) yang dilakukan melalui dua langkah: Pertama, deskripsi B¹
dan B², dan kedua perbandingan antara keduanya.116 Untuk mengetahui deskripsi
bahasa, maka kategori-kategori bahasa hendaknya dikaji dan dipahami terlebih
dahulu. Pemahaman “kontras”, yang dapat didefinisikan sebagai “perbandingan
dilihat dari latar belakang kesamaannya atau perbedaannya. Dan perbedaan
merupakan variabel yang diperhatikan oleh analisis kontrastif.
115 Ahsin Sakho Muhammad, “Aspek-aspek Penyempurnaan Terjemah dan Tafsir
Departemen Agama ”, Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 3, No. 1 (Januari 2005), h. 157. 116 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa (Bandung: Angkasa, 1992),
h, 133.

lxx
Di antara model analisis kontrastif untuk tujuan komparasi adalah analisis
struktural. Analisis ini berangkat dari asumsi bahwa membandingkan dua bahasa
secara keseluruhan itu tidak mungkin. Karena itu asumsi yang dibangun adalah
bahwa bahasa itu pada hakikatnya “system of system”, misalnya fonologi,
morfologi dan sintaksis. Sintaksis merupakan sistem bahasa yang dibandingkan
secara praktis dalam terjemahan. Makna-makna bahasa apapun dapat dilacak
dengan instrumen ini melalui relasi-relasi struktur bahasa yang ada. Oleh karena
I’jâz-il al`Dalâbukunya dalam ) truksisonk(m zNa-alJurjâniy melalui teori -al, itu
menyimpulkan bahwa bahasa bukanlah semata-mata kumpulan dari kosa kata
melainkan kumpulan dari sistem relasi.117 Penjelasan kata dalam hubungannya
dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu ujaran dibicarakan dalam
sintaksis yang membahas fungsi dan kategori kata dalam bahasa tertentu.
Dalam bahasa Arab, makna sebuah kalimat hanya bisa dipahami melalui
setiap kata dalam , liydFa-Menurut al. hubungan antarkata pada kalimat itu
kalimat memiliki tempat tertentu yang selaras dengan kaidah pembentukan
kalimat.118 Pada posisi itulah sebuah kata menjalankan fungsinya melalui
hubungannya dengan kata lain yang memiliki fungsi dan posisi yang juga lain
dalam kalimat itu. Peran kata dalam kalimat bahasa Arab ditunjukkan oleh i’râb,
, ammahdvokal pendek dan panjang yang dilambangkan dengan tanda yaitu
. `ây dan waw, alif, kasrah, ahhfat
Menurut Badri, struktur sintaksis dalam bahasa Arab terdiri dari enam
tahwîldan trâbi, tâbi’, mukammil, musnad, musnad ilaihyaitu , macam fungsi
dengan berbagai subfungsinya.119
1. Musnad Ilaih
117 ‘Abd al-Qâhir al-Jurjâniy, Dalâ il al-I’jâz (Kairo: ‘Abd al-Salam Harun, t.t.), h. 12. 118 Al-Fadliy, Dirâsah fi al-I’râb (Jeddah: Tihamah, 1984), h. 108. 119 Kamal Badri, Binyah al-Kalimât wa Nazm al-Jumlah Mutabbaqan ‘alâ al-Lughah al-
‘Arabiyyah al-Fushâ- (Jakarta: LIPIA, 1986), h. 26.

lxxi
Musnad Ilaih ialah kata atau frase yang disandari oleh musnad.
Menurut al-Ghalayainiy,120 fungsi ini dapat ditempati oleh beberapa
subfungsi, di antaranya fâ’il, nâ`ib al-fâ’il, mubtada`, ism kâna, ism inna dan
ism lâ. Subfungsi ini tidak jauh berbeda dengan konsep peran di dalam
linguistik umum. Sementara itu, kategori kata yang dapat menempati fungsi
Musnad Ilaih ialah ism atau nomina (N).
Contoh:
�اش��ي )1 (�� =membeli bukuMuhammad آ��ب�
= itu telah dibeliBuku ا���Kباش��ي )2 (
) 3(w�3ا��:��+ terbitMatahari =
= ��A berilmuGuru itu��ا���رسآ�ن )4 (
6���ا�إن )5 ( MahakuasaAllahSungguh =
) 6( FL = di rumah ituseseorangTak ada @7 ا��ارر
Berdasarkan contoh-contoh di atas, semua kata yang bergaris bawah
adalah berkategori ism atau nomina (N) yang menempati fungsi sebagai
Musnad Ilaih atau Subyek (S) dengan subfungsinya sebagai fâ’il (1), nâ`ib al-
fâ’il (2), mubtada (3), ism kâna (4), ism inna (5) dan ism lâ (6).
2. Musnad
Musnad ialah kata atau frase yang menerangkan musnad ilaih dan
yang bersandar padanya. Fungsi ini dapat ditempati oleh fi’l, ism fi’l, khabar,
khabar kâna, khabar inna dan khabar lâ. Kategori yang menempati fungsinya
adalah ism atau nomina (N) dan fi’l atau verba (V).
Contoh:
� ض�]�أآ�م)1 (�� tamumemuliakanMuhammad =
) 2(B�' ! !Kabulkanlah =
120 Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah,
1984), jilid 1, h. 13.

lxxii
. a) 3( w�3ا��:��+ terbitMatahari =
. b ا�&1م�� = jiwamembersihkanPuasa ا��]1س�>
) 4( D��<اآ�ن ا����� atgiMahasiswa itu =
�ا )5 (�� = orang yang suksesSungguh Muhammad ن� �إن
��نF �6ئL ح� )6( penakutTak ada seorang pembicara kebenaran itu =
Berdasarkan contoh-contoh di atas, semua kata yang bergaris bawah
dalam struktur sintaksis adalah berfungsi sebagai Musnad atau Predikat (P)
dengan dua kategori yaitu ism (nomina) dan fi’l (verba). Kategori nomina (N)
terletak pada subfungsi khabar (3a), khabar kâna (4), khabar inna (5) dan
khabar lâ (6), sedangkan kategori verba (V) terletak pada subfungsi fi’l (1),
ism fi’l (2),121 khabar (3b).
3. Mukammil
Mukammil adalah kata atau kelompok kata yang melengkapi informasi
yang disampaikan oleh musnad dan musnad ilaih. Adapun subfungsinya
adalah al-mafâ’il al-khamsah, keterangan keadaan dan keterangan penjelas.
Sedangkan kategorinya adalah ism atau nomina (N).
Contoh:
) 1( � = pintuKhalid membuka ا���ب@�� خ��
) 2( 5�6���6 bangun benar-benarAku =
) 3( 52 = ilmukarena cintaKamu datang @7 ا�:Xر���
= G�� di malam hariAku pergi"�@�ت )4 (
= dengan malambersamaan Aku berjalan وا��L"�ت )5(
= dengan selamatAyahku pulang "����ر M أب7 )6 (
) 7( �3A � = siswaTelah datang sebelas ��� ا �ء أح
121 Ism Fi’l terbagi menjadi tiga: (1) Ism Fi’l Mâdi (perfektif), seperti ت�� artinya ه�
“mustahil”, (2) Ism fi’l mudâri’ (imperfektif), seperti أف artinya “ah” (suatu ungkapan susah), (3) Ism fi’l Amr (imperatif), seperti Zص artinya “diamlah”. Lihat, al-Ghalâyainiy, jilid 1, h. 157.

lxxiii
Dari contoh-contoh yang bergaris bawah di atas, dapat diketahui
bahwa kata-kata tersebut berkategori ism atau nomina (N) yang memberikan
informasi bagi kejelasan musnad ilaih (S) atau musnad (P). Kata yang
bergaris bawah pada (1) menjelaskan (P), (2) menjelaskan (P), (3)
menjelaskan (P), (4) menerangkan (P), (5) menerangkan (S), (6) menerangkan
(S) dan (7) menerangkan (S).
4. Tâbi’
Tâbi’ adalah kata yang menerangkan musnad ilaih (S). Subfungsinya
kategori , mukammilSeperti halnya . aftadan taukîd , badal, na’tterdiri dari
tâbi’ berupa nomina.
Contoh:
) 1( D��<ء ا�� �� = yang giatdatang mahasiswa Telah ا����
= suku( kabilah sebagianTelah sampai( ن&]��وص5 ا�)��� )2 (
) 3(52 = benar datang- benarKamu أن5
= pergi ke AisyahFatimah dan ذه�5 @�+�� و�Aئ3� ا�7 ا���ر"�)4 (
sekolah
Dari beberapa contoh di atas, kata-kata yang bergaris bawah berfungsi
menerangkan musnad ilaih (S) dan musnad (P). Semua kata yang bergaris
bawah dari (1) hingga (4) menerangkan (S) yang berkategori nomina.
Keempat subfungsi di atas, hanya taukid yang bisa berkategori lebih, yaitu
berupa partikel, nomina, verba dan klausa.122
5. Râbit
ialah kata yang berfungsi menghubungkan kata atau kelompok tbiâR
kata yang memiliki fungsi-fungsi di atas. Subfungsinya terdiri dari kata sarana
jarr-harf al )preposisi( ).eksepsi (stitsnâ’i-harf al, )konjungtif( fta‘-harf al,
122 Al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid 3, h. 232.

lxxiv
Contoh:
) 1( 77 -5 أA7"�Kا� kursidi atasIbuku duduk =
= minumlaluAku makan ش�بX�5أآ5 )2 (
(3) ���[�إFص7 ا��-�1ن @7 ا��-� = Orang-orang Islam shalat di
. orang yang sakitkecualimasjid
6. Tahwîl
kalâm (rfungsi mengubah kalimat deklaratif yang be ialah kata wîl hTa
itsbât) menjadi kalimat yang bermakna non deklaratif. Kata-kata yang
berfungsi demikian disebut dengan kata sarana (partikel) yang tidak memiliki
). îfiyzma’nâ wa(tetapi makna fungsi , )ma’nâ mu’jamiy(makna leksikal
Karena itu setiap kata sarana tidak dapat mempunyai makna tersendiri selama
tidak berhubungan dengan kelas kata lainnya, seperti nomina maupun verba.
Perlu diketahui di sini, bahwa kata sarana yang berfungsi sebagai
pengubah kalimat deklaratif harus dibedakan dengan kata sarana yang
berfungsi sebagai penghubung kata, klausa bahkan kalimat. Kata sarana yang
berfungsi sebagai penghubung telah dijelaskan pada nomor sebelumnya yang
dan )fta‘-harf al(kata sarana konjungtif , )Jarr-harf al(terdiri dari preposisi
kata sarana pengecualian (adâh al-Istitsnâ’). Kata sarana yang berfungsi
-alassân menamakannya kata sarana pokok atau H, sebagai penghubung itu
awwilahhMu-Adâh al-al dan kata sarana pengubah atau liyyahsA-Adâh al
bagi kata sarana lainnya yang berfungsi sebagai pengubah makna kalimat
deklaratif menjadi makna kalimat lainnya dinamakan.123
123 Tammâm Hassân, al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma’nâhâ wa Mabnâhâ, (Kairo: ‘Âlam al-
Kutub, 1998), h. 123.

lxxv
yang )partikel(15 n menyebutkan bahwa terdapat âassH, Kemudian
dapat berfungsi sebagai pengubah makna kalimat deklaratif menjadi kalimat
lain, seperti yang terlihat dalam bagan berikut:124
أص1ات
إخ�Fت
�ح أو
ذم
D�:� D�:أداة ا��
���U�"وا �ب� أداة ا���ب� وا��U�"F� ن
إ@&�
ح
X-6 X-(أداة ا�
ش�ط أداة ا��3ط إ�Kن7
7A��� �1 و�F1 ا
أداة ا���اء ءن�ا
أداة ا��� 7 ��ج
B�� 7��أداة ا��
�]��
ض
� أداة ا���[�
أداة ا�:�ض �Aض
7� أداة ا���7 ن
� ا���
إ������
D+
�� وا�&�U� أPم اGب
124 Tammâm Hassân, al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma’nâhâ wa Mabnâhâ, h. 124.

lxxvi
��م ا"�]��م[�"Fأداة ا
� أداة ا���آ�� ��آ�
أداة ا��]7 ن]7
���ی�
إ���ت
Berdasarkan bagan di atas, pada intinya semua kalimat Bsu baik
khabariyyah maupun insyâ`iyyah tersusun atas dua unsur pokok, yaitu S
(musnad ilaih) dan P (musnad) sebagaimana yang telah dikemukakan
sebelumnya. Dua unsur pokok itu yang nantinya akan dimasuki oleh salah satu
kata sarana (partikel) yang selanjutnya, akan mengubah makna kalimat semula.
Misalnya, sebuah kalimat dimasuki kata sarana negatif, seperti � , F , B� , X� , atau ��� maka kalimat tersebut menjadi kalimat negatif (jumlah manfiyyah).
Contohnya: Fون��:� � ��Aأ // Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.
Kalimat yang dimasuki kata sarana asertif (penegas), seperti أن , إن atau
.maka kalimat tersebut menjadi kalimat asertif (jumlah mu`akkadah) إن��
: Contohnyaش:�ئ� ا�إن B // Safa dan Marwah Sesungguhnya ا�&]� وا���وة
bagian dari syi’ar (agama) Allah.
Kalimat yang dimasuki kata-kata tanya, seperti Lه , � , B dan
sebagainya maka kalimat tersebut menjadi kalimat tanya (jumlah istifhâmiyyah).
: ContohnyaL7 وا��&��ه�AP1ي ا�-� orang buta sama dengan Apakah //
orang yang melihat?.
Kalimat perintah (jumlah al-Amr) atau imperatif dapat dinyatakan dengan
ggunakan verba bentuk isa dengan mentau b aâri’ dmudan verba m âlpartikel
: Contohnya. perintah�Z�:" B //orang yang Hendaklah ��]� ذو":� mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Atau bisa juga

lxxvii
: sebagai pengganti verba imperatif sepertidar smadengan B�� إح-�ن�وب��1ا�
atau bisa juga menggunakan kata yang berkategori nomina tetapi fungsinya
sebagai verba imperatif seperti: B�' .
Kalimat larangan (jumlah al-Nahy) dapat dinyatakan dengan partikel F.
Contohnya: وا�-[� F // janganlah berbuat kerusakan.
atau ) d‘Ar-al(berfungsi untuk menyatakan sindiran Kata sarana yang
seperti ) dîhdta-al(anjuran Fأ :Contohnya . XK� Zzا� �[U� 1����ن أن Fأ Apakah //
kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni kamu?.
Kata sarana yang berfungsi untuk menunjukkan kalimat yang menyatakan
angan-angan (al-Tamanniy) antara lain 5��. Contohnya: 7�أو � L= ��� 5�� �� Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah // �6رون
diberikan kepada Karun.
Kemudian, kata sarana yang digunakan untuk menunjukkan kalimat yang
menyatakan harapan (al-Tarajjiy) antara lain L:�. Contohnya: 1ن(z�� XKz:� // agar
kamu bertakwa.
Kemudian partikel yang digunakan untuk kalimat panggilan (al-Nidâ`)
antara lain ��. Contoh: س�zا�� �� .hai manusia // �� أ��
Sedangkan partikel yang digunakan untuk menyatakan makna kalimat
antara lain ) iyyahtjumlah syar(syarat F1� seperti Zzا� ����K� F1�Mengapa //
Allah tidak berbicara dengan kita; dan partikel 1� seperti 1ا(z1�ا وا�' X�zو1� أن //
Dan jika mereka benar-benar beriman dan bertakwa.
Kata sarana yang berfungsi untuk menyatakan kalimat sumpah (al-Qasam)
antara lain و, seperti contoh �&:�وا // Demi masa.

lxxviii
Selanjutnya, kata sarana yang digunakan untuk menyatakan kalimat seru
(al-Nudbah) antara lain وا seperti contoh: واCا� .Wahai Khalid // خ��
Dan partikel yang digunakan untuk menunjukkan makna interjektif (al-
Ta’ajjub) adalah � seperti dalam kalimat ا�-��ء B-أح � // Alangkah indahnya
langit itu?
Melalui penjelasan tentang struktur fungsi B¹, yaitu bahasa Arab secara
deskriptif di atas, maka perlu dilakukan satu perbandingan dengan struktur fungsi
B², yaitu bahasa Indonesia. Perbandingan yang hendak dilakukan harus mengacu
kepada tujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan sebagai instrumen dalam
penentuan strategi terjemahan al-Quran.
Untuk mengetahui perbandingan kedua bahasa itu, penulis memulai
dengan membandingkan unsur-unsur kalimat Bsu dan Bsa. Unsur kalimat adalah
fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim dikenal
dengan sebutan jabatan kata atau peran kata, yaitu subjek (S), predikat (P), objek
(O), pelengkap (Pel) dan keterangan (Ket). Di antara kelima fungsi sintaksis ini
yang merupakan keharusan dalam satu kalimat bahasa Indonesia adalah fungsi S
dan P.125
1. Subjek (S)
Subjek (S) adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh,
sosok (benda), sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok
pembicaraan. Ia diisi oleh sebagian kategori kata atau frasa nominal, klausa
dan frasa verbal.
Contoh:
(a) Ayahku sedang membaca
125 Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2007), h. 126.

lxxix
(b) Meja direktur besar
(c) Yang berpakaian batik dosen saya
(d) Berjalan kaki menyehatkan badan
(e) Membangun jalan layang sangat mahal
Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat (a) sampai (e) adalah S.
Contoh (a) dan (b) adalah S yang diisi oleh kategori kata atau frasa benda
(nomina); (c) adalah S yang diisi oleh kategori klausa; sedangkan (d) dan (e)
adalah S yang diisi oleh frasa verbal.
2. Predikat (P)
Predikat (P) adalah bagian kalimat yang memberi tahu melakukan apa
atau dalam keadaan bagaimana S di dalam suatu kalimat. Satuan bentuk
yang mengisi P dapat berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba
atau ajektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina atau frasa nominal.
Contoh:
(a) Ayam berkokok
(b) Adik sedang tidur siang
(c) Putrinya cantik jelita
(d) Daerah itu dalam keadaan aman
(e) Kucingku belang tiga
(f) Sastro mahasiswa baru
(g) Mobil Pak Hermawan lima
Kata-kata yang dicetak tebal dalam kalimat (a) hingga (g)
memberitahukan S. Hanya saja P yang memberitahukan S pada kalimat (a)
dan (g) berupa kata verbal dan numeral dan selain dua kalimat itu P diisi oleh
frasa atau kelompok kata (sedang tidur siang, cantik jelita, dalam keadaan
aman, belang tiga, mahasiswa baru).

lxxx
3. Objek (O)
Objek (O) adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada
umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Letak O selalu di
belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib
adanya O.
Contoh:
(a) Petani menimbang ...
(b) Arsitek merancang ....
(c) Juru masak menggoreng...
Verba transitif menimbang, merancang, menggoreng pada contoh di
atas adalah P yang menuntut untuk dilengkapi. Adapun unsur yang akan
melengkapi P bagi ketiga kalimat di atas itulah yang dinamakan objek.
4. Pelengkap (Pel)
Pelengkap (Pel) atau komplemen adalah bagian kalimat yang
melengkapi P. Letak Pel umumnya di belakang P yang berupa verba. Pel
sama dengan O dalam posisinya dalam kalimat juga kategori kata yang
mengisinya, yaitu nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun demikian
keduanya tetap ada perbedaan.
Contoh:
(a) Pimpinan upacara // membacakan // Pancasila
S P O
(b) Banyak partai politik // berlandaskan // Pancasila
S P Pel
Kedua kalimat tersebut dapat dibedakan dengan cara kalimat itu
dibuat kalimat pasif, sehingga kalimat (a) menjadi Pancasila dibacakan oleh
Pimpinan upacara dan kalimat (b) menjadi Pancasila dilandasi oleh banyak

lxxxi
partai politik. Kalimat (b) yang mengandung Pel. Itu tidak bisa diubah
menjadi kalimat pasif, kalaupun bisa kalimat tersebut termasuk kalimat yang
tidak gramatikal.
Di samping itu, Pel tidak selalu berada di belakang O, jika kalimat itu
sudah memenuhi pola yang lengkap, yaitu pola S-P-O-Pel.
5. Keterangan (Ket)
Keterangan (Ket) adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai
hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Ket dapat berfungsi menerangkan
S, P, O dan Pel. Posisinya bersifat manasuka, dapat di awal, di tengah, atau di
akhir kalimat. Kategori yang dapat diisikan pada unsur ini adalah frasa
nominal, frasa preposisional, adverbia atau klausa.
Berdasarkan maknanya dalam kalimat, para ahli membagi Ket atas
sembilan macam, yaitu: Ket. Tempat (dari rumah), Ket. Waktu (sekarang),
Ket. Alat (dengan gunting), Ket. Tujuan (demi orang tuanya), Ket. Cara
(dengan hati-hati), Ket. Penyerta (dengan teman-temannya), Ket. Similatif (
(bagaikan pengacara), Ket. Penyebab (karena malas belajar) dan Ket.
Kesalingan (satu sama lain).126
Berdasarkan deskripsi fungsi sintaksis dua bahasa, yaitu Bsu dan Bsa,
maka dapat diketahui perbandingan keduanya sebagaimana yang tertulis
dalam tabel berikut:
Tabel 1
Perbandingan Fungsi Sintaksis Bsu dan Bsa
Fungsi Sintaksis Bsu Fungsi Sintaksis BSa
126 Lihat, Hasan Alwi (Ed.), Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2003), h. 366.

lxxxii
Fungsi dan Sub Kategori Fungsi Kategori
(1) (2) (3) (4) Musnad Ilaih:
fâ’il, nâ ib al-fâ’il, mubtada ,
ism kâna, ism inna dan ism lâ
- Ism
-Murakkab:
, yfiâdi, ywasfi
ismiy (yliûsmau
dan harfiy)
Subjek (S)
- nomina
- Frasa nominal
- Klausa
- Frasa Verbal
(1) (2) (3) (4)
Musnad:
fi’l, ism fi’l, khabar, khabar
kâna, khabar inna dan
khabar lâ
- Ism
- fi’l
- Murakkab
Predikat (P)
- kata (nominal,
ajektiva, verbal)
- frasa
Mukammil:
l âh, khamsah-mafâ’il al-al
(keterangan keadaan), tamyîz
(keterangan penjelas)
Ism Objek (O) - nomina
- frasa nominal
- klausa
Tabi:
afta‘dan taukîd , badal, na’t
Ism
Pelengkap (Pel) - nomina
- frasa nominal
- klausa
Rabit:
ngan waktu dan ketera(arf Z
tempat), harf al-Jarr
)preposisi( f t‘A-harf al,
(konjungtif), harf al-Istitsnâ`
(eksepsi)
Keterangan
(Ket)
- frasa nominal
-frasa preposisional
- adverbia
- klausa
Berdasarkan tabel di atas, maka fungsi sintaksis Bsu dapat dianalogikan
bahwa fâ’il, nâ`ib al-fâ’il, mubtada`, ism kâna, ism inna dan ism lâ menjadi (S)
dalam Bsa , fi’l, ism fi’l, khabar, khabar kâna, khabar inna dan khabar lâ

lxxxiii
menjadi (P), maf’ûl bih menjadi (O) dan selain itu bisa masuk pada (Pel) atau
(Ket).
Sedangkan kategori Bsu dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori,
Dan yang kategori yang terakhir ini .lifâkhaw-al dant âdawâ, arfZ, fi’l, ismyaitu
tidak dimasukkan ke dalam empat kategori sebelumnya.127 Karena itu kategori
Bsu dan Bsa dapat diperbandingkan melalui tabel berikut:
Tabel 2
Perbandingan Kategori Bsu dan Bsa
Bsu BSa
Kategori
dan Rumpun
Ciri Kategori
dan Rumpun
Ciri
(1) (2) (3) (4)
Ism :
Nama, sifat dan
kata ganti
Dapat dibubuhi tanda
penunjuk jumlah, jenis,
definitif, vokal rangkap
dan preposisi
Nomina :
Nomina,
pronomina,
numeralia,
Dapat diingkari dengan
kata bukan, diikuti oleh
gabungan kata yang+
kata sifat atau yang
sangat + kata sifat
Fi’l :
Verba perfektif,
impefektif dan
imperatif
Dapat diubah menurut
waktu dan aspek
melalui afiksasi
Verba :
Verba asal, verba
turunan, verba
reduplikasi, verba
majemuk, verba
berpreposisi
Dapat diberi aspek
waktu (akan, sedang,
telah), dapat diingkari
dengan kata tidak, dapat
diikuti oleh gabungan
kata dengan+ nomina
atau sifat
: arfZ
Zarf penunjuk
waktu dan tempat
Tidak dapat diubah
dengan proses
morfologis
Adverbia:
Memberi keterangan
pada verba, ajektiva,
nomina predikatif atau
kalimat
Adâwât : Tidak mempunyai arti Kata Sarana: Tidak mempunyai arti
127 Lihat, Kamal Badri, Binyah al-Kalimât wa Nazm al-Jumlah Mutabbaqan ‘alâ al-Lughah
al-‘Arabiyyah al-Fushâ, h. 10-25.

lxxxiv
Kata konjungtif
dan transformator
leksikal, kecuali
berkaitan dengan kata
lain
Kata depan, kata
sambung, kata
seru, kata sandang
dan partikel
leksikal, kecuali
berkaitan dengan kata
lain
Dari semua kategori di atas, ada satu kategori Bsa yang tidak bisa
dibandingkan dengan lima kategori Bsu, yaitu kata sifat. Kata sifat Bsa memiliki
ciri: (1) dapat diberi kata keterangan pembanding seperti lebih, kurang dan
paling, (2) dapat diberi kata keterangan penguat seperti sangat, amat, benar dan
terlalu dan (3) dapat diingkari dengan kata ingkar tidak atau bukan.128 Meskipun
demikian, karena fungsinya untuk menerangkan sifat, keadaan, watak, tabiat
orang atau suatu benda, maka kategori ini dapat dipadankan dengan kategori ism
dengan rumpun sifat.
B. Strategi Struktural
Ragam atau metode terjemahan merupakan petunjuk teknis yang masih
umum. Sedangkan prinsip-prinsip terjemahan merupakan acuan umum. Semuanya
itu hendaknya dipertimbangkan pada level keseluruhan teks atau wacana
terjemahan.129
128 Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 80. 129 Bentuk-bentuk terjemahan berdasarkan jenis teks yang diterjemahkannya, menurut ‘Abd
al-Ghaniy dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk, al-Tarjamah al-Adabiyyah, al-Tarjamah al-Sya’biyyah, al-Tarjamah al-‘Ilmiyyah, atau disebut juga al-Tarjamah al-Sinâ’iyyah wa al-Taqniyyah, al-Tarjamah al-‘Âdiyyah. Lihat, ‘Abd al-Ghaniy ‘Abd al-Rahmân Muhammad, Dirâsah fi Fanni al-Ta’rîb wa al-Tarjamah (Ttp, t.p. t.t.), h. 72-74. Al-Jailâniy menambahkan dua bentuk terjemahan, yaitu al-Tarjamah al-Âliyah dan al-Tarjamah al-Qur’âniyyah. Lihat, Ibrâhîm Badâwi al-Jailâniy, ‘Ilm al-Tarjamah wa Fadlu al-Lughah al-‘Arabiyyah ‘alâ al-Lughât (Kairo: al-Maktab al-‘Arabiyy li al-Ma’ârif, 1997), h. 70-74. Juga Salihen Moentaha mengelompokkan jenis teks ke dalam lima ragam, yaitu: 1) ragam sastra dengan subragam: prosa, puisi dan drama, 2) jurnalistik dengan subragam: oratoria, esai dan artikel, 3) koran/ surat kabar dengan subragam: editorial, headline, iklan, pengumuman, 4) ilmiah dengan subragam: rangkaian ujaran, pola kalimat, nukilan, catatan kaki (footnote) dan 5) dokumen resmi dengan subragam: dokumen undang-undang, dokumen militer, diplomatik dan bisnis. Lihat, Salihan Moentaha, Bahasa dan Terjemahan (Bekasi Timur, Kesaint Blanc, 2006), h. 30.

lxxxv
Tuntunan teknis untuk menerjemahkan kata, kelompok kata atau kalimat-
kalimat dalam suatu teks atau wacana disebut dengan strategi terjemahan. Dalam
beberapa literatur terjemahan, sebagian pakar menggunakan istilah prosedur
terjemahan (translation procedures) dan teknik terjemahan. Ada dua macam
strategi dalam terjemahan, yaitu strategi yang berkenaan dengan struktur kalimat
(strategi struktural) dan strategi yang berkaitan dengan makna (strategi semantis).
Strategi yang dilakukan dalam terjemahan Bsu yang berkaitan dengan
struktur kalimat adalah transposisi. Newmark mengemukakan bahwa transposisi
merupakan prosedur atau strategi terjemahan yang berkaitan dengan aspek
gramatikal dari BSu ke dalam BSa.130 Sementara Kridalaksana menganggap
transposisi sebagai proses atau hasil perubahan fungsi atau kelas kata tanpa
penambahan apa-apa.131 Dengan demikian, yang dimaksud transposisi dalam
uraian di sini ialah bentuk-bentuk perubahan fungsi sintaksis dan kategori kata
dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Adanya persamaan dan perbedaan fungsi dan kategori sintaksis Bsu dan
Bsa telah menjadi acuan utama dalam menentukan pola-pola transposisi dalam
strategi terjemahan. Untuk menunjukkan kesamaan pola Bsu dan Bsa, penulis
menggunakan tanda = (sama dengan). Sedangkan untuk menunjukkan perbedaan
Bsu dan Bsa yang kemudian dilakukan pengalihan fungsi dan kategori, penulis
menggunakan tanda →.
Sehubungan data yang hendak dianalisis adalah terjemahan al-Quran
Depag RI, maka pola-pola kalimat Bsu yang penulis ambil adalah surah al-
Baqarah, kemudian penulis bandingkan melalui persamaan dan perbedaan
dengan Bsa. Dari sinilah akan nampak strategi terjemahan strukturalnya baik
melalui padanan maupun melalui transposisi atau pengalihan fungsi dan kategori.
130 Newmark, Textbook of Translation, h. 85. 131 Kridalaksana, Kamus Linguistik, h. 220.

lxxxvi
1. Padanan Fungsi dan Kategori dalam Strategi Terjemahan
Padanan fungsi dalam terjemahan sangat berpengaruh terhadap
kemudahan dalam menerjemahkan teks Bsu. Sehingga, jika dilihat dari
bentuk dan formalnya, terjemahan yang muncul seperti terjemahan harfiyah
atau kata demi kata. Adapun padanan fungsi yang penulis peroleh dari
terjemahan al-Quran Depag RI adalah sebagai berikut:
a. S + P = S + P
�:�1ن أنX� و (1)
P (Fi+Fa) S (I) (R)
// mengetahui// kamu // Padahal
(KS) S (N) P (V)
(2) � Zzود ا�� ح
P (M) S (I)
ketentuan // Itu // Allah
S (N) P (FN)
Pola kalimat di atas adalah termasuk kalimat dasar yang paling
dapat rMeskipun te. P+ yang terdiri dari S)ahtîsjumlah ba (sederhana
perbedaan dalam kategorinya, Bsu tetap diterjemahkan seperti pola Bsa.
Strategi ini lazim digunakan untuk menerjemahkan Bsu yang digolongkan
pada struktur jumlah ismiyyah, yaitu klausa atau kalimat yang terdiri dari
mubtada` dan khabar baik khabar tunggal seperti contoh (2) pada ayat
187 dan 229 surah al-Baqarah, maupun khabar non tunggal seperti contoh
(1) pada surah yang sama ayat 22 dalam bentuk klausa dengan dua
kategori, yaitu fi’l dan ism.132 Pola Bsu S+P sepadan dengan pola S+P
132 Ism dalam klausa ini perannya sebagai fâ’il (pelaku). Pelakunya berupa pronomina
eksplisit (damîr bâriz).

lxxxvii
Bsa, karena Bsa hanya memiliki satu pola, yaitu S+P, baik dalam kalimat
tunggal maupun kalimat majemuk.
b. S + P + O = S + P + O
� ا��]- �:X ا�Zz و O (I) P (Fi+S) S(I) R
// orang yang berbuat kerusakan // mengetahui // Allah
S (N) P (V) O (F)
Contoh ayat di atas terdapat pada ayat 220 surah al-Baqarah. Pola
kalimat di atas dapat digolongkan sebagai kalimat lengkap yang terdiri
dari S+P+O dengan struktur kalimat dengan pola jumlah ismiyyah.
Predikat Bsu dan Bsa sama yaitu berupa verba transitif aktif, sehingga
susunan terjemahannya sepadan, yaitu S+P+O. Perbedaan keduanya
terletak pada predikat, yakni predikat Bsu mengandung S implisit berupa
pronomina persona ketiga tunggal yang mengacu kepada S, sedangkan
Bsa tidak menyatakannya.
c. P + S = P + S
Zz� �ب و ا��3�قU��ا S (N) P (F)
dan barat// timur // lah -Allah// Milik
P (V) S (N)
Contoh di atas terdapat pada ayat 142 surah al-Baqarah. Pola Bsu
dan Bsa di atas sama, yakni P+S. Kalimat yang mengikuti pola inilah yang
kemudian dinamakan kalimat inversi.133 Perbedaan keduanya terletak pada
P dan S, yakni P Bsu menggunakan frasa partikel yang terdiri dari partikel
133 Kalimat inversi adalah kalimat yang P-nya mendahului S. Urutan P-S dipakai untuk
penekanan atau ketegasan makna. Kata atau frasa tertentu yang mendahuluinya akan menjadi kata kunci yang mempengaruhi makna dalam hal menimbulkan kesan tertentu. Contoh: Telah meninggal si A pada jam 22.00 di rumah sakit. Lihat, Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h, 146.

lxxxviii
lâm dan nomina Allâh; sedangkan P Bsa menggunakan verba milik.
Sebenarnya antara partikel lâm dengan verba milik terdapat kesesuaian
makna, karena partikel lâm pada contoh di atas mengandung makna
kepemilikan (li al-milk).134 Kemudian, S Bsu menempati pada kata al-
Masyriq sedangkan S Bsa menempati pada kata Allah. Untuk
menunjukkan ketegasan makna dalam kalimat inversi di atas, maka
partikel –lah diletakkan pada P Bsu yang terdiri dari partikel dan nomina.
Contoh yang sama juga ditemukan pada ayat 284 surah al-Baqarah berikut
ini: 7 ا��رض@ �� @7 ا�-z��وات و Zz� // Milik Allah-lah apa yang ada
di langit dan apa yang ada di bumi.
2. Transposisi Fungsi dan Transformasi Kategori sebagai Strategi Terjemahan
Penelitian tentang transposisi melalui linguistik komparatif dan
kontrastif akan mempermudah penerjemah dalam memilih alternatif struktur
Bsa yang paling tepat dalam mengungkapkan sebuah makna. Prosedur
transposisi menjadi lebih penting lagi karena strukturlah yang akan mewadahi
padanan-padanan yang dihasilkan oleh prosedur atau strategi terjemahan.
Terjemah al-Quran Depag RI juga sebagai karya terjemahan
menggunakan prosedur itu. Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka
terdapat tiga strategi transposisi dengan pola-pola sebagai berikut:
a. P + S + O → S + P + O
1�ا و ا�Zz ���د1Aن' B� zا� O2 (R) O (I) S (Fa)+P (Fi)
//orang yang beriman-orang// dan // Allah// menipu // Mereka
S (N) P (V) O1 (N) KS O2 (FV)
134 Lihat, Muhammad ‘Ali Sultâniy, al-Adawât al-Nahwiyyah wa Ma’ânîhâ fî al-Qurân al-
Karîm (Suriah: Dâr al-‘Asmâ`, 2000), h. 13 dan Al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid 3, h. 183.

lxxxix
Pola kalimat Bsu (P+S+O) diubah fungsinya dalam Bsa menjadi
(S+P+O). Pola (P+S+O) dalam bahasa Arab dinamakan dengan jumlah
fi’liyyah, yaitu stuktur kalimat yang terdiri dari fi’l dan fa’il. Pengalihan
fungsi tersebut dimaksudkan supaya terjemahan berterima maksud yang
dikandungnya juga berterima dengan pembaca Bsa. Pengalihan P+S+O →
S+P+O ini merupakan suatu keharusan dalam terjemahan, apabila
terjemahan itu tidak sesuai dengan makna atau maksud yang dikandung
dalam teks Bsu. Seperti terjemahan ayat di atas: mereka menipu Allah jika
terjemahan ini dipadankan dengan teks Bsu-nya maka bunyi
terjemahannya menipu mereka Allah. Terjemahan semacam ini mungkin
berterima oleh pembaca Bsa dengan menggunakan intonasi: menipu
mereka, Allah, sehingga makna teks itu “Allah-lah yang menipu mereka”.
Dan ini berlawanan dengan makna teks Bsu, yaitu mereka menipu Allah.
b. P + S → P
ن:�7� اذآ�وا (1)O (FN) S (Fa)+ P (Fi)
// Ku-nikmat// Ingatlah
P O (FN)
(2) BK"أن5 ا
S S + P
// engkau // Tinggallah
P S
Pola kalimat Bsu (P+S) diubah fungsinya dalam Bsa menjadi (P).
Pengalihan fungsi itu dilakukan pada kalimat verbal yang menggunakan
verba imperatif (fi’l al-amr). Setiap verba imperatif Bsu mengandung S
persona kedua, baik persona tunggal, dual maupun jamak. S persona

xc
kedua jamak seperti pada ayat 45, yaitu contoh (1) S dieksplisitkan, dan
persona kedua tunggal seperti pada ayat 35, yaitu contoh (2) S
diimplisitkan.
Persona kedua baik tunggal, dual maupun jamak dalam kalimat
verbal imperatif harus dihilangkan dalam Bsa, karena Bsa tidak
memerlukan kehadiran S.135 Sementara contoh (2) terdapat S secara
eksplisit, yaitu engkau tetap dan harus diterjemahkan dalam Bsa, karena
apabila dalam sebuah kalimat atau klausa terdapat dua S, yang satu
eksplisit dan yang lainnya implisit maka S implisit yang harus
dihilangkan. Dan inilah yang menurut al-Dîdâwiy disebut al-hadzf.136
Karena itu, S engkau yang diterjemahkan dalam Bsa adalah S eksplisit
dari kata 5أن .
c. P + O + S → S + P + O
�� Xاخ آ � Zzا� S O P (Fi) KS
//kamu// menghukum // tidak // Allah
S KS P O
Pola Bsu ini, sebagaimana yang terdapat pada ayat 225 surah al-
Baqarah merupakan pola yang lazim dalam Bsu, dengan syarat O (maf’ûl
bih) berupa pronomina persona yang bergandengan dengan verba.137
Namun, pola tersebut sebaliknya tidak lazim dalam Bsa. Hal itu
disebabkan oleh letak O sebelum S, padahal O dalam Bsa selalu
diletakkan setelah P, jika P berupa verba transitif, yaitu verba yang
135 Anton M. Moeliono (ed.), Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1988), h. 285. 136 Muhammad al-Dîdâwiy, ‘Ilm al-Tarjamah baina al-Nazariyyah wa al-Tatbîqiyyah (Tunis:
Dâr al-Ma’ârif wa al-Nasyr, 1992), h. 106. 137 Muhammad Hamâsah ‘Abd al-Latîf, dkk., al-Nahw al-Asâsiy (Kairo: Dâr al-Fikr al-
‘Arabiy, 1997), h. 322.

xci
menuntut wajib hadirnya O.138 Sementara kata sarana negasi selalu
terletak sebelum verba baik dalam Bsu maupun Bsa. Pola demikian dan
strategi terjemahan yang sama juga ditemukan dalam ayat lain, seperti
pada ayat 204 dalam surah yang sama: 7@ Z�16 ��:� BوB ا���zس Dan di antara manusia ada yang pembicaraanya tentang // ا����ة ا���ن��
kehidupan dunia mengagumkan kepadamu. Bahkan ada pola Bsu yang
kedua objeknya didahulukan, sementara subjeknya diakhirkan, tetapi pola
terjemahannya yang digunakan adalah S+P+O+O, seperti pada ayat 137
dalam surah yang sama: Zzا� X�K�[K�-@// maka Allah mencukupkan
engkau terhadap mereka.
d. P + S + Ket + O → S + P + O + Ket
ا���� بXK @6��� وإذ O Ket P + S (Fi+Fa) KS
//untukmu// laut //membelah // Kami//ketika) Ingatlah(Dan
S P O Ket
Contoh di atas adalah ayat 50 surah al-Baqarah. Menurut pola ini,
konstruksi Ket dalam Bsu maupun Bsa tidak ada perbedaan, sebab Ket
dapat berfungsi menerangkan S, P, O dan Pel serta posisinya bersifat
manasuka, dapat di awal, di tengah atau di akhir kalimat. Namun
demikian, ketika Bsu menggunakan pola di atas dengan posisi Ket terletak
sebelum O, pola tersebut dialihkan dalam Bsa sehingga O terletak
sebelum Ket. Sebab letak O selalu di belakang P jika V di dalam kalimat
itu verba intransitif, yaitu verba yang menuntut keberadaan O seperti
contoh di atas. Demikian pula seperti contoh-contoh yang terletak di
dalam surah al-Baqarah ayat 63: ا�>�1ر XK61@ ��:@ور // Dan Kami angkat
138 Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 129.

xcii
gunung (Sinai) di atasmu; dan 59: B@�نA ���b� ا� z�B \�1ا ر bا -Maka Kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang // ا�-z��ء
orang yang zalim itu.
e. S + (P (aktif) + O + S) → S + P (pasif)
(1) B� zإذا ا� X�&��� أص�ب�
)Fa (S +)I (O )Fi (P KS )N (S
Klausa
// musibah// ditimpa // yang apabila // orang -Orang
S (N) (KS) P (V) O (N)
B خ�� U]�ة و 16ل :�وف (2) �6��� ص:��� أذى
)Fa(S )Fi (P) + I(O S )KS( P )Pel( )R( )Pel( S
Klausa
Perkataan yang baik // dan // pemberian maaf // lebih baik // daripada
S (FN) KS Pel. P KS
//tindakan yang menyakiti// yang diiringi // sedekah
S (N) P (V) Pel. (FN)
Pola kalimat Bsu dan Bsa seperti di atas terdapat perbedaan dari segi
jumlah fungsi, yaitu Bsu terdiri dari dua fungsi sedangkan Bsa tiga fungsi.
Sebenarnya dua pola Bsu itu adalah pola inti S+P. Hanya pada P tersebut
terdiri atas klausa verbal sehingga menjadi S+(P(aktif)+O+S). Pola yang
demikian ini dalam Bsu disyaratkan antara S dan P ada relasi makna atau
) ominapron (r îamdyaitu berupa , kata yang menghubungkan keduanya
yang terdapat pada fungsi O. Pola P(aktif)+O+S) bisa berfungsi sebagai P
atau tâbi’ (Pel). Lihat contoh berikut:
آ��ب اش��اC أب7 ه ا)1 (

xciii
P S
أ�]Z ا��آ�1ر A�� ه ا ا���Kب (2)
P S
Dua contoh kalimat di atas jika diterjemahkan menurut struktur
Bsu, maka terjemahannya sebagai berikut:
(1) Ini kitab yang membelinya ayahku.
(2) Kitab ini mengarangnya Dr. Umar.
Demikian pula terjemahan ayat di atas, terjemahannya sebagai
berikut:
(1) orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah
(2) ...daripada sedekah yang mengiringinya tindakan yang
menyakiti.
Terjemahan yang mengikuti pola Bsu di atas menurut Bsa termasuk
kalimat yang tidak efektif, karena kejelasan informasi yang diperoleh
tidak tepat. Padahal kalimat efektif139 harus mampu mewakili penulis atau
penutur sehingga pembaca memahami informasi atau pikiran tersebut
dengan mudah, jelas dan lengkap. Di antara kriteria kalimat efektif adalah
menggunakan bentuk variasi aktif-pasif.140
Contoh lain dalam surah al-Baqarah yang terjemahannya sama
dengan cara alih fungsi S + P (aktif) + O + S → S + P (pasif) adalah pada
ayat 265: Lواب �� �z� ب�ب1ة أص�ب L=�آ // Seperti kebun yang terletak di
139 Finoza menjelaskan bahwa kalimat efektif harus memenuhi paling tidak enam syarat, yaitu
adanya (1) kesatuan, (2) kepaduan, (3) keparalelan, (4) ketepatan, (5) kehematan dan (6) kelogisan. Lihat, Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 147.
140 Kalimat efektif juga mengutamakan variasi bentuk pengungkapan atau gaya kalimatnya. Variasi itu dapat dicapai dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, variasi aktif-pasif dan variasi panjang pendek. Lihat, Mustakim, Membina Kemampuan Berbahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 107.

xciv
dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat; dan ayat 266 dalam surah
yang sama: ر�&Aإ �� .Lalu kebun itu ditiup angin keras // @�ص�ب
Jadi transposisi di sini digunakan untuk menciptakan kalimat efektif,
sehingga terjemahan al-Quran berterima dengan struktur Bsa juga
berterima oleh pembacanya.
f. P + S → S + P + O
�� �LK� و (1) و
S (I) P (R+M) (R)
//kiblat // mempunyai // setiap umat // Dan
(KS) S (F) P (K) O (N)
�X و )2( � X��اب أ A S (M) P (R+I) (R)
// azab yang pedih // mendapat // mereka / /Dan
KS S (N) P (V) O (F)
Kedua contoh di atas dalam Bsu dinamakan konstruksi taqdîm dan
ta`khîr (anastrophe).141 Yang dimaksud taqdîm dan ta`khîr di sini adalah
mendahulukan khabar (P) dan mengakhirkan mubtada (S).142 Pengalihan
fungsi tersebut dikarenakan P pada Bsu mengandung frasa partikel, yakni
partikel lâm yang juga termasuk hurûf al-ma’ânî (huruf-huruf bermakna).
Dan di antara makna yang terkandung di dalam huruf lâm adalah
kepemilikan dab semi kepemilikan (syibh al-milk).143 Jika terjemahan itu
141 Taqdim dan ta`khir adalah mengubah posisi kata dalam klausa atau kalimat dengan
menyalahi aturan yang baku karena tujuan retorikal. Muhammad Ali al-Khuli, A Dictionary of Theoretical Linguistics (Beirut: Librairie du Liban, 1982), h. 16.
142 Khabar (P) wajib didahulukan daripada mubtada (S) jika memenuhi empat syarat: (1) mubtada berasal dari ism nakirah (nomina indefinitif), (2) khabar diambil dari ism istifhâm (nomina interogatif) (3) mubtada memiliki damîr yang merujuk kepada khabar dan (4) makna maupun lafal khabar terkandung di dalam mubtada . Lihat, Al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid 2, h. 268.
143 Partikel lâm cenderung mengandung makna li al-milk, yaitu huruf lâm yang terletak di antara dua nomina yang konkrit. Contoh: � atau mengandung makna (rumah itu milik Khalid) ا��ار ����

xcv
mengacu pada terjemahan harfiyah, tentunya tidak ada pengalihan fungsi.
Namun terjemahan seperti contoh ayat di atas merupakan terjemahan
semantis, sehingga pengalihan fungsi dilakukan untuk menghasilkan Bsa
yang luwes. Makna partikel lâm dapat dialihkan kepada makna kata verbal
seperti mempunyai, memperoleh, mendapat dan berhak.
Contoh lainya yang sejenis dalam surah al-Baqarah seperti pada ayat
Dan di akhirat dia tidak memperoleh // و� Z� @7 ا��خ�ة B خGق :200
bagian apapun; ayat 277: X�� رب��A X�ه �X أ� // Mereka memperoleh
pahala di sisi Tuhannya; ayat 286: 5�-آ � ��� // Dia mendapat
(pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannnya; ayat 279: رؤوس XK@ XK�1ا .Maka kamu berhak atas pokok hartamu // أ
g. KS + S + KS + P + → S + KS + P
�1���ن إ��z هX إن وP (Fi+Fa) KS S KS
//adug-menduga// hanya // mereka // Dan
KS S KS P
dalam 144 rsqadi atas merupakan bentuk 78 pada ayat sepertiPola
kajian retorika Bahasa Arab. Di antara kata sarana yang dapat membentuk
kalimat seperti di atas adalah kata sarana negasi seperti إن dan kata sarana
eksepsi Fإ. Kata hanya dalam terjemahan Bsa merupakan makna
gramatikal dari dua kata sarana yang tertulis dalam teks Bsu, yaitu إن dan
syibh al-milk (semi kepemilikan), yakni ikhtisâs, yaitu partikel lâm yang terletak sebelum atau di antara dua nomina konkrit, seperti ��b� خPا dan istihqâq, yaitu partikel lâm yang terletak di antara nomina abstrak dan konkrit, seperti � � :Lihat, Sanâ Jihâd, Mu’jam al-Tâlib wa al-Kâtib (Beirut .ا���Maktabah Lubnân Nâsyirûn, 1997), h. 102.
144 Qasr adalah mengkhususkan satu hal terhadap hal lainnya dengan menggunakan cara tertentu. Ada empat cara untuk membentuk kalimat dengan makna qasr, yaitu 1) kata sarana negasi dan eksepsi, 2) kata sarana empasis ��3 , إن) kata sarana konjungtif ( F ,Lب ,BK� ) dan 4) mendahulukan lafaz yang seharusnya diakhirkan. Lihat, ‘Ali al-Jârim dan Mustafâ Amîn, al-Balâghah al-Wâdihah. Penerjemah Mujiyo Nurkholis, dkk. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 307.

xcvi
Fإ. Jadi, penggunaan kata itu merupakan gaya bahasa yang ditampilkan
Bsa sebagai padanan gramatikal Bsu. Contoh kalimat serupa yang
menggunakan cara itu juga diterjemahkan oleh terjemahan al-Quran
Depag RI dengan terjemahan yang sama pada contoh ayat 144 surah Âli
‘Imrân berikut ini:
� إ��z ر"1لz�� � و
Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul.
Kemudian strategi pengalihan atau perubahan dalam terjemahan al-
Quran Depag RI tidak hanya dilakukan pada tataran fungsi sintaksis Bsu dan
Bsa, namun kategori juga bisa dilakukan untuk mendapatkan terjemahan yang
adekuat. Pengalihan dari satu kategori ke kategori lainnya disebut dengan
tranformasi. Sebagaimana yang dikemukakan di depan bahwa kategori Bsu
dan Bsa dapat dipadankan untuk menjadi instrumen analisis kategori dalam
strategi terjemahan al-Quran.
Adapun transformasi yang berkaitan dengan kata adalah kategori.
Kategori Bsu yang dapat dipadankan dengan Bsa adalah ism (I) = nomina
(N), fi’l (Fi) = verba (V), murakkab (M) = frasa (F), jumlah (J) = klausa (K)
Untuk memudahkan ). KS( kata sarana = )R( tRâbiunsur -unsurdan
pemahaman dalam perubahan kategori nanti, penulis cenderung menggunakan
istilah kategori Bsa, yaitu N, V, F, K, KS. Dan kategori yang mungkin
berkembang adalah F menjadi FN, FV.
Di antara sekian kategori yang berubah menurut terjemahan al-Quran
Depag RI adalah sebagai berikut:
1. N → F
Nomina Bsu yang mengandung makna peran (pelaku) biasanya
ditambahkan vokal-vokal pada keseluruhan kata dasarnya, seperti ism al-

xcvii
Fâ’il. Penambahan seperti itu dinamakan transfiks yang banyak
ditemukan dalam Bsu. Terjemahan yang paling mudah dilakukan pada
bentuk kata yang mengandung makna peran adalah menambahkan
imbuhan pe- pada awal kata dasarnya dengan cara morfologis. Contohnya
kâtib diterjemahkan penulis. Namun tidak semua kata dapat diterjemahkan
dengan cara itu. Seperti contoh berikut ini:
A �B�(z�� = kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa� ا�ح)
X��إن آ B�6ص�د = jika kamu orang-orang yang benar
Munculnya kesulitan untuk menerjemahkan kata-kata seperti yang
bergaris bawah itu dengan cara penambahan pe-, maka perlu dilakukan
dengan cara mengubah bentuk dari N ke F. Untuk menandai bentuk kata
indikatif aktif, maka Bsa menambahkannya dengan imbuhan ber- atau
imbuhan lainnya yang sama maknanya seperti me-. Sehubungan kata ini
nomina ajektival, maka Bsa menerjemahkannya dengan orang yang
dengan makna acuannya nama atau benda. Kemudian, untuk menunjukkan
bahwa N Bsu itu bentuk jamak, digunakanlah bentuk reduplikasi145 dalam
terjemahan Bsa-nya, seperti orang-orang. Frasa yang berlaku pada kedua
contoh di atas adalah frasa nominal (FN).
Atau N Bsu yang mengandung makna ajektif (sifat), maka N Bsu
bisa dialihkan kepada F juga, hanya saja bukan frasa nominal melainkan
frasa artikel (FA). Sedangkan N yang mengandung makna sifat-sifat Allah
dialihkan menjadi frasa verbal (FV). Contoh:
= yang pedihazab أAX�� اب
A X��A = azab yang berat اب
145 Reduplikasi ialah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan
(seperti meja-meja), secara parsial (seperti lelaki) maupun dengan perubahan bunyi (seperti bolak-balik). Lihat, Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 182.

xcviii
���6 = Mahakuasa
Mahamelihat = ب&��
Atau N yang mengandung makna sifat perbandingan juga dialihkan
kepada frasa ajektival (FAdj). Contoh:
�� (yang) lebih keras = أش
lebih baik (yang) = خ��
lebih besar (yang) = أآ��
2. N → V :
Nomina Bsu yang mengandung makna peran (pelaku) sementara
dalam Bsa tidak bisa diterjemahkan dengan penambahan pe-, atau dengan
FN seperti di atas, maka N dapat dialihkan kepada kategori V. Contohnya
seperti pada ayat 14 dan 30 berikut ini:
B�ن ��zئ1نإنb��- Kami hanya berolok-olok.
@7 ا��رض خ�]� �LAإن�7 Sungguh Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.
Pengubahan bentuk nomina Bsu (ism al-Fâ’il) kepada bentuk verba
Bsa (berolok-olok) merupakan upaya penurunan kelas kata. Oleh karena
itu, penurunan kelas semacam itu dinamakan denominal, karena berasal
dari kata nominal; dan verba yang dihasilkan dari penurunan itu
dinamakan verba denominal.146
3. V → F:
V Bsu yang di dalamnya mengandung S implisit maupun eksplisit
maka V dialihkan kepada F. Contoh:
146 Abdul Chaer, Linguistik Umum, h. 182.

xcix
1�اوب�3�' B� zا� = dan sampaikanlah kabar gembira kepada
orang-orang yang beriman
Pengalihan V Bsu kepada F Bsa seperti di atas disebabkan oleh
ketercakupan makna V. Oleh karena itu, frasa sampaikanlah kabar
gembira sebenarnya mengandung kata verbal inti, yakni kabarkanlah.147
Contoh-contoh pengalihan V kepada F banyak ditemukan di beberapa ayat
surah al-Baqarah, seperti pada ayat 6, kata verbal andzara (memberi
peringatan) dengan kata inti peringatan; pada ayat 57, 172 dan 254, verba
razaqa (memberi rezeki) dengan kata inti rezeki; pada ayat 54, verba tâba
(menerima taubat) dengan kata inti taubat; pada ayat 61, verba istabdala
ahistaftaverba , 89pada ayat ; idengan kata inti gant) meminta ganti(
(memohon kemenangan) dengan kata inti kemenangan; pada ayat 45,
verba ista’âna (memohon pertolongan) dengan kata inti pertolongan; pada
ayat 256, verba istamsaka (berpegang teguh) dengan kata inti berpegang;
pada ayat 131, verba aslama (berserah diri) dengan kata inti berserah.
4. V (pasif) → V (aktif)
Seluruh V Bsu memang harus sepadan untuk diterjemahkan ke
dalam V Bsa, baik V aktif maupun pasif. Namun di dalam surah al-
Baqarah terdapat kategori Bsu V (pasif) dialihkan kepada kategori Bsa V
(aktif). Contoh:
1z@1�� B� z148نوا�XK� = dan orang-orang yang mati
Z� 7[A B�@149 = tetapi barang siapa memperoleh maaf
147 Al-Jalâlain, Tafsîr al-Jalâlain (Damsyiq: Dâr al-Jail, 1995), h. 5. adalah bentuk fi’l mudâri’ (verba imperfektif) pasif dan fi’l mâdi-nya (verba ��1@1ن 148
perfektif) 7@1� yang berarti mati, meninggal. Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1572.
149 Z� 7[A berasal dari verba aktif 7[A)Zأو� Z�A( yang berarti memaafkan atau mengampuni. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, h. 950.

c
C. Strategi Semantis
Strategi semantis adalah strategi terjemahan yang dilakukan atas dasar
pertimbangan makna. Tidak semua makna Bsu dapat diterjemahkan sepenuhnya
ke dalam Bsa. Oleh karena itu, strategi ini dipergunakan pada tataran kata, frasa
maupun klausa atau kalimat.
Di antara strategi semantis yang digunakan dalam terjemah al-Quran Depag
RI meliputi beberapa strategi sebagai berikut:
1. Transliterasi
Transliterasi adalah strategi terjemahan yang mempertahankan kata-
kata BSu tersebut secara utuh, baik bunyi maupun tulisannya. Dalam karya
tulis maupun karya terjemahan dalam bidang keagamaan (Islam), transliterasi
atau alih aksara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. 150 Tujuannya
adalah untuk menjaga konsistensi Bsu baik lafal maupun maknanya.
Terjemahan al-Quran Depag RI menggunakan transliterasi pada kata-
kata atau frasa tertentu yang memang tidak sepadan dalam konteks yang
dimaksud. Di dalam surah al-Baqarah, penulis menemukan strategi
transliterasi pada kata-kata, frasa dan kalimat sebagai berikut: alif lâm mîm
â’inâr, )65ayat (sabt , )62ayat (n î`âbis, )57ayat (â salwdanmann , )1ayat (
â ilaihi hi wa innâ lillâInn, )125ayat (m Ibrahim âmaq, )104ayat ( âurnzdan un
âtWusdan ) 228ayat ( `ûQur, )198ayat (m âarharil ’Masy, )156ayat (râji’ûna
(ayat 238).
Semua kata, frasa dan kalimat di atas yang diterjemahkan menurut
Quran itu dapat digolongkan pada nama gelar seperti -bunyi dan tulisan ayat al
150 Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara (transliterasi), antara
lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan Diknas RI serta versi Paramadina. Umumnya pedoman alih aksara tesebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (font) tertentu. Lihat, Hamid Nasuhi, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jakarta: CeQDA, 2007), h. 46.

ci
nama makanan dan 152,m Ibrahimâmaq nama tempat seperti 151,nî`âbis
minuman seperti mann dan salwâ,153 nama hari seperti sabt,154 dan istilah-
ungkapan - serta ungkapan157,ibghat AllahS 156,âtWus 155,`ûQuristilah seperti 159.râji’ûnaâ ilaihi hi wa innâ lillâInn 158,âurnz un danâ’inârseperti
Adapun huruf-huruf Hijaiyyah yang lazim terletak di permulaan surah
Baqarah atau pada - pada surah alalif lâm mîmseperti , )suwar- alhfawâti(
surah-surah lainnya, seluruh terjemahan al-Quran menerjemahkannya menurut
bunyi dan tulisannya. Huruf-huruf yang terletak di permulaan beberapa surah
ini digolongkan pada ayat-ayat mutasyâbihât,160 sehingga para mufassir dalam
beberapa kitab tafsirnya menafsirkannya dengan Allâhu a’lam bimurâdihi.
suwar- alhfawâtilain penggunaan transliterasi dilakukan pada lasan A
(pembukaan surat-surat) karena dinilai oleh Ibn Katsir sebagai bukti adanya
151 Sâbi în ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW., yang mengetahui adanya Tuhan
Yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. 152 Tempat Nabi Ibrahim, A.S., berdiri ketika membanguna Ka’bah. 153 Mann ialah sejenis madu dan salwâ ialah sejenis burung puyuh. 154 Sabt ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. 155 Qurû bentuk jamak dari qar`u yang berarti suci, atau haid. 156 Shalat Wustâ yaitu shalat Ashar menurut hadits shahih. 157 Sibghat Allah artinya celupan Allah, maksudnya agama Allah. 158 Râ’inâ artinya perhatikanlah kami, kemudian klausa tersebut diplesetkan oleh orang
Yahudi dengan dengan ru’ûnah yang artinya bodoh sekali yang ditujukan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah memerintahkan sahabat Rasulullah untuk menukar râ’inâ dengan unzurnâ yang artinya sama.
159 Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji’ûna adalah kalimat Istirja’ (pernyataan kembali kepada Allah). Ungkapan ini sunnah diucapkan tatkala ditimpa musibah, baik besar maupun kecil.
160 Ayat-ayat mutasyâbihât merupakan lawan kata ayat-ayat muhkamât. Lihat, Q.S. Ali ‘Imran: 7. Pengertian tentang ayat-ayat mutasyâbihât maupun muhkamât masih diperdebatkan di kalangan ulama. Namun satu definisi yang dapat diambil antara lain, ayat muhkamât yaitu ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya. Dengan demikian ayat mutasyâbihât yaitu ayat yang tidak dapat diketahui maksudnya, kecuali Allah. Di antara ayat-ayat yang termasuk ayat mutasyâbihât ialah ayat-ayat tentang keberadaan Allah dan sifat-sifat-Nya, hakikat hari akhir, tanda-tanda kiamat dan huruf-huruf di permulaan surat. Lihat, Mannâ’ al-Qattân, Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qurân (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), h. 207.

cii
I’jâz al-Qurân,161 karena manusia tidak mampu untuk membuat karya yang
sejenis huruf-huruf tersebut, apalagi seluruh al-Quran.162
2. Naturalisasi
Naturalisasi adalah ucapan atau tulisan Bsu tersebut disesuaikan dengan
aturan BSa. Naturalisasi merupakan lanjutan dari transliterasi atau sering
disebut adaptasi.163 Misalnya: Islâm menjadi Islam.
Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kaya dengan kata serapan dari
bahasa Arab, diperkirakan sekitar 2.000-3.000 kosakata. Namun frekuensinya
tidak terlalu besar dan secara relatif diperikirakan jumlah ini antara 10%-
15%.164 Sebagian kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti yang sesuai antara
lafal dan maknanya seperti awal, akhir, halal, haram, kiamat, kitab dan
syari’at. Kemudian lafal dan arti berubah dari lafal semula seperti kabar, lafal,
mungkin, rezeki dan masalah. Bagian lainnya, lafalnya benar, artinya berubah
seperti ahli, kalimat dan siasat.
Kata-kata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab
sangat dipengaruhi oleh teks-teks keagamaan seperti al-Quran. Karena itu,
dalam terjemahan al-Quran juga terdapat kata-kata yang dipungut langsung
dari bahasa al-Quran itu sendiri.
161 I’jâz berarti melemahkan. Dan I’jâz al-Qurân bermakna pengokohan al-Quran sebagai
sesuatu yang mampu melemahkan berbagai tantangan untuk penciptaan karya sejenis. Lihat, al-Zarqâniy, Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qurân ,jilid 2, h. 331. I’jâz al-Qurân dalam kaitannya dengan fungsi kerasulan Nabi Muhammad SAW., berarti memperlihatkan kebenaran kerasulan dan fungsi kenabiannya serta kitab suci yang dibawanya. Selain itu, untuk memperlihatkan kekeliruan bangsa Arab yang menentangnya, karena tantangan-tantangan yang dilontarkan Allah dalam al-Quran tidak dapat mereka layani. Lihat, Sya’bân Muhammad Ismâil, al-Madkhal li Dirâsah al-Qurân wa al-Sunnah wa al-‘Ulûm al-Islâmiyyah (Kairo: Dâr al-Ansâr, t.th), h. 323.
162 Muhammad ‘Ali al-Sâbûniy, Safwah al-Tafâsîr (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), jilid 1, h. 25. 163 Naturalisasi disebut juga teknik penerjemahan fonologis, yaitu terjemahan yang dilakukan
dengan cara membuat kata baru yang diambil dari bunyi kata Bsu untuk disesuaikan dengan sistem bunyi (fonologi) dan ejaan (grafologi) Bsa, seperti kata demokratie (Belanda) → demokrasi. Lihat, Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan, h. 76.
164 Wikipedia Indonesia, Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia. Sunting diakses pada tanggal 21 April 2008 dari http://id.wikipedia.org/wiki.

ciii
Kata-kata al-Quran yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa
Indonesia melalui naturalisasi juga banyak ditemukan di dalam surah al-
Baqarah terjemahan Depag RI. Di antara kata-kata itu adalah Allah, Kitab,
nama-nama malaikat seperti Jibril, Roh Kudus, Mikail, nama-nama nabi,
seperti Adam, Musa, Isa, Sulaiman, Ibrahim, Ya’kub, Dawud, nama-nama raja
seperti Fir’aun, Talut dan Jalut, nama kaum (umat) seperti Yahudi, Bani
Israil, nama-nama tempat seperti Masjidil haram, Safa dan Marwah, nama
bulan seperti Ramadan, serta istilah-istilah dalam Fiqh Islam seperti shalat,
zakat, haji, umrah, qisas, riba, sedekah, dan fidyah. Semua kata-kata itu ditulis
menurut bunyi dan tulisan Indonesia, meskipun semuanya berasal dari bahasa
al-Quran atau Arab.
Melalui strategi naturalisasi ini, satu kata bisa juga menghasilkan kata
Bsa dengan makna yang berbeda dari makna kata Bsu (al-Quran), seperti
”kitab” diartikan buku dalam kalimat: Mahasiswa itu suka membaca kitab-
kitab klasik.
Jadi, pungutan (borrowing) dapat dianggap sebagai strategi semantis
dalam terjemahan al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata, frasa atau
kalimat untuk menerjemahkan nama orang, nama tempat, nama kitab, nama
gelar, nama lembaga (institusi) dan istilah-istilah pengetahuan yang belum
didapatkan di Bsa. Hanya kemudian, jika kata, frasa atau kalimat itu sudah
menjadi kata serapan dalam Bsa tidak perlu menggunakan transliterasi
melainkan naturalisasi.
Mengenai naturalisasi dalam terjemahan al-Quran harus mengacu
kepada terjemahan resmi yang telah dibakukan. Untuk itu, penerjemah perlu
memiliki wawasan dan pedoman tentang pengindonesiaan nama atau kata-kata
Bsu yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

civ
Depdikbud R.I. Di antara kata-kata Arab terdapat kata yang salah satu
hurufnya dilambangkan dengan dua huruf latin, seperti huruf خ (kh)ص , (ş),
Sehingga terjemahan kata khalifah, shalat dan ghaib tidak menyalahi .(g)غ
aturan Bahasa Indonesia. Ketiga contoh kata khalifah, shalat dan ghaib yang
benar naturalisasinya adalah khalifah, sedangkan shalat dan ghaib
naturalisasinya menjadi salat dan gaib.165
Kedua strategi semantis di atas, menurut Suryawinata dinamakan
strategi pungutan (borrowing), yaitu strategi terjemahan yang mengambil kata
Bsu ke dalam teks Bsa. Penerjemah sekedar memungut kata Bsu yang ada.
Alasan strategi ini digunakan untuk menunjukkan penghargaan terhadap kata-
kata tersebut, atau belum ditemuinya padanan di dalam Bsa.166
3. Penjelasan Tambahan (Contextual Conditioning)
Penjelasan tambahan dalam strategi semantis ini dilakukan karena untuk
memperjelas makna kata-kata. Di sini penerjemah memasukkan informasi
tambahan di dalam teks terjemahan, karena ia berpendapat bahwa pembaca
memang memerlukannya. Newmark menjelaskan bahwa informasi tambahan
itu bisa dimasukkan dalam teks terjemahan atau diletakkan di bawah halaman
(berupa catatan kaki) atau di bagian akhir dari teks terjemahan.167
Strategi ini digunakan oleh Terjemahan al-Quran Depag RI untuk
menjelaskan beberapa aspek, antara lain:
a. Aspek keimanan, seperti pada terjemahan ayat 154:
Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di
jalan Allah (mereka) telah mati. Sebenarnya (mereka) hidup,....
165 Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1976), h. 288, 503, 856. 166 Suryawinata, Translation, h. 70. 167 Newmark, Textbook of Translation (Oxford: Pergamon Press, 1988)h. 91-92

cv
Dalam kata hidup, penerjemah menambahkan informasi dalam
bentuk catatan kaki, maksudnya hidup di alam lain yang bukan alam kita
ini. Mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah dan hanya Allah yang
mengetahui bagaimana kehidupan di alam itu.
b. Aspek hukum syariat, seperti pada terjemahan ayat 158:
Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah,
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.
Dalam terjemahan ayat ini, penerjemah menjelaskan dua hal, yaitu
tidak ada dosa dan sa’i. Frasa tidak ada dosa diperjelas dengan catatan
kaki sebagai berikut:
“sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa’i di situ,
karena pada masa jahiliyyah tempat itu adalah tempat berhala sekaligus
juga sebagai tempat sa’i mereka. Untuk menghilangkan rasa keberatan
para sahabat itu, Allah menurunkan ayat ini.”
Sedangkan kata sa’i diperjelas oleh penerjemah dengan memberikan
definisi pada catatan kaki, berjalan dan berlari-lari kecil sebanyak tujuh
kali antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umrah.
c. Aspek sejarah, seperti terjemahan ayat 49:
“Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari Fir’aun
dan pengikut-pengikut (Fir’aun).”
Dalam catatan kaki, penerjemah menjelaskan Fir’aun menurut
catatan sejarah, yaitu Fir’aun yang hidup pada masa Nabi Musa AS.,
ialah Menephthan (1232-1224 SM) anak Ramses.
d. Aspek kemasyarakatan, seperti pada terjemahan ayat 143:
“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)
manusia.”

cvi
Dalam terjemahan “umat pertengahan”, penerjemah
menambahkannya dalam bentuk catatan kaki, umat yang adil, yang tidak
berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara
keduanya.
Strategi di atas oleh Depag dimaksudkan untuk memperjelas makna
kata-kata yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pada umumnya
strategi penambahan yang berupa catatan kaki pada terjemahan al-Quran
Depag RI berupa uraian panjang dalam bentuk kalimat. Dan strategi itu tidak
jauh berbeda dengan terjemahan al-Quran yang disusun oleh Abdullah Yusuf
Ali dengan dalam bentuk komentar yang berdasarkan nomor catatan kaki.
Berbeda dengan penambahan informasi lainnya yang terdapat dalam
teks terjemahan al-Quran Depag RI, yakni penjelasan itu cukup singkat dalam
bentuk kata, frasa dan klausa.
a. Penambahan kata nominal banyak dilakukan dalam teks terjemahan untuk
memperjelas kata. Selain itu, penambahan nominal banyak dilakukan pada
pronomina (kata ganti) yang mengacu pada personifikasi tokoh-tokoh yang
muncul dalam cerita, seperti pada ayat 71: Dia (Musa) menjawab,
“Sungguh Dia (Allah) berfirman, sesungguhnya dia (sapi) itu adalah sapi
betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah... Pada ayat
tersebut, terdapat kata dia yang terulang sebanyak tiga kali, yakni dia yang
mengacu kepada Musa, kepada Allah dan sapi. Kemudian, penambahan
kata Musa, Allah dan sapi tersebut dilakukan untuk memperjelas
pronomina yang dimaksudkan serta untuk menghindari kekeliruan dalam
penetapan acuan persona yang ada dalam ayat tersebut. Selain itu,
ketiaadaan penambahan kata nominal seringkali terjemahan menjadi kabur,
apalagi penetapan persona yang salah. Hal ini terjadi pada terjemahan al-

cvii
Quran Depag RI, seperti pada ayat 144: ...maka hadapkanlah wajahmu ke
arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada maka hadapkanlah
wajahmu ke arah itu; pada ayat 149: ...hadapkanlah wajahmu ke arah
Masjidilharam; dan pada ayat 150: ...maka hadapkanlah wajahmu ke arah
Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah
wajahmu ke arah itu... Ketiga ayat tersebut mengandung perintah untuk
menghadap kiblat dengan dua persona kedua (mukhâtab) yang dituju,
yakni anta (engkau) yang mengacu kepada Nabi Muhammad SAW., dan
antum (kamu) yang mengacu kepada umat Islam. Akan tetapi, terjemahan
ayat 144 dan 150 terdapat perbedaan dalam penetapan acuan pronomina,
yakni kalimat kedua pada ayat 144 menggunakan pronomina engkau,
kemudian pada ayat 150 menggunakan pronomina kamu. Padahal
keduanya sama-sama mengacu pada persona kedua jamak, yakni antum.
Menurut bahasa standar Bsa, penggunaan engkau ditujukan bagi persona
kedua tunggal, sedangkan kamu ditujukan bagi persona kedua jamak.168 Di
sinilah, ketidaktepatan dalam pemilihan kata untuk terjemahan kedua ayat
tersebut.
b. Penambahan kata verbal, seperti pada ayat 44: Mengapa kamu menyuruh
orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu
sendiri. Kata verbal yang menunjukkan arti mengerjakan tidak ditemukan
pada ayat tersebut. Namun, beberapa terjemahan al-Quran Indonesia
menambahkan kata verbal seperti pada contoh ayat di atas. Mahmud
Yunus dan HB. Jassin juga menambahkannya dengan verba berbuat.
168 Pronomina yang mengandung makna persona kedua tunggal menurut bahasa standar dapat
berbentuk engkau, saudara, bung, anda, tuan, nyonya, nona. Sedangkan yang mengandung makna persona kedua jamak dapat berbentuk kamu, kalian, saudara-saudara, tuan-tuan. Di samping itu, pronomina yang dianggap sub-standar seperti lu, jang, neng. Lihat, Samsuri, Analisis Bahasa (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 283.

cviii
c. Penambahan frasa dalam teks terjemahan seperti pada ayat 14: Dan
apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata,
“Kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan
(para pemimpin) mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama
kamu, kami hanya berolok-olok”. Pada ayat ini penambahannya dalam
bentuk frasa partikel, yakni para pemimpin.
d. Penambahan klausa dalam teks terjemahan seperti pada ayat 30: Dan
(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak
menjadikan khalifah di bumi.” Klausa ingatlah merupakan verba imperatif
yang dilesapkan dengan memperkirakan klausa Bsu-nya “udzkur idz” atau
“udzkur waqta (hîna)” // ingatlah ketika.169 Berkaitan dengan partikel idz,
al-Mubarrid membedakan antara partikel idz dan idzâ. Menurutnya,
apabila partikel idz berbarengan dengan verba imperfektif, maka makna
aspek yang dikandungnya adalah aspek perfektif, seperti pada ayat 30
surah al-Anfal: kemudian apabila partikel idzâ ; وإذ ��K� ب
berdampingan dengan verba perfektif, maka aspeknya bermakna
prospektif, seperti pada ayat 1 surah al-Nasr: ��[�وا Zzء ن&� ا�� 170 .إذا
Beberapa contoh penambahan dalam teks terjemahan al-Quran itu pada
umumnya diselipkan di antara dua kurung (...) untuk membedakan bahwa
kata, frasa atau klausa dalam kurung tersebut bukan teks Bsu yang orsinil
melainkan teks tambahan yang dipahami penerjemah.
Selain itu, penambahan juga dilakukan ketika bagian teks Bsu
dianggapnya elipsis (al-hadzf) dari komponen kalimat, seperti pada ayat 196
dan 127 surah al-Baqarah berikut ini: (1) ����م @7 ا�z�أ ��G� ��م&@ ... //
169 Muhammad ‘Ali al-Sâbûniy, Safwah al-Tafâsîr, jilid 1, h. 40. 170 Muhammad Ibn Ahmad al-Ansâriy al-Qurtubiy, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân (Beirut: Dâr
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), jilid 1, h. 181.

cix
Maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam musim haji; (2) �z� Lz�(� ��zرب ... // (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami.”
Bagian teks pada contoh (1) yang dianggap hilang adalah khabar yang
terletak setelah kata sarana konjungtif fâ` al-jawâb. Dan bagian teks yang
diperkirakannya adalah Z�:@171. ص��م
Bagian teks pada contoh (2) yang dianggap hilang adalah fi’l al-qaul
(verba ucapan) yang terdiri dari kata qâla, yaqûlu, yuqâlu. Penghilangan kata-
kata tersebut di dalam al-Quran banyak dijumpai dalam beberapa surah. Di
antaranya contoh (2), menurut al-Zajjâj bahwa makna kata yang terkandung
dalam teks tersebut adalah yaqûlâni, yang mengandung subjek persona ketiga
dual yang mengacu kepada dua orang, yakni Ibrahim dan Isma’il.172
4. Penghapusan (omission atau deletion)
Penghapusan berarti penghilangan kata atau bagian teks Bsu di dalam
teks Bsa. Atau dengan kata lain, penghapusan berarti kata atau bagian teks Bsu
itu tidak diterjemahkan dalam Bsa. Pertimbangannya adalah kata itu tidak
penting bagi keseluruhan teks, atau kalaupun penting tetap sulit untuk
diterjemahkan. Meskipun penerjemah memaksakan kata atau bagian teks itu
diterjemahkan perbedaan maknanya tidak signifikan, karena Bsu menghendaki
adanya penghapusan.
Dalam terjemahan al-Quran Depag RI penghapusan itu dilakukan pada
salah satu tataran sintaksis, yaitu kata. Di antara kata yang dihilangkan dalam
Dan di antara KS yang ). KS( atau kata sarana trâbiterjemahan Bsa adalah
dihapus dalam terjemahan Bsa adalah preposisi dan konjungtif.
171 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuh (Beirut: ‘Âlam al-Kutub, 1998), jilid 1, h. 257. 172 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuh, jilid 1, h.188.

cx
Preposisi atau hurûf al-Jarr termasuk kata yang tidak berdiri sendiri,
maka dia mempunyai relasi dengan kata lainnya yaitu ism (nomina) dan fi’l
(verba). Fungsi preposisi dalam kalimat Bsu bisa dinilai sebagai hurûf al-
Ma’ânî, huruf tambahan gramatikal atau bisa sebagai penjelas dari unsur kata
sebelumnya.
Adapun contoh preposisi yang berfungsi sebagai hurûf al-Ma’ânî
seperti pada ayat 130 dan 238 surah al-Baqarah berikut ini:
(1) D��� BZ[" B ن]-BAZو �zإ� Xإب�اه� �z
Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang
yang memperbodoh dirinya sendiri.
ا�&z1ات وا�&Gzة اA�<"1��ح�@1�ا (2)
Peliharalah semua salat dan salat wusta.
Kata yang bergaris bawah pada contoh (1) dan (2) adalah preposisi yang
dikategorikan sebagai huruf ma’ânî, dan salah satu makna yang dikandungnya
adalah untuk menghubungkan verba transitif terhadap objeknya (al-
Ta’diyyah). Kedua verba yang terletak sebelum preposisi, maknanya
tergantung pada preposisi yang mengikutinya. Dan kedua preposisi yang
bergaris bawah itu tidak diterjemahkan di dalam Bsa, karena verba yang
terletak sebelumnya merupakan relasi kata dan makna yang tidak bisa
dipisahkan.173
Preposisi yang berfungsi sebagai huruf tambahan gramatikal dan
maknanya dilesapkan dalam terjemahan, seperti pada ayat 105 surah al-
Baqarah: XK�A لzb�� أنBXKرب� B suatu kebaikan apapun dari // خ��
173 Rofi’i, Bimbingan Tarjamah Arab-Indonesia (Jakarta: Persada Kemala, 2002), jilid 1, h.
29.

cxi
Tuhanmu diturunkan kepadamu. Demikian pula pada ayat 120 dalam surah
yang sama: Zzا� B � �B Tidak ada bagimu pelindung // و�7� وF ن&��
dan penolong dari Allah. Preposisi yang bergaris bawah tersebut dinilai oleh
al-Zajjâj sebagai huruf tambahan gramatikal, karena itu makna ayat tersebut
Tujuan adanya penambahan .îrsmâ laka min Allâhi waliyyun wa lâ namenjadi
huruf tersebut untuk penegasan makna (al-taukîd).174
Kemudian, preposisi yang berfungsi sebagai penjelas kata yang terletak
sebelumnya, seperti pada ayat 272: [�� �B )1ا وXK-[�نخ�� @ // Harta
apapun yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri.
Preposisi yang bergaris bawah itu sebagai penjelas dari kata yang terletak
sebelumnya, yakni �. Oleh karena itu preposisi tersebut dinamakan min
bayâniyyah dengan pola ���11ص�B ب��ن��+ . Pola seperti ini dan pola-
pola lainnya yang hampir serupa, seperti B+� , B+B , dan B+B seringkali menyulitkan penerjemah untuk merekonstruksi terjemahannya ke
dalam Bsa, dan tidak sedikit penerjemah terjebak pada terjemahan harfiah,
karena pola seperti ini tidak ditemukan dalam Bsa.175 Mengenai strategi untuk
menerjemahkan kalimat yang mengandung �ب��ن� B dengan pola � +B ,
atau B + B adalah seperti contoh berikut:
اPش��ء B 1نا��-��K إ��Z ����ج � @7 ا�-1ق
7 6 5 4 3 2 1
. para konsumen dibutuhkan yang barang-ada barang Di pasar
174 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuh, jilid 1, h. 166 dan 181. Preposisi min yang dinilai
sebagai huruf tambahan gramatikal harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: 1) sebelumnya didahului oleh kata sarana negasi, larangan, atau tanya; 2) nomina yang di-jar-kannya dalam bentuk nomina non definitif (nakirah) serta menempati sebagai subjek atau musnad ilaih. Lihat, Sanâ Jihâd, Mu’jam al-Tâlib wa al-Kâtib, h. 148.
175 Moh. Mansyur dan Kustiwan, Pedoman Bagi Penerjemah Arab-Indonesia (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), h. 96.

cxii
1 7 2 3+4 5
B ��ش�ن� و �:��� B ن���م B�"ر� ا��
7 6 5 4 3 2 1
.membimbing kami dan mengajar yang guru-guru Kami menghormati
1 7 2 3 4 5
Kemudian di antara preposisi lainnya yang dinilai sebagai huruf
tambahan gramatikal adalah partikel bâ` (ا���ء) , seperti pada ayat 8 surah al-
Baqarah: Xه �B��بو � // Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
Partikel yang bergaris bawah itu merupakan huruf tambahan yang mempunyai
fungsi untuk menegaskan makna negatif.176 Dengan demikian, setiap preposisi
yang dianggap sebagai huruf tambahan gramatikal dilesapkan dalam
terjemahannya.
Kemudian, di antara kata sarana konjungtif yang dilesapkan dalam
terjemahannya adalah partikel � . Partikel � memiliki banyak fungsi yang
dapat merubah kalimat deklaratif menjadi non deklaratif, seperti kalimat
tanya, kalimat negatif, kalimat syarat. Karena itu, partikel � menyandang
banyak nama tergantung letaknya di dalam kalimat.
Sementara partikel � yang biasa dilesapkan dalam terjemahan Bsa
adalah � huruf tambahan, seperti pada ayat 26 surah al-Baqarah: G=� 13� // nyamukperumpamaan seekor;ب:1ض� seperti pada ayat , dariyyahsma
surah al-Baqarah: 1�ا آB ا���zس��'' // berimanlah sebagaimana orang lain
; telah beriman� :106 seperti pada ayat ,iyyahtsyar ��' B� ن�-� Ayat //
yang Kami batalkan. Partikel � pertama, seperti pada ayat 26 terletak di
176 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuh, jilid 1, h. 50. Lihat juga Bahjat ‘Abd al-Wâhid
Sâlih, al-I’râb al-Mufassal li Kitâb Allâh al-Murattal (Amman: Dâr al-Fikr, 1998), jilid 1, h. 17.

cxiii
kata yang ( mubdal minhdan ahdûba’yakni , )kata pengganti (badalantara
digantikan), yakni matsalan. Sehubungan partikel tersebut dinilai sebagai
huruf tambahan, maka partikel tersebut dilesapkan dan makna terjemahannya
Sedangkan partikel 177.ahdûmatsalan ba’menjadi �seperti pada ayat , kedua
13 terletak sebelum klausa verbal tanpa relasi kata atau makna yang kembali
dan partikel ini disebut , kepada partikel tersebut�Partikel . dariyyahsma tersebut dilesapkan dan makna terjemahannya menjadi ن ا���س���c178.آ
Kemudian partikel � ketiga, seperti pada ayat 106 terletak sebelum klausa
verbal dan antara keduanya tidak terdapat relasi kecuali relasi makna, yakni
frasa preposisional sebagai penjelas partikel �. Kebanyakan preposisi B yang terletak setelah partikel � berfungsi sebagai penjelas, karena maknanya
yang terlalu samar.179 Dengan demikian, semua partikel tersebut di atas
mengalami penghapusan atau pelesapan dalam terjemahan.
5. Penggantian (Replacement)
Penggantian yang dimaksud dalam terjemahan adalah menggantikan
satuan gramatikal Bsu dengan satuan gramatikal yang lain dalam Bsa.
Penggantian tersebut dimaksudkan untuk menjadikan teks terjemahan lebih
efektif. Di antara satuan gramatikal Bsu yang dapat digantikan adalah kata
sarana atau partikel. Kata sarana konjungtif, yakni partikel و biasanya diganti
dengan tanda baca koma dalam Bsa, seperti pada ayat 83 surah al-Baqarah:
Pada ayat ini terdapat . ا��-�آ�B وا����� وذي ا�)�ب� ووب�1�ا���B إح-�ن�
177 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuh, jilid 1, h. 70. Ada beberapa partikel � yang
dianggap sebagai huruf tambahan selain yang terletak seperti di atas, misalnya partikel � yang terletak setelah kata qalîlan, seperti pada ayat 88 surah al-Baqarah: 1�ن � � G�(@ // tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Lihat, Muhammad Ahmad Khidîr, ‘Alâqah al-Zawâhir al-Nahwiyyah bi al-Ma’nâ fi al-Qurân al-Karîm (Kairo: Maktabah Anglo al-Misriyyah, t.t.) h, 83.
178 Bahjat ‘Abd al-Wâhid Sâlih, al-I’râb al-Mufassal li Kitâb Allâh al-Murattal, jilid 1, h. 20. 179 Jamâl al-Dîn Ibn Hisyâm al-Ansâriy, Awdah al-Masâlik ilâ Alfiyyah Ibn Mâlik (Beirut: al-
Maktabah al-‘Asriyyah, 1994), jilid 3, h. 21.

cxiv
empat partikel و yang fungsinya menghubungkan makna kata atau klausa
yang terletak sesudahnya dengan kata atau klausa sebelumnya. Kata sarana
konjungtif Bsu yang sering digunakan untuk itu adalah partikel و . Kalimat
yang di dalamnya terdapat satuan kata sarana konjungtif biasanya
diterjemahkan apa adanya, kecuali terdiri dari beberapa kata sarana konjungtif
yang sama seperti pada ayat di atas. Dengan demikian, penggantian partikel و dengan tanda koma perlu dilakukan agar kalimat itu menjadi efektif, karena
tidak melakukan pengulangan kata yang sama. Penggantian tersebut
menunjukkan bahwa kalimat itu paralel dan hemat, padahal keparalelan dan
kehematan merupakan di antara syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat
efektif.180 Sehingga melalui penggantian, terjemahan ayat itu menjadi “Dan
berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan
orang-orang miskin.”
Penggantian juga terjadi pada beberapa kelas kata yang dilesapkan
maknanya namun kemudian diganti dengan kelas kata lainnya. Kelas kata itu
antara lain nomina dalam bentuk pronomina (kata ganti) yang menempati
posisi sebagai pronomina pemisah antara S (musnad ilaih) dan P (musnad).
Contohnya dapat ditemukan dalam beberapa ayat surah al-Baqarah, misalnya
pada ayat 5: Kata . ا��z1zاب ا��zح�Xه1إنdan ayat 37: Zz ; ا��]1�نهXوأو2�
yang bergaris bawah pada dua contoh tersebut adalah pronomina pemisah
yang dilesapkan maknanya, kemudian untuk menunjukkan ketegasan
maknanya kelas kata itu diganti dengan partikel –lah. Sehingga terjemahan
kedua ayat tersebut menjadi “Sungguh Dialah Penerima taubat, Maha
Penyayang” dan “Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
180 Lihat, Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 148.

cxv
Penggantian dengan partikel –lah pada dua contoh tersebut dimaksudkan
untuk menegaskan makna.181
Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terjemahan al-
Quran Depag RI ternyata juga memiliki strategi terjemahan baik strategi struktural
maupun semantis. Kedua strategi tersebut dimaksudkan untuk menerjemahkan kata-
kata atau kelompok kata, atau kalimat penuh bila kalimat tersebut tidak bisa dipecah
lagi menjadi unit yang lebih kecil untuk diterjemahkan.
Strategi struktural dan strategi semantis merupakan jenis strategi utama dalam
terjemahan. Pertama adalah strategi yang berkenaan dengan struktur kalimat. Strategi
ini bersifat wajib diupayakan, sebab jika tidak maka hasil terjemahannya akan tidak
berterima secara struktural di dalam Bsa. Jenis kedua adalah strategi yang langsung
terkait dengan makna kata atau kalimat yang diterjemahkan.
181 -lah merupakan partikel yang gunanya untuk menekankan kata yang di depannya baik
yang mengandung arti suruhan, penguatan maksud, penunjuk aspek dsb. Lihat, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 550.

cxvi
BAB IV
PADANAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL SERTA MAKNANYA
DALAM TERJEMAHAN AL-QURAN DEPAG RI
Terjemahan merupakan proses penggantian teks dalam satu bahasa dengan teks
dalam bahasa lain berlangsung tanpa mengubah tingkat isi teks asli. Hal ini berarti
bahwa dalam terjemahan telah terjadi penggantian satuan-satuan bahasa di tingkat
pengungkapan dengan tingkat isi yang dipertahankan tanpa perubahan. Dari sini
dapat dipahami, bahwa tugas penting penerjemah dalam pengalihbahasan adalah
mencari dalam teks Bsu satuan-satuan minimal yang layak diterjemahkan, yakni
satuan-satuan bahasa yang harus dicari padanannya dalam teks Bsa. Satuan-satuan
seperti itu disebut satuan terjemahan (unit of translation). Jadi, satuan terjemahan
ialah satuan Bsu yang mempunyai padanan dalam Bsa.
Mencari padanan merupakan salah satu problematika dalam terjemahan, karena
antara Bsu dan Bsa tidak persis sama. Menurut Barclay M. Newman, bahwa di antara
kesulitan bahasa dalam terjemahan antara lain: kata, struktur kalimat, istilah,
tatabahasa dan kiasan.182 Kata, struktur kalimat, tatabahasa dan kiasan merupakan
unsur-unsur mikroteks sebagaimana yang telah dijadikan objek dalam analisis
struktural.183 Kata itu bermacam-macam menurut jenisnya (parts of speech), seperti
kata benda, kata kerja, kata keterangan, kata depan dan sebagainya. Struktur kalimat
juga berbeda-beda menurut jenisnya, seperti kalimat menurut struktur gramatikalnya,
kalimat menurut fungsinya dan kalimat menurut bentuk gayanya. Sedangkan istilah
Bsu seringkali sulit dicarikan padanannya dalam Bsa, karena keterbatasan istilah-
istilah Bsa yang sepadan dengan Bsu dan istilah yang dimaksud dalam terjemahan
182 Barclay M. Newman, Rambut Sama Hitam, dalam Nurachman Hanafi, Teori dan seni
Menerjemahkan (Ende Flores: Nusa Indah, 1986), h. 35. 183 Dick Hartoko dan B. Rahmanto, Pemandu di Dunia Sastra (Yogyakarta: Kanisius, 1986),
h. 136.

cxvii
adalah istilah yang terdiri dari satu suku kata, dan istilah ini bisa berupa idiom atau
frasa (gatra). Kemudian tatabahasa dalam terjemahan sangat terikat dengan
penggolongan tatabahasa (grammatical categories) yaitu apabila kata benda
diterjemahkan dengan kata benda, kata benda dengan kata kerja, kata kerja dengan
kata kerja dan seterusnya. Dan kiasan dimiliki oleh setiap bahasa, namun untuk
menemukan padanannya dari Bsu ke dalam Bsa sangat sulit.
Demikian pula, menurut Ahsin Sakho Muhammad, salah seorang anggota tim
penerjemah al-Quran itu menyatakan bahwa kesulitan itu dapat dirasakan langsung
oleh para anggota tim penerjemah al-Quran Depag, ketika menerjemahkan unit-unit
bahasa al-Quran yang sulit ditemukan padanannya secara tepat dalam bahasa
Indonesia, sehingga harus menerjemahkannya dengan padanannya yang kurang tepat
menurut tingkat bahasanya serta harus menjelaskannya secara panjang lebar. Hal itu
disebabkan oleh bahasa al-Quran yang sangat sastrawi dan hanya bisa dipahami oleh
mereka yang mempunyai rasa bahasa yang sudah tinggi pula serta faktor bahasa
Indonesia yang memang terasa ‘kerdil’ menghadapi bahasa al-Quran yang demikian
indah, kukuh dan mantap.184
Sehubungan hal itu, bab ini penulis bagi ke dalam tiga pembahasan, yaitu
padanan gramatikal, padanan leksikal dan makna dalam terjemahan. Padanan
gramatikal akan dibahas menurut unit-unit terjemahan. Sedangkan padanan leksikal
akan dibahas berdasarkan penggantian kata-kata Bsu dengan kata-kata Bsa, karena
sebuah kata Bsu mungkin mempunyai banyak padanan di dalam Bsu atau juga
sebaliknya.
Pembahasan ketiga adalah makna dalam terjemahan, karena makna dan
terjemahan mempunyai hubungan yang sangat erat, sebagaimana yang dinyatakan
184 Ahsin Sakho Muhammad, “Aspek-aspek Penyempurnaan Terjemah dan Tafsir
Departemen Agama ”, Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 3, No. 1 (Januari 2005), h. 156.

cxviii
oleh Newmark bahwa menerjemahkan berarti memindahkan makna dari serangkaian
atau satu unit linguistik dari satu bahasa ke bahasa yang lain.185
A. PADANAN GRAMATIKAL
Untuk memudahkan mencari padanan Bsu dan Bsa secara keseluruhan
menurut tingkat satuan bahasa, maka dalam Bab ini padanan gramatikal antara
kedua bahasa akan disajikan berdasarkan ilmu linguistik kontemporer yang
mencatat hierarki (tingkat) bahasa sebagai berikut: tingkat fonem, tingkat morfem,
tingkat kata, tingkat rangkaian kata (frasa), tingkat kalimat dan teks.186
1. Terjemahan pada tingkat fonem
Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna.187 Untuk
mengidentifikasi sebuah bunyi fonem atau bukan, harus dicari sebuah satuan
bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu
dibandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa
yang pertama. Jika ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka
berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem, karena dia berfungsi membedakan
makna kedua satuan bahasa itu. Misalnya, kata Bsu Xأ�� dan X�A . Kedua kata
itu mirip benar. Masing-masing terdiri dari empat bunyi. Yang pertama
mempunyai bunyi [`a], [l], [î] dan [m]; dan yang kedua mempunyai bunyi
[‘a], [l], [î] dan [m]. Dan perbedaan antara keduanya hanya terletak pada
huruf pertama yaitu bunyi [`a] dan bunyi [‘a].
Atau satuan Bsa misalnya raba dan laba. Kedua kata itu juga mirip
benar, karena masing-masing terdiri dari empat buah bunyi. Yang pertama
185 Newmark, About Translation (Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 1991), h. 27. 186 Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemahan (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), h. 33. 187 Fonem berbeda dengan huruf. Fonem adalah bunyi dari huruf dan huruf adalah lambang
dari bunyi. Jadi, fonem sama dengan bunyi untuk didengar, sedangkan huruf adalah lambang untuk dilihat. Jumlah huruf hanya 26. Jika seluruh huruf itu dilafalkan berarti 26 bunyi huruf itu telah diperoleh. Lihat, Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2007), h. 73.

cxix
mempunyai bunyi [r], [a], [b] dan [a]; dan yang kedua mempunyai bunyi [l],
[a], [b] dan [a]. Ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama,
yaitu bunyi [r] dan [l]. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua
contoh Bsu dan Bsa di atas merupakan masing-masing dua buah fonem yang berbeda.
Jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan
jumlah yang dimiliki oleh bahasa lain. Bahasa Arab memiliki jumlah fonem
28 buah. Seluruh fonem tersebut dikategorikan fonem konsonan. Sementara
fonem vokalnya terbagi dua, yaitu tiga buah fonem vokal pendek dan tiga
lainnya fonem vokal panjang. Sedangkan bahasa Indonesia memiliki lebih dari
24 buah fonem, yaitu 6 buah fonem vokal (a, i, u, e, o dan ə) dan 18 buah
fonem konsonan (p, t, c, k, b, d, j, g, m, n, n, η, s, h, r, l, w dan y). Kemudian
ada yang menambahkan jumlah fonem itu sebanyak empat buah yang berasal
dari bahasa asing, yaitu fonem f, z, x dan ∫. Selain itu juga ada yang
menambahkan tiga buah fonem diftong, yaitu aw, ay dan oy.188
Dalam terjemahan ditemukan, bahwa satuan terjemahan justru adalah
juga fonem, yakni fonem-fonem Bsu diganti dengan fonem-fonem Bsa
menurut artikulasi serta bunyi yang lebih dekat. Dan terjemahan di tingkat
fonem secara prinsipil berbeda dengan jenis-jenis terjemahan lainnya, sebab
fonem bukan pengemban makna apapun. Karena itu, wajarlah kalau
penggunaan jenis terjemahan ini sangat terbatas.
Terjemahan al-Quran Depag RI di tingkat fonem sering digunakan
dalam penerjemahan nama, baik nama diri, geografis, menu dan nama lainnya.
Nama-nama tersebut dalam terjemahan al-Quran dilakukan sepenuhnya
sebagaimana penulis kemukakan pada Bab sebelumnya, misalnya Âdam
188 Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 132.

cxx
, ]Masjidil haram[ mâarH- alsjidMa, ]Fir’aun [Fir’aun ,]Kitab[b âKit, ]Adam[
]. salat[t âalS, ]Ramadan [nâdRama
Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka terjemahan al-Quran dari Bsu
ke Bsa di tingkat fonem tidak menimbulkan kesulitan dalam terjemahan
menurut ragam tulis, karena hanya menulis apa yang tertulis dalam teks Bsu.
Meski demikian, ada faktor subjektif menurut ragam terjemahan lisan yang
mungkin menyebutkan nama-nama di atas yang sesuai dengan lafal-lafal Bsu,
terutama fonem-fonem yang dilambangkan dengan huruf-huruf konsonan
rangkap (ts, ch, kh, dz, sy, sh, dl, th, dh, gh), vokal rangkap (ai dan au) dan
fonem suprasegmental, yaitu fonem yang menempel pada tiga vokal tunggal
(a, i, u) atau jika dalam tulisan Arab fonem tersebut dilambangkan dengan
huruf mad (panjang) yaitu alif, wau atau yâ`.189
2. Terjemahan pada tingkat morfem
Berbeda dengan fonem, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang
mempunyai makna. Morfem juga termasuk dalam satuan terjemahan, yaitu
setiap morfem dalam Bsu berpadanan dengan morfem dalam Bsa.190
Terjemahan di tingkat morfem relatif jarang sebagaimana terjemahan di
tingkat fonem. Struktur morfem kata yang mengandung makna yang sama
dalam berbagai bahasa lebih sering tidak sebangun, terutama yang
menyangkut tidak hanya morfem leksikal, tapi juga morfem gramatikal
(perubahan kata), yang komposisinya dalam berbagai bahasa berbeda.
189 Fonem dapat dibagi empat, yaitu fonem vokal, fonem konsonan, fonem semivokal, dan
fonem suprasegmental. Keempat fonem tersebut yang dimiliki oleh Bsu adalah fonem vokal, konsonan dan fonem suprasegmental sedangkan fonem yang dimiliki oleh Bsa juga tiga yaitu fonem vokal, fonem konsonan dan fonem semivokal (e (teleng), e (pepet) dan o). Lihat, Sudarno, Kata Serapan dari Bahasa Arab (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1990), h. 25.
190 Menurut bentuk dan maknanya, morfem dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: 1) morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain, 2) morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Lihat, Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 75.

cxxi
Adapun morfem Bsu yang dipadankan dengan morfem Bsa dalam
terjemahan al-Quran Depag memang relatif sedikit, yaitu al-Qurân dan Allâh.
Dua kata ini tersusun atas dua morfem, yaitu morfem terikat {al}191 dan
morfem bebas yaitu {Qurân} dan {ilâh}.
Dua contoh di atas merupakan morfem Bsu yang mempunyai dua
bentuk alomorf,192 yaitu (1) yang tetap berbentuk {al}, seperti al-Qurân; dan
(2) yang berubah atau berasimilasi dengan fonem awal bentuk dasarnya,
seperti Allâh. Kalangan linguis Arab berbeda pendapat mengenai bentuk asal
kata Allah.193 Namun Sîbawaih menyebutkan bahwa asal kata Allah adalah
ilâhun, kemudian melalui proses morfofenemik, yaitu dengan cara
memasukkan al pada kata ilâhun, menjadi al-ilâhu, lalu harakat hamzah yaitu
kasrah dipindahkan kepada huruf lâm, dan huruf lâm tersebut dilesapkan
sehingga menjadi alilâhu. Dari bentuk ini baru huruf lâm pertama di-sukûn-
kan dan bunyinya dimasukkan ke dalam huruf lâm kedua sambil dibaca tebal
sehingga menjadi Allâh.
Jadi pada tingkat ini, terjemahan al-Quran dapat dilakukan pada kata-
kata yang mengandung dua morfem, yaitu morfem terikat dan morfem bebas.
3. Terjemahan pada tingkat kata
191 Al atau alif lâm dapat dikategorikan ism atau harf (partikel). Al yang termasuk ism
dinamakan ism al-mausûl yang semakna dengan al-ladzî dan yang sejenisnya. Biasanya ia masuk pada ism al-fâ’il dan ism al-maf’ûl, seperti contoh: � ا��[�وب خ��� (Yang memukul itu Zaid) dan ا�[�رب ز�(Yang dipukul itu Khalid). Sedangkan al yang termasuk huruf adalah al-Ta’rîf, seperti ر�Uإذ ه�� @7 ا� dan al-Zâi`dah, seperti ا� ي,ا�ن . Lihat, Sanâ Jihâd, Mu’jam al-Tâlib wa al-Kâtib (Beirut: Maktabah Libnân Nâsyirûn, 1997), h. 31-33 dan Ibn Hisyâm al-Ansâriy, Mughnî al-Labîb (Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ` al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), jilid 1, h. 47-49.
192 Alomorf adalah bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama, atau perwujudan konkret dari sebuah morfem. Seperti bentuk me- pada melihat dan merasa, atau {-s} sebagai morfem jamak reguler pada kata-kata Inggris cats {keits}, books {buks}. Lihat, Abdul Chaer, Linguistik Umum, h. 150.
193 Ada yang menyebutkan asal kata Allâh adalah al-ilâhu, lâhu dan ilâhun. Lihat, Bahjat ‘Abd al-Wâhid Sâlih, al-I’râb al-Mufassal li Kitâb Allâh al-Mursal (Amman: Dâr al-Fikr, 1998), jilid 1, h. 7.

cxxii
Kata juga dapat bertindak sebagai satuan terjemahan. Jenis terjemahan
seperti ini lebih sering digunakan daripada satuan terjemahan sebelumnya.
Meskipun demikian, penggunaan terjemahan di tingkat kata terbatas. Biasanya
hanya sebagian kata-kata dalam satu kalimat yang bisa diterjemahkan di
tingkat kata, sedangkan sebagian yang lain di tingkat yang lebih tinggi,
misalnya di tingkat rangkaian kata karena tidak bisa diterjemahkan di tingkat
kata.
Menurut linguis Arab tradisional bahwa setiap kalimat dalam bahasa
Arab tidak hanya berasal dari satu macam bentuk kata, melainkan berasal dari
tiga macam bentuk, yaitu ism, fi’l dan harf (huruf).194 Ketiga bentuk itulah
yang menempati fungsinya masing-masing dalam kalimat dan jenis kata itu
pula yang akan mengantarkan arti dan makna dalam terjemahan. Karena itu,
penulis identifikasikan terjemahan pada tingkat kata ini menurut kategori dan
jenis katanya sebagai berikut:
a. Kata nominal
Nomina yang dapat dipadankan secara gramatikal antara Bsu dan Bsa
dalam terjemahan al-Quran Depag RI adalah sebagai berikut:
1) Kata Ganti (Pronomina)
Kata ganti yang dimaksud oleh penulis dalam rangka mencari
padanan gramatikal Bsu dan Bsa adalah kata ganti yang mengacu
kepada benda (ism) atau dalam tata bahasa Indonesia dikenal dengan
istilah Pronomina. Oleh karena itu, ada tiga jenis kata yang harus
dipadankan secara gramatikal dalam kategori ini, yaitu pronomina yang
pronomina penunjuk umum , )amaîrD-al(mengacu kepada persona
194 Muhammad Hamâsah ‘Abd al-Latîf, dkk., al-Nahw al-Asâsiy (Kairo: Dâr al-Fikr al-
‘Arabiy, 1997), h. 8.

cxxiii
- al`Asmâ-al (penghubung dan pronomina )Isyârah- al`asmâ(
. )ahûlsMau
yang pronomina persona ialah dalam Bsu amâirD-lA
menunjukkan mutakallim (persona pertama), mukhâtab (persona kedua)
atau ghâib (persona ketiga), seperti 1195 .أن�, أن5, ه Secara umum,
pronomina persona terbagi atas dua bagian, yaitu pronomina yang nyata
bentuknya (bâriz) dan pronomina yang tidak nyata (mustatir).196
Dalam Bsu, pronomina persona sangat rumit terutama dalam
penentuan jenis kelamin (genitif) dan jumlah. Namun untuk
memudahkan dalam mencari padanannya pronomina tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu kelompok kata, klausa
verbal dan klausa nominal dengan bentuk-bentuk pronomina
personanya sebagaimana yang tertulis dalam tabel berikut:
Tabel 3
Pronomina Persona Bsu dan Bsa
Pronomina Persona Bsu Pronomina Persona Bsa
No Kata
Klausa Verbal
Klausa Nominal
Kata Klausa Verbal
Klausa Nominal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Aku Aku {v} {n} ku ي... ت... أن� .1
2. Bن... ن�... ن�� Kami Kami {v} {n} kami
Engkau Engkau {v} {n} mu ك... ت... أن5 .3
Kamu Kamu {v} {n} mu آ��... ���... أن��� .4
5. Xأن� ...X� ...Xآ Kamu Kamu {v} {n} mu
Engkau Engkau {v} {n} mu ك... ت... أن5 .6
Kamu Kamu {v} {n} mu آ��... ���... أن��� .7
8. Bأن� ...B� ...ك Kamu Kamu {v} {n} mu
C Dia Dia {v} {n} nya... ... ه1 .9
195 Iman Saiful Mu`minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf (Jakarta: Amzah, 2008), h. 147. 196 Hamâsah ‘Abd al-Latîf, dkk., al-Nahw al-Asâsiy, h. 16.

cxxiv
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Mereka Mereka {v} {n} mereka ه��... ا... ه�� .10
11. Xوا... ه ...Xه Mereka Mereka {v} {n} mereka
Dia Dia {v} {n} nya ه�... ... ه7 .12
Mereka Mereka {v} {n} mereka ه��... ا... ه�� .13
14. Bن... ه ...Bه Mereka Mereka {v} {n} mereka
Pronomina persona pada kolom (2) padanan gramatikalnya sama
dengan Bsa sebagaimana pronomina persona pada kolom (5), hanya Bsa
tidak menyatakan pronomina tersebut dengan genitif dan jumlah,
sehingga perbedaan itu nampak sekali pada personanya. Bsu mengenal
persona tunggal, dual dan jamak, sedangkan Bsa hanya mengenal
tunggal dan jamak seperti pronomina persona bahasa Inggris, juga Bsa
tidak mengenal kelas kata persona maskulin dan feminin.197 Dengan
perbedaan itu, maka persona dual Bsu pada nomor (4, 7, 10 dan 13)
tidak dapat dinyatakan dalam Bsa, kecuali dengan persona jamak baik
persona II maupun III.
Kemudian pronomina persona pada kolom (2) ada yang
diterjemahkan secara lengkap menurut Bsa-nya, seperti dalam surah al-
Baqarah ayat 22: وX�1نأن�:� // padahal kamu mengetahui; dan ada
pronomina yang tidak diterjemahkan, tetapi diganti dengan partikel –
lah. Penggantian tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa persona
tersebut berfungsi sebagai empatik (taukîd).198 Contohnya seperti pada
197 O. Setiawan Djuharie, Teknik dan Panduan Menerjemahkan Bahasa Inggris-Bahasa
Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 38. Lihat juga, Samsuri, Analisis Bahasa (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 238-239.
198 Persona yang berfungsi sebagai empatik disebut persona pemisah (Damîr al-Fasl). Nama ini diistilahkan oleh kalangan linguis Arab untuk memisahkan unit-unit kalimat yang terdiri dari subjek (mubtada`) dan predikat (khabar), atau predikat (khabar) dan sifatnya dengan syarat nomina yang terletak sebelum atau sesudah persona tersebut berupa kata nominal definitif (ism al-ma’rifah). Lihat, Hamâsah ‘Abd al-Latîf, dkk., al-Nahw al-Asâsiy, h. 18; dan Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1984), jilid I, h. 126.

cxxv
ayat 12 surah al-Baqarah: X�zإن FأXونه� sesungguhnya // ا��]-
merekalah yang berbuat kerusakan; dan ayat 120 dalam surah yang
sama: ى�� L6 // katakanlah:”Sesungguhnya إنz ه�ى ا�Zz ه1 ا�
petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”.
Kemudian, pronomina persona pada kolom (3) disebut klausa
verbal, karena persona tersebut harus bergandengan dengan verba.199
Meskipun letak persona itu setelah verba ia bukan merupakan frasa
melainkan klausa. Ia termasuk klausa bebas, yakni klausa yang
mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai
subjek dan predikat.200 Karena itu, klausa Bsu itu sepadan dengan Bsa
karena terdiri dari S (musnad ilaih) dan P (musnad). Hanya pola
terjemahannya harus dilakukan transposisi, yakni mengubah posisi Bsu
(P+S) menjadi posisi Bsa (S+P). Contoh: �\X� // kamu menzalimi
bukan menzalimi kamu, 1�ا' // mereka beriman.
Selain itu, persona yang tidak tampak bentuknya (mustatir)201
seperti kolom (3) pada nomor 9 dan 12, masih tetap pola terjemahannya
seperti contoh sebelumnya. Contoh: �خ // Dia menciptakan, 5خ //
dia berlalu.
Adapun persona yang terdapat pada kolom (4) merupakan klausa
nominal yang termasuk ke dalam klausa terikat, yakni klausa yang tidak
memiliki struktur kalimat yang lengkap. Karena itu, kemungkinan
199 Persona yang harus bergandengan dengan verba dan nomina disebut Damîr Muttasil. 200 Abdul Chaer, Linguistik Umum, h. 236. 201 Persona yang tidak tampak bentuknya (mustatir) dalam Bsu terbagi atas dua kelompok: (1)
Persona yang wajib disimpan, yakni tidak mungkin meletakkan nomina atau persona yang tampak bentuknya (bariz) pada tempat di mana nomina itu berada, seperti verba imperfektif yang diawali hamzah mutakallim (persona I tunggal), nun mutakallim (persona I jamak), ta`mukhatab mufrad mudzakkar (persona II tunggal maskulin), dan verba perintah untuk persona II tunggal maskulin; (2) Persona yang boleh disimpan, yakni persona yang mengacu pada persona III tunggal baik yang maskulin maupun feminin. Lihat, Iman Saiful Mu`minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, h. 148.

cxxvi
klausa macam ini hanya menempati kedudukan subjek, objek atau
pelengkap, seperti: XK� // penduduknya, XK� // أهTuhan kamu, Z // وإ�bagimu.
Bentuk-bentuk persona pada kolom (4) juga bisa menjadi klausa
bebas, yakni klausa yang mempunyai kecenderungan menjadi kalimat
mayor, jika persona tersebut bergandengan dengan verba dan persona
tersebut menempati posisi objek, seperti: 1�6واXه // bunuhlah mereka,
.mereka bertanya kepadamu // �-1��ن
Kemudian, pronomina penunjuk umum (asmâ` al-Isyârah)
banyak dinyatakan dalam ayat-ayat al-Quran sebagai penunjuk nama
tertentu dengan menggunakan isyarah baik secara indrawi atau
maknawi. Penggunaan pronomina penunjuk dapat dinyatakan dengan
menggunakan kata sarana yang mengandung makna isyarah, seperti: ذا ,C^, ذ202.ه��, �2^أو, � Seluruh pronomina penunjuk terikat oleh genitif
dan jumlah, sebagaimana pronomina yang tampak pada tabel berikut:
Tabel 4
Pronomina Penunjuk Bsu
Pronomina Penunjuk Bsu No.
Jumlah Maskulin Feminin
(1) (2) (3) (4)
1. I يه , ذي ذ�^, ذاك, ه ا, ذا ,C ه ,^�
2. II ه���ن, ��ن ذان^, ه ان, ذان
3. III ءFء, أوF`ء أو�2^, هFء, أوF`أو�2^, ه
202 Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid I, h. 127.

cxxvii
Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa penggunaan pronomina
penunjuk (asmâ` al-Isyârah) untuk menunjukkan nomina yang
dimaksud (musyâr ilaih) dalam Bsu cukup bervariatif dalam kalimat.
Yang menjadi titik perhatian bagi pronomina penunjuk adalah
nominanya, baik nomina yang telah disebutkan sebelum maupun
sesudah pronominanya, yakni jika nominanya maskulin maka
pronominanya maskulin; dan jika nominanya feminin maka
pronominanya juga femini. Demikian pula harus ada kesesuaian
jumlahnya antara keduanya, baik tunggal, dual maupun jamak. 203
Berkaitan dengan hal itu, maka relasi makna fungsi antara
pronomina dan nomina dalam surah al-Baqarah terbagi atas dua
kelompok, yaitu: (1) ada nomina yang hanya dinyatakan dengan
pronomina penunjuk, seperti pada ayat 259 surah al-Baqarah: �z�6ل أن 7���C ه���1 � Dia berkata: “Bagaimana Allah // ا�Zz ب:
menghidupkan ini setelah hancur?”. Pronomina pada ayat tersebut
mengacu kepada nomina feminin, yakni al-baldah (negeri);204 (2) ada
yang keduanya dinyatakan dalam kalimat itu, seperti pada ayat 35
dalam surah yang sama: �ب�(� FوC ��ة هz3ا� // Janganlah dekati
pohon ini.
Apabila nomina yang ditunjuk itu kata tunggal maskulin, maka
pronomina yang digunakan adalah ^ذ� atau kata lainnya sebagaimana
pada tabel nomor (1) kolom (3), seperti ayat 2: ��بK�ا ر�F Z�@ D ذ�
// kitab ini tidak ada keraguan padanya. Frasa nominal ini menjadi S
(musnad ilaih); atau jika nomina yang ditunjuk itu kata tunggal feminin,
maka pronomina yang digunakan adalah ^� atau kata lainnya
203 Hamâsah ‘Abd al-Latîf, dkk., al-Nahw al-Asâsiy, h. 18. 204 Muhammad ‘Ali al-Sabûniy, Safwah al-Tafâsîr (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid 1, 149.

cxxviii
sebagaimana tabel nomor (1) kolom (4), seperti ayat 141: � �z� أ6 itu umat yang telah lalu. Fungsi kedua kata itu menjadi S+P dan // خ5
ini berbeda dengan fungsi kata pada contoh ayat 2.
Antara pronomina penunjuk Bsu dan Bsa sepadan dari segi
gramatikalnya. Sedangkan arti atau makna yang dapat dipadankan
dengan Bsa berdasarkan strukturalnya terdapat dua kecenderungan,
yaitu: pertama, apabila nomina yang terletak setelah pronomina
penunjuk itu berupa kata nominal non definitif, maka strukturnya sama
seperti contoh pada ayat 141 di atas; kedua, apabila nomina yang
terletak setelah pronomina penunjuk itu berupa nomina definitif, maka
perlu digunakan transposisi dalam struktur terjemahan Bsa-nya, seperti
contoh pada ayat 2 di atas.205
Selain itu, tidak semua pronomina penunjuk dapat ditemukan
padanannya dalam struktur Bsa, yakni ketika ia terletak setelah
pronomina persona, seperti contoh ayat 85 surah al-Baqarah, dalam
ayat tersebut pronomina penunjuk jamak terletak setelah pronomina
persona II jamak: X�أن zX�ءF kemudian kamu // �)�1ن أن]-XKه
membunuh dirimu sendiri. Pronomina penunjuk pada ayat ini tidak
diterjemahkan oleh tim penerjemah al-Quran Depag RI sama sekali,
karena pronomina tersebut mengandung beberapa kemungkinan fungsi,
sebagai ) 2 ()lûsism mau(penghubung pronomina sebagai ) 1: (yakni
pronomina penunjuk, (3) sebagai kata empatik (taukîd) dan (4) sebagai
nomina yang dipanggil (munâdâ). Kemungkinan yang pertama adalah
205 Pengubahan posisi kata pada frasa nominal Bsu yang berpola D-M dapat dilakukan,
sehingga frasa nominal Bsa menjadi pola M-D, karena transposisi dapat dilakukan dengan cara mengubah struktur kalimat secara keseluruhan, atau mengubah posisi kata, mengubah bentuk jamak ke dalam bentuk tunggal. Lihat Peter Newmark, A Textbook of Translation (Oxford: Pergamon Press, 1988), h. 85.

cxxix
madzhab Kufah, sedang tiga kemungkinan lainnya menurut madzhab
Basrah.206
dilihat dari segi )ûlahsMau-al` Asmâ-al(Pronomina penghubung
definisinya tidak berbeda dengan pronomina sebelumnya, yakni
mengacu pada nomina tertentu, hanya dari segi fungsinya ia
menghubungkan klausa atau kalimat yang terletak sesudahnya. Dan
-Silah alklausa atau kalimat yang terletak setelahnya disebut dengan
pronomina penghubung juga ,Berdasarkan konteks kalimat 207.ûlsMau
mengenal berbagai bentuk menurut genitif dan jumlahnya, sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 5
Pronomina Penghubung Bsu
Pronomina Penunjuk Bsu No.
Jumlah Maskulin Feminin
(1) (2) (3) (4)
1. I ا��7 ا� ي
2. II ان ن ا���ا�
3. III B� 7 ا��G1ا�7, ا�ءي, ا�Gا�
Selain bentuk-bentuk pronomina di atas, ada pronomina yang
tidak terikat dengan genitif dan jumlah, seperti ذا, أي, ذو ,� ,B.
Sehubungan seluruh pronomina yang telah disebutkan itu berfungsi
menghubungkan nomina dengan klausa atau kalimat yang terletak
sesudahnya, maka padanan gramatikalnya dengan Bsa hanya
206 Lihat, Kamâl al-Dîn Abî al-Barakât, al-Insâf fî Masâ il al-Khilâf (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1998), jilid II, h. 223-225. 207 Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid I, h. 129.

cxxx
menggunakan kata sarana penghubung yaitu kata “yang” untuk nomina
yang telah disebutkan sebelumnya dan “orang yang” atau “apa yang”
untuk nomina yang tidak disebutkan sebelumnya, seperti contoh ayat 21
surah al-Baqarah:
XKzوا رب��Aس ا�zا�� ���6 B:� XKXKz ا� z�B خ)XK وا�z ي�� أ�� z��)1ن
“Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”.
Ayat tersebut mengandung dua pronomina penghubung yaitu,
alladzî yang mensifati kata rabbukum dengan padanannya “yang”;
sedangkan pronomina kedua, yakni alladzîna sebagai objek dari verba
khalaqa bukan mengacu pada nomina sebelumnya, sehingga padanan
yang muncul dalam terjemahan Bsa menjadi “orang-orang yang”.
Berdasarkan padanan pronomina di atas, pada ayat 17 surah al-
Baqarah, L=�آ X�= penerjemahan al-Quran Depag ; ا"61�� ن�راا�z ي
terhadap pronomina penghubung yang bergaris bawah tersebut
ditemukan padanan Bsa-nya yang tidak tepat, yaitu dengan terjemahan:
“Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api...”.
Padahal pronomina al-Ladzî menunjukkan nomina tunggal maskulin
seperti yang tertulis dalam tabel di atas pada kolom (3) nomor (1). Dan
terjemahan tersebut seharusnya berbunyi: “Perumpamaan mereka
seperti orang yang menyalakan api”, seperti yang diterjemahkan oleh
beberapa terjemahan al-Quran Indonesia maupun asing.208 Bahkan
208 Mahmud Junus menerjemahkan “Umpama mereka itu seperti orang yang menyalakan
api”. Mahmud Junus, Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia (Jakarta: Al-Hidajah, 1971), h. 20. HB. Jassin menerjemahkan “Perumpamaan mereka adalah seperti orang menyalakan api”. HB. Jassin, al-Quran al-Karim Bacaan Mulia (Djakarta: Djambatan1978), h. 3. Demikian pula Abdullah Yusuf Ali

cxxxi
dalam literatur tafsir, pronomina tersebut ditafsiri dengan bentuk
tunggal maskulin.209
Akhirnya, ketiga pronomina di atas dalam tataran gramatikal
Bsa, seperti penggunaan pronomina dia, nya, ini, itu, yang atau orang-
orang merupakan rujukan anaforis.210 Dengan menggunakan rujukan
anaforis, maka bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang,
melainkan diganti dengan pronomina tersebut, seperti contoh kalimat
Indonesia: Mahasiswa itu bahagia sekali. Dia yakin besok akan
diwisuda. Kata dia menjadi alat penghubung kalimat sebelumnya.
Unsur dia pada kalimat kedua menunjuk mahasiswa pada kalimat
pertama. Oleh karena itu, kalimat-kalimat tersebut menjadi saling
berhubungan. Dan inilah gramatikal yang kohesif, yakni kepaduan
bentuk secara struktural.
2) Kata Bilangan (Numeralia)
Kata bilangan (numeralia) termasuk rumpun nomina, karena
berkaitan dengan nomina yang dibilang. Dilihat dari definisinya,
numeralia digunakan dalam kalimat untuk menghitung banyaknya
orang, binatang atau barang.211
Bilangan Bsu mempunyai aturan yang sangat rumit dibanding
dengan Bsa, baik yang berkaitan dengan bilangan (al-‘Adad) itu sendiri
menerjemahkan “Their similitude is that of a man who kindled a fire”. Lihat Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur-an: Text Translation and Commentary (Lahore: SH Muhammad Ashraf, t.t.), h. 20.
209 Al-Sabûniy menafsirkannya dengan ن�را � Ibn Katsîr menafsirkan dengan , آ��ل ش�� أو6redaksi yang berbeda, yakni ن� �راض�ب ا� ����@)�B ه اا��=L ب�B ا"�61 . Semuanya dipadankan dengan bentuk tunggal maskulin. Lihat, Muhammad ‘Ali al-Sabûniy, Safwah al-Tafâsîr, jilid 1, h. 31.
210 Anaforis merupakan unsur wacana yang menunjuk pada unsur lain yang telah disebutkan sebelumnya. Lihat, Abdul Chaer, Linguistik Umum, h. 270 dan Mulyana, Kajian Wacana (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 27.
211 Hasan Alwi (Ed.), Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 301.

cxxxii
maupun dengan nomina yang dibilang (al-Ma’dûd). Bentuk-bentuk
bilangan Bsu dan nominanya masing-masing berbeda menurut genitif,
dan volumenya sebagaimana tabel berikut:
Tabel 6
Numeralia Bsu dan Bsa
Numeralia Bsu No.
Genitif Volume Bilangan dan Nomina Numeralia Bsa
(1) (2) (3) (4) (5)
1. 1 � Satu buku آ��ب واح
Dua buku آ��ب�ن ا���ن 2 .2
3. 3 – 10 Dآ� ��G�–D�3ة آ�A 3 buku – 10 buku
buku – 12 buku 11 ا��� �3A آ��ب�–أح� �3A آ��ب� 12 – 11 .4
:-� 13 buku – 19 buku� �3A آ��ب�–��G� �3A آ��ب� 19 – 13 .5
6. 21 – 22
ا���ن و�3Aون -واح� و�3Aون آ��ب�
ب�آ��
21 buku – 22 buku
6. 23 – 29 ��G�3ون آ��ب��Aو - �:-�
و�3Aون آ��ب�
23 buku – 29 buku
�ئ� آ��ب 100 .7 100 buku
8.
Maskulin
buku 1000 أ�e آ��ب 1000
Satu kisah 6&� واح�ة 1 .9
Dua kisah 6&��ن ا����ن 2 .10
G�–�&6 �3A 3 kisah – 10 kisahث 6&� 10 – 3 .11
kisah – 12 kisah 11 ا���� �3Aة 6&�– 6&�إح�ي �3Aة 12 – 11 .12
�3A M-� 13 kisah – 19 kisahة &6�G�–ث �3Aة 6&� 19 – 13 .13
14.
Feminin
ا����ن -إح�ي و�3Aون 6&� 22 – 21
و�3Aون 6&�
21 kisah – 22 kisah

cxxxiii
�-G�- Mث و�3Aون 6&� 29 – 23
Aو��3ون 6&
23 kisah – 29 kisah
�ئ� 6&� 100 .15 100 kisah
16. 1000 �&6 e1000 أ� kisah
Berkaitan dengan bilangan Bsu dan nomina yang dibilangnya serta
padanan gramatikalnya dalam Bsa, maka penulis kelompokkan ke
dalam tiga bagian sesuai dengan terjemahan al-Quran Depag RI, yaitu:
(1) Padanan bilangan dan nominanya; (2) Padanan bilangan tanpa
nomina yang dibilang, dan (3) Padanan nomina yang dibilang tanpa
bilangan.
Pertama, padanan bilangan dan nominanya dalam Bsa tidak
variatif dan kontradiktif sebagaimana Bsu-nya, yakni semua bilangan
dan nomina dipadankan dengan menggunakan pola DM (Diterangkan
mendahului Menerangkan), sebagaimana pada tabel di atas kolom (5).
Kemudian, nomina yang dibilang baik itu bentuk tunggal, dual maupun
bentuk jamak dalam Bsu, seluruhnya diubah dengan bentuk tunggal,
seperti contoh dalam surah al-Baqarah ayat 196 dan 226: ��G� م�z�أ //
tiga hari bukan tiga hari-hari, �:أرب �� empat bulan juga bukan // أش
empat bulan-bulan. Sedangkan bilangan dan nomina yang keduanya
dipisahkan oleh preposisi, maka padanannya sama dengan padanan
kedua contoh di atas tanpa mengartikan preposisi itu, seperti pada ayat
260: . ��z<ا� B .ambillah empat ekor burung // @� أرب:�
Kedua, bilangan Bsu tanpa nomina yang dibilang, padanannya
sama dengan bagian pertama, dan nomina yang tidak disebutkan dalam

cxxxiv
teks Bsu dinyatakan dalam Bsa, seperti pada ayat 234 dalam surah yang
sama: �:و أرب �� �3A // empat bulan sepuluh hari.212اأش
Ketiga, nomina yang dibilang tanpa bilangan, padanan yang dapat
disesuaikan dengan Bsa melihat bentuknya, yakni apabila nominanya
itu bentuk tunggal tanpa disertai kata sarana definitif seperti al, maka
padanannya Bsa-nya nomina disertai dengan kata “seorang” untuk
manusia, seperti pada ayat 101: Xءه� �z��ر"1لوZzا� ��A B // dan
tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari Allah; atau “seekor”
untuk binatang, seperti pada ayat 67: �� Zzا� zأن � ب1�ا إن Xب)�ة�آ //
sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor
sapi betina.213 Sedangkan apabila nominanya berbentuk dual, maka
nomina tersebut dinyatakan dengan didahului bilangan “dua”, seperti
pada ayat 102: �A لbأن � dan apa yang diturunkan // ا��B�Kو
kepada dua malaikat.
Namun demikian, ada nomina yang mengandung bilangan dual di
dalamnya, tetapi terjemahan al-Quran Depag tidak menerjemahkannya
menurut bilangan itu melainkan dalam bentuk tunggal, yaitu pada ayat
128: ��: -�B�ربz�� وا � // Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang
yang berserah diri kepada-Mu. Padahal dalam terjemahan al-Quran
lainnya, seperti Mahmud Junus menerjemahkannya : “Ya Tuhan kami,
212 Apabila nomina yang dibilang tidak dinyatakan dalam teks Bsu, maka penentuan
bilangannya boleh dalam bentuk maskulin atau feminin sesuai dengan perkiraan nomina yang dibuang itu, seperti contoh di atas. Lihat, Sanâ Jihâd, Mu’jam al-Tâlib wa al-Kâtib (Beirut: Maktabah Lubnân Nâsyirûn, 1997), h. 351.
213 Terjemahan al-Quran versi Depag menerjemahkan baqarah dengan sapi betina dengan dasar tâ marbûtah menunjukkan tunggal feminin. Sedangkan menurut Quraish Shihab, sebagaimana dalam kamus bahasa bahwa baqarah adalah bentuk tunggal baqar, sementara tâ marbûtah di situ menunjukkan arti seekor atau sebuah bagi nomina maskulin maupun feminin. Lihat, M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi: Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 324 dan lihat juga Syihâb al-Dîn Ahmad al-Misriy, al-Tibyân fî Tafsîr Gharîb al-Qurân (Kairo: Dâr al-Sahâbah li al-Turâts, 1992), h. 92.

cxxxv
jadikanlah kami dua orang yang muslim”. Yusuf Ali juga
mengungkapkannya dengan bentuk jamak, karena bahasa Inggris tidak
mengenal bentuk dual: “Our Lord! Make of us muslims, bowing to Thy
(Will).214
3) Nomina Abstrak dan Konkrit (Abstract and Concrete Noun)
Kedua nomina yang dimaksudkan di sini adalah nomina yang
bentuk-bentuknya mengalami perubahan dan penyesuaian dalam
kalimat. Pembentukan kedua nomina Bsu terjadi karena proses derivasi,
yakni membentuk kata baru dengan identitas leksikal berbeda dengan
kata dasarnya; dan proses inflektif, yakni membentuk kata baru dengan
identitas leksikalnya tidak berbeda dengan kata dasarnya.215
Umpamanya, dari kata islam terbentuk kata muslim; dari kata iman
terbentuk kata mu`min. Kata Islam dengan muslim keduanya berbeda
identitas leksikalnya, meskipun keduanya berkelas nomina. Berbeda
dengan pembentukan secara inflektif, umpamanya kata muslim
terbentuk kata muslimân, muslimûn, muslimah dan muslimât. Semua
kata yang terbentuk itu sama identitas leksikalnya, karena semuanya
terdiri dari huruf dasar yang sama juga semuanya berkelas nomina,
hanya perbedaannya terletak pada makna.
Sehubungan itu, perlu diketahui bahwa nomina-nomina Bsu yang
bercirikan demikian itu terbagi atas nomina yang abstrak dan konkrit.
214 Lihat, Mahmud Junus, Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia, h. 18. Abdullah Yusuf Ali,
The Holy Quran: Text, Translation and Commentary, h. 53. 215 Alat yang digunakan untuk penyesuaian bentuk itu biasanya berupa afiks, yang mungkin
berupa prefiks, infiks, dan sufiks; atau juga berupa modifikasi internal, yakni perubahan yang terjadi di dalam bentuk dasar. Lihat, Abdul Chaer, Linguistik Umum, h. 170; dan O. Setiawan Djuharie, Teknik dan Panduan Menerjemahkan Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, h. 42

cxxxvi
sebagai nomina dar saM-al mengelompokkan sahâamHMuhammad
abstrak.216
kna merupakan nomina yang sekedar menunjukkan madarsMa-Al
peristiwa tanpa terikat dengan waktu serta mengandung semua huruf
yang terdapat di dalam verbanya.217 Karena itu, ia merupakan sumber
derivasi bagi bentuk verba maupun nomina lainnya. Ia dapat berfungsi
sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Namun,
untuk mencari padanannya dalam Bsa sesuai dengan terjemahan al-
dapat digunakan untuk menyatakan beberapa darsMa-Almaka , Quran
keterangan, antara lain: (1) untuk menyatakan keterangan cara, seperti
pada ayat 235: أن �)1�1ا �zإ�F16�@�و: // kecuali kamu mengucapkan
kata-kata yang baik; (2) untuk menyatakan keterangan sebab, seperti
pada ayat 90: Zzل ا�b�وا ب�� أن[K� أن X� // ب�U�ب2-�� اش��وا بZ أن]-
sangatlah buruk mereka menjual dirinya, dengan mengingkari apa
yang diturunkan Allah karena dengki; (3) untuk menyatakan
keterangan similatif, seperti pada ayat 185: Z�@ لbي أن zن ا��]ش�� ر � // Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya��zسه�ىا�)�'ن
diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia; (4) untuk
menyatakan keterangan alasan, seperti pada ayat 207: BوB ا���zس Z-[3�ي ن�ء�U�اب Zz�ض�ت ا� // Dan di antara manusia ada orang
yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah.
yang dikelompokkan pada nomina darsMa-AlBerbeda dengan
abstrak, berikut ini adalah nomina-nomina yang bisa dikategorikan pada
nomina abstrak juga konkrit, yaitu: ism al-Fâ’il, ism al-Maf’ûl, al-Sifah
216 Hamâsah ‘Abd al-Latîf, dkk., al-Nahw al-Asâsiy, h. 83. 217 Apabila nomina itu menunjukkan makna peristiwa tetapi tidak mengandung semua huruf
verbanya dinamakan ism al-Masdar, seperti tawadda`a-wudû`an, takallama-kalâman. Lihat, Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid I, h. 161

cxxxvii
-al(bentuk hyperbola -bentuk, lîdfTa-ism al, Musyabbahah-al
Mubâlaghah), ism al-Zamân, ism al-Makân dan ism al-Âlah.
Ism al-Fâ’il biasanya dipadankan dengan menggunakan partikel
pe-, seperti pembuat, penulis dan pembaca. Namun, ketika nomina
tersebut sulit dipadankan dengan cara itu, maka bisa dilakukan dengan
dua cara lain, yaitu: (1) dengan menggunakan kata kerja, seperti pada
ayat 30 : 7إن�LA� Sungguh Aku hendak // @7 ا��رض خ�]�
menjadikan khalifah, juga seperti pada ayat 145: أن5 ب ��X��بMو��6 // dan engkaupun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Cara itu biasanya
digunakan pada ism al-Fâ’il yang berfungsi seperti verbanya, yakni
verba yang membutuhkan objek atau pelengkap; (2) dengan merujuk
kepada pelaku baik manusia atau lainnya kemudian ditambahkan kata
yang, seperti ayat 23 : X��إن آB�6ص�د // jika kamu orang-orang
yang benar.218 Dan kedua cara itu sesuai dengan definisi ism al-Fâ’il
itu sendiri, yakni sifat yang dipungut dari kata verbal aktif.219
Kemudian, ism al-Maf’ûl dilihat dari definisinya merupakan
kebalikan dari ism al-Fâ’il, yakni terambil dari verba pasif. Sehingga
padanan yang lazim adalah dengan menggunakan partikel di atau ter.
Sehubungan ism al-Maf’ûl juga merupakan sifat, maka terjemahannya
selalu diletakkan kata yang setelah acuan namanya. Tetapi ada juga ism
al-Maf’ûl yang kemudian dipadankan dengan cara lain, seperti kata :�وف pada ayat 263 diartikan yang baik tidak diartikan yang dikenal
atau yang diketahui, juga seperti kata B�"���ا pada ayat 252 diartikan
para rasul tidak diartikan orang-orang yang diutus. Terjemahan jenis
218 Untuk menunjukkan bahwa bentuk ism al-Fâ’il itu jamak ditandai dengan sufiks ون atau
B� , kemudian biasanya dipadankan dengan cara reduplikasi, seperti orang-orang. 219 Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid I, h. 178.

cxxxviii
ini dinamakan terjemahan komunikatif, karena berusaha menciptakan
efek yang dialami pembaca Bsa sama dengan efek yang dialami
pembaca Bsu. Keluwesan kata-kata dan struktur diupayakan dengan
cara menghilangkan bagian struktur kata atau kalimat, atau
menghilangkan pengulangan serta memodifikasi penggunaan jargon.220
Kata nominal Bsu yang digunakan untuk menunjukkan dua hal
. lîdTaf-sm ali disebutyang sama sifatnya dan salah satunya melebihi
Kata yang digunakan untuk menunjukkan kelebihan itu diikutkan pada
pola kata L:@أ / af’alu untuk maskulin dan 7:@ / fu’lâ untuk
feminin.221
yang dapat dipadankan dalam lîdTaf-sm ali pola Adapun
terjemahan terbagi ke dalam dua pola, yaitu:
(1) Nomina yang tidak disertai al dan tidak disandarkan pada nomina
berikutnya, seperti pada ayat 217: ���[�أآ��واL�(�ا B //
Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pola ini
merupakan ungkapan perbandingan (The Comparative expresses)
dan lîdTaf-sm alidua nomina yang terletak sebelum sifat antara
reposisi psesudahnomina yang BKarena ). al ‘alaihddMufa-al( dan setelahnya terdapat frasa preposisinal lîdTaf-ism al, ituB ,
maka pola kalimat tersebut dapat dipadankan secara gramatikal
dalam Bsa-nya dengan pola kalimat “lebih ... daripada ...”222
220 Peter Newmark, Approaches to Translation (Oxford: Pergamon Press, 1981), h. 42 221 Terkecuali pada tiga nomina, yakni khair, syarr dan habb, hamzah pada pola kata af’alu
wajib dibuang, karena tiga kata tersebut secara baku telah banyak digunakan. 222 Ungkapan perbandingan sifat antara dua nomina dalam bahasa Indonesia berbeda dengan
bahasa Inggris. Untuk menunjukkan bahwa ajektiva yang melekat pada nomina itu dibandingkan, bahasa Indonesia hanya menyatakannya dengan lebih ...daripada...tanpa ada perubahan secara flektif pada ajektivanya. Sedangkan bahasa Inggris menyatakannya melalui afiksasi (-er) pada akhir ajektivanya yang kurang dari dua suku kata dan ditambahkan kata than setelahnya. Ajektiva yang terdiri dari tiga suku kata, sebelumnya ditambahkan kata more tanpa afiksasi pada ajektivanya. Lihat,

cxxxix
)2( pada ) fahâdi( disandarkan dan alisertai omina yang tidak dN
nomina berikutnya, seperti pada ayat 96: X�zن� // أح�ص ا���zسو���
Engkau akan mendapati mereka manusia yang paling tamak. Frasa
yang bergaris bawah pada ayat tersebut merupakan ungkapan
b îtarkdengan )esxpressEuperlative SThe (”...ter“paling” atau “
Ungkapan Bsu ini mengandung pola MD dan secara .fiyâdi
gramatikal dapat dipadankan ke dalam Bsa-nya dengan pola DM,
seperti terjemahan pada ayat di atas.
nya dapat dengan segala bentuklîdTaf-ism al, Dengan demikian
dipadankan secara gramatikal dengan penyusunan pola lebih ...daripada
untuk ungkapan perbandingan (comparative) dan perubahan dari pola
MD ke pola DM untuk ungkapan “paling” atau “ter...” (The Superlative
Expresses).
Sedangkan bentuk-bentuk yang hyperbola (mubâlaghah)223 Bsu
dimaksudkan untuk memberikan makna lebih dan banyak pada suatu
bentukan katanya terambil dari bentuk , Pada umumnya. perbuatan
transitif yang memiliki tiga huruf dasar dan terambil dari verbadarsma
serta mengikuti pola kata (wazn) yang populer, seperti fa’’âl, mif’âl,
fa’ûl, fa’îl, fa’il, fi’’îl, fu’alah dan mif’îl.224 Adapun bentuk hyperbola
yang melekat pada nama dan sifat-sifat Allah dapat dipadankan dengan
‘Abd al-Halîm al-Sayyid Munsiy dan ‘Abd al-Razzâq Ibrâhîm, al-Tarjamah: Usûluhâ wa Mabâdi`uhâ wa Tatbîquhâ (Riyad: Dar al-Murîkh, t.t.), h. 53.
223 Bentuk-bentuk kata hyperbola diterima sesuai dengan hasil pendengaran (samâ’iy). Karena itu menurut para peneliti bentuk-bentuknya dikembalikan kepada makna sifat, karena kebanyakan verba itu dijadikan sebagai sifat yang melekat pada diri seseorang. Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid I, h. 193.
224 Yâsîn al-Hâfiz, al-Tahlîl al-Sarfiy (Damsyiq: Dâr al-‘Asmâ`, 1997), h. 123-124.

cxl
menambahkan kata Maha,225 seperti pada ayat 181: X�A M��" Zzا� zإن // Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Ism al-Makan226 bisa saja dipadankan dengan keterangan tempat,
sehingga terjemahannya memunculkan kata tempat, seperti pada ayat
ا��&�� : 285 dan kepada-Mu tempat kembali; tetapi selain itu // وإ��
ada juga kata tempat itu tidak dicantumkan untuk penghematan kata,
seperti pada ayat 115 : �بU��ا��3�ق وا Zz�و // dan milik Allah timur
dan Barat. Padahal al-Masyriq mempunyai makna leksikal, tempat
matahari terbit, kemudian beralih menjadi makna gramatikal, demikian
pula dengan kata al-Maghrib.227
b. Kata verbal
Verba Bsu mengenal adanya tenses atau konsep kala.228 Kala ini
lazimnya menyatakan waktu sudah lampau, sekarang dan akan datang. Kala
yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang lampau disebut kala
dan kala yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang ) îdâm(perfektif
sedang berlangsung disebut kala progresif (hâl). Sedangkan kala yang
menunjukkan perbuatan yang akan berlangsung disebut kala imperfektif
(istiqbâl).
225 Leksikal Maha mempunyai makna besar atau agung. Ia termasuk unsur prefiks sebagai
padanan leksikal bahasa asing dan sebagai unsur pembentuk kata-kata baru, seperti mahakuasa, mahaadil, maha penyayang, maha pengasih, mahaguru, mahasiswa, mahaputra. Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 80.
226 Ism al-Zamân dan ism al-Makân memiliki bentuk-bentuk kata yang sama, perbedaannya terletak pada definisi, yang pertama menunjukkan waktu terjadinya peristiwa sedangkan yang kedua menunjukkan tempat terjadinya; juga perbedaan itu terletak pada makna tekstual, yakni suatu kata yang ditentukan oleh hubungannya dengan kata lain.
227 Makna Gramatikal disebut juga makna konotasi atau makna struktural adalah makna yang timbul akan bergantung pada struktur tertentu sesuai dengan konteks dan situasi di mana kata itu berada. Makna gramatikal biasanya digunakan sebagai pigura bahasa untuk memperoleh makna estetis. Lihat, Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 62.
228 Kala atau tenses adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan dalam predikat. Lihat, Abdul Chaer, Lingusitik Umum, h. 260.

cxli
Bsu termasuk salah satu bahasa yang menandai kala secara morfemis;
artinya pernyataan kala itu ditandai dengan bentuk kata tertentu pada
verbanya. Sehingga verba yang menyatakan kala lampau dikenal dengan
ngkan verba yang menyatakan kala yang Seda). îdmâ(verba perfektif
). âri’dmu(sedang atau akan berlangsung dikenal dengan verba imperfektif
Perubahan verba secara morfemis dari kala perfektif kepada imperfektif
dapat dilihat pada contoh berikut:
Verba perfektif (Bsu) Verba imperfektif (Bsu) Verba Bsa
berkata �)1ل �6ل
XA X:� mengetahui
mengambil ��خ أخ
Berdasarkan contoh di atas, maka bentuk-bentuk verba tersebut
merupakan kata yang sama, yang berarti juga mempunyai identitas leksikal
yang sama, yakni terdiri dari tiga huruf pada verba perfektif, yang
menunjukkan kala lampau. Kemudian menjadi verba imperfektif setelah
mengalami proses derivasional berupa imbuhan (prefiks) huruf yâ`, yang
menunjukkan kala sedang atau akan berlangsung. Meskipun telah terjadi
perubahan, keduanya masih merupakan kelas kata yang sama, yakni verba.
Berbeda dengan Bsa yang tidak menandai kala secara morfemis,
melainkan secara leksikal, antara lain dengan kata sudah untuk kala
lampau, sedang untuk kala kini dan akan untuk kala nanti. Untuk
mengetahui perbedaan ketiga leksikal itu dapat diketahui melalui contoh
berikut:
(1) Dosen itu sudah mengajar
(2) Dosen itu sedang mengajar
(3) Dosen itu akan mengajar

cxlii
Konsep kala Bsu baik yang lampau, kini maupun akan tidak
seluruhnya dipadankan dengan konsep kala Bsa dengan mencantumkan
kata sudah, sedang atau akan pada teks terjemahannya, melainkan jika
konsep kala Bsu tersebut sudah jelas dengan ditandai KS yang
menunjukkan kala lampau, seperti pada ayat 60: XA �6X� // آ�L أن�س 3�ب
Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya; atau KS yang
menunjukkan kala kini, seperti pada ayat 241: س"�)1ل�zا�� B // ا�-�]��ء
Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata; atau KS
yang menunjukkan kala akan, seperti pada ayat 71: ����52 ب� // 1��6ا ا��ن
Mereka berkata, “sekarang barulah engkau menerangkan (hal) yang
sebenarnya.”
Contoh pada ayat 60 di atas, kala Bsu yang ditandai dengan qad dapat
dipadankan dengan kala Bsa telah. Kedua leksikal tersebut mengandung
makna kala lampau. Sementara itu verba yang ditandai dengan qad dan
dipadankan artinya dengan telah terdapat pada enam tempat dari tujuh qad
yang ada dalam surah al-Baqarah. Sedangkan satu qad yang tidak
dipadankan dengan kata telah adalah seperti contoh pada ayat 144 surah al-
Baqarah: ء��z-7 ا�@ � � ن�ى �)�D و6 // Kami melihat wajahmu
menengadah ke langit.
Adapun alasan terjemahan al-Quran Depag RI tidak menerjemahkan
letaknya sebelum verba imperfektif memang karena telah dengan kata qad
) ri’âdMu(letak sebelum verba imperfektif terqad Dan apabila ). ri’âdMu(
maka dipastikan tidak berarti telah melainkan dimungkinkan dua makna,
yaitu mengandung makna sedikit/ jarang (al-taqlîl) atau makna banyak/
sering (al-taktsîr). Untuk menunjukkan bahwa qad di situ mempunyai

cxliii
makna, seharusnya terjemahan al-Quran Depag menerjemahkannya dengan
salah satu maknanya. , yakni jarang atau sering.
Tetapi menurut pendapat al-Zamakhsyariy bahwa qad pada ayat
tersebut mengandung arti banyak (al-taktsîr).229 Dan penggunaan makna
banyak (al-taktsîr) pada kata qad diterapkan terjemahannya oleh
terjemahan al-Quran Depag yang diterbitkan oleh Mujamma’ al-Malik
Fahd.230
c. Kata sarana (Partikel)
Partikel tidak mempunyai arti leksikal, selama ia tidak berkaitan
dengan kelas kata lainnya seperti nomina dan verba. Oleh karena itu, untuk
memudahkan padanan kedua bahasa yang berkaitan dengan kata sarana di
dalam surah al-Baqarah, maka semuanya dapat dikelompokkan ke dalam
tiga bagian, yaitu: (1) Partikel yang berkaitan dengan nomina, seperti fî,
ilâ, ‘alâ, min; (2) Partikel yang berkaitan dengan verba, seperti saufa, qad,
lan; (3) Partikel yang dapat berkaitan dengan keduanya, seperti hamzah,
hal.231 Struktur partikel dalam kalimat menempati posisinya sebelum
nomina dan verba, kecuali partikel nûn taukîd (penegas) yang posisinya
setelah verba.
Kata sarana (partikel) dalam al-Quran sangat variatif menurut
fungsinya, yakni menghubungkan unit-unit kalimat baik kata, frasa, klausa
maupun kalimat dan merubah kalimat deklaratif menjadi kalimat tertentu.
Kemudian, partikel tersebut terbagi dua macam, yaitu: (1) partikel yang
berfungsi sebagai konjungtor yang meliputi preposisi (hurûf al-Jarr),
229 Jamâl al-Dîn Ibn Hisyâm al-Ansâriy, Mughnî al-Labîb (T.t.p.: Dâr Ihyâ`i al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.t.), jilid 1, h. 150. 230 Lihat, Khâdim al-Haramain al-Syarîfain, al-Qurân al-Karîm wa Tarjamah Ma’ânih bi al-
Lughat al-Indûnisiyyah (al-Madînah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Tibâ’at al-Mushaf al-Syarîf, 1418 H), h. 37.
231 Hamâsah ‘Abd al-Latîf, dkk., al-Nahw al-Asâsiy, h. 201.

cxliv
partikel yang ) 2(; )`Istitsnâ-dât alâ(dan ekseptor ) ft‘a-hurûf al(konektor
berfungsi sebagai transformator, partikel yang dapat merubah kalimat
deklaratif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7
Kata Sarana Bsu dan Bsa
Kelas Kata yang
dimasuki No. Jenis KS Bsu
Nomina Verba
Padanan KS Bsa
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Al-Nafy X X Negasi : Bukan, tidak
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Al-Ta`kîd X X Asertif: Sungguh, hanya
3. Al-Istifhâm X X Tanya: Apa (kah), siapa
4. Al-Amr X Perintah: hendaklah
5. Al-Nahy X Larangan: Janganlah
6. drA‘-Al X Sindiran: apakah
7. dîhdTa-Al X Anjuran: mengapakah
8. al-Tamanniy X Harapan nihil: andaikan
9. Al-Tarajjiy X Harapan pasti: andaikan
10. Al-Nidâ’ X Seruan: Wahai, hai
11. tSyar-al X X Syarat: Barangsiapa
12 Al-Qasam X Sumpah: Demi
Seluruh kata sarana Bsu yang terdapat di dalam bagan di atas, secara
struktural menempati posisi sebelum nomina atau verbanya. Demikian pula
padanannya dalam Bsa sama, kecuali kata sarana negasi yang masuk pada
nomina padanannya melalui pengubahan posisi (transposisi) seperti contoh
ayat 8 surah al-Baqarah: B�� mereka bukanlah orang-orang // و� هX ب�
yang beriman. Bsa menempatkan kata bukan setelah nominanya, karena ini

cxlv
merupakan ciri bahwa kata yang terletak sebelum kata bukan adalah
nomina.232
Sementara kata sarana bukanlah jenis kata dalam Bsu, berbeda
dengan jenis kata utama, yakni nomina dan verba. Oleh karena itu, seluruh
kata sarana tidak mempunyai arti leksikal, yakni arti kata secara lepas tanpa
kaitan dengan kata lain. Arti kata sarana barulah jelas setelah dikaitkan
dengan kata lain, misalnya inna Allâh // sesungguhnya Allah; bi al-haqq //
dengan kebenaran; tsumma antum // kemudian kamu; lâ tufsidû //
janganlah berbuat kerusakan. Di samping tidak mempunyai arti leksikal,
kata sarana tidak dapat berubah bentuknya dari kata dasar menjadi kata
turunan.
Padanan kata dan maknanya dalam Bsu maupun Bsa tidak selamanya
mengacu pada makna leksikal, tetapi banyak kata-kata yang dapat
ditentukan maknanya jika kata itu telah berada dalam satuan yang disebut
kalimat. Untuk mengetahui padanan leksikal dan maknanya tentang
partikel, akan penulis jelaskan pada sub bab berikutnya. Itu sebabnya kata-
kata seperti itu disebut kata yang terikat konteks. Kata-kata yang dimaksud
adalah kata sarana.
4. Terjemahan pada tingkat rangkaian kata (Frasa)
Jenis terjemahan di tingkat frasa biasanya merupakan frasa idiom atau
konstruksi frasa yang mapan. Namun frasa yang dimaksudkan di sini adalah
frasa non idiom. Dalam kajian Bsu, frasa dinamakan tarkîb yang
tarkîb dan 233fiy starkîb wayaitu , dikelompokkan menjadi dua macam
232 Ciri kata nominal ada dua, yaitu: (1) dapat diingkari dengan kata bukan; (2) dapat diikuti
oleh kata yang+KS atau yang sangat+KS. Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 82. 233 Tarkîb Wasfiy ialah dua kata atau lebih yang membentuk satuan frasa dengan pola
hubungan benda yang disifati (man’ût) dan sifatnya (na’t).

cxlvi
frasa non idiom dibentuk menurut , Sedangkan dalam kajian Bsa234.âfiydi
hukum DM (Diterangkan mendahului Menerangkan). Dengan demikian,
kedua frasa Bsu di atas tidak ditemukan kesulitan terjemahannya ke dalam
Bsa, karena kesamaan konstruksi, seperti ayat 211 dan 144 surah al-Baqarah:
Contoh:
(1) B X����ه' Xآ Lب7� إ"�ائ� L" ��ب�� ��' @1ل� (2) � ش>� ا��-�� ا���امو
Dan .fiystarkîb waadalah ) 1(Frasa yang bergaris bawah pada contoh
konstruksi Bsu yang digunakan menggunakan hukum DM. Jika diperhatikan
dari susunannya terjemahannya sepadan dengan Bsa (12 = 12), yaitu âyah //
bayyinah (bukti // nyata). Hanya saja, pada frasa Bsu ini seringkali
diterjemahkan dalam Bsa dengan penambahan leksikal “yang” di antara dua
kata, karena memang susunannya tersusun dari nomina dan adjektiva seperti
contoh di atas, sehingga terjemahan itu bisa ditambahkan kata “yang”, dan
terjemahannya menjadi bukti (yang) nyata. Namun ada juga yang
terjemahannya dengan penambahan leksikal “dan”, seperti halâlan // tayyiban
(halan dan baik).235 Bahkan terjemahan sejenis frasa di atas tanpa melalui
penambahan apapun, seperti contoh (1) atau contoh-contoh frasa yang sudah
mapan dan lazim digunakan seperti al-lughah // al-‘arabiyyah (bahasa //
Arab), al-mujtama’ // al-hadîts (masyarakat // modern) dan al-tafkîr // al-
siyâsiy (pemikiran // politik).
Jika . âfiydtarkîb iadalah ) 2( yang bergaris bawah pada contoh Frasa
dilihat dari segi konstruksinya frasa tersebut tidak berbeda dengan frasa Bsu
234 Tarkîb idâfiy ialah dua kata atau lebih yang membentuk satuan frasa dengan pola
hubungan kata pokok yang disandarkan (mudâf) dan kata tambahan yang disandari (mudâf ilaih). 235 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah: Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 76.

cxlvii
pertama, yaitu frasa yang dibentuk menurut hukum DM, sehingga terjemahan
di tingkat frasa ini sepadan (12 = 12), yaitu:
Wajah = muZ ك و 1 2 2 1
Ayat lain, yaitu ayat 164 dalam surah yang sama juga dipadankan
dengan hukum DM, seperti khalqi // al-samâwât (penciptaan // langit), ikhtilâfi
// al-lail (pergantian // malam). Atau juga frasa yang tersusun dari lebih dua
kata terjemahannya sepadan (123 = 123), seperti frasa yang terletak pada ayat
). Allah// keridaan // mencari ( hâAll //tiâd mar // a`âibtigh, 207
Berbeda dengan frasa bahasa Inggris yang konstruksinya menggunakan
hukum MD (Menerangkan mendahului Diterangkan). Terjemahan rangkaian
kata itu dibalik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hukum DM,
sehingga padanannya bukan (12 = 12), tetapi (12 ↔ 21), seperti wajha // ka
(your face). Sementara frasa yang tersusun lebih dari dua kata dan rangkaian
kata pertama tetap diterjemahkan seperti Bsu-nya dan rangkaian dua kata
terakhir menggunakan hukum MD, sehingga padanannya (123 ↔ 132), seperti
ada juga , Namun 236).Pleasure// God’s // gain ( hâ All //tâd mar // a`âibtigh
frasa bahasa Inggris yang tersusun lebih dari dua kata menggunakan hukum
DM seperti bahasa Indonesia dan itupun hanya berlaku pada dua kata yang
// a`âibtighseperti , penghubungsebagai ofkata gunakan engmterakhir dengan 237).of Allah// the pleasure // to earn ( hâ All //tâd mar
Namun demikian, kedua frasa Bsu di atas dalam terjemahan Bsa ada
yang menggunakan hukum MD seperti bahasa Inggris. Hal itu berarti
tarkîb frasa Bsu yang menggunakan seperti, ) 21↔12 (padanannya menjadi
236 Ahmad Zidan dan Dina Zidan, The Glorious Qur`an: Text and Translation (Kairo: Islamic
Inc. Publishing & Distribution, 1996), h. 22 dan 32. 237 Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur-an: Text, Translation & Commentary (Lahore: SH.
Muhammad Ashraf, t.t.), h. 82.

cxlviii
atau dalam bahasa Inggrisnya ) umat// satu (idatan hâw// ummatan , fiyswa
ilâhun Tetapi pada frasa ).makanan// satu (idin hwâ// a’âmin t, )nation// one (
satu ahkannya dengan Quran tidak menerjem-dalam terjemahan al idun hwâ//
// Tuhan melainkan dengan terjemahan padanan budaya yaitu Tuhan // Yang
Maha Esa.238 Dan terjemahan seperti ini dilakukan pada semua frasa yang
-al, 163/Baqarah-yaitu surah al, sebelas tempatdi idun hilâhun wâbertuliskan
-al, 51dan 22 / lhNa-al, 52/ Ibrâhîm, 19/ An’âm-al, 73/ idah`Mâ-al, 171/`âNis
beberapa ayat dan .6/ ilatssdan Fu34 / ajjH-al, 108/ `Anbiyâ-al, 110/ Kahf
surah lainnya.
5. Terjemahan pada tingkat kalimat
Dalam beberapa hal, jika ternyata tingkat frasa tidak bisa dijadikan
satuan terjemahan, maka untuk mencapai padanan yang tepat terjemahan
dilakukan pada tingkat kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini adalah kalimat
menurut struktur gramatikal, kalimat menurut fungsi, dan kalimat menurut
bentuk gayanya. Pengelompokan kalimat seperti itu dimaksudkan untuk
mencari padanan kalimat Bsu dengan Bsa dalam terjemahan.
Kalimat menurut struktur gramatikalnya meliputi beberapa kalimat,
antara lain: a) kalimat tunggal; b) kalimat majemuk; c) kalimat majemuk
setara; d) kalimat majemuk bertingkat.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu
predikat. Gramatika bahasa Arab menyebutnya kalimat sederhana (al-Jumlah
-al(yaitu kalimat nominal , Kalimat ini terdiri dua macam 239).ahtBasî-al
Jumlah al-Ismiyyah) dan kalimat verbal (al-Jumlah al-Fi’liyyah). Adapun
padanan gramatikal Bsu dan Bsa yang berkaitan dengan terjemahan adalah
238 Lihat juga, HB. Jassin, al-Quran al-Karim: Bacaan Mulia (Djakarta: Djambatan, 1978), h.
32 dan Mahmud Junus, Tafsir Quran Karim (Djakarta: Al-Hidajah, 1971), h. 22. 239 Muhammad Ibrâhîm ‘Ubâdah, al-Jumlah al-‘Arabiyyah: Mukawwanâtuhâ-Anwâ’uhâ-
Tahlîluhâ (Kairo: Maktabah al-Âdâb, 2001), h. 136.

cxlix
mengubah pola struktur kata (transposisi). Kalimat verbal Bsu diubah menjadi
kalimat nominal Bsa, seperti pada ayat 7: X� Allah telah // ...خX� ا�A Zz� 61ب
mengunci hati mereka.... Ayat tersebut tidak diterjemahkan mengunci Allah
hati mereka... Kalimat ini tidak lazim dalam bahasa Indonesia, kecuali pada
kalimat yang dianggap kalimat inversi, seperti contoh dalam bahasa Indonesia:
Sepakat kami untuk membantu mereka.
Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua
kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk disebut dalam gramatika bahasa
Arab dengan istilah kalimat bersusun (al-Jumlah al-Murakkabah). Mengingat
hal yang dibicarakan adalah kalimat majemuk, maka maksud dari dua kalimat
tunggal adalah dua klausa. Kalimat majemuk terbagi atas dua macam, yaitu:
a) Kalimat majemuk setara, seperti contoh terjemahan ayat 7: Allah telah
mengunci hati dan pendengaran mereka. Terjemahan ini mengandung dua
klausa yang setara dengan subjek dan predikat yang sama. Kemudian dua
klausa itu dihubungkan dengan menggunakan kata dan. Biasanya kalimat
majemuk setara menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan jenis
hubungan antarklausa. Adapaun jenis hubungan yang muncul dalam
kalimat majemuk setara ini bermacam-macam, antara lain: (1) jenis
penjumlahan, biasanya menggunakan kata penghubung dan, serta, baik,
maupun. Kata-kata ini berfungsi untuk menyatakan penjumlahan atau
gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa dan proses, contohnya seperti di
atas; (2) jenis pertentangan, kata yang digunakannya seperti tetapi,
sedangkan, melainkan. Kata-kata ini berfungsi untuk menyatakan bahwa
hal yang dinyatakan dalam klausa pertama bertentangan dengan klausa
kedua, seperti pada ayat 12 surah al-Baqarah: Ingatlah, sesungguhnya
merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari; (3)

cl
jenis pemilihan, biasanya kata yang sering digunakan adalah atau. Kata ini
berfungsi untuk menyatakan pilihan di antara dua kemungkinan, seperti
pada ayat 135: Dan mereka berkata: “Jadilah kamu (penganut) Yahudi
atau Nasrani; (4) jenis perurutan, dan kata penghubung yang digunakannya
adalah lalu, kemudian. Kata penghubung ini digunakan untuk
menyatakan kejadian yang berurutan, seperti pada ayat 28: Bagaimana
kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia
menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu lalu Dia
menghidupkan kamu kembali.
b) Kalimat majemuk bertingkat, seperti pada terjemahan ayat 23:
“Dan jika kamu meragukan (al-Quran) yang Kami turunkan kepada hamba
Kami, maka buatlah satu surah semisal dengannya...”
Terjemahan ayat di atas adalah kalimat majemuk tak setara, karena terdiri
dari dua klausa, salah satunya klausa bebas dan lainnya terikat. Induk
gagasan dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan pertaliannya dari
sudut pandang yang lain dituangkan ke dalam anak kalimat. Maka
terjemahan ayat itu yang menjadi induk kalimat adalah maka buatlah satu
surah semisal dengannya; sedangkan jika kamu meragukan(al-Quran) yang
Kami turunkan kepada hamba Kami adalah anak kalimat, dengan ciri
adanya penanda kata jika.
Dengan demikian, kalimat majemuk bertingkat ini memiliki jenis hubungan
yang lebih banyak daripada kalimat majemuk setara, antara lain: (1) waktu,
biasanya menggunakan kata penghubung sejak, setelah, sebelum, ketika.
Kata-kata ini mempunyai fungsi untuk menyatakan waktu terjadinya
peristiwa atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama, seperti pada
ayat 254: Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan

cli
kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli; (2) syarat,
seperti kata penghubung apabila, jika, kalau, seandainya. Fungsi kata ini
untuk menyatakan syarat atau pengandaian terlaksananya hal yang disebut
dalam klausa utama, contohnya seperti pada ayat 23 di atas; (3) tujuan,
seperti kata penghubung agar, supaya, untuk. Fungsi kata ini untuk
menyatakan satu tujuan yang disebutkan dalam klausa utama, seperti pada
ayat 207: Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya
untuk mencari keridaan Allah; (4) konsesif, seperti kata penghubung
walaupun, sekalipun, meskipun. Kata ini digunakan untuk menyatakan
pernyataan klausa bawahan yang tidak akan mengubah pernyataan yang
terdapat dalam klausa utama, seperti pada ayat 221: Sungguh hamba
sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik
meskipun dia menarik hatimu; (5) pembandingan, seperti kata penghubung
seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana. Kata ini berfungsi untuk
menyatakan perbandingan antara pernyataan pada klausa utama dengan
pernyataan pada klausa bawahan, seperti pada ayat 17: Perumpamaan
mereka seperti orang yang menyalakan api; (6) penyebaban, seperti kata
penghubung sebab, karena, oleh karena. Kata ini berfungsi untuk
menyatakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu yang dinyatakan dalam
klausa utama, seperti pada ayat 10: dan mereka mendapat azab yang pedih,
karena mereka berdusta; (7) pengakibatkan, seperti kata penghubung
sehingga, maka. Kata ini berfungsi untuk menyatakan akibat apa yang
dinyatakan dalam klausa utama, seperti pada ayat 55: Kami tidak akan
beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas; (8) cara,
seperti kata penghubung dengan, tanpa. Kata ini digunakan untuk
menyatakan cara pelaksanaan dan alat dari apa yang dinyatakan oleh klausa

clii
utama, seperti pada ayat 212: Dan Allah memberi rezeki kepada orang
yang Dia kehendaki tanpa perhitungan; (9) kemiripan, seperti kata
penghubung seolah-olah, seakan-akan. Kata ini untuk menyatakan adanya
kenyataan yang mirip dengan keadaan yang sebenarnya, seperti pada ayat
101: Seakan-akan mereka tidak tahu.
Dalam contoh di atas dapat dilihat dengan jelas jenis hubungan antarklausa,
konjungtor atau kata penghubung, dan fungsinya dalam kalimat majemuk
bertingkat.
Adapun kalimat Bsu menurut fungsinya lebih banyak jenisnya daripada
kalimat Bsa. Perbandingan itu dapat dilihat pada tabel partikel Bsu dan Bsa
sebelum ini. Suatu kalimat menurut fungsinya akan berbeda dengan kalimat
lainnya tergantung kata sarana (partikel) yang masuk ke dalam kalimat itu.
Oleh karena itu, kalimat Bsu menurut fungsinya dapat dipadankan dengan
kalimat Bsa yang meliputi empat macam kalimat, yaitu: a) kalimat berita
(deklaratif); b) kalimat tanya (interogatif); c) kalimat perintah (imperatif); d)
kalimat seru.240
a) Kalimat berita (deklaratif) adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk
menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasinya. Bentuk kalimat
berita bersifat bebas, boleh inversi atau versi, aktif atau pasif, tunggal atau
majemuk, dan sebagainya. Yang terpenting isinya merupakan
pemberitaan.241 Kalimat berita Bsu dapat diungkapkan dalam bentuk
kalimat positif (itsbât), kalimat negatif (nafy), dan kalimat penegas
240 Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 142-145. 241 Kalimat berita mengandung konsekuensi pada pembicara/ penutur dan menimbulkan efek
pada pembaca atau pendengar, apakah berita itu benar atau dusta. Sehingga kalimat yang mengandung pemberitaan itu, dalam Balaghah dinamakan kalâm khabar. Berbeda dengan kalâm insyâ , pembicaranya tidak bisa disebut sebagai orang yang benar atau dusta. Lihat, ‘Ali al-Jârim dan Mustafâ Amîn, al-Balâghah al-Wâdihah. Penerjemah Mujiyo Nurkholis, dkk. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 198.

cliii
(ta`kîd), seperti pada ayat 12 surah al-Baqarah: ون��X هX ا��]-zإن Fأ . Ayat
ini merupakan kalimat berita yang mengandung penegasan melalui empat
partikel, yaitu Fأ untuk peringatan; إن untuk menegaskan; pronomina Xه ; lsFa-r alîamdsebagai ون� ngan kata definitif yang ditandai deا��]-
adanya al,242 sehingga kalimat terjemahannya : ingatlah sesungguhnya
merekalah yang berbuat kerusakan.
b) Kalimat tanya (interogatif) dipakai oleh penutur/ penulis untuk memperoleh
informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra
komunikasinya. Kalimat tanya pada ayat-ayat al-Quran tidak terdapat
penanda berupa tanda tanya, hanya seringkali kalimat itu diawali dengan
kata tanya. Oleh karena itu, dilihat dari bentuknya kalimat tanya Bsu
sepadan dengan kalimat Bsa, yakni penggunaan kata tanya. Namun, dalam
beberapa ayat yang berbentuk kalimat tanya, terjemahan al-Quran Depag
menggunakan tanda tanya di samping kata tanya, seperti pada ayat 44 surah
al-Baqarah: 1ن(:� G@أ // tidakkah kamu mengerti?.
c) Kalimat perintah (imperatif) digunakan oleh penutur untuk menyuruh atau
melarang orang berbuat sesuatu. Dengan demikian, kalimat perintah Bsu
dapat dipadankan dengan kalimat perintah Bsa pada dua macam kalimat,
yaitu: a) kalimat perintah suruhan (jumlah al-Amr); b) kalimat perintah
larangan (jumlah al-Nahy). Keduanya dapat dicontohkan seperti pada ayat
60 surah al-Baqarah: 1ا @7 ا��رض=:� Fو Zzرزق ا� Bآ1ا واش�ب1ا B��-[ // makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan
janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
d) Kalimat seru (esklamatif) dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan
perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan
242 Muhammad Husain Salâmah, al-I’jâz al-Balâghiy fî al-Qurân al-Kârim (Kairo: Dâr al-
Âfâq al-‘Arabiyyah, 2002), h. 18.

cliv
memerlukan reaksi spontan. Pada bahasa tulisan, kalimat ini diakhiri
dengan tanda seru, akan tetapi ayat-ayat al-Quran tidak menggunakannya,
tetapi cukup menggunakan kata sarana yang mengandung perasaan emosi
dan reaksi spontan, misalnya nama-nama yang diawali dengan partikel yâ`
nidâ` atau sejenisnya yang berarti wahai atau hai.243
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan
penutur/ penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar/
pembaca secara tepat pula.244 Sebuah kalimat bisa dikatakan kalimat efektif
jika memenuhi beberapa ciri, antara lain: kesepadanan struktur, keparalelan
bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan
gagasan, dan kelogisan bahasa.245
Di sini, kalimat efektif yang dimaksudkan adalah kalimat Bsa dalam
bentuk terjemahan al-Quran oleh Depag RI. Oleh karena itu, ciri-ciri kalimat
efektif perlu diterapkan dalam terjemahan al-Quran agar pembaca terjemahan
langsung memahami dengan cepat dan tepat.
Di antara kriteria kalimat yang sepadan strukturnya dan kehematan kata
adalah tidak ditemukan subjek yang ganda dalam kalimat itu. Kalimat Bsu
banyak ditemukan subjek yang ganda, misalnya subjek yang berkelas nomina
yang terdiri dari dua pronomina yang terletak setelah partikel penegas, seperti
pada ayat 37: zإنZ 1ه Xح�zاب ا��z1zا�� // Sungguh Allah Maha Penerima taubat,
Maha Penyayang. Ayat tersebut mengandung dua pronomina, yakni Hû yang
mengiringi kata penegas inna dan huwa, yang kalau diterjemahkan sungguh
Dia Dia.... dan ini memunculkan dua subjek, dan untuk menjadikan kalimat
243 Ya nida dalam beberapa tempat boleh dibuang, namun mengandung makna kalimat seru,
seperti seruan nabi Ibrahim kepada Allah dalam bacaan doanya, seperti pada ayat 127: Rabbanâ taqabbal minnâ // sehingga terjemahannya Ya Tuhan kami, terimalah amal kami.”
244 Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 146. 245 E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, Cermat Berbahasa Indonesia (Jakarta: Akademika
Pressindo, 2006), h. 99.

clv
efektif, salah satunya digantikan dengan partikel –lah sebagai penegasan
makna.
Kemudian di antara ciri kalimat efektif adalah ketegasan makna.
Ketegasan makna dapat dinyatakan dengan penggunaan partikel penekanan
(penegasan) seperti partikel –lah pada contoh ayat di atas. Di samping itu,
ayat-ayat al-Quran banyak menggunakan partikel penekanan lainnya baik
dalam kalimat nominal maupun verbal. Partikel-partikel penegasan (taukîd)
dalam terjemahan harus dicarikan padanannya dan juga harus diterjemahkan
untuk menunjukkan adanya ketegasan makna dalam kalimat tersebut.
Ada beberapa ayat yang mengandung kalimat penegasan itu tidak
diterjemahkan oleh Depag RI, seperti pada ayat 30: 7 ا��رض@ LA� إن�7 �آAku hendak menjadikan khalifah ; dan pada ayat 67: X // خ�]��� Zzا� zإن
// Allah memerintahkan kamu. Yang seharusnya terjemahan itu menggunakan
kata sarana penegasan, seperti sungguh atau sesungguhnya.246
Kalimat tidak lengkap (minor) biasa ditemukan dalam bahasa lisan
maupun tulisan. Kalimat itu bisa dinamakan kalimat tidak lengkap, karena ada
unsur-unsur atau satuan-satuan kebahasaan yang dilesapkan. Harimurti
mengistilahkan kalimat ini dengan elipsis.247 Elipsis dalam mikro struktur teks
memegang peranan penting dalam teks susastra, sehingga al-Jurjaniy
248).abtkhi-maziyyah al( memandangnya sebagai aspek keindahan ungkapan
246 Di antara partikel yang termasuk kata sarana penegas adalah inna, anna, lâm al-ibtidâ ,
nûn taukîd, lâm yang terletak sebagai bentuk jawaban sumpah dan qad. Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid 3, h. 264.
247 Harimurti Kridalaksana, Kamus Lingustik (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 40. Elipsis (al-hadzf) termasuk kajian penting dalam sintaksis Bahasa Arab terutama tentang kajian i’râb, mulai dari penggantian vokal tunggal (dammah, fathah, kasrah) dengan sukun atau vokal rangkap (tanwîn) dengan vokal tunggal (fathah) ketika penghentian bacaan dilakukan pada kata atau kalimat, hingga penghilangan huruf pada kata dan penghilangan kata serta klausa pada struktur kalimat. Lihat, Ahmad Sa’d Muhammad, al-Usûl al-Balâghiyyah fî Kitâb Sîbawaih (Kairo: Maktabah al-Âdab, 1999), h. 76. Dan menurut Fokker, unsur yang biasa dilesapkan dalam suatu kalimat adalah subjek atau predikat. Lihat, AA Fokker, Sintaksis Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), h. 88.
248 ‘Abd al-Qâhir al-Jurjâniy, Dalâ il al-I’jâz (Kairo: ‘Abd al-Salâm Hârûn, t.t.), h. 40.

clvi
Tujuan pemakaian elipsis ini, salah satunya yang terpenting adalah untuk
mendapatkan kepraktisan bahasa sehingga bahasa lebih singkat, padat dan
mudah dimengerti dengan cepat.
Dalam struktur Bsu mulai dari huruf, kata, frasa hingga klausa dapat
dilesapkan di dalam kalimat yang mengandung kesejajaran struktur
(paralelisme). Menurut pakar gramatika Bsu bahwa struktur Bsu dapat dinilai
paralel jika memenuhi dua komponen kalimat, yaitu fi’l – fâ’il dan mubtada` -
khabar atau diistilahkan Sîbawaih dengan sebutan musnad – musnad ilaih.
Jika salah satu komponennya tidak terdapat dalam kalimat tersebut, maka
komponen yang dilesapkan itu harus diperkirakan untuk menciptakan kalimat
yang sempurna atau berfaedah.249
Meskipun dalam beberapa ayat al-Quran elipsis digunakan, namun
elipsis itu tidak bisa dipadankan dalam terjemahan Bsa, karena keterpahaman
pembaca terhadap terjemahan diperlukan dalam memahami ayat-ayat al-
Quran, sehingga terjemahan al-Quran Depag tetap menampilkan satuan-satuan
bahasa yang dianggap elipsis.
Adapun di antara komponen kalimat Bsu yang dilesapkan dalam surah
al-Baqarah kemudian pelesapan itu muncul dalam terjemahan al-Quran Depag
RI, antara lain:
a) Nomina, seperti pada ayat 220 surah al-Baqarah berikut : Xوإن ����>1هXKخ1انc@ adalah merekamaka , Dan jika kamu mempergauli mereka‘’//
saudara-saudaramu.’’ Kata yang bergaris bawah, seperti yang terdapat
pada ayat 220 surah al-Baqarah adalah kata nominal yang dilesapkan yaitu
kata ganti nama (pronomina). Adapun pronomina yang dimaksud pada
contoh itu adalah damîr Xه (persona ketiga jamak) yang merujuk kepada
249 Muhammad Ahmad Khidîr, ‘Alâqah al-Zawâhir al-Nahwiyyah bi al-Ma’nâ fi al-Qurân al-
Karîm (Kairo: Maktabah Anglo al-Misriyyah, t.t.) h, 107-108.

clvii
7 (anak-anak yatim).250 Damîr tersebut menempati posisi S atau ا����
musnad ilaih dengan subfungsinya mubtada`.
b) Verba, seperti pada ayat 127: �z� Lz�(� ��zرب // (seraya berdoa), “Ya Tuhan
kami, terimalah (amal) dari kami. Kata verbal yang dilesapkan adalah kata
yaqûlâni (mereka berdua berkata) yang terletak sebelum frasa rabbanâ.
Verba yaqûlâni mengandung S eksplisit yang merujuk kepada Nabi
Ibrahim dan Ismail.251
c) Frasa, seperti pada ayat 196 dalam surah yang sama: 7@ م�z�أ ��G� ��م&@ Maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam ( musim) haji.’’ Pada’‘ // ا����
contoh itu pelesapan terjadi pada fungsi P atau musnad dengan subfungsi
khabar yang terletak setelah KS fâ` jawâb. Dan P yang dimaksud di sini
adalah predikat yang didahulukan (khabar muqaddam) yang terdiri dari
frasa preposisional Z�:@ yang mengandung makna verba imperatif dia
wajib.252
d) klausa, seperti pada ayat 58 surah al-Baqarah: �z<و1�16ا ح // Dan
katakanlah, “Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami).” Pelesapan yang
terjadi pada contoh tersebut adalah pelesapan fungsi S atau musnad ilaih
dengan subfungsi mubtada` yang terletak setelah kata qaul atau setelah
kata-kata yang secara morfemis berasal dari kata qaul, seperti verba
perfektif aktif (qâla), verba perfektif pasif (qîla), verba imperfektif aktif
(yaqûlu), verba imperfektif pasif (yuqâlu), verba imperatif (qul) dan verba
noun (qaul). Sementara verba yang terdapat pada contoh itu adalah verba
imperatif dengan S persona kedua jamak yang merujuk kepada Bani Israil.
250 Demikian menurut pendapat para pakar i’râb al-Quran seperti al-Akhfasy, al-Farrâ`, Abû
‘Ubaidah, al-Zajjâj dan al-Nahhâs. Lihat, Muhammad Ahmad Khidîr, ‘Alâqah al-Zawâhir al-Nahwiyyah bi al-Ma’nâ fi al-Qurân al-Karîm, h, 116.
251 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuhu, jilid 1, h. 188. 252 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuhu, jilid 1, h. 257.

clviii
Sedangkan klausa yang dilesapakan dari konstruksi kalimat ada dua
kemungkinan yaitu klausa �<ح ��A �<اح dan �<ح ���2- .253 Selain itu,
elipsis juga terjadi pada klausa lain, yakni verba imperatif, seperti pada ayat
135 surah al-Baqarah: �[��ح Xإب�اه� �z Lب L6 // ‘’ Katakanlah, “(tidak!)
Tetapi (ikutilah) agama Ibrahim yang lurus.‘’ Menurut Abû ‘Ubaidah,
verba imperatif yang dihilangkan pada ayat tersebut adalah ittabi’û
(ikutilah).254
Kalimat inversi adalah kalimat yang P-nya mendahului S. Urutan P-S
dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Kata atau frasa yang
menempati posisi pertama dalam kalimat itu akan menjadi kata kunci yang
mempengaruhi makna dalam hal menimbulkan kesan tertentu.255 Dengan
demikian, pada kalimat inversi ini tidak terjadi transposisi teks Bsu terhadap
teks Bsa, seperti perubahan fungsi P-S menjadi P-S atau jumlah fi’liyyah
menjadi jumlah ismiyyah.
Pada kenyataannya, kalimat inversi Bsu tidak hanya terjadi pada pola P-
S semata, melainkan pola-pola lainnya juga banyak ditemukan dalam beberapa
ayat al-Quran. Namun, kesepadanan kalimat inversi Bsu dan Bsa harus terjadi
pada Terjemahan al-Quran. Dalam beberapa ayat yang termasuk kalimat
inversi, terjemahan al-Quran Depag juga menerjemahkan dengan kalimat
inversi juga. Oleh karena itu, padanan kalimat inversi Bsu dengan Bsa dapat
dikelompokkan pada dua jenis kalimat (jumlah), yaitu :
a) kalimat nominal (jumlah ismiyyah), seperti pada ayat 142 surah al-Baqarah:
Zz� L6�با��3�قU��وا // katakanlah: “Milik Allah-lah timur dan
253 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuhu, jilid 1, h. 110. 254 Abû ‘Ubaidah, Majâz al-Qurân (Beirut: Mu`assasah al-Risâlah, 1981), jilid 1, h. 57. 255 Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, h. 146.

clix
barat.” Pada contoh ini, kata yang bergaris bawah adalah mubtadâ` (S)
yang seharusnya di permulaan kalimat 256 dan khabarnya (P) setelahnya.
b) kalimat verbal (jumlah fi’liyyah), seperti pada ayat 215 surah al-Baqarah:
X�A Zب Zzا� zنc@ ��خ B dan kebaikan apa saja yang kamu // و� �]:1ا
kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Pada contoh ini
yang didahulukan dalam kalimat tersebut adalah objek (maf’ûl bih)
` mâHal itu disebabkan oleh pentakwilan . sementara verbanya diakhirkan
Wa ayya khairin yakni , syarat dan jawab sebagai pentakwilan ûlahsmau
taf’alû fa inna Allâha bihî ‘alîm.257
Berkaitan dengan inversi dalam kalimat verbal, ternyata ada ayat yang
tidak diterjemahkan menurut kalimat inversi Bsu, seperti pada ayat 41 surah
al-Baqarah: 1ن(z��@ ي�z�وإ // dan bertakwalah hanya kepada-Ku dan juga pada
ayat sebelumnya, ayat 40: ي @�ره1�ن�z�وإ // dan takutlah kepada-Ku saja.
Ayat tersebut maf’ûl bih (O) didahulukan daripada verbanya. Padahal dilihat
ah yang hFâti-surah al5 ama dengan ayat dari bentuknya ayat ini s
terjemahannya : Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Perbedaannya terletak pada
verbanya, yakni verba di atas menggunakan verba imperatif, sedangkan verba
dalam surah al-Fatihah menggunakan verba imperfektif. Padanan terjemahan
yang menunjukkan kalimat inversi pada dua ayat tersebut memang sulit,
sehingga terjemahan al-Quran pada edisi baru merevisinya dengan
mendahulukan verbanya seperti terjemahan di atas. Di sinilah, inkonsistensi
terjadi dalam terjemahan al-Quran Depag edisi baru. Revisi ini seharusnya
256 Berdasarkan definisi mubtadâ , yakni nomina definitif yang dibaca rafa’ yang mestinya
didahulukan serta tidak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka menurut Tammâm Hassân ini merupakan kaidah pokok bagi mubtadâ . Lihat, Tammâm Hassân, al-Usûl: Dirâsah Istimûlujiyyah li al-Fikr al-Lughawiy ‘inda al-‘Arab (Kairo: ‘Âlam al-Kutub, 2000), h. 125.
257 Al-Zajjâj, Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuhu, jilid I, h. 452.

clx
juga melihat terjemahan al-Quran Depag sebelumnya yang dicetak oleh
pemerintah Saudi Arabia yang berbunyi: Dan hanya kepada-Ku-lah kamu
harus bertakwa. Dalam terjemahan al-Quran itu, kalimat inversi Bsu tetap
diterjemahkan menurut kalimat inversi Bsu-nya. Sebab kalimat itu merupakan
kalimat efektif dan indah serta mempunyai maksud, jika ditinjau dari segi gaya
bahasa (retorika) yang benar-benar diperhatikan dan dipentingkan
pembahasannya oleh ahli Balaghah.258 Mungkin ini sebagai alternatif
terjemahan yang berorientasi pada kalimat inversi, meskipun tidak sepenuhnya
benar, yakni dan hanya kepada Aku, hendaklah kamu bertakwa; dan hanya
kepada Aku, hendaklah kamu takut. Munculnya kata hendaklah merupakan
apresiasi makna dari verba imperatif, sebagaimana verba imperfektif yang
dimasuki partikel lâm al-Amr (partikel imperatif), seperti pada ayat 29:
”Barang siapa menghendaki (beriman) maka hendaklah dia beriman, dan
barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.”
6. Terjemahan pada tingkat teks
Terjemahan jenis ini dilakukan apabila terjemahan pada tingkat kalimat
sudah tidak menjadi satuan terjemahan. Teks terjemahannya ialah teks secara
keseluruhan dari beberapa kelompok kalimat mandiri. Menurut Salihen,
bahwa teks yang digunakan untuk terjemahan tingkat ini adalah teks-teks
puisi. Alasan teks puisi menjadi satuan terjemahan, karena antara teks Bsu dan
Bsa tidak bisa ditentukan padanan-padanannya baik di tingkat kata, frasa,
maupun di tingkat kalimat.259
B. PADANAN LEKSIKAL
258 Lihat ‘Abd al-Qâhir al-Jurjâniy, Dalâ il al-I’jâz, h. 108. 259 Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemahan, h. 42.

clxi
Bagaimanapun, sebuah terjemahan adalah kreasi dan ijtihad manusia yang
tidak luput dari kekurangan. Faktor eksternal juga sangat mempengaruhi dalam
terjemahan, yakni bahasa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan
teks Bsu. Karena itu, tugas penerjemah tidak hanya menyampaikan pesan atau
makna teks, melainkan juga menyusunnya dalam Bsa serta memperbaiki
kekurangan-kekurangannya akibat tidak berterima oleh pembaca. Oleh karena itu,
agar bisa dipahami oleh kalangan umum, para penerjemah al-Quran Depag
sepakat untuk tidak menggunakan bahasa ilmu sosial yang sedang berkembang
saat ini, tetapi lebih memilih bahasa Indonesia yang sederhana.260
Terjemahan al-Quran Depag RI juga tidak berbeda jauh dengan
terjemahan-terjemahan pada umumnya. Harus diketahui bahwa menerjemahkan
satu ungkapan al-Quran berarti juga menafsirkan terhadap ungkapan tersebut. Jika
ungkapan al-Quran tersebut mempunyai beberapa kemungkinan arti, maka
penerjemah harus memilih salah satu saja dari sekian arti tersebut. Tidaklah elok,
apabila semua arti tersebut dikemukakan secara keseluruhan. Untuk itu, terjadi
tarik ulur antara satu penerjemah dengan penerjemah lainnya.261
Sehubungan hal itu, antara kata dan arti atau makna tidak bisa dipisahkan
dan itulah yang dibicarakan oleh semantik leksikal yang menekankan kajian
makna pada tingkat kata.262 Dengan demikian, kata merupakan momen
kebahasaan yang bersama-sama dalam kalimat untuk menyampaikan pesan dalam
suatu komunikasi.
260 Ahsin Sakho Muhammad, “Aspek-aspek Penyempurnaan Terjemah dan Tafsir
Departemen Agama ”, h. 162. 261 Ahsin Sakho Muhammad, “Aspek-aspek Penyempurnaan Terjemah dan Tafsir
Departemen Agama ”, h. 156. 262 Verhaar berkata, “Perbedaan antara leksikon dan gramatikal menyebabkan bahwa dalam
semantik kita bedakan pula antara semantik leksikal dan semantik gramatikal.” Mengenai semantik leksikal tidak terlalu sulit: sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal; makna tiap kata diuraikan di situ. Lihat, Verhaar, Pengantar Linguistik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), h. 9.

clxii
Melihat kenyataan yang terdapat di dalam al-Quran maupun terjemahannya
bentukan kata dapat dibagi atas: 1) bentuk dasar (leksem) yang bermakna leksikal,
2) paduan leksem, 3) bentuk imbuhan, 4) bentuk berulang, 5) bentuk majemuk, 6)
bentuk yang terikat dengan konteks kalimat.
1. Leksem dan makna leksikal
Setiap kata mempunyai bentuk, dan dalam beberapa hal, ada kata yang
memiliki bentuk dasar yang oleh para linguis disebut leksem.263 Leksikal
adalah bentuk ajektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon (vokabuler,
kosakata, perbendaharaan kata). Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu
satuan bentuk bahasa yang bermakna. Kalau leksikon disamakan dengan
kosakata atau perbendaharaan kata, maka leksem dapat dipersamakan dengan
kata.264 Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang
bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata.
Kemudian, makna leksikal juga dapat dikatakan makna yang sesuai
dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau
makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Umpamanya kata
jannah makna leksikalnya adalah taman yang memiliki pepohonan sehingga
bumi tertutupinya.265 Jannah dalam bentuk tunggal yang diartikan kebun
dalam surah al-Baqarah hanya terdapat pada dua ayat, yakni ayat 265 dan 266:
L=�آ�z� Lواب �� seperti sebuah kebun yang terletak di dataran // ب�ب1ة أص�ب
tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Sedangkan jannah yang diartikan surga
bisa berbentuk tunggal dan jamak. Namun jannah yang mempunyai arti surga
secara umum dinyatakan dalam bentuk jamak, yakni jannât seperti pada ayat
25: X�� zتأن�z� �� ا��ن��ر ��� B sesungguhnya mereka disediakan // ���ي
263 P.H. Mattews, Morphology an Introduction to The Theory of Word Structures (Cambridge:
Cambridge University Press, 1972), h. 22. 264 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 60. 265 Al-Husain Ibn Muhammad al-Asfahâniy, al-Mufradât fî Gharâ ib al-Qurân, h. 105.

clxiii
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menurut Ibn ‘Abbâs
jannah yang berarti surga seringkali dijamakkan, karena keberadaan surga itu
jumlahnya tujuh, yaitu al-Firdaus, ‘Adn, al-Na’îm, Dâr al-Khuld, al-Ma`wâ`,
Dâr al-Salâm dan ‘Illiyyîn.266 Sebenarnya yang terjadi adalah pepohonan pada
pengertian kebun, lalu digunakan secara metaforis, perbandingan. Yang
diperbandingkan adalah pepohonan sebagai komponen utama kebun, sehingga
surga diserupakan dengan kebun atau taman di bumi, meskipun antara
keduanya terdapat perbedaan.
Makna yang dimaksud di sini adalah bentuk yang sudah dapat
diperhitungkan sebagai kata. Dalam kata-kata al-Quran terdapat kata kharaja,
dan kata ini menghasilkan bentuk kata turunan menjadi khurija, akhraja,
kharraja, takharraja dan istikhraja. Demikian pula dalam terjemahannya, kata
keluar dapat menghasilkan kata turunan mengeluarkan, dikeluarkan. Dua kata
tadi, yakni kharaja dan keluar telah memiliki makna leksikal, dan demikian
pula kata turunannya. Dan bentuk-bentuk kata ini dapat ditemukan di dalam
kamus bahasa. Jadi, makna dalam leksem di sini adalah makna leksikal yang
terdapat dalam leksem yang berwujud kata, yang makna leksikalnya dapat
dicari dalam kamus.
2. Bentuk paduan leksem dan maknanya
Kata-kata al-Quran yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia juga banyak ditemukan yang berbentuk paduan leksem, yakni
gabungan dua leksem atau lebih yang diperhitungkan sebagai kata.267
266 Al-Husain Ibn Muhammad al-Asfahâniy, al-Mufradât fî Gharâ ib al-Qurân, h. 106. 267 Harimurti Kridalaksana, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia,
1989), h. 104.

clxiv
Pada bagian ini, penulis ambil beberapa contoh paduan leksem yang
terdapat di dalam surah al-Baqarah dalam bentuk kata Bsu dan terjemahannya
menurut terjemahan al-Quran Depag, di antaranya:
Inti Paduan Makna
(a) Ahl Ahl al-Kitâb Ahli Kitab
(b) Millah Millah Ibrâhîm Agama Ibrahim
(c) Maqâm Maqâm Ibrâhîm Maqam Ibrahim
(e) Wajh Wajh Allâh Rida Allah
Kata Ahl secara leksikal berarti famili, keluarga, kerabat. Sedangkan
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia di samping bermakna famili, keluarga
juga bermakna orang yang mahir dalam sesuatu ilmu (pengetahuan,
kepandaian).268 Dan al-Kitâb merupakan kata yang memiliki makna kognitif
dan emotif ,269 yakni makna kognitif jika diartikan buku, kitab. Sedangkan
makna emotifnya bisa bermacam-macam kitab, seperti kitab al-Quran, kitab
Injil dan Taurat, sebagaimana kata kitâb banyak disebut-sebut dalam al-Quran.
Kata Ahl al-Kitâb itu sendiri juga banyak disebutkan dalam al-Quran
sebanyak 31 kali. Delapan surah masuk kategori Madaniyah dan satu surah
Makkiyah. Dari beberapa surah yang menceritakan Ahl al-Kitâb itu dapat
dirujukan kepada umat yang beragama Yahudi, Nasrani, dan agama lain
seperti Sabiin dan Majusi serta agama lainnya di luar Islam.270
268 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.
19. 269 Makna kognitif disebut juga makna deskriptif atau denotatif adalah makna yang
menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Ini berarti makna tersebut memiliki acuan (referent) sesuatu yang telah disepakati oleh masyarakat, karena itu makna kognitif disebut juga makna referensial. Sedangkan makna emotif adalah makna yang melibatkan perasaan (pembicara dan pendengar; penulis dan pembaca). Lihat, T. Fatimah Djajasudarma, Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna (Bandung: Refika Aditama, 1999), h. 11.
270 M. Yudhie R. Haryono, Bahasa Politik al-Quran (Bekasi: Gugus Press, 2002), h. 239.

clxv
Sedangkan Ahli Kitab menurut kamus bahasa Indonesia mengandung
dua pengertian, yaitu: (1) orang-orang yang berkitab suci; (2) orang yang ahli
dalam pengetahuan kitab suci.271 Dengan demikian, terdapat kesepadanan
leksikal, yaitu kitab. Ia termasuk kata bebas, yakni kata yang dapat berdiri
sendiri dalam ujaran tanpa mendapat imbuhan atau tanpa di dampingi kata
yang lain, serta kata bebas maknanya bisa bergeser apabila kata tersebut
berada di dalam kalimat.272
Millah mengandung makna leksikal syariat agama (al-Syarî’ah fî al-
Dîn) dan agama (al-Dîn).273 Baik kata millah maupun al-Dîn keduanya
diterjemahkan dengan agama. Padahal makna keduanya berbeda, yakni kata
al-Dîn diungkapkan untuk menyatakan ketaatan dan ketundukan kepada
syari’at.274 Kata millah adalah nama syariat Allah untuk dilaksanakan oleh
para hamba-Nya melalui para nabi. 275 Perbedaannya bahwa kata millah tidak
disandarkan kecuali hanya pada nabi tertentu, seperti pada ayat 135 surah al-
Baqarah: �[��ح Xإب�اه� �z Lب L6 // katakanlah: “Tidak! Tetapi kami
mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Bahkan hampir tidak ditemukan kata
millah disandarkan pada nama Allah, apalagi kepada umat nabi.
Kata Maqâm diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menurut
transliterasinya, karena sulit untuk dicarikan padanannya, sehingga kata
tersebut dijelaskan dalam catatan kaki. Hal itu disebabkan oleh makna yang
terkandung dalam kata Maqâm tidak ditemukan padanannya. Meskipun,
bahasa Indonesia memiliki kata makam, kata ini tidak bisa dipadankan, karena
kata makam mempunyai arti (1) tempat tinggal, kediaman ; (2) kubur,
271 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 19. 272 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 139. 273 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), h. 1360. 274 Al-Husain Ibn Muhammad al-Asfahâniy, al-Mufradât fî Gharâ ib al-Qurân, h. 181. 275 Al-Husain Ibn Muhammad al-Asfahâniy, al-Mufradât fî Gharâ ib al-Qurân, h. 476.

clxvi
permakaman.276 Padahal Maqâm yang dimaksudkan dalam ayat tersebut
adalah batu yang dijadikan tempat berdiri nabi Ibrahim saat membangun
Ka’bah.277
wajhKetika ). anggota tubuh (ahhriJâ-alpada asalnya adalah Wajh
diartikan muka, maka anggota tubuh itulah yang pertama kali menghadap.278
Inilah yang dinamakan makna leksikal.
Kata nominal wajh seperti pada ayat 115 dan 272 surah al-Baqarah
diterjemahkan dengan arti yang berbeda. Pada ayat 115 diterjemahkan dengan
wajah, maksudnya adalah arah Allah (al-Jihah); dan pada ayat 272
Meskipun kata yang sama tersebut ). ât Allahdmar( ridaditerjemahkan dengan
diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda, pada esensinya kedua kata
tersebut disandarkan pada Allah. Sehingga arah Allah yang dimaksudkan
adalah arah yang diridai Allah dan diperintahkah untuk menghadapnya.279
Sedangkan wajh yang diterjemahkan rida Allah termasuk metaphora (majâz
mursal), meskipun yang dinyatakan itu sebagian (wajh) namun yang
dimaksudkan adalah keseluruhan. Inilah yang diistilahkan dalam retorika
bahasa Arab dengan majâz mursal ‘alâqatuhu al-Juz`iyyah.280
3. Bentuk kata berimbuhan dan maknanya
Setiap leksem atau kata yang mendapatkan imbuhan akan
mengakibatkan munculnya makna baru. Bahkan Ibn Jinniy mengakui adanya
makna tambahan dari makna kata dasar karena adanya tambahan huruf atau
harakat.281 Baik kata-kata yang terdapat di dalam al-Quran maupun bahasa
276 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 622. 277 Muhammad ‘Ali al-Sâbûniy, Safwah al-Tafâsir (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid I, h. 83. 278 Lihat, Al-Husain Ibn Muhammad al-Asfahâniy, al-Mufradât fî Gharâ ib al-Qurân, h. 529.
Lihat juga W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 1145. 279 Muhammad ‘Ali al-Sâbûniy, Safwah al-Tafâsir (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid I, h. 78. 280 Al-Sâbûniy, Safwah al-Tafâsir, jilid I, h. 91. 281 Abû al-Fath ‘Utsmân Ibn Jinniy, al-Khasâis (Kairo: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiy, 1957), jilid I,
h. 223.

clxvii
Indonesia tidak jauh berbeda mengenai perubahan makna akibat imbuhan itu.
Sehingga kata-kata berimbuhan dalam al-Quran menjadikan kata-kata
terjemahanpun berbeda dengan leksem atau kata sebelumnya.
Kebanyakan kata-kata nominal dan verbal Bsu yang mengalami derivasi
dan fleksi akan mengalami perubahan makna. Misalnya kata nominal yang
yang semula , akan berpengaruh terhadap maknaah tmarbu` taditambahkan
maskulin berubah menjadi feminin. Namun tidak semua kata yang
ditambahkan ta` marbutah menjadi feminin, seperti kata kitâbah yang berarti
tulisan. Untuk itu, imbuhan kata nominal maupun verbal Bsu terdiri dari
morfem bebas dan morfem terikat. Penambahan itu bisa dilakukan dengan
cara derivasional (isytiqâqiy) maupun flektif (i’râbiy), seperti contoh berikut
ini:
a. Qatala : yaqtulu, qatlah, qitlah, qâtil, maqtûl dan seterusnya.
b. Qatala-yaqtulu : qâtala-yuqâtilu, taqâtala-yataqâtalu, iqtatala-yaqtatilu.
. âdiqâtS , âdiqatânS , âdiqahS , âdiqûnS , âdiqânS: diqâS. c
Contoh pada (a) Qatala verba perfektif dengan makna (telah
membunuh); beralih kepada bentuk berikutnya yaitu verba imperfektif dengan
imbuhan huruf yâ` dengan makna (akan / sedang membunuh); kemudian dua
dengan ahtmarbû` tâdengan imbuhan darsmakata berikutnya adalah bentuk
makna (pembunuhan): Qâtil dan Maqtûl adalah ism al-Fâ’il dan ism al-Maf’ûl
masing-masing memiliki makna (orang yang membunuh atau pembunuh) dan
(orang yang terbunuh). Penambahan sejenis ini dinamakan perubahan secara
derivasional (isytiqâqiy).
Sedangkan contoh (b) adalah imbuhan yang terjadi pada verba, sehingga
yang asalnya verba tersebut terdiri dari tiga huruf dasar menjadi beberapa
empat dan lima huruf. Masuknya imbuhan pada verba akan mempengaruhi

clxviii
maknanya, seperti yang digambarkan dengan jelas serta perbedaan maknanya
nampak sekali, jika dilihat dari segi terjemahannya seperti pada ayat 154
surah al-Baqarah : B�� 1�1ا(� FوL�(� ... // Dan janganlah kamu mengatakan
orang-orang yang terbunuh ...191: F1و��(� Xه // Dan janganlah kamu
perangi mereka ;ayat 253: � Zz1او1� ش�ء ا�ا6�� // kalau Allah menghendaki
tidaklah mereka berbunuh-bunuhan.
Kemudian, contoh (c) adalah bentuk nomina yang perubahannya secara
inflektif, di mana imbuhan-imbuhan yang terletak di akhir kata itu akan
menjadi penentu dalam kalimat dari segi perubahan akhir kata (i’râb).
Contohnya pada ayat 23 surah al-Baqarah: B�6ص�د X��إن آ // Jika kamu
orang-orang yang benar. Kata B�6ص�د adalah bentuk jamak maskulin,
sehingga terjemahannya ditunjukkan dengan cara reduplikasi.
Dengan demikian, bahwa kata-kata Bsu yang mengalami imbuhan
, qatalaseperti , )bebas (hurrmorfem ) 1: (yaitu, tersusun dari tiga morfem
pada verba `yâseperti huruf , )terikat (qiyâmuqayyad isytiqmorfem ) 2(; âdiqs
nûn dan ` yâ huruf seperti, )terikat (muqayyad i’râbiymorfem ) 3(imperfektif
yaitu , Ketiga morfem ini menurut Abdul Chaer dibagi dua. âdiqînspada
morfem utuh yang dinamakan dengan morfem bebas, dan morfem terbagi
yaitu morfem terikat yang terletak di awal atau pertengahan kata dan morfem
yang terletak di akhir sebagai tanda perubahan (i’râb). 282
4. Bentuk kata berulang dan maknanya
282 Morfem utuh dinamakan juga morfem bebas, yakni morfem yang tanpa kehadiran morfem
lain dapat muncul dalam pertuturan, seperti rumah, satu. Sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah, seperti kata rumah menjadi perumahan; satu menjadi kesatuan. Lihat, Abdul Chaer, Linguistik Umum, h. 153.

clxix
Bentuk kata berulang banyak digunakan oleh Bsa, sementara Bsu tidak
menggunakannya kecuali untuk menegaskan (taukîd) kata yang dimaksud.283
Kata berulang atau reduplikasi merupakan pengulangan satuan gramatik, baik
seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak.284
Adapun pengulangan bentuk kata Bsa mengandung beberapa makna,
antara lain: 1) menyatakan banyak (jamak). Kata-kata Bsu yang dianggap
jamak dipadankan secara leksikal dengan pengulangan kata, seperti al-
Khâsyi’ûn/ al-Khâsyi’în // orang-orang yang khusyuk bermakna banyak orang
yang khusyuk, al-Malâikat // malaikat-malaikat bermakna banyak malaikat ,
Syayâtîn // setan-setan bermakna banyak setan; 2) menyatakan bermacam-
macam, seperti tsamarah // buah-buahan; 3) menyatakan perbuatan yang
disebutkan pada leksem dilaksanakan berulang-ulang, seperti yastahzi`u //
memperolok-olokkan, ya’mahûn // terombang-ambing. 4) menyatakan paling,
tingkat yang paling tinggi yang dapat diperoleh, seperti asyadd al-‘Adzâb//
siksa yang seberat-beratnya yang bermakna siksa yang paling berat.
5. Bentuk kata majemuk dan maknanya
Ramlan mendefinisikan kata majemuk adalah kata yang terdiri dari dua
kata sebagai unsurnya.285 Dari batasan ini, makna yang muncul bukanlah
gabungan makna pada tiap unsurnya, melainkan makna lain dari unsur yang
membentuknya. Misalnya rumah sakit. Kata rumah mempunyai makna
leksikal, kata sakit mempunyai makna leksikal, tetapi yang dimaksud dengan
makna rumah sakit adalah rumah tempat orang sakit.
283 Pengulangan kelas kata yang sama baik berupa nomina maupun verba dimaksudkan untuk
menegaskan. Penegasan bisa dilakukan dengan mengulang kata yang sama, klausa atau kalimat yang sama. Lihat, Mustafâ al-Ghalâyainiy, Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah, jilid III, h. 232.
284 M. Ramlan, Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif (Yogyakarta: CV. Karyono, 1983), h. 55. 285 M. Ramlan, Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif , h. 145.

clxx
Dengan demikian, kata majemuk dapat ditelusuri melalui kategori kata
yang membentuknya. Kemudian, yang perlu diketahui di sini, adalah kata-kata
Bsu yang dipadankan secara leksikal dalam bentuk kata majemuk.286
Adapun makna yang terkandung dalam kata majemuk antara lain: (a)
tKhai- alseperti, warna) b(; bulan Ramadan// nâdsyahr Ramaseperti , waktu
, dan) d(; bulan sabit // Ahillah-alseperti , bentuk) c(; benang putih// dAbya-al
seperti dzurriyyah // anak cucu; (e) dari, seperti lahm al-Khinzîr// daging babi.
Berdasarkan contoh-contoh dan maknanya di atas, maka tidak semua
kata majemuk (tarkîb) Bsu dapat dipadankan secara leksikal dengan padanan
kata majemuk Bsa lagi, karena seringkali kata majemuk (tarkîb) Bsu hanya
merupakan paduan leksem dalam Bsa, seperti yang dijelaskan pada bagian
sebelumnya, atau merupakan kata majemuk itu sendiri.
6. Bentuk kata yang terikat dengan konteks kalimat
Padanan kata dan maknanya dalam Bsu maupun Bsa tidak selamanya
mengacu pada makna leksikal, tetapi banyak kata-kata yang dapat ditentukan
maknanya jika kata itu telah berada dalam satuan yang disebut kalimat. Itu
sebabnya kata-kata seperti itu disebut kata yang terikat konteks, sebagaimana
yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa kata yang maknanya terikat dengan
konteks adalah kata sarana. Kata sarana bukanlah merupakan kata yang
mandiri dan tidak mempunyai makna leksikal. Oleh karena itu, dia harus
disandingkan dengan kata utama lainnya, seperti nomina dan verba. 287
286 Ada beberapa ciri yang dapat membedakan kata majemuk dengan unsur lainnya, antara
lain: (1) tidak dapat diperluas, (2) tidak dapat disela, (3) tidak dapat diubah strukturnya, (4) tidak dapat dijauhkan. Lihat, Hasan Alwi, dkk., Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud, 1993), h. 165.
287 Kata sarana pada umumnya memiliki karakteristik sendiri, antara lain: (1) urutannya terletak sebelum kelas kata lainnya, (2) persandingannya dengan kata lain tidak bisa dipisahkan dalam kalimat, (3) relasi maknanya mengubah makna leksikal menjadi makna fungsi, (4) makna kalimat menjadi berubah dengan kehadirannya, (5) penulisannya menjadi berubah ketika dia bersambungan atau tidak bersambungan dengan nomina, seperti preposisi dalam bahasa Arab yang bersambungan dengan pronomina persona dan dengan non pronomina persona. Karakteristik yang kelima ini tidak

clxxi
Adapun makna kata yang berdampingan dengan nomina antara lain: (a)
pembatasan, seperti kata hanya dan saja. Contohnya pada ayat 102:
Sesungguhnya kami hanyalah cobaan; (b) tempat berada, seperti kata di,
pada, dalam. Contohnya pada ayat 11: Janganlah berbuat kerusakan di
bumi; (c) asal, seperti kata dari. Contohnya pada ayat 4: Mereka mendapat
petunjuk dari Tuhannya; (d) hal atau perkara, seperti kata tentang. Contohnya
pada ayat 189: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit; (e) batas
tempat dan waktu, seperti kata sejak, hingga. Contohnya pada ayat 187:
Kemudian sempurnakanlah puasa hingga (datang) malam.
Sedangkan makna kata yang berdampingan dengan verba antara lain: (a)
pembatasan, seperti kata hanya dan saja. Contohnya pada ayat 169:
Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji;
(b) pengingkaran, seperti kata tidak. Contohnya pada ayat 48: Dan mereka
tidak akan ditolong; (c) berbagai aspek, seperti kata telah, sedang, akan.
Contohnya pada ayat 47: Dan sungguh Aku telah melebihkan kamu dari
semua umat yang lain di alam ini.
Demikian leksikal dan maknanya dalam terjemahan al-Quran yang
semestinya dicarikan padanannya, untuk lebih mengetahui sejauh mana
perbadingan keduanya baik dalam bentuk leksem maupun maknanya.
Kenyataannya, sebagai bahasa yang berbeda rumpun, adalah suatu
keniscayaan bahwa perbedaan dan persamaan itu ada. Hanya kemudian,
perbedaan dan persamaan itu harus dibuktikan dengan contoh-contoh dan
alasan yang sesuai menurut kaidah-kaidah kebahasaan. Begitu pula al-Quran
yang memuat berbagai macam leksem atau kata mengandung berbagai macam
makna (multi makna) yang dikontrastifkan dengan bahasa terjemahannya,
dimiliki oleh bahasa lainnya, kecuali bahasa Arab. Lihat Tammâm Hassân, al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma’nâhâ wa Mabnâhâ, (Kairo: ‘Âlam al-Kutub, 1998), h. 125-127.

clxxii
yakni bahasa Indonesia. Sehingga, keterpaduan antara kata dan makna dapat
dipahami dengan mudah oleh para pembaca, yang sekiranya mereka membaca
terjemahan seperti membaca teks aslinya.
C. JENIS MAKNA DALAM TERJEMAHAN AL-QURAN
Makna288 dalam terjemahan al-Quran tidak berbeda jauh dengan makna
atau tipe makna dalam kajian linguistik, karena sarana terjemahan adalah bahasa
juga. Sesungguhnya jenis makna memang dapat dibedakan berdasarkan beberapa
kriteria dan sudut pandang. Pada bagian ini, ternyata ada beberapa makna yang
dapat ditemukan dalam terjemahan kaitannya dengan ayat-ayat al-Quran.
Berdasarkan jenis semantiknya, jenis makna dapat dibedakan antara makna
leksikal dan makna gramatikal, yang sebagian sudah dijelaskan pada sub bab
sebelumnya. Makna leksikal biasanya dipertentangkan atau dioposisikan dengan
makna gramatikal. Kalau makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem
atau kata yang sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal ini adalah
makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi,
proses reduplikasi dan proses komposisi.289 Proses afiksasi misalnya awalan yâ`
karena , akan berbeda maknanya) âri’dMu-fi’il al(rfektif pada verba impe` tâdan
mengandung subjek yang berbeda. Kalau yâ` subjeknya adalah persona ketiga
yaitu dia, sedangkan tâ` adalah persona kedua yaitu kamu, dan seterusnya.
288 Persoalan makna dalam suatu bahasa tidak lepas dari tiga hal, yang menurut Ullmann tiga
hal itu adalah name, sense dan thing. Soal makna terdapat dalam sense, dan terdapat hubungan timbal balik antara sense dan name. Apabila seseorang mendengar kata tertentu, ia dapat membayangkan bendanya atau sesuatu yang diacu, dan apabila seseorang membayangkan sesuatu, ia segera dapat mengatakan pengertiannya itu. Hubungan antara nama dan pengertiannya itu disebut dengan makna. Acuan dalam makna tidak disebut-sebut oleh Ullmann, karena ia di luar jangkauan linguis. Lihat, Stephen Ullmann, Semantics an Introduction to The Science of Meaning, (Oxford: Basil Balckwell, 1972), h. 57.
289 Makna gramatikal (gramatical meaning) mempunyai kesamaan istilah dengan makna fungsional (fungsional meaning), makna struktural (structural meaning), makna internal (internal meaning) adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, h. 103.

clxxiii
Kemudian, berdasarkan acuannya jenis makna dapat dibagi kepada dua
bagian, yaitu: (1) makna referensial, dan (2) makna nonreferensial. Bila kata-
kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu,
maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial. Kalau kata itu tidak
mempunyai referen (acuan), maka kata itu bermakna nonreferensial.
Dapat dikatakan bahwa kata-kata yang termasuk kategori kata penuh (full
word) adalah termasuk kata-kata yang bermakna refensial, misalnya syajarah
(pohon), nakhîl (kurma), a’nâb (anggur), kursiy (kursi), dan sebagainya. Contoh
kata yang terakhir, yakni kursi bisa mengandung beberapa kemungkinan makna.
Kata kursi sebagaimana dalam terjemahan ayat 255 surah al-Baqarah yang
disandarkan pada pronomina persona ketiga yang mengacu kepada Allah bisa
mengandung beberapa makna, antara lain: (1) makna referensial, yaitu apabila
kata kursi tersebut masih menunjuk pada referen dasar sesuai dengan berbagai
fakta maupun ciri yang dimiliki, misalnya adalah 290 ; (2) makna konseptual,
yaitu apabila denotasi makna kata yang dihasilkan dari konseptualisasi
pemakainya, misalnya kursi ialah “tempat duduk”; (3) makna intensional, yaitu
pemberian makna sangat ditentukan oleh motivasi, minat, maksud maupun tujuan
pemakainya. Makna ketiga ini secara subjektif dapat diacukan pada makna
tertentu. Oleh karena itu, terjemahan kursi ditambahkan penjelasannya pada
catatan kaki dengan memunculkan pendapat mufassir, antara lain pendapat Ibn
‘Abbas dan Ibn Katsir, kursi dimaksudkan ilmu Allah.291
290 Pemberian makna referensial suatu kata pada sisi lain tidak dapat dilepaskan dari
pemahaman pemberi makna itu sendiri terhadap ciri referen yang diacu. Referen yang dinamai kambing misalnya, dapat diberi ciri “hewan berkaki empat, berbulu, berjanggut, berbau tidak sedap”. Sebenarnya pemberian ciri itu bertolak dari ciri komponen yang terkandung dalam abstraksi wujud kambing secara keseluruhan. Aminuddin, Semantik : Pengantar Studi tentang Makna (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), h. 89.
291 Muhammad ‘Ali al-Sâbûniy, Safwah al-Tafâsir, jilid 1, h. 147. Bandingkan dengan al-Zamakhsyariy, al-Kasyyâf (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 297.

clxxiv
Dan kata yang bermakna nonreferensial adalah kata tugas (al-adâwât),
dan kata tugas ) ft‘A-hurûf al(dan konjungsi ) Jarr-hurûf al(seperti preposisi
lainnya. Semua kata tugas tidak mempunyai referen, maka kata-kata ini tidak
memiliki makna. Kata-kata ini hanya memiliki fungsi atau tugas. Oleh karena itu,
kata tugas ini akan mempunyai makna jika berdampingan dengan kelas kata
lainnya, seperti nomina dan verba. Dari sinilah, kata tugas akan mempunyai
makna, tetapi bukan makna referensial tetapi makna fungsi (al-Ma’nâ al-
Wazîfiy).292
Perlu diketahui bahwa ada kata-kata yang referennya tidak tetap, dapat
berpindah dari satu rujukan kepada rujukan lain atau dapat juga berubah
ukurannya. Kata-kata ini disebut deiktis.293 Di antara kata yang masuk kategori
deiktis adalah kata ganti (pronomina). Meskipun pronomina dalam Bsu menjadi
kata definitif (ism mu’ayyan), namun acuannya berpindah-pindah. Misalnya ini
pada terjemahan surah al-Baqarah ayat 25: Mereka berkata, “Inilah rezeki yang
diberikan kepada kami dahulu; ayat 79: Kemudian mereka berkata, “Ini dari
Allah,”; ayat 126: Ya Tuhanku, jadikanlah ini negeri yang aman. Yang dijadikan
acuan kata ini yang pertama adalah rezeki dari surga; acuan kata ini yang kedua
adalah catatan-catatan kitab yang ditulis oleh ahli kitab; dan acuan kata ini yang
ketiga adalah negeri Mekkah.
Selanjutnya, makna yang berdasarkan ada atau tidaknya “nilai rasa” pada
sebuah kata terbagi atas dua bagian, yaitu: (1) makna denotatif; dan (2) makna
konotatif. Makna denotatif disebut juga makna konseptual, makna kognitif,
makna referensial, sebab makna ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang
sesuai dengan hasil observasi, menurut penglihatan, penciuman, pendengaran,
292 Tammâm Hassân, al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma’nâhâ wa Mabnâhâ, h. 342. 293 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, h. 64.

clxxv
perasaan, atau pengalaman lainnya.294 Karena itu, makna denotatif disebut juga
sebagai “makna yang sebenarnya”. Umpamanya, dalam beberapa ayat al-Quran
yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dalam surah al-Baqarah lebih
banyak menggunakan kata perempuan, seperti perempuan musyrik, hamba
sahaya perempuan, perempuan-perempuan yang diceraikan, dan selainnya lebih
banyak menggunakan kata istri untuk menerjemahkan kata al-Nisâ`.
Istri sebagai terjemahan dari kata al-Nisâ`pada beberapa ayat yang
berkaitan dengan kehidupan keluarga merupakan cara mendekatkan makna dari
perempuan atau wanita. Cara ini bisa dilakukan melalui dua pendekatan, yakni
pendekatan analitik (referensial) dan pendekatan operasional.295 Dilihat dari
pendekatan analitik, kata istri dapat diuraikan menjadi: istri = manusia,
perempuan, telah bersuami, kemungkinan telah beranak, pendamping suami,
mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga. Jika dilihat dari pendekatan
operasional, kata istri dapat terlihat dari beberapa kemungkinan kalimat yang
muncul seperti: Si Dulah mempunyai istri, istri Ali telah meninggal; tetapi tidak
mungkin orang mengatakan: Istri Ali berkaki tiga, istri tidak pernah melahirkan.
Kata perempuan mempunyai makna denotasi yang sama dengan kata
wanita. Walaupun kedua kata ini memiliki makna yang sama, namun dewasa ini
kedua kata itu mempunyai nilai rasa yang berbeda. Kata perempuan mempunyai
nilai rasa yang “rendah”, sedangkan kata wanita memiliki nilai rasa yang
“tinggi”.296 Ini terbukti dengan tidak digunakannya kata perempuan pada nama-
nama lembaga dan organisasi, seperti Dharma Wanita, gedung wanita, Ikatan
294 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, h. 66. 295 Pendekatan analitik bertujuan untuk mencari makna dengan cara menguraikannya atas
segmen-segmen utama, sedangkan pendekatan operasional bertujuan untuk mempelajari kata dalam penggunaannya. Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, h. 86.
296 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 1147.

clxxvi
Wanita Pengusaha. Persamaan itu disebabkan oleh adanya ciri-ciri semantik yang
melekat pada dua nama tersebut, misalnya dengan ciri-ciri sebagai berikut:
Ciri Wanita Perempuan
Insan
Betina
Dewasa
Bersuami
+
+
+
+
+
+
+
-
Dua buah kata atau lebih yang makna denotasinya sama dapat menjadi
berbeda makna keseluruhannya, akibat pandangan masyarakat berdasarkan nilai-
nilai atau norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat itu. Seperti kata
yahudi, pada awalnya mengandung makna orang hidup yang memeluk agama
Yahudi, tetapi kemudian dewasa ini beralih makna, yakni orang yang rakus,
bakhil, banyak menipu dan selalu melakukan intervensi. Dan ini yang kemudian
, Demikian halnya297.âfiydI-Ma’nâ al-almenjadi makna tambahan atau
perbedaan makna kata perempuan dan wanita bisa terjadi akibat peristiwa sejarah
atau juga adanya perbedaan fungsi sosial kata tersebut.
Kemudian, makna konotasi disebut sebagai makna tambahan. Makna
tambahan juga mengandung makna yang bernilai rasa, baik positif maupun
negatif. Teks-teks al-Quran tidak pernah mengungkapkan kata-kata secara vulgar.
Bahkan kata-kata itu lebih banyak diperhalus dengan menggunakan kata-kata
metonimia (kinâyah),298 seperti kata 187: “Dihalalkan bagimu pada malam hari
297 Lihat, Ahmad Mukhtâr ‘Umar, ‘Ilm al-Dilâlah (Kuwait: Maktabah Dâr al-‘Arûbah, 1982),
h. 37. 298 Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan
suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Lihat, Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 142. Kinayah adalah lafadz yang dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian lazimnya, tetapi dimaksudkan untuk makna asalnya. Lihat, ‘Ali al-Jârim dan Mustafâ Utsmân, al-Balâghah al-Wâdihah. Penerjemah Mujiyo Nurkholis, dkk., h. 175.

clxxvii
puasa bercampur dengan istrimu..... Maka sekarang campurilah mereka.” Kata
bercampur yang pertama adalah terjemahan dari nomina al-Rafats dan kata
bercampur yang kedua merupakan terjemahan verba bâsyirû. Kata lainnya yang
identik maknanya dengan kata bercampur adalah kata fa`tû hartsakum yang
terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 223, dan taghasysyâhâ yang terdapat di
dalam surah al-A’râf ayat 189.
Berdasarkan ketepatan makna dalam penggunaannya secara umum dan
khusus, makna dalam terjemahan al-Quran dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:
(1) makna kata, dan (2) makna istilah. Makna sebuah kata, walaupun secara
sinkronis tidak berubah, tetapi karena berbagai faktor dalam kehidupan, dapat
menjadi bersifat umum. Makna kata itu baru menjadi jelas kalau sudah digunakan
di dalam suatu kalimat. Misalnya kata Tuhan. Apa makna Tuhan? Mungkin saja
yang dimaksud adalah Allah bagi orang-orang yang beriman, atau bisa saja
Tuhan lainnya, seperti yang diyakini oleh orang-orang kafir Arab pada zaman
Rasulullah.
Berbeda dengan makna istilah, ia memiliki makna yang pasti. Ketepatan
makna istilah karena hanya digunakan dalam bidang kegiatan atau keilmuan
tertentu.299 Terjemahan al-Quran banyak memuat istilah-istilah, misalnya salat,
zakat, puasa, haji, ‘umrah dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut sudah tidak
dijelaskan secara singkat maupun dengan uraian panjang, karena frekuensi
penggunaanya lebih tinggi digunakan oleh umat Islam sendiri serta istilah
tersebut sudah merupakan istilah dalam bidang keagamaan, sehingga maka
299 Di sinilah letak perbedaan antara istilah sebagai hasil pengistilahan dan nama sebagai hasil
penamaan. Istilah memiliki makna yang tepat dan cermat serta digunakan hanya untuk satu bidang tertentu, sedangkan nama masih bersifat umum, karena digunakan tidak dalam bidang tertentu. Misalnya kata <telinga> dan <kuping> sebagai nama dianggap bersinonim. Tetapi dalam bidang kedokteran telinga dan kuping digunakan sebagai istilah untuk acuan yang berbeda; telinga adalah alat pendengaran bagian dalam, sedangkan kuping adalah bagian luarnya. Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, h. 53.

clxxviii
masyarakat umum lebih mengenal kata-kata ini sebagai istilah keagamaan. Oleh
karena itu, kata-kata dapat berubah maknanya disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain faktor keagamaan.300
Demikian, padanan gramatikal dan leksikal serta maknanya dalam
terjemahan al-Quran. Perbedaan gramatikal maupun leksikal al-Quran menuntut
adanya suatu kiat (a craft) penerjemah untuk mencari padanannya. Perbedaan
antara kedua teks selalu membayangi proses penerjemahan. Terjemahan dapat
dinilai salah jika kesalahan itu muncul semata-mata karena kesalahan bahasa. Di
samping itu pula penerjemah berhadapan dengan pemahaman pembaca. Karena
terjemahan adalah teks juga, maka terjemahannya pun bersifat “terbuka”.
300 ‘Abd al-Karîm Mujâhid, al-Dilâlah al-Lughawiyyah ‘inda al-‘Arab (Kuwait: Maktabah
Dâr al-‘Arûbah, 1982), h. 144.

clxxix
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis penulis terhadap terjemahan al-Quran Depag RI edisi
2002, penulis menyimpulkan bahwa terjemahan al-Quran Depag RI edisi 2002
memiliki strategi dan padanan dalam penerjemahannya. Strategi itu secara
keseluruhan tidak berbeda dengan strategi yang ditawarkan secara teoritis oleh
pakar-pakar terjemahan seperti Newmark, Nida dan Taber. Atas dasar itu, dapat
diketahui bahwa terjemahan al-Quran Depag RI edisi 2002 termasuk jenis
terjemahan semantis sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya oleh Suryawinata.
Pada dasarnya, terjemahan semantis merupakan terjemahan yang bersifat
objektif. Karena berusaha menerjemahkan apa yang ada, tidak menambah,
mengurangi atau mempercantik. Ragam terjemahan ini hanya ingin memindahkan
makna dan gaya bahasa teks BSu ke dalam teks BSa. Gaya bahasa BSu tidak bisa
dikorbankan selama bisa dimengerti di dalam BSa. Banyak ayat-ayat al-Quran
yang mengandung gaya bahasa yang memang maknanya langsung bisa dipahami,
sehingga teks Indonesia tetap mencerminkan teks bahasa al-Quran.
Kemudian, untuk mengarah kepada kesimpulan itu, analisis yang dilakukan
penulis adalah analisis struktural yang terbagi atas dua macam strategi, yaitu
strategi struktural dan semantis. Strategi struktural dilatarbelakangi oleh
perbedaan sistem dan unsur-unsur bahasa yang digunakan al-Quran dan bahasa
Indonesia yang digunakan oleh penerjemah. Strategi ini dimaksudkan untuk
mencari padanan struktur Bsu dan Bsa yang tepat dan untuk memperoleh
terjemahan yang wajar dan berterima oleh pembaca.
Adapun strategi struktural yang ada dalam terjemahan al-Quran itu secara
praktis terbagi atas dua bentuk, yaitu: (1) transposisi, dan (2) transformasi.

clxxx
Transformasi yang dimaksudkan dalam penerjemahan al-Quran adalah
pengalihan fungsi sintaksis Bsu kepada fungsi sintaksis Bsa yang berbeda, seperti
pengalihan jumlah fi’liyyah Bsu kepada jumlah ismiyyah Bsa, kalimat aktif Bsu
kepada kalimat pasif Bsa. Sedangkan transformasi yang dimaksudkan dalam
penerjemahan al-Quran adalah pengalihan kategori kata kepada kategori kata
lainnya, seperti nomina menjadi verba, atau nomina menjadi frasa dan sebagainya.
Sedangkan strategi semantis digunakan mencari padanan makna kata-kata
al-Quran, karena kosakata al-Quran mengandung banyak makna dan luas.
Sehingga padanan makna itu harus dicarikan alternatifnya melalui strategi
semantis yang mencakup makna atau pesan yang dimaksud. Oleh karena itu
strategi semantis ini cukup beragam, mulai dari penambahan penjelasan,
transliterasi dan naturalisasi, penghapusan, dan penggantian dan seterusnya.
Selanjutnya, padanan gramatikal maupun leksikal dalam terjemahan al-
Quran pasti ada, karena itu merupakan tugas penerjemah untuk menemukan
padanan yang benar dan berterima dalam Bsa. Padanan gramatikal dan leksikal
berkaitan erat dengan siapa yang menjadi pembaca Bsu dan siapa yang menjadi
pembaca terjemahan itu, kemudian pesan (message) al-Quran harus bisa dipahami
oleh mereka dengan mudah dan tepat.
Gramatikal dan leksikal dalam terjemahan al-Quran Depag RI harus
dibandingkan dan disepadankan dengan gramatika, leksem atau kata yang
terdapat di dalam kamus serta terjemahan al-Quran lainnya, baik terjemahan al-
Quran Depag RI edisi sebelumnya atau menurut penerjemah al-Quran lainnya,
serta didukung oleh literatur tafsir. Dan ternyata, ada beberapa perbedaan
meskipun tidak terlalu substansial bagi pembaca yang belum memahami bahasa
al-Quran. Misalnya, penggunaan
B. SARAN-SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang dibangun, penulis menyertakan saran-saran
yang dimaksudkan sebagai bahan penelitian berikutnya, baik dari Departemen

clxxxi
Agama maupun peneliti lainnya yang memiliki perhatian besar terhadap
terjemahan al-Quran.
Pertama, kepada Departemen Agama, terutama tim penerjemah al-Quran
Depag RI untuk menginventarisir kesalahan-kesalahan pada edisi sebelumnya,
sehingga pada edisi berikutnya perbaikan itu tidak menimbulkan kesalahan untuk
kedua kalinya. Hal ini perlu dilakukan agar kualitas terjemahan al-Quran Depag
RI dapat meningkat. Pengoreksian ulang terhadap terjemahan al-Quran edisi
2002, telah ditemukan beberapa kesalahan yang terdapat di dalam surah al-
Baqarah, terutama yang berkaitan dengan padanan gramatikal dan makna serta
pesan Bsu yang tak tersampaikan seperti kalimat inversi (ayat 40, 41);
penghilangan kata sesungguhnya atau sungguh sebagai padanan kata sarana
; )37ayat ( lsFa-amîr ald sebagai padanan lah–partikel ; )67, 30ayat (inna penegas
penggantian makna tunggal kepada makna jamak pada pronomina penghubung
(17) , ketiadaan makna partikel qad (144), kesalahan pronomina engkau pada
verba kuntum (ayat 144).
Kedua, kepada para peneliti terjemahan, secara khusus terjemahan al-Quran
untuk melakukan penelitian ulang atau lanjutan dengan sudut pandang dan
metode yang berbeda, karena masih ada hal yang harus diteliti pada terjemahan
al-Quran, seperti pengujian pemahaman dan kesan oleh pembaca terjemahan al-
Quran, perbandingan pemahaman dan kesan yang didapat oleh pembaca teks al-
Quran dan pembaca teks terjemahannya, dan analisis kesilapan (error analysis)
yang menggunakan terjemahan al-Quran sebagai instrumen dan sebagainya.
Demikian, kesimpulan dan saran yang dapat tersampaikan oleh penulis sebagai
penutup dari tesis ini untuk sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister
konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab.

clxxxii
DAFTAR PUSTAKA

clxxxiii
‘Abd al-Latîf, Muhammad Hamâsah, dkk. al-Nahw al-Asâsiy. Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, 1997.
Abdul Chaer. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta Karya, cet. II, 2003. ------. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Abî al-Barakât, Kamâl al-Dîn. al-Insâf fî Masâ`il al-Khilâf. Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1998. Abû ‘Ubaidah. Majâz al-Qurân. Beirut: Mu`assasah al-Risâlah, 1981. Al-Ansârî, Jamâl al-Dîn Ibn Hisyâm. Awdah al-Masâlik ilâ Alfiyyah Ibn Mâlik.
Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1994. ------, Jamâl al-Dîn Ibn Hisyâm. Mughnî al-Labîb. T.t.p.: Dâr Ihyâ`i al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.t.. Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Qur-an: Text Translation and Commentary. Lahore:
SH Muhammad Ashraf, t.t. Alwi, Hasan (Ed.). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
2003. Aminuddin. Semantik : Pengantar Studi tentang Makna. Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2003. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik
Indonesia. Kegiatan Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, artikel diakses pada tanggal 17 April 2008 dari http/www.Depag.
Badrî, Kamâl. Binyah al-Kalimât wa Nazm al-Jumlah Mutabbaqan ‘alâ al-Lughah
al-‘Arabiyyah al-Fushâ. Jakarta: LIPIA, 1986. Departemen Agama Republik Indonesia. al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta:
Yamunu, 1965. Departemen Agama RI. al-Quran dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar Surabaya,
2004. Al-Dîdâwî, Muhammad. ‘Ilm al-Tarjamah baina al-Nazariyyah wa al-Tatbîqiyyah.
Tunis: Dâr al-Ma’ârif wa al-Nasyr, 1992.

clxxxiv
Djajasudarma, T. Fatimah. Semantik 2 Pemahaman Ilmu Makna. Bandung: Refika Aditama, 1999.
Djuharie, O. Setiawan. Teknik dan Panduan Menerjemahkan Bahasa Inggris-Bahasa
Indonesia. Bandung: Yrama Widya, 2005. Eriyanto. Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. Al-Fadlî. Dirâsah fi al-I’râb. Jeddah: Tihamah, 1984. Finoza, Lamuddin. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2007. Fokker, AA. Sintaksis Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988. Al-Ghalâyainî, Mustafâ. Jâmi’ al-Durûs al-‘Arabiyyah. Beirut: al-Maktabah al-
‘Asriyyah, 1984. Gusmian, Islah. Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Idiologi.
Jakarta: Teraju, 2003. Al-Hâfiz, Yâsîn. al-Tahlîl al-Sarfî. Damsyiq: Dâr al-‘Asmâ`, 1997. Hanafi, Nurachman. Teori dan Seni Menerjemahkan. Ende Flores: Nusa Indah, 1986. Hartoko, Dick dan B. Rahmanto. Pemandu di Dunia Sastra. Yogyakarta: Kanisius,
1986. Haryono, M. Yudhie R. Bahasa Politik al-Quran. Bekasi: Gugus Press, 2002. Hassân, Tammâm. al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma’nâhâ wa Mabnâhâ. Kairo: ‘Âlam
al-Kutub, 1998. ------. Al-Usûl: Dirâsah Istimûlûjiyyah li al-Fikr al-Lughawiy ‘inda al-‘Arab. Kairo:
‘Âlam al-Kutub, 2000. Hatim, Basil dan Ian Mason. Discourse and Translator. Longman: Longman Group
Limited, 1990. Hoed, Benny Hoedoro. Penerjemahan dan Kebudayaan. Bandung: Pustaka Jaya,
2006. Ibn Jinnî, Abû al-Fath ‘Utsmân. al-Khasâis. Kairo: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiy, 1957.

clxxxv
Ibnu Burdah. Menjadi Penerjemah: Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab.
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004. Ismâil, Sya’bân Muhammad. al-Madkhal li Dirâsah al-Qurân wa al-Sunnah wa al-
‘Ulûm al-Islâmiyyah. Kairo: Dâr al-Ansâr, t.th. Al-Jailânî, Ibrâhîm Badâwi. ‘Ilm al-Tarjamah wa Fadlu al-Lughah al-‘Arabiyyah
‘alâ al-Lughât. Kairo: al-Maktab al-‘Arabiyy li al-Ma’ârif, 1997. Al-Jalâlain. Tafsîr al-Jalâlain. Damsyiq: Dâr al-Jail, 1995. Al-Jamîlî, Rasyîd. Harakah al-Tarjamah fi al-Masyriq fi al-Qarnaini al-Tsâlits wa
al-Râbi’ al-Hijri. Baghdad: Dâr al-Syu’ûn al-Tsaqâfiyah al-‘Âmmah, 1986. Al-Jârim, ‘Ali dan Mustafâ Amîn. al-Balâghah al-Wâdihah. Penerjemah Mujiyo
Nurkholis, dkk. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993. Jassin, HB., al-Quran al-Karim Bacaan Mulia. Djakarta: Djambatan1978. Jihâd, Sanâ. Mu’jam al-Tâlib wa al-Kâtib. Beirut: Maktabah Lubnân Nâsyirûn, 1997. Al-Jurjânî, ‘Abd al-Qâhir. Dalâ`il al-I’jâz. Kairo: ‘Abd al-Salam Harun, t.t.. “Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia”. Sunting diakses pada tanggal
21 April 2008 dari http://id.wikipedia.org/wiki. Keraf, Gorys. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Kerajaan Saudi Arabia. al-Qurân al-Karîm wa Tarjamah Ma’ânih bi al-Lughat al-
Indûnisiyyah. al-Madînah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Tibâ’at al-Mushaf al-Syarîf, 1418 H.
Khidîr, Muhammad Ahmad. ‘Alâqah al-Zawâhir al-Nahwiyyah bi al-Ma’nâ fi al-
Qurân al-Karîm. Kairo: Maktabah Anglo al-Misriyyah, t.t. Al-Khûlî, Muhammad Ali. A Dictionary of Theoretical Linguistics. Beirut: Librairie
du Liban, 1982. Kridalaksana, Harimurti. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. ------. Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1989.

clxxxvi
Larson, Mildred L. Meaning-based Translation: A Guide to Cross-language Equivalence. London: University Press of America, 1984.
Lubis, Ismail. Falsifikasi Terjemahan al-Quran Departemen Agama Edisi 1990.
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001. Lyons, John. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Mahmud Junus. Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia. Jakarta: Al-Hidajah, 1971. Mahnâ, Ahmad Ibrâhim. Dirâsah haula Tarjamah al-Qurân. T.tp.: Matbû’ât al-
Sya’b, 1978. Mansyur, Moh. Studi Kritis Terhadap al-Quran dan Terjemahnya Depag RI.
Disertasi S2 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998. Mansyur, Moh. dan Kustiwan. Pedoman Bagi Penerjemah Arab-Indonesia. Jakarta:
Moyo Segoro Agung, 2002. Mattews, P.H., Morphology an Introduction to The Theory of Word Structures.
Cambridge: Cambridge University Press, 1972. Al-Misrî, Syihâb al-Dîn Ahmad. al-Tibyân fî Tafsîr Gharîb al-Qurân. Kairo: Dâr al-
Sahâbah li al-Turâts, 1992. Moeliono, Anton M. (ed.). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 1988. Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake, 1988. Muhammad, ‘Abd al-Ghaniy ‘Abd al-Rahmân. Dirâsah fi Fanni al-Ta’rîb wa al-
Tarjamah. Ttp, t.p. t.t. Muhammad, Ahmad Sa’d. al-Usûl al-Balâghiyyah fî Kitâb Sîbawaih. Kairo:
Maktabah al-Âdab, 1999. Muhammad, Ahsin Sakho. “Aspek-aspek Penyempurnaan Terjemah dan Tafsir
Departemen Agama ”, Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 3, No. 1 (Januari 2005). Mujâhid, ‘Abd al-Karîm. al-Dilâlah al-Lughawiyyah ‘inda al-‘Arab. Kuwait:
Maktabah Dâr al-‘Arûbah, 1982.
Mulyana. Kajian Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

clxxxvii
Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997. Mushthofa, Bisyri. Al-Ibrîz. Kudus: Menara Kudus, t.th. Mustakim, Membina Kemampuan Berbahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1994. Nababan, M. Rudolf. Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2003. Al-Nabî, Manshûr Muhammad Hasb. al-Qurân wa ‘Ilm al-Hadîts. Mesir: al-Hayyah
al-Mishriyah al-‘Ammah li al-Kuttâb, 1991. Nasuhi, Hamid, dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: CeQDA, 2007. Newmark, Peter. About Translation. Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1991. ------. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, 1981. ------. Paraghrafs on Translation. Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1993. ------. Textbook of Translation. Oxford: Pergamon Press, 1988. Nida, Eugene A. dan Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation.
Leiden: E.J. Brill, 1982. Pateda, Mansoer. Semantik Leksikal. Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
1976. Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B. Jassin tentang al-Quranul Karim Bacaan
Mulia. Jakarta: Mutiara, 1979. Al-Qattân, Mannâ’. Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qurân. Kairo: Maktabah Wahbah, 2007. Al-Qurtubî, Muhammad Ibn Ahmad al-Ansârî. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân. Beirut:
Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988. Rachmadie, Sabrony dkk., Materi Pokok Translation. Jakarta: Karunika dan
Universitas Terbuka, 1988.

clxxxviii
Ramlan, M. Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif. Yogyakarta: CV. Karyono, 1983. Rofi’i. Bimbingan Tarjamah Arab-Indonesia. Jakarta: Persada Kemala, 2002. Al-Sâbûnî, Muhammad ‘Ali. al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qurân. Damsyiq: Maktabah al-
Ghazâliy, 1981. ------. Safwah al-Tafâsîr. Beirut: Dar al-Fikr, 2001. Said, Mashadi. Socio-Cultural Problems in the Translation of Indonesian Poems into
English: A Case Study on “Foreign Shore”. Tesis Magister IKIP Malang, 1994.
Saiful Mu`minin, Iman. Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf. Jakarta: Amzah, 2008. Salâmah, Muhammad Husain. al-I’jâz al-Balâghiy fî al-Qurân al-Kârim. Kairo: Dâr
al-Âfâq al-‘Arabiyyah, 2002. Sâlih, Bahjat ‘Abd al-Wâhid. al-I’râb al-Mufassal li Kitâb Allâh al-Murattal.
Amman: Dâr al-Fikr, 1998. Salihen Moentaha. Bahasa dan Terjemahan. Bekasi Timur, Kesaint Blanc, 2006. Samsuri. Analisis Bahasa. Jakarta: Erlangga, 1985. Al-Sayyid Munsî, ‘Abd al-Halîm dan ‘Abd Allâh ‘Abd al-Râziq Ibrâhîm, al-
Tarjamah: Usuluhâ wa Mabâdi`uhâ wa Tatbîquhâ. Riyad: Dâr al-Murîkh, t.t. Setiawan, Phil M. Nur Kholis. al-Quran Kitab Sastra Terbesar. Yogyakarta: elSAQ
Press, 2005. Simatupang, Maurits. Peranan Teori Menerjemahkan dalam Menunjang
Pertumbuhan Penerjemahan Indonesia dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980.
Shihab, M. Quraish. Menabur Pesan Ilahi. Jakarta: Lentera Hati, 2006. Sudarno. Kata Serapan dari Bahasa Arab. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1990. Sultânî, Muhammad ‘Ali. al-Adawât al-Nahwiyyah wa Ma’ânîhâ fî al-Qurân al-
Karîm. Suriah: Dâr al-‘Asmâ`, 2000.

clxxxix
Suryawinata, Zuchridin dan Sugeng Hariyanto. Translation: Bahasan Teori dan Penuntun Praktis Menerjemahkan. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Suryawinata, Zuchridin. Terjemahan: Pengantar Teori dan Praktek. Jakarta:
Depdikbud, Dirjen Dikti, PPLPTK, 1989. Syamsu, Nazwar. Koreksi Terjemahan Bacaan Mulia HB. Jassin. Padang Panjang:
Pustaka Saadiyah, 1916. Syarbasî, Ahmad. Yas’alûnaka fi al-Dîn wa al-Hayâh. Beirut: Dâr al-Jîl, 1980. Syihabuddin. Penerjemahan Arab Indonesia. Bandung: Humaniora, 2005. Tarigan, Henry Guntur. Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa. Bandung: Angkasa,
1992. ‘Ubâdah, Muhammad Ibrâhîm. al-Jumlah al-‘Arabiyyah: Mukawwanâtuhâ-
Anwâ’uhâ-Tahlîluhâ. Kairo: Maktabah al-Âdâb, 2001. Ullmann, Stephen. Semantics an Introduction to The Science of Meaning. Oxford:
Basil Balckwell, 1972. ‘Umar, Ahmad Mukhtâr. ‘Ilm al-Dilâlah. Kuwait: Maktabah Dâr al-‘Arûbah, 1982. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:
Bumi Aksara, 2006. Verhaar. Pengantar Linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983. Widyamartaya, A. Seni Menerjemahkan. Jakarta: Kanisius, 1989. Wills, Wolfram. The Science of Translation. Stuttgart: Gunter Narr Verlag Tubingen,
1982. Yusuf, Suhendra. Teori Terjemah: Pengantar ke Arah Pendekatan Linguistik dan
Sosiolinguistik. Bandung: Mandar Maju, 1994. Al-Zajjâj. Ma’ânî al-Qurân wa I’râbuh. Beirut: ‘Âlam al-Kutub, 1998. al-Zamakhsyarî. al-Kasyyâf. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995. Al-Zarqânî, Muhammad ‘Abd al-‘Adhîm. Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm al-Qurân.
Mesir: ‘Isa al-Bab al-Halbi, t.t..

cxc
Zainal Arifin, E. dan S. Amran Tasai. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta:
Akademika Pressindo, 2006. Zidan, Ahmad dan Dina Zidan. The Glorious Qur`an: Text and Translation. Kairo:
Islamic Inc. Publishing & Distribution, 1996.