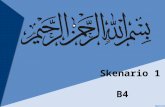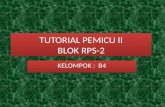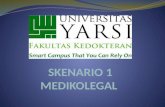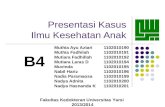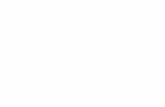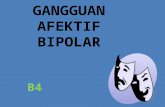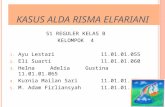kognosi B4 3A
-
Upload
selvi-dwi-cahyaningsih -
Category
Documents
-
view
197 -
download
1
Transcript of kognosi B4 3A

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Obat tradisional merupakan obat yang sekarang banyak dipilih oleh masyarakat, terlebih
adanya kecenderungan gaya hidup untuk kembali ke alam. Seiring dengan berkembangnya
pengobatan dengan obat tradisional maka banyak dilakukan praktikum yang dilaporkan
membuktikan manfaat tanaman obat untuk mencegah dan menanggulangi penyakit sehingga
menjadi perhatian khusus bagi pelayanan kefarmasian. Obat tradisional yang terkenal di
Indonesia adalah “jamu” yang merupakan warisan asli budaya bangsa Indonesia yang
penggunaannya dikenal secara turun temurun sejak dahulu.
Jumlah sediaan obat tradisional yang didaftar pada Badan POM akhir 2006 adalah
14.217 termasuk diantaranya 2.036 produk impor dan 52 produk lisensi (Sudiyani dalam
editorial Pengembangan Obat Tradisional Indonesia Menjadi Fitofarmaka, 2007). Obat
tradisional dan obat herbal produksi pabrik yang ada di pasaran telah lebih dari 5000 produk,
belum termasuk jamu yang tidak wajib daftar (jamu gendong dan racikan). Hampir semua
obat tradisional merupakan campuran lebih dari satu macam tanaman. Lebih dari 90% produk
tersebut masih didasarkan manfaat empirik, tanpa pembuktian preklinik. Dilain pihak,
sebagian pengobatan tradisional juga menggunakan obat tradisional berupa ramuan dalam
praktek pengobatannya dan jenis tanaman obat yang digunakan kemungkinan besar juga
termasuk bahan yang belum memiliki data uji preklinik dan digunakan berdasarkan data
empirik.
Meningkatkan produksi, peredaran dan penggunaan jamu, di sisi lain dicemari oleh
beredarnya obat tradisional yang tidak terdaftar, obat tradisional yang mengandung bahan
kimia obat serta obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Peredaran dan
penggunaan obat tradisional seperti ini selain sangat membahayakan kesehatan/jiwa
konsumen juga merusak citra obat tradisional secara keseluruhan. Kejadian tidak diinginkan
berupa reaksi efek samping obat dapat terjadi akibat interaksi antar komponen, penggunaan
kronik, ataupun interaksi dengan obat-obat konvensional yang dikonsumsi secara bersamaan.
Produk herbal seringkali dicampurkan dengan Bahan Kimia Obat (BKO) untuk
memperoleh efek pengobatan yang cepat. Penggunaan produk herbal secara umum tidak
dapat memberikan efek penyembuhan dalam waktu hanya beberapa jam atau cespleng, akan
tetapi memerlukan waktu tertentu untuk dapat menunjukkan efek yang diinginkan. Kenyataan
1

ini sering tidak dimengerti oleh masyarakat, bahkan ada masyarakat yang memang meminta
produk herbal yang cespleng dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab dengan cara mencampurkan BKO ke dalam produk herbal untuk
mendapatkan efek yang diinginkan dengan cepat. Perbuatan ini jelas melanggar peraturan
yang berlaku di Indonesia yang mempersyaratkan bahwa produk herbal atau obat tradisional
tidak diperbolehkan mengandung BKO. Oleh karena itu, dilakukanlah praktikum identifikasi
jamu dalam praktikum Farmakognosi II secara KLT.
1.2. Rumusan Masalah
Apakah Jamu “X” teridentifikasi mengandung bahan kimia obat secara KLT?
1.3 Tujuan Praktikum
1.3.1 Tujuan umum
Mengetahui identifikasi bahan kimia obat pada jamu “X” secara KLT.
1.3.2 Tujuan khusus
Mengetahui bahan kimia obat yang terkandung dalam jamu “X” berdasarkan system TC,
TD, TE.
1.4 Manfaat Praktikum
1.4.1 Bagi penulis
1. Mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat terutama mata kuliah farmakognosi.
2. Memperluas wawasan mengenai identifikasi bahan kimia obat pada jamu “X” secara KLT.
1.4.2 Bagi Akademik
1. Menambah khasanah bacaan mengenai identifikasi bahan kimia obat pada jamu “X” secara
KLT.
2. Sebagai referensi untuk praktikum selanjutnya dan menambah literatur untuk KTI.
2

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Jamu
2.1.1 Pengertian
Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dibuat dari bahan atau ramuan
bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik),
atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk
pengobatan berdasarkan pengalaman (BPOM RI, 2005).
2.1.2 Persyaratan Jamu
Menurut Badan POM RI, obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tamabahan yang memenuhi persyaratan mutu,
keamanan dan kemanfaatan atau khasiat,
b. Dibuat sesuai dengan ketentuan tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik atau
Cara Pembuatan Obat yang baik berlaku,
c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan
obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara tepat, rasional, aman sesuai
hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran.
Larangan Obat Tradisional
(1) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dilarang mengandung :
a. bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
b. narkotika atau psikotropika;
c. bahan yang dilarang seperti tercantum pada Lampiran 14;
d.hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Obat tradisional dilarang dalam bentuk sediaan :
a. intravaginal;
b. tetes mata;
c. parenteral;
d. supositoria, kecuali digunakan untuk wasir.
3

(3) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dalam bentuk sediaan cairan
obat dalam tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih besar dari 1% (satu
persen), kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran.
2.2 Monografi
2.2.1 Coffein
Kofeina mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0% C8H10N4O2,
dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan.
Pemerian. Serbuk atau hablur bentuk jarum mengkilat biasanya menggumpal; putih; tidak
berbau; rasa pahit.
Kelarutan. Agak sukar larut dalam air dan dalam etanol (95%) P, mudah larut dalam
kloroform P; sukar larut dalam eter P.
Identifikasi A. Spektrum serapan inframerah zat yang telah dikeringkan pada suhu 80°
selama 4 jam dan didispersikan dalam parafin cair P menunjukkan maksimum hanya
pada panjang gelombang yang sama seperti pada kofeina PK.
B. Lebih kurang 5mg larutkan dalam 1 ml asam klorida P dalam cawan porselin,
tambahkan 50 mh kalium klorat P, uapkan di atas tangas air hingga kering. Tempatkan
cawan terbalik di atas bejana yang berisi beberapa tetes amonia P; sisa berwarna violet
yang hilang dengan penambahan larutan alkali.
Jarak lebur antara 235° dan 237,5°; penetapan dilakukan menggunakan zat yang telah
dikeringkan pada suhu 80° selama 4 jam.
Arsen Tidak lebih dari 3 bpl.
Logam berat Tidak lebih dari 20 bpl.
Timbal Tidak lebih dari 10 bpl.
Alkaloida lain Pada 5 ml larutan 2% b/v tambahkan larutan kalium tetralodohidrargirat
(II) P; tidak terbentuk endapan.
Zat terarangkan Larutkan 500 mg dalam 5 ml asam sulfat encer P; larutan tidak berwarna
lebih tua dari warna larutan pembanding yang dibuat dengan mencampur 0,3 ml larutan
primer kuning.0,6 ml larutan primer merah, 0,4 ml larutan primer biru yang tertera pada
Tingkat Warna Cairan dan 3,7 ml air.
Susut pengeringan Tidak lebih dari 0,5%; pengeringan dilakukan pada suhu 80° selama 4
jam.
Sisa pemijaran Tidak lebih dari 0,1 %.
4

Penetapan kadar Lakukan penetapan menurut Cara I yang tertera pada Titrasi bebas air
menggunakan 400 mg yang ditimbang seksama larutkan dalam 40 ml anhidrat asetat P,
panaskan, dinginkan; tambahkan 80 ml benzen P.
1 ml asam perklorat 0,1 N setara dengan 19,42 mg C8H10N4O2
Penyimpanan Dalam wadah tertutup baik.
Khasiat dan penggunaan Stimulan syaraf pusat, kardiotonikum.
Dosis maksimum Sekali 500 mg, sehari 1,5 g.
2.2.2 Parasetamol
Asetaminofen mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0%
C8H9NO2, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan.
Pemerian Hablur atau serbuk hablur putih; tidak berbau; rasa pahit.
Kelarutan Larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol (95%) P, dalam 13 bagian
aseton P, dalam 40 bagian gliserol P dan dalam 9 bagian propilenglikol P; dalam larutan
alkali hidroksida.
Identifikasi A. Larutkan 100 mg dalam 100 ml air, tambahkan 0,05 ml larutan besi (III)
klorida P; terjadi warna biru violet.
B. larutkan 200 mg dalam 4 ml piridina P, tambahkan 500 mg para nitrobenzoilklorida P,
didihkan selama 2 sampai 3 menit, dinginkan, tuangkan dalam 40 ml air sambil diaduk.
Cuci endapan berturut-turut dengan 30 ml air, dengan 30 ml larutan natrium karbonat P 1
% b/v dan dengan 30 ml air; hablurkan kembali dengan etanol (95%) P; suhu lebur hablur
lebih kurang 210.
C, Larutkan 50 mg dalam 100 ml metanol P; pada 1 ml asam klorida 0,1 N kemudian
metanol P secukupnya hingga 100,0 ml. Serapan 2 cm larutan pada 249 nm lebih kurang
0,90.
D, Didihkan 100 mg dengan 1 ml asam klorida P selama 3 menit, tambahkan 10 ml air,
dinginksn; tidak terbentuk endapan. Tambahkan 0,05 ml kalium bikromat 0,1 N; terjadi
perlahan-lahan warna violet yang tidak berubah menjadi merah (perbedaan dari
fenasetina).
Suhu lebur 169° sampai 172°.
Timbal Tidak lebih dari 10 bpj.
Para minofenol Larutkan 5,0 g dalam campuran yang terdiri dari air dan metanol P
volume sama secukupnya hingga 100,0 ml. Tambahkan 1,0 ml larutan natrium
nitrograsida basa P, campur, biarkan selama 30 menit; warna biru larutan tidak lebih tua
dari warna larutan pembanding yang dibuat sebagai berikut: Larutkan 5,0 g asetaminofen
5

bebas paraminofenol P dalam campuran metanol P dan air volume sama, tambahkan 5 ml
larutan paraminofenol P 0,005% b/v dalam campuran metanol P dan air volume sama,
encerkan dengan campuran di atas secukupnya hingga 100,0 ml. Tambahkan 1,0 ml
larutan natrium nitroprosida basa P, campur, biarkan selama 30 menit.
Susut pengeringan Tidak lebih dari 0,5%.\
Sisa pemijaran Tidak lebih dari 0,1%.
Penetapan kadar Lakukan penetapan dengan cara Penetapan kadar nitrogen, menggunakan
300 mg yang ditimbang saksama dan 8 ml asam sulfat bebas nitrogen P.
1 ml asam sulfat 0,1 N setara dengan 15,116 mg C8H9NO2
Penyimpanan Dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya.
Khasiat dan penggunaan Analgetikum; antipiretikum.
2.2.3 Methampyron
Metampiron mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0%
C13H16N3NaO4S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan.
Pemerian Serbuk hablur; putih atau putih kekuningan.
Identifikasi A. Pada 3 ml larutan 10% b/v tambahkan 1 ml sampai 2 ml asam klorida
enver P dan 1 ml larutan besi (III) klorida P 10% b/v; terjadi warna biru yang jika
dibiarkan berubah menjadi merah, kemudian tidak berwarna B. Panaskan 2 ml larutan
10% b/v yang telah diasamkan dengan asam klorida encer P; terjadi gas belerangdioksida.
Natrium bisulfit Larutkan 100 mg dalam 10 ml air; larutan berwarna jenih dan jika
ditambahkan larutan biru bromtimol P berwarna hijau.
Arsen berat Tidak lebih dari 20 bpj
Susut pengeringan Tidak lebih dari 5,5%; pengeringan dilakukan menggunakan 250 mg
yang ditimbang seksama.
Penetapan kadar Timbang seksama 200 mg, larutkan dalam 5 ml air. Tambahkan 5 ml
asam klorida 0,02 N dan segera titrasi dengan larutan iodium 0,1 N, menggunakan
indikator larutan kanji P, dengan sekali-sekali dikocok hingga terjadi warna biru yang
mantap selama 2 menit.
1 ml larutan iodium 0,1 N setara dengan 16,67 mg C13H16N3NaO4S.
Penyimpanan Dalam wadah tertutup baik.
Khasiat dan penggunaan Analgetikum, antipiretikum.
2.2.4 Kloroform
6

Kloroform adalah triklormetana, mengandung etanol 1,0% v/v sampai 2,0% v/v sebagai
zat penstabil.
Pemerian Cairan, mudah menguap; tidak berwarna; bau khas; rasa manis dan membakar.
Kelarutan Larut dalam kemih lebih kurang 200 bagian air; mudah larut, dalam etanol
mutlak P dalam eter P, dalam sebagian besar pelarut organik, dalam minyak atsiri dan
dalam minyak lemak.
Identifikasi A. Tidak dapat terbakar. Upaya dalam nyala Bunsen memberikan nyala
berwarna hijau dan menghasilkan uap beracun berbau khas.
B. hangatkan 1 tetes dengan 1 tetes anilina P dan 1 ml larutan natrium hidroksida P 8%
b/v; terjadi fenilkarbilamina yang berbau khas dan beracun.
Bobot per ml 1,474 g sampai 1,479 g.
Jarak didih Tidak lebih dari 5,0% v/v tersuling pada suhu di bawah 60°; sisa tersuling
pada suhu antara 60° dan 62°.
Bau asing Uapkan 10 ml pada sepotong kertas saring lebar yang ditempatkan di atas
cawan hangat; tidak terjadi bau asing selama penguapan.
Keasaman-kebasaan ; Klorida; Klor bebas Kocok 10 ml dengan 20 ml air bebas
karbondioksida P selama 3 menit, biarkan memisah; lapisan air memnuhi syarat berikut :
Keasaman-kebasaan Pada 5 ml larutan tambahkan 0,1 ml larutan lakmus P; warna yang
terjadi tidak berbeda dari warna larutan yang dibuat dengan menambahkan 0,1 ml larutan
lakmus P pada 5 ml air bebas karbondioksida P.
Klorida Pada 5 ml tambahkan 5 ml air dan 0,2 ml larutan perak nitrat P; tidak terjadi
opalesensi.
Klor bebas Pada 10 ml larutan, tambahkan 1 ml larutan kadmium iodida P dan 2 tetes
larutan kanji P; tidak terjadi warna biru.
Aldehida Kocok 5 ml dengan 5 ml air dan 0,2 ml larutan kalium tetraiodohidrargirat (II)
basa P dalam labu bersumbat. Biarkan di tempat gelap selama 15 menit; hanya boleh
berwarna kuning pucat.
Zat organik asing; senyawa klor asing Kocok 20 ml dengan 10 ml asam sulfat bebas
klorida P selama 5 menit dalam labu bersumbat yang telah dibilas dengan asam sulfat
bebas klorida P biarkan di tempat gelap selama 30 menit; lapisan asam dan lapisan
kloroform tetap tidak berwarna.
Zat organik asing Pada 2 ml lapisan asam tambahkan 5 ml air; cairan tetap jernih, tidak
berwarna dan tidak memberikan bau yang tidak enak. Tambahkan 10 ml air dan 0,2 ml
larutan perak nitrat P; tidak terjadi opalesensi.
7

Senyawa klor asing Kocok 15 ml lapisan kloroform dengan 30 ml air dalam lab bersumbat
selama 3 menit, biarkan memisah. Pada lapisan air tambahkan 0,2 ml larutan perak nitrat
P, biarkan di tempat gelap selama 5 menit; tidak terjadi opalesensi.
Hasil peruraian Masukkan 20 ml ke dalam labu bersumbat yang telah dibilas dengan asam
sulfat P. Tambahkan 15 ml asam sulfat P dan 4 tetes formaldehida P. Kocok selama 30
menit, biarkan selama 30 menit; lapisan asam hanya boleh berwrna lemah. Selama
pengujian labu terlindung dari cahaya.
Sisa penguapan Tidak lebih dari 1 mg; penguapan dilakukan menggunakan 25 ml,
kemudian dikeringkan pada suhu 105° hingga bobot tetap.
Penyimpanan Dalam wadah tertutup baik bersumbat kaca, terlindung dari cahaya.
Khasiat dan penggunaan Anestetikum umum; pengawet; zat tambahan.
2.2.5 Natrium Hidroksida
Natrium Hidroksida mengandung tidak kurang dari 97,5% alkali jumlah dihitung sebagai
NaOH dan tidak lebih dari 2,5% Na2CO3
Pemerian Bentuk batang, butiran, massa hablur atau keoing, kering, keras, rapuh dan
menunjukkan susunan hablur; putih, mudah meleleh basah. Sangat alkalis dan korosif.
Segera menyerap karbondioksida.
Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%) P
Identifikasi Larutan bereaksi alkalis kuat, jika dinetralkan dengan asam klorida encer P,
menunjukkan reaksi Natrium yang tertera pada Reaksi identifikasi.
Klorida Larutan 500 mg dalam air dengan penambahan 1,8 ml asam nitrat P, memenuhi
Uji batas klorida
Sulfat Memenuhi Uji bagan sulfat : pengujian dilakukan menggunakan larutan yang
dibuat sebagai berikut : Larutkan 500 mg dalam 5 ml air, tambahkan 4,5 ml asam klorida
encer P.
Alumunium, besi, zat larut dalam asam klorida Tidak lebih dari 5 mg. Pengujian
dilakukan sebagai berikut : Didihkan 5,0 g dengan 50 ml asam klorida encer P, dinginkan.
Basakan dengan amonia encer P, didihkan, saring, cuci sisa dengan larutan amonium
nitrat P 2,5% b/v, pijarkan, timbang.
Arsen Tidak lebih dari 4 bpj.
Logam berat Tidak lebih dari 5 bpj.
Penetapan kadar Timbang saksama 2 g, larutkan dalam 25 ml air, tambahkan 5 ml larutan
barium klorida P. Titrasi dengan asam klorida 1 N menggunakan indikator larutan
8

fenolftalein P. Lanjutkan titrasi dengan asam klorida 1 N menggunakan indikator larutan
biru bromfenol P.
1 ml asam klorida 1 N setara dengan 40,0 mg NaoH
Penyimpanan Dalam wadah tertutup baik.
Khasiat dan penggunaan Zat tambahan.
2.2.6 Asam Klorida
Asam Klorida mengandung tidak kurang dari 35,0% dan tidak lebih dari 38,0% HCL.
Pemerian Cairan; tidak berwarna; berasap, bau merangsang. Jika diencerkan dengan 2
bagian air, asap dan bau hilang.
Bobot per ml Lebih kurang 1, 18 g.
Keasaman-kebasaan Larutan yang sangat encer masih bereaksi asam kuat terhadap kertas
lakmus P.
Brom bebas dan klor bebas; Bromida dan Iodida; Sulfat dan Sulfit
Campur 1 bagian volume dengan 2 bagian volume air; larutan memenuhi syarat berikut :
Brom bebas dan klor bebas Pada 10 ml larutan tambahkan 1 ml larutan kalium iodida P
dan 1 ml kloroform P, kocok : lapisan kloroform tidak berwarna violet dalam waktu tidak
kurang dari 1 menit.
Bromida dan iodida Pada campuran 10 ml larutan dan 1 ml kloroform P tambahkan tetes
demi tetes larutan klor P yang telah diencerkan dengan air volume sama, sambil terus
menerus dikocok; lapisan kloroform tidak berwarna kuning, jingga atau violet.
Sulfat Pada campuran 3 ml larutan dan 5 ml air tambahkan 5 tetes larutan barium klorida
P; tidak terjadi kekeruhan atau endapan dalam waktu 1 jam.
Sulfit Pada larutan yang telah digunakan untuk Sulfat tambahakan 2 tetes iodium 0,1 N;
tidak terjadi kekeruhan atau warna iodium hilang.
Arsen Tidak lebih dari 5 bpj.
Logam berat Tidak lebih dari 5 bpj; pengujian dilakukan menggunakan 25 ml yang dibuat
sebagai beriut : Uapkan 4 g di atas tangas air hingga kering, tambahkan 2 ml asam asetat
encer P, encerkan dengan air hingga 25,0 ml.
Penetapan kadar Ke dalam labu bersumbat kaca yang telah ditera yang berisi 20 ml air,
masukkan 3 ml zat uji yang diukur saksama, encerkan dengan 25 ml air. Titrasi dengan
natrium hidroksida 1 N menggunakan indikator larutan merah metil P.
1 ml natrium hidroksida 1 N setara dengan 36,46 mg HCL
Penyimpanan Dalam wadah tertutup rapat.
Khasiat dan penggunaan Zat tambahan.
9

2.2.7 Aqua Destilata
Air suling Dibuat dengan menyuling air yang dapat ---------
------- Cairan jernih; tidak berwarna; tidak berbau; tidak mempunyai rasa.
Keasaman-kebasaan Pada 10 ml tambahkan 2 tetes larutan merah metil P; tidak terjadi
warna merah. Pada 10 ml tambahkan 5 tetes larutan biru bromtimal P; tidak terjadi warna
biru.
Amonium Pada 50 ml tambahkaan 2 ml larutan kalium tetraiodohidrargirat (II) basa P.
Amati warna dalam tabung pembanding di atas dasar putih; warna tidak lebih tua dari
warna larutan pembanding yang dibuat dengan mencampur 50 ml air bebas amoniak P
dan 2 ml amonium klorida encer P, yang dibedakan dengan cara yang sama.
Besi, tembaga dan timbal Pada 100 ml tambahkan 1 tetes larutan natrium sulfida P, cairan
tetap jernih dan tidak berwarna.
Kelarutan Pada 100 ml tambahkan 2 ml larutan amonium oksalat P; tidak terjadi
kekeruhan.
Korida Pada 10 ml tambahkan 1 ml larutan perak nitrat P, biarkan selama 5 menit, cairan
jernih tidak berwarna.
Nitrat Tuangkan hati-hati 5 ml di atas 5 ml larutan ----------; tidak terjadi warna biru, ada
bidang batas.
Sulfat Pada 10 ml tambahkan 1 ml larutan barium klorida P, biarkan selama 5 menit;
cairan jernih tidak berwarna.
Karbondioksida Pada 25 ml tambahkan 25 ml larutan kalsium hidroksida P, biarkan
selama 5 menit; larutan jernih.
Zat teroksidasi Didihkan 100 ml dengan 10 ml asam sulfat encer P dan 0,5 ml kalium
permanganat 0,01 N, warna tidak hilang.
Sisa penguapan Tidak lebih dari 0,001% b/v; penguapan dilakukan di atas tangas air
hingga kering.
Penyimpanan Dalam wadah tertutup baik.
2.3 Kromatografi
2.3.1 Definisi
Kromatografi adalah cara pemishan zat khasiat dan zat lain yang ada dalam sediaan
dengan jalan penyarian berfraksi, penyerapan atau penukaran ion pada zat berpori,
menggunakan cairan atau gas yang mengalir (FI III, 1979).
10

Kromatografi didefinisikan sebagaiprosedur pemisahan zat terlarutoleh suatu proses
migrasi diferensial dinamisdalam sistem yang terdiri dari dua fase atau lebih, salah satu
diantaranya bergerak secara berkesinambungan dalam arah tertentu dan dalam nya zat – zat
itu menunjukkan perbedaan mobilitas, disebabkan adanya perbedaan dalam absorbs, partisi,
kelarutan, tekanan, uap, ukuran molekul atau kerapatan muatan ion (FI IV, 1995).
2.3.2 Macam – macam Kromatografi
Menurut Watson (2009), kromatografi dibedakan menjadi :
1. Kromatografi kolom,
2. Kromatografi kertas,
3. Kromatografi lapis tipis,
4. Kromatografi gas,
5. Kromatografi cair kinerja tinggi.
2.3.3 Definisi Kromatografi Lapis Tipis
Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan zat secara cepat dengan
menggunakan zat penjerap berupa serbuk halus yang dilapiskan serba rata pada lempeng kaca
(BPOM RI 1995).
2.3.4 Prinsip Kromatografi Lapis Tipis
Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. Mempunyai lapisan
pemisah yang terdiri dari bahan yang berbulir – bulir (fase diam), ditempatkan pada
penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah
berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah lapisan atau pelat dimasukkan di
dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak),
pemisahan terjadi selama pengembangan. Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus
ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985).
Pada kromatografi, komponen akan dipisahkan oleh dua buah fase yaitu fase diam dan
fase gerak. Fase diam akan menahan komponen campuran sedangkan fase gerak akan
melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan
tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih
cepat. Fase gerak mengalir melalui fase diam dan membawa komponenkomponen yang
terdapat dalam campuran. Komponen-komponen yang berbeda bergerak pada laju yang
berbeda( Haqiqi, 2008).
11

Senyawa yang memiliki afinitas lebih besar terhadap fase gerak (atau afinitas yang
lebih kecil terhadap fase diam) akan bergerak lebih cepat daripada senyawa yang memiliki
sifat sebaliknya. Perbedaan laju perpindahan ini merupakan dasar dari semua pemisahan
secara kromatografi
2.3.5 Sistem Kromatografi
Dibedakan berdasarkan senyawa :
a. Basic Nitrogen Drug General Screen
Sistem TA
Lempeng : Silika gel 6,250 μm
Fase gerak : Metahon, larutan amoniak kuat (100:1,5)
Referensi : Diazepam Rf 79, Codein Rf 33
Sistem TB
Lempeng : Silika gel 6,250 μm
Fase gerak : Sikloheksana:toluena:dietilamin (75:15:10)
Referensi : Codein Rf 06
Sistem TC
Fase gerak : Chloroform:metanol (90:10)
Referensi : Coffein Rf 58, Meclozine Rf 79
b. Acidic and Neutral Drug General Screen
Sistem TD
Lempeng : Silika gel 6,250 μm
Fase gerak : Chloroform:aseton (4:1)
Referensi : Parasetamol Rf 15, Metohexiton Rf 73, Quinalbarbitone Rf 55
Sistem TE
Fase gerak : Etil asetat:metanol:larutan amoniak kuat (85:10:5)
Referensi : Prazepam Rf 81, HCT Rf 34
Sistem TF
Fase gerak : Etil asetat
Referensi : Fenasetin Rf 38
c. Analgetic, non Steroid, Antiinflamasi dan Asam berbahaya lain
Digunakan sistem TG sampai sistem TW. Sistem TK untuk referensi Glikosida
jantung
Pemilihan Sistem :
12

1. Basic Nitrogen : TA, TB, TC
2. Acid and Neutral Drug : TD, TE, TF
Amfetamin, stimulan lain dan adorectic : TA, TB, TC
Analgetik, non steroid, antiinflamasi dan asam kuat lain : TD, TF, TG
Antikonvulsan : TD, TE, TF
Antidepressan : TA, TB, TC
Histamin : TA, TB, TC
Barbiturat : TD, TE, TH
Benzodiazepin : TD, TE, TF
Cannabianoids : TI, TJ
Glikosida jantung : TK
Diuretik : TD, TE, TF
Alkaloid ergot : TI, TM
Anastetik lokal : TA, TB, TC, TL
Analgetik Narkotik : TA, TB, TC
Fenotiazin dan transquilizer lainnya : TA, TB, TC
Quaternary amonium compound : TN, TO
Steroid : TP, TQ, TR, TS
Sulponadrida : TT, TU, TV
Pestisida : TW
2.3.6 Fase Diam
Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penjerap berukuran kecil dengan
diameter partikel antara 10-30 µm. Semakin kecil ukuran rata- rata partikel fase diam dan
semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal
efisiensinya dan resolusinya (Rohman, 2009).
Penjerap yang paling sering digunakan pada KLT adalah silika dan serbuk selulosa,
sementara mekanisme sorpsi-desorpsi (suatu mekanisme perpindahan solut dari fase diam ke
fase gerak atau sebaliknya) yang utama pada TLC adalah partisi dan adsorbsi. Penjerap yang
paling banyak digunakan adalah silica gel. Silica gel ini menghasilkan perbedaan dalam efek
pemisahan yang tergantung kepada cara pembuatannya. Hal yang harus diingat bahwa
penjerap seperti aluminium oksida dan silica gel mempunyai kadar air yang berpengaruh
nyata terhadap daya pemisahnya (Stahl, 1985).
13

2.3.7 Fase Gerak
Fase gerak merupakan medium akut yang terdiri dari satu atau beberapa pelarut. Ia
begerak di dalam fase diam yaitu lapisan berpori karena terdapat gaya kapiler. Yang
digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik dan bila diperlukan, sistem pelarut
multikomponen ini harus berupa suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas
maksimum 3 komponen( Stahl, 1995).
Campuran yang sederhana sebagai fase gerak yakni dua pelarut organik karena daya
elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan
dapat terjadi secara optimal. Berikut adalah beberapa petunjuk dalam memilih dan
mengoptimasi fase gerak :
1. Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT merupakan
teknik yang sensitif.
2. Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf terletak antara
0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan.
3. Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel, polaritas
fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti juga menentukan
nilai Rf. Penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar seperti dietil eter ke dalam
pelarut non polar seperti metil benzen akan meningkatkan harga Rf secara signifikan.
4. Solut-solut ionik dan solut-solut polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai
fase geraknya seperti campuran air dan metanol dengan perbandingan tertentu.
Penambahan sedikit asam etanoat atau amonia masing-masing akan meningkatkan
solut-solut yang bersifat basa dan asam (Kaelay,2002).
2.3.8 Penjenuhan Bejana Kromatografi
Bejana harus dapat menampung pelat 200x200 mm dan harus tertutup rapat. Untuk
kromatografi dalam bejana yang jenuh, secarik kertas saring bersih yang lebarnya 18 – 20
cm dan panjangnya 45 cm ditaruh pada dindin sebelah dalam bejana berbentuk U dan
dibasahi dengan pelarut pengembang. Tingkat kejenuhan bejana dengan uap pelarut
pengembang mempunyai pengaruh yang nyata pada pemisahan dan letak bercak pada
kromatogram. Laju aliran pelarut pengembang lebih cepat di dalm bejana tanpa kertas saring
dibandingkan bercak yang terbentuk pada bejana yang dijenuhkan sempurna dengan uap
14

pelarut pengembang. (Stahl, 1989). Kertas saring berfungsi untuk mencegah terjadinya
penguapan dari lapisan fasa diam.
2.3.9 Penotolan Sampel
Pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya jika
menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin. Hasil praktikum
menunjukkan bahwa penotolan sampel secara otomatis lebih dipilih daripada penotolan secara
manual terutama jika sampel yang akan ditotolkan lebih dari 15 µl. Penotolan sampel yang
tidak tepat akan menyebabkan bercak yang menyebar dan puncak ganda.
2.3.10 Deteksi Bercak
Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak bewarna. Untuk
penentuannya dapat dilakukan secara kimia dengan mereaksikan bercak dengan suatu
pereaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Kadang-kadang lempeng
dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas
warna bercak. Cara fisika yang dapat digunakan untuk menampakkan bercak adalah dengan
fluoresensi sinar ultraviolet. Lapisan tipis sering mengandung indikator fluoresensi yang
ditambahkan untuk membantu penampakan bercak tanwarna pada lapisan yang telah
dikembangkan. Indikator fluoresensi ialah senyawa yang memancarkan sinar tampak jika
disinari dengan sinar berpanjang gelombang lain, biasanya sinar ultraviolet. Indikator
fluoresensi yang paling berguna ialah sulfida anorganik yang memancarkan cahaya jika
disinari pada 254 nm. Indikator fluoresensi terdapat dalam penjerap niaga dan lapisan siap
pakai sekitar 1% dan tampaknya tidak berperan dalam proses kromatografi (Rohman, 2009;
Gritter, 1991).
2.3.11 Perhitungan Harga Retention Factor (Rf)
Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan dengan angka
Rf atau hRf. Retension factor atau Rf adalah perbandingan jarak rambat penotolan terhadap
jarak rambat fase gerak diukur dari titik penotolan. Angka Rf berjangka antara 0,00 dan 1,00
dan hanya ditentukan dua decimal, sedangkan hRf ialah angka Rf dikalikan factor 100
menghasilkan angka 0 – 100 (Stahl, 1985).
Rf =
15

2.4 Kerangka Konsep
2.5 Definisi Operasional
No. Variabel Definisi
Operasional
Alat
ukur
Hasil Ukur Skala Ukur
A. Independent
Jamu yang
beredar di
masyarakat
Obat Tradisional
Indonesia yang
beredar dan
sering digunakan
oleh masyarakat
Nama
Jamu
Tercantum
Tidak
tercantum
Tercantum
dalam Public
Warning No.
HM.03.03.1.43.
08.10.8013
tanggal 13
agustus 2010
B. Dependent
Identifikasi
Bahan Kimia
Obat (BKO)
Bahan kimia obat,
paracetamol,
Coffein,
Methampiron
yang ditambahkan
dalam jamu.
KLT Positif BKO
Negatif BKO
Nominal
16
Jamu yang beredar di masyarakat
Ada atau tidaknya BKO dalam jamu
Variabel dependenVariabel Independen
Uji KLT

BAB III
METODE PRAKTIKUM
3.1 Desain Praktikum
Praktikum ini menggunakan metode eksperimental. Eksperimen dilakukan dengan
mengidentifikasikan bahan kimia dalam jamu. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling atau sampling pertimbangan yaitu sampel jamu yang beredar dan banyak
digunakan oleh masyarakat di pasar DKI Jakarta.
3.2 Tempat dan waktu Praktikum
Praktikum dilakukan di laboratorium Farmakognosi Politeknik Kemenkes Jakarta II
Jurusan Farmasi pada 14 November 2011.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi adalah semua jamu yang beredar di pasar DKI Jakarta. Sampel adalah jamu
yang beredar dan banyak digunakan oleh masyarakat di pasar DKI Jakarta.
3.4 Alat dan Bahan
Bejana kromatografi, lempeng kromatografi, pipa kapiler, oven, lampu UV, corong pisah,
corong, Erlenmeyer, beaker glass, gelas ukur, cawan uap, kertas saring, kertas pH universal
dan indikatornya, batang pengaduk, spatula, pipet tetes, timbangan, waterbath(WB), jamu ,
coffeinum, methampyron,parasetamol, eluen = kloroform:etanol = 4:1 (50 ml), aqua
destillata, NaOH 1 N, HCl 0,1 N, kloroform, etanol.
3.5 Prosedur Praktikum
3.5.1 Pembuatan Fase Gerak (Eluen)
Fase gerak dalam praktikum ini menggunakan sistem TD yaitu menggunakan pelarut
Chloroform : Aseton (4:1) sebanyak 5 ml.
3.5.2 Penjenuhan Bejana
Masukkan 50 ml fase gerak ke dalam bejana kromatografi, biarkan bejana dalam
keadaan tertutup selama 24 jam hingga bejana jenuh.
3.5.3 Persiapan Lempeng Kromatografi
17

Fase diam menggunakan silica gel GF 254. Siapkan lempeng kromatografi dengan
ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm.
3.5.4 Larutan Percobaan
Satu dosis cuplikan serbuk jamu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml
ditambah 50 ml air, dibasakan dengan NaOH 1N sampai pH 9 – 10, kocok selama 30 menit
kemudian saring. Filtrat diasamkan dengan beberapa tetes HCl 0,1N sampai pH 3 – 4,
diekstraksi empat kali, masing – masing dengan 20 ml kloroform. Ekstrak kloroform
diuapkan di atas water bath sampai hamper kering. Sisa larutkan dalam 5 ml etanol.
3.5.5 Larutan Kontrol Positif
Menggunakan cara yang sama dilakukan ekstraksi satu dosis jamu yang telah
ditambah masing – masing dengan 10 mg kofein, 15 mg methampiron, dan 15 mg
paracetamol.
3.5.6 Larutan Baku Standar
Sejumlah kurang lebih 10 mg coffein, 15 mg methampiron, dan 15 mg paracetamol,
ditimbang seksama dilarutkan 5 ml etanol.
3.5.7 Penotolan
Totolkan larutan percobaan pada lempeng kromatografi dengan bantuan pipa kapiler
dan pengering hair dryer. Beri tanda. Masukkan lempeng KLT yang telah ditotolkan ke dalam
bejana, biarkan naik. Angkat lempeng, biarkan kering dan deteksi noda dengan UV 254 dan
366 nm, beri tanda dan hitung Rf.
3.6 Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh merupakan data primer dari hasil pengamatan terhadap harga Rf
pada kromatografi lapis tipis yang menunjukkan adanya penambahan bahan kimia.
18

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Berdasarkan system TC, jamu “Wantong” diduga mengandung coffein dan
methampiron karena nilai Rf pada larutan percobaan mendekati nilai Rf coffein dan
methampiron. Begitu pula jamu “Sepet Wangi” diduga mengandung parasetamol karena
nilai Rf pada larutan percobaan mendekati nilai Rf parasetamol. Selengkapnya dapat
dilihat pada tablel 4.1.
Tabel 4.1. Hasil data Rf dari berbagai jamu dengan Sistem TC
Jamu Wantong
kapsul
Jamu jaya asli
nyentul serbuk
Jamu wantong
kapsul
Jamu sepet wangi
sediaan pelet
Larutan Percobaan
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2
Rf 0,65 0,88 0,78 0,10,19
0,47
0,06
0,21
0,71
0,18
0,28
0,5
0,75
0,83
Larutan Kontrol
Rf 0,62 0,88 0,17 0,12
0,23
0,34
0,93
0,99
0,15
0,20
0,57
0,32
0,61
0,78
0,42
0,6
0,7
0,75
0,88
Larutan Baku
Rf coffein 0,62 - - 0,81 0,99 0,7 -0,67
0,92
Rf
Methampyro
n
0,8 0,87 0,37 0,75 0,93 0,59 -0,61
0,94
19

Rf PCT 0,71 - 0,3 0,76 0,03 0,14 0,180,16
0,92
Berdasarkan system TD, jamu “Wantong” diduga mengandung parasetamol karena nilai Rf
pada larutan percobaan mendekati nilai Rf parasetamol. Begitu pula jamu “Jaya Asli Nyentul”
diduga mengandung methampyron karena nilai Rf pada larutan percobaan mendekati nilai Rf
methampyron. Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.2
Tabel 4.2. Hasil data Rf dari berbagai jamu dengan Sistem TD
Jamu Wantong
Kapsul
Jamu jaya asli nyentul
serbuk
Jamu wantong
kapsul
Jamu sepet wangi
sediaan pellet
A3 A4 B3 B4 C3 C4 D3 D4
Larutan Percobaan
Rf 0,70 0,69 0,42 0,62 0,14
0,55
0,93
0,24
0,95
- -
Larutan Kontrol
Rf 0,69 0,69 0,42 0,54 0,19
0,35
0,54
0,91
0,28
0,48
0,94
0,55
0,81
0,475
0,68
0,84
Larutan Baku
Rf coffein 0,76 0,79 0,46 - 0,36 0,52 0,82 0,68
Rf
Methampyron
0,86 0,85 0,42 - 0,19 0,3 - -
Rf PCT 0,69 0,69 0,24 0,55 0,2 0,28 0,63 0,37
20

Berdasarkan system TE, jamu “Sepet Wangi” diduga mengandung coffein dan parasetamol
karena nilai Rf pada larutan percobaan mendekati nilai Rf coffein serta parasetamol. Jamu
“Wantong” juga diduga mengandung parasetamol karena nilai Rf pada larutan percobaan
mendekati nilai Rf parasetamol. Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.3
Tabel 4.3. Hasil data Rf dari berbagai jamu dengan Sistem TE
Jamu Wantong
kapsul
Jamu jaya asli
nyentul serbuk
Jamu wantong
kapsul
Jamu sepet wangi
sediaan pelet
A5 A6 B5 B6 C5 C6 D5 D6
Larutan Percobaan
Rf 0,17
0,82
0,64 0,31 0,23 0,21
0,7
0,9
0,24
0,95
0,04
0,81
0,91
0,7
0,8
0,9
Larutan Kontrol
Rf 0,82 0,55 0,37 0,35 0,15
0,5
0,64
0,94
0,28
0,48
0,94
0,04
0,25
0,51
0,55
0,66
0,81
0,88
0,91
0,6
0,65
0,7
0,81
Larutan Baku
Rf coffein - - 0,38 0,42 0,56 0,53 0,56
0,91
0,62`
Rf
Methampyron
- - 0,36 0,38 0,6 0,3 0,02
0,52
0,91
-
Rf PCT - - 0,65 - 0,63 0,28 0,68
0,91
0,66
21

4.2 Pembahasan
Penambahan BKO coffein, methampiron, dan parasetamol pada jamu akan
mempercepat kerja jamu dalam memberikan efek pengobatan, namun bila dikonsumsi
terus menerus coffein akan mengakibatkan efek samping seperti insomnia kronik, gelisah,
dan ulkus. Metampiron dapat menyebabkan gangguan saluran cerna seperti mual,
pendarahan lambung, rasa terbakar serta gangguan sisten saraf seperti tinitus (telinga
berdenging), syok, kematian dan lain-lain. Sedangkan parasetamol mengakibatkan seperti
kerusakan hati serta iritasi lambung.
Hasil penotolan pada lempeng kromatografi diamati dengan lampu uv 254 nm dan 366
nm, kemudian dihitung Rf-nya. Hasil pengamatan coffein seperti yang tercantum pada
table 4.1, menunjukkan bahwa jamu “Wantong” memiliki nilai Rf 0,7 memiliki selisih 0,01
dari nilai Rf larutan baku coffein. Selain itu jamu “Wantong juga memiliki nilai Rf 0,88
yang berselisih 0,01 terhadap larutan baku methampyron. Sedangkan hasil pengamatan
parasetamol seperti yang tercantum pada table 4.1, menunjukkan bahwa jamu “Sepet
Wangi” memiliki nilai Rf 0,19 tidak memiliki selisih dari nilai Rf larutan baku
parasetamol.
Hasil pengamatan parasetamol seperti yang tercantum pada table 4.2, menunjukkan
bahwa jamu “Wantong” memiliki nilai Rf 0,69 tidak memiliki selisih dari nilai Rf larutan
baku coffein. Sedangkan hasil pengamatan parasetamol seperti yang tercantum pada table
4.2, menunjukkan bahwa jamu “Jaya Asli Nyetul” memiliki nilai Rf 0,4125 memiliki
selisih 0,075 dari nilai Rf larutan baku parasetamol.
Hasil pengamatan coffein seperti yang tercantum pada table 4.3, menunjukkan bahwa
jamu “Sepet Wangi” memiliki nilai Rf 0,91 sama dengan dari nilai Rf larutan baku coffein.
Selain itu jamu “Sepet Wangi” memiliki nilai Rf 0,7 yang memiliki selisih 0,04 dari nilai
Rf larutan baku parasetamol. Jamu “Wantong” memiliki Rf 0,7 memiliki selisih Rf 0,07
dengan parasetamol .
Jamu “Wantong” teridentifikasi mengandung coffein, methampyron, dan parasetamol,
jamu “Jaya Asli Nyetul” mengandung methampyron. Sedangkan jamu “Sepet Wangi”
mengandung coffein dan parasetamol.
Pada identifiksi jamu dengan KLT ini ada beberapa data yang tidak mempunyai harga
Rf sebab bercak tidak muncul. Tidak munculnya bercak pada beberapa lempeng KLT
dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu :
22

1. Human Error dapat terlihat karena kurang terampilnya praktikan saat melakukan
penotolan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap nilai Rf yang nantinya akan
mempengaruhi pengambilan kesimpulan apakah jamu tersebut mengandung bahan
kimia obat atau tidak.
2. Alat dan Bahan
Sebagian data praktikum tidak mempunyai Rf, hal ini bisa terjadi dari instrument
error, seperti :
1. Fase diam. Dapat disebabkan oleh kualitas penjerap, adanya pengotor, dan
ketebalannya harus dijaga secara hati – hati. Gel silica sebagai fase diam dalam
praktikum ini harus dihindarkan kontak dengan uap air agar tidak teradsorpsi oleh
selain fase gerak. Hal yang harus diperhatikan dalam pengaktifan lempeng yaitu
lempeng disimpan dalam suhu ruangan, noda harus ditotol sedikitnya 2 cm dari
pinggir lempeng dan sampel ditotolkan dalam keadaan kering sebelum dielusi.
2. Fase gerak. Eluen harus dibuat murni atau tidak ada bahan pengotor dan segar
karena sifatnya yang higoskopis.
3. Bejana Elusi. Bejana harus jenuh oleh eluen sebelum proses elusi. Dapat
disempurnakan dengan menggunakan bejana kecil dengan kertas saring dan eluen
yang cukup serta penutup yang harus cocok.
4. Temperature. Bejana harus dihindarkan dari sumber pana, sinar matahari lagsung.
Jika temperaturnya naik, eluen mudah menguap, aluen mengelusi lebih cepat dan
nilai Rf umumnya menurun.
5. Jarak elusi. Kurang berpengaruh signifikan pada nilai Rf dengan perubahan jarak
elusi jika sistem tetap dibuat jenuh.
6. Sampel. Meningkatnya massa sampel pada lempeng sering meningkatkan nilai Rf
dari obat (Stahl, 1985).
Menurut Sastrohamidjojo (1991), Rf pada KLT dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain:
a. Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan.
b. Sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya.perbedaan penyerap akan memberikan
perbedaan yang besar terhadap harga Rf meskipun menggunakan fase gerak dan diam
yang sama.
c. Tebal dan kerataan lapisan penyerap. Ketidakrataan akan menyebabkan aliran
pelarut menjadi tak rata pula dalam daerah yang kecil dari plat.
d. Derajat kemurnian fase gerak.
23

e. Derajat kejenuhan uap pengembang dalam bejana.
f. Jumlah cuplikan. Penotolan sampel yang berlebihan dapat menyebabkan
terbentuknya ekordan efek tak kesetimbangan lain hingga noda menjadi satu sehingga
menyebabakan kesalahan pada harga Rf.
g. Suhu. Sebaiknya dalam suhu tetap untuk mencegah perubahan komposisi pelarut
yang disebabakan oleh penguapan .
Sistem yang digunakan mempunyai faktor juga terhadap hasil KLT. Menurut Stahl
(1985) fase gerak yang mempunyai bahan yang berbeda – beda untuk identifikasi zat yang
berbeda pula. Dapat dilihat bahwa hasil KLT pada sistem TC untuk coffein dan
paracetamol mempunyai nila Rf yang berbeda. Pada identifikasi jamu “Wantong”, sistem
TC dapat menegaskan bahwa jamu mengandung coffein dan methampiron, sedangkan
pada sistem TD menegaskan bahwa jamu mengandung paracetamol dan sistem TE tidak
dapat mengidentifikasi. Hal ini disebabkan karena perbedaan sistem gerak pada masing –
masing sistem.
Menurut Stahl (1986), untuk mengidentifikasi senyawa obat digolongkan menjadi
beberapa sistem sesuai dengan khasiat senyawa obat. Pada praktikum ini menggunakan
paracetamol dan methampiron yang berkhasiat sebagai analgetik dan antiinflamasi.
Berdasarkan khasiat tersebut, identifikasi dapat menggunakan sistem TD, TF, atau TG.
Sedangkan untuk coffein yang berkhasiat sebagai stimulant diidentifikasi menggunakan
sistem TA, TB atau TC.
24

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Jamu “Wantong” mengandung Coffein dan Methampyron, jamu “Jaya Asli Nyetul” mengandung Methampyron, sedangkan jamu “Sepet Wangi” mengandung Coffein dan Parasetamol.
5.2 Saran
Praktikan diharapkan terampil dalam menotolkan
DAFTAR PUSTAKA
46 Jamu Mengandung Bahan Kimia Obat www.detikhealth.com, 13 Agustus 2010.
Badan POM RI, 2010, Apakah Produk Herbal Yang Anda Konsumsi Aman, Bermutu,
dan Bermanfaat, Info POM, No. 4, Vol. XI, Halaman 1-4.
Badan POM, 2008, Peraturan Perundang – Undangan diBidang Obat Tradisional,
Obat Herbal Terstandar, dan Fitokimia, Jakarta.
BPOM Awasi 21 Obat Tradisional, Seberapa Berbahaya? www.portal.cbn.net.id, 10
Oktober 2011.
25

Count, L. B., 2011, Identifikasi Paracetamol, Fenilbutazon dan Diklofenak pada Jamu
yang Telah Dilarang oleh Badan POM dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis, KTI,
Jurusan Farmasi, Jakarta.
Gritter, R. J., Bobbitt, J. M., dan Schwarting, A. E., 1991, Pengantar Kromatografi,
Edisi 2, ITB, Bandung.
Inilah Daftar Obat Ilegal yang Dilarang BPOM www.jdih.jatimprov.go.id, 7 Oktober
2011.
Moffat, A. C., 1986, I, Edisi 2, The Pharmaceutical Society and Great Britain, The
Pharmaceutica Press, London.
Nassa, F., 2011, Uji Pendahuluan Kualitatif Adanya Penambahan Fenilbutazon Dalam
Jamu Rematik, KTI, Jurusan Farmasi, Jakarta.
Rohman, A.,2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Sastrohamidjojo, Hardjono, 2005, Kromatografi, Liberty, Yogyakarta.
Stahl, Egon, 1985, Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi, Penerjemah
Purnawinata, K., Sudiro, I., dan Niksolihin, S., ITB, Bandung.
Watson, G. D., 2009, Pharmaceutical analysis, Edisi Kedua, penerjemah Winny R.
Syarief, EGC, Jakarta.
26