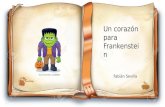KITIN & KITOSAN_Melita Mulyani_12.70.0080_A1_Unika Soegijapranata
Kitin Kitosan Cindy Corazon 13.70.0028 E1 UNIKA Soegijapranata
-
Upload
praktikumhasillaut -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
description
Transcript of Kitin Kitosan Cindy Corazon 13.70.0028 E1 UNIKA Soegijapranata

Acara II
KITIN KITOSAN
LAPORAN RESMI PRAKTIKUM
TEKNOLOGI HASIL LAUT
Disusun Oleh:
Nama : Cindy Corazon
NIM : 13.70.0028
Kelompok : E1
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2015

1. MATERI METODE
1.1. Alat dan bahan
Alat – alat yang digunakan selama praktikum adalah blender, ayakan, oven, peralatan
gelas. Sedangkan bahan – bahan yang digunakan meliputi limbah udang, HCl 0,75 N; 1
N dan 1,25 N, NaOH 3,5%, NaOH 40%, 50% dan 60%.
1.2. Metode
DEMINERALISASI
Limbah udang dicuci menggunakan air mengalir dan dikeringkan
Dicuci dengan air panas sebanyak 2x dan dikeringkan
Bahan dihancurkan dan diayak menggunakan ayakan 40-60 mesh dan
ditimbang
Dicampur dengan HCl 0,75N, 1N dan 1,25N dengan perbandingan
10:1

2
Dipanaskan hingga suhu 80oC dan diaduk selama 1 jam
Dicuci hingga pH netral dan dikeringkan pada suhu 90oC selama 24
jam

3
DEPROTEINASI
Hasil demineralisasi dicampur dengan NaOH 3,5% dengan
perbandingan 6:1
Dipanaskan pada suhu 70oC selama 1 jam dan dilakukan pengadukan
Residu disaring dan dicuci hingga pH netral dan dikeringkan pada suhu 90oC
selama 24 jam dan dihasilkan chitin

4
DEASETILASI
Dipanaskan pada suhu 80oC selama 1 jam dan dilakukan pengadukan
Residu dicuci dan disaring hingga pH netral dan dikeringkan pada suhu
90oC selama 24 jam dan dihasilkan chitosan
Hasil deproteinasi dicampur dengan NaOH 40%, 50% dan 60%
dengan perbandingan 20:1

2. HASIL PENGAMATAN
Hasil pengamatan dari rendemen kitin dan kitosan dari percobaan yang dilakukan oleh
kloter E disajikan oleh Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengamatan Kitin dan Kitosan
Kel Perlakuan Rendemen
Kitin I (%)
Rendemen
Kitin II (%)
Rendemen
Kitosan (%)
E1 HCl 0,75 N + NaOH 3,5% +
NaOH 40%
26,35 28,57 32
E2 HCl 0,75 N + NaOH 3,5% +
NaOH 40%
37,93 27,78 17,23
E3 HCl 1 N + NaOH 3,5% +
NaOH 50%
23,53 30,77 28,89
E4 HCl 1 N + NaOH 3,5% +
NaOH 50%
35 18,18 15,33
E5 HCl 1,25 N + NaOH 3,5% +
NaOH 60%
29,17 25 42,5
Dilihat dari hasil pengamatan pada tabel 1, diketahui dalam praktikum kitin kitosan
memperoleh hasil perhitungan kitin rendemen I dan II serta rendemen kitosan dari
berbagai perlakuan . kelompok E1 dan E2 memiliki perlakuan yang sama terhadap sampel
yaitu pemberian HCl 0,75 N + NaOH 3,5% + NaOH 40%. Kelompok E 3 dan E4 juga
memiliki perlakuan yang sama terhadap sampel yaitu penambahan HCl 1 N + NaOH
3,5% + NaOH 50%. Kelompok E5 memberi HCl 1,25 N + NaOH 3,5% + NaOH 60%.
Penambahan kadar NaOH yang penambahan pertama masing-masing kelompok adalah
sama yaitu sebesar 3,5%. Pada kelompok E2, E4 dan E5 hasil rendemen kitin II
mengalami penurunan namun hal sebaliknya terjadi pada sampel E1 dan E3. Rendemen
kitin I terkecil adalah sampel E1 namun hasil terbesar diperoleh E2 yang memberi
perlakuan sampel yang sama. Nilai rendemen kitin II terbesar adalah sampel kelompok
E3 dan yang terkecil diperoleh kelompok E4 dengan perlakuan sampel yang sama. Hasil
rendemen kitosan kelompok E1, E4 dan E5 lebih besar dibanding jumlah rendemen kitin
II. Hasil terbesar diperoleh sampel E5 dan yang terkecil pada sampel E4.

3. PEMBAHASAN
Dalam praktikum ini dilakukan pengamatan dan pembahasan pembentukan kitin kitosan
yang berasal dari sisa bagian yang tidak terpakai dalam pengolahan udang. Sebagian besar
atau bahkan semua yang tergolong dalam organisme kelompok crustaceae mengandung
kitin dan kitosan. Contoh dari organisme crustaceae adalah kepiting, lobster, udang, dan
masih banyak lagi (Puvvada, 2012). Khusus untuk limbah dari udang yang merupakan
bahan yang digunakan dalam praktikum, menurut Dutta et al. (2004) memiliki kandungan
protein dan mineral yang cukup tinggi. Selain mengandung protein dan mineral yang
tinggi di dalam cangkang udang, terdapat pro vitamin A yang bernama asthaxanthin yang
merupakan komponen penyusun warna dalam udang. Menurut Patria (2013), kandungan
kitin dan kitosan yang terdapat pada Crustaceae mencapai sekitar 20 – 60% dari berat
bahan total. Dari data yang sudah dikumpulkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan
(2000) menyatakan bahwa limbah dari pengolahan crustaceae hanya dibuang begitu saja
tanpa adanya pemanfaat lebih lanjut untuk diproses menjadi produk yang lebih
bermanfaat. Limbah kulit crustaceae yang belum diolah adalah 56.200 metrik ton per
tahun.
Kitin merupakan polisakarida yang terkandung secara melimpah dalam cangkang
krustasea seperti kepiting dan udang. Kitin bersifat biokompatibel, biodegradable dan
polimer antimikrobial (Abdou 2012). Ciri fisik yang dimiliki oleh senyawa kitin yang
diperoleh secara murni adalah bentuk kristal putih yang amorphous, tidak memiliki bau
dan rasa, dan tidak larut dalam pelarut organik serta berbagai jenis asam (asam anorganik)
dan basa (basa encer) (Muzzarelli, 1985). Dengan ketidaklarutan kitin dalam berbagai
jenis pelarut termasuk beberapa jenis asam dan basa maka masih sangat jarang dijumpai
adanya industri yang secara khusus mengolah kitin dari sampah crustaceae. Penerapan
penggunaan kitin secara murni juga masih sangat jarang digunakan karena hal tersebut.
Dalam industri pangan, sifat kitin yang sangat sulit ditemukan dalam kondisi yang murni,
membuat kitin jarang digunakan dalam kegiatan industri seperti produksi (Brugnerotto et
al., 2001).
Untuk memperoleh kitin dalam bentuk yang murni langkah - langkah yang dilakukan
adalah penghilangan mineral dan protein dari bagian tubuh crustaceae yang digunakan

7
yaitu dengan demineralisasi dengan asam dan diproteinasi dengan basa. Selain
menggunakan asam dan basa dalam menghilangkan kitin dan kitosan, dapat digunakan
pula bantuan enzim dan bantuan mikroba dengan jalan fermentasi asam laktat. Namun
kelemahan demineralisasi dan deproteinasi dengan menggunakan mikroorganisme adalah
waktu yang digunakan lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar dan juga resiko
dari kegagalan proses sangat lebih tinggi dibandingkan dengan metode kimiawi karena
kontrol atas parameter keberhasilan proses biologis tersebut harus dikontrol dengan baik
seperti pH, suhu, dan banyak parameter lain yang harus terjaga (Tarafdar & Biswas 2013).
Sturktur kimia dari kitin ditunjukkan oleh Gambar 1.
Gambar 1. Struktur Kimia Kitin
(Zhang et al., 2011)
Dalam tubuh dari organisme crustaceae, kitin akan ditemukan bersatu dengan protein dan
garam organik (CaCO3) serta pigmen. Menurut Suhardi (1992), menyatakan bahwa dalam
tubuh makhluk hidup chitin akan bersatu dengan beberapa komponen yang ada di dalam
tubuh organisme tersebut. Dari kitin, dapat mendukung peran beberapa enzim yang
berguna bagi tubuh yaitu laktase, papain, asam fosfatase, dan glukisa isomerase (Peter,
1995). Sebenarnya, jika teknologi mendapatkan kitin murni bisa diproduksi secara masal,
untuk memperoleh kitin dibutuhkan harga produksi yang sangat murah karena kitin
berasal dari zat sisa yang berasal dari crustaceae yang berasal dari makanan laut (Wang
et al., 2010). Perubahan struktur dari kitin menjadi kitosan disebabkan karena perubahan
yang terjadi pada gugus yang dimiliki oleh kitin yaitu gugus asetamida (-NHCOCH3)
menjadi gugus amina yang terdapat pada kitosan. Struktur kimia dari kitosan memiliki
struktur yang hampir mirip dengan struktur kimia yang dimiliki oleh selulosa hanya

8
berbeda pada gugus amino dari kedua bahan tersebut (Robert, 1992
Gambar 2. Struktur Kimia dari Kitosan
(Zhang et al., 2011)
Kitosan merupakan kopolimer linear yang terdiri dari β 1-4 yang menghubungkan unit-
unit 2-asetamido-2deoksi-d-glukopiranosa dan amino-2-deoksi-d-glukopiranosa. Kitosan
umumnya adalah komponen dinding sel jamur namun dapat diperoleh dari proses
diasetilasi kitin. Kitosan memiliki sifat-sifat fungsional seperti aktivitas antimikroba,
kemampuan untuk membentuk lapisan pelindung, pembentuk tekstur, agen pengkelat dan
sebagai antioksidan (Abdou, 2012). Karena memiliki sifat fungsional yang banyak,
kitosan digunakan dalam pengawetan makanan, pertanian, kosmetik, suplemen makanan
dan diaplikasikan dalam ilmu medis. Dalam industri pangan sifat anti mikroba dalam
kitosan dimanfaatkan dalam pembuatan lapisan antimikroba yang digunakan sebagai
bahan pengemas untuk makanan, persediaan medis atau lapisan pelindung dari
kontaminasi mikroba (Puvvada et al. 2012). Dalam dunia medis, kitosan yang memiliki
sifat anti koagulan dimanfaaatkan dalam penyembuhan luka, jahitan paska operasi dan
perawatan lainnya seperti menurunkan oksidasi dalam sel (Tarafdar & Biswas 2013).
Sifat – sifat fungsional tersebut tergantung pada berat molekul dan viskositasnya. Secara
umum ada 4 langkah dasar dalam memperoleh kitosan dari cangkang krustasea yaitu
demineralisasi, deproteinasi, dekolorasi dan deasetilasi (Islam et al. 2011). Kualitas
kitosan yang utama ditentukan oleh derajat diasetilasi dimana derajat deasetilasi ini
tergantung dari material dan kondisi selama proses seperti konsentrasi larutan alkali, suhu
dan waktu (Patria 2013)
Langkah kerja dalam praktikum ini dilakukan tiga tahapan kerja utama yaitu
demineralisasi yang menghilangkan mineral, deproteinasi yang dapat memecah protein,
dan diasetilasi untuk memperoleh kitin dan kitosan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang

9
disampaikan oleh Rahayu et al. (2007) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah
utama untuk membuat kitosan dan kitin dari limbah crustaceae yaitu demineralisasi,
diproteinasi, dan deasetilasi. Dalam tahap demineralisasi, pertama limbah udang (kulit
udang) dipersiapkan dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan. Setelah
kering, sampel dicuci kembali menggunakan air panas sebanyak dua kali. Pencucian
bahan dilakukan untuk mencegah bahan pengotor yang ada di dalam bahan akan
mengotori produk dan mempengaruhi proses ekstraksi. Selain itu proses pencucian yang
kedua kalinya dengan menggunakan air panas bertujuan agar senyawa larut air dapat
dihilangkan dan memiliki sifat larut air. Proses ini bertujuan agar zat pengotor yang
terdapat dalam bahan limbah crustaceae yang akan digunakan sebagai bahan baku kitin
memiliki kemurniaan yang lebih baik.
Hasil dari pencucian limbah adalah limbah dengan kemurnian yang lebih baik. Setelah
itu dikeringkan kembali dan dihancurkan hingga membentuk serbuk, lalu dilakukan
pengayakan dengan ayakan 40-60 mesh. Penggilingan dan pengayakan dengan
menggunakan ayakan dijelaskan oleh Bastaman (1989) sebagai sebuah proses yang dapat
memperluas bahan yang digunakan dan meningkatkan kecepatan reaksi karena luas
permukaan yang jauh menjadi lebih besar. Kontak antara serbuk dan pelarut akan
berlangsung dengan lebih maksimal ketika bahan dihancurkan. Tujuan dilakukannya
pengeringan kedua adalah untuk menghilangkan sisa air panas yang masih menempel
pada kulit udang, sehingga kadar air pada kulit udang secara keseluruhan akan berkurang
dan kulit udang akan menjadi kering, sedangkan menurut Muzzarelli, et al. (1997),
penumbukan atau penghancuran menjadi serbuk berfungsi agar proses selanjutnya
berlangsung lebih cepat dan sempurna karena semakin luas permukaan sampel, maka
akan semakin banyak dan cepat penyerapan larutan alkali / pelarut yang akan diberikan.
Setelah diayak, serbuk dari limbah udang tersebut dicampur HCl dengan perbandingan
10 : 1. Kadar dari HCl yang digunakan adalah 0,75N, 1N, dan 1,25 N. Perbedaan dari
HCl yang digunakan untuk menguji kandungan HCl mana kah yang terbukti dapat
menghasilkan rendemen kitin dan kitosan yang paling banyak. Penambahan asam seperti
HCl dilakukan untuk menurunkan atau menghilangkan kandungan garam mineral yang
terdapat pada bahan crustaceae. Garam mineral yang sering ada di dalam udang adalah

10
kalsium karbonat dan kalsium fosfat (Bastaman, 1989). Dengan pencampuran antara HCl
dan kalsium karbonat akan menghasilkan kalsium klorida, asam karbonat, dan asam
sulfat. Dengan garam – garam yang dihasilkan merupakan garam yang larut dalam air,
maka ketika proses penyaringan terjadi yang tersisa adalah kitin yang tidak larut dalam
air. Gelembung udara yang nampak pada saat penambahan HCl menandakan adanya
kehilangan mineral dari bahan yang digunakan.
Reaksi kimia yang berlangsung saat demineralisasi adalah :
HCl (aq) H+ (aq) + Cl-(aq)
H+ (aq) + H2O H3O+ (aq)
Ca3(PO4)2 (s) + 2 H3O+ (aq) 3 Ca2+ (aq) + 2 H3PO4 (aq) + O2(g)
CaCO3 (s) + 2 H3O+ (aq) Ca2+ (aq) + CO2 (g) + 3 H2O (l).
(Mudasir, 2008).
Campuran tersebut diaduk selama 1 jam dengan pemanasan pada suhu 80°C. Setelah suhu
dari larutan HCl sudah turun, larutan akan dicuci dengan menggunakan air bersih sampai
pH menajdi netral. Proses pencucian sampel yang sudah diberi HCl dengan menggunakan
air merupakan proses netralisasi. Menurut Fennema (1985), netralisasi merupakan suatu
upaya yang dilakukan dengan menambahkan air atau zat tertentu ke dalam suatu larutan
dengan tujuan agar pH mendekati pH yang netral. Pengaruh dari proses netralisasi adalah
akan munculnya penggembungan antara kitin dan alkali.. Hal ini akan menyebabkan
efektivitas proses hidrolisis basa terhadap gugus asetamida pada rantai kitin akan semakin
baik. Setelah itu sampel dikeringkan dengan suhu 80°C selama 24 jam. Tahapan ini
disebut dengan tahapan deproteinasi. Deproteinasi menurut Wu et al. (2005) merupakan
suatu proses yang dapat mengurangi protein yang terdapat pada kulit crustaceae. Menurut
Hagono dan Djaeni (2008) protein yang terkandung dalam limbah udang mencapai 30%
dari berat bahan totalnya.
Hasil dari demineralisasi yang sudah dikeringkan berupa tepung ditambah larutan NaOH
dengan perbandingan 6:1. Menurut Rogers (1986), tujuan dari penambahan NaOH dalam
proses ekstraksi kitin dan kitosan adalah NaOH akan mengalami ionisasi dalam air dan
akan membentuk ion natrium dan ion hidroksida. Setiap ion hidroksida dan ion hidrogen

11
yang terbentuk akan membentuk molekul air. Ketika di dalam larutan terdapat ion
hidrogen lebih banyak dibandingkan dengan ion hidroksida maka larutan akan bersifat
asam dan ketika larutan memiliki ion hidroksi yang lebih banyak larutan akan bersifat
basa. Campuran tersebut diaduk selama 1 jam kemudian dipanaskan pada suhu 70oC
selama 1 jam.
Proses yang sudah dibahas merupakan proses pembuatan kitin. Sebelum membuat
kitosan, maka pembuatan kitin harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari
Robert (1992) yang menyatakan bahwa pembuatan kitosan dengan menggunakan metode
ekstraksi dapat dilakukan setelah dilakukannya esktraksi kitin. Proses pembuatan kitosan
dari bahan dasar kitin disebut dengan diasetilasi. Derajat diasetilasi merupakan satuan
dan parameter baku dalam menentukan kualitas dari kitosan yang terbentuk. Gugus asetil
akan hilang seiring dengan terbentuknya kitosan dari kitin akibat reaksi dengan larutan
basa. Derajat diasetilasi yang tinggi maka menandakan ikatan hidrogen dan ion hidrogen
akan semakin kuat seirig dengan semakin rendahnya ikatan antara gugus asetil kitosan
(Knoor, 1984). Penambahanan NaOH 40%, 50%, 60% akan terjadi setelah proses
demineralisasi dan diproteinasi. Perbandingan NaOH yang ditambahkan dan rendemen
kitin yang dihasilkan adalah 1:20. Tujuan dari penambahan NaOH dan penerapan pada
suhu tinggi adalah deasetilasi untuk mendapatkan kitosan dari kitin. Dalam kitin terdapat
ikatan yang kuat antara ion nitrogen dan gugus karboksil. Dengan penambahan NaOH
akan membuat membuat ikatan tersebut menjadi lebih renggang. Dilengkapi oleh
Martinou (1995) bahwa larutan alkali dengan konsentrasi yang tinggi dapat memutus
ikatan karboksil dengan atom nitrogen dalam kitin.
Dari hasil analisa yang diperoleh kelompok E1 dan E2 memiliki perlakuan yang sama
terhadap sampel yaitu pemberian HCl 0,75 N + NaOH 3,5% + NaOH 40%. Kelompok E
3 dan E4 juga memiliki perlakuan yang sama terhadap sampel yaitu penambahan HCl 1
N + NaOH 3,5% + NaOH 50%. Kelompok E5 memberi HCl 1,25 N + NaOH 3,5% +
NaOH 60%. Penambahan kadar NaOH yang penambahan pertama masing-masing
kelompok adalah sama yaitu sebesar 3,5%. Pada kelompok E2, E4 dan E5 hasil rendemen
kitin II mengalami penurunan namun hal sebaliknya terjadi pada sampel E1 dan E3.

12
Rendemen kitin I terkecil adalah sampel E1 namun hasil terbesar diperoleh E2 yang
memberi perlakuan sampel yang sama
Hasil yang diperoleh kelompok E1 dan E3 tidak sesuai dengan pernyataan Puspawati et
al. (2010) bahwa dalam proses deproteinasi hasil rendemen selanjutnya akan
menghasilkan rendemen yang lebih rendah dibandingkan dengan rendemen I. Beberapa
zat yang terlarut dalam protein larut seiring dengan proses deproteinasi di mana zat – zat
tersebut memiliki massa molar yang tinggi sehingga penurunan massa akan terjadi pada
proses pembentukan rendemen II. Ditambahkan oleh Hong et al.(1989) bahwa dengan
meningkatnya NaOH yang digunakan akan meningkatkan kemungkinan untuk kitin
memisahkan diri dari gugus amino dan protein yang ada di dalam kitin akan ikut berpisah
dari rendemen dan membuat berat rendemen menjadi lebih rendah. Dari hasil rendemen
hasil proses deproteinasi, nilai rendemen kitin II terbesar adalah sampel kelompok E3 dan
yang terkecil diperoleh kelompok E4 dengan perlakuan sampel yang sama. Beberapa
faktor yang dapat melatarbelakangi hal ini adalah proses deproteinasi yang kurang
sempurna, kesalahan pada penetralan sehingga sebagian besar rendemen terbawa air,
proses pengeringan yang tidak sesuai dengan prosedur praktikum, dan proses
demineralisasi menggunakan larutan dan suhu yang tidak sesuai.
Tingginya konsentrasi dari larutan NaOH yang digunakan dalam proses deasetil akan
berbanding lurus dengan derajat diasetilasi dari kitosan yang dihasilkan. Aktifnya gugus
fungsional amino yang merupakan substitusi dari gugus asetil kitin, dengan demikian
proses deasetilasi berjalan dengan lebih sempurna. Sedangkan penggunaan suhu tinggi
akan menyebabkan gugus asetil terlepas dari molekul kitin.Konsentrasi NaOH yang
tinggi pada proses deasetilasi akan menghasilkan kitosan dengan derajat deasetilasi
tinggi. Hal ini disebabkan karena gugus fungsional amino yang mensubstitusi gugus asetil
kitin di dalam larutan menjadi semakin aktif, sehingga proses deasetilasi akan lebih
sempurna. Sedangkan penggunaan suhu tinggi akan menyebabkan gugus asetil terlepas
dari molekul kitin.
Rantai amina bebas dari reaksi pembentukan kitosan merupakan hasil dari ikatan antara
Gugus amina yang ada pada kitin dengan gugus hydrogen yang bermuatan positif

13
(Mekawati et al., 2000). Suhu yang digunakan dalam proses diasetilasi sangat
mempengaruhi derajat diasetilasi (Puspawati et al., 2010). Pemanasan dapat
meningkatkan derajat diasetilasi dari kitosan. Suhu semakin tinggi akan berbanding lurus
dengan derajat diasetilasi. Setelah diaduk dan dipanaskan maka kitin akan segera
didinginkan. Proses pendinginan pada saat pembuatan kitin dan kitosan dijelaskan oleh
Rogers (1986) sebagai suatu proses yang berguna untuk mnejaga agar kitosan dapat
mengendap dengan maksimal dan tidak terbuang dalam proses netralisasi dengan
pencucian. Dalam pencucian harus dilakukan sampai pH dari kitosan mencapai pH yang
netral. Setelah pH netral, akan dioven dalam suhu 70°C selama 24 jam.
Hasil rendemen kitosan kelompok E1, E4 dan E5 lebih besar dibanding jumlah rendemen
kitin II. Hasil terbesar diperoleh sampel E5 dan yang terkecil pada sampel E4. Hasil
kelompok E5 tidak sesuai dengan pernyataan Hong et al. (1989) yang menyatakan bahwa
dengan meningkatnya konsentrasi dari NaOH maka degradasi yang terjadi pada susunan
struktur kimia kitin akan berlangsung dengan cepat dan rendemen yang dihasilkan akan
semakin sedikit. Pelepasan gugus asetil juga akan terjadi ketika penambahan NaOH
terlalu banyak digunakan sehingga rendemen kitosan akan semakin sedikit. Hasil
kelompok E5 tidak sesuai dengan teori dapat disebabkan oleh proses destilasi dimana
Fennema (1985), menyatakan bahwa kitin yang dihasilkan tidak maksimal ini
dikarenakan proses deproteinasi yang tidak sempurna yang diakibatkan adanya kitin yang
terikut dengan air selama proses penetralan. Hal ini didukung oleh Johnson dan Peterson
(1974), bahwa dengan meningkatnya konsentrasi asam atau basa yang digunakan akan
menyebabkan lepasnya ikatan protein dan mineral dengan kitin yang terkandung dalam
kulit udang. Warna akhir yang dihasilkan adalah putih kecoklatan.

4. KESIMPULAN
Kulit udang mengandung kitin dan kitosan
Kitin tidak dapat diperoleh secara murni di alam tanpa proses tertentu karena di alam
kitin akan bercampur dengan protein dan bahan lain dalam tubuh crustaceae
Kitin tidak larut dalam air dan pelarut organik serta asam dan basa
Untuk memperoleh kitin harus menghilangkan mineral dan protein yang terdapat
dalam tubuh udang
Demineralisasi yang dilakukan pada kulit udang menggunakan asam
Kitosan merupakan produk turunan dari kitin
Pengadukan dan pemanasan selama prosedur pembuatan kitin dan kitosan bertujuan
agar mineral dan protein cepat larut dan diperoleh zat yang benar - benar murni
Proses pembuatan kitosan dilakukan dengan melakukan penambahan basa
Kitosan dapat terbentuk karena gugus asetil dari kitin dipecah oleh larutan basa
menjadi gugus amino bebas.
Pemansan dilakukan untuk mengurangi kandungan air yang terdapat pada kitin
maupun kitosan
Penyaringan dilakukan agar zat pengotor dapat hilang dari rendemen kitin
HCl dalam proses demineralisasi dapat melarutkan garam anorganik
Semakin tinggi nilai NaOH yang ditambahkan pada rendemen kitin dapat menurunkan
angka rendemen kitosan
Semarang, 4 November 2015 Asisten dosen
Tjan, Ivana Chandra
Cindy Corazon
13.70.0028

15
5. DAFTAR PUSTAKA
Abdou, E.S., 2012. Effect of Chitosan and Chitosan-Nanoparticles as Active Coating on
Microbiological Characteristics of Fish Fingers. International Journal of Applied
Science and Technology, 2(7), pp.158–169.
Bastaman, S. (1989). Studies on Degradationb and Extraction of Chitin and Chitosan
from Prawn Shells. Thesis. The Depatment of Mechanical. Manufacturing Aeronautical
and Chemical Engineering. The Queen's University. Belfast.
Brugnerotto, J., J. Lizardi, F.M. Goycoolea, W. ArguÈelles-Monal, J. DesbrieÁres, dan
M. Rinaudo. (2001). An infrared investigation in relation with chitin and chitosan
characterization. Polymer 42 (2001) 3569±3580.
Dutta, Pradip Kumar; Joydeep Dutta; dan V. S. Tripathi. (2004). Chitin and Chitosan:
Chemistry, properties, and applications. Journal of Scientific and Industrial Research Vol.
63 January 2004. pp 20-31.
Fennema, O.R. (1985). Food Chemistry.Second Edition.Marcel Dekker, Inc., New York.
Hong H, No K, Meyers SP, Lee KS. (1989). Isolation and Characterization of Chitin from
crawfish shell waste. J Agric Food. Chem 33:375-579.
Isa, M.T., Ameh, A.O., Gabriel, J.O., Adama, K.K. (2012). Extraction and
Characterization of Chitin from Nigerian Resources. Leonardo Electronics Journal of
Practices and Technologies pp 73 – 81.
Islam, M. et al., 2011. Preparation of Chitosan from Shrimp Shell and Investigation of
Its Properties. International Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS-IJENS,
11(February), pp.77–80.
Johnson, A.H. dan M.S. Peterson.(1974). Encyclopedia of Food Technology Vol. II. The
AVI Publishing Co., Inc., Connecticut.
Knoor. (1984). Faktor- Faktor yang Berpengaruh terhadap Tahap Deproteinisasi
Menggunakan Enzim Protease dalam Pembuatan Khitin dari Cangkang Rajungan
(Portunus pelagicus). BIOSAIN, VOL. 2, NO. 1 : 68-77.

16
Martinou, A.D., D. Kafetzopoulos dan V. Bouriotis. (1995).Chitin deacetylation by
enzymatic means.
Mekawati, Fachriyah, E. dan Sumardjo, D. (2000).Aplikasi Kitosan Hasil tranformasi
Kitin Limbah Udang (Penaeus merguiensis) untuk Adsorpsi Ion Logam Timbal.Jurnal
Sains and Matematika, FMIPA Undip, Semarang, Vol. 8 (2), hal. 51-54.
Muzzarelli, R.A.A. (1985). Chitin in the Polysaccharides Vol. 3. Academic Press Inc.
Orlando. San Diego.
Patria, A. (2013). Production and Characterization of Chitosan from Shrimp Shells
Waste. International Journal of The Bioflux Society pp 339 – 344.
Peter, Martin G. (1995). Application and Environmental Aspects of Chitin and
Chitosan.Journal of Pure and Appl. Chem. Marcel Dekker, Inc., Germany. Hlm. 629-639.
Puspawati, N. M dan I. N. Simpen. (2010). Optimasi Deasetilasi Khitin dari Kulit Udang
dan Cangkang Kepiting Limbah Restoran Seafood Menjadi Khitosan Melalui Variasi
Konsentrasi NaOH. Jurnal Kimia Vol 4 hal 79 – 90.
Puvvada, Y.S., Vankayalapati, S. & Sukhavasi, S., 2012. Extraction of chitin from
chitosan from exoskeleton of shrimp for application in the pharmaceutical industry.
International Current Pharmaceutical, 1(9), pp.258–263. Available at:
http://www.icpjonline.com/documents/Vol1Issue9/06.pdf.
Rahayu & Purnavita (2007). Optimasi Pembuatan Kitosan Dari Kitin Limbah Cangkang
Rajungan (Portunus pelagicus) Untuk Absorben Ion Logam Merkuri
Radhakumary, C., Nair, P.D., Mathew, S., and Nair, C.P.R. (2005). Biopolymer
Composite of Chitosan and Methyl Methacrylate for Medical Applications. Trends
Biomater Artificial Organisms 18(2): 117 – 124.
Rinaudo, Marguerite. (2006). Chitin and chitosan: Properties and applications. Prog.
Polym. Sci. 31 (2006) 603–632.
Robert, G.A.F. (1992). Chitin Chemistry. The Macmillan Press Ltd., London.
Rogers, E.P. (1986). Fundamental of Chemistry. Books/Cole Publishing Company.
California.

17
Suhardi, U. Santoso dan Sudarmanto. (1992). Limbah Pengolahan Udang untuk Produksi
Kitin, Laporan penelitian, BAPPINDO-FTP UGM. Yogyakarta.
Tarafdar, A. & Biswas, G., 2013. Extraction of Chitosan from Prawn Shell Wastes and
Examination of its Viable Commercial Applications. International Journal on
Theoretical and Applied Research in Mechanical Engineering (IJTARME), 2(3), pp.17–
24.
Wang, Zhengke; Qiaoling Hu; Lei Cai. (2010). Chitin Fiber and Chitosan 3D Composite
Rods. International Journal of Polymer Science Volume 2010, Article ID 369759, 7
pages.
Wu, Tao; Svetlana Zivanovic, F. Ann Draughon, William S. Conway,Dan Carl E. Sams.
(2005). Physicochemical Properties and Bioactivity of Fungal Chitin and Chitosan. J.
Agric. Food Chem. 2005, 53, 3888-3894.
Zhang, Hongyin; Renping Li dan Weimin Liu. (2011). Effects of Chitin and Its Derivative
Chitosan on Postharvest Decay of Fruits: A Review. Int. J. Mol. Sci. 2011, 12, 917-934;
doi:10.3390/ijms12020917.

6. LAMPIRAN
6.1. Perhitungan
Kelompok E1
Rendemen kitin I
=berat kering
berat basah I× 100%
=5
19× 100% = 26,32%
Rendemen kitin II
=berat kering
berat basah I× 100%
=2
7× 100% = 28,57%
Rendemen kitin III
=berat kering
berat basah I× 100%
=1,76
5,5× 100% = 32%
Kelompok E2
Rendemen kitin I
=berat kering
berat basah I× 100%
=5,5
14,5× 100% = 37,93%
Rendemen kitin II
=berat kering
berat basah I× 100%
=2,5
9× 100% = 27,78%
Rendemen kitin III
=berat kering
berat basah I× 100%
=1,12
6,5× 100% = 17,23%

19
Kelompok E3
Rendemen kitin I
=berat kering
berat basah I× 100%
=4
17× 100% = 23,53 %
Rendemen kitin II
=berat kering
berat basah I× 100%
=2
6,5× 100% = 30,77%
Rendemen kitin III
=berat kering
berat basah I× 100%
=1,3
4,5× 100% = 28,89%
Kelompok E4
Rendemen kitin I
=berat kering
berat basah I× 100%
=3,5
10× 100% = 35 %
Rendemen kitin II
=berat kering
berat basah I× 100%
=2
11× 100% = 18,18%
Rendemen kitin III
=berat kering
berat basah I× 100%
=0,23
1,5× 100% = 15,33%
Kelompok E5
Rendemen kitin I

20
=berat kering
berat basah I× 100%
=3,5
12× 100% = 29,17%
Rendemen kitin II
=berat kering
berat basah I× 100%
=2
8× 100% = 25%
Rendemen kitin III
=berat kering
berat basah I× 100%
=0,85
2× 100% = 42,5%
6.2. Laporan sementara