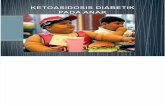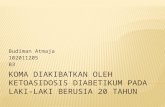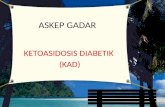KETOASIDOSIS DIABETIKUM
-
Upload
mohammad-hafidz-ramadhan -
Category
Documents
-
view
100 -
download
15
description
Transcript of KETOASIDOSIS DIABETIKUM

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Ketoasidosis Diabetikum merupakan komplikasi akut yang paling serius yang
terjadi pada anak-anak pada DM tipe 1, dan merupaka kondisi gawat darurat yang
menimbulkan morbiditas dan mortalitas, walaupun telah banyak kemajuan yang
diketahui baik dari patogenesisnya maupun dalam hal diagbosis dan tata laksananya.
Diagnosis KAD didapatkan sekitar 16-80 % pada penderita anak baru dengan DM tipe
1, tergantung lokasi geografi. Di Eropa dan Amerika Utara angkanya berkisar 15-67 %,
sedangkan di Indonesia dilaporkan antara 33-66 %
Prevalensi KAD di Amerika Serikat diperkirakan sebesar 4,6 – 8 per 1000
pebderita diabetes, dengan mortalitas kurang dari 5 % atau sekitar 2-5 %. KAD juga
merupakan penyebab kematian tersering pada anak dan remaka dengan DM tipe 1,
yang diperkirakan setengah dari penyebab kematian penderita DM di bawah usia 24
tahun. Sementara itu di Indonesia belum didapatkan angka yang pasri mengenai hal
ini. Diagnosis dan tata laksana yang tepat sangat diperlukan dalam pengelolaan kasus-
kasus KAD untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas.

BAB II
PEMBAHASAN
A. DEFINISI
Diabetes melitus adalah sindrom yang disebabkan ketidakseimbangan antara
tuntunan dan suplai insulin. Sindrom ditandai oleh hiperglikemi dan berkaitan
dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Abnormalitas
metabolik ini mengarah pada perkembangan bentuk spesifik komplikasi ginjal,
okular, neurologik dan kardiovaskuler.
Ketoasidosis diabetik (KAD) adalah komplikasi akut diabetes melitus yang
serius, suatu keadaan darurat yang harus segera diatasi. KAD memerlukan
pengelolaan yang cepat dan tepat, mengingat angka kematiannya yang tinggi.
Pencegahan merupakan upaya penting untuk menghindari terjadinya KAD.
Ketoasidosis diabetik merupakan akibat dari defisiensi berat insulin dan
disertai gangguan metabolisme protein, karbohidrat dan lemak. Keadaan ini
terkadang disebut “akselerasi puasa” dan merupakan gangguan metabolisme yang
paling serius pada diabetes ketergantungan insulin.
Ketoasidosis diabetikum adalah kasus kedaruratan endokrinologi yang
disebabkan oleh defisiensi insulin relatif atau absolut. Ketoasidosis Diabetikum
terjadi pada penderita IDDM (atau DM tipe II)
B. ETIOLOGI
Insulin Dependen Diabetes Melitus (IDDM) atau diabetes melitus tergantung
insulin disebabkan oleh destruksi sel B pulau langerhans akibat proses autoimun.
Sedangkan non insulin dependen diabetik melitus (NIDDM) atau diabetes melitus
tidak tergantung insulin disebabkan kegagalan relatif sel B dan resistensi insulin.
Resistensu insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang
pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa
oleh hati. Sel B tidak mampu mengimbangi resistensi insulin ini sepenuhnya. Artinya
terjadi defisiensi relatif insulin. Ketidakmampuan ini terlihat dari berkurangnya
sekresi insulin pada perangsangan sekresi insulin, berarti sel B pankreas mengalami
desensitisasi terhadap glukosa.

Ketoasidosis diabetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akibat hiperglikemia
dan akibat ketosis, yang sering dicetuskan oleh faktor-faktor :
1. Infeksi
2. Stress fisik dan emosional; respons hormonal terhadap stress mendorong
peningkatan proses katabolik . Menolak terapi insulin
C. KLASIFIKASI DM
Klasifikasi etiologis DM American Diabetes Assosiation (1997) sesuai anjuran
perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) adalah :
1. Diabetes tipe 1 (destruksi sel B ), umumnya menjurus ke definisi insulin absolut :
o Autoimun
o Idiopatik
2. Diabetes tipe 2 (bervariasi mulai terutama dominan risestensi insulin disertai
definisi insulin relatif sampai terutama defek sekresi insulin disertai resistensi
insulin)
3. Diabetes tipe lain
a. Defek generik fungsi sel B
o Maturity Onset Diabetes Of The Young (MODY) 1,2,3
o DNA mitokondria
b. Defek generik kerja insulin
c. Penyakit eksoskrin pankreas
o Pankreastitis
o Tumor / pankreatektomi
o Pankreatopati fibrokalkulus
d. Endokrinopati : Akromegali, Syndrom Cushing, Feokromositoma dan
hipertiroidisme.
e. Karena obat / zat kimia.
o Vacor, pentamidin, asam nikotinat
o Glukokortikoid, hormon tiroid
o Tiazid, dilatin, interferon α, dll.
f. Infeksi : Rubela kongenital, sitomegalovirus.
g. Penyebab imunologi yang jarang ; antibodi ; antiinsulin.

h. Syndrom generik lain yang berkaitan dengan DM : Sindrom Down, Sindrom
Klinefelter, Sindrom Turner, dll.
4. Diabetes Melitus Gestasional (DMG)
D. EPIDEMIOLOGI
Secara umum di dunia terdapat 15 kasus per 100.000 individu pertahun yang
menderita DM tipe 1. Tiga dari 1000 anak akan menderita IDDM pada umur 20 tahun
nantinya. Insiden DM tipe 1 pada anak-anak di dunia tentunya berbeda. Terdapat
0.61 kasus per 100.000 anak di Cina, hingga 41.4 kasus per 100.000 anak di Finlandia.
Angka ini sangat bervariasi, terutama tergantung pada lingkungan tempat tinggal.
Ada kecenderungan semakin jauh dari khatulistiwa, angka kejadiannya akan semakin
tinggi. Meski belum ditemukan angka kejadian IDDM di Indonesia, namun angkanya
cenderung lebih rendah dibanding di negara-negara eropa.
Lingkungan memang mempengaruhi terjadinya IDDM, namun berbagai ras
dalam satu lingkungan belum tentu memiliki perbedaan. Orang-orang kulit putih
cenderung memiliki insiden paling tinggi, sedangkan orang-orang cina paling rendah.
Orang-orang yang berasal dari daerah dengan insiden rendah cenderung akan lebih
berisiko terkena IDDM jika bermigrasi ke daerah penduduk dengan insiden yang
lebih tinggi. Penderita laki-laki lebih banyak pada daerah dengan insiden yang tinggi,
sedangkan perempuan akan lebih berisiko pada daerah dengan insiden yang rendah.
Secara umum insiden IDDM akan meningkat sejak bayi hingga mendekati pu-
bertas, namun semakin kecil setelah pubertas. Terdapat dua puncak masa kejadian
IDDM yang paling tinggi, yakni usia 4-6 tahun serta usia 10-14 tahun. Kadang-kadang
IDDM juga dapat terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan, meskipun
kejadiannya sangat langka. Diagnosis yang telat tentunya akan menimbulkan
kematian dini. Gejala bayi dengan IDDM ialah napkin rash, malaise yang tidak jelas
penyebabnya, penurunan berat badan, senantiasa haus, muntah, dan dehidrasi.
Insulin merupakan komponen vital dalam metabolisme karbohidrat, lemak,
dan protein. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan cara memfasilitasi ma-
suknya glukosa ke dalam sel, terutama otot serta mengkonversi glukosa menjadi
glikogen (glikogenesis) sebagai cadangan energi. Insulin juga menghambat pelepasan
glukosa dari glikogen hepar (glikogenolisis) dan memperlambat pemecahan lemak
menjadi trigliserida, asam lemak bebas, dan keton. Selain itu, insulin juga

menghambat pemecahan protein dan lemak untuk memproduksi glukosa
(glukoneogenesis) di hepar dan ginjal. Bisa dibayangkan betapa vitalnya peran insulin
dalam metabolisme.
Defisiensi insulin yang dibiarkan akan menyebabkan tertumpuknya glukosa di
darah dan terjadinya glukoneogenesis terus-menerus sehingga menyebabkan kadar
gula darah sewaktu (GDS) meningkat drastis. Batas nilai GDS yang sudah dikate-
gorikan sebagai diabetes mellitus ialah 200 mg/dl atau 11 mmol/l. Kurang dari itu
dikategorikan normal, sedangkan angka yang lebih dari itu dites dulu dengan Tes
Toleransi Glukosa Oral (TTGO) untuk menentukan benar-benar IDDM atau kategori
yang tidak toleran terhadap glukosa oral.
E. PROGNOSIS PENYAKIT
Pada DM yang tidak terkendali dengan kadar gula darah yang terlalu tinggi
dan kadar hormon insulin yang rendah, tubuh tidak dapat menggunakan glukosa
sebagai sumber energi. Sebagai gantinya tubuh akan memecah lemak untuk sumber
energi.
Pemecahan lemak tersebut akan menghasilkan benda-benda keton dalam
darah (ketosis). Ketosis menyebabkan derajat keasaman (pH) darah menurun atau
disebut sebagai asidosis. Keduanya disebut sebagai ketoasidosis.
Pasien dengan KAD biasanya memiliki riwayat masukan kalori (makanan) yang
berlebihan atau penghentian obat diabetes/insulin.
F. TANDA DAN GEJALA
Gejala dan tanda-tanda yang dapat ditemukan pada pasien KAD adalah:
1. Kadar gula darah tinggi (> 240 mg/dl)
2. Terdapat keton di urin
3. Banyak buang air kecil sehingga dapat dehidrasi
4. Sesak nafas (nafas cepat dan dalam)
5. Nafas berbau aseton
6. Badan lemas
7. Kesadaran menurun sampai koma
8. KU lemah, bisa penurunan kesadaran
9. Polidipsi, poliuria
10. Anoreksia, mual, muntah, nyeri perut

11. Bisa terjadi ileus sekunder akibat hilangnya K+ karena diuresis osmotik
12. Kulit kering
13. Keringat <<<
14. Kussmaul ( cepat, dalam ) karena asidosis metabolik
Faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya KAD adalah:
1. Infeksi, stres akut atau trauma
2. Penghentian pemakaian insulin atau obat diabetes
3. Dosis insulin yang kurang
G. PEMERIKSAAN PENUNJANG
Pemeriksaan Laboratorium
Glukosa.
Kadar glukosa dapat bervariasi dari 300 hingga 800 mg/dl. Sebagian pasien mungkin
memperlihatkan kadar gula darah yang lebih rendah dan sebagian lainnya mungkin
memiliki kadar sampai setinggi 1000 mg/dl atau lebih yang biasanya bergantung
pada derajat dehidrasi.
Harus disadari bahwa ketoasidosis diabetik tidak selalu berhubungan dengan
kadar glukosa darah. Sebagian pasien dapat mengalami asidosis berat disertai kadar
glukosa yang berkisar dari 100 – 200 mg/dl, sementara sebagian lainnya mungkin
tidak memperlihatkan ketoasidosis diabetikum sekalipun kadar glukosa darahnya
mencapai 400-500 mg/dl.
Natrium.
Efek hiperglikemia ekstravaskuler bergerak air ke ruang intravaskuler. Untuk setiap
100 mg / dL glukosa lebih dari 100 mg / dL, tingkat natrium serum diturunkan oleh
sekitar 1,6 mEq / L. Bila kadar glukosa turun, tingkat natrium serum meningkat
dengan jumlah yang sesuai.
Kalium.
Ini perlu diperiksa sering, sebagai nilai-nilai drop sangat cepat dengan perawatan.
EKG dapat digunakan untuk menilai efek jantung ekstrem di tingkat potasium.
Bikarbonat.

Kadar bikarbonat serum adalah rendah, yaitu 0- 15 mEq/L dan pH yang rendah (6,8-
7,3). Tingkat pCO2 yang rendah ( 10- 30 mmHg) mencerminkan kompensasi
respiratorik (pernapasan kussmaul) terhadap asidosisi metabolik. Akumulasi badan
keton (yang mencetuskan asidosis) dicerminkan oleh hasil pengukuran keton dalam
darah dan urin. Gunakan tingkat ini dalam hubungannya dengan kesenjangan anion
untuk menilai derajat asidosis.
Sel darah lengkap (CBC).
Tinggi sel darah putih (WBC) menghitung (> 15 X 109 / L) atau ditandai pergeseran
kiri mungkin menyarankan mendasari infeksi.
Gas darah arteri (ABG).
pH sering <7.3. Vena pH dapat digunakan untuk mengulang pH measurements.
Brandenburg dan Dire menemukan bahwa pH pada tingkat gas darah vena pada
pasien dengan KAD adalah lebih rendah dari pH 0,03 pada ABG. Karena perbedaan
ini relatif dapat diandalkan dan bukan dari signifikansi klinis, hampir tidak ada alasan
untuk melakukan lebih menyakitkan ABG. Akhir CO2 pasang surut telah dilaporkan
sebagai cara untuk menilai asidosis juga.
Keton.
Diagnosis memadai ketonuria memerlukan fungsi ginjal. Selain itu, ketonuria dapat
berlangsung lebih lama dari asidosis jaringan yang mendasarinya.
β-hidroksibutirat.
Serum atau hidroksibutirat β kapiler dapat digunakan untuk mengikuti respons
terhadap pengobatan. Tingkat yang lebih besar dari 0,5 mmol / L dianggap normal,
dan tingkat dari 3 mmol / L berkorelasi dengan kebutuhan untuk ketoasidosis
diabetik (KAD).
Urinalisis (UA)
Cari glikosuria dan urin ketosis. Hal ini digunakan untuk mendeteksi infeksi saluran
kencing yang mendasari.
Osmolalitas

Diukur sebagai 2 (Na +) (mEq / L) + glukosa (mg / dL) / 18 + BUN (mg / dL) / 2.8.
Pasien dengan diabetes ketoasidosis yang berada dalam keadaan koma biasanya
memiliki osmolalitis > 330 mOsm / kg H2O. Jika osmolalitas kurang dari > 330
mOsm / kg H2O ini, maka pasien jatuh pada kondisi koma.
Fosfor
Jika pasien berisiko hipofosfatemia (misalnya, status gizi buruk, alkoholisme kronis),
maka tingkat fosfor serum harus ditentukan.
Tingkat BUN meningkat.
Anion gap yang lebih tinggi dari biasanya.
Kadar kreatinin
Kenaikan kadar kreatinin, urea nitrogen darah (BUN) dan Hb juga dapat terjadi pada
dehirasi. Setelah terapi rehidrasi dilakukan, kenaikan kadar kreatinin dan BUN serum
yang terus berlanjut akan dijumpai pada pasien yang mengalami insufisiensi renal.
Tabel 1. Sifat-sifat penting dari tiga bentuk dekompensasi (peruraian) metabolik pada diabetes.
Diabetic
ketoacidosis (KAD)
Hyperosmolar
non ketoticcoma
(HONK)
Asidosis laktat
Glukosa plasma Tinggi Sangat tinggi Bervariasi
Ketone Ada Tidak ada Bervariasi
Asidosis Sedang/hebat Tidak ada hebat
Dehidrasi Dominan dominan bervariasi
Hiperventilasi Ada Tidak ada ada
Pemeriksaan Diagnostik
Pemeriksaan diagnostik untuk ketoasidosis diabetik dapat dilakukan dengan cara:

Tes toleransi Glukosa (TTG) memanjang (lebih besar dari 200mg/dl).
Biasanya tes ini dianjurkan untuk pasien yang menunjukkan kadar glukosa meningkat
dibawah kondisi stress.
Gula darah puasa normal atau diatas normal.
Essei hemoglobin glikolisat diatas rentang normal.
Urinalisis positif terhadap glukosa dan keton.
Kolesterol dan kadar trigliserida serum dapat meningkat menandakan
ketidakadekuatan kontrol glikemik dan peningkatan propensitas pada terjadinya
aterosklerosis.
DIAGNOSIS
Didasarkan atas adanya "trias biokimia" yakni : hiperglikemia, ketonemia, dan asidosis.
Kriteria diagnosisnya adalah sebagai berikut :
Hiperglikemia, bila kadar glukosa darah > 11 mmol/L (> 200 mg/dL).
Asidosis, bila pH darah < 7,3.
kadar bikarbonat < 15 mmol/L).
Derajat berat-ringannya asidosis diklasifikasikan sebagai berikut :
Ringan: bila pH darah 7,25-7,3, bikarbonat 10-15 mmol/L.
Sedang: bila pH darah 7,1-7,24, bikarbonat 5-10 mmol/L.
Berat: bila pH darah < 7,1, bikarbonat < 5 mmol/L.
DIAGNOSIS BANDING
KAD juga harus dibedakan dengan penyebab asidosis, sesak, dan koma yang lain
termasuk : hipoglikemia, uremia, gastroenteritis dengan asidosis metabolik, asidosis
laktat, intoksikasi salisilat, bronkopneumonia, ensefalitis, dan lesi intrakranial.
H. KOMPLIKASI
Komplikasi dari ketoasidoisis diabetikum dapat berupa:
1. Ginjal diabetik ( Nefropati Diabetik )
Nefropati diabetik atau ginjal diabetik dapat dideteksi cukup dini. Bila penderita
mencapai stadium nefropati diabetik, didalam air kencingnya terdapat protein.
Dengan menurunnya fungsi ginjal akan disertai naiknya tekanan darah. Pada

kurun waktu yang lama penderita nefropati diabetik akan berakhir dengan gagal
ginjal dan harus melakukan cuci darah. Selain itu nefropati diabetik bisa
menimbulkan gagal jantung kongesif.
2. Kebutaan ( Retinopati Diabetik )
Kadar glukosa darah yang tinggi bisa menyebabkan sembab pada lensa mata.
Penglihatan menjadi kabur dan dapat berakhir dengan kebutaan.
3. Syaraf ( Neuropati Diabetik )
Neuropati diabetik adalah akibat kerusakan pada saraf. Penderita bisa stres,
perasaan berkurang sehingga apa yang dipegang tidak dapat dirasakan (mati
rasa).
4. Kelainan Jantung.
Terganggunya kadar lemak darah adalah satu faktor timbulnya aterosklerosis
pada pembuluh darah jantung. Bila diabetesi mempunyai komplikasi jantung
koroner dan mendapat serangan kematian otot jantung akut, maka serangan
tersebut tidak disertai rasa nyeri. Ini merupakan penyebab kematian mendadak.
5. Hipoglikemia.
Hipoglikemia terjadi bila kadar gula darah sangat rendah. Bila penurunan kadar
glukosa darah terjadi sangat cepat, harus diatasi dengan segera. Keterlambatan
dapat menyebabkan kematian. Gejala yang timbul mulai dari rasa gelisah sampai
berupa koma dan kejang-kejang.
6. Hipertensi.
Karena harus membuang kelebihan glokosa darah melalui air seni, ginjal
penderita diabetes harus bekerja ekstra berat. Selain itu tingkat kekentalan
darah pada diabetisi juga lebih tinggi. Ditambah dengan kerusakan-kerusakan
pembuluh kapiler serta penyempitan yang terjadi, secara otomatis syaraf akan
mengirimkan signal ke otak untuk menambah takanan darah.
I. PENATALAKSANAAN

Tujuan penatalaksanaan : 1) Memperbaiki sirkulasi dan perfusi jaringan
(resusitasi dan rehidrasi), 2) Menghentikan ketogenesis (insulin), 3) Koreksi gangguan
elektrolit, 4) Mencegah komplikasi, 5) Mengenali dan menghilangkan faktor
pencetus.
Berikut adalah beberapa tahapan tatalaksana KAD :
Penilaian Klinik Awal
1. Pemeriksaan fisik (termasuk berat badan), tekanan darah, tanda asidosis
(hiperventilasi), derajat kesadaran (GCS), dan derajat dehidrasi.
2. Konfirmasi biokimia: darah lengkap (sering dijumpai gambaran lekositosis), kadar
glukosa darah, glukosuria, ketonuria, dan analisa gas darah.
Resusitasi
a. Pertahankan jalan napas.
b. Pada syok berat berikan oksigen 100% dengan masker.
c. Jika syok berikan larutan isotonik (normal salin 0,9%) 20 cc/KgBB bolus.
d. Bila terdapat penurunan kesadaran perlu pemasangan naso-gatrik tube untuk
menghindari aspirasi lambung.
Observasi Klinik
Pemeriksaan dan pencatatan harus dilakukan atas :
a. Frekwensi nadi, frekwensi napas, dan tekanan darah setiap jam.

b. Suhu badan dilakukan setiap 2-4 jam.
c. Pengukuran balans cairan setiap jam.
d. Kadar glukosa darah kapiler setiap jam.
e. Tanda klinis dan neurologis atas edema serebri :
f. EKG : untuk menilai gelombang T, menentukan tanda hipo/hiperkalemia.
g. Keton urine sampai negatif, atau keton darah (bila terdapat fasilitas).
Rehidrasi
Penurunan osmolalitas cairan intravaskular yang terlalu cepat dapat meningkatkan
resiko terjadinya edema serebri.
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
a. Tentukan derajat dehidrasi penderita.
b. Gunakan cairan normal salin 0,9%.

c. Total rehidrasi dilakukan 48 jam, bila terdapat hipernatremia (corrected Na)
rehidrasi dilakukan lebih perlahan bisa sampai 72 jam.
d. 50-60% cairan dapat diberikan dalam 12 jam pertama.
e. Sisa kebutuhan cairan diberikan dalam 36 jam berikutnya.
Penggantian Natrium
a. Koreksi Natrium dilakukan tergantung pengukuran serum elektrolit.
b. Monitoring serum elektrolit dapat dilakukan setiap 4-6 jam.
c. Kadar Na yang terukur adalah lebih rendah, akibat efek dilusi hiperglikemia yang
terjadi.
d. Artinya : sesungguhnya terdapat peningkatan kadar Na sebesar 1,6 mmol/L setiap
peningkatan kadar glukosa sebesar 100 mg/dL di atas 100 mg/dL.
e. Bila corrected Na > 150 mmol/L, rehidrasi dilakukan dalam > 48 jam.
f. Bila corrected Na < 125 mmol/L atau cenderung menurun lakukan koreksi dengan
NaCl dan evaluasi kecepatan hidrasi.

g. Kondisi hiponatremia mengindikasikan overhidrasi dan meningkatkan risiko edema
serebri.
Penggantian Kalium
Pada saat asidosis terjadi kehilangan Kalium dari dalam tubuh walaupun
konsentrasi di dalam serum masih normal atau meningkat akibat berpindahnya Kalium
intraseluler ke ekstraseluler. Konsentrasi Kalium serum akan segera turun dengan
pemberian insulin dan asidosis teratasi.
a. Pemberian Kalium dapat dimulai bila telah dilakukan pemberian cairan resusitasi,
dan pemberian insulin. Dosis yang diberikan adalah 5 mmol/kg BB/hari atau 40
mmol/L cairan.
b. Pada keadaan gagal ginjal atau anuria, pemberian Kalium harus ditunda.
Penggantian Bikarbonat
a. Bikarbonat sebaiknya tidak diberikan pada awal resusitasi.
b. Terapi bikarbonat berpotensi menimbulkan:
a. Terjadinya asidosis cerebral.
b. Hipokalemia.
c. Excessive osmolar load.
d. Hipoksia jaringan.
c. Terapi bikarbonat diindikasikan hanya pada asidossis berat (pH < 7 dengan
bikarbonat serum < 5 mmol/L) sesudah dilakukan rehidrasi awal, dan pada syok yang
persistent.
d. Jika diperlukan dapat diberikan 1-2 mmol/kg BB dengan pengenceran dalam waktu 1
jam, atau dengan rumus: 1/3 x (defisit basa x KgBB). Cukup diberikan ¼ dari
kebutuhan.
Pemberian Insulin

a. Insulin hanya dapat diberikan setelah syok teratasi dengan cairan resusitasi.
b. Insulin yang digunakan adalah jenis Short acting/Rapid Insulin (RI).
c. Dalam 60-90 menit awal hidrasi, dapat terjadi penurunan kadar gula darah walaupun
insulin belum diberikan.
d. Dosis yang digunakan adalah 0,1 unit/kg BB/jam atau 0,05 unit/kg BB/jam pada anak
< 2 tahun.
e. Pemberian insulin sebaiknya dalam syringe pump dengan pengenceran 0,1 unit/ml
atau bila tidak ada syringe pump dapat dilakukan dengan microburet (50 unit dalam
500 mL NS), terpisah dari cairan rumatan/hidrasi.
f. Penurunan kadar glukosa darah (KGD) yang diharapkan adalah 70-100 mg/dL/jam.
g. Bila KGD mencapai 200-300 mg/dL, ganti cairan rumatan dengan D5 ½ Salin.
h. Kadar glukosa darah yang diharapkan adalah 150-250 mg/dL (target).
i. Bila KGD < 150 mg/dL atau penurunannya terlalu cepat, ganti cairan dengan D10 ½
Salin.
j. Bila KGD tetap dibawah target turunkan kecepatan insulin.
k. Jangan menghentikan insulin atau mengurangi sampai < 0,05 unit/kg BB/jam.
l. Pemberian insulin kontinyu dan pemberian glukosa tetap diperlukan untuk
menghentikan ketosis dan merangsang anabolisme.
m. Pada saat tidak terjadi perbaikan klinis/laboratoris, lakukan penilaian ulang kondisi
penderita, pemberian insulin, pertimbangkan penyebab kegagalan respon
pemberian insulin.
n. Pada kasus tidak didapatkan jalur IV, berikan insulin secara intramuskuler atau
subkutan. Perfusi jaringan yang jelek akan menghambat absorpsi insulin.
Tatalaksana edema serebri

Terapi harus segera diberikan sesegera mungkin saat diagnosis edema serebri dibuat,
meliputi:
a. Kurangi kecepatan infus.
b. Mannitol 0,25-1 g/kgBB diberikan intravena dalam 20 menit (keterlambatan
pemberian akan kurang efektif).
c. Ulangi 2 jam kemudian dengan dosis yang sama bila tidak ada respon.
d. Bila perlu dilakukan intubasi dan pemasangan ventilator.
e. Pemeriksaan MRI atau CT-scan segera dilakukan bila kondisi stabil.
Fase Pemulihan
Setelah KAD teratasi, dalam fase pemulihan penderita dipersiapkan untuk: 1) Memulai diet
per-oral. 2) Peralihan insulin drip menjadi subkutan.
a. Memulai diet per-oral.
1. Diet per-oral dapat diberikan bila anak stabil secara metabolik (KGD < 250 mg/dL, pH >
7,3, bikarbonat > 15 mmol/L), sadar dan tidak mual/muntah.
2. Saat memulai snack, kecepatan insulin basal dinaikkan menjadi 2x sampai 30 menit
sesudah snack berakhir.
3. Bila anak dapat menghabiskan snacknya, bisa dimulai makanan utama.
4. Saat memulai makanan, kecepatan insulin basal dinaikkan menjadi 2x sampai 60 menit
sesudah makan utama berakhir.
b. Menghentikan insulin intravena dan memulai subkutan.
1. Insulin iv bisa dihentikan bila keadaan umum anak baik, metabolisme stabil, dan anak
dapat menghabiskan makanan utama.

2. Insulin subkutan harus diberikan 30 menit sebelum makan utama dan insulin iv
diteruskan sampai total 90 menit sesudah insulin subkutan diberikan.
3. Diberikan short acting insulin setiap 6 jam, dengan dosis individual tergantung kadar
gula darah. Total dosis yang dibutuhkan kurang lebih 1 unit/kg BB/hari atau disesuaikan
dosis basal sebelumnya.
c. Dapat diawali dengan regimen 2/7 sebelum makan pagi, 2/7 sebelum makan siang, 2/7
sebelum makan malam, dan 1/7 sebelum snack menjelang tidur.
Algoritma Tatalaksana Ketoasidosis Diabetic
Anamnesis Poliuria Polidipsia Penurunan BB Nyeri perut Lemas/lemah Muntah-muntah pusing
Pemeriksaan fisik Tentukan derajat dehidrasiNafas cepat& dalam(kusmaul)Nafas bau ketonLethargy&muntah
Laboratotium Ketonuria Hipoglikemia>300 mg/dl Asidosis metabolic Pemeriksaan lain:Elektrolit darah,BUN
Diabetes ketoasidosis
Syok+dehidrasi berat Penurunan kesadaran Dehidrasi >5%
Asidosis(hiperventilasi)Syokmuntah
-krisis sedang-bisa makan/minum
Resusitasi:-Airway/nasogastric tube-Berikan oksigen masker 100%-Terapi syok: NS 20ml/kg(bisa diulang)
IVFD:-Tentukan kebutuhan cairan+deficit-Koreksi deficit dalam 48 jam-Menggunakan normal salin-EKG-Tambahan KCL 40 mmol/L cairan
-Berikan insulin sc-Rehidrasi oral
Tidak ada perbaikan
Insulin IV:o,1 u/kg/jam(0,05 u/kg/jam bila<2th)
Observasi ketat:-kadar gula darah setiap 1 jam-balans cairan setiap 1jam-status neurologis-elektrolit darah-EKG:perubahan gel T
Asidosis tidak membaik
Kesadaran menurun,sakit kepala,penurunan HR,irritable/gelisah,inkontinensia,specific neurological sign

Evaluasi kembali:-balans cairan?-insulin:dosis,macet?-infeksi,sepsis
KGD 200-300mg/dl. AtauPenurunan KGD>100mg/dl/jam
-Pastikan bukan hipoglikemia-Edema cerebri
IVFD:-ganti cairan dengan D5 0,45 salin-turunkan dosisulin(jangan<0,05 u/kg/jam-periksa elektrolit darah koreksi bila perlu
Krisis membaik,bisa makan/minum per-oral
Perubahan insulin:berikan insulin scstop insulin iv 60 menit kemudian
-konsul neurologi-pertimbangan:Manitol 1g/kg BB-Restraksi cairan 50%