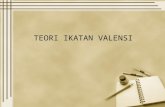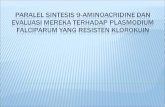kapsel anor
-
Upload
yunita-pare -
Category
Documents
-
view
240 -
download
4
description
Transcript of kapsel anor

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tembaga (Cu)
2.1.1 Karakteristik dan Sifat Tembaga
2.1.2 Toksisitas Logam Tembaga
2.1.3 Tembaga dalam tubuh
Tembaga merupakan unsur esensial yang bila kekurangan dapat
menghambat pertumbuhan dan pembentukan hemoglobin. Tembaga sangat
dibutuhkan dalam proses metabolisme, pembentukan hemoglobin, dan proses
fisiologis dalam tubuh hewan (Richards 1989; Ahmed et al. 2002).
Tembaga ditemukan dalam protein plasma, seperti seruloplasmin yang
berperan dalam pembebasan besi dari sel ke plasma. Tembaga juga merupakan
komponen dari protein darah, antara lain eritrokuprin, yang ditemukan dalam
eritrosit (sel darah merah) yang berperan dalam metabolisme oksigen (Darmono
1995; 2001).
Selain ikut berperan dalam sintesis hemoglobin, tembaga merupakan
bagian dari enzimenzim dalam sel jaringan. Tembaga berperan dalam aktivitas
enzim pernapasan, sebagai kofaktor bagi enzim tirosinase dan sitokrom oksidase.
Tirosinase mengkristalisasi reaksi oksidasi tirosin menjadi pigmen melanin
(pigmen gelap pada kulit dan rambut). Sitokrom oksidase, suatu enzim dari gugus
heme dan atom-atom tembaga, dapat mereduksi oksigen (Davis dan Mertz 1987;
Mills 1987; Sharma et al.2003).
6

2.2 Vitamin C (Asam aksorbat)
2.2.1 Karakteristik dan Sifat Vitamin C
Vitamin C merupakan senyawa yang sangat mudah larut dalam air,
mempunyai sifat asam dan sifat pereduksi yang sangat kuat. Sifat-sifat tersebut
terutama disebabkan adanya struktur enediol yang berkonjugasi dengan gugus
karbonil dalam cincin lakton. Bentuk vitamin C yang ada di dalam terutama
adalah L-asam askorbat. D-asam askorbat jarang terdapat di alam dan hanya
memiliki 10 persen aktivitas vitamin C. Biasanya D-asam askorbat ditambah
kedalam bahan pangan sebagai antioksidan, bukan sebagai sumber vitamin C
(Andarwulan dan Koswara, 1992).
Vitamin C yang mempunyai rumus empiris C6H8O6 dalam bentuk murni
merupakan kristal putih, tidak berwarna, tidak berbau dan mencair pada suhu 190-
192 ˚C. Senyawa ini bersifat reduktor kuat dan mempunyai rasa asam
(Andarwulan dan Koswara, 1992).
Sifat yang paling utama dari vitamin C adalah kemampuan mereduksinya
yang kuat dan mudah teroksidasi yang dikatalisis oleh beberapa logam, terutama
Cu dan Ag. Potensial oksidasi reduksi vitamin C pada pH 4 dan suhu 35 ˚C.
Senyawa ini juga menyerap spektrum ultraviolet pada panjang gelombang 244-
299 nm dengan panjang gelombang maksimum pada 265 nm (Andarwulan dan
Koswara, 1992).
Stabilitas asam askorbat bersifat sangat sensitif terhadap pengaruh-
pengaruh luar yang menyebabkan kerusakan seperti suhu, konsentrasi gula dan
garam, pH, oksigen, Enzim, katalisator logam, konsentrasi awal baik dalam
7

larutan, maupun sistem model, dan rasio antara asam askorbat, dan dehidro asam
askorbat (Andarwulan dan Koswara, 1992).
2.2.2 Faktor yang mempengaruhi kerusakan vitamin C
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan vitamin C selama
pemprosesan termasuk perlakuan panas dan pelindian. Tingkat kekerasan kondisi
pemprosesan sering dapat dinilai dari persentase asam askorbat yang hilang.
Tingkat kehilangan bergantung pada bayaknya air yang telah dipakai (Deman,
1997).
2.2.2 Pengaruh Vitamin C dalam Tubuh
Vitamin C dalam tubuh aktif dalam 2 bentuk yaitu asam askorbat dan
dehidroaskorbic acid (DHA). Vitamin C dalam bentuk asam askorbat berperan
sebagai scavenger radikal bebas, selain itu juga mampu menghambat
pembentukan radikal bebas,(Carr et al., 2000)sedangkan dalam bentuk DHA akan
menghambat secara langsung aktifasi nuclear factor-kappa beta (NF-kB)faktor
Transkripsi inflamasi.( Carcamo et al., 2004) Beberapa penelitian melaporkan
bahwa vitamin C lebih efektif dibandingkan dengan α-tokoferol dalam
mengurangi proses patofisiologi akibat stres oksidatif seperti aterosklerosis,
karena vitamin C mempunyai kemampuan menangkap oksigen dan nitrogen
reaktif secara efektif, dan vitamin ini mempunyai kemampuan untuk regenerasi α-
tokofer
ol sehingga avaibilitas vitamin α-tokoferol ini dalam tubuh tetap terjaga.(Carr et
al., 2000)Setelah bereaksi dengan radikal bebas, vitamin C pun akan menjadi
8

produk radikal, namun karena degradasinya sangat singkat (10-5 detik) sehingga
ia tidak reaktif, salah satu alasan vitamin C disukai sebagai antioksidan.
2.2 Tinjauan Umum Tentang Mikobakteria
Mikobakteria berbentuk basil, merupakan bakteri aerobik yang tidak
membentuk spora. Meskipun tidak terwarnai dengan baik, segera setelah
diwarnai bakteri ini mempertahankan dekolorisasi oleh asam atau alkohol, oleh
karena itu dinamakan basil “cepat asam”. Mycobacterium Tuberculosis
menyebabkan tuberkulosis dan merupakan patogen manusia yang sangat penting.
Mycobacterium leprae menyebabkan leprosy. Mycobacterium avium-intraseluler
(M. avium komplek atau MAC) dan mikobakterium atipikal lain sering
menginfeksi pasien AIDS, bersifat pathogen opportunistic pada orang
immunokompromis, dan kadang-kadang menyebabkan penyakit pada pasien
dengan sistem imun normal. Ada lebih dari 50 spesies mikobakterium, termasuk
beberapa saprofit (Brooks dkk, 2005).
2.2.1 Uraian Mycobacterium Tuberculosis
Mycobacterium Tuberculosis bersifat non motil dan obligat aerob, dan
karena itu dapat hidup dalam rongga paru-paru yang kaya akan oksigen, dan juga
berupa parasit intraseluler di dalam makrofag karena memiliki dinding sel yang
impermeabel terhadap senyawa litik yang dilepaskan oleh makrofag. Basil
9

tuberkel adalah bakteri batang lurus dengan ukuran sekitar 0,4-3 µm.
Mikobakteria tidak dapat dikelompokkan sebagai gram positif. Basil tuberkel
ditandai dengan “pencepat asam” misalnya 95% etil alkohol yang berisi 3% asam
hidroklorat (asam beralkohol) mendekolorisasi semua bakteri dengan cepat
kecuali mikobakteria. Mikobakteria merupakan aerobik obligat yang memperoleh
energi dari beberapa senyawa karbon sederhana. Penambahan CO2 dapat
meningkatkan pertumbuhannya. Mikobakteria cenderung lebih resisten terhadap
agen kimia dari pada bakteri lain karena sifat hidrofobik permukaan sel dan
pertumbuhannya (Brooks dkk, 2005).
2.2.2 Morfologi Mycobacterium Tuberculosis
Klasifikasi ilmiah (Microbewiki, 2011)
Kingdom : Bacteria
Filum : Actinobacteria
Ordo : Actinomycetales
Upaordo : Corynebacterineae
Famili : Mycobacteriaceae Gambar 3.
M. tuberculosis (google.com)
Genus : Mycobacterium
Spesies : Mycobacterium tuberculosis
2.2.3 Mycobacterium tuberculosis Strain H37Rv
Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv adalah jenis M.tuberculosis
yang bersifat patogen, aerobik, berbentuk batang, non motil, dan yang paling
penting jenis bakteri strain H37Rv ini yang paling sering menyebabkan penyakit
10

TBC. Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv memiliki urutan pasangan
genom yang terdiri atas 4.411.529 pasangan basa, dan memiliki jumlah gen
sekitar 4000 gen, dan memiliki kandungan guanin dan sitosin yang relatif sangat
tinggi yang tercermin pada asam amino bebas dari proteinnya. Jenis strain H37Rv
ini merupakan jenis strain yang terbaik karena memiliki urutan genom yang
terlengkap dan jenis strain H37Rv ini lebih mudah ditentukan dan lebih mudah
dianalisis dalam laboratorium sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan
pemahaman kita tentang bakteri patogen dan membantu dalam memperoleh terapi
obat baru untuk mengobati M.tuberculosis (Bifani dkk., 2005).
2.3 Tinjauan Umum Tentang Antibiotik Uji
Pengembangan obat-obat kemoterapi baru merupakan suatu kebutuhan
dunia untuk meningkatkan kontrol tuberkulosis, terutama di negara berkembang.
Obat-obat yang digunakan dalam pengobatan tuberculosis ada dua lini. Lini
pertama yaitu Isoniazid, rifampisin, pirazinamid, etambutol dan streptomisin. Lini
kedua yaitu amikasin dan kanamisin, viomycin dan kapreomisin,
fluoroquinolones, tioamida, sikloserin dan asam p-aminosalisilat (Kamal dkk,
2008).
Resistensi terhadap obat antituberkulosis dapat terjadi apabila terdapat
mutasi pada gen yang mengkode target obat atau gen yang mengkode enzim
bakteri yang diperlukan untuk mengkonversi proobat menjadi bentuk aktifnya.
Sebagai contoh, resistensi terhadap rifampisin dapat disebabkan oleh mutasi pada
gen rpoB yang mengkode sub unit beta dari RNA polymerase yang merupakan
target obat. Resistensi terhadap isoniazid dapat disebabkan oleh mutasi pada gen
katalase peroksida (katG) yang mengkode enzim katalase peroksidase yang
11

dibutuhkan untuk mengkonversi isoniazid menjadi bentuk aktifnya (Nuermberger
dkk, 2010).
Resistensi obat utama pada M. Tuberculosis terjadi pada sekitar 10 % dan
sebagian besar adalah terhadap isoniasid (INH) dan streptomisin. Resistensi
terhadap rifampin atau ethambutol tidak banyak ditemui. Isoniasid dan rifampin
adalah obat utama adalah obat utama yang digunakan prosedur pengobatan
standar, obat pilihan pertama yang lain adalah pirasinamid, etambutol dan
streptomisin. Kekurangnyamanan pengobatan merupakan faktor utama dalam
perkembangan resistensi obat selama terapi. Pengendalian terhadap tuberculosis
yang resisten merupakan masalah dunia yang penting (Brooks, 2001).
Umumnya, resistensi pada M. tuberculosis melibatkan perubahan genetik
baik mutasi titik maupun delesi genetik pada gen di kromosom. Hanya satu mutasi
titik yang mengakibatkan substitusi asam amino dapat bertanggung jawab
terhadap timbulnya fenotip resistensi. Mutasi titik dan delesi genetik pada
beberapa gen yang terlibat dalam fenotip resistensi multi-drug terhadap isoniazid,
rifampisin, streptomisin, pirazinamid, kuinolon dan etambutol (Retnoningrum,
2004). Resistensi obat pada M. tuberculosis adalah terutama disebabkan
akumulasi mutasi pada gen obat target mutasi ini menyebabkan baik untuk target
diubah (Rattan dkk, 1998).
Ada 2 macam resistensi obat pada M. Tuberculosis yaitu MDR (Multi
Drug Resistance) dan XDR (extreme drug resistance, atau extensive drug
resistance). Bakteri M. Tuberculosis yang resisten terhadap obat lini pertama
disebut MDR sedangkan XDR adalah kuman MDR yang juga kebal terhadap 3
atau lebih obat lini ke dua. XDR adalah masalah besar dalam terapi tuberkulosis
12

karena bukan saja mematikan dengan cepat tetapi juga obatnya belum tersedia
(Aditama, 2006).
2.3.1 Isoniazid (INH)
Isoniazid (isonicotinic acid hydrazide; C8H7N3O, BM: 137.1) merupakan
bubuk kristal putih yang larut dalam air. Larutannya dapat disterilkan dengan
autoklaf (Palomino dkk, 2007). Isoniazid (INH), hidrazid dari asam nikotinat,
adalah suatu analog sintetik piridoksin (gambar 4). Isoniazid adalah obat
antituberkulosis yang paling poten, tetapi tidak pernah diberikan sebagai obat
tunggal dalam pengobatan tuberculosis aktif. Penemuannya membuat revolusi
dalam pengobatan tuberculosis (Mycek dkk, 2001).
Isoniazid adalah prodrug yang diaktifkan oleh enzim mikobakterium
katalase peroksidase (Kat-G). INH sangat aktif terhadap M. tuberculosis
kompleks (M. tuberculosis, M. bovis, M. atricanum, M. microti) dengan MICs
sangat rendah (0,02-0,06 µg/mL) (Tripathi dkk, 2004). INH bekerja pada enzim
yang berperan dalam penyusunan asam mikolat ke dalam lapisan luar mikobakteri
suatu struktur yang unik untuk organism ini. Asam mikolat ini penting untuk sifat
tahan asam (acid-fastness) dari mikobakteri tersebut: sifat tahan asam ini hilang
setelah tercampur dengan isoniazid (Mycek dkk, 2001).
Resistensi INH berhubungan dengan ketidakmampuan organisme untuk
menimbun obat tersebut. Juga terdapat bukti bahwa enzim target bisa berubah
sehingga tidak mengikat isoniazid atau mungkin juga enzim tersebut dihasilkan
dalam jumlah berlebihan sehingga obat tidak cukup. Resistensi ini diakibatkan
oleh mutan KatG R436L yang juga memiliki kerja yang sama dengan KatG tetapi
substrat yang diikatnya berbeda (Johnsson dkk, 1997). Tidak ada resistensi silang
13

antara isoniazid dengan obat-obat antituberkulosis lainya. INH berdifusi ke dalam
seluruh cairan tubuh, sel-sel tubuh dan bahan kaseosa (jaringan nekrotik seperti
keju). Jaringan yang terinfeksi cenderung menahan obat tersebut lebih lama. INH
mengalami N-asetilasi dan hidrolisis yang menghasilkan produk-produk yang
tidak aktif (Mycek dkk, 2001).
Penyakit hati kronik akan mengurangi metabolisme dan dosis harus
dikurangi. Fungsi ginjal yang sangat berkurang menyebabkan akumulasi obat
tersebut. (Mycek dkk, 2001). Drug induced liver disease (obat dapat menginduksi
timbulnya penyakit hati). Hipersensitivitas terhadap
isoniazid atau komponen lain dalam sediaan ; penyakit hati akut,
riwayat kerusakan hati selama terapi dengan isoniazid (Depkes,
2010).
Gambar 4. Struktur Isoniazid
2.3.2 Streptomisin (SM)
Streptomisin (O-2-deoxy-2-methylamino- α-L-glucopyranosyl-(1-2)-O-5-
deoxy- 3-C-formyl-α-L-lyxofuranosyl- (1-4)-N,N-diamidino-D-streptamine;
C21H39N7O12; BM: 581.6) bentuknya berupa kristal keputih-putihan yang mudah
larut dalam air, sangat higroskopik sehingga harus disimpan dalam wadah kedap
udara (Palomino dkk, 2007).
Sebagian besar basil-basil tuberkel dihambat oleh streptomisin, in vitro.
Spesies mikobakteri non tuberkulosis selain Mycobacterium avium complex
14

(MAC) dan Mycobakterium kansasii semuanya resisten. Seluruh populasi besar
dari basil-basil tuberkel mengandung beberapa mutan yang resisten-streptomisin
(Katzung, 2004).
Streptomisin sulit menembus ke dalam sel-sel, dan konsekuensinya obat
ini hanya aktif utamanya untuk melawan basil-basil tuberkel ekstraseluler.
Streptomisin menembus sawar darah otak dan mencapai konsentrasi terapeutik
pada radang selaput otak. Obat ini dapat menyebabkan ototoksik dan nefrotoksik.
Vertigo dan kehilangan pendengaran merupakan efek-efek samping utamanya dan
kemungkinan menjadi permanen (Katzung, 2004).
Gambar 5. Streptomisin
2.3.3 Etionamid (ETA)
Etionamid (2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide, C8H10N2S, BM: 166.24 )
adalah padatan yang larut dengan sangat sedikit air, eter. Larut dengan sedikit
methanol, etanol, dan propilen glikol. Larut dalam aseton panas dan dikloroetana
panas dan larut bebas dengan piridin (Elsevier, 2008).
Etionamid secara kimia berhubungan dengan isoniazid, juga menghambat
sintesis mycolic acid (Katzung, 2004). Etionamid memiliki struktur yang mirip
15

dengan isoniazid dan bekerja dengan cara yang mirip dengan isoniazid yaitu
menghambat sintesis protein, menghambat biosintesis asam mikolat dan
mempengaruhi membran sel. Etionamid adalah bentuk prodrug dan harus
dikonversi menjadi bentuk aktifnya terlebih dahulu oleh enzim bacterial EthA
(Arbex dkk, 2010).
Gambar 6. Struktur Etionamid
2.4 Tinjauan Umum Tentang Ester
Ester salah satu dari golongan-golongan senyawa organik yang sangat
berguna, dapat diubah menjadi aneka ragam senyawa lain. Ester lazim dijumpai
dalam alam. Lemak dan lilin adalah ester. Ester juga digunakan untuk polimer
sintetik, Dacron misalnya. Ester atsiri menyebabkan aroma yang sedap dalam
banyak buah dan parfum. Cita rasa buah alamiah merupakan ramuan rumit
bermacam-macam ester bersama dengan senyawa organik lain. Cita rasa buah
sintetik biasanya hanya merupakan ramuan sederhana dari beberapa ester dengan
beberapa zat lain. Oleh karena itu, cita rasa sintetik jarang dapat menyamai cita
rasa alamiah sesungguhnya (Fessenden dan Fessenden, 1986).
2.4.1 Sintesis Ester
Bila suatu asam karboksilat dan alkohol dipanaskan dengan kehadiran
katalis asam (biasanya HCl atau H2SO4), kesetimbangan tercapai dengan ester dan
16

air. Proses ini disebut esterifikasi Fischer, berdasarkan Emil Fischer yang
mengembangkan metode ini (Hart, 2003). Keaktifan alkohol terhadap esterifikasi
bertambah dengan berkurangnya efek sterik dan panjang rantai alkil (ROH tersier
< ROH sekunder < ROH primer < CH3OH). Keaktifan asam karboksilat terhadap
esterifikasi sama seperti alkohol (R3CCO2H < R2CHCO2H < RCH2CO2H <
CH3CO2H < HCO2H). Salah satu teknik untuk mencapai reaksi kearah ester
adalah menggunakan salah satu zat pereaksi yang murah secara berlebihan.
Teknik lain adalah memindahkan salah satu produk dari dalam campuran reaksi
misal dengan destilasi air secara azeotropik (Fessenden dan Fessenden, 1982).
Telah lama diketahui bahwa proses esterifikasi dapat sangat dipercepat
dengan penambahan asam kuat seperti asam sulfat. Ada juga metode untuk
esterifikasi menggunakan reagen spesifik dehidrasi. Esterifikasi klasik memiliki
beberapa kelemahan yaitu kekorosifan asam kuat, dengan reaksi samping yang
menyertainya seperti karbonisasi dan oksidasi. Ada banyak reagen esterifikasi
asam karboksilat telah dikembangkan, penelitian di bidang ini masih sangat aktif.
Untuk esterifikasi langsung asam karboksilat dalam kondisi ringan, asam
karboksilat harus diaktifkan untuk spesies reaktif lebih dengan menggunakan
aktivator (Kim dkk, 2004).
Alternatif lain untuk esterifikasi menggunakan reagen reaksi kopling
seperti DCC (Steglich Esterifikasi), ester preformed (transesterifikasi), klorida
asam karboksilat atau anhidrida. Reaksi ini menghindari produksi air. Jalur lain
untuk produksi ester adalah pembentukan suatu anion karboksilat, yang kemudian
bereaksi sebagai nukleofil dengan elektrofil. Ester juga dapat diproduksi melalui
17

reaksi oksidasi, yaitu oleh oksidasi Baeyer-Villiger dan esterifications oksidatif
(Anonim a, 2011).
Gambar 7. Mekanisme reaksi esterifikasi (Anonim a, 2011)
2.4.2 Uraian 2-(feniletil)heptanoat
Senyawa 2-(feniletil)heptanoat (C15H22O2) memiliki warna cairan mulai
dari tidak berwarna sampai kuning muda dengan berat molekul 234,334, densitas
1,034 pada 25 oC, Indeks refraksinya 1,48050 pada 25 oC dan titik didihnya 321-
322 oC pada tekanan 1 atm. Senyawa ini memiliki bau seperti bunga mawar
apricot (Anonim b, 2011). Mekanisme reaksi pembentukan 2-(feniletil)heptanoat
dapat dilihat pada Gambar 8.
18

Gambar 8. Mekanisme reaksi pembentukan 2-(feniletil)heptanoat
2.5 Tinjauan Umum Tentang Uji Aktivitas Antibakteri
Penentuan kepekaan bakteri patogen terhadap antimikrobia dapat
dilakukan dengan salah satu dari dua metode pokok yaitu dilusi atau difusi.
Metode dilusi mennggunakan antimikrobia dengan kadar yang menurun secara
bertahap, baik dengan media cair maupun padat. Kemudian media diinokulasi
bakteri uji dan dieramkan. Tahap akhir dilarutkan antimikrobia dengan kadar yang
19

menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan
penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. Uji kepekaan cara dilusi cair
dengan menggunakan tabung reaksi, tidak praktis dan jarang dipakai. Namun kini
ada cara yang lebih sederhana dan banyak dipakai, yakni menggunakan
microdilution plate. Keuntungan metode mikrodilusi cair adalah uji ini
memberikan hasil kuantitatif yang menunjukkan jumlah antimikrobia yang
dibutuhkan untuk mematikan bakteri (Brooks, 2005).
Metode kedua yaitu metode difusi. Metode difusi yang paling sering
digunakan adalah metode difusi agar. Cakram kertas saring berisi sejumlah
tertentu obat ditempatkan pada permukaan medium padat yang sebelumnya telah
diinokulasi bakteri uji pada medium pertumbuhan (Brooks, 2005).
2.5.1 Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Konsentrasi hambat minimum (MIC) didefinisikan sebagai konsentrasi
terendah dari suatu antimikroba yang akan menghambat pertumbuhan
mikroorganisme terlihat setelah inkubasi semalam, dan konsentrasi bakterisida
minimum (MBCs) sebagai konsentrasi terendah antimikroba yang akan mencegah
pertumbuhan organisme setelah subkultur pada media bebas antibiotik. MIC
digunakan oleh laboratorium diagnostik terutama untuk mengkonfirmasi
resistensi, tetapi paling sering sebagai alat penelitian untuk menentukan aktivitas
in vitro antimikroba baru, dan data dari studi tersebut telah digunakan untuk
menentukan breakpoints MIC. Penentuan MBC yang dilakukan lebih sering dan
penggunaan utama mereka telah dicadangkan untuk isolat dari darah pasien
dengan endokarditis (Andrews, 2001).
20

Aktivitas antimikroba ditentukan dengan mengukur diameter
hambatannya, yaitu daerah bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram.
Antimikroba dikatakan mempunyai aktivitas yang tinggi terhadap mikroba apabila
nilai konsentrasi penghambatan bakteri yang terendah (MIC) kecil, tetapi
mempunyai diameter penghambatannya besar (Irianto, 2007). Suatu bahan
dikatakan mempunyai aktivitas antibakteri apabila diameter hambatan yang
terbentuk lebih besar atau sama dengan 6 mm (Bell, 1984).
Menurut (Nester dkk., 1973) terdapat dua teknik MIC yaitu :
a. MIC cair (Tube diluting)
Metode uji ini menggunakan teknik Tube Dillution Test. Fungsinya untuk
mengetahui hasil MIC secara langsung.
b. MIC padat
Metode uji ini berupa metode Difusi Lempeng Agar (DLA). Uji ini
dilakukan pada permukaan medium padat. Mikroba ditumbuhkan pada medium
dan kertas saring yang berbentuk cakram yang telah mengandung mikroba.
Setelah diinkubasi diameter zona penghambatan diukur. Diameter zona
pengambatan merupakan pengukuran MIC secara tidak langsung dari antibiotika
terhadap mikroba.
21