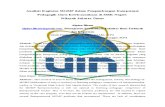jurnal 1
-
Upload
pamel-liskardani -
Category
Documents
-
view
560 -
download
2
Transcript of jurnal 1
Majalah Ilmiah ISSN : 1410 - 8291
SK Kep. LIPI No. 536/D/2007 tanggal 26 Juni 2007
1
JURNAL
PENELITIAN
KOMUNIKASI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA BANDUNG
ii Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No.1
JURNAL
PENELITIAN
KOMUNIKASI
Merupakan terbitan berkala setiap caturwulan, yang menyajikan hasil-hasil penelitian : pendapat
khalayak, mencakup : praktek dan teori, tinjauan buku, gagasan dan ide-ide baru serta
pengembangan dan rekayasa di bidang komunikasi dan informatika.. Merupakan media informasi dan sarana pengembangan ilmu yang diharapkan dapat menjadi
masukan bagi Departemen Komunikasi dan Informatika dalam menyusun kebijakan di bidang
komunikasi dan informatika. Sasaran penyebaran ditujukan bagi masyarakat ilmiah, para peneliti dan praktisi komunikasi.
PENERBIT Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung
PENANGGUNG
JAWAB
Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung
KETUA
PENYUNTING
C. Suprapti Dwi Takariani, SH.
PENYUNTING
AHLI
Prof. Ris. Rusdi Mukhtar, MA.
Dr. Atie Rachmiati, M.Si.
Drs. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si. Dra. Siti Karlinah, M.Si.
PENYUNTING
PELAKSANA
Drs. Ramon, M.Si. Drs. Mulyono Yalia
Drs. Nana Suryana
SEKRETARIS
PENYUNTING
Dra. Betty Djuliati
ADMINISTRASI
Yoyo Suhawaya, Sm. Hk.
DISAIN & TATA
LETAK
Widdie Budhiarta, A.Md.
KOREKTOR
Ati Sumiati
PELAKSANA
DISTRIBUSI
Hj. Rosariah (Distribusi : Cuma-cuma, tukar menukar, dihadiahkan)
ALAMAT
REDAKSI
Jl. Pajajaran No. 88 Bandung 40173; Telp. : (022) 6017493. Fax. (022) 6021740 E-mail : [email protected]
PENGIRIMAN
NASKAH
Redaksi menerima kiriman naskah dari pembaca yang ditujukan pada alamat redaksi. Naskah yang
diterima harus asli dan belum pernah diterbitkan/dimuat di media lain, diketik dengan spasi 1,5 pada
kertas A4 minimal 15 halaman maksimal 20 halaman, dilengkapi dengan identitas jati diri penulis.
Sumber dituliskan : nama pengarang, tahun karangan dan halaman sumber di antara kurung.
Contoh : (Amri Jahi, 1988 : 33). Daftar Pustaka ditulis pada halaman terpisah dan disusun menurut
abjad, dengan urutan : nama pengarang atau penyunting, tahun penerbitan, judul buku, artikel, kota dan nama penerbit.
Contoh : Costanza R. (ed.) 1991, Ecological Economic, New York : Colombia University Press. Naskah yang tidak diterbitkan menjadi hak milik redaksi dan tidak dapat diminta kembali
ISSN : 1410-8291
Jurnal Edisi Perdana Terbit Tahun 1997
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 iii
KATA PENGANTAR
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini
begitu pesat dan telah merambah di segala bidang kehidupan
masyarakat. Beberapa lembaga-lembaga masyarakat telah
memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk memberdayakan
masyarakatnya, namun masih banyak ditemukan berbagai kendala
dalam memanfaatkan TIK tersebut. Dalam Jurnal volume 12 No. 1
Tahun 2009 ini, disajikan tujuh tulisan yang merupakan resume hasil
penelitian.
Ketersediaan alat komunikasi dan informasi yang belum cukup
dan belum maksimal serta kemampuan Sumber Daya Manusia yang
masih terbatas dalam menggunakan TIK menjadi salah satu kendala
dalam menyongsong Manado Kota Pariwisata Dunia (MKPD), hal
tersebut terungkap dalam hasil penelitian yang diangkat oleh Ramon,
dengan judul tulisan ”Kesiapan Infrastruktur Komunikasi Informasi
Menyongsong Manado Kota Pariwisata Dunia (MKPD) 2010”.
Kendala tersebut juga ditemukan dalam lembaga-lembaga masyarakat
yang mencoba memanfaatkan TIK untuk memberdayakan
masyarakatnya, seperti terungkap dalam penelitian tentang ”BALAI
INFORMASI MASYARAKAT (BIM) CIHIDEUNG :
Memberdayakan Masyarakat Perdesaan Melalui Teknologi Informasi
dan Komunikasi” yang diangkat oleh Sumarsono. Sementara itu
keberadaan Warung Masyarakat Informasi (warmasif) yang
merupakan model pengembangan Community Access Point (CAP)
dan dibangun untuk mempercepat tercapainya masyarakat informasi
ternyata belum dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan
dan sasarannya. Syarif Budhirianto dalam tulisannya, ” Motivasi
Pengguna Warung masyarakat Informasi dalam Pemenuhan
Kebutuhan Bermedia di Propinsi Jawa Barat”, menyimpulkan
keberadaan warmasif untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan
komunikasi kurang optimal, warmasif baru dimanfaatkan sebatas
untuk memenuhi kebutuhan hiburan bagi masyarakat.
Perkembangan TIK dewasa ini telah dimanfaatkan oleh
Perguruan Tinggi Negeri dengan mempraktekkan penggunaan social
software sebagai media komunikasi dalam proses pengajaran. Dalam
tulisan, ”Social Software sebagai Media Komunikasi dalam Proses
Pengajaran di Perguruan Tinggi Negeri”, Akhmad Riza Faizal dan
Wulan Suciska, menyimpulkan penggunaan social software sebagai
iv Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No.1
media komunikasi dalam proses pengajaran mampu mendorong
kemampuan menulis siswa, menyebarkan materi perkuliahan,
menerbitkan hasil ujian semester. Namun di sisi lain perkembangan
TIK telah mengubah dunia jurnalistik yakni dengan hadirnya citizen
journalism, dimana setiap warga bisa melaporkan peristiwa yang
terjadi kepada media. Bagaimana sikap Jurnalis terhadap citizen
journalism? Permasalahan tersebut diangkat oleh Dida Dirgahayu
dalam penelitiannya yang berjudul ”Sikap Jurnalis Terhadap Citizen
Journalism”
Dalam tulisan lainnya, ”Konstruksi Identitas Sosial Kaum
Remaja Marjinal” studi kasus di kalangan remaja pengamen jalanan di
Purwokerto, Agus Ganjar Runtiko, mengkaji mengenai kaum
pengamen jalanan yang selama ini selalu identik dengan
ketidaktertiban, dan selalu ditertibkan, namun jumlah mereka dari
tahun ke tahun tidak pernah menyusut. Hasil penelitian tersebut adalah
terbentuknya model penanganan yang lebih tepat bagi para pengamen
jalanan.
Sementara itu, dalam tulisan ”Perilaku Politik Pemilih Pada
Pemilihan Gubernur Jawa Timur Periode 2008-2013”, yang ditulis
oleh Irtanto, menyimpulkan bahwa preferensi pemilih lebih banyak
karena kesamaan asal daerah, agama, kesamaan jenis kelamin
terutama pada budaya arek, budaya mataraman, dan budaya
pandalungan.
Penyunting
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 v
VOL. 12 No. 1 Tahun 2009 ISSN : 1410 - 8291
JURNAL
PENELITIAN
KOMUNIKASI
DAFTAR ISI
STUDI KESIAPAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI
INFORMASI MENYONGSONG MANADO KOTA
PARIWISATA DUNIA (MKPD) 2010
Ramon ...................................................................................... 1-22
KONSTRUKSI IDENTITAS SOSIAL KAUM REMAJA
MARJINAL (Studi Kasus di Kalangan Remaja Pengamen
Jalanan di Purwokerto)
Agus Ganjar Runtiko ............................................................... 23-42
PERILAKU POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR JAWA TIMUR PERIODE 2008-2013
Irtanto ....................................................................................... 43-62
BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM)
CIHIDEUNG : Memberdayakan Masyarakat Perdesaan
Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sumarsono ................................................................................ 63-80
SOCIAL SOFTWARE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI
DALAM PROSES PENGAJARAN DI PERGURUAN
TINGGI NEGERI
Akhmad Riza Faizal dan Wulan Suciska ............................... 81-98
vi Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No.1
MOTIVASI PENGGUNA WARUNG MASYARAKAT
INFORMASI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN
BERMEDIA DI PROVINSI JAWA BARAT
Syarif Budhirianto ................................................................. 99-118
SIKAP JURNALIS TERHADAP CITIZEN
JOURNALISM Dida Dirgahayu ...................................................................... 119-137
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 1
STUDI KESIAPAN INFRASTRUKTUR
KOMUNIKASI INFORMASI MENYONGSONG
MANADO KOTA PARIWISATA DUNIA (MKPD) 2010
Ramon*
Abstraksi
Penelitian ini ingin melihat kesiapan infrastruktur komunikasi
informasi dalam menyongsong Manado Kota Pariwisata Dunia
(MKPD) tahun 2010. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan
analisis deskriptif, sedangkan metode penelitian bersifat
sosiologis/empiris. Instrumen utama interview guide bersifat terbuka
dan terstruktur. Ketersediaan alat komunikasi dan informasi belum
cukup serta belum maksimal sebagai dukungan sarana dan prasarana
menyongsong MKPD tahun 2010. Yang menjadi kendala lainnya
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) -nya. Penggunaan internet
hanya dipakai untuk mengakses informasi saja belum sampai pada
taraf penambahan pengetahuan/referensi tentang dunia wisata dalam
persiapan menyongsong MKPD tahun 2010. Oleh karena itu perlu
sosialisasi secara kontinyu kepada wisatawan mancanegara dan
domestik baik melalui dunia maya maupun secara langsung.
Kata kunci : Infrastruktur, MKPD 2010, Komunikasi Informasi.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia terkenal kaya sumber daya alamnya, baik yang bisa
diperbaharui (renewable resources) maupun yang tidak bisa di
perbaharui (non-renewable resources). Laut Indonesia itu seluas dua
per tiga dari kawasan Nusantara, namun baru dimanfaatkan sebagian
kecil saja-terutama potensi ikannya saja. Padahal dari laut ini bisa
* Drs. Ramon, M.Si., Penulis adalah Peneliti Madya bidang Komunikasi Politik
pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BP2KI)
Bandung.
2 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
dihasilkan sebagai energi melalui pemanfaatan gelombang air laut
atau angin laut yang dihasilkannya.
Persoalan saat ini adanya pengkaplingan batas-batas territorial
oleh pemerintah daerah dalam menyikapi implementasi desentralisasi
dan Otonomi Daerah saluas-luasnya itu. Pengkaplingan tersebut
berimplikasi pada pembagian 18.100 pulau di Indonesia ke dalam
wilayah-wilayah territorial kabupaten dan kota. Hal ini berakibat
pengelolaan kelautan semakin runyam dengan berbagai pengkaplingan
dan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus. Tentu,
ini membuat munculnya berbagai konflik antara nelayan dan nelayan,
nelayan dengan pemangku kekuasaan daerah dan antar pemangku
kekuasaan daerah walaupun ikan yang akan ditangkap para nelayan itu
“tidak paham batas territorial daerah”.
Selanjutnya akan terdapat keengganan daerah untuk
memberdayakan kekayaan alam yang terkandung di daerah batas
wilayah tersebut, sebelum batas wilayah ini jelas. Penetapan batas
titik-titik itu sekaligus tak hanya menetapkan diantara peran dan
fungsinya, tetapi juga terkait kewenangan daerah untuk
mengeksploitasikan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Otonomi
Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pada
sumber daya alam sekaligus sumber daya manusianya.
Pembangunan sebagai program yang direncanakan untuk
melakukan perubahan-perubahan dengan sengaja untuk
menyejahterakan masyarakat, dan dipandu oleh visi tertentu dalam tahapan tertentu pula. Oleh karena adanya Otonomi Daerah ini, maka
pembangunan daerah harus bertumpu pada kemampuan daerah dengan
segala sumber yang ada serta juga dituntut adanya kreatifitas daerah
dalam mewujudkan pembangunan Propinsi Sulawesi Utara khususnya
ibukota propinsinya yaitu Kota Manado, dalam usaha mencapai
tujuannya menetapkan visi Kota Manado sebagai “Manado Kota
Pariwisata Dunia 2010”.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Manado No.04
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Manado Tahun 2005-2010. Visi Kota Manado secara
lebih lengkap adalah “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010
menuju terwujudnya masyarakat Kota Manado yang aman, berdaya
saing, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat”.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 3
Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi:
“Menciptakan lingkungan perkotaan yang menyenangkan dimana
setiap orang dapat mewujudkan potensi dan impiannya”. Dalam
melaksanakan misi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran
strategis yaitu: terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan
publik yang efisien dan efektif; terwujudnya tata ruang kota berbasis
pariwisata; terwujudnya infrastruktur perkotaan bertaraf internasional;
terciptanya lingkungan perkotaan yang menyenangkan.
Salah satu sasaran strategisnya adalah “terbangunnya
infrastuktur perkotaan bertaraf internasional” yang akan diwujudkan
melalui strategi-strategi pembangunan yaitu : “Infrastruktur
Telekomunikasi dan Informasi yang handal dan mampu
menghubungkan masyarakat kota Manado dengan dunia
internasional“. Dari ketentuan ini, maka sektor infrastruktur
komunikasi informasi menjadi faktor penunjang keberhasilan
mewujudkan visi dan misi Kota Manado.
Manado yang terletak di pulau Sulawesi menjadi salah satu
andalan Indonesia dari keindahan alamnya untuk mendatangkan
devisa negara melalui pariwisata. Berdasarkan kekayaan alam yang
dimiliki Pulau Sulawesi khususnya wisata bahari, maka kita dapat
tampilkan kekayaan dasar laut yang dikenal dengan nama BUNAKEN
sebagai salah satu obyek wisatanya.
Upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan ditopang oleh
berbagai faktor salah satu yang berperan ialah komunikasi. Sesuai
dengan strategi pembangunan yang salah satunya peran komunikasi -
dan informasi, dalam hal ini akan terwujud jika ditunjang oleh
infrastruktur yang dibutuhkan, terutama infrastruktur komunikasi
informasi.
Namun ternyata belum terlihat adanya kesiapan infrastruktur
komunikasi informasi di Kota Manado dalam menyongsong Manado
Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010. Hal ini terbukti dengan masih
kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi informasi
serta pengelolaan informasi dan diseminasi yang efektif dari kalangan infrastruktur secara terorganisasi, terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis, untuk dapat secara cepat mengakses berbagai informasi di
bidang pariwisata di Kota Manado yang akan ditawarkan kepada
publik.
Untuk mendapatkan gambaran tentang peran komunikasi dan
informasi dalam pembangunan menuju Manado Kota Pariwisata
4 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Dunia Tahun 2010, maka perlu dilakukan penelitian tentang Studi
Kesiapan Infrastruktur Komunikasi Informasi di Kota Manado dalam
rangka menuju Manado Kota Pariwisata Dunia di tahun 2010.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemasalahan di atas, maka
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Bagaimana Kesiapan Infrastruktur Komunikasi Informasi Kota
Manado Menyongsong Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010 ?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan
Untuk mengetahui Kesiapan Infrastruktur Komunikasi
Informasi Kota Manado Menyongsong Manado Kota Pariwisata
Dunia Tahun 2010.
Kegunaan
1. Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu
komunikasi informatika, dan agar dapat menjadi referensi bagi
penelitian selanjutnya dibidang teknologi informasi dan
komunikasi.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai bahan informasi tentang kesiapan infrastruktur komunikasi
informasi kota Manado Menyongsong Manado Kota Pariwisata
Dunia Tahun 2010 untuk menjadi bahan masukan kepada
Pemerintah Kota Manado dan pimpinan Departemen Komunikasi
dan Informatika dalam pengambilan kebijakan.
Tinjauan Teori
Sarjana komunikasi sepakat bahwa tujuan utama teori ialah
eksplanasi (Hawes, 1975, Miller & Nicholson, 1976; Monge, 1973;
Tucker et al, 1981). Monge (1973) mengatakan :
“The primary purpose of a scientific theory is scientific explanation …
To establish a theory of communication is to seek a set of propositians
that explain how communication operates, i.e. why various
communication events are related. (pp. 5-6) (Tujuan utama suatu teori
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 5
ilmiah adalah memberi eksplanasi secara ilmiah. Untuk membangun
suatu teori komunikasi diperlukan adanya seperangkat proposisi yang
mampu menjelaskan bagaimana komunikasi memiliki keterkaitan satu
sama lain).
Dalam ilmu pengetahuan, eksplanasi untuk satu peristiwa
memerlukan spesifikasi sebab-sebab atau kondisi-kondisi anteseden
yang menyebabkan peristiwa itu dan menguraikan kondisi-kondisi
bagaimana sehingga eksplanasi itu berlaku (Monge, 1973; Harre,
1983).
Dalam penelitian ini, akan dilihat faktor-faktor yang
menyebabkan peristiwa yang terkait dengan kesiapan infrastruktur
komunikasi informasi sebagai salah satu strategi pembangunan yang
akan diwujudkan dalam Misi Manado Kota Wisata Dunia 2010.
Kesiapan, berasal dari kata dasar “siap”, (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1990:835) yang berarti sudah sedia; sudah disediakan
(tinggal memakai atau menggunakan saja) ; sudah selesai (dibuat atau
dikerjakan). Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan kesiapan
komunikasi informasi adalah sebagai kesudah-tersediaan sarana dan
prasarana komunikasi dan informasi yang dapat digunakan untuk
mendukung program Manado Kota Wisata Dunia Tahun 2010.
Sri Astuti, (2001) berpendapat bahwa penggunaan teknologi
informasi, pemanfaatan informasi oleh individual, kelompok atau
organisasi merupakan variabel inti dalam riset sistem informasi,
sebab sebelum digunakan pertama terlebih dahulu dipastikan tentang
penerimaan atau penolakan di gunakannya teknologi informasi
tersebut, hal ini berkaitan dengan perilaku yang ada pada individu/
organisasi yang menggunakan teknologi komputer.
Dalam dekade terakhir ini sangat dirasakan peran teknologi
komunikasi informasi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam
rangka menunjang kesuksesan Manado sebagai Kota Wisata Dunia di
Tahun 2010, sangat besar peran komunikasi informasi di dalamnya.
Teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi hampir
semua kegiatan manusia. Pada saat yang bersamaan dan dalam
perkembangan kebutuhan akan akses informasi yang cepat terlebih
informasi yang terkait dengan pariwisata di Kota Manado, maka
kehadiran perangkat infrastruktur komunikasi informasi menjadi suatu
keharusan yang sangat mendesak.
Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini berupa peralatan
komputerisasi, internet serta sarana dan prasarana lain yang
6 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
menggunakan teknologi informasi dalam mengomunikasikan
pariwisata di Kota Manado guna mendukung program Manado Kota
Wisata Dunia di Tahun 2010.
Kesiapan untuk menuju Manado menjadi Kota Wisata Dunia
tersebut telah dimulai sejak tahun 2005 sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Manado No. 04 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado
Tahun 2005-2010.
Jika kesiapan telah dilakukan sejak Tahun 2005, maka
kesiapan infrastruktur komunikasi informasi dalam hal ini mengenai
ketersediaan alat komunikasi yang telah menggunakan teknologi
informasi dan komputerisasi juga seharusnya telah dilakukan sejak
tahun 2005.
Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan
paradigma. Pandangan jauh kedepan untuk menumbuhkan
perekonomian yang berkelanjutan, dengan kekuatan yang bertumpu
pada keunggulan potensi daerah. “Selain mendatangkan manfaat nyata
berupa pendapatan daerah yang akan meningkat, upaya menggali dan
mengoptimalkan potensi daerah juga bisa menjadi masukan penting
untuk branding suatu daerah” ungkap Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo
Harry Sarundayang. Bagi Harry, branding yang tepat dan bagus
niscaya membuat suatu daerah tampil lebih atraktif dan eksotis,
sehingga memikat para investor untuk berlomba-lomba menanamkan
investasinya . “Ujung-ujungnya, sumber pendapatan daerah juga akan
timbul dengan sendirinya. Ragamnya pun akan semakin banyak, dan
multifier effect yang ditimbulkan jauh lebih banyak.“ tandasnya.
Tujuh tahun sudah implementasi Desentralisasi dan Otonomi
Daerah (OTDA) seluas-luasnya di Indonesia. Hasil yang tampak jelas,
jumlah propinsi meningkat dari 26 menjadi 33 Propinsi, sementara
jumlah Kabupaten/Kota meningkat, dari 300 menjadi 458
Kabupaten/Kota.
Namun yang menyedihkan, bahwa arogansi lokal muncul
diantara propinsi, kabupaten maupun kota dalam menjalankan
berbagai kewenangan yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Di lain sisi, keengganan pemerintah pusat untuk
menyerahkan kewenangan yang harus dimiliki Pemerintah Daerah
(berdasarkan Undang-Undang yang berlaku), tampaknya masih belum
secara tegas dan jelas. Hal ini diperkuat oleh statement Johnny
Karinda “Manado sebagai pusat kegiatan nasional di Sulawesi Utara
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 7
sebagaimana arahan RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional) menjadi penting sebagai kota tujuan utama (Primary
Destination) maupun sebagai kota transit sekaligus pusat pertumbuhan
wilayah di kawasan Indonesia Timur.“ (Manado Post, 13 juli 2008, hal
4 ).
Dengan kedudukan dan posisi strategis dalam konstalasi
ekonomi lokal, regional maupun nasional secara geografis berada di
kawasan Pasifik Rim memberi peluang bagi Kota Tinutuan ini
berkembang menjadi kota pariwisata penting dan unggulan di skala
nasional maupun internasional.
Kini Sulawesi Utara bertekad menggarap sektor pariwisata,
perkebunan kelapa dan perikanan sebagai tumpuan ekonominya.
Apalagi “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010“ sudah
dijadikan Peraturan Daerah. Selanjutnya sedang gencar-gencarnya
pula Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. dan Gubernur
Sulawesi Utara SHS Sarundayang mempromosikannya secara
domestik maupun ke mancanegara secara besar-besaran.
Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Metode Penelitian dalam hal ini adalah sosiologis atau empiris
atau non doctrinal, dalam hal ini adalah terhadap ketersediaannya
sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sekaligus sumber daya
manusianya dalam menyongsong Manado Kota Pariwisata Dunia
Tahun 2010.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan sosiologis terhadap kasus, yaitu suatu pendekatan
yang dilakukan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu
individu, kelompok, institusi, atau interaksi-interaksi (sosial) yang
terjadi di dalamnya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
analisis yang bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa data
dikumpulkan dengan menggunakan interview guide (pedoman
wawancara) yang bersifat terbuka dan terstruktur, yang akan menjadi
instrumen utama dalam analisis data, kemudian didukung oleh
perolehan data dari informan yang terkait dengan permasalahan yang
akan diteliti.
8 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota
Manado sebagai responden yang menggunakan teknologi informasi
dalam kaitannya dengan persiapan menyambut Manado Kota
Pariwisata Dunia Tahun 2010.
2. Sampel
Dalam penarikan sampelnya digunakan teknik purposive
random sampling yang dipilih secara sengaja. Yang berarti bahwa
setiap individu yang menjadi responden akan dipilih secara sengaja
dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dalam hal ini
adalah :
Masyarakat yang menggunakan alat komunikasi informasi
untuk mengakses informasi terkait dengan kepariwisataan di Kota
Manado, sehingga terpilih: Dosen Pariwisata, Pengamat Pariwisata,
Akademisi bidang IT, Pakar Komunikasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Lintas Agama, Sosiolog, Pengusaha yang tergabung dalam PHRI,
LSM bidang terkait, Pengusaha Warnet, Dunia Hiburan (Pub,
Diskotik, Karaoke, Café, Bar).
Aparat Pemerintah Kota Manado yang terkait bidang tugasnya dengan
kepariwisataan di kota Manado, dalam hal ini terpilih : Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, Dinas Komunikasi dan
Informatika, Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelola
Pelabuhan Darat Laut maupun Udara, BPDE, Sekertariat MKPD
Provinsi dan Kota, Bappeda Kota Manado.
Selanjutnya untuk kebutuhan akurasi data akan dilakukan
cross check (cek silang) terhadap informan yang menjadi sasaran
penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam (eksploratif),
dalam hal ini adalah masyarakat umum pihak dinas terkait yakni
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelola Pelabuhan (laut, darat,
dan udara), Balai Pengelola Data Elektronik (BPDE), PT. Pos dan
Giro, PT. Telkom dan Dinas Kominfo Kota Manado.
Teknik Pengumpulan Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yang akan
dilakukan data dikumpulkan dengan menggunakan interview
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 9
guide (pedoman wawancara) yang bersifat terbuka dan
terstruktur, yang akan menjadi instrumen utama dalam analisis
data, kemudian didukung oleh perolehan data dari informan yang
terkait dengan permasalahan yang akan di teliti. Dengan demikian
saat berlangsungnya wawancara sangat dimungkinkan
berkembang sesuai dengan kenyataan yang diperoleh di
lapangan. Artinya walaupun jawaban sedikit diluar kuesioner
asalkan dalam koridor substansi masih dimungkinkan diteruskan
pertanyaan lanjutan.
Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan terstruktur
tersebut sangat tergantung pada tanggapan para responden
maupun informan yang menjadi sasaran penelitian. Pertanyaan
yang diajukan akan berkisar pada kesiapan infrastruktur
komunikasi informasi dalam menyongsong Manado Kota
Pariwisata Dunia Tahun 2010. Demikian juga faktor-faktor
pendorong yang menyebabkan ketidaksiapan infrastruktur
komunikasi informasi dalam menyongsong Manado Kota
Pariwisata Dunia 2010.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur, majalah, koran
yang terkait dengan permasalahan penelitian serta juga diperoleh
melalui internet.
Analisis Data
Analisis data yang bersifat deskriptif, artinya bahwa data yang
diperoleh akan dianalisis dengan cara menggambarkan secara kritis
data dikumpulkan dengan menggunakan interview guide (pedoman
wawancara) yang bersifat terbuka dan terstruktur. Data yang diperoleh
akan menjadi instrumen utama dalam analisis deskriptif tersebut,
kemudian didukung oleh perolehan data dari informan yang terkait
dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memberikan gambaran
secara kritis.
Definisi Konsep
1. Kesiapan
Kesiapan adalah sebagai kesudah-tersediaan sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi yang dapat digunakan untuk
mendukung program Manado Kota Pariwisata Dunia 2010.
10 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
2. Infrastruktur Komunikasi Informasi
Infrastruktur komunikasi informasi yang dimaksud dalam hal ini
berupa peralatan komputerisasi, internet serta sarana dan prasarana
lain yang menggunakan teknologi informasi yang dapat digunakan
untuk mengakses informasi yang cepat terkait dengan pariwisata
di Kota Manado guna mendukung program Manado Kota
Pariwisata Dunia Tahun 2010.
3. Menyongsong Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010
Yang dimaksud dalam hal ini adalah menyambut diadakannya
perhelatan besar Pemerintah Kota Manado sebagai tujuan
wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara yang
puncaknya di tahun 2010.
Definisi Operasional
1. Kesiapan
Dengan indikator telah tersedianya komputer, internet, telepon dan
semua peralatan komunikasi di tempat-tempat yang berhubungan
dengan kepariwisataan untuk menginformasikan pariwisata di
Kota Manado; yang dalam hal ini diambil di hotel-hotel,
perusahaan biro perjalanan, pusat-pusat perbelanjaan, warung
internet, warung telepon dan juga kantor pemerintah maupun
swasta yang berhubungan dengan dunia pariwisata.
2. Infrastruktur Komunikasi Informasi
Infrastruktur komunikasi informasi yang dimaksud dalam hal ini
berupa peralatan komputer, internet, telepon serta sarana dan
prasarana lain yang menggunakan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi yang cepat terkait dengan
pariwisata di Kota Manado guna mendukung program Manado
Kota Pariwisata Dunia 2010.
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Kondisi Geografis
Kota Manado terletak diujung utara pulau Sulawesi dan
merupakan kota terbesar di belahan Sulawesi Utara sekaligus sebagai
ibukota Propinsi Sulawesi Utara secara geografis Kota Manado
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 11
terletak diantara : 10 25‟ 88”-10 39‟ 50” LU dan 1240 47‟ 00-1240
56‟ 00 BT.
Sedangkan batas administratif adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Kecamatan Wori dan Teluk Manado
Kabupaten Minahasa Utara.
b. Sebelah Timur : Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa.
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
d. Sebelah Barat : Laut Manado /Laut Sulawesi.
Luas Kota Manado adalah 15.726 hektar (157,26 Km2). Kota Manado
mempunyai 3 wilayah pulau dan berpenghuni, yaitu Pulau Manado
Tua, Pulau Bunaken dan Pulau Siladen.
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk tahun 2006 berdasarkan data Survei Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS 2005) berjumlah 417.700 jiwa.
Dengan luas wilayah 157,26 Km2, berarti kepadatan penduduknya
mencapai 2.656 jiwa/Km2. Berdasarkan SUSENAS 2006, rasio jenis
kelamin penduduk Kota Manado lebih dari 100 dengan angka 93,41
persen. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di
Kota Manado lebih kecil daripada jumlah penduduk perempuan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kesiapan Infrastruktur Komunikasi Informasi
Tabel 1
Ketersediaan Alat Komunikasi Informasi Menyongsong
“Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”
No Ketersediaan alat komunikasi informasi N F
(%) Keterangan
1 Ya 91 100 Internet
2 Tidak - - -
3 Belum - - -
4 Jawaban lain - - -
Jumlah 91 100
n = 60 responden + 31 informan
Sumber : Data diolah oleh peneliti.
12 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Bahwa telah tersedia alat komunikasi dan informasi (100%)
dalam rangka menunjang persiapan menyambut Manado Kota
Pariwisata Dunia Tahun 2010, hal ini terlihat dari telah banyak
dijumpai internet. Pengertian “telah tersedia” dalam hal ini dapat
dikonotasikan relatif tersedia, karena kalau ditinjau dari jenis sarana
dan prasarana yang tersedia sebagian besar dari masyarakat hanya
melihat ketersediaan atau ketidak tersedianya internet, jadi yang
menjadi barometernya adalah tersedia atau tidaknya internet. Padahal
alat komunikasi informasi tidak hanya internet saja, namun yang
dijadikan barometer masyarakat saat ini adalah internet.
Kemudian bila dilihat lebih lanjut ketersediaan internet harus
juga di barengi dengan kemanfaatannya sekitar persiapan menyambut
“Manado Kota Pariwisata Dunia 2010”. Inilah yang menjadi tanda
tanya lebih lanjut apakah internet yang ada telah digunakan
sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini ?
Ternyata berdasarkan cross check di lapangan dari informan
dapat dicermati bahwa penggunaan internet masih terbatas untuk
kepentingan pribadi masing-masing pengguna, sehingga belum
maksimal sebagai dukungan sarana dan prasarana menyongsong
“Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”. Sehingga dapat
dikatakan bahwa ketersediaan infrastruktur komunikasi informasi
kurang menunjang program “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun
2010”.
Jumlah Ketersediaan Alat Komunikasi dan Informasi
Tabel 2
Ketersediaan Alat Komunikasi Informasi Berdasar Jumlah
Dalam Menunjang “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”
No Ketersediaan alat
komunikasi informasi N
F
(%) Keterangan
1 Sangat memadai - - Internet
2 Cukup memadai 21 23,08 -
3 Kurang memadai 57 62,63 -
4 Tidak memadai 13 14,29 -
Jumlah 91 100
n = 60 responden + 31 informan
Sumber : Data diolah oleh peneliti.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 13
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketersediaan alat
komunikasi informasi dalam menunjang program “Manado Kota
Pariwisata Dunia Tahun 2010” Kurang memadai (62,63%), maka
selama ini persiapan dari sisi infrastuktur komunikasi informasi masih
dapat dikatakan belum cukup. Oleh karena itu, jika dirasa dari sisi
jumlah Pemerintah Kota Manado tidak dapat memenuhi jumlah
idealnya, tidak salah jika pihak swasta yang terkait dengan
penyelenggaraan kepariwisataan di kota Manado terlibat maupun
dilibatkan, karena sektor swasta lebih merasakan dampak dari
keterbatasan jumlah alat komunikasi informasi dari sisi promosi
produknya untuk di jual kepada masyarakat.
Hal tersebut didukung juga oleh sebuah artikel dari Johnny
Karinda yang mengatakan : “Kegiatan promosi dan pemasaran
pariwisata tampak kurang padu antara pihak-pihak yang berkompeten
(Pemprov, Pemkot, serta stakeholder) masing-masing berjalan sendiri-
sendiri sehingga sasaran yang dituju kurang maksimal. Tidak heran
bila pariwisata Manado kalah bersaing dengan DTW (Daerah Tujuan
Wisata) lain seperti Bali, Lombok dan lain-lain di Nusantara”
(Manado Post, 16 juli 2008, hal 4).
Kemudian jika dilihat dari sisi jumlahnya, ketersediaannya alat
komunikasi informasi masih dikategorikan kurang memadai (62,63%)
jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Manado. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan alat komunikasi
informasi dalam menunjang program “Manado Kota Pariwisata Dunia
Tahun 2010” secara kuantitatif dapat dikatakan cukup memadai, tetapi
secara kualitatif masih sangat kurang.
Tabel 3
Ketersediaan Alat Komunikasi Informasi Menunjang
“Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”
No Ketersediaan alat komunikasi informasi
dalam menunjang “MKPD” N
F
(%) Keterangan
1 Telah menunjang 7 7,70 Internet
2 Kurang menunjang 11 12,09 -
3 Belum menunjang 60 65,93 -
4 Tidak menunjang 13 14,28 -
Jumlah 91 100
n = 60 responden + 31 informan
Sumber : Data diolah oleh peneliti.
14 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Dengan demikian menjadi bahan perenungan bersama, apakah
alat komunikasi informasi yang belum menunjang tersebut akan
segera dapat diatasi permasalahannya?. Sangat kompleks
permasalahan yang ada di dalamnya, karena menyangkut semua
komponen kepariwisataan yang ada di Kota Manado. Dengan
demikian masih perlu ditingkatkan lagi ketersediaan alat komunikasi
informasi sekaligus dibarengi dengan ketersediaan sumber daya
manusia yang kapabel.
Apapun program yang dikampanyekan, kalau tidak dibarengi
dengan upaya untuk secara nyata dan terarah segala kemampuan
terfokus pada program tersebut, maka kita menjadi pesimis melihat
perencanaan waktu yang tidak lama lagi yaitu tahun 2010 tersebut.
Hal selaras dengan pendapat informan dari hasil wawancara yang
menunjukkan bahwa ada keyakinan bahwa program “Manado Kota
Pariwisata Dunia 2010” akan tercapai, tetapi terdapat keraguan kerena
waktu yang sudah dekat, namun pembenahan tidak segencar
kampanyenya.
Menurut observasi peneliti sudah lebih dari cukup (minimal 20
kali) berkunjung ke Bandara Sam Ratulangi Manado tapi ternyata
Ruangan Tourist Information Centre (TIC) kosong melompong tidak
ada penjaganya. Hal ini sangat disesalkan pengamat Pariwisata Sulut
Chefie Nelwan SE, Par dengan mengatakan : “Mestinya Disparbud
Sulut tetap stand by untuk memberikan informasi sebanyak mungkin
obyek wisata yang ada di Sulut, lanjutnya lagi dengan adanya
informasi yang jelas tentang potensi pariwisata membuat wisatawan
tidak ragu-ragu untuk memperpanjang Length Of Stay di Sulut. “
(Manado Post, 3 Oktober 2008, hal 8).
Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik dari semua
komponen masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam kesiapan menyongsong program “Manado Kota
Pariwisata Dunia 2010”. Disamping itu informan juga menambahkan
perlu adanya satu pusat informasi yang dapat diakses dengan mudah
tentang program “Manado Kota Pariwisata Dunia 2010” yang akan
dapat memberikan informasi secara lengkap kepada semua pihak
terkait dengan program tersebut. Informasi yang diberikan baik berupa
informasi langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tulisan serta
media lain yang tersedia.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 15
Sebaran Lokasi Ketersediaan Alat Komunikasi dan Informasi
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4 bahwa sebaran
keberadaan alat tersebut belum merata, karena berdasarkan data di
lapangan alat tersebut masih berada ditempat tertentu selain di kampus
(33,50%) ataupun perkantoran swasta (11,49%) maupun pemerintah
(5,74%), hanya terdapat disekitar pusat perbelanjaan tertentu (Mall
sebesar 5,26%), Warung Internet (16,74%) serta biro perjalanan
(21,53%) dan juga lain-lain yang dalam hal ini dimaksud adalah
internet maupun komputer milik pribadi sebesar 5,74%.
Tabel 4
Sebaran Lokasi Ketersediaan Alat Komunikasi Informasi
Dalam Menunjang “Manado Kota Pariwisata Dunia 2010”
No Lokasi Ketersediaan
alat komunikasi informasi N
F
(%) Keterangan
1 Kampus 70 33,50 Internet,computer
2 Kantor Pemerintah 12 5,74 Internet,computer
3 Kantor swasta 24 11,49 Internet,computer
4 Mall 11 5,26 Internet
5 Warung Internet 35 16,74 Internet
6 Biro Perjalanan 45 21,53 Internet
7 Lain-Lain 12 5,74 Internet,computer
Jumlah 209 100
n = 60 responden + 31 informan, responden boleh memilih jawaban lebih dari satu.
Sumber : Data diolah oleh peneliti.
Berdasarkan hasil wawancara rechecking dengan informan
dari PHRI (Perusahaan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang
Manado, sebaran alat komunikasi informasi tersebut belum dibarengi
dengan kemampuan sumber daya manusianya atau SDM nya, karena
masih sangat kurangnya pengetahuan maupun kemampuan
penggunaan alat-alat teknologi informasi yang tersedia. Lebih lanjut
diungkapkan bahwa sebenarnya dari alat yang tersedia itupun masih
kurang dibandingkan jumlah penduduk di Kota Manado, namun
karena yang dapat menggunakan hanya sebagian kecil masyarakat,
maka tampaknya ketersediaan alat komunikasi untuk sementara dapat
dikatakan cukup memadai, namun belum dapat menunjang
sepenuhnya persiapan Program “Manado Kota Pariwisata Dunia
Tahun 2010”.
16 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Selanjutnya terkait dengan ketersediaan infrastruktur
komunikasi informasi data di lapangan menunjukkan bahwa di
samping perlu disediakan infrastruktur komunikasi informasi juga
perlu sumber daya manusia yang handal di bidang tersebut. Untuk
tingkat pemanfaatan komputer yang dalam hal ini penggunaan fasilitas
internet, masih terbatas pada fasilitas standar, karena fungsi internet
belum dapat dimaksimalkan sebagai media mengakses informasi,
mempermudah komunikasi. Penggunaan internet sampai saat ini
hanya untuk mengakses informasi saja, belum sampai pada taraf
penambahan pengetahuan atau mencari referensi yang diperlukan
tentang dunia wisata di Kota Manado terkait dengan persiapan
“Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”.
Selanjutnya terkait dengan penyediaan fasilitas komunikasi
informasi sebagai infrastruktur, sebagian besar responden maupun
informan menghendaki sebaiknya persiapan alat komunikasi informasi
pertama-tama diawali dari pihak Pemerintah Kota Manado khususnya
Dinas Pariwisata Kebudayaan,
Pengetahuan Tentang Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun
2010
Sementara itu, kalau ditinjau dari konten info yang disediakan
melalui internet maupun media massa lain, info tentang “Manado
Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010” tetapi apa itu dan bagaimana itu,
masih sangat kurang memuat informasi dan pengetahuan seputar
rencana besar tersebut, Walaupun data menunjukkan bahwa responden
sangat mengetahui adanya program “Manado Kota Pariwisata Dunia
Tahun 2010” sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
Tabel 5
Pengetahuan Tentang
“Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”
No. Mengetahui tentang MKPD N F
(%)
1 Ya 91 100
2 Tidak - -
3 Jawaban lain - -
Jumlah 91 100
n = 60 responden + 31 informan
Sumber : Data diolah oleh peneliti.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 17
Berdasarkan tabel tersebut di atas tampak sangat menyakinkan
bahwa semua komponen masyarakat, pariwisata di Kota Manado
mengetahui adanya program Pemerintah Kota Manado yakni “Manado
Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa program ini telah diketahui oleh masyarakat Manado
seluruhnya khususnya masyarakat yang terkait langsung dengan
penyelenggaraan pariwisata di Kota Manado. Selanjutnya “tahu”nya
perlu dipertanyakan lebih lanjut, apakah benar-benar tahu adanya
Program “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010” tersebut dalam
artian bahwa konten dari isi pesan kampanye Pemerintah Kota
Manado tersebut benar diketahui?. Ternyata tampak penyajian
informasi terkait dengan program “Manado Kota Pariwisata Dunia
Tahun 2010” sebagai pesan, belum efektif, hal ini terbukti dengan
ketidaktahuan secara mendalam konten dari pesan kampanye
Pemerintah Kota Manado tersebut.
Dalam efektifitas penyajian informasi dalam bentuk gambar,
secara deskriptif menunjukkan tingkat efektifitas yang tinggi, terhadap
komponen afeksi dari masyarakat usaha pariwisata yang sebagian
besar memiliki tingkat intensitas penerimaan tinggi. Jelas di sini,
bahwa pesan yang berbentuk gambar atau foto dengan latar belakang
musik, lebih menyentuh perasaan seseorang, sehingga menimbulkan
rasa senang untuk mengamatinya. Namun tidak begitu tinggi efeknya
terhadap tingkat pemahaman dan komunikasi dari isi pesan tersebut.
Hal ini terungkap dari hasil observasi di lapangan melalui wawancara
dengan para pengusaha yang tergabung dalam PHRI.
Pengaruh penyajian pesan dalam bentuk naturalis persuatif
terhadap perilaku masyarakat mengenai program Pemerintah Kota
Manado menuju “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”, ada
kecenderungan persamaan dengan penyajian pesan dalam bentuk
atraktif informatif, yaitu pengaruh terhadap perilaku menunjukkan
lebih besar dibandingkan dengan pengaruh terhadap sikap mengenai
Program “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”.
Pendidikan Terakhir Responden
Penyajian pesan dalam bentuk gambar, efektif dalam
memengaruhi perilaku, sudah barang tentu tidak terlepas dari variabel
lain yang dimiliki oleh masyarakat usaha pariwisata, diantaranya
unsur pendidikan. Mereka yang berpendidikan tinggi mampu
18 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
memahami pesan yang sangat abstrak yaitu berupa gambar. Teori
mengatakan : “Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka
semakin tinggi kemampuannya untuk memahami pesan-pesan
(stimulus) yang bersifat visual, non verbal dan emosional”.
(Betinghaus EP. 1973).
Tabel 6
Pendidikan Terakhir Responden
No. Pendidikan Terahir N F
(%)
1 Tamat SD - -
2 Tamat SMP 1 1,67
3 Tamat SMU 25 41,67
4 Tamat D 1/2/3 21 35
5 Tamat S1/Sederajat 11 18,33
6 Tamat S2/Sederajat 2 3,33
7 Tamat S3/Sederajat - -
Jumlah 60 100
n = 60 responden.
Sumber : Data diolah oleh peneliti.
Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, data memperlihatkan
bahwa tingkat pendidikan terakhir responden tamatan SMU yakni
sebanyak 41,67%, tidak ada yang tamatan SD dan S3; Sedangkan
yang terkecil adalah tamatan SMP yakni 1,67%.
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat pendidikan,
intensitas penerimaan suatu pesan, dan tingkat persuasibilitas yang
ditentukan oleh pengetahuan pemahaman, perhatian, motif, dan
kemampuan mendapatkan informasi, ikut menentukan adanya
kesenjangan efek komunikasi. Hal ini mendukung pada penemuan-
penemuan terdahulu yang dilakukan oleh Schramm, 1977; Schramm,
Nelson, dan Betham, 1981; yang menyatakan ketrampilan
berkomunikasi yang diperlukan, penggunaan media yang tinggi, juga
melengkapi mereka dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi
dalam beberapa topik. (Rager, 1983).
Kesenjangan efek komunikasi terjadi karena :
1. Perbedaan tingkat ketrampilan berkomunikasi di antara segmen-
segmen suatu khalayak secara keseluruhan;
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 19
2. Tingkat pengetahuan tentang suatu isu yang dikuasai sebelumnya;
3. Kontak sosial yang relevan dengan orang-orang yang memiliki
lebih banyak informasi;
4. Persepsi selektif;
5. Kerelevanan fungsional atau utilitas;
6. Akses yang berbeda pada sumber daya yang terbatas;
7. Bias urban pada media massa;
8. Bantuan yang tidak memadai dari badan yang melakukan
intervensi sosial;
9. Kurangnya partisipasi dari khalayak sasaran dalam pembuatan
keputusan dan implementasi keputusan tersebut;
10. Perbedaan pendidikan, minat, atau motivasi, (Esman dan Uphoff,
1984; Fett, 1972; Goulet, 1983; Hyman dan Sheatley, 1974; Shingi
dan Mody, 1976; Techenor, dkk, 1973).
Memang masyarakat yang sedang membangun sangat
berkepentingan dengan inovasi, disertai dengan penemuan-penemuan
atau rangsangan-rangsangan, baik yang berupa gagasan, tindakan atau
informasi yang relevan dengan kebutuhannya. Apabila faktor ini
dipenuhi, maka peran serta masyarakat akan lebih tergugah.
Penekanan pada peran serta atau partisipasi masyarakat sangat popular
dalam program pembangunan, yang menunjukkan adanya komunikasi
umpan balik (komunikasi resiprokal ).
Umpan balik dapat diperoleh dengan sengaja, misalnya dengan
mengadakan riset tentang salah satu unsur kepariwisataan. Riset
mengenai kepariwisataan merupakan umpan balik yang dicari dan
dilakukan secara formal. Sebab masih ada umpan balik yang bersifat
non-formal. Misalnya dengan adanya keluhan-keluhan dari
masyarakat yang mengunjungi suatu obyek wisata, karena fasilitas
yang tidak bersih atau keadaan kurang aman di tempat rekreasi,
kurangnya informasi rambu-rambu di tempat strategis, perlunya buku
petunjuk/guide, dan lain-lain.
Menurut kaum behaviorism, orang cenderung mengulangi
kembali pengalaman yang menyenangkan selama hidupnya. Tugas
usaha pariwisata adalah menciptakan kondisi yang menyenangkan ini.
Tidak hanya mengadakan perbaikan obyek-obyek wisata, tetapi
mampu memasyarakatkan pemahaman yang baik mengenai psikologi
wisatawan melalui komunikasi antar budaya, sebab bukan lingkungan
20 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
yang menyenangkan dan menyusahkan kita, tetapi persepsi kita yang
memberi makna terhadap lingkungan tersebut.
Kemudian dalam meninjau persiapan infrastruktur komunikasi
informasi, data di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur
komunikasi informasi yang telah ada sudah dapat dikatakan “siap”
untuk menyongsong “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”,
artinya bahwa kata “siap” ini belum dapat dikatakan siap yang
sesungguhnya sesuai dengan tingkat kebutuhan akan alat komunikasi
informasi seputar dunia wisata di Kota Manado.
Berkaitan dengan obyek wisata yang ditawarkan, terlihat baik
responden maupun informan menghendaki tidak hanya wisata bahari
yakni Pulau Bunaken yang ditawarkan, tetapi juga wisata lain yang
saat ini belum dikelola secara baik namun cukup punya potensi untuk
dikembangkan sebagai alternatif pilihan yaitu Pulau Siladen, Pulau
Manado Tua kemudian misalnya keindahan kota sekitar Manado
seperti Kota Bunga Tomohon, Pantai Malalayang, kemudian Obyek
wisata lain di luar Kota Manado yang menarik seperti Bukit Kasih,
Danau Tondano, Makam Imam Bonjol, Rurukan, dan lain-lain.
Suatu kenyataan, bahwa keberhasilan dari program ini
bergantung pada daya tarik pribadi yang dirasakan oleh sebagian
khalayak. Hampir semua jenis informasi, tidak menjadi soal
bagaimana cara pelaksanaannya, akan tetapi diterima bergantung pada
hal ini. Intensitas dari kebutuhan yang pasti akan adanya informasi
adalah faktor yang merupakan kunci untuk memperkirakan tingkat
penerimaan suatu kampanye.
Di bawah faktor inilah elemen-elemen kualitatif dari pesan
yang akan disampaikan, dikonsepkan dan di produksi secara baik.
Program ini menggunakan gaya hiburan yang cukup tinggi guna
menghadirkan atau mengangkat keadaan yang sesungguhnya melalui
bahasa yang mampu dipahami serta berasal dari sumber yang
terpercaya, meskipun durasinya pendek namun program ini
dipublikasikan lewat jaringan luas ke seluruh jaringan komunikasi
informasi yang telah dipercaya dan mempunyai kredibilitas.
Dengan demikian WOC (World Ocean Converence) atau
Konferensi Kelautan Sedunia yang akan dilangsungkan tanggal 5-11
Mei 2009, sangat membantu implementasi MKPD 2010, sebab untuk
mendukung kesuksesan WOC tersebut pemerintah dan stakeholder
sudah melakukan persiapan-persiapan yang selanjutnya dapat
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 21
dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mendukung MKPD tahun
2010.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa kesiapan infrastruktur komunikasi informasi
Kota Manado Menyongsong Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun
2010 dapat dikatakan belum siap, karena masih kurangnya
ketersediaan alat komunikasi informasi yang terfokus untuk
memberikan informasi Seputar Dunia Wisata Kota Manado sebagai
pusat informasi.
Saran-saran
1. Kepada Pemerintah Kota Manado, perlu adanya kerja keras dalam
penyediaan infrasruktur komunikasi informasi yang terfokus pada
info tentang dunia wisata di Kota Manado. Seperti : Penambahan
Baliho, Spanduk, Brosur, Leaflet, Banner, di lokasi-lokasi
strategis.
2. Pemerintah Kota Manado diharapkan dapat bekerjasama dengan
pihak swasta yang terkait dengan dunia wisata di Kota Manado
untuk bersama-sama mengusahakan Pusat Informasi Wisata dalam
rangka Program “Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010”.
3. Perlunya segera menyediakan tenaga yang terampil
mengoperasikan peralatan komunikasi informasi yang semakin
canggih (SDM IT), termasuk kemampuan bahasa Inggris sebagai
bahasa Internasional.
4. Pemerintah Kota Manado perlu memberikan alternatif obyek
wisata dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kota maupun
Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Utara, yang mempunyai
obyek wisata yang layak jual sebagai satu paket wisata. Misalnya
membuat MOU atau pertukaran informasi antar Kabupaten/Kota
dengan Pemkot Manado yang ada di Propinsi Sulawesi Utara
tentang infrastruktur komunikasi dan informasi, serta seputar
obyek pariwisata yang belum dikelola dengan baik.
5. Perlu segera dilakukan sosialisasi yang sifatnya sustainable di era
globalisasi, salah satunya dengan memasukkan program MKPD
2010 ke dunia maya (internet) secara berkesinambungan.
22 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
DAFTAR PUSTAKA
Betinghaus EP. 1973. Persuasive Communication. New York : Holt,
Rinehart and Winston, Inc.
Sawyer, 2003. Berkomunikasi Dengan Teknologi. Jakarta :
Gunadarma.
Suryadarma, 2003. Perkembangan Teknologi Informatika. Bandung :
Armico.
Fransisca, Wesart, 2004. Komputerisasi dan Perkembanganny.
Bandung : Yrama Widya.
Haris, Blade, 2005. E-Governance Dalam Era Informasi. Jakarta :
Sentra Informasi Mandala.
Ginsu, A, 2006. Birokrasi dan Teknologi informatika. Jakarta : Elex
Media Komputindo.
Ishadi, 2006. Teknologi Komputerisasi Dalam Pemerintahan.
Bandung : Yrama Widya.
Peraturan Perundang-undangan :
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Teknologi
Informasi.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Manado No.04 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2005-2010.
Bacaan Tambahan :
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Depdikbud
Jakarta, 1990.
Harian Manado Post : Rabu, 16 Juli 2008, halaman 4.
Harian Manado Post : Jumat, 3 Oktober 2008, halaman 8.
Artikel judul “ Mewujudkan Manado Tujuan Utama Pariwisata ”
Oleh Drs. Johnny Karinda.
Harian Komentar Manado.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 23
KONSTRUKSI IDENTITAS SOSIAL
KAUM REMAJA MARJINAL
(Studi Kasus di Kalangan Remaja Pengamen Jalanan
di Purwokerto)
Agus Ganjar Runtiko*
Abstraksi
Kaum pengamen jalanan selama ini selalu identik dengan
ketidaktertiban. Di mana-mana para pengamen ini selalu
„ditertibkan‟. Kebanyakan mereka diarahkan untuk menghuni panti-
panti yang telah didirikan oleh pemerintah. Namun, jumlah mereka
dari tahun ke tahun tidak pernah menyusut. Dengan mengkaji tentang
konstruksi identitas sosial mereka, memahami faktor-faktor penyebab,
respon remaja pengamen ketika penertiban akan membentuk model
penanganan yang lebih tepat terhadap mereka.
Kata kunci : identitas sosial, remaja marjinal.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemberitaan di media massa seputar penertiban pengamen
jalanan sudah bukan hal asing lagi ditemui di negeri ini. Lewat berita
di surat kabar atau tayangan televisi, kita disuguhi pemandangan yang
memprihatinkan bahwa ternyata tidak sedikit kaum muda atau remaja
yang tidak bisa meneruskan sekolah dengan berbagai sebab tentunya
dan harus memilih mengisi hidupnya dengan mengamen. Wacana
yang berkembang di media, tidak jauh dari persoalan klasik bahwa
pengamen adalah salah satu faktor pengganggu ketertiban dan
kenyamanan masyarakat.
Ironisnya, jumlah remaja pengamen jalanan dari tahun ke
tahun cenderung mengalami peningkatan. Secara kuantitatif, jumlah
remaja pengamen jalanan di Purwokerto menurut data dari Sub Dinas
* Agus Ganjar Runtiko, S.Sos., adalah pengajar di FISIP Universitas Jendral
Sudirman Purwokerto Jurusan Ilmu Komunikasi.
24 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Kesejahteraan Sosial Banyumas tahun 2003 menunjukkan angka
mencapai 723 remaja, sementara pada tahun 2000 hanya terdapat 354
remaja (Suara Merdeka, Senin, 24 Agustus 2003). Khusus di
Purwokerto, pada tahun 2003 terdapat 214 remaja pengamen jalanan.
Jumlah ini menunjukkan semakin banyaknya remaja yang memilih
jalanan sebagai tempat mencari uang dan menjalani
kehidupannya.
Bila kita mencoba menengok kehidupan remaja pengamen
sesungguhnya kita perlu tergugah untuk bisa menanganinya dengan
pendekatan yang tidak semata represif. Para pengamen jalanan ini
tidak harus selalu ditempatkan sebagai semata penyakit sosial tanpa
melihat terlebih dahulu akar penyebab timbulnya tindakan seperti itu.
Bagaimanapun remaja pengamen adalah sebagian generasi bangsa
yang kepada mereka pemerintah dan lembaga sosial lainnya turut
bertanggung jawab mempersiapkannya agar tidak terlanjur menjadi
generasi tanpa masa depan. Mereka tidak perlu dianggap semata-mata
sebagai penyakit atau seonggok persoalan yang harus disingkirkan
melainkan harus ditempatkan sebagai bagian masyarakat yang
memiliki hak hidup yang sama dan tentu saja memiliki segenap
kemungkinan yang sama untuk tumbuh dan berkarya di negeri ini.
Berangkat dari fenomena inilah maka penelitian ini beranjak.
Dengan mencoba mengkaji persoalan dengan pendekatan
konstruktivis penelitian ini mencoba memahami secara mendalam
bagaimana kaum remaja pengamen ini membangun/mengkonstruksi
identitas sosial mereka.
Melakukan kajian dengan fokus sebagaimana dimaksud di atas
maka setidaknya akan diperoleh konsepsi pemahaman menurut
kacamata mereka sendiri tentang siapa dan bagaimana identitas sosial
kaum remaja pengamen ini. Informasi ini akan sangat bermanfaat
sebagai dasar bagi perumusan berbagai kebijakan pemerintah yang
utamanya ditujukan untuk kaum remaja terpinggirkan ini.
Pertanyaan Penelitian
Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana proses pembentukan/konstruksi identitas sosial di
kalangan remaja pengamen jalanan di Purwokerto?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga kaum remaja ini
memilih tinggal di jalanan dan menjadi pengamen?
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 25
3. Bagaimana respon kaum remaja pangamen terhadap segala bentuk
tindakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah?
4. Bagaimana model penanganan terhadap persoalan remaja
pengamen jalanan yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga-
lembaga terkait?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini mengarahkan kajiannya secara teliti mengenai :
1. Proses pembentukan/konstruksi identitas sosial di kalangan remaja
pengamen jalanan di Purwokerto
2. Faktor-Faktor penyebab sehingga kaum remaja ini memilih tinggal
di jalanan dan menjadi pengamen
3. Model penanganan terhadap persoalan remaja pengamen jalanan
yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait
4. Respon kaum remaja pangamen terhadap segala bentuk tindakan
penertiban yang dilakukan oleh pemerintah
Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Kajian Pustaka
Penelitian mengenai remaja marjinal, atau lazim disebut
sebagai anak-anak jalanan salah satunya dilakukan oleh Astutik
(2004). Penelitian yang membahas mengenai model pembinaan anak
jalanan ini memilih perspektif pemerintah dalam membina anak
jalanan. Artinya disini, perspektif yang diambil adalah dari
stakeholder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan
pembinaan anak jalanan selama ini sesuai dengan standar layanan dari
Dinas Sosial. Terdapat variasi pengembangan sesuai kebutuhan di
lapangan menurut perkiraan para penentu dan pelaksana program.
Semuanya dinyatakan masih dalam taraf proses program pembinaan
dengan menggunakan gabungan beberapa pendekatan yang ada.
Selain mengenai anak jalanan, penelitian yang berhubungan
adalah mengenai konsep diri, yang dilakukan oleh Rahman (2004).
Penelitian yang berlokasi di Jakarta ini berfokus pada konsep diri
pengguna narkoba. Kesimpulan penelitian ini antara lain adalah bahwa
para pengguna narkoba ini rata-rata mempunyai konsep diri yang
negatif, diantaranya adalah rendah diri. Selain itu para pengguna
narkoba juga cenderung susah untuk kembali ke hubungan
komunikasi antarpribadi yang normal seperti sebelum memakai
26 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
narkoba, sekali lagi karena diakibatkan konsep diri mereka yang
negatif.
Kerangka Pemikiran
1. Remaja Pengamen dalam Tinjauan Sosiologis
Remaja pengamen di kawasan perkotaan secara teoritis dapat
ditinjau dari perspektif struktur sosial dalam masyarakat. Kelompok
ini bisa dikatakan sebagai kelas rendah di perkotaan.
Radikal, kriminal, apatis dan patologis adalah kata-kata yang sering
dilabelkan pada kelas proletar marjinal oleh baik kelas borjuis maupun
kelas menengah. Gambaran negatif tentang kelas proletar marjinal ini
beberapa bahkan didapatkan oleh seorang antropolog (Lihat Lewis,
dalam Keesing, 1992 : 233 – 249). Labelisasi seperti ini akan terus
menjebak kelas proletar marjinal ke dalam kemiskinan struktural (lihat
Soemardjan, dalam Alfian et. al., 1980 :1-11), sehingga mereka
semakin tak berdaya untuk keluar dari kungkungan marjinalisasi
struktural.
UNICEF (dalam Musyarofah, 2006 : 27) mengelompokkan
remaja/anak-anak yang mencari penghidupannya dijalanan sebagai on
the street dan of the street. Pengelompokan tersebut terkait dengan
periode mereka dijalanan. Dalam kategori on the street, adalah remaja
/anak-anak yang berada dijalanan dalam tempo sesaat. Mereka antara
lain terbagi dalam kelompok :
a. Remaja/Anak-Anak Miskin Perkotaan
Kelompok ini berasal dari dalam kota dan masih tinggal bersama
orangtuanya, yang merupakan penduduk asli maupun para
urbanisan yang mendiami tempat-tempat kumuh (slum area)
perkotaan. Sebagian anak-anak ini masih sekolah dan berada di
jalanan sekadar mencari tambahan bagi nafkah keluarga.
b. Remaja/Anak-Anak yang memberontak dan lepas dari orangtua
Kelompok ini biasanya masih memiliki orangtua, tetapi
memberontak dan sepenuhnya melepaskan diri dari keluarga.
c. Remaja/Anak-Anak dari Luar Kota
Kelompok ini tinggal bersama teman sebaya dan orang yang lebih
tua, sementara orangtua berada di kampung. Remaja kelompok ini ada
yang memiliki „bos‟ terkait dengan pekerjaan mereka, adapula „bos‟
sebagai penguasa kelompok tempat ia berada, yakni orang yang
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 27
mewajibkan setoran untuk kelangsungan pekerjaan atau jaminan
keamanan.
Sedangkan, kelompok yang dikategorikan sebagai of the street,
adalah mereka yang berpartisipasi penuh baik secara ekonomi maupun
sosial di jalanan. Mereka tidak mempunyai rumah, tinggal di emperan
toko, stasiun, terminal, kolong jembatan atau taman-taman kota.
Umumnya berasal dari keluarga yang berkonflik atau tidak tahu siapa
orang tuanya dan dimana keluarganya.
2. Konsep Diri dalam Perspektif The Social Construction Of
Reality
Konsep diri menjadi perhatian utama tidak saja bagi teoritisi
yang menggeluti fenomena sosial dalam perspektif interaksi simbolik
namun juga bagi para ahli yang mengembangkan teori konstruksi
realitas sosial. Premis dasar teori ini tentang self adalah bahwa
seseorang memahami dirinya sendiri dengan menggunakan “teori”
yang mendefinisikan dirinya (Littlejohn, 2002).
Adapun thesis dasar tentang “realitas” menurut teori konstruksi
realitas sosial adalah bahwa “reality is not an objective set of
arrangements outside ourselves, but is constructed through a process
of interaction in groups, communities, and culture” (Littlejohn, 2002).
Konsep diri termasuk “realitas”, yang sesungguhnya adalah
hasil konstruksi sosial. Demikian menurut Rom Harre (seperti dikutip
Littlejohn, 2002: 168) “the idea of self as a socially constructed
“object” is profound and important in the constructionist movement”.
Selanjutnya masih menurut Rom Harre, terdapat dua sisi yang
melekat pada personalitas seseorang : yakni Person dan Self. Person
adalah karakteristik yang melekat pada diri seseorang yang bisa dilihat
atau dikenali oleh publik yang ditandai oleh beberapa atribut dan
karakter yang relatif mapan dalam sebuah kebudayaan atau kelompok
sosial tertentu. Sedangkan Self adalah gambaran pribadi seseorang
atas dirinya sendiri. Ini didapat dari interaksi seseorang itu dengan
orang-orang lain.
Self terdiri dari seperangkat elemen yang bisa dikaji secara
relatif terpisah. Pertama, Display yakni sejauh mana aspek-aspek
dalam diri seseorang bisa diketahui oleh publik atau sebaliknya tetap
menjadi bagian pribadi seseorang. Kedua, Realization, sejauh mana
gambaran terhadap diri seseorang diyakini berasal dari orang itu
28 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
sendiri atau dari kelompok-keompok yang ada di sekeliling dia.
Ketiga, Agency : sejauh mana kekuatan aktif menjadi atribusi diri
seseorang. Di sini ada dua elemen; Active elemen seperti percakapan
dan Passive elements seperti mendengarkan.
3. Identitas Sosial
Identitas sosial berkenaan dengan bagaimana seseorang
menggunakan kelompok sosial tertentu yang dipandangnya dapat
memberikan perasaan positif tertentu pada dirinya. Secara umum
konsep ini diterjemahkan menjadi 3 (tiga) ide utama, yaitu
kategorisasi, identifikasi dan komparasi (Tajwel, 1978)
Menurut Hogg & Abrams (1998) pada dasarnya proses
kategorisasi menghasilkan persepsi stereotype, yaitu persepsi terhadap
anggota suatu kelompok yang memiliki karakteristik tertentu yang
dapat dijadikan acuan untuk membedakannya dari kelompok lain.
Berkaitan dengan hal ini, proses kategorisasi merupakan proses
pengelompokkan obyek yang dilakukan untuk memahami obyek
tersebut. Kategorisasi individu, merupakan proses pengelompokkan
individu dalam upaya memahami lingkungan sosialnya. Penggunaan
kategorisasi misalnya murid, guru, Muslim, Kristiani, hitam, putih,
dan seterusnya. Sedangkan proses identifikasi terjadi pada saat
seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tempat ia
bergabung. Tajfel (1978) menyatakan bahwa, identitas sosial
dikonsepsikan dengan mengaitkan pengetahuan individu tentang
perasaan memiliki suatu kelompok sosial tertentu dan emosi, juga
evaluasi signifikan yang dihasilkan dari keanggotaan suatu kelompok.
Setiap individu mengidentifikasikan dirinya lebih dengan in-
groupnya dan hal ini akan mengurangi perbedaan di antara diri dan in-
groupnya. Jika terjadi peningkatan identifikasi terhadap kelompok (in-
group). Seseorang merubah dari kutub personal ke intergorupnya.
Seseorang menggunakan penanda adalah dalam rangka mencari
konsep diri yang dipandang positif, dan hal ini merupakan bagian dari
fungsi normal psikologi seseorang. Untuk menghadapi dunia ini,
individu membutuhkan pandangan positif yang melekat pada sikap
dan perilaku dirinya. Pernyataan tentang baik, buruk, pintar, bodoh,
bersih, tinggi dan lainnya lahir dari adanya komparasi (perbandingan).
Identitas sosial menghadirkan relasi antar kelompok dalam
konteks sosial yang nyata (Tajfel 1978; Tajfel & Turner 1979) di
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 29
mana secara komprehensif memaparkan relasi antar kelompok dalam
perubahan sosial dalam masyarakat yang terkelompokkan secara
sosial, konflik sosial, serta relasi antar kelompok. Secara sederhana,
masyarakat membutuhkan identitas sosial positif yang menuntut
mereka untuk membangun nilai pembeda yang positif bagi kelompok
mereka sendiri yang dibandingkan dengan kelompok lain.
Keanggotaan dalam kelompok itu membuat individu memiliki
identitas diri dan self esteem. Pada saat kelompok memperolah
kesuksesan, self esteem individu akan ikut naik, dan sebaliknya ketika
kelompok mendapatkan kegagalan maka self esteem individu turut
terancam. Pada keadaan itu individu merasa harus mempertinggi
ketertarikan kepada kelompoknya dan meningkatkan rasa nyaman
kepada kelompok lain. Alih-alih identitas personal yang berhubungan
dengan perilaku interpersonal yang berarti perbedaan di antara diri
dan orang lain maka identitas sosial terkait dengan perilaku
intergroupnya yang berarti perbedaan di antara kelompok atau „kita‟
dan „mereka‟
Identitas sosial, dalam bentuk kategorisasi seperti nasionalitas,
religiusitas, gender, profesi, etnisitas, atau orientasi politik,
terinternalisasi dan membentuk suatu bagian penting yang potensial
dari self-concept seseorang di mana fokus pada konsep ini adalah pada
definisi „ke-kita-an‟ (we-ness) suatu anggota kelompok dalam konteks
„kita milik dari satu kelompok‟.
Konsepsi awal menunjukkan bahwa keyakinan kelompok
termasuk semua keyakinan terdapat di dalam alam pikir individu.
Namun saat ini, konsepsi tersebut digambarkan melalui fenomena
yang dikenal luas, di mana anggota kelompok berbagi keyakinan dan
keyakinan itu dipandang menghadirkan dasar bagi identitas sosial
anggota, selain itu juga diartikan sebagai esensi kelompok.
4. Cultural Biases dalam Intercultural Communication
Konsepsi teoritik yang dipakai dalam melihat respon kaum
remaja pengamen jalanan dalam menghadapi tindakan pemerintah
diambil dari perspektif teori komunikasi antar budaya.
Komunikasi antarbudaya didefinisikan sebagai interaksi di
antara orang-orang yang setidaknya memiliki satu perbedaan budaya
di antara mereka (Lustig & Koester, 2003). Dalam konteks
komunikasi antar budaya semacam ini akan membawa persoalan
30 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
dalam hal rasa aman, kenyamananan dan tingkat sejauh mana kita bisa
memprediksikan lawan interaksi kita. Terdapat beberapa situasi dan
nilai-nilai yang kemudian memengaruhi respon atau persepsi
seseorang terhadap orang lain yang berbeda budayanya. Dalam
konteks penelitian ini, kaum remaja pengamen jalanan diasumsikan
memiliki identitas kultural yang berbeda dengan misalnya kaum
remaja umumnya yang bisa menikmati kehidupan rumah tangga biasa
dan menjalankan aktivitas hidup layaknya remaja mapan (sekolah, dan
lain-lain). Faktor–faktor yang memengaruhi proses pengolahan
informasi tentang orang lain dalam konteks komunikasi antarbudaya
lalu diidentifikasi sebagai aspek yang dikenal dengan cultural biases.
Secara singkat, bagan kerangka pemikiran penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Metode Penelitian
a. Bentuk dan Strategi Penelitian
Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang
lebih menekankan pada masalah proses dan makna (konstruksi
identitas sosial), maka jenis penelitian dengan strateginya yang
terbaik adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 31
akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan
deskriptif teliti dan penuh nuansa, yang lebih berharga daripada
sekedar pernyataan jumlah atau pun frekuensi dalam bentuk
angka.
Strategi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi
kasus, dan karena sasaran studi kasus ini hanyalah di kalangan
kaum remaja pengamen jalanan. Maka studi kasus ini termasuk
penelitian dengan strategi kasus tunggal (Yin, 1987). Selain itu,
karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam
usul penelitian ini maka jenis strategi penelitian kasus ini secara
khusus bisa disebut studi kasus terpancang (embedded case study
research).
b. Jenis dan Informasi Sumber Data
Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan
dikaji dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif.
Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data, dan jenis
sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini
meliputi:
1. Informan atau nara sumber, dalam hal ini adalah kaum
remaja pengamen jalanan di Purwokerto, pemerintah
Kabupaten Banyumas, dan lembaga terkait.
2. Dokumen, baik hasil liputan media atau browsing internet
c. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber
data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara mendalam (in-depth interviewing)
Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak
terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan bisa
dilakukan berulang pada informan yang sama (Sutopo, 2002)
2. Observasi langsung
Observasi ini dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai
observasi berperan pasif (Spradley, 1980)
3. Focus Group Discussion (FGD).
Metode ini bermanfaat untuk memperoleh data bagaimana
individu sebagai bagian dari sebuah kelompok mendiskusikan
sesuatu topik atau isu tertentu, jadi tidak semata melihat
32 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
informan sebagai individu. Dengan kata lain, FGD diterapkan
untuk memahami orang menanggapi berbagai pandangan
orang-orang lain dalam kelompok diskusi, dan bagaimana
kemudian informan membangun sebuah pandangan tersendiri
berdasarkan interaksi yang dilakukannya dalam sebuah
kelompok. (Bryman, 2001)
Sampling
Penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan
yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan
konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan pribadi peneliti,
karakteristik empirisnya, dan lain-lain. Oleh karena itu cuplikan yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat purposive
sampling, atau lebih tepat disebut sebagai cuplikan dengan “criterion-
based selection” (Goetz & Le Compte, 1984). Dalam hal ini peneliti
akan memilih informan yang dipandang paling tahu, sehingga
kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan
kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Patton,
1980).
Pengembangan Validitas
Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan
dikumpulkan dalam penelitian ini maka diperlukan teknik
pengembangan validitas data sebagaimana biasa digunakan dalam
penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi. Dari empat teknik
triangulasi yang ada (Patton, 1980), hanya akan digunakan tiga di
antaranya yakni (1) Triangulasi data (sumber) yaitu mengumpulkan
data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. (2) Triangulasi
peneliti yaitu mendiskusikan data yang diperoleh dengan peneliti lain
dalam hal ini adalah rekan sejawat dalam sebuah forum diskusi
informal yang menyajikan draft awal hasil penelitian lapangan. (3)
Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih
dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.
Model Analisis
Proses analisis dalam penelitian kualitatif pada dasarnya
bersifat induktif di mana analisis dilakukan secara bersamaan dengan
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 33
proses pelaksanakan pengumpulan data. Ada tiga komponen analisis
yang saling berkaitan dan berinteraksi, tak bisa dipisahkan dengan
kegiatan pengumpulan data yaitu reduksi data, sajian data dan
penarikan kesimpulan. Model analisis yang akan dipakai dalam
penelitian ini adalah model analisis interaktif (Miles dan Huberman
1984). Dalam model analisis ini, tiga komponen aktivitasnya
dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data
sebagai suatu proses siklus. Dalam melaksanakan proses ini peneliti
aktivitasnya tetap bergerak di antara komponen analisis dengan
pengumpulan datanya selama proses pengumpulan data masih
berlangsung. Kemudian selanjutnya peneliti hanya bergerak di antara
tiga komponen analisis tersebut sesudah pengumpulan data selesai
pada setiap unitnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa
dalam penelitian ini.
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Eks-Kota Administratif Purwokerto terletak di sebelah barat
daya Propinsi Jawa Tengah, dan merupakan bagian dari Kabupaten
Banyumas. Terletak di antara garis Bujur Timur 108° 39' 17'' sampai
109° 27' 15'' & di antara garis Lintang Selatan 7° 15' 05'' sampai 7° 37'
10'' yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Jumlah
penduduk Purwokerto sebanyak 239.532 jiwa, yang terbagi menjadi
73.019 jiwa di Kecamatan Purwokerto Selatan, 52.922 jiwa penduduk
Kecamatan Purwokerto Barat, 63.360 jiwa penduduk Kecamatan
Purwokerto Timur, dan 50.231 penduduk Kecamatan Purwokerto
Utara (www.banyumas.go.id diakses pada 2 Juli 2008).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Pelaku Penelitian dan Informan Pendukung
Terdapat beberapa orang remaja marjinal yang diwawancarai
dalam proses penelitian ini. Pertama, Andri yang berusia 24 tahun.
Andri adalah seorang lulusan SMU tahun 2001, semenjak tahun 2002
sudah „mangkal‟ di pertigaan Sri Ratu Purwokerto. Andri merupakan
34 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
salah seorang remaja marjinal yang selalu memperhatikan
perkembangan politik dan berita yang terjadi saat ini.
Pelaku penelitian kedua adalah Jalak, berusia 21 tahun. Jalak
baru lulus STM tiga tahun lalu (2005). Alasan Jalak masuk STM
adalah agar bisa meneruskan pekerjaan bapaknya di bengkel. Jalak
mengerti sedikit-sedikit tentang mesin. Jalak hidup dalam keluarga
yang utuh, artinya bukan keluarga berantakan.
Pelaku penelitian ketiga adalah Tomi, 27 tahun. Tomi ini
merupakan salah satu anggota „senior‟ dalam komunitas mereka.
Namun, saat disebut sebagai ketua dalam komunitas, Tomi
menolaknya. Alasannya bahwa komunitas tersebut muncul untuk
menolak segala bentuk keteraturan (komunitas remaja marjinal yang
peneliti masuki ternyata adalah komunitas Punk dan komunitas
Skinheads), sehingga dalam komunitasnya tidak dikenal adanya ketua,
wakil atau sebagainya.
Pelaku penelitian keempat adalah Anjar. Anjar hanya
bersekolah sampai tingkat SMP saja. Keluarga yang berantakan
mendorongnya untuk masuk ke jalanan. Awalnya dia mengamen,
berdagang asongan, selanjutnya jalanan menjadi rumahnya, dan dia
salah seorang anggota komunitas yang paling rajin mangkal.
Informan pendukung dalam penelitian ini antara lain adalah
Pak Rujito. Pak Rujito berusia 52 tahun. Beliau adalah Ketua RW di
Kampung Sri Rahayu, atau lebih banyak dikenal sebagai Kampung
Dayak. Kampung Dayak sendiri merupakan sebuah kampung yang
terletak di belakang terminal lama Purwokerto. Di kampung ini
terdapat banyak komunitas marjinal, dan memang kampung ini identik
dengan dunia marjinal; seperti wanita tuna susila, waria, serta anak-
anak jalanan.
Informan pendukung kedua adalah Pak Budi. Pak Budi adalah
pemilik ruko yang terasnya sering dijadikan tempat mangkal oleh
anak-anak komunitas. Pak Budi sampai hapal siapa-siapa yang sering
mangkal, bagaimana tingkah polah mereka, serta perbedaan-
perbedaan antara beberapa komunitas yang mangkal di depan rukonya
tersebut.
Informan pendukung ketiga adalah Bapak Adi. Bapak Adi
adalah pegawai Dinas Sosial yang sering berhubungan dengan anak-
anak jalanan, waria dan sebagainya. Pak Adi telah bekerja di Dinas
Sosial Purwokerto semenjak tahun 1991.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 35
Masalah Kaum Remaja Marjinal
Masalah kaum remaja marjinal tidak hanya dirasakan
pemerintah atau masyarakat semata, namun juga dirasakan oleh
mereka sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh informan pendukung,
yakni Pak Rujito, seorang sesepuh di Kampung Sri Rahayu, yang
dikenal sebagai tempat berkumpulnya para kaum marjinal, “Kadang-
kadang malah (kegiatannya di rumah singgah) ndak sesuai.
Sebenarnya disuruh bertempat ke rumah singgah buat istirahat, tapi
malah digunakan yang lain, kadang-kadang fasilitas disitu juga hilang.
Mereka yang kesitu seringnya nggak punya identitas, sehingga
bingung mendatanya.”
Masalah kaum remaja marjinal ini juga muncul berkaitan
dengan interaksi sesama mereka. Sebagaimana diceritakan oleh Jalak,
“(Kita itu) akrab, tapi kalau ada masalah apa gitu dipanjang-panjangin.
Misalnya pakaian, apa kaos atau sepatu, kan punyanya cuma sedikit,
jadi sering barter. Aku pakai ini, kamu pakai itu, terus lama nggak
balik-balik, ilang atau dibarter sama yang lain, jadi masalah. Jadi
kayak masalah-masalah sepele gitu.”
Keberadaan rumah singgah bagi kaum remaja marjinal ini
nampaknya juga merupakan masalah tersendiri. Karena rumah
singgah yang biasanya dijadikan tempat mereka berkumpul ternyata
sudah tidak difungsikan lagi, seperti kata Pak Rujito, “Dulu kan ada
rumah singgah, tapi sekarang rumah singgahnya sudah nggak ada,
sudah dirusak sama anak-anak. Sekarang mereka sudah ndak punya
rumah singgah. Jadi nggak mesti kumpul-kumpul, kumpul-kumpulnya
ya kalau ada kegiatan-kegiatan.”
Konsep Diri
Terdapat beberapa nilai yang menjadi bentuk-bentuk identitas
sosial. Salah satunya adalah keharusan untuk berkarya. Anjar, salah
seorang pelaku penelitian mengatakan, “Jangan bicara kematian dong,
belum mempunyai karya nih. Kalau mati, apa yang ditinggalkan di
dunia ini? Harus meninggalkan karya. Sosialisme kamu, komunisme
kamu itulah karya kamu!”
Komunitas remaja marjinal ini juga bukan tidak percaya
Tuhan. Terbukti, ketika diwawancara mereka juga sempat
membicarakan puasa. Seperti Anjar yang mengatakan, “Kalau puasa
aku nggak kaget, masalah laper-laper aku nggak kaget, sebelum bulan
36 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
puasa sering nggak makan, sering laper.” Tetapi konsep kepercayaan
kepada Tuhan ini tidak diaplikasikan sebagaimana umumnya pemeluk
agama. Seperti yang dikatakan Jalak, “Kalau aku nggak puasa sih, tapi
ada orang baik yang ngasih makananlah, rokok, kadang-kadang duit.
Pernah dulu waktu tidur disini, pas saur ada orang yang ngasih
makanan.” Konsep kepercayaan kepada Tuhan diaplikasikan oleh para
remaja marjinal sebagai perilaku sosial manusia. Sehingga, mereka
cenderung membedakan orang berdasarkan terminologi „orang baik‟
dan „orang tidak baik‟. „Orang baik‟ menurut remaja marjinal ini
adalah orang yang mempunyai rasa keberpihakan kepada mereka.
Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak menaruh keberpihakan
kepada mereka akan mendapat label sebagai „orang tidak baik‟.
Uniknya konsep baik yang kita kenal dengan simbolisasi „kanan‟,
tidak dikenal mereka secara sama, sebagaimana yang dikatakan Tomi,
“Malem kalau mau di sini, ya disini, kalau mau pulang ya pulang.
Kalau di sini paling dibelakang sana, di empang. Masalahnya kalau
tidur di sini (di emper toko) nanti di garuk juga sama orang-orang
kanan (orang-orang yang tidak mau kehilangan tempat tinggal
mereka).” Para remaja marjinal ini mengkonstruksi identitas sosial
mereka sebagai orang kiri, orang yang senantiasa selalu berbagi.
Konstruksi identitas sosial yang mereka miliki selanjutnya
adalah bahwa sebenarnya mereka tidak begitu menikmati menjadi
remaja marjinal. Sebagaimana yang dikatakan Jalak, “Pernah dulu aku
ditanyain, cari kerja (aja) kenapa mas? Apa enak jadi pengamen mas?
Gimana jawabnya, bingung kan!” Tomi ketika itu menambahkan, “Ya
ngomong enak bae.” Bahkan Jalak merasa bahwa kehidupannya saat
ini merupakan titik nadhir, bahwa dia sedang berada di bawah, bahwa
dia sedang merasa tidak enak, tapi dia mempunyai keyakinan
mengenai kemungkinannya kembali menikmati hidup, sebagaimana
dikatakannya, “Ya udah pernah sih ngrasain kerja, jadi orang enak.
Ada siang ada malem, ada baik ada buruk, ada kaya ada miskin, ada
gundul ada gondrong.”
Model Penanganan
Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan penanganan
anak-anak jalanan ini kepada Dinas Sosial. Pada keadaan-keadaan
tertentu, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dan kadang-
kadang juga melibatkan aparat kepolisian. Pelibatan aparat kepolisian
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 37
ini sebagai bentuk antisipasi apabila terdapat pelaku kriminal diantara
anak-anak jalanan. Selain dua instansi pemerintah ini, Dinas Sosial
juga bekerja sama dengan LSM yang bergerak dalam penanganan
anak jalanan. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Adi, Kabid Dinas
Sosial Banyumas, “Selama ini penanganannya bekerja sama dengan
pihak-pihak terkait, terutama dengan beberapa LSM. Ada beberapa
LSM yang sering berhubungan dengan kita, antara lain Biyung Emban
dan Kuncup Mas.”
Model penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial selama
ini melalui metode pemantian, yakni anak jalanan dirazia, untuk
dimasukkan ke panti-panti yang umumnya ada di luar kota. Di panti-
panti ini pembinaan dilakukan. Umumnya pembinaan itu berupa
materi-materi yang dianggap dapat membekali anak jalanan ini,
sehingga mereka tidak perlu kembali lagi ke jalan.
Selain panti-panti, bagi anak jalanan juga tersedia rumah
singgah. Sifat rumah singgah sendiri sebenarnya bukan merupakan
tempat pendidikan, melainkan tempat anak-anak jalanan ini
berkumpul saja. Tujuannya disamping anak-anak jalanan ini lebih
terkontrol, rumah singgah juga dapat digunakan pengelola untuk
menyisipkan pesan-pesan mengenai hal-hal positif. Pendekatan
penanganan di rumah singgah ini bermacam-macam, sesuai dengan
tujuan awal pendiriannya.
Penanganan terhadap anak jalanan juga meliputi perlakuan
terhadap keluarga mereka. Keluarga yang mandiri secara ekonomi
akan mengurangi peluang anak-anak turun ke jalan. Mengenai
masalah kesehatan, pemerintah memberikan anak jalanan ini Askeskin
untuk digunakan di Puskesmas-Puskesmas terdekat. Selain itu, anak
jalanan juga diberi penyuluhan mengenai HIV/AIDS, mengingat
perilaku seks mereka. Menurut Bapak Adi, anak jalanan ini mengenal
seks semenjak mereka berusia sepuluh tahun. Seks bebas dengan
berganti-ganti pasangan sudah mereka jalani pada usia belasan.
Lingkungan tempat tinggal mereka yang permisif terhadap perilaku
seks bebas membuat rentan munculnya penyakit menular seksual.
Persepsi terhadap Model Penanganan
Komunitas remaja marjinal ini umumnya mempunyai
pandangan negatif terhadap model penanganan dari pemerintah. Jalak
misalnya mengatakan, “(Ketika ditangkap Satpol PP) ada juga yang
38 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
nanyain, berapa hari nggak mandi, aku jawabnya tiga hari nggak
mandi. Namanya mandi itu kan urusan pribadi ya. Kita nggak mandi
apa dia mau mandiin kita, kita nggak makan apa dia mau nawarin,
nggak mungkin lah. Jarang orang baik itu jarang. (Ada yang) ngerasa
dirinya baik, tapi yang menilai itu kan orang lain.” Tampak dari hasil
wawancara ini, bahwa komunitas ini merasa penangkapan itu tidak
diperlukan. Bahkan, apabila ada aparat yang menangkap mereka,
dipandang tidak mempunyai kerjaan, disebut sebagai aparat murah,
“Yang nangkepin kita itu polisi yang murah. Soalnya nangkepnya
yang mudah dicari, kalau ngamen kan jelas lokasinya disini, tapi kalau
penjahat kan susah nangkepnya (karena lari terus).”
Saat ditanya apa saja yang mereka dapatkan ketika berada
ditempat penampungan sementara, Jalak mengatakan, “Paling kalau
ditangkep di omeli thok. Pernah dulu aku ditanyain, jadi cari kerja
(aja) kenapa mas? Apa enak jadi pengamen mas? Gimana jawabnya,
bingung kan?” Model penanganan yang seperti ini sebenarnya tidak
terjadi setiap saat. Hanya saja program pemerintah dirasakan hanya
sesaat-sesaat saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Rujito, Ketua
RW Kampung Sri Rahayu (dulu Kampung Dayak), “Pemerintah
biasanya kan memberikan program, tapi kan program itu kan seolah-
olah tidak berjalan, biasanya tidak kontinyu. Paling tahun ini program
apa itu saja. Seolah-olah sepintas hanya meluncurkan program saja.
Ya pihak manapun yang meluncurkan program tidak berkelanjutan, itu
ya hasilnya sesaat-sesaat. Jadi hasilnya juga sangat minim.”
Bentuk Komunikasi Antarpersona
Remaja marjinal ini kebanyakan membentuk komunitas secara
terbuka. Organisasi mereka tidak mengenal ketua atau pimpinan.
Struktur komuniksi antarpersona mereka sangat egaliter, sangat
terbuka. Namun, keterbukaan ini tidak berlaku untuk publikasi.
Publikasi, kata mereka, merupakan salah satu bentuk keterikatan
dengan aturan. Mereka tidak ingin dipublikasi.
Keseharian mereka berkumpul di pelataran gedung toko, atau
di tanah kosong ternyata tidak semata-mata berkumpul saja. Demikian
juga pilihan mereka untuk mabuk ternyata tidak semata-mata
kesenangan. Jadi berkumpul adalah salah satu bentuk progresifitas
mereka, bentuk pernyataan mereka, bentuk karya mereka. Mabuk pun,
kata Andi lagi, merupakan proses pencarian ide.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 39
Selain sehari-hari berkumpul di tempat-tempat yang telah
ditentukan, pada saat-saat tertentu mereka juga mengadakan
pertemuan. Tentu saja pertemuan ini bukan pertemuan rutin, maklum
mereka adalah komunitas yang antikemapanan. Pertemuan ini lazim
disebut sebagai „Punk Party‟ atau „Skinhead Party‟. Pertemuan seperti
ini biasanya diisi dengan pertunjukan musik-musik keras, serta tidak
lupa pesta minuman beralkohol. Bahkan, pesta minuman beralkohol
ini identik dengan rasa solidaritas antarsesama mereka. Minuman
beralkohol merupakan perekat komunikasi antarpersona mereka.
Kerekatan mereka dalam jalinan komunikasi antarpersona juga
sering diwarnai dengan konflik. Pemicu konflik ini kerapkali adalah
masalah-masalah yang sebenarnya dianggap sepele oleh mereka
sendiri. Seperti kata Jalak, ketika ditanya mengenai keakraban
antaranggota komunitasnnya, “(Hubungannya) akrab tapi, kalau ada
masalah apa gitu (sukanya) dipanjang-panjangin.” Mafhum kiranya
kalau konflik tersebut kadangkala menimbulkan perkelahian
antarsesamanya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Kaum remaja marjinal pengamen jalanan ini ada yang tidak
mengakui labelisasi kebanyakan orang. Mereka lebih suka
mendapatkan sebutan sebagai komunitas tertentu. Hal ini lebih
mengungkap realitas bahwa mereka juga ingin mendapatkan
pengakuan mengenai eksistensinya. Secara lebih dalam eksistensi
mereka sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlakuan adil.
Secara garis besar, kelompok atau komunitas remaja marjinal
pengamen jalanan terbagi menjadi tiga, yakni komunitas Punk,
komunitas Skinhead dan komunitas pengamen jalanan biasa.
Masing-masing mempunyai ciri khas. Komunitas Punk dicirikan
dengan pakaian yang seadanya, terkesan kumuh, akan tetapi sangat
peka dengan isu-isu sosial yang sedang berkembang. Komunitas
Skinhead, terkesan „lebih bersih‟ tetapi cenderung kurang responsif
dengan isu-isu sosial saat ini. Sedangkan komunitas ketiga,
cenderung tidak peduli dengan isu-isu sosial saat ini, namun lebih
mementingkan kebutuhan ekonomi.
40 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
2. Faktor-faktor yang menyebabkan para remaja pengamen jalanan ini
memilih tinggal di jalanan dan menjadi pengamen antara lain
adalah faktor keluarga yang berantakan, namun ada juga yang
karena faktor pengaruh teman. Pada komunitas Punk dan Skinhead,
remaja yang bermasalah dengan keluarga kurang begitu diterima.
Lain halnya dengan komunitas pengamen biasa, yang cenderung
tidak mempedulikan latar belakang keluarga teman-temannya.
3. Kaum remaja pengamen jalanan ini cenderung tidak suka dengan
perlakuan yang mereka terima dari pemerintah. Terbukti dengan
tindakan mereka yang selalu melarikan diri dari panti-panti yang
disediakan oleh pemerintah. Mereka menyebut pihak-pihak yang
berlaku 'kurang adil' itu sebagai 'orang jahat'. Sementara label
'orang baik' disematkan pada mereka yang dianggap 'tidak adil'.
4. Model penanganan yang ada selama ini adalah 'pemantian'. Yakni
para remaja pengamen jalanan dimasukkan di panti untuk dilatih
keterampilan-keterampilan guna bekal hidup mereka. Penanganan
pemerintah tidak hanya terpancang pada remaja pengamen jalanan
saja, tetapi juga terhadap keluarganya. Bentuk penanganan ini
berupa pengarahan atau penyuluhan.
Saran-Saran
1. Penanganan anak jalanan selama ini cenderung hanya dipandang
dari sebuah sisi, tanpa pernah berusaha mengungkap sisi lain dunia
mereka. Akibatnya bagaimanapun penanganannya, remaja
marjinal pengamen jalanan akan kembali beroperasi sebagaimana
biasa. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu berusaha menggali
hal-hal yang dirasakan oleh mereka.
2. Remaja marjinal pengamen jalanan perlu dipandang sebagai bentuk
pemiskinan struktural, bukan sebagai penyakit. Sehingga,
penanganan mikro saja, yakni penanganan yang hanya berorientasi
pada remaja pengamen jalanan saja tidak akan pernah
menyelesaikan masalah. Penanganan secara makro, yakni
penanganan secara menyeluruh, yang meliputi penanganan
terhadap remaja pengamen jalanan, penyuluhan kepada keluarga,
dan pelatihan bagi petugas lapangan yang berhubungan langsung
dengan mereka akan lebih memberikan hasil.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 41
3. Perlu dibangun sebuah komunikasi dialogis segitiga antara
pemerintah atau lembaga yang terkait, remaja marjinal pengamen
jalanan dan keluarga, sehingga diperoleh kesepahaman.
DAFTAR PUSTAKA
Tajfel, H. 1978. Differentiation between social gorups : Studies om
the social psychology of intergroup relation. London:
Academic Press.
Tajfel, H. & Turner, J.C. 1979. An Integrative Theory of Intergroup
Conflict : the Social Psychology of Intergroup relation. C.A.
Monterey : Brooks.
Alfian, Mely G. Tan, Selo Soemardjan 1980. Kemiskinan Struktural :
Suatu Bunga Rampai. Jakarta : YIIS
Patton, M.Q. 1980. Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills,
CA. :Sage Publication
Spradley. J.P. 1980. Participation Observation. New York, N.Y.:
Holt, Rinehart, and Winston
Tajfel, H. 1981. Human Groups and Social Categories: studies in the
Social Psychology. Cambridge : Cambridge University Press
Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. 1984. Ethnography And Qualitative
Design on Educational Research. New York, N.Y.: Academic
Press, Inc.
Turner, J.C. 1987. Rediscovering the social group : A Self-
categorization theory. Blackwell : Oxford
Yin, R.K. 1987. Case Study Research : Design and Methods. Beverly
Hills, CA : Sage Publications
Hogg, M.A.& Abrams, D. 1988. Social Identification: A Social
Psychology of Intergroup relations and Group Processes. U.K.
London : Routledge.
Keesing, Roger M. 1992. Antropologi Budaya : Suatu Perspektif
Kontemporer. (edisi kedua). Alih bahasa : R.G. Soekadijo.
Jakarta : Erlangga
Bryman, Alan. 2001. Social Research Methods. USA : Oxford
University Press.
Astutik, Dwi. 2004. Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan
melalui Rumah Singgah di Jawa Timur. Dalam
www.damandiri.or.id / search.php?q=Surabaya
42 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Littlejohn,Stephen W. 2002. Theories of Human Communication.
(7ed). USA : Wadsworth /Thomson Learning
Lustig, Myron W. & Koester, Jolene. 2003. Intercultural Competence
:Interpersonal Communication across Cultures. USA : Allyn
& Bacon
Musyarofah, D. Muhayatun 2006. Konsep Diri Anak Jalanan (Studi
Deskriptif Konsep Diri Anak Jalanan di Terminal Purwokerto
dengan Menggunakan Perspektif Interaksi Simbolik).
Purwokerto : tidak diterbitkan
Sumber lain :
Astutik, Dwi. 2004. Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan
Melalui Rumah Singgah di Jawa Timur. Dalam
www.damandiri.or.id, diakses 9 Juli 2008
Pemerintah Kabupaten Banyumas. Letak Geografis Banyumas. Dalam
www.banyumas.go.id, diakses pada 2 Juli 2008
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 43
PERILAKU POLITIK PEMILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
PERIODE 2008-2013
Irtanto*
Abstraksi
Penelitian ini bersifat eksploratif dengan pendekatan kualitif
bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi pemilih kandidat
gubernur Jawa Timur periode 2008-2013.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pemilih lebih banyak
karena kesamaan asal daerah, agama, kesamaan jenis kelamin
terutama pada budaya arek, putra daerah baik itu pada budaya
mataraman, budaya pendalungan dan budaya arek, pengalaman
memimpin organisasi, status pendidikan memiliki status ekonomi
tinggi, kalangan profesional, intelektual, isu-isu kampanye menarik,
visi dan misi kandidat, kredibilitas calon, dan program kerja yang
jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik pemilih pilgub
periode 2008-2013 antara lain seagama, teman, iklan politik, orang
yang lebih tua usianya. Sedangkan sumber informasi tentang pilgub
kebanyakan media massa televisi.
Kata Kunci: pemilihan gubernur, budaya, pilihan, kandidat.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Perilaku politik massa tentu tidak lepas dari pengaruh faktor
budaya dan sistem politik yang berlaku saat itu. Sistem politik di
Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan
bergantian rezim yang berkuasa. Di era reformasi sistem politik
demokrasi mengalami penguatan dan legitimate sebagai harapan akan
munculnya ruang partisipasi politik yang semakin transparan.
Transparansi dan terbukanya ruang partisipasi dalam sistem politik
* Drs. Irtanto adalah peneliti politik dan pemerintahan pada Balitbang Propinsi
Jawa Timur.
44 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
demokrasi sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak pemilu
2004, demikian pula demokratisasi di tingkat lokal
Sistem politik demokratis semakin dirasakan masyarakat Jawa
Timur, terutama pilkada langsung berupa Pilgub Jawa Timur periode
2008-2013. Perkembangan politik lokal di Jawa Timur cukup menarik
publik terutama persoalan pemilihan gubernur Jawa Timur. Sistem
Pilkada langsung oleh rakyat yang telah menggeser sistem perwakilan,
baik partai politik maupun kandidat kepala daerah harus mendekat
pada rakyat.
Konsekuensi perubahan sistem pemilihan rakyatlah yang
menentukan pilihan politik bukan lagi pada sekelompok elit politik
yang namanya legislatif. Strategi pendekatan terhadap publik sebagai
pemilik suara banyak dilakukan oleh para calon kandidat kepala
daerah. Akibatnya iklan-iklan politik bertebaran dimana-mana dalam
bentuk baliho maupun bentuk lainnya seperti memanfaatkan media
massa baik media cetak maupun media elektronika. Melalui iklan
politiknya, merekapun mencoba-coba untuk menawarkan berbagai
janji-janji politiknya. Sistem Pilkada langsung lebih menjanjikan
dibandingkan sistem yang berlaku sebelumnya. Pilkada langsung
termasuk pemilihan gubernur Jawa Timur diyakini memiliki kapasitas
yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat,
sehingga masyarakat di daerah memiliki kesempatan untuk memilih
secara bebas pemimpin daerahnya. Pilkada langsung merupakan
munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadikan
berbagai faktor determinan dalam melakukan tindakan politiknya
untuk mengapresiasi sistem politik demokrasi tersebut. Masyarakat
Jawa Timur mempunyai banyak latar belakang kultur, kultur
mataraman, kultur pendalungan, dan kultur arek. Demikian pula
banyak latar belakang geografis seperti desa dan kota. Latar belakang
kultur maupun geografis tersebut diperkirakan akan mempengaruhi
pilihan politiknya.
Dalam pilgub Jawa Timur 2008-2013 diikuti oleh lima
kandidat. Berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Jawa Timur Nomor: 821.1/71/KPU-Jtm/VI/2008 tentang penentuan
dan penetapan nomor urut pasangan calon kepala daaerah dan wakil
kepala daerah, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
periode 2008-2023 yang dapat memenuhinya adalah sebagai berikut:
Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji Mantep) diusulkan oleh
PPP dan Partai Patriot, Soetjipto-Ridwan Hisyam (SR) diusung oleh
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 45
PDIP, Soenaryo-Ali Maschan Musa (Salam) diusung oleh Partai
Golkar, Achamady-Suhartono (Achsan) dicalonkan PKB dan
Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) dicalonkan oleh Partai Demokrat
dan PAN.
Perumusan Masalah
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1)
Bagaimana preferensi pemilih kandidat gubernur Jawa Timur periode
2008-2013?; 2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi perilaku politik
pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode
2008-2013?; 3) Bagaimana pendapat publik terhadap nilai-nilai
demokrasi dalam pilgub ? 4) Media apa yang dipakai untuk
memperoleh informasi tentang pilgub Jatim ?. 5) Kapan mereka
menentukan pilihan politiknya ?
Lingkup Penelitian
Penelitian tentang perilaku memilih Gubernur Jawa Timur
periode 2008-2013 ini dilaksanakan pada bulan Juli 2008 sampai
Desember 2008 yang difokuskan pada ruang lingkup perilaku yang
pendekatan dilihat dari sisi sosiologi, psikologis, rasional dan
struktural sosial.
KERANGKA PEMIKIRAN
Pendekatan Perilaku Pemilih
1. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik
sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai
pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih
seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan
sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti
agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya) merupakan
faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pemahaman
terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti kelompok
keagamaan, organisasi profesi, maupun pengelompokan informal
seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok kecil lainnya
memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan
46 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
orientasi seseorang, yang nanti sebagai dasar atau preferensi dalam
menentukan pilihan politiknya. (Anwar, 2004 : 23-24). Gerald Pomper
(dalam Asfar, 2006) memerinci pengaruh pengelompokan sosial
dalam studi voting behavior ke dalam variabel, yaitu variabel
predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-
ekonomi pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial pemilih dan
keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan
perilaku memilih seseorang. Preferensi-preferensi politik keluarga,
apakah preferensi politik ayah atau preferensi politik ibu akan
berpengaruh pada preferensi politik anak. (Lipset, 1995: 1346-1353)
Aspek geografis mempunyai hubungan dengan perilaku
memilih. Adanya rasa kedaerahan memengaruhi dukungan seseorang
terhadap partai politik. Penelitian-penelitian Rose di Norwegia
menunjukkan bahwa ikatan-ikatan kedaerahan, seperti desa-kota,
merupakan faktor-faktor yang cukup signifikan dalam menjelaskan
aktivitas dan pilihan politik seseorang.Ikatan kedaerahan terutama
sangat kuat dalam mempengaruhi pilihan seseorang terhadap kandidat.
(Asfar, 2006: 140) Dalam berbagai ragam perbedaan struktur sosial,
yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik adalah faktor
kelas (status ekonomi).
2. Pendekatan Psikologis
Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang-sebagai
refleksi dari kepribadian seseorang, merupakan variabel yang cukup
menentukan dalam memengaruhi perilaku politik seseorang.
Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis, yaitu
ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu
dan orientasi terhadap kandidat. (Niemi and Herbert F. Weisberg,
1984: 9-12) Pendekatan psikologis menganggap sikap merupakan
variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik seorang.
3. Pendekatan Rasional
Ada faktor situasional yang ikut perperan dalam
mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih
tidak hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh
karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor
situasional itu bisa berupa isu-isu politik ataupun kandidat yang
dicalonkan. Dengan demikian isu-isu politik menjadi pertimbangan
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 47
yang penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan
penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan.
Mereka melihat adanya analogi antar pasar (ekonomi) dan perilaku
memilih (politik).
Seseorang memilih kontestan atau kandidat tertentu dapat
dilihat dari lima pendekatan yakni pendekatan struktural melihat
kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang luas,
seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum,
permasalahan dan program yang ditonjolkan. Pendekatan sosiologis
cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan
konteks sosial, pilihan seseorang dipengaruhi latar belakang
demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal
(kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.
Pendekatan ekologis cenderung hanya relevan apabila dalam suatu
daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih
berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan
kabupaten. Pendekatan psikologi sosial, secara emosional dirasakan
sangat dekat dengan partai politik atau kandidat. Pendekatan pilihan
rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung
dan rugi.
Peran Media Massa
Peran media massa sangat penting dalam memengaruhi
pemilih. Salah satu kunci persaingan politik adalah media massa.
Media massa ini diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki peran
dan fungsi untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan
informasi dari dan ke masyarakat. Efektivitas komunikasi politik
membutuhkan peran serta media massa, karena merekalah salah satu
profesi penting yang memiliki perangkat dan kemampuan
berkomunikasi dengan masyarakat luas. Komunikasi politik kerapkali
terjadi secara tidak langsung melalui pemberitaan-pemberitaan yang
dilakukan oleh media massa.(Firmansyah,2008:265)
METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN
Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah
Jawa Timur. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah mereka
48 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
yang sudah memiliki hak-hak politik dalam pilgub 2008-2010. Selain
itu pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan jenis
penelitian fenomenologi yang berusaha memahami perilaku manusia
dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang itu sendiri
(Upe,2008:135).
Daerah penelitian adalah dengan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut. Daerah tapalkuda yang identik dengan budaya
pendalungan yang didominasi dengan budaya Madura diwakili oleh
daerah penelitian Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo dan
Kabupaten Probolinggo. Sedangkan budaya mataraman, diwakili oleh
Kabupaten Blitar dan Kota Kediri serta Kabupaten Blitar dan Kota
Blitar. Kemudian budaya arek akan diwakili oleh Kota Surabaya dan
Kota Mojokerto.
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan
instrumen kuesioner tertutup dan terbuka kepada mereka yang
mempunyai hak politik pada Pilgub Jatim. Pengumpulan data
kualitatif berupa data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi.
Sedangkan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan
instrumen daftar pertanyaan yang semi terstruktur baik terbuka
maupun tertutup dengan mewancarai pemilih pada pilgub Jatim 2008-
2013.
Adapun sasaran pendistribusian kuesioner adalah para pemilih
yang terpilih dengan mempertimbangkan penelitian yang bersifat
deskriptif dan eksploratif, maka pengambilan sampel menggunakan
sistem acak yang dapat mewakili tiga budaya yang ada di Jawa Timur.
Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan
teknis analisis komparasi (Muhadjir, 2007). Metode penentuan sampel
dengan sistem kuota atas dasar mereka mempunyai hak-hak politik
dalam pilgub Jatim 2008-2013. Masing-masing daerah penelitian
yang menjadi lokasi penelitian masing-masing ditentukan sebanyak
200 orang, sehingga semua responden sebanyak 600 orang.
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Identitas Reponden
Responden sebanyak 600 orang pemilih calon gubernur Jawa
Timur memiliki agama yang berbeda satu sama lainnya. Menurut
pengakuan mereka mayoritas beragama Islam. Sedangkan mereka
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 49
berjenis kelamin laki-laki 57,0% dan perempuan 43,0%. Responden
yang diambil sebagai sampel di daerah Mataraman ini kebanyakan
Suku Jawa yaitu sebanyak 85,0%, Suku Madura 1,0%, dan Keturunan
Thionghoa sebanyak 14,0%. Pendidikan responden bervariasi yaitu
lulusan SD sebanyak 15,0%, SMP sebanyak 19,0%, SLTA sebanyak
36,0%, Akademi sebanyak 14,0% dan Sarjana/Pasca Sarjana sebanyak
16,0%.
Preferensi Pemilih Kandidat Gubernur : Perbandingan Budaya
Dalam realitasnya mereka yang mempunyai budaya
mataraman dalam memilih kandidat gubernur Jatim periode 2008-
2013 cenderung tidak mempertimbangkan latar belakang kesamaan
parpol yang mereka pilih pada saat pemilu 2004 yang lalu, mereka
yang menyatakan tidak mempertimbangkan soal latar belakang parpol
kandidat sebanyak 63,0%. Bagaimana mereka yang mempunyai latar
belakang budaya pendalungan, mereka yang menempati daerah
tapalkuda. Perilaku dalam memilih ada kecenderungan yang sama
dengan mereka yang mempunyai budaya mataraman, mereka dalam
memilih tidak mempertimbangkan pula asal parpol atau partai apa
yang mencalonkannya.
Mereka yang mempunyai budaya pendalungan ada kesamaan
dalam memilih kandidat gubenur Jatim periode 2008-2013 baik pada
putaran pertama maupun kedua. Mereka yang mempunyai budaya
pendalungan yang kebanyakan menempati daerah tapalkuda yaitu di
daerah bagian pantai utara Jawa Timur yang menggunakan bahasa
sehari-harinya bahasa Madura dalam memilih kandidat gubernur
mempunyai kecenderungan yang sama dalam memilih terutama
mereka tidak mempertimbangkan kesamaan parpol (54,0%).
Demikian pula mereka yang memiliki budaya mempunyai
kecenderungan yang sama pula dalam memilih kandidat gubernur
Jatim 2008-2013. Mereka yang memiliki budaya arek juga tidak
mempersoalkan latar belakang parpol kandidat gubernur (58,0%).
Walaupun demikian mereka yang memiliki budaya mataraman
(30,0%), budaya pendalungan (35,0%) dan budaya arek (30,0%) ada
yang mempertimbangkan kesamaan parpol, bahkan ada pula yang
sangat pertimbangan kesamaan parpol dalam memilih calon gubernur.
Hampir relatif sama dengan mereka yang memiliki budaya
mataraman, budaya pendalungan dan budaya arek, ada
50 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
kecenderungan dalam memilih calon gubernur tidak
mempertimbangkan parpol yang mengusungnya atau mereka
cenderung meninggalkan parpol yang mereka pilih pada pemilu tahun
2004.
Tampaknya ada kesamaan dalam mempertimbangkan kandidat
apakah berasal dari daerah atau tidak, dalam realitasnya pada budaya
mataraman, budaya pendalungan, budaya arek mempertimbangkan
asal daerah dalam memilih calon gubernur Jatim menjadi salah satu
faktor yang ikut mewarnainya. Mereka yang mempunyai budaya
mataraman, budaya pendalungan maupun budaya arek dalam
memilih calon gubernur masih ada unsur pertimbangan
primordialisme yaitu latar belakang agama calon gubernur. Hal ini
terbukti mereka yang tinggal di daerah budaya mataraman sebanyak
53,0% mempertimbangkan, budaya pendalungan mereka bertempat
tinggal di daerah tapalkuda sebanyak 51,0% mempertimbangkan, dan
budaya arek sebanyak 72,0% mempertimbankan agama kandidat
gubernur. Dan mereka yang menyatakan sangat mempertimbangkan
pada budaya mataraman 15,0%, pada budaya pendalungan 21,0 dan
pada budaya arek sebanyak 20,0%. Dengan demikian mereka yang
mempertimbangkan asal agama, pemuka agama dalam pilgub Jatim
periode 2008-2013 baik putaran pertama maupun putaran kedua
jumlahnya sangat besar.
Apakah latar belakang putra daerah dijadikan referensi dalam
memilih kandidat gubernur Jawa ? Mereka yang mempunyai latar
belakang budaya mataraman, pendalungan dan arek sama-sama lebih
mempertimbangkan putra daerah, artinya mereka lebih menghendaki
yang menjadi gubernur berasal dari daerah Jawa Timur. Kondisi
seperti ini dapat dilihat bahwa mereka yang memiliki budaya
mataraman yang menyatakan mempertimbangkan dan sangat
mempertimbangkan putra daerah untuk dipilih sebanyak 63,0%. Hal
yang sama terjadi pada budaya pendalungan yang menyatakan putra
daerah dipertimbangkan untuk dipilih sebanyak 57,0% dan mereka
yang menyatakan sangat dipertimbangkan sebanyak 6,0%. Demikian
juga mereka yang memiliki budaya arek, sebanyak 4,0% yang
menyatakan putra daerah sangat dipertimbangkan untuk memilih dan
sebanyak 66,0% yang menyatakan dipertimbangkan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan
antara mereka yang berbudaya mataraman, pendalungan maupun arek
yang mempertimbangkan untuk memilih kandidat yang
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 51
berpengalaman untuk memimpin sebuah organisasi. Mereka yang
berbudaya mataraman lebih memilih mempertimbangkan kandidat
yang berpengalaman untuk memimpin sebuah organisasi (71,0%),
bahkan ada yang sangat mempertimbangkannya (11,0%). Demikian
juga mereka yang berbudaya pendalungan banyak yang menyatakan
mempertimbangkannya (61,0%) bahkan ada yang sangat
mempertimbangkan (14,0%) pengalamannya dalam memimpin sebuah
organisasi apakah organisasi itu formal pemerintahan, meliter, ataupun
organisasi partai politik maupun ormas. Hal yang sama terjadi pada
mereka yang memiliki budaya arek, mereka lebih cenderung kandidat
yang memiliki latar belakang pengalaman memimpin organisasi
dipertimbangkan untuk dipilih (61,0%).
Mereka yang memiliki budaya mataraman dalam memilih
juga lebih cenderung mempertimbangkan status pendidikan kandidat
gubernur (63,0%) yang mempersyaratkan status pendidikan calon
berpendidikan tinggi, bahkan mereka ada pula yang sangat
mempertimbangkan status pendidikan calon (16,0%). Demikian pula
hal yang hampir sama terjadi pada mereka yang mempunyai latar
belakang budaya pendalungan cenderung mempertimbangkan status
pendidikan kandidat gubernur (57,0%) yang mempersyaratkan status
pendidikan calon berpendidikan tinggi. Demikian pula mereka yang
memiliki budaya arek lebih cenderung status pendidikan
dipertimbangkan untuk dipilih (74,0%), bahkan mereka ada pula yang
sangat mempertimbangkannya untuk dipilih dalam pilgub Jatim
periode 2008-2013. Dengan demikian masalah status pendidikan dan
tentunya kemampuan intelektualitasnya serta kredibilitasnya dijadikan
hal yang sangat penting dalam pemilihan gubernur.
Tampak sekali hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidat
yang profesional dalam menangani sebuah organisasi birokrasi,
profesional dalam mengurus organisasi massa lainnya dijadikan
referensi untuk dipilih dalam pilgub Jatim 2008-2013. Pada budaya
mataraman ada kecenderungan kandidat yang profesional
dipertimbangkan untuk dipilih (74,0%) bahkan ada yang sangat
dipertimbangkannya (12,0%). Demikian juga mereka yang memiliki
budaya pendalungan lebih cenderung kandidat yang profesional
dipertimbangkan untuk dipilih (72,0%). Demikian pula pada budaya
arek ada kecenderungan kuat pula kandidat yang profesional
dipertimbangkan untuk dipilih (88,0%).
52 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Latar belakang intelektualitas kandidat menjadi pertimbangan
pula dalam pilgub Jatim periode 2008-2013, baik itu putaran pertama
maupun putaran kedua. Kondisi ini dapat dilihat pada budaya
mataraman, pendalungan maupun budaya arek. Pada budaya
mataraman mereka yang menyatakan sangat mempertimbangkan
intelektualitas kandidat sebanyak 13,0% dan mereka yang
mempertimbangkannya sebanyak 72,0%. Kecenderungan yang sama
juga terjadi pada mereka yang memiliki budaya pendalungan,
intelektualitas kandidat sangat dipertimbangkan sebanyak 15,0%,
bahkan mereka yang menyatakan dipertimbangkannya sebanyak
(72,0%). Demikian juga pada budaya arek yang menyatakan sangat
dipertimbangkan kemampuan intelektualitasnya sebanyak 8,0%,
sedangkan mereka yang menyatakan dipertimbangkan sebanyak
87,0%. Namun demikian ada pula yang tidak mempersoalkan
kemampuan intelektualitas kandidat, tetapi dari sisi jumlahnya sangat
relatif kecil sekali.
Selain persyaratan intelektualitas kandidat yang menjadi salah
satu pertimbangan dalam memilih juga ketertarikan isu-isu kampanye
yang menarik. Para pemilih yang berada di lingkungan yang
mempunyai budaya mataraman isu-isu kampanye menjadi salah satu
pertimbangan untuk memilih, demikian pula tentunya terjadi pada
budaya pendalungan maupun budaya arek isu-isu kampanye menarik
salah satu menjadi perhatian para pemilih. Hal ini bisa dilihat pada
budaya mataraman mereka mempertimbangkan memilih karena isu-
isu kampanye sebanyak 61,0%, dan mereka yang menyatakan sangat
mempertimbangkan isu-isu kampanye sebanyak 9,0%. Demikian juga
yang terjadi pada budaya pendalungan isu-isu kampanye menarik
dijadikan pertimbangan sebanyak 65,0%, dan mereka yang
menyatakan sangat dipertimbangkan sebanyak 11,0%. Sedangkan
budaya arek isu-isu kampanye yang dijadikan pertimbangan untuk
memilih gubernur sebanyak 76,0% dan mereka yang menyatakan
sangat dipertimbangkannya sebanyak 6,0%.
Kredibilitas kandidat gubernur Jawa Timur memengaruhi
perilaku politik pemilih baik itu budaya mataraman, pendalungan
maupun arek. Hasil penelitian membuktikan hal itu, yaitu pada budaya
mataraman mereka yang menyatakan kredibilitas calon sangat
dipertimbangkan untuk dipilih dalam pemilihan gubernur Jawa Timur
yaitu sebanyak 31,0%, dan mereka yang menyatakan
dipertimbangkanya sebanyak 66,0%. Dengan demikian kalau kedua
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 53
hal antara mereka yang sangat mempertimbangkan dan yang
mempertimbangkannya jumlahnya sangatlah besar yaitu sebanyak
97,0%. Hasil temuan ini menggambarkan bahwa kredibilitas calon
sangat memengaruhi perilaku politik pemilih pada pilgub Jatim.
Demikian pula mereka yang mempunyai budaya pendalungan, mereka
yang tinggal di wilayah pantai utara Jawa Timur yang dikenal dengan
daerah tapalkuda memperlihatkan bahwa perilaku politik pada pilgub
Jatim dipengaruhi juga oleh kredibiltas calon. Hasil penelitian
membuktikan sebanyak 39,0% menyatakan kredibilitas calon sangat
dipertimbangkan dan sebanyak 61,0% yang menyatakan kredibilitas
calon dipertimbangkan untuk dipilih. Dengan demikian mereka semua
yang mempertimbangkan kredibilitas calon untuk dipilih pada pilgub
Jatim. Hal yang sama terjadi pada budaya arek, perilaku politik
mereka pada pilgub Jatim dipengaruhi oleh kredibilitas calon.
Faktor yang Memengaruhi Pilihan Politik
Pemilih gubernur dalam menentukan pilihannya tampak
terlihat lebih independen tidak dipengaruh oleh atasan dalam bekerja,
baik itu mereka yang memiliki budaya mataraman (77,0%), budaya
pendalungan (70,0%) dan budaya arek (76,0%). Berbeda dengan
saran dari orang yang lebih tua usianya dalam memilih tampaknya
mempunyai pengaruh, walaupun pengaruhnya tidak dominan sekali.
Namun sebaliknya faktor agama pada budaya mataraman (61,0%),
budaya pendalungan (58,0%) dan budaya arek (80,0%) cenderung
dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan politiknya dalam
pilgub Jatim 2008-2013, bahkan mereka ada sebagian yang
menyatakan sangat memengaruhi dalam menentukan pilihan
politiknya. Mereka yang mempunyai budaya mataraman, budaya
pendalungan dan budaya arek perilaku politiknya dipengaruhi iklan
politik, baik itu dalam bentuk kampanye maupun iklan politik berupa
baliho, maupun bentuk lainnya. Iklan politik efektif memengaruhi
perilaku politiknya dapat dibuktikan bahwa mereka yang menyatakan
memengaruhi cenderung besar jumlahnya.
Tampaknya fatwa ulama pada budaya tertentu tidak begitu
memengaruhi pilihan politik pemilih, tetapi pada budaya tertentu
masih efektif untuk memengaruhi perilaku politik pemilih. Fatwa
ulama masih mempunyai pengaruh terhadap perilaku pemilih pada
budaya pendalungan yang mereka tinggal di daerah tapalkuda, yaitu
54 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
daerah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso,
Situbondo dan Banyuwangi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebanyak
10,0% yang menyatakan sangat berpengaruh dan sebanyak 50,0%
menyatakan berpengaruh. Namun mereka ada pula yang menyatakan
tidak memengaruhinya (40,0%). Mereka yang menyatakan tidak
berpengaruh ini kebanyakan pemilih rasional dan rata-rata
berpendidikan tinggi dan ada pula yang berpendidikan SLTA.
Fatwa ulama tidak begitu mempunyai pengaruh terhadap
perilaku pemilih yang mempunyai budaya mataraman maupun
mereka yang memiliki budaya arek.
Sumber Informasi
Sumber informasi tentang pemilihan gubernur langsung yang
mereka peroleh beraneka ragam, baik itu dari media massa elektronik,
radio maupun televisi, media cetak seperti surat kabar harian (Koran),
umbul-umbul, baliho, selebaran, teman, tetangga, kampanye/rapat
umum, organisasi keagamaan dan organisasi partai politik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber informasi yang
mereka dapatkan tentang kandidat calon gubernur kebanyakan
bersumber dari media televisi. Mereka mengenal pasangan calon
gubernur Khofifah-Mudjiono baik yang memiliki budaya mataraman,
budaya pendalungan dan budaya arek lebih banyak mengenalnya
lewat televisi. Demikian juga pasangan kandidat pasangan Soekarwo-
Saifullah dikenal oleh para pemilih lewat media televisi. Tampak
bahwa media televisi lebih efektif dijadikan sarana kampanye dari
pada media lainnya. Mereka yang memperoleh informasi pemilihan
gubernur langsung dari akses media massa tersebut dari berbagai
kalangan profesi, baik itu sebagai dosen, guru, pengusaha, wiraswasta,
karyawan swasta, PNS, TNI/Polri, mahasiswa, pegawai
BUMN/BUMD, dan berbagai kalangan pendidikan baik
berpendidikan tidak sekolah sampai sarjana/pascasarjana serta mereka
yang aktif di berbagai organisasi maupun yang tidak aktif yang
kapasitasnya sebagai pengurus dan sebagai anggota.
Bukan berarti media lainnya tidak digunakan, namun
jumlahnya relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan media televisi.
Media radio lebih banyak digunakan oleh masyarakat memiliki
budaya arek. Sedangkan media massa surat kabar hampir merata
digunakan oleh semua kalangan yang baik yang memiliki budaya
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 55
mataraman, budaya pendalungan dan budaya arek. Tidak ketinggalan
juga mereka memperoleh informasi berasal dari media televisi dan
radio, elektronika dan cetak, serta mereka memperoleh informasi atau
mengenal kandidat berasal dari selebaran/baliho, umbul-umbul.
Mereka yang mengandalkan sumber informasi pilkada langsung
tersebut selain tersebut di atas juga berasal dari organisasi keagamaan,
organisasi partai politik. Dari sinilah terlihat dengan jelas mereka
mengenal program-program kampanye lewat berbagai media tersebut.
Pendapat Publik Terhadap Nilai-nilai Demokrasi
Proses Demokratisasi
Dalam pilgub langsung dipandang oleh sebagian besar rakyat
yang memiliki budaya mataraman (75,0%), budaya pendalungan
(69,0%), dan budaya arek (66,0%) siapapun yang terpilih akan
memosisikan sebagai representasi rakyat. Namun mereka ada yang
tidak setuju bahkan tidak tahu menahu apakah kepala daerah akan
memosisikan sebagai representasi rakyat ataukah tidak, tetapi jumlah
mereka hanya relatif kecil sekali.
Namun mereka ada yang berpendapat bahwa pilgub langsung
tidak membatasi pengaruh konfigurasi politk DPRD dengan gubernur
terpilih. Mereka yang berpendapat seperti ini sebagian kecil berbudaya
mataraman (9,0%), budaya pendalungan (11,0%), dan budaya arek
(8,0%). Dengan adanya pilgub langsung tersebut legitimasi
pemerintahan daerah lebih kuat, sehingga pemerintahan menjadi lebih
efektif. Mereka yang berpandangan seperti ini kebanyakan memiliki
budaya mataraman (84,0%), budaya pendalungan (81,0%), dan
budaya arek (82,0%). Mereka berpandangan seperti itu dikarenakan
gubernur terpilih akan sulit dijatuhkan oleh DPRD kecuali ada kasus
pidananya.
Mereka yang memiliki ketiga budaya, baik itu budaya
mataraman (81,0%), budaya pendalungan (80,0%) dan budaya arek
(87,0%) mempunyai kecenderungan yang sama dalam memandang
pilgub langsung. Mereka kebanyakan berpendapat bahwa dengan
adanya pilgub langsung akan berdampak positif terhadap praktek-
praktek politik uang atau paling tidak mengurangi praktek politik uang
dalam proses pilgub. Praktek politik uang tidak lagi berada hanya
pada elit politik seperti pada masa berlakunya UU No 22 tahun 1999,
seperti pada proses laporan pertanggung jawaban kepala daerah. Tidak
56 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
itu saja, pilgub langsung selain akan mengurangi praktek-praktek
politik uang hal ini diakui oleh sebagian besar mereka yang memiliki
budaya mataraman (81,0), budaya pendalungan (80,0) dan mereka
yang memiliki budaya arek (87,0%). Pilgub langsung juga akan
meningkatkan partisipasi politik, dan dengan keterlibatan rakyat
secara langsung akan berdampak pada peningkatan demokratisasi di
tingkat lokal. Mereka yang menyatakan seperti ini di kalangan mereka
yang memiliki budaya mataraman (89,0%), budaya pendalungan
(77,0%) dan budaya arek (84,0%). Namun mereka sedikit yang tidak
mengakui bahwa dengan pilgub langsung tidak akan meningkatkan
partisipasi politik dan keterlibatan rakyat secara langsung tidak selalu
akan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal. Walaupun
demikian mereka ada yang tidak tahu-menahu akan persoalan
partisipasi politik rakyat di daerahnya.
Mereka rupanya sebagian besar sepakat bahwa dengan pilgub
langsung, rakyat akan dapat menentukan siapa calon pemimpinnya
yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan di daerah. Mereka
yang mempunyai pandangan seperti ini relatif sama pada ketiga
budaya mataraman (95,0%), budaya pendalungan (88,0%) dan
budaya arek (90,0%). Namun mereka ada yang tidak sependapat kalau
pilgub langsung tersebut akan dapat menentukan pemimpin yang
mampu menyelesaikan persoalan di daerah. Tidak selamanya
pemimpin dapat menyelesaikan secara sendirian ada faktor lain yang
ikut berperan.
Keyakinan Rakyat Terhadap Pilgub
Mereka baik yang memiliki budaya mataraman (92,0%),
pendalungan (88,0%) dan budaya arek (96,0%) cenderung
mempunyai keyakinan bahwa pilgub langsung dengan perangkat UU
No. 32 tahun 2004 akan berdampak positif terhadap menegakkan
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Mereka yang berpendapat seperti itu kebanyakan profesinya sebagai
mahasiswa, dosen, guru, wiraswasta, TNI/Polri, PNS, wartawan dan
berpendidikan peguruan tinggi serta mereka kebanyakan aktif di
organisasi. Bagaimana hubungannya dengan kualitas gubernur
teripilih?. Mereka baik yang memiliki budaya mataraman (83,0%),
pendalungan (79,0%) dan budaya arek (82,0%) sebagian besar
mempunyai keyakinan bahwa pilgub langsung akan muncul kepada
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 57
daerah yang lebih berkualitas. Mereka yang memandang bahwa pilgub
langsung akan memunculkan kepala daerah yang berkualitas
kebanyakan profesinya sebagai dosen, mahasiswa, wiraswasta, PNS,
TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD, aktif di organisasi dan
berpendidikan menengah ke atas.
Namun mereka tidak semua berkeyakinan gubernur terpilih
lebih berkualitas, hal ini terbukti masih ada budaya mataraman
(9,0%), pendalungan (17,0%) dan budaya arek (10,0%) yang
berpendapat seperti itu. Walaupun calon gubernur mendapatkan suara
mayoritas, namun tidak menjamin soal kualitasnya. Selama ini
semuanya harus melalui parpol yang mau tidak mau rakyat harus
memilih diantara mereka yang disodorkan oleh parpol tersebut.
Mereka yang berpendapat seperti itu kebanyakan berpendidikan
akademi, sarjana, mahasiswa, sedangkan profesinya sebagai PNS,
Polri/TNI, wiraswasta, pengusaha dan aktifis organisasi baik di parpol,
RT, RW, LSM, maupun PKK. Bahkan mereka ada sebagian kecil
yang tidak tahu menahu soal apakah dalam pilgub tersebut akan
memunculkan kepala daerah yang berkualitas atau tidak. Mereka yang
tidak tahu menahu soal kualitas tidaknya gubernur terpilih kebanyakan
profesinya sebagai petani penggarap, ibu-ibu rumah tangga,
berpendidikan SD, SLTP maupun sebagian besar SLTA serta mereka
bukan aktifis organisasi.
Mereka yang memiliki budaya mataraman (91,0%),
pendalungan (90,0%) dan budaya arek (81,0%) cenderung
berkeyakinan pilgub langsung akan berdampak positif terhadap
pelayanan publik. Mereka sebagian besar berkeyakinan bahwa dengan
adanya pilgub langsung akan mampu meningkatkan pelayanan
pemerintah kepada rakyatnya. Mereka baik yang memiliki budaya
mataraman, pendalungan dan budaya arek kebanyakan mempunyai
keyakinan bahwa dengan adanya pilgub langsung publik akan lebih
mudah melakukan kontrol. Namun mereka ada yang tidak yakin
bahwa publik akan mudah untuk mengontrol gubernur terpilih.
Mereka melihat masih ada kelemahannya yaitu civil society masih
belum berkembang, masih minimnya NGO atau tidak ada lembaga
independen untuk mengontrol kekuasaannya. Mereka yang
berpendapat publik tidak mudah untuk melakukan kontrol kebanyakan
berpendidikan akademi sampai pascasarjana, profesinya sebagai
dosen, guru, mahasiswa, wiraswasta, PNS, kebanyakan aktif di
organisasi LSM, kemahasiswaan, partai politik.
58 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Tidak semua mempunyai keyakinan bahwa pilgub langsung
mempunyai dampak positif terhadap pemerintah lokal. Mereka yang
melihat bahwa salah satu dampak positif pilgub terhadap kepekaan
pemerintah lokal akan kebutuhan masyarakat, transparan dan mampu
mengelola sumber daya. Mereka yang menyatakan demikian itu
mayoritas memiliki budaya mataraman (86,0%), pendalungan
(73,0%) dan budaya arek (84,0%). Namun ada sebagian kecil mereka
yang tidak sependapat kalau pilgub langsung ini akan menghasilkan
gubernur yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, apalagi akan
semakin transparan dalam mengelola anggaran daerah. Birokrasi
selama ini selalu tertutup dalam mengelola anggaran. Mereka yang
mempunyai pendapat seperti itu kebanyakan latar belakang profesinya
sebagai dosen, guru, PNS, TNI/Polri, pengusaha, wiraswasta,
berpendidikan minimal lulus SLTA dan aktifis di organisasi.
Pilgub langsung akan menciptakan stabilitas politik dan
pemerintahan lokal, mereka yang mempunyai keyakinan seperti ini
adalah mereka yang mempunyai budaya mataraman (90,0%),
pendalungan (76,0%) dan budaya arek (88,0%). Mereka beralasan
dengan memilihan langsung oleh rakyat merupakan implementasi
demokrasi di daerah. Mereka yang mempunyai pendapat bahwa
pilgub langsung dapat menciptakan stabalitas politik kebanyakan
berpendidikan lulus SLTA sampai pascasarjana, profesinya sebagai
mahasiswa, dosen, pengusaha, karyawan swasta, pegawai
BUMN/BUMD. Namun sebagian kecil lainnya mereka menyatakan
bahwa pilgub langsung tidak menjamin dapat menciptakan stabilitas
politik dan pemerintahan di tingkat lokal
Aspek Pembelajaran Politik
Pilgub langsung mempunyai aspek pembelajaran politik.
Mereka sebagian besar berpendapat bahwa pilgub langsung
meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal. Hal ini terjadi pada
budaya mataraman (92,0%), budaya pendalungan (90,0%) dan
budaya arek (98,0%). Mereka beralasan dengan adanya pilgub
langsung, rakyatlah yang menentukan pimpinannya dan rakyat akan
semakin sadar akan hak-hak politiknya. Namun demikian ada
sebagian kecil dari mereka yang tidak sepenuhnya sependapat bahwa
pilgub langsung meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal,
terutama mereka yang memiliki budaya mataraman (2,0%). Tetapi
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 59
ada pula mereka yang tidak tahu menahu apakah dengan adanya
pilgub langsung ini akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat
lokal atukah tidak, hal ini terjadi pada budaya mataraman (6,0%),
budaya pendalungan (10,0%) maupun budaya arek (2,0%).Mereka
yang tidak tahu menahu soal itu kebanyakan latar belakang pendidikan
hanya lulus SD, SLTP, profesinya sebagai ibu rumah tangga, petani
penggarap dan sebagian karyawan swasta.
Demikian juga pilgub langsung akan berdampak terhadap
mengorganisir masyarakat ke dalam suatu aktivitas politik yang
memberi peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi,
mereka yang mempunyai pendapat seperti itu terjadi pada semua
budaya. Mereka beralasan dengan adanya pilgub langsung akan
tumbuh NGO atau LSM baru yang memberi peluang terhadap
aktivitas politk rakyat yang dapat melakukan kontrol terhadap
berbagai kebijakan pemerintah.
Disamping itu mereka sebagian besar tidak sependapat kalau
dikatakan bahwa pilgub langsung mempunyai aspek pembelajaran
politik terutama memperluas akses masyarakat lokal untuk
memengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan masyarakat lokal. Hal ini terjadi di ketiga budaya.
Mereka berpendapat masyarakat lokal masih akan sulit untuk
mengakses kekuasaan di tingkat propinsi, apalagi memengaruhi proses
pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat lokal. Sangat
ironis masyarakat daerah dalam jangka pendek dapat mengakses
kekuasaan. Hal itu masih dipengaruhi oleh masih elitisme kekuasaan
dan pengaruh geografis yang jauh untuk dijangkaunya, mana mungkin
masyarakat lokal akan dapat mengakses dan memengaruhi proses
pengambilan keputusan. Mereka yang mempunyai pendapat seperti itu
profesinya sebagai dosen, mahasiswa, guru, PNS, TNI/Polri,
karyawan swasta, berpendidikan minimal lulus SLTA serta aktif di
organisasi yang kapasitasnya sebagai pengurus maupun sebagai
anggota.
KESIMPULAN
Preferensi pemilih pada pemilihan gubernur Jawa Timur
periode 2008-2013 lebih banyak dilatar belakangi oleh beberapa hal
yaitu kesamaan asal daerah, kesamaan agama, kesamaan jenis kelamin
60 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
terutama pada budaya arek, putra daerah baik itu pada budaya
mataraman, budaya pendalungan dan budaya arek, pengalaman
memimpin organisasi, status pendidikan calon gubernur, memiliki
status ekonomi tinggi, kalangan professional, kalangan intelektual,
isu-isu kampanye menarik, visi dan misi kandidat, kredibilitas calon,
dan program kerja yang jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi
perilku politik pemilih pemilihan gubernur periode 2008-2013 antara
lain seagama, teman atau orang lain yang status ekonominya lebih
tinggi, Karena iklan politik, orang yang lebih tua usianya terutama
bagi mereka yang memiliki budaya pendalungan. Sedangkan sumber
informasi tentang pilgub kebanyakan media massa televisi
Pendapat publik terhadap nilai-nilai demokrasi pada pilgub,
yaitu tentang a. penguatan proses demokratisasi. Tentang penguatan
proses demokratisasi mereka berpendapat bahwa dengan pilgub
langsung gubernur memosisikan sebagai representasi masyarakat,
mengurangi arogansi DPRD, membatasi pengaruh konfigurasi politik
DPRD dengan gubernur terpilih, menjamin terciptanya legitimasi
pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan menjadi lebih efektif,
mengurangi praktek politik uang terutama dalam proses laporan
bertanggung jawaban gubernur, keterlibatan rakyat secara langsung
akan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, rakyat akan dapat
menentukan pilihan calon pemimpinnya yang dianggap mampu
menyelesaikan persoalan di daerah. b. Keyakinan rakyat terhadap
pilgub. Mereka yang memiliki budaya mataraman, pendalungan
maupun arek berpendapat bahwa dengan pilgub langsung menegakkan
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gubernur
yang terpilih akan kuat legitimasinya. Salain itu akan muncul
gubernur yang lebih berkualitas, mampu meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Pemerintah daerah akan lebih responsif, peka
terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas calon yang
terpilih akan lebih tinggi. Merek juga berkeyakinan kontrol menjadi
lebih mudah dilakukan oleh publik. Pemerintah lokal lebih peka
terhadap kebutuhan masyarakat dan akan dapat menciptakan stabilitas
politik. c. Dari aspek pembelajaran politik. Dengan adanya pilgub
langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal.
Selain itu memberi peluang lebih besar pada setiap orang untuk
berpartisipasi. d. Pengaruh pemilihan gubernur terhadap kinerja
birokrasi. Dengan adanya pilgub langsung akan meningkatkan kinerja
pemerintah, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan,
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 61
meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Sedangkan mereka yang
memiliki budaya mataraman, budaya pendalungan dan budaya arek
dalam memutuskan untuk menentukan pilihan politik sudah
ditentukan beberapa minggu sebelum mencoblosan.
DAFTAR PUSTAKA
Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek..
Bandung : Rosdakarya.
………………...1993. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan
Media. Bandung : Rosdakarya
Liliweri, Alo. 1991. Memahami Peran Komunikasi Massa dalam
Masyarakat. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Surbakti, Ramlan . 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Widiasarana.
Depari, Eduard dan Mac Colin, Andrews (Ed). 1995. Peranan
Komunikasi Massa dalam Pembangunan. Yogyakarta : Gajah
Mada University Press.
Franklin, Mark N.. “Voting Behavior”, dalam Symour Martin Lipset.
1995. The Encyclopedia of Democracy, Volume IV.
Washington DC : Congressional Quarterly Inc.
Mc. Quali, Denis and Seven Weindahl. 1995. Model-Model
Komunikasi, Jakarta, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Mubarok, M. Mufti, 2005. Suksesi Pilkada. Surabaya : Java
Pustaka.
Mc Quail, Dennis. 1996. Teori Komunikasi Massa. Jakarta, Erlangga.
Rakhmat, Jalahuddin. 1998. Psikolgi Komunikasi. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Gafar, Afan. 1999. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokasi.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Rosadi, Udi. 1999. “Teori dan Model Penelitian Efek Agenda Setting
Media Masa”. Jakarta : makalah Pendidikan dan Latihan
Penelitian Deppen RI
Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogjakarta
: Pustaka Pelajar.
Huda, Ni‟matul. 2004. “Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung di
Era Otonomi Luas, dalam Memperkokoh Otonomi Daerah
Kebijakan, Evaluasi dan Saran. Yogyakarta : UII Pres.
62 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Thalhah M. 2004. “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung:
Garansi Moral dan Demokrasi?, dalam Memperkokoh
Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran. Yogyakarta :
UII Pres.
Bambang Ilkobar, Saptopo. 2005. Pemilihan Kepala daerah
Langsung, Hubungan Kepala daerah dengan DPRD, dan
Akuntabilitas Pemerintah Daerah, dalam Subhan Afiti
(Editor), Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah
Daerah. Yogyakarta : FISIP UPUN “Veteran‟.
Afiti, Subhan dkk. 2005. Pilkada Langsung dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Fisip UPN”Veteran”.
Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa
pada masa Transisi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sanit, Arbi. 2005. Sistim Politik Indonesia: Kestabilan, Peta,
Kekuatan Politik dan Pembangunan. Jakarta : Raja Grafindo
Persada
Anwar, M. Khoirul dkk. 2006. Perilaku Partai Politik Studi Perilaku
Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih
pada Pemilu 2004. Malang : Universitas Muhammadyah.
Firmanzah. 2008. Marketing Politik. Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia.
Muhtadi, Asep Saeful. 2008. Komunikasi Politik di Indonesia :
Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Upe, Ambo. 2008. Sosiologi Politik Kontemporer, Kajian Tentang
Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung. Jakarta : Prestasi Pustaka.
Prihatmoko, Joko J. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filsafat,
Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
Tempointeraktif. PNS Kediri Terlibat Pilkada Akan Dipecat. http://www.tempointeraktif.com/hg/ nusa/jawamadura/2008/01/25.
Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Perintahan Daerah.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 63
BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM) CIHIDEUNG :
Memberdayakan Masyarakat Perdesaan Melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Sumarsono*
Abstraksi
Balai Informasi Masyarakat (BIM) Cihideung adalah lembaga
informasi masyarakat yang didirikan atas prakarsa Masyarakat
Telekomunikasi (MASTEL) bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat perdesaan sekitarnya melalui Teknologi Informasi dan
Komunikasi.Penelitian ini dilaksanakan di desa Cihideung, sebuah
desa penghasil tanaman hias yang sangat terkenal di Bandung.
Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan
mendeskripsikan profil BIM berikut berbagai kegiatannya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa BIM Cihideung dalam upaya
memberdayakan masyarakat masih banyak menemui permasalahan
yang tidak hanya terkait pada pemanfaatan/penguasaan teknologinya
tetapi juga dengan penyerapan dan pengolahan informasi sebagai
kontennya
Kata kunci : BIM, pemberdayaan masyarakat, teknologi informasi
dan komunikasi
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dahulu desa seringkali dianggap sebagai simbol
keterbelakangan, tradisional dan nyaris tanpa dinamika. Desa
seringkali juga dikonotasikan sebagai serba kekurangan, sanitasi yang
buruk, kemiskinan, kesenjangan dan lain-lain. Anggapan yang
demikian tidak sepenuhnya benar, kini banyak desa yang mulai
menggeliat dan berangsur angsur berubah menjadi lebih maju, terbuka
pada berbagai akses informasi dan isolasi, bahkan menuju tingkatan
sejahtera.
* Drs. Sumarsono, M.Si., adalah Peneliti Madya di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Profesi Balitbang SDM Depkominfo RI.
64 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Namun demikian kita juga tidak menutup mata bahwa masih
banyak desa yang tetap menyandang sebutan miskin dan tidak mudah
untuk mencari tahu penyebab utamanya, apalagi menemukan jalan
keluarnya. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat kini
semakin kompleks, saling terkait dan memengaruhi yang satu dengan
yang lainnya.
Padahal pemerintah juga sudah banyak campur tangan dalam
penanggulangan kemiskinan ini. Banyak program yang telah
dicanangkan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ada yang konsisten dan
berkesinambungan dari tahun ke tahun serta menyeluruh secara
nasional namun ada pula yang parsial lokal sifatnya. Sebenarnya
program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ini
sudah lama diterapkan, contohnya pada era Orde Baru, tepatnya pada
Pelita III tahun 1979/80 s/d 1983/84 kita kenal dua program pokok
yang dicanangkan pemerintah waktu itu, yaitu (1) mengurangi jumlah
penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan (2)
melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan
pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah,
kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja,
berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan
memperoleh keadilan.
Pada masa pemerintahan presiden SBY kita juga kenal
program subsidi BBM atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan
pembagian beras untuk masyarakat miskin, Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan lain-lain. Namun
pada kenyataannya kemiskinan masih tetap ada hanya saja jumlahnya
bergeser maju mundur sesuai dengan cara mengukur atau memaknai
konsep kemiskinan itu sendiri. Sebagai contoh Bappenas memaknai
kemiskinan dengan konsep absolut yaitu dirumuskan dengan membuat
ukuran tertentu yang konkrit (a fixed yardstick) dan berorientasi pada
kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yaitu sandang,
pangan dan papan. Selain absolut, kita kenal pula konsep kemiskinan
relatif dan konsep kemiskinan subjektif . Konsep kemiskinan relatif
dirumuskan berdasarkan the idea of relative standard, yaitu dengan
memperhatikan dimensi tempat dan waktu (Sunyoto,2004 : 126) yang
artinya kemiskinan di suatu daerah tidak sama dengan kemiskinan di
daerah lain dan demikian juga pada suatu waktu tertentu tidak sama
dengan waktu yang lain. Sedangkan konsep kemiskinan subjektif yaitu
ukurannya berdasarkan perasaan diri sendiri. Boleh saja kita mengira
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 65
bahwa seseorang itu berada di bawah garis kemiskinan tetapi menurut
perasaan mereka sendiri tidak dan demikian pula sebaliknya seseorang
yang kita anggap hidup layak tapi perasaan mereka menganggap
dirinya miskin.
Masih menurut Sunyoto sedikitnya ada dua macam perspektif
yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu:
perspektif kultural dan perspektif struktural atau perspektif situasional.
Masing-masing perspektif tersebut memiliki tekanan, acuan dan
metodologi sendiri yang berbeda dalam menganalisis masalah
kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada
tiga tingkat analisis : individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat
individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut a
strong feeling of marginality seperti : sikap parokial, apatisme,
fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada
tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga
yang besar dan free union or consensual marriages. Dan pada tingkat
masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak
terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat
secara efektif. (Sunyoto,2004: 128). Selanjutnya dijelaskan pula
bahwa perspektif situasional/struktural masalah kemiskinan dilihat
sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi
kapital dan produk-produk teknologi modern.
Jika demikian halnya, bagaimana mencari jalan keluar atau
strategi untuk memberdayakan masyarakat atau mengentaskan dari
kemiskinan. Jawabnya apabila kita menganggap bahwa akar
kemiskinan berkaitan dengan faktor kultural, kita perlu menyusun
strategi yang meningkatkan etos kerja kelompok miskin,
meningkatkan pendidikan supaya lebih memiliki pola pikir yang
melihat ke masa depan, dan menata kembali institusi-institusi ekonomi
kita supaya dapat mewadahi kebutuhan serta aspirasi kelompok
miskin. Sedangkan apabila kita mengganggap bahwa kemiskinan
berakar pada masalah struktural, strategi pembangunan kita perlu
dirumuskan kembali. Strategi pembangunan tidak lagi mementingkan
pertumbuhan, tetapi seharusnya lebih mementingkan pemerataan
kesempatan (Sunyoto, 2004:130).
Kini indikator penentu kemiskinan bertambah lagi dengan
kemudahan pada akses informasi. Kesenjangan informasi dapat
ditempatkan sebagai salah satu indikator kemiskinan. “Kesenjangan
info” menunjukkan ketidak mampuan mengakses dan menggunakan
66 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
informasi yang akan berdampak pada kesejahteraan seseorang. (Pe-PP
Bappenas-UNDP;2007:18)
Sekarang ini perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) demikian pesatnya hingga merambah keberbagai
kota di berbagai negara belahan dunia ini. Perkembangan ini tidak
berhenti di sini akan tetapi ketika diciptakan sistem hubungan antara
satu komputer ke komputer yang lain maka lahirlah apa yang disebut
internet. Agenda World Summit of the Information Society (WSIS)
dimana Indonesia bergabung di dalamnya menegaskan bahwa pada
tahun 2015 mendatang separuh penduduk dunia telah memiliki akses
ke internet termasuk penduduk perdesaan agar mereka menjadi lebih
berdaya. Oleh karena itu diperlukan jalan pintas untuk percepatan
penguasaan teknologi informasi tersebut terutama ke perdesaan
melalui berbagai cara diantaranya fasilitasi untuk pembangunan
Community Acces Point (CAP) atau sejenisnya seperti Telecenter,
Balai Informasi Masyarakat (BIM),Warung Informasi Teknologi
(Warintek), Warmasif, dan lain-lain baik yang stasioner maupun yang
mobile.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan BIM
Cihideung beserta seluruh kegiatannya sebagai lembaga informasi
masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
sekitarnya melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi
Metodologi
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif,
pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai berbagai key
person diantaranya Kepala Desa Cihideung, Ayi Sudrajat; Ketua
Kelompok Tani Giri Mekar (KTGM), Landjar Nursalim;
Bendaharawan KTGM, Ida Hidayat; Humas KTGM, Adil Hendra, dan
pengelola BIM antara lain Fitria, Trisna, Ika serta Pengujung BIM dari
SMA Cisarua. Wawancara dilakukan secara langsung di lapangan dan
bagi yang sulit ditemui, wawancara dilakukan dengan melalui telepon.
Materi pertanyaan sekitar keberadaan dan peranan BIM beserta
seluruh kegiatannya di lapangan sehingga dengan demikian
diharapkan dapat diperoleh gambaran ataupun deskripsi tentang profil
BIM secara utuh dan lengkap.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 67
Untuk memperkaya data dan informasi dilakukan pengamatan
langsung di lapangan serta studi banding di Telecenter, Muneng,
Madiun, Jawa Timur dan Pabelan, Yogyakarta serta studi kepustakaan
dari berbagai sumber data.
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Cihideung adalah salah satu desa yang terletak di wilayah
Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mencapai
desa Cihideung tidaklah terlalu sulit, banyak kendaraan umum menuju
desa yang terkenal dengan tanaman hiasnya ini. Desa Cihideung bisa
dicapai dari terminal Ledeng, yang berada tidak jauh dari Kampus
Universitas Pendidikan (UPI) Bandung. Dengan menyusuri jalan
Sersan Bajuri menuju desa Cihideung yang memiliki luas wilayah
445,44 ha ini kita dapat menikmati pemandangan hijaunya perbukitan
dan tegalan yang penuh dengan tanaman bunga dan strowbery.
Diperkirakan lebih dari 80% penduduk desa Cihideung yang
berjumlah sekitar 12.900 jiwa ini hidup sebagai petani bunga/tanaman
hias yang secara lebih rinci 50% diantaranya sebagai petani bunga
hias yaitu jenis tanaman yang berfungsi untuk memperindah taman,
sisanya (30%) sebagai petani bunga potong yang umumnya
dipergunakan sebagai bahan dekorasi. Sedangkan pusat penjualan
tanaman hias yang luasnya sekitar 1.150 meter persegi ini terletak
memanjang dipinggir kanan-kiri jalan utama desa Cihideung. Sentra
penjualan tanaman hias Cihideung ini diatur sedemikian rupa sehingga
menarik minat calon pembeli yang lewat di sekitarnya. Jenis tanaman
yang dijualnya antara lain meliputi bunga seperti mawar, krisan, aster,
dahlia, lili, melati, kemuning, bougenvile, sedap malam, macam-
macam anggrek, dan lain-lain. Budidaya tanaman hias ini cukup maju
sehingga dapat menopang kehidupan para petaninya secara lebih baik.
Budidaya tanaman hias dan bunga potong di desa ini telah berjalan
cukup baik dimana telah berperannya beberapa kelompok tani seperti
Kelompok Petapa, Giri Mekar, Mekarsari Putra, dan lain-lain, yang
selalu berupaya memajukan keterampilan budidaya para petani
terutama yang menjadi anggotanya. Disisi lain, agar hasil produksi
tanaman hias ini harganya tidak anjlog di pasaran karena
dipermainkan oleh tengkulak atau kelompok orang tertentu, maka
telah dibentuk Asosiasi Pedagang dan Petani Tanaman Hias
Cihideung yang selalu berupaya melancarkan tata niaga sekaligus
68 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
melindungi para petani dan pedagang dari pengaruh sindikat yang
mengakibatkan kerugian .
Sebagai sentra penjualan tanaman hias dan bunga, Cihideung
memiliki potensi wisata yang prospektif. Banyak pengunjung dari
berbagai daerah baik sekitar Bandung atau kota lain seperti Jakarta
terutama dihari libur. Sebagai daerah wisata selain ditunjang
keindahan alam dan tanaman hiasnya, Cihideung juga memiliki
potensi wisata kuliner dimana sekitar desa ini banyak terdapat café-
café yang sudah cukup populer di seantero Bandung.
Balai Informasi Masyarakat (BIM) Cihideung
Berdirinya BIM Cihideung diprakarsai oleh Masyarakat
Telekomunikasi (MASTEL) dengan tujuan memberikan pengenalan
kepada masyarakat terhadap teknologi informasi (internet) yang
sekaligus pada gilirannya diharapkan dapat memetik manfaatnya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
BIM yang ada sekarang ini merupakan BIM generasi ketiga
di desa Cihideung yang didirikan kembali pada tanggal 10 November
2006. Sebagai lembaga informasi masyarakat yang berada di
perdesaan BIM dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pokok dan
pendukung yang diharapkan akan melegitimasi eksistensi dan
memperlancar operasionalnya di lapangan.
Berbeda dengan BIM sebelumnya kepengurusan BIM kali ini
sepenuhnya dipegang oleh anak-anak muda. Pusat kegiatan atau yang
disebut sekretariat BIM berada di gedung seluas 28 meter persegi
yang lokasinya berada di RT 03/RW 10 Kampung Penyairan Desa
Cihideung, Bandung Barat. Pelatihan komputer yang pernah
diselenggarakan diikuti oleh 52 orang yang umumnya terdiri dari
pelajar SD dan SLTP dengan membayar masing masing Rp 20.000,-
Adapun materi pelatihan meliputi : pengenalan komputer, Word
Processor, Spread Sheet. Sedangkan pelatihnya adalah para
sukarelawan setempat yang dianggap sudah melek komputer yang
tentu saja sebelumnya mendapatkan pengarahan dari Staf IT Specialist
MASTEL yaitu Rochman Fathoni. Dari kegiatan-kegiatan pelayanan
tersebut di atas, BIM mendapatkan pemasukan sebesar Rp 875.800,-
yang sebagian besar diperoleh dari biaya pelatihan komputer.
Dalam operasionalnya sehari-hari BIM yang dibuka mulai
jam 8 pagi sampai jam 20 malam hari rata-rata dikunjungi oleh 8
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 69
orang yang pada umumnya pelajar untuk berbagai keperluan seperti
mengerjakan tugas sekolah, dan lain-lain. Masyarakat sekitarnya
khususnya yang berprofesi sebagai dekorator ada pula yang sering
mengunjungi BIM untuk mencari inspirasi dari model- model dekorasi
bunga dari berbagai situs.
Permasalahan yang sering ditemui di lapangan adalah apabila
komputer tersebut rusak maka harus tunggu ahlinya yang tinggal di
Jakarta. Oleh karena itu mereka berharap punya teknisi sendiri yang
selalu stand by kapanpun kalau ada kerusakan.
Kelembagaan
Di perdesaan masih berlaku sistem sosial tertentu yaitu suatu
kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam
kerjasama untuk memecahkan masalah, dalam rangka mencapai
tujuan bersama. Anggota atau unit-unit sistem sosial itu bisa berupa
perorangan (individu), kelompok informal, organisasi modern atau sub
sistem. (Rogers, 1991: 31). Anggota sistem sosial yang berbeda
tersebut menciptakan struktur di dalamnya dimana ada heararki sosial
yang harus diperhatikan. Di perdesaan kita kenal tokoh-tokoh agama,
adat dan tokoh formal yang masing masing diakui peranannya bagi
masyarakat.Tokoh-tokoh tersebut dihormati dan disegani oleh
masyarakat perdesaan karena peranannya sebagai orang yang
dianggap lebih tahu dibidangnya.Oleh karena itu tidak jarang mereka
dijadikan panutan dan teladan bagi masyarakat sekitarnya. Sikap dan
pendapat mereka selalu diperhitungkan dan dipedomani. Mereka juga
mendominasi forum-forum yang ada di perdesaan seperti rembug desa
atau musyawarah desa, keputusan keputusan komunal dan lain-lain.
Singkat kata mereka memiliki tempat tersendiri yang lebih tinggi dan
terhormat di masyarakat. Oleh karena itu setiap kali ada pengenalan
ide-ide baru atau inovasi dipedesaan akan selalu melibatkan para
tokoh tersebut untuk mendukungnya.Tanpa restu mereka jangan harap
ide-ide baru akan bisa masuk dan diterima masyarakat. Oleh karena
itu pendirian BIM juga memperhitungkan peran para tokoh
masyarakat Desa Cihideung . BIM didirikan dengan melibatkan
tokoh-tokoh masyarakat yang disebut Dewan Pembina BIM yang
terdiri dari Kepala Desa Cihideung (Ayi Sudrajat), Ketua Kelompok
Tani Giri Mekar (KTGM) Landjar Nursalim, Tokoh Masyarakat
70 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
(H.Tayub), Perwakilan Pemuda (Deden Kosasih), perwakilan ibu-ibu
PKK (Ny.Ayi Sudrajat).
Pengelola BIM
BIM Cihideung dikelola oleh staf pengelola yang terdiri dari
pengelola definitif dan pengelola sukarelawan. Staf Pengelola definitif
terdiri dari Project Manager : Taru J Wisnu dari Mastel; Site Manager:
Ida Elvira; Koordinator Kegiatan : Deden Kosasih; Humas : Rusli;
Sekretaris : Mega; Bendahara : Fitri; Koordinator Sukarelawan: Dani.
Sukarelawan umumnya terdiri dari para pemuda/pemudi setempat
yang bertugas menjaga sekretariat BIM sehari-harinya. Mereka
melayani pengunjung yang datang dengan berbagai keperluan seperti
mengetik, mencari data yang terkait penugasan guru di sekolah atau
sekedar chatting atau main game.
Struktur kepengurusan BIM yang demikian tidaklah terlalu
muluk karena memang BIM diharapkan menjadi lembaga milik
masyarakat, yang berbasis masyarakat oleh karena itu sudah
seharusnya sederhana dan tidak elitis untuk ukuran perdesaan.
Tidak semua staf pengelola BIM seperti tersebut di atas aktif
melaksanakan tugasnya karena berbagai alasan. Hanya beberapa orang
sukarelawan yang biasa menunggu pelanggan di sekretariat BIM
diantaranya ialah Fitria yang menyebut dirinya sebagai Ketua,
sedangkan kedua orang tadi yaitu Trisna dan Ika sebagai pengurus
harian. Sebagai reward yang sekaligus upaya meningkatkan
wawasannya para pengurus BIM ini pernah diajak ke Seminar di
Yogyakarta, Pelatihan komputer di Politeknik Telkom di
Gegerkalong, Bandung dan mengunjungi pameran ICT Expo di
Jakarta yang diselenggarakan tanggal 20-24 Mei 2008.
Menurut buku panduan untuk Fasilitator Infomobilisasi,
pengelola Telecenter atau sejenisnya yang ideal terdiri dari tiga orang
yang disebut tim-3 (The Three Musketeer) yaitu manager telecenter,
staf pengembangan media/IT admin dan staf pengembangan
komunitas/Fasilitator Infomobilisasi (FI) yang bertugas mengelola
kegiatan Infomobilisasi melalui kegiatan pendampingan kelompok.
Mereka bertiga inilah yang disebut Badan Pengelola Harian (BPH)
telcenter. (Pe-PP, Bappenas UNDP; 2007:39). BPH ini merupakan tim
inti yang berfungsi sebagai motor penggerak lembaga, oleh karena itu
seharusnya bekerja secara penuh dan mendapatkan imbalan/gaji.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 71
Sebagai tanggung jawabnya BPH, khususnya manager harus dapat
mencari dana untuk membiayai sendiri operasionalnya dari penjualan
jasa dan layanan lembaga. Seperti diketahui bahwa kegiatan BIM ada
yang bersifat layanan komersial dan ada pula yang bersifat sosial
dimana keduanya mempunyai bobot yang sama.
Kegiatan BIM
Sebagaimana diuraikan terdahulu kegiatan BIM selain
melaksanakan layanan rutin sekretariat juga kegiatan terjadwal yang
telah tersusun dalam program kerja ataupun Rencana Aksi BIM.
Rencana Aksi ini disusun cukup bagus dan rinci yang dimulai pada 3
Januari 2007. Kegiatan-kegiatan dimaksud sangat beragam yang
antara lain mulai dari persiapan pendirian BIM, peresmian BIM,
penyelenggaraan berbagai pelatihan dan praktek, kegiatan publikasi,
kompetisi, festival, studi banding dan perpustakaan. Macam-macam
pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan meliputi antara lain:
pelatihan partisipasi masyarakat, pelatihan komputer, bahasa Inggris,
membuat coklat candy, dekorasi tanaman hias, pembuatan data basis
tanaman hias, manajemen, usaha sampingan, fund raising, dan lain-
lain. Untuk kegiatan publikasi meliputi : pembuatan buletin BIM,
majalah dinding, website, pemetaan daerah, dan lain-lain.
Sebagai lembaga yang bergerak dibidang informasi, kegiatan
BIM akan lebih lengkap apabila ditambahkan dengan kegiatan
Infomobilisasi atau pendampingan masyarakat/kelompok dalam hal
pencarian, pengolahan dan penerapan informasi di lapangan. Kegiatan
pencarian informasi dapat berupa menyediakan informasi dari
berbagai sumber apakah media massa, website atau nara sumber yang
kompeten. Untuk pengolahannya dapat dilakukan melalui saling
belajar, seleksi, evaluasi, diskusi dan pemecahan masalah, sedangkan
penerapan di lapangan berupa aplikasi atau praktek di lapangan yang
biasanya didampingi oleh tenaga ahli/pengalaman dibidangnya.
Pendampingan kelompok dapat dilakukan secara berkala atau
insidental atas insiatif sendiri ataupun permintaan dari kelompok.
Partisipasi Masyarakat
Sebagai lembaga informasi perdesaan BIM telah dirancang
sedemikian rupa agar mampu berperan sebagai agen pembaharuan di
perdesaan. Sebagaimana diuraikan terdahulu BIM telah dibentuk
72 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
dengan berbagai infrastruktur dan sarana penunjangnya agar mudah
memainkan peranannya di perdesaan secara maksimal. BIM telah
dilengkapi dengan struktur organisasi beserta personil pengurusnya,
dewan pembina, sekretariat tetap, program kerja dan peralatan yang
berupa komputer, printer, kamera, scanner, perangkat pendukung
jaringan, dan lain-lain. Secara teoritis, bagi sebuah lembaga di
perdesaan, dengan infrastruktur dan sarana perlengkapan yang boleh
dibilang telah memadai tentunya lembaga tersebut telah dapat
melaksanakan programnya dan berperan banyak bagi masyarakat
sekelilingnya. Memang biaya operasional BIM sehari-harinya tidak
disediakan namun partisipasi dan swadaya masyarakatlah yang
diharapkan untuk dapat mengisi kegiatan lembaga tersebut. Pada
kenyataannya menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat ini
tidaklah mudah ini terbukti bahwa kegiatan BIM pernah vakum atau
terhenti selama beberapa tahun karena berbagai alasan. Padahal
sebagaimana diketahui bahwa keberadaan BIM ini didesain untuk
memberdayakan masyarakat itu sendiri. Tentu ada permasalahan
diantara keduanya yang mengakibatkan terciptanya jarak atau
hambatan itu.
Kekosongan kegiatan memang terjadi di BIM periode yang
lalu dan mudah-mudahan permasalahan tersebut tidaklah terulang
kembali atau setidaknya masih menjadi ganjalan. Bila kita lihat BIM
periode sekarang dimana hubungannya dengan para tokoh masyarakat
setempat yang cukup baik maka boleh jadi permasalahan yang timbul
tidaklah terlalu banyak dan substansial. Menurut penelitian
permasalahan yang timbul hanyalah bagaimana menarik partisipasi
dan swadaya masyarakat secara lebih baik.
Keberadaan BIM sudah pasti dikenal oleh masyarakat luas,
malahan masyarakat desa-desa sekitar Cihideung pun banyak yang
mengenalnya, hal ini terbukti bila kita mau berkunjung ke sana tidak
akan mengalami kesulitan ketika menanyakan arah menuju ke lokasi
BIM kepada penduduk. Sedangkan bila dilihat pada pengunjung yang
datang, seringkali juga ditemui para pelajar yang berasal dari desa
tetangga. Popularitas BIM ini didapat dari upaya berbagai publikasi
yang dilakukan pengelola melalui berbagai cara. Popularitas BIM
yang tinggi identik dengan tingginya pengenalan masyarakat terhadap
BIM. Ibarat kata pepatah: tak kenal maka tak sayang sehingga
tingginya pengenalan dapat diartikan tinggi pula pemanfaatan BIM
oleh masyarakat. Kenyataan yang menunjukkan kurang maksimalnya
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 73
pemanfaatan BIM bukan karena pengenalan masyarakat yang rendah
akan tetapi bisa jadi karena kondisi masyarakat desa itu sendiri yang
masih belum melek komputer. Selain itu bidang usaha BIM seperti
foto copy, pembuatan pas foto, jasa komputer, dan lain-lain yang
masih kurang diperlukan masyarakat desa yang pada umumnya
merupakan petani tanaman hias. Mereka hanya sesekali saja memakai
jasa-jasa tersebut. Oleh karena itu para pengelola BIM harus lebih
proaktif memecahkan permasalahan tersebut dengan membuka
sumber pendapatan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat desa.
Selain aktifitas ke dalam untuk menggali dana operasionalnya
sendiri, pengelola BIM khususnya Fasilitator Infomobilisasi (FI) juga
dituntut proaktif untuk mengadakan pendekatan dan pendampingan
pada kelompok-kelompok yang ada maupun masyarakat yang
memerlukan. Tujuannya adalah agar kelompok dan masyarakat
merasa lebih dekat dengan BIM, merasa ikut memiliki dan
memanfaatkannya sehingga dengan demikian kapasitas masyarakat
dalam penggunaan TIK meningkat. Selain itu mereka juga termotivasi
untuk saling belajar/bertukar pengetahuan,tersambungkan dengan
sumber informasi, saluran dan simpul komunikasi-informasi
terpercaya.
Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut bisa
dimulai dari hal hal yang kecil dan dimulai sejak dini. Partisipasi
umumnya tidak tumbuh secara spontan. Langkah-langkah yang perlu
diambil untuk menumbuhkan partisipasi diantaranya : pertama,
menumbuhkan pemahaman awal yang benar atas fungsi CAP/BIM
serta manfaat yang dapat diambil dari keberadaannya; kedua,
meningkatkan kesadaran masyarakat desa atas manfaat teknologi
informasi dan komunikasi dan kegunaannya untuk kemudahan hidup
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; ketiga, memperoleh
persetujuan dan dukungan masyarakat desa atas pendirian BIM untuk
menumbuhkan rasa memiliki terhadap BIM sejak awal (Djuzan, 2006:
13).
Agar partisipasi masyarakat lebih mantap lagi para pengelola
BIM harus dapat membuktikan bahwa kegiatan BIM memang
bermanfaat bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi.
Untuk membuktikannya harus dicoba menerobos keberbagai lembaga
perdesaan yang berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat
seperti kelompok-kelompok tani, asosiasi petani dan pedagang bunga,
74 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
asosisi pembibitan, produsen pupuk dan asosiasi lain yang ada serta
penguasa setempat. Terobosan disini dapat diartikan kerjasama
ataupun kemitraan yang saling memerlukan dan menguntungkan bagi
anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.Kemitraan
sudah seharusnya dijaga agar tetap berkelanjutan dan selalu bersifat
terbuka untuk melakukan hal-hal yang inovatif.
Peran Dewan Pembina
Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa BIM telah memiliki
Dewan Pembina yang terdiri dari para tokoh masyarakat setempat baik
formal maupun informal.
Apakah upaya menempatkan para tokoh masyarakat tersebut
sebagai Dewan Pembina BIM akan berhasil memperlancar
operasionalnya ? Ini sangat tergantung pada kemampuan dan aktifitas
para tokoh masyarakat tersebut. Dari beberapa tokoh masyarakat yang
terpilih sebagai Dewan Pembina, tidak semuanya aktif melaksanakan
pembinaan.Hal yang demikian dapat dimaklumi karena para tokoh
tersebut kesehariannya memiliki kesibukannya sendiri sesuai
bidangnya. Boleh jadi mereka juga menganggap kedudukannya
sebagai Dewan Pembina adalah sebagai kehormatan sehingga mereka
tidak perlu repot-repot ikut turun tangan. Oleh karena itu ada baiknya
jika dipilih pembina yang fungsional yaitu pembina yang betul betul
bisa aktif dan mempunyai tugas yang ada relevansinya dibidang itu.
Sebagai contoh wakil dari Depatemen Pertanian, Depkominfo dan
Instansi lain yang terkait. Keberadaan Dewan pembina yang aktif
dapat mendinamisir kegiatan BIM. Mereka dapat memberi arahan
operasional dengan membuat program kerja yang baik dan sekaligus
memotivasinya, membuat pola pembinaan, monitoring dan evaluasi
serta kegiatan lainnya seperti kompetisi antar lembaga sejenis,
festival,pemberian reward, dan lain-lain. Satu hal lain yang juga
sangat penting untuk dilakukan oleh Dewan Pembina ialah
memfasilitasi lembaga untuk menjalin kemitraan dengan berbagai
fihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kemitraan ini sangat
penting dalam upaya aktualisasi informasi,produksi konten, antisipasi
permasalahan sekaligus koordinasi untuk solusinya.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 75
PEMBAHASAN
BIM Yang Ideal
Sebelum BIM dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya,
sudah seharusnya BIM terlebih dahulu berdaya. Artinya BIM dapat
melaksanakan atau mengontrol seluruh kegiatan operasionalnya secara
baik dan dapat mengatasi semua hambatan yang ditemuinya. Menurut
Andrew Sargent: all organizations are driven by a series of “core
values”. Generically expressed, these values are about: quality,
output,time, cost,customers/consumers, safety. Most smart companies
or organizations quickly realize that succes depends on your ability to
control not just a couple of these core value-but all of them at the
same time . (Sargent, 2001 :27)
Secara umum pembangunan BIM bertujuan untuk
menyejahterakan masyarakat disekitarnya melalui penyediaan akses
informasi dari berbagai sumber dan media terutama internet. BIM
sengaja dibangun di daerah perdesaan karena masyarakat perdesaan
dianggap masih perlu lebih diberdayakan dalam rangka mencapai
tingkat kesejahteraannya yang lebih baik.
Konsep BIM dapat disamakan dengan Telecenter dan
sejenisnya yang berperan sebagai fasilitator program komunikasi-
informasi (Infomobilisasi), yaitu : mendampingi kelompok,
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penggunaan TIK,
memfasilitasi proses saling belajar/bertukar pengetahuan, dan
sebagainya. Selain itu juga dapat berperan sebagai pelaku komunikasi
di desanya, yaitu menjadi sumber informasi, menjadi saluran/media
komunikasi-informasi,menjadi simpul komunikasi-informasi dan
sebagainya. (Tim Pe-PP Bappenas-UNDP,2007:39)
Lebih jauh BIM sebagai sumber informasi, dapat
mengembangkan diri menjadi Pusat Informasi Pembangunan Desa,
Kantor Berita Komunitas, Pusat Informasi Desa, Bank Data
Desa,Sentra Pembelajaran Masyarakat, dan lain-lain
Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Istilah pemberdayaan masyarakat telah secara luas
dipergunakan di negara kita paska krisis ekonomi 1997. Istilah ini
76 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
diterjemahkan dari kata empowerment yang memiliki arti lebih
komprehensif. Simon dalam bukunya Rethinking Empowerment
(1990) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah aktifitas reflektif,
atau proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh
agen atau subyek tertentu yang mencari kekuatan atau penentuan diri
sendiri (self-determination). Sementara itu, proses lainnya hanya
memberikan iklim, menciptakan hubungan, sumber-sumber dan alat-
alat prosedural yang dengan perantaranya masyarakat dapat
meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemberdayaan merupakan
sistem yang berinteraksi dan berkolaborasi dengan lingkungan sosial
dan fisik (Harry Hikmat, 2006 : 134). Selanjutnya pengertian tersebut
diperjelas sebagai berikut : pemberdayaan bukanlah merupakan upaya
pemaksaan kehendak, atau proses yang dipaksakan, atau kegiatan
untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, atau keterlibatan dalam
kegiatan tetentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan
pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki
oleh masyarakat yang bersangkutan. (Harry Hikmat, 2006 : 135).
Sementara itu pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) bukanlah suatu hal yang mudah.
Pada dasarnya pemberdayaan melalui TIK tidak hanya mengenalkan
masyarakat pada komputer saja tetapi lebih kearah bagaimana
mengambil manfaat dari informasi yang didapat dari Internet. Yang
jadi nilai ekonomis (economic value) dari teknologi ini bukanlah
komputer dan komponen-komponennya secara fisik, melainkan
penekanan pada informasi yang dibawa dan diolahnya. (Indrajit,
2000:208)
Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki
kesadaran dan kebutuhan terhadap informasi sebagai sumber kekuatan
(power). Masyarakat yang dapat menggunakan informasi untuk
mengambil keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara
kritis dalam upaya memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya
sendiri, mampu terlibat dalam proses-proses sosial dan politik
termasuk dalam proses pengambilan keputusan publik yang dilakukan
komunitasnya (Tim Pe-PP Bappenas-UNDP,2007:5)
Memberdayakan masyarakat dengan informasi tidaklah mudah
apalagi menyejahterakannya sebab informasi memiliki dimensi yang
sangat luas dan beragam serta taksonomikal oleh karena itu tidak
secara langsung merubah keadaan dari kurang sejahtera menjadi lebih
sejahtera. Kita boleh berharap banyak bahwa masyarakat Cihideung
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 77
menjadi semakin sejahtera ketika BIM didirikan di desa tersebut.
Karena masyarakat dapat informasi tentang berbagai jenis tanaman
hias yang berprospek ekonomi lebih baik, juga mendapat informasi
berkaitan dengan dimana bibit-bibit tananam hias yang berkualitas itu
didapatkan. Selanjutnya juga bagaimana menyemai bibit bibit unggul
tersebut hingga besar dan laku dijual. Tidak berhenti disitu , informasi
tentang pasar yang baik dan bagaimana mengirimkannya juga sangat
diperlukan, karena tidak jarang produsen tanaman hias diperdaya oleh
tengkulak karena kurangnya informasi ini. Diharapkan dengan
informasi-informasi yang berharga tersebut masyarakat mendapatkan
kemudahan dalam membudidayakan tanaman hias sekaligus dapat
menjualnya dengan harga yang baik. Pada kenyataannya di lapangan
tidak semua informasi seperti tersebut di atas tersedia, bilamana
tersedia itupun baru informasi ”mentah” yang masih perlu diolah,
diterjemahkan, dipilah dan disaring agar dapat diambil manfaatnya.
Dari kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa informasi dari
internet belum dapat di akses dan dimanfaatkan oleh semua orang
karena adanya hambatan teknis atau hambatan digital. Banyak orang
yang belum faham dengan teknologi internet ini sedangkan bagi yang
sudah memanfaatkan informasi umumnya masih mempergunakannya
untuk keperluan mereka sendiri. Selain hambatan digital, hambatan
budaya juga sangat berperan dalam pemanfaatan internet sebagai
sumber informasi. Selain internet merupakan barang baru yang
dianggap canggih di perdesaan, umumnya masyarakat juga masih
terbiasa dengan komunikasi lisan. Mereka mencari informasi dari
kawan, tetangga, atau opinion leader setempat melalui forum dan
arena sosial yang ada. Sedangkan mereka menyebarkannya melalui
getok-tular atau dari mulut kemulut diberbagai kesempatan. Mereka
masih terbiasa ngobrol di warung kopi daripada nongkrong di depan
komputer layaknya orang kantoran.
Salah satu cara sederhana yang mungkin dapat membantu
mengenalkan masyarakat terhadap komputer sekaligus memperlancar
pencarian situs penting ialah disediakannya para pendamping yang
memahami internet dan mampu berbahasa Inggris. Karena bahasa
yang dipergunakan di internet tidak hanya bahasa Indonesia tetapi
banyak yang mempergunakan bahasa Inggris.
Dari uraian di atas terlihat bahwa untuk memberdayakan
masyarakat melalui BIM memang masih diperlukan kerja keras dan
perlu dicari terobosan agar terhindar dari berbagai hambatan.
78 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Peranan Kelompok
Di perdesaan dengan mudah dapat kita jumpai berbagai
kelompok masyarakat. Selain kelompok formal yang dibentuk
pemerintah ada juga kelompok yang terbentuk karena interest,
primordialisme dan tatanan sosial tradisional. Kelompok-kelompok ini
biasanya berperan penting dalam memecahkan berbagai permasalahan
desa termasuk permasalahan yang ada di BIM.
Kelompok masyarakat yang ada di desa Cihideung
diantaranya kelompok tani, kelompok tani nelayan andalan, kelompok
arisan. Masing masing kelompok punya kegiatan yang berbeda tetapi
tujuannya sama yaitu berkeinginan memberdayakan dan
menyejahterakan anggotanya. Oleh karena itu tidaklah salah bila ada
upaya memfasilitasi kelompok-kelompok yang ada untuk
memberdayakan masyarakat sekitarnya. Karena kelompok diyakini
memiliki potensi dan ciri-ciri yang menunjang upaya pemberdayaan
yang diantaranya : (1) orang-orang dalam kelompok cenderung untuk
berlomba (2), mereka membentuk identitas mereka sendiri yang
menjadikan personaliti kelompok. (3), kekompakan yaitu daya tarikan
anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu;
(4), ada komitmen terhadap tugas. (Arni Muhammad,2000 ;186).
Namun ketika kelompok-kelompok telah terbentuk dan
memiliki potensi, upaya untuk menarik partisipasi mereka pada
kegiatan BIM tidaklah berjalan linier. Sebab kegiatan BIM yang
berbasis internet merupakan hal yang baru dan sama halnya dengan
memperkenalkan inovasi atau ide-ide baru pada masyarakat. Sebuah
inovasi biasanya penuh liku sehingga memperkenalkannya ke
masyarakat sebaiknya dilakukan secara pelan-pelan,
berkesinambungan dan hati-hati dengan melalui berbagai cara seperti
penyuluhan, komunikasi kelompok dan diskusi pemecahan masalah,
demonstrasi atau percontohan, dan lain-lain. Fisher telah
mengidentifikasikan empat fase yang dilalui pemecahan masalah yaitu
:orientasi, konflik, pemunculan ide, dan dukungan terhadap ide-ide
baru. (Goldberg & Larson, 1985 :45).
Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa peran kelompok
dalam sebuah inovasi sangatlah diharapkan oleh karena itu Fasilitator
Infomobilisasi haruslah dapat mendekati kelompok-kelompok yang
ada di desa ini .Kelompok-kelompok yang ada di desa ini memiliki
potensi dan dapat berperan banyak untuk menarik partisipasi
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 79
masyarakat dalam memanfaatkan BIM sekaligus memberdayakan
masyarakat desa pada umumnya dan anggota kelompok pada
khususnya.
KESIMPULAN
Mengaktifkan dan membesarkan lembaga informasi
masyarakat di perdesaan seperti halnya BIM ini memang tidak mudah,
banyak kendala teknis dan non teknis yang selalu
menghadang.Kendala yang paling dominan ialah upaya
memperkenalkan masyarakat perdesaan yang masih memiliki banyak
keterbatasan dan masih cenderung menyukai komunikasi lisan, untuk
memanfaatkan komputer/ internet sebagai sumber informasi yang
bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Untuk mendorong
masyarakat agar melek komputer saja sudah sulit karena
komputer/internet merupakan teknologi baru yang tergolong
canggih.Apalagi mengambil manfaat dari informasi yang terdapat di
internet untuk memberdayakan diri mereka sendiri dimana diperlukan
upaya pencarian, pemilahan dan pengolahan sehingga mendatangkan
manfaat bagi masyarakat. Bantuan dan bimbingan orang lain dalam
hal ini sangat diperlukan karena selain materi yang ada di internet
begitu luas dan beragam juga seringkali disajikan dalam bahasa asing.
Oleh karena itu peran para pengelola BIM khususnya Fasilitator
Infomobilisasi (FI) sangat diharapkan. Tanpa peran FI yang lebih aktif
tidak akan terjadi pembelajaran-pembelajaran serta jalinan hubungan
ataupun interaksi positif dengan masyarakat sekelilingnya yang pada
dasarnya telah memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
Peran kelompok yang ada di masyarakat juga sangat penting sebab
melalui kelompok ini FI akan terbantu dalam hal deseminasi,
pemahaman dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat melalui
diskusi dan kegiatan lainnya.Oleh karena itu kerjasama hendaknya
diperluas dengan kelompok lain yang ada di masyarakat dengan tanpa
mengabaikan peran Kelompok Tani Giri Mekar (KTGM) yang telah
terjalin dengan baik.
Keberadaan BIM yang sudah populer itu telah menjadi modal
untuk menarik minat masyarakat dalam memanfaatkan BIM secara
lebih aktif apalagi bila dibarengi program program yang menarik dan
dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.Oleh karena itu peran
manajer sebagai pencari dana untuk membiayai operasionalnya sendiri
80 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
juga tidak kalah pentingnya agar program yang telah tersusun secara
baik tersebut dapat terealisir. Lebih lengkap lagi bila peran Dewan
Pembina lebih diaktifkan untuk memfasilitasi dan mengarahkan setiap
program dan kegiatan BIM agar lebih menyentuh kepentingan
masyarakat sekitarnya.
DAFTAR PUSTAKA
Alvin A. Goldberg & Carl E Larson. 1985. Komunikasi Kelompok,
Proses-Proses Diskusi Dan Penerapannya. Jakarta : UI-Press.
Sosrodihardjo, Soedjito. 1987. Aspek Sosial Budaya dalam
Pembangunan Perdesaan. Yogyakarta : Tiara Wacana.
Indrajit, Richardus Eko. 2000. Manajemen Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Muhammad, Arni. 2000. Komunikasi Organisasi. Jakarta : Bumi
Aksara.
Sargent, Andrew. 2001. How to Motivate People. Mumbai : Jaico
Publishing House.
Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Djusan, Aizirman. Bisnis Model Community Acces Point (CAP) Yang
Ideal Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, kuliah
umum mahasiswa jurusan teknik informatika, Politeknik Pos
Indonesia, Bandung 24 November 2006.
Hikmat, Harry. 2006. Strategi Memberdayakan Masyarakat. Bandung
: Humaniora Utama Press.
Tim Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP). 2007.
Memberdayakan Masyarakat dengan Mendayagunakan
Telecenter. Jakarta : Bappenas- UNDP.
Rogers, Everett M & F. Floyd Shoemaker. Communication of
Innovations, diterjemahkan Abdillah Hanafi dengan judul
Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Surabaya : Usaha Nasional.
Sumber lain :
Kompas, Sabtu 25 Oktober 2008
http://www.cihideung.blogspot.com
http://www.mastel.or.id
http://www.ruangkeluarga.com
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 81
Social Software Sebagai Media Komunikasi Dalam Proses
Pengajaran Di Perguruan Tinggi Negeri
Akhmad Riza Faizal*
Wulan Suciska*
Abstraksi
Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seiring kemajuan
teknologi Web menjadikan fenomena ini sangat menarik untuk dikaji
dalam kacamata ilmu komunikasi. Studi ini bertujuan untuk
memberikan bukti empirik secara kualitatif dan mendukung contoh-
contoh penggunaan ”social software” sebagai media komunikasi
dalam proses pengajaran pada beberapa perguruan tinggi negeri
(PTN) di Indonesia. ”Social software” dapat diartikan sebagai
perangkat lunak yang dapat mendukung interaksi kelompok.
Penggunaannya semakin terkenal bersamaan dengan munculnya
teknologi Web 2.0. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada
situs-situs PTN di Indonesia didapati bahwa penggunaan ”social
software” masih rendah. Pendalaman data ditelusuri melalui metode
wawancara dengan beberapa dosen PTN. Hasilnya, terungkap
beberapa praktek penggunaan ”social software” sebagai media
komunikasi dalam proses pengajaran antara lain; (1) mendorong
kemampuan menulis siswa dengan menggunakan blog, (2)
menggunakan contoh-contoh dari “media-sharing website” untuk
menjelaskan materi kelas, (3) menerbitkan hasil ujian semester pada
blog sang dosen, (4) menyebarluaskan materi perkuliahan dengan
menggunakan “file-sharing websites”, menunjukkan empati sang
pengajar melalui situs jejaring sosial.
Kata kunci : social software, teknologi komunikasi, teknologi
pendidikan
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penggunaan social software sebagai bagian dari komunikasi
dalam proses belajar-mengajar telah diteliti dan dilaporkan oleh
* Akhmad Riza Faizal, S.Sos., dan Wulan Suciska, S.I.Kom., Pengajar Jurusan
Komunikasi, FISIP Universitas Negeri Lampung.
82 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
banyak ahli di negara-negara maju (Alexander, 2006; Anderson, 2007;
Bryant, 2007; Franklin, G., 2007; Franklin, T., 2007; Kirriemuir ,
2007; Maxymuk, 2007; Miners & Pascopella, 2007; Shim dkk., 2007;
Topper, 2007; Eijkman, 2008; Virkus, 2008). Namun, informasi atau
penelitian yang menulis tentang implementasi software ini di negara-
negara berkembang masih tetap rendah bahkan tidak terlalu signifikan.
Kondisi ini cukup ironis, karena munculnya berbagai teknologi web
ini telah berdampak secara global dan penggunaan perangkat lunak ini
pun sebenarnya cukup besar di Indonesia. Penggunan internet di
Indonesia telah mencapai 20 juta orang atau masuk kelompok
pengguna besar di Asia setelah Cina (210 juta), diikuti Jepang, India,
dan Korea kemudian Indonesia (APJII, 2008). Namun, kondisi
penggunaan perangkat lunak ini terutama dalam kaitannya dengan
proses belajar-mengajar di Indonesia masih belum jelas sehingga perlu
untuk ditelaah dan diteliti. Argumentasi tersebut didasarkan pada dua
hal :
1. Munculnya fenomena teknologi Web 2.0 telah dirasakan beberapa
tahun belakangan ini di Indonesia. Namun, penelitian spesifik yang
bisa menyajikan dasar terutama dalam kacamata ilmu komunikasi
masih kurang. Terutama mengenai pemanfaatan teknologi ini pada
berbagai bidang, salah satunya sebagai media komunikasi pada
bidang pendidikan.
2. Jika topik ini dapat ditelaah lebih lanjut, maka akan dapat diteliti
pula bagaimana memanfaatkan teknologi ini sesuai dengan
perkondisian Indonesia. Sehingga diharapkan dapat dihasilkan
teknologi lanjutan karya anak bangsa yang sesuai dengan karakter
bangsa Indonesia. Setidaknya sesuai dengan karakter pendidikan di
Indonesia.
Peneliti mengkhususkan objek penelitian pada proses
pengajaran di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia
dikarenakan; pertama, PTN di Indonesia adalah gerbang terdepan
(center of exellence) dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi
dibandingkan pada beberapa institusi-institusi pendidikan lainnya
seperti sekolah dasar atau sekolah kejuruan. Kedua, belum adanya
data kuat tentang pemanfaatan social software sebagai media
komunikasi pada pendidikan di Indonesia itu sendiri menjadikan dasar
bahwa penelitian ini bisa dianggap sebagai studi perintis (pilot study).
Untuk itu pembatasan lingkup penelitian dapat dianggap sebagai
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 83
generator bagi peneliti lain untuk meneliti pada bidang-bidang
pendidikan yang searah (linear).
Artikel ini adalah bertujuan untuk menyajikan informasi
mengenai praktek-praktek penerapan social software sebagai suatu
media komunikasi dalam proses belajar-mengajar di Indonesia.
Khususnya, pada penerapannya sebagai bagian dari sistem pendidikan
yang digunakan oleh universitas-universitas negeri di tanah air.
Dengan menemukan beberapa contoh penggunaan dan menggunakan
perangkat lunak ini pada sistem pendidikan di Indonesia, hal ini bisa
menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. Baik menggunakan
pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk mencari dan mendesain
penggunaan yang sesuai dengan pola pendidikan yang sudah
diterapkan di Indonesia. Signifikansi dari artikel ini terutama
ditujukan untuk pendidik dan peneliti yang memiliki minat untuk
menyelidiki lebih lanjut dan menerapkan teknologi web pada berbagai
bidang. Mudah-mudahan, dengan minat yang sama kita dapat
membangun jaringan pada topik ini.
Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengajukan
pertanyaan bagaimana penggunaan social software sebagai media
komunikasi dalam proses pengajaran pada perguruan tinggi di
Indonesia?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan
1. Menyajikan informasi mengenai praktek-praktek penerapan social
software sebagai suatu media komunikasi dalam proses belajar-
mengajar di Indonesia. Khususnya, pada penerapannya sebagai
bagian dari sistem pendidikan yang digunakan oleh universitas-
universitas negeri di tanah air. Dengan menemukan beberapa
contoh penggunaan dan menggunakan perangkat lunak ini pada
sistem pendidikan di Indonesia, hal ini bisa menjadi acuan untuk
penelitian berikutnya. Baik menggunakan pendekatan kuantitatif
atau kualitatif untuk mencari dan mendesain penggunaan yang
sesuai dengan pola pendidikan yang sudah diterapkan di Indonesia.
84 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
2. Memperkaya kajian ilmu komunikasi di Indonesia terutama
mengenai penelitian pemanfaatan teknologi komunikasi, dan social
software pada khususnya, dalam bidang pendidikan.
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini terutama ditujukan untuk pendidik
dan peneliti yang memiliki minat untuk menyelidiki lebih lanjut dan
menerapkan teknologi web pada berbagai bidang. Mudah-mudahan,
dengan minat yang sama kita dapat membangun jaringan pada topik
ini.
METODE PENELITIAN
Fokus dari penelitian adalah memberikan penjelasan mengenai
praktik-praktik penggunaan social software sebagai media komunikasi
dalam proses pengajaran pada perguruan tinggi di Indonesia,
sebagaimana terefleksi dalam pertanyaan penelitian. Metode yang
digunakan dalam memperoleh data kualitatif adalah studi kasus (case
study). Robson, dengan mengutip pendapat Robert Yin, (1994, dalam
Robson, 2002:178-179) menjelaskan bahwa metode studi kasus dalam
penelitian kualitatif mengikutsertakan strategi investigasi secara
empirik terhadap fenomena tertentu pada konteks kehidupan nyata
(real life context).
Pada teknik pengumpulan data, untuk lebih memahami tentang
kualitas penggunaan social software pada proses pengajaran di tingkat
universitas maka dilakukan kombinasi pengamatan berupa survei pada
situs-situs PTN Indonesia dan wawancara dengan beberapa dosen
PTN yang telah menggunakan social software sebagai bagian media
komunikasi dari proses pengajaran yang mereka lakukan. Proses
pengumpulan dan analisa data dilakukan antara Juli hingga Desember
2008, untuk wawancara dilakukan kombinasi antara wawancara
melalui email, telepon dan tatap muka. Sebagai validasi, maka data
hasil wawancara telah diulang pada Februari 2009 untuk melihat
apakah informan masih mengajukan jawaban yang sama pada
pertanyaan yang sama. Hasil dari validasi kemudian digunakan untuk
melengkapi hasil penelitian
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 85
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Sosial Software : Sebuah Tinjauan
Istilah social software sebenarnya bukan merupakan sebuah
aplikasi yang baru muncul walaupun akhir-akhir ini pengertiannya
mengarah pada konteks penggunaan yang lebih pada konteks
"kemanusiaan" dibandingkan konteks "teknologi" (Bryant, 2007). Hal
yang harus diingat adalah bahwa social software tidak sama
pengertiannya dengan Web 2.0. Walaupun kemunculan social
software dapat dikatakan hadir sebagai komponen utama dari
fenomena Web 2.0 (Bryan, 2006) tetapi sejarah teknologi ini mungkin
akan berjalan dalam arah yang berbeda dengan perkembangan
teknologi Web itu sendiri. Christopher Allen (2004) telah melakukan
pekerjaan yang sangat bagus dalam menelusuri sejarah social
software. Dia mengaitkan keberadaan social software hingga kembali
ke tahun 1940-an ketika Vannevar Bush menulis artikelnya yang
terkenal, "as We May Think", lalu pada perkembangan selanjutnya
dari teknologi yang dapat mendukung kerja kolaboratif (collaborative
technology) seperti ARPA, Licklider dan teknologi augmentation (
1960-an), office automation dan Electronic Information Exchange
System/EIES (1970-an), Groupware dan Computer-Supported
Collaborative Work/CSCW (1980-an and 1990-an).
Futurelab, sebuah organisasi nirlaba di bidang pendidikan yang
berbasis di Inggris, berusaha untuk memperjelas konsep social
software dengan menunjukkan beberapa atribut kunci dari social
software dalam kaitannya dengan pendidikan. Atribut-atribut tersebut
antara lain; perangkat lunak ini menjembatani komunikasi antar
kelompok, memungkinkan komunikasi antara banyak orang,
menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan dan berbagi informasi,
dapat mengumpulkan dan mengindeks informasi, memungkinkan
sindikasi informasi dan membantu personalisasi dari prioritas-prioritas
yang dibuat pengguna, menyediakan fasilitas untuk menyatukan
pengetahuan (knowledge aggregation) dan menciptakan pengetahuan
baru, serta menyebarluaskan pengetahuan tersebut ke banyak platform
yang sesuai dengan keinginan pencipta pengetahuan, dan konteks
penerimanya (Futurelab, 2006).
Patrick dan Dotsika (2006), berbeda, argumentasi bahwa social
software sebuah konvergensi pemikiran dari domain jaringan sosial
86 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
manusia, interaksi manusia-komputer (human-computer
interaction/HCI) dan layanan web. Menurut mereka, dibandingkan
meminta pengguna untuk menyesuaikan diri dengan perangkat lunak
tersebut, social software sebaliknya lebih berupaya agar bisa
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan pengguna sehingga
pemanfaatannya lebih intuitif dan menarik pengguna untuk terus
menggunakannya (Patrick & Dotsika, 2006). Perubahan ini membalik
arah teknologi informasi yang sebelumnya lebih ke arah menarik
(pull) menjadi mendorong (push). Teknologi ini kemudian lebih
menonjol seiring dengan hadirnya model terkini dari teknologi web
atau yang oleh O'Reilly disebut sebagai Web 2.0 (O'Reilly, 2005),
implikasinya adalah aplikasi social software dapat ditemukan di
sebagian besar dari teknologi Web "2.0 ". Wikipedia mencoba
mendaftar kategori social software dari pendekatan fungsional.
Futurelab melihat berbagai macam social software dalam kaitannya
dengan teknologi pendidikan, sedangkan Patrick & Dotsika lebih
memahami social software sebagai variasi dari berbagai layanan Web.
Sosial Software Untuk Pendidikan
Personalisasi merupakan salah satu aspek kunci dalam
pengembangan social software saat ini dan selanjutnya. Shim, dkk.
(2007) telah melakukan penelitian dengan menggunakan teori
kekayaan-media (media richness theory) untuk menguji faktor yang
memengaruhi siswa untuk menggunakan RSS podcast dan juga fitur
yang sudah termasuk dalam teknologi ini, dikaitkan dengan proses
belajar mereka. Mereka menemukan bahwa teknologi podcast telah
memberikan banyak manfaat termasuk mudahnya siswa dalam
memahami materi melalui teknologi baru ini dan tingkat efektivitas
biaya dalam jangka panjang yang lebih baik. Meskipun begitu
teknologi podcasting tidak dapat digunakan untuk mengganti model
pengajaran kelas konvensional. Sebaliknya Shim, dkk. menambahkan,
teknologi podcast dapat digunakan untuk mendukung materi-materi
yang diberikan di kelas sehingga siswa dapat lebih memahami konsep,
teori, dan aplikasi yang mungkin belum disampaikan di kelas. (Shim
dkk., 2007).
Wiki adalah salah satu platform menulis paling populer
diantara platform social software lainnya (Alexander, 2006) dan
keberadaaannya telah digunakan dalam berbagai cara dalam bidang
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 87
pendidikan. Contoh penggunaan wiki itu yaitu sebagai sebuah situs
sebuah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah di mana siswa dapat
mempresentasikan hasil belajar mereka. Selain itu Wiki dapat
dipergunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data yang
berkaitan dengan proses belajar-mengajar di kelas. Franklin, G. (2007)
menyoroti alat seperti Wiki menawarkan cara-cara baru untuk terlibat
dan berkomunikasi dengan para siswa. Pada tingkatan tertentu Wiki
dapat digunakan sebagai suatu refleksi terutama bila berkaitan dengan
tingkat literasi informasi (information literacy) para siswa, bahkan
termasuk gurunya sendiri. Literasi informasi merupakan salah satu
keterampilan literasi baru (Miners dan Pascopella, 2007) yang
dianggap sebagai suatu standar keterampilan abad ke-21 di samping
literasi media (media literacy) dan literasi ICT (ICT literacy). Dengan
menggunakan Wiki, siswa dan guru dapat dengan cepat dan mudah
menjelajahi wilayah pengetahuan yang sedang dibahas dan
mengembangkan struktur informasi sebanyak yang mereka perlukan.
Dengan memungkinkan kerja kolaborasi ini Wiki tidak hanya
menyediakan media dalam proses belajar-mengajar melainkan juga
mendorong baik siswa dan guru agar aktif berdasarkan kemampuan
mereka sendiri dalam menulis (Bryant, 2007).
Meskipun beberapa perangkat lunak dengan akses-terbuka
(open access software) seperti Wikipedia, GoogleDocs, Socialtext,
dan TWiki telah terbukti sangat berguna untuk menjadi media
komunikasi dalam pendidikan, masih ada beberapa keraguan dan
perdebatan tentang kredibilitas dan konsistensi isinya. Diskursus
tersebut muncul karena muatan dari social software itu sendiri yang
rentan terhadap suntingan tidak bertanggungjawab, vandalisme, dan
sabotase oleh kelompok-kelompok tertentu ( Stvilia dkk., 2005 dalam
Anderson, 2007; Futurelab, 2006). Rector (2007) telah melakukan
studi perbandingan antara artikel dari Wikipedia dan artikel dari
Encyclopedia Britannica, the Dictionary of American History dan
American National Biography Online tentang kelengkapan dan
keakuratan muatan artikel. Dia mengungkapkan ketidakakuratan
dalam delapan dari sembilan masukan (entries) dan memiliki cacat
keakuratan yang besar dalam setidaknya dua dari sembilan artikel
Wikipedia. Secara keseluruhan, Rector menilai bahwa tingkat akurasi
Wikipedia berkisar 80 persen dibandingkan dengan tingkat akurasi
sumber-sumber lain yang mencapai 95-96 persen. Kajian ini
88 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
mendukung klaim bahwa Wikipedia kurang dapat diandalkan
dibandingkan sumber-sumber referensi lainnya.
Selain Wiki, platform social software yang menyediakan
wadah untuk menulis adalah weblog (blogs) dan mungkin adalah
perangkat lunak yang paling banyak digunakan dalam praktek
pendidikan (Bryant, 2007). Contoh kegiatan yang menggunakan blog
untuk tujuan pendidikan antara lain guru dapat menggunakan blog
untuk sebagai media pengumuman, berita dan umpan balik ke
mahasiswa dan dalam penggunaanya dapat digabungkan dengan
teknologi sindikasi (RSS feed) yang memungkinkan kelompok peserta
didik dengan mudah melacak tulisan (posting) yang baru (Franklin, T.,
2007). Dengan menggunakan fitur RSS atau tag, guru dan siswa juga
dapat menggunakan situs-situs seperti Technorati dan IceRocket untuk
mencari blog tertentu berkaitan dengan subjek pelajaran.
Platform social software lainnya adalah social bookmark, yaitu
fasilitas di internet yang dapat digunakan untuk menandai (bookmark)
atau memberikan label (tagging) dari halaman situs yang ingin
disimpan. Dengan fasilitas ini, penguna dapat membuka dan
mengakses halaman situs yang sama tanpa perlu mencarinya kembali
lewat mesin pencari (search engine). Bryant (2007) menekankan
bahwa social bookmark ideal dan cocok untuk digunakan sebagai
bagian dari proses belajar-mengajar di ruang kelas dengan
memungkinkan sekelompok siswa untuk membangun berbagai jenis
struktur informasi untuk topik tertentu.
Adopsi Internet di Indonesia
Jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat pesat
lebih dari 1,150% dari 2 juta pengguna di tahun 2000 menjadi 25 juta
pengguna pada kuartal kedua 2008 (Internet World Statistic, 2008).
Walaupun cukup mencengangkan dalam segi kuantitas tingkat
pertumbuhan tetapi mengingat jumlah penduduknya yang sudah 238
juta jiwa, kepadatan pengguna internet di Indonesia hanyalah 10,5%
dari total penduduk. (Internet World Statistic, 2008). Sebuah studi
yang dilakukan pada tahun 2004 menemukan bahwa dua pertiga dari
pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui warung
internet (warnet) dan 68% dari pengguna warung internet adalah laki-
laki (Wahid, Furuholt, dan Kristiansen, 2004 dalam Wahid, 2007).
Dengan menggunakan model adopsi teknologi (Technology Adoption
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 89
Model /TAM) Wahid (2007) meneliti perbedaan adopsi internet di
antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Studinya menemukan
bahwa adopsi internet di kalangan laki-laki lebih dipengaruhi oleh
persepsi dari kegunaan internet dibandingkan persepsi kemudahan
penggunaannya, fenomena sebaliknya ditemui dalam adopsi internet
oleh perempuan. Studi itu juga menujukkan bahwa laki-laki
menujukkan fleksibelitas tempat akses internet yang lebih tinggi
dibandingkan perempuan. Proporsi perempuan yang menggunakan
internet untuk berbincang (chatting) dan aktivitas yang berkaitan
dengan proses belajar lebih besar dari laki-laki. Sebaliknya, proporsi
laki-laki yang menggunakan internet untuk membaca berita online,
pengujian dan download software, berbelanja, hiburan, mencari
lowongan pekerjaan, dan mengunjungi situs porno lebih besar dari
perempuan.
Biaya akses internet yang tinggi, rendahnya kecepatan akses
internet dan kurangnya kemampuan berbahasa Inggris diidentifikasi
menjadi kendala paling besar dalam adopsi internet di Indonesia.
Namun, Wahid memberikan kesimpulan umum bahwa tingkat adopsi
internet di Indonesia pada kalangan wanita lebih rendah daripada laki-
laki.
Penggunaan Social Software Pada PTN-PTN di Indonesia
Di tahun 2004 telah terdapat 46 PTN dan lebih dari 2.200
institusi pendidikan tinggi, termasuk lembaga, perguruan tinggi, dan
akademi di seluruh Indonesia (DIKTI, 2004). Untuk mendapatkan
landasan data yang kuat sehingga dapat dipergunakan untuk
menyelidiki lebih dalam mengenai perilaku penggunaan social
software di tingkat universitas maka langkah awal yang peneliti
lakukan adalah mengumpulkan data mengenai penggunaan social
software sebagai bagian dari infrastrukstur-maya (cyber-
infrastructure) dari PTN-PTN di Indonesia. Oleh karena itu survei
yang sederhana dilakukan untuk melihat seberapa banyak dari situs-
situs PTN tersebut yang telah memasukkan setidaknya satu dari
banyak platform social software di situs mereka. Untuk definisi
operasional, peneliti mengambil kategori social software berdasarkan
daftar yang dibuat oleh Wikipedia. Peneliti menggunakan daftar yang
ada di Wikipedia dikarenakan dua alasan; pertama, daftar kategori
yang dimuat Wikipedia menggunakan istilah yang sudah dikenal oleh
90 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
pengguna social software secara umum. Kedua, penggunaan kategori-
kategori yang dibuat dimiliki oleh Wikipedia adalah untuk
menghindari ambiguisitas dari penggunaan label social software itu
sendiri.
Sebagai perbandingan keberadaan infrastruktur-maya di bidang
pendidikan, peneliti juga menghitung keberadaan perpustakaan digital
(digital library) pada situs-situs PTN tersebut. Asumsi di balik
pengikutsertaan ini adalah bahwa melihat perkembangan teknologi
yang pesat membuat kebutuhan atas social software berada pada
tingkatan yang sama dengan keberadaan perpustakaan digital. Hasil
dari survei sederhana sebagaimana ditunjukkan oleh Diagram 1.
menunjukkan bahwa keberadaan e-Learning dan perpustakaan digital
berdiri di persentase tertinggi di antara aplikasi dan perangkat lunak
lainnya (50%). Diantara platform lainnya, peneliti menemukan dari 18
kategori social software di Wikipedia hanya 5 yang digunakan dalam
situs-situs diamati termasuk e-Learning. Persentase penggunaan dapat
dikatakan tidak cukup signifikan berdasarkan kuantitas terutama jika
kita mengingat bahwa aplikasi Web 2.0 telah dikenal di seluruh dunia
setidaknya sejak 2004. Walaupun demikian, terdapat satu hal yang
sangat positif pada situs Universitas Paddjajaran yang telah
menciptakan sebuah media-sharing websites
(http://video.unpad.ac.id/). Di mana dokumen-dokumen visual
perkuliahan dapat disimpan dan terbuka untuk umum. Situs ini
merupakan suatu terobosan terdepan diantara situs-situs resmi PTN di
Indonesia bahkan di tingkat Asia Tenggara dalam melaksanakan
pendidikan berbasis teknologi web.
Berdasarkan data awal seperti terlihat pada diagaram 1 peneliti
kemudian memberikan skor penggunaan social software oleh PTN.
Skor tersebut didistribusikan sebagai 1-2 (skor rendah), 3-4 (skor
sedang), dan 5-6 (skor tinggi). 9 undangan kemudian didistribusikan
ke 9 PTN berdasarkan penggunaan social software di situs mereka. 3
undangan untuk masing-masing tingkat skor PTN dengan skor tinggi,
menengah dan rendah untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari 9
undangan, peneliti hanya menerima tanggapan dari 4 perguruan tinggi,
2 tanggapan dari PTN dengan skor tinggi yaitu Universitas
Padjadjaran dan Universitas Lampung, dan 2 dari PTN dengan skor
rendah yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Jenderal
Soedirman. Kemudian proses wawancara dilakukan antara Juli hingga
Oktober 2008 terhadap 4 responden, 3 laki-laki dan 1 perempuan,
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 91
dengan rentang usia responden antara 26 hingga 38 tahun. Responden
pada penelitian ini mempunyai kriteria sebagai tenaga pengajar tetap
pada universitas yang bersangkutan, berpendidikan sekurang-
kurangnya S2 dan telah mempunyai pengalaman menggunakan social
software, karakteristik responden lain yang muncul kemudian adalah
responden telah mempunyai pengalaman mengajar antara 3 sampai 6
tahun.
Diagram 1
Penggunaan Social Software Pada Website PTN Di Indonesia
(Per Juli 2008)
Tehnik wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan
data dikarenakan waktu penelitian yang dilakukan selama masa
liburan perkuliahan dan awal tahun ajaran 2008/2009 sehingga
sulit bagi peneliti untuk melakukan pengamatan lapangan terhadap
responden di lingkungan mereka sebenarnya. Selain itu, penelitian
ini bersifat independen atau tidak didanai oleh siapapun sehingga
peneliti berusaha menekan biaya pengeluaran seminimal mungkin.
Fokus utama dalam wawancara adalah mencari data mengenai
aktivitas dan pengalaman para responden berkaitan dengan
penggunaan social software dan proses pengajaran yang mereka
lakukan.
PEMBAHASAN
Keberadaan fasilitas internet memang memengaruhi
penggunaan internet di antara para informan, 3 dari mereka
mengatakan bahwa fasilitas wifi yang disediakan oleh pihak
92 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
universitas memang meningkatkan waktu mereka mengakses internet
(online) antara 6 hingga 12 jam per minggu. Hanya seorang informan
yang menggunakan sambungan dial-up (modem) untuk mengakses
internet dikarenakan tidak adanya fasilitas wifi di fakultasnya. Alasan
utama mereka memilih untuk mengakses internet dari universitas
dikarenakan fasilitas tersebut gratis. Tempat kedua para informan
mengakses internet setelah universitas adalah di warung internet
(warnet) dengan intensitas antara 1 sampai 6 jam per minggu.
Mengenai asal mulanya mereka belajar internet seorang informan
mengatakan bahwa seorang teman yang mengajarkan kepada dia
bagaimana cara menggunakan internet. Sedangkan informan lainnya
mengatakan bahwa mereka belajar bagaimana menggunakan internet
dan social software secara otodidak. Temuan ini mungkin tidak
mendukung penelitian sebelumnya tentang adopsi internet di
Indonesia oleh Wahid (2007). Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih
melihat pada aspek kualitatif dari penggunaan internet di Indonesia
terlebih pada karakteristik informan yang spesifik sekali. Sekalipun
demikian, data di atas mendukung penelitian yang terdahulu oleh
Wahid, Furuholt, dan Kristiansen (2004 dalam Wahid, 2007) bahwa
sebagian besar pengguna internet di Indonesia mendapat akses mereka
dari warung internet.
Dari wawancara, peneliti menemukan bahwa penggunaan
social software telah dilakukan oleh para informan sebagai media
komunikasi dari proses pengajaran di kelas. Popularitas adalah motif
utama mengapa mereka menggunakan social software sementara ada
juga beberapa yang berpendapat hal ini sebagai usaha mereka untuk
lebih dekat dengan perkembangan teknologi terbaru. Dengan alasan
tersebut maka mudah dimengerti ketika para informan ditanya
mengenai social software apa sajakah yang mereka gunakan,
kesemuanya menjawab dari social software yang paling populer
seperti situs-situs jejaring sosial yaitu Facebook, Multiply, dan
Friendster, kemudian YouTube untuk media-sharing website,
Blogspot untuk weblog, dan Wikipedia. Untuk platform lainnya
mereka akui bahwa mereka mengetahui aplikasi tersebut tetapi tidak
pernah menggunakannya. Salah seorang informan mengatakan bahwa
dia baru saja mulai mengakrabkan diri dengan penggunaan social
software sekitar setahun belakangan dan menurutnya sangat
melelahkan untuk terus menerus beradaptasi dengan versi-versi
terbaru dari social software.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 93
Beberapa perilaku dasar dari penggunaan internet seperti
mengunduh (download), meng-upload, mencari (searching),
menjelajah (browsing), membaca, dan menonton adalah aktivitas yang
paling banyak informan-informan tersebut lakukan dengan
menggunakan social software. Sementara fitur fitur social software
seperti berbagi (sharing), komentar (commenting), melabel (tagging),
memberikan tanda bendera (flagging), dan mengikutsertakan
(embedding) adalah fasilitas-fasilitas yang paling sedikit digunakan
oleh para informan. Temuan ini menarik dikarenakan sesungguhnya
fasilitas-fasilitas yang paling sedikit digunakan itulah yang membuat
social software begitu terkenal penggunaannya. Namun, berkaitan
dengan penggunaan social software sebagai media komunikasi dalam
proses pengajaran, peneliti menemukan beberapa model kegiatan,
antara lain;
a. Mendorong kemampuan menulis mahasiswa dengan
menggunakan blog.
Belajar tidak selalu tentang hasil akhir, terutama bagi mahasiswa
ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, mereka juga harus dimotivasi
dan didorong untuk mengemukakan pendapatnya tentang
fenomena sosial di dunia nyata. Salah satu kegiatan yang dapat
membawa mahasiswa untuk belajar bagaimana mengekspresikan
pemikiran mereka adalah dengan menulis artikel. Mudahnya
penggunaan dan banyaknya pilihan platform membuat blog tidak
hanya cocok sebagai media untuk membantu mahasiswa dalam
proses belajar mereka tetapi juga media bagi sang dosen untuk
mengekspresikan pemikiran mereka mengenai bahan kuliah yang
diajarkannya. Seorang informan berusaha untuk menggabungkan
apresiasi mahasiswa di kelasnya dengan kesukaan mereka untuk
menulis di blog. Ia menugaskan mahasiswanya untuk
menempatkan tulisan-tulisan mereka dalam blog yang sudah
dipersiapkan oleh sang dosen. Setelah itu dia memilih beberapa
artikel terbaik sebagai komponen dalam ujian semester. Dari 40
mahasiswa yang berpartisipasi dalam matakuliah komunikasi
politiknya, 23 mahasiswa kemudian memiliki blog mereka
pribadi.
b. Menggunakan contoh dari media-sharing website untuk
menjelaskan materi kelas.
Ada banyak subjek studi yang kadang-kadang membuat
mahasiswa benar-benar harus berusaha keras untuk bisa
94 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
memahaminya, kecuali jika sang dosen membantu mereka dengan
visualisasi contoh. Semua informan mengakui mereka adalah
pengguna YouTube tetapi hanya seorang informan yang telah
menggunakan YouTube sebagai bagian dari proses
pengajarannya. Sang informan mengatakan bahwa dia
menggunakan video contoh iklan layanan masyarakat (Public
Service Adds/PSA) yang ia temukan dari YouTube di dalam kelas
Social Marketing-nya. Sebelumnya ia kesulitan memberikan
contoh video PSA dikarenakan hak cipta dan keterbatasan
anggaran untuk kegiatan pengajaran di universitasnya. Dengan
menggunakan media-sharing website seperti YouTube, ia dapat
membantu mahasiswanya untuk memiliki pemahaman yang lebih
baik mengenai fenomena sosial yang sedang dibahas dikelasnya.
c. Menerbitkan hasil ujian semester pada blog sang dosen.
Ketika mereka ditanya apakah mereka telah menggunakan
perangkat lunak sosial untuk membantu aktivitas mereka
mengajar dan untuk alasan apa, sebagian besar dari mereka
mengakui bahwa mereka telah menggunakan sekurang-kurangnya
memublikasikan nilai ujian kelas dan juga bahan kuliah di blog
mereka. Seorang informan memberikan alasan bahwa dia memilih
untuk menggunakan blog dalam menyebarluaskan materi
kuliahnya dikarenakan dengan memanfaatkan media komunikasi
tersebut lebih mudah baginya untuk menjangkau mahasiswa-
mahasiswanya. Dia juga berpendapat bahwa dengan
menggunakan blog, dia memberikan kepada mahasiswa waktu
yang lebih leluasa untuk mengakses materi kuliah di luar kelas
atau membaca bahan ujian atau nilai tanpa harus kuatir tercampur
dengan jam belajar mereka di kampus. Informan lain juga
merasakan bahwa mahasiswanya terlihat lebih aktif dalam
mencari bahan perkuliahan dan lebih bisa mengingatnya.
d. Menyebarluaskan materi perkuliahan dengan menggunakan
file-sharing websites.
Fasilitas yang menonjol dari file-sharing website seperti
Megaupload, Rapidshare dan Slideshare adalah kemampuannya
untuk menyimpan dokumen-dokumen digital secara gratis
ataupun mengunduh dokumen-dokumen lainnya. Bagi informan,
situs seperti ini membantu mereka untuk menyebarluaskan materi
perkuliahan dan menyediakannya secara online sepanjang waktu
sehingga bisa diakses mahasiswanya kapan saja dan dimana saja.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 95
e. Menunjukkan empati sang pengajar melalui situs jejaring
sosial.
Peneliti menemukan fakta menarik yang berkaitan dengan
penggunaan social software, terutama yang populer, seperti
menjadi anggota situs jejaring sosial. Dua orang informan
menyatakan dengan bergabung pada situs jejaring sosial tersebut
mereka merasa lebih dekat dengan anak didiknya dibandingkan
sebelum menggunakannya. Seorang informan menyebutkan
bahwa sejak ia bergabung di tahun 2005 sebagai anggota salah
satu situs jejaring sosial yang populer, ia bertemu dengan
mahasiswanya lebih sering dibandingkan dia bertemu dengan
rekan-rekannya seprofesi. Dengan menyetujui undangan
mahasiswanya untuk menjadi teman-teman mereka, ia merasa
lebih dekat dengan anak-anak didiknya atau anak didiknya pun
lebih terbuka kepadanya. Mahasiswa-mahasiswa tersebut kadang
bertanya kepadanya mengenai jadwal kelas, dan ingin berbicara
'dari hati ke hati' dengannya.
f. Beberapa Tantangan Dalam Penerapan Social Software
Meskipun penggunaan social software sudah terbukti membantu
dan dapat berperan sebagai media komunikasi dalam proses
pengajaran tetapi dalam penyebarluasannya masih menemui
banyak tantangan. Tantangan tersebut terutama datang dari pihak-
pihak yang belum dirangkul oleh teknologi ini. Seorang informan
berkata bahwa ia pernah memberikan tugas di kelasnya dengan
menggunakan blog dan meminta mahasiswanya untuk mengirim
jawaban mereka melalui email kepadanya. Kemudian, dia
menerima protes dari salah seorang mahasiswa karena hal
tersebut menyebabkan sang mahasiswa menghabiskan lebih
banyak uang dan waktu untuk mengakses internet di warnet, pada
saat itu memang belum ada akses internet gratis di universitas
sang informan. Tantangan tidak hanya datang dari mahasiswa
tetapi juga dari rekan-rekan informan lainnya yang tidak
menggunakan teknologi tersebut karena banyak faktor, terutama
karena sudah berumur/senior dan biaya yang mesti dikeluarkan.
Seperti yang dikatakan seorang informan; " Secara umum di
lingkungan fakultas saya memang belum banyak yang paham.
Meskipun pihak fakultas telah memfasilitasinya. Karena pada
dasarnya ketidaktahuan mereka hanyalah pada kurangnya
keinginan mereka untuk belajar. "(Informan 2). Diluar hambatan
96 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
di atas, tantangan mungkin datang dari diri mereka sendiri, seperti
pengetahuan mereka tentang perangkat lunak dan bagaimana
menggunakannya. Meskipun sebagian besar social software yang
populer saat ini sangat mudah digunakan dan lebih intuitif. Salah
seorang informan mengatakan bahwa dia mengalami hambatan
dalam menggunakan beberapa social software dikarenakan
kurangnya pemahaman dia tentang penggunaan perangkat lunak
itu sendiri.
KESIMPULAN
1. Hadirnya social software atau juga dikenal sebagai social media
telah memengaruhi berbagai aspek kegiatan manusia saat ini.
Walaupun berbagai studi tentang penggunaan teknologi web ini
dalam dunia pendidikan telah dilakukan di banyak negara maju,
studi tentang pemanfaatannya di negara-negara berkembang masih
rendah termasuk di Indonesia.
2. Social software sebagai suatu media komunikasi dalam proses
belajar-mengajar di Indonesia sudah diterapkan oleh sebagian
sistem pendidikan di universitas-universitas negeri di tanah air.
Survei awal ini menemukan bahwa penggunaan social software
oleh PTN-PTN di Indonesia masih rendah.
3. Temuan selanjutnya bahwa, model praktek-praktek penggunaan
social software sebagai media komunikasi dalam proses
pengajaran adalah : pertama, mendorong kemampuan menulis
siswa dengan menggunakan blog. Kedua, dosen menggunakan
contoh-contoh dari media-sharing website untuk menjelaskan
materi kelas. Ketiga, dosen menerbitkan hasil ujian semester pada
blog dan menyebarluaskan materi perkuliahan dengan
menggunakan file-sharing websites. Keempat, dapat menunjukkan
empati sang pengajar melalui situs jejaring sosial kepada
mahasiswa.
DAFTAR PUSTAKA
Yuhetty, H. 2002. ICT and Education in Indonesia. Diunduh pada
tanggal 24 Oktober 2008, dari Indonesia Ministry of National
Education official website:
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 97
http://eprints.rclis.org/archive/00007507/01/Indonesia-ICT-
paper.pdf
Allen, C. (2004, October 13). Tracing the Evolution of Social
Software. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2008, dari Life With
Alacrity:
http://www.lifewithalacrity.com/2004/10/tracing_the_evo.ht
ml
DIKTI. 2004. Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010.
Jakarta: DIKTI.
Alexander, B. 2006, March/April. Web 2.0; A New Wave of
Innovation for Teaching and Learning? Educause Review ,
pp. 33-44.
O'Reilly, T. 2005, September 30. What Is Web 2.0; Design Patterns
and Business Models for the Next Generation of Software.
Diunduh pada tanggal 12 Juni 2008, dari O'Reilly:
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/3
0/what-is-web-20.html
Dotsika, F. a. 2006. Towards The New Generation of Web Knowledge.
VINE: The Journal of Information and Knowledge
Management Systems , 36 (4), 406-422.
Futurelab. 2006. Opening Education; Social Software and Learning.
UK: Futurelab.
Anderson, P. 2007. What is Web 2.0? Ideas, technologies and
implications for education. UK: JISC Technology and
Standards Watch.
APJII. 2007, December. Statistik APJII. Diunduh pada tanggal 6
Oktober 2008, dari APJII:
http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind
Bryant, L. 2007. Emerging Trends in Social Software for Education.
Emerging Technologies for Learning , 2, pp. 8-20.
Farkas, M. G. 2007. Social software in libraries: building
collaboration, communication, and community online.
Medford, NJ: Information Today Inc.
Franklin, G. 2007. Wiki anyone? Reflections on an information
literacy class wiki. Journal of information literacy , 1 (3).
Franklin, T., & Harmelen, M. v. 2007. Web 2.0 for Content for
Learning and Teaching in Higher Education. London, UK:
Franklin Consulting.
98 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Kirriemuir, J. 2007, October. The Second Life of UK Academics.
Ariadne (53).
Maxymuk, J. 2007. Bits & Bytes, Whose Space? The Bottom Line:
Managing Library Finances , 20 (2), 97-100.
Miners, Z., & Pascopella, A. 2007, October. The New Literacies.
District Administration , pp. 26-34.
Shim, J., Shropshire, J., Park, S., Harris, H., & Campbell, N. 2007.
Podcasting for e-learning, communication, and delivery.
Industrial Management & Data Sytems , 107 (4), 587-600.
Topper, E. F. 2007. What's New In Libraries; Social Networking In
Libraries. New Library World , 108 (7/8), 378-380.
Wahid, F. 2007. Using the Technology Adoption Model to Analyze
Internet Adoption and Use Among Men and Women in
Indonesia. EJISDC , 32 (6), 1-8.
Eijkman, H. 2008. Web 2.0 as a Non-foundational Network-centric
Learning Space. Campus-Wide Information Systems , 25 (2),
93-104.
Ofcomm. 2008. Social Networking: A Quantitative and Qualitative
Research Report Into Attitudes, Behaviours, and Use.
London: Ofcomm Media.
Rector, L. H. 2008. Comparison of Wikipedia and other encyclopedias
for accuracy, breadth, and depth in historical articles.
Reference Services Review , 36 (1), 7-22.
Seegmüller, K. 2008, August. Can Social Software Change Teaching
and Learning? Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2008, dari
Check Point e-Learning: http://www.checkpoint-
elearning.com/article/5813.html
Stats, I. W. 2008, August. Internet Usage in Asia. Diunduh pada
tanggal 12 Oktober 2008, from Internet World Stats:
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
Virkus, S. 2008. Use of Web 2.0 technologies in LIS education:
experiences at Tallinn University, Estonia. Electronic
Library and Information Systems , 262-274.
Wikipedia. 2008, October 8. List of Social Software. Diunduh pada
tanggal 8 Oktober 2008, dari Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_software
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 99
MOTIVASI PENGGUNA WARUNG MASYARAKAT
INFORMASI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN
BERMEDIA DI PROVINSI JAWA BARAT
Syarif Budhirianto*
Abstraksi
Warung Masyarakat Informasi (Warmasif) merupakan model
pengembangan Community Access Point (CAP), yang ditempatkan
dan dikelola oleh unit Bisnis Kantor Pos setempat. Keberadaannya
penting dalam mempercepat tercapainya masyarakat informasi yang
ditargetkan tahun 2015 tercapai, yakni dengan melakukan akses
informasi, interaksi sosial/komunikasi melalui fasilitas teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan tentang motivasi pengguna Warmasif
dalam pemenuhan kebutuhan bermedia bagi masyarakat 7 (tujuh)
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan
bahwa keberadaan Warmasif untuk pemenuhan kebutuhan informasi
dan komunikasi kurang optimal dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
dan sasarannya, sementara pemenuhan kebutuhan hiburan dinilai
cukup tinggi pemanfaatannya.
Kata kunci: CAP, Warmasif, kebutuhan bermedia.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah
satu pilar utama pembangunan bangsa saat ini, dan tidak satu bidang
kehidupan/sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan
penggunaan TIK. Bahkan maju tidaknya suatu negara ditentukan
oleh penguasaan TIK oleh masyarakatnya. Dengan penguasaan
teknologi tersebut, segala aktivitas informasi dan komunikasi dapat
berjalan dengan cepat tanpa ada hambatan batas-batas suatu negara..
* Drs. Syarif Budhirianto adalah peneliti muda di Balai Pengkajian dan
Pengembangan Komunikasi dan Informatika(BP2KI) Bandung.
100 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Untuk terwujudnya masyarakat informasi yang efektif dan
efisien dalam meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah
memberikan fasilitas teknologi informasi dan telematika (TIK) kepada
masyarakat. Salah satu fasilitas yang sudah dilakukan adalah dengan
pemberdayaan telematika dan pemerataan infrastruktur informasi ,
seperti memfasilitasi pembangunan Community Access Point (CAP) di
berbagai daerah di Indonesia.
CAP merupakan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat di
bidang TIK, sehingga mereka dapat mengenal lebih jauh tentang
manfaat dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di
bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta mengurangi
kesenjangan digital/digital device (Infomobilitas,2007:25) . Keterlibatan
masyarakat dalam pemberdayaannya harus mampu mendorong upaya
mewujudkan masyarakat informasi dalam menciptakan peluang-
peluang digital. Saat ini keterlibatan masyarakat lebih banyak
difasilitasi oleh sejumlah inisiatif penyediaan TIK yang berorientasi
bisnis, misalnya wartel atau warnet, komunitas sekolah atau kampus
yang didukung dengan fasilitas internet.
CAP sebagai wahana multiguna untuk pengembangan
masyarakat sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Di Indonesia
tempat-tempat sejenis ini tumbuh dengan beragam nama, diantaranya
Balai Informasi Masyarakat (BIM), Warung Informasi Teknologi
(WARINTEK), Community Learning Centre, Community Training
and Learning Center (CTLC), Warung Masyarakat Informasi
(Warmasif), Telecenter, dan lain-lain. Salah satu model
pengembangan CAP hasil kerja sama Ditjen Aplikasi Telematika cq
Dit. E-Business dengan Kanwil Pos setempat dan Pemerintah Daerah
setempat adalah Warmasif. Salah satu tujuannya adalah mempercepat
dan menunjang tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, usaha
kelautan dan perdagangan komoditi unggulan melalui e-commerce
atau e-UKM yang terdapat di wilayah setempat (Studi Pemberdayaan
CAP,2007 :20).
Dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkan informasi
secara optimal melalui sarana CAP, diantaranya mengetahui harga-
harga pasar dari produk pertanian atau perikanan, sehingga seorang
petani dapat memperkirakan harga yang sesuai untuk hasil
produksinya dan dapat belajar mengenai cara mengolah hasil tani.
Di negara berkembang lainnya, jenis CAP sudah dilakukan
dengan baik, seperti Peru, China, Jordan , India dan lain-lain. Namun
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 101
dengan tidak bermaksud menutupi fakta, ada juga CAP yang dibangun
dan menuai kegagalan memberikan manfaat ekonomis untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dari kasus-kasus
gagal inilah masyarakat pada umumnya menganggap bahwa strategi
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan TIK
tidak tepat sasaran.
Keberadaan 7 (tujuh) Warmasif yang berlokasi di Provinsi
Jawa Barat (Kota Bekasi, Kota Bandung, Kab. Garut, Kota
Tasikmalaya, Kab. Kuningan, Kab. Karawang, dan Kab.Purwakarta)
yang berdiri awal tahun 2007 perkembangannya belum memenuhi
harapan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.Upaya dalam
pembangunan Warmasif memang bukan hal yang mudah dilakukan,
karena diperlukan upaya dan pemahaman yang cukup mendalam.
Tuntutannya bukan saja agar masyarakat mendapatkan akses terhadap
informasi, melainkan juga tatanan kehidupan masyarakat itu, baik
sosial, budaya dan ekonomi juga memerlukan dukungan agar menjadi
lebih baik, lebih transparan dan membuka peluang setiap anggota
masyarakat dalam memanfaatkan TIK. Selain itu dapat bermanfaat
untuk membantu mengatasi masalah kehidupan masyarakat dengan
tidak mengabaikan faktor manusia, perubahan budaya, sikap dan
perilaku yang melandasi kearifan budaya lokal merupakan sesuatu
yang penting dan strategis.
Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka masalah penelitian ini
adalah bagaimana motivasi pengguna Warmasif dalam memenuhi
kebutuhan bermedia di Provinsi Jawa Barat? Identifikasinya adalah :
1. Bagaimana motivasi pengguna dalam mengakses fasilitas-fasilitas
di Warmasif dalam pemenuhan kebutuhan informasinya.
2. Bagaimana motivasi pengguna dalam pemenuhan kebutuhan
hiburannya
3. Bagaimana motivasi pengguna dalam pemenuhan kebutuhan
komunikasi (interaksi sosial).
Tujuan
1. Untuk mengetahui pemanfaatan warmasif oleh pengguna dalam
pemenuhan kebutuhan informasi.
102 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
2. Untuk mengetahui motivasi pengguna dalam mengakses fasilitas-
fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan hiburan dan
komunikasi/interaksi sosialnya.
3. Untuk mengetahui motivasi pengguna dalam pemenuhan
kebutuhan berkomunikasi (interaksi sosial).
Manfaat
1. Bermanfaat bagi Ditjen Aplikasi dan Telematika Departemen
Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyusunan program,
strategi dan kebijakan pemberdayaan Warmasif sebagai sarana
pemenuhan kebutuhan informasi sesuai dengan sasaran dan
tujuannya.
2. Berguna bagi pengelola Warmasif dalam meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
3. Melalui peningkatan fungsi, peran dan pemanfaatan secara optimal
berguna bagi masyarakat untuk mendukung upaya mempercepat
tercapainya masyarakat informasi Indonesia yang ditargetkan
tahun 2015.
Kerangka Pemikiran
Motivasi dan Kebutuhan Media
Kebutuhan manusia yang berkaitan dengan media menurut
McQuail dalam Lull (1998:120) meliputi kebutuhan akan informasi,
hiburan dan integrasi sosial. Lebih lanjut menurut Katz, bahwa untuk
memenuhi kebutuhan bermedia , setiap individu dapat mencapainya
dengan cara pemenuhan kebutuhan yang didapatkan dengan cara
mengakses/menggunakan media yang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhannya itu.
Menurut Gerungan (1983: 25), motif merupakan suatu
pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan, atau
dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat
sesuatu “. Berkaitan dengan motif manusia yang menggunakan media
internet, hal ini didasarkan pada suatu kebutuhan tertentu. , menurut
Katz dalam Marshall (2000), beberapa kategori kebutuhan individu
yang semuanya berasal dari fungsi sosial dan psikologi dari media
diantaranya kebutuhan kognitif, afektif, integrative personal, interaksi
sosial, dan kebutuhan akan pelarian.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 103
Media internet merupakan salah satu media massa yang pada
pemunculannya bisa disebut membuat revolusi tersendiri baik untuk
dunia komputer maupun pada dunia media massa. Media ini memiliki
daya tarik tersendiri. Dalam hal daya tarik komunikasi, internet
menawarkan kemampuan berkomunikasi secara elektronik (e-mail
dan chatting) yang relatif mudah dan murah selama 24 jam penuh.
Internet juga memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk
mencari dan mengakses berbagai macam informasi.
Hunter beranggapan bahwa “Audiens tidak sepenuhnya pasif
tetapi mereka merupakan individu yang secara sadar memilih jenis
dan isi media. Dari media inilah mereka mencari informasi dan
mendapatkan hiburan untuk memuaskan kebutuhan pribadi dan sosial
mereka”. Dengan kata lain, teori ini menunjukan bahwa “ yang
menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah
sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi
kebutuhan pribadi dan sosial khalayak” (Effendi,1993:289)
Kemudian Katz Hass dan Gurevitch memberikan beberapa
kategori kebutuhan individu, yang semuanya berasal dari fungsi sosial
dan psikologi dari media, kategori ini antara lain:
1. Kebutuhan interaksi sosial : memperkuat hubungan dengan
keluarga, teman, dengan alam sekitar.
2. Kebutuhan akan pelarian : hasrat melarikan diri dari kenyataan,
melepaskan ketegangan, kebutuhan akan hiburan. (Marshall,Jr.,
2000)
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dicapai dengan dua
cara, yaitu : (1) Pemenuhan kebutuhan yang didapatkan dengan cara
mengakses/menggunakan media yang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan (2) Pemenuhan kebutuhan didapatkan dengan cara
mempelajari isi informasi dalam media yang kemudian diterapkan
dalam praktek.
Berdasarkan hal tersebut, dapatlah diambil suatu modifikasi
tentang macam-macam kebutuhan yang menjadi dasar motivasi para
pengguna media internet ke dalam empat bagian yang mencakup
fenomena penggunaan media internet dan www, yaitu :pemenuhan
kebutuhan informasi, hiburan, interaksi sosial, serta kebutuhan
pendidikan. Sehingga bagi masyarakat pengguna teknologi informasi
dan komunikasi dapat meningkatkan terpaan media alternatif , di
samping penggunaan media ini sebagai pemberdayaan dalam
104 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
meningkatkan pemakaian TIK, atau mengeleminir kesenjangan digital
di masyarakat digital divide. (Kominfo,2002)
Adapun pengertian dari motivasi menurut Sumantri adalah
suatu proses penting untuk memahami tentang mengapa dan
bagaimana perilaku seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu,
yakni :
1. Kebutuhan (needs): kebutuhan merupakan suatu kekurangan dalam
pengertian keseimbangan, kebutuhan tercipta apabila terjadi
ketidakseimbangan fisiologis, psikologis atau sosiologis.
2. Dorongan (drives): berorientasi pada tindakan untuk mencapai
tujuan.
3. Tujuan (goals): segala sesuatu yang akan meredakan suatu
kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. (Sumantri,2001:54)
Manusia mempunyai kebutuhan yang diusahakan untuk
dipenuhi atau berusaha untuk dipuaskan. Kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan inilah yang menjadi motivasi setiap individu. Menurut
Halloran, motivasi adalah proses yang terdiri dari 3 tahap , yaitu :
kebutuhan internal (internal need), kegiatan untuk memuaskan
kebutuhan (a behavioral action to satisfy that need), dan pelaksanaan
pemuasan kebutuhan itu (the accomplishment or the satisfaction of
that need)(Effendi, 1993:113).
Media Internet dan Community Access Point
Di Provinsi Jawa Barat termasuk di tujuh kabupaten dan kota
yang terdapat Warmasif, kini semakin banyak orang yang
memanfaatkan internet untuk bermacam-macam kebutuhan, seperti
kebutuhan akan informasi, hiburan maupun interaksi sosial, bahkan
untuk keperluan bisnis. Selain telah secara revolusioner mengubah
metode komunikasi massa dan penyebaran data atau informasi,
internet juga telah membuktikan sebagai medium berjangkauan massal
yang paling fleksibel.
Media internet dapat dengan mudah mengintegrasikan seluruh
bentuk media massa konvensional seperti media cetak dan audio
visual bahkan tradisi lisan (oral tradition) melalui fasilitas-fasilitas
yang ada. Fasilitas tersebut menurut Yuswanto adalah :
1. Fasilitas search engine : fasilitas pada media internet yang
dirancang khusus untuk menyimpan serta menyusun jutaan alamat
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 105
situs yang sudah didaftarkan sebelumnya berdasarkan topik-topik
tertentu, seperti www.yahoo.com
2. Fasilitas situs web (web sites) : fasilitas pada media internet yang
menyimpan semua jenis informasi (file tulisan, gambar, video dan
suara). Pada situs web ini tersimpan halaman web (web page) yang
saling terhubung.
3. Fasilitas e-mail (electronic mail) : fasilitas pada media internet dan
www yang berguna untuk mengirimkan pesan dalam format data
elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya. Ketika
mengirimkan e-mail, pesan tersebut dikirimkan ke komputer yang
ada di ISP (internet service provider) yang kemudian dikirimkan
kepada penerima pesan.
4. Fasilitas Internet Relay Chat (chatting) : fasilitas pada media
internet dan www yang memungkinkan para penggunanya untuk
melakukan percakapan mengenai topik tertentu
5. Fasilitas FTP (file transfer protocol) : fasilitas pada media internet
yang dirancang untuk mengirimkan (upload) dan menerima
(download) suatu data.
6. Fasilitas order : fasilitas pada media internet yang memungkinkan
para penggunanya melakukan suatu transaksi ekonomi dengan
sistem keamanan yang sangat pribadi. (Yuswanto,2000:3)
CAP merupakan sebuah pusat atau sentra di mana masyarakat
(khususnya yang berada di perdesaan) dapat melakukan berbagai
aktivitas komunikasi dan pengaksesan informasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia,
terutama telepon, faksimili, komputer berikut perangkat
pendukungnya, akses internet, dan layanan informasi lainnya, serta
layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
seperti peningkatan wawasan, ketrampilan, keahlian melalui
pendidikan dan latihan bagi masyarakat.
Proyek Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) kerjasama
Bappenas dengan UNDP, dengan pengembangan telesenter sebagai
model dari CAP, merupakan suatu fasilitas tempat masyarakat dapat
berinteraksi, belajar , bekerja dan mendapat hiburan dengan
memanfaatkan komputer, internet dan berbagai teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) lainnya. Telecenter memungkinkan
masyarakat melakukan hal tersebut dengan pihak di luar daerahnya,
bahkan dengan dunia internasional melalui internet. Walaupun
106 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
berbeda-beda bentuknya, telecenter mempunyai karakteristik khusus,
yaitu mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti
membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan
bernegara, berdemokrasi dan pembangunan, meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam berorganisasi dan melakukan usaha , meningkatkan
peran serta pemuda/i dan perempuan, mengurangi keterisoliran,
mengurangi kesenjangan digital, dan sebagainya. (Proyek Bappenas &
UNDP, 2007:17).
Pada dasarnya CAP bertujuan untuk : Pertama, meningkatkan
kesadaran masyarakat perdesaan tentang arti penting informasi dan
penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sekaligus
mengurangi kesenjangan akses informasi antara masyarakat perkotaan
dan perdesaan. Kedua, memberikan peluang untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat perdesaan dengan memanfaatkan ICT. Ketiga,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui perbaikan
tingkat pendapatan. Keempat, memerangi kemiskinan dengan
memanfaatkan ICT.
Metode Penelitian
1. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, pendekatannya kuantitatif,
yakni untuk mengungkapkan motivasi pengguna (user) Warmasif
sebagai pemenuhan kebutuhan bermedia di 7 ( tujuh )
kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap pemenuhan bermedia.
Lokasi penelitian adalah di Provinsi Jawa Barat. Dari 26 jumlah
kota dan kabupaten yang ada, hanya ada 7 (tujuh) kabupaten dan
kota yang terdapat fasilitas Warung Masyarakat Informasi (
Warmasif ), yaitu berdasarkan kesepakatan Direktorat Aplikasi dan
Telekomunikasi (Depkominfo) dengan PT. Pos Indonesia yakni,
Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kab. Karawang,
Kab. Kuningan, Kab. Garut, dan Kab. Purwakarta.
2. Responden penelitian untuk masing-masing Warmasif adalah 10
orang , jumlah keseluruhan 70 responden. Pengambilan responden
untuk masing-masing Warmasif dilakukan dengan sampel random
secara ordinal (Ordinal random sampling). Adapun dalam konteks
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan
daftar catatan pengunjung dalam sebulan terakhir, kemudian
daftar tersebut di satukan untuk diberi nomor secara berurutan
mulai dari nomor satu sampai terakhir. Untuk pengambilan sampel,
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 107
diambil secara purposif mulai dari nomor ganjil terkecil (nomor
1,3,5 dan seterusnya sampai mendapat 10 sampel)
Adapun data populasi atau pengunjung warung masyarakat
informasi tanggal 1 – 30 April 2007 (Minggu tutup) per lokasi
penelitian berdasarkan data hasil pra penelitian, sebagai berikut :
No. Lokasi Warmasif Jumlah Pengguna
1. Kota Bandung 130 orang
2. Kota Bekasi 35 orang
3. Kota Tasikmalaya 78 orang
4. Kab. Karawang 52 orang
5. Kab.Kuningan 12 orang
6. Kab. Garut 101 orang
7. Kab. Purwakarta 19 orang
Sumber:Pengelola Warmasif Setempat, April 2007 (diolah)
3. Pengumpulan data primer adalah kuesioner serta wawancara
dengan pengelola dan nara sumber di lokasi penelitian. Sedangkan
data sekunder melalui studi kepustakaan dan literatur.
4. Pengolahan data dilakukan dengan menginventarisir seluruh data
yang terkumpul dari hasil pengisian kuesioner serta hasil
wawancara, selanjutnya dilakukan perhitungan tabulasi frekuensi,
dan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi.
Definisi dan Operasionalisasi Konsep
Definisi Konsep
Motivasi merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua
penggerak, alasan-alasan, atau dorongan-dorongan dalam diri manusia
yang menyebabkan ia berbuat sesuatu . Motif manusia merupakan
kebutuhan tertentu dalam mengakses media internet di Warmasif,
macam-macam kebutuhan yang menjadi dasar motivasi para pengguna
media internet digolongkan ke dalam empat bagian yang mencakup :
pemenuhan kebutuhan informasi, hiburan, dan interaksi
sosial/komunikasi . (Gerungan,1983)
Warmasif adalah model pengembangan Community Access
Point (CAP) dimana masyarakat yang berada di suatu wilayah dapat
melakukan komunikasi, akses informasi global, pemasaran melalui
108 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
internet, transaksi online dan akses perpustakaan digital.Warmasif
dibentuk berdasarkan kesepakatan kerja sama antara Ditjen Aplikasi
Telematika Depkominfo dengan Dirut PT POS INDONESIA.
Operasionalisasi Variabel
Variabel motivasi kebutuhan bermedia terdiri atas sub variabel :
pemenuhan kebutuhan informasi, pemenuhan kebutuhan hiburan, dan
pemenuhan kebutuhan berkomunikasi.
1. Pemenuhan kebutuhan informasi, dengan indikator : asal mula
mengenal Warmasif, jenis-jenis informasi, fasilitas internet
Warmasif dalam proses pencarian informasi, dan sikap para
pengguna tentang informasi yang didapat.
2. Pemenuhan kebutuhan hiburan, dengan indikator : pengetahuan
para pengguna tentang hiburan , pengguna menggunakan fasilitas
internet untuk mencari hiburan, dan sikap para pengguna tentang
hiburan.
3. Pemenuhan kebutuhan komunikasi, dengan indikator :
pengetahuan para pengguna tentang komunikasi pada media
internet, penggunaan fasilitas internet di Warmasif untuk
melakukan interaksi sosial, dan sikap para pengguna tentang
interaksi sosial .
WARUNG MASYARAKAT INFORMASI
Tujuan dan Sasaran
Warmasif dibentuk berdasarkan kesepakatan kerja sama antara
Ditjen Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika
dengan Dirut PT POS INDONESIA, yaitu dalam upaya
mengembangkan perdagangan komoditi unggulan melalui
perdagangan elektronik / e-commerce atau e-UKM, meningkatkan
layanan informasi dan pendidikan masyarakat.
Tujuan Warmasif adalah :
1. Mempercepat tercapainya masyarakat informasi Indonesia (MII)
yang ditargetkan tahun 2015 tercapai.
2. Mempercepat dan menunjang tumbuh dan berkembangnya usaha
pertanian, usaha kelautan dan perdagangan komoditi unggulan
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 109
melalui e-commerce atau e-UKM yang terdapat di wilayah
setempat.
3. Pendidikan masyarakat melalui perpustakaan digital dan layanan
informasi kesehatan serta layanan informasi lain-lain.
4. Mempercepat terwujudnya Universal Service Obligation (USO)
dalam bidang komunikasi dan informasi.
HASIL PENELITIAN
Identitas Responden
Jumlah responden penelitian adalah 70 (tujuh puluh) orang ,
identitasnya meliputi : jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan.
Jenis kelamin responden, laki-laki (Bandung):7,Bekasi: 5,Karawang:
9,Tasikmalaya: 6,Purwakarta: 3,Garut: 5, Kuningan: 8 = 43
(61,42%)), perempuan (Bandung) : 3, Bekasi: 5,
Karawang:1,Tasikmalaya:4,Purwakarta:7,Garut:5,Kuningan:2 = 27
(38,58%)). Dari 70 responden yang berada di 7 (tujuh) lokasi
Warmasif di kota dan kabupaten di Jawa Barat, sebagian besar
berjenis kelamin laki-laki. Tetapi Kategori jenis kelamin ini bukan
merupakan satu-satunya faktor yang diteliti.
Sedangkan usia mereka yang terbesar adalah antara 17 – 24
tahun, disusul antara 25 – 32 tahun, dan sebagian kecil lagi adalah
mereka yang berumur lebih dari 57 tahun. Banyaknya mereka yang
mengunjungi Warmasif dari kalangan usia muda, karena pengetahuan
dan pergaulan mereka semasa di bangku sekolah lebih tertarik
mempelajari TIK.
Usia mereka sebagian besar adalah antara 17 – 24 tahun yaitu
sejumlah 41 orang atau 58,57 %. Pekerjaan responden sebagian besar
adalah dari kalangan pelajar dan mahasiswa, yakni 40 orang dan
sebagian kecil lainnya adalah petani, pengusaha, profesional, dan
pensiunan, yaitu masing-masing satu orang. Sedangkan pendidikannya
sebagian besar berlatarbelakang SMA, dan hanya sebagian kecil saja
dari sekolah dasar. Hal ini menunjukan keberadaan Warmasif masih
didominir oleh mereka yang berlatar belakang pelajar dan mahasiswa.
Data secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.
110 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Tabel 1
Identitas Responden
Identitas
Responden Bdg. Bks. Krwng Tskml Pwkrt Grt. Kng
Total 7 kota
(Persentase)
Usia
Krg. Dr. 17 th. 4 3 3 2 1 3 4 20 (28,95%)
17-24 th. 2 4 1 7 1 3 3 21 (29,57 %)
25-32 th. - 1 3 - 5 3 1 13 (18,57 %)
33-40 th. 1 - 3 1 - - - 5 (7,14 %)
41-48 th. 2 - - - 1 - 2 5 (7,14 %)
49-56 th. - 2 - - 1 1 - 4 (5,71 %)
57 th. lebih 1 - - - 1 - - 2 (2,85 %)
Jumlah 10 10 10 10 10 10 10 70 (100 %)
Pekerjaan
Pelajar/mhsw. 5 6 5 7 8 3 6 40 (57,14 %)
Karyawan 2 1 - - 1 2 - 6 (8,57 %)
Petani/nelayan - - - - 1 - - 1 (1,42 %)
PNS/ABRI - - 1 - - 2 - 3 (4,28 %)
Pengusaha - - - - - 1 - 1 (1,42 %)
Profesional - - 1 - - - - 1 (1,42
%)
Pensiunan - - - 1 - - - 1 (1,42 %)
Tidak kerja 3 2 1 - - 1 2 9 (12,85 %)
Ibu rumah tgg. - 1 - 1 - 1 2 5 (7,14 %)
Lain-lain ... - - 2 1 - - - 3 (4,28 %)
Jumlah 10 10 10 10 10 10 10 70 (100 %)
Pendidikan
SD 1 - - - - - 1 2 (2,85%)
SMP 2 3 - 2 1 - 1 9 (12,85 %)
SMA 5 4 5 6 7 7 4 38 (55,14 %)
Diploma - 3 4 2 - - 3 12 (18,57 %)
Sarjana 2 - 1 - 2 3 1 9 (12,85 %)
Jumlah 10 10 10 10 10 10 10 70 (100 %)
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 111
Berdasarkan karakteristik/identitas responden tersebut, secara
keseluruhan dari jawaban yang diberikan dipandang cukup memenuhi
syarat untuk diikutsertakan dalam pembahasan hasil penelitian.
Pemanfaatan Warmasif
Frekuensi pemanfaatan Warmasif di Kantor Pos sejak berdirinya
awal tahun 2007, adalah 1-3 kali 51 (72,86%); 4-6 kali 15 (21,43%);
7-9 kali 4 (5,71%).
Keberadaan Warmasif tergolong baru, dan belum semua
masyarakat mengetahui , hal ini karena sosialisasi belum optimal.
Sebagian besar pengguna Warmasif pemanfaatannya antara 1 sampai
3 kali , dan tidak ada seorangpun yang telah mengunjungi 10 kali
lebih. Kurangnya masyarakat menggunakan Warmasif dimungkinkan
karena letaknya hanya di kantor pos, serta ada persaingan dari usaha
sejenis yang bertebaran di sudut-sudut kota, seperti warnet (warung
internet).
Tabel 3
Asal Mula Mengetahui Warmasif
No. Sumber Frekuensi Persentase
1. Keluarga 9 15,71
2. Teman 11 21,43
3. Tempat kerja 1 2,86
4. Pemerintah - -
5. Media cetak (surat kabar,majalah
dll.) 7 11,43
6. Media elektronik (televisi, radio,
internet dll.) 8 14,28
7. Di Kantor Pos 28 27,14
8. Lainnya 5 2,86
Jumlah 70 100
Asal mula para responden mengetahui keberadaan Warmasif,
sebagian besar dari Kantor Pos, baik sewaktu ada urusan dengan
perposan, atau mengetahui ketika lewat ke kantor pos secara tidak
sengaja. Hal ini wajar karena Warmasif keberadaannya masih satu
112 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
atap dengan Kantor Pos, dan masih dikelola oleh pegawai pos
sendiri. Sedangkan dari kalangan pemerintah dinilai usaha sosialisasi
kurang optimal, sehingga dari 70 responden tidak ada yang tersentuh.
Selanjutnya , asal mula mengetahui Warmasif dari pihak
keluarga, teman, dan dari media elektronik berimbang. Bila dari
keluarga dan teman diperoleh dari informasi langsung, sedangkan
media didasarkan pada terpaan yang mereka peroleh. Sedangkan
mereka yang menyatakan lainnya adalah yang tidak menyebut secara
pasti darimana asal mula mengetahui istilah Warmasif atau ragu
menyebut sumber beritanya.
Tabel 4
Motif Pemanfaatan Warmasif
No.
Motif
Ya Tidak
F % F %
1. Pemenuhan kebutuhan informasi 61 87,14 9 12,86
2. Pemenuhan kebutuhan hiburan 60 85,71 10 14,29
3 Pemenuhan kebutuhan komunikasi/interaksi sosial 49 70,00 21 30,00
Motif penggunaan Warmasif oleh pengguna sebagian besar adalah
untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan hiburan, dan sebagian
kecil lainnya adalah untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun
tulisan. hal ini menunjukkan bahwa media ini sangat berguna untuk
dijadikan sebagai media untuk mencari informasi dan hiburan.
Sebagaimana dikemukakan oleh MC Quail bahwa “media massa harus
dapat digunakan untuk mencari informasi tentang peristiwa dan
kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan
dunia. (McQuail,1987:72).
Pemenuhan Kebutuhan Informasi
Pemenuhan kebutuhan informasi yang diungkap adalah :
kebiasaan dalam mencari informasi, jenis informasi yang dicari,
fasilitas yang sering digunakan , frekuensi per minggu , dan sikap
mengenai informasi media internet.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 113
Tabel 5
Jenis Informasi
No. Jenis Informasi Frekuensi Persentase
1
Informasi yang berhubungan dengan ilmu
pengetahuan dan bidang pendidikan (e-learning
atau e-education)
22 13,25
2 Informasi yang berhubungan dengan bidang
kesehatan 14 8,43
3 Referensi perpustakaan (library online) 27 16,26
4
Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam
bidang perdagangan, sep. Menjual, membeli,
promosi produk (e-commerce)
10 6,02
5 Belajar tentang menggunakan komputer 8 4,82
6 Mencari pekerjaan melalui internet 30 18,07
7 Mencari informasi pemerintahan (e-
government) 5 3,01
8 Informasi sosial, politik, budaya, olah raga dll.
(umum). 43 25,90
9. Lainnya 7 4,21
J u m l a h 166 100
n: 70, lebih dari satu jawaban.
Jenis informasi yang bersifat umum (sosial,politik, budaya,
olah raga dan lain-lain) yang sering di akses oleh para pengunjung
warmasif, disamping itu tidak sedikit yang mengakses tentang
informasi di bidang pendidikan (e-education), mencari referensi
perpustakaan (library online), dan informasi tentang lowongan
pekerjaan.
Sebaliknya informasi yang berhubungan dengan bidang
perdagangan, seperti menjual, membeli, promosi produk (e-
commerce) utamanya dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) ,
serta di bidang kesehatan yang notabene program dari Warmasif
kurang diminati oleh penggunanya. Hal ini karena sebagian
pengunjung Warmasif dari kalangan generasi muda (pelajar dan
mahasiswa) yang kurang begitu berkepentingan (concern) dengan
masalah-masalah perdagangan dan kesehatan, mereka justru sering
mengakses dengan tren-tren yang berkembang dengan tuntutannya.
114 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Fasilitas yang paling sering digunakan para responden untuk
mencari informasi adalah fasilitas search engine (mesin untuk mencari)
diantaranya yang paling terkenal adalah yahoo dan google yakni 40
(73%). Selanjutnya Website atau situs 8 (8,1%), e-mail (surat
elektronik) 5 (9,5%), Chatting 7 (5,4%), FTP/order 1(4,1%)Sikap
pengguna tentang informasi yang di akses di Warmasif tergolong
bagus , kecuali mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan sesuai
dengan yang diinginkan yang tergolong berimbang atau cukup bagus.
Dari berbagai informasi yang ada di internet ternyata sebagian
besar responden menyatakan berita-berita yang ada pada media ini
sangat aktual serta selalu mendapatkan topik informasi tertentu yang
dicari. Hal ini karena pemegang website atau situs di internet selalu di
updating sesuai dengan kejadian faktual di masyarakat. Dengan cara
inilah keberadaan media internet akan eksis dicari oleh user serta
menyediakan data terbaru ( actual information) dibandingkan dengan
media lainnya, seperti media televisi, radio, koran ataupun majalah.
Sebaliknya, sebagian kecil dari mereka yang menilai bahwa
berita-beritanya tidak aktual dan kurang dipercaya, dikarenakan saat
mengakses pemegang website tidak meng up date data yang terbaru.
Pemenuhan Kebutuhan Hiburan
Tabel 6
Jenis Hiburan Ketika Mengakses Media Internet
No. Jenis Hiburan Frekuensi Persentase
1. Lagu (MP3) 8 13,4
2. Chatting 22 35,8
3. On-line games 5 9
4. Adult web, situs porno - -
5. Lagu (MP3) danchatting 7 7,5
6. Lagu (MP3) dan on-line games 5 9
7. Lagu (MP3) dan situs porno 10 17,9
8. Chatting dan on-line games - -
9. Chatting dan situs porno 3 7,5
Jumlah 60 100
Dari tabel di atas tergambar bahwa salah satu jenis hiburan yang
paling banyak dicari oleh pengguna Warmasif adalah chatting . Hal ini
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 115
dilakukan tidak hanya untuk berinteraksi dengan teman atau dengan
sanak saudara yang tinggal saling berjauhan, tetapi juga dilakukan
dengan individu yang sama sekali tidak saling mengenal, tidak hanya
sekedar berkenalan secara online. Jenis hiburan lainnya adalah
mendengarkan dan men-download lagu-lagu berformat MP3, baik
lagu baru atau lama yang tak kalah kualitasnya dengan CD audio yang
berformat Wav. Salah satu situs yang paling terkenal dan paling
banyak digemari adalah www.mp3.com.
Fasilitas yang paling sering digunakan untuk mencari hiburan
adalah : search engine 46,3%, website atau situs 4,5%, e-mail 1,5%,
chatting 38,8%, FTP 9%. Hampir setengah responden menggunakan
search engine karena tidak mengetahui alamat situs yang akan dituju,
sehingga penggunaan fasilitas ini sangat membantu dalam hal
pencarian alamat situs yang dimaksud. Fasilitas chatting juga dapat
digunakan untuk menghibur diri dengan cara melakukan percakapan
dengan teman, keluarga, bahkan berkenalan dengan orang yang
tinggal di luar negeri.
Pemenuhan Kebutuhan Berkomunikasi
Jenis interaksi sosial yang sering dilakukan adalah percakapan
online dinyatakan oleh 53,7%, dan berkirim surat secara online 46,3%.
Banyaknya yang melakukan interaksi berupa percakapan secara online
dengan sebutan chatting, karena sebagai salah satu cara menjalin
komunikasi dengan kerabatnya secara realtime. Begitu pula
berkiriman surat secara online, tidak hanya dalam kecepatan proses
pengiriman, tetapi menyangkut biaya yang murah.
Fasilitas yang sering digunakan untuk berkomunikasi / interaksi
sosial tergambar sebagai berikut : search engine 2 orang (3,7%),
website atau situs 4 orang (6,1%), e-mail 21 orang (30,5%), chatting
39 orang (53,7%) dan e-mail serta chatting 4 orang (6,1%).
Banyaknya yang tertarik menggunakan fasilitas chat dikarenakan
mereka dapat menjadi bagian dari penduduk dunia yang sedang on
line. Begitu pula penggunaan e-mail, mereka dapat berkiriman surat
dengan berbagai macam data, seperti file gambar, lagu, suara bahkan
file video.
Responden beranggapan bahwa berkirim surat secara online
cukup mudah, begitu pula dalam hal kerahasiaan atau privacy
menyatakan penggunaan e-mail cukup terjaga. Hal ini karena pada
116 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
setiap alamat e-mail yang responden miliki dilindungi oleh password
atau kata kunci yang hanya diketahui oleh para responden itu sendiri.
Seperti terlihat pada tabel berikut,
Tabel 7
Sikap Pengguna Tentang berkomunikasi Pada Media Internet
No. Interaksi Sosial/komunikasi
Sikap
Ya Tidak
F % F %
1 Berkiriman surat secara on-line
cukup mudah 48 98,8 1 1,1
2 Berkiriman surat secara on-line
kerahasiaannya cukup terjaga 35 55,7 14 44,3
3 Merasa aman berbicara terus
terang ketika chatting 37 53,4 12 46,6
4 Mempercayai perkataan lawan
bicara ketika chatting 10 18,2 39 81,8
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pemenuhan kebutuhan informasi pada warung masyarakat
informasi (Warmasif) di Provinsi Jawa Barat kurang optimal
dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna (user) sesuai dengan
tujuan dan sasarannya, yakni dalam upaya mengembangkan
perdagangan komoditi unggulan melalui perdagangan elektronik/e-
commerce, serta meningkatkan layanan informasi pendidikan
masyarakat. Sebaliknya mereka lebih banyak mengakses jenis
informasi bersifat umum, yaitu informasi politik, budaya, olah raga,
cari kerja, dan lainnya.
2. Motivasi dalam pemenuhan kebutuhan hiburan di Warmasif dinilai
tinggi, yakni keinginan untuk sejenak melarikan diri dari realitas
hidup, mencari kesenangan hedonistik, mencari kepuasan pribadi
dan pelepasan emosi, serta jenis hiburan yang berbeda dengan yang
didapat media lainnya. Pemenuhan kebutuhan hiburan biasanya
dilakukan dengan cara melakukan chatting, men-download atau
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 117
mendengarkan lagu berformat MP3, bermain game online, atau
membuka situs-situs porno.
3. Motivasi dalam melakukan komunikasi dapat menyerupai interaksi
dunia nyata yakni dengan menggunakan webcam ketika
melakukan chatting. Pemenuhan kebutuhan interaksi sosial
biasanya dilakukan dengan percakapan secara on-line dengan
sebutan internet relay chat (IRC) atau chatting, karena sebagai
salah satu cara menjalani komunikasi dengan kerabatnya secara
realtime. Begitu pula berkiriman surat secara online, tidak hanya
dalam kecepatan proses pengiriman, tetapi menyangkut biaya yang
murah.
Saran
1. Hendaknya kesepakatan kerja sama antara Ditjen Aplikasi
Telematika dengan PT POS Indonesia tentang Warmasif lebih
ditingkatkan sosialisasinya, sehingga masyarakat dapat
mengetahui keberadaannya didalam upaya meningkatkan layanan
informasi dan pendidikan masyarakat.
2. Hendaknya pengelola Warmasif untuk lebih meningkatkan
kemampuan mengakses internet, menambah fasilitas yang dapat
memanjakan pelanggan, serta biaya akses internet yang lebih
murah lagi kepada masyarakat, sehingga akan termotivasi lagi
menggunakannya sebagai media informasi dan komunikasi.
3. Idealnya Warmasif berada di daerah-daerah yang memiliki
komoditas unggulan tetap, seperti pertanian, perikanan, hasil
kerajinan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya dapat diberdayakan
lagi, seperti pemasaran melalui internet, transaksi online, promosi
barang dan akses digital lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Gerungan, WA,. 1983. Psychology Sosial. Bandung : PT Erasco.
Arikunto, Suharsimi.1993. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan
Praktek, Yogyakarta : Rineka Cipta.
Effendi, Onong U. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.
Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mc.Quail. Denis. 1994. Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Erlangga.
118 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Rakhmat, Jalaluddin. 1996. Psikologi Komunikasi. Bandung : Remaja
Rosda Karya.
-------------------------. 2000. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung :
Remaja Rosda Karya.
Yuswanto, Toni Edi. 2000. Web Design Plus. Bandung : Multiunion.
Sumantri, Suryana. 2001. Perilaku Organisasi. Bandung : Universitas
Pajajaran.Febrian, Jack. 2002. Menggunakan Internet.
Bandung : Informatika.
Kominfo,2002, Sistem Informasi Nasional. Departemen Komunikasi
dan Informatika. Tersedia di : http//www.depkominfo.go.id
Pareno,Sam Abede,2005. Media Massa, Antara Realitas dan Mimpi.
Surabaya : Papyrus.
Sumber lainnya :
1. Departemen Komunikasi dan Informatika, Direktorat E-Business,
Dirjen Aplikasi Telematika. Warung Masyarakat Informasi
Indonesia, 2006.
2. Proyek Bappenas dan UNDP, Infomobilisasi , 2007, Jakarta.
3. Badan Litbang SDM, Pusat Litbang Aptel dan SKDI, Studi
Pemberdayaan CAP Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Pedesaan, Depkominfo, 2007
4. Situs resmi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
(http://www.apjii.or.id) dan situs http://www.
Indonesiatelecenter.co.id
5. Situs lainnya : yahoo.com, google.com, berita.com, dan detik .com.
6. Hasil Pengumpulan Data Basis Tentang Lembaga Komunikasi
Massa di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006, BPPI Wil. III
Bandung, Depkominfo RI.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 119
SIKAP JURNALIS TERHADAP CITIZEN JOURNALISM
Dida Dirgahayu*
Abstraksi
Saat ini, pers berada dalam situasi di mana pengertian wartawan dan
media mengalami pergeseran penting sebagai akibat dari
berkembangnya dua hal. Yaitu perkembangan jurnalistik dan
perkembangan media. Dunia jurnalistik kini mulai mengalami
perubahan, dulu reportase adalah tugas khusus yang dibebankan
kepada wartawan atau reporter media massa, maka sekarang setiap
warga bisa melaporkan peristiwa kepada media. Inilah yang
kemudian disebut sebagai citizen journalism. Permasalahan
penelitian ini adalah : bagaimana sikap jurnalis terhadap citizen
journalism. Merupakan penelitian deskriptif (descriftive studies)
dengan metode pendekatan kuantitatif. Manfaat penelitian ini
diantaranya untuk memberikan gambaran tentang eksistensi citizen
journalism diantara civic journalis (media mainstream) yang lazim
disebut media massa.
Kata kunci : Sikap, Jurnalis, Citizen Journalism
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hakekat
media. Dengan internet, kini berkembang situs-situs lembaga maupun
pribadi. Selain itu, berkembang juga weblog atau blog, di mana setiap
orang bisa melaporkan peristiwa di sekelilingnya, atau paling tidak,
melaporkan gagasannya kepada publik. Dengan demikian, kalau dulu
media didirikan oleh lembaga, atau individu yang mempunyai uang
dan kekuasaan (power), kini setiap individu bisa membuat media.
Karena itu, di zaman internet ini, setiap individu juga adalah media.
Dengan perkawinan jurnalistik baru dengan perkembangan teknologi
* Dida Dirgahayu, S.Sos adalah peneliti pertama Balai Pengkajian dan
Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BP2KI) Bandung.
120 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
media kita menyaksikan bahwa setiap individu adalah reporter, dan
setiap individu adalah media. Pada saat bom Bali I dan II meluluh
lantakkan bangunan, hasil rekaman masyarakat awam lah yang
ditayangkan oleh media elektronik, dan menjadi foto utama media
cetak. Ketika banjir, misalnya, begitu banyak warga masyarakat yang
memberikan informasi kepada radio, televisi, media online. Begitu
banyak peristiwa di sudut kota yang tidak ter-cover oleh media
mainstream, tetapi dikabarkan dengan baik oleh masyarakat. Dengan
berkembangnya citizen journalism, ternyata fungsi melaporkan sudah
bukan tugas eksklusif wartawan/ reporter. Pertanyaannya adalah,
apakah laporan awam bisa dikatagorikan sebagai berita. Apakah
citizen journaslism dapat disetarakan atau masuk dalam katagori jenis
jurnalistik ( media mainstream) atau sebatas ruang publik.
Berdasarkan realitas inilah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana sikap jurnalis surat kabar terhadap citizen journaslism.
Permasalahan Pokok Dan Indetifikasi Masalah
Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah : Bagaimana
sikap jurnalis terhadap citizen journaslism?
Identifikasi masalahnya adalah :
1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman jurnalis tentang citizen
journaslism ?
2. Bagaimana penilaian jurnalis terhadap citizen journaslism ?
3. Bagaimana reaksi jurnalis terhadap citizen journalism ?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menggambarkan :
1. Pengetahuan dan pemahaman jurnalis tentang citizen journaslism
2. Penilaian jurnalis terhadap citizen journaslism
3. Reaksi jurnalis terhadap citizen journalism
Manfaat
Penelitian ini layak dilakukan karena bermanfaat untuk
memperoleh gambaran tentang sikap jurnalis terhadap citizen
journaslism. Hasil penelitian dan kajian ini akan memberikan data
awal, gambaran dan aspirasi para jurnalis.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 121
Kerangka Teori
Kognisi menurut Scheerer, adalah proses sentral yang
menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar (eksternal) dan di dalam
(internal) diri sendiri. Penekanan Scheerer tidak hanya peristiwa-
peristiwa yang sifatnya eksternal tetapi lebih jauh adalah peristiwa
yang ada dalam dirinya atau faktor internal. Komponen kognisi
menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (senang atau tidak
senang) terhadap obyek. komponen konasi akan menjawab pertanyaan
bagaimana kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap obyek
(Shaver,177). Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, akan
tetapi menunjukkan bahwa manusia merupakan suatu sistem kognitif.
Ini berarti bahwa yang dipikirkan seseorang tidak akan terlepas dari
perasaannya. Masing-masing komponen tidak dapat berdiri sendiri,
namun merupakan interaksi dari komponen-komponen tersebut secara
komplek. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan
karena informasi yang diterima menentukan perasaan dan kemauan
berbuat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan secara kognitif, afektif, dan konatif.
Berdasarkan pendekatan ini setiap orang akan mencari keseimbangan
dalam bidang kognisinya dan terbentuk dari sikap yang bersangkutan.
Apabila terjadi ketidakseimbangan, individu akan berusaha
mengubahnya sehinggga terjadi keseimbangan kembali.(Severin-
Tankard 2005:295).
Operasional konsep dari sikap mengacu kepada tiga komponen
dari sikap sebagai indikator, dimana masing-masing mempunyai
fungsi yang diarahkan terhadap objek tertentu/ stimulus tertentu. Yaitu
: 1. Komponen kognitif, pengetahuan, pengalaman, pengertian,
pemahaman jurnalis tentang citizen journalism. 2. Komponen afektif,
menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu
objek sikap. Objek dirasakan sebagai hal yang menyenangkan, hal
disukai atau tidak. Reaksi ini dipengaruhi kepercayaan atau apa yang
kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi suatu objek. 3.
Komponen konatif, berhubungan dengan kecenderungan untuk
beraksi, bertingkah laku dengan cara tertentu, tapi konatif ini tidak
meramalkan tingkah laku aktual itu sendiri.(Severin-Tankard,2005 :
295)
Citizen journalism, menurut Lily Yulianti (panyingkul.com,
2006), merupakan model jurnalistik baru ini disebut sebagai
122 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
“Jurnalisme Orang Biasa” .Seperti namanya, Citizen Jurnalism ini
memberi pengertian bahwa, setiap individu bebas melakukan
kegiatan-kegiatan jurnalistik. Menuliskan pengalaman yang ditemui
sehari-hari di lingkungannya, maupun melakukan interperetasi
terhadap suatu peristiwa tertentu. Semua individu bebas melakukan
hal itu, dengan perspektif masing-masing. Citizen Journalism tidak
hadir sebagai saingan, tapi sebagai alternatif yang memperkaya pilihan
dan referensi. Berita tidak lagi dilihat sebagai produk yang didominasi
wartawan dan institusi pers. Masyarakat biasa seharusnya masuk
dalam ekosistem media sebagai unsur yang aktif berinteraksi
(http://sulungz.blogs. friendster.com).
Tinjauan Pustaka
Sikap
Menurut Louis Thurstone dan Charles Osgood, sikap
merupakan suatu bentuk evolusi atau reaksi perasaan terhadap suatu
objek, baik perasaan mendukung atau memihak ( favourable ), atau
perasaan tidak mendukung (unfavourable) pada objek tersebut.
(Azwar, 2003:5). Menurut Gerungan (1996:150), sikap merupakan
kecenderungan bereaksi terhadap objek-objek, dimana kecenderungan
bereaksi ini merupakan cara yang khas tergantung dari motivasi,
emosi, persepsi, dan proses kognitifnya.
Jurnalis
Wartawan (journalist) adalah orang yang terlibat dalam
pencarian, pengolahan, dan penulisan berita. Mulai dari Pemimpin
Redaksi hingga koresponden yang terhimpun dalam bagian redaksi.
Menurut UU No.40/1999 tentang Pers (pasal 1 poin 4), wartawan
adalah ”orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Wartawan ( journalist ) adalah orang yang secara rutin melakukan
aktivitas jurnalistik, yakni aktivitas peliputan, perekaman, dan
penulisan berita, opini, dan feature untuk media massa. Dalam sebuah
lembaga penerbitan pers, wartawan masuk dalam Bagian Redaksi
(Editor Department) yang dipimpin oleh Pemimpin Redaksi (Editor in
Chief). Jadi, tidak semua orang yang bekerja di sebuah perusahaan
pers (media massa) adalah wartawan. Merekalah yang memburu berita
(fakta atau kejadian), meliput berbagai peristiwa, dan menuliskannya
untuk dikonsumsi orang banyak. ”Di mana terjadi suatu peristiwa,
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 123
wartawan akan berada disana” kata M.L Stein (1993:5), ”Seperti mata
dan telinga para pembaca suatu harian.” Wartawan adalah suatu
profesi yang penuh tanggungjawab dan risiko. Karenanya, ia harus
memiliki idealisme dan ketangguhan. Wartawan bukanlah dunia bagi
orang yang ingin bekerja dari jam sembilan pagi hingga jam lima sore
setiap hari dan libur pada hari minggu. Tidak ada seorangpun tahu
kapan kebakaran atau bencana lain akan terjadi. (Romli :2003 :8)
Citizen Journalism
Internet kini menjadi new media, media kontemporer yang
memberi wahana baru dalam aktualitas pemberitaan. Lebih dari media
apa pun yang telah ada. Keunggulan itu akhirnya dipergunakan oleh
sebagian pihak untuk menjadikan media internet sebagai salah satu
wadah media mainstream. Kendati begitu, pemberitaan atau
penyebaran informasi di media internet ini tetap terpolarisasi pada
model diktum. Bahkan lebih kuat dan leluasa. Karena regulasi pers
maupun undang-undang pada media internet ini sangat kabur dan
tidak tegas. Walhasil, awan pun mendapatkan kembali posisi lamanya.
Perbedaan mendasar antara media mainstream yang tumbuh lebih
awal dengan media mainstream pada internet, hanya terletak pada
kecepatan penyampaian. Berdasar kesadaran itu, sejumlah orang
melakukan pemikiran-pemikiran untuk menembus batas ini.
Blog sebenarnya sebuah website juga. Website seperti kita
ketahui adalah satu lembaran informasi yang ada di internet. Jadi
ketika kita masuk ke internet, misalnya membaca berita surat kabar
atau salah satu informasi departemen pemerintah atau perusahaan, itu
yang kita sebut dengan Website. Weblog atau blog adalah versi
mutakhir dari web. Disebut mutakhir karena di weblog kita bisa
berkomunikasi, berdialog dengan orang yang memiliki blog.
(http://www.pontianakpost.com)
Pemberitaan Citizen Journalism lebih mendalam dengan
proses yang tak terikat waktu, seperti halnya tenggat deadline di
media mainstream. Bentuk Citizen Journalism dapat dilihat pada
proses penayangan berita di televisi, dengan menggunakan visual dari
masyarakat (kameramen amatir). Citizen Journalism dinilai sebagai
bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk menyuarakan pendapat
secara lebih leluasa, terstruktur, serta dapat diakses secara umum dan
sekaligus menjadi rujukan alternatif.
124 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
Antara jurnalis dengan aktifitas bloger
Penulisan informasi adalah aktifitas penulisan atau penyusunan
berita, opini, dan feature untuk dipublikasikan atau dimuat di media
massa tentang peristiwa atau gagasan. Aktivitas tersebut dilakukan
oleh wartawan (journalist) dan penulis (writter). Karenanya,
jurnalistik disebut sebagai “dunia kewartawanan”. Menurut UU No.
40/1999 tentang Pers (pasal 1 poin 4), wartawan adalah orang yang
secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.(M. Romli, 2005 : 6)
Sebagai ujung tombak bagi suatu penerbitan surat kabar atau media
massa lainnya, wartawan setidaknya mempunyai standar profesi sejati
(real journalist) disamping aturan profesi lainnya.
Wartawan media mainstream melakukan peliputan atas
peristiwa berdasar pada tugas keredaksian, wartawan media
mainstream membatasi diri pada 'informasi apa dan yang bagaimana'
diinginkan pasar. Dalam aktifitas seorang bloger, sangat pasti tidak
mengenal polarisasi pemberitaan karena semuanya tergantung kepada
interest kemampuan penulis (bloger). Perbedaan nyata antara citizen
journalist dan wartawan yang bekerja di media massa, dijelaskan
dengan rinci oleh Bentley (2005) sbb: "Seorang wartawan yang
bekerja di media massa, melakukan liputan karena penugasan,
sementara seorang citizen journalist menuliskan pandangannya atas
suatu peristiwa karena didorong oleh keinginan untuk membagi apa
yang dilihat dan diketahuinya." Seorang penulis pada Citizen
Journalism melakukan tugasnya dengan proses penetrasi terhadap
obyek pemberitaan dengan totalitas dan penuh atmosfir. Citizen
Journalism menjadi wadah 'gairah bercerita' dari semua individu.
Jurnalisme yang berkembang saat adalah jurnalisme yang
berbasis pada penggunaan teknologi internet, salah satunya adalah
penggunaan weblog yang memungkinkan orang untuk menyuarakan
opini terhadap berbagai peristiwa secara bebas. Citizen journalism
adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. Clyde H.
Bentley, guru besar madya pada Sekolah Tinggi Jurnalistik Missouri
AS, menilai bahwa meski sebagian besar masyarakat tidak ingin
menjadi jurnalis, tapi mereka ingin berkontribusi secara nyata dengan
menuliskan pikiran atau pendapat mereka tentang suatu hal. Citizen
Journalism menjadi pengimbang dari media-media yang selama ini
melakukan pemberitaan berdasar kepentingan. Perspektif pembaca
yang muncul dari suatu berita media mainstream yang terbiasa terpola
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 125
berdasar visi dan misi suatu media, relatif akan lebih murni di citizen
journalism ini.
Jumlah informasi yang di tawarkan citizen journalism akan
lebih banyak dan beragam sementara media mainstream terikat
dengan jumlah halaman (suratkabar), durasi penayangan (televisi) atau
durasi penyiaran (radio). Berdasarkan kaidah jurnalistik dan teori
tentang media massa seperti dikemukakan di atas, aktifitas maupun
media yang digunakan dalam citizen journalism bukanlah sebuah
jurnalistik baru atau bagian dari civic journalism, berbeda dan tidak
bisa disamakan dengan dengan media mainstream pada umumnya.
Demikian pula dipandang dari sudut pelakunya, aktifitasnya seorang
bloger tidak sama dengan profesi seorang wartawan. Hal positif yang
perlu disambut baik oleh kalangan citizen journalism maupun civic
journalism adalah bahwa keduanya dapat saling mengisi dan
memosisikan dirinya sebagai sumber informasi.
Media massa sebagai media mainstream (civic journalism)
Sebenarnya apa yang disebut sebagai civic journalism.
Mungkin akan banyak orang yang rancu dengan istilah citizen
journalism, padahal keduanya sama sekali berbeda. Citizen journalism
adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu (dalam
pengertian setiap orang adalah wartawan dan kerja wartawan bisa
dilakukan oleh setiap orang). Sedangkan civic journalism adalah
upaya wartawan profesional dan media tempat mereka bekerja untuk
lebih mendekat dengan persoalan warga (pembacanya), serta ikut
terlibat dalam menyelesaikan persoalan itu secara langsung. Bukan
hanya memberitakan peristiwa atau fenomena dalam sikap yang
objektif dan imparsial, tapi lebih menyatu dan terlibat dalam
membimbing warga dan mendorong warga untuk melakukan sesuatu.
Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan
realitas suatu fakta atau peristiwa yang dipilihnya, diantaranya realitas
dari proses kampanye pemilu. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa
pekerjaan media massa adalah menceriterakan peristiwa-peristiwa,
maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan
(constructed reality). Isi media pada hakikatnya adalah hasil
rekonstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya,
sedangkan bahasa bukan saja alat untuk merefresentasikan realitas,
126 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan
oleh bahasa tentang realitas tersebut. (Sobur, 2002 : 88).
Institusi media menyelenggarakan produksi, reproduksi dan
distribusi pengetahuan dalam pengertian serangkaian simbol yang
mengandung acuan bermakna tentang pengalaman dalam kehidupan
sosial. Pengetahuan tersebut membuat kita mampu untuk memetik
pelajaran dari pengalaman, membentuk persepsi kita terhadap
pengalaman itu, dan memperkaya khasanah pengetahuan masa lalu,
serta menjamin kelangsungan perkembangan pengetahuan kita. Secara
umum, dalam beberapa segi media massa berbeda dengan institusi
pengetahuan lainnya (misalnya seni, agama, pendidikan, dan lain-lain)
: Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap
macam pengetahuan. Jadi, media massa juga memainkan peran
institusi lainnya.
Pada dasarnya hubungan antara pengirim dan penerima
seimbang dan sama. Media menjangkau lebih banyak orang daripada
institusi lainnya dan sudah sejak dahulu ”mengambil alih” peran
sekolah, orang tua, agama, dan lain-lain. Menurut asumsi dasar di atas,
lingkungan simbolik di sekitar (informasi, gagasan, kepercayaan, dan
lain-lain) seringkali kita ketahui melalui media massa, dan media
pulalah yang dapat mengaitkan semua unsur lingkungan simbolik
yang berbeda. Lingkungan simbolik itu semakin kita memiliki
bersama jika kita semakin berorientasi pada sumber media yang sama.
Meskipun setiap individu atau kelompok memang memiliki dunia
persepsi dan pengalaman yang unik, namun mereka memerlukan
kadar persepsi yang sama terhadap realitas tertentu sebagai prasyarat
kehidupan sosial yang baik. Sehubungan dengan itu, sumbangan
media massa dalam menciptakan persepsi demikian mungkin lebih
besar daripada institusi lainnya. Asumsi dasar kedua ialah media
massa memiliki peran mediasi (penengah/ penghubung) antara realitas
sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi.
Media massa berperan sebagai penengah dan penghubung
dalam pengertian bahwa: media massa seringkali berada diantara kita;
media massa dapat saja berada diantara kita dengan institusi lainnya
yang ada kaitannya dengan kegiatan kita; media massa dapat
menyediakan saluran penghubung bagi berbagi institusi yang berbeda;
media juga menyalurkan pihak lain untuk menghubungi kita, dan
menyalurkan kita untuk menghubungi pihak lain; media massa
seringkali menyediakan bahan bagi kita untuk membentuk persepsi
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 127
kita terhadap kelompok dan organisasi lain, serta peristiwa tertentu.
Melalui pengalaman langsung kita hanya mampu memperoleh sedikit
pengetahuan.
Definisi Konsep Dan Operasional Konsep
Definisi konsep dalam penelitian ini adalah :
1. Sikap
Menurut Gerungan ( 1996:150), sikap merupakan kecenderungan
bereaksi terhadap objek-objek, dimana kecenderungan bereaksi ini
merupakan cara yang khas tergantung dari motivasi, emosi,
persepsi, dan proses kognitifnya. Operasional konsep dari sikap
mengacu kepada tiga komponen dari sikap sebagai indikator,
dimana masing-masing mempunyai fungsi yang diarahkan
terhadap objek tertentu/ stimulus tertentu. Yaitu : 1. Komponen
kognitif, pengetahuan, pengalaman, pengertian, pemahaman
jurnalis tentang citizen journalism. 2. Komponen afektif,
menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu
objek sikap. Objek dirasakan sebagai hal yang menyenangkan, hal
disukai atau tidak. Reaksi ini dipengaruhi kepercayaan atau apa
yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi suatu objek. 3.
Komponen konatif, berhubungan dengan kecenderungan untuk
beraksi, bertingkah laku dengan cara tertentu, tapi konatif ini tidak
meramalkan tingkah laku aktual itu sendiri.
2. Citizen journalism Menurut Lily Yulianti (panyingkul.com, 2006), di Indonesia
model jurnalistik baru ini disebut sebagai “Jurnalisme Orang
Biasa” .Seperti namanya, Citizen Jurnalism ini memberi
pengertian bahwa, setiap individu bebas melakukan kegiatan-
kegiatan jurnalistik. Menuliskan pengalaman yang ditemui sehari-
hari di lingkungannya, maupun melakukan interperetasi terhadap
suatu peristiwa tertentu. Semua individu bebas melakukan hal itu,
dengan perspektif masing-masing.
Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif ( descriptive research),
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan
faktual, mengenai situasi-situasi, fakta-fakta dari populasi tertentu
(Suryabrata,1983:19) Menggambarkan sikap jurnalis terhadap citizen
128 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
journalism. Sejalan dengan paradigma tersebut, penelitian dilakukan
melalui pengumpulan data kuantitatif, dan untuk memperoleh data
yang lebih mendalam dilakukan juga pengumpulan data kualitatif
melalui wawancara mendalam. Tehnik penelitian ini adalah survey.
Survey adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi
dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-
pertanyaan; satu cara mengumpulkan data melalui komunikasi dengan
individu-individu dalam suatu sampel (Zikmund,1997).
Populasi penelitian ini adalah jurnalis surat kabar di Kota
Bogor. Jurnalis dalam penelitian ini dibatasi pada jurnalis yang
bekerja / mempunyai bidang tugas redaksi/ baik redaktur maupun
wartawan pada media massa surat kabar dan melakukan pencarian
(peliputan) berita yang ada di Kota Bogor. Sampel ditentukan secara
purposive sampling yaitu 64 jurnalis ( yang bekerja / mempunyai
bidang tugas redaksi/ baik redaktur maupun wartawan, melakukan
pencarian (peliputan) berita, calon responden memiliki pengetahuan
tentang citizen journalism. Pemilihan sampel dilakukan secara tidak
acak (non probability sampling).
Dengan keterbatasan yang ada, tidak dimungkinkan dibuat
kerangka sampling. Pengolahan data dilakukan dengan mengolah
jawaban hasil wawancara dan kuesioner, dimasukan dalam tabel
frekuensi dan persentase yang selanjutnya diinterpretasikan dan
dianalisis.
Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2007 di Kota
Bogor, lokasi ini dipilih karena berdasarkan data dari Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Kota Bogor mempunyai
jumlah wartawan yang bertugas sebanyak 317 orang.di daerah tersebut
mempunyai jumlah wartawan yang banyak, merupakan daerah
perkotaan sehingga akses jurnalis terhadap internet relatif lebih
dimungkinkan.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 129
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan, dan Pemahaman Jurnalis Tentang Citizen
Journaslism
Dari 64 orang responden, sebanyak 56 responden (86,15%)
memiliki handphone sebagai alat yang memiliki/ bisa koneksi internet,
8 responden (13,85%) memiliki handphone tidak memiliki koneksi
internet. Semua responden ( 64 orang ) memiliki perangkat komputer,
dan sebanyak 47 orang (73,43%) memiliki fasilitas internet, dan 17
responden (26,57%) memiliki perangkat komputer tanpa koneksi
internet. Bagi responden yang tidak memiliki handphone dan
perangkat komputer berkoneksi internet, semuanya menyatakan tetap
mengakses internet di kantor tempat bekerja.
Data di atas menunjukan bahwa handphone dan internet telah
menjadi bagian dari seorang jurnalis (wartawan), handphone bukan
saja berfungsi sebagai komunikasi diantara perseorangan, tetapi
kelengkapan fitur internet menunjukan bahwa kebutuhan informasi
yang bisa diperoleh melalui akses internet lewat handphone telah
menjadi kebutuhan.
Demikian pula dengan kepemilikan perangkat komputer yang
mempunyai fasilitas koneksi internet, telah memungkinkan seorang
jurnalis melakukan pencarian sumber informasi, bahkan inspirasi
melalui content yang tersedia dalam internet. Secara aplikatif, koneksi
internet memungkinksn seorang jurnalis di lapangan untuk mengirim
berita, baik dalam bentuk kata-kata atau gambar kepada perusahaan/
penerbitnya.Jawaban di atas menunjukan, bahwa handphone dan
internet sebagai salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi
telah menjadi fasilitas yang dimiliki dan mendukung pekerjaan
jurnalis.
Tingginya tingkat kebutuhan responden terhadap berbagai
ragam informasi yang tersedia di berbagai situs internet. Analisis di
atas diperjelas dengan gambaran tentang frekuensi penggunaan
fasilitas internet. Dari 64 responden, sebanyak 58 responden (90,62%)
mengakses internet setiap hari, dan 6 responden (9,38%) mengakses
internet sesuai keperluan.
Analisis tentang tingkat kebutuhan jurnalis terhadap teknologi
informasi berupa akses internet, dan teknologi komunikasi handphone
berkoneksi internet, diperkuat dengan gambaran tentang frekuensi
130 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
penggunaa, dimana sebagian besar responden menyatakan setiap hari
mengakses internet.
Dalam mengakses internet, 37 responden (57,81%)
melakukannya antara 1 – 2 jam, 9 responden (14,6%) antara 3 – 4 jam,
dan 18 responden (38,13%) menyatakan memgkses internet dengan
frekuesi yang tidak menentu. Data ini menunjukan bahwa, semua
responden menyatakan dalam setiap mengakses internet rata-rata di
atas satu jam.
Dalam mempergunakan fasilitas internet, 57 responden
(89,06%) melakukannya berkaitan dengan pekerjaan, dan 9 responden
(10,94%) mengakses tidak berhubungan dengan pekerjaan sebagai
jurnalis. Data ini menunjukan, bahwa handphone berakses internet
serta perangkat komputer berkoneksi internet merupakan perangkat
atau fasilitas pendukung responden yang berprofesi wartawan.
Dari 57 responden, 23 responden (40,35%) mengakses internet
untuk mengirim e-mail tentang berita ke redaksi, 11 responden
(19,29%) untuk mencari data / berita , 8 responden (14,03%)
melakukan komunikasi , 15 responden (26,33%) mengakses internet
dengan keperluan yang beragam ( keperluan lainnya).
Data di atas menunjukan bahwa, frekuensi maupun kebutuhan
responden terhadap internet berkaitan langsung dengan pekerjaannya,
hal ini tergambar dari sebagian besar responden mempergunakan
internet untuk mengirim e-mail, dapat dianalisis bahwa soorang
responden yang melakukan pekerjaan sebagai jurnalis dapat
mengirimkan beritanya ke penerbit dengan mempergunakan e-mail,.
Tentang citizen journalism, Dari 64 responden, seluruhnya
mengenal istilah bloger sebagai aktifitas citizen journalism, .
Sebanyak 52 responden (81,25%) sangat mengetahui aktifitas bloger,
12 responden (18,75%) menyatakan cukup mengetahui aktifitas
citizen journalism.
Data di atas menununjukan, bahwa responden selain
mempergunakan fasilitas yang berhubungan langsung dengan
pekerjaannya sebagai jurnalis, tetapi mengenal juga perkembangan
dalam dunia internet, seperti halnya istilah blog dan bloger. Data di
atas diperkuat dengan jawaban responden yang sebagain besar
menyatakan selain mengenal juga mengetahui aktifitas bloger dalam
dunia citizen journalism.
Dari 64 responden yang mengenal istilah citizen journalism,
sebanyak 51 responden (79,68%) mengenal dari internet, 5 responden
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 131
(7,81%) mengenal dari artikel surat kabar, 3 responden (4,30%)
mengenal dari pembicaraan non formal, dan 5 responden (7,81%)
mengenal citizen journalism membaca dari buku.
Jawaban responden di atas sangat cocok dan sinkron dengan
jawaban sebelumnya, dimana internet telah menjadi sumber informasi
tentang perkembangan dunia internet. Sebagian besar responden
menyatakan mengetahui istilah dan aktifitas citizen journalism justru
dari media internet sendiri. Hal ini menunjukan bahwa memang
responden memanfaatkan internet dalam menunjang pekerjaannya
serta sebagai sumber informasi bagi penambahan wawasannya.,
Sebanyak 27 responden (42,18%) menyatakan setiap hari
membuka web-bloger, 29 responden (45,31%) menyatakan dua hari
sekali , dan , 8 responden (12,51%) menyatakan kadang-kadang
membuka web bloger.
Sama halnya dengan jawaban responden dalam membuka situs
internet, responden dalam mengakses situs atau blog cukup tinggi
frekuensinya. Sebagian besar responden menyatakan rata-rata setiap
hari membuka blog dalam internet.
Tentang keperluan membuka web para bloger, Sebanyak 39
responden (60,93%) menyatakan mencari informasi lokal yang tidak
tercover oleh media massa, 17 responden (26,56%) menyatakan
mencari artikel tentang informasi aktual, 8 responden (12,51%)
menyatakan membuka blog karena sesuai dengan keperluan.
Data di atas menunjukan bahwa, citizen journalism telah
berfungsi sebagai media informasi dan sumber data bagi pekerjaannya
sebagai jurnalis. Responden telah menempatkan citizen journalism
sebagai back up data dan informasi terhadap hala-hal yang tidak
diperoleh oleh dirinya sebagai jurnalis.
Penilaian Jurnalis Tentang Citizen Journalism
Sebanyak 49 responden (76,06.%) menyatakan bahwa citizen
journalism membantu tugas mereka sebagai wartawan, dan sebanyak
15 responden (23,94%) menyatakan tidak membantu tugas wartawan .
Sebagian besar responden menyatakan bahwa citizen journalism telah
membantu dirinya sebagai jurnalis seperti telah di analisa pada
jawaban sebelumnya. Namun bagi reponden yang menyatakan bahwa
citizen journalism tidak membantu pekerjaanya, dimungkinkan karena
132 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
sumber informasi lain diluar internet masih memadai responden dalam
melakukan pekerjaannya.
Tentang isi atau content yang ada dalam aktifitas citizen
journalism, 52 responden (81,25%) menyatakan bersifat opini, 9
responden (14,06%) menyatakan informasi, data atau lainnya, dan 5
responden (4,69%) menyatakan lebih bersifat ulasan atau pendapat
pribadi.
Tentang penilaian responden, dapat dianalisis bahwa di
samping menyatakan bahwa citizen journalism bermanfaat bagi
mendukung bidang kerjanya, responden sangat kritis dan selektif
dalam memberikan penilaian tentang isi blog atau isi dari citizen
jounalism. Sebagian responden menilai bahwa isi dari aktifitas citizen
journalism sebagian besar hanya berupa opini penulis.Jawaban ini
menyiratkan bahwa responden menempatkan citizen journalism
sebatas sebagai pendukung dan bukan sebagai sumber berita.
Tentang data, fakta, atau informasi yang ada dalam aktifitas
citizen journalism, 17 responden (26,56%) menyatakan percaya, 39
responden (60,93%) menyatakan tidak percaya dan 8 responden
(12,51%) menyatakan ragu-ragu.
Terdapat jawaban responden yang menarik untuk dianalisis,
bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak percaya terhadap
isi citizen journalism. Hal ini dimungkinkan karena penilaian
responden sebagai jurnalis yang tidak begitu saja menyerap informasi
tanpa melalui penelusuran kebenaran informasi.
Reaksi Jurnalis Terhadap Citizen Journalism
Dari 64 responden, seluruhnya merasa senang dengan
kehadiran citizen journalism. 23 responden (35,93%) senang karena
menambah sumber informasi, 13 responden (20,31%) karena dapat
menambah wawasan, 17 responden (26,56%) karena alasan hiburan,
dan 11 responden (11,20%) menyatakan senang terhadap kehadiran
citizen journalism karena menunjukan aktifitas menulis masyarakat
yang tinggi.
Data di atas menunjukan bahwa semua responden menyambut
baik aktifitas citizen journalism, selain sebagai sumber informasi,
sarana penambahan wawasan dan sarana hiburan, responden sebagai
seorang jurnalis menyatakan apresiasinya terhadap aktifitas menulis
oleh kalangan bloger.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 133
Namun berkaitan dengan kontribusi citizen journalism
terhadap tugas responden sebagai wartawan, 12 responden (18,75%)
menyatakan ada kontrinbusinya, 52 responden (91,25%) menyatakan
bahwa citizen journalism tidak berkontribusi terhadap tugas responden
sebagai jurnalis.
Kendatipun menyambut baik kehadiran citizen journalism,
dalam hal kontribusi terhadap pekerjaannya, kembali responden
menunjukan sikap kritis dan objektifnya. Data di atas menunjukan,
sebagian responden menyatakan bahwa citizen jounalism tidak
berkontribusi secara langsung terhadap profesinya sebagai
jurnalis.Jawaban tersebut dimungkinkan karena memang tidak ada
keterkaitan langsung antara seorang jurnalis aktifitas blog yang lazim
disebut bloger. Tidak ada keterkaitan antara civic journalism/ media
mainstream (media massa pada umumnya) dengan citizen journalism.
Bagi 12 responden yang menyatakan citizen journalism
berkontribusi terhadap profesi wartawan, 3 responden (24%) beralasan
karena citizen jornalism biasa menjadi sumber informasi, 5 responden
(41,66%) karena bisa menjadi sumber inspirasi, dan 4 responden
(33,34%) menyatakan bahwa citizen journalism berkontribusi dalam
hal memberikan wartawan ruang untuk beraktifitas di luar media
mainstream. Data yang menunjukan jawaban responden yang
menyatakan bahwa terdapat kontribusi citizen journalism bagi dirinya
sebagai jurnalis, menegaskan bahwa citizen journalism hanya
berkontribusi sebagi sumber inspirasi.
Tentang eksistensi citizen journalism dalam media mainstream
(media massa pada umumnya), sebanyak 58 responden (90,62%)
menyatakan tidak setuju apabila citizen journalis disamakan dengan
media mainstream, dan 6 responden (9,38%) menyatakan tidak tahu.
Data di atas menunjukan kesamaan dengan pendapat para pakar/ ahli
dibidang jurnalistik, bahwa memang tidak bisa disamakan antara
media massa pada umumnya dengan citizen journalism.
Jawaban responden di atas, sama dengan pernyataan responden
tentang eksistensi antara bloger dengan wartawan. Sebanyak 58
responden (90,62%) menyatakan tidak setuju apabila bloger
disamakan dengan wartawan, dan 6 responden (9,38%) menyatakan
tidak tahu. Pernyataan responden melalui jawabannya tentang tidak
bisa disamakannya antara media massa dengan citizen journalism,
diperkuat dengan jawaban responden di atas. Sebagian besar
responden menyatakan bahwa tidak bisa disamakan antara aktifitas
134 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
bloger dengan aktifitas seorang jurnalis. Lebih jelas sebagian
responden menyatakan bahwa tidak setuju apabila aktifitas bloger
disamakan dengan profesi wartawan.
Persentase jawaban yang sama juga diperoleh dari jawaban
tentang eksistensi citizen journalism dengan media mainstream (civic
journalism) atau media massa pada umumnya. Sebanyak 58 responden
(90,62%) menyatakan tidak setuju apabila citizen journalism
disamakan dengan media massa (media mainstream), dan 6 responden
(9,38%) menyatakan tidak tahu. Senada dengan ketidak setujuan dan
penolakannya terhadap disamakannya antara aktifitas bloger dengan
profesi wartawan, sebagian besar menyatakan tidak setuju apabila
media massa pada umumnya (surat kabar, radio, 134rgument,dll)
disamakan dengan citizen journalism. Jawaban responden tersebut
memang objektif dan sangat argumentatif, media massa dan segala
perangkatnya, dibentuk dan melaksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan aturan main yang baku.
Tentang alasan tidak bisa disamakannya antara citizen
journalism dengan civic journalism (media massa) yang diberikan
oleh 58 responden, sebanyak 37 responden (53,79%) beralasan karena
medianya berbeda, 21 responden (36,20%) karena audiensnya
berbeda, dan 6 responden (10,01%) beralasan karena tidak ada
persamaan sama sekali. Selain bentuk medianya yang berbeda,
responden menilai bahwa tidak bisa disamakannya antara civic
journalism/ media mainstream atau media massa pada umumnya
dengan citizen journalism, karena faktor audiencenya pun sangat
berbeda.
PEMBAHASAN
Berdasarkan jawaban responden yang diberikan dan telah
dianalisis di atas, pengetahuan, pemahaman sebagai (aspek kognitif),
penilaian (aspek afektif), dan kecenderungan reaksi ( aspek konatif)
responden sebagai seorang jurnalis sangat sesuai dengan teori yang
dipakai dalam penelitian ini. Responden sebagai seorang yang
berprofesi jurnalis melalui jawabannya telah memberikan gambaran
dan reaksinya tentang citizen journalism.
Sebagai jurnalis, jawaban responden yang menggambarkan
pengetahuan, pemahaman, penilaian dan reaksinya terhadap citizen
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 135
journalism. Gambaran sikap responden tersebut secara teoritis
mengacu kepada teori atau konsep tentang sikap. Yaitu : 1. Komponen
kognitif, pengetahuan, pengalaman, pengertian, pemahaman jurnalis
tentang citizen jounalism. 2. Komponen afektif, menyangkut masalah
emosional subjektif seorang jurnalis terhadap citizen journalism,
dipengaruhi kepercayaan atau apa yang responden percayai sebagai
benar dan berlaku bagi suatu objek. 3. Komponen konatif,
berhubungan dengan kecenderungan untuk beraksi, bertingkah laku
dengan cara tertentu, tapi konatif ini tidak meramalkan tingkah laku
aktual itu sendiri.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pengetahuan dan pemahaman jurnalis tentang citizen
journaslism. Para jurnalis dalam penelitian ini telah mengetahui
dan memahami istilah dan aktivitas citizen journalism. Sumber
informasi tentang citizen journalism berasal dari informasi/
content dalam internet dan buku . Dalam memanfaatkan blog
sebagai aktivitas citizen journalism, para jurnalis mempunyai
frekuensi dan intensitas waktu yang tinggi. Selain sebagai sumber
informasi dan data tambahan, citizen journalism juga berfungsi
sebagai sumber inspirasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai
jurnalis. Para jurnalis memahami timbulnya citizen journalism
sebagai ruang publik melalui media internet dalam rangka
partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya,
menceriterakan apa yang terjadi disekitarnya. Para jurnalis telah
mempergunakan weblog dengan frekuensi dan intensitas waktu
penggunaan yang cukup tinggi
2. Penilaian jurnalis tentang citizen journaslism. Terdapat
penilaian yang kritis dan objektif dari para jurnalis, bahwa isi atau
content dari blog sebagai media citizen journalism sebagian
merupakan tulisan berbentuk opini dan ulasan. Dari penilaian
tersebut memunculkan penilaian lainnya bahwa opini dan ulasan
kurang dipercaya validitasnya, penilaian ini argumentatif karena
sebagai seorang jurnalis dalam membuat berita tidak
mencampurkan antara opini dan fakta. Para jurnalis menilai bahwa
136 Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1
kehadiran citizen journalism melalui aktifitas bloger telah
membantu pekerjaannya sebagai jurnalis. Kontribusi yang
diberikan citizen journalism diantaranya berupa sumber informasi
dan inspirasi dalam hal informasi.
3. Reaksi jurnalis tentang citizen journalism. Para jurnalis merasa
senang dan menyambut baik aktifitas citizen journalism, karena
merupakan satu media bagi penyaluran dan peningkatan
kemampuan menulis, penyampaikan pendapat, serta mengangkat
sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Kendatipun
demikian, para jurnalis menyatakan bahwa tidak ada kontribusi
atau manfaat secara langsung antara keberadaan citizen journalism
dengan profesinya sebagai jurnalis. Terhadap anggapan bahwa
setiap individu adalah reporter, dan setiap individu adalah media,
secara eksplisit, tegas dan argumentatif, para jurnalis menyatakan
bahwa tidak bisa disamakan atau tidak sama antara citizen
journalism yang berkiprah dalam dunia internet dengan civic
journalism ( media mainsteram) atau media massa umumnya
seperti surat kabar, radio, televisi. Lebih jauh para jurnalis
menyatakan sukapnya, bahwa tidak bisa disamakan atau tidak
sama antara aktifitas bloger melalui media blog dalam citizen
journalism dengan profesi wartawan. Kesimpulan ini sesuai
dengan eksistensi wartawan dimana seorang wartawan adalah
orang yang profesional, seperti halnya dokter atau pengacara. Ia
memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki profesi lain
(memburu, mengolah, dan menulis berita). Ia juga punya
tanggungjawab dan kode etik tertentu.
Saran
Perlu adanya kesamaan persepsi yang konstruktif diantara
jurnalis, bloger, praktisi pers dan komunikasi, praktisi telematika dan
masyarakat pengguna media tentang keberadaan citizen journalism.
Kesamaan persepsi diantaranya mengenai perbedaan, dan persamaan
tentang tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja dan pelakunya.
Perbedaan secara substantif maupun kelembagaan, sehingga dapat
mendudukan keduanya dalam porsi, eksistensi, dan keberadaannya
masing-masing.
Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 12 No. 1 137
DAFTAR PUSTAKA
Sobur, Alex, 2002, Analisis Teks Media, Bandung : Remaja Rosda
Karya
Romli, Asep Syamsul M. 2003. Jurnalistik Terapan. Bandung : Batic
Press.
Severin, Werner J., James W. Tankard Jr.. 2005. Teori Komunikasi :
Sejarah, Metode, & Terapan Di Dalam Media Massa, Edisi
kelima. Jakarta : Prenada Media.
Sumber lain :
http://sulungz.blogs.friendster.com
http://www.pontianakpost.com
Pikiran Rakyat, 2006, Pusat Data Redaksi (Unit: Cyber Media-
Dokumentasi Digital), Bandung
.