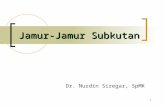Isolasi Dan Seleksi Jamur Indigenous
-
Upload
fakultaspertanian -
Category
Documents
-
view
414 -
download
8
description
Transcript of Isolasi Dan Seleksi Jamur Indigenous
Isolasi dan Seleksi Jamur Indigenous Asal Limbah Batik untuk Dekolorisasi Zat Warna Remazol Biruoleh : Dra. Ina Darliana, Msi Dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bandung Raya
Abstrak Telah dilakukan penelitian tentang Isolasi dan Seleksi Jamur Indigenous asal limbah batik untuk dekolorisasi zat warna remazol biru. Penelitian bertujuan untuk memperoleh jamur indigenous terpilih yang dapat mendekolorisasi zat warna remazol biru. Isolat jamur indigenous diperoleh dari limbah batik di Desa Trusmi Cirebon. Tiga Isolat diperoleh dari limbah batik dan salah satu isolat terpilih hasil seleksi adalah Aspergilus sp. Kata Kunci : Isolasi, Jamur indigenous, Limbah Batik, Aspergillus sp. PENDAHULUAN Zat warna dan bahan pembantunya adalah komponen utama pada proses pembuatan kain batik yang tidak seluruhnya akan terfiksasi pada proses pembatikan. Karakteristik limbah cair berwarna banyak dipengaruhi jenis zat warna yang digunakan dalam proses, terutama perbedaan dari sumber dan struktur kimia zat warna. Menurut sumbernya zat warna digolongkan menjadi zat warna alam dan zat warna sintetik. Secara umum zat warna alam lebih mudah terbiodegradasi dibandingkan dengan zat warna sintetik. Namun demikian, pada kenyataannya zat warna sintetik lebih banyak digunakan pada industri tekstil modern. Zat warna sintetik terdiri dari gabungan zat organik tidak jenuh diantaranya adalah senyawa hidrokarbon aromatik dan turunannya, fenol dan turunannya serta senyawa-senyawa hidrokarbon yang mengandung nitrogen (Manurung,2004). Pembuatan kain batik biasanya menggunakan zat warna sintetik, karena pengusaha batik jarang yang menggunakan zat warna alam. Zat warna sintetik lebih disukai karena dapat memenuhi kebutuhan skala besar, warna lebih bervariasi dan pemakaiannya lebih praktis dengan hasil pencelupan sangat baik (Montano, 2007). Zat warna sintetis yang banyak digunakan ialah zat warna remazol yang termasuk zat warna reaktif . Zat warna ini merupakan zat warna sintetik yang mengandung paling sedikit satu ikatan ganda N=N dan mempunyai gugus reaktif yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan gugus OH, -NH atau SH pada serat. Zat warna remazol banyak digunakan dalam pencelupan kain
terutama yang terbuat dari serat selulosa dan rayon. Hal ini disebabkan karena zat warna remazol dapat terikat kuat pada kain, memberikan warna yang lebih baik dan tidak mudah luntur (Blackburn and Burkinshaw, 2002). Zat warna reaktif disintesis untuk tidak mudah rusak oleh perlakuan kimia maupun fotolitik. Dengan demikian, apabila terbuang ke lingkungan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mengalami akumulasi dalam lingkungan sampai pada tingkat konsentrasi tertentu dan menimbulkan dampak negatif terhadap daya dukung lingku ngan. Potensi biodegradasi zat warna sintetik pada limbah cair dipengaruhi oleh kekuatan ikatan kimia dari gugus kromofor yang dimilikinya. Karena aplikasinya yang cukup luas, biodegradasi zat warna azo paling banyak dipelajari dengan berbagai macam teknologi pengolahan biologi baik aerobik maupun anaerobik melalui banyak pengembangan metode. Pada dasarnya teknik pengolahan biologi mampu memutuskan ikatan kimia gugus azo dan menghilangkan warna, namun efisiensi pengolahan bervariasi dan menghasilkan kualitas effluen pada level yang berbeda-beda (Manurung,dkk., 2004). Pengelolaan limbah cair bagi industri batik merupakan masalah yang sulit diatasi, karena industri batik umumnya berupa Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang terbatas akan penyediaan lahan dan ketidak mampuan mengolah limbah (Astirin dan Winarno, 2000). Selain dibuang ke sungai kebanyakan cara pengolahan limbah dilakukan secara kimia dan fisika yang dilakukan dengan menggunakan metode adsorpsi, koagulasi dan oksidasi. Pengolahan limbah dengan cara ini cukup efektif menghilangkan warna, akan tetapi memerlukan biaya yang besar dan menggunakan bahan kimia yang banyak. Selain itu, proses tersebut menimbulkan limbah sampingan berupa sludge yang banyak yang dapat menyebabkan pendangkalan pada bak pengolahan limbah, sehingga perlu dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap sludge tersebut (Bidendhi et al., 2007., Aslam et al.,2004). Untuk mengatasi kelemahan pengolahan limbah secara fisika dan kimia, maka pengolahan limbah dapat dilakukan secara biologis yang merupakan salah satu alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pengolahan limbah secara biologis menggunakan mikroorganisme sebagai agensia pengurai zat warna. Penggunaan mikroorganisme untuk mengolah limbah sangat potensial untuk dikembangkan, karena limbah tekstil mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme tertentu sebagai sumber nutrisi (Pandey et al.,2007) Kandungan bahan organik yang ada dalam limbah memungkinkan mikroorganisme indigenous dapat tumbuh pada limbah cair batik (Mayanti dan Herto 2009).
Mikroba indigenous adalah mikroba yang secara alamiah mampu hidup pada lingkungan tertentu yang merupakan tempat tumbuh mikroba tersebut sejak awal, seperti limbah dan substrat lain. Mikroba tersebut sudah teradaptasi dan diharapkan mampu melakukan degradasi senyawa-senyawa organik dan pencemar yang terdapat pada limbah pada kondisi yang sesuai. Mikroba indigenous yang diduga ada dalam limbah umumnya dari kelompok bakteri dan jamur (Mayanti dan Herto, 2009). Beberapa mikroba indigenous tertentu memiliki kemampuan untuk menggunakan zat warna sebagai sumber karbon dan nitrogen dan mereduksi zat warna tersebut dengan enzim azo reduktase (Sharma et al, 2009). Penggunaan mikroba indigenous lebih menguntungkan dibanding menggunakan mikroba komersial. Selain harganya mahal, mikroba komersial juga belum tentu sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah, selain itu dapat menyebabkan terjadinya kompetisi dengan mikroba alami yang terdapat di dalam limbah. Isolat-isolat lokal dari daerah tercemar memiliki kemampuan mendegradasi limbah dengan baik. Mikroba yang diisolasi dari limbah batik kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk mendekolorisasi zat warna. Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan mikroba untuk proses dekolorisasi zat warna adalah dari jenis jamur pelapuk putih yaitu Trametes vilosa, Phanerochaete chrysosporium (Machado et al, 2006). Selain jamur pelapuk putih, terdapat juga jamur lain yang memiliki kemampuan dalam menurunkan kadar zat warna, antara lain Aspergillus sp (Ramya et al, 2007), Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum dan Trichoderma harzianum, Penicillium simplicissimum (Torralba et al., 2009). Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini akan dilakukan isolasi, dan identifikasi jamur indigenous asal limbah cair batik dari daerah Trusmi Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya akan diseleksi kemampuan isolat jamur terpilih tersebut untuk dekolorisasi zat warna remazol biru yang merupakan zat warna yang paling banyak digunakan pada industri batik di Cirebon. Proses dekolorisasi menggunakan jamur indigenous hingga saat ini belum banyak dikembangkan, adanya jamur indigenous yang sudah lama teradaptasi dengan lingkungan limbah batik diharapkan mempunyai kemampuan untuk merombak zat warna.
BAHAN DAN METODE Sumber Isolat Isolat yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil isolasi dari limbah cair batik. Bahan Zat warna Remazol biru yang digunakan dalam penelitian adalah produk Ciba-Geigi. HCl, NaOH, Buffer asetat dll. Media yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Potato Dextrose Agar (PDA), Potato Dextrose Broth (PDB) produk Pronadisa. Metode Isolasi dan seleksi Jamur Indigenous asal limbah batik Tahap pertama yaitu persiapan isolasi jamur indigenous dari sampel yang berasal dari limbah cair industri batik menggunakan metode tuang dengan melakukan serangkaian pengenceran dan dikultur pada medium Potato Dextrose Agar (PDA). Isolat jamur yang diperoleh tersebut kemudian diseleksi dengan metode SmF (Submerged Fermentation) dengan cara merendam langsung suspensi jamur dalam zat warna remazol biru pada konsentrasi 50 ppm dan diinkubasi di rotary shaker pada kecepatan 100 rpm. Perubahan warna yang terjadi diamati setiap 24 jam sekali untuk mendapatkan isolat jamur yang paling cepat dalam menurunkan kadar warna remazol biru. Dari hasil seleksi isolat jamur tersebut, didapatkan satu isolat jamur unggul berdasarkan waktu dekolorosasi tercepat. Selanjutnya adalah pembuatan starter jamur untuk proses dekolorisasi pada medium Potato Dextrose Broth (PDB) yang mengandung zat warna remazol biru 50 mg/L. Uji aktivitas dekolorisasi secara SmF (submerged fermentation) pada inkubator shaker selama 7 hari fermentasi. Diberikan perlakuan pH untuk melihat pH optimal bagi pertumbuhan jamur. Perubahan warna diamati, diambil sampel setiap hari untuk dibuat kurva pertumbuhan, sehingga bisa diamati korelasi antara pengurangan warna dengan jumlah koloni jamur. HASIL DAN PEMBAHASAN Isolasi, Seleksi dan Identifikasi Jamur Indigenous Limbah Cair Batik Berdasarkan hasil isolasi dari limbah cair batik melalui serangkaian pengenceran, diperoleh tiga isolat jamur indigenous yang berpotensi untuk menurunkan kadar warna pada limbah cair batik. Ketiga isolat jamur tersebut diseleksi dengan metode fermentasi kultur terendam atau Submerged Fermentation (SmF), hasil identifikasi menunjukkan ketiga isolat jamur tersebut merupakan jenis jamur Aspergillus sp. Rhizopus sp. dan Penicillium sp. seperti ditampilkan pada gambar berikut.
1. Aspergillus sp. .A
B
Gambar
1. (A) Koloni
Aspergillus sp. (B) Spora Aspergillus sp. (Sumber gambar : Dokumentasi Pribadi, 2011)
Klasifikasi Aspergillus sp. menurut Barnet, (1960) Kerajaan Fungi Divisi Ascomycota Kelas Deuteromycetes Ordo Moniliales Famili Moniliaceae Genus Aspergillus Spesies Aspergillus sp. Pada pengamatan secara makroskopis (Gambar 1A), tampak koloni Aspergillus sp. berbentuk bulat dengan pinggiran rata dengan warna putih kehijauan, putih kekuningan dan hijau kekuningan. Pada awal pertumbuhan koloni, permukaannya tampak cembung dan terdapat lekukan ke dalam koloni yang tampak membagi koloni menjadi beberapa bagian dan bagian tengahnya seperti kawah. Spora sangat banyak dan menempel pada hifa dengan warna kuning kehijauan. Pada pengamatan secara mikroskopis (Gambar 1.B), tampak hifa memiliki septa dengan struktur halus yang muncul dari permukaan koloni. 2. Rhizopus sp. .A B
Gambar 2. (A) Koloni Rhizopus sp. (B) Spora Rhizopus sp.
(Sumber gambar : Dokumentasi Pribadi, 2011)
Klasifikasi Rhizopus sp. menurut Barnet, (1960) Kerajaan Fungi Divisi Zygomycota Kelas Deuteromycetes Ordo Moniliales Famili Moniliaceae Genus Rhizopus Spesies Rhizopus sp. Ciri makroskopis dari Rhizopus sp. adalah koloni berbentuk bulat dengan pinggiran merata. Pada awal pertumbuhan, hifa tampak putih dengan jumlah yang sangat banyak seperti serabut dan semakin lama menjadi berwarna coklat kehitaman. Spora tampak menempel di bagian atas hifa seperti butiran kecil berwarna coklat kehitaman (Gambar 2A). Secara mikroskopis (Gambar 2B), hifa tampak bermunculan dari permukaan koloni, hifa berwarna putih dan tidak bersekat, terdapat askus berwarna coklat kehitaman sebagai tempat dihasilkannya spora.
3. Penicillium sp.A B
Gambar
3. (A) Koloni
Penicillium sp. (B) Spora Penicillium sp. (Sumber gambar : Dokumentasi Pribadi, 2011)
Klasifikasi Penicillium sp. menurut Barnet, (1960) Kerajaan Fungi Divisi Eumycophyta Kelas Ascomycetes Ordo Aspergillales Famili Aspergillaceae Genus Penicillium Spesies Penicillium sp.
Bentuk koloni bulat dengan tepi koloni tidak beraturan, permukan bagian tengah berwarna coklat kehijauan tampak cembung membentuk suatu puncak, sedangkan pada bagian tepi berwarna abu kehijauan dan terdapat lekukan (Gambar 3A). Secara mikroskopis (Gambar 3B), tampak hifa memiliki septa dengan struktur halus yang muncul dari permukaan koloni. Pada hifa terdapat cabang sebanyak dua buah dan tiap cabang memiliki rantai-rantai dan pada tiap ujung rantai terdapat sterigmata. Ketiga isolat jamur tersebut kemudian diseleksi dengan metode SmF (Submerged Fermentation) dengan cara merendam langsung suspensi jamur dalam zat warna remazol biru pada konsentrasi 50 ppm dan diinkubasi di rotary shaker pada kecepatan 100 rpm. Perubahan warna yang terjadi diamati setiap 24 jam sekali untuk mendapatkan isolat jamur yang paling cepat dalam menurunkan kadar warna remazol biru. Dari hasil seleksi pada ketiga isolat jamur tersebut, didapatkan satu isolat jamur unggul berdasarkan waktu dekolorosasi tercepat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa jamur tersebut adalah jenis Aspergilus sp. Isolat jamur Aspergilus sp. dapat mendekolorisasi zat warna remazol biru dalam waktu inkubasi 2 X 24 jam, larutan berubah menjadi lebih bening dengan endapan berwarna biru. Terbentuknya endapan berwarna biru karena adanya proses adsorpsi oleh micelium jamur. Seleksi isolat jamur terpilih dapat dilihat pada Gambar 4 berikut :
Gambar 4. Seleksi isolat jamur terpilih melalui fermentasi terendam
Uji Aktivitas Dekolorisasi Aspergillus sp. Pada Variasi Konsentrasi Zat Warna dan pH Pengukuran pertumbuhan jamur dilakukan dengan menghitung jumlah koloni jamur secara langsung atau Direct Count. Penghitungan koloni jamur dilakukan melalui TPC (Total Plate Count) selama 7 hari inkubasi pada masing-masing variasi konsentrasi zat warna dan variasi pH seperti ditampilkan pada Gambar 5 berikut :
Pertumbuhan Jamur (x108 Sel/ml)
Kurva Pertumbuhan Jamur Pada Konsentrasi 50 PPM 7060 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7
pH 5 pH 6 pH 7
Waktu Inkubasi (Hari)
Kurva Pertumbuhan Jamur Pada Konsentrasi 100 PPMPertumbuhan Jamur (x108 se/ml)60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7
pH 5 pH 6
Waktu Inkubasi (Hari)
Kurva Pertumbuhan Jamur Pada Konsentrasi 200 PPMPertumbuhan Jamur (x108 sel/ml)60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7
pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
Waktu Inkubasi (Hari)
Gambar 5 Kurva pertumbuhan jamur pada variasi konsentrasi zat warna dan variasi pH
Jamur pada medium fermentasi diduga mampu memanfaatkan nutrisi yang ada dalam zat warna untuk proses metabolisme. Berdasarkan kurva pertumbuhan jamur pada Gambar 5(A,B,C), dapat diketahui bahwa pada konsentrasi zat warna 50 ppm, 100 ppm dan 200 ppm dengan variasi pH 5, 6, 7, 8 dan 9, fase adaptasi (lag phase) pertumbuhan Aspergillus sp. berada pada hari pertama hingga hari ketiga fermentasi. Pertumbuhan Aspergillus sp. memasuki fase eksponensial dengan jumlah pertumbuhan tertinggi pada hari ke-4 fermentasi. Kondisi pH optimum untuk berlangsungnya proses pertumbuhan jamur pada konsentrasi 50, 100, dan 200 ppm selama 7 hari inkubasi adalah pH 57 . Jamur pada konsentrasi zat warna 50, 100 dan 200 ppm dapat tumbuh dan beraktivitas baik, beberapa jamur dapat tumbuh dalam lingkungan basa atau pH diatas normal namun kebanyakan jamur tumbuh pada pH asam sampai netral (Cutright, 2001). Pada masing-masing variasi konsentrasi zat warna, Aspergillus sp. tumbuh maksimum pada fase eksponensial dengan kondisi pH 5, hal ini disebabkan karena jamur memiliki pertumbuhan yang baik pada medium atau substrat dengan suasana asam. Kondisi pH dapat mempengaruhi fungsi sel, transport dalam membran sel, serta kesetimbangan reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian HeFang, (2004) yang menyatakan bahwa pH sangat mempengaruhi persentase pertumbuhan jamur, jamur akan memiliki pertumbuhan yang baik pada kondisi asam hingga netral. Terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan Aspergillus sp. memasuki fase kematian (death phase) dengan penurunan pertumbuhan koloni hingga hari ke-7 pada akhir fermentasi. Pada kondisi pH 9 untuk setiap konsentrasi zat warna, Aspergillus sp. memiliki pertumbuhan terendah dibandingkan dengan variasi pH lainnya, hal ini disebabkan karena jamur memiliki pertumbuhan yang kurang baik pada medium atau susbtrat dengan kondisi basa. Jamur pada kondisi pH diatas netral mengalami penurunan pertumbuhan disebabkan fungsi sel tidak bisa berjalan optimal dan menyebabkan transportasi dalam membran sel terganggu. Pertumbuhan dan aktifitas jamur sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. . hari ke-0 dan hari ke-1 belum terjadi perombakan zat warna atau bahan organik. Starter jamur pada saat dimasukan kedalam medium fermentasi berada pada fase eksponensial, sehingga proses dekolorisasi yang terjadi bukan karena perombakan zat warna, tetapi karena adanya proses adsorpsi atau penyerapan oleh micelium jamur yang terlihat dari endapan berwarna biru. Pada hari ke-3 dan ke-4 inkubasi jamur memasuki fase eksponensial dimana jumlah koloni jamur pada fase ini jumlahnya banyak, jamur mulai merombak zat warna untuk memenuhi
kebutuhan nutrisi dan energi untuk kelangsungan metabolisme sel. Didalam proses perombakan, jamur memerlukan bantuan enzim sebagai katalis. Pada kondisi yang optimal jamur membentuk enzim, hal ini dimungkinkan karena kondisi lingkungan yang mendukung. Pada konsentrasi 50 ppm dan 100 ppm kandungan nutrisi relatif hampir sama, sehingga perombakan yang terjadi pada kondisi yang sama. Untuk 200 ppm jumlah bahan organik yang ada dalam zat warna lebih banyak sehingga jamur memerlukan fase adaptasi yang lebih lama untuk dapat merombak zat warna. Pada konsentrasi 200 ppm jamur menyesuaikan diri dengan kondisi medium fermentasi, setelah kondisi optimum tercapai, baru proses metabolisme melalui reaksi reduksi dan oksidasi dimulai. Ini sesuai dengan pendapat Gosczczynsky et al., (1994). Proses dekolorisasi zat warna remazol biru konsentrasi 50 ppm, 100 ppm, dan 200 ppm diamati hingga hari ke-7 inkubasi. Laju penghilangan warna oleh Aspergillus sp. untuk konsentrasi 50 ppm dan 100 ppm tidak terlalu jauh berbeda kecuali untuk konsentrasi 200 ppm. Secara umum dapat dikatakan persentase penghilangan warna konsentrasi 50 ppm dan 100 ppm menunjukkan laju penghilangan warna yang lebih baik dibandingkan konsentrasi 200 ppm. Kualifikasi proses dekolorisasi ini didasarkan hanya pada pengamatan secara visual. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut 1. Isolat jamur indigenous yang paling efektif dalam menurunkan kadar zat warna remazol biru adalah Aspergillus sp. 2. Konsentrasi zat warna dan pH optimum untuk pertumbuhan jamur dalam merombak zat warna remazol biru adalah 100 mg/L dan pH 5.
SARAN 1. Peningkatan efisiensi dekolorisasi untuk menurunkan kadar zat warna remazol biru melalui pengaturan parameter fermentasi seperti suhu dan agitasi serta penambahan kofaktor untuk meningkatkan pertumbuhan jamur dan aktivitas enzim selama proses dekolorisasi. 2. Peningkatan efisiensi dekolorisasi dengan konsorsium mikroba melalui penggabungan kultur jamur Aspergillus sp. dengan kultur jamur lainnya atau dengan kultur bakteri.
DAFTAR PUSTAKA Aslam, M.M., M.A. Baig., I. Hasan., I.A. Qozi., M.Malik and H. Saed. 2004. Textile Wastewater Characterization and Reduction of its COD and BOD By Oxidation. Electron. J.Environ. Agric.Food.Chem. Astirin, O. dan Winarno, K. 2000. Peran Pseudomonas dan Khamir dalam Perbaikan Kualitas dan Dekolorisasi Limbah Cair Industri Batik Tradisional. http://www.uns.ac.id/datainformasi/profil/MIPA/okid.xls. Diakses tanggal : 02 Februari 2010. BergstenToralba,L.R.,Nishikawa,M.M.,Baptista,D.I.,Magalhaes,D.P.,daSilv a,M. Decolorization of Different Textile Dyes By Penicillium simplicisimum and Toxicity Evaluation After Fungal Treatment. 2009. Brazillian Journal of Microbiology(2009)40:808-817. Bidhendi, G.R., A. Torabian., H. Ehsani. and N.Razmkhah. 2007. Evaluation of Industrial Dyeng Wastewater Treatment With Coagulant and Polyelectrolite as a Coagulant Aid. Iran.J.Environt.Health.Sci.Eng. 4(1). Blackburn, R.S. and S.M. Burkinshaw. 2002. A Greener to Cotton Dyeing With Excellent Wash Fastness. Green. Chem. 4:47-52. Cutright, T.J. 2001. Biotechnology Principles and Advances in Waste Control. Department Of Civil Engineering. University of Akron. Goszczynsky. et al. 1994. New Pathway For Degradation Of Sulfonated Azo Dyes By Microbial Peroxidase Of Phanerochaete chrysosporium and Streptomyces chromofuscus. J. Bacteriol. He Fang., HuWenrong and LiYuezhong. 2004. Biodegradation Mechanism and kinetic Of Azo Dyes 4 BS By a Microbial Consortium. Chemosphere. Machado, K.M.G., Compart, R.O., Morais, L.H., Rosa, M.H. and Santos. 2006. Biodegradation of Reactive Textile Dyes By Basidiomycetous Fungi From Brazillian Ecosystems. Brazillian. J. Microbiol. Mayanti,B dan Herto Dwi Arysyadi.2009. Identifikasi Keberagaman Bakteri Pada Comercial Seed Pengolah Limbah Cair Cat. Institut Teknologi Bandung. Mohandass Ramya.m, Bhaskar Anusha.,S.Kalavathy and S.Devilaksmi. 2007. Biodecolorization and Biodegradation of Reactive Blue By Aspergillus sp. African Journal of Biotechnology Vol.6(12).pp.14411445,18 june 2007.
Montano, J.G. 2007. Combination Of Advanced Oxidation Processes and Biological Treatments For Commercial Reactive Azo Dyes Removal. Theses. Universitait Autonoma de Barcelona. Bella terra. Pandey, A., P.Singh. and L.Iyengar. 2007. Bacterial Decolorization and Degradation of Azo Dyes [Review]. Int Biodet and Biodeg. Sharma,P.Singh,L.,Dilbaghi,N.2009. Optimation Of Process Variable For Decolorization of Disperse Yellow 211 by Bacillus subtilis using Box Behnken Design. Jounal of Hazardous Materials Vol 164.pp 10241029