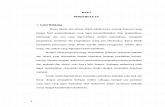Isi Makalah
-
Upload
anggun-oktavia-adityas -
Category
Documents
-
view
452 -
download
17
Transcript of Isi Makalah

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat
tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.
Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini
dikenal dengan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya). Bahan ini dirumuskan
sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi
mencemarkan/merusakkan lingkungan kehidupan dan sumber daya.
Beberapa kriteria berbahaya dan beracun telah ditetapkan antara lain mudah
terbakar, mudah meledak, korosif, oksidator dan reduktor, iritasi bukan radioaktif,
mutagenik, patogenik, mudah membusuk dan lain-lain. Industri kain sasirangan
dapat dijuluki sebagai penghasil utama limbah cair, hal ini disebabkan dari proses
penyempurnaan tekstil yang memang selalu menggunakan air sebagai bahan
pembantu utama dalam setiap tahapan prosesnya. Pencemaran air dari industri kain
sasirangan dapat berasal dari : buangan air proses produksi, buangan bahan-bahan
kimia sisa proses produksi, sampah potongan kain dan lainnya. Dalam jumlah
tertentu dengan kadar tertentu, kehadirannya dapat merusakkan kesehatan bahkan
mematikan manusia atau kehidupan lainnya sehingga perlu ditetapkan batas-batas
yang diperkenankan dalam lingkungan pada waktu tertentu.
Adanya batasan kadar dan jumlah bahan beracun dan berbahaya pada suatu
ruang dan waktu tertentu dikenal dengan istilah nilai ambang batas, yang artinya
dalam jumlah demikian masih dapat ditoleransi oleh lingkungan sehingga tidak
membahayakan lingkungan ataupun pemakai. Karena itu untuk tiap jenis bahan
beracun dan berbahaya telah ditetapkan nilai ambang batasnya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ingin diajukan yaitu
sebagai berikut.
1. Apakah kain sasirangan itu?
2. Apa saja bahan untuk membuat kain sasirangan?
3. Bagaimana cara pembuatan kain sasirangan?
4. Apa saja bahan pencemar yang terdapat dalam industri kain sasirangan di
“Zahra Sasirangan”?
5. Apa saja dampak limbah dari industri kain sasirangan di “Zahra Sasirangan”?
6. Bagaimana teknik pengolahan limbah di industri “Zahra Sasirangan” dan
teknik penanganannya?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.
1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kain sasirangan.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan bahan-bahan untuk membuat kain sasirangan.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan cara pembuatan kain sasirangan.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam bahan pencemar yang terdapat
dalam industri kain sasirangan khususnya di industri “Zahra Sasirangan”.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan dampak yang terjadi dari limbah industri kain
sasirangan di “Zahra Sasirangan”.
6. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik pengolahan limbah sasirangan dan
teknik penanganannya.

BAB II
ISI
2.1 Sejarah Kain Sasirangan
Kain sasirangan adalah kain khas Kalimantan Selatan. Kain ini dipercaya
sebagai kain sakral warisan abad XII saat Lambung Mangkurat menjadi Patih Negara
Dipa yang sering dipergunakan dalam pengobatan (batatamba). Pada waktu dulu
tidak semua orang bisa menjadi pengrajin kain sasirangan, karena umumnya sebagai
keterampilan yang bersifat keturunan, sehingga keterampilan tersebut tidak mudah
dinalarkan kepada sembarang orang.
Berbeda dengan zaman dahulu, pembuatan kain sasirangan pada dewasa ini
bersifat terbuka. Artinya siapa saja dapat membikin kain khas Banjar tersebut,
asalkan ada memiliki keterampilan. Diperlukan adanya kesungguhan, ketelitian dan
kecermatan, sehingga menghasilkan selembar kain sasirangan yang baik, sempurna
dan bermutu.
Perkembangan zaman yang semakin maju dengan adanya sarana dan
prasarana sektor pendidikan dan kesehatan serta faktor agama Islam, sangat
berpengaruh terhadap tradisi masyarakat Banjar dengan cara batatamba (pengobatan)
dengan mempergunakan kain sasirangan ini.
2.2 Bahan untuk Membuat Kain Sasirangan
Untuk membuat kain sasirangan kita harus menyiapkan bahan yang digunakan
terlebih dahulu.
Bahan –bahan yang digunakan adalah sebagai berikut.
1. Kain
Bahan baku untuk membuat kain sasirangan adalah serat kapas (katun). Bahan
baku lain tidak hanya kapas, tetapi juga nonkapas seperti polyester, rayon, sutera

dan lain-lain. Namun, karena saat ini sudah tersedia kain yang siap pakai jadi kita
tidak perlu lagi memulai dengan pemintalan kapas. Hanya saja kain yang dijual di
toko-toko itu sudah difinish atau di kanji. Padahal, kanji itu dapat menghalangi
penyerapan kain oleh zat pewarna. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan
kanji tersebut dengan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut.
a. Direndam dengan air
Kain yang hendak dibuat Sasirangan direndam dalam air selama satu atau dua
hari, kemudian dibilas. Namun cara ini tidak banyak disukai, karena
prosesnya terlalu lama dan ada kemungkinan timbul mikro organisme yang
dapat merusak kain.
b. Direndam dengan asam
Kain direndam dalam larutan asam sulfat atau asam chloridaselama satu
malam, atau hanya membutuhkan waktu dua jam jika larutan zat asam
tersebut dipanaskan pada suhu 350 C. Setelah itu, kain dibilas dengan air
sehingga kain terbebas dari zat asam.
c. Direndam dengan enzim
Bahan kain yang hendak dibuat Sasirangan dimasak dengan larutan enzim
(Rapidase, Novofermasol dan lain-lain) pada suhu sekitar 450 C selama 30 s/d
45 menit. Setelah itu, kain direndam dalam air panas dua kali masing-masing
5 menit, dan kemudian dicuci dengan air dingin sampai bersih.

2. Pewarna
Yang harus diperhatikan dalam pengadaan pewarna kain adalah sebagai berikut.
a. Harus mempunyai warna sehingga dapat mengabsorbs cahaya
b. Dapat larut dalam air atau mudah dilarutkan
c. Zat warna harus mempunyai afinitas terhadap serat (dapat menempel), tidak
luntur, dan tahan terhadap sinar matahari.
d. Zat warna harus dapat berdifusi pada serat.
e. Zat warna harus mempunyai susunan yang stabil setelah meresap ke dalam
serat.
Alam lingkungan hidup sekitar rumah tangga memberikan kemudahan bagi
pengolah kain sasirangan untuk mengolah warna dalam berbagai corak, namun
tentu saja masih sangat terbatas. Pada umumnya warna-warna yang diperoleh dari
alam adalah warna-warna pokok saja, seperti :
1) Kuning berasal dari kunyit dan temulawak.
2) Merah berasal dari zat gambir buah mengkudu atau cabe merah.
3) Hijau berasal dari daun pudak atau jahe.
4) Hitam berasal dari kabuau atau uar.
5) Ungu berasal dari biji gandaria atau buah karamunting.
6) Coklat berasal dari uar atau kulit buah rambutan.
Dari enam macam warna pokok tersebut berdasarkan pengalaman yang sudah
turun temurun, dicampur dengan berbagai rempah-rempah, dengan tujuan untuk
mengawetkan warna, menajamkan warna atau mengubah warna menjadi lebih tua
atau lebih muda. Rerempahan yang dipergunakan pada waktu dahulu adalah
seperti garam, jintan, lada, pala, cengkeh, jeruk nipis, kapur, tawas, cuka atau
terusi.
Pada dewasa ini para pengrajin sasirangan tidak lagi bersusah payah meramu
reramuan alam untuk membikin warna guna mewarnai kain sasirangan. Dengan

membanjirnya zat warna sintesis sebagai barang import ke Indonesia dari luar
negeri yaitu dari Eropa (Inggris, Jerman, Prancis, Swiss), jepang dan Cina RCC,
sekaligus menyingkirkan ramuan-ramuan warna tradisional dalam negeri,
termasuk daerah Kalimantan Selatan. Memang ada usaha-usaha untuk mengolah
zat pewarna secara alami dengan mempergunakan bahan-bahan dari alam sekitar
kehidupan kita. Namun prosesnya memerlukan waktu dan justru pula
memerlukan biaya lebih besar manakala dibandingkan dengan membeli zat warna
sintesis. Namun terdapat hal positif dari zat pewarna alami ini yaitu ramah
lingkungan, tidak berdampak yang merugikan dari limbahnya.
Zat warna sintesis produk industri luar negeri misalnya dari WLS, Willy dan
Son Chemical Industries yang diproduksi kaleng plastic. Isinya berupa bubuk
warna dalam berbagai warna seperti merah, merah muda, hijau, hijau muda,
kuning, coklat, krim, ungu, biru, biru tua, hitam dan lainnya.
Jenis - jenis zat warna yang dikenal antara lain :
* Zat warna Direct
* Zat warna Basis
* Zat warna Asam
* Zat warna Belerang
* Zat warna Hydron
* Zat warna Bejana
* Zat warna Bejana Larut
* Zat warna Napthol
* Zat warna Dispersi
* Zat warna reaktif
* Zat warna Rapid
* Zat warna Pigmen
* Zat warna Oksidasi

3. Perintang atau pengikat
Biasanya terbuat dari benang kapas, benang polyester, rafia, benang ban, serat
nanas dan lainnya.
Fungsi bahan perintang adalah untuk menjaga agar bagian-bagian tertentu dari
kain terjaga dari warna yang tidak diinginkan.Oleh karena itu, bahan perintang
harus mempunyai spesifikasi khusus, diantaranya adalah sebagai berikut.
a) Tidak dapat terwarnai oleh zat warna, sehingga mampu menjaga bagian-bagian
tertentu dari zat warna yang tidak diinginkan.
b) Mempunyai konstruksi anyaman maupun twist yang padat.
c) Mempunyai kekuatan tarik yang tinggi.
2.3 Cara Pembuatan Kain Sasirangan
Secara kronologis proses pembuatan kain sasirangan tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Melukis atau Menggambar
Mula-mula pada kain putih dilukis suatu motif yang diinginkan. Kain yang akan
dilukis tersebut telah dipotong menurut ukuran yang diinginkan, misalnya 2 meter

atau 3 meter. Kain putih ini bisa dari kain katun, shantung, balacu, kaci, king,
primasima, satin atau sutera, sesuai yang diinginkan. Melukis, cukup dengagn
mempergunakan pensil biasa asalkan hasil garis-garis lukisan tersebut tampak
dengan jelas. Pekerjaan melukis atau menggambar ini dapat dibedakan dalam dua
cara, yaitu :
a. Melukis atau menggambar dengan langsung dan bebas sesuai dengan lukisan
atau gambar apa yang diinginkan, misalnya melukis selembar daun, bunga,
bintang dan lain-lain.
b. Melukis atau menggambar dengan mempergunakan pola atau mal yang telah
ada. Lukisan atau gambar yang dihasilkan tentu saja telah terikat dengan pola
yang sudah ada. Pola atau mal yang telah berlubang-lubang seperti garis lurus,
garis lengkung, bundar, dan sebagainya. Pola atau mal itu diletakkan di atas
kain putih yang dilukis. Setelah selesai, pola atau mal itu diletakkan lagi ke
samping kain tersebut untuk mendapatkan gambar-gambar yang sama.
Pekerjaan disini sebenarnya bukan melukis atau menggambar, tetapi hanya
menggaris-garis dengan pensil menurut alur garis-garis sesuai pola yang
sudah ada.
Motif gambar yang dihasilkan di sini umumnya adalah untuk mendapatkan
kain sasirangan yang seragam motifnya dalam jumlah yang banyak.

2. Menjahit atau Menjelujur
Setelah lukisan selesai tergambar pada lembaran kain putih tersebut, pekerjaan
berikutnya adalah menjahit. Dengan mempergunakan jarum tangan yang telah
diberi benang yang kuat. Kain tersebut dijahit (dijelujur) dengan cara mengikuti
garis-garis hasil lukisan. Kadang-kadang jahitan itu bisa saja berupa ikatan dengan
benang.Manakala jahitan (jel/ujur) dengan benang tersebut telah selesai untuk
selembar kain, maka benang-benang tersebut ditarik kuat (disisit), sehingga
tampak hasilnya, kain yang dijahit tersebut menjadi mengkerut.
3. Memberi warna
Baskom yang telah disediakan ditaburi bubuk warna yang diinginkan. Bubuk
warna yang digunakan adalah zat pewarna sintetik, seperti zat warna naphtol.
Bubuk warna itu dicairkan dengan air panas, kemudian diaduk dengan wancuh
sampai cairan warna itu benar-benar tampak telah merata. Setelah cairan warna
sudah agak dingin, kain yang telah dijahit (dijelujur) tadi dicelupkan ke dalam
baskom yang berisi cairan warna tersebut. Harus diingatkan, mencelupkan kain ke
dalam baskom tersebut, kedua belah tangan harus mempergunakan sarung tangan
dari karet tebal yang panjangnya sampai ke siku.
Kain yang diberi warna tersebut tidak sekedar dicelupkan begitu saja ke dalam
baskom. Tetapi kain tersebut harus diremas-remas, dibolak balik beberapa kali,
sehingga warna yang diinginkan benar-benar telah merata dengan baik pada kain

tersebut. Pekerjaan memberi warna ini biasanya berlangsung antara 5 sampai 10
menit.
Setelah selesai memberi warna di dalam baskom tersebut kain itu kemudian
ditempatkan pada balok rentang guna dikeringkan, tetapi tidak dijemur langsung
kena cahaya matahari. Perendaman kain ke dalam baskom itu bisa beberapa kali,
sesuai dengan jumlah warna yang diinginkan. Kain yang telah diberi warna
tersebut dibiarkan (ditiriskan) lebih kurang 30 menit.
Setelah selesai ditiriskan, kemudian dilakukan penciciran terhadap kain
dengan menggunakan spoons. Setelah itu kain dicuci untuk menghilangkan aroma
dari zat pewarna yang dipakai. Kemudian kain yang telah dicuci tersebut ditiriskan
(dikeringkan).
Harus diingat pula, untuk memberi kain sasirangan ini, yaitu begitu selesai
pekerjaan mewarnai, hendaklah mencuci tangan bersih-bersih dengan sabun.
Lebih-lebih kalau akan memegang makanan, karena bubuk warna itu adalah bahan
kimia.

4. Melepaskan Benang Jahitan
Apabila kain yang telah diberi warna tersebut sudah agak kering, selanjutnya
kain itu digelar di atas tikar purun, benang-benang jahitan atau ikatan pada kain
tersebut dilepaskan seluruhnya. Akan tampak kain tersebut telah berwarna sesuai
dengan warna yang diinginkan.
5. Dicuci dan Dikeringkan
Selanjutnya kain yang sudah selesai diberi warna dan cairan pengawet itu
dicuci dengan sabun dan dikeringkan. Mengeringkan kain tersebut dengan cara
digelar (dijemur) di tempat teduh dan tidak terkena cahaya matahari.

6. Disetrika
Setelah kain tersebut benar-benar telah kering, selanjutnya disetrika agar kain
itu menjadi licin. Jadilah selembar kain sasirangan khas banjar.
2.4 Bahan Pencemar pada Industri Kain Sasirangan
Pencemaran yang ditimbulkan industri karena ada limbah keluar mengandung
bahan beracun dan berbahaya. Bahan pencemar keluar bersama bahan buangan
melalui media udara, air dan bahan padatan. Bahan buangan yang keluar dari pabrik
masuk dalam lingkungan dapat diidentifikasi sebagai sumber pencemar. Sebagai
sumber pencemar perlu diketahui jenis bahan pencemar yang keluar, jumlah dan
jangkauannya. Antara industri satu dengan yang lain berbeda jenis, dan jumlahnya
tergantung pada penggunaan bahan baku, sistem proses, dan cara kerja karyawan
dalam industri.

Pencemaran terjadi akibat bahan beracun dan berbahaya dalam limbah lepas
masuk lingkungan hingga terjadi perubahan kualitas lingkungan. Sumber bahan
beracun dan berbahaya dapat diklasifikasikan:
1. Industri kimia organik maupun anorganik,
2. Penggunaan bahan beracun dan berbahaya sebagai bahan baku atau bahan
penolong dan
3. Peristiwa kimia, fisika, dan biologi dalam industri.
Limbah tersebut bisa berasal dari zat warna tekstil yang dipakai atau sisa zat
warna yang tidak terpakai, zat – zat pembantu, zat yang digunakan saat proses
preparasi dan limbah saat proses pencucian alat. Bila air limbah tersebut di tampung,
maka rata-rata akan mengandung 750 mg/l padatan tersuspensi dan 500 mg/l BOD.
Perbandingan COD : BOD adalah dalam kisaran 1,5 : 1 sampai 3 : 1.
Salah satu kandungan limbah industri yang dapat menimbulkan
dampak negatif adalah logam berat seperti timbal, tembaga, krom, cadmium, raksa
dan arsen. Kasus keracunan krom secara incidental cukup berbahaya bagi manusia,
yakni mengakibatkan kanker paru-paru, luka bernanah kronis dan merusak selaput
tipis hidung. Sumber pencemaran krom dilingkungan dapat dilacak dari air buangan
industri-industri pabrik tekstil. Sasirangan merupakan kain khas Kalimantan Selatan
yang dihasilkan dari pewarnaan tekstil secara jumput. Limbah cair pewarna industri
kain sasirangan yang mengandung logam berat krom, kebanyakan dibuang
ke perairan yang ada disekitarnya, yang merupakan lahan gambut.
Air gambut sebagai salah satu jenis air yang ada di Kalimantan Selatan yang
secara alamiah mengandung C-organik dan kebanyakan dikonsumsi masyarakat yang
ada disekitarnya.
Karakteristik air limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Karakteristik Fisika
Karakteristik fisika ini terdiri dari beberapa parameter, diantaranya
a) Total Solid (TS)
Merupakan padatan didalam air yang terdiri dari bahan organik
maupunanorganik yang larut, mengendap, atau tersuspensi dalam air.
b) Total Suspended Solid (TSS)
Merupakan jumlah berat dalam mg/l kering lumpur yang ada didalam
air limbah setelah mengalami penyaringan dengan membrane berukuran
0,45mikron.
c) Warna
Pada dasarnya air bersih tidak berwarna, tetapi seiring dengan waktu dan
menigkatnya kondisi anaerob, warna limbah berubah dari yang abu-abu
menjadi kehitaman.
d) Kekeruhan
Kekeruhan disebabkan oleh zat padat tersuspensi, baik yang bersifat
organik maupun anorganik.
e) Temperatur
Merupakan parameter yang sangat penting dikarenakan efeknya terhadap
reaksi kimia, laju reaksi, kehidupan organisme air dan penggunaan air
untuk berbagai aktivitas sehari ± hari.
f) Bau
Disebabkan oleh udara yang dihasilkan pada proses dekomposisi materi
atau penambahan substansi pada limbah. Pengendalian bau sangat penting
karenaterkait dengan masalah estetika.
2. Karateristik Kimia
a) Biological Oxygen Demand(BOD)

Menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup
untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air.
b) Chemical Oxygen Demand(COD)
Merupakan jumlah kebutuhan oksigen dalam air untuk proses reaksi secara
kimia guna menguraikan unsur pencemar yang ada. COD dinyatakan
dalam ppm ( part per milion) atau ml O2/ liter.
c) Dissolved Oxygen(DO)
Adalah kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk respirasi aerob
mikroorganisme. DO di dalam air sangat tergantung pada temperature dan
salinitas.
d) Ammonia (NH3)
Ammonia adalah penyebab iritasi dan korosi, meningkatkan pertumbuhan
mikroorganisme dan mengganggu proses desinfeksi dengan chlor. Ammonia
terdapat dalam larutan dan dapat berupa senyawa ion ammonium atau
ammonia tergantung pada pH larutan.
e) Sulfida
Sulfat direduksi menjadi sulfida dalam sludge digester dan dapat
mengganggu proses pengolahan limbah secara biologi jika konsentrasinya
melebihi 200mg/L. Gas H2S bersifat korosif terhadap pipa dan dapat merusak
mesin.
f) Fenol
Fenol mudah masuk lewat kulit. Keracunan kronis menimbulkan gejalagastero
intestinal, sulit menelan, dan hipersalivasi, kerusakan ginjal dan hati,serta
dapat menimbulkan kematian.
g) Derajat keasaman( pH)
pH dapat mempengaruhi kehidupan biologi dalam air. Bila terlalu rendah atau
terlalu tinggi dapat mematikan kehidupan mikroorganisme.Ph normal
untuk kehidupan air adalah 6-8.

h) Logam Berat
Logam berat bila konsentrasinya berlebih dapat bersifat toksik sehingga
diperlukan pengukuran dan pengolahan limbah yang mengandung
logam berat.
3. Karakteristik Biologi
Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air
yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih.Parameter yang biasa
digunakan adalah banyaknya mikroorganisme yang terkandung dalam air limbah.
2.5 Dampak Limbah Kain Sasirangan
Industri tekstil termasuk industri kain sasirangan dapat dijuluki sebagai
penghasil utama limbah cair, hal ini disebabkan dari proses penyempurnaan tekstil
yang memang selalu menggunakan air sebagai bahan pembantu utama dalam setiap
tahapan prosesnya.
Pencemaran air dari industri kain sasirangan dapat berasal dari : buangan air
proses produksi, buangan bahan-bahan kimia sisa proses produksi, sampah potongan
kain dan lainnya. Pencemaran itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai,
dapat merubah warna, bau bahkan mengakibatkan matinya makhluk-makhluk air
yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Timbulnya warna itu dikarenakan sisa-sisa zat warna yang tidak terpakai dan
kotoran-kotoran yang berasal dari sutera alam. Disamping dapat mengganggu
keindahan, mungkin juga dapat bersifat racun, serta biasanya sukar dihancurkan.
Genangan air yang berwarna, banyak menyerap oksigen dalam air, sehingga dalam
waktu lama akan membuat air berwarna hitam dan berbau.
Bau dari air buangan menandakan adanya pelepasan gas yang berbau seperti
hidrogen sulfida. Gas ini timbul dari hasil penguraian zat organik yang mengandung
belerang atau senyawa sulfat dalam kondisi kekurangan oksigen. Suhu air buangan

biasanya lebih tinggi dari suhu air tempat pembuangannya. Pada suhu yang lebih
tinggi kandungan oksigen dalam air berkurang sehingga memungkinkan tumbuhnya
tanaman-tanaman air yang tidak diinginkan.
Pada industri “Zahra Sasirangan”, limbah yang dihasilkan yaitu berupa limbah
cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah cairnya yaitu berupa sisa buangan zat
pewarna, limbah gasnya berupa aroma dari zat pewarna yang dipakai, sedangkan
limbah padat yang dihasilkan yaitu dari benang-benang sisa bekas jahitan/jelujur serta
sisa dari potongan-potongan kain.
Limbah cair dari industri tersebut dibuang ke sungai tanpa melalui proses
pengolahan terlebih dahulu, yang mana limbah tersebut mengandung zat-zat kimia
berbahaya dari pewarna tekstil. Sedangkan aroma yang dihasilkan dari zat pewarna
tersebut sangat menyengat sehingga mengganggu masyarakat sekitar.
Masyarakat sekitar merasa terganggu akibat adanya limbah dari produksi kain
sasirangan tersebut. Terutama dengan air limbah yang dibuang langsung ke sungai
yang dapat mencemari perairan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan kesimpulan dari
Analisis Pengujian Logam Berat di Perairan. Pemerintah Kota Banjarmasin
menjelaskan bahwa Sungai martapura di Banjarmasin telah terdapat kadar
pencemaran airnya yang berasal dari limbah zat pewarna sasirangan, limbah cuci
foto, dan limbah dari radiologi rumah sakit. Seperti yang kita tahu Banjarmasin
adalah kota seribu sungai, sangat sayang sekali apabila sungai-sungainya tercemar
diakibatkan oleh hal itu.
Pada beberapa Negara maju, termasuk di Indonesia telah ada peraturan
pemerintah yang mengatur tentang baku mutu bahan buangan yang diizinkan untuk
dibuang langsung ke dalam lingkungan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka
industri tekstil termasuk industri kain sasirangan boleh membuang limbah cairnya
langsung ke lingkungan dengan ketentuan bahwa kandungan bahan kimia atau bahan

lainnya dalam air buangannya tidak melebihi konsentrasi yang telah ditetapkan atau
dengan kata lain memenuhi persyaratan.
2.6 Teknik pengolahan limbah dan penanganannya
Untuk mencegah terjadinya pencemaran yang diakibatkan pembuangan
limbah kain sasirangan sembarangan ada beberapa teknik pengolahan limbah yang
dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.
1. Dengan menggunakan zat pewarna alami
Menggunakan zat pewana alami memang memerlukan waktu dalam
pengolahannya, tetapi dengan zat pewarna alami, tidak akan mengganggu
kesehatan para pengrajin dan lingkungan sekitarnya.
2. Dengan melakukan pengolahan limbah
Ada 3 tahap dalam pengolahan limbah yaitu :
a. Pembentukan Inti Endapan
Pada tahap ini diperlukan zat koagulan yang berfungsi untuk penggabungan
antara koagulan dengan polutan yang ada dalam air limbah. Agar
penggabungan dapat berlangsung diperlukan pengadukan dan pengaturan pH
limbah. Pengadukan dilakukan pada kecepatan 60 s/d 100 rpm selama 1 s/d 3
menit, pengaturan pH tergantung dari jenis koagulan yang digunakan,
misalnya untuk :
Alum pH 6 s/d 8
Fero Sulfat pH 8 s/d 11
Feri Sulfat pH 5 s/d 9
PAC pH 6 s/d 9
b. Tahap Flokulasi
Pada tahap ini terjadi penggabungan inti-inti endapan sehingga menjadi
molekul yang lebih besar, pada tahap ini dilakukan pengadukan lambat

dengan kecepatan 40 s/d 50 rpm selama 15 s/d 30 menit. Untuk mempercepat
terbentuknya flok dapat ditambahkan flokulan misalnya polielektrolit.
Polielektrolit digunakan secara luas, baik untuk pengolahan air proses maupun
untuk pengolahan air limbah industri. Polielektrolit dapat dibagi menjadi tiga
jenis yaitu non ionik, kationik dan anionik; biasanya bersifat larut air. Sifat
yang menguntungkan dari penggunaan polielektrolit adalah : volume lumpur
yang terbentuk relatif lebih kecil, mempunyai kemampuan untuk
menghilangkan warna, dan efisien untuk proses pemisahan air dari lumpur
(dewatering).
c. Tahap Pemisahan Flok dengan Cairan
Flok yang terbentuk selanjutnya harus dipisahkan dengan cairannya, yaitu
dengan cara pengendapan atau pengapungan. Bila flok yang terbentuk
dipisahkan dengan cara pengendapan, maka dapat digunakan alat klarifier,
sedangkan bila flok yang terjadi diapungkan dengan menggunakan gelembung
udara, maka flok dapat diambil dengan menggunakan skimmer.
Gambar diagram air proses koagulasi dengan pengendapan adalah sebagai
berikut.
Klarifier berfungsi sebagai tempat pemisahan flok dari cairannya. Dalam
klarifier diharapkan lumpur benar-benar dapat diendapkan sehingga tidak
terbawa oleh aliran air limbah yang keluar dari klarifier, untuk itu diperlukan

perencanaan pembuatan klarifier yang akurat. Kedalaman klarifier
dipengaruhi oleh diameter klarifier yang bersangkutan. Misalkan dibuat
klarifier dengan diameter lebih kecil dari 12 m, diperlukan kedalaman air
dalam klarifirer minimal sebesar 3,0 m dan disarankan.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan