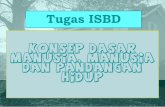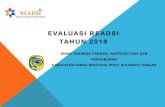Isbd Fix Tugas Klp Bab 3
-
Upload
agus-hendra-jaya -
Category
Documents
-
view
31 -
download
5
Transcript of Isbd Fix Tugas Klp Bab 3

I. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL
A. Manusia sebagai makhluk individu
Kata individu merupakan sebutan yang dipakai untuk menyatakan satu
kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia secara
keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu
perseorangan manusia.
Manusia sebagai makhluk individual bermakna tidak terbagi atau tidak
terpisahkan antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk
individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi pribadi
yang khas dengan corak kepribadiannya, termasuk kemampuan kecakapannya.
Manusia sebagai makhluk individu berbeda dengan manusia lain dan sebgai pribadi
yang khas yang berupaya menggali potensi dirinya.
Kata individu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata in artinya tidak, serta
divided yang berarti terbagi. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu individum, yang
artinya tidak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang
makna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raganya. Dalam
perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan
antara jiwa dan raga,tetapi akan menjadi hal yang khas dengan corak kepribadiannya.
Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :
a. Pandangan nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar
faktor individu itu sendiri.
b. Pandangan empiristik yang menyatakan bahwa pertumbuhan didasarkan atas
faktor lingkungan.
c. Pandangan konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan dipengaruhi atas
dasar individu dan lingkungannya
B. Manusia sebagai Makhluk Sosial
Sebagai makhluk individu manusia juga tidak mampu hidup sendiri artinya
manusia juga harus hidup bermasyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu
bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat
dalam naluri manusia, misalnya :

1. Hasrat untuk memenuhi keperluan makanan dan minuman.
2. Hasrat untuk membela diri.
3. Hasrat untuk mengadakan keturunan.
Hal ini dinyatakan semenjak manusia lahir yang dinyatakan untuk mempunyai
dua keinginan pokok, yaitu :
1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia disekelilingnya.
2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam disekitarnya.
C. Peranan Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial
1. Peranan manusia sebagai makhluk individu
Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai individu, yang dapat
diketahui bahwa manusia memilki harkat dan martabat yang mempunyai hak-hak
dasar,dimana setiap manusia memiliki potensi diri yang khas,dan setiap
manusiamemiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dirinya.
Sebagai makhluk individu manusia berperan untuk mewujudkan hal-
hal sebagai berikut :
1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya.
2. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia.
3. Merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani.
4. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya.
2. Peranan manusia sebagai makhluk sosial
Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Artinya manusia
akan selalu berhubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia
terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah
laku manusia dalam kelompok. Norma-norma yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
1. Norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umat-
Nya.

2. Norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani
manusia untuk mengajarkan kebaikan.
3. Norma kesopanan atau adat, yaitu norma yang bersumber dari masyarakat atau
dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
4. Norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang
pelaksanaannya dapat dipaksakan.
Berdasarkan hal diatas, maka manusia sebagai makhluk sosial memiliki
implikasi-implikasi sebagai berikut :
1. Kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri.
2. Kesadaran untuk senatiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain.
3. Penghargaan atas hak-hak orang lain.
4. Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku.
Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan
peran-peran sebagai berikut :
1. Melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok.
2. Membentuk kelompok-kelompok sosial.
3. Menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan
kelompok tersebut.
D. Korelasinya terhadap Budaya Daerah di Indonesia
1. Budaya Bali
a) Megibung
Megibung adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
atau sebagian orang untuk duduk bersama saling berbagi satu sama lain, terutama
dalam hal makanan. Tidak hanya perut kenyang yang didapat dari kegiatan ini namun
sembari makan kita dapat bertukar pikiran bahkan bersenda gurau satu sama lain.
Megibung bersasal dari kata dasar gibung yang mendapat awalan me-. Gibung
berarti kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yaitu saling berbagi antara orang
yang satu dengan yang lainnya, sedangkan awalan me- berarti melakukan suatu
kegiatan. Saat ini kegiatan megibung kerap kali dapat dijumpai pada saat prosesi

berlangsungnya upacara adat dan keagamaan seperti misalnya dalam upacara Dewa
Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya, Rsi Yadnya dan Manusa Yadnya. Pada
kegiatan ini biasanya yang punya acara memberikan undangan kepada kerabat serta
sanak saudaranya guna menyaksikan prosesi kegiatan upacara keagamaan tersebut.
Sehingga prosesi upacara dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Proses
penyembelihan babi pun dilakukan sebagai salah satu menu di dalam mempersiapkan
hidangan yang disebut Gibungan ini. Daging babi diolah sedemikian rupa dan di kasi
bumbu tertentu sehingga daging yang mentah menjadi menu pelengkap yang
menggugah selera seperti sate, lawar, sup (komoh), Gegubah/lempyong, pepesan serta
yang lainnya. Menu yang dihidangkan dalam Megibung tidaklah harus daging babi,
namun daging ayam, kambing serta daging sapipun tidaklah masalah.
Dalam Megibung biasanya terdiri dari lima hingga tujuh orang, yang
dilakukan dengan duduk bersama membentuk lingkaran. Adapun ciri khas dari
megibung ini adalah :
Duduk bersila membentuk lingkaran yang terdiri dari 5-7 orang.
Nasi yang disuguhkan ditaruh dalam satu wadah (nare besar).
Lauk atau pelengkap nasi berupa sate, lawar, soup, gegubah/lempyong,
pepesan yang ditempatkan dalam satu wadah (nare kecil).
Kegiatan makan dilakukan secara bersamaan dan makan menggunakan
tangan.
Pada saat makan tidak boleh ada yang terjatuh di wadah/tempat nasi namun
harus di luar nare tempat nasi tersebut.
Apabila ada salah seorang peserta megibung ada yang terlebih dahulu
kenyang, orang tersebut tidak boleh terlebih dahulu bangun atau meninggalkan
tempat megibung namun harus menunggu yang lain selesai makan dan bangun
secara bersama-sama.
Kegiatan megibung ini merupakan salah satu contoh kebudayaan yang
menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial karena kegiatan ini menunjukkan
makna sangatlah besar bagi kita semua terutama dalam hal kebersamaan serta saling
berbagi satu sama lain tanpa melihat kasta dan materi yang dimiliki seseorang.
Kegiatan megibung ini menunjukkan adanya interaksi sosial yang setara antar
masyarakat di Bali, hal ini terlihat jelas dengan tidak adanya perbedaan status sosial
yang memperngaruhi posisi maupun menu makanan yang di dapatkan saat acara

tersebut. Cengkrama serta diskusi yang terjadi selama kegiatan ini juga menunjukkan
terjadi suatu interaksi sosial yang dinamis.
b) Nguopin
Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam
komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas. Gotong-royong terjadi dalam
beberapa aktivitas kehidupan, seperti gotong-royong dalam bentuk kerja bakti,
dilakukan untuk kepentingan bersama; gotong-royong dalam bentuk tolong menolong
pada saat melakukan pesta pernikahan, atau khitanan, beberapa hari sebelum pesta
akan dilakukan terjadi sumbangan dari kenalan, tetangga ataupun kerabat datang
membantu dalam bentuk bahan makanan, uang, ataupun tenaga, kemudian bantuan ini
harus dikembalikan minimal dengan nilai yang sama. Bahkan gotong-royong dapat
pula terjadi pada saat adanya musibah ataupun kematian salah seorang warga
komunitas, hal ini tidak dapat disebut kepentingan bersama ataupun kepentingan
peribadi tetapi rasa kemanusiaan yang muncul di antara warga, karena musibah
datangnya tidak diperhitungkan ataupun diketahui, sehingga warga yang mendapat
musibah tersebut memerlukan bantuan dari warga lainnya.
Dalam kehidupan berkomuniti dalam masyarakat Bali dikenal sistem gotong
royong (nguopin) yang meliputi aktivitas di sawah (seperti menanam, menyiangi,
panen dan sebagainya), sekitar rumah tangga (memperbaiki atap rumah, dinding
rumah, menggali sumur dan sebagainaya), dalam perayaan-perayaan atau upacara-
upacara yang diadakan oleh suatu keluarga, atau dalam peristiwa kecelakaan dan
kematian. nguopin antara individu biasanya dilandasi oleh pengertian bahwa bantuan
tenaga yang diberikan wajib dibalas dengan bantuan tenaga juga. kecuali nguopin
masih ada acara gotong royong antara sekaha dengan sekaha. Cara serupa ini disebut
ngedeng (menarik). Misalnya suatu perkumpulan gamelan ditarik untuk ikut serta
dalam menyelenggarakan suatu tarian dalam rangka suatu upacara odalan. bentuk
yang terakhir adalah kerja bhakti (ngayah) untuk keperluan agama, masyarakat
maupun pemerintah
Dalam budaya Bali, gotong royong dikenal dengan istilah nguopin. Nguopin
merupakan kegiatan yang kerap dilakukan masyarakat untuk membantu anggota
masyarakat lainnya yang akan mengadakan upacara adat seperti pernikahan,

kematian, maupun upacara lainnya. Nguopin biasa dilakukan dalam bentuk kegiatan
bersih-bersih, membuat banten (sesajen), maupun menyiapkan makanan bagi orang-
orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Biasanya kaum laki-laki melakukan
nguopin berupa memotong hewan yang akan digunakan sebagai sarana upacara
maupun mempersiapkan peralatan seperti bambu, kayu, maupun dekorasi. Sedangkan
para wanita nguopin dengan mejejaitan (membuat banten) maupun memasak untuk
keluarga dan tamu yang hadir.
c) Sistem Kekerabatan keluarga Bali
Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang
kepada prinsip sistem klen-klen (dadia) dan sistem kasta (wangsa). Perkawinan
merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena pada
saat itulah ia dapat dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru sesudah
itu ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seorang warga dan warga kelompok
kerabat. Maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-klen, atau
setidak-tidaknya antara orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Orang-orang yang
masih satu kelas (tunggal kawitan, tunggal dadia dan tunggal sanggah) sama-sama
tinggi tingkatannya. Dalam perkawinan klen dan kasta ini yang paling ideal adalah
antara pasangan dari anak dua orang laki-laki bersaudara.
d) Tingkat kedudukan
Orang orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan
demikian juga dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk kawin dalam batas
klennya, terjagalah kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dan noda-noda
keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar kasta yang berbeda derajatnya.
Dalam hal ini terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta yang tinggi jangan
sampai kawin dengan pria yang lebih rendah derajat kastanya, karena perkawinan itu
akan membawa malu kepada keluarga, serta menjatuhkan gengsi dari seluruh kasta
dari anak wanita tersebut.
e) Kasta

Masyarakat Bali Hindu terbagi ke dalam pelapisan sosial yang dipengaruhi
oleh tiga sistem nilai, yaitu utama, madya dan nista. Kasta utama atau tertinggi adalah
golongan Brahmana, kasta Madya adalah golongan Ksatrya dan kasta nista adalah
golongan Waisya. Selain itu masih ada golongan yang dianggap paling rendah atau
tidak berkasta yaitu golongan Sudra, sering juga mereka disebut Jaba Wangsa (tidak
berkasta). Dari kekuatan sosial kekerabatannya dapat pula dibedakan atas klen Pande,
Pasek, Bujangga dan sebagainya. Sistem Penamaan Keluarga Bali: Sistem penamaan
keluarga Bali didasarkan pada kasta: Brahmana : Ida Bagus (Laki-Laki), Ida Ayu
(Wanita). Ksatria : Anak Agung, Waisya : Gusti Bagus (Laki – Laki), Gusti Ayu
(Wanita). Sudra : Wayan (Anak Pertama), Made (Anak Kedua), Nyoman (Anak
Ketiga), Ketut (Anak Keempat).
f) Sistem Sosial Budaya Masyarakat Bali
Kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sehari-hari hampir smuanya
dipengaruhi oleh keyakinan mereka kepada agama Hindu Dharma yang mereka anut.
Oleh karena itu studi tentang masyarakat dan kebudayaan Bali tidak bisa dilepaskan
dari pengaruh sistem religi Hindu. Agama Hindu Dharma atau Hindu Jawa yang
mereka anut mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep Tri Murti, yaitu
Tuhan yang mempunyai tiga wujud, yaitu Brahma (Pencipta), Wisnu (Pelindung) dan
Siwa (Pelebur Segala yang Ada). Semuanya perlu di hormati dengan mengadakan
upacara dan sesajian. Mereka juga mengangap penting konsepsi tentang Roh abadi
yang disebut Atman, adanya buah setiap perbuatan (Karma Phala), kelahiran kembali
sang jiwa (Punarbawa) dan kebebasan jiwa dari kelahiran kembali (Moksa). Dalam
menyelenggarakan pemakaman anggota keluarga orang Bali selalu melaksanakan tiga
tahapan upacara kematian. Pertama, upacara pembakaran mayat (ngaben), kedua,
upacara penyucian (nyekah) dan ketiga, upacara ngelinggihang. Ajaran-ajaran di
agama Hindu Dharma itu termaktub dalam kitab suci yang disebut Weda.
g) Sistem Kemasyarakatan
Sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan
atas kesatuan wilayah/teritorial administrasi (perbekelan/kelurahan) yang pada
umumnya terpecah lagi menjadi kesatuan sosial yang lebih kecil yaitu banjar &

teritorial adat. Banjar mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan, adat & masyarakat
lainnya. Dari sistem kemasyarakatan yang ada ini maka warga desa bisa masuk
menjadi dua keanggotaan warga desa, yaitu: sistem pemerintahan Desa Dinas sebagai
wilayah administratif. Dari kehidupan masyarakat setempat terdapat pula kelompok-
kelompok adat. Sistem kemasyarakatan di Bali adalah sebagai berikut : 1). Banjar
merupakan bentuk kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah.
Kesatuan sosial itu diperkuat oleh ksatuan adat & upacara-upacara keagaman. Di
daerah pegunungan, sifat keanggotaan banjar hanya terbatas pada orang yang lahir di
wilayah banjar tersebut. Sedangkan di daerah dataran, sifat keanggotaannya tidak
tertutup & terbatas kepada orang-orang asli yang lahir di banjar itu.
h) Subak
Subak di Bali seolah-olah lepas dari Banjar dan mempunyai kepala sendiri.
Orang yg menjadi warga subak tidak semuanya sama dengan orang yang menjadi
anggota banjar. Warga subak adalah pemilik/para penggarap sawah yang menerima
air irigasinya dari bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu subak. Sekeha dalam
kehidupan kemasyarakatan di Bali, ada organisasi-organisasi yang bergerak dalam
lapangan kehidupan yang khusus, ialah sekeha. Organisasi ini bersifat turun-temurun,
tapi ada pula yg bersifat sementara. Ada sekeha yang fungsinya adalah
menyelenggarakan upacara yang berkenaan dengan desa, misalnya sekeha baris
(perkumpulan tari baris), sekaha teruna-teruni. Sekaha tersebut sifatnya permanen,
tapi ada juga sekeha yang sifatnya sementara, yaitu sekaha yang didirikan berdasarkan
atas suatu kebutuhan tertentu, misalnya sekeha memula (perkumpulan menanam),
sekeha manyi (perkumpulan menuai), sekeha gong (perkumpulan gamelan) dll.
Sumber : Tradisi Megibung dari Karangasem: Kiriman I Gede Suwidnya, Mahasiswa PS Seni
Karawitan.
Bintarto, R. 1980. Gotong-Royong : Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia. Surabaya
: PT. Bina Ilmu.
Koentjaraningrat. 1983. Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia.
dalam Sajogyo dan Sajogyo, Pudjiwati. Sosiologi Pedesaan. Jilid 1. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.

http://www.slideshare.net/mayasungeb/sistem-kekerabatan-bali diakses tanggal 15
Oktober 2012.
Maya Sungeb, Meilina K. Ayu, Miftakul Prasetya, K M. Fahim R, 2011. Keluarga
Bali. Bali: Presentation Transcript.
2. Budaya Sumatera Barat
Salah satu budaya atau suku yang terdapat di Sumatera Barat adalah
Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal.
Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu
masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang
anak laki-laki atau perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat
memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem
patrilineal. Dengan kata lain seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku
ibunya. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. Tidak ada sanksi
hukum yang jelas mengenai keberadaan sistem matrilineal ini, artinya tidak ada sanksi
hukum yang mengikat bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap sistem ini.
Sistem ini hanya diajarkan secara turun temurun kemudian disepakati dan dipatuhi,
tidak ada buku rujukan atau kitab undang-undangnya. Namun demikian, sejauh
manapun sebuah penafsiran dilakukan atasnya, pada hakekatnya tetap dan tidak
beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri.
Peran dan kedudukan Perempuan
Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau
memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga,
melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah
pusaka dan sawah ladang. Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai
pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adatnya
amban puruak atau tempat penyimpanan. Itulah sebabnya dalam penentuan peraturan
dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikut sertakan. Perempuan menerima
bersih tentang hak dan kewajiban di dalam adat yang telah diputuskan sebelumnya
oleh pihak ninik mamak. Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus
melalui sebuah prosedur apalagi bantahan.
Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin

keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka
menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan
mempertahankannya. Perempuan tidak perlu berperan aktif seperti ninik mamak.
Perempuan minangkabau yang memahami konstelasi seperti ini tidak memerlukan
lagi atau menuntut lagi suatu prosedur lain atas hak-haknya. Mereka tidak
memerlukan emansipasi lagi, mereka tidak perlu dengan perjuangan gender, karena
sistem matrilineal telah menyediakan apa yang sesungguhnya diperlukan perempuan.
Peran dan Kedudukan Laki-laki
Kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam adat Minangkabau berada dalam
posisi seimbang. Laki-laki punya hak untuk mengatur segala yang ada di dalam
perkauman, baik pengaturan pemakaian maupun pembagian harta pusaka. Perempuan
sebagai pemilik dapat mempergunakan semua hasil itu untuk keperluannya anak
beranak. Peranan laki-laki di dalam dan di luar kaumnya menjadi sesuatu yang harus
dijalankannya dengan seimbang dan sejalan. Sebagai rentetan dari hasil perkawinan
menimbulkan tali kerabat – tali kerabat antara keluarga istri dengan keluarga rumah
gadang suami dan sebaliknya. Tali kerabat itu seperti tali induak bako anak pisang,
tali kerabat sumando dan pasumandan, tali kerabat ipar, bisan dan menantu.
1. Tali kerabat induak bako anak pisang, yaitu hubungan kekerabatan antara
seseorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan
seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Saudara-saudara
perempuan dari seorang bapak, adalah induak bako dari anak-anaknya.
Sedangkan anak-anak dari seorang bapak merupakan anak pisang dari saudara-
saudara perempuan bapaknya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara
perempuan bapak adalah “bakonya”.
2. Tali kekerabatan sumando dan pasumandan. Dengan adanya perkawinan maka
terjadi hubungan sumando pasumandan. Bagi seluruh anggota rumah gadang istri,
suaminya, menjadi urang sumando (orang semenda) seseorang istri bagi keluarga
suaminya menjadi pasumandan.
3. Sumando berasal dari bahsa sansekerta yaitu “sandra”, sedangkan dalam bahasa
Minangkabau menjadi “sando” dengan sisipan “um” menjadi sumando.
Persamaan kata sando adalah gadai. Dalam kehidupan sehari-hari ada istilah
pagang gadai. Bagi pihak yang menerima jaminan berupa benda harta yang

digadaikan disebut sando, sedangkan orang yang memberikan hartanya sebagai
jaminan dikatakan menggadaikan. Demikianlah sebagai penerima dari keluarga
perempuan terhadap seorang menjadi suami anak kemenakannya dikatakan
sebagai sumando. Namun demikian jangan lah diartikan secara negatif seperti
terjadinya pegang gadai dalam kehidupan sehari-hari.
4. Seorang istri yang menjadi pasumandan dari anggota rumah gadang suaminya di
aberperan sebagai komunikator antara suaminya dengan tungganai dan mamak
rumah gadangnya. Sedang untuk mengkomunikasikan kepentingan sendiri
sebagai istri, biasanya melalui saudara-saudara perempuan suami.
5. Tali kekerabat ipar, bisan dan menantu. Bagi seorang suami, saudara-saudara
perempuan istrinya menjadi bisannya. Sedangkan saudara-saudara laki-laki dari
istrinya adalah menjadi iparnya. Sebaliknya, saudara-saudara perempuan
suaminya adalah merupakan bisannya, dan saudara laki-laki suaminya menjadi
iparnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau menyebut ipar, bisan
ini “ipa bisan” dan kadang-kadang disambung saja jadi “pabisan”
Sumber :
- Safwan, Drs. Mardanas, 2011. Sistim Kekerabatan Matrilineal Dalam Masyarakat
Minangkabau. pakguruonline.pendidikan.net.
- Floresyona, Dita. 2008. Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Asrama Bundo
Kanduang. Yogyakarta.
- http://mersi.wordpress.com/2008/08/14/sistem-kekerabatan-di-minangkabau. Diakses
tanggal 15 Oktober 2012.
- http://palantaminang.wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/f-sistem-kekerabatan.
Diakses tanggal 15 Oktober 2012.
3. Budaya Jawa Timur
Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan serta sifatnya
yang keras dan mudah tersinggung, tetapi mereka juga dikenal hemat, disiplin dan
rajin bekerja. Untuk naik haji, orang Madura sekalipun miskin pasti menyisihkan
sedikit penghasilannya. Prof. Dr. Deliar Noer menyebutkan bahwa Madura
adalah benteng Islam di Indonesia sebab kekentalan agamis masyarakat
dan akar paham yang sangat kuat sekalipun kadang melakukan ritual Petik

Laut atau Rokat Tasse (sama dengan Larung Sesaji). Jadi tidak perlu heran jika Aceh
dikenal sebagai serambi Mekkah, maka Madura adalah serambi Madinah-nya. Tak
banyak daerah yang mendapat kehormatan dilekati label istimewa ini. Dari kedua
atribut tersebut dengan mudah terlihat posisi dan kultur yang khas, yakni
kelekatannya dengan tradisi keislaman, bahkan menurut Rasul Junaidy suku Madura
memiliki tiga nilai yang sangat menjadi acuan berpikir dan bertindak, ketiga
nilaitersebut di tuangkan kedalam unsur – unsur prilaku kehidupan sehari – hari yaitu:
- Kesopanan
Walau orang di luar Madura menilai mereka sangat kasar, namun
penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan sangat tinggi sekali. Betapa
pentingnya nilai kesopanan ini nampak dari ungkapan ta'tao batona langgar (tidak
pernah merasakan lantainya langgar). Maksudnya, orang tersebut belum pernah
masuk langgar dan mengaji atau belum pernah mondok, sehingga tidak tahu tata
krama kesopanan. Ungkapan ini untuk orang yang tidak tahu atau melanggar
nilai-nilai kesopanan. Ungkapan lain yang memberikan nasihat danajaran
tentang keharusan bersopan santun adalah pa tao ajalan jalana jalane, pa
taon eng ngenneng, pa tai a ca ca (yang menjadi kewajiban harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan. Harus tahu saatnya diam, harus tahu saatnya
berbicara). Hal ini bermakna bahwa orang Madura harus selalu tahu aturan,
nilai dan tatakrama dalam setiaptindakannyaSelain itu, setiap kewajiban harus
dilaksanakan dengan mendasarkan pada aturan-aturan tata krama yang ada.
Orang dan masyarakat Madura selalu menekankan bahwa mon oreng riya
benni bagusse, tape tata kramana, sanajjan bagus tapi tata kramana jube', yang
terpenting bukan ketampanan atau kecantikan, namun tata kramanya. Dasar utama
dari nilai-nilai kesopanan adalah penghormatan orang Madura kepada orang lain,
terutama yang lebih tua. Nilai-nilai kesopanan ini mengatur hubungan antargenerasi,
kelamin, pangkat dan posisi sosial.
- Kehormatan
Masyarakat Madura sangat mengutamakan penghormatan dan penghargaan,
apalagi kepada yang lebih tua atau yang mempunyai kedudukan sosial yang lebih
tinggi, sehingga menjadikan nilai-nilai kesopanan menjadi sangat penting sekali
dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Madura tidak mau
diremehkan, namun demikian penonjolan diri juga tidak dihargai.
contohnya ungkapan madu ben de re (madu dan darah), yang berarti bila

orang Madura diperlakukan secara baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan
dan penghormatan, maka balasannya adalah kebaikan pula. Sebaliknya,bila
ia diperlakukan secara sewenang-wenang dan tidak adil, maka balasannya jauh lebih
berat bahkan dapat menimbulkan pertumpahan darah. Hubungan sosial
masyarakat Madura selalu saling menghormati dan menghargai s eba ga i
s e sa ma man us i a dan men j ag a un t uk t i d ak s a l i ng menyak i t i . Ha l i n i
s anga t nampak dari ajaran ja'nobi' oreng mon aba'na e tobi' sake (janganlah
menyakiti orang lain, kalau diri sendiri merasa sakit jika disakiti orang). Harga diri
atau martabat adalah nilai yang sangat mendasar dalam masyarakat
Madura. Harga diri harus selalu dipertahankan agar tidak diremehkan
orang lain. Dasar utama dari harga diri adalah rasa malu ( r a sa ma lu atau
todus. Orang Madura selalu menekankan bahwa tambana todus mate' (obatnya
malu adalah mati), apotetolang etembang apote mata (lebih baik mati daripada malu
tidak dapat mempertahankan harga diri). Nilai-nilai harga diri bagi masyarakat
Madura selain berkaitan dengan ego, wanita dan agama juga berkait erat dengan
masalah tanah dan air.
Sumber :
- http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/7749. Diakses 15
Oktober 2012.
- http://madib.blog.unair.ac.id/ethnography-of-madura/adaptasi-sosial-ekonomi-
masyarakat-petani-keturunan-madura/. Diakses 15 Oktober 2012.
4. Budaya Sumatra Utara
a. Hubungan Sosial
Nilai kekerabatan masyarakat Batak utamanya terwujud dalam
pelaksanaan adat Dalian Na Talu, dimana seseorang harus mencari jodoh diluar
kelompoknya, orang-orang dalam satu kelompok saling menyebut Sabutuha
(bersaudara), untuk kelompok yang menerima gadis untuk diperistri disebut Hula-
hula. Kelompok yang memberikan gadis disebut Boru.
b. Perkawinan
Pada tradisi suku Batak seseorang hanya bisa menikah dengan orang

Batak yang berbeda klan sehingga jika ada yang menikah dia harus mencari
pasangan hidup dari marga lain selain marganya. Apabila yang menikah adalah
seseorang yang bukan dari suku Batak maka dia harus diadopsi oleh salah satu
marga Batak (berbeda klan). Acara tersebut dilanjutkan dengan prosesi
perkawinan yang dilakukan di gereja karena mayoritas penduduk Batak beragama
Kristen.Untuk mahar perkawinan-saudara mempelai wanita yang sudah menikah.
c. Kekerabatan
Kelompok kekerabatan suku bangsa Batak berdiam di daerah pedesaan
yang disebut Huta atau Kuta menurut istilah Karo. Biasanya satu Huta didiami
oleh keluarga dari satu marga. Ada pula kelompok kerabat yang disebut marga
taneh yaitu kelompok pariteral keturunan pendiri dari Kuta. Marga tersebut
terikat oleh simbol-simbol tertentu misalnya nama marga. Klen kecil tadi
merupakan kerabat patrilineal yang masih berdiam dalam satu kawasan.
Sebaliknya klen besar yang anggotanya sudah banyak hidup tersebar sehingga
tidak saling kenal tetapi mereka dapat mengenali anggotanya melalui nama marga
yang selalu disertakan dibelakang nama kecilnya, Stratifikasi sosial orang Batak
didasarkan pada empat prinsip yaitu perbedaan tigkat umur, perbedaan pangkat
dan jabatan, perbedaan sifat keaslian dan status kawin.
d. Mata Pencaharian
Pada umumnya masyarakat batak bercocok tanam padi di sawah dan
ladang. Lahan didapat dari pembagian yang didasarkan marga. Setiap kelurga
mandapat tanah tadi tetapi tidak boleh menjualnya. Selain tanah ulayat adapun
tanah yang dimiliki perseorangan . Peternakan juga salah satu mata pencaharian
suku batak antara lain perternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek.
Penangkapan ikan dilakukan sebagian penduduk disekitar danau Toba. Sektor
kerajinan juga berkembang. Misalnya tenun, anyaman rotan, ukiran kayu,
tembikar, yang ada kaitannya dengan pariwisata.
Sumber :
- Hidayah, Zuliyani, 1997, Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta:
LP3ES.
- Koentjaraningrat, 1971, Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta:
Djambatan.

- Melalatoa, M. Junus, 1997, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Budaya Kalimantan Selatan
Sistem kekerabatan suku Banjar pada umumnya adalah sama, untuk daerah
seluruh Kalimantan Selatan. Suku Banjar mendasarkan kekerabatan mereka menurut
garis dari keturunan ayah dan garis keturunan ibu atau bilateral. Tetapi di akui bahwa
dalam hal-hal tertentu terutama yang menyangkut masalah kematian, perkawinan
yang menjadi wali asbah adalah garis dari pihak ayah. Dalam hal masalah keluarga
besar dan pengertian keluarga besar, maka berlaku garis keturunan ayah dan garis
keturunan ibu, keduanya diberlakukan sama.
Masyarakat suku Banjar mengenal istilah Bubuhan, yang dimaksud dengan
istilah bubuhan dalam masyarakat Banjar adalah kelompok kekerabatan yang
merupakan kumpulan dari keluarga batih yang merupakan satu kesatuan. Bentuk dari
kelompok bubuhan ini paling sedikit mempunyai lima unsur atau ciri sebagai berikut :
1. Mempunyai suatu sistem norma yang mengatur kelakuan warga kelompok.
2. Mempunyai rasa kepribadian kelompok yang didasari rasa kesadaran oleh semua
warganya.
3. Aktivitas berkumpul warga kelompok bubuhan pada waktu-waktu tertentu.
4. Adanya suatu sistem hak dan interaksi serta kewajiban dari warga bubuhan.
5. Adanya satu orang yang ditokohkan dalam kelompok bubuhan ini.
Bubuhan ini yang menurut pengertian sosiologi adalah keluarga besar, yaitu
yang terdiri dari dua keluarga batih atau lebih yang masih mempunyai hubungan
keturunan satu sama lain, baik menurut garis keturunan ayah atau ibu. Keluarga
bubuhan, yang disebut keluarga besar, tetapi disebut pula keluarga luas. Dari
perkawinan terbentuklah suatu kelompok kekerabatan yang sering disebut keluarga
inti atau keluarga batih. Satu keluarga batih terdiri dari satu suami dan satu istri (atau
lebih). Selama satu tahun tersebut, keluarga batih baru ini diberi kesempatan untuk
mengerjakan sawah atau ladang sendiri dan orang tua istri, mereka selalu membantu
kehidupan keluarga baru ini. Tetapi kalau keluarga baru ini belum mempunyai
kemampuan hidup berpisah dari rumah keluarga istrinya, kecenderungan menetap
dalam keluarga istri ini disebut matrilokal atau uksorilokal. Kalau ikut di keluarga

pihak suami disebut patrilokal. Kalau mereka telah mempunyai kemampuan untuk
hidup sendiri dan berpisah dari orang tua (dari istri atau suami) disebut neolokal.
Sumber :
- http://lizaanggraini.wordpress.com/2009/04/07/sistem-kekerabatan-bubuhan. Diakses
15 Oktober 2012
6. Budaya Papua
Struktur sosial masyarakat Papua, kita harus mulai dengan hubungan sosial,
yaitu cara mereka berinteraksi, hal-hal yang mereka katakan dan lakukan dalam
hubungan mereka satu sama lain. Tetapi terdapat juga gagasan mereka tentang
hubungan mereka, konsepsi masing-masing tentang pihak yang lain, pemahaman dan
strategi serta pengharapan yang menuntun perilaku mereka. Baik pola perilaku
maupun sistem konseptual mempunyai struktur, dalam arti tidak kacau balau atau
sembarangan, tetapi kedua hal tersebut merupakan struktur yang berbeda jenis
(Keesing, 1989 : 2008-209). Pouwer (1966) berdasarkan studi antropologinya,
menunjukan bahwa dalam pengelompokan orang Papua paling sedikit dapat dibagi ke
dalam empat golongan berdasarkan sistem kekerabatan :
1. Kelompok kekerabatan menurut tipe Iroquois. Sistem ini mengklasifikasikan
anggota kerabat saudara sepupu parallel dengan istilah yang sama dengan saudara
kandung. Juga untuk menyebut istilah yang sama untuk ayah maupun sesama
saudara laki-laki ayah dan saudara laki-laki ibu. Adapun kelompok etnik Papua
yang tergolong dalam tipe ini adalah : orang Biak, Iha, Waropen, Senggi, Marind-
anim, Teluk Humboldt dan orang Mee.
2. Kelompok kekerabatan menurut tipe Hawaian. Sistem pengelompokan yang
menggunakan istilah yang sama untuk menyebut saudara-saudara sekandung dan
semua saudara-saudara sepupu silang dan parallel. Adapun kelompok etnik yang
tergolong tipe ini adalah : Orang Hatam-Manikion, Mairsai, Mimika, Asmat dan
Pantai Timur Sarmi.
3. Kelompok kekerabatan menurut tipe Omaha. Sistem ini mengklasifikasikan
saudara-saudara sepupu silang matrilateran dan patrilateral dengan istilah yang
berbeda dan untuk saudara sepupu silang dipengaruhi oleh tingkat generasi dan

bersifat tidak simetris. Sebutan untuk anak laki-laki saudara laki ibu (MBS) adalah
sama dengan saudara laki-laki ibu (MB). Istilah untuk anak laki-laki saudara
perempuan ayah (FZS) adalah sama untuk anak laki-laki saudara perempuan (Z).
Adapun etnik yang tergolong dalam kelompok ini adalah orang Awyu, Dani,
Meibrat, Mek di Pegunungan Bintang dan Muyu.
4. Kelompok kekerabatan menurut tipe Iroquois-Hawaian. Tipe ini adalah tipe
campuran. Kelompok yang tergolong dalam tipe ini adalah Orang Bintuni, Tor dan
Pantai Barat Sarmi.
Kecuali penggolongan berdasarkan istilah kekerabatan, orang Papua juga
dibedakan berdasarkan prinsip pewarisan. Ada dua prinsip pewarisan keturunan
yaitu :
1. Melalui garis keturunan ayah atau patrilineal, dan terdapat pada orang Meibrat,
Mee, Dani, biak, Waropen, Wandamen, Sentani, Marind-anim dan Nimboran.
2. Melalui prinsip bilateral yaitu melalui garis keturunan ayah dan ibu, terdapat pada
orang dipedalaman Sarmi.
3. Masyarakat berdasarkan struktur ambilateral atau ambilineal, dimana kadang-
kadang diatur menurut garis keturunan pihak ibu dan ayah. Terdapat pada orang
Yagai, Manikion, Mimika (De Brijn, 1959 : 11 of van der Leeden, 1945, Pouwer,
1966).
Orang Papua juga mengenal pembagian masyarakat ke dalam phratry atau
moiety yang terbagi atas dua paroh masyarakat. Terdapat pada orang Asmat (aipmu-
aipem), Dani (Waita-Waya), Waropen (buriworai-buriferai) dalam (Mansoben, 1974,
1995; Held, 1947; Kamma, 1972; Schoorl, 1957; Heider, 1979-1980).
Sumber:
- http://www.artpapua.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=65
7. Budaya Sulawesi Selatan
Di daerah Sulawesi Selatan sangat menonjol perasaan kekeluargaan. Hal ini
mungkin didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari

satu rumpun. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan sistem kekerabatan.
Sistem kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut:
a) Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam
bahasa Bugis keluarga ini dikenal dengan istilah Sianang , di Mandar Saruang
Moyang, di Makassar Sipa’anakang/sianakang, sedangkan orang Toraja
menyebutnya Sangrurangan. Keluarga ini biasanya terdiri atas bapak, ibu, anak,
saudara laki-laki bapak atau ibu yang belum kawin.
b) Sepupu. Kekerabatan ini terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah
tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak. Bagi orang Bugis
kekerabatan ini disebut dengan istilah Sompulolo, orang Makassar
mengistilkannya dengan Sipamanakang. Mandar Sangandan Toraja
menyebutkan Sirampaenna. Kekerabatan tersebut biasanya terdiri atas dua
macam, yaitu sepupu dekat dan sepupu jauh. Yang tergolong sepupu dekat
adalah sepupu satu kali sampai dengan sepupu tiga kali, sedangkan yang
termasuk sepupu jauh adalah sepupu empat kali sampai lima kali. Keturunan.
Kekerabatan yang terjadi berdasarkan garis keturunan baik dari garis ayah
maupun garis ibu. Mereka itu biasanya menempati satu kampung. Terkadang
pula terdapat keluarga yang bertempat tinggal di daerah lain. Hal ini bisanya
disebabkan oleh karena mereka telah menjalin hubungan ikatan perkawinan
dengan seseorang yang bermukim di daerah tersebut. Bagi masyarakat Bugis,
kekerabatan ini disebut dengan Siwija orang Mandar Siwija, Makassar
menyebutnya dengan istilah Sibali dan TorajaSangrara Buku.
c) Pertalian sepupu/persambungan keluarga. Kekerabatan ini muncul setelah
adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang
lain. Kedua rumpun keluarga tersebut biasanya tidak memiliki pertalian
keluarga sebelumnya. Keluarga kedua pihak tersebut sudah saling menganggap
keluarga sendiri. Orang-orang Bugis mengistilahkan kekerabatan ini
dengan Siteppang-teppang, Makassar Sikalu-kaluki,
Mandar Sisambungsangana dan Toraja Sirampe-rampeang.
d) Sikampung. Sistem kekerabatan yang terbangun karena bermukim dalamsatu
kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali
tidak ada hubungan darahnya/keluarga. Perasaan akrab dan saling menganggap
saudara/ keluarga muncul karena mereka sama-sama bermukim dalam satu
kampung. Biasanya jika mereka itu kebetulan berada di perantauan, mereka

saling topang-menopang, bantu-membantu dalam segala hal karena mereka
saling menganggap saudara senasib dan sepenaggungan. Orang Bugis menyebut
jenis kekerabatan ini dengan Sikampong, Makassar Sambori, suku Mandar
mengistilahkan Sikkampung dan Toraja menyebutkan Sangbanua.
Karena masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan
pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan
nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang.
Selain itu masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni
bidang pendidikan.
Sumber :
Abd. Kadir Ahmad, 2004, Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tenggara, Makassar, Balai Litbang Agama Makassar.
Mattuladda, 1974. Bugis Makassar, Manusia dan Kebudayaan. Makassar. Berita
Antropologi No. 16 Fakultas Sastra UNHAS.
------------, 1975. Latoa, Suatu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang
Bugis., Makassar: Disertasi.
8. Budaya Jawa Barat
Orang Sunda mengenal pengelompokan status dalam masyarakat berdasarkan
materi. Ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin biasanya bekerja sebagai
petani, buruh, pedagang asongan, dll. Sekalipun secara vertikal terdapat hubungan
yang bersifat super suboordinasi, tetapi secara horizontal menunjukan hubungan
kooperatif-inferior. Kenyataan bahwa hampir seluruh masyarakat Sunda yang hidup
di pedesaan adalah berprofesi sebagai petani.
Berdasarkan umur seseorang dalam masyarakat Sunda, dikenal kelompok
orang dewasa dan kelompok orang tua yang berpartisipasi penuh dalam kehidupan
sosialnya. Kelompok tua lebih berperan sebagai pembimbing. Terdapat etika dan adab
yang dijalankan oleh setiap individu pada masyarakat Sunda tanpa pemaksaan. Disini
kita akan melihat betapa luhur dan agungnya budaya Sunda dalam aspek etika
pergaulan di masyarakat. Seorang anak (kelompok dewasa) yang bertingkah
mencampuri urusan orang tua (kelompok tua) disebut kokolot begog. Kurang baik
apabila kelompok muda lebih berpartisipasi aktif melampaui perang kelompok tua,

walaupun kapabilitas seorang pemuda lebih tinggi dari seorang tua, hal ini terkait adat
dan kebiasaan masyarakat Sunda.
Penerapan tenggang rasa dapat kita rasakan ketika melihat realitas di atas.
Namun, dalam beberapa kasus, masih ada peran pemuda yang memporsikan lebih dari
perang orang tua. Misalnya, seorang anak menjadi penanggungjawab keutuhan dan
kebutuhan hidup keluarga dengan bekerja lebih dari pekerjaan orang tua. Terlepas dari
hal ini, etika dalam sistem organisasi kemasyarakat Sunda merupapak potret ideal
dalam menjalani kehidupan yang lebih dinamis. Kehidupan bersama dalam balutan
gotong royong tampak terasa dalam kebiasaan nguyang, yaitu memberikan sesuatu
(biasanya palawija) kepada orang lain dengan mengharap balasan yang lebih besar.
Hubungan dalam masyarakat Sunda sifatnya subjektif. Artinya, kepentingan individu
adalah kepentingan bersama dan kepentingan kelompok juga merupakan kepentingan
individu (perseorangan).
Menyangkut masalah internal keluarga, dalam masyarakt Sunda, ayah biasa
dipanggil abah dan ibu dipanggil ema. Kakek dipangil aki dan nenek dipanggil nini.
Adik ayah dan ibu yang laki-laki dipanggil amang sedangkan adik ayah dan ibu yang
perempuan dipanggil bibi. Dalam perkawinan, suami biasa panggil salaki dan istri
dipanggil pamajikan. Masyarakat Sunda menganut garis keturunan secara bilateral
yaitu dari kedua belah pihaknya baik dari garis laki-laki maupun dari garis
perempuan. Antara kerabat si ayah dan si ibu itu derajatnya sama dalam
keluarga. Namun ada juga perbedaannya yaitu kerabat jauh dan kerabat dekat.
Sumber :
- Buku Salam Sahabat Nusantara: Jawa Barat yang Memesona, Penerbit: Doenia
Aksara.
- Muflihah, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap Sekolah Dasar, Penerbit: Puspa
Swara, Jakarta, 2007.