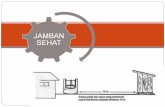ikm penyuluhan
-
Upload
indahichtiani100 -
Category
Documents
-
view
79 -
download
1
description
Transcript of ikm penyuluhan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teoritik
1. Angka Kematian Ibu dan ANC
Angka kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat
kesehatan perempuan. AKI di Jawa Tengah, masih cukup tinggi mencapai
116,01/100.000 kelahiran pada tahun 2011. Angka tersebut mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 104,97/100.000 kelahiran hidup.1
Salah satu upaya penurunan angka kematian ibu adalah dengan melakukan
antenatal care.2 Kunjungan Antenatal Care (ANC) adalah kunjungan ibu hamil ke bidan
atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan
pelayanan/asuhan Antenatal. Pada setiap kunjungan Antenatal care (ANC), petugas
mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi ibu melalui anamnesis dan
pemeriksaan fisik untuk mendapatkan diagnosis kehamilan intrauterine, serta ada tidaknya
masalah atau komplikasi.Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah
ditentukan dalam tujuan ke lima yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang
akan tahun dicapai 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Dari
hasil survei yang dilakukan terhadap telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu yang
terus-menerus, namun demikian membutuhkan komitmen dan usaha keras, apabila hal ini
tidak menjadi perhatian kita semua maka diperkirakan angka pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan sebesar 90% pada tahun 2015 tidak akan tercapai, konsentrasi lebih lanjut
bisa berimbas pada resiko angka kematian ibu meningkat.3
Penyebab kematian ibu yang paling umum di Indonesia adalah penyebab obstetri
langsung yaitu perdarahan 28 %, preeklampsi/eklampsi 24 %, infeksi 11 %, sedangkan
penyebab tidak langsung adalah trauma obstetri 5 %, dll.
2. Perdarahan Separuh dari kematian ibu disebabkan oleh perdarahan. Dua pertiga dari semua
kasus perdarahan pascapersalinan terjadi pada ibu tanpa faktor risiko yang diketahui
sebelumnya, duapertiga kematian akibat perdarahan tersebut adalah dari jenis retensio

plasenta,dan tidak mungkin memperkirakan ibu mana yang akan mengalami atonia uteri
maupun perdarahan. Perdarahan, khususnya perdarahan post-partum, terjadi secara
mendadak dan lebih berbahaya apabila terjadi pada wanita yang menderita anemia.
Seorang ibu dengan perdarahan dapat meninggal dalam waktu kurang dari satu jam.
Kondisi kematian ibu secara keseluruhan diperberat oleh “tiga terlambat” yaitu terlambat
dalam pengambilan keputusan, terlambat mencapai tempat rujukan, terlambat dalam
mendapatkan pertolongan yang tepat di fasilitas kesehatan.
3. Preeklamsia
a. Pengertian
Sesuai dengan batasan dari National Institutes of Health (NIH) Working
Group on Blood Pressure in Pregnancy13,24-26 preeklampsia adalah timbulnya
hipertensi disertai dengan proteinuria pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu
atau segera setelah persalinan. Saat ini oedema pada wanita hamil dianggap dianggap
sebagai hal yang biasa dan tidak spesifik dalam diagnosis preeklampsi. Hipertensi
didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik 140 mmHg atau tekanan
darah diastolik 90 mmHg. Tekanan darah diastolik ditetapkan pada saat hilangnya
bunyi korotkoff ( korotkoff 5 ). Proteinuria didefinisikan sebagai adanya protein
dalam urin dalam jumlah 300 mg/ml dalam urin tampung 24 jam atau 30 mg/dl dari
urin acak tengah yang tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran kencing 25,26.
Preeklampsia sendiri dibagi menjadi 2, yaitu preeklampsia ringan dan
preeklampsia berat. Preeklampsia ringan adalah preeklampsia, dengan tekanan darah
sistolik 140 - <160 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 - <110 mmHg. Disebut
dengan preeklampsia berat bila pada penderita preeklampsia didapatkan salah satu
gejala berikut : Tekanan darah sistolik 160 mmHg dan tekanan darah diastolik 110
mmHg ; Proteinuria 5 gr / jumlah urin selama 24 jam atau dipstick 4 + ; Oliguria ;
Peningkatan kadar kreatinin serum (> 1,2 mg/dl) ; Edema paru dan sianosis ;
Gangguan visus dan serebral disertai sakit kepala yang menetap ; nyeri epigastrium
yang menetap ; Trombositopenia < 100.000 sel/mm3; Peningkatan enzim hepar
(alanin aminotransferase [ALT] atau aspartate aminotransferase [AST] ; Hemolisis ;
Trombositopenia (< 100.000/mm3), sindroma HELLP 13,25.

Eklampsia adalah preeklampsia yang disertai kejang tonik klonik disusul
dengan koma26. Superimposed preeklampsia/eklampsia adalah timbulnya proteinuria
pada wanita hamil yang sebelumnya telah mengalami hipertensi. Proteinuria hanya
timbul setelah kehamilan 20 minggu26. Penyakit hipertensi kronis adalah
ditemukannya desakan darah 140/90 mmHg sebelum kehamilan atau sebelum
kehamilan 20 minggu dan tidak menghilang setelah 12 minggu pasca persalinan26.
b. Epidemiologi
Dari data berbagai kepustakaan didapat angka kejadian preeklampsia di
berbagai negara antara 7–10%27. Di Indonesia sendiri angka kejadian preeklampsia
berkisar antara 3,4 – 8,5 %26. Pada penelitian di RS. Dr. Kariadi Semarang tahun
1997 didapatkan angka kejadian preeklampsia 3,7 % dan eklampsia 0,9 % dengan
angka kematian perinatal sebesar 3,1 %28. Sedang pada periode tahun 1997 – 1999
didapatkan angka kejadian preeklampsia 7,6 % dan eklampsia 0,15 % 29. Penelitian
pada bulan Juni 2002 – Februari 2004 di RS. Dr. Kariadi Semarang didapatkan 28,1
% kasus persalinan dengan preeklampsia berat30. Dari data ini terlihat 10
kecenderungan peningkatan angka kejadian preeklampsia di RS. Dr.Kariadi dari
tahun ke tahun.
c. Faktor risiko
Faktor risiko pada preeklamsi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor
risiko maternal, faktor risiko medikal maternal, dan faktor risiko plasental atau fetal.
Beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia
diantaranya adalah sebagai berikut :
- Kehamilan pertama
- Riwayat keluarga dengan pre-eklampsia atau eklampsia
- Pre-eklampsia pada kehamilan sebelumnya
- Ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
- Wanita dengan gangguan fungsi organ (diabetes, penyakit ginjal, migraine, dan
tekanan darah tinggi)
- Kehamilan kembar

d. Etiologi
Etiologi penyakit ini sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Secara
teoritik urutan urutan gejala yang timbul pada preeklamsi ialah edema, hipertensi,
dan terakhir proteinuri. Sehingga bila gejala-gejala ini timbul tidak dalam urutan
diatas dapat dianggap bukan preeklamsi.
Dari gejala tersebut timbur hipertensi dan proteinuria merupakan gejala yang
paling penting. Namun, penderita serinhkali tidak merasakan perubahan ini. Bila
penderita sudah mengeluh adanya gangguan nyeri kepala, gangguan penglihatan atau
nyeri epigastrium, maka penyakit ini sudah cukup lanjut.
e. Gambaran Klinis Preeklampsia
1) Gejala subjektif
Pada preeklampsia didapatkan sakit kepala di daerah frontal, skotoma, diplopia,
penglihatan kabur, nyeri di daerah epigastrium, mual atau muntah-muntah.
Gejala-gejala ini sering ditemukan pada preeklampsia yang meningkat dan
merupakan petunjuk bahwa eklampsia akan timbul. Tekanan darah pun akan
meningkat lebih tinggi, edema dan proteinuria bertambah meningkat.
2) Pemeriksaan fisik
Pada pemeriksaan fisik yang dapat ditemukan meliputi; peningkatan tekanan
sistolik 30mmHg dan diastolik 15 mmHg atau tekanan darah meningkat lebih dari
140/90mmHg. Tekanan darah pada preeklampsia berat meningkat lebih dari
160/110 mmHg dan disertai kerusakan beberapa organ. Selain itu kita juga akan
menemukan takikardia, takipnu, edema paru, perubahan kesadaran, hipertensi
ensefalopati, hiperefleksia, pendarahan otak.
f. Patofisiologi Preeklampsia
Pada preeklampsia yang berat dan eklampsia dapat terjadi perburukan
patologis pada sejumlah organ dan sistem yang kemungkinan diakibatkan oleh
vasospasme dan iskemia. Wanita dengan hipertensi pada kehamilan dapat mengalami
peningkatan respon terhadap berbagai substansi endogen (seperti prostaglandin,
tromboxan) yang dapat menyebabkan vasospasme dan agregasi platelet.
Penumpukan trombus dan pendarahan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang
ditandai dengan sakit kepala dan defisit saraf lokal dan kejang. Nekrosis ginjal dapat

menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus dan proteinuria. Kerusakan hepar
dari nekrosis hepatoseluler menyebabkan nyeri epigastrium dan peningkatan tes
fungsi hati. Manifestasi terhadap kardiovaskuler meliputi penurunan volume
intravaskular, meningkatnya cardiac output dan peningkatan tahanan pembuluh
perifer. Peningkatan hemolisis microangiopati menyebabkan anemia dan
trombositopeni. Infark plasenta dan obstruksi plasenta menyebabkan pertumbuhan
janin terhambat bahkan kematian janin dalam rahim. Perubahan pada organ-organ:
1) Perubahan kardiovaskuler
Gangguan fungsi kardiovaskuler yang parah sering terjadi pada
preeklampsia dan eklampsia. Berbagai gangguan tersebut pada dasarnya berkaitan
dengan peningkatan afterload jantung akibat hipertensi, preload jantung yang
secara nyata dipengaruhi oleh berkurangnya secara patologis hipervolemia
kehamilan atau yang secara iatrogenik ditingkatkan oleh larutan onkotik atau
kristaloid intravena, dan aktivasi endotel disertai ekstravasasi ke dalam ruang
ektravaskular terutama paru.
2) Metabolisme air dan elektrolit
Hemokonsentrasi yang menyerupai preeklampsia dan eklampsia tidak
diketahui penyebabnya. Jumlah air dan natrium dalam tubuh lebih banyak pada
penderita preeklampsia dan eklampsia daripada pada wanita hamil biasa atau
penderita dengan hipertensi kronik. Penderita preeklampsia tidak dapat
mengeluarkan dengan sempurna air dan garam yang diberikan. Hal ini disebabkan
oleh filtrasi glomerulus menurun, sedangkan penyerapan kembali tubulus tidak
berubah. Elektrolit, kristaloid, dan protein tidak menunjukkan perubahan yang
nyata pada preeklampsia. Konsentrasi kalium, natrium, dan klorida dalam serum
biasanya dalam batas normal.
3) Mata
Dapat dijumpai adanya edema retina dan spasme pembuluh darah. Selain
itu dapat terjadi ablasio retina yang disebabkan oleh edema intra-okuler dan
merupakan salah satu indikasi untuk melakukan terminasi kehamilan. Gejala lain
yang menunjukan tanda preeklampsia berat yang mengarah pada eklampsia adalah
adanya skotoma, diplopia, dan ambliopia. Hal ini disebabkan oleh adanya

perubahan preedaran darah dalam pusat penglihatan di korteks serebri atau di
dalam retina.
4) Otak
Pada penyakit yang belum berlanjut hanya ditemukan edema dan anemia
pada korteks serebri, pada keadaan yang berlanjut dapat ditemukan perdarahan.
5) Uterus
Aliran darah ke plasenta menurun dan menyebabkan gangguan pada
plasenta, sehingga terjadi gangguan pertumbuhan janin dan karena kekurangan
oksigen terjadi gawat janin. Pada preeklampsia dan eklampsia sering terjadi
peningkatan tonus rahim dan kepekaan terhadap rangsangan, sehingga terjadi
partus prematur.
6) Paru-paru
Kematian ibu pada preeklampsia dan eklampsia biasanya disebabkan oleh
edema paru yang menimbulkan dekompensasi kordis. Bisa juga karena terjadinya
aspirasi pneumonia, atau abses paru.
g. Diagnosis Preeklampsia
Diagnosis preeklampsia dapat ditegakkan dari gambaran klinik dan
pemeriksaan laboratorium. Dari hasil diagnosis, maka preeklampsia dapat
diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu;
1) Preeklampsia ringan, bila disertai keadaan sebagai berikut :
- Tekanan darah 140/90 mmHg, atau kenaikan diastolik 15 mmHg atau lebih,
atau kenaikan sistolik 30 mmHg atau lebih setelah 20 minggu kehamilan
dengan riwayat tekanan darah normal.
- Proteinuria kuantitatif ≥ 0,3 gr perliter atau kualitatif 1+ atau 2+ pada urine
kateter atau midstream.
2) Preeklampsia berat, bila disertai keadaan sebagai berikut:
- Tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih.
- Proteinuria 5 gr atau lebih perliter dalam 24 jam atau kualitatif 3+ atau 4+.
- Oligouri, yaitu jumlah urine kurang dari 500 cc per 24 jam.
- Adanya gangguan serebral, gangguan penglihatan, dan rasa nyeri di
epigastrium.

- Terdapat edema paru dan sianosis
- Trombositopeni
- Gangguan fungsi hati
- Pertumbuhan janin terhambat
h. Penatalaksanaan Preeklampsia
Diagnosis dini, supervisi medikal yang ketat, waktu persalinan merupakan
persyaratan yang mutlak dalam penatalaksanaan preeklamsi. Persalinan merupakan
pengobatan yang utama. Setelah diagnosis ditegakkan, penatalaksanaan selanjutnya
harus berdasarkan evaluasi awal terhadap kesejahteraan ibu dan janin. Berdasarkan
hal ini, keputusan dalam penatalaksanaan dapat ditegakkan, yaitu apakah
hospitalisasi, ekspektatif atau terminasi kehamilan serta harus memperhitungkan
beratnya penyakit, keadaan ibu dan janin, dan usia kehamilan. Tujuan utama
pengambilan strategi penatalaksanaan adalah keselamatan ibu dan kelahiran janin
hidup yang tidak memerlukan perawatan neonatal lebih lanjut dan lama.
Penatalaksanaa pada preeklamsi dibagi berdasarkan beratnya preeklamsi, yaitu :
1) Preeklamsi ringan
Pada preeklamsi ringan, observasi ketat harus dilakukan untuk mengawasi
perjalanan penyakit karena penyakit ini dapat memburuk sewaktu-waktu. Adanya
gejala seperti sakit kepala, nyeri ulu hati, gangguan penglihatan dan proteinuri
meningkatkan risiko terjadinya eklamsi dan solusio plasenta. Pasien-pasien
dengan gejala seperti ini memerlukan observasi ketat yang dilakukan di rumah
sakit. Pasien harus diobservasi tekanan darahnya setiap 4 jam, pemeriksaan
klirens kreatinin dan protein total seminggu 2 kali, tes fungsi hati, asam urat,
elektrolit, dan serum albumin setiap minggu. Pada pasien preeklamsi berat,
pemeriksaan fungsi pembekuan seperti protrombin time, partial tromboplastin
time, fibrinogen, dan hitung trombosit. Perkiraan berat badan janin diperoleh
melalui USG saat masuk rumah sakit dan setiap 2 minggu. Perawatan jalan
dipertimbangkan bila ketaatan pasien baik, hipertensi ringan, dan keadaan janin
baik. Penatalaksanaan terhadap ibu meliputi observasi ketat tekanan darah, berat
badan, ekskresi protein pada urin 24 jam, dan hitung trombosit begitu pula

keadaan janin (pemeriksaan denyut jantung janin 2x seminggu). Sebagai
tambahan, ibu harus diberitahu mengenai gejala pemburukan penyakit, seperti
nyeri kepala, nyeri epigastrium, dan gangguan penglihatan. Bila ada tanda-tanda
progresi penyakit, hospitalisasi diperlukan. Pasien yang dirawat di rumah sakit
dibuat senyaman mungkin. Ada persetujuan umum tentang induksi persalinan
pada preeklamsi ringan dan keadaan servik yang matang (skor Bishop >6) untuk
menghindari komplikasi maternal dan janin. Akan tetapi ada pula yang tidak
menganjurkan penatalaksanaan preeklamsi ringan pada kehamilan muda. Saat ini
tidak ada ketentuan mengenai tirah baring, hospitalisasi yang lama, penggunaan
obat anti hipertensi dan profilaksis anti konvulsan. Tirah baring umumnya
direkomendasikan terhadap preeklamsi ringan. Keuntungan dari tirah baring
adalah mengurangi edema, peningkatan pertumbuhan janin, pencegahan ke arah
preeklamsi berat, dan meningkatkan outcome janin. Medikasi anti hipertensi tidak
diperlukan kecuali tekanan darah melonjak dan usia kehamilan 30 minggu atau
kurang. Pemakaian sedatif dahulu digunakan, tatapi sekarang tidak dipakai lagi
karena mempengaruhi denyut jantung istirahat janin dan karena salah satunya
yaitu fenobarbital mengganggu faktor pembekuan yang tergantung vitamin K
dalam janin. Sebanyak 3 penelitian acak menunjukkan bahwa tidak ada
keuntungan tirah baring baik di rumah maupun di rumah sakit walaupun tirah
baring di rumah menurunkan lamanya waktu di rumah sakit. Sebuah penelitian
menyatakan adanya progresi penyakit ke arah eklamsi dan persalinan prematur
pada pasien yang tirah baring di rumah. Namun, tidak ada penelitian yang
mengevaluasi eklamsi, solusio plasenta, dan kematian janin. Pada 10 penelitian
acak yang mengevaluasi pengobatan pada wanita dengan preeklamsi ringan
menunjukkan bahwa efek pengobatan terhadap lamanya kehamilan, pertumbuhan
janin, dan insidensi persalinan preterm bervariasi antar penelitian. Oleh karena itu
tidak terdapat keuntungan yang jelas terhadap pengobatan preeklamsi ringan.
Pengamatan terhadap keadaan janin dilakukan seminggu 2 kali dengan
NST dan USG terhadap volume cairan amnion. Hasil NST non reaktif
memerlukan konfirmasi lebih lanjut dengan profil biofisik dan oksitosin challenge
test. Amniosentesis untuk mengetahui rasio lesitin:sfingomielin (L:S ratio) tidak

umum dilakukan karena persalinan awal akibat indikasi ibu, tetapi dapat berguna
untuk mengetahui tingkat kematangan janin. Pemberian kortikosteroid dilakukan
untuk mematangkan paru janin jika persalinan diperkirakan berlangsung 2-7 hari
lagi. Jika terdapat pemburukan penyakit preeklamsi, maka monitor terhadap janin
dilakukan secara berkelanjutan karena adanya bahaya solusio plasenta dan
insufisiensi uteroplasenter.
2) Preeklamsi berat
Tujuan penatalaksanaan pada preeklamsi berat adalah mencegah konvulsi,
mengontrol tekanan darah maternal, dan menentukan persalinan. Persalinan
merupakan terapi definitif jika preeklamsi berat terjadi di atas 36 minggu atau
terdapat tanda paru janin sudah matang atau terjadi bahaya terhadap janin. Jika
terjadi persalinan sebelum usia kehamilan 36 minggu, ibu dikirim ke rumah sakit
besar untuk mendapatkan NICU yang baik.
Pada preeklamsi berat, perjalanan penyakit dapat memburuk dengan
progresif sehingga menyebabkan pemburukan pada ibu dan janin. Oleh karena itu
persalinan segera direkomendasikan tanpa memperhatikan usia kehamilan.
Persalinan segera diindikasikan bila terdapat gejala impending eklamsi, disfungsi
multiorgan, atau gawat janin atau ketika preeklamsi terjadi sesudah usia
kehamilan 34 minggu. Pada kehamilan muda, bagaimana pun juga, penundaan
terminasi kehamilan dengan pengawasan ketat dilakukan untuk meningkatkan
keselamatan neonatal dan menurunkan morbiditas neonatal jangka pendek dan
jangka panjang.
Pada 3 penelitian klinis baru-baru ini, penatalaksanaan secara konservatif
pada wanita dengan preeklamsi berat yang belum aterm dapat menurunkan
morbiditas dan mortalitas neonatal. Namun, karena hanya 116 wanita yang
menjalani terapi konservatif pada penelitian ini dan karena terapi seperti itu
mengundang risiko bagi ibu dan janin, penatalaksanaan konservatif hanya
dikerjakan pada pusat neonatal kelas 3 dan melaksanakan observasi bagi ibu dan
janin. Semua wanita dengan usia kehamilan 40 minggu yang menderita
preeklamsi ringan harus memulai persalinan. Pada usia kehamilan 38 minggu,
wanita dengan preeklamsi ringan dan keadaan serviks yang sesuai harus diinduksi.

Setiap wanita dengan usia kehamilan 32-34 minggu dengan preeklamsi berat
harus dipertimbangkan persalinan dan janin sebaiknya diberi kortikosteroid. Pada
pasien dengan usia kehamilan 23-32 minggu yang menderita preeklamsi berat,
persalinan dapat ditunda dalam usaha untuk menurunkan morbiditas dan
mortalitas perinatal. Jika usia kehamilan < 23 minggu, pasien harus diinduksi
persalinan untuk terminasi kehamilan.
Tujuan obyektif utama penatalaksanaan wanita dengan preeklamsi berat
adalah mencegah terjadinya komplikasi serebral seperti ensefalopati dan
perdarahan. Ibu hamil harus diberikan magnesium sulfat dalam waktu 24 jam
setelah diagnosis dibuat. Tekanan darah dikontrol dengan medikasi dan pemberian
kortikosteroid untuk pematangan paru janin. Batasan terapi biasanya bertumpu
pada tekanan diastolik 110 mmHg atau lebih tinggi. Beberapa ahli menganjurkan
mulai terapi pada tekanan diastolik 105 mmHg , sedangkan yang lainnya
menggunakan batasan tekanan arteri rata-rata > 125 mmHg. Tujuan dari terapi
adalah menjaga tekanan arteri rata-rata dibawah 126 mmHg (tetapi tidak lebih
rendah dari 105 mmHg) dan tekanan diastolik < 105 mmHg (tetapi tidak lebih
rendah dari 90 mmHg). Terapi inisial pilihan pada wanita dengan preeklamsi berat
selama peripartum adalah hidralazin secara IV dosis 5 mg bolus. Dosis tersebut
dapat diulangi bila perlu setiap 20 menit sampai total 20 mg. Bila dengan dosis
tersebut hidralazin tidak menghasilkan perbaikan yang diinginkan, atau jika ibu
mengalami efek samping seperti takikardi, sakit kepala, atau mual, labetalol (20
mg IV) atau nifedipin (10 mg oral) dapat diberikan. Akan tetapi adanya efek fetal
distres terhadap terapi dengan hidralazin, beberapa peneliti merekomendasikan
penggunaan obat lain dalam terapi preeklamsi berat. Pada 9 penelitian acak yang
membandingkan hidralazin dengan obat lain, hanya satu penelitian yang
menyebutkan efek samping dan kegagalan terapi lebih sering didapatkan pada
hidralazin.
Bila ditemukan masalah setelah persalinan dalam mengontrol hipertensi
berat dan jika hidralazin intra vena telah diberikan berulang kali pada awal
puerperium, maka regimen obat lain dapat digunakan. Setelah pengukuran
tekanan darah mendekati normal, maka pemberian hidralazin dihentikan. Jika

hipertensi kembali muncul pada wanita post partum, labetalol oral atau diuretik
thiazide dapat diberikan selama masih diperlukan.
Pemberian cairan infus dianjurkan ringer laktat sebanyak 60-125 ml
perjam kecuali terdapat kehilangan cairan lewat muntah, diare, diaforesis, atau
kehilangan darah selama persalinan. Oliguri merupakan hal yang biasa terjadi
pada preeklamsi dan eklamsi dikarenakan pembuluh darah maternal mengalami
konstriksi (vasospasme) sehingga pemberian cairan dapat lebih banyak.
Pengontrolan perlu dilakukan secara rasional karena pada wanita eklamsi telah
ada cairan ekstraselular yang banyak yang tidak terbagi dengan benar antara
cairan intravaskular dan ekstravaskular. Infus dengan cairan yang banyak dapat
menambah hebat maldistribusi cairan tersebut sehingga meninggikan risiko
terjadinya edema pulmonal atau edema otak.
Pada masa lalu, anestesi dengan cara epidural dan spinal dihindarkan pada
wanita dengan preeklamsi dan eklamsi. Pertimbangan utama karena adanya
hipotensi yang ditimbulkan akibat blokade simpatis. Ada juga pertimbangan lain
yaitu pada keamanan janin karena blokade simpatis dapat menimbulkan ipotensi
dan menurunkan perfusi plasenta. Ketika teknik analgesi telah mengalami
kemajuan beberapa dekade ini, analgesi epidural digunakan untuk memperbaiki
vasospasme dan menurunkan tekanan darah pada wanita penderita preeklamsi
berat. Selain itu, klinisi yang lebih menyenangi anestesi epidural menyatakan
bahwa pada anestesi umum dapat terjadi penigkatan tekanan darah tiba-tiba akibat
stimulasi oleh intubasi trakea dan dapat menyebabkan edema pulmonal, edema
serebral dan perdarahan intrakranial. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wallace
dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggunaan anestesi baik metode anestesi
umum maupun regional dapat digunakan pada persalinan dengan cara seksio
sesarea pada wanita preeklamsi berat jika langkah-langkah dilakukan dengan
pertimbangan yang hati-hati. Walaupun anestesi epidural dapat menurunkan
tekanan darah, telah dibuktikan bahwa tidak ada keuntungan signifikan dalam
mencegah hipertensi setelah persalinan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah
anestesi epidural aman digunakan selama persalinan pada wanita dengan
hipertensi dalam kehamilan, tetapi bukan merupakan terapi terhadap hipertensi.

Indikasi persalinan pada preeklamsi dibagi menjadi 2, yaitu :
a) Indikasi ibu
- Usia kehamilan ≥ 38 minggu
- Hitung trombosit < 100.000 sel/mm3
- Kerusakan progresif fungsi hepar
- Kerusakan progresif fungsi ginjal
- Suspek solusio plasenta
- Nyeri kepala hebat persisten atau gangguan penglihatan
- Nyeri epigastrium hebat persisiten, nausea atau muntah
b) Indikasi janin
- IUGR berat
- Hasil tes kesejahteraan janin yang non reassuring
- Oligohidramnion.
4. Mutu Layanan Kesehatan
Globalisasi mempertinggi arus kompetisi disegala bidang termasuk bidang kesehatan
dimana perawat dan bidan terlibat didalamnya. Untuk dapat mempertahankan
eksistensinya, maka setiap organisasi dan semua elemen-elemen dalam organisasi harus
berupaya meningkatkan mutu pelayanannya secara terus menerus. Sistem pengembangan
dan manajemen kinerja klinis (SPMKK) bagi perawat dan bidan terkait erat dan sinkron
dengan program jaminan mutu (Quality Assurance). Kecenderungan masa kini dan masa
depan menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya peningkatan dan
mempertahankan kualitas hidup (quality of life). Oleh karena itu pelayanan kesehatan yang
bermutu semakin dicari untk memperoleh jaminan kepastian terhadap mutu pelayanan
kesehatan yang diterimanya. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya kesehatan untuk mempertahankan kualitas hidup, maka customer akan
semakin kritis dalam menerima produk jasa, termasuk jasa pelayanan keperawatan dan
kebidanan, oleh karena itu peningkatan mutu kinerja setiap perawat dan bidan perlu
dilakukan terus menerus.8
1. Pengertian Mutu

″Mutu" adalah tingkat dimana pelayanan kesehatan pasen ditingkatkan mendekati
hasil yang diharapkan dan mengurangi faktor-faktor yang tidak diinginkan.8
Mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan yang
berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan kebutuhan kepuasan. Mutu adalah
kesesuaian terhadap permintaan persyaratan. Mutu pelayanan kesehatan dasar adalah
kesesuaian antara pelayanan kesehatan dasar yang disediakan/diberikan dengan
kebutuhan yang memuaskan pasien atau kesesuaian dengan ketentuan standar
pelayanan.9
Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.10 Pengertian
layanan kesehatan bermutu adalah suatu layanan yang dibutuhkan,dalam hal ini akan
ditentukan oleh profesi layanan kesehatan, dan sekaligus diinginkan baik oleh pasien
ataupun masyarakat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.11
2. Dimensi mutu layanan kesehatan
Dimensi mutu layanan kesehatan antara lain11 :
a. Dimensi kompentensi teknis ( keterampilan,kemampuan,dan penampilan atau kinerja
pemberi layanan kesehatan ).
b. Keterjangkauan / akses ( layanan kesehatan harus dapat dicapai oleh masyarakat
tanpa terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi,organisasi dan bahasa ).
c. Efektifitas ( bagaimana standar layanan kesehtanitu digunakan dengan tepat,
konsisten, dan sesuai situasi setempat ) dan sangat berkaitan dengan ketrampilan
dalam mengikuti prosedur yang terdapat dalam layanan kesehatan.
d. Efesiensi ( dapat melayani lebih banyak pasien /masyarakat ).
e. Kesinambungan ( pasien harus dapat dilayanai sesuai kebutuhan ).
f. Keamanan ( aman dari resiko cedera, infeksi dan efek samping atau bahaya yang
ditimbulkan oleh layanan kesehtan itu sendiri ).
g. Kenyamanan (kenyamanan dapat menimbulkan kepercayaan pasienkepada organisasi
layanan kesehatan).
h. Informasi ( mampu memberikan informasi yang jelas tentang
apa,siapa,kapan,dimana,dan bagaimanan layanan kesehatan akan dan telah
dilaksanakan. Ini penting untuk tingkat Puskesmas dan RS )

i. Ketepatan waktu ( agar berhasil, layanan kesehtan itu harus dilaksanakan dalam
waktu dan cara yang tepat, oleh pemberi pelayanan yang tepat, dan menggunakan
peralatan dan obat yang tepat, serta biaya yang efesien ).
j. Hubungan antar manusia (merupakan interaksi antar pemberi pelayanan kesehatan
dengan pasien, antar sesama pemberi layanan kesehatan). HAM ini akan memberi
kredibilitas dengan cara salingmenghargai,menjaga rahasia,saling
menghormati,responsifmemberi perhatian.
Dalam menilai kualitas jasa/ pelayanan, terdapat sepuluh ukuran kualitas jasa/
pelayanan, yaitu12 :
a. Tangible (nyata/berwujud)
b. Reliability (keandalan)
c. Responsiveness (Cepat tanggap)
d. Competence (kompetensi)
e. Access (kemudahan)
f. Courtesy (keramahan)
g. Communication (komunikasi)
h. Credibility (kepercayaan)
i. Security (keamanan)
j. Understanding the Customer (Pemahaman pelanggan)
Namun, dalam perkembangan selanjutnya dalam penelitian dirasakan adanya
dimensi mutu pelayanan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya yang
dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Dimensi tersebut difokuskan menjadi 5 dimensi
(ukuran) kualitas jasa/pelayanan, yaitu12 :
a. Tangible (berwujud); meliputi penampilan fisik dari fasilitas, peralatan, karyawan
dan alat-alat komunikasi.
b. Realibility (keandalan); yakni kemampuan untuk melaksanakan jasa yang telah
dijanjikan secara konsisten dan dapat diandalkan (akurat).
c. Responsiveness (cepat tanggap); yaitu kemauan untuk membantu pelanggan
(konsumen) dan menyediakan jasa/pelayanan yang cepat dan tepat.
d. Assurance (kepastian); mencakup pengetahuan dan keramah-tamahan para karyawan
dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, kesopanan

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau
keragu-raguan.
e. Empaty (empati); meliputi pemahaman pemberian perhatian secara individual kepada
pelanggan, kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, dan memahami
kebutuhan pelanggan.
3. Kebutuhan pelanggan layanan kesehatan11
a. Kebutuhan terhadap akses layanan kesehatan, artinya kemudahan memperoleh
layanan kesehatan yang dibutuhkan.
b. Kebutuhan terhadap layanan yang tepat waktu, artinya tingkat ketersediaan layanan
kesehatan pada saat dibutuhkan.
c. Kebutuhan terhadap layanan kesehtan yang efesien dan efektifartinya biaya layanan
kesehtan terjangkau.
d. Kebutuhan layanan kesehtan yang tepat dan layak artinya layanan kesehatan
diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien.
4. Cara mengukur mutu
Banyak kerangka pikir yang dapat digunakan untuk mengukur mutu. Pada awal
upaya pengukuran mutu layanan kesehatan, tiga kategori penggolongan layanan
kesehatan yaitu struktur, proses, dan keluaran.11
a. Standar struktur
Standar struktur adalah standar yang menjelaskan peraturan sistem, kadang-
kadang disebut juga sebagai masukan atau struktur. Termasuk kedalamnya hubungan
organisasi, misi organisasi,kewenangan, komite-komite, personel, peralatan gedung,
rekam medik, keuangan, perbekalan obat dan fasilitas. Standar struktur merupakan
ruler of the game.
b. Standar proses
Standar proses adalah sesuatu yang menyangkut semua aspek pelaksanaan
kegiatan layanan kesehatan, melakukan prosedur dan kebijaksanaan. Standar proses
akan menjelaskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya dan
bagaimana sistem bekerja. Dengan lain, standar proses adalah playing the game.
c. Standar keluaran

Standar keluaran merupakan hasil akhir atau akibat dari layanan kesehatan.
Standar keluaran akan menunjukan apakah layanan kesehatan berhasil atau gagal.
Keluaran (outcame) adalah apa yang diharapkanakan terjadi sebagai hasil dari
layanan yang diselenggarakan dan terhadap apa keberhasilan itu diukur.
5. Kualitas Pelayanan Antenatal
Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa
kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang mencakup anamnesis,
pemeriksaan fisik umum dan kebidanan, pemeriksaan laboratorium atas indikasi tertentu
serta indikasi dasar dan khusus.11 Selain itu aspek yang lain yaitu penyuluhan, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE), motivasi ibu hamil dan rujukan.11
Tujuan asuhan antenatal adalah memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan
kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan
fisik, mental dan sosial ibu dan bayi, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau
komplikasi yang mungkin selama kehamilan, termasuk riwayat penyakit secara umum,
kebidanan dan pembedahan, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan
selamat,ibu maupun bayinya dengantrauma seminimal mungkin, mempersiapkan ibu agar
masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif, mempersiapkan peran ibu dan
keluarga dalam menerimakelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal serta
optimalisasi kembalinya kesehatan reproduksi ibu secara wajar. Keuntungan layanan
antenatal sangat besar karena dapat mengetahui resiko dan komplikasi sehingga ibu hamil
dapat diarahkan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit. Layanan antenatal dilakukan
sehingga dapat dilakukan pengawasan yang lebih intensif, pengobatan agar resiko dapat
dikendalikan, serta melakukan rujukan untuk mendapat tindakan yang adekuat.13
Pelayanan yang dilakukan secara rutin juga merupakan upaya untuk melakukan deteksi
dini kehamilan beresiko sehingga dapat dengan segera dilakukan tindakan yang tepat untuk
mengatasi dan merencanakan serta memperbaiki kehamilan tersebut. Kelengkapan
antenatal terdiri dari jumlah kunjungan antenatal dan kualitas pelayanan antenatal.14
Pelayanan antenatal mempunyai pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan janin atau
lama waktu mengandung, baik dengan diagnosis maupun dengan perawatan berkala
terhadap adanya komplikasi kehamilan. Pertama kali ibu hamil melakukan pelayanan

antenatal merupakan saat yang sangat penting, karena berbagai faktor resiko bisa diketahui
seawal mungkin dan dapat segera dikurangi atau dihilangkan.15
Kualitas pelayanan Antenatal erat hubungannya dengan penerapan. Standar pelayanan
kebidanan, yang mana standar pelayanan berguna dan penerapan norma dan tingkat kinerja
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan standar pelayanan akan
sekaligus melindungi masyarakat, karena penilaian terhadap proses dan hasil penilaian
dapat dilakukan dengan dasar yang jelas. Mengukur tingkat kebutuhan terhadap standar
yang baik input, proses pelayanan dan hasil pelayanan khususnya tingkat pengetahuan
pasien terhadap pelayanan antenatal yang dikenal standar mutu yaitu16 :
1. Standar pelayanan Antenatal
Terdapat enam standar dalam standar pelayanan antenatal seperti berikut ini :
a. Standar : Identifikasi Ibu Hamil
Standar ini bertujuan mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan
kehamilannya.
Pernyataan standar : Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan
masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu,
suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan
kehamilannya sejak dini dan secara teratur.
b. Standar : Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal
Pemeriksaan dan pemantauan antenatal bertujuan memberikan pelayanan
antenatal berkualitas dan diteliti dalam komplikasi.
Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi
anamnesa dan pemantauan ibu dan dan janin dengan seksama untuk menilai apakah
perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan
risti/kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS/ Infeksi HIV ;
memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas
terkait lainnya yang diberikan oleh Puskesmas. Mereka harus mencatat data yang
tepat padu setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, mereka harus mampu
mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya.
c. Standar : Palpasi Abdominal

Standar palpasi abdominal bertujuan memperkirakan usia, kehamilan,
pemantauan pertumbuhan jenis, penentuan letak, posisi dan bagian bawah janin.
Bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama & melakukan palpasi
untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa
posisi, bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk
mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu.
Secara tradisional perkiraan tinggi fundus dilakukan dengan palpasi fundus dan
membandingkannya dengan beberapa patokan antara lain simfisis pubis, umbilikus
atau prosesus sifoideus. Cara tersebut dilakukan dengan tanpa memperhitungkan
ukuran tubuh ibu. Sebaik-baiknya pemeriksaan (perkiraan) tersebut, hasilnya masih
kasar dan dilaporkan hasilnya bervariasi.
Dalam upaya standardisasi perkiraan tinggi fundus, para peneliti saat ini
menyarankan penggunaan pita ukur untuk mengukur tinggi fundus dari tepi atas
simfisis pubis karena memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan.
Pengukuran tinggi fundus uteri tersebut bila dilakukan pada setiap kunjungan oleh
petugas yang sama, terbukti memiliki nilai prediktif yang baik, terutama untuk
mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan intrauterin yang berat dan
kehamilan kembar. Walaupun pengukuran tinggi fundus uteri dengan pita ukur
masih bervariasi antar operator, namun variasi ini lebih kecil dibandingkan dengan
metoda tradisional lainnya. Oleh karena itu penelitian mendukung penggunaan pita
ukur untuk memperkirakan tinggi fundus sebagai bagian dari pemeriksaan rutin
pada setiap kunjungan.
d. Standar : Pengelolaan Anemia pada Kehamilan
Standar ini bertujuan menemukan anemia pada kehamilan secara dini dan
melakukan tindakan lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum
persalinan berlangsung. Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan,
penanganan dan/atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan Hemoglobin (Hb) secara rutin selama kehamilan merupakan
kegiatan yang umumnya dilakukan untuk mendeteksi anemia. Namun ada
kecendurungan bahwa kegiatan ini tidak dilaksanakan secara optimal selama masa

kehamilan. Perubahan normal ini di kenal sebagai Hemodilusi dan biasanya
mencapai titik terendah pada kehamilan minggu ke-30. Oleh karena itu
pemeriksaan Hb dianjurkan untuk dilakukan pada awal kehamilan dan diulang
kembali pada minggu ke-30 untuk mendapat gambaran akurat tentang status Hb.
e. Standar :Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan
Standar ini bertujuan mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada
kehamilan dan melakukan tindakan diperlukan. Bidan menemukan secara dini
setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala
preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.
f. Standar : Persiapan Persalinan.
Standar Persiapan Persalinan dengan tujuan untuk memastikan bahwa persalinan
direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan
terampil. Bidan memberikan saran yang tepat Kepada ibu hamil, suami/keluarganya
pada trisemester III memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman dan
suatu suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping
persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat
darurat. Bidan mengusahakan untuk melakukan kunjungan ke setiap rumah ibu
hamil untuk hal ini.
2. Kebijakan Program Pelayanan Antenatal
Pelayanan Antenatal merupakan cara untuk memonitor dan mendukung kesehatan
ibu hamil normal dan mendeteksi komplikasi. Pelayanan Antenatal penting untuk
menjamin bahwa proses alamiah dari kehamilan berjalan normal dan tetap demikian
seterusnya. Kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap
saat. Sekarang ini sudah umum diterima bahwa setiap kehamilan membawa resiko
bagi ibu.
Kebijakan program dalam pelayanan antenatal yaitu kunjungan antenatal
sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan, satu kali pada triwulan

pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga. Penerapan
operasionalnya dikenal standar minimal (7T) yang terdiri atas :
a. (Timbang) berat badan dan pengukuran tinggi badan, suatu teknologi tepat guna
yang dapat dimanfaatkan untuk menilai status gizi ibu bila tidak tersedia
timbangan pada waktu pemeriksaankehamilan yang pertama, adalah pengukuran
lingkar lengan atas (LLA).
b. Ukur (Tekanan) darah.
c. Ukur (Tinggi) fundus uteri.
d. Pemberian imunisasi (Tetanus Toxoid) / TT lengkap.
e. Pemberian (Tablet besi), minimal 90 tablet selama kehamilan.
f. (Tes) terhadap Penyakit Menular Seksual.
g. (Temu) wicara dalam rangka persiapan rujukan.
Kebijakan teknis pelayanan antenatal setiap kehamilan dapat berkembang menjadi
masalah atau komplikasi setiap saat. Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan
pemantauan selama kehamilannya. Penatalaksanaan ibu hamil secara keseluruhan
meliputi komponen-komponen sebagai berikut : mengupayakan kehamilan yang sehat,
melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan, persiapan persalinan
yang bersih dan aman, perencanaan antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan
rujukan jika terjadi komplikasi.
3. Pelaksanaan Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil.17
a. Mengumpulkan Data Dasar / Pengkajian Data
Mengumpulkan data subyektif dan data obyektif,berupa data fokus yang
dibutuhkan untuk menilai keadaan ibu sesuai dengan kondisinya, menggunakan
anamnesis,pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium.
1) Data Subyektif terdiri dari :
a) Biodata ibu dan suami
b) Alasan ibu memeriksakan diri
c) Riwayat kehamilan sekarang
d) Riwayat kebidanan yang lalu
e) Riwayat menstruasi
f) Riwayat KB

g) Riwayat kesehatan
h) Riwayat bio-psikososial-spiritual
i) Pengetahuan tentang tanda bahaya persalinan
j) Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data subyektif adalah dengan
dengan melakukan anamnesis.
2) Data objektif terdiri dari :
a) Hasil pemeriksaan umum (tinggi badan, berat badan,lingkar lengan, suhu,
nadi, tekanan darah, pernapasan).
b) Hasil pemeriksaan kepala dan leher.
c) Hasil pemeriksaan tangan dan kaki.
d) Hasil pemeriksaan payudara.
e) Hasil pemeriksaan abdomen.
f) Hasil pemeriksaan denyut jantung janin.
g) Hasil pemeriksaan darah dan urine.
Sumber data baik data subyektif maupun data obyektif yang paling akurat
adalah ibu hamil yang diberi asuhan, namun apabila kondisi tidak
memungkinkan dan masih diperlukan data bisa dikaji dari status ibu yang
menggambarkan pendokumentasian asuhan sebelum ditangani dan bisa juga
keluarga atau suami yang mendampingi ibu saat diberi asuhan.
b. Menginterpretasikan /menganalisa data /merumuskan diagnosa
Pada langkah ini data subyektif dan obyektif yang dikaji dianalisis menggunakan
teori fisiologis dan teori patologis sesuai dengan perkembangan kehamilan
berdasarkan umurkehamilan ibu pada saat diberi asuhan, termasuk teori tentang
kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil. Hasil analisis dan interpretasi data
menghasilkan rumusan diagnosis kehamilan.
Rumusan diagnosis kebidanan pada ibu hamil disertai dengan alasan yang
mencerminkan pikiran rasional yang mendukung munculnya diagnosis selanjutnya.

c. Menyusun rencana asuhan yang menyeluruh
Dalam menyusun rencana asuhan yang menyeluruh mengacu pada diagnosis
mengacu pada diagnosis, masalah asuhan serta kebutuhan yang telah sesuai dengan
kondisi klien saat diberi asuhan.
d. Melaksanakan asuhan sesuai perencanaan secara efisien dan aman
Pelaksanaan rencana asuhan bisa dilaksanakan bidan langsung, bisa juga dengan
memberdayakan ibu.
e. Melaksanakan evaluasi terhadap rencana asuhan yang telah dilaksanakan.
Evaluasi ditujukan terhadap efektivitas intervensi tentang kemungkinan
pemecahan masalah, mengacu pada perbaikan kondisi/kesehatan ibu dan janin.
Evaluasi mencangkup jangka pendek, yaitu sesaat setelah intervensi dilaksanakan,
dan jangka panjang, yaitu menunggu proses sampai kunjungan berikutnya /
kunjungan ulang.
f. Pendokumentasian dengan SOAP
Pendokumentasian asuhan kebidanan menggunakan teknik pencatatan Subjectif
Objective Assessment Planing ( SOAP ) meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mencatat data subyektif dan objektif
2) Mencatat data hasil pengkajian,diagnosis,masalah klien/ibu hamil yang diberi
asuhan berdasarkan masalahnya.
3) Mencatat perencanaan asuhan yang meliputi perencanaan tindakan asuhan,
pelaksanaan tindakan asuhan.
Adapun tujuannya adalah :
a. Sebagai bahan komunikasi antar petugas/bidan
b. Sebagai bahan evaluasi
c. Sebagai bahan tindak lanjut
d. Sebagai bahan laporan
e. Sebagai bahan pertanggungjawaban dan tanggung gugat
f. Meningkatkan kerja sama antar tim
g. Sebagai bahan acuan dalam pengumpulan data

6. Faktor – faktor yang dapat menunjang kualitas pelayanan antenatal
1. Kompetensi Teknis
Kompetensi teknis menyangkut ketrampilan, kemampuan, dan penampilan atau
kinerja pemberi layanan kesehatan. Kompetensi teknis itu berhubungan dengan
bagaimana pemberi layanan kesehatan mengikuti standar layanan kesehatan yang telah
disepakati, yang meliputi kepatuhan, ketepatan, kebenaran dan konsistensi. Tidak
dipenuhinya kompetensi teknis dapat mengakibatkan berbagai hal, mulai dari
penyimpangan kecil terhadap standar layanan kesehatan, sampai kepada kesalahan fatal
yang dapat menurunkan mutu layanan kesehatan dan membahayakan jiwa pasien.11
2. Prosedur / Standar
Aplikasi program jaminan mutu di Puskesmas adalah dalam bentuk penerapan
standar dan prosedur tetap pelayanan, agar hasil yang diperoleh tetap terjaga
kualitasnya, meskipun pada kondisi lingkungan dan petugas yang berbeda/bergantian.
Standar adalah suatu suatu pernyataan yang dapat dipergunakan untuk mengukur atau
menilai efektifitas suatu sistem pelayanan.13Sedangkan standar menurut Donabedian
adalah rentang variasi yang dapat diterima dari suatu norma atau kriteria.11
Menurut Utari, et al standar adalah pernyataan yang dapat diterima dan
disepakati tentang sesuatu ( produk, proses, kegiatan, barang ) yang dipergunakan untuk
mengukur atau menilai efektifitas suatu sisitem pelayanan.18
Standar menurut Meissenheimer dalam Koentjoro adalah ukuran yang ditetapkan
dan disepakati bersama, merupakan tingkat kinerja yang diharapakan. Dalam PP 102
tahun 2000 dijelaskan bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang
dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua
pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan,
kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
pengalaman, yakni perkembangan masa kini dan masa yang akan datang. Dalam UU
No. 23 tahun 1992 pasal 53 ayat 2 disebutkan bahwa standar adalah pedoman yang
harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi dengan baik.19
Keberadaan standar dalam pelayanan kesehatan akan memberikan manfaat,
antara lain merupakan persyaratan profesi, dan dasar untuk mengukur mutu. Ditetapkan

standar juga akan menjamin keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan
kesehatan.Pedoman standar pelayanan antenatal untuk memandu para pelaksana
program agar tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, sehingga ada
protokol dan petunjuk pelaksanaan. Protokol adalahsuatu pernyataan tertulis yang
disusun secara sistematis yang dipakai sebagai pedoman atau cara kerja oleh para
pelaksana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Semakin dipenuhi pedoman atau
prosedur tetap pelayanan maka semakin tercapai standar yang ditetapkan.20
Pedoman atau prosedur tetap merupakan gambaran bagi karyawan mengenai
cara kerja atau tata kerja yang dapat dipakai sebagai pegangan apabila terdapat
pergantian /perubahan karyawan sehingga dapat dipakai untuk menilai.18
3. Fasilitas / alat
Lingkungan dan fasilitas / alat merupakan faktor yang mendukung untuk
melaksanakan tindakan atau kegiatan. Lingkungan meliputi ruangan pemeriksaan ibu
hamil yang memenuhi standar kesehatan yaitu tersedianya air bersih yang memenuhi
syarat fisik, kimia dan bakteriologik, pencahayaan yang cukup, ventilasi yang cukup
serta terjamin keamananya.21
Sedangkan fasilitas suatu alat atau sarana untuk mendukung melaksanakan
tindakan/kegiatan, pengelolaan logistik yang baik dan mudah diperoleh serta pencatatan
dan pelaporan yang lengkap dan konsisten.21
7. Konsep Puskesmas
Indonesia dengan visinya: “Indonesia sehat 2010” menggambarkan bahwa masyarakat
Indonesia di masa depan yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat,
mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan Tujuan nasional Bangsa
Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.19
Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, maka perlu
diselenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standart profesi serta
pelayanan yang memuaskan pelanggan. Hal itu perlu segera diwujudkan untuk memenuhi
tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akan pelayanan kesehatan yang bermutu.
Tuntutan masyarakat tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi semua
kalangan yang berkompeten, khususnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Pada bagian ini akan dipaparkan konsep Puskesmas sebagai unit populasi dalam
penelitian ini. Puskesmas adalah pusat pembangunan kesehatan di kecamatan yang
mandiri.19
Dalam bidang organisasi, sesuai dengan PP 8 tahun 2000 pasal 8 ayat 4, Puskesmas
dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Kabupaten/Kota dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.3
1. Pengertian Puskesmas3,19
Suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan
kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping
memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat
di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
2. Fungsi Puskesmas3,19
Fungsi utama Puskesmas adalah sebagai : 1) pusat pembangunan berwawasan
kesehatan, 2) pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan 3) pusat
pelayaan kesehatan tingkat dasar.Pada fungsi pertama, Puskesmas diharapkan dapat
bertindak sebagai motor, motivator dan memantau terselenggaranya proses
pembangunan di wilayah kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan. Pada
fungsi kedua, Puskesmas ikut memberdayakan masyarakat agar masyarakat tahu, mau
dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Sedangkan
sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas
wajib melaksanakan program pokok yang bersifat nasional dan bersifat lokal sesuai
dengan permasalahan dan kebutuhan daerah.

Input Proses Outcome
3. Program Pokok Puskesmas3,19
a. KIA
b. KB
c. Usaha Kesehatan Gizi
d. Kesehatan Lingkungan
e. Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular
f. Pengobatan termasuk penaganan darurat karena kecelakaan
g. Penyuluhan kesehatan masyarakat
h. Kesehatan sekolah
i. Kesehatan olah raga
j. Perawatan Kesehatan Masyarakat
k. Kesehatan kerja
l. Kesehatan Gigi dan Mulut
m. Kesehatan jiwa
n. Kesehatan mata
o. Laboratorium sederhana
p. Pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK
q. Pembinaan pemgobatan tradisional
r. Kesehatan remaja
s. Dana sehat
8. Teori Pendekatan Sistem
Lingkungan : Kebijakan, logistik, manajemen dan lain – lain
a. Standar
pelayanan
b. Tenaga terlatih
c. Peralatan
d. Ibu Hamil
e. Ruang periksa
h. Anamnesa
i. Pemeriksaan fisik
j. Diagnosis / deteksi
k. Pemberian obat
l. Penyuluhan/konseling
perdarahan, BBLR,dsb
m. Pengetahuan ibu
tentang kehamilan,
persalinan, dan
gizi.
n. Tidak terjadi
kelainan pada

f. Kartu ibu/KMS
ibu hamil
g. Tablet Fe, dsb
kehamilan dan
persalinan
B. Kerangka Teori
C. Kerangka Konsep
DAMPAK
- KESAKITAN
- UMUR HARAPAN HIDUP
- STATUS GIZI
- KEMATIAN
PROSES
P1
P2
P3
MUTUCAKUPAN HASIL
LINGKUNGAN
SIMPLE PROBLEM
INPUT
COMPLEX PROBLEM
Output outcome


DAFTAR PUSTAKA
1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom K, Hypertensive
Disorders in Pregnancy, dalam William Obstetrics, edisi ke-22, New York: McGraw-
Hill, 2005 : 761-808
2. Mariam siti, Makalah pre-eklampsia, 14 april 2013, diakses tanggal 27 juni 20013
dari, http://sitimaryamhsb.makalah-pre-eklamsia.html
3. Gopar adul, pdf.Preeklampsi, 12 mey 2012, diakses tanggal 27 juni 2013 dari,
http://adulgopar.files.wordpress.com/preeklampsia.pdf
4. Prawirohardjo S, Pre-eklampsia dan Eklampsia, dalam Ilmu Kebidanan, edisi ke-3,
Wiknjosastro H, Saifuddin A, Rachimhadhi T, penyunting, Jakarta : Yayasan Bina
Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005: 281-301