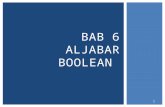Hukum Civil2
-
Upload
anwar-saleh-al-yasir -
Category
Documents
-
view
201 -
download
0
Transcript of Hukum Civil2
3 TRADISI HUKUM SIPIL
A. Ide Revolusioner Hukum Sipil Istilah hukum sipil (civil law) biasanya dipakai secara umum untuk merujuk kepada sistem hukum Eropa yang berasal dari hukum Romawi dan berbeda dari sistem common law. Istilah civil law itu sendiri berasal dari bahasa Latin jus civile, yang berarti hukum yang hanya bisa diterapkan pada rakyat Romawi. Pada masa kerajaan Romawi istilah itu dibedakan dari istilah jus gentium, atau hukum yang diterapkan dalam kasus yang melibatkan orang Romawi dari berbagai provinsi yang berbeda atau antara penduduk Romawi dengan penduduk asing. Meskipun hukum Romawi inilah yang menjadi basis hukum sipil di berbagai negara modern saat ini, namun tidaklah tepat mengatakan bahwa seluruh aspek hukum sipil berasal dari atau dipengaruhi oleh hukum Romawi, karena banyak aturan-aturan substantif hukum Romawi itu ditolak dalam sistem hukum sipil modern saat ini. Dengan kata lain, tradisi hukum sipil memang banyak berhutang pada logika hukum Romawi, tapi perbedaan kondisi masyarakat, politik dan ekonomi telah membelokkan hukum sipil dari asalnya. Karena itu, tidaklah benar mengatakan bahwa tradisi hukum sipil diambil seluruhnya dari hukum Romawi. Sejauh menyangkut asal usul tradisi hukum sipil ini, Alan Watson lebih cenderung memandangnya sebagai sistem hukum yang berasal dari Kode Justinian, Corpus Juris Civilis.1 Dalam pandangannya, bahan mentah tradisi hukum sipil adalah kodifikasi hukum Romawi yang telah diperbarui dan dikodifikasi pada masa raja Byzantium
Justinian I, diterbitkan antara tahun 529 dan 565 M., dan bukan hukum Romawi yang sebelumnya. "sistem hukum sipil adalah sistem dimana sebagian atau keseluruhan Corpus Juris Civilis Justinian di masa lalu atau saat ini diposisikan sebagai hukum yang hidup di suatu daerah atau, paling tidak, dijadikan kekuatan yang mengarahkan secara persuasif; ."2 Terbentuknya hukum sipil hingga dalam bentuknya yang modern sekarang ini sesungguhnya bukanlah suatu proses yang langsung dan sederhana. Perkembangannya melibatkan revolusi intelektual yang kompleks, sehingga memunculkan cara berpikir baru mengenai hukum yang kemudian memiliki konsekuensi massal terhadap organisasi dan administrasi sistem hukum, aturan-aturan serta prosedur-prosedur substantif hukum yang baru. Bila dilihat terutama dari sudut pandang hukum publik, munculnya tradisi hukum sipil adalah hasil dari revolusi pemikiran terus menerus yang dimulai di Eropa pada masa peralihan abad ke-11, saat hukum Romawi direvitalisasi di Benua itu. Revolusi ini bisa terjadi karena ada sejumlah kekuatan intelektual yang berdampingan dengan datangnya berbagai tradisi intelektual dari penjuru dunia lain. Karena pada saat hukum Romawi direvitalisasi di Eropa sebagai elemen tradisi hukum sipil, common law pun pun tengah mengalami masa perkembanganya. Pada saat yang sama, hukum Talmud juga dalam proses reformasi yang dilakukan oleh Maimonides, sementara tradisi intelektual Islam meluaskan pengaruhnya ke lembah Mediterania, terutama Spanyol.3 Oleh karena itu, lahirnya tradisi hukum sipil modern di Barat tidak bisa dipisahkan dari sejumlah kekuatan intelektual yang mendorong munculnya pemikiran hukum baru di tengah proses reformulasi berbagai nilai. Jadi, ada berbagai kondisi substansial yang mengarah kepada munculnya hukum sipil, termasuk diantaranya
sekularisasi hukum, rasionalisasi, anti feodalisme, pemisahan berbagai lembaga pemerintahan, serta statisme dan nasionalisme yang kebanyakan mencapai titik kulminasinya pada abad ke-17 dan 18 di Eropa.4 Dorongan untuk mensekulerkan hukum adalah salah satu kekuatan lain di balik munculnya tradisi hukum sipil. Gagasan intinya adalah memisahkan antara hukum dan agama. Hukum tidak lagi didasarkan pada atau diambil dari doktrin, keyakinan atau otoritas agama, tapi didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang semua terpisah dari wilayah agama. Karakter pemikiran ini sesungguhnya sederhana tapi revolusioner untuk konteks saat itu, yaitu semua manusia tercipta setara. Manusia itu memiliki hak alami tertentu terhadap properti dan kebebasan, termasuk hidup itu sendiri. Gagasannya adalah, hanya perwakilan yang terpilihlah yang akan membentuk pemerintahan. Tugas utama pemerintah itu adalah mengakui dan mempertahankan hak-hak rakyat di samping menjamin kesetaraan di antara semua rakyat. Ini adalah posisi mazhab intelektual yang saat itu dikenal mendukung hukum alam sekuler (dalam bahasa Jerman: Vernunftrecht).5 Anggota mazhab ini percaya pada sistem hukum universal yang tidak berubah-ubah, valid untuk setiap masa dan negara,6 sebuah prinsip yang bisa diamati pada alam.7 Dengan penghargaan kepada akal manusia, mazhab itu juga memahami konsep bahwa masyarakat bisa diubah melalui institusi hukum.8 Gerakan ini bisa dilihat sebagai hasil dari munculnya gelombang rasionalisme yang mengakar di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Rasionalisme memang merupakan kekuatan dominan dalam gerakan intelektual ini. Kepercayaan terhadap kesetaraan umat manusia dipadukan dengan asumsi baru bahwa manusia memiliki kekuatan akal, dan dengan akal manusia bisa
mengontrol berbagai aktivitas dan mengatasi berbagai tantangan hidup. Penggunaan akal secara tepat diyakini bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia; jadi institusi hukum dilihat sebagai hasil ciptaan kecerdasan manusia, sebagai suatu aturan yang bisa didorong atau dibatalkan dan diganti dengan aturan yang baru kalau memang akal menuntut demikian, tanpa harus merujuk kepada Tuhan atau otoritas suci. Ideologi dasar yang dikembangkan oleh gerakan ini adalah hukum merupakan produk akal, bukan produk agen sakral. Ideologi ini tidak bisa dihindari berdampak pada perjuangan menuntut kebebasan individual, karena seluruh manusia yang diberkati dengan akal bisa membuat pilihan mereka sendiri. Maka penekanan bukan diletakkan pada kewajiban manusia, tapi pada hak; hak setiap manusia untuk melakukan urusannya sendiri, hak untuk memiliki properti dan mendapatkan perlindungan hukum atas hak miliknya. Perjuangan tersebut sejatinya juga merupakan reaksi terhadap kecenderungan feodalisme yang masih kuat di Barat pada abad pertengahan. Akibatnya, revolusi intelektual dalam hukum sipil lebih diorientasikan kepada gerakan anti feodalisme tersebut.9 Penekanan lebih besar karena itu diberikan oleh tradisi hukum sipil terhadap hak milik pribadi dan kebebasan berkontrak ketimbang pada aspek-aspek lainnya. Jadi, tidaklah mengejutkan kalau institusi semisal feodalisme atau pemerintahan aristokrasi dijadikan target oleh gerakan tersebut. Termasuk ke dalam gerakan ini juga adalah gerakan untuk memisahkan kekuasaan pemerintahan agar dibedakan secara jelas antara legislatif dan eksekutif di satu pihak, dan yudikatif di pihak lain, atau antara aktivitas pembuatan hukum dan aktivitas penerapan hukum. Tujuan utamanya sudah jelas: kekuatan politik tidak boleh merongrong kekuasaan yudikatif. Seperti pemahaman
Montesquieu bahwa satu-satunya cara yang efektif untuk menghindari kesewenang-wenangan tersebut adalah dengan memisahkan kekuasaan yudisial dari tipe kekuasaan lainnya dan untuk mengatur kekuasaan yudisial hanya sepanjang untuk menjamin bahwa ia menerapkan hukum tanpa intervensi apapun dari pejabat publik.10 Ketika feodalisme sudah dihapuskan, langkah besar selanjutnya adalah menempatkan negara sekuler sebagai sumber hukum. Segala sesuatu yang memiliki aspek hukum akan ditentukan dan diatur oleh negara sebagai agennya. Berbagai tradisi hukum yang berbeda-beda akan disederhanakan dan diberi satu dimensi perekatnya, yaitu negara. Ketika hukum dan aparatnya telah digabungkan dalam satu sistem hukum nasional maka komitmen setiap orang diberikan kepada negara, bukan kepada seorang individu atau sekelompok individu. Di sini nasionalisme menyediakan bahasa yang sama untuk mengagungkan negara. Melalui nasionalisme, sistem hukum diharapkan mengekspresikan gagasan-gagasan nasional serta kesatuan budaya bangsa. Hasilnya, hukum menjadi ekspresi nasionalisme negara karena hukum hanya bisa disampaikan melalui media bahasa nasional dan dimasukkan ke dalam idealitas konsep dan institusi hukum nasional. Revolusi intelektual ini memiliki beberapa konsekuensi terhadap karakteristik dan praktik tradisi hukum sipil. Berakhirnya dominasi gereja di Eropa mendorong orang melihat kehidupan manusia itu terpisah dari ranah agama. Hidup di dunia ini tidak lagi berhubungan dengan gagasan mengenai hari akhirat yang biasanya ada dalam ajaran agama. Manusia seharusnya bebas memutuskan bagaimana mereka mau membawa hidupnya selama keputusan itu dibuat berdasarkan pilihan rasional dan kuasa-
kehendak. Keyakinan terhadap kekuatan intelek manusia inilah yang memberi manusia jaminan bahwa mereka bisa membuat hukum dan merubahnya sekehendak hati mereka. Jadi hukum hanya sesuatu yang profan, yang dalam penciptaannya akal memainkan peran utama; ia tidak lagi dilihat sebagai derivasi yang sakral, tapi sebagai ekspresi nilai-nilai duniawi. Revolusi intelektual ini memberi tradisi hukum sipil dasar epistemologi yang sangat berbeda dari konsep hukum sebagai ekspresi nilainilai ketuhanan yang sebelumnya lazim dianut di Eropa, apakah berdasarkan hukum kitab suci, atau berdasarkan pada karakter manusia sebagai ciptaan Tuhan yang ditemukan dalam hukum alam Katolik Roma. Oleh sebab itu, gerakan menuju sekularisasi di Eropa menjadi latar belakang lahirnya tradisi hukum sipil, dan ketika kecenderungan untuk melihat Tuhan sebagai pencipta hukum telah hilang dari hati masyarakat, sumber-sumber sakral hukum pun harus diganti dengan sumber-sumber baru untuk mendukung keyakinan terhadap hukum sipil profan yang baru, yang sudah menjadi ideologi anutan banyak orang. Jawabannya adalah, kecenderungan baru untuk mempercayakan kepada negara sebagai satu-satunya agen yang berhak membuat hukum. Ini karena keyakinan mereka bahwa administrasi negara bisa mengelola organisasi hukum dan menjalankan kekuasaan hukum. Oleh karena itu hukum menjadi bagian dari aparat negara dan akibatnya semenjak itu kehadiran paham positivisme hukum semakin kuat. Dengan demikian, fenomena kemunculan tradisi hukum sipil ini tidak lain adalah tantangan langsung terhadap pendekatan feodal dan monarkhis dalam menjalankan negara yang telah mendominasi Eropa sampai saat itu. Negara-bangsa modern muncul dan institusi hukum sipil menjadi bagian utama dan sepenuhnya dari otoritas negara.
Dengan kemunculan negara-bangsa modern, kekuasaan pun sepenuhnya terletak di tangan negara. Ideologi sentralisme negara pun tidak bisa dihindari, di mana justifikasi bagi kemandirian hukum hanya diberikan kepada negara demi ideologi sistem hukum nasional. Dampaknya, hukum kanonik Romawi, yang sejak lama dianggap sebagai sumber hukum utama di Eropa era feodal disingkirkan dan diganti dengan hukum nasional yang sesuai dengan logika pembentukan positivisme hukum.11 Dengan adanya perkembangan seperti ini, kekuasaan untuk membuat hukum sepenuhnya dimiliki oleh negara, sehingga tidak ada individu atau kelompok di dalam negara yang bisa menciptakan hukum. Konsep revolusioner di balik prinsip positivisme legislatif ini adalah bahwa hanya ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga legislatiflah yang bisa disebut hukum. Pada level praksis, hal itu berarti bahwa pembuatan undang-undang harus didelegasikan kepada organ khusus negara yang berhak membuat hukum dan organ itu betul-betul terpisah dari organ negara lainnya. Karena tidak ada lembaga lain yang berhak membuat hukum, maka secara teori ketentuan yang memiliki kekuatan hukum di negara hanyalah yang ditetapkan oleh lembaga legislatif formal, atau aturan-aturan dari lembaga administratif negara lainnya, yang diberi kekuasaan oleh lembaga legislatif untuk mengeluarkan hukum. Itulah sebabnya mengapa tradisi hukum sipil hanya mengakui undang-undang dan peraturan negara lainnya sebagai sumber hukum. Di sebagian jurisdiksi hukum sipil, adat memang juga diterima sebagai sumber hukum lain selama tidak melanggar penerapan undang-undang atau regulasi negara. Tapi penerimaan ini menimbulkan persoalan teoretis, karena ia bisa merusak prinsip dasar positivisme negara serta ideologi pembedaan antara cabang legislatif dari cabang-cabang lainnya dalam pemerintahan.
Dampak dari prinsip sentralisme hukum negara dan pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadikan tradisi hukum sipil lebih memfokuskan diri pada gagasan untuk menuangkan setiap hukum ke dalam buku yang ditulis secara detil. Usaha ini sebagian didukung oleh keinginan tradisi hukum sipil untuk menempatkan sistem hukum yang sederhana dan gamblang sesuai dengan kebutuhan terhadap masyarakat baru dan pemerintahan baru. Cara paling efektif untuk melakukan tugas ini adalah dengan merumuskan hukum sesederhana mungkin sehingga orang awam pun bisa memahaminya dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka tanpa perlu meminta bantuan pengacara. Ini juga berlaku bagi prinsip pemisahan legislatif dari yudikatif, dalam arti kekuasaan pembuat hukum yang terletak pada badan legislatif tidak boleh diintervensi oleh lembaga yudisial, karena kejelasan hukum sangat dibutuhkan. Karenanya para ahli hukum sipil selalu menegaskan bahwa hakim harus menolak dari kekuasaan untuk membuat hukum, karena tugas mereka hanya menerapkan hukum. Jadi menurut doktrin pemisahan kekuasaan, pengadilan sedapat mungkin harus "menolak menjalankan fungsi penafsiran dan harus diwajibkan untuk mencari solusi bagi persoalan penafsiran undang-undang kepada badan legislatif itu sendiri".12 Kalau demikian, hukum yang dibuat oleh badan legislatif harus lengkap, menyeluruh, dan jelas agar bisa menjamin dua aktivitas membuat dan menerapkan hukum tetap terpisah. Pada gilirannya pemisahan ini melahirkan ideologi kodifikasi dalam tradisi hukum sipil. Perhatian yang besar untuk menuangkan hukum ke atas kertas sebelum kasus serupa terjadi telah menjadikan aktivitas mengkodifikasikan hukum salah satu karakteristik paling penting dari tradisi hukum sipil.13
Tersebarnya ideologi kodifikasi di Eropa selama dekade awal abad ke-17 betul-betul merupakan titik kulminasi revolusi intelektual tersebut di atas yang meliputi benua itu sebelum munculnya negara-bangsa versi Barat. Di sini, kodifikasi sistematis hukum sipil Perancis yang disusun oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh Napoleon I, merupakan sebuah model bagi kitab undang-undang sipil di berbagai tempat di Eropa dan Amerika Latin selama bagian pertama abad ke-19.14 Undang-Undang Sipil Napoleon sendiri yang diberlakukan pada awal 1804, berhasil merepresentasikan pemikiran hukum progresif saat itu. Ia mewujudkan cita-cita hukum sipil bahwa hukum sedapat mungkin harus bisa diakses dengan mudah dan jelas oleh masyarakat awam. Dalam hal ini, kodifikasi hukum Napoleon yang secara resmi diundangkan pada saat yang sama membatalkan seluruh hukum Romawi yang ada sebelumnya. Ketetapan administratif, Undang-Undang, dan adat lokal dalam bidang apa pun diliputi oleh undang-undang baru itu.15 Pada periode berikutnya, undangundang dan sejumlah peraturan lainnya yang kemudian dibuat di bawah administrasi Napoleon masih menjadi landasan bagi hukum Perancis saat ini dan juga berfungsi sebagai model bagi undangundang hukum sipil di seluruh Eropa serta belahan dunia lainnya, termasuk negara-negara Asia.16 Meski dikagumi, undang-undang Perancis itu bukannya tanpa kritik, terutama di Jerman di mana gaya pemikiran hukum Friedrich Karl von Savigny dianggap sebagai ekspresi gagasan hukum yang lebih baik dalam sistem hukum Jerman saat itu.17 Berbeda dari konsep kodifikasi ala Perancis sebagai cerminan keyakinan terhadap hukum alam sekuler, gagasan hukum sipil Jerman tampaknya lebih didasarkan pada pandangan bahwa hukum masyarakat tidak boleh dilepaskan dari akar sejarahnya. 18
Menurut Pemikiran Savigny (dan para pengikutnya), yang biasanya dianggap sebagai protagonis "mazhab sejarah" (historical school), hukum merupakan derivasi "kesadaran bersama" masyarakat tertentu, karena hukum pada dasarnya adalah Volksgeist ("ruh masyarakat"); jadi bagi mereka hukum bukanlah entitas yang bisa dicangkokkan ke sembarang tempat.19 Karena proses pembuatan hukum sipil harus didasarkan pada pemahaman hukum masyarakat pribumi maka rekonstruksi sistem hukum Jerman dilakukan sesuai dengan prinsip dan karakter yang menyatu dengannya. Akibatnya, sistem hukum yang dikembangkan di Jerman berlainan dengan trend sistem hukum di negara-negara Eropa lainnya walaupun sama-sama mengadopsi sistem hukum sipil, di mana kodifikasi dibuat dengan jelas dan mudah diakses sehingga peran pengacara menjadi sangat sedikit. Dari sudut pandang sistem hukum Jerman, peran pengacara tidak bisa diabaikan. Bahkan dalam pandangan Jerman, pembuatan hukum tidak bisa terjadi tanpa melibatkan para pengacara dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat awam.20 Itulah mengapa Jerman tidak dengan serta merta menolak institusi-institusi hukum lama seperti halnya yang dilakukan para pengacara sipil Perancis; sebaliknya, Undangundang Sipil Jerman (Brgerliches Gesetzbuch, BGB) tahun 1896 bahkan menetapkan jalan yang berlawanan dengan memunculkan pengkajian hukum Romawi di Jerman di tengah maraknya penolakan terhadap hukum Romawi di Eropa.21 Jadi, sebagai usaha alternatif untuk menemukan prinsip-prinsip hukum (yang merupakan alternatif bagi corak hukum alam sekuler Perancis), Jerman berusaha mencari prinsip-prinsip mendasar dari konteks sejarah negeri mereka sendiri, karena menganggap kodifikasi
hukum tertulis lebih merupakan alat bagi pengacara dan bukan bagi orang awam.22 Penjelasan tentang tradisi pemikiran hukum Jerman dan Perancis di atas memperlihatkan bahwa dalam perkembangannya ideologi kodifikasi dibangun sesuai dengan sikap yang berbedabeda terhadap masa lalu.23 Namun kedua tradisi tersebut memiliki persamaan di mana kodifikasi hukum sipil muncul sebagai akibat ideologi revolusi di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terpisah, tapi sebagai sesuatu yang melekat pada gagasan tentang negara-bangsa monolitis yang sedang bertumbuh. Karenanya sejarah tradisi hukum sipil sangat terikat pada gerakan ideologi ini; bahkan gerakan seperti inilah yang menciptakan karakter hukum sipil yang berbeda bila dibanding dengan tradisi common law, atau tradisi hukum lainnya yang memiliki latar belakang ideologi berbeda. Menariknya, hanya dengan memahami gerakan seperti itulah maka perkembangan hukum di negara-negara yang memiliki hukum sipil di luar benua Eropa bisa dimengerti. B. Konsep Hukum Substantif Sesuai dengan ideologi yang digambarkan di atas, hukum sipil muncul sebagai tradisi hukum yang unik, baik dalam karakternya yang formal maupun pendekatannya yang sekuler. Ia bersifat formal karena perkembangan sistem hukum sipil tidak bisa dipisahkan dari pembentukan organ negara yang ditunjuk secara khusus untuk membuat undang-undang atas nama orang-orang yang hidup di dalam batasan negara tersebut. Jadi aspek substantif hukum sipil dikembangkan sesuai dengan jurisdiksi masing-masing negara; karena setiap negara mengembangkan sistem hukumnya masing-masing maka substansi hukum hanya
bisa diterapkan kepada penduduk masing-masing negara. Ideologi kodifikasi juga berkontribusi terhadap karakter formal hukum sipil di mana proses pembuatan hukum hanya terdapat di tangan badan legislatif negara. Lebih jauh, karena secara teoretis negara adalah satu-satunya agen pembuat hukum, maka ketentuan yang diproduksi dalam sebuah sistem hukum bersifat sekuler. Tidak ada persoalan apakah hukum itu berasal dari pejabat keagamaan, atau mencerminkan suatu dasar keagamaan, hukum atau filsafat tertentu, ia sama sekali tidak memiliki nilai-nilai kesakralan apa pun. Klasifikasi hukum adalah salah satu aspek paling utama dalam sistem hukum sipil. Dalam ajaran dasar hukum sipil, semua aturan hukum harus dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat. Meskipun cakupan pembagian ini berbeda-beda di antara berbagai negara yang berbeda (karena ia mencerminkan analisis teoretis dan pemikiran yang dikembangkan pada masing-masing negara),24 pada dasarnya klasifikasi hukum tersebut berangkat dari logika yang sama, yaitu untuk memfasilitasi doktrin formalitas hukum seperti dikembangkan dalam pengajaran dan penyampaian tradisi hukum sipil. Oleh sebab itu, pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat bisa dilihat baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis. Secara teoretis, klasifikasi itu dibuat untuk membedakan secara lebih jelas antara subjek-subjek hukum yang berbeda yang secara lebih natural mungkin bisa dikelompokkan di bawah judul hukum tertentu seperti hukum perdata, hukum niaga, hukum acara kriminal dan lain sebagainya. Susunan seperti itu juga mempunyai keuntungan praktis, yaitu bisa memasukkan persoalan-persoalan hukum tertentu ke dalam jurisdiksi masing-masing pengadilan, atau
menerapkan berbagai prinsip penafsiran kepada aturan-aturan yang menjadi bagian dari kategori-kategori tertentu.25 Pembagian hukum sipil menjadi dua kategori besar publik dan privat itu sesungguhnya berakar pada tradisi hukum Romawi, karena sudah jamak diketahui bahwa hukum Romawi membagi semua hukum menjadi dua bidang publik dan privat.26 Para ahli hukum bangsa Romawi memahami hukum publik sebagai aturan hukum yang mengatur urusan komunitas dan hubungan antar komunitas serta tindakan hukum otoritas (pemegang kekuasaan) di mana individu-individu adalah subjeknya. Sementara hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pribadi dengan pribadi lain sebagai individu, meskipun dalam hukum Romawi saat itu perhatian lebih difokuskan untuk sekadar membedakan antara hukum negara dan yang berhubungan dengan hak miliknya (ius publicum) dan hukum individu dan keluarganya (ius privatum) ketimbang mensistematiskan hukum menjadi dua wilayah besar yang kita temukan dalam tradisi hukum sipil modern.27 Oleh karena itu, doktrin pengklasifikasian tersebut tidak bisa diisolasi dari latar belakang kesejarahan tradisi hukum sipil itu sendiri. Hal ini sangat benar karena secara historis, perbedaan antara hukum publik dan hukum privat tersebut dalam praktiknya tidak dikenal di Eropa pada abad pertengahan. Makanya gagasan pengklasifikasian hukum itu merupakan respon terhadap model hukum kesatuan yang lazim di anut di negaranegara Eropa feodal. Hukum feodal, di mana atribut kepemilikan dan atribut kekuasaan tidak dibedakan secara memadai dan seringkali diposisikan secara sama, ditantang oleh munculnya gagasan pembagian hukum sipil. Bahkan di Eropa sekalipun sesungguhnya ada teori pembagian hukum, tapi teori itu tidak berusaha membedakan wilayah publik dan wilayah privat;
pembagian yang ada dalam teori itu malah didasarkan pada hubungan berbagai kelompok orang,28 seperti halnya dalm hukum feodal, hukum manorial, hukum servitary dan lain sebagainya. Bahkan di sini batasannya tidak jelas, sehingga hukum sipil bisa mengintrodusir perubahan besar-besaran hingga kini dalam organisasi hukum. Dengan munculnya negara terpusat, praktik pembedaan antara hukum publik dan hukum privat memberikan momen kepada munculnya tradisi hukum sipil yang berkarakter modern. Meskipun memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, dan karenanya juga memiliki teori klasifikasi hukum yang juga berbeda,29 semua negara yang mempraktekan hukum sipil sepakat dengan beberapa prinsip dasar penyusunan sistem hukum menjadi dua bagian besar, yaitu hukum publik dan hukum privat.30 Di seluruh negara tersebut, klasifikasi hukum secara umum mengikuti pembagian hukum menjadi beberapa undangundang. Makanya, hukum privat, hukum niaga, prosedur sipil, hukum pidana, dan prosedur kriminal biasanya disusun dalam undang-undang terpisah. Bagaimanapun juga, perbedaan paling penting antara hukum publik dan hukum privat adalah bahwa kalau sebagian besar hukum privat itu dikodifikasikan, maka tidak begitu halnya dengan hukum publik. Ini tidak berarti sebagian besar hukum publik bukan hukum yang diundangkan; pernyataan itu hanya menunjuk pada fenomena umum di negara yang memiliki hukum sipil bahwa bagian-bagian hukum publik biasanya tercerai berai dalam berbagai pengundangan khusus dan tidak disistematiskan dalam satu perundang-undangan. Jadi aturan dan prinsip umum yang terkait dengan hukum masih sangat banyak yang belum diundangkan.
Dari doktrin pembagian hukum itu kita bisa melihat bahwa dalam banyak hal undang-undang sipil mengadopsi teori kategori yang logika dasarnya dikembangkan pada masa Romawi. Namun, muatan substantif hukum di negara berhukum sipil dibuat oleh dan untuk diri mereka sendiri karena pada dasarnya untuk merespon kebutuhan hukum dan menyesuaikan hukum dengan perubahan waktu dan kondisi. Bahkan konstruksi tradisi hukum yang dijelaskan di atas bisa terlihat dalam berbagai aspek hukum substantif tersebut. Ia tercermin dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena terutama berdasarkan aspek inilah hukum itu mendefinisikan, mengatur, dan mengelola hubungan individuindividu (seperti dalam hukum privat) dan antara individu dan negara (seperti dalam hukum publik). Karenanya substansi hukum pada dasarnya hanyalah manifestasi weltanschauung yang dikembangkan pada masing-masing era. Orang mungkin menggunakan logika yang sama dalam membangun hukum walaupun dari sisi muatannya hukum itu berbeda dan beragam. Itulah yang tampak dalam sejarah perkembangan substansi hukum sipil. Semangat untuk mensekulerkan hukum bersamaan dengan gerakan menghilangkan feodalisme dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih egaliter berdampak pada konstruksi sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai baru. Dalam hal ini, selama periode revolusi berlangsung, pemerintahan negara-negara yang menerapkan hukum sipil berkomitmen untuk memperkuat perubahan hukum itu dalam serangkaian undangundang baru. Di Perancis misalnya, akibat revolusi intelektual, hubungan keluarga tidak lagi dilihat dari sudut pandang tradisional, di mana keluarga dipusatkan pada suami (yang mewarisi otoritas dan kekuasaan yang besar dari tradisi keluarga paternal Romawi),31 tapi ditransformasikan sesuai dengan prinsip-
prinsip kebebasan dan kesetaraan gender.32 Jadi istri dinyatakan setara dengan suami; bahkan sejalan dengan semangat revolusi, perempuan itu dianggap memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun pemikiran yang revolusioner ini tidak serta merta dikodifikasikan di Perancis, pada awal abad ke-20 undang-undang dalam banyak hal telah berhasil mengurangi otoritas suami atas istri serta memberi si istri kapasitas hukum yang penuh. Lebih jauh, undang-undang yang diundangkan pada tahun 1970 dirancang untuk menghilangkan pengaruh ajaran tradisional bahwa "suami adalah kepala keluarga" dan diganti dengan prinsip baru yang lebih egaliter dimana suami dan istri mempunyai kekuasaan bersama dalam membuat keputusan keluarga.33 Menariknya, kecenderungan untuk memberikan hak matrimonial kepada istri yang lebih besar seperti itu ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain. Pada tahun-tahun belakangan, trend yang berkembang mengarah pada kemitraan dalam hak kepemilikan yang diperoleh setelah pernikahan di mana masing-masing pihak (suami dan istri) tetap menguasai hak milik yang masing-masing dapatkan sebelum masuk ke dalam hubungan perkawinan.34 Ketika revolusi hukum berlangsung, pernikahan di Eropa mengalami evolusi menjadi tindakan yang sangat bersifat sipil di mana upacara pernikahan dirayakan sebelum peresmian secara sekuler disahkan sesuai dengan hukum; lebih jauh, otoritas orang tua dibatasi dan persetujuan orang tua tidak lagi disyaratkan bagi pernikahan anak yang sudah berusia di atas 21 tahun.35 Menariknya, hukum perceraian juga mengalami perubahan serupa. Gerakan kesetaraan gender yang merembes di Eropa pada abad ke-19 telah mengikis nilai-nilai kesatuan keluarga Kristen di mana perceraian dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dengan adanya revolusi Perancis, perceraian
dibuat lebih mudah dan bahkan diizinkan melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama.36 Para perancang hukum Perancis berargumen bahwa jika para individu tidak merasa tergugah oleh ajaran agama tentang pernikahan yang abadi sehingga berusaha bercerai, maka bukanlah tugas pembuat hukum untuk menghalangi pasangan yang tidak bahagia tersebut untuk mengakhiri ikatan pernikahan dan masuk ke dalam ikatan hukum yang baru. Karena itu, terdapat sejumlah syarat yang ditetapkan sebagai landasan bagi perceraian, yaitu perzinahan, terkena hukuman karena kejahatan yang sangat serius, kebiasaan berjudi, berlaku boros, perlakuan kejam atau penghinaan serius.37 Negara-negara berhukum sipil lainnya di Eropa mengikuti kecederungan prinsip seperti ini, dan hanya berbeda pada aspekaspek detilnya.38 Gagasan revolusioner yang diadopsi oleh undang-undang Napoleon juga bisa dilihat imbasnya dalam hukum pewarisan. Dalam persoalan pewarisan nir-wasiat misalnya, para pembuat undang-undang mendasarkan hukum mereka pada dua prinsip dasar: pertama, tidak ada pembedaan terhadap harta warisan orang yang meninggal; kedua, bagian yang sama harus diberikan kepada semua ahli waris yang berada pada tingkat yang sama dalam hubungan keluarga. Karena itu, keuntungan yang biasanya diberikan kepada anak pertama atau anak laki-laki dihilangkan.39 Berdasarkan prinsip itu, undang-undang tersebut kemudian menekankan bahwa harta warisan utamanya diberikan kepada anak atau keturunan lainnya. Cucu yatim menerima bagian warisannya berdasarkan prinsip perwakilan seperti halnya anak tidak sah, meskipun yang kedua ini tidak bisa mewarisi dalam jumlah yang sama dengan anak sah. Karena pewarisan difokuskan kepada anak maka istri tidak termasuk sebagai pihak yang
menerima warisan kalau tidak ada keturunan. Tentu saja ini adalah contoh diskriminasi terhadap perempuan, namun di abad ke-20, hak pasangan yang masih hidup atas warisan semakin diakui, seiring dengan semakin majunya sikap terhadap kesetaraan gender. Sekarang, suami atau istri yang masih hidup bahkan bisa mewarisi keseluruhan harta warisan bila orang yang meninggal itu tidak memiliki kerabat sedarah pada tingkat tertentu dalam keanggotaan keluarga. Lebih jauh, dalam hukum wasiat, pewasiat bisa dengan bebas membuat surat wasiat meskipun tidak ada saksi. Dalam kasus ini, baik Jerman maupun Perancis tampaknya mengikuti pola yang sama, yaitu mengizinkan secara legal orang membuat wasiat baik secara formal maupun secara informal, dan menuntut pewasiat menyusun wasiat itu secara tertulis, diberi tanggal dan ditandatangani sendiri olehnya.40 Bahkan di Jerman saat ini, wasiat publik bisa dibuat secara lisan di depan petugas pemerintah yang akan mencatatnya dalam format tertulis atau pewasiat sendiri menyatakan wasiatnya dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada petugas. Baik Perancis maupun Jerman tampaknya juga berkoordinasi dalam membatasi wasiat maksimal setengah dari keseluruhan harta yang dimiliki agar tidak menghabiskan bagian warisan yang akan diberikan kepada anak cucu atau keturunan.41 Hal penting lainnya yang dikembangkan dalam sistem hukum sipil sejak awal adalah tentang hak milik. Sebagai hubungan yang normal antara orang dengan barang, kepemilikan dipahami sebagai hak yang menyeluruh, mutlak, bebas dan jelas. Dalam hal ini, Perancis dan Jerman tampaknya menerima gagasan bahwa penggunaan hak milik pribadi sampai ke tingkat tertentu dikenai berbagai bentuk batasan yang ditetapkan berdasarkan kepentingan publik.42 Di Jerman, hal ini sangat penting terkait
dengan tanah pertanian yang bisa dibagi dan diredistribusikan untuk menghasilkan produksi yang lebih bagus. Ragam barang dibagi menjadi dua klasifikasibergerak dan tidak bergerak. Yang pertama mencakup seluruh barang yang berada pada tempat yang tidak tetap, dan yang kedua adalah semua barang yang tidak masuk ke dalam kategori pertama.43 Para pembeli barang yang bergerak langsung menjadi pemiliknya, dan tidak ada orang yang bisa membuktikan paling berhak atas kepemilikannya kecuali hak milik itu sebelumnya hilang atau dicuri. Hak pakai (usufruct) dimungkinkan terjadi dalam undang-undang sipil Perancis, meskipun hak atas aset tidak pernah menyaratkan orang yang menguasai aset untuk melakukan apa pun.44 Hak atas tanah bisa diperoleh dalam sepuluh atau dua puluh tahun bila si pemilik yakin dia adalah pemilik yang sesungguhnya. Menyangkut hukum hipotek, sejak tahun 1798 undang-undang baru sebetulnya telah dikembangkan untuk menetapkan sistem yang komprehensif untuk mendaftar semua peralihan hak atas tanah dan hak hipotek. Dengan adanya aturan tersebut, pembeli bisa yakin tentang perbedaan yang jelas antara membeli tanah dari pemilik biasa dan mendapatkan tanah sebagai hipotek. Para perancang undang-undang kemudian memutuskan untuk menerapkan sistem pendaftaran hanya untuk hibah dan hipotek berdasarkan kontrak dan membiarkan penjualan properti dan beberapa hipotek legal tidak terdaftar. Meskipun ketentuan ini membuat kreditor atau pembeli tidak memiliki informasi yang memadai, undang-undang itu tetap dipertahankan sampai diperbaiki melalui reformasi undang-undang yang berturut-turut terjadi pada tahun 1855, 1935, dan 1955.45 sebaliknya, di Jerman kasus seperti ini kelihatannya tidak begitu menjadi persoalan, karena semenjak awal undang-undang telah menyatakan bahwa
setiap pembuatan, pengalihan, penghalangan atau pembatalan hak atas tanah disyaratkan adanya registrasi dari Badan Pencatat Tanah (Grundbuch), di samping perlu ada kesepakatan antar kedua pihak.46 Berlawanan dengan kategori di atas yang tampaknya telah mengalami perubahan ketika munculnya revolusi intelektual dalam hukum sipil, hukum kontrak dan ganti rugi (tort) relatif tidak tersentuh oleh gelombang transformasi ini. Di Perancis, revolusi tersebut tidak banyak berdampak pada hukum ini; bahkan para perancang undang-undang sipil di negeri itu dalam banyak kesempatan hanya menyatakan kembali hukum yang sudah dikembangkan selama berabad-abad sebelumnya. Undangundang Perdata Perancis menetapkan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak dengan informalitas dan kebebasan. Menurut undangundang tersebut, kesepakatanlah yang memberikan dampak hukum terhadap sebuah kontrak.47 Namun tidak banyak aspek hukum yang disentuh oleh undang-undang itu. Menyangkut hukum ganti rugi, keseluruhan persoalan hanya dibahas dalam lima pasal pendek. Jadi landasan umum bagi pertanggungjawaban hukum di sini adalah bahwa setiap tindakan seseorang yang menyebabkan orang lain terluka maka orang yang melukai tersebut harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang terluka. Pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang tersebut mengatur pertanggungjawaban hukum bagi kerusakan yang disebabkan oleh sesuatu benda, binatang, anak-anak, dan pekerja, meskipun undang-undang itu masih memberi tugas kepada hakim untuk menyempurnakan sistem hukum kerugian secara menyeluruh.48 Di Jerman, undang-undang keperdataan serupa tampaknya juga mengikuti pola yang sama. Para pihak dibebaskan untuk mengatur hubungan mereka dengan kontrak, meskipun mereka
juga mungkin dibatasi oleh larangan-larangan tertentu berdasarkan ukuran moral atau praktik yang lumrah dilakukan (kebiasaan). Praktik kebiasaan inilah yang memberi ruang bagi perubahan dalam mengantisipasi perubahan kondisi secara mendadak. Menyangkut persoalan delik, undang-undang sipil mereka mengatur bahwa siapa pun diharuskan memberikan kompensasi bagi kerusakan apapun yang ditimbulkan, baik secara sengaja atau karena kelalaian, terhadap nyawa, tubuh, kesehatan, hak milik, dan hak mutlak orang lain dalam bentuk apapun.49 Diskusi di atas hanya memberikan beberapa contoh bagaimana revolusi intelektual saat itu berhasil melakukan perubahan dalam bidang hukum di benua Eropa, terutama setelah peralihan abad ke-19. Fenomena yang dijelaskan di atas, tampaknya memperlihatkan bahwa dalam kenyataan transformasi hukum memiliki dampak langsung lebih banyak pada hukum privat dibanding hukum publik. Sejarah tradisi hukum sipil agaknya mendukung gagasan bahwa mewajibkan individu untuk menghormati hukum selalu jauh lebih mudah ketimbang mewajibkan hal yang sama kepada negara. Mungkin ini juga karena kecenderungan untuk menempatkan proses pembuatan hukum hanya di tangan aparat negara. Bahkan, pembagian antara hukum publik dan hukum privat biasanya dibuat untuk merespon gagasan hukum sebagai sesuatu yang berasal dari "tatanan alami sesuatu yang lebih dulu sekaligus lebih tinggi dari konsep 'negara' apa pun".50 Jadi, tidaklah mengherankan kalau selama berabadabad hanya aspek hukum privat yang diberi perhatian serius oleh kalangan akademis, sementara hukum publik dianggap oleh banyak kalangan sebagai "subjek yang berbahaya".51 Banyak aspek hukum publik, bahkan pada periode awal, dikembangkan di bawah bayang-bayang hukum privat, meskipun lebih sering dalam
banyak hal melibatkan negara. Namun berbagai ketentuan hukum publik menjadi semakin sistematis dan mendapatkan posisi setara dengan hukum privat seiring dengan penguatan institusi politik dan mekanisme pemerintahan Negara-bangsa di sejumlah negara Eropa. Gelombang perubahan ini kemudian mempengaruhi dan mendorong berbagai bentuk transformasi hukum di berbagai sudut dunia yang jauh dari tempat kelahiran tradisi hukum sipil itu sendiri. Melalui berbagai kontak antara orang-orang Eropa dan non-Eropa, tradisi hukum ini diekspor ke seluruh dunia, dan mempengaruhi pembuatan hukum di masing-masing wilayah. Terutama di negara-negara Asia dan Afrika, media yang paling lazim bagi perjumpaan itu adalah melalui kolonialisasi, yang pada saat itu sebagian negara Eropa langsung berusaha memasukkan gagasan hukum sipil ke negeri baru itu. Berkat proses kolonialisasi inilah Belanda membawa tradisi hukum sipil ke Indonesia, sebuah proses yang dimulai dengan pendudukan pada abad ke-16. Masalah inilah yang akan dibahas pada bagian berikut. C. Tradisi Hukum Sipil dan Penjajahan Belanda di Indonesia Ketika pada akhir abad ke-17 perusahaan dagang Belanda VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sampai di Nusantara,52 Belanda sendiri saat itu tengah melakukan revolusi menentang tirani bangsa Spanyol yang kejam dan berusaha merebut kemerdekaan. Pada awalnya hanya provinsi bagian utara saja yang mendapatkan kemerdekaan penuh sementara bagian Selatan masih di bawah kekuasaan Spanyol dan kemudian jatuh ke tangan Austria selama lebih dari seabad (sejak tahun 1648 seluruh provinsi sudah tidak diperintah lagi oleh Spanyol).53 Selama perang Napoleon tahun 1795, Belanda Serikat menjadi
Republik Batavia, dan kemudian menjadi kerajaan di bawah kekuasaan saudara Napoleon, Louise Napoleon. Setelah perdamaian Vienna tahun 1815, Belanda bagian Utara menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Istana Kuning, Sementara Belanda bagian Selatan memberontak pada tahun 1839, dan kemudian menjadi kerajaan Belgia setelah bersatu dengan Utara.54 Jadi cukup adil kiranya mengatakan bahwa ketika orang-orang Belanda memulai misi mereka di kepulauan Indonesia, situasi politik di negara mereka sendiri masih berada dalam keadaan berfluktuasi, di mana bentuk pemerintahan masih terombang ambing di antara bentuk republik dan kerajaan. Tradisi hukum di Belanda, semenjak awal abad pertengahan, sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Jerman, di mana peran adat lokal masih memiliki posisi yang penting.55 Dalam perjalanan waktu, hubungan dekat dengan Perancis dan Jerman membukakan pintu bagi Belanda untuk menerima hukum Romawi. Penerimaan ini pada dasarnya untuk merespon kebutuhan terhadap sistem hukum yang lebih umum dan lebih baik ketimbang yang disediakan oleh tradisi hukum setempat. Pengaruh hukum Romawi semakin meluas pada abad ke-15, terutama dengan didirikannya Universitas Louvain oleh Duke of Brabant tahun 1425. Oleh karena itu, apa yang kemudian disebut dengan hukum Roma-Belanda pada dasarnya adalah hukum Romawi seperti yang dikenal saat itu yaitu Corpus Juris Civilis sebagaimana yang diedit dan ditafsirkan oleh para komentator dan penerus mereka, dan digaungkan oleh para sarjana Perancis, Jerman, Italy, Spanyol dan belakangan juga oleh sarjana Belanda.56 Tradisi hukum inilah yang dibawa oleh Belanda ke kepulauan Indonesia, di mana mereka pertama kali datang sebagai "pedagang"57 dan kemudian menjadi "penguasa".58
Belanda sebetulnya mengunjungi kepulauan Indonesia pertama kali sebagai pedagang, tidak jauh berbeda seperti halnya pedagang Muslim yang datang lebih dahulu ke daerah itu. Salah satu perbedaan antara kedua invasi pedagang tersebut tampaknya adalah semangat mereka untuk menyebarkan gagasan hukum ke kalangan masyarakat pribumi. Kalau bagi pedagang Muslim penyebaran tradisi hukum Islam berjalan seiring dengan penyebaran ajaran agama mereka, maka Belanda di lain pihak, terutama pada fase pertama penjajahannya, tampaknya tidak menganggap penyebaran tradisi hukum sipil sebagai misi yang utama dalam kedatangan mereka ke Nusantara. Pada awal kehadiran Belanda, kegiatan bisnis mereka didominasi oleh tugas untuk mengeksploitasi sebanyak dan secepat mungkin daerahdaerah penghasil bahan pertanian, sehingga persoalan hukum masyarakat pribumi sama sekali tidak diacuhkan. Perusahaan dagang Belanda tampaknya enggan terlibat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, terutama kalau persoalan tersebut tidak berhubungan kepentingan bisnis mereka. Seperti dijelaskan oleh John Ball dengan gamblang, "Kebijakan pemerintah terutama didasarkan pada persoalan apakah masalah itu akan menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap VOC, dan apakah masalah itu bisa mengakibatkan kerusakan sedikit mungkin".59 Hal itu disebabkan karena kepentingan VOC dan para pembantunya secara umum hanya untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin atau mengamankan pasarnya. Oleh karena itu penyebaran tradisi hukum sipil tidak begitu mendapatkan perhatian dari mereka. Sementara itu beberapa peraturan yang diundangkan sebagian besar hanyalah bersifat de facto, yang dikembangkan untuk melindungi status quo dan
terlebih penting lagi untuk mendukung misi perdagangan mereka.60 Sikap semacam itu sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani persoalan hukum masyarakat pribumi. Waktu dan energi VOC dihabiskan terutama untuk misi perdagangan; sangat sedikit perhatian yang diberikan untuk perencanaan dan pemerintahan. VOC mungkin sudah menyadari semenjak awal bahwa kekuasaan bisa mendukung usaha perdagangannya, tapi mereka menahan diri mewujudkan pilihan tersebut karena biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan ambisi itu sangat besar. Akibatnya, hanya hukum-hukum yang sangat penting untuk kepentingan bisnis mereka saja yang sengaja dibuat oleh Belanda selama periode dominasi perdagangan mereka di daerah tersebut. Karenanya, meski periode kekuasaan VOC di Nusantara bertahan selama dua abad, dan menyebabkan sedikit pergeseran dalam kecenderungan untuk sekadar melakukan petualangan bisnis menjadi "bisnis sekaligus kekuasaan". Hal itu ditunjukkan oleh fakta bahwa pada masa kekuasaan mereka lebih banyak diundangkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan ketimbang ketentuan yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kecenderungan mereka hanya akan membuat undangundang ketika hal tersebut berhubungan dengan pertimbangan bisnis, yang berarti VOC pada awalnya mengabaikan kepentingan membuat pemerintahan di Nusantara ini. Meskipun Belanda mungkin telah mengambil pelajaran dari pengalaman penjajah Eropa dalam menata daerah kekuasaan di luar negeri, mereka tampaknya tidak begitu tertarik melakukannya, kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting atau menguntungkan bagi VOC. Mereka misalnya sangat enggan
memisahkan antara wilayah administrasi dan sistem peradilan, terutama yang berhubungan dengan pengadilan lokal; oleh karena itu, hingga dibubarkannya VOC pada tahun 1800, administrator setempat biasanya diberi kepercayaan dengan dua fungsi, yaitu eksekutif dan yudikatif.61 Di samping itu, keseragaman juga jarang menjadi prioritas bagi VOC dalam memerintah penduduk setempat. Bahkan di Jawa, pusat usaha perdagangan mereka, penduduk pribumi tidak diatur dengan kebijakan yang sama.62 VOC bahkan menghancurkan kekuatan politik penguasa lokal, tapi sejauh mana mereka menjalankan kendali atas mereka tergantung pada kemungkinan mereka akan melakukan revolusi atau sejauh mana daya tarik perdagangan yang ditawarkan oleh daerah tersebut. Jadi, hanya kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya saja di mana tugas-tugas administratif kebanyakan dilakukan oleh petugas VOC Eropa, sementara di luar kota-kota ini sebagian besar tanggungjawab masih berada di tangan penduduk pribumi, sehingga beberapa orang Jawa memiliki kontak langsung dengan bangsa Eropa.63 Semenjak membangun landasan kekuasaannya pada seperempat pertama abad ke-17, pengalaman VOC di Hindia Belanda menyadarkannya tentang perlunya sistem hukum yang lebih maju; namun Belanda tampaknya tidak tertarik dengan persoalan hukum masyarakat pribumi kecuali kalau itu penting untuk mempertahankan disiplin para pelayan mereka atau untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Pada saat inilah Belanda menyadari administrasi peradilan penting untuk kepentingan bisnis mereka, terutama dengan meluasnya kekuasaan dagang mereka ke seantero Nusantara. Meskipun begitu, pengaruh Belanda tidak bisa menembus daerah-daerah terpencil dan mereka terpaksa berkonsentrasi di kota-kota di
sekeliling wilayah pusat kekuasaan kolonial, Batavia. Administrasi peradilan yang berorientasi Eropa dimulai dengan penunjukan Bailiff oleh Gubernur Jenderal Coen pada tanggal 29 Maret 1620 sebagai penguasa kota, jurisdiksi Batavia dan daerah sekitarnya. Tidak lama setelah itu, beberapa jabatan di bidang hukum juga dibuat untuk membantu Bailiff tersebut. Pada tanggal 24 Juni 1620 didirikan College Aldermen untuk Batavia dan daerah bekas kerajaan Jakarta, dan tanggal 15 Agustus 1620 VOC juga mendirikan pengadilan yang kemudian berkembang menjadi Dewan Peradilan (Raad van Justitie) di Batavia.64 Meskipun institusi hukum ini dirancang terutama untuk membantu pelayan-pelayan dan serdadu VOC untuk mencari keadilan, tapi pendirian institusi semacam itu telah menandai perkembangan awal tradisi hukum sipil di Nusantara. Dibalik kenyataan tidak semua bagian Hindia Belanda berada di bawah pengaruh hukum sipil (karena VOC tampaknya tidak mampu menjangkau daerah-daerah terpencil yang jumlahnya banyak sekali), pendirian pengadilan pusat serta institusi hukum di Batavia merepresentasikan prasasti dalam sejarah penggunaan logika hukum sipil di Nusantara. Semenjak periode awal ini VOC menerapkan hukum yang sebagian besar landasannya menggunakan landasan yang dipakai di Belanda, sehingga baik isi maupun institusi hukum yang merupakan bagian penting hukum kolonial menyerupai apa yang sudah ada di Belanda. Ini sesuai dengan prinsip "kesesuaian" (concordancy) yang menetapkan bahwa hukum yang diterapkan di HindiaBelanda secara umum harus sesuai dengan hukum di Belanda. Prinsip ini sebenarnya telah diterapkan semenjak tahun 1621, ketika Dewan Tujuh Belas merekomendasikan agar wilayah kekuasaan VOC mengadopsi hukum-hukum Negara Belanda dan
West Friesland, terutama hukum yang berkaitan dengan hukum waris yang dijelaskan dalam Ketetapan Politik tanggal 1 April 1580 dan penafsiran atas ketetapan itu tertanggal 13 Mei 1594 dan Dekrit 18 Desember 1599. Dewan tersebut juga menetapkan bahwa kalau sebuah kasus tidak tercakup dalam hukum ini, maka hukum sipil khusus seperti yang dipraktikkan di Belanda Serikat harus dijadikan rujukan. Ketentuan yang sama juga diundangkan pada tanggal 16 Juni 1625 untuk mendukung prinsip kesesuaian, dan kemudian pasal 1 Instruksi tahun 1632 lebih jauh menetapkan bahwa "Peradilan di Batavia dan daerah-daerah lain di bawah kekuasaan VOC diatur sesuai dengan instruksi dan adat yang merupakan aturan yang diterapkan di provinsi-provinsi Belanda Serikat baik dalam kasus sipil maupun kasus kriminal".65 Pada tingkat implementasi, prinsip kesesuaian itu terbukti bukan soal sederhana, sebagian karena hukum yang ada di Belanda saat itu bukanlah hukum yang seragam (masing-masing provinsi di Belanda Serikat memiliki hukum dan organisasi peradilannya sendiri) sehingga konflik hukum kadang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, mengandalkan hukum Belanda berarti pengalihan yang efektif tradisi pluralisme hukum ke dalam kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Para hakim Belanda saat itu pasti menyadari persoalan ini; jadi dalam menyelesaikan persoalan hukum di Hindia-Belanda mereka juga menggunakan karya-karya para sarjana Belanda seperti Hugo Grotius (15831645), yang karyanya tentang jurisprudensi Belanda terbit pada tahun 1631,66 dan berfungsi sebagai rujukan umum bagi hukum Belanda. Merujuk tulisan semacam itu terasa sangat penting terutama karena kasus-kasus tertentu tidak didapati keputusannya dalam berbagai undang-undang yang ada. Jadi ketika hakim tidak menemukan ketetapan yang berhubungan
dengan persoalan hukum baru di daerah koloni, mereka harus menyelesaikannya berdasarkan sumber-sumber yang urutannya sebagai berikut: hukum yang diterapkan di seluruh provinsi Belanda; hukum yang diterapkan pada salah satu provinsi; hukum yang secara khusus berlaku untuk suatu distrik, kota, desa atau wilayah tertentu; hukum yang secara khusus berlaku untuk individu tertentu; hukum Romawi-Belanda; hukum Romawi; dan hukum kanon.67 Oleh karena itu, melalui prinsip kesesuaian ini bisa dipahami kalau VOC bertanggungjawab untuk mengalihkan beberapa aspek tradisi hukum sipil seperti yang ada di Belanda ke Hindia-Belanda, walaupun yang menjadi perhatian utama mereka saat itu hanya hukum yang berkaitan dengan orang Eropa (Belanda) atau orang non-Eropa yang memiliki hubungan dengan orang Eropa. Memang, proses pengalihan hukum pada periode awal penjajahan Belanda di bawah kekuasaan VOC belum berpengaruh terhadap orang-orang pribumi, tapi logika administrasi hukum yang digunakan pada periode ini telah membukakan jalan bagi hubungan antara tradisi hukum sipil dan tradisi hukum pribumi di daerah tersebut. Pada awalnya yang menjadi tugas utama Belanda adalah menerapkan hukum yang seragam dan konsisten yang mereka anggap sebagai salah satu kebijakan paling penting yang harus diterapkan di daerah koloni. Oleh karena itu, melalui logika hukum sipil yang mereka bawa dari negeri asal mereka, VOC pada awal tahun 1632 berusaha membuat undang-undang dari kompilasi berbagai dekrit dan ketetapan yang telah diundangkan oleh Gubernur Jenderal beserta Dewan. Usaha itu kemudian terwujud dalam "Undang-undang Batavia" dan kemudian "Undang-undang Batavia Baru"hasil revisi atas undang-undang lama.68 Para hakim diharapkan untuk mencari hukum-hukum terkait di dalam
undang-undang tersebut untuk diterapkan sebelum berpaling pada hukum dan adat yang berlaku di berbagai provinsi di Belanda dan kemudian pada sumber-sumber hukum lainnya sebagaimana digambarkan di atas.69 Dengan prinsip ini, penerapan tradisi hukum sipil dalam kehidupan masyarakat Hindia Belanda, terutama kalau dilihat dari perspektif hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari aparatur negara kolonial, sudah diterapkan dalam kehidupan nyata. Memang ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh VOC dalam menjalankan administrasi sipil peradilan. Di antara kesulitan yang paling berat adalah rendahnya kualitas hakim serta ketergantungan mereka yang kuat terhadap pihak eksekutif sebagai akibat dari kebijakan mereka yang memprioritaskan kepentingan perdagangan ketimbang hukum. Sikap Belanda berubah manakala kendali atas Nusantara berpindah dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda. Ini adalah fase kedua dalam penjajahan,70 sebuah fase ketika pengalihan hukum sipil ke Nusantara menjadi lebih serius seiring dengan perubahan pendekatan Belanda terhadap Nusantara dari sekadar penundukan ekonomi menjadi sepenuhnya penjajahan. Jadi bisa dibilang bahwa kemunculan pertama tradisi hukum sipil di Nusantara pada dasarnya melekat pada praktik penjajahan, dimana ideologi sentralisme hukumnya langsung mengukuhkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat pribumi. Melalui penjajahan inilah Belanda menegakkan tradisi sipil, yang mereka bawa dari negeri asalnya untuk membangun ideologi hukum negara di tengah berbagai nilai hukum yang sebelumnya sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja ideologi ini merupakan salah satu perhatian utama Belanda, karena itu sesuai dengan kebutuhan penguasa kolonial untuk mengendalikan
seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dijajahnya. Dalam hal ini, bisa saja dikemukakan bahwa meskipun Belanda mungkin telah memanfaatkan sejarah hukum sipil dalam mendukung misi mereka untuk menjajah aspek hukum masyarakat pribumi, kebijakan kolonial dalam hal sentralisme hukum sesungguhnya berlawanan dengan logika anti-feodalisme yang diklaim sebagai alasan bagi kemunculan tradisi hukum sipil semenjak abad ke-11 dan ke-12 di Eropa. Dalam sejarahnya, materialisasi tradisi hukum sipil itu didukung oleh gerakan rakyat untuk menghilangkan budaya feodal di Eropa; namun, sebaliknya, Belanda dengan penjajahannya malah memanfaatkan ideologi feodalisme untuk mendukung misi sentralisme hukum mereka. Memang, sejarah kemunculan tradisi hukum sipil di kedua wilayah tidaklah sama, dan ini pada gilirannya menciptakan karakter perkembangan hukum sipil yang unik di kepulauan Indonesia. Ketika mengambil alih wilayah jajahan ini, pemerintah Belanda sesungguhnya telah menyadari perlunya meningkatkan administrasi peradilan; adanya kesadaran itu ditunjukkan oleh usaha mereka meliberalkan manajemen urusan kolonial sesuai dengan aparatur negara modern yang berorientasi pada Eropa. Gerakan liberal ini sesungguhnya adalah warisan dari gelombang revolusi yang terjadi pada beberapa dekade terakhir abad ke-18 di Belanda, yang membuat Belanda dianeksasi untuk sementara waktu oleh Perancis pada tahun 1810. Dengan dianutnya gagasan liberalisme ini oleh beberapa pejabat Belanda semisal Dirk van Hogendrop, Gubernur Pesisir Timur-Laut Jawa, doktrin kebebasan dan kesetaraan untuk semua dianggap sebagai sesuatu yang harus didukung, terutama bila mereka ingin Hindia- Belanda lebih menguntungkan bagi penjajah. Salah satu hasil yang sangat penting dari gagasan baru ini adalah perbaikan administrasi
peradilan di Hindia-Belanda yang mencakup pembentukan institusi peradilan yang independen dan bisa memberi hakim kemandirian dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh tiran.71 Meskipun penerapan gagasan yang sangat liberal itu terbukti terlalu revolusioner saat itu, namun konsep Hogendorp mungkin bisa dilihat sebagai dasar bagi kebijakan baru kolonial dan sikap yang lebih positif terhadap masyarakat pribumi di Hindia Belanda . Catatan kritis yang diberikan oleh Komite dalam Laporan tahun 1803 untuk memperbaiki administrasi peradilan sebagian juga didasarkan pada rekomendasi Hogendorp ini. Salah satu rekomendasi paling penting dalam Laporan itu adalah usulan untuk mempertahankan hukum-hukum, adat, dan sikap hidup masyarakat Jawa yang baik. Ini adalah indikasi kesediaan Belanda untuk memberikan lebih banyak perhatian terhadap institusi hukum masyarakat pribumi. Pada fase kedua penjajahan Belanda ini, proses pembentukan negara yang terpusat semakin intensif. Pada masa Deandels yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia dari tahun 18081811, ideologi ini digunakan untuk memperkuat kekuasaan kolonial di Nusantara. Pergeseran kepentingan Belanda dari kepentingan perniagaan menjadi kepentingan teritorial kekuasaan membukakan jalan bagi Deandels untuk bergerak lebih lanjut mentransformasikan perniagaan yang sudah ada dan organisasi pemerintahan yang longgar menjadi kekuasaan negara yang terpusat.72 Salah satu indikasi dari transformasi tersebut adalah reformasi menyeluruh terhadap administrasi pemerintah kolonial, terutama di Pulau Jawa. Reformasi itu mencakup penggantian aturan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan bisa menyisihkan sistem lama VOC dan membangun landasan bagi sistem yang baru. Dalam bidang hukum, Deandels
juga menyadari bahwa reformasi dalam bidang administrasi peradilan juga dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan transformasi tersebut. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan dalam Laporan tahun 1803, Deandels melakukan beberapa perbaikan pada institusi hukum yang sudah ada pada masa VOC, misalnya: mengganti hakim-hakim tua dengan hakim yang lebih muda yang diyakini memiliki kemampuan yang bagus dan moral serta intelektual yang cocok; menaikkan gaji hakim; dan melakukan perubahan institusi peradilantidak saja di Ibu Kota Batavia, tapi juga di kota-kota di seluruh Jawa, dan lain-lain.73 Bagaimanapun juga kebijakan ini masih menerapkan sistem hukum ganda yang juga dipraktikkan pada masa sebelumnya. Makanya, dengan mengikuti sistem hukum ganda, Deandels melanjutkan metode yang menetapkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda di Nusantara akan diadili sesuai dengan hukum mereka masing-masing di pengadilan mereka masing-masing.74 Namun demikian, kebanyakan pendapat menyatakan bahwa perubahan yang diperkenalkan pada masa Deandels, mengikuti istilah Ball, sebetulnya adalah "reformasi di atas kertas" sehingga banyak usulan reformasi tidak mewujud dalam praktik; bahkan mungkin ada yang menganggap bahwa reformasinya hanyalah pemanis mulut, karena Deandels sendiri, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam banyak kesempatan mengintervensi pekerjaan pengadilan. Keadaan ini sebetulnya adalah gambaran nyata dari kebingungan pemerintah kolonial dalam menangani administrasi negara jajahan pada masa peralihan abad ke-19; di satu sisi mereka merasa harus menerapkan administrasi "tangan besi" untuk mendukung efektifitas proyek kolonial dalam jangka panjang; namun di sisi lain, mereka juga tergoda untuk mengikuti
gelombang modernisasi dalam membangun aparat negara kolonial untuk memaksimalkan keuntungan material dari pendudukan itu. Deandels sering dipuji karena telah membangun sistem peradilan formal di Hindia-Belanda sehingga penggantinya bisa menggunakan sistem itu sebagai dasar untuk melakukan perbaikan selanjutnya terhadap administrasi peradilan di daerah tersebut. Pada masanya, penghulu75di samping tugasnya sebagai hakim dalam persoalan hukum keluarga pada pengadilan agama juga ditunjuk sebagai penasehat dalam kasus yang sebagian berhubungan dengan agama, pernikahan, pewarisan di beberapa pengadilan yang didirikan oleh Deandels. Meskipun inovasi ini berdampak pada dualisme hukum yang membingungkan (karena keberadaan penghulu di pengadilan bisa dianggap sebagai intervensi terhadap peran yudisial jaksa), penunjukan penghulu sebagai penasehat di pengadilan nonagama memperlihatkan kesadaran Belanda terhadap komplikasi persoalan pluralisme hukum di negeri jajahan. Terutama ketika menghadapi persoalan hukum adat, Deandels tampaknya lebih tertarik mengikuti jalan tengah di mana hukum masyarakat pribumi yang akan diterapkan disaratkan tidak berlawanan dengan hukum pemerintah kolonial atau prinsip-prinsip utama keadilan dan kewajaran (serta tidak berlawanan juga dengan keamanan publik). Jadi, dengan kebijakan ini Belanda memulai tradisi penggunaan ideologi sentralisme hukum yang dijalankan oleh institusi negara (dalam kasus ini oleh institusi pemerintahan kolonial) untuk menghadapi tradisi hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat pribumi di luar aparatur negara kolonial. Dengan kata lain, meski mengakui kondisi de facto pluralisme hukum di daerah itu, Belanda masih menggunakan sentralisme
hukum sebagai pendekatan formal untuk menghadapi sistem hukum yang plural. Penggunaan sentralisme hukum sebagai pendekatan terhadap persoalan pluralisme hukum sebenarnya merupakan karakter yang melekat pada tradisi hukum sipil seperti dikembangkan di Hindia-Belanda. Semenjak masa-masa awal, pejabat VOC sebetulnya memandang sentralisasi hukum sebagai ideologi yang menubuh pada kolonialisme; oleh karena itu, ketika mereka berhadapan dengan fenomena pluralisme hukum pada tingkat budaya pribumi, mereka menanggapinya dengan mengakui sistem hukum pribumi sambil perlahan-lahan berusaha memusatkan berbagai persoalan dengan membuat semua hukum dan adat menjadi persoalan yang menuntut keterlibatan negara. Karenanya semua institusi hukum yang ada di masyarakat dipertahankan kecuali yang berlawanan dengan kriteria negara mengenai prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran. Tradisi seperti inilah yang kemudian diformalkan oleh Deandels (dan secara prinsip kemudian dilanjutkan oleh penerusnya) yang menerbitkan sejumlah aturan semisal ketetapannya tanggal 13 Maret 1809 dan 4 April 1809 yang mengizinkan penerapan semua hukum dan adat pribumi selama hukum itu sesuai dengan "hukum, akal dan keadilan".76 Namun begitu, dengan mengizinkan hukum pribumi untuk terus berfungsi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kriteria akal dan keadilan yang longgar, penguasa menempatkan hukum ini dalam posisi yang sulit, karena penerapannya hanya tergantung pada definisi negara mengenai kriteria-kriteria itu. Karena, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, penerapan hukum itu tergantung pada hakim kolonial yang bertindak atas nama aparat negara.77 Situasi inilah yang membentuk gambaran awal pluralisme hukum di Nusantara; dan sebenarnya tradisi
hukum yang terpusat di negara ini menjadi pendekatan standar di Nusantara, paling tidak sampai bermulanya era dekolonialisasi dan munculnya tradisi hukum sipil yang kuat di negara Indonesia. D. Penerimaan Tradisi Hukum Sipil: dari Imposisi Menuju Akulturasi Pragraf-pragraf di atas telah memperlihatkan bahwa tradisi hukum sipil sampai di Nusantara melalui kolonialisme. Dari tradisi kolonialisme itu pula ideologi nasionalisme negara pertama kali diperkenalkan ke daerah ini, yang pada gilirannya menciptakan landasan bagi banyak institusi hukum di bawah logika sentralisme hukum. Ini menjadi preseden bagi tradisi hukum yang dikembangkan di era kemerdekaan Indonesia. Sebagai pelaku utama bagi kedatangan tradisi hukum Barat ke Nusantara, Belanda dapat dipahami kalau mentransfer ke daerah ini hukum Romawi-Belanda yang dikembangkan pada masa Belanda. Proses pengalihan yang berlangsung melalui prinsip kesesuaian, yang menetapkan bahwa semua kasus hukum yang terjadi di Nusantara harus diselesaikan menurut hukum Belanda, adalah landasan teoritik utama dalam proses transfer tradisi hukum ini. Meskipun selama masa peralihan pemerintahan ke tangan Inggris di Nusantara, tradisi hukum common law juga diperkenalkan seiring dengan kolonialisasi Inggris, terutama di Jawa pada masa administrasi Raffles, namun masa kekuasaan Inggris yang pendek dan tradisi hukum sipil yang sudah mapan berpadu menggagalkan usaha penjajah Inggris menanamkan akar tradisi common law di Nusantara.78 Jadi, tampaknya tidaklah berlebihan mempertahankan pandangan bahwa tradisi hukum Barat yang paling berhasil ditransfer ke Nusantara adalah tradisi hukum sipil. Lebih jauh, karena transfer tradisi tersebut tergantung pada
penegakan hukum kekuasaan kolonial di daerah ini, maka karakter hukum sipil yang dikembangkan di Nusantara hanya bisa dikatakan berasal dari institusi negara yang dibangun sebagai kelanjutan dari aparatur kolonial. Dari pernyataan inilah makanya tradisi hukum sipil di Indonesia dalam kenyataannya tidak bisa dipahami di luar ideologi nasionalisme negara yang telah ditransfer melalui kolonialisme di negara ini sebelumnya. Di balik kenyataan sejarah tentang tradisi hukum sipil dan transformasinya ke Nusantara sebagai entitas tidak terpisahkan dari kekuasaan kolonial Belanda, penerimaan tradisi hukum Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi di negara ini bukanlah sebuah proses yang sederhana. Di dalamnya ada perjumpaan sejumlah tradisi hukum; yang paling penting darinya adalah perjumpaan antara tradisi hukum Barat yang dibawa oleh kolonialisme dan tradisi hukum pribumi yang hidup di bawah eksistensi hukum adat yang memiliki beragam bentuk di banyak daerah di Indonesia. Perjumpaan tersebut berdampak pada lamanya proses penerimaan tradisi hukum di Indonesia, dan hasil akhirnya sebetulnya tidak pernah pasti sampai akhirnya terjadi pergeseran politik di Nusantara dari kekuasaan kolonial kepada kekuasaan nasional. Dalam hal bangunan ideologi hukum sebagai aparatur yang menyatu dengan organisasi negara, maka penjajah Belanda telah berhasil mengalihkan gagasan tersebut semenjak awal pendudukan mereka di wilayah ini. Namun, pengalihan tradisi hukum ke dalam kehidupan sehari-hai masyarakat pribumi terbukti bukan soal yang mudah. Hal ini disebabkan karena meski kekuasaan kolonial telah mampu membangun sejumlah institusi hukum di sebagian besar kota-kota utama, terutama di Jawa, hukum yang diterapkan pada masyarakat pribumi masih merupakan hukum asli mereka sendiri (dengan beberapa nuansa
hukum yang diambil dari ajaran agama), sementara hukum yang diterapkan kepada orang Belanda yang menetap di wilayah ini diimpor dari Barat. Jadi semenjak awal, prinsip-prinsip "kesesuaian" tidak lebih dari sekadar jalan, sebuah sarana untuk menyelesaikan persoalan hukum personil Belanda di HindiaBelanda. Baru setelah itu, melalui ideologi imposisi hukum yang diterapkan oleh penguasa kolonial, prinsip kesesuaian diperluas untuk juga mencakup masyarakat pribumi. Oleh sebab itu, penerimaan tradisi hukum di Indonesia sebenarnya bisa dibilang baru bermula ketika Belanda menggunakan prinsip-prinsip imposisi hukum untuk menjustifikasi penerapan berbagai hukum mereka dalam kehidupan masyarakat pribumi.79 Ini bisa dianggap sebagai fase pertama proses penerimaan hukum di Nusantara. Dalam fase ini rangkaian hukum yang pertama diberlakukan pada penduduk lokal adalah hukum kriminal. Melalui hukum ini kejahatan didefinisikan dan dihukum sesuai dengan hukum kolonial. Disini, meski Belanda telah mulai mengintervensi kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh penduduk lokal semenjak awal masa pemerintahan Gubernur Deandels, penerapan hukum kriminal Belanda yang sesungguhnya tidak pernah berjalan sampai tahun 1847. Dengan diundangkannya Algemeene Bepalingen van Wetgeving (A.B.) dalam Staatsblad (S.) 1847 No. 23, terutama pasal 11, hukum kriminal Belanda mulai diterapkan bukan saja untuk orang-orang Belanda tapi juga untuk penduduk pribumi. Kebijakan yang sama ditegaskan dalam Regeringsreglement (RR) 1854 No. 2 pasal 75 (2 & 6), dan aturan itu diikuti aturan lain dalam Indische Staatsregelings (IS) 1925 No. 415 pasal 131, meskipun ada sedikit perubahan.80 Berkat dua hukum terakhir ini, penerimaan hukum diperluas untuk mencakup beberapa aspek hukum perdata
Belanda, dengan diperkenalkannya Burgelijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK), di mana hukum perdata divalidasi penerapannya bagi masyarakat pribumi dan masyarakat non-Eropa lainnya (termasuk Asia Timur) yang tinggal di HindiaBelanda. Melalui keputusan ini, BW dan WvK mulai digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kasus-kasus sipil yang muncul di kalangan masyarakat ini; dengan demikian secara literal pemerintah kolonial menerapkan hukum Belanda terhadap semua orang di Nusantara tanpa membedakan etnis dan asal-usul mereka. Seperti dinyatakan dalam IS 1925, pasal 163 (5) ketika masyarakat pribumi mematuhi hukum Belanda maka mereka disamakan (gelijkgesteld) dengan masyarakat Eropa.81 Proses penerimaan tentu saja tidak berlangsung serta merta; sebaliknya prosesnya berangsur setahap demi setahap sehingga hukum penguasa kolonial akhirnya ditetapkan sebagai sarana penyelesaian konflik ketika muncul persoalan di tengahtengah kehidupan masyarakat. Terutama menyangkut penerimaan hukum perdata, Belanda pada awalnya memberikan pilihan kepada masyarakat pribumi apakah akan mematuhi hukum Belanda, baik sebagiannya atau keseluruhannya.82 Melalui metode ini Belanda berusaha memperkenalkan tradisi hukum mereka dalam kehidupan penduduk Nusantara. Lebih jauh, sejalan dengan prinsip kesesuaian (concordance) Belanda mengalihkan tradisi kodifikasi hukum ke dalam tradisi hukum masyarakat pribumi. Karenanya, tiga undang-undang utama bagi hukum kriminal, hukum perdata dan hukum komersial yang telah dijalankan di Belanda (undang-undang Belanda ini sendiri adalah versi lain dari Undang-undang Napoleon) dialihkan ke dalam sistem hukum yang ada di Nusantara. Dengan begitu, prinsip-prinsip kodifikasi
Undang-undang Napoleon dialihkan oleh Belanda ke daerah koloni. Prinsip-prinsip tersebut terus diterapkan di Indonesia sampai saat ini, kecuali ketika substansi hukum Belanda yang lama diganti dengan undang-undang baru. Belakangan, ketika hukum kolonial telah diterapkan di daerah jajahan, proses penerimaan hukum Barat berlanjut ke tahap seterusnya, di mana struktur dukungan akademis mulai diperkenalkan. Melalui cara ini Belanda berusaha melembagakan hukum tersebut dengan menawarkan kepada penduduk pribumi, terutama yang memiliki status sosial yang tinggi, kesempatan untuk mempelajari hukum Belanda. Melalui orang-orang terdidik itu tradisi hukum Belanda akan lebih efektif merasuk ke dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga bisa menjamin keberlangsungan proses pengalihan tradisi hukum Barat ke wilayah ini. Dengan begitu, semenjak peralihan ke abad ke-20, Belanda telah bisa merekrut penduduk pribumi untuk menduduki posisi pengacara yang mempraktikkan hukum Belanda, terutama beberapa aspek hukum kriminal, untuk menyelesaikan kasuskasus yang melibatkan penduduk pribumi. Untuk melengkapi usahanya itu, Belanda membangun sekolah hukum (rechtsschool) untuk tujuan mendidik lebih banyak mahasiswa pribumi untuk menjadi apa yang mereka sebut penerap-hukum (wetstoepasser).83 Kebijakan ini terutama digunakan pada fase awal proses penerimaan ketika kasus yang dihadapi di tengah masyarakat belumlah begitu rumit seperti yang terjadi belakangan ketika diterapkan hukum perdata di samping hukum pidana. Belanda menyadari bahwa agar proses penerimaan berjalan lancar, tradisi hukum mereka tidak boleh hanya dipahami dalam aspek substantif dan teknisnya saja tapi juga harus dipahami landasan filosofis sistemnya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan
pengacara yang berasal dari masyarakat pribumi, Belanda membuat sekolah hukum (rechtshogerschool) di Batavia pada tahun 1924.84 Ini sebenarnya adalah sekolah hukum pertama yang dibangun oleh penguasa kolonial, dan itu terjadi hanya beberapa dekade sebelum berakhirnya administrasi Belanda di Kepulauan Indonesia. Lembaga akademik formal yang telah melahirkan banyak pengacara dari penduduk pribumi ini mendorong penerimaan hukum sipil di Nusantara lebih cepat lagi. Para hakim dan pengacara pribumi inilah yang diberi kepercayaan untuk menerapkan hukum Barat, sehingga pada akhirnya banyak kasus yang muncul dalam masyarakat diselesaikan dengan merujuk pada hukum Belanda. Seiring dengan inovasi akademik di atas, pengalihan tradisi hukum Belanda tidak hanya berlangsung melalui imposisi hukum, tapi juga melalui kebijakan akulturasi hukum Belanda dalam tradisi hukum masyarakat pribumi. Jadi pengalihan itu tidak hanya melalui institusi yudikatif, tapi juga melalui institusi pendidikan. Kebijakan ini menandai langkah penting dalam kebijakan kolonial yang mencakup penempatan masyarakat pribumi dalam posisi yang lebih setara dengan tuannya yang tercermin dalam tradisi hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Lebih dari itu, institusi pendidikan versi Belanda menguntungkan Belanda sendiri, dimana gagasan hukum bisa dialihkan dengan mudah ke dalam kehidupan masyarakat pribumi, karena pada dasarnya masyarakat pribumi ini tidak mampu mencerap tradisi hukum asing tanpa media bahasa mereka sendiri. Melalui para pengacara pribumi itu, masyarakat pribumi bisa belajar dan menerapkan secara berhatihati hukum Belanda dalam kehidupan mereka, sehingga proses akulturasi hukum bisa berjalan efisien karena hukum pada akhirnya adalah hukum yang hidup bagi masyarakat. Berkat
gerakan akademis ini, "kesesuaian" dicapai tidak hanya dengan penerapan hukum substantif Belanda di pengadilan tapi juga melalui keterlibatan masyarakat pribumi dalam proses memahami filsafat hukum Barat. Dengan begitu Weltanschauung hukum Barat meresap ke dalam kehidupan mereka. Meski sedikit telat, pendirian institusi pendidikan Belanda di Hindia-Belanda telah membawa serangkaian kodifikasi baru ke Nusantara, sehingga tradisi hukum Belanda bisa berdampingan dengan tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat pribumi yang sudah ada sebelumnya. Pada dasarnya skenario inilah yang dicapai selama sisa waktu kehadiran Belanda di Nusantara, sampai datangnya era kemerdekaan di pertengahan bad ke-20. Dalam perspektif hukum, pergeseran politik di Indonesia dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional mungkin sudah diperkirakan akan disertai oleh perbaikan menyeluruh terhadap sistem hukum yang lama. Namun, sejarah panjang kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara telah meninggalkan tradisi hukum Barat begitu kokoh mengakar dalam kehidupan masyarakat sehingga untuk menghilangkan tradisi ini dari kehidupan masyarakat pribumi terasa mustahil. Pada saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945, proses penerimaan hukum sipil Belanda di negara ini sudah sampai pada tahap perkembangan yang sangat matang, sehingga praktis hukum itu menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sistem hukum Belanda, khususnya hukum pidana, perdata dan niaga, sebetulnya mendapatkan keuntungan sosial karena para pengacara pribumi yang dididik di institusi pendidikan Belanda, baik di Indonesia maupun di Belanda, bisa menjamin pelaksanaan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat, terutama dengan menggunakan bahasa pribumi (meski untuk beberapa lama
bahasa Belanda masih menjadi media utama untuk memahami hukum). Oleh karena itu ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, pergeseran politik tidak mengakibatkan perubahan yang besar terhadap situasi dunia hukum di negara yang masih belia itu. Di samping hukum impor dari Belanda itu sudah begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat, para elit negara yang belia itu belum terbentuk dari elemen-elemen radikal yang tertarik untuk mereformulasi aparatur negara kolonial sebelumnya. Keadaan ini tentu saja berdampak terhadap "de facto" kebijakan hukum yang ada, sehingga untuk menghindari kekosongan hukum, para pemimpin baru itu terpaksa menggunakan kembali hukum-hukum yang diwarisi dari era kolonial. Disinilah proses pemertahanan keberadaan tradisi hukum Belanda yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.85
Oleh karena itu bisa dipahami kalau Undang-Undang Dasar 1945 malah mendukung kebijakan untuk tidak merubah hukum yang sudah mapan di dalam masyarakat sampai hukum yang baru bisa dibuat.86 Oleh karena itu, munculnya negara Indonesia baru dan bergesernya organisasi pemerintahan dari pola kolonial kepada pola nasional sebetulnya tidak mencegah berlanjutnya penerimaan hukum sipil dalam sistem hukum negara itu. Meskipun penundukan sepenuhnya oleh penjajah Belanda telah berakhir semenjak pertengahan 1940an, tradisi hukum yang pertama kali dibawa oleh Belanda ke negeri ini tetap boleh dipertahankan dan karenanya berpengaruh terhadap tradisi hukum yang dibangun di sini. Perbedaan antara proses penerimaan hukum antara sebelum dan sesudah kemerdekaan mungkin terletak pada berakhirnya pengaruh langsung para pengacara Belanda dalam menjalankan proses penerimaan itu.
Walhasil, kalau pada masa Belanda penerimaan hukum dilakukan terutama melalui dominasi pengacara Belanda serta menggunakan bahasa dan budaya Belanda sebagai media pentransferan hukum, maka pada masa kemerdekaan --terutama setelah kembalinya dasar konstitusi negara kepada UndangUndang Dasar 1945 pada tahun 1959--,87 para ahli hukum pribumi Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam proses penerimaan hukum, sementara bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa resmi yang bisa digunakan dalam proses peradilan.88 Jadi bisa dibilang semenjak awal tahun 1960-an proses penerimaan tradisi hukum Barat di Indonesia telah mencapai fase yang menentukan di mana budaya Indonesia sudah digunakan sebagai pendekatan untuk menjalankan proses itu. Ini sesuai dengan kembalinya orientasi konstitusi Indonesia kepada UUD 1945, di mana budaya hukum Indonesia dianggap sebagai landasan filosofis bagi pembuatan hukum Indonesia, sehingga semangat untuk menerapkan hukum sipil yang berasal dari pemahaman terhadap budaya dan tradisi Indonesia menjadi semakin besar dari sebelumnya.89 Prinsip-prinsip tradisi hukum Barat kemudian diterapkan bukan lagi berdasarkan pemahaman Barat terhadap hukum, seperti dilakukan oleh para hakim dan pengacara Belanda pada masa-masa awal, tapi lebih didasarkan pada persepsi hukum berdasarkan budaya hukum Indonesia. Indikasinya bisa ditemukan dalam perubahan gelar akademik lulusan sekolah hukum di negara ini dari Meester in de Rechten (Mr.) menjadi Sarjana Hukum (SH) sejak tahun 1960.90 Kalau gelar yang pertama (Mr.) mencerminkan keahlian dalam bidang hukum Belanda (rechten) maka yang kedua (SH.) mencerminkan keahlian dalam bidang hukum Indonesia. Karenanya, penerimaan terhadap hukum sipil Barat pada fase ini berarti bukan sekadar
mengimpor hukum Belanda ke dalam sistem hukum Indonesia tapi lebih sebagai penafsiran terhadap hukum impor tersebut sehingga bisa diterapkan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat pribumi. Pemahaman terhadap tradisi hukum sipil Belanda dalam kondisi mutakhir tergantung pada pemahaman ahli hukum Indonesia terhadap hukum Barat; oleh karenanya penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat juga tergantung pada penafsiran hakim dan pengacara Indonesia terhadap hukum Barat. Periode penerimaan inilah yang oleh seorang ahli hukum Indonesia lulusan Universitas Leiden, Belanda, disebut sebagai "pertumbuhan liar", di mana perkembangan hukum Barat dalam sistem hukum Indonesia sampai pada kondisi tak menentu, karena karakternya telah bercampur baur dengan hukum-hukum lain yang hidup di tengah masyarakat.91 Koesnoe tampaknya merasa pesimis dengan fase penerimaan hukum di Indonesia saat itu, karena dalam pandangannya hukum yang dikembangkan di negara ini tidak lagi jelas apakah murni hukum Barat atau sekadar rekayasa orang Indonesia terhadap hukum. Dia yakin karakter hukum sipil Belanda telah melemah sehingga kinerja tradisi hukum Barat pun jadi kabur dalam sistem hukum Indonesia; hasil akhirnya adalah hukum "hybrid" di mana hukum yang dikembangkan bukan hukum Barat dan juga bukan hukum adat, tapi hukum yang didasarkan pada asumsi ahli hukum Indonesia tentang hukum Barat. Meskipun dia mungkin benar dengan keberatannya terhadap perkembangan tradisi hukum sipil di Indonesia, Koesnoe tampaknya keliru ketika berbicara bahwa proses penerimaan hukum sipil dalam kehidupan masyarakat pribumi sudah berakhir.92 Apa yang mungkin terjadi adalah bahwa ahli hukum Indonesia tidak cukup siap untuk melanjutkan proses akademis
dalam transfer hukum dari pendahulunya bangsa Belanda, sehingga perkembangan tradisi hukum sipil dalam kehidupan masyarakat pribumi tampaknya melemah. Namun, seperti telah dinyatakan sebelumnya, proses akulturasi tradisi hukum Belanda di dekade awal kemerdekaan Indonesia sudah terjadi secara massif, terutama dalam aspek substantif hukum pidana dan beberapa aspek hukum perdata, termasuk hukum perdagangan, sehingga tradisi hukum Belanda sesungguhnya sudah bercampur dengan sistem hukum Indonesia. Pencampuran tradisi hukum Barat dengan hukum masyarakat pribumi sudah pasti terjadi di negara Indonesia yang plural. Semenjak awal, para ahli hukum Belanda juga sudah menyadari bahwa perjumpaan hukum impor dengan hukum pribumi sesungguhnya tidak bisa dihindari, sehingga kebijakan akulturasi hukum dalam kenyataannya merupakan jawaban paling baik. Oleh karena itu, asimilasi hukum menjadi konsekuensi logis dari perjumpaan antara berbagai hukum tersebut karena adanya proses akulturasi hukum sipil Belanda dalam tradisi hukum pribumi. Kokohnya keberadaan tradisi hukum sipil di Indonesia juga lazim dalam praktik yang melekat pada hukum negara di mana proses pembuatan hukum sepenuhnya berada di tangan institusi negara. Karena institusi negara Indonesia merdeka sesungguhnya adalah keberlanjutan dari kekuasaan kolonial Belanda, maka administrasi negara pun menggunakan logika administrasi kolonial dengan membuat beberapa perubahan dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan situasi negara baru. Di sinilah penerapan tradisi hukum sipil di Indonesia dalam kenyataannya tidak bisa dilepaskan dari ideologi sentralisme negara yang sudah melekat padanya semenjak periode awal proses pembangunan negara. Dengan adanya sentralisme hukum tersebut, akhirnya muncul
ideologi baru yang menekankan bahwa hukum seharusnya dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat negara secara formal sementara hukum yang ada di luar organisasi negara akan diabaikan karena keberadaannya tidak bisa diterima. Pembuatan hukum melalui badan legislatif negara sebagai satu-satunya institusi yang diakui untuk membuat undang-undang dan peraturan juga sesuai dengan ideologi ini. Politik hukum ini akhirnya mengarah kepada gerakan untuk membedakan tiga agen pemerintahan, yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Gerakan ini muncul semenjak dekade awal kemerdekaan untuk mengikuti teori Trias Pollitica Montesquieu, di mana aktivitas pembuatan hukum dipisahkan dari aktivitas penerapannya. Atau, paling tidak dalam teori, kebijakan hukum Indonesia telah mengikuti tradisi untuk tidak menginterfensi proses penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif dengan aktivitas politik hukum yang dijalankan oleh badan eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu kita melihat bahwa sejarah awal kemunculan ideologi negara baru di Eropa Barat tampaknya menemukan gemanya di negara Indonesia yang masih belia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia memunculkan keinginan baru untuk membangun aparat negara baru yang dipercayai mampu membawa negara ini menuju kemakmuran dan kemerataan yang lebih besar seperti negara-negara lebih maju lainnya di dunia. Di sinilah kecenderungan untuk menjadikan negara Barat sebagai model dalam proses pembangunan negara terasa sangat kuat sehingga banyak usaha yang dilakukan semenjak awal kemerdekaan untuk meniru model Barat agar diterapkan di negara yang belia ini. Dalam wilayah hukum, semangat untuk mengikuti model Barat dalam pembangunan negara membukakan jalan bagi pencampuran lebih jauh tradisi hukum sipil dalam
proses pembangunan hukum Indonesia. Jadi penerimaan hukum sipil di negara ini tidak bisa dibilang telah berakhir saat terjadinya kemerdekaan; bahkan perkembangan hukum nasional Indonesia bukanlah sebuah proses yang sudah selesai. Lebih jauh, dengan sekadar melewati proses pergeseran politik dari kekuasaan kolonial kepada kekuasaan nasional dalam kenyataannya tidak menyelesaikan proses pembangunan hukum nasional; oleh karena itu, penerimaan tradisi hukum sipil dalam pembangunan hukum nasional harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan di mana pengaruh tradisi itu masih bisa dirasakan dalam situasi negara sat ini. Hasil lainnya dari prinsip sentralisme hukum dan pemisahan kekuasaan pemerintahan (seperti dijelaskan sebelumnya) adalah apa yang membuat institusi negara baru Indonesia lebih banyak memberi perhatian pada gagasan untuk menuliskan setiap hukum ke dalam penulisan yang detil. Sebenarnya ini adalah bagian dari pengaruh tradisi hukum sipil yang menempatkan sistem hukum yang sederhana dan gamblang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang baru. Jadi, kita bisa lihat bahwa salah satu tugas terberat yang dijalankan dalam proyek pembangunan hukum nasional adalah aktivitas membuat hukum dan regulasi sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan tradisi hukum yang dikembangkan di negara ini. Akibatnya, tradisi itu memandang fungsi hakim bukan sebagai pembuat hukum tapi hanya sebagai pelaksana hukum, karena proses pembuatan hukum tidak dijalankan oleh institusi peradilan tapi hanya dalam lembaga perwakilan. Karena negara adalah satu-satunya institusi yeng memiliki hak untuk membuat hukum maka badan pemerintahan dipercayai dengan tugas bahwa ia harus mampu membuat hukum yang sederhana sehingga masyarakat awam
bisa memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka tanpa membutuhkan bantuan pengacara. Tugas ini harus dilakukan untuk menerapkan prinsip bahwa kekuasaan badan legislatif untuk membuat hukum tidak akan diintervensi oleh lembaga peradilan, karena pengadilan tidak boleh diberi hak untuk menafsirkan hukum yang secara teoretis dimiliki oleh legislatif. Konsekuensinya tidak bisa dihindari bahwa kodifikasi tradisi hukum sipil adalah salah satu tugas yang harus dijalankan oleh institusi negara agar bisa memanggul tanggungjawab menyediakan hukum yang lengkap dan jelas bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari penjelasan di atas, sebetulnya penerimaan tradisi hukum sipil yang telah berhasil dimasukkan ke dalam tradisi hukum Indonesia sejalan dengan tradisi Barat yang memandang hukum sebagai entitas sekuler. Karena institusi hukum berkaitan erat dengan institusi negara, akibatnya pembuatan hukum dianggap sebagai proses sekuler, karena satusatunya institusi yang terlibat dimiliki oleh negara yang tidak mendapatkan otoritas apapun dari institusi yang bercorak keagamaan. Ini sebetulnya adalah gagasan dasar dari hukum yang telah berhasil ditransfer ke dalam tradisi hukum Indonesia: hukum dibuat oleh negara, bukan oleh Tuhan; oleh karena itu tidak ada pertimbangan ketuhanan yang masuk ke dalam proses pembuatan hukum. Akibatnya jelas, tradisi hukum sipil sengaja mentransfer nilai-nilai hukum formal dan sekuler yang khas dan berbeda dari nilai-nilai hukum yang dikembangkan sebelumnya di negara ini oleh tradisi hukum lainnya semisal hukum Islam atau hukum Adat. Kesekuleran hukum sipil tentu saja sangat berlawanan dengan hukum Islam, karena prose pembuatan hukum sipil itu sepenuhnya terletak di tangan negara, tanpa
merujuk kepada sumber-sumber suci sebagaimana lazimnya dalam hukum Islam. Lebih jauh, dibandingkan dengan hukum adat, tradisi hukum sipil lebih bersifat formal karena ia sepenuhnya berasal dari usaha negara dan perwakilannya sebuah konsep yang sama sekali asing bagi hukum adat. Oleh karena itu, pluralisme hukum merupakan konsekuensi logis dari kondisi tersebut, bukan saja dalam hal aspek sistem hukum tapi juga dalam aspek tradisi-tradisi hukum yang ada di negara ini.
Corpus Juris Civilis sendiri terdiri dari empat bagian: (1) Codex Constitutionum, suatu kumpulan ketetapan (constitutiones) kerajaan secara kronologis, dengan menghilangkan segala kontradiksi, anomali dan lain sebagainya; (2) Digest, sebuah kumpulan pernyataan hakim mengenai berbagai persoalan hukum; (3) Institutes, buku teks bagi mahasiswa hukum yang menjelaskan institusi hukum; dan (4) Novellae atau Novels, ketetapan baru yang dikeluarkan oleh Justinian setelah penerbitan Codex. 2 Alan Watson, The Making of the Civil Law (Cambridge and London: Harvard University Press, 1981), hlm. 4. 3 Patrick Glenn, Legal Traditions of the World (Oxford: OUP, 2000), hlm. 122 4 John Henry Merryman, The Civil Law Tradition, edisi 2 (Stanford, California: Stanford University Press, 1985), hlm. 14-18. 5 Istilah Vernunftrecht secara literal berarti hukum akal; penggunaan istilah ini bertujuan untuk membedakan dari hukum alam sekuler (naturrecht) sebelumnya versi Kristen seperti yang didukung oleh kebanyakan sarjana semisal St. Thomas Aquinas. Program Vernunftrecht berupa usaha mengelaborasi sistem hukum dalam pengertian yang rasional, yaitu sebagai serangkaian prinsip-prinsip saling berkaitan yang mendefinisikan dirinya sendiri dan menggunakan penalaran deduktif. Lihat Alain Wijffels, European Perdatae Law: A New Software-Package for an Outdated Operating System? edit oleh Mark van Hoecke & Franois Ost, The Harmonization of European Perdatae Law (Oxford: Portland Oregon, 2000) 101, hlm. 109-110. Secara umum mengenai teori Aquinas tentang Naturrecht, lihat W. Friedmann, Legal Theory, 5th ed. (London: Stevens & Sons, 1967) hlm. 108-112. 6 Bluntschli, The Philosophical School of Law, (1888) 32 Journal of Jurisprudence 225; Rudolph Leonhard, Methods Followed in Germany by the Historical School of Law, (1907) 7 Columbia Law Review hlm. 573-575. (Mazhab ini menyatakan bahwa hukum tergantung kepada manusia dan harus diputuskan oleh manusia.) 7 Folke Schmidt, The German Abstract Approach to Law: Comments on the System of the Brgerliches Gesetzbuch, (1965) 9 Scandinavian Study of Law 131 hlm. 137. 8 Lihat Carleton Kemp Allen, Law in the Making, ed. 7 (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 12-13. 9 Merryman, supra note 3, hlm. 17. 10 Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, terj. Thomas Nugent (New York: Hafner Press, 1975), Buku XI Of the Laws which Establish Political Liberty with Regard to the Constitution, terutama hlm 151-162. (Ketika kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan pada diri orang yang sama atau pada tubuh lembaga kehakiman yang sama, maka tidak akan ada kebebasan; karena, mungkin muncul kekhawatiran, kalau monarki atau senat yang sama pasti akan menegakkan hukum tiran, dan mengeksekusi mereka dengan cara yang tiran pula. Sekali lagi, tidak ada kebebasan, kalau kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Segala sesuatunya akan berakhir bila orang atau lembaga yang sama, apakah orang itu terhormat atau orang biasa, melaksanakan ketiga kekuasaan itu, yaitu menegakkan hukum, melaksanakan resolusi pidana dan menyelesaikan persoalan-persoalan individual.) 11 Merryman, supra note 3, hlm. 20-21. 12 Merryman, supra note 3, hlm. 39. 13 Berawal dari ideologi kodifikasi inilah tradisi hukum sipil muncul sebagai tradisi hukum yang berbeda dengan beberapa karakteristik yang tidak ditemukan dalam tradisi hukum lainnya. Sebagian karakteristik itu berasal dari ideologi kodifikasi itu misalnya, sistematisasi hukum dan pilihan yang programatis untuk melanjutkan sistematisasi (yang masih ada hingga sekarang); penggunaan penalaran silogisme; dan tidak adanya pengakuan terhadap otoritas preseden yang mengikat. Pembahasan detil tentang karakter tradisi hukum sipil di bandingkan dengan hukum khusus, lihat Jan Smits, The Making of European Perdatae Law: Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System, trans. by Nicole Kornet (Antwerp, Oxford, N