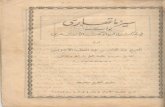Hubungan Antara as Sinar Matahari Dan Kelembaban Terhadap
-
Upload
martiadikurniawan -
Category
Documents
-
view
569 -
download
7
Transcript of Hubungan Antara as Sinar Matahari Dan Kelembaban Terhadap
Hubungan antara Intensitas Sinar Matahari dan Kelembaban Terhadap Produksi Tanaman Lada (Piper nigrum L.)1 Oleh Ida Roma Tio Uli Siahaan, SP2
I. Pendahuluan Tanaman lada (Piper nigrum L.) merupakan salah satu komoditas rempahrempah yang mempunyai prospek cukup cerah bagi peningkatan pendapatan petani dan penambah devisa negara. Peranan lada sebagai penghasil devisa adalah terbesar dalam kelompok rempah dan kelima setelah karet, teh, kelapa sawit dan kopi. Luas areal tanaman lada di Indonesia hampir 90% dimiliki oleh perkebunan rakyat estimasi tahun 2000 seluas 130.178 ha dari total areal 130.557 ha, dengan total potensi produksi lada Indonesia sekitar 65.227 ton. Daerah penghasil lada terbesar di Propinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Hasil pengolahan lada ada 3 jenis yaitu lada hitam, putih dan hijau, dari 3 jenis olahan yang dikenal hanya lada hitam dan putih. Untuk hasil olahan lada dari Propinsi Lampung dikenal dengan sebutan Lampung black pepper dan hasil olahan lada dari Propinsi Kepulauan BangkaBelitung dikenal dengan sebutan Muntok white pepper. Sebutan tersebut dikenal karena Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia (Ditjenbun, 2000 dalam Kadir dan Darmawidah, 2005). Produktivitas lada yang bagus dapat diperoleh dengan memperhatikan penerapan faktor-faktor budidaya tanaman meliputi syarat pertumbuhan dan teknis budidaya hingga pascapanen. Syarat-syarat pertumbuhan tanaman lada meliputi faktor iklim dan media tanamnya. Berikuti ini akan diulas sedikit mengenai hubungan antara intesitas sinar/cahaya matahari dan kelembaban di dalam kebun lada. Ulasan ini merupakan hasil studi literatur, penelitian dan hasil uji terap dari para peneliti.1
Disampaikan pada pemaparan tugas matakuliah Ekofisiologi Tanaman Sekolah Pascasarjana Program Studi Agroekoteknologi Universitas Sumatera Utara Medan, Aula D.H. Penny, 10 Nopember 2011. Mahasiswi Sekolah Pascasarjana Program Studi Agroekoteknologi Tahun 2011 Universitas Sumatera Utara di Medan.
2
II. Pembahasan . Untuk menghasilkan buah yang banyak tanaman lada harus melalui perawatan yang optimal. Elemen lingkungan yang mempengaruhi produktivitas tanaman adalah temperatur, kelembaban relatif, intensitas cahaya, angin, polutan, konsentrasi CO2, serta pH, kadar nutrisi, dan kadar air media tanam Cahaya merupakan faktor lingkungan yang paling penting bagi tanaman karena merupakan sumber energi bagi fotosintesis tanaman. Cahaya yang paling penting bagi tanaman adalah cahaya tampak, yang memiliki panjang gelombang antara 390-700 nm (Wikipedia, 2011). Tanaman yang kurang mendapat intensitas cahaya matahari akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cahaya yang dibutuhkan, sehingga pertumbuhan cabang primernya lebih panjang. Namun demikian yang penting justru bukan pertumbuhan cabang primer saja melainkan semua komponen pertumbuhan harus baik. Pertumbuhan jumlah daun yang merupakan tempat proses fotosintesis akan berpengaruh terhadap produksi tanaman (Rojudin dan Slamet, 2003). Tanaman lada tergolong adaptif terhadap naungan, namun untuk mendukung pertumbuhan dan produksinya memerlukan intensitas sinar matahari yang optimal (BPTP Jawa Barat, 2002). Menurut Syakir (2001) dalam Rajati (2011), Lada dapat tumbuhn dan berproduksi dengan baik pada tingkat intensitas radiasi minimal 50% atau setara dengan energi radiasi rata-rata 251,8 kalori/cm2/hari. Sementara itu Wahid et.al.(1999) dalam Rajati (2011), melaporkan bahwa antara varietas-varietas lada perdu terdapat perbedaan respon terhadap intensitas radiasi surya. Pada intensitas radiasi 100% (cahaya) penuh produksi lada perdu terbaik ditunjukkan oleh varietas Petaling 1. Sedangkan pada intensitas radiasi 50-75% produksi terbaik ditunjukkan oleh varietas Bengkayang. Dengan sifat ini maka lada perdu dapat dikembangkan sebagai tanaman sela diantara tanaman tahunan (BPTP Jawa Barat, 2002). Cahaya yang dibutuhkan tanaman lada untuk tumbuh baik adalah minimal 50% (Wahid, 1984 dalam Rajati, 2011). Peningkatan intensitas radiasi cahaya dapat meningkatkan indeks pertumbuhan dan laju tumbuhan tanaman dengan hasil terbaik pada naungan 27% (Syakir, 1994 dalam Rajati, 2011). Pertumbuhan terbaik tanaman lada perdu diperoleh pada intensitas radiasi 50-75% atau setara dengan 173,17-297,10 kal/cm2/hari (Indriasanti, 1998 dalam Rajati, 2011).
Tanaman lada memerlukan setidaknya 10 jam penyinaran sinar matahari selama satu hari dengan suhu udara 200-340 C. Bila suhu udara terlalu tinggi di pertanaman lada maka akan memacunya tingginya penguapan tanaman (evapotranspirasi). Penguapan tanaman tersebut akan memacu akar tanaman untuk mengabsorbsi air dari dalam tanah sebanyak-sebanyaknya untuk mempertahankan kebutuhan airnya. Dengan demikian unsur hara yang terangkut juga akan semakin banyak seiring absorbs air tersebut. Namun bila kondisi suhu yang terlalu tinggi berlangsung dalam jangka waktu yang terlalu lama maka bisa saja tanaman lada mengalami cekaman atau layu. Akibatnya tanaman menjadi kekurangan air lalu layu kemudian perlahan mengalami kematian. Berdasarkan karakter fisiologisnya lada tergolong tanaman yang adaptif terhadap naungan karena mempunyai lintasan fotosintesis (Syakir, 2001 dalam Rajati, 2011). Oleh karena itu lada perdupun termasuk dalam kelompok tanaman lindung, yaitu tanaman yang dapat tumbuh baik dalam keadaan ternaungi. Tanaman lada termasuk tanaman memanjat yang memiliki dua sulur yaitu sulur panjat dan sulur cabang buah. Apabila digunakan sebagai bibit, sulur panjat akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat memanjat sulur panjat dan sulur cabang buah, sedangkan sulur cabang buah akan menghasilkan tanaman yang tidak memanjat atau lada perdu (BPTP Jawa Barat, 2002).Penggunaan tiang panjat banyak kelemahan, diantaranya apabila menggunakan tiang panjat mati maka modal yang dipergunakan sangat banyak yakni dapat menyerap 60% dari modal. Sedangkan apabila menggunakan tiang panjat hidup (tanaman) akanberakibat produksi rendah karena adanya persaingan tanaman dalam memperoleh sinar matahari, hara tanah, air dan CO2 (BPTP Jawa Barat, 2002).
Gambar 1.Lubang tanam dengan Tajar Gliricidae (a); dan guludan dengan tajar dadap cangkring (b).Pada lokasi-lokasi yang lebih tinggi, pertumbuhannya kurang baik bahkan ada kemungkinan untuk tidak berbuah. Curah hujan yang dikehendaki antara 2.000-3.000 mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 177 hari. Selain itu tidak terdapat bulan-bulan kering dengan curah hujan kurang dari 60 mm/bulan (BPTP Jawa Barat, 2002). Tanaman lada membutuhkan kelembaban udara 50-100% dan optimal pada kelembaban 60-80%.
Tanaman lada tumbuh kurang baik pada areal yang tergenang, oleh sebab itu air yang berlebihan harus dialirkan/dibuang melalui saluran drainase 30 x 20 cm (lebar x dalam) dan parit keliling yang berukuran lebar 40 cm, dalam 30 cm (Gambar 2).
Gambar 2. Parit keliling
Sulur gantung adalah sulur panjat yang tumbuhnya tidak melekat pada tajar, karena tidak dilakukan pengikatan, sehingga tumbuh menggantung. Sulur cacing atau sulur tanah adalah sulur panjat yang tidak melekat pada tajar dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Sulur gantung dan
sulur cacing merupakan sulur yang bersifat parasit atau turut menguras nutrisi/makanan tapi tidak produktif, oleh sebab itu sulur tersebut harus selalu dibuang/dipangkas. Pemangkasan kedua sulur tersebut harus dilakukan secara rutin. Cabang-cabang yang menutupi tanah pada pangkal batang yang menghalangi sinar matahari dan sirkulasi udara harus dipangkas, untuk me n g u r a n g i
k e l e mb a b a n p a n g ka l b a t a n g ya n g d a p a t me mi cu berjangkitnya penyakit busuk pangkal batang.
Gambar 3. Sulur gantung (a); dan sulur cacing atau sulur tanah (b).
Penyiangan harus dilakukan secara rutin yaitu membersihkan sekitar pangkal batang tanaman lada. Pada awal musim kemarau setiap guludan diberi mulsa daun-daunan seperti alang-alang, semak belukar, hasil pangkasan tajar lain-lain setebal 5-10 cm. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan dan menghindari kekeringan yang berlebihan, tetapi tidak membuat kondisi yang terlalu lembab yang menciptakan keadaan yang dapat memicu perkembangan penyakit BPB dan lain-lain setebal 5-10 cm yang disebabkan jamur
Phytophtora capsici.
Penggunaan tajar sangat dianjurkan karena budidaya lada dengan tiang panjat merupakan budidaya yang intensif dan membutuhkan input tinggi. Sehingga, saat harga lada, rendah, pemupukan tidak dapat dilakukan akibatnya tanaman menjadi lemah dan peka terhadap serangan hama dan patogen. Biomas basil pangkasan tajar (dadap cangkring/gliricidae) bila dibenamkan dalam tanah akan meningkatkan kesuburan tanah, merangsang pertu mbuhan dan perkembangan mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Hal ini akan lebih baik apabila disertai dengan pupuk kandang, sehingga proses pembusukan akan lebih cepat dan dapat menghambat perkembangan patogen berbahaya di dalam tanah. Kebun lada yang baik harus mempunyai saluran drainase, sehingga tidak ada air yang tergenang di dalam kebun, karena air yang tergenang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan patogen BPB. Pemeliharaan tanaman lada, meliputi pemangkasan/pembuangan sulur cacing dan sulur gantung yang tidak berguna, bekas pangkasan tersebut ditutup dengan ter atau insektisida. Pembuangan sulur cacing juga akan mengurangi kemungkinan terinfeksinya tanaman lada oleh P. capsici dari tanah.
III. Kesimpulan 1. Tanaman lada membutuhkan intensitas sinar matahari minimal 50% dan optimal pada kisaran 60-80%. 2. Tanaman lada memerlukan setidaknya 10 jam penyinaran sinar matahari selama satu hari dengan suhu udara 200-340 C. 3. Penggunaan tajar diperlukan tanaman lada untuk mengurangi penguapan maksimum akibat intensitas cahaya matahari penuh (100%). 4. Pembuatan parit-parit keliling dan isolasi merupakan faktor penting untuk menghasilkan pertumbuhan lada yang baik dan mencegah penyebaran penyakit busuk pangkal batang.
Daftar Pustaka Anonim, 1984. Pedoman Pengolahan Hasil Ikutan/ Limbah Tanaman Perkebunan. Dalam : Kerjasama Ditjen. Perkebunan dengan IPB, Bogor Anonim, 1985. Vademekum Pengolahan Hasil Perkebunan. Dalam : Direktorat Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Jakarta Anonim, 2011. Lingkungan dan Bangunan Pertanian. "http://id.wikipedia.org/w/ index.php?title=Lingkungan_dan_bangunan_pertanian&oldid=4380354". Diunduh 21 Oktober 2011. BPTP Jawa Barat, 2002. Petunjuk Teknis Pembibitan Lada Perdu. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Lembang Jawa Barat. http://www.softwarelabs.com. Diunduh 21 Oktober 2011. Kadir, S. dan A. Darmawidah A. 2005. Pemupukan Tanaman Lada Piper nigrum L.) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan dan Komponen Hasil. Jurnal Agrivigor 4 (3): 214-220; Agustus 2005. ISSN:1412-2286.h 214-220. Rajati, T. 2011. Lada Perdu Sebagai Alternatif Dalam Pemanfaatan Lahan Kehutanan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan. FKIP Universitas Terbuka Jakarta. Gea, Vol.11, No.1 April 2011. h 77-84. Rojudin, E. dan A.H. Slamet 2003. Teknik Pengukuran dan Penghitungan Pertumbuhan Vegetatif Lada Peru di Bawah Tegakan Kelapa. Buletin Teknik Pertanian Vol. 8. Nomor 1, 2003. h 34-36. Wikipedia, 2011. Lingkungan dan Bangunan Pertanian. "http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingkungan_dan_bangunan_pertanian &oldid=4380354". Diunduh 8 Noember 2011.







![Perancangan dan Pengujian Sistem Pengukuran Sinar UV Dari ......1 Perancangan dan Pengujian Sistem Pengukuran Sinar UV Dari Intensitas Matahari. Yulia Imelda Piyoh[1], Made Rai Suci](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/612230859d4fae774b0b280a/perancangan-dan-pengujian-sistem-pengukuran-sinar-uv-dari-1-perancangan.jpg)