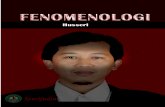filsafat fenomenologi
-
Upload
priyono-haryono -
Category
Documents
-
view
409 -
download
8
Transcript of filsafat fenomenologi

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita
berbagai macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani ini akan selalu
membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada
kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita
capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat.
Terima kasih sebelum dan sesudahnya saya ucapkan kepada Dosen Mata
Kuliah Filsafat serta teman-teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan
berupa moril maupun materil, sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu
yang telah ditentukan.
Saya menyadari sekali, didalam penyusunan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan serta banyak kekurangan-kekurangnya, baik dari segi tata bahasa
maupun dalam hal pengkonsolidasian kepada dosen serta teman-teman sekalian,
yang kadangkala hanya menturuti egoisme pribadi, untuk itu besar harapan saya
jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan
makalah-makalah saya dilain waktu.
Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-
mudahan apa yang saya susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-
teman, serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau
mengambil hikmah dari judul ini (Fenomenologi) sebagai tambahan dalam
menambah referensi yang telah ada.
Serang, Desember 2012
Penulis
i

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………….….. i
DAFTAR ISI…………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………….………………………. 1
B. Ruang Lingkup Pembahasan................................... 2
C. Tujuan Penulisan ................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Definisi Fenomenologi……........................... 3
B. Tokoh Fenomenologi.................................... 4
C. Kelebihan dan kekurangan Filsafat Phenomenologik 9
BAB III PENUTUP
A. Simpulan ……………………………………… 10
B. Saran-Saran ....................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………….. 11
ii

MAKALAH
FENOMENOLOGI
Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Individu Mata Kuliah Filsafat
Disusun Oleh :
Nama : Widya Septiwi
NIM : 11400071
Jurusan : BKI B / 3
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAHINSTITUR AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
MAULANA HASANUDIN(IAIN SMH BANTEN)
2012 M / 1334 H
iii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Fuad Hasan dalam buku beliau Pengantar Filsafat barat di
kemukakan bahwa : “Sejak era Renaissance hingga memasuki abad ke 20 M.
alam pikiran di eropa barat ditandai oleh kemunculannya berbagai aliran filsafat
yang tidak mudah dipertemukan. Pertemuan tersebut menghasilkan pertentangan,
sehingga filsafat justru mengaburkan adanya landasan yang pasti sebagai titik
pijak untuk mengembangkan pemikiran sebagai proses penalaran yang sistematis
dan konsisten”.
Dalam era renaissance tersebut merupakan masa jayanya rasionalisme.
Pada masa itu pula di Prancis masanya kebebasan berkembang dengan
bermunculannya golongan yang tersebut kaum philosophes. Pada tempat yang
sama (Prancis) muncul tokoh penting yang tidak sepaham dengan rasionalisme, ia
adalah Hendri Bergson (1859-1941); bahwa rasionalisme selalu berlaku tidak
cukup untuk memahami semua gejala dalam kenyataan; tidak kalah pentingnya
ialah peran intuisi. Sebagai daya manusia untuk memahami dan menafsirkan
kenyataan.
Epistemologi berarti berbicara tentang “bagaimana cara kita memperoleh
ilmu pengetahuan?”. Dalam memperoleh pengetahuan inilah akan ada sarana
dipergunakan seperti akal, akal budi, pengalaman atau kombinasi antara akal dan
pengalaman institusi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologik
rasionalisme, empisisme, kritisisme atau rasionalisme kritis, positivisme dan
phenomenologik dengan berbagai variasinya.
Di dalam kehidupan praktis sehari-hari, manusia bergerak di dalam dunia
yang telah diselubungi dengan penafsiran-penafsiran dan kategori-kategori ilmu
pengetahuan dan filsafat. Penafsiran-penafsiran itu seringkali diwarnai oleh
kepentingan-kepentingan, situasi-situasi kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan,
sehingga ia telah melupakan dunia apa adanya, dunia kehidupan yang murni,
tempat berpijaknya segala bentuk penafsiran. Dominasi paradigma positivisme
1

selama bertahun-tahun terhadap dunia keilmuwanl, tidak hanya dalam ilmu-ilmu
alam tetapi juga pada ilmu-ilmu sosial bahkan ilmu humanities, telah
mengakibatkan krisis ilmu pengetahuan. Persoalannya bukan penerapan pola pikir
positivistis terhadap ilmu-ilmu alam, karena hal itu memang sesuai, melainkan
positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu masyarakat dan manusia sebagai
makhluk historis.
Problematik positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, yang menghilangkan
peranan subjek dalam membentuk ‘fakta sosial’, telah mendorong munculnya
upaya untuk mencari dasar dan dukungan metodologis baru bagi ilmu sosial
dengan ‘mengembalikan’ peran subjek kedalam proses keilmuwan itu sendiri.
Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan fenomenologi
B. Ruang Lingkup Pembahasan
Dalam makalah ini saya akan membahas salah satu cara yang
ditempuh akal manusia untuk mencapai kebenaran ilmu, yaitu epistemologi
phenomenologi.
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah :
1. Untuk memenuhi tugas yang di berikan oleh dosen pengasuh mata kuliah
Filsafat
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bersama dalam pembahasan
masalah filsafat terutama filsafat phenomologi
.
2

BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Fenomenologi
Fenomenologi (Inggris: Phenomenology) berasal dari bahasa
Yunaniphainomenon dan logos. Phainomenon berarti tampak dan phainen berarti
memperlihatkan. Sedangkan logos berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan.
Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian
terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Lorens Bagus memberikan dua
pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu
tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang
gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita.1 Sebagai sebuah arah
baru dalam filsafat, fenomenologi dimulai oleh Edmund Husserl (1859–1938).
Namun istilah fenomenologi itu sendiri sudah ada sebelum Husserl. Istilah
fenomenologi secara filosofis pertama kali dipakai oleh J.H. Lambert (1764).2
Immanuel Kant memakai istilah fenomenologi dalam karyanya Prinsip-
Prinsip Pertama Metafisika (1786). Maksud Kant adalah untuk menjelaskan kaitan
antara konsep fisik gerakan dan kategori modalitas, dengan mempelajari ciri-ciri
dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indera-indera lahiriah.
Hegel (1807) memperluas pengertian fenomenologi dengan
merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yakni suatu
pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan
yang sebenarnya. Bagi Hegel, fenomena tidak lain merupakan penampakkan atau
kegejalaan dari pengetahuan inderawi: fenomena-fenomena merupakan
manifestasi konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia.
1 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 1996, Gramedia, Jakarta, h. 247. Farida Hamid dalam kamus ilmiah popular lengkap, yang diterbitkan oleh Apollo Surabaya, h. 150, menjelaskan bahwa fenomena adalah penampakan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah. Sedangkan fenomenologi sendiri diartikan sebagai sebuah ilmu penentuan kesimpulan dari adanya gejala, sebuah filsafat yang mengkaji tentang manusia dan kesadarannya dan pengetahuan yang bisa dicapai oleh kesadaran manusia.
2 Makmun Anshari, http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/05/mengenal-filsafat fenomenologi.html, akses 01-12-2012, 15.08 wib.
3

Sementara itu, anggapan para ahli tertentu lebih mengartikan
fenomenologi sebagai suatu metode dalam mengamati, memahami, mengartikan,
dan memaknakan sesuatu sebagai pendirian atau suatu aliran filsafat. Sebagai
metode, fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil
sehingga kita sampai pada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dan
melukiskan ciri-ciri intrinsik (inti) fenomen-fenomen sebagaimana fenomen-
fenomen itu sendiri menyingkapkan diri kepada kesadaran. Kita harus bertolak
dari subjek (manusia) serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada
“kesadaran murni”. Untuk mencapai bidang kesadaran murni, kita harus
membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari.
Sebagai filsafat, fenomenologi menurut Husserl memberi pengetahuan yang perlu
dan esensial mengenai apa yang ada. Dengan demikian fenomenologi dapat
dijelaskan sebagai metode kembali ke benda itu sendiri (Zu den Sachen Selbt),
dan ini disebabkan benda itu sendiri merupkan objek kesadaran langsung dalam
bentuk yang murni.3
Secara umum pandangan fenomenologi bisa dilihat pada dua posisi.
Pertama ia merupakan reaksi terhadap dominasi positivisme, dan kedua, ia
sebenarnya sebagai kritik terhadap pemikiran kritisisme Immanuel Kant, terutama
konsepnya tentang fenomena – noumena. Kant menggunakan kata fenomena
untuk menunjukkan penampakkan sesuatu dalam kesadaran, sedangkan noumena
adalah realitas (das Ding an Sich) yang berada di luar kesadaran pengamat.
B. Tokoh Fenomenologi
1. Edmund Huserl
Nama lengkapnya adalah Edmund Husserl (1859-1939). Ia lahir di
Morvia, Jerman, sehingga ia digolongkan dalam seorang filsuf Jerman. Pada
awalnya, ia adalah seorang pakar matematika yang memperoleh gelar Ph.D. dalam
bidang ini serta mengajar ilmu tersebut selama beberapa tahun. Namun setelah itu,
ia tertarik kepada filsafat setelah selama tiga tahun mengikuti kulih-kuliah dari
3 Poejawijatna, Pembimbing Kearah Alam Filsafat, PT Rineka Cipta, Cet. XII, 2005, Jakarta, h. 139
4

Franz brentano di Wina. Ia dipandang sebagai perancang fenomenologi lewat
karyanya Logical Investigation(1900), Ideas (1913) dan sejumlah karya lain.
Fenomenologi menurut Husserl adalah studi tentang perbedaan dan
berbagai bidang objek, yang disebut neomata, yaitu ciri-ciri yang membuat
kesadaran terhadap objek-objek. Kita dapat sampai kepada ciri-ciri ini melalui
sebuah refleksi khusus yakni terhadap kesadaran kita yang disebut epoche.
Husserl mengonsentrasikan diri terhadap ciri-ciri atau sifat kesadaran yang
membuat tindakan-tindakan kita seperti sebuah objek.
Sedangkan untuk memahami fenomenologi Husserl, orang harus paham
istilahnoema. Neoma adalah kumpulan semua sifat objek. Noema ini tidak lain
hanyalah sebuah generalisasi ide tentang makna mengenai lapangan segala
tindakan. Dengan membedakan antara sebuah ekspresi makna dengan rujukannya,
seseorang menerangkan penggunaan makna dari ekspresi-ekspresi yang tidak ada
rujukannya. Noema ini memiliki dua komponen, yaitu:
a) Object meaning yang menyatukan berbagai komponen dari pengalaman
kita kepada pengalaman-pengalaman dari berbagai ciri sebuah objek.
b) The tethic yaitu yang membedakan tindakan-tindakan yang berbeda,
misalnya tindakan merasakan sebuah objek dengan tindakan mengingat
atau memikirkannya. 4
Dalam tindakan merasa, neoma kita dibatasi oleh permukaan-permukaan
sensori kita, tetapi pembatasan ini tidak mengiringi kepada satu kemungkinan
saja. Bisa saja dalam satu situasi kita merasakan kehadiran seseorang manusia,
tetapi disaat berikutnya melihat orang itu sebagai sebuah boneka. Hal ini terjadi
sesuai dengan perubaha noema. Neoma berubah karena terjadi perasaan itu tidak
dapat diyakini.
Periode perkembangan pemikiran fenomenologi Husserl dapat dabagi
dalam empat periode:
a) Ia berangkat dari matematika dan ini disebut periode pra-fenomenologi
b) Awal fenomenologi sebagai korelasi subjektif atas logika murni sebagai
tahapan usaha epistemologi yang terbatas.
4 Zubaedi, Filsafat Barat…, h. 125
5

c) Fenomenologi dianggap sebagai the firs philosophy.
d) Pengatasan idealisme.
Husserl mengajukan dua langkah yang harus ditempuh untuk mencapai
esensi fenomena, yaitu metode epoche dan eidetich vision. Kata epoche berasal
dari bahasa Yunani, yang berarti: “menunda keputusan” atau “mengosongkan diri
dari keyakinan tertentu”. Epoche bisa juga berarti tanda kurung (bracketing)
terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari suatu fenomena yang nampak,
tanpa memberikan putusan benar salahnya terlebih dahulu. Fenomena yang tampil
dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi
pengamat. Untuk itu, Husserl menekankan satu hal penting: Penundaan
keputusan. Keputusan harus ditunda (epoche) atau dikurung dulu dalam kaitan
dengan status atau referensi ontologis atau eksistensial objek kesadaran.
Selanjutnya, menurut Husserl, epoche memiliki empat macam, yaitu :
a) Method of historical bracketing; metode yang mengesampingkan aneka
macam teori dan pandangan yang pernah kita terima dalam kehidupan
sehari-hari, baik dari adapat, agama maupun ilmu pengetahuan.
b) Method of existensional bracketing; meninggalkan atau abstain terhadap
semua sikap keputusan atau sikap diam dan menunda.
c) Method of transcendental reduction; mengolah data yang kita sadari
menjadi gejala yang transcendental dalam kesadaran murni.
d) Method of eidetic reduction; mencari esensi fakta, semacam menjadikan
fakta-fakta tentang realitas menjadi esensi atau intisari realitas itu.
Dengan menerapkan empat metode epoche tersebut seseorang akan sampai
pada hakikat fenomena dari realitas yang dia amati. 5
Husserl meninggal di Freiburg disaat ia menghindar dari penangkapannya
oleh pasukan Nazi karena ia adalah keturunan Yahudi. Keluarganya, pustaka, dan
semua manuskrip yang berjumlah 40.000 halaman dipindahkan dari jerman oleh
Franciskan Van Breda. Breda juga yang mendirikan badan arsip Husserl di
Louvain dimana karya Husserl dapat diperoleh oleh para peneliti sekarang. 6
5 Makmun Anshari, http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/05/mengenal-filsafat fenomenologi.html, akses 01-12-2012, 15.08 wib.
6 Jokosiswanto, Sistem-Sistem Filsafat Barat…, h. 99
6

2. Max Scheler
Max Scheler adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh dalam
bidangfenomenologi, filsafat sosial, dan sosiologi pengetahuan.Ia berjasa dalam
menyebarluaskan fenomenologi Husserl. Scheler dilahirkan pada tahun 1874
diMuenchen. Ia menempuh studi di Muenchen, Berlin, Heidelberg,dan Jena.
Setelah itu, ia menjadi dosen di Jena dan Muenchen, di mana ia berkenalan
dengan fenomenologi Husserl. Pada tahun 1919, Scheler menjabat guru besar
di Koln. Kemudian ia meninggal dunia di Frankfurt pada tahun 1928.
Inti pemikiran filsafat Scheler adalah nilai. Ia mengatakan bahwa manusia
bertindak berdasarkan bukan berdasar kepuasan diri semata, Scheler menyatakan
bahwa nilai adalah hal yang dituju manusia. Jika ada orang yang mengejar
kenikmatan, maka hal itu bukan demi kepuasan perasaan, melainkan karena
kenikmatan dipandang sebagai suatu nilai. Nilai tidak bersifat relatif, melainkan
mutlak. Nilai bukan ide atau cita-cita, melainkan sesuatu yang kongkret, yang
hanya dapat dialami dengan jiwa yang bergetar dan dengan emosi. 7
Dari sini ia tidak puas denga etika Kant, karena hanya mengembalikan
seluruh etika kepada kewajiban. Adapun gejalanya tidak demikian, sebab bukan
hanya sekedar mengetahui kewajiban, lebih jauh juga harus diketahui apa
sesungguhnya yang harus dilakukan menurut kewajiban itu. 8
3. Martin Heidegger
Martin Heidegger lahir di Mebkirch, Jerman, 26 September 1889 –
meninggal 26 Mei 1976 pada umur 86 tahun, adalah seorang filsuf asal Jerman. Ia
belajar di Universitas Freiburg di bawah Edmund Husserl, penggagas
fenomenologi, dan kemudian menjadi profesor di sana 1928. Ia memengaruhi
banyak filsuf lainnya. Selain hubungannya dengan fenomenologi, ia mempunyai
pengaruh yang besar terhadap eksistensialisme, dekonstruksi, hermeneutika dan
pasca-modernisme. Ia berusaha mengalihkan filsafat Barat dari pertanyaan-
pertanyaan metafisis dan epistemologis ke arah pertanyaan-pertanyaan ontologis,
7 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Kanisius, 1983, Yogyakarta. h. 145-148.
8 Poejawijatna, Pembimbing Kearah…, h. 140
7

artinya, pertanyaan-pertanyaan menyangkut makna keberadaan, atau apa artinya
bagi manusia untuk berada.
Heidegger menjadi tertarik akan pertanyaan tentang "Ada" (atau apa
artinya "berada"). Karyanya yang terkenal Being and Time (Ada dan Waktu)
dicirikan sebagai sebuah ontologi fenomenologis. Gagasan tentang Ada berasal
dari Parmenides dan secara tradisional merupakan salah satu pemikiran utama dari
filsafat Barat. Persoalan tentang keberadaan dihidupkan kembali oleh Heidegger
setelah memudar karena pengaruh tradisi metafisika dari Plato hingga Descartes,
dan belakangan ini pada Masa Pencerahan. Heidegger berusaha mendasarkan Ada
di dalam waktu, dan dengan demikian menemukan hakikat atau makna yang
sesungguhnya dalam artian kemampuannya untuk kita pahami.
Upaya besar Heidegger adalah menangani kembali gagasan Plato dengan
serius, dan pada saat yang sama menggoyahkan seluruh dunia Platonis dengan
menantang saripati Platonisme - memperlakukan Ada bukan sebagai sesuatu yang
nirwaktu dan transenden, melainkan sebagai yang imanen (selalu hadir) dalam
waktu dan sejarah.
Heidegger memepertanyakan makna dari ada, apa maknanya bila sesuatu
entitas dikatakan ada? Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan mendasar dalam
cakupan wilayah ontologi. Dalam pendekatannya Heidegger terpisah dari tradisi
Aristotelian dan Kantian yang mendekati pertanyaan itu dari sudut pandang
logika. Secara implisit mereka mengatakan bahwa pengetahuan teoritis mewakili
relasi mendasar antara individu dan ada di dunia sekitarnya (mencakup juga
dirinya sendiri).
Selanjutnya Heidegger menolak kategori subjek-ojek yang kerap
dikenakan oleh filsuf pasca Descartes. Sesuatu bermakna bagi kita hanya dalam
penggunaannya pada konteks tertentu yang telah ditetapkan oleh norma sosial. 9
C. Kelebihan dan kekurangan Filsafat Phenomenologik
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger, akses 01-12-2012, 15.08 wib.
8

Kelebihan filsafat phenomenoligik diantaranya dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Phenomenologik sebagai suatu metode keilmuan, dapat mendiskripsikan
penomena dengan apa adanya dengan tidak memanipulasi data, aneka
macam teori dan pandangan
2. Phenomenologik mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran
dengan benar-benar yang objektif
3. Phenomenologik memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh
tidak terpisah dari objek lainnya
Dengan demikian phenomenologik menuntut pendekatan yang holistik,
bukan pendekatan partial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai
objek yang di amati, hal ini lah yang menjadi kelebihan filsafat ini sehingga
banyak dipakai oleh ilmuan-ilmuan dewasa ini terutama ilmuan sosial, dalam
berbagai kajian keilmuan mereka termasuk bidang kajian agama
Dari berbagai kelebihan tersebut, phenomenologik sebenarnya juga tidak
luput dari berbagai kelemahan, seperti :
1. Tujuan phenomenologik untuk mendapatkan pengetahuan yang murni
objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari
adat, agama ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu yang absurd
2. Pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai (value-free), tapi bermuatan
nilai (value-bound)
Dari kelebihan dan kekurangan tersebut maka kebenaran yang dihasilkan
cenderung subjektif, yang hanya berlaku pada kasus tertentu, situasi dan kondisi
tertentu pula serta dalam waktu tertentu. Dengan ungkapan lain pengetahuan dan
kebenaran yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan.
BAB III
9

P E N U T U P
A. Simpulan
Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :
1. Phenomenologik merupakan suatu metode analisa juga sebagai aliran
filsafat, yang berusaha memahami realitas sebagaimana adanya dalam
kemurniannya
2. Epistemologi phenomenologi yang diperkanalkan oleh Husserl dengan
kajian berpusat pada analisis terhadap gejala yang nampak dalam
kesadaran manusia. Untuk melahirkan suatu teori tersebut maka
seseorang jangan berpedoman pada teori orang lain (bukan menguji teori
yang ada) tapi mengamati tanpa dasar apapun.
3. Dalam pemikiran phenomenologi seseorang yang mengamati terkait
langsung dengan perhatiannya, dan juga terkait pada konsep-konsep
yang telah dimilikinya sendiri (sangat relatif). Kebenaran logik, ethik
dan transendental (kebenaran di luar empirik inderawi) diterima oleh
fenomenologi. Metode ini banyak mempengaruhi segala cabang ilmu
filsafat.
B. Saran-saran
Adapun beberapa hal yang dapat saya sarankan yaitu :
1. Hendaknya setiap kita selalu menanamkan pemahaman yang realistis
terhadap aliran-aliran yang ada dalam filsafat sebagai wahana pengaya
pengetahuan tentang filsafat llmu
2. Kekurangan dari penyusunan dan penulisan ini hendaknya menjadi
pemacu bagi rekan mahasiswa yang lain untuk lebih membuka ide,
wawasan dan menggali lebih dalam akan makna filsafat itu yang
sesungguhnya.
DAFTAR PUSTAKA
10

Abdul Munin al-Hifni, al-Mausu’ah al-Falsafiyah, beirUt Libanon, Dar Ibn Zaidun, tt. Cet. ke I
Burhanuddin Salam, Logika Materiil (Filsafat Ilmu Pengetahuan), Jakarta, Renika Cipta
Dirjarkara, Percikan Filssafat, Jakarta PT. Pembangunan, tahun 1978.
Fuad Hasan, Pengantar Filsafat Barat, Jakarta, Pustaka Jaya, tahun 1996, cet. ke I
Hasan Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yogyakarta, Kanisius, tahun 1993, cet. ke 9
http://id.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger, akses 01-12-2012, 15.08 wib.
Http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/05/mengenal-filsafat fenomenologi.html, akses 01-12-2012, 15.08 wib
Koento Wibisono Siswoniharjo, Ilmu Pengantar Sebuah Sketsa Umum Untuk Mengenal Kalahiran dan Perkembangan Sebagai Pengantar Untuk Memahami Filsafat Ilmu Dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu, Yogyakarta, Leberty, 1996.
Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 1996, Gramedia, Jakarta
Moh, Muslih, Filsafat Ilmu Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan., Yogyakarta, Belukar, 2005
Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, Yogyakarta, Reka Sarasin, tahun 1998.
Poedjawijatna, Pembimbing ke Arah Alam Filsafat, Jakarta, Pt, Pembangunan, 1974.
Sutrisno, et.al., Para Filusuf Penentu Gerak Zaman, Yogyakarta, Kanisius, 2005
Titus, Living Issnes In Philosophy (Persoalan-Persoalan Filsafat), alih bahasa oleh M. Rasyidi, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.
11