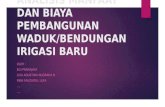Evapro TB (ikm)
description
Transcript of Evapro TB (ikm)

EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS
DI UPT PUSKESMAS KECAMATAN BEJI
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2014
Disusun oleh:
Dessy Krissyena, S.Ked 1320221128
Pembimbing:
Dr. Hanna Windyantini, MPdKed
KEPANITERAAN KLINIK
ILMU KESEHATA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “VETERAN” JAKARTA
2015

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh
kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang
paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (Depkes, 2011). Penyakit ini
bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi
berbahaya hingga kematian. Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang
masih menjadi perhatian dunia. Hingga saat ini, belum ada satu negara pun yang
bebas TB. Angka kematian dan kesakitan akibat kuman Mycobacterium
tuberculosis ini pun tinggi. WHO menyatakan bahwa Tuberkulosis merupakan
global emergency pada awal tahun 1990-an. Hingga saat ini, TB merupakan
penyakit menular yang masih menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia.
Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan beban TB tinggi di dunia
(Depkes, 2013).
Tahun 2009, 1,7 juta orang meninggal karena TB (600.000 diantaranya
perempuan) sementara ada 9,4 juta kasus baru TB (3,3 juta diantaranya
perempuan). Sepertiga dari populasi dunia sudah tertular dengan TB dimana
sebagian besar penderita TB adalah usia produktif (15-55 tahun). Dunia telah
menempatkan TB sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian MDGs.
Secara umum ada 4 indikator yang diukur, yaitu Prevalensi, Mortalitas, Penemuan
kasus dan Keberhasilan pengobatan. Dari ke-4 indikator tersebut 3 indikator
sudah dicapai oleh Indonesia, angka kematian yang harus turun separuhnya pada
tahun 2015 dibandingkan dengan data dasar (baseline data) tahun 1990, dari
92/100.000 penduduk menjadi 46/100.000 penduduk. Indonesia telah mencapai
angka 39/100.000 penduduk pada tahun 2009. Angka Penemuan kasus (case
detection rate) kasus TB BTA positif mencapai lebih 70%. Indonesia telah
mencapai angka 73,1% pada tahun 2009 dan mencapai 77,3% pada tahun 2010.
Angka ini akan terus ditingkatkan agar mencapai 90% pada tahun 2015 sesuai
target RJPMN. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) telah mencapai
lebih dari 85%, yaitu 91% pada tahun 2009.3 Indonesia mendapatkan Champion

Award for Exeptional Work in the Fight Againts TB yang diperoleh dari USAID
Global Health atas prestasi luar biasa dalam penanggulangan Tuberkulosis (TB).
Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan Peringatan Hari Tuberkulosis
Sedunia tahun 2013, kepada Pemerintah Indonesia (Depkes, 2013).
Pengendalian TB di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman penjelajahan
Belanda namun masih terbatas pada kelompok tertentu. Setelah perang
kemerdekaan, TB ditanggulangi melalui Badan Pengobatan Penyakit Paru Paru
(BP-4). Sejak tahun 1969 pengendalian TB dilakukan secara nasional melalui
Puskesmas. Pada tahun 1995, program pengendalian TB mulai menerapkan
strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (DOTS =
Directly Observed Treatment Shortcourse) yang dilaksanakan di Puskesmas
secara bertahap (Kemenkes, 2015).
Strategi nasional pengendalian TB telah sejalan dengan petunjuk
internasional (WHO DOTS dan strategi baru Stop TB). Strategi yang
direkomendasikan untuk mengendalikan TB (DOTS = Directly Observed
Treatment Shortcourse) terdiri dari 5 komponen yaitu komitmen pemerintah untuk
mempertahankan control terhadap TB; deteksi kasus TB di antara orang-orang
yang memiliki gejala-gejala melalui pemeriksaan dahak; pengobatan teratur
selama 6-8 bulan yang diawasi; persediaan obat TB yang rutin dan tidak terputus;
dan sistem laporan untuk monitoring dan evaluasi perkembangan pengobatan dan
program (Depkes, 2013). Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara
Nasional di seluruh Fasyankes terutama Puskesmas yang diintegrasikan dalam
pelayanan kesehatan dasar (Kemenkes, 2015). DOTS sangat penting untuk
penanggulangan TB selama lebih dari satu dekade, dan tetap menjadi komponen
utama dalam strategi penanggulangan TB yang terus diperluas.
Telah banyak kemajuan yang dicapai dalam pengendalian TB di Indonesia
tetapi tantangan masalah TB ke depan tidaklah semakin ringan. Tantangan
tersebut diantaranya berupa meningkatnya koinfeksi TB-HIV, kasus TB-MDR,
kelemahan manajemen dan kesinambungan pembiayaan program pengendalian
TB. Walaupun jumlahnya sudah berhasil ditekan, tapi jumlah pasien TB dan
kematiannya masih juga cukup banyak. Oleh karena itu, pengendalian TB
memerlukan partisipasi semua pihak dan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Masalah
Belum adanya evaluasi program Pengendalian Tuberkulosis di
Puskesmas Beji tahun 2014 serta untuk melihat sejauh mana keberhasilan
puskesmas dalam program Pengendalian TB.
1.3 Tujuan
I.3.1. Tujuan umum
Melakukan evaluasi program Pengendalian Tuberkulosis agar
dapat diketahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya di Puskesmas
Beji.
I.3.2. Tujuan khusus
a. Mengetahui pelaksanaan dan pencapaian program Pengendalian
Tuberkulosis di Puskesmas Beji
b. Mengetahui masalah-masalah pada program Pengendalian
Tuberkulosis di Puskesmas Beji
c. Mengetahui kemungkinan penyebab masalah-masalah dari program
Pengendalian Tuberkulosis di Puskesmas Beji dan membuat prioritas
masalah
d. Membuat alternatif pemecahan masalah untuk program Pengendalian
Tuberkulosis di Puskesmas Beji
1.4 Manfaat
1.4.1.Manfaat bagi Puskesmas
a. Mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan dan masalah-masalah
yang dihadapi selama pelaksanaan program Pengendalian Tuberkulosis
di Puskesmas Beji
b. Mendapatkan alternatif penyelesaian masalah dalam pelaksanaan
program Pengendalian Tuberkulosis Puskesmas Beji.
c. Sebagai bahan masukan untuk melakukan penyuluhan kesehatan guna
meningkatkan keberhasilan program Pengendalian Tuberkulosis
Puskesmas Beji pada tahun-tahun berikutnya.

1.4.2.Manfaat bagi Universitas
Sebagai tempat penyelenggaraan tugas kedokteran terutama dalam
kepaniteraan kedokteran komunitas serta siap bekerja di masyarakat.
1.4.3.Manfaat bagi penulis
a. Penulis dapat melakukan evaluasi program puskesmas dengan
mengaplikasikan ilmu kesehatan komunitas
b. Mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program Pengendalian
Tuberkulosis di Puskesmas Beji
c. Penulis dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif
penyelesaian masalah sebagai masukan untuk pelaksanaan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Program Pengendalian Tuberkulosis
2.1.1.Definisi Tuberkulosis
Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi
Mycobacterium tuberculosis complex (PDPI, 2006).
2.1.2.Epidemiologi Tuberkulosis
Global Tuberculosis Report 2014, melaporkan bahwa Indonesia
masuk dalam 10 besar negara dengan insidensi tertinggi. Indonesia
merupakan negara kelima dengan Insidensi TB di dunia setelah India,
China, Nigeria, Pakistan (WHO, 2014). Angka ini menunjunkkan bahwa
angka insidensi TB di Indonesia masih tinggi. Meskipun memiliki beban
penyakit TB yang tinggi, Indonesia merupakan negara pertama diantara
High Burden Country (HBC) di wilayah WHO South-East Asian yang
mampu mencapai target global TB untuk deteksi kasus dan keberhasilan
pengobatan pada tahun 2006 (Kemenkes, 2011).
2.1.3.Tujuan dan Sasaran Pengendalian TB
Tujuan dari Pengendalian TB adalah Menurunkan angka kesakitan
dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Depkes RI,
2011).
Sasaran strategi nasional pengendalian TB ini mengacu pada rencana
strategis kementerian kesehatan dari 2009 sampai dengan tahun 2014 yaitu
menurunkan prevalensi TB dari 235 per 100.000 penduduk menjadi 224
per 100.000 penduduk. Sasaran keluaran adalah: (1) meningkatkan
persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang ditemukan dari 73%
menjadi 90%; (2) meningkatkan persentase keberhasilan pengobatan kasus
baru TB paru (BTA positif) mencapai 88%; (3) meningkatkan persentase
provinsi dengan CDR di atas 70% mencapai 50%; (4) meningkatkan

persentase provinsi dengan keberhasilan pengobatan di atas 85% dari 80%
menjadi 88% (Depkes RI, 2011).
2.1.4. Kebijakan Pengendalian TB
a. Pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan azas
desentralisasi dalam kerangka otonomi dengan Kabupaten/kota sebagai
titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan
sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).
b. Pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS dan
memperhatikan strategi Global Stop TB partnership.
c. Penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah
terhadap program pengendalian TB.
d. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap
peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan
pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan
mencegah terjadinya MDR-TB.
e. Penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan
oleh seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), meliputi
Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Balai/Klinik Pengobatan, Dokter
Praktek Swasta (DPS) dan fasilitas kesehatan lainnya.
f. Pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangan kerja sama dan
kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan
masyarakat dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian TB
(Gerdunas TB).
g. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan
ditujukan untuk peningkatan mutu dan akses layanan.
h. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pengendalian TB diberikan secara
cuma-cuma dan dikelola dengan manajemen logistk yang efektif demi
menjamin ketersediaannya.
i. Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk
meningkatkan dan mempertahankan kinerja program.

j. Pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan
kelompok rentan lainnya terhadap TB.
k. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.
l. Memperhatikan komitmen internasional yang termuat dalam MDGs
(Depkes RI, 2011).
2.1.5.Strategi
Strategi nasional program pengendalian TB nasional terdiri dari 7 strategi:
a. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu
b. Menghadapi tantangan TB/HIV, MDR-TB, TB anak dan kebutuhan
masyarakat miskin serta rentan lainnya
c. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyarakat
(sukarela), perusahaan dan swasta melalui pendekatan Public-Private
Mix dan menjamin kepatuhan terhadap International Standards for TB
Care
d. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB.
e. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan dan
manajemen program pengendalian TB.
f. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program
TB.
g. Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi
strategis (Depkes RI, 2011).
2.1.6.Kegiatan
a. Tatalaksana dan Pencegahan TB
Kegiatan yang dilakukan seperti penemuan kasus tuberkulosis,
pengobatan tuberkulosis, pemantauan dan hasil pengobatan tuberkulosis
Pengendalian infeksi pada sarana layanan, serta pencegahan tuberkulosis.
b. Manajemen Program TB
Kegiatan-kegiatan pada manajemen Program TB antara lain
perencanaan program tuberkulosis, monitoring dan evaluasi program
tuberkulosis, manajemen logistik program tuberkulosis dan

pengembangan ketenagaan program tuberkulosis, serta promosi program
tuberkulosis.
c. Pengendalian TB komprehensif
Kegiatan yang dilakukan antara lain penguatan layanan
laboratorium tuberkulosis, Public - Private Mix (pelibatan semua fasilitas
pelayanan kesehatan), kolaborasi TB-HIV, pemberdayaan masyarakat
dan pasien TB, pendekatan kolaborasi dalam kesehatan paru, manajemen
TB resisten obat, serta penelitian tuberkulosis (Depkes RI, 2011).
2.1.7.Organisasi Pelaksanaan
Organisasi pelaksanaan Pengendalian TB terdiri dari aspek
manajemen program dan aspek tatalaksana pasien TB.
a. Aspek manajemen program
Tingkat Pusat
Upaya pengendalian TB dilakukan melalui Gerakan Terpadu
Nasional Pengendalian Tuberkulosis (Gerdunas-TB) yang merupakan
forum kemitraan lintas sektor dibawah koordinasi Menko Kesra.
Menteri Kesehatan R.I. sebagai penanggung jawab teknis upaya
pengendalian TB. Dalam pelaksanaannya program TB secara Nasional
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan, cq. Sub Direktorat Tuberkulosis.
Tingkat Propinsi
Di tingkat propinsi dibentuk Gerdunas-TB Propinsi yang
terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan struktur
organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaan
program TB di tingkat propinsi dilaksanakan Dinas Kesehatan
Propinsi.
Tingkat Kabupaten/Kota
Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Gerdunas-TB kabupaten /
kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan
struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten / kota.

Dalam pelaksanaan program TB di tingkat Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
b. Aspek Tatalaksana pasien TB
Dilaksanakan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, BP4/Klinik dan Dokter
Praktek Swasta.
Puskesmas
Dalam pelaksanaan di Puskesmas, dibentuk kelompok
Puskesmas Pelaksana (KPP) yang terdiri dari Puskesmas Rujukan
Mikroskopis (PRM), dengan dikelilingi oleh kurang lebih 5 (lima)
Puskesmas Satelit (PS). Pada keadaan geografis yang sulit, dapat
dibentuk Puskesmas Pelaksana Mandiri (PPM) yang dilengkapi tenaga
dan fasilitas pemeriksaan sputum BTA.
Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum, Balai/Baiali Besar Kesehatan Paru
Masyarakat (B/BKPM), dan klinik lannya dapat melaksanakan semua
kegiatan tatalaksana pasien TB.
Dokter Praktek Swasta (DPS) dan fasilitas layanan lainnya.
Secara umum konsep pelayanan di Balai Pengobatan dan DPS
sama dengan pelaksanaan pada rumah sakit dan Balai Penobatan
(klinik).
2.1.8.Penemuan Kasus Tuberkulosis
Tahap awal penemuan dilakukan dengan menjaring mereka yang
memiliki gejala:
Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3
minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu
dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu
makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam
hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan.
Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada penyakit paru
selain TB, seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru,
dan lain-lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih

tinggi, maka setiap orang yang datang ke Fasyankes dengan gejala
tersebut diatas, dianggap sebagai seorang tersangka (suspek) pasien
TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis
langsung.
Suspek TB MDR adalah semua orang yang mempunyai gejala TB
dengan salah satu atau lebih kriteria suspek dibawah ini:
1. Pasien TB yang gagal pengobatan kategori 2 (kasus kronik)
2. Pasien TB tidak konversi pada pengobatan kategori 2.
3. Pasien TB dengan riwayat pengobatan TB di fasyankes Non DOTS.
4. Pasien TB gagal pengobatan kategori 1.
5. Pasien TB tidak konversi setelah pemberian sisipan.
6. Pasien TB kambuh.
7. Pasien TB yang kembali berobat setelai lalai/default.
8. Pasien TB dengan riwayat kontak erat pasien TB MDR
9. ODHA dengan gejala TB-HIV.
Setelah menjaring mereka yang memiliki gejala, tahap selanjutnya
adalah pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak berfungsi untuk
menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan
potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis
dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan
dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa Sewaktu-Pagi-Sewaktu
(SPS).
S (sewaktu): dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang
berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah
pot dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua.
P (Pagi): dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera
setelah bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri kepada
petugas di Fasyankes.
S (sewaktu): dahak dikumpulkan di Fasyankes pada hari kedua, saat
menyerahkan dahak pagi.

2.1.9.Diagnosis Tuberkulosis
Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari,
yaitu sewaktu - pagi - sewaktu (SPS). Selanjutnya, diagnosis TB Paru pada
orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB. Pada program
TB nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis
merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto toraks, biakan
dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis sepanjang
sesuai dengan indikasinya. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya
berdasarkan pemeriksaan foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu
memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi
overdiagnosis (Depkes, 2011).
Diagram 2.1 Alur Diagnosis TB Paru
2.1.10. Pengobatan Tuberkulosis
a. Prinsip Pengobatan
Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah
kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan

mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap Obat Anti Tuberkulosis
(OAT). Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip
sebagai berikut:
OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat,
dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori
pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian
OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan
sangat dianjurkan.
Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan
pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh
seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).
Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan
lanjutan.
Tahapan pengobatan Tuberkulosis terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap
awal (intensif) dan tahap lanjutan.
Tahap awal (intensif) : pada tahap intensif (awal) pasien mendapat
obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah
terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut
diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam
kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien TB BTA positif
menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 bulan.
Tahap Lanjutan : Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih
sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan
penting untuk membunuh kuman persisten sehingga mencegah
terjadinya kekambuhan.
b. Paduan OAT yang digunakan di Indonesia
Paduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) disediakan dalam bentuk
paket, dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin

kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai. Satu (1) paket
untuk satu (1) pasien dalam satu (1) masa pengobatan.
1. Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian
Tuberkulosis di Indonesia:
Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3.
Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3.
Disamping kedua kategori ini, disediakan paduan obat sisipan
(HRZE)
Kategori Anak: 2HRZ/4HR
Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien TB resistan obat di
Indonesia terdiri dari OAT lini ke-2 yaitu Kanamycin, Capreomisin,
Levofloksasin, Ethionamide, sikloserin dan PAS, serta OAT lini-1,
yaitu pirazinamid and etambutol.
2. Paduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan dalam bentuk paket
berupa obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini
terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya
disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam
satu paket untuk satu pasien.
3. Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid,
Rifampisin, Pirazinamid dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk
blister. Paduan OAT ini disediakan program untuk digunakan dalam
pengobatan pasien yang mengalami efek samping OAT KDT.
c. Paduan OAT lini pertama dan peruntukannya.
1. Kategori-1 (2HRZE/ 4H3R3) Paduan OAT ini diberikan untuk pasien
baru:
• Pasien baru TB paru BTA positif.
• Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif
• Pasien TB ekstra paru
Tabel 2.1 Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 1

Tabel 2.2 Dosis paduan OAT-Kombipak untuk Kategori 1
2. Kategori -2 (2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3)
Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah
diobati sebelumnya:
• Pasien kambuh
• Pasien gagal
• Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (default)
Tabel 2.3 Dosis untuk paduan OAT KDT Kategori 2
Tabel 2.4 Dosis paduan OAT Kombipak untuk Kategori 2
Catatan:

• Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk
streptomisin adalah 500mg tanpa memperhatikan berat badan.
• Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB dalam keadaan khusus.
•Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram yaitu dengan
menambahkan aquabidest sebanyak 3,7ml sehingga menjadi 4ml.
(1ml = 250mg).
3. OAT Sisipan (HRZE)
Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk
tahap intensif kategori 1 yang diberikan selama sebulan (28 hari).
Tabel 2.5 Dosis KDT untuk Sisipan
Tabel 2.6 Dosis OAT Kombipak untuk Sisipan
Penggunaan OAT lini kedua misalnya golongan aminoglikosida
(misalnya kanamisin) dan golongan kuinolon tidak dianjurkan
diberikan kepada pasien baru tanpa indikasi yang jelas karena potensi
obat tersebut jauh lebih rendah daripada OAT lini pertama. Disamping
itu dapat juga meningkatkan terjadinya risiko resistensi pada OAT lini
kedua.
2.1.11. Pemantauan dan Evaluasi Program
Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen
untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Pemantaun
dilaksanakan secara berkala dan terus menerus, untuk dapat segera

mendeteksi bila ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan, supaya dapat dilakukan tindakan perbaikan segera.
Evaluasi dilakukan setelah suatu jarak-waktu (interval) lebih lama,
biasanya setiap 6 bulan s/d 1 tahun. Dengan evaluasi dapat dinilai sejauh
mana tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya dicapai. Dalam
mengukur keberhasilan tersebut diperlukan indikator. Hasil evaluasi
sangat berguna untuk kepentingan perencanaan program.
Masing-masing tingkat pelaksana program (UPK, Kabupaten/Kota,
Propinsi, dan Pusat) bertanggung jawab melaksanakan pemantauan
kegiatan pada wilayahnya masing-masing.
Seluruh kegiatan harus dimonitor baik dari aspek masukan (input),
proses, maupun keluaran (output). Cara pemantauan dilakukan dengan
menelaah laporan, pengamatan langsung dan wawancara dengan petugas
pelaksana maupun dengan masyarakat sasaran.
Untuk menilai kemajuan atau keberhasilan penanggulangan TB
digunakan beberapa indikator. Indikator penanggulangan TB secara
Nasional ada 2 yaitu:
Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR)
CDR adalah persentase jumlah pasien baru BTA positif yang
ditemukan dan diobati dibanding jumlah pasien baru BTA positif
yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Case Detection Rate
menggambarkan cakupan penemuan pasien baru BTA positif pada
wilayah tersebut.
Case Detection Rate menggambarkan cakupan penemuan
pasien baru BTA positif pada wilayah tersebut.
Rumus :
Jumlah pasienbaruTB BTA positif yangdilaporkanPerkiraan jumlah pasien baruTB BTA positif
x100 %
Perkiraan jumlah pasien baru TB BTA positif diperoleh
berdasarkan perhitungan angka insidens kasus TB paru BTA positif
dikali dengan jumlah penduduk. Target Case Detection Rate
Program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional minimal 70%.

Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate = SR).
Angka kesembuhan adalah angka yang menunjukkan persentase
pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan
(baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien
baru TB paru BTA positif yang tercatat. Dengan demikian angka ini
merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka
pengobatan lengkap.
Rumus :
JumlahbaruTB BTA positif (sembuh+¿ pengobatanlengkap)Jumlah pasienbaru TB BTA yangdiobati
x 100 %
2.2 Sistem
2.3.1.Pengertian Sistem
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah erangkat
unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu
totalitas (KBBI, 2015). Sedangkan, menurut Ryans, sistem adalah
gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses
atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya
menghasilkan sesuatu yang ditetapkan.
2.3.2.Unsur-unsur Sistem
Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem dapat dikelompokkan menjadi
enam unsur yaitu :
a. Masukan (input) adalah kumpulan bagian atau elemen yang
terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat
berfungsinya sistem tersebut. Dalam sistem pelayanan kesehatan,
masukan terdiri dari tenaga, dana, metoda, sarana/material.
b. Proses (process) adalah kumpulan bagian atau elemen yang
terdapat dalam sistim dan yang berfungsi untuk mengubah
masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Dalam sistem
pelayanan kesehatan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan penilaian.
c. Keluaran (output) adalah kumpulan bagian atau elemen yang
dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem.

Lingkungan
Masukan Proses Keluaran Dampak
Umpan Balik
d. Umpan balik (feed back) adalah kumpulan bagian atau elemen
yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai
masukan bagi sistem tersebut.
e. Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran
suatu sistem.
f. Lingkungan (environment) adalah dunia di luar sistem yang tidak
dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap
sistem (Azrul, 1996).
Diagram 2.2 Hubungan Unsur-unsur Sistem
2.3.3.Pendekatan Sistem
Dibentuknya suatu sistem pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan
tertentu yang telah ditetapkan. Untuk terbentuknya sistem tersebut perlu
dirangkai berbagai unsur atau elemen sedemikian rupa sehingga secara
keseluruhan membentuk suatu kesatuan dan secara bersama-sama
berfungsi untuk mencapai tujuan kesatuan. Apabila prinsip pokok atau
cara kerja sistem ini diterapkan pada waktu menyelenggarakan pekerjaan
administrasi, maka prinsip pokok atau cara kerja ini dikenal dengan nama
pendekatan sistem (system approach).
Pendekatan sistem adalah penerapan suatu prosedur yang logis dan
rasional dalam merancang suatu rangkaian komponen-komponen yang
berhubungan sehingga dapat berfungsi sebagai suatu kesatuan mencapai
tujuan yang telah ditetapkan (Marliana, 2008).

2.3.4.Evaluasi Program
Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing
menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan
program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan
penaksiran (appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian
(assessment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil
kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik,
evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau
manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan
mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada
tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program
telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa
masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.
Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian
evaluasi sering digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolahan
program yang mencakup :
a. Evaluasi pada tahap perencanaan (EX-ANTE).
Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk
memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan
kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan
sebelumnya.
b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ON-GOING).
Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk
menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (EX-POST)
Pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk
melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.
Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai

relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil
dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan
hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan
keluaran) dari suatu program (Anonim, 2011).
BAB III
METODE EVALUASI

3.1 Pengumpulan Data
Pengumpulan data bersumber dari data primer dan data sekunder.
Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan koordinator
pelaksana Program Pengendalian Tuberkulosis di UPT Puskesmas
Kecamatan Beji. Selain itu, data sekunder didapatkan dari Profil UPT
Puskesmas Kecamatan Beji 2014 dan Buku Registrasi Pasien TB Tahun 2014
di Klinik TB Paru.
3.2 Cara penilaian dan Evaluasi
3.2.1.Penetapan Indikator dan tolok ukur penilaian
Evaluasi dilakukan pada Program Pengendalian Tuberkulosis di UPT
Puskesmas Beji. Sumber rujukan tolak ukur penilaian yang digunakan
adalah sebagai berikut :
1. Profil UPT Puskesmas Kecamatan Beji 2014
2. Pedoman Nasional Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis Paru tahun
2011
3. Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010-2014
Tabel 3.1 Penetapan Indikator dan tolok ukur penilaian
Variabel Definisi operasional atau rumus Target
Prevalensi TB
(per 100.000)
Jumlah suspek yangdiperiksaJumlah penduduk
x 100.000 180%
Case Detection
Rate (%)
Jumlah pasienbaruTB BTA positif yangdilaporkanPerkiraan jumlah pasien baruTB BTA positif
x100 %
90%
Success Rate
(%)
JumlahbaruTB BTA positif (sembuh+¿ pengobatanlengkap)Jumlah pasien baruTB BTA yang diobat i
x 100 %88%
Sumber : Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010-2014
3.3 Cara Analisis
3.3.1.Menetapkan indikator dan tolok ukur dari unsur keluaran.

Mengetahui atau menetapkan indikator dan tolok ukur atau standar
yang ingin dicapai merupakan langkah pertama untuk menentukan adanya
suatu masalah dari pencapaian hasil output. Indikator didapatkan dari
berbagai rujukan, rujukan tersebut harus realistis dan sesuai sehingga layak
digunakan untuk mengukur. Tolok ukur juga diperoleh dari rujukan.
3.3.2.Membandingkan pencapaian masing-masing indikator keluaran dengan
tolok ukurnya.
Langkah selanjutnya adalah memabandingkan hasil pencapaian
program (output) dengan tolok ukurnya. Jika terdapat kesenjangan antara
tolok ukur dengan hasil pencapaian pada unsur keluaran maka disebut
sebagai masalah.
3.3.3.Menetapkan prioritas masalah.
Masalah bisa lebih dari satu, tergantung dari indikator yang dipakai.
Sehingga perlu dibuat prioritas masalah. Tujuan menetapkan prioritas
masalah adalah menetapkan masalah yang akan dipecahkan masalahnya
terlebih dahulu. Jika masalah lebih dari satu, maka penetapan prioritas
masalah dilakukan dengan teknik kriteria matriks. Kriteria ini dibedakan
atas tiga macam, yaitu:
a) Pentingnya masalah (importancy / I), makin penting masalah tersebut,
makin diprioritaskan penyelesainnya. Ukuran pentingnya masalah yaitu :
1) Besarnya masalah (prevalence / P)
2) Akibat yang ditimbulkan oleh masalah (severity / S)
3) Kenaikan besarnya masalah (rate of increase / RI)
4) Derajat keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi (degree of
unmeet need / DU)
5) Keuntungan sosial karena selesainya masalah (social benefit / SB)
6) Rasa prihatin masyarakat terhadap masalah (public concern / PB)
7) Suasana politik (political climate / PC)
b) Kelayakan teknologi (technical feasibility / T), makin layak teknologi
yang tersedia dan yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah, makin
diprioritaskan masalah tersebut. Kelayakan teknologi yang dimaksud
adalah menunjuk penguasaan ilmu dan teknologi yang sesuai.

c) Sumber daya yang tersedia (resources availability / R), makin tersedia
sumber daya yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah makin
diprioritaskan masalah tersebut. Sumber daya yang dimaksud adalah yang
menunjuk pada tenaga (man), dana (money) dan sarana (material).
Beri nilai antara 1 (tidak penting) sampai dengan 5 (sangat penting)
untuk setiap kriteria yang sesuai. Perhitungan prioritas masalah dilakukan
dengan rumus “I x T x R”. Masalah yang dipilih sebagai prioritas adalah
yang memiliki nilai tertinggi.
3.3.4.Membuat kerangka konsep dari masalah yang diprioritaskan.
Untuk menentukan penyebab masalah, gambarkan terlebih dahulu
proses terjadinya masalah atau kerangka konsep prioritas masalah,
sehingga diharapkan semua faktor penyebab masalah dapat diketahui dan
diidentifikasi.
3.3.5. Identifikasi penyebab masalah.
Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan unsur masukan,
proses, umpan balik dan lingkungan sebagai faktor yang diperkirakan
berpengaruh terhadap prioritas masalah. Selanjutnya menentukan tolok
ukur dari masing-masing unsur tersebut. Setelah itu, bandingkan
pencapaian dari unsur-unsur tersebut dengan tolok ukurnya, kesenjangan
yang ada ditetapkan sebagai penyebab masalah.
3.3.6.Membuat alternatif jalan keluar.
Sesuai dengan penyebab masalah yang ditemukan, maka dibuat
alternatif jalan keluar. Alternatif jalan keluar dibuat dengan melihat
kerangka konsep prioritas masalah, sehingga tersusun daftar alternatif
jalan keluar, dengan melihat kondisi dan situasi fasilitas kesehatan di
puskesmas.
3.3.7.Menentukan prioritas cara pemecahan masalah.
Setelah membuat alternatif jalan keluar yang dianggap paling baik dan
memungkinkan, laangkah selanjutnya adalah menentukan prioritas cara
pemecahan masalah. Pemilihan cara pemecahan masalah ini dengan
memakai teknik kriteria matriks. Dua kriteria yang lazim digunakan
adalah:

a) Efektifitas jalan keluar (effectifity/ E), menetapkan nilai efektifitas
untuk setiap alternatif jalan keluar, yakni dengan memberikan angka 1
(paling tidak efektif) sampai dengan angka 5 (paling efektif). Prioritas
jalan keluar adalah yang nilai efektifitasnya paling tinggi. Untuk
menentukan efektifitas jalan keluar, dipergunakan kriteria tambahan
sebagai berikut:
1) Besarnya masalah yang dapat diselesaikan (magnitude/ M) Makin
besar masalah yang dapat di atasi, makin tinggi prioritas jalan keluar
tersebut.
2) Pentingnya jalan keluar (importancy/ I) Pentingnya jalan keluar
dikaitkan dengan kelanggengan masalah. Makin langgeng selesai
masalahnya, makin penting jalan keluar tersebut.
3) Sensivitas jalan keluar (vuneberality/ V) Sensitivitas dikaitkan
dengan kecepatan jalan keluar mengatasi masalah. Makin cepat masalah
teratasi, makin sensitif jalan keluar tersebut.
b) Efisiensi Jalan Keluar (efficiency/C), menetapkan nilai efisiensi untuk
setiap alternatif jalan keluar, yakni dengan memberikan angka 1 (paling
tidak efisien) sampai dengan angka 5 (paling efisien). Nilai efisien ini
biasanya dikaitkan dengan biaya (cost) yang diperlukan untuk
melaksanakan jalan keluar. Makin besar biaya yang diperlukan, makin
tidak efisien jalan keluar tersebut.
Menghitung nilai P (prioritas) untuk setiap alternatif jalan keluar yaitu
dengan membagi hasil perkalian nilai M x I x V dengan nilai C. Jalan
keluar dengan nilai P tertinggi, adalah prioritas jalan keluar terpilih. Lebih
jelas rumus untuk menghitung prioritas jalan keluar dapat dilihat dibawah
ini :
P= M x I x VC
Keterangan = P: priority, M: Magnitude, I: Importancy , V: Vulnerability,
C : Cost
3.4 Cara Evaluasi
3.4.1.Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual dengan data di tabel-
tabel yang tersedia, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan secara
komputerisasi.
3.5 Waktu dan Lokasi
Pengambilan data dilakukan mulai Mei 2015 – Juni 2015 di Klinik TB
Paru UPT Puskesmas Beji.
BAB IV
PENYAJIAN DATA

4.1 Data Umum
4.1.1. Keadaan Geografis
Kode Puskesmas : P.3.27.606.02.01
Nama Puskesmas : BEJI
Kecamatan : BEJI
Kabupaten/Kotamadya : DEPOK
Propinsi : JAWA BARAT
Puskesmas Beji merupakan Puskesmas Rawat Jalan yang terletak
di Jl. Bambon Raya no 7B Kelurahan Beji Timur,berdiri sekitar bulan
Agustus tahun 1981, pada awal berdirinya karyawannya hanya
berjumlah 12 orang. Seiring dengan berjalannya waktu Puskesmas Beji
berkembang pesat, dan terus meningkatkan pelayanan. Saat ini
Puskesmas Beji mempunyai karyawan 66 orang, sejak bulan April 2014
mulai menjadi Puskesmas 24 jam dan PONED (Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar) dan klinik dampak merokok. Saat ini
Puskesmas menyelenggarakan Rawat jalan 24 Jam dan melayani
persalinan normal. Dan pada tahun yang sama Puskesmas Beji juga mulai
membuka Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terletak di Jl. Halmahera
Depok Utara Kelurahan Beji.
Puskesmas Beji adalah Puskesmas Kecamatan yang membawahi 2
Puskesmas Kelurahan, yaitu : Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas
Tanah Baru. Dalam kegiatannya Puskesmas Beji bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 2 wilayah kelurahan yaitu
6 Kelurahan Beji dan Beji Timur dengan luas wilayah kerja 3,17 km2.
Kondisi alam di wilayah kerja Puskesmas Beji sebagian besar merupakan
daerah pemukiman dimana apabila musim penghujan lokasi daerah yang
rawan bencana terutama banjir ada di Kelurahan Beji yaitu di RW 03
dan Kelurahan Beji Timur di RW 01.
Letaknya dekat dengan perumahan dan dekat dengan Kampus UI
Depok sehingga cukup mudah dilalui kendaraan mobil dan motor sampai
ke lokasi Puskesmas, disamping juga dilalui oleh jalur angkot. Adapun

wilayah kerja Puskesmas Beji dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai
berikut :
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Beji
Keterangan :
- Batas Utara : Kelurahan Kukusan
- Batas Selatan : Kecamatan Pancoran Mas
- Batas Barat : Kelurahan Tanah Baru
- Batas Timur : Kelurahan Kemiri Muka
Semakin berkembangnya jumlah dan jenis pelayanan kesehatan
dan beragamnya tuntutan dari masyarakat saat ini dan di masa yang akan
datang maka UPT Puskesmas Kecamatan Beji selalu berusaha untuk
dapat memenuhi kriteria mutu pelayanan kesehatan yang baik dengan
selalu meningkatkan kinerja sumber daya manusia serta mengembangkan
fungsi sosial Puskesmas.
4.1.2. Data Demografis
Berdasarkan proyeksi penduduk BPS Kota Depok penduduk
wilayah Puskesmas Beji tahun 2014 meliputi Kelurahan Beji dan Beji
Timur berjumlah 66.645 orang . Penduduk Kelurahan Beji berjumlah
54.569 orang dengan kepadatan penduduk pada sebesar 3818 orang/km2

dan pada kelurahan Beji Timur berjumlah 12.076 orang dengan
kepadatan penduduk 980 orang/km2.
Jumlah Penduduk : 66.645 orang
Kepadatan : 2.505 orang/km2
Jumlah KK : 19.458
Laki-laki : 33.414 orang
Perempuan : 33.231 orang
Jumlah Ibu Hamil : 1760 orang
Jumlah Bulin/Bufas : 1680 orang
Jumlah Bayi : 1536 orang
Jumlah Balita : 5910 orang
Jumlah PUS : 24.423 orang
Jumlah Lansia : 2035 orang
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok
Umur
Grafik 4.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Beji tahun 2014
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian
Tabel 4.1 Peduduk Puskemas Beji Berdasarkan Mata pencarian

3. Jumlah Penduduk menurut Agama
Tabel 4.2 Peduduk Puskemas Beji Menurut Agama
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar
pembangunan karena pelaksanaan pembangunan tidak cukup hanya
mengandalkan sumber daya alam tetapi tergantung juga pada sumber
daya manusia. Mutu penduduk wilayah Puskesmas Beji dapat dilihat
dari kemampuan baca tulis juga tingkat pendidikan formal yang
diselesaikan. Tingkat pendidikan formal penduduk dapat dijadikan
dasar perencanaan program kesehatan khususnya bidang promotif dan
preventif.
Grafik 4.2 Jumlah Penduduk Wilayah Puskesmas Beji Menurut
Pendidikan
5. Persentase Penduduk berdasarkan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Pra Bayar

Penduduk wilayah Puskesmas Beji yang mendapatkan jaminan
kesehatan prabayar berupa Askes PNS, Jamkesmas dan Jamkesda
sebanyak 30.120 jiwa atau 45 % dari jumlah penduduk Puskesmas
Beji.
Grafik 4.3 Persentase Cakupan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar di
Wilayah Puskesmas Beji Tahun 2014
4.2 Data Puskesmas
4.2.1. Gambaran Umum dan Sarana Kesehatan
Sejak pertengahan tahun 2012, tepatnya 1 Juli 2012 Puskesmas
Beji telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008 pada beberapa pelayanannya. Adapun pelayanan yang telah
menerapkan antara lain : Poli Umum, Poli Gigi, Poli MTBS,
Laboratorium,Loket, Farmasi dan TU sebagai Penunjang. Pada tanggal 4
Desember 2012 Puskesmas Beji telah 7 dilakukan audit sertifikasi ISO
9001:2008 oleh Badan Sertifikasi Beureu Veritas (BV) dan berhak untuk
mendapatkan sertifikat ISO: 9001:2008. Dengan di terapkannya Sistem
Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan ISO 9001 : 2008 diharapkan
Puskesmas Kecamatan Beji dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Pada bulan
Juli 2014 dan Januari 2015 UPT Puskesmas Beji telah dilakukan audit

Surveilance ISO 9001:2008 oleh Badan Sertifikasi SAI Global pada
beberapa pelayanan yaitu : poli umum, Poli KIA/KB, poli gigi, Farmasi,
Loket dan TU sebagai pendukung.
Tabel 4.3 Bangunan Fisik
Puskesmas Beji juga memiliki sarana penunjang kesehatan yaitu
kendaraan. Kendaraan-kendaraan tersebut antara lain Pusling (1 dengan
kondisi kurang baik), Ambulan Siaga (2 dengan kondisi baik), Motor 3 (2
dengan kondisi baik dan 1 kurang baik).
Puskesmas Beji pada tahun 2014 memiliki 66 karyawan, terdiri
dari pegawai negeri sipil dan 8 sukwan/swakelola dengan berbagai
kualifikasi bidang pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel
berikut :
Tabel 4.4 Keadaan SDM di Puskesmas Beji Tahun 2014

4.2.2. Kegiatan Puskesmas
Puskesmas Beji termasuk kategori Puskesmas kawasan perkotaan,
Puskesmas Beji dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di
wilayahnya melakukan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat,yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional
merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga,
kelompok, dan masyarakat. Upaya Kesehatan Perseorangan yang
selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian
kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan,
pencegahan,penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

1. Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Upaya Pelayanan Masyarakat Esensial
- Pelayanan Promosi Kesehatan (Promkes)
- Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pelayanan Kesehatan Ibu,anak dan keluarga Berencana
- Pelayanan Gizi - Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
- Upaya kesehatan Olahraga
- Upaya kesehatan Jiwa
- Upaya Kerja dan Indra
- Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
- Usaha Kesehatan Sekolah
- Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- Upaya Kesehatan Tradisional
- Upaya Kesehatan Lansia
2. Upaya Kesehatan Perorangan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan
pemeriksaaan penunjang
a. Layanan Umum dan 24 Jam dan Kegawatdaruratan
b. Layanan Gigi dan Mulut
c. MTBS
d. Lansia
e. Layanan KIA dan KB
f. Konseling Gizi dan Menyusui
g. Klinik Sanitasi
h. Klinik TB Paru
i. Layanan Farmasi
j. Layanan Laboratorium
k. PONED
l. Puskesmas Pembantu (Pustu)

4.2.3. Struktur Organisasi

4.3 Data Khusus
Grafik 4.5 Gambaran Kasus BTA + Puskesmas Beji tahun 2010-2014
Tabel 4.5 Jumlah Pasien Baru TB BTA (+) dan BTA (-) Tahun 2014
BTA (+) BTA (-) Total
Laki-laki 31 37 68
Perempuan 19 10 29
Diobati 50 47 97
Tabel 4.6 Pasien Sembuh dan Pengobatan Lengkap Tuberkulosis Tahun 2014
Sembuh Lengkap
Triwulan I 7 11
Triwulan II 11 11
Triwulan III 2 7
Triwulan IV 3 2
Total 23 31
Tabel 4.7 Suspek Tuberkulosis Tahun 2014
Suspek
Tahun 2014 99

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
5.1 Identifikasi Masalah
Masalah merupakan kesenjangan antara tolok ukur dengan hasil
pencapaian pada unsul keluaran. Proses identifikasi masalah dimulai dengan
mengetahui keluaran program kerja Puskesmas. Kemudian jika ditemukan
kesenjangan antara keluaran dengan tolok ukur, maka hal tersebut
merupakan masalah pada program di Puskesmas. Masalah yang ditemukan
pada program Pengendalian TB di Puskesmas Beji adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1 Evaluasi Keluaran
VariabelDefinisi operasional atau rumus
Targe
t
Masala
h
Prevalens
i TB (per
100.000)
Jumlah suspek yang diperiksaJumlah penduduk
x 100.000
9966.645
x100 %=148.54 %
180% -
Case
Detection
Rate (%)
Jumlah pasienbaruTB BTA positif yangdilaporkanPerkiraan jumlah pasien baruTB BTA positif
x100 %
50205
x100 %=24.3%
90% +
Success
Rate (%)
JumlahbaruTB BTA positif (sembuh+¿ pengobatanlengkap)Jumlah pasienbaru TB BTA yangdiobati
x 100 %
(23+31)97
x 100 %=55.6 %
88% +
5.2 Menetapkan daftar masalah

Masalah yang ditemukan pada program Pengendalian TB di Puskesmas
Beji Tahun 2014 adalah :
a. Case Detection Rate (CDR) puskesmas adalah 24.3%, lebih kecil dari
indikator yang seharusnya dicapai, yaitu 90%.
b. Success Rate puskesmas adalah 55.6%, lebih kecil dari indikator yang
seharusnya dicapai, yaitu 88%.
5.3 Penetapan prioritas masalah
Dalam menetapkan prioritas masalah, terdapat kriteria matriks
pemilihan prioritas masalah. Pada tehnik ini, setiap masalah diberikan skor
berdasarkan variabel pentingnya masalah (Importancy = I) yang diukur
bedasarkan pada besarnya masalah (Prevalence = P), akibat yang
ditimbulkan (Severity = S), kenaikan besarnya masalah (Rate of Increase =
RI), derajat keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi (Degree of Unmeet
need = DU), keuntungan sosial karena terselesaikannya masalah (Social
Benefit = SB), perhatian masyarakat (Public Concern = PCo) dan iklim
politik (Political Climate = PC). Selain itu digunakan juga variabel
kelayakan tehnologi (Tehnical feasibility = T) yaitu semakin layak tehnologi
yang tersedia dan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah, semakin
diprioritaskan masalah tersebut. Digunakan pula variabel sumber daya yang
tersedia (Reasources availability = R) yaitu semakin tersedia sumber daya
yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah, makin diprioritaskan masalah
tersebut. Diberikan skor antara 1 (tidak penting) sampai dengan 5 (sangat
penting) untuk setiap variabel dan kriteria.
Tabel 5.2 Penentuan Prioritas Masalah
Daftar Masalah
Impotancy (I) T R Jumlah
IxTxRP S RI DU SB PCo PC
Belum tercapainya CDR 5 5 3 5 5 1 5 2 5 290
Belum tercapainya SR 4 3 5 3 4 1 5 5 2 250

a. Penetapan prioritas masalah berdasarkan besarnya masalah (Prevalence)
Nilai untuk besarnya masalah pada target pencapaian CDR
diberikan nilai 5 karena semakin banyak penemuan pasien TB dengan
BTA (+) maka pencegahan penularan TB akan semakin baik. SR juga
penting dalam pencegahan penularan TB, karena berkaitan dengan
pengobatan pasien TB, namun tidak sepenting penemuan kasus BTA (+)
pada deteksi kasus TB. Selain itu, jarak kesenjangan antara target dan
pencapaian CDR lebih besar dibandingkan SR, sehingga penulis
memberikan nilai 4 untuk masalah belum tercapainya SR.
b. Penetapan prioritas masalah berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari
masalah ini (Severity).
Pendeteksian kasus pasien TB paru BTA (+) yang belum tercapai
atau masih kurang dari target mengindikasikan bahwa masih ada sumber
infeksi TB di masyarakat yang berpotensi untuk menularkan ke orang
sekitarnya. Sehingga akibat yang ditimbulkan akan semakin besar, yaitu
jumlah penderita TB semakin banyak. Oleh karena itu, penulis
memberikan nilai 5 untuk belum tercapainya CDR, sedangkan nilai 3
untuk belum tercapainya SR walaupun sama-sama memberikan
kontribusi dalam penularan TB, namun pada penyebut SR terdapat angka
pasien yang sembuh dari TB yang tidak menularkan ke orang lain.
c. Penetapan prioritas masalah berdasarkan kenaikan besarnya masalah
(Rate of Increase).
Pasien TB yang tidak diobati akan menyebabkan semakin
bertambah banyaknya masyarakat yang tertular TB sehingga jumlah
pasien TB akan bertambah. Kenaikan besarnya masalah lebih besar
akibat kurangnya pencapaian SR dibandingkan CDR. Sehingga penulis
memberikan nilai 5 pada kurang tercapainya SR, sedangkan nilai 3 untuk
kurang tercapainya CDR.

d. Penetapan prioritas masalah berdasarkan derajat keinginan masyarakat
yang tidak terpenuhi (Degree Of Unmeet need).
Keinginan masyarakat akan penyakit TB adalah bebas dari
penularan TB, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Selain
itu, masyarakat juga menginginkan penyakitnya untuk terdeteksi lebih
awal sehingga kemungkinan untuk sembuh lebih baik dan terhindar dari
komplikasi yang diakibatkan oleh penyakit TB. Oleh karena itu, penulis
memberikan nilai 5 pada masalah belum tercapainya CDR, sedangkan
nilai 3 pada masalah belum tercapainya SR.
e. Penetapan prioritas masalah berdasarkan keuntungan sosial (Social
Benefit)
Jika tingkat keberhasilan pengobatan tercapai, maka produktivitas
pasien TB akan semakin tinggi, sehingga kebutuhan ekonomi dapat
terpenuhi. Keuntungan sosial yang didapat juga semakin besar. Oleh
karena itu, penulis memberikan nilai 5 pada masalah kurang tercapainya
SR, sedangkan nilai 4 pada keuntungan sosial untuk pemenuhan
kurangnya CDR.
f. Penetapan prioritas masalah berdasarkan rasa prihatin masyarakat
terhadap masalah (Public Concern)
Rendahnya angka CDR dan SR di puskesmas sama-sama kurang
mendapat perhatian dari masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena
kurangnya sosialisasi mengenai target nasional terhadap pengendalian
TB, sehingga kedua masalah diberikan nilai 1.
g. Penetapan prioritas masalah berdasarkan suasana politik (Political
Climate)
Dunia telah menempatkan TB sebagai salah satu indikator
keberhasilan pencapaian MDGs. Secara umum ada 4 indikator yang
diukur, yaitu Prevalensi, Mortalitas, Penemuan kasus dan Keberhasilan

pengobatan. Dari ke-4 indikator tersebut 3 indikator sudah dicapai oleh
Indonesia, angka kematian yang harus turun separuhnya pada tahun 2015
dibandingkan dengan data dasar (baseline data) tahun 1990, dari
92/100.000 penduduk menjadi 46/100.000 penduduk. Indonesia telah
mencapai angka 39/100.000 penduduk pada tahun 2009. Angka
Penemuan kasus (case detection rate) kasus TB BTA positif mencapai
lebih 70%. Indonesia telah mencapai angka 73,1% pada tahun 2009 dan
mencapai 77,3% pada tahun 2010. Angka ini akan terus ditingkatkan
agar mencapai 90% pada tahun 2015 sesuai target RJPMN. Angka
keberhasilan pengobatan (success rate) telah mencapai lebih dari 85%,
yaitu 91% pada tahun 2009.
Indikator-indikator diatas merupakan sasaran program
pengendalian TB sehingga penilaian masalah berdasarkan suasana politik
mendapat nilai yang sama, yaitu 5.
h. Penetapan prioritas masalah berdasarkan dari sudut kelayakan tehnologi
(Technical feasibility)
Teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah CDR
antara lain penggunaan reagen pemeriksaan, mikroskop, dan alat rontgen.
Sedangkan dalam menyelesaikan masalah SR hanya pencatatan dan
mengelompokan obat sesuai nama pasien menggunakan kardus, kedua
hal tersebut dilakukan dengan manual. Oleh karena itu, teknologi yang
mudah digunakan akan semakin tinggi nilainya, maka diberikan nilai 5
pada penyelesaian masalah kurang tercapainya SR, sedangkan nilai 2
untuk masalah kurang tercapainya CDR.
i. Penetapan prioritas masalah berdasarkan sumber daya yang tetrsedia
(Resources availability)
Sumber daya terdiri atas tenaga (man), dana (money) dan sarana
(material). Ketersediaan sumber daya pada masalah penemuan kasus
(CDR) baru BTA (+) lebih besar dibandingkan masalah keberhasilan

pengobatan. Oleh karena itu, nilai 5 untuk masalah kurang tercapainya
CDR, sedangkan nilai 2 untuk masalah kurang tercapainya SR.
5.4 Kesimpulan prioritas masalah
Dari hasil perhitungan matriks, maka ditetapkan masalah yang
menjadi prioritas yaitu belum tercapainya Case Detection Rate.
5.5 Kerangka konsep masalah
Sasaran CDR yang belum tercapai di UPT Puskesmas Kecamatan Beji
merupakan keluaran yang tidak sesuai dengan target. Keluaran merupakan
salah satu unsur sistem, sehingga untuk mengatasi keluaran yang tidak
sesuai target harus dilihat kemungkinan adanya masalah dari masukan,
proses, uman balik dan lingkungan. Penyebab masalah dapat ditetapkan
dengan menggambarkan terlebih dahulu proses terjadinya masalah atau
kerangka konsepnya, sehingga diharapkan semua faktor penyebab masalah
dapat diketahui dan diidentifikasi.
Kerangka konsep belum tercapainya sasaran CDR di UPT Puskesmas
Beji dapat dilihat sebagai berikut :

Belum tercapainya CDR
MasukanProses
Lingkungan Umpan Balik
SDM
Kualitas dan kuantitas SDM
Sarana
Medis & Non Medis
Metode Penemuan tersangkaPenegakan diagnosis
Pengobatan
Dana
Biaya pelaksanaan program
Penyuluhan
Akses pelayanan kesehatanSosial ekonomi dan pendididkan
Lingkungan pemukiman Masukan hasil pelaporan
PenilaianPencatatan dan pelaporan
Pengawasan program
Pelaksanaan
Pemeriksaan ulag dahak
PMO
Organisasi
Job list
Perencanaan
Belum Tercapai CDR
Pembinaan & pelatihan kader
Pencatatan dan pelaporan
Bagan 1 . Kerangka Konsep
5.6 Estimasi penyebab masalah
Estimasi penyebab masalah belum tercapainya sasaran CDR akan
dibahas dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan unsur
masukan, proses, lingkungan dan umpan balik.
Komponen masukan terdiri dari banyak unsur, dari unsur tenaga yang
berpotensi menjadi penyebab masalah adalah kurangnya tenaga petugas
administrasi yang mencatat laporan maupun proses yang sedang berjalan
pada pasien TB. Selama ini, perawat merangkap juga menjadi petugas
administrasi. Selain itu, unsur metode juga berpotensi menjadi penyebab
masalah. Penyuluhan terhadap penderita dan keluarga serta masyarakat
belum maksimal. Poster mengenai TB di ruang tunggu pasien TB hanya
satu, hal ini menunjukan kurangnya sosialisasi TB secara pasif. Penyuluhan
terhadap pasien TB dan keluarga sudah dilakukan, namun kurang efisien
karena hanya memberitahu untuk menggunakan masker saat pasien dan
keluarga mengambil obat ke puskesmas. Penyuluhan kepada masyarakat

juga kurang efektif dan efisien, sehingga tindakan preventif juga minimal.
Oleh karena itu bila tenaga kurang memadai dan penyuluhan yang minimal,
hal ini dapat menyulitkan pelaksanaan program ini.
Komponen proses terdiri dari beberapa unsur, seperti pencatatan dan
pelaporan. Pengisian laporan tertulis pada tahun 2014 tidak rapih dan tidak
lengkap. Hal ini terlihat dari pelaporan penjumlahan kategori-kategori
pasien TB tidak lengkap.
Komponen umpan balik terdiri dari masukan hasil pelaporan setelah
dilaksanakannya program selama satu periode tidak didapatkan adanya
masukan untuk perbaikan program berikutnya. Hasil pelaporan ini
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Puskesmas untuk menyusun
rencana program pada periode selanjutnya sehingga diharapkan adanya
perbaikan dari yang sebelumnya.
5.7 Konfirmasi penyebab masalah
Konfirmasi penyebab masalah dibuat dengan melihat kembali
pencapaian di Puskesma dengan tolok ukur berdasarkan unsur sistem yang
bermasalah yaitu unsur masukan, proses dan umpan balik.
Tabel 5.2 Konfirmasi penyebab masalah pada komponen masukan
Unsur Tolok Ukur PencapaianPenyebab Masalah
Tenaga Tenaga pelaksana minimal: 1 dokter, 1 perawat, 1 petugas administrasi, dan 1 analisis sebagai pemeriksa laboratorium
Terdapat 1 dokter, hanya terdapat 1 perawat merangkap menjadi tenaga administrasi.
(+)
Dana Tersedianya dana khusus untuk pelaksanaan program yang berasal dari APBD dan APBN
Tersedianya dana yang cukup lancar dari APBD, APBN dan GF.
(-)
Sarana Tersedianya sarana:1. Sarana medis: alat-alat
pemeriksaan seperti stetoskop, senter, timbangan, tersimeter, dan termometer
2. Sarana non medis: ruangan dilengkapi dengan ruang tunggu yang terbuka , ruang periksa pasien , ruang laboratorium, ruang suntik, ruang obat, tempat untuk memeriksa, lemari
1. Tersedia
2. Tersedia
(-)

penyimpanan obat, bangku untuk ruang tunggu, status, alat tulis, buku catatan
3. Sarana penyuluhan: brosur, poster
4. Sarana khusus pencatatan dan pelaporan
5. Laboratorium
3. Tersedia, walaupun hanya 1 poster.
4. Tersedia
5. Tersedia
Metode Pengobatan penderita Tuberkulosis Paru sesuai dengan pedoman pemberantasan penyakit Tuberkulosis Paru :
a. Penemuan tersangka pasien TB parub. Penentuan diagnosis pasien TB paruc. Pengobatan pasien TB paru
Penyuluhan kesehatana. Penyuluhan kepada
penderita dan keluargab. Penyuluhan ke masyarakat
Pembinaaan dan pelatihan kader Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis Paru
a. Penemuan tersangka TB dilakukan secara pasif dengan pasien datang sendiri ke puskesmas dan secara aktif oleh kader yang terlatih jika menunjukan gejala khas TB.
b. Sudah sesuai prosedurc. Sudah sesuai prosedurPenyuluhan kesehatan :a. Sudah dilakukan namun
kurang efisienb. Jarang dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukan
(+)
Tabel 5.3 Konfirmasi penyebab masalah pada komponen proses
Unsur Tolok Ukur PencapaianPenyebab Masalah
Perencanan Adanya perencanaan
operasional yang
jelas: jenis kegiatan,
target kegiatan,
waktu kegiatan.
Perencanaan sudah dibuat (-)
Organisasi Adanya struktur pelaksana program Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
Terdapat struktur pelaksana
Sudah terdapat pembagian tugas yang jelas
(-)
Pelaksanaan Penemuan tersangka pasien TB paruPenentuan diagnosis pasien TB paruPengobatan pasien TB paruPengawasan Menelan ObatPemeriksaan ulang dahak pasien TB paru
Sudah sesuai prosedur
Sudah sesuai prosedur
Sudah sesuai prosedurPMO telah ditentukanSudah sesuai prosedur
(-)

Penyuluhan TB Sudah dilakukan saat proses pengobatan
Pencatatan dan pelaporan
Penilaian kegiatan dalam bentuk laporan tertulis secara periodikPengisian laporan tertulis yang lengkapPenyimpanan laporan tertulis yang benar
Laporan tertulis dilakukan secara periodik tahunan
Laporan tertulis tidak lengkapPenyimpanan laporan sudah baik
(+)
Pengawasan Adanya pengawasan eksternal maupun internal
Pengawasan program dilakukan oleh Dinas Kesehatan Depok dan secara internal oleh kepala puskesmas
(-)
Tabel 5.4 Konfirmasi penyebab masalah pada komponen umpan balik
Unsur Tolok Ukur PencapaianPenyebab Masalah
Digunakan data-data
tentang hasil kegiatan
dan analisis sebagai
masukan dan
perbaikan program
selanjutnya
Tidak ada masukan untuk perbaikan program
(+)
5.8 Berbagai penyebab masalah
Berdasarkan tabel konfirmasi berdasarkan komponen masukan, proses dan
umpan balik diatas maka masalah belum tercapainya CDR untuk program
pengendalian TB di UPT Puskesmas Beji tahun 2014 adalah :
1. Komponen masukan :
- kurangnya tenaga atau SDM
- penyuluhan yang masih kurang efektif dan efisien kepada
penderita TB, pasien dan masyarakat.
2. Komponen proses :
- Pencatatan dan pelaporan yang kurang lengkap.
3. Komponen umpan balik :
- Tidak ada masukan untuk perbaikan program sebagai umpan
balik program.

5.9 Penetapan prioritas penyebab masalah
Setelah dilakukan penyaringan penyebab masalah yang berpotensi
menyebabkan belum tercapainya CDR, maka harus dilakukan pemilihan
prioritas penyebab masalah. Prioritas penyebab masalah harus dipilih karena
penyebab masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan semuanya dalam
waktu bersamaan dan karena adanya keterbatasan kemampuan dalam
menyelesaikan masalah. Penetapan prioritas masalah dilakukan dengan
menggunakan teknik kriteria matriks.
Tabel 5.5 Prioritas Penyebab Masalah
No Masalah
Penentu Prioritas Penyebab
Total
C x T x R
C T R
1. Kurangnya tenaga atau SDM 5 3 5 75
2. Penyuluhan yang masih kurang efektif dan
efisien kepada penderita TB, pasien dan
masyarakat.
5 5 5 125
3 Pencatatan dan pelaporan yang kurang lengkap 4 4 4 64
4 Tidak ada masukan untuk perbaikan program
sebagai umpan balik program.
3 4 3 36
Poin Contribution/C kurangnya tenaga kesehatan menyebabkan
kurang maksimalnya pelayanan yang dilakukan di Puskesmas, sehingga
pekerjaan menjadi tumpang tindih dan tidak terfokus, maka diberikan nilai
5. Penyuluhan yang kurang efektif dan efisien juga diberikan nilai 5 karena
penyuluhan pada proses masukan bertujuan untuk pencegahan tertularnya
infeksi TB. Pencatatan dan pelaporan yang kurang lengkap diberikan nilai 4
serta nilai 3 pada masalah umpan balik yaitu tidak adanya masukan untuk
perbaikan program.
Poin Technical Feasibility/T tentang tenaga kesehatan memiliki
kelayakan teknologi yang sudah cukup maka hal ini diberi poin 3.
Penyuluhan membutuhkan sarana seperti poster, lembar balik, dan brosur
bahkan membutuhkan banyak sarana untuk membuat suatu acara

penyuluhan kepada masyarakat, sehingga diberikan nilai 5. Pencatatan dan
pelaporan serta masukan untuk perbaikan program masing-masing diberikan
nilai 4.
Poin Resources/R sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga atau SDM sangatlah penting untuk menunjang program
Pengendalian TB, begitu juga dengan kegiatan penyukuhan sehingga
masing-masing diberi nilai 5. Pencatatan dan pelaporan diberikan nilai 4 dan
untuk masukan untuk program diberikan nilai 3.
Berdasarkan tabel teknik kriteria matriks di atas maka prioritas
penyebab masalah adalah penyuluhan yang masih kurang efektif dan efisien
kepada penderita TB, pasien dan masyarakat.
5.10 Alternatif penyelesaian masalah
Berdasarkan penetapan prioritas penyebab masalah, didapatkan
alternatif pemecahan masalah dan penjabaran programnya adalah:
1. Penyuluhan kepada penderita TB, pasien dan masyarakat
Latar belakang : Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung. Penyuluhan secara langsung seperti seminar
dan diskusi kelompok. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung
seperti menggunakan media yaitu poster, banner, brosur dan
spanduk. Semakin banyaknya penyuluhan mengenai TB, diharapkan
semakin meningkatnya pengetahuan tentang TB. Sehingga angka
penularan dan angka kejadian TB dapat ditekan.
Tujuan : memberikan informasi penyakit Tuberkulosis dan
memodifikasi perilaku pasien, keluarga dan masyarakat agar
kondusif bagi kesehatan.
Alokasi dana :
Media promosi Rp. 100.000
Penyuluh/Ahli acara penyuluhan Rp. 250.000
Acara penyuluhan target > 50 peserta Rp. 500.000 +
Total Rp. 750.000

2. Pelatihan petugas dan kader kesehatan dalam rangka
meningkatkan kualitas penyuluhan
Latar belakang : petugas dan kader kesehatan perlu dilatih secara
berkala. Pelatihan ini sangat bermanfaat di masyarakat, terutama
untuk penjaringan suspek TB. Selain itu, meningkatnya pengetahuan
petugas kesehatan dan kader juga meningkatkan pengetahuan
masyrakat akan penyakit TB.
Tujuan : memberikan pelatihan kepada petugas dan kader
kesehatan agar pengetahuan tentang TB meningkat sehingga dapat
mendeteksi suspek TB di masyarakat dan dapat mensosialisasikan
penyakit TB secara berkala.
Alokasi dana :
Media promosi saat pelatihan Rp. 100.000
Ahli pelatihan Rp. 200.000
Konsumsi Rp. 70.000
ATK Rp. 30.000 +
Total Rp. 400.000
5.11 Memilih prioritas pemecahan masalah
Cara pemecahan masalah telah dibuat dan akan dipilih satu cara
pemecahan masalah yang dianggap paling baik dan memungkinkan.
Pemilihan prioritas cara dari pemecahan masalah ini dengan menggunakan
teknik kriteria matriks, yaitu dengan menentukan:
1. Efektifitas
Efektifitas terdiri dari beberapa faktor yaitu Magnitude (M),
Importancy (I), dan Vulnerability (V). Menetapkan nilai efektifitas
(effectiveness) untuk setiap alternatif jalan keluar, yaitu dengan
memberikan angka 1 (paling tidak efektif) sampai angka 5 (paling
efektif). Prioritas jalan keluar adalah yang nilai efektifitasnya paling
tinggi.

2. Efisiensi (C)
Nilai efisiensi berkaitan dengan biaya (Cost) yang diperlukan
untuk melaksanakan pemecahan masalah. Semakinkecil biaya, semakin
efisien, maka semakin kecil nilainya agara nilai pembaginya lebih kecil,
sehingga jalan keluarnya semakin baik.
3. Prioritas Pemecahan Masalah (P)
Nilai prioritas dinilai dari pembagian nilai C oleh hasil perkalian
nilai M x I x V. Hasil nilai yang tertinggi berarti prioritas jalan keluar
yang terpilih.
Tabel 5.6 Penentuan prioritas pemecahan masalah
No Alternatif Pemecahan Masalah
Efektifitas Efisiensi (C)
Jumlah (P)
M I V MxIxVC
1. Penyuluhan kepada penderita TB, pasien dan masyarakat
5 3 4 4 15
2. Pelatihan petugas dan kader kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyuluhan
4 5 1 2 10
Hasil perhitungan matriks diatas menentukan bahwa prioritas
pemecahan masalah yang terpilih adalah penyuluhan yang dilakukan kepada
penderita TB, keluarga dan masyarakat .
Penyuluhan yang dilakukan kepada penderita TB, keluarga dan
masyarakat secara langsung akan berdampak semakin besarnya masalah TB
yang dapat diselesaikan, seperti mengenal lebih dini gejala TB, mengetahui
cara penularan, faktor risiko, dan pengobatan TB. Sehingga mendapatkan
nilai Magnitude yang besar dibandingkan dengan pelatihan petugas dan kader
kesehatan, yaitu 5. Pelatihan petugas dan kader kesehatan dalam rangka
meningkatkan kualitas penyuluhan juga penting untuk dilakukan, sehingga
diberikan nilai 4.
Importancy (I) atau pentingnya jalan keluar, berhubungan dengan
kelanggengan penyelesaian masalah. Semakin langgeng selesai suatu

masalah, semakin penting jalan keluar tersebut. Pelatihan petugas dan kader
kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyuluhan diberikan nilai
yang lebih besar karena dengan terlatihnya petugas dan kader kesehatan,
maka program promotif dan preventif akan berjalan sesuai dengan target yang
ada. Sedangkan untuk penyuluhan yang dilakukan kepada penderita TB,
pasien dan keluarga akan berdampak hanya sesaat, sehingga diberikan nilai
yang lebih kecil.
Vulnerability (V) dinilai dari kecepatan jalan keluar dalam mengatasi
masalah yang ada. Penyuluhan yang dilakukan kepada penderita TB, pasien
dan keluarga secara langsung akan memberikan waktu yang lebih singkat
dalam mengatasi masalah dibandingkan pelatihan petugas dan kader
kesehatan, karena pelatihan petugas dan kader kesehatan masih menunggu
hasil keluaran dari pelatihan itu sendiri. Sehingga nilai yang lebih besar
diberikan pada penyuluhan dibandingkan dengan pelatihan, yaitu 4 dan 1
Efisiensi (cost) jalan keluar pada pelatihan petugas dan kader kesehatan
mendapatkan nilai yang kecil yaitu 2, penyuluhan yang dilakukan kepada
penderita TB, pasien dan keluarga diberikan nilai 4.
5.12 Proposal prioritas alternatif penyelesaian masalah
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Kesimpulan evaluasi program Pengendalian Tuberkulosis di UPT
Puskesmas Beji Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
a. Masalah dalam pelaksanaan program Pengendalian Tuberkulosis di
UPT Puskesmas Beji tahun 2014 adalah belum tercapainya Case
Detection Rate (CDR) puskesmas (24.3%) lebih kecil dari indikator
yang seharusnya dicapai, yaitu 90%.

b. Penyebab masalahnya adalah pada komponen masukan yaitu
penyuluhan yang masih kurang efektif dan efisien kepada penderita TB,
pasien dan masyarakat.
c. Alternatif pemecahan masalah bagi pelaksanaan program tersebut
adalah penyuluhan kepada penderita TB, pasien dan masyarakat secara
langsung dan pelatihan petugas dan kader kesehatan dalam rangka
meningkatkan kualitas penyuluhan.
d. Pemecahan masalah yang terpilih adalah penyuluhan kepada penderita
TB, pasien dan masyarakat secara langsung.
6.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
1. Departemen Kesehatan. 2011. Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis di
Indonesia. Jakarta

2. Departemen Kesehatan RI. 2013. Identifikasi dan Obati, Mari Ciptakan
Dunia yang Bebas TB. Tersedia pada :
www.depkes.go.id/article/view/2280/menkes-identifikasi-dan-obati-mari-
ciptakan-dunia-yang-bebas-tb.html [Diakses tanggal 29 Juni 2015]
3. Departemen Kesehatan RI. 2011. TBC Masalah Kesehatan Dunia. Tersedia
pada : www.depkes.go.id/article/view/1444/tbc-masalah-kesehatan-
dunia.html [Diakses tanggal 29 Juni 2015]
4. Kementerian Kesehatan RI. 2015. Infodatin : Tuberkulosis ; Temukan Obati
Sampai Sembuh. Jakarta. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
RI. Hal. 1-7.
5. World Health Organization. 2014. Global Tuberkulosis Report 2014.
Switzerland. WHO Press. Hal. 32-33.
6. Kementerian Kesahatan RI. 2011. Strategi Nasional Pengendalian TB di
Indonesia 2010-2014. Jakarta. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan.
7. Departemen Kesehatan RI. 2011. Pedoman Nasional Pengendalian
Tuberkulosis. Jakarta. Departemen Kesehatan.
8. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. kbbi.web.id/sistem.
9. Azwar, Azrul. 1996. Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu.
Jakarta. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia. Hal. 103.
10. Marliana, Lina. 2008. Pelaksanaan Program. Tersedia pada : lib.ui.ac.id/file?
file=digital/122947-S-5237-Pelaksanaan%20program-Literatur.pdf [Diakses
tanggal 30 Juni 2015]
11. Anonim. 2011. Evaluasi Program. Tersedia pada :
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23917/3/Chapter%20II.pdf
[Diakses tanggal 30 Juni 2015]