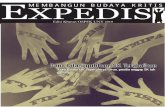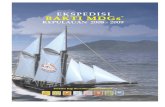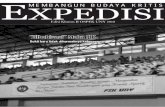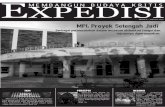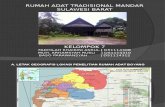Ekspedisi Bumi Mandar
-
Upload
muhammad-ridwan -
Category
Documents
-
view
673 -
download
20
description
Transcript of Ekspedisi Bumi Mandar
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaLingkup Hak CiptaPasal 2 :
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan PidanaPasal 72 :
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
EKSPEDISI BUMI MANDAR Copyright©Muhammad Ridwan Alimuddin, 2013
Diterbitkan kembali oleh
Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: [email protected]
facebook: Penerbit Ombak Dua
website: www.penerbitombak.com
PO.***.**.’13
Penulis: Muhammad Ridwan Alimuddin
Tata letak: Nanjar Tri Mukti
Sampul: Dian Qamajaya
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)EKSPEDISI BUMI MANDAR
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013** + *** hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-258-***-*
v
DAFTAR ISI
PENGANTAR
SELAMATKAN KALUMPANGPeradaban Tertua Kita adalah KalumpangTabir Sejarah Pertanian Awal Pulau SulawesiWarisan Dunia yang Harus Kita JagaSikomande, Sarung Ikat Tertua di DuniaDunia Akan Mengutuk Sulbar
PERTAHANKAN LERE-LEREKANGLere-lerekang atau Lari-lariang?Pulau Lere-lerekang Bagian Kepulauan Bala-balakang?Mandar Itu Pelaut UlungMengungsi ke Pulau yang Mereka KenalHak Ulayat LautPulau Lere-lerekang dalam Bingkai OtodaBerlayar ke Garis Depan Sulawesi BaratSesaat Sebelum Mendarat, Pistol DisiapkanKondisi LingkunganJadikan Laboratorium Alam atau DPL!(Jika Betul) Pulau Lere-lerekang Lepas, Siapa Salah?Kepulauan Bala-balakang
vi Muhammad Ridwan Alimuddin
Sebab “Database” Kita PayahMengapa Membicarakan Lere-lerekang?Kali Ini Bupati Ikut BerlayarMemperjuangkan Mempertahankan Lere-lerekangLautnya Sulbar Ternyata Terbagi-bagiMenuju Kilang yang “Diperebutkan”
GALUNG LOMBOKPanyapuang di Galung Lombok” dan WesterlingHubungan Antara Peristiwa Taloloq dan “Panyapuang”Laporan Rahasia Belanda Tentang Peristiwa Galung LombokWesterling, si TurkiWesterling Bersekongkol dengan Darul IslamWesterling, Mati Karena Lalunya Diungkit-ungkit
KEANGGUNAN BUNGGUTabuhan Musik Terpanjang Diiringi Ayunan ParangMasyarakatnya Tak Primitif LagiBunggu Itu Suku Kaili?Ngovi, Daerah Kesekian yang Diabaikan Sulbar!Mantap, Tari Dero Diiringi “House Music”“The Rock” yang KebalTikam Babi Hingga Potong GigiBeristri Cantik, Jangan Cepat Tidur
EKSPEDISI BUMI MANDAREkspedisi Keliling Mandar Ala Jurnalis Radar SulbarJam Tiga Sore Ekspedisi Dimulai
viiEkspedisi Bumi Mandar
Terima Kasih “Kambossolnya”Totolisi Selatan, Sentra “Gamacca” di MandarMajene, Negeri Seribu TelukMenyisir Pesisir Barat TappalangPulau Karampuang, Sempurna untuk “Cross Country”Sungai Kalukku, Seperti Sungai di AmerikaEkspedisi Ini Merekam PerubahanTopoyo, Riwayatmu KiniPaku – Suremana Kampung HalamankuDiaspora Orang Mandar di Mandar“Benu”, “Kaqdaro” dan “Bokaq”Berniat Menghentikan EkspedisiSuremana, “Sureq” Orang “Mene”
PENULIS
viii
PENGANTAR
Buku ini adalah kumpulan tulisan (feature) saya yang dibuat berseri di harian Radar Sulbar pada sepanjangtahun 2012
hingga pertengahan 2013. Itu juga merupakan tahun pertama saya aktif secara resmi sebagai jurnalis di Radar Sulbar. Meski demikian, sejak tahun 2006 tulisan berseri saya telah dimuat Radar Sulbar (sebelumnya bernama Radar Mandar), khususnya tentang sandeq. Bukan hanya sandeq, kebudayaan Mandar secara umum juga. Seri-seri tulisan tersebut juga sudah terwujud dalam bentuk buku, yaitu “Sandeq Perahu Tercepat Nusantara” (2010), dan “Mandar Nol Kilometer” (2011). Bedanya, tulisan yang ada dalam buku ini, serinya tematik. Judul buku ini saya ambil dari seri tulisan terakhir, “Ekspedisi Bumi Mandar”, yang juga merupakan nama kegiatan saya sewaktu bersepeda sendirian dari Paku hingga Suremana atau dari ujung selatan batas Sulawesi Barat ke ujung utaranya.
Dulu, saya membenci buku yang isinya hanya kompilasi atas tulisan di media massa. Seorang penulis mengumpulkan tulisan-tulisannya di media massa lalu mewujudkannya menjadi sebuah buku. Kelihatannya; seolah-olah menulis buku itu gampangan.Ketika ada banyak tulisan terserak di media massa, yang saya sendiri tidak memiliki klipping-nya, baru terasa dirasa perlu
ixEkspedisi Bumi Mandar
mewujudkan tulisan-tulisan itu ke dalam satu buku. Agar bisa dibaca setiap saat.
Manfaatnya jelas, memudahkan pencarian, memudahkan membaca. Bukan untuk saya, tapi orang lain juga. Jika ada bukunya, gampang sekali mencarinya; membacanya. Dan bagi yang mau file digitalnya atau pembaca lain yang tidak mendapatkan bukunya, tulisan-tulisan saya (sekitar 80% dari total tulisan yang pernah saya buat) dapat diakses di www.ridwanmandar.com. Artinya, antara dalam bentuk buku dengan yang berada di dunia maya saling melengkapi. Tujuannya jelas, memudahkan pembaca.
Pun, saya tidak terlalu mengandalkan buku yang merupakan kompilasi saja. Beberapa buku saya yang lain adalah murni sebagai sebuah buku, misalnya Orang Mandar Orang Laut. Beberapa buku berikut, yang naskahnya “teronggok” sebagai file dalam hardisk, malah belum pernah saya publish ke publik. Yaitu tentang riset saya mengenai pemboman ikan di Selat Makassar.
Buku ini terdiri dari lima tema: Kalumpang, Lerelerekang, Galung Lombok, Bunggu, dan hasil catatan lapangan saya sewaktu “keliling” Sulawesi Barat menggunakan sepeda. Total jenderal hampir 50 tulisan.
Kalumpang, nama situs bersejarah di kawasan Asia. Termasuk situs neolitik terbesar di Asia. Ironisnya, situs tersebut akan dimusnahkan oleh proyek PLTA Karama. Tulisan dalam bab itu membahas tentang Kalumpang, mulai dari lingkungannya hingga kebudayaan yang tak ternilai di tempat itu.
Lerelerekang, awalnya tak ada yang mengindahkannya. Termasuk pemerintah dan rakyat Sulawesi Barat sendiri. Tetapi ketika diketahui ada kandungan minyak dan gas dibawahnya, pulau kecil itu menjadi
x Muhammad Ridwan Alimuddin
rebutan antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Barat. Kabarnya, sampai titik darah penghabisan akan terus diperjuangkan agar tetap milik Sulawesi Barat. Saat tulisan pengantar ini saya buat (September 2012), entah bagaimana kasusnya. Apakah “ending-nya” dimiliki oleh Sulawesi Barat ataukah Kalimantan Selatan?
Galung Lombok, nama desa di Kecamatan Tinambung. Di sana ada pemakaman, korban pembantaian oleh Pasukan Westerling. Agar masyarakat Sulawesi Barat mendukung usaha advokasi agar korban dan ahli warisnya mendapat kehormatan dan keadilan atas penderitaan yang mereka alami, seri tulisan “Galung Lombok dan Westerling” saya buat. Khusus tulisan ini saya lebih banyak mengandalkan referensi tertulis, misalnya tulisan mengenai kejadian Korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan dan tentang Westerling. Selebihnya mendapat di Arsip Nasional di Makassar dan wawancara. Jadi ada perbedaan dengan seri lain, yang semuanya pengamatan lapang.
Bunggu, nama sub suku dari Suku Kaili. Tak adanya referensi ilmiah tentang masyarakat, yang oleh pemerintah disebut “suku terasing”, mendorong saya untuk melakukan liputan mengenai komunitas di pedalaman Sulawesi tersebut. Beberapa hari di tengah masyarakat Bunggu memperlihatkan bentuk-bentuk kebudayaan yang telah lama ditinggalkan masyarakat Sulawesi yang tinggal di pesisir. Yang unik, ada benang merah antara Lerelerekang dengan Bunggu. Yaitu sama-sama di daerah perbatasan provinsi; sama-sama tidak dipedulikan pemerintah Sulawesi Barat.
Terakhir, Ekspedisi Bumi Mandar. Bukan perjalanan saya paling jauh dan paling lama bila dibanding beberapa ekspedisi pelayaran yang pernah saya lalui. Tapi merupakan ekspedisi terberat yang pernah saya
xiEkspedisi Bumi Mandar
lakukan. Dan itu solo, seorang diri. Di bagian ini adalah tulisan yang saya buat di malam menjelang istirahat, yang saya buat di dalam kemah bulan berdiamater lebih semeter.
Tulisan yang ada dalam buku ini terwujud berkat dukungan banyak pihak. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Naskah M. Nabhan (Direktur Radar Sulbar), Muhammad Ilham dan Sudirman Samual (keduanya wartawan senior di Radar Sulbar) yang telah memberi ruang atas tulisan-tulisan saya. Terkhusus pada saudara Mahbub Amiruddin, yang mengajak saya bergabung di Radar Sulbar, untuk kemudian mendorong dan membantu dalam pelaksanaan Ekspedisi Kalumpang, sebuah ekspedisi sederhana yang menyejarah bagi saya dan berdampak luas.
Mandar, Agustus 2013
Muhammad Ridwan Alimuddin
1
SELAMATKAN KALUMPANG
Peradaban Tertua Kita adalah Kalumpang
Sulawesi Barat hanya memiliki satu situs peradaban tertua, yang oleh para arkeolog menjadi salah satu mata rantai di
dalam mengetahui perkembangan manusia pra sejarah Nusantara, yang terentang 3.500 tahun lalu. Yaitu Kalumpang.
Kalumpang tak begitu banyak diketahui, sehingga di situs ensiklopedia online, Wikipedia, hanya memiliki defenisi pendek tentang Kalumpang, “sebuah kecamatan di Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia”. Apalagi kita di Sulawesi Barat, mungkin hanya menganggap Kalumpang sebagai nama tempat, sebagaimana nama tempat-tempat lain di Sulawesi Barat.
Kalumpang lebih dari itu. Jika ada pengelompokkan “status sosial” tempat-tempat di Sulawesi Barat berdasar kesejarahan, maka Kalumpang berada di kasta paling atas. Ya, kita lebih banyak mendengar nama-nama situs di provinsi kita ini, seperti Tammejarra, Luyo, Salabose, dan lain-lain. Tapi, tempat tersebut sebagai situs bersejarah, masih berumur “anak bawang” dibanding Kalumpang.
Kalumpang hampir tak ada arti di mata pemerintah kita, apalagi para investor dari Cina, sehingga untuk membangun PLTA
2 Muhammad Ridwan Alimuddin
Karama, penduduk Kalumpang (dan Bonehau) tinggal direlokasi saja. Ya, tidak apa-apa kampung mereka (baca: Kalumpang) tenggelam.
Kalumpang hampir tak ada pentingnya, sehingga pembangunan PLTA Karama butuh waktu 4-5 tahun saja. Sehingga tak butuh waktu lama untuk mikirkan dampaknya, membicarakannya dalam sebuah seminar. Ya, tak perlu dilindungi, tak perlu dilestarikan atau dijaga perabannya. Tidak apa-apa hilang dibawah genangan air dam PLTA Karama. Kan, mungkin sebagian orang berpikir, tak ada gunanya juga.
Bila memang kita sepakat untuk itu (menenggelamkan Kalumpang demi sebuah proyek bernama PLTA Karama), terlalu kasar bila saya mengatakan, kita memang tidak beradab.
Kalumpang atau Galumpang (setidaknya ada enam tempat bernama “Kalumpang” di kawasan Asia Tenggara) adalah salah satu wilayah atau kecamatan di Kabupaten Mamuju. Letaknya 35 km dari pantai (persis sejajar Pelabuhan Belang-belang) atau sekitar 65 km dari kota Mamuju.
Dalam dunia arkeologi Asia, Kalumpang sangat terkenal. Ekskavasi yang pernah dilaksanakan di wilayah Kalumpang secara ringkas digambarkan sebagai berikut. Mei 1933 penggalian percobaan dilakukan oleh A.A. Cense di lembah Sungai Karama. Ditemukan sejumlah alat-alat batu dan gerabah. Penggalian tersebut memberi arti penting dalam sejarah pertumbuhan kebudayaan prasejarah Indonesia.
Kemudian pada 25 September sampai 17 Oktober 1933 penggalian oleh P.V. Van Stein Callefels di sebelah timur bukit Kamassi. Dia mem peroleh temuan berbagai alat dari batu berupa
3Ekspedisi Bumi Mandar
pisau, kapak batu segi empat yang halus, pecahan-pecahan tembikar yang berdekorasi.
Lalu pada 13 Agustus hingga September 1949 penggalian oleh Dr. H. R. Van Heekeren, di bagian selatan puncak bukit Kamassi 13 meter di atas permukaan sungai. Ditemukan berbagai alat batu dan gerabah berhias. Alat-alat batu berupa kapak batu yang ada kesamaannya dengan alat neolithic seperti yang ditemukan Luzon, Filipina, di Manchuria, Mongolia, di Hongkong, dan lain-lainnya.
Gerabah yang berhias dinilai oleh para ahli arkeologi mempunyai corak yang tinggi dan desain yang halus memberikan pertanda bahwa kebudayaan Kalumpang terlingkup satu wilayah “sahuynh kalanay”, desain yang meliputi wilayah Cina, Filipina dan Vietnam, malah diperkirakan mempengaruhi beberapa daerah Pasifik. Hipotesa itu dikemukakan oleh Solheim WG. Demikian dikemukakan Drs. Darmawan Masud dalam kertas ilmiah yang dipresentasikan pada saat Seminar Kebudayaan Mandar I di Majene pada 31 Juli s.d. 2 Agustus 1984.
Menurut salah seorang sahabat saya, yang disiplin ilmunya arkeologi dan pernah membuat film dokumenter tentang Kalumpan, Asfriyanto, “Untuk mencari bukti arkeologis mengenai pertanian orang Kalumpang purba, justru harus dicari di sekitar perbukitan yang secara spasial jauh dari tepian sungai saat ini”.
Tambahnya, “Bukti arkeologis menunjukkan, temuan beliung berbahan batu yang banyak tersebar di perut Kalumpang mengindikasikan adanya ekploitasi orang Kalumpang purba pada bidang pertanian. Hal itu dikuatkan juga melalui banyaknya temuan yang masih utuh maupun pecahan periuk dan belanga dari bahan tanah liat merah”.
4 Muhammad Ridwan Alimuddin
Para ahli arkeologi percaya bahwa penduduk Kalumpang purba merupakan satu suku dari ras Aus tronesia yang membawa tradisi pertanian dan gerabah (dua artefak masa lalu yang berasosasi dengan tradisi pertanian) dari daratan Asia yang bermigrasi ke daerah ini sekitar 3.500 tahun yang lalu.
Menurut salah satu pendapat, kaki-kaki perbukitan Kalumpang telah dihuni oleh penduduk asli sebelum kedatangan orang-orang Proto Melayu pada 3600 SM. Kedatangan kaum Melayu Tua pun tak lepas dari sejarah pengusiran mereka dari kawasan pesisir pantai, akibat kedatangan peradaban baru yang dibawah oleh Deutero Melayu, yang tentu lebih hebat dari segi teknologi dan keterampilan.
Mulanya mereka menghuni daerah Sipakko, sekitar 1,5 kilometer dari pusat Kecamatan Kalumpang saat ini. Tapi, karena banjir besar akibat luapan sungai Karama sekitar seribu tahun yang lalu, warga pun terpencar- pencar. Banyak yang lari ke atas bukit karena trauma akan banjir yang telah meluluhlantakkan sawah dan pemukimannya.
Tabir Sejarah Pertanian Awal Pulau Sulawesi
Pada 1926, Zending Belanda mulai mendirikan Sekolah Rakyat (SR) di Tamalea untuk kelas satu hingga tiga. Setahun berikutnya, 1927 didirikan lagi SR di Malolo, namun bukan di Kota Kalumpang. Tahun 1930 di Pulo Karama, lalu di Pa’bentengan berupa sekolah lanjutan untuk kelas empat hingga enam dengan sebutan Veer Volog School (VVS).
Setelah perang dunia kedua, Universitas Sorbonne, Paris, melibatkan diri dalam penelitian situs Sampaga (kawasan dekat
5Ekspedisi Bumi Mandar
muara Sungai Karama). Perhatian mereka terpusat pada relief pola desain tembikar yang ditemukan di Minanga Sipakko. Penelusuran situs sampai ke hulu Sungai Karama (yang biasa juga disebut Sungai Sampaga dalam beberapa tulisan) membawa mereka pada masyarakat Kalumpang.
Kalumpang adalah situs yang oleh para arkeolog dianggap bisa membuka tabir sejarah pertanian awal orang-orang di Pulau Sulawesi. Menurut Asfriyanto, seorang arkeolog muda, “Menariknya, daerah Kalumpang juga memiliki mitos suci tentang padi yang berbeda dengan mitos padi seperti yang termaktub dalam naskah La Galigo, naskah yang selama ini dipandang para ahli sebagai ingatan sejarah orang-orang Bugis yang paling purba.”
Tambahnya, “Jika mitos orang Bugis mengatakan tanaman padi berasal dari badan Sangiang Seri, salah satu anak dari Patotoqe sang penguasa di Botting Langi’, maka mitos padi orang Kalumpang justru berasal dari tumbuhan Dewa, yang muasal benihnya dari tanah dewa di seberang lautan yang kemudian dibawa oleh nenek moyang dengan perahu ke Kalumpang dan ditanam di atas batu di puncak gunung. Mitos tentang padi ditemukan dalam nyanyian “ma’ole” atau nyanyian panjang orang Kalumpang yang menggunakan bahasa Kalumpang purba yang saat ini penuturnya tinggal dua orang tua berusia lanjut.
Konon, benih padi itu masih ada di puncak gunung yang terletak tidak jauh dari kampung Kalumpang. Setiap tahun padi itu tetap tumbuh. Sampai tahun 1960-an orang-orang Kalumpang masih mengandalkan benih padi yang berasal dari puncak gunung itu.
Padi yang tumbuh di puncak bukit batangnya lebih besar dari batang padi yang ada sekarang, bulir padinya lebih kecil, namun
6 Muhammad Ridwan Alimuddin
sangat rimbun. Selain dimanfaaatkan sebagi bibit, tumbuhnya batang padi di puncak bukit itu dijadikan penanda bagi orang Kalumpang untuk memulai menanam padi. Sayang, usia panennya mencapai enam bulan. Karena itu, dengan masuknya program intensifikasi pertanian oleh pemerintah diawal tahun 1970-an, bibit padi lokal tersebut diganti dengan bibit yang lebih bagus dengan masa panen tiga bulan sekali.
Sejak proses pergantian varietas padi itulah orang-orang Kalumpang mulai mengenal hama padi dan insektisida. Asfriyanto mengutip pendapat pendeta Mardi Tamandalan, “Masih ada penduduk yang menanam bibit padi gunung seperti itu, tapi letaknya di hulu sungai Karama. Padi gunung itu rasanya enak sekali. Saya dulu sering makan waktu masih kecil, tapi sekarang sudah susah dicari.”
Patung Sikendeng
Sungai Karama menyimpan banyak misteri dan pernah menjadi saksi sejarah peradaban Nusantara. Di Sikendeng, sekitar 10 km dari muara Sungai Karama, pernah ditemukan patung Buddha berbahan perunggu, yang kemudian diberi nama Patung Sikendeng, sebab ditemukan di Sikendeng.
Situs bersejarah ini ditemukan oleh A. Maula, seorang penilik sekolah daerah setempat. Dan atas perintah Caron, gubernur waktu itu, patung dibawa ke Makassar. Untuk kemudian Dr. F.D.K. Bosch membandingkannya dengan patung-patung Buddha yang ada di Borobudur dan Palembang yang termasuk tradisi Hindu Jawa dan Hindu Sumatera.
Dari hasil penelitian di simpulkan, gaya patung Sikendeng mempunyai ciri yang khas sebagaimana mantel biarawan Sanghati
7Ekspedisi Bumi Mandar
yang berlipat-lipat dilukiskan. lipatan-lipatan terjadi karena kain penutup bahu kiri ditarik keras, menyebabkan jalur-jalur dangkal pada kain tersebut. Di samping itu badan yang ramping seperti wanita, raut muka bulat, leher berisi, mulut kecil bibir tebal.
Dibandingkan dengan gaya dan bentuk patung perunggu Buddha lainnya seperti dari Solok jambi, Kotabangun Kalimantan Barat dan patung dari Gunung Lawu Jawa Hindu kelihatannya tidak mempunyai kesamaan. Kelihatannya patung itu dipengaruhi oleh gaya Buddha Greeco yang terdapat di India Selatan.
Di Amarawaty India Selatan pernah ada tradisi pembuatan patung yang mirip dengan gaya patung yang ditemukan di Sikendeng, terutama cara pemakaian dengan jalur-jalur yang dangkal dan cara menutup bahu dengan kain yang berlipat-lipat.
Dr. Bosch akhirnya berkesimpulan bahwa patung Sikendeng dibawa langsung dari India Selatan dan mungkin dari Amarawaty. Masa penyebarannya mungkin terjadi antara abad ke-2 - 7 M. Penemuan tersebut mengisyaratkan, pernah terdapat kerajaan atau perkampungan tua, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa kerajaan atau perkampungan di wilayah penemuan benda-benda atau alat-alat dari batu dan gerabah adalah kerajaan atau perkampungan tertua di Mandar atau Sulawesi Barat.
Warisan Dunia yang Harus Kita Jaga
“Seusai penelitian yang dilakukan oleh Heekeren tersebut, Situs Minanga Sipakko menjadi salah satu situs terpenting di Indonesia yang kaya dengan tinggalan-tinggalan budaya prasejarahnya… Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya publikasi data temuan
8 Muhammad Ridwan Alimuddin
ekskavasi yang terbaru mengingat keterancaman hilangnya Situs Minanga Sipakko di masa depan akibat erosi dan banjir karena letak situs yang berada di tepi Sungai Karama”.
Di atas adalah kutipan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia, Ricky Meinson Binsar Simanjuntak (2009) dalam bagian pengatar skripsinya tentang Kalumpang. Artinya, situs Kalumpang mau tidak mau harus dijaga, dilestarikan. Sebab, bila situs tersebut dimusnahkan dengan cara menenggelamkannya, maka, satu-satunya peradaban tertua yang pernah ditemukan di Sulawesi Barat hilang dalam hitungan hari.
Agar kita, masyarakat Sulawesi Barat, lebih menyadari akan arti penting Kalumpang, edisi hari ini dan esok, isinya dalah saduran dari penelitian mahasiswa Universitas Indonesia di atas. Tujuannya, agar kita, khususnya warga Sulawesi Barat, sama-sama bertanggung jawab atas kelestarian situs Kalumpang. Jika situs itu tetap ada, itu karena kita; jika situs itu musnah, itu karena kita juga.
Kalumpang pada awalnya merupakan sebuah nama yang ditujukan untuk menyebut Situs Kamassi, tempat P .V . van Stein-Callenfels melakukan penggalian pertama kalinya pada tahun 1933. Van Stein-Callenfels memperkenalkan Situs Kamassi dengan nama Kalumpang berdasarkan keletakan desa Situs Kamassi berada, namun seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan saat ini Kalumpang mengacu pada sebuah kawasan situs yang terdiri dari beberapa situs prasejarah termasuk Situs Kamassi dan Minanga Sipakko.
Minanga Sipakko terletak di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sekitar 3 km di sebelah barat Kalumpang. Menurut bahasa lokal, Minanga Sipakko memiliki arti
9Ekspedisi Bumi Mandar
“cabang sungai” (minanga atau binanga = sungai, sipakko atau sipakka = cabang).
Minanga Sipakko muncul dalam dunia prasejarah Indonesia berkat penelitian yang dilakukan oleh Heekeren pada tahun 1949, berlatarbelakang pada serangkaian penemuan situs-situs Neolitik di tepi Sungai Karama. Awalnya Heekeren melakukan penggalian di Kamassi melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh van Stein-Callenfels, namun pada saat yang bersamaan ditemukan temuan yang sejenis di Minanga Sipakko yang terletak tidak jauh dari Kamassi sekitar 1 km ke arah barat.
Penelitian yang dilakukan di Situs Minanga Sipakko terbilang jarang. Sepeninggal Heekeren tidak ada penelitian lebih lanjut di tempat ini, yang ada hanya sebatas survei permukaan dan peninjauan lapangan. Pada tahun 1994 dan 1995 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (sekarang Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional) yang bekerjasama dengan Balai Arkeologi Makassar melakukan ekskavasi dengan membuka kotak uji (test pit) di Situs Minanga Sipakko dan survei di Situs Kamassi.
Baru pada tahun 2004, 2005, dan 2007 penelitian di Situs Minanga Sipakko mulai intensif dilakukan oleh Puslitbang Arkenas bersama Balar Makassar. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Situs Minanga Sipakko merupakan situs Neolitik murni.
Penelitian yang dilakukan di Situs Minanga Sipakko tersebut menemukan berbagai alat-alat litik, alat tulang, sisa fauna, sisa-sisa pembakaran, dan pecahan tembikar. Khususnya tembikar ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak dan secara kuantitas maupun kualitas memperlihatkan keberagaman motif hias yang dihasilkan.
10 Muhammad Ridwan Alimuddin
Pada tahun 1933 penelitian dilanjutkan oleh Stein-Callenfels di Situs Kamassi. Penggalian yang dilakukan berhasil menemukan alat-alat batu Hoabinhian, kapak, beliung, mata panah, dan tembikar.
Hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan oleh Stein-Callenfels pada Kongres Prasejarah Asia Timur di Manila tahun 1951 yang menjadikan Kalumpang dikenal di dunia internasional.
Sepeninggal Stein-Callenfels penelitian dilanjutkan oleh H.R. van Heekeren pada tahun 1949 di Situs Kamassi. Ketika melakukan penggalian, Heekeren mendapatkan laporan dari penduduk setempat yang menemukan temuan yang serupa di Minanga Sipakko. Kemudian pada saat perjalanan pulang ke Kalumpang, Heekeren mencoba melakukan peninjauan langsung ke Minanga Sipakko yang hanya sebatas survei permukaan. Hasilnya ditemukan pecahan- pecahan tembikar polos dan berhias, beliung persegi, kapak lonjong, mata tombak, mata panah, pahat batu, batu asah, batu pipisan, dan alat pemukul kulit kayu.
Pada tahun 1969 R.P. Soejono dan D.J. Mulvaney mengadakan penelitian berupa peninjauan lapangan di gua-gua Maros di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Batu Ejaya, Gua Ulu Leang 2, dan Gua Ulu Wao. Dari hasil peninjauan tersebut ditemukan beberapa pecahan tembikar yang jika dilihat dari motif dan teknik hiasnya memperlihatkan kesamaan dengan tembikar Kalumpang.
Dari perbandingan tersebut disimpulkan bahwa tembikar dari situs-situs tersebut merupakan bagian dari perkembangan tembikar Kalumpang yang selanjutnya disebut sebagai kompleks tembikar Kalumpang.
11Ekspedisi Bumi Mandar
Pada tahun 1970 penelitian dilanjutkan oleh Uka Tjandrasasmita dan Abu Ridho yang menyatakan bahwa tembikar Kalumpang memiliki persebaran yang cukup luas di Sulawesi Selatan, yaitu hingga ke daerah Maros (Ulu Wae, Ulu Leang, Leang Burung, dan Batu Ejaya, dekat Bantaeng) dan juga ke arah selatan Makassar, tepatnya di Desa Takalar.
Pada tahun 1981 pembahasan tembikar Kalumpang dilakukan oleh Nurhadi dalam skripsinya yang berjudul Gerabah Prasejarah Kalumpang. Dalam penelitiannya Nurhadi menggunakan data himpunan tembikar koleksi Museum Nasional yang merupakan hasil temuan ekskavasi Stein-Callenfels tahun 1933, Heekeren tahun 1949, dan himpunan tembikar dari pemerintah daerah setempat
Secara keseluruhan total pecahan tembikar yang digunakan sebanyak 601 buah yang terdiri dari 351 tembikar berhias dan 250 tembikar polos. Dari hasil penelitiannya tersebut, Nurhadi berhasil mengenali bentuk-bentuk tembikar Kalumpang yang terdiri dari jenis cawan, kendi, periuk, buyung, tempayan, buli- buli, jambangan, tutup, dan tungku. Nurhadi juga berpendapat bahwa tembikar Kalumpang tidak dibuat di Kalumpang dengan alasan tidak ditemukannya alat- alat pembuatan tembikar di Kalumpang.
Pada tahun 1988 Tim Ikatan Mahasiswa Arkeologi Indonesia (IMAI) Universitas Hasanuddin melakukan survei di Kalumpang, disusul oleh R.P. Soejono dari Puslitbang Arkenas tahun 1990. Kemudian pada tahun 1993 Tim Ekspedisi Kalumpang II Universitas Hasanuddin melakukan survei lanjutan yang kedua di Situs Kamassi dan Minanga Sipakko.
12 Muhammad Ridwan Alimuddin
Di Situs Kamassi ditemukan kapak lonjong, batu pelontar, batu gandik, batu inti, batu asah, dan pecahan tembikar; sedangkan di Situs Minanga Sipakko ditemukan kapak lonjong, calon kapak lonjong (yang baru mengalami pengerjaan primer atau belum terupam), batu gandik, batu asah, batu inti, kapak persegi, beliung persegi, calon pahat, dan pecahan tembikar.
Penelitian eksploratif di Kalumpang dimulai tahun 1994 dan 1995 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama-sama dengan Balai Arkeologi Makassar. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sebaran wilayah tinggalan arkeologis di Situs Kamassi dan Minanga Sipakko, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta karakteristik kedua situs. Serangkaian penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Kalumpang merupakan situs berciri Neolitik-Paleometalik dengan tinggalan pokok berupa pecahan tembikar, beliung persegi, kapak batu, sisa fauna, dan benda-benda yang terbuat dari logam.
Pada tahun 1995 tembikar Kalumpang diteliti oleh St. Fatimah. Dalam penelitian skripsinya yang berjudul Unsur Tradisi Sahuynh-Kalanay Pada Tembikar di Kalumpang: Tinjauan Berdasarkan Analisis Teknologis Dan Tipologis” Fatimah menggunakan data hasil ekspedisi Kalumpang II dan survei yang dilakukannya di Situs Kamassi dan Minanga Sipakko. Data tersebut terdiri dari 897 tembikar polos dan 42 tembikar berhias.
Hasil penelitiannya menyebutkan bentuk-bentuk tembikar dari Kalumpang adalah cawan, buli-buli, tempayan, kendi, pinggan, periuk, dupa, dan tutup. Bahan baku tembikar terbuat dari tanah liat (lempung) yang ditambahkan dengan bahan campuran (temper) dari pasir dan hancuran cangkang binatang laut. Hasil
13Ekspedisi Bumi Mandar
lainnya juga diketahui adanya penggunaan roda putar dan tatap pelandas pada pembuatan tembikar di Kalumpang, sedangkan jika dilihat dari motif dan pola hiasnya menunjukkan adanya kesamaan dengan tradisi Sahuynh-Kalanay.
Pada tahun 1998 penelitian tentang tembikar Kalumpang juga dilakukan oleh Ning Suryati. Dalam skripsinya yang berjudul Tradisi Gerabah Sa Huynh- Kalanay Pada Gerabah Kalumpang, Sulawesi Selatan, Suryati memfokuskan pada komposisi kandungan mineral tembikar Kalumpang dan menjelaskan proses persebaran tradisi Sa Huynh-Kalanay di Kalumpang.
Data yang digunakan adalah data yang sama dipakai oleh Fatimah pada tahun 1995. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, diketahui bahwa komposisi bahan baku tembikar Kalumpang menunjukkan kesamaan dengan komposisi sedimen yang ditemukan di Kalumpang sehingga menurut Suryati tembikar Kalumpang dibuat di Kalumpang. Kemudian untuk proses persebaran tradisi Sa Huynh-Kalanay di Kalumpang disebabkan oleh proses stimulus diffusion, yaitu kebudayaan Sa Huynh-Kalanay yang dibawa ke dalam kebudayaan Kalumpang.
Dari hasil penelitian mahasiswa UI tersebut, didapati bahwa keanekaragaman tinggalan arkeologis di Kalumpang menempatkan kawasan situs ini penting dalam pengkerangkaan kehidupan manusia prasejarah di Indonesia. Berbagai tinggalan arkeologis seperti alat-alat litik, alat tulang, sisa- sisa fauna, dan tembikar ditemukan di Kalumpang.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tembikar merupakan tinggalan budaya yang paling banyak ditemukan di Kalumpang. Tinggalan-tinggalan budaya di
14 Muhammad Ridwan Alimuddin
Kalumpang secara umum mencerminkan budaya Neolitik yang terdapat di Sulawesi.
Secara geografis Sulawesi merupakan salah satu pulau yang memegang peranan penting dalam persebaran manusia petutur Austronesia di Indonesia. Letaknya yang strategis di antara persilangan jalur pelayaran Asia bagian tenggara menjadikan Sulawesi sebagai titik terjadinya persilangan kebudayaan (melting pot) di Indonesia, baik dari arah barat maupun timur. Dari perspektif arkeologis keberadaan situs-situs Neolitik di Sulawesi adalah kunci untuk menjelaskan sifat alami penyebaran dan asal-usul penutur Austronesia di Indonesia.
Tinggalan-tinggalan arkeologis di Minanga Sipakko merupakan bukti hadirnya budaya Neolitik di Sulawesi. Budaya Neolitik tersebut dibawa oleh petutur Austronesia hingga Indonesia bahkan lebih luas ke kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Salah satu artefak yang mencirikan budaya Neolitik Austronesia tersebut adalah tembikar. Ditinjau dari aspek motif hiasnya, tembikar Minanga Sipakko memperlihatkan kemiripan dengan tembikar tradisi Sa Huynh- Kalanay. Menurut Solheim II tembikar tradisi Sa Huynh-Kalanay dapat dijumpai pada tembikar-tembikar di situs-situs Neolitik di Indonesia, termasuk di Situs Minanga Sipakko.
Kehadiran tembikar di Situs Minanga Sipakko menarik untuk diamati sebagai suatu usaha untuk mengungkapkan salah satu aspek kehidupan yang berlangsung di situs tersebut. Pengamatan terhadap motif hias menjadi penting dengan pertimbangan bahwa dari segi inilah dapat diungkapkan salah satu aspek teknologi pembuatan tembikar di samping adanya unsur-unsur kesamaan dengan motif dan teknik hias tembikar dari situs-situs lainnya di
15Ekspedisi Bumi Mandar
Indonesia maupun luar Indonesia.
Dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (Puslitbang Arkenas) di Situs Minanga Sipakko tahun 2004, 2005, dan 2007 menghasilkan banyak temuan tembikar. Temuan tersebut saat ini disimpan di Puslitbang Arkenas, Jakarta dan belum dianalisis lebih lanjut.
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, oleh penelitia mengajukan pertanyaan, motif dan teknik apa saja yang digunakan untuk menghias tembikar Minanga Sipakko? Motif hias tembikar Minanga Sipakko apa saja yang memperlihatkan kemiripan dengan motif hias tembikar tradisi Sa Huynh-Kalanay?
Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut dapat dijelaskan berbagai jenis motif hias yang diterapkan di Situs Minanga Sipakko serta bagaimana teknik pembuatannya. Selain itu juga dapat diketahui motif-motif apa saja di Situs Minanga Sipakko yang juga dihasilkan oleh tembikar tradisi Sa Huynh-Kalanay. Tujuan lainnya dari penelitian tersebut adalah untuk melengkapi informasi dari hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat menambah pengetahuan tentang masa prasejarah di Situs Minanga Sipakko dan Indonesia umumnya.
Sebab, Minanga Sipakko merupakan salah satu situs prasejarah yang sangat penting di Indonesia. Berdasarkan laporan dari banyak penelitian, dalam konteks mikro Situs Minanga Sipakko merupakan bukti adanya hunian manusia masa lalu dengan rentang waktu 3.600-2.500 BP, yang dicirikan oleh pengembangan teknologi tembikar; beliung dan kapak batu serta adanya eksploitasi sumber daya fauna dan flora.
16 Muhammad Ridwan Alimuddin
Dalam konteks makro, Sungai Karama menjadi jalur lalu lintas perdagangan antar komunitas hulu dan hilir, bahkan dengan dunia luar. Secara geografis ada dua hal yang menonjol berkaitan dengan kehidupan manusia yang berlangsung di tempat ini, yaitu keterisolasian di pedalaman dengan lingkungan yang bergunung-gunung dan keberadaan Sungai Karama sebagai pembuka keterisolasian. Faktor geografis tersebut merupakan faktor yang berperan penting dalam memberi kekhasan pada kehidupan dan kebudayaan yang berlangsung di Situs Minanga Sipakko.
Dalam periode tertentu sejak situs Minanga Sipakko dihuni hingga kondisi situs saat ini Sungai Karama telah mengalami perubahan aliran sungai. Perubahan tersebut erat kaitannya dengan keletakan Situs Minanga Sipakko yang saat ini berada dalam kondisi yang terancam longsor dan hilangnya situs Minanga Sipakko di masa depan, apalagi dengan adanya rencana pembangunan PLTA Karama.
Sikomande, Sarung Ikat Tertua di Dunia
Mengapa rencana pembangunan PLTA Karama harus di kawasan Batu Menggaragaji? Dugaan saya, salah satu penyebabnya sebab kawasan itu adalah DAS (daerah aliran sungai) yang sumberdaya airnya paling tidak berasal dari dua sungai utama, Sungai Bonehau dan Sungai Karama.
Dalam hitung-hitungan teknis, bisnis, dan tingkat daya/energi yang akan dihasilkan nanti, alasan tersebut amat masuk akal. Malah dianjurkan. Akan beda debit air bila PLTA dibangun sebelum kawasan pertemuan dua sungai tersebut, misalnya di Sungai Karama saja atau Sungai Bonehau saja.
17Ekspedisi Bumi Mandar
Sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kata “bonehau”. Sebenarnya antara “bone” dengan “hau” itu terpisah. Tapi karena lama-lama menjadi nama sebuah tempat, akhirnya disatukan, menjadi “Bonehau”. Jadi bila konsisten, Karama juga dipasangi “bone” didepannya, menjadi “Bonekarama”.
Kata “bone” kemungkinan besar nama kuno dari “sungai besar” dalam cabang-cabang bahasa Austronesia. Ada beberapa varian dari penyebutan sungai dalam bahasa daerah di Sulawesi Barat, seperti “salu” (mungkin berarti sungai yang lebih kecil dari ukuran “bone”), “binanga” (misal Binanga Karaeng di perbatasan Mandar – Bugis), “lembang” (seperti Lembang Matama di Alu, dan “wai”, tapi kata ini lebih dimaknai sebagai air.
Hal di atas masih hipotesa saya pribadi, baik berdasarkan saya sebagai pengguna bahasa Mandar maupun atas analisis peta yang mana ada saat simbol aliran sungai disebut “bone” (untuk sungai yang besar), ada saat ditulis kata “salu” untuk cabang-cabang sungai yang lebih kecil. Masih perlu penelitian lebih mendalam, khususnya oleh para ahli bahasa.
Artinya, situs Kalumpang dan kampung-kampung sekitarnya masih memendam harta karun akan akar kebudayaan kita yang belum digali sepenuhnya. Sejauh pengataman saya dari beberapa referensi ilmiah, situs Kalumpang masih diteliti sebatas peninggalan-peninggalan budaya bendawinya, misalnya tembikar. Sedang bentuk kebudayaan lainnya, belum pernah saya temukan (mungkin sudah ada tapi belum saya lihat/baca).
Dan ketika Bonehau, Kalumpang, Tamaletua, Sumuak, Pabettenagan, Tollondok, Tammalea, dan kampung lain (akan) ditenggelamkan, maka upaya penggalian bentuk-bentuk
18 Muhammad Ridwan Alimuddin
kebudayaan Kalumpang akan semakin sulit dilakukan. Alasannya jelas, sebab para penutur atau pewaris bentuk-bentuk kebudayaan Kalumpang akan terdiaspora ke berbagai tempat, berpindah dari lingkungan yang mempengaruhi kebudayaannya.
Bentuk-bentuk budaya Kalumpang masih belum terdokumentasi dengan baik sehingga sangat menyedihkan bila peradaban tertua kita itu harus dilenyapkan dalam hitungan hari. Saat pintu dam PLTA Karama mulai ditutup, ketika air mulai naik di sisi timur dam.
Bila memang menenggelamkan Kalumpang menjadi pilihan, sebelumnya harus ada upaya atau kerja keras untuk merekam apa saja bentuk-bentuk kebudayaan Kalumpang, mulai dari bahasa-bahasanya, teknologinya, pranata sosialnya, hingga ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Setelah itu, dibuatkan museum Kalumpang. Dan itu tak akan bisa selesai 4-5 tahun, sebagaimana target Anwar Adnan Shaleh selesainya PLTA Karama.
Para ahli etnografi mengategorikan orang Kalumpang ke dalam rumpun budaya Toraja. Hal itu tidak sepenuhnya salah, sebab saat ini, beberapa ragam budaya orang Kalumpang semisal penguburan di liang dan tebing batu, kain tenun, juga bahasa mirip dengan budaya orang Toraja.
Bahasa juga demikian. Kalumpang satu kelompok dengan Mamasa, Rongkong, Toraja Sa’dan (Makale, Rantepao atau Kesu’ dan Toraja Barat atau Mappa – Pana) dan Toala’ (Toala’ dan Palili’), yaitu Sub-famili Toraja Sa’dan.
Jadi, meskipun secara geografis Kalumpang masuk wilayah Mamuju atau Sulawesi Barat (Mandar), dari segi budaya, Kalumpang agak berbeda dengan kebudayaan Mandar atau
19Ekspedisi Bumi Mandar
kebudayaan Mamuju secara umum.
Berdasarkan penelitian terbaru terutama berdasarkan tradisi lisan dan bukti arkeologis, kebudayaan orang Kalumpang justru lebih tua dan ada kemungkinan budaya Toraja justru berakar dari kebudayaan orang Kalumpang purba.
Salah satu bentuk kebudayaan Kalumpang yang harus dilestarikan adalah teknik pembuatan dan corak sikomande. Corak sikomande tidak hanya terdapat di sarung, tapi juga tembikar. Sebagaimana hasil penelitian tim dari Universitas Sorbonne, Prancis.
Dalam bahasa tradisional setempat, sarung sikomande diistilahkan “baba deata”. Dari hasil penelitian ilmiah, corak sikomande sering dinyatakan sebagai pola desain tenunan ikat tertua di dunia. Pola desainnya sendiri disebut Sah Hyun Kalanay, yang mulai tersebar ke seluruh Asia dan Oceania sejak abad pertama masehi.
Corak atau teknik pembuatan sarung sikomande ada kemiripan dengan teknik pembuatan sarung ikat di beberapa pulau di Nusa Tengga Timur (Flores). Sewaktu saya melakukan penelitian tentang kebudayaan pemburu ikan paus di Lamalera (Larantuka), dalam cerita rakyat disebutkan bahwa moyang mereka berasal dari pantai timur Pulau Sulawesi, yaitu daerah Luwuk sekarang ini.
Adapun jalur migrasinya dari Pulau Sulawesi hingga sampai ke Flores melalui Kep. Sula, P. Buru, P. Seram hingga Kep. Kei, ke Kep. Tanimbar, sampai memutar kembali ke arah barat, menuju P. Leti, P. Wetar, P. Flores, dan sekitarnya.
Dengan kata lain, dugaan yang mengatakan bahwa teknik dan corak sarung sikomande sebagai yang tertua di dunia amat masuk
20 Muhammad Ridwan Alimuddin
akal, sekaitan dengan pola migrasi di atas. Sebab, dari Kalumpang ke Toraja hingga Luwuk ada jalur purba. Artinya, teknik-corak sikomande jauh lebih tua dibanding yang ada di pulau-pulau Nusa Tenggara sekarang ini.
Sayangnya, orang Sulawesi Barat sendiri (baca: pemerintah kita) amat bersemangat untuk meluluhlantakkan warisan dunia yang dipercayakan ke Sulawesi Barat itu atas nama membangun PLTA. Kita jangan menyalahkan orang Cina yang ingin berinvestasi, tapi harus kita tuntut orang-orang kita (yang menentukan sebab mereka pengambil kebijakan) untuk tidak menenggelamkan satu-satunya peradaban tertua yang kita miliki.
Wajar masyarakat di bantaran Sungai Karama dan Sungai Bonehau menolak pembangunan PLTA Karama, sebab bila betul terjadi, bukan hanya kebudayaan mereka yang akan rusak, tapi kenangan masa lalu akan sirna. Makam orangtua kita saja bila mau dipindah atau dihilangkan sudah terasa berat, apalagi kalau itu makam nenek moyang dan peradaban. Pasti amat menyakitkan bila itu musnah.
Dunia Akan Mengutuk Sulbar
Dunia akan menuntut Sulawesi Barat bila Situs Kalumpang dan kawasan disekitarnya ditenggelamkan! Ya, sebab apa yang ada di tempat itu bukan semata-mata benda fisik saja, tapi lebih dari itu. Ada hal-hal tertentu yang masih berbingkai misteri, yang merupakan akar kebudayaan kita ribuan tahun lalu.
Memang bila dinilai dengan uang itu hampir tak bernilai, tapi penghancurannya akan memberi kita kerugian tak ternilai
21Ekspedisi Bumi Mandar
harganya. Jauh melampaui sebuah unit PLTA yang hanya bernilai 12 triliun rupiah. Sebuah PLTA bisa dibangung lima tahun saja, tapi peradaban, seperti peradaban Kalumpang, tak akan bisa dibangun meski dengan biaya 1000 triliun rupiah pun.
Saya pribadi tak menolak pembangunan PLTA, sejauh dia tidak berdampak negatif ke situs kebudayaan Kalumpang. PLTA bukan satu-satunya pembangkit listrik, masih ada sumber energi alternatif lain, semisal angin dan panas matahari.
Ada banyak kasus, pembangunan PLTA di Indonesia ternyata tidak berdampak signifikan ke penduduk setempat, sebagaimana yang terjadi di Sumatera. PLTA Siguragura, PLTA Tangga, dan Peleburan Aluminium Kuala Tanjung adalah milik perusahaan patungan Indonesia dengan 12 perusahaan Jepang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Perbandingan saham antara Pemerintah Indonesia dan 12 perusahaan Jepang bersama pemerintahan Jepan didirikan adalah 10%:90 %. Oktober 1978 perbandingannya menjadi 25%:75% dan 1987 menjadi 41,13 %:58,87 %. Sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12 %:58,88 %. Proyek kerja sama ini akan berakhir 2013.
Ternyata ada motif pihak Jepang membantu pembagunan PLTA Siguragura dan PLTA Tangga. Yaitu sebagai sumber energi untuk industri peleburan aluminium, yang juga ada di Sumatera Utara, yang keuntungannya lebih banyak mengalir ke Jepang.
Menurut harian Kompas, sejak pertama kali beroperasi tahun 1983, listrik dari PLTA Siguragura dan PLTA Tangga tak perna benar bisa dinikmati rakyat. Selama kurun waktu 2002-2007, masyarakat Sumut justru mengalami krisis listrik Siguragura dan PLTA Tangga tidak banyak membantu.
22 Muhammad Ridwan Alimuddin
Kapasitas pembangkit yang dimiliki PLN di Sumut pun hanya 900-1.000 MW. Kebutuhan listrik saat beban (pukul 18.00-23.00) mencapai 1.200 MW. Tak heran, masyarakat Sumut selalu mengalami pemadaman list Kondisi itu berdampak pada ekonomi karena banyak pabrik yang tutup atau mengurangi jam produksinya. rumah tangga juga mengeluh karena peralatan elektroniknya cepat rusak akibat listrik sering mati tiba-tiba.
Saat krisis itulah rakyat Sumut ngiler melihat besarnya listrik yang dihasilkan PLTA Siguragura dan PLTA Tangga hanya untuk menghidupi pabrik peleburan aluminium. Hasil produksi aluminium pun 60 % diekspor ke luar negeri dan hanya 40 % untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan, selama ini pemda hanya menikmati “annual fee” dari Inalum Rp 74 miliar per tahun. Jumlah ini tak sebanding seandainya Proyek Asahan dikuasai Pemerintah Indonesia kemudian listrik PLTA Siguragura dan PLTA Tangga dijual ke PT PLN.
Bisa saja muncul pertanyaan, mengapa investor dari Cina begitu bersemangat membantu pembangunan PLTA Karama? Dari hitung-hitungan bisnis, pasti ada motif di balik itu. Pertama adalah pembagian keuntungan dari hasil penjualan listik. Pasti lebih banyak mengalir ke mereka, bukan hanya sampai di BEP (break event point), tapi beberapa tahun setelah itu. Sehingga yang diperoleh pemerintah Sulawesi Barat tak seberapa.
Saya pribadi tak terlalu percaya statemen yang dikemukakan pemimpin provinsi ini. Anwar Adnan Saleh mengatakan (dimuat di Radar Sulbar beberapa waktu lalu) bahwa “Imbal beli dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) wilayah Sulbar merupakan nilai tawar
23Ekspedisi Bumi Mandar
dalam pembangunan tersebut. Potensi itu diantaranya kakao, hasil laut, serta persawahan. China ingin berinvestasi sebab merupakan konsumen coklat yang besar dan mereka butuh suplai dari kita. Begitu pun dengan ikan segar karena mereka sangat gemar ikan. Imbal beli ini akan menjadi dasar untuk pembangunan proyek itu.”
Bila hanya mengandalkan coklat sama ikan, Cina tak akan bersemangat seperti sekarang. Pasti lebih dari itu. Coklat sama ikan itu mainan bisnis seujung kuku. Tak sebanding untuk berinvestasi triliunan rupiah.
Saya lebih cenderung pada motif kedua. Yaitu, ada kemungkinan kasus yang terjadi di Sumatera Utara bisa juga terjadi di Sulawesi Barat. Memang saat ini belum ada industri pertambangan yang membutuhkan energi listrik super besar. Tapi ke depan, akan ada kegiatan itu. Mamuju memiliki potensi tambang yang hanya diketahui segelintir negara-negara maju atau perusahaan multinasional.
Wajar sumber energi dibangun dulu, industrinya belakangan. Itu alasan sangat masuk akal. Masalahnya, pihak investor (dan mungkin juga pemerintah) tidak transparan dalam hal ini. Pemerintah hanya mendengun-dengunkan dampak positif, bla…bla…bla…
Saya kembali mengutip dalih pak gubernur Sulawesi Barat mengapa PLTA perlu dibangun di DAS Sungai Karama, katanya, “Megaproyek pembangunan PLTA ini diyakini dapat mendatangkan efek lain yang juga sangat menguntungkan masyarakat. Efek tersebut diantaranya pengairan persawahan, penyediaan air bersih masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, serta dapat difungsikan sebagai pusat wisata baru. Sehingga, dapat
24 Muhammad Ridwan Alimuddin
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.”
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh juga memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Sampaga Mamuju bahwa tidak akan ada dampak negatif dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di daerah tersebut. Dia menambahkan jaminan tempat tinggal baru yang bakal dibangun oleh investor sebagai tempat relokasi warga akan lebih baik dari sebelumnya. Selain konsekuensi relokasi, Anwar yakin tidak akan ada hal lain.
Tapi apakah betul itu yang akan terjadi? Ya, kita berpikir positif saja bahwa keuntungan di atas yang akan terjadi. Tapi, jangan sampai Situs Kalumpang dikorbankan! Bila itu yang terjadi, dunia akan mengutuk Sulawesi Barat.
Masyarakat internasional, khususnya yang memberi perhatian pada pelestarian budaya tradisional, mulai dari komunitas arkeologi hingga badan dunia di PBB yang mengurusi kebudayaan (UNESCO) akan mengecam habis-habisan Sulawesi Barat.
Kita jangan mencontoh habis-habis Cina, demi bendungan “Tiga Raksasa”, mereka rela menenggelamnkan ratusan kampung, memindahkan jutaan penduduk, dan beberapa situs bersejarah mereka.
Pertama, Cina negara industri. Kebutuhan energi sangat mendesak. Kedua, mereka negara militer yang bisa memaksakan kehendak. Ketiga, mereka memiliki banyak situs bersejarah. Hilang satu dua tidak apa-apa, masih ada puluhan (sedang kita, di Sulbar hanya ada satu). Keempat, DAM yang dibangun bisa mencegah banjir rutin yang terjadi di Sungai Kuning. Dan kelima, Cina tidak
25Ekspedisi Bumi Mandar
perlu mengutang duit untuk membangunnya.
Kesimpulannya, jika memang gubernur kita seorang yang kreatif, visioner, dan seorang bapak pembangunan yang beradab, maka dia akan bisa membangun PLTA Karama dengan tetap melestarikan situs Kalumpang.
Tetapi jika hanya berhasil membangun PLTA Karama dengan menjadikan situs Kalumpang sebagai tumbal, entah apa gelarannya.
Semoga saudara-saudara kita di Kalumpang bisa mempertahankan hak kebudayaan dan warisan leluhurnya, walau berhadapan kekuatan maha dahsyat. Kami di Balanipa, akan mendukungmu.
Ekspedisi Ini Nyawa Taruhannya
Saya seperti seorang navigator di atas mobil dalam sebuah lomba ‘rally car’ dengan rute punggung bukit berbatas jurang, jalan terjal tak beraspal, melintas anak sungai berbatu cadas, dan jalan sempit. Sabuk pengaman kupasang, sebab bila mobil menghantam sesuatu, saya pasti terlempar keluar. Kecepatan mobil tak wajar di jalur berbahaya. Digas terus, padahal kami sedang tidak balapan. Beberapa kali kepala saya julurkan ke luar jendela sebab mual. Seakan mau muntah.
Ide awalnya, Ekspedisi Save Our Kalumpang akan saya laksanakan sendiri. Ide ini saya sampaikan ke beberapa pihak/individu dan mendapat respon yang sangat baik. Ada yang memberi dukungan moril ada dalam bentuk materi, khususnya Harian Radar Sulbar. Singkat kata, berkat adanya bantuan dari
26 Muhammad Ridwan Alimuddin
banyak pihak, persiapan ekspedisi dapat saya matangkan dan pelaksanaannya pun dapat segera dilakukan.
Sebelum masuk Kalumpang, saudara Muhammad Ilham, Direktur Sulbar Ekspres, mengantar ke rumah pak Kalvin Kalambo. Di situ saya pertama kali melihat langsung dan berkenalan pak Kalvin. Selama ini hanya lewat media. Demikian juga sebaliknya, beliau kepada saya.
Ternyata saudara Ilham meminta kesediaan pak Kalvin menemani saya ke Kalumpang. Pertimbangannya, saya ini pertama kali ke Kalumpang. Bila tak ada teman, bisa repot di dalam. Padahal sih saya sudah siap untuk sendiri, sebagaimana riset-riset saya di daerah lain.
Rencana awal juga berubah. Selain rencana sendiri saja, sebelumnya saya ingin ke Kalumpang menggunakan moda transportasi umum, yakni mobil “india”, demikian istilah saudara Ilham. Disebut demikian, sebab modifikasi mobil mirip-mirip di film-film India, yakni ‘openkap’ lalu dibagian terbuka tersebut dipasangi kerangka besi. Tapi saudara Ilham mau mengantar dengan menggunakan mobil kantor (Sulbar Ekspress), setidaknya sampai ke Bonehau.
Sebab saudara Ilham ingin melibatkan bapak Kalvin Kalambo (putra Kalumpang yang juga anggota DPRD Sulbar), dan saudara Ilham belum begitu terbiasa mengemudikan mobil jalur Kalukku – Kalumpang, dia mengajak serta iparnya. Maka jadilah kami berempat menuju Kalumpang. Jauh berbeda rencana awal, yaitu ekspedisi solo atau sendiri.
Bagi saya pribadi, ada untung-rugi berombongan. Untungnya, bisa lancar ke dalam, demikian juga saat di lapangan. Mudah
27Ekspedisi Bumi Mandar
menjalin jaringan dengan masyarakat setempat, demikian pula informasi yang dibutuhkan. Ruginya, ada hal-hal yang tidak bisa saya rasakan langsung, misalnya nuansa saat menggunakan mobil ‘india’ ke Kalumpang. Tapi tak apa, yang penting tujuan bisa tercapai nantinya.
Berangkatlah kami berempat ke Kalumpang, 13 Januari 2012, sekitar jam lima sore meninggalkan kota Mamuju. Saya duduk di depan, di samping sopir, di kursi tengah saudara Ilham dan bapak Kalvin Kalambo. Sebelum masuk Kalumpang, kami singgah bermalam di Talondo, Bonehau. Nanti esoknya terus ke Kalumpang.
Tujuan Ekspedisi
Ekspedisi yang dilakukan oleh perusahaan media massa (cetak) jarang dilakukan. Yang rutin melaksanakan ekspedisi, setahu saya, hanya harian nomor satu di Indonesia, Kompas. Ekspedisi yang telah dilakukan, seperti Ekspedisi Bengawan Solo, Ekspedisi Papua, dan sekarang ini, Ekspedisi Cincin Api. Semua hasil ekspedisi mereka dibukukan, yang isinya artikel dan laporan-laporan berkaitan ekspedisi yang dimuat di media mereka (Kompas).
Ekspedisi oleh media bertujuan mendapatkan hasil liputan lebih mendalam, sebab berbasis riset (ilmiah), dilakukan dalam waktu lama, dan biasanya dalam bentuk tim. Menjadikan hasil liputan lebih berkualitas dibanding ‘strike news’.
Jurnalis melakukan ekspedisi hal yang amat penting, sebab bisa memberi wawasan baru bagi seorang jurnalis. Bukan hanya itu, dengan penggunaan kaidah-kaidah ilmiah, informasi yang diperoleh jurnalis lebih kuat. Tak mudah dipatahkan oleh argumen ‘ngomong saja’.
28 Muhammad Ridwan Alimuddin
Nah, itulah yang ingin dicapai dari Ekspedisi Save Our Kalumpang. Radar Sulbar sebagai harian terkemuka dan berpengaruh di Sulawesi Barat, tidak ingin memberitakan persoalan Kalumpang dengan informasi ala kadarnya, yang tak berbasis riset. Bagaimana pun, persoalan Kalumpang amat kompleks, yang berpihak pada kepentingan semua pihak. Baik masyarakat Kalumpang, lingkungan, kebudayaan, dan sejarah, maupun pemerintah.
Tujuan Ekspedisi Save Our Kalumpang antara lain adalah mendapat informasi data ketinggian kampung-kampung yang kemungkinan akan tenggelam bila betul PLTA Karama jadi dibangun sebagaimana kontruksi yang direncanakan, pendapat masyarakat Kalumpang, data ketinggian lokasi pembangunan PLTA Karama, mengamati keseharian penduduk di perkampungan DAS (daerah aliran sungai) Karama, mendokumentasikan dalam bentuk film dan foto DAS Karama dari Karama hingga Tarailu, melihat langsung situs-situs budaya yang telah diteliti (Minanga Sipakko dan Kamassi), mendokumentasikan bentuk-bentuk kebudayaan di Kalumpang, dan melihat langsung kondisi geografis Kalumpang, khususnya DAS.
Sebelum melaksanakan ekspedisi, telah dilakukan riset pustaka. Sebagaimana yang dimuat di harian Radar Sulbar, alam tulisan berseri “Selamatkan Kalumpang” beberapa waktu lalu.
Agar bisa memperoleh data yang dibutuhkan, dalam ekspedisi tim, yang langsung ke lapangan, menggunakan beberapa peralatan khususnya GPS dan kamera digital yang dilengkapi fasilitas GPS ‘built in’. Dengan digunakannya dua alat tersebut, hasil dokumentasi foto dan koordinat setiap tempat dapat diperoleh
29Ekspedisi Bumi Mandar
dalam waktu singkat dan akurat. Bukan hanya angka-angka, tetapi setiap foto yang diambil di semua tempat yang didatangi di Kalumpang terekam data koordinatnya. Jadi datanya bukan hanya tanggal, waktu kapan foto diambil (dipotret), tapi lokasinya juga.
Artinya, Ekspedisi Save Our Kalumpang adalah kegiatan serius sebab berbasis riset dan pengumpulan data langsung dari lapangan. Hingga nyawa pun dipertaruhkan, sebab berhadapan lingkungan Sungai Karama yang ganas.
Perahu Kuno dan Serakan Tulang Manusia di Tallondok
Hari pertama ekspedisi dimulai di Tallondok, masuk Kecamatan Bonehau. Transit di situ sebelum ke Kalumpang. Tallondok terletak di persis bagian barat daerah aliran Sungai Bonehau. Berdasar GPS, tempat ini berada di ketinggian sekitar 85 meter dpl (di atas permukaan laut). Bila turun ke Sungai Bonehau, ketinggiannya lebih rendah lima meter, sekitar 79 dpl.
Data ketinggian penting diketahui, sebab bisa dijadikan dasar apakah tempat tersebut tenggelam atau tidak. Tallondok letaknya sekitar 17 km dari Tomatua, tempat yang rencananya di situ akan dibangun dam PLTA Karama. Dengan asumsi tinggi dam nantinya 100 meter, Tallondok bisa tenggelam.
Yang menarik saya lihat di Sungai Tallondok adalah sampan. Sekilas sampannya biasa-biasa saja. Hanya berupa batang kayu yang dikeruk tengahnya dengan palatto di sisi kiri-kanan. Tapi bila dicermati dari kacamata teknik pembuatan perahu tradisional Mandar dan jejak-jejak teknik kuno, sampan atau “lepalepa’ di
30 Muhammad Ridwan Alimuddin
Tallondok cukup menarik. Di bagian dalam ada bagian yang timbul. Dalam bahasa Mandar disebut “tambuku”.
“Tambuku” adalah bagian kayu, berbentuk segiempat dengan dimensi sekitar 10x10x10cm yang sengaja dibuat ada (tidak ikut dikeruk) agar ada bagian tempat mengait tali pengikat, baik ketika menyusum papan lambung (“tobo” atau “tombo”) maupun ketika mengikat “baratang” (cadik). Nah, menurut penelitian ilmiah, teknik demikian adalah teknik sangat kuno, mulai digunakan ribuan tahun lalu. Khas Austronesia.
“Tambuku” yang sebenarnya hampir tak ditemukan lagi di perahu-perahu jenis baru, semisal sandeq atau kapal motor. Alasannya, sekarang digunakan paku atau pasak untuk menyusun papan. Sebelum ada teknologi bor (untuk membuat lubang masuk di sisi papan), maka tekniknya adalah menyusun papan dengan cara mengikatnya. Yaitu papan atas dan papan dibawahnya ada “tambuku” yang timbul keluar. Nah, disitu tali (biasanya rotan atau ijuk) dikaitkan. Agar lebih kuat, biasa digunakan kayu yang melintang di dalam lambung perahu.
Desain lepalepa juga unik, ramping dan panjang. Bentuk demikian perlu agar gaya geseknya dengan arus air tidak begitu besar. Jadi manuver di alur deras lebih mudah, dan bisa gampang melawan arus. Kekurangannya, daya muatnya sedikit. Bisa dibayangkan orang-orang dulu, “mattokong” (mendayung dengan menggunakan galah bambu) dari Sampaga hingga kawasan hulu. Berhari-hari baru tiba.
Sepertinya bentuk atau desain perahu “kulubelang” yang digunakan di Mamuju terinspirasi dari perahu yang ada di kawasan Kalumpang.Ada juga kemungkinan teknik maupun desain sampan-
31Ekspedisi Bumi Mandar
sampan yang digunakan di muara Sungai Mandar (Teluk Mandar) awalnya dikembangan di kawasan Kalumpang. Dengan kata lain, diwarisi dari nenek moyang kita di sana.
Menuju goa
Salah seorang penduduk Tallondok mengatakan, di sana dia pernah melihat tulang-tulang yang berserakan di dalam gua. Di sana juga ditemukan patung kecil. Penasaran dengan informasi tersebut, sekitar jam 9 pagi, 14 Januari 2012, tim Ekspedisi Save Our Kalumpang (saya, bapak Kalvin Kalambo dan Muhammad Ilham) menuju goa diantar beberapa lelaki di Tallondok.
Seakan diri seperti “bintanna” dalam film “Mummy”, yaitu petualang yang tertarik pada situs-situs bersejarah dan benda-benda kuno. Ya, bila betul apa yang diinformasikan tersebut, ada kemungkinan goa tersebut pernah dihuni manusia pra sejarah. Setidaknya sebagai tempat menyimpan mayat atau tulang-belulang jenazah.
“Kira-kira jaraknya satu kilometer,” menurut penduduk yang mengantar kami. Agar tak kecele, sebab biasanya bila orang gunung menginformasikan jarak biasanya tidak sesuai realitas atau lebih jauh, saya menganggap jaraknya 2km atau 3km.
Berjalan melintasi kebun coklat yang buahnya hitam-kering, pohon langsat, enau, bambu, dan menyusuri sungai kecil berbatu. Hati-hati juga berjalan di batu-batu sungai, bila terpeleset, resiko biasanya ada dua, terantuk ke batu atau kaki masuk lobang mengakibatkan translokasi.
Yang menjadi pionir sesekali tebas kanan-kiri membuka jalan. Beberapa bagian jalan di sisi sungai tersembul dari dalam tanah
32 Muhammad Ridwan Alimuddin
pipa ‘paralong’. Ternyata penduduk di perkampungan mengambil air minum dari sungai ini. Ya, meski tak menggunakan mesin, sebab sungainya berada di ketinggian, bisa mengalir lancar ke rumah-rumah.
Di dekat hulu sungai kecil, ada bak penampung air. Ukurannya sekitar 2x2x2 meter. Darinya keluar beberapa pipa berdiameter sebesar paha orang dewasa. Saat tiba di situ, yang mengantar kami berkata sambil menunjuk, “Itu di atas goa-nya”. Melihat ke atas, ada tumpukan batu terlindung rimbun semak.
Mendaki naik, agak susah sebab becek apalagi ke atas saya meng-on-kan terus kamera video. Sekitar 10an meter dari lokasi bak, terdapat goa kecil. Tidak begitu dalam, hanya 2-3 meter. Di dalam ada beberapa tumpukan batu besar, khususnya yang ada di sisi lain. Batu besar tersebut dengan bagian rendahnya diantarai lubang. Jadi bila mau ke sana, baiknya pasang kayu sebagai tempat meniti. Atau kalau tidak, bisa memanjat dari sisi lainnya.
Setelah bersusah payah memanjat, bukan karena tinggi, tapi karena saya membawa peralatan yang rentan pecah (kamera), akhirnya tiba di atas batu besar. Tulang-tulang manusia berserakan di atas. Kelihatan sebagai tulang manusia sebab ukurannya besar. Semakin ditelisik, tulangnya bisa ditebak. Ada tempurung kelapa, ada juga gigi dengan rahangnya. Bila ada wujud tengkorak utuh, mungkin suasananya menyeramkan.
Bersama tulang-belulang, ditemukan serpihan-serpihan tembikar. Sepertinya tembikar itu wadah penyimpanan tulang. Ternyata di beberapa bagian goa ada banyak tumpukan tulang. Selain di atas, juga ada di bawah. Saudara Ilham sempat menggali-gali tempatnya berdiri, juga ada tulang. Tapi karena kami bukan
33Ekspedisi Bumi Mandar
peneliti yang menfokuskan pada goa, untuk eskavasi besar-besaran tidak kami lakukan. Itu nantinya dilakukan arkeolog asli.
Yang saya cari-cari di dalam goa adalah lukisan dinding. Biasanya begitu di goa-goa purbakala. Seperti yang terdapat di Maros, di Kalimantan Timur, dan Papua. Apalagi kalau ada gambar perahu, akan lebih menarik. “Oh sepertinya itu lukisan,” ucap saya kepada saudara Ilham. Tapi saya agak ragu juga sebab gambarnya tidak jelas dan tak berwarna (misalnya warna merah), hanya gores-goresan.
Setelah puas mendokumentasikan, kami meninggalkan goa. Saya minta pak Kalvin membawa contoh-contoh tulang yang bisa dikirim ke Jakarta. Bila dilakukan uji karbon C14, umur tulang bisa diketahui dengan tepat.
Tiba di Tallondok, kami menuju rumah pemuka masyarakat yang mana anaknyalah, bernama Guntur, pertama kali menemukan tulang belulang di dalam goa sekitar dua tahun lalu. Saat itu dia mencari sarang burung walet.
Sewaktu menemukan tulang pertama kali, di sana juga ada patung kecil dan gelang terbuat dari perunggu. Nah benda itu dia simpan. Saat kami kerumahnya, benda-benda tersebut diperlihatkan. Betul, memang ada patung dan gelang. Bentuk patungnya sangat kuno, berbentuk manusia. Tapi kaki dan tangan tak ada lagi. Diameternya sebesar ibujari kaki. Saat melihatnya, saya langsung ingat bentuk patung-patung pra sejarah.
Dalam ilmu arkeologi, penyimpanan tulang belulang di dalam tempayangtanah liat jamak terjadi pada masa awal tahap logam, yaitu 200 sebelum masehi sampai 1000 M. Adapun fungsi gelang dan patung adalah bekal si mayat di alam baka. Memang begitu
34 Muhammad Ridwan Alimuddin
kepercayaan nenek moyang kita dulu.
Adanya bukti-bukti peninggalan arkeologis kembali bisa menjadi bukti sah, bahwa kawasan Kalumpang dan Bonehau adalah tempat awal berkembangnya peradaban nenek moyang kita, baik orang Mandar (Sulawesi Barat) maupun orang-orang di Pulau Sulawesi dan Indonesia bagian tengah. Sayangnya, masih banyak situs yang belum diteliti.
Lombeng Susu dan Banua Batang
Legenda Tokombong di Bura Tobisse di Tallang ternyata juga ada di Bonehau dan Kalumpang. Informasi ini diceritakan salah seorang tokoh masyarakat di Talondok, sesaat setelah balik dari goa Talondok. Menarik, sebab legenda tersebut juga menjadi cerita turun temurun di Mandar pesisir. Dengan kata lain, ada hubungan sejarah antara Kalumpang di pedalaman dengan pantai.
Bukan hanya itu, tentang Lombeng Susu, yang juga berkaitan dengan cerita Tokombong di Bura Tobisse di Tallang dalam cerita lisan di Kalumpang, adalah orang tua yang anak-anaknya tersebar di seantero Mandar. Kesebelas anaknya dan tujuan mereka adalah Daeng Matama ke Mambi, Dettu Manang ke Aralle, Tahalima ke Tabang, Daeng Kamahu ke Taramanuk, Daeng Mailullung ke Balanipa, Ta’ayoang ke Matangnga, Bitti Padang ke Rante Bulahan, Makke Daeng ke Mamuju, Tammi ke Bambang, Tala’binna ke Loe, dan Tambuli Bassi ke Tappalang.
Masih ada legenda lain, misalnya lima bersaudara yang berpisah untuk kemudian tersebar ke beberapa tempat. Mereka adalah Pong Lalong ke Rongkong, Pong Lewong ke Sabbang, Toketara ke Tabulahan, Tala’binna ke Karataun, dan Taura-ura ke Mandar.
35Ekspedisi Bumi Mandar
Bersama bukti-bukti fisik (peninggalan arkeologi) dan bahasa, cerita di atas menjadi bukti sahih bahwa nenek moyang orang Mandar di pesisir berasal dari Kalumpang.Jadi tak salah, bila ada hubungan emosional antara pedalaman dengan Mandar pesisir.
Menjelang tengah hari 14 Januari 2012, tim Ekspedisi Save Our Kalumpang melanjutkan perjalanan, menuju Kalumpang. Untuk bapak Kalvin Kalambo ikut. Saya dan Ilham dibawa ke kampung halamannya, yang mana di situ ada peninggalan rumah tua khas Kalumpang milik neneknya. Rumah adat Kalumpang disebut “banua batang”.
“Banua batang” cukup menarik. Pertama dari penggunaan istilah, yaitu adanya kata “banua”. Pemahaman kita selama ini “banua” atau “wanua” berarti kampung atau perkampungan. Ternyata, di Kalumpang “banua” itu berarti rumah. Tesis saya, akar kata “banua” sebagai kampung adalah “banua” sebagai rumah.
Alasannya, dulu rumah di Kalumpang diisi oleh puluhan kepala keluarga. Bisa sampai 60 kepala keluarga atau 100 jiwa di atas satu rumah. Artinya, rumah itu tak lain adalah “kampung”.
“Banua batang” di Kalumpang sama dengan tradisi rumah panjang di Kalimantan, dalam tradisi Suku Dayak. Yaitu rumah yang sengaja dibuat besar agar diatasnya bisa hidup beberapa kepala kelaurga. Alasan ini juga bisa menjadi dasar bila ada pendapat yang mengatakan hubungan budaya antara Kalumpang dengan Dayak amat sangat dekat.
Hal menarik lain, bila selama ini Kalumpang diidentikkan dengan Toraja (menjadi bagian dari budaya Toraja), berdasar bahasa dan arsitektur rumah, “banua batang” sangat berbeda jauh dengan rumah tongkonan Toraja.
36 Muhammad Ridwan Alimuddin
Khusus rumah, tak ada kemiripan. Demikian juga dengan rumah khas Mamasa. Yang mana, kedua tempat tersebut (Toraja dan Mamasa) bentuk atap rumahnya seperti perahu atau tanduk kerbau. Sedang di Kalumpang atapnya biasa saja, layaknya rumah-rumah panggung di Mandar.
Keunikan “banua batang” yang lain adalah, ukurannya sangat besar, bisa sampai 60 meter panjang dengan lebar lima meter. Bagian tiang dan kayu di struktur di bawah lantai, terbuat dari batang-batang kayu yang masih bulat, tidak ada penggunaan pasak atau paku, dan desain bagian bawah rumah seperti bangunan tahan gempa. Agak mirip-mirip dengan rumah panggung di Nias.
Apakah kawasan Kalumpang dulunya adalah kawasan gempa sehingga kakek-nenek kita mendesain rumah yang tahan gempa? Jika betul demikian, jika betul ada dam PLTA Karama, ada bahaya terpendam!
Pembangunan “banua batang” cukup rumit dan memakan waktu lama, bisa sampai tahunan. Sebab, kayu-kayu besar harus didatangkan dari dalam hutan. Membawa kayu dari dalam hutan pekerjaan yang sangat repot, melelahkan, dan melibatkan puluhan orang. Inilah sebab hampir tak ada lagi “banua batang” dibangun setelah tahun 70an.
Dalam pembuatan “banua batang”, juga ada aturan-aturan. Antara lain, ujung-ujung kayu tidak boleh saling bersentuhan (sidollik). Maknanya, agar penghuni rumah tidak saling menularkan penyakit. Persentuhan itu juga dianggap menghalangi pertumbuhan.
“Banua batang” dibangun berorientasi ke gunung. Bila ada gunung besar di selatan, maka orientasi bangunannya melintang
37Ekspedisi Bumi Mandar
utara-selatan. Yang cukup menarik, di “banua batang” juga ada “possiq” atau tiang agung. Yang letaknya persis di tengah. Perbedaan “possiq” dengan tiang lain, “possiq” ukurannya pendek, tidak menembus naik ke atas. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah, kepercayaan “possiq” juga ada di Mandar pesisir. Artinya, sekali lagi, ada hubungan kebudayaan yang erat antara pedalaman dan pesisir.
Dulu, sewaktu masih “sekampung” tinggal di dalam “banua batang”, setiap KK mempunyai kamar dan dapur sendiri. Tapi ada juga bangunan umum, seperti ruangan di depan tangga yang disebut “babana”. “Babana” memisahkan kamar pada satu bagian sisi dengan kamar di sisi yang lain.
Dalam setiap rumah juga menyiapkan tempat tidur bagi para tamu. Para tamu yang berkeluarga ditempatkan pada “tando-tando”. Rata-rata “banua batang” memiliki 1-3 “tando-tando”. Sedang tamu yang masih bujang, ditempatkan di “babana”.
Saat ini di Kalumpang dan Bonehau, sepertinya jumlah “banua batang” bisa dihitung dengan jari alias jarang ditemukan apalagi yang bagian-bagiannya lengkap. Beberapa rumah yang sempat disinggahi tim ekspedisi hanya bisa memperlihatkan keaslian struktur bagian bawah atau tiangnya. Sedang bagian tengah, sudah menggunakan struktur modern.
Tenun Ikat Sekomandi
Selesai menjelaskan bagian-bagian “banua batang”, R. E. Sipayo, seorang Tobara di Kalumpang, dengan rasa antusias yang terus membara, menjelaskan kapada tim Ekspedisi Save Our
38 Muhammad Ridwan Alimuddin
Kalumpang salah satu keterampilan khas Kalumpang. Tenun ikat.
Pemahaman selama ini, penyebutan nama sarung ikat dari Kalumpang disebut “sekomandi”, sebagaimana menyebut “lipaq saqbe” untuk tenunan sutra dari Mandar. Ternyata, “sekomandi” itu hanya salah satu jenis sarung ikat di Kalumpang. Adapun jenis yang lain adalah “rundun lolo” dan “marilotong”.
“Sekarang di rumah saya ada sekomandi dan rundun lolo, marilotong sudah saya pesan ke penenun. Nanti kita ke sana lihat cara membuatnya,” ungkap R. E. Sipayo sambil masuk kamar mengambil koleksi tenun ikatnya. Kainnya kelihatan tua, warna buram.
Penamaan tenun ikat berdasar pada coraknya. “Marilotong” itu berwarna hitam dan polos. Sedang “sekomandi” dan “rundun lolo” ada motifnya. Yang membedakan, “rundun lolo” motif atau coraknya garis panjang. Memang sekilas mirip, tapi “rundun lolo” lebih dominan garis-garis panjangnya.
Setelah mendokumentasikan koleksi tenun ikat Kalumpang, tim ekspedisi diajak R. E. Sipayo ke penenun. Kami berjalan sekitar 100 meter, melalui lapangan Kalumpang. Dari jauh, tampak seorang wanita muda menghadap ke dinding, mengikat-ikat bentangan lilitan benang.
“Oh, ternyata itu alasannya mengapa disebut tenun ikat”, guman saya dalam hati. Mengikat kumpulan benang adalah salah satu teknik sebelum mewarnai benang yang akan ditenun.
Prosedur lengkap pembuatannya sebagai berikut. Dalam pembuatan tenunikat digunakan beberapa alat, yaitu “apiq” atau alat pengikat pinggang penenun (“topaq tannun”); “talekoq” atau
39Ekspedisi Bumi Mandar
alat menahan benang yang berada di belakang penenun; “balo” atau alat menahan benang yang dipasang di perut penenun; “tittiq” atau alat mengangkat/mengatur benang yang digerakkan secara bergantian dengan “baloq”; “balido” atau alat untuk merapatkan benang; dan “kalimuran” atau “laso katadan” atau alat untuk menahan benang pada saat diikat agar motif tertata rapi dan menjadi tempat mengukir motif.
Tahapan pembuatan terbagi atas tiga, yakni pemintalan, pewarnaan benang, dan penenunan. Proses tersebut bisa memakan waktu enam sampai dua belas bulan. Itulah alasan, saat ini, sarung ikat Kalumpang amat mahal harganya.
Dulu, sarung ikat menggunakan kapas yang ditanam sendiri oleh masyarakat Kalumpang. Tapi sekarang, benang didatangkan dari luar. Sewaktu masih menggunakan kapas produk sendiri, untuk pengolahannya sebagai berikut. Kapas dijemur sampai kering lalu dibuat menjadi benang dengan menggunakan “unuran”. Benang yang dihasilkan kemudian digulung ke “balekoan”.
Berikutnya adalah tahap pewarnaan. Tahap pertama adalah pemberian bahan perekat warna. Bahannya berupa campuran cabe (“marisa” atau “pendawa”), kemiri, lengkuas, dan “kaju pallin”. Bahan-bahan tersebut ditumbuk sampai halus lalu dimasak.
Di wadah lain, dibuat rendaman abu yang terbuat dari kayu “bakkudu”. Air rendaman abu, hanya diambil bagian atas yang agak jernih setelah terjadi pengendapan. Air rendaman dan bahan campuran perekat warna selanjutnya dipoles ke benang sampai meresap. Setelah itu, dijemur selama 30 hari terus menerus agar warna yang diberi kuat dan tidak luntur.
40 Muhammad Ridwan Alimuddin
Benang yang sudah diberi warna dasar, yang terlihat kekuning-kuningan, dimasukkan ke dalam “kalimuran”. Bentuknya segiempat, kira-kira panjangnya hampir dua meter dan lebar sekitar 60cm. Benang direntang. Nah, rentangan benang diikat per kelompok, kira-kira terdiri dari 10 helai benang. Susunan benang yang diikat itulah yang akan membentuk motif atau corak kain.
Dulu, digunakan kulit batang pisang (“kuli’ puttiq”)tapi saat ini digunakan tali rafiah. Alasannya, lebih praktis. Kalau kulit batang pisang, harus diolah. Itu memakan waktu lama.
Pada pengikatan pertama, warna yang diberikan adalah warna dasar yaitu merah (“bakkudu”, sebab bahannya akar pohon mengkudu) dan biru (“tarun”, digunakan daun tarun). Daun “tarun” juga digunakan orang Kajang, Bulukumba dalam membuat sarung. Bahasa Inggris warna yang dihasilkan “tarun” adalah indigo.
Warna tidak diberikan langsung ke benang yang berada di “kalimuran”, melainkan direbus. Bahan, seperti “bakkudu” diiris tipis dulu kemudian ditumbuk halus. Direbus bersama benang sekiatar 12 jam.
Setelah proses tersebut, kembali diulang proses memasang benang ke “kalimuran” untuk kembali diukir (baca: diikat) dengan tali rafiah.Fungsi ikatan adalah untuk menutupi (melindungi) warna merah yang tercipta berkat direbus bersama “bakkudu”.Adapun yang tidak diikat, akan berubah warnanya bila direbus dengan bahan lain, misalnya “tarun” untuk warna biru. Jadi, disitulah tercipta motif-motifnya. Makin unik motifnya, makin rumit ikatannya.
Yang menarik, untuk membuat motif, tidak digunak sketsa atau menggambarkan ke benang yang ada di “kalimuran”. Tetapi berada di imajinasi penenun. Ada banyak motif di kain Kalumpang, seperti
41Ekspedisi Bumi Mandar
motif “ulu karua kaselle”, “ulu karua barinni”, “toboalang”, “rundung lolo”, “leleq sepu”, dan lain-lain. Motif tersebut memiliki makna.
Misalnya motif “ulu karua kasella” bermakna bahwa di Kalumpang terdapat delapan dewan adat sebagai pilar, yaitu Tobarak Pondan, Tobarak Timba, Tobarak Lolo, Topakkalo, Tomaq Dewata, Totumado, dan Tomakaka.
Berikutnya adalah tahap terakhir, yaitu penenunan. Benang yang telah direbus bersama bahan pewarna dibuka tali pengikatnya. Agar susunan benang tidak rusak (susunan warna tidak bergeser), benang diangkat satu per satu dengan hati-hati untuk selanjutnya dipasang ke alat tenun. Sebelumnya, benang terlebih dahulu “diitto” yaitu menganyam dengan menggunakan lidi.
Dulu, selain digunakan sendiri (hanya dipakai dalam upacara atau pakaian adat, tikar untuk tamu terhormat), tenun ikat dijadikan sebagai alat penukaran (barter) dengan kerbau atau babi. Sebab memang tenun ikat amat mahal harganya.
Saat ini pengerajin tenun ikat sangat sedikit. Di Desa Kalumpang saja, menurut R. E. Sipayo mungkin hanya dua orang saja. Selain di Desa Kalumpang, juga ada di Malolo dan Kampung Batuisi. Gabungan atas keduanya kira-kira ada 30 pengerajin. Ironis memang, padahal motif tenun ikat dari Kalumpang dikenal sebagai salah satu motif tertua di dunia.
Katinting Super Penguasa Sungai Karama
Satu dekade saya mempelajari kebudayaan maritim nusantara, yang mana salah satunya tentang perahu, di Kalumpang-lah saya pertama kali melihat perahu kecil yang menggunakan lima
42 Muhammad Ridwan Alimuddin
mesin sekaligus. Itulah katinting, si penguasa Sungai Karama.Bila di tempat lain katintingnya biasa-biasa saja, di Sungai Karama, katintingnya super.
Sejatinya, pengaruh kebudayaan bahari di Kalumpang telah ada ribuan tahun lalu, seiring datangnya migrasi orang Austronesia di muara Sungai Karama (Sampaga). Teknologi pelayaran (perahu) mereka gunakan masuk ke pedalaman, hingga ke hulu Sungai Karama. Teknologinya amat sederhana, hanya berupa batang kayu yang dikeruk tengahnya dan atau rakit bambu.
Teknologi demikian terus bertahan sampai saat ini. Sampan tak mengalami perubahan bentuk. Palingan teknik pembuatan, yang mungkin dulunya dikeruk dengan menggunakan kulit kerang atau batu untuk kemudian besi. Dulunya perkakas mereka masih sangat kasar, seiring pengaruh dari luar, benda-benda tajam yang lebih keras digunakan. Seperti parang, kapak dan ketam.
Hingga kemudian pada tahun 70-an, mesin mulai diperkenalkan. Perlahan, perahu yang menggunakan mesin mulai menggantikan sampan kecil. Saat ini sampan kecil digunakan untuk menyebrang saja. Bila ada yang menggunakan melakukan perjalanan dari Kalumpang ke Tarailu atau sebaliknya, mungkin dianggap gila saat ini.
Penggunaan mesin mengakibatkan waktu tiba ke kawasan hulu menjadi lebih singkat dengan kapasitas bawaan lebih banyak. Dulu, saat masih sampan, perjalanan dari Sampaga ke Kalumpang bisa memakan waktu satu minggu. Saat mesin digunakan, satu-dua hari saja. Bila mesinnya banyak, bisa sehari saja.
Perahu yang dipakaikan mesin disebut katinting. Kentara jenis perahu tersebut introduksi dari luar, sebab istilah “katinting”
43Ekspedisi Bumi Mandar
adalah istilah Bugis. Yang mana istilah terserbut muncul ketika perahu mulai menggunakan mesin.
Secara umum, kantinting adalah perahu kecil, bercadik dan menggunakan mesin. Bentuk perahu katinting di Sungai Karama dan sungai-sungai sekitarnya amat sederhana. Terdiri dari “balakang” (kayu utuh yang dikeruk) untuk kemudian ditambahi papan “tobo”, biasanya satu atau dua.
Panjang katinting berkisar enam sampai delapan meter. Di kiri kanan ada “palatto”. Istilahnya sama dengan Mandar pesisir, seperti “baratang” untuk cadik, “palatto” untuk katir, dan “tadiq” untuk kayu berbentuk huruf “L” yang menghubungkan cadik dengan katir. Dilihat dari teknik mengikat cadik,paling tidak ada dua dugaan: pengaruh dari pelaut Mandar atau memang demikian teknik ikat dulu (amat kuno) yang dibawa oleh orang Austronesia.
Teknik mengikat cadik di perahu Mandar amat khas. Sejauh pengamatan saya di beberapa tempat di Nusantara, tak ada yang menggunakan teknik demikian selain pelaut Mandar (belakangan saya lihat juga di perahu orang Kalumpang). Lilitan talinya saling-silang dan posisi “tadiq” yang saling berhadapan.
Keunikan perahu atau katinting di Kalumpang adalah jumlah mesin yang digunakan. Bila di pesisir Mandar paling banter satu (saya tidak pernah lihat menggunakan dua unit mesin), maka di Sungai Kalumpang minimal menggunakan tiga, rata-rata empat, beberapa lima.Itu merupakan proses adaptasi agar bisa melawan arus Sungai Karama yang deras.
Mesin dipasang persis di atas baratang yang menembus bagian atas lambung perahu, kiri-kanan; baik baratang depan maupun belakang. Bila menggunakan lima mesin, dipasang di
44 Muhammad Ridwan Alimuddin
tengah, di sisi kanan. Di situ dibuatkan tempat agar tak berada di tengah lambung perahu.
Agar semburan air dari baling-baling tidak mengenai penumpang perahu, di bagian atas baling-baling dipasangi karung “karoroq”. Fungsinya mirip pelindung di atas ban motor atau sepeda, agar lumpur yang “dilemparkan” roda tidak mengotori.
Sebab ukuran katinting kecil, otomatis suara mesin memekakkan telinga. Tidak seperti mesin kapal kayu, yang berada di bagian bawah lantai. Kalau katinting, bisa persis di samping, depan, belakang penumpang. Entah berapa desibel keras suara yang dihasilkan. Telinga saya sampai “ngiiiiiing” dalam waktu lama sewaktu menyelesaikan perjalanan dari Kalumpang ke Karama. Hampir tiga jam saya duduk berdampingan mesin yang kerasnya melebihi keras musik cadas. Saat perjalanan, tangan saya tempelken ke telinga. Khawatir gendang telinga rusak.
Keunikan lain di katinting Sungai Karama adalah kemudi (“guling”) yang pendek. Katinting di pesisir (laut) ukuran terpendek lebih semeter. Pada sandeq, bisa sampai 2,5 meter. Tapi pada katinting Sungai Karama, panjangnya tak sampai semeter. Ya, wajar pendek. Sebab bila panjang, bisa dipastikan terkait ke dasar sungai. Dasarnya bukan pasir, tapi batu cadas. Sekali terantuk keras, pasti patah.
Memang pelaut-pelaut Mandar, khususnya passandeq, jago mengemudikan sandeq. Tapi “motoris” (ini istilah saudara M. Ilham untuk menyebut pengemudi katinting) punya keahlian dan keberanian yang berbeda. Sebagian besar alur yang dilalui ada bahayanya, mulai dari batu besar, dasar sungai yang dangkal, alur sempit, golakan air, air deras, hingga perputaran arus. Adapun di
45Ekspedisi Bumi Mandar
laut, bahaya sesekali saja ada. Malah biasa tidak ada.
Di laut salah satu bahaya yang paling ditakuti pelaut adalah “kala-kala”, yaitu air yang bergolak sebab ada pertemuan arus. Tapi di Sungai Karama, hampir tia seratusan meter ada “kala-kalanya”. Dan itu bisa dilalui dengan lembut oleh para pengemudi katinting.
Pengemudi katinting minimal dua orang. Nakhoda duduk di buritan, mengendalikan kemudi. Dia mengontrol mesin yang ada di bagian belakang. Sedang pembantunya mesin bagian tengah atau depan. Pembantu juga mengawasi haluan perahu. Memberi peringatan bila ada bahaya di depan. Salah satu tugas pembantu adalah menaik-turunkan gas mesin. Bila arus deras, gas dinaikkan, bila tidak gas diturunkan.
Sewaktu dalam perjalanan dari Kalumpang ke Karama, yang jaraknya sekitar 25km dengan menggunakan lima mesin berkekuatan 11 PK, kecepatan katinting rata-rata 20 km/jam (kadang 16 km/jam, kadang 25 km/jam, tergantung deras arus yang dilalui) waktu tempuhnya sekitar tiga jam.
Katinting adalah sarana transportasi utama di Sungai Karama, khususnya di bagian hulu (antara Desa Kalumpang dan Desa Karama). Untuk membawa komoditas hasil perkebunan, misalnya coklat dan kopi, atau bahan-bahan bangunan serta transportasi manusia, katinting amat berperan. Memang ada motor (ojek), tapi hanya bisa membawa satu orang atau barang yang terbatas.
Menggunakan katinting siap-siap merogoh kantong dalam-dalam. Perjalanan dari Desa Kalumpang ke Karama bayarannya lebih 100 ribu per orang. Padahal jaraknya cuma 25 km. Bila menggunakan pete-pete, misalnya dari Majene ke Campalagian, bayarannya paling 7 ribu. Sewaktu saya dan pak Kalvin Kalambo
46 Muhammad Ridwan Alimuddin
mencarter katinting dari Kalumpang hingga ke Tarailu, bayarannya Rp 800.000. Itu untuk turun, bila naik (dari Tarailu ke Kalumpang) bisa dua kali lipat.
Penyebab mahal, pertama adalah harga bahan bakar. Bensin 1 botol di Kalumpang Rp 15.000. Makin ke arah hulu makin mahal. Kedua, bila melawan arus, jelas lebih banyak bahan bakar yang digunakan. Beda bila menurun, dua mesin cukup. Kalau naik, setidaknya empat mesin.
Ya, begitulah cerita tentang katinting super di Kalumpang. Kekhasannya tak kalah dengan pengemudi perahu yang melakukan perjalanan di hulu-hulu sungai di Kalimantan.
Pakaian Tradisional, Percampuran Laut dengan Hutan
Pakaian tradisional Kalumpang jauh berbeda dengan pakaian adat Mandar pesisir, juga Toraja. Sebab, Kalumpang mempunyai bentuk kebudayaan sendiri. Walau pada dasarnya ada banyak kesamaan, baik bahasa, pranata sosial, ilmu pengetahuang dan lain-lain. Yang menarik di pakaian Kalumpang, di situ ada perpaduan unsur laut dan hutan.
Kaum wanita di Kalumpang warna pakaian adatnya berwarna hitam atau ungu dengan hiasan cangkang salah satu jenis siput laut. Bentuknya seperti “kacelo” (sejenis hewan laut yang biasa dijadikan mainan) tapi ukurannya amat kecil, lebih kecil daripada jari kelingking. Cangkang atau hewan laut tersebut oleh masyarakat Kalumpang disebut “bei”, maka pakaian adatnya disebut “bei”.
Cangkang diasah sampai halus dan rata (tak ada bagian yang cembung) untuk kemudian dijahit satu-satu ke kain hitam hingga
47Ekspedisi Bumi Mandar
kemudian membentuk pola tertentu.
Untuk pria pakaian adatnya disebut “pewo puang” yang terbuat dari kain yang lebarnya sekitar 60cm. Diberi warna hitam setelah ditetesi “pattiq” atau lilin dari sarang lebah. Dalam proses mengukir, sarang lebah dipanaskan terus-menerus dalam periuk (kuriq-kuriq) agar terus mencair.
Untuk warna hitam pada motif “pewo puang” digunakan dari lumpur tanah ditambah tumbuhan “bilatte”.
Kain “pewo” atau “peo” ada dua jenis. Yang pertama, seperti yang disebutkan di atas untuk kalangan bangsawan. Untuk masyarakat umum hanya disebut “pewo”. Terbuat dari kain putih polos (dari kapas yang ditenun). Jadi perbedaan antara “pewo” biasa dengan “pewo puang” ada tidaknya motif.
Penggunaannya dengan cara melilitkannya ke pinggang sampai pusar lalu ke selangkang di antar kedua pangkal paha dan kedua belah ujungya masing-masing menutupi pusar sampai melewati sedikit lutut di depan dan belakang.
Pasangannnya dengan baju “ambulea” yaitu kain berwarna hitam atau kuning tanpa kerah. Berlengan panjang dengan ornamen manik-manik. Untuk penutup kepala digunakan “passappuq”, sebagaimana yang juga ada di Mandar.
Bukan hanya pakaian yang terbuat dari kain. Dari kulit kayu, dulu, juga ada. Berdasar fungsi, dibedakan atas tiga. Yaitu “pekkaro”, yang dikenanakan laki-laki untuk kegiatan sehari-hari. Kedua “sassang”, untuk berburu. Bentuknya seperti rok berlapis menjumbai ke bawah untuk melindungi pakaian dalam agar tak basah dan tidak tertusuk duri. Dan yang ketiga disebut “kundai”, pakaian dari kulit kayu untuk perempuan.
48 Muhammad Ridwan Alimuddin
Untuk membuat pakaian dari kulit kayu, jenis kayu yang digunakan adalah “polosan”, “lambaku”, dan “passe”. Bahan tersebut diolah melalui beberapa proses. Pertama, kulit kayu diiris selebar 10 cm dan panjang sesuai kebutuhan. Kulit kayu tersebut kemudian dipukul-pukul dengan kayu pemukul di atas batu.
Saat bahan tersebut telah lunak, bahan direndam (“dirammei”) sambil dipisah-pisah untuk selanjutnya disulam. Sebelum dijadikan pakaian, bahan tersebut dijemur.
Salah satu artefak yang ditemukan dalam penggalian beberapa situs di Kalumpang (Bukit Kamassi dan Minanga Sipakko) adalah alat pemukul kulit kayu. Artinya, tradisi pembuatan pakaian dari kulit kayu adalah tradisi yang bertahan ribuan tahun. Yang bertahan sampai tahun 70-an. Saat ini mungkin sudah tidak ada lagi yang mengenakan sebab kain lebih praktis dan lebih mudah memperolehnya.
Akan tetapi, pakaian adat Kalumpang masa kini dengan masa lampu ada beberapa perbedaan. Secara umum sama, tapi bila saya melihat pakain “bei” saat ini bentuknya seperti rompi. Itu berbeda dengan foto-foto wanita Kalumpang, yang didokumentasikan pada tahun 30-an, kainnya mirip baju bodo (agak tipis dan lentur).
Adapun motif hiasan “bei” tetap sama. Wanita juga mengenakan gelang “potto balusu” dari cangkang laut (mungkin lola), serta kalung dari manik-manik. Dan yang unik di foto wanita Kalumpang lampau, anting-anting “saluq” dipasang di cuping telinga bagian atas.
Demikian juga bawahannya. Dulu mengenakan kain panjang yang dilipat-lipat masuk di bagian luar paha, baik kiri maupun kanan. Menurut R. E. Sipayo, panjang kain rok, baik lelaki maupun perempuan bisa bermeter-meter.
49Ekspedisi Bumi Mandar
“Passappu” orang Kalumpang lampau juga unik. Ukurannya lebar. Kemungkinan besar itu adalah kain “pewo” yang digulung lalu dililitkan di atas kepala. Pada lelaki, juga mengenakan kalung.
Kesimpulannya, pakaian tradisional Kalumpang, khususnya yang dulu, sangat unik dan ada keanggunan di situ.
Kalumpang Lampau di Belanda
Sebagai ekspedisi ilmiah, Ekspedisi Save Our Kalumpang tak hanya menghimpun informasi di lapangan. Tapi juga dari referensi, baik itu buku, makalah maupun sumber-sumber lain di internet. Riset pustaka dilakukan jauh sebelum penelitian di lapangan. Salah satu sumber penting adalah koleksi foto-foto kuno Kalumpang yang menjadi koleksi Museum Tropen Belanda.
Meski tim ekspedisi tidak langsung ke Belanda, tapi dokumentesi foto tersebut bisa diakses dari jauh. Yakni lewat internet, dengan alamat (www.tropenmuseum.nl). Foto tentang Kalumpang tidak langsung ada di halaman laman tersebut, tetapi ada di halaman khusus. Selain tentang Kalumpang, juga ada foto-foto kuno tentang suku lain, baik Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, maupun suku lain di Nusantara.
Khusus tentang Kalumpang, setidaknya ada delapan foto. Walau judul foto menggunakan Bahasa Belanda, tapi judu foto tersebut ada kata “Galoempang” (kata kuno dari Kalumpang). Bila tak ada kata tersebut, kata lain bisa dijadikan referensi, misalnya “Karama rivier” (Sungai Karama).
Foto pertama adalah foto yang memperlihatkan Dr. P. van Stein Callenfels, arkeolog berkebangsaan Belanda yang pertama
50 Muhammad Ridwan Alimuddin
kali melakukan eskavasi di Kalumpang (Bukit Kamassi) untuk kemudian memperkenalkan Kalumpang ke dunia internasional. Foto ini tak ada di ‘folder’ tentang Galoempang, tapi tentang dirinya sendiri (Dr. P. van Stein Callenfels).
Dalam foto tersebut, tampak Dr. P. van Stein Callenfels duduk di atas tandu yang dipikul beberapa orang. Dia diberi gelar “Ivan yang Mengerikan” sebab tubuhnya yang besar (tinggi hampir dua meter) dan selalu makan dengan lahap. Tapi orangnya ramah, gampang bergaul dengan masyarakat pribumi, dan daya ingatnya cukup kuat.
Selain Dr. P. van Stein Callenfels dan para pemikulnya, juga ada belasan orang lain. Ada yang mengenakan kopyah, ada juga “sokkok biring”. Yang mengenakan “sokkok biring” mungkin aristokrat dari pesisir (Sampaga?) yang berperan sebagai penghubung Dr. P. van Stein Callenfels dengan penduduk Kalumpang. Lokasi pengambilan foto tidak diketahui.
Foto yang lain memperlihatkan si orang ber-”sokkok biring” duduk berdua dengan Dr. P. van Stein Callenfels, dengan janggutnya yang lebat, dengan minuman di atas meja depan mereka. Tampak di belakang bangunan rumah sederhana. Kemungkinan tempat tinggal sementara Dr. P. van Stein Callenfels di Kalumpang. Juga tampak empat orang yang jongkok dan berdiri di dekat mereka berdua.
Berikutnya tiga foto yang tujuannya sama, memperlihatkan pakaian adat dan keseharian orang Kalumpang dan sama-sama berlatar belakang pohon bambu. Foto tidak diketahui siapa fotografernya tapi kemungkinan besar didokumentasikan antara tahun 1910 dengan 1916 atau 1924.
51Ekspedisi Bumi Mandar
Pertama foto tiga orang dua wanita mengapit seorang lelaki (lihat foto Laporan Seri ke-6). Foto kedua, hanya seorang wanita (wanita di bagian kiri foto sebelumnya). Pakaiannya tetap sama, yaitu pakaian “bei”.
Foto ketiga, empat orang lelaki yang hanya mengenakan kain sebatas dada. Mungkin “pewo”. Adapun penutup kepalanya berupa “passappu”. Dua yang di depan “pewo-nya berwarna putih, sedang dua yang dibelakang mengenakan sarung kotak-kotak.
Berikutnya foto sepasang lelaki dan wanita. Yang wanita mengenakan pakaian adat “bei”, sedang lelakinya baju kemeja putih dan sarung (“pewo”?) putih. Mereka berfoto dengan latar rumah, bukan bambu. Fotografernya diketahui, bernama A. Bikker. Foto dikutip sebelum tahun 1943.
Dua foto yang lain memperlihatkan kerumunan orang di samping rumah. Yang menarik di foto ini, memperlihatkan pakaian masyarakat umum Kalumpang, baik dewasa, remaja, maupun anak-anak. Dan tak kalah penting adalah ada bagian dari rumah “banua batang” yang terlihat dalam foto ini, yaitu dindingnya.
Dinding sangat sederhana, mungkin hanya batang “gamo” atau batang nipah. Belum menggunakan papan. Atapnya juga dari rumbia atau daun kelapa. Sayangnya, bagian lain dari “banua batang” tidak terlihat. Jadi konstruksi “banua batang” pada tahun 1910-an tidak terlihat sempurna.
Kesimpulannya, walau hanya delapan foto, foto tersebut amat penting untuk memahami kehidupan Kalumpang masa lampau, walau itu 100 tahun lalu. Dengan berdasar foto, kita bisa membandingkan perbedaan, kesamaan atau perubahan yang terjadi. Sebagaimana yang saya tuliskan kemarin, tentang baju
52 Muhammad Ridwan Alimuddin
adat Kalumpang. Apa yang ada sekarang ternyata berbeda dengan baju dulu. Yang tetap mirip adalah pola atau motif di baju.
Dengan berdasar foto, ada banyak analisis yang bisa dilakukan. Semakin banyak referensi atau pengetahuan seseorang tentang bentuk-bentuk atau simbol-simbol dalam kebudayaan, analisis foto semakin mudah dan tepat. Misalnya bentuk ikat kepala, gaya berfoto, tempat ayam di dinding rumah, dan gaya berpakaian.
Masih banyak foto lain yang bisa menjadi rujukan untuk memahami Kalumpang, khususnya foto-foto tentang Poso dan Toraja. Bagaimana pun, oleh Belanda, dulu Kalumpang diidentikan dengan Toraja. Makanya dalam beberapa foto, ada keterangan yang kira-kira berarti “Kalumpang, sebuah daerah yang berada dekat dengan Toraja”.
Ada foto bangunan rumah, yang bagian bawahnya mirip konstruksi “banua batang”. Tapi saya tidak berani menyimpulkan itu “banua batang” sebab keterangan fotonya tak jelas menyebut “Galoempang”. Di sisi lain, judul foto “Een Toraja geestenhuis ten zuiden van het Poso meer” memberi kemungkinan bahwa itu adalah “banua batang”.
Untuk menyimpulkan apakah foto tersebut “banua batang” atau bukan amat mudah, tinggal memperlihatkan ke tetua-tetua orang Kalumpang. Pasti mereka bisa kenali.
Orang Kalumpang Menukar Kerbau dengan Budak
“Memang dulu di Kalumpang juga banyak dipelihara kerbau, tapi bukan untuk dipakai upacara seperti di Toraja melainkan dibarter dengan budak dari sana. Kan orang Toraja butuh banyak
53Ekspedisi Bumi Mandar
kerbau untuk upacara-upacaranya. Jadi orang Kalumpang sebagai pedagang perantara. Budak dibawa ke Sampaga, di sana dijual sama orang Bugis – Makassar atau orang Mandar yang berdagang budak,” demikin informasi dari R. E. Sipayo tentang fungsi kerbau di Kalumpang.
Informasi itu sedikit mengejutkan. Saya tidak pernah menduga Toraja – Kalumpang – Sampaga adalah salah satu rute distribusi budak dari Toraja. Memang Toraja (bersama dengan Bali dan beberapa tempat di kawasan timur Indonesia) dulu dikenal sebagai daerah penghasil budak di Nusantara, tapi pikirnya rutenya lewat selatan Toraja saja (Enrekang – Pinrang atau lewat Luwu). Ternyata ada yang lewat utara juga, keluar dari Sungai Karama.
Anwar Toshibo, dalam bukunya “Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX”, tak ada catatan yang menyebut salah satu rute penyaluran budak adalah lewat Kalumpang. Jadi, informasi yang saya peroleh mungkin sebuah penemuan.
Dalam buku tersebut di atas, Sulawesi Selatan telah lama menjadi pusat perdagangan utama budak sebelum ditaklukkan Belanda pada 1667. Pelabuhan Makassar adalah gudang penyaluran yang menghubungkan Indonesia Timur dan Barat. Dalam beberapa laporan diketahui bahwa sebagian besar dari mereka adalah hasil tangkapan dari suatu ekspedisi perburuan budak oleh orang Bugis-Makassar terhadap orang Toraja.
Alasan Bugis-Makassar memburu orang Toraja diantaranya adalah adanya stereotipe bahwa orang Toraja merupakan penduduk yang paling ganas dan tak dapat dikendalikan dan sikap mereka yang menolak Islam pada waktu itu. Ada juga faktor
54 Muhammad Ridwan Alimuddin
internal di Toraja, yang mana strata sosial memang sangak ketat, antara bangsawan dengan budak.
Para bangsawan atau aristrokrat Toraja jelas mengambil keuntungan dari budak Toraja yang mereka jual keluar. Keuntungan tidak langsung adalah untuk mengurangi jumlah penduduk di kawasan Toraja. Kebiasaan berjudi, khususnya sabung ayam, yang ketika kalah menjual diri juga ‘menyuburkan’ tumbuhnya budak dari Toraja.
Pada umumnya budaya perbudakan hampir ada di semua suku utama di Sulawesi Selatan (Barat), Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Tapi bentuk perbudakan di Sulawesi Selatan agak berbeda dengan bentuk perbudakan oleh orang Barat. Umumnya di Sulawesi Selatan berdasar pada kesukarelaan (patron – klien yang mentradisi), di barat cenderung dipaksakan dan menjadi komoditas perdagangan. Jadi, defenisi perbudakan di Sulawesi Selatan membutuhkan penjelasan tersendiri. Tidak boleh langsung menyamakan dengan defenisi perbudakan di barat.
Ketika dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, mulai dari perkebunan, buruh hingga prajurit perang, permintaan budak semakin tinggi. Maka cara perekrutan budak di luar kebiasaan pun terjadi. Terjadilah ekspedisi penaklukan atau suatu wilayah, misalnya dari kerajaan-kerajaan pesisir yang menyerbut ke pedalaman.
Kembali ke Kalumpang. Dulu, budak didatangkan dari Toraja dengan berjalan kaki. Waktu tempuh sekitar dua hari jalan kaki. Setelah tiba di Kalumpang, budak dibawa ke pesisir (Sampaga) dengan menggunakan rakit. Perjalanan yang pasti berbahaya sebab alur Sungai Karama yang deras penuh batu cadas.
55Ekspedisi Bumi Mandar
Selain dibawa ke Sampaga untuk dijual atau ditukar dengan benda lain, budak juga dipekerjakan di Kalumpang, khususnya oleh kaum bangsawan. Meski saya belum membaca catatan tersurat bahwa tukang pikul tandu arkeolog yang pertama kali melakukan eskavasi di Kalumpang pada tahun 1937, Dr. P. van Stein Callenfels (seperti yang terlihat di foto), adalah budak, saya menduga mereka adalah budak-budak dari Toraja. Bila dikaitkan dengan informasi bahwa orang Kalumpang dulunya berperan dalam perdagangan budak.
Ketika membayangkan orang-orang Toraja membawa orang Toraja yang menjadi budak berjalan kaki puluhan kilometer. Apakah tangan mereka diikat, sebagaimana di film-film barat? Yang jelas, menurut R. E. Sipayo, dulu budak-budak diikat tangannya saat istirahat malam. Agar mereka tak lari.
Demikian halnya saat mereka dibawa ke pesisir melalui Sungai Karama dengan menggunakan rakit. Apakah mereka duduk dengan tangan terikat di atas rakit atau menjadi tukang dayung?
Akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan bila ada napak tilas jalur perdagangan budak dari Toraja ke Kalumpang dengan berjalan kaki untuk kemudian dengan rakit dari Kalumpang ke Sampaga. Dengan kata lain, ada semacam rekonstruksi atau reka ulang.
Selain informasi tentang perbudakan, hal menarik lainnya adalah bahwa ternyata masyarakat Kalumpang tidak terlalu mengagungkan kerbau, sebagaimana tetangga mereka di Toraja dan Mamasa. Ini seakan sebuah paradoks, bahwa pemahaman selama ini, kerbau adalah hewan suci orang-orang dulu.
Itulah sebabnya tak ada pemotongan kerbau besar-besaran saat ada upacara kematian. Kerbau “keramat” di mata orang Toraja
56 Muhammad Ridwan Alimuddin
tak demikian bagi orang Kalumpang. Di rumah orang Kalumpang sepertinya juga tak ada tengkorak kerbau yang disusun di depan rumah (seperti orang Toraja dan Mamasa) atau diikat di tiang rumah (seperti orang Kajang, Bulukumba).
Informasi ini adalah bukti dalam bentuk kebudayaan bahwa memang orang Kalumpang berbeda dengan orang Mamasa atau Toraja. Penyamaan itulah yang ditolak olah Tobara di Kalumpang, R. E. Sipayo.
Dalam makalahnya tentang Kalumpang, dia menulis, “Masyarakat adat Kalumpang yang selama ini dikenal sebagai bagian dari suku Toraja berdasarkan kemiripan bahasa dan oleh artian kata Toraja yaitu “to ri aya” atau dari atas, maka sampai di sini penggolongan itu dapat dibenarkan. Tetapi apabila kata Toraja diartikan sebagai etnis berdasarkan perbedaan-perbedaan bahasa, susunan kekerabatan, adat istiadar, kesenian, teknologi dan sebagainaya, maka jelaslah bahwa masyarakat adat Kalumpang tidak identik dengan masyarakat Toraja.”
Sungai Karama, Sungai Terpajang, Sungai Peradaban
Jumlah sungai besar yang mengalir di wilayah Sulawesi Barat tercatat sekitar delapan aliran sungai. Jumlah terbesar di Kabupaten Polewali Mandar, yakni 5 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada dua sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama di Kabupaten Mamuju. Panjang kedua sungai tersebut masing-masing 150 km.
57Ekspedisi Bumi Mandar
Adapun sungai yang lain adalah Sungai Mapilli 95km, Mandar 90km, Malunda 38km, Kalukku 32km, Matakali 28km, dan Sungai Manyamba 28km. Demikian data statistik Sulawesi Barat.
Sungai-sungai tersebut signifikan perannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Mandar. Misalnya sebagai sumber air minum, pertanian, dan transportasi.
Namun tidak semua sungai di atas berperan signifikan sebagai bagian dalam pembangunan peradaban di Mandar. Ya, memang semua sungai bisa dipastikan berperan dalam sejarah Mandar, tapi besarnya berbeda-beda. Dengan kata lain, hanya beberapa yang meninggalkan bukti bersejarah bahwa sungai tersebut berperan dalam peradaban.
Misalnya Sungai Mapilli atau Sungai Maloso, dulunya adalah jalur perdagangan dari muara (sekitar Tanjung Buku dan Tanjung Mampie) ke arah hulu. Yaitu sekitar daerah aliran sungai sekitar Luyo. Tesis saya, mengapa Luyo dijadikan tempat pertemuan Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Baqbana Binaga yang memunculkan kesepakatan “Allawungan Batu di Luyo”, sebab dulunya di kawasan tersebut adalah tempat pertemuan orang gunung dengan orang pantai. Nah, Sungai Maloso adalah media yang mempertemukan mereka.
Sungai Mandar juga demikian. Setidaknya ada beberapa pusat peradaban di DAS Mandar. Dua diantaranya Alu dan Balanipa (muara). Awalnya pusat peradaban Kerajaan Balanipa ada di perbukitan (Napo dan sekitarnya). Saat mulai marak perdagangan global (khususnya kopra), pusat kerajaan dipindah ke kawasan Tinambung saat ini. Adapun Alu, salah satu kerajaan tertua di kawasan Sungai Mandar.
58 Muhammad Ridwan Alimuddin
Tapi dari sekian sungai di atas, yang paling signifikan perannya adalah Sungai Karama, Mamuju. Yang kebetulan juga sungai terpanjang di Sulawesi Barat; mulai hulu hingga muara berada di Sulawesi Barat.
Mulai muaranya (Sampaga) hingga hulunya (Karama), ada beberapa titik yang di situ, berdasar hasil penelitian atau eskavasi arkeolog, pernah ditemukan artefak-artefak pra sejarah. Untuk itulah kawasan hulu Sungai Karama ditetapkan sebagai salah satu situs pra sejarah penting di Indonesia. Status itu tak dimiliki sungai lain di Sulawesi Barat dan juga sungai-sungai lain di Pulau Sulawesi.
Untuk itu, kita jangan dengan mudahnya menyamakan Sungai Karama dengan sungai-sungai lain berkaitan dengan pembangunan PLTA atau bendungan. Misalnya membandingkan pembangunan PLTA Karama dengan DAM Bili-bili. Tidak sesederhana itu persoalannya.
Dari kurang lebih 150km panjang Sungai Karama, bagian Sungai Karama dari Desa Karama (kawasan hulu) hingga Tarailu (kawasan muara) yang panjangnya sekitar 90 km telah disurvei oleh tim Ekspedisi Save Our Kalumpang. Survei tersebut salah satu bagian penting dalam ekspedisi.
Dalam survei, selain mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video beberapa titik DAS Karama, khususnya dari Desa Karama hingga Tarailu (jembatan), tim juga mencatat data ketinggian DAS Karama dari/di atas permukaan laut. Bukan hanya Sungai Karama, tapi Sungai Bonehau.
Titik yang dianggap penting oleh tim ekspedisi dari Desa Karama hingga jembatan Tarailu adalah kawasan Tomatua atau beberapa ratus meter dari tempat pertemuan Sungai Karama
59Ekspedisi Bumi Mandar
dengan Sungai Bonehau. Sebab rencananya di tempat itulah akan dibangun dam setinggi 100 meter, yang berfungsi membendung Sungai Karama dan Sungai Bonehau.
Titik berikutnya adalah kampung-kampung dan situs-situspra sejarah/purbakala yang ada di DAS Karama dan DAS Bonehau. Baik yang di situ telah diadakan penggalian (penelitian) maupun yang di duga di situ banyak mengandung peninggalan-peninggalan pra sejarah. Misalnya situs Bukit Kamassai (di belakang Puskesmas Kalumpang) dan situs Minanga Sipakko (sekitar 4km dari ibukota Kecamatan Kalumpang ke arah barat/muara).
Data yang disajikan berikut tidaklah persis atau sangat akurat. Sebab pengukurannya menggunakan GPS ‘mobile’ dan dilakukan sambil jalan (kadang di atas perahu yang berjalan cepat). Berbeda dengan pengukuran ‘penting dan sangat serius’, menggunakan GPS berukuran lebih besar dan GPS tersebut didiamkan di titik yang akan diukur selama beberapa menit.Tapi perbedaannya hanya menyimpang beberapa meter dari ukuran sebenarnya. Tidak puluhan, tidak ratusan meter penyimpangannya.
Untuk mengurangi kesalahan atau penyimpangan besar, digunakan data dari peralatan lain sebagai pembanding. Yaitu data GPS dari kamera digital ber-GPS (Nikon Coolpix AW-100), Peta Rupabumi Kalumpang dan Bonehau skala 1:50.000 yang diterbitkan Bakosurtanal, dan peta digital Google Earth (hasil pencitraan satelit NASA).
Kalumpang dan Bonehau, Korban PLTA Karama
Bila memang terwujud ambisi membangun PLTA Karama di Sulawesi Barat, dua kecamatan yang menerima dampak negatif
60 Muhammad Ridwan Alimuddin
terbesar adalah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau. Masing-masing jumlah penduduknya Kalumpang 13.536 jiwa dan 9.257 jiwa untuk Bonehau. Ini menurut Data Statistik Kabupaten Mamuju 2009.
Kalumpang, kecamatan terluas di Kabupaten Mamuju, dengan luas wilayah 1.178,21 km persegi. Setara 22,19% dari total luas Kabupaten Mamuju. Adapun Kecamatana Bonehau, yang awalnya masuk wilayah Kecamatan Kalumpang, 11,86% atau separuh dari luas wilayah Kecamatan Kalumpang.
Meskipun bagian Kalumpang dan Bonehau yang akan tenggelam bila PLTA Karama jadi dibangun hanya sebagian kecil saja (di kawasan DAS Karama dan DAS Bonehau), tapi di kawasan tersebut sebagian besar penduduk dua kecamatan tersebut tinggal.
Kecamatan Kalumpang memiliki 13 desa dengan 66 dusun, sedangkan Kecamatana Bonehau 9 desa dengan 60 dusun. Berikut nama-nama desa di Kecamatan Kalumpang beserta jaraknya ke ibukota kecamatan (Desa Kalumpang): Karataun 18km, Siraun 39km, Karama 33km, Salumakki 49km, Polio 41km, Limbong 17km, Sandapang 39km, Kondobulo 11km, Makkaliki 33km, Batu Makkada 49km, Lasa 53km, dan Tumonga 24km.
Informasi jarak di atas tercatat di dalam buku Statistik Kabupaten Mamuju 2009. Sedangkan menurut atau versi papan jarak di ibukota Kec. Kalumpang, yang signifikan perbedaannya ke Desa Makkaliki hanya 7km, Desa Lasa sekitar 45km.
Sedangkan desa-desa dan jaraknya ke ibukota kecamatan di Bonehau: Buttuada 43 km, Salutiwo 3km, Tamalea 3km, Lumika I 3km, Mappu 5km, Hinua 15km, Kinatang 35km, dan Salueno 30km.
61Ekspedisi Bumi Mandar
Adapun jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten (kota Mamuju), untuk Kalumpang 121 km, Bonehau 97km. Bila akan ke Kalumpang lewat darat, harus melewati Bonehau, jadi jarak dari Bonehau ke Kalumpang sekitar 24km.
Kalumpang berbatasan dengan Kec. Tommo di utara, selatan dan timur Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja),dan barat berbatasan dengan Kec. Bonehau. Sedang Bonehau utara dan timur dengan Kec. Kalumpang, selatan dengan Kab. Mamas dan Barat dengan Kec. Kalukku, Papalang dan Kec. Sampaga
Sungai besar yang melintas Kalumpang S. Karama, S. Bulo, S. Tulasi, S. Lebuttang, S. Salole, S. Mabubu. Adapun di Kecamatan Bonehau adalah S. Bonehau, S. Sukinatang, S. Hinua, S. Mao, S. Salumasin, S. Takalama, S. Salundoan, S. Saruru, S. Paniki, S. Pullale, S. Salunene, S. Pasio. Hampir semua sungai tersebut menjadi penyumbang debit air Sungai Karama.
Ekspedisi Save Our Kalumpang, untuk Kecamatan Kalumpang hanya mendatangi empat desa, yaitu Desa Kalumpang (ibukota kecamatan), Limbong, Tumonga, dan Karama. Adapun Kecamatan Bonehau, semua didatangi kecuali Desa Kinatang (sebab letaknya tidak berada di jalur jalan darat, jadi tidak dilewati).
Khusus desa-desa yang berada tak jauh dari Sungai Karama dan Sungai Bonehau (yang akan menerima dampak bila air Sungai Karama dibendung), berikut data ketinggiannya dari permukaan laut: Kalumpang 90m, Limbong 130m, Tumonga lebih200, Karama, 149m. Untuk Kecamatan Bonehau rata-rata ketinggian desa-desa yang dilalui berkisar 90m sampai 110m.
Seperti yang dikemukakan di tulisan kemarin, ukuran ini tidaklah persis sebab perangkat teknologi yang digunakan adalah
62 Muhammad Ridwan Alimuddin
GPS ‘mobile’ (Garmin 60CSx) dan beberapa tempat diukur dengan cara bergerak. Meski demikian, akurasi ukurannya tidak menyimpang terlalu jauh sebab peta rupabumi yang dikeluarkan badan resmi pemetaan di Indonesia, yakni Bakosurtanal, dan citra satelit badan antariksa Amerika Serikat (NASA) dijadikan sebagai data pembanding.
Walaupun data yang didapat tidak sangat detail (presisi), namun dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa tempat-tempat tersebut kemungkinan besar menerima dampak (baca: tenggelam) bila air Sungai Karama dibendung.
Berikut hitung-hitungannya. Kawasan Tomatua, yang rencananya di situ akan dibangun dam/pembendung, ketinggiannya dari permukaan laut sekitar 40-50 meter. Berdasar rencana konstruksi dam, tingginya akan mencapai 100m. Nah, 50 + 100 m = 150m. Dengan kata lain, tinggi dam dari permukaan laut hitungannya adalah tinggi Tomatua dari permukaan laut ditambah tinggi dam.
Artinya, tempat-tempat yang ketinggiannya berada di bawah 150m akan tenggelam. Tingkat kepastian akan tenggelamnya bertingkat-tingkat, tergantung jarak dari lokasi dam. Semakin dekat, tingkat kepastiannya juga semakin tinggi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kalumpang (90m dpl), Sumuaq 65m dpl (kampung kecil di DAS Karama, letaknya tak jauh dari Situs Minanga Sipakko), situs Minanga Sipakko (96m dpl), Situs Kamassi 95m dpl.
Faktor lainnya adalah tinggi maksimal air di dalam reservoir nantinya. Di atas kan dianggap hitungan tinggi dam 150m dpl, tapi kemungkinan besar tinggi atau batas air di dalam reservoir yang
63Ekspedisi Bumi Mandar
persis di dam tidaklah persis 150m. Mungkin 130m atau 140m.
Untuk mengetahui kawasan mana saja yang akan tenggelam, bisa dilakukan dengan melakukan simulasi. Cara paling sederhana, peta rupabumi yang di situ telah ada garis-garis konturnya, ketinggian di bawah 150m ditandai atau dibuat arsip. Namun data yang ditampilkan hanyalah prakiraan saja. Perhitungan tepat bisa dihasilkan dengan software khusus. Tentu itu dimiliki oleh investor yang berniat berinvestasi dalam rencana pembangunan PLTA Karama.
Kalumpang, Pembuktian Kita Memiliki Harga Diri
Menyusuri Sungai Karama sejauh 90km bukan hanya perjalanan fisik bersama katinting. Tapi juga perjalanan imajinasi kembali ke 4.000 tahun lalu, membayangkan saat nenek moyang kita, nenek moyang orang Indonesia, bertaruh nyawa melawan arus keras ke hulu Sungai Karama.
Pikir kita, yang mengatasnamakan orang modern, mau-maunya kakek-nenek kita dengan hanya menggunakan rakit paling sederhana menyusuri sungai yang banyak buaya, melalui hutan belantara nan perawan.
Perjalanan berbahaya itu memang penuh marabahaya. Tapi itulah salah satu langkah atau mata rantai peradaban kita. Bukan hanya orang Kalumpang, orang Mandar, tapi orang Indonesia. Khususnya sebagian besar Pulau Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia (yang berdarah Austronesia).
Kawasan Sungai Karama sepertinya kawasan terakhir yang ditemukan kaum penjajah Belanda, sebab baru mulai dijelajahi
64 Muhammad Ridwan Alimuddin
pada awal tahun 1910-an. Ada hikmah peradaban Kalumpang ditemukan terakhir, sebab tradisi Austronesia yang belum “tercemar” (oleh peradaban lain, misalnya Eropa dan Timur Tengah dan Cina) terpelihara di sana.
Suatu waktu, para pejabat Hindia Belanda mendapat informasi dari orang-orang di Sampaga, ada patung bergaya kuno di muara Sungai Karama. Itu mengagetkan orang Belanda. Kekagetan mereka bertambah saat mendapat informasi bahwa di bagian hulu sungai, ada masyarakat yang masih menjaga tradisi dan memiliki banyak peninggalan pra sejarah.
Maka diadakanlah ekspedisi singkat ke sana. Sebab penumuan itu amat penting, oleh A. A. Cense, salah satu pejabat Hindia Belanda di Sulawesi Selatan, mengundang arkeolog terkenal masa itu, Dr. P. Stein Callenfels. Seorang arkeolog yang amat terkenal di kawasan Asia Tenggara. Dia juga terlibat dalam proses upaya rekonstruksi candi di Jawa, Bali dan Sumatera.
Karena usaha dan karyanya, pria bertubuh raksasa (tinggi hampir 2 meter) menerima penghargaan dari banyak negara, seperti Inggris, Thailan, Jepang, Annam, Kamboja, dan dari negaranya, Belanda. Dr. P. Stein Callenfels menyambut antusias dan dia pun ke belantara Kalumpang (saat itu belum bernama demikian) pada tahun 1933.
Singkat cerita, hasil penemuannya dipublikasikan ke dunia internasional, pada sebuah konferensi di Manila, Filipina. Dunia arkeolog gempar waktu itu, menggambarkan betapa pentingnya penemuan Dr. P. Stein Callenfels.
Penggalian dan penemuan benda-benda pra sejarah di Bukit Kamassi ternyata baru sebagian kecil. Penggalian terus dilakukan,
65Ekspedisi Bumi Mandar
salah satunya di Minanga Sipakko. Belakangan oleh ilmuwan Indonesia, di lokasi yang sama, penggalian dan penelitian semakin intensif. Tapi menurut Prof. Truman Simanjuntak, pemimpin tim arkeolog Indonesia yang melakukan penelitian terakhir di Kalumpang pada paruh pertama tahun 2000-an, “Apa yang ditemukan masih sangat sedikit dibanding apa yang dikandung Kalumpang”.
Di atas sekilas ‘setback’ tentang penemuan di Kalumpang. Kalumpang oleh dunia internasional dianggap situs pra sejarah teramat penting di Indonesia dan dunia. Ironisnya, pemimpin kita di Sulawesi Barat seakan menutup mata akan kekayaan di bumi Kalumpang. Kekayaan itu bukan emas, batubara, mangan, tapi harga diri, akar budaya, dan hakikat karakter kita.
Memang sulit menilaikannya dengan uang, tapi gampang menganalogikannya.Perandaiannya seperti ini.Si C memberi tawaran keA, “Saya kasih kamu uang 10 juta, tapi saya tampar dirimu”. Atau, si C memberi tawaran “Saya buang tulang-tulang mayat orangtuamu, nanti saya kasih uang 1 miliar”. Atau, si C menawari si A, “Okelah, saya kentuti saja mukamu nanti saya kasih 500 juta”.
Ya, si A akan kaya raya dalam sekejap. Tanpa efek fisik yang serius. Ditampar sekali, paling memar saja beberapa saat. Esoknya juga sembuh. Apalagi kalau tulang belulang orangtuanya dibuang, tak ada efek apa-apa ke fisik. Buat apa juga tulang-tulang, kan ga’ ada gunanya juga. Kentut apalagi, paling baunya tidak sampai semenit. Kena hembusan kentut pun paling tiga detik, tak sakit sedikit pun.
Jika si A menerima, pasti ada dua pendapat. Si A cerdas dan si A harga dirinya segitu saja. Ya, memang dia mendapat uang, tapi
66 Muhammad Ridwan Alimuddin
sampai dia mati, dan anak cucunya pun akan kena imbas, akan dicap sebagai orang yang teramat murah!
Si C dalam kacamata orang Mandar, sosok yang tak punya “siriq” dan “lokkoq”. Mau-maunya dia dihina seperti itu. Telah menjadi budaya kita, bila berkaitan dengan “siriq” dan “lokkoq”, banyak orang yang rela mati.
Apa yang terjadi saat ini, berkaitan rencana pembangunan PLTA Karama di kawasan Kalumpang (yang efek negatifnya berdampak ke Kalumpang dan Bonehau), memang tidak sesederhana kasus si C dan si A. Saya hanya memberi gambaran, bahwa apa yang terjadi berkaitan dengan harga diri dan karakter kita.
Pemerintah harus cerdas dalam hal ini. Tidak menyederhanakan persoalan. Kasus Bandara Tampa Padang dan Universitas Sulawesi Barat terjadi depan mata, yang hanya melibatkan lebih sedikit pihak dibanding kasus Kalumpang. Tapi masalahnya tak beres-beres.
Kira-kira bagaimana nanti kasus Kalumpang? Yang letaknya di pedalaman, menyangkut hajat hidup ribuan orang, berkaitan dengan harga diri, dan melibatkan dunia internasional. Apakah akan selesai dalam lima tahun?
Yang harus dilakukan pemerintah adalah bijaksana dalam membangun. PLTA Karama bisa saja dibangun tapi situs harus tetap terjaga. PLTA tidak usah sebuah megaproyek yang ambisius, cukuplah untuk listrik Sulawesi saja, seperti halnya Bakaru.
Atau bila masyarakat Kalumpang dan Bonehau sendiri rela ditenggelamkan bumi mereka, demi PLTA Karama, selain memberi ganti rugi, menyiapkan tempat, dan jaminan pekerjaan
67Ekspedisi Bumi Mandar
selama beberapa tahun ke korban pembangunan PLTA Karama, pemerintah atau investor harus menyiapkan dana tak terbatas untuk membiayai riset ilmiah tentang Kalumpang.
Semua tempat yang diduga ada peninggalan pra sejarah dilakukan penggalian dan penelitian. Ahli-ahli terbaik arkeolog dunia diundang. Mahasiswa yang mau skripsi, tesis, desertasi tentang Kalumpang dibiayai sepenuhnya. Untuk kemudian, hasilnya diseminarkan, dibukukan lalu di sebar ke pelosok dunia.
Bukan hanya itu, juga harus dibangun museum super lengkap tentang Kalumpang di Kalumpang. Hingga menjadi museum pra sejarah terbaik dan terlengkap di Indonesia.Jika itu yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajarlah disebut pemerintah yang bijaksana dan beradab. Jika bukan itu yang dilakukan, berarti tidak bijaksana dan tidak beradab.
72 Muhammad Ridwan Alimuddin
17
18
19
KalumpangDr. P. van Stein Callenfels (duduk di atas kursi yang ditandu) saat melakukan penelitian di Kalumpang (Koleksi
foto Tropen Museum)Baju adat masyarakat KalumpangBaju tradisional masyarakat Kalumpang pada tahun 30-an (Koleksi foto Museum Tropen Belanda)Kalvin Kalambo (ketiga dari kiri) dan M Ilham (keempat dari kiri) bersama masyarakat di situs pra sejarah
di BonehauJenis jembatan yang banyak melintasi Sungai Karama dan Sungai BonehauLembah Sungai KaramaJenis perahu katinting adalah moda transportasi utama di Sungai KaramaMasyarakat Kalumpang pada tahun 1910-an. Sumber Museum Tropen BelandaMotoris atau juru mudi perahu katinting yang melintas di riam Sungai KaramaPapan penunjuk lokasi kampung yang berada di sekitar KalumpangPenulis saat mendokumentasikan tulang belulang di salah satu goa tak jauh dari BonehauProses pembuatan tenun ikat di KalumpangRiam yang banyak terdapat di Sungai Karama adalah ancaman utama bagi perahu yang melintas di sungai
tersebutSalah satu benda purbakala yang ditemukan di salah situ pra sejarah di sekitar BonehauSalah satu lubang bekas eskavasi benda-benda pra sejarah yang banyak terdapat di sekitar KalumpangSalah satu jenis kain ikat di Kalumpang di pangkuan tokoh adat Kalumpang ResipayoSitus Minanga Sipakkovan stein dan bangsawan setempat
73
PERTAHANKAN LERE-LEREKANG
Lere-lerekang atau Lari-lariang?
Dua pekan terakhir hangat pemberitaan di harian Radar Sulbar tentang sengketa Pulau Lerelerekang (atau P. Larilariang)
antara Sulawesi Barat dengan Kalimantan Selatan. Bila di Sulawesi Barat hangat saja, di Kalimantan Selatan, panas bukan main! Ada demo segala. Pemberitaan dimulai Februari, April hingga Oktober – November ini.
Berikut judul-judul beritanya: DPRD Kalsel Siap Berjuang Untuk Pulau Lari-Larian; Kalsel Pertahankan Pulau Lari-larian; Memanas, Kalsel dan Sulbar Rebutan Pulau Lari-larian; Pemprov Disarankan Bentuk Tim Pulau Lari-Larian; Mendagri Siap Digugat, Tetapkan Pulau Lerelerekang Milik Majene; Kotabaru Merasa Dizalimi; Kotabaru Ajukan Judicial Review ke MA; Warga Kotabaru Akan Demo; Gubernur: Jangan Saling Menyalahkan Soal Lari-Larian; Denny dan Hatta Siap Gugat Mendagri; Sengketa Pulau Lari-Larian, Bupati Kotabaru Siap Lawan Mendagri; Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel Galang Kekuatan; Bupati: Telah Terjadi Kebohongan Publik; Irhami: Kemendagri Lakukan Pembohongan Publik.
Seakan-akan Kalimantan Selatan sebuah negara yang bersengketa dengan negara lain. Padahal masih saudara (se-negera), belum lagi bila melihat komposisi penduduk Kalimantan
74 Muhammad Ridwan Alimuddin
Selatan, banyak yang berasal dari Sulawesi Barat (Mandar).
Kalimantan Selatan ‘marah’ sebab dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2011, Pulau Larilariang sah sebagai milik Provinsi Sulawesi Barat. Putusan tersebut final adanya dan telah masuk ke dalam lembaran negara tahun 2011. Perjuangan berbulan-bulan Kalimantan Selatan berbuah hasil: P. Lerelerekang bukan milik mereka, tapi masuk wilayah Sulawesi Barat.
Menurut Kepala Pusat PeneranganKemendagri, Reydonnyzar Moenek, “Kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan matang dengan mempersandingkan data dan fakta antara dua daerah yang sebelumnya bersengketa, yakni Provinsi Sulbar dan Provinsi Kalimantan Selatan. Jika Kalimantan Selatan keberatan, Kemendagri membuka kesempatan lebar-lebar kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan. Pengalaman sudah empat kali kita di-yudisil review, kita menang, diperkuat oleh peradilan.”
Sengketa atas P. Larilariang berawal pada pertemuan tim Pembinaan dan pembakuan Nama-nama Pulau di Kalsel pada 9 – 11 Juli 2008 di Banjarmasin. Tim dari Pemprov Kalsel bersama Pemkab Kotabaru menyampaikan, bahwa Pulau Lari-Larian masuk dalam daftar 134 pulau yang ada di Kalsel. Namun kenyataannya, karena titik koordinatnya sama dengan nama salah satu pulau di Sulawesi Barat, yakni Pulau Lerelerekang, maka tim dari Kemendagri meminta masalah pulau tersebut ditunda.
Setelah rapat beberapa kali di Jakarta yang melibatkan pihak Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat serta Kementerian Dalam Negeri, maka keluarlah putusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun hal itu tak diterima oleh Kalimantan Selatan.
75Ekspedisi Bumi Mandar
P. Lerelerekang = P. Larilariang
Bila media di Kalimantan Selatan menggunakan nama “Larilariang”, maka di Sulawesi Barat nama pulau yang dimaksud adalah “Lerelerekang”.
Dalam tulisan ini saya juga menggunakan “Lerelerekang” sebab oleh nelayan Mandar, khususnya di Majene, lebih jamak menggunakan nama itu dibanding Larilariang.
Media di Kalimantan Selatan memuat pendapat Bupati Kotabaru, H. Irhami Ridjani, “Pulau ini disebut Larilarian yang berarti tempat pelarian masyarakat Kotabaru karena takut dikejar-kejar gerombolan.”
Pertanyaannya, “gerombolan” apa yang dimaksud? Apakah di Kalimantan Selatan ada juga pengikut Kahar Mudzakkar yang memaksakan ideologinya ke penduduk dan merampas harta milik penduduk? Apakah penduduk Kalimantan Selatan juga bermigrasi ke tempat lain karena ketakutan? Sebagaimana yang dialami penduduk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di waktu lampau?
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, ada masa yang mendorong ribuan penduduknya melakukan migrasi besar-besaran. Itu terjadi di masa pemberontakan DI/TII (tahun 1951 - 1965). Oleh penduduk setempat, para pengacau diistilahkan “gerombolan”.
Itulah sebab, ada banyak orang Bugis, Makassar dan Mandar yang bermukim di ratusan pulau-pulau kecil di Selat Makassar, termasuk Pulau Laut dan pesisir Kalimantan Selatan.
Hal tersebut adalah fakta bahwa ada gelombang migrasi dari timur (pesisir barat Pulau Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) ke
76 Muhammad Ridwan Alimuddin
barat (pulau-pulau kecil, pesisir timur Pulau Kalimantan). Bukan sebaliknya!
Jadi agak aneh bila ada pendapat yang mengatakan bahwa penduduk Kalimantan Selatan juga mengungsi, berlawanan arah dengan pengungsi dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Apalagi Pulau Lerelerekang itu hanya pulau kecil, tidak layak untuk dimukimi. Jadi untuk bermukim di sana amat sulit. Untuk singgah berlabuh saja tidak apa-apa. Tapi untuk menjadi tujuan mengungsi, bukan hal ideal.
Jika pun Kalimantan Selatan mengklaim bahwa kepemilikan Pulau Lerelerekang di masa “lari dari gerombolan” (itu pun kalau memang betul ada juga gerombolan di Kalimantan Selatan), itu masih sangat muda, 50 tahun lalu. Sedangkan bagi orang Mandar di Sulawesi Barat, mereka sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar P. Lerelerekang setidaknya abad ke-18.
Pulau Lere-lerekang Bagian Kepulauan Bala-balakang?
P. Lerelerekang terletak kurang lebih 170 km dari kota Majene. Arahnya dari Majene persis “baraq tappaq” (persis arah barat). Sebab jika ingin menuju P. Larilariang dari Majene (misalnya Luwaor), jika kompas-nya (alat magnetik penunjuk arah) terus pada angka 270 derajat (dengan sedikit penyesuaian), bisa sampai ke pulau tersebut. Terletak pada koordinat 03°30.7’ LS dan 117°27. 9’ BT (berdasar GPS tim patroli laut Polairud Sulawesi Selatan, 15 Oktober 2003).
Jarak 170 km hampir sama jarak pelayaran dari Majene
77Ekspedisi Bumi Mandar
ke Makassar. Bila berlayar dengan menggunakan kapal kayu berkecepatan rata-rata 9 knot (mil per jam), maka bisa sampai dalam waktu 9 sampai 10 jam.
Adapun jarak P. Lerelerekang ke daratan terdekat yang sah milik Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 100 km, yakni ke P. Sebuku atau Kep. Sambergelap (pulau di timur P. Laut). Itu lebih dekat dibanding daratan P. Sulawesi.
Tapi bila menjadikan P. Lumulumu (yang juga wilayah Sulawesi Barat) sebagai titik terdekat, jaraknya hanya berkisar 65 km. Jadi, dari segi geografis jarak P. Lerelerekang ke Sulawesi Barat masih lebih dekat dibanding ke Kalimantan Selatan.
Hal tersebut dengan sendirinya membantah pendapat pemberitaan media massa di Kalimantan Selatan yang mengatakan, “Kenyatannya di lapangan, Pulau Lari-larian berjarak dengan Pulau Sebuku yang merupakan ibukota kecamatan hanya sekitar 60 mil laut (110 km, red), adapun dengan Pulau Sambergelap yang masih dalam satu wilayah kecamatan sekitar 40 mil laut (75 km, red). Sedangkan jarak Pulau Lari-larian dengan wilayah daratan Sulawesi Barat sekitar 80 mil laut (150 km, red).”
Ya, memang jauh bila menjadikan darat Sulawesi sebagai patokan. Tapi karena P. Lumulumu juga adalah wilayah Sulawesi Barat, maka sah-sah saja menjadikannya patokan. Sebagaimana pihak di Kalimantan Selatan yang menjadikan P. Sebuku (yang juga pulau kecil) sebagai titik dasar, bukan daratan Pulau Kalimantan.
Adapun Kepulauan Balabalakang, yang juga wilayah Sulawesi Barat, jaraknya ke P. Lerelerekang relatif sama dengan jarak antara P. Lerelerekang dengan P. Sebuku, yakni sekitar 110 km
Meski demikian, jarak ke pulau utama bukanlah dasar utama
78 Muhammad Ridwan Alimuddin
dalam menentukan kepemilikan atas sebuah pulau. Sebagaimana pulau-pulau kecil milik Kabupaten Pangkep (Sulawesi Selatan) yang “menjorok” ke Laut Jawa, yang lebih dekat ke Jawa Timur atau Bali atau Nusa Tenggara. Tapi karena ada nilai historis, pulau-pulau kecil di pertemuan Selat Makassar dengan Laut Jawa dan Laut Flores masuk wilayah Sulawesi Selatan, bukan Jawa Timur, bukan Bali, bukan Nusa Tenggara Barat, dan bukan Nusa Tenggara Timur.
P. Lerelerekang adalah pulau kecil. Menurut informasi dari beberapa sumber dan film dokumenter yang pernah dibuat tempat saya bekerja dulu, luasnya tak seberapa, hampir seluas lapangan bola. Demikian juga informasi nelayan Majene yang sering ke sana, P. Lerelerekang memang kecil. Di sana tidak bisa dimukimi sebab luasnya tidak seberapa, tidak ada sumber air, dan terlalu jauh dari daratan utama. Yang di sana hanya tumbuhan semak khas pulau.
Pada film dokumenter tentang pemboman ikan di sekitar P. Lerelerekang yang sempat merekam suasana pulau (Oktober 2003), pulau dikelilingi pasir putih, banyak kayu yang terdampar di atas pasir, dan belukar. Tak ada tanaman keras (tinggi) apalagi bangunan. Kabarnya pernah ada lampu suar. Tapi rusak sebab ada yang mengambil aki-nya.
P. Lerelerekang terletak di atas kawasan atau bagian pinggir Paparan Sunda. Rata-rata kedalaman lautnya berkisar 40-60 meter. Nanti 40 km ke arah timur baru dalam lautnya, yaitu kedalaman 100 – 600 meter.
Sebab masuk wilayah Paparan Sunda, Anggota Tim Koordinasi soal Pulau Lari-larian dari Kotabaru, Taufik Rifani, M. Hum. berpendapat, “Secara geografi, di Selat Sulawesi yang memisahkan
79Ekspedisi Bumi Mandar
dataran Kalimantan dengan Sulawesi terdapat palung laut yang seharusnya dijadikan bukti rujukan, bahwa kedua pulau tersebut dipisahkan oleh batas alam. Di mana Pulau Kalimantan dan Pulau Lari-Larian berada pada paparan Sunda sebelah barat. Sedangkan Pulau Sulawesi berada di paparan Sahul, sebelah timur palung.”
Yang perlu dipahami oleh Taufik Rifani, penggunaan landasan kontinen dalam penentuan batas negara tidak serta merta diterapkan untuk batas provinsi. Beda kasus. Apalagi P. Lerelerekang masih terhitung wilayah Kep. Balabalakang. Jika memang menggunakan landasan kontinen, Kep. Balabalakang mestinya milik Kalimantan Timur. Tapi kenyataannya pemerintah Republik Indonesia memasukkan Kep. Balabalakang sebagai wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Salah satu dasar hukum Permendagri Kepmendagri Nomor 43/2011 adalah UU No. 26/2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa wilayah paling barat adalah gugusan Kepulauan Balabalakang. Yang mana Kepulauan Balabalakang, berbatasan dengan Kabupaten Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan).
Jadi, meskipun tidak ada keterangan rinci koordinat, tapi karena sudah menyebut bahwa bagian paling barat adalah gugusan Kepulauan Balabalakang, maka dengan sendirinya P. Lerelerekang masuk.
Memang P. Lerelerekang relatif jauh dari gugusan utama Kep. Balabalakang, sekitar 100 km (hanya 60 km dari P. Lumulumu), tapi bila berdasar pada defenisi Konvensi Hukum Laut 1982 Bab IV pasal 46 butir b, kepulauan adalah “suatu gugusan pulau-pulau,
80 Muhammad Ridwan Alimuddin
termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian.”
Nah, antara P. Lerelerekang dengan gugusan pulau-pulau di utara itu memiliki hubungan erat, baik dari segi ekonomi maupun historis. Sejak abad ke-19 nelayan-nelayan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bugis, Makassar, Mandar, dan Bajau) telah menjadikan kawasan Kep. Balabalakang hingga ratusan pulau kecil di selatan (misalnya Sabaru, Kalukalukuang, Masalima dan Masalambu) sebagai daerah penangkapan ikan (fishing ground) dan tujuan migrasi saat ada kekacauan di kampung halaman.
Faktanya jelas, mayoritas penduduk di pulau tersebut adalah orang-orang Mandar dan Bugis dan hingga saat ini nelayan-nelayan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menangkap ikan di kawasan tersebut. Pertanyaannya, apakah hal yang sama juga dilakukan penduduk asli Kalimantan Selatan (Banjar dan Dayak)?
Lalu, di atas peta yang diterbitkan Bakosurtanal dan Dihidros – AL pada tahun 1992, amat jelas (sebab ada garis perbatasan di laut) P. Larilariang (yang dimaksud adalah P. Lerelerekang) masuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab masuk wilayah Sulawesi Selatan, maka Polisi Air dan Udara (Polairud) Sulawesi Selatan menjadikan perairan P. Lerelerekang dan sekitarnya sebagai daerah patroli.
Mandar Itu Pelaut Ulung
Sebenarnya P. Lerelerekang atau P. Larilariang hanyalah
81Ekspedisi Bumi Mandar
‘halaman depan’ orang Mandar di laut. Letaknya termasuk dekat dan sepertinya pelaut Mandar bisa “menutup mata” bila mau ke sana dengan menggunakan perahu.
Orang Mandar memiliki akar kemaritiman yang kuat dan terangkai ratusan tahun lampau. Pada gilirannya, ada alasan kuat dan ilmiah bahwa semenjak dulu orang Mandar telah melaut, menangkap ikan dan memanfaatkan P. Lerelerekang.
Untuk lebih jelas, dalam tulisan ini saya akan membahas sedikit banyak tentang sejarah kemaritiman orang Mandar. A. A. Cense dan H. J. Heeren (1972), mengatakan bahwa pelaut-pelaut Sulawesi Selatan sering berlayar ke Australia Utara yang oleh orang Sulawesi Selatan dinamakan Merege.
Nelayan Mandar juga dikenal sebagai nelayan yang menghasilkan beberapa inovasi, sebagaimana ilmuwan perikanan nasional, Subani (1972:7) dalam buku yang berisi hasil-hasil penelitiannya mengenai beberapa alat tangkap di berbagai daerah di nusantara, “... daerah Sulawesi terutama Sulawesi Selatan dan Tenggara adalah termasuk darah jang paling banjak mentjiptakan bentuk2 alat penangkapan. Alat2 jang berasal dari daerah ini umunja tersebar luas diseluruh daerah perikanan terutama Indonesia bagian timur. […] Selandjutnya untuk pantjing disamping pantjing2 biasa, rawai kita kenal pula matjam pantjing seperti: pantjing uloro (line without sinkers), vertikal longline (Bone, Mandar). Untuk djaring insang kita dapati misalnja: lanra antoni, soma antoni, lanra belanak, lanra sangiri, pukat djadjela, pukat sibola dll.nja. Untuk bubu jang merupakan chiri2 chas ialah “bubu hanjut/apung” (drift fish pot) atau biasa disebut “pakadja”. Mengenai rumpon (lure) jang merupakan tjiri chas ialah adanja
82 Muhammad Ridwan Alimuddin
rumpon Mandar (rumpon chusus untuk laut dalam).”
Adapun pelaut (dari etnis) Mandar secara khusus, menurut Pelras, penulis buku The Bugis, “Sebenarnya orang Bugis bukanlah pelaut ulung seperti yang banyak dikatakan orang selama ini. Orang Bugis sebenarnya adalah pedagang. Laut dan kapal hanyalah media atau sarana yang digunakan untuk memperlancar aktivitas perdagangan mereka. Kalau mau menyebut pelaut ulung, maka yang paling tepat adalah orang Mandar.”
Horst Liebner yang mengutip pendapat Pires (1944:226-227) mengemukakan alasan mengapa orang Mandar lebih berorientasi ke laut daripada pertanian, “Salah satu di antara suku-suku Sulawesi Selatan yang mencari kehidupannya di laut adalah Suku Mandar yang mendiami pesisir pantai utara Propinsi Sulawesi Selatan [...] kampung-kampung yang dihuni oleh perantau Mandar didapatkan sepanjang pantai Sulawesi bagian barat; di Teluk Bone, bahkan di beberapa pulau di Selat Makassar dan di pantai timur Kalimantan sampai ke ujung utaranya. Oleh karena tanah daerah Mandar tidak subur, maka orang Mandar sejak dahulu berorientasi ke laut.”
Bagaimana corak dari inti kebudayaan masyarakat Mandar dapat dilihat dari segi perwatakannya. AJF Eerdmaans seorang orientalis yang menulis buku Het Landschap Balanipa, mendiskripsikan orang Mandar, “Sungguh pun demikian harus diakui bahwa di dalam keadaan-keadaan sulit ia tidak menampakkan sifat-sifat pengecut dan banyak kali menunjukkan bukti-bukti keberanian pribadinya yang mengagungkan. Di dalam peperangan acap kali ia dapat memilih titik-titik yang strategis; sejarah dapat membuktikannya seperti gerakan-gerakan jasmani, naik kuda, berenang, berlayar
83Ekspedisi Bumi Mandar
adalah termasuk hiburan sepanjang hidupnya”.
Khusus mengenai jalur-jalur pelayaran oleh orang-orang Mandar dahulu, dapat kita lihat dalam tulisan L. J. J. Caron, yaitu: De Mandarezen toch bevaren meest de route: Mandar – Singapare – Mandar – Borneo en Mandar – Singapore – Mandar – Molukken.
Dalam Memorie Leijdst, Assistant Resident van Mandar (1937 – 1940) ditemukan catatan jalur-jalur pelayaran yang ditempuh oleh pelaut-pelaut Mandar (yang berlangsung sampai saat penjajahan Belanda), bukan hanya terbatas sampai Maluku, tetapi bahkan sampai ke Papua Nugini.
Selain itu dari keterangan seorang pemuka masyarakat yang bernama Kambo, sebagaimana ditulis Baharuddin Lopa dalam desertasinya (1982), menjelaskan bahwa ia mengingat betul nenek moyangnya sekitar tahun 1850 telah naik haji dengan menggunakan perahu layar dari Mandar.
Dari catatan Caron dan Leijdst serta tulisan-tulisan lainnya, dapat diketahui bahwa jalur pelayaran utama para pelaut Mandar mengikuti garis timur-barat, yaitu Mandar – Borneo – Jawa – Sumatera – Singapura ke barat, dan sekembalinya dari Singapura mereka menempuh pula jalur pelayaran ke Ambon, Ternate, Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar, Irian dan juga ke Australia Utara untuk menangkap/membeli teripang.
Didapati juga jalur-jalur pelayaran utara – selatan, yaitu jalur utara ke pelabuhan di Sulawesi Utara (Donggala – Tolitoli ) sampai ke Philipina. Jalur ke selatan menuju ke Pulau Jawa dan terus ke pulau-pulau di NTB, NTT, dan Timor. Rute-rute tersebut tidak ditetapkan secara kaku tetapi bisa saja berubah, tergantung
84 Muhammad Ridwan Alimuddin
faktor-faktor ekonomis dan alam.
Menurut De Graaf (1949) orang Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Barat kala itu) sudah melakukan pelayaran dan berlabuh di pulau-pulau di Selat Makassar setidaknya pada tahun 1642.
Dalam buku “Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850 – 1940” karya Masyuri (peneliti LIPI) disebutkan bahwa sejak abad ke-19 nelayan-nelayan dari Sulawesi Selatan telah menjadi pemasok utama ikan asin ke Jawa. Pendapat tersebut sesuai dengan tradisi nelayan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nelayan Mandar di Sulawesi Barat telah melakukan kebiasaan menangkap ikan di perairan Kalimantan hingga Laut Jawa untuk kemudian dipasarkan dalam bentuk ikan kering. Baik untuk berlindung dari badai atau mendapat air tawar mereka singgah atau berlabuh di pulau-pulau kecil.
Beberapa hari lalu (9/11) saya bertanya kepada seorang nelayan tua dari Luwaor (Majene), setelah menangkap ikan di perairan P. Lerelerekang, ikannya dijual ke mana? Jawabnya, “Kita biasa jual ikan di Pasuruan dan Panarukan di Jawa Timur.”
Mengungsi ke Pulau yang Mereka Kenal
Ketika kampung halaman mereka mengalami kekacauan, tidak aman, banyak pembunuhan dan perampasan harta benda, para nelayan tersebut beserta tetangga mereka mengungsi ke tempat aman yang jauh dari jangkauan “gerombolan”. Yaitu pulau-pulau kecil di Selat Makassar. Maka berlangsunglah eksodus signifikan pada tahun 1951 - 1965, masa kekacauan (Pemberontakan DI/TII).
Pilihan menuju pulau kecil amat masuk akal. Tidak
85Ekspedisi Bumi Mandar
menghanyut-hanyut saja lalu kebetulan tiba di pulau. Mungkin dulu mereka berkata kepada kerabat atau tetangganya, “Kampung halaman sudah tidak aman lebih baik kita pindah ke Pulau X. Saya sering menangkap ikan di sana. Pulaunya lumayan, ada air tawar, juga luas dan yang lebih penting aman.”
Itulah sebab, hampir semua pulau-pulau kecil yang ada di Selat Makassar hingga Laut Jawa utara Laut Bali dihuni oleh orang Bugis, Makassar, dan Mandar. Hingga kini, orang Mandar sering ke sana untuk bertemu dengan kerabatnya, demikian juga sebaliknya.
Setidaknya saya telah mengunjungi selusin pulau di kawasan tersebut, semuanya ada orang Bugis dan Mandar. Misalnya di P. Pagarungan dan sekitarnya (Kep. Kangean, masuk wilayah Jawa Timur), dan P. Masalembu (Jawa Timur). Khusus di Masalembu, ada Kampung Luwaor (Luwaor nama kampun di Majene). Demikian juga pulau lain. Bila spesifik orang Mandar apa yang banyak di pulau-pulau, jawabannya adalah orang-orang Majene, khususnya Rangas, Luwaor, dan Pamboang.
“Mallekker lapurang”
Dalam kebudayaan Mandar ada istilah “mallekker lapurang”, yaitu pindah ke tempat lain dengan membawa serta “isi dapur”, yaitu keluarga (bila sudah menikah) dan peralatan rumah tangga, serta banyak kejadian, telah menjual harta milik di daerah asal (misalnya tanah) sebagai ongkos perjalanan atau modal kerja di daerah tujuan.
Ada beberapa motivasi “mallekker lapurang”, diantaranya mencari kehidupan yang lebih baik dan menghindari kekacauan (merasa tidak aman di masa perang atau pemberontakan). Di daerah yang dituju, mereka bisa berdagang, bisa juga bekerja
86 Muhammad Ridwan Alimuddin
sebagai nelayan.
Bila “mallekker lapurang” bisa dianggap pindah total, maka “sumombal” lain lagi. Selain berarti berlayar, kata “sumombal” bisa juga dimaknai pergi berburu ikan di tempat relatif jauh. Ada yang tetap tinggal di atas perahu ada juga yang berlabuh di sekitar pulau kecil atau gosong.
Bila pulaunya besar, mereka biasa membangun bangunan sederhana di daratan. Meski bermukim lama tapi tetap akan kembali ke kampung halaman sebab keluarga ada di sana. Contoh kasus ini adalah nelayan Sulawesi yang menangkap ikan di Australia Utara (Marege atau Darwin sekarang ini).
“Mallarung”
Ada juga istilah lain dalam tradisi penangkapan ikan nelayan Mandar, yaitu “mallarung”. Secara umum, istilah mallaqdhu atau mallarung digunakan untuk menyebut nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing ulur. Diistilahkan demikian karena mereka harus meneggelamkan atau menurunkan pancing mereka ke dalam laut.
Hal yang sama juga dilakukan oleh nelayan yang beroperasi di perairan karang. Pada musim barat nelayan Mandar menuju ke pulau-pulau yang berada di Selat Makassar, khususnya di perairan yang dangkal (dekat Pulau Kalimantan) untuk menangkap ikan-ikan karang atau baukaqmea (‘ikan merah’).
Ikan karang tersebut kemudian mereka awetkan dengan garam. Ikan yang dihasilkan tersebut diistilahkan “bombangan”. “Bombangan” itulah oleh mereka dibawa ke Jawa (Surabaya, Gresik, Panarukan, Pasuruang dan daerah sekitarnya) dan ke
87Ekspedisi Bumi Mandar
Kalimantan (Balikpapan, Batulicin, dll.).
Tradisi “mallarung” oleh nelayan Mandar telah lama berlangsung lama, kurang lebih 200 tahun. Itulah sebab beberapa orientalis menyebutkan orang-orang Mandar sebagai pelaut ulung, sebab mereka telah berlayar jauh baik untuk berdagang maupun untuk menangkap ikan. Selat Makassar masih terhitung dekat, mereka malah sampai Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Flores dan utara Australia.
Hak Ulayat Laut
Saya belum pernah membaca lontar (atau terjemahannya) yang mengatakan bahwa kawasan Mandar juga mencakup P. Lerelerekang. Sebagaimana istilah “Dari Binanga Karaeng di selatan hingga Lalombi di utara; dari Paku hingga Suremana”.
Kata lain, dulunya P. Lerelerekang tidaklah menjadi wilayah kekuasaan dari tujuh kerajaan di pantai “Pitu Ba’bana Binanga”. Yang ada kemungkinan untuk memilikinya ialah Kerajaan Balanipa, Kerajaan Banggae, dan Kerajaan Sendana. Tapi saya pikir bangsawan-bangsawan dari kerajaan tersebut tidak pernah mengklaim bahwa P. Larilariang adalah politiknya.
Namun, sekelompok orang dari wilayah tersebut (Balanipa, Banggae, dan Sendana) telah memanfaatkan P. Larilariang dan perairan disekitarnya. Mereka adalah para nelayan “pallarung”! Nelayan Mandar secara tidak sadar telah “memasang patok” di tempat tersebut bahwa P. Lerelerekang adalah bagian dari Mandar.
Simbol pemasangan patok bukan dalam arti betul-betul memasang tanda atau prasasti atau batas wilayah tersebut melainkan aktivitas mereka yang melakukan eksploitasi atau
88 Muhammad Ridwan Alimuddin
pengelolaan sumberdaya di wilayah tersebut.
Lalu mungkin muncul pertanyaan, “Apakah orang asli Kalimantan tidak memanfaatkan P. Lerelerekang”? Sepertinya tidak pernah, sebab penduduk asli Kalimantan adalah suku, Banjar dan Dayak, yang berorientasi daratan (hutan). Jadi untuk menjadi penjelajah lautan amat kecil.
Hal inilah yang harus diketahui pihak Kalimantan Selatan, bahwa tidak ada bukti ilmiah nenek moyang mereka (yang bukan orang Bugis, Makassar, Mandar, dan Bajau) pernah memanfaatkan P. Lerelerekang. Kalau nenek orang Majene hingga anak cucunya sekarang ini masih melakukan aktivitas menangkap ikan di sekitar P. Lerelerekang.
Tidak usah jauh-jauh hingga P. Lerelerekang, pulau-pulau terdekat saja, di bagian timur dan selatan P. Laut (pulau terbesar di timur Kalimantan Selatan). Siapa saja yang tinggal di situ. Siapa yang mengelolanya dari dulu. Jawabnya orang-orang dari Sulawesi Selatan. Kalau bukan Mandar pasti Bugis atau Makassar.
Hak Ulayat laut
Walau tak ada catatan tertulis, misalnya di dalam lontar, yang mengatakan P. Lerelerekang adalah wilayah salah satu kerajaan di Mandar, wilayah perairan di sekitar pulau tersebut mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk hak ulayat di laut.
Alasannya, sebab nelayan Mandar telah lama menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah penangkapan ikan. Hanya saja nelayan Mandar (dan juga nelayan Bugis, Makassar dan Bajau) memandang laut sebagai milik umum “common property”, jadi tak bisa diklaim sebagai milik. Kecuali ada alat tangkapnya terpasang
89Ekspedisi Bumi Mandar
di situ, semisal rumpon (roppong).
Hak penggunaan wilayah pada perikanan (territorial use rights in fisheries) telah ada sejak berabad-abad. Hak-hak ini sudah ada untuk sumberdaya yang menetap. Di samping itu, hak-hak ini telah ada pada sejumlah usaha perikanan laut dalam masyarakat tradisional dan juga sedang diperjuangkan melalui ketentuan hukum. Sebab dianggap sebagai hukum adat.
Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstitutory law), yang meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hak ulayat merupakan bagian dari konsepsi hukum adat tentang hak-hak atas tanah dan air.
Hukum adat dirumuskan sebagai konsepsi yang “komunalistik religius”, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Meskipun hanya tanah yang disebut secara eksplisit, tetapi hal itu tidak berarti perairan bukan bagian dari konsepsi hukum adat sebab pada kenyataannya di berbagai masyarakat hukum adat, perairan juga merupakan bagian dari sistem hak ulayat.
Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, “sea tenure”, Sudo (1983) mengatakan bahwa istilah “sea tenure” mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut.
Akamichi (1991) mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan
90 Muhammad Ridwan Alimuddin
(property rights) mempunyai konotasi sebagai memiliki (to own), memasuki (to access), dan memanfaatkan (to use). Baik konotasi memiliki, memasuki maupun memanfaatkan tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan (fishing ground), tetapi juga berdasar pada teknik-teknik penangkapan, peralatan yang digunakan (teknologi) atau bahkan sumberdaya yang ditangkap dan dikumpulkan.
Jadi yang dimaksud dengan hak ulayat laut adalah seperangkat aturan atau praktik pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya Perangkat aturan atau hak ulayat laut tersebut menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi sumberdaya yang diperbolehkan yang ada di suatu wilayah laut.
Apakah pengelolaan perairan sekitar P. Lerelerekang adalah salah satu bentuk hak ulayat laut? Untuk menjawab itu harus ada penelitian. Yang jelas ada kemungkinan untuk itu sebab memang ada pemanfaatan dalam waktu lama lingkungan perairan di tempat tersebut oleh nelayan Suku Mandar
Pulau Lere-lerekang dalam Bingkai Otoda
Sengketa perbatasan atau “kepemilikan” atas suatu wilayah banyak muncul di era otonomi daerah. Sebelumnya, semenjak Indonesia merdeka hingga berakhirnya rezim Orde Baru, perebutan wilayah antar ‘saudara’ jarang terdengar. Berbeda di masa reformasi ini, sering terjadi sengketa, baik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, dan antar provinsi.
Saya beri tanda kutip (“…”) di kata kepemilikan sebab ada
91Ekspedisi Bumi Mandar
kesalahpahaman di banyak pihak. Mereka menganggap wilayah mereka adalah milik, akan tetapi dalam undang-undang sebatas hak administratif, untuk mengelola saja.
Yang agak rumit pengukurannya adalah batas di laut. Secara teori, wilayah administratif atau hak untuk mengelola kabupaten berjarak 4 mil laut (sekitar 7,4 km) dari surut terendah ke arah laut dan provinsi 12 mil laut (22,4 km). Di luar itu pengelolaannya di tangan pemerintah pusat.
Bila dua atau lebih provinsi yang ‘berhadapan’ di laut, jika jarak antar keduanya sekitar 50 km atau lebih tidak ada masalah. Atau kalau kurang, misalnya 30 km saja, jarak itu tinggal dibagi dua (masing-masing 15 km).
Yang agak rumit bila dua daerah di perbatasannya ada banyak pulau, misalnya Sulawesi Barat (Kep. Balabalakang) dengan Kalimantan Timur. Di daerah perbatasan harus ditentukan terlebih dahulu “titik dasar” (TD) pengukuran. Untuk Indonesia, ada 92 pulau terluar yang menjadi TD.
Sebab berkaitan dengan kedaulatan negara, peran TD amat penting, walau itu hanya seonggok batu karang di atas permukaan laut. Beda kasus dengan provinsi. TD tidak serta merta meluaskan wilayah geografis. Ada hitung-hitungannya tersendiri.
Sebagai contoh Sulawesi Barat. Sebab Kep. Balabalakang masuk wilayah administratif, karena jaraknya dengan pulau utama (P. Sulawesi) cukup jauh (sekitar 90 km atau 48 mil laut), maka ada “wilayah kosong” sebab kurang dari 24 mil. Bagiang “kosong” tersebut mungkin adalah kewenangan pusat, apalagi di bagian tersebut ada Alur Laut Kepulauan Indonesia (kapal perang asing hanya bisa lewat di situ).
92 Muhammad Ridwan Alimuddin
Dalam konfigurasi gugusan Kep. Balabalakang yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Barat, ada dua pulau letaknya relatif jauh, P. Lumulumu dan P. Lerelerekang. Yang jaraknya melewati batas kewenangan provinsi (12 mil laut).
Bila Sulawesi Barat adalah sebuah negara, pulau-pulau terluarnya bisa menjadi TD. Satu TD dihubungkan dengan TD yang lain. Untuk menentukannya ada aturan khusus, diantaranya garis lurus yang menghubungkan tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali bila tiga persen dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut maka dapat digunakan batas maksimum 125 mil laut; tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut; rasio antar luas wilayah perairan dengan daratan minimal harus memiliki luas perairan yang sama besar atau maksimal hanya sembilan kali dari luas wilayah daratannya; dan lain-lain.
Jadi perkiraan saya (sebab yang berhak menentukan adalah pemerintah lewat Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut dan Badan Koordinasi Survei Nasional) garis imajiner batas laut Sulawesi Barat di Kep. Balabalakang berbentuk mata panah yang mengarah ke bawah (selatan).
Yang menjadi sengketa adalah P. Lerelerekang. Diperebutkan sebab ada kemungkinan ada deposit minyak dan gas di bawahnya. Pertanyaannya, apakah deposit tersebut persis di bawah pulau? Kemungkinan itu bisa ya bisa tidak.
Jika tidak, mengapa pulau tersebut diperebutkan? Alasannya adalah sebab P. Lerelerekang bisa menjadi TD bagi Kalimantan Selatan untuk memperluas wilayah perairannya. Sebab nantinya
93Ekspedisi Bumi Mandar
akan ada garis lurus yang ditarik dari salah satu titik di pesisir Kalimantan Selatan, misalnya Karang Grogol (pulau terluar yang masuk wilayah Kalimantan Selatan, terletak di utara dekat P. Balabalakang), menuju P. Lerelerekang, lalu ditarik lagi ke pulau paling selatan Kep. Laurot. Garis tersebut akan menjadi wilayah administratif Kalimantan Selatan di laut.
Nah di perairan tersebut besar kemungkinan ada titik yang akan dijadikan tempat pemboran minyak. Jadi bukan pulaunya yang langsung dibor. Hal yang sama juga berlaku bagi Sulawesi Barat. Tinggal ditentukan TD-nya, setelah berkoordinasi dengan Dihidros, Bakosurtanal, dan Depdagri.
Apa yang Harus Dilakukan?
Sebab pemerintah, lewat Kementerian Dalam Negeri, telah menetapkan P. Lerelerekang atau P. Larilariang sebagai wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat (dalam hal ini Kabupaten Majene), maka Pemprov Sulawesi Barat bersama Pemkab Majene harus menindaklanjuti bahwa mereka serius mengurus pulau kecil tersebut.
Untuk jangka pendek, yang bisa dilakukan Pemprov Sulawesi Barat bersama Pemkab Majene adalah melakukan riset lapangan atas pulau tersebut. Riset yang mencakup letak koordinat pulau (membawa serta GPS ke sana), mengukur luasnya, sumberdaya apa saja yang ada di sana baik di atas pulau maupun sekitarnya, dan memasang patok permanen bahwa wilayah tersebut adalah wilayah wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Aksi simbolis juga bisa dilakukan, Pemprov Sulawesi Barat bersama Pemkab Majene melakukan pelayaran atau kunjungan ke P. Lerelerekang. Bisa oleh gubernur atau bupati langsung, bisa
94 Muhammad Ridwan Alimuddin
juga bawahannya yang ditunjuk. Sebab lokasinya jauh, harus ada persiapan matang untuk perencanaannya.
Setelah ada riset dan kunjungan di sana, Pemprov Sulawesi Barat bersama Pemkab Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, baik kepada rakyat Sulawesi Barat maupun kepada masyarakat Indonesia. Sosialisasi bisa dilakukan dalam bentuk seminar yang menghadirkan pembicara yang berkaitan dengan pengelolaan P. Lerelerekang.
Seminar juga bisa bertujuan meminta masukan dari masyarakat atau pihak lain terhadap Pemkab Majene akan bentuk ideal pengelolaan P. Lerelerekang dan sekitarnya. Apakah sebagai daerah tambang lepas pantai atau dalam bentuk lain, misalnya situs budaya kemaritiman Mandar. Bahwa dulunya nenek moyang orang Mandar sering menangkap ikan di kawasan tersebut.
Berlayar ke Garis Depan Sulawesi Barat
Dua hari ini terjadi hal bersejarah bagi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Majene, dalam diplomasi geopolitiknya. Kabupaten Majene menunjukkan keseriusannya dalam hal mengurus wilayahnnya. Dan, walau sedikit terlambat, melakukan langkah signifikan dalam “perang urat syaraf” dengan “lawannya”, yakni Provinsi Kalimantan Selatan.
Selasa, 29 November 2011, Bupati Majene, Kalma Katta, melepas rombongan tim observasi yang akan menuju Pulau Lerelerekang (atau P. Larilariang) di dermaga Pelabuhan Majene. Acara berlangsung sekitar jam 10.30 pagi.
Tim terdiri dari beberapa unsur, yaitu staf dari Kantor Pemkab Majene, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (syahbandar), Dinas
95Ekspedisi Bumi Mandar
Pertambangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, humas, peneliti, dan jurnalis. Saya belum mencatat siapa saja mereka. Yang jelas, bersama awak kapal (sekitar 7 orang), total jiwa di atas KM Irama Indah sekitar 50 orang.
Suara Bupati Majene nyaris tak terdengar saat memberi kata sambutan di upacara kecil-kecilan di atas dermaga, jadi saya tak bisa menyimpulkan apa yang beliau sampaikan. Tapi tentu berkaitan dengan apa yang akan kami lakukan. Setidaknya hati-hati dalam perjalanan dan melalukan apa yang telah diputuskan dalam rapat yang dilakukan Pemkab Majene berkaitan dengan Pulau Lerelerekang.
***
Jarak kota Majene dengan P. Lerelerekang sekitar 163 km. Saat berangkat jam 11 siang dari Majene, KM Irama Indah tiba sekitar jam 11 malam. Jauh memang. Tapi jarak jauh itu tak berarti P. Lerelerekang bukan wilayah Majene.
Kami tiba di perairan sekitar P. Lerelerekang menjelang tengah malam. Gelap. Tak ada rembulan yang membantu daya pandang. Dalam perjalanan, saya lebih banyak tidur. Alasannya, esok, saat tiba pasti banyak kegiatan. Jadi harus siapkan fisik. Nanti sekitar tujuh mil lagi jarak ke pulau (berdasar GPS) saya bangun untuk kemudian bergabung dengan awak kapal dan anggota tim lain di ruang kemudi dan haluan kapal.
Sudah banyak orang yang kumpul di sana. Penasaran dan ingin segera melihat seperti apa itu P. Lerelerekang. Ada tiga awak kapal bertugas pas di ujung haluan perahu. Mereka memegang senter, mengawasi haluan kapal. Sesekali ‘menyenter’ ke dalam laut, mengecek apa dangkal atau tidak.
96 Muhammad Ridwan Alimuddin
Kemudi perahu langsung ditangani H. Bachtiar, nakhoda kapal yang juga sebagai juragan (pemilik kapal). Sebab navigasi perahu berada di daerah berbahaya (dekat pulau, banyak karang). Beda di laut lepas, kemudi perahu dilakukan bergantian antar kru kapal, khususnya jurumudi. Di dalam ruang kemudi H. Bachtiar didampingi beberapa orang, khususnya Pak Harun. Menuntun arah kapal berdasar koordinat di GPS.
Samar-samar dari kejauhan, tampak pendaran cahaya di atas horizon. Sumber cahaya tak kelihatan, sebab berada di balik horizon. Bahasa Mandarnya “pandaraq”. “Pandaraq” salah satu bagian penting dalam navigasi. Sebab bisa menjadi dasar di mana posisi perahu.
Biasanya “pandaraq” bersumber dari cahaya perkotaan atau pemukiman penduduk. Jika memang demikian, koq “pandaraq” ini amat terang? Koq letaknya di selatan? Apakah itu “pandaraq” kota di Jawa? Ah tidak mungkin, jarak ke P. Jawa juga puluhan mil. Saya pun bertanya ke awak kapal, jawabnya, “Itu pandaraq dari kapal-kapal pursin”.
Yang dimaksud adalah armada penangkap ikan yang menggunakan jaring yang disebut purse seine atau “gae” dalam bahasa Mandar. Memang, nelayan purse seine, khususnya dari Jawa, sangat banyak menggunakan lampu di atas kapalnya. Dan lampunya amat terang benderang. Ikan-ikan yang tertarik pada cahaya sepertinya terhisap ke sana. Dan daerah penangkapan mereka (fishing ground) adalah perairan di mana bertemu tiga perairan: Laut Flores, Selat Makassar dan Laut Jawa, tepatnya di daerah tenggara P. Kalimantan.
97Ekspedisi Bumi Mandar
“Lagi dua mil”, ucap pak Harun. Artinya semakin dekat. Sesekali saya mengecek GPS punyaku. Informasinya relatif sama. Tapi namanya juga alat, tak boleh juga percaya betul sebab ada hal-hal tertentu yang bisa membedakan informasi di alat dengan realitas. Saya dan pak Harun meng-input data koordinat ke GPS akan lokasi P. Lerelerekang berdasar informasi pihak lain (saya dari data GPS petugas patroli kelautan Polairud Sulsel).
Dengan kata lain, tidak jelas dimana posisi GPS saat “mark” di GPS ditekan. Apakah di tengah pulau, di pinggir pulau, atau di sekitar pulau (mungkin kapal tidak berlabuh). Jadi, sebagai pedoman saat akan mendekat tidak boleh terlalu mengandalkan GPS. Harus visual langsung. Lagian GPS tak menginformasikan sampai radius berapa kawasan dangkal di sekeliling pulau. Jadi harus tetap dicek kondisi perairan.
“Hati-hati, sudah ada “bayang””, teriak salah satu kru yang bertugas mengecek kondisi perairan. Mesin dibuat netral. Memang, samar-samar batu karang mulai nampak saat cahaya senter diarahkan ke dalam laut. Kami makin penasaran di mana posisi P. Lerelerekang. Jika terang, pasti kelihatan.
Semakin menuju ke arah haluan kapal (mendekati koordinat yang dituju berdasar GPS), KM Irama Indah makin hati-hati. Kecepatan kapal tak laju lagi. Asal jalan. Mata orang-orang di atas haluan semakin awas. Seakan berlomba menjadi orang pertama yang melihat (menemukan) P. Lerelerekang.
“Itu pulaunya,” teriak salah seorang di haluan. Ya, telah ada bayangan yang menunjukkan bahwa itu pulau. Seperti awan gelap di atas horizon.
98 Muhammad Ridwan Alimuddin
Sebab sudah kelihatan pulaunya dan perairan telah dangkal, diputuskan untuk menurunkan sauh (jangkar). Saat kami tiba, kondisi perairan tidak tenang tapi tidak juga buruk. Ada keinginan dari nakhoda untuk memutar agar bisa berlindung dari angin. Tapi tak dijalani juga pilihan tersebut sebab tidak ada informasi sejauh mana kawasan dangkal di sekitar pulau. Jadi, perahu diputuskan berlabuh.
Perasaan lega sebab telah berada dekat pulau. Nanti esok pagi mendekat untuk kemudian mendarat dengan menggunakan perahu karet milik Syahbandar Majene. Saya pun kembali bobo setelah men-set kamera bawah air. Tidak tunggu esok agar tidak buru-buru memasangnya. Bahaya jika ada salah-salah saat dipasang, kameranya bisa-bisa rusak terkena air laut. Memang tujuan utama saya ke pulau mengetahui kondisi di sekitar pulau. Untuk bagian atas pulau bisa sekilas saja sebab pulaunya kecil. Keliling dan transek sudah mencukupi sebab masih observasi.
Sesaat Sebelum Mendarat, Pistol Disiapkan
KM Irama Indah kapal transportasi yang berasal dari Soreang, Majene. Biasanya kapal ini menempuh rute Majene ke pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan. Yang mana di pulau-pulau tersebut banyak tinggal orang Mandar.
Ukuran kapal hampir 50 meter. Didesain sebagai kapal penumpang yang bisa memuat barang banyak. Ada beberapa ruang atau bagian di kapal ini. Pertama adalah haluan. Haluan berbentuk segitiga. Lebih enak duduk di haluan bila tak hujan. Setelah itu ruang kemudi. Ukurannya kecil, ndak bisa muat orang banyak. Hanya bisa sekitar lima orang. Di dalam ruang kemudi
99Ekspedisi Bumi Mandar
ada poster Salim S. Mengga, K. H. Syahabuddin, dan ulama dari Kalimantan Selatan. Apakah kebetulan ada dua figur ulama dari Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan?
Juga ada lafas doa-doa bertuliskan arab di dinding. Di balik kemudi ada kompas atau pedoman. Tak ada peta laut, juga tak ada alat komunikasi radio. Dari aspek keselamatan berlayar, KM Irama Indah tak layak. Saat ditanya mengapa tak ada radio komunikasi, jawab H. Bachtiar, “Yang ada rusak. Dan sekarang sudah ada hp yang bisa membantu komunikasi”. Ya, memang ada hp, tapi jangkauan hp tidak sampai setelah 10 mil meninggalkan daratan.
Di sisi kiri-kanan ruang kemudi ada lorong kecil untuk menuju ruang utama. Ruang utama untuk penumpang. Ada dua tingkat. Hanya bisa duduk di dalam. Tak bisa berdiri sebab tingginya, khususnya yang bagian atas, hanya semeter. Jadi bila bergerak ke arah lain harus jalan jongkok atau tiarap. Kepala sering terantuk sebab tak biasa.
Di bagian bawah juga begitu, tapi di sisi kiri-kanan ada lorong menuju ruang belakang. Ruang belakang adalah dapur. Juga da toilet di situ. Adapun buritan ada teras. Bisa untuk mancing.
Bagian paling bawah adalah ruang untuk barang. Sedangkan bagian atas atau atap ruang ada tempat lapang. Biasanya juga sebagai tempat barang.
***
Sekitar jam 7 pagi, 30 November 2011, anggota tim yang diutus Pemkab Majene, bersiap-siap untuk mendarat di P. Lerelerekang. Ternyata KM Irama Indah bergeser sekitar 3 km dari posisi awalnya, tempat berlabuh semalam. Itu informasi di GPS.
100 Muhammad Ridwan Alimuddin
Sebab pulau telah terlihat jelas, untuk menuju ke sana dan menentukan tempat berlabuhnya jauh lebih aman dibanding semalam. Perahu mendekat ke pulau, atau berpindah sekitar 3 km dari posisi.
Itulah canggihnya GPS. Ukuran sebesar hp lawas tersebut bisa memberi informasi amat akurat. Memang kelihatannya kecil, tapi di baliknya ada 24 satelit super canggih yang memasok informasi ‘real time’ dalam kecepatan tinggi, sepersekian detik. Satelit terletak puluhan kilometer di luar angkasa. Milik Amerika Serikat.
Saat mendekat, ada rasa tegang di atas kapal. Samar-samar di pulau ada benda yang nampak seperti perahu. Saya yang duduk di atas dek (atap) sempat melihat polisi yang mengkode temannya untuk menyiapkan pistol. Temannya yang duduk di buritan segera menuju haluan, memberi atasannya pistol.
Bukan hanya pistol yang siap sedia dari kemarin. Juga senapan serbu khas polisi. Setidaknya ada dua unit yang saya lihat. Juga ada pistol colt di samping anggota TNI yang ikut.
Dari beberapa kali saya mendatangi pulau-pulau kecil di perbatasan, baru kali ini saya bersama serta dengan aparat keamanan lengkap dengan senjatanya. Uniknya lagi, ini pulau yang berbatasan antar provinsi saja. Bukan negara dengan negara. Jadi, senjata untuk apa? Siapa juga mau ditembak. Bila pun ada pihak yang menjaga P. Lerelerekang tidak mungkin juga baku tembak.
Tapi saya juga memberi dalih atas pertanyaan saya sendiri tersebut. Senjata itu alat diplomasi. Setidaknya untuk membuat keder jika berhadapan lawan. Tidak selalu harus ditembakkan. Dan, membuat awak atau anggota tim observasi lebih pede dan merasa aman.
101Ekspedisi Bumi Mandar
Tapi kami kecele, ternyata bukan perahu, tapi kayu dan pondasi suar.
Setelah berlabuh, kami pun sarapan. Hanya mie siram. Perahu karet telah diturunkan. Tim pertama turun, sekitar 8 orang. Ada pak Asisten II, pak Harun, dan teman jurnalis. Semuanya mengenakan pelampung. Saya dan teman-teman jurnalis serta awak kapal yang lain duduk-duduk di haluan, memperhatikan perahu karet yang menuju pulau. Menunggu giliran diangkut.
Tampaknya ada banyak karang di sekeliling pulau. Perahu karet kesulitan untuk langsung mendekat ke pulau. Mereke menuju arah lain dulu agar bisa sampai ke garis pantai berpasir putih. Kami yang berada di kapal merasa sok pintar, “Koq perahu ke sana, ndak langsung ke situ.” Ada yang menimpal, “Kayaknya mereka mau keliling-keliling dulu.” Yang lain menanggapi, “Seharusnya jangan dulu, baiknya semen, pasir, kerikil dan plank diturunkan dulu agar pekerjaan utama ke pulau bisa segera selesai.”
Selain menggunakan perahu karet, ada juga yang pake sampan (lepa-lepa) ke sana. Ukuran sampannya besar, khas kapal. Tidak seperti sampan nelayan yang kecil, mungil, rampin, ringan. Ada tiga orang yang memilih pakai sampan. Salah satunya sepertinya jarang naik sampan. Susah menyeimbangkan diri. Bila pakai sampan nelayan, sudah pasti jatuh kalau begitu gayanya. Untung pakai sampan bongsor dan besar, jadi tak terbalik.
Ada juga yang memilih berenang. Namanya Wiwin, keturunan Mandar – Bajau Filipina. Menurut percakapan yang saya dengar di atas kapal, Wiwin itu jago menyelam dan menembak ikan. Tak ada takutnya, walau malam. Dan dia pintar bahasa Tagalog, sebab ada banyak kerabatnya di sana, termasuk di Filipina Selatan.
102 Muhammad Ridwan Alimuddin
Saya juga mau berenang ke pulau, tak terlalu jauh. Tapi karena harus membawa serta alat-alat observasi (kamera bawah air, GPS, kompas, buku catatan, alat snorkling, dll) harus pakai sekoci. Dan saya telah siap dari tadi. Tampaknya saya yang paling banyak bawaannya. Agar duluan berangkat, dari haluan saya pindah ke samping kapal, yang ada pintu untuk naik turun sekoci.
Tidak lama kemudian, perahu karet datang, merapat ke sisi KM Irama Indah. Sebelum kami turun, terlebih dulu diturunkan dua zak semen, dua karung kerikil, dua jerigen air tawar, dan sekop. Saat sekoci telah sarat, sekoci putar haluan, kedua kalinya menuju P. Lerelerekang.
“Bismillah”, ucap dalam hati saat pertama kali menginjak P. Lerelerekang. Walau secara fisik P. Lerelerekang tak amat spesial, tak ada yang indah kecuali pasir putihnya, bagi saya yang telah menginjak puluhan pulau-pulau kecil, pulau kecil yang ini terasa spesial.
Kondisi Lingkungan
Setelah mengamankan alat-alat, observasi pertama mulai saya lakukan, yaitu mengukur keliling pulau. Amat gampang, bawa saja GPS sambil berjalan. Agar mudah analasis datanya, setiap 50 langkah saya membuat ‘mark’ (tanda) di dalam GPS.
Saya mulau berjalan ke arah utara, dimulai sekitar pukul 07.18. Agar akurat luasnya, saya berjalan pas di pinggir, pertemuan laut dengan pasir. Tapi untuk betul akurat tidak bisa sebab kemungkinan air masih akan surut. Nanti tinggal lihat kondisi surut, kira-kira berapa lebarnya. Jadi dalam analisis data tinggal diperkirakan berapa penambahan luas.
103Ekspedisi Bumi Mandar
Berjalan ke utara, memutar ke timur lalu ke selatan (di selatan ada sisa pondasi lampu suar, yang tadi dikira kapal), kembali ke barat. Akhirnya saya tiba kembali ke titik awal, sekitar pukul 07.30. Biasanya, kalau berjalan 15 menit di jalur datar, itu sama dengan 1 km.
Dari hasil keliling pulau, dapat diketahui bentuk pulau bila dilihat dari atas. Juga dapat diketahui luasnya. Setelah data di GPS dimasukkan ke komputer (menggunakan perangkat lunak Garmin Bascamp dan Google Earth), keliling pulau ukurannya sekitar 1 km sedangkan luasnya kurang lebih 64.000 meter persegi atau 6,4 hektar. Adapun jarak terjauh timur-barat sekitar 371 m sedang utara-selatan 341 m.
Untuk memanfaatkan waktu, setelah berkeliling pulau, observasi bawah air mulai saya lakukan. Peralatan yang saya gunakan alat selam dasar (masker, snorkel, baju selam, fin) dan kamera bawah air Nikon D300s dengan “housing” Ikelite. Awalnya, waktu di dermaga Majene, banyak yang bilang “Siap-siap mancing ya?”. Pikirnya boks biru yang saya bawa tempat ikan. Saya tersenyum saja dengar pertanyaan itu. Atau jawab “Kamera”.
Areal komunitas terumbu karang di sekeliling P. Lerelerekang relatif luas. Bila diukur dari terumbu karang di tempat berlabuh sampai garis pantai pulau, jaraknya bisa sampai 300 meter. Dengan asumsi sekeliling pulau ada karangnya dengan jarak atau lebarnya sekitar 300 meter, setidaknya komunitas terumbu karang P. Lerelerekang sekitar 60 hektar. Ini adalah hitung-hitungan kasar, tapi jika melihat sekeliling pulau, angka tersebut amat memungkinkan.
Saya melakukan pengamatan bawah air sekitar 50 – 100 meter dari garis pantai. Dari sisi barat pulau, menuju ke selatan
104 Muhammad Ridwan Alimuddin
lalu naik ke utara (sisi timur pulau). Tidak sampai ke utara pulau sebab kondisi perairan telah mulau surut saat saya berada di sisi timur.
Terumbu karang di Pulau Lerelerekang didominasi terumbu karang Acropora. Cirinya mudah dikenal, berbentuk tanduk rusa. Terumbu karang ini amat rapuh jika terinjak atau terlindas lunas perahu atau dikena jangkar. Acropora mendominasi di sisi barat pulau. Banyak yang masih sehat tapi lebih banyak yang rusak.
Kerusakan Acropora di kawasan tersebut sepertinya disebabkan surut yang terlalu ekstrim atau lama terpapar sinar matahari. Itu ditandai dengan bentuk fisik yang masih bagus, tapi sejatinya sudah rusak sebab tak ada lagi zooxanthellae di situ. Lebih banyak berlumut, khususnya di “pucuk-pucuk” karang. Apakah surut ekstrim karena pengaruh pemanasan global? Harus riset lebih lanjut.
Di beberapa titik karang hancur karena pengaruh fisik, seperti terinjak. Tapi pada umumnya masih luas yang tidak mengalami kehancuran. Ada banyak bulu babi di beberapa tempat. Banyak bulu babi juga salah satu paramater terjadi ketidakseimbangan. Tapi saya belum menemukan bulu seribu atau Acanchaster Plancii, predator terumbu karang.
Semakin ke utara, semakin hancur. Substrat atau pecahan-pecahan Acropora ada di mana-mana membentuk kawasan yang luas. Bagian yang tidak hancur diselimuti lumut. Kontras dengan kawasan yang saya lalui sebelumnya di barat pulau. Dekat ke pondasi mercusuar Acropora atau softcoral hanya ada satu dua. Mungkin karang hancur di kawasan ini sebab dulunya kapal untuk membangun mercusuar lalu lalang di situ.
105Ekspedisi Bumi Mandar
Adapun kawasan tenggara pulau tak lagi dengan pecahan-pecahan karang, tapi telah berpasir. Ada kemungkinan bagian ini dulunya adalah bagian pulau. Tapi karena mengalami abrasi, sekarang berada di bawah permukaan laut. Bergerak ke sisi timur pulau, juga ada perbedaan dengan sisi yang lain. Acropora tidak lagi mendominasi, hanya ada di beberapa titik. Di kawasan ini saya tidak menemukan kelompok bulu babi. Dan yang menarik, ada beberapa koloni anemon beserta ikan badut (sebab hidup bersama anemon, ikan badut lebih dikenal dengan nama ikan anemon).
Apakah perairan di sekitar P. Lerelerekang adalah lokasi pemboman ikan? Ya! Sebab selain berdasar informasi dari nelayan pembom, melihat kerusakan terumbu karangnya, khususnya yang berada di kedalam dua meter lebih, itu disebabkan oleh pemboman dan pembiusan ikan.
Banyak karang masif dan karang bercabang ukuran besar (yang mendominasi di kedalaman ini) rusak karena bom.
Kesimpulannya, bila dikira-kira tingkat kerusakan terumbu karang di sekeliling P. Lerelerekang, perkiraan saya 80-90%. Yang masih sehat berada di kawasan dangkal, yang tak ‘layak’ dibom (sebab terlalu dangkal dan jarang gerombolan ikan konsumsi ada di situ). Masalahnya, terumbu karang tersebut banyak yang rusak gara-gara terpapar panas matahari dalam waktu lama dan dilalui kapal yang mendekat ke pulau.
Jadikan Laboratorium Alam atau DPL!
Lalu bagaimana dengan ekosistem di atas permukaan, di P. Lerelerekang. Dalam ilmu kelautan, ekosistem P. Lerelerekang dimasukkan ke dalam ekosistem pesisir yang tidak tergenangi
106 Muhammad Ridwan Alimuddin
air (uninundated coast), tepatnya formasi Percarpae. Disebut demikian, sebab vegetasi pionir di tempat tersebut didominasi oleh tumbuhan Impomea pescarpae atau kankung laut. Juga ada rumput di beberapa tempat. Di bagian dalam pulau terdapat tumbuhan rimbun, seperti pandan laut yang nampak seperti pohon kelapa dari kejauhan.
Pulau Lerelerekang adalah pulau tak berpenghuni. Sebenarnya pulau tersebut bisa dihuni oleh manusia, sebab bagian tengah pulau ada kolam (galian di atas pasir) penampungan air hujan. Airnya tawar tapi agak payau. Hanya saja, sebab lokasinya terisolasi (jauh dari pulau lain), maka tak dihuni. Yang biasa ke sini hanyalah nelayan-nelayan yang berlindung dari badai atau sekedar ‘menanti’. Baik dari Bugis – Makassar, Madura, terkhusus ‘posasiq’ Mandar.
Di beberapa tempat terdapat jejak-jejak bahwa manusia sering ke sini, misalnya kolam di tengah pulau. Ada struktur bambu yang berbentuk gawang, seperti bekas memasang tenda.
Sekeliling pulai bisa ditemukan bekas tempat telur penyu. Memang kondisi fisik P. Lerelerekang baik bagi penyu menyimpan telur-telurnya. Selain tak ada cahaya yang mengganggu, juga tidak ada manusia yang tinggal di sini. Tapi itu tak berarti betul-betul aman, sebab para pemburu penyu pasti sering ke pulau ini untuk mencari penyu atau telurnya.
***
Semua anggota tim naik ke P. Lerelerekang. Mereka melakukan pengamatan atas kondisi pulau dan melakukan transek sederhana. Masuk ke bagian tengah pulau dan menentukan akan dipasang di mana plank.
107Ekspedisi Bumi Mandar
Pukul 07.30 dan 08.30 wita dilakukan pemasangan plank di sisi barat dan timur pulau. Plank bertuliskan: PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PULAU LEREKLEREKAN PROVINSI SULAWESI BARAT // THE ISLAND OF LEREKLEREKA THE GOVERMENT OF MAJENE DISTRIC PROVINCE OFWEST SULAWESI //PERMENDAGRI NO. 43 TAHUN 2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI KAB. MAJENE TANGGAL 07 OKTOBER 2011.
Plank atau papan nama tersebut terbuat dari papan berukuran sekitar 1 x 1,5 meter, dipasang pada kedua balok kayu yang tingginya sekitar 2,5 meter. Baik papan maupun balok tiangnya dicat putih. Bagian atas ada atap berbentuk genteng berwarna merah maron, terbuat dari logam. Agar kuat, bagian bawah plank dipondasi.
Terlepas dua plank tersebut berumur pendek (mungkin karena dirusak manusia, sebab papannya bisa digunakan, atau rusak alami), pemasangan tersebut adalah langkah penting. Bahwa pemerintah Kabupaten Majene terbukti melakukan perhatian terhadap P. Lerelerekang. Mudah-mudahan di masa mendatang ada langkah lebih berarti terhadap pulau tersebut dibanding hanya datang untuk memasang plank.
***
Setelah plank dipasang, anggota tim observasi menikmati P. Lerelerekang. Tentu mereka mengabadikan diri di depan plank, baik dengan kamera hp maupun kamera foto. Ada juga yang menuliskan nama instansinya di pondasi plank.
Menikmati P. Lerelerekang beragam macam, ada yang mandi-mandi juga ada yang berburu ikan karang dengan menggunakan panah laut (harpoon). Yang tak mandi-mandi, memilih bersantai di darat sambil menunggu makan siang.
108 Muhammad Ridwan Alimuddin
Dipilih untuk makan siang di pulau, sebab hasil mancing ikan karang di atas kapal cukup banyak. Lumayan buat acara bakar-bakar ikan. Agar lebih nikmat, dipasang tenda biru (betul warna biru terpalnya). Adapun nasi dan lauk lain, yakni “bau piapi” telah disiapkan di atas kapal. Jadi tinggal dibawa ke pulau.
‘Bau piapi’ dan nasi dimasak oleh awak KM Irama Indah di dapur kapal. Awak KM Irama Indah ramah-ramah awaknya. Nakhoda sekaligus juragannya, H. Bachtiar, sering saya lihat shalat di atas geladak kapal. Ada juga seorang tua walau tengah malam, selalu terjaga menjaga kapal.
Akhirnya nasi yang ditunggu-tunggu tiba di pulau, di bawa dengan perahu karet. Kebetulan saya ikut ke kapal saat perahu karet ke sana untuk ambil makanan. Jadi saat balik, saya pegang tutup panci ‘bau piapi’. Agar tak ‘tiseo-seoq’ oleh gelombang.
Tiba di pulau, anggota tim observasi menikmati hidangan makan siang. Walau sederhana, tapi karena dinikmati di pulau dan ikan yang dibakar hasil tangkapan anggota tim, menikmatinya amat spesial. Begitula, sisi lain kebahagiaan para peng-observasi, selain suksesnya menunaikan tugas memasang plank.
Akhirnya, menjelang sore, KM Irama Indah balik ke Majene. Sebenarnya bisa berangkat siang, tapi karena air surut yang menyebabkan ‘ulang-alik’ perahu kareta menjemput anggota tim agak lambat dan cuaca buruk, keberangkatan ditunda sampai sore. Rencananya setelah maghrib agar tiba siang di Majene, tapi karena, mungkin, banyak yang mabuk dan sudah rindu pulang, sang nakhoda KM Irama Indah, H. Bachtiar, “menarik lonceng agar mesin dibunyikan”. Yang mabuk merasa lega. Walau perjalanan lagi 10 jam lebih.
109Ekspedisi Bumi Mandar
Hampir semua terlelap, kecuali awak kapal. Perjalanan ke Majene terasa lebih cepat. Mungkin karena didorong ombak dan di haluan di pasang layar. Menurut Pak Harun, setelah melihat GPS, setidaknya kecepatan bertambah 1 knot, dari rata-rata 9 menjadi 10 knot. Betul juga, kami tiba sekitar jam 3 malam, lebih cepat hampir dua jam dari pada perjalanan ke pulau.
Alhamdulillah, tugas ‘nasionalisme’ anggota tim observasi yang dibentuk pemkab Majene berhasil menyelesaikan tugas mulianya. Itu berkat kerjasama dengan semua pihak yang berlayar ke P. Lerelerekang.
***
Jika ada yang bertanya, idealnya P. Lerelerekang diapakan? Menurut saya, pulau tersebut harus dijaga. Bukan dari “rampasan” daerah lain, tapi dari kerusakan. Jika terumbu karangnya terus hancur, lambat laun pulau akan tenggelam. Dan secara otomatis, titik dasar (TD) batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat akan hilang. Pada gilirannya, akan kehilangan wilayah puluhan kilometer persegi. Itu kerugian luar biasa.
Jadi apa langkah konkrit? Ya, bila disekitar pulau menjadi tambang minyak dan gas, di atas kertas akan menguntungkan. Tapi siapakah yang lebih banyak mengambil keuntungan? Apakah rakyat Sulawesi Barat atau para investor?
Lalu, apakah pengeboran akan berlangsung esok, pekan depan atau bulan depan? Bisa dipastikan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jika pun ada proses observasi hingga eksplorasi, itu akan terjadi 5 – 10 tahun mendatang.
Usul saya, baiknya dalam waktu dekat ini Pulau Lerelerekang dicanangkan sebagai laboratorium Universitas Sulawesi Barat atau
110 Muhammad Ridwan Alimuddin
Daerah Perlindungan Laut (DPL). Bukan hanya dipasangi plank.
Dari segi ilmu pengetahuan, P. Lerelerekang cukup penting sebab dia pulau kecil yang agak terisolasi. Kita belum tahu mungkin ada spesies endemik di sana. Memang Sulawesi Barat memiliki beberapa pulau kecil, misalnya di Teluk Polewali atau di Kepulauan Balabalakang, tapi P. Lerelerekang memiliki nilai tersendiri, baik keterisolasiannya maupun dari segi geopolitik.
Menjadi laboratorium untuk perguruan tinggi di Sulawesi Barat, sebagaimana hutan yang dikelola dan dijadikan tempat praktek mahasiswa, misalnya Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur.
Dan, jika mahasiswa pecinta alam di Sulawesi Barat lebih kreatif dan tak lupa akar budayanya, jangan hanya mendaki gunung. Tapi kalau betul pemberani, belajarlah melayarkan sandeq, berlayarlah ke P. Lerelerekang, tinggal di sana 1-2 malam, dan pelajari bawah lautnya.
Jangan mau kalah sama mahasiswa Universitas Hasanuddin, yang mereka bukan orang Mandar, tapi dengan niat tulus belajar melayarkan sandeq Mandar untuk kemudian mereka layarkan ke Australia, yang tiba beberapa pekan lalu.
Kesimpulannya, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Majene serta rakyatnya, harus melakukan langkah konkrit lebih lanjut dalam pengelolaan P. Lerelerekang yang berkelanjutan. Memang luasnya 6,4 hektar, tapi kalau pulau tersebut tenggelam, puluhan kilometer persegi (sama dengan ribuan hektar) akan lepas dari provinsi yang insya Allah ‘malaqbiq’ ini. Wallahualam.
111Ekspedisi Bumi Mandar
(Jika Betul) Pulau Lere-lerekang Lepas, Siapa Salah?
Beberapa hari belakangan, pembicaraan mengenai pulau yang ada di Sulawesi Barat, terkhusus P. Lerelerekang, setahu saya, baru pertama kali hangat dibicarakan. Parameternya, barusan ada pertemuan besar yang melibatkan banyak pihak, mulai pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Majene hingga “stakeholder” lainnya. Entah siapa lagi yang hadir. Saya tidak hadir acara, soalnya baru tahu bila ada acara tersebut saat redaksi Radar Sulbar mengirim berita untuk saya “posting” masuk www.radar-sulbar.com.
Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Majene, Ahad malam, 20 Mei 2012. Unik, sekaligus ironi, sebab pertemuan seperti itu baru dilaksanakan setelah ada kabar bahwa Pulau Lerelerekang, yang menurut Permendagri Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, berhasil (?) direbut Provinsi Kalimantan Selatan. Situs resmi MA memuat hasil putusan tersebut. Meski demikian, Pemerintah Sulawesi Barat, lewat gubernur Anwar Adnan Shaleh, membantahnya.
Idealnya pertemuan semacam itu, dan yang lebih ilmiah, mengundang lebih banyak pihak (khususnya ahli toponim dari Jakarta serta para antropolog kemaritiman) dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Jangan baru kemarin dong. Laksana lawan sudah kasih masuk bola ke gawang, kita baru sadar bahwa sekarang kita main bola. Saat bola masuk, kita sibuk mencari kesalahan, mengatakan bahwa ada “offside”, dan lain sebagainya.
Sebagai pemerhati masalah kelautan, termasuk pulau-pulau kecil, saya melihat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terlalu ‘pede’ (percaya diri) untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan
112 Muhammad Ridwan Alimuddin
Pulau Lerelerekang. Sebab berjuang sendiri, sepertinya mereka berjuang dengan gaya khas pemerintah juga. Yakni hanya mengandalkan bukti-bukti peraturan pemerintah, bukti formalitas saja. Nyaris tak terdengar ada gerakan ilmiah (misalnya seminar), tak ada usaha upaya ‘meng-counter’ pembentukan opini dari Kalimantan Selatan bahwa pulau itu adalah pulau mereka.
Sebab terlalu ‘pede’, masyarakat umum tak dilibatkan secara maksimal. Dalam hal ini, pendapat dari kalangan pelaut tua dan ilmuwan. Memang pernah ada acara yang mengundang pelaut Majene, Pua Nawar, dari Rangas. Tapi itu sebatas pertemuan di Mamuju. Yang dengar pendapat Pua Nawar hanya pejabat-pejabat sendiri. Juga tak pernah terdengar kabar antropolog kemaritiman Mandar, semisal Horst Liebner, dimintai pendapat ilmiahnya.
Idealnya, mereka harus membentuk tim yang berasal dari kalangan perguruan tinggi (kan sudah ada Universitas Sulawesi Barat, koq tidak difungsikan?). Tugas mereka, cari bukti-bukti ilmiah. Bila perlu, adakan penelitian arsip mulai dari Makassar, Jakarta, hingga Belanda. Biaya tak seberapa bila dibanding kerugian jikalau pulau tersebut lepas.
Hasil penelitian kemudian diseminarkan di beberapa tempat, mulai dari Majene, Mamuju, Makassar, hingga Jakarta. Tapi apakah itu dilakukan? Entahlah.
Jika pulau tersebut lepas, siapa yang salah? Membandingkan kegetolan memperjuangan memiliki Pulau Lere-lerekang, kayaknya Provinsi Kalimantan Selatan lebih mantap. Kabarnya, mereka siapkan dana miliaran rupiah untuk memperjuangkan tujuannya. Setidaknya bila membaca di media massa online. Mulai masyarakat akar rumput sampai pemerintah provinsi hingga
113Ekspedisi Bumi Mandar
keturunan Kalimantan Selatan yang berada di pemerintahan pusat turun berjuang. Kita di Sulawesi Barat bagaimana?
Tanggal 25 Maret 2012 atau tiga bulan lalu, lewat BBM (Blackberry Messenger), saya diskusi dengan praktisi hukum Sulawesi Barat, Aco Hatta, yang aktif berjuang mempertahankan Pulau Lerelerekang lewat lembaga yang dia terlibat di dalamnya (saya lupa namanya).
Berikut transkripsi pesan dari saya: “Bbrp bulan lalu sdh diingatkan pemkab/pemprov ttg seriusx hal ini. Tp lambat gerakanx. Padahal Denny indrayana getol di jakarta. Disini qt adem2 saja. Untung ada gerakan perlindungan pulau yg kita’ koordinir. Kalo ndak pake dasar historis bisa2 qt kalah. Sy liat, dasar2 yg dipake pak gub mmg kuat, tp rata2 baru. Kalau kalsel, sampe zaman belanda. Kalo pake pengalaman sipadan ligitan, kalsel bisa menang. Usul sy pribadi, pemprov harus adakan seminar nasional ttg pulau lere2kang. Undang ahli2 toponim, survei, bakosurtanal dr jakarta. Baru dibuat film dokumenter yg isix wwncarai nelayan2 tua yg sering ke sana. Bahan2 itu dilempar ke media. Agar publik tau. Karna publik kurang paham soal pulau terluar kita. Hasyim Djalal (bapakx dubes RI di Amerika) enak itu diajak diskusi. Kalau beliau diundang, pasti Jakarta serius lihat sulbar. Blm lg ahli2 lain. Seminar tdk seberapa biaya dibanding datangkan banyak mentri. Tp hasilx lebih signifikan.”
Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Sebab katanya masih ada langkah hukum lain, ya itu tadi, meski sangat terlambat, pemerintah harus mengerahkan segala sumberdaya yang ada. Langkah hukum dibarengi dan didukung gerakan di luar itu (riset ilmiah lalu diseminarkan dengan bertaraf nasional). Dengan kata lain, dengan dana tak terbatas, adakanlah usulan sebagaimana yang saya kemukakan di atas.
114 Muhammad Ridwan Alimuddin
Jika tak ada aksi-aksi ‘luar biasa’, jangan harap Pulau Lerelerekang tetap ada di pangkuan Provinsi Sulawesi Barat.
Kepulauan Bala-balakang
Langkah lebih cerdas dilakukan oleh Bupati Mamuju, Suhardi Duka. Meski jauh sebelumnya sudah ada tanda-tanda Kepulauan Balabalakang diupayakan oleh Provinsi Kalimantan Timur agar masuk wilayahnya, tapi hal tersebut agak ngawur. Ada banyak bukti Kepulauan Balabalakang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju.
Walau demikian, bupati Mamuju tidak berpangku tangan. Sebagaimana yang diberitakan Radar Sulbar (22/5), Pemerintah Kabupaten Mamuju akan melakukan segala upaya untuk menutup celah keinginan Provinsi Kalimantan Timur. Kepulauan tersebut harus dipertahankan.
Tindakan seperti itu amat cemerlang. Jangan seperti kasus Pulau Lerelerekang, menyadari bukti hukum agak lemah, gerakannya juga lemah. Harus sebaliknya, getol dan agresif mempertahankan yang disertai dengan penguatan bukti-bukti.
Dalam tulisan ini, saya akan mengutip tulisan saya yang juga dimuat Radar Sulbar beberapa tahu lalu. Juga menjadi salah satu esei saya di dalam buku “Mandar Nol Kilometer” (Ombak, 2011), halaman 260. Saya pikir masih “update”, prihal Kepulauan Balabalakang.
Tak ada banyak yang tahu bahwa Provinsi Sulawesi Barat memiliki kepulauan. Pemahaman di banyak khalayak, Sulawesi Barat (bisa dibaca: Mandar) itu dari Paku hingga Suremana, hanya selatan – utara, di Pulau Sulawesi. Kalau timur – barat apa?
115Ekspedisi Bumi Mandar
Saya belum tahu “kampung” apa yang akan dijadikan sebagai patokan di pegunungan (timur), di pertemuan antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, dengan batas antara Sulawesi Barat dengan Kalimantan Timur. Yang jelas, kalau di barat, salah satu pulau di Kepulauan Balabalakang-lah yang dijadikan patokan. Mudah-mudahan ada “kalinda’da’” kontemporer tentang itu.
Perlu juga diketahui, jarak timur – barat lebih jauh daripada selatan – utara (secara garis lurus), yaitu kurang lebih 300 km untuk “lebar” Sulawesi Barat (timur – barat) dan 260 km “tinggi” Sulawesi Barat (selatan – utara). Jadi luas kan?
Untuk sebagian komunitas masyarakat di Sulawesi Barat dan pemerintah, Kepulauan Balabalakang adalah periperal atau pinggiran. Ya, secara geografis memang berada di pinggir. Kalau berada di darat, mungkin masuk kategori pedalaman.
Berikut gambaran kasar jarak ke Kepulauan Balabalakang dari kota Mamuju, dengan Kota Balikpapan sebagai perbandingan. Dari Balikpapan, bagian terdekat atau barat kepulauan berjarak 100 km dan bagian terjauh atau timur kepulauan berjarak 187 km. Sedangkan dari kota Mamuju, dari bagian terdekat atau timur kepulauan berjarak 100 km dan terjauh atau barat kepulauan sekitar 200 km.
Karena Kepulauan Balabalakang berada di laut dan tak ada akses reguler kesanalah yang membuat banyak orang “emoh” melirik Kepulauan Balabalakang.
Tapi beda dengan orang di pesisir Teluk Mandar, khususnya di Kabupaten Majene, tepatnya dari Rangas, Luwaor, hingga Malunda. Banyak dari mereka yang bermigrasi ke sana. Demikian juga nelayan-nelayan Mandar dari kampung lain, biasa berlabuh
116 Muhammad Ridwan Alimuddin
di beberapa pulau di Kepulan Balabalakang. Biasanya mereka mengambil air minum, menjual hasil tangkapan, dan berlindung dari badai.
Jadi, meskipun kepulauan tersebut masuk wilayah administrasi Kabupaten Mamuju, tapi secara kultural, dipengaruhi banyak oleh budaya dari masyarakat yang bermukim di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.
Paling tidak ada selusin pulau di Kepulauan Balabalakang, yaitu Ambo (tertulis di peta laut: Balabalagang), Kabaladua, Seturian, Pina’at, Seloang, Melambir, Lamuda’an, Pongpong, Samataha, Sangai, Ambungi, dan Salissingang. Sebagian besar berpenduduk, misalnya di Pulau Ambo yang cukup dikenal di kalangan nelayan Mandar.
Berada di periperal, bukan berarti masyarakat di Kepulauan Balabalakang “kampungan” dan ketinggalan. Kehidupan mereka tak jauh beda dengan masyarakat pesisir di Sulawesi Barat. Rumah panggung, ada yang haji, ada elekton, ada VCD player, ada banyak parabola yang sudah digital, kapal motor berukuran sedang, dan kapal kecil yang juga bermesin. Mungkin kalau pulau luas, juga ada mobil (setidaknya saya tidak melihat motor waktu saya ke sana pada awal tahun 2004).
Karena lingkungan penduduk adalah laut, maka sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan. Umumnya menangkap ikan-ikan laut dangkal (ikan karang), misalnya sunu atau kerapu, biji nangka, ekor kuning, dan lain sebagainya. Mereka juga menangkap teripang.
Lalu ke mana mereka memasarkan hasil tangkapan? Kalau saya penduduk di sana, jelas saya memilih memasarkan hasil
117Ekspedisi Bumi Mandar
tangkapan di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Mengapa? Kan di sana harga lebih mahal dan jarak lebih dekat. Kalau ke Mamuju, mungkin karena pertimbangan tertentu baru dipasarkan di sana. Jadi, DKP Kabupaten Mamuju dan DKP Provinsi Sulawesi Barat jangan heran atau marah-marah bila nelayan lebih banyak membawa hasil ke Kalimantan Timur daripada ke Sulawesi Barat. Saya hanya bisa menyimpulkan, birokrat di Sulawesi Barat yang seharusnya mengurusi kelautan dan perikanan tidak memahami lapangan kerja mereka!
Wajar, wajar, wajar, penduduk di Kepulauan Balabalakang merasa dianaktirikan. Fasilitas publik yang seharusnya disediakan pemerintah sangat tidak memadai, khususnya pendidikan. Perhatian pun demikian, baik dalam khazanah politik, kebudayaan, dan ekonomi. Saya tidak tahu, apakah bupati Mamuju saat ini sudah pernah ke sana atau belum. Bupati-bupati yang dulu bagaimana yah?
Selain penambahan dan perbaikan sarana-prasarana fisik dan SDM yang bekerja di layanan publik, idealnya pemerintah, lewat perguruan tinggi, mengkaji secara ilmiah kehidupan sosial di Kepulauan Balabalakang. Hasil dari kajian dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembangunan yang tepat di kepulauan tersebut. Dengan kata lain, memberi bantuan tidak hanya disimbolkan dengan anggaran yang banyak, tapi haruslah tepat. Pepatahnya, “Memberi pancing, bukan ikan”.
Geografisnya yang berada di lingkungan laut, jauh dari pulau induk, dan kebiasaan masyarakat tentu tidak sama dengan masyarakat di daratan (pulau besar). Misalnya, jika membangun fasilitas sekolah, tentu komposisi semen dengan pasir tidak sama
118 Muhammad Ridwan Alimuddin
dengan bangunan di darat. Tentu ada pengaruh faktor lingkungan. Demikian juga ketika merekrut guru, petugas kesehatan, dan politik. Mau pakai orang darat, efeknya bisa ditebak: malas masuk kerja atau sama sekali tak pernah ke sana, sebagaimana yang terjadi selama ini. Kalau memang ada SDM yang memenuhi dari Kepulauan Balabalakang, mengapa tidak?
Standar SDM pun tidak adil jika harus disejajarkan dengan generasi yang menimba ilmu di darat, yang dilimpahi fasilitas. Singkat kata, SDM dari pulau harus ada perhatian khusus, tapi tidak berarti KKN.
Dalam pembangunan perikanan pun, pemerintah jangan hanya mengangankan mendapat banyak retribusi dari nelayan dari Kepulauan Balabalakang. Usul saya, pahamilah dulu kehidupan bahari masyarakat di sana. Kalau langsung membuat cetak biru pembangunan kelautan dan perikanan di Kepulauan Balabalakang tanpa ada kajian mendalam, sama saja bohong. Tak percaya? Ayo, ke Kepulauan Balabalakang!
Sebab “Database” Kita Payah
Sebenarnya sederhana saja sehingga Provinsi Sulawesi Barat dan atau Kabupaten Majene keteteran menghadapi kasus Pulau Lerelerekang. “Database” tentang kekayaan yang dimiliki sangat menyedihkan. Salah satunya adalah koleksi peta.
Awal-awal kasus Pulau Lerelerekang muncul ke permukaan, saya datang ke kantor pemerintah (tidak usah saya sebut) yang berkaitan kasus ini, saya (pura-pura) tanya apakah mereka punya peta yang memperlihatkan posisi Pulau Lerelerekang? Ternyata
119Ekspedisi Bumi Mandar
tidak ada. Lalu saya keluarkan peta koleksi saya. Pejabat setempat kaget, koq saya punya? Dapat dari mana? Tak jauh berbeda dengan lembaga setingkat diatasnya. Lewat telepon, salah satu pejabat meminta saya membantu mencarikan data-data tentang Lerelerekang.
Di atas adalah gambaran betapa birokrasi kita belum memiliki kesadaran akan pentingnya arsip. Arsip bisa bersifat apa saja. Bukan hanya dokumen lembaran negara, tapi juga peta, tulisan ilmiah, foto dan lain sebagainya. Dan kadang, media-media itu bisa sangat membantu.
Tanpa bermaksud sombong, saya memiliki koleksi semua peta pesisir Sulawesi Barat (dan sebagian pedalaman) dengan skala detail jauh lebih lengkap daripada apa yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan dan gabungan koleksi empat kabupaten berpantai. Ini ironi, sebab saya hanya seorang individu, beda dengan kantor pemerintahan yang merupakan instansi besar. Memiliki SDM dan anggaran amat banyak. Padahal, untuk memiliki koleksi itu, sama dengan uang SPPD pejabat eselon II Sulawesi Barat kalau ada tugas ke Jakarta 2-3 hari.
Mengapa peta penting? Dengan memiliki peta, suatu wilayah gampang dikuasai, baik secara teritorial maupun dalam pemahaman terhadap sebuah wilayah. Itulah sebab, sebagaimana yang kita lihat di film-film bajak laut, peta adalah benda yang selalu diperebutkan. Contoh, seri terakhir film kolosal Pirates of Caribian.
Waktu zaman perang pun, peta benda yang digolongkan sebagai dokumen sangat rahasia. Tak mengherankan, langkah pertama yang dilakukan negara penjajah (atau negara/pihak lain
120 Muhammad Ridwan Alimuddin
yang berencana menguasai suatu wilayah) adalah memetakan tempat yang ingin dikuasainya. Bisa dengan metode resmi (riset), fotografi udara, juga bisa dengan intelijen (mencuri peta lawan atau mengumpulkan data-data penting).
Belanda, Inggris dan Amerika Serikat (yang kemudian tergabung menjadi “sekutu” melawan Jepang) adalah negara yang paling rajin memetakan Nusantara pada tahun 1930 – 1940an. Itu sebab, peta yang mereka hasilkan amat detail. Saya pernah melihat peta Majene 1:250.000 yang dicetak militer Amerika pada tahun 40-an, isinya sangat detail. Sampai nama-nama kampung. Wajar, negara penjajah dengan mudah menguasai tempat kita.
Pengalaman saya pribadi, peta amat berguna dalam sebuah kajian. Perkiraan saya, dari peta, bisa dihasilkan 20-30% isi sebuah penelitian. Sebab darinya kita bisa membayangkan kondisi geografis suatu tempat, membandingkannya dengan wilayah tetangganya. Dengan kata lain, memudahkan analisis.
Peta digital “Google Earth” yang muncul tahun 2000-an amat mendukung. Meskipun tak ada nama-nama kampung, tapi citranya yang persis seperti layaknya melihatnya dari angkasa, amat membantu. Beberapa titik sangat detail sehingga rumah dan perahu pun bisa dihitung. Demikian juga menghitung jarak dan luas. Bisa dilakukan dalam hitungan detik dengan amat detail.
Mudah-mudahan saja pegawai-pegawai di kantor pemerintahan di provinsi maupun kabupaten di Sulawesi Barat pernah membuak “Goole Earth” untuk selanjutnya memperlihatkan ke bos-nya.
Kembali ke peta kertas. Untuk kawasan Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Barat, skala yang rinci masih sebatas 1:50.000.
121Ekspedisi Bumi Mandar
Di Jawa sudah ada yang 1:25.000. Ukuran fisik satu lembar peta 1:50.000 sekitar 75cm x 65cm. Merupakan jenis Peta Rupa Bumi, untuk membedakannya dengan Peta Lingkungan Laut yang mengedepankan detail kedalaman laut, sedang topografi di darat tidak lengkap.
Lalu apa kaitan konkrit antara peta dengan Pulau Lerelerekang? Pertama, dengan memiliki peta wilayah, itu simbol awal bahwa ada kesadaran geografis akan wilayah. Kedua, setelah adanya peta, idealnya apa yang ada di dalam peta (khususnya wilayah yang dimiliki) dianalisis satu-satu. Misal, apa potensi ekonominya dan apakah sudah kuat dasar hukumnya (khususnya bagian di perbatasan dengan daerah lain).
Tak salah bila ada kalimat, bila pemerintah provinsi dan atau kabupaten tak ada data tentang wilayahnya, logikanya dia tidak punya wilayah itu. Padahal dari segi hukum itu termasuk wilayahnya. Artinya, pemerintah tidak sadar dia memiliki wilayah tersebut.
Payahnya lagi, bukan hanya tak sadar memiliki sebuah pulau; sadar pun kalau pulau itu miliknya, pulau tersebut tak diurus. Sebagaimana pulau-pulau kecil di depan pelupuk mata. Jadi, tidak beres memang!
Sebenarnya ada kelemahan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene yang bisa menjadi celah hukum yang bisa digunakan lawan di meja hijau. Tapi tak etis bila saya kemukakan di sini. Modal saya sederhanya saja, aturan-aturan hukum dan selembar peta.
Kesimpulannya, agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, sekaligus bisa menjadi hikmah, pemerintah di daerah kita ini
122 Muhammad Ridwan Alimuddin
harus getol mengoleksi peta penting, data-data, dokumen-dokumen untuk kemudian mengarsipkannya dengan baik. Tidak hanya sebatas mengoleksi, “database” tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam analisis-analisis untuk membangun dan mempertahankan keutuhan daerah ini.
Mengapa Membicarakan Lere-lerekang?
Pulau Lerelerekang luasnya sekitar enam hektar saja. Lapangan Tinambung, yang lebih mirip kubangan kerbau raksasa daripada sebuah lapangan bola, masih lebih luas. Dalam peta skala 1: 500.000, ukurannya amat kecil. Masih lebih besar ujung korek api. Tapi, walau hanya bagai titik dalam peta, memiliki Pulau Lerelerekang sama saja Rp 3 triliun ke PAD Majene setiap tahun!
Jika ada PAD seperti itu, pada gilirannya pembangunan akan lebih banyak (semoga korupsinya juga tidak tambah banyak) di daerah kita ini. Bila pemimpinnya bijak, siswa TK sampai mahasiswa dari Majene akan gratis pendidikannya. Malah akan diberi beasiswa untuk menutut ilmu ke luar negeri. Pembangunan kampus Universitas Sulawesi Barat (dan penegeriannya) akan segera, dan pembangunan-pembangunan lainnya tumbuh di mana-mana. Baik itu fisik maupun non-fisik.
Singkat kata, membicarakan Pulau Lerelerekang itu berguna. Dan memperjuangkan agar tetap sebagai milik Provinsi Sulawesi Barat, bukan penting saja, tapi harus. Itulah tujuan mengapa harian ini, Radar Sulbar, getol memberitakan persoalan Pulau Lerelerekang serta pulau kecil lain di Sulawesi Barat. Dampak konkritnya yang akan terjadi, posisi Majene sebagai golongan kabupaten miskin di Indonesia tak akan lagi.
123Ekspedisi Bumi Mandar
Ada persoalan di daerah kita ini, sebagaima yang ditulis di seri sebelumnya, bahwa kesadaran “sense belonging” (rasa memiliki) pulau kecil yang jauh sangatlah kecil. Baik masyarakatnya maupun pemerintahnya. Nanti ada kasus baru tahu bahwa itu miliknya; nanti ketahuan potensi kekayaannya baru mau menjaganya. Ketiadaannya diiringi ketidakadaaan “database”.
Amat terkenal pameo, tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dengan Pulau Lerelerekang. Sebab kita tidak kenal dan tidak tahu, maka tak sayang; maka tak merasa perlu untuk memperjuangkannya. Dalam tulisan ini, saya memberi apresiasi khusus KNPI Provinsi Sulawesi Barat yang menginisiasi membicarakan persoalan pulau kita dalam sebuah diskusi. Demikian juga terhadap Aliansi Pemuda Pecinta Budaya Mandar (APPBM), organisasi mahasiswa di Universitas As Syariah Mandar di Polewali, yang hari ini juga akan mengadakan diskusi sederhana bertema pulau kecil.
Juga ingin saya kemukakan kegundahan teman saya di Mamuju yang putra Majene. “Koq pemuda-pemuda di Majene malah sama sekali tidak ada gerakannya padahal kabupaten merekalah yang memiliki Pulau Lerelerekang”. Saya sependapat dengan gundah gulana teman tersebut. Kan agak aneh, generasi yang akan mewarisi Pulau Lerelerekang malah ndak ada gerakannya. Sedang pemuda – mahasiswa di kabupaten lain (setidaknya Mamuju dan Polewali Mandar) malah telah ada aksi.
Bila dibandingkan gerakan pemuda dan mahasiswa di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kotabaru, amat menyedihkan sikap pemuda di daerah kita ini.
Di sisi lain, saya juga berempati. Mungkin masih banyak yang belum tahu duduk persoalannya. Misalnya tak tahu apa itu Pulau
124 Muhammad Ridwan Alimuddin
Lerelerekang, apa fungsinya, dan apa perannya dalam geopolitik Provinsi Sulawesi Barat. Sebab sebelum kasus ini muncul ke permukaan, mungkin hanya nelayan Mandar yang tahu bahwa Pulau Lerelerekang itu ada.
Dalam seri terakhir tulisan ini juga perlu saya utarakan. Baiknya kita tak sematkan lagi ke diri, bahwa kita ini cucu para pelaut ulung, bila persoalan Pulau Lerelerekang (dan masalah apa saja di pesisir dan pulau-pulau kecil) tak kita pedulikan.
Semangat sebagai pelaut di masa sekarang jangan diterjemahkan secara harafiah. Bahwa kita harus menjadi nelayan atau pelaut. Bukan itu maksudnya. Tapi juga bisa dalam memperjuangkan kekayaan kita dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat, terkhusus di pesisir.
Mungkin ada juga yang berpendapat, tidak apa-apa diambil Kalimantan Selatan. Kan masih sama-sama NKRI. Ya, bisa saja berpendapat seperti itu. Tapi tidak sesederhana itu. Pembangun di daerah kita jauh tertinggal dengan daerah lain. Kita ini miskin. Adapun Kalimantan Selatan, PAD dari tambang, khususnya batubara telah lama mereka nikmati. Adapun motif Kalimantan Selatan juga sama dengan kita. Sama-sama atas dalih ekonomi.
Untuk itu, demi mempertahankan hak kekayaan kita dan untuk memajukan daerah kita, Pulau Lerelerekang harus kita pertahankan semaksimal mungkin. Bentuk perjuangan bisa beraneka ragam, disesuaikan kemampuan kita. Laksana perjuangan kemerdekaan dulu. Ada yang angkat senjata, ada negosiator, ada penyedia logistik, ada kontra spionase, dan ada pemberi semangat.
Sekecil apa pun perjuangan itu amat penting. Misalnya mengabari orang-orang di sekitar kita bahwa Pulau Lerelerekang
125Ekspedisi Bumi Mandar
itu ada, bahwa Pulau Lerelerekang mau direbut Kalimantan Selatan padahal itu kekayaan kita. Itu jauh lebih berharga daripada tidak berbuat sama sekali.
Terakhir, perjuangan haruslah tetap dengan cara baik. Dengan akal sehat, tidak main sogok-sogok, tak emosional, dan tak membenci saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, khususnya warga Mandar di sana. Mungkin ada warga Mandar di Kalimantan Selatan mendukung Pulau Lerelerekang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, itu hak mereka. Mungkin juga ada yang menolak.
Bagi yang menolak, jangan kita dorong untuk melakukan penolakan yang terang-terangan di muka umum. Sebab itu ada efeknya, seperti mereka dikucilkan atau diteror. Persoalan ini janganlah digiring yang bisa berujung pada aksi kekerasan. Itu jangan sampai terjadi. Cukuplah do’a dan keyakinan bahwa Pulau Lerelerekang adalah milik Sulawesi Barat.
Kali Ini Bupati Ikut Berlayar
“Tongani mallimbang limbong // Pulau Lerelerekang // I’dai lalllaq // di wanua Majeneq” demikian bait “kalindaqdaq” yang spontan disyairkan Bapak Syamsuddin Ahmad, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene sesaat setelah tiba di Pulau Lere-lerekang (Selasa, 4/6).
Perjalanan dari Kota Majene makan waktu lebih sepuluh jam, berangkat malam tiba pagi. Soalnya jaraknya hampir 200 km, kira-kira setara Majene – Pangkep. Rombongan dinakhodai langsung Bupati Majene, Kalma Katta, sesuatu yang luar biasa bila
126 Muhammad Ridwan Alimuddin
dibandingkan pelayaran-pelayarang sebelumnya ke Pulau Lere-lerekang.
Kedatangan tim “Ekspedisi Lere-lerekang” (ini istilah informal saja) disambut “suqba” (gerombolan ikan yang berenang-renang di permukaan laut). Seakan menyimbolkan bahwa di balik Pulau Lerek-lerekang itu ada banyak rezeki; juga sebuah pertanda baik. Bahwa perjalanan ini diberkahi. Cuaca juga demikian, ombak tenang dan terik matahari tiada adanya. Tak nampak wajah lelah walau perjalanan ini relatif jauh bagi beberapa orang, yang pertama kali berlayar.
Sesaat sebelum tiba, awak-awak kapal melakukan sarapan. Ada yang makan mi gelas, minum kopi, dan kue-kue sisa semalam. Tak ada jarak antara pejabat dengan kru-kru lain. Istilahnya, baik pejabat eksekutif maupun legislatif begitu merakyat. Semalam pun, di kala tidur, tubuh yang bila di darat berbaring di kasur empuk, di atas perahu papan-papan saja. Yang membuat bulu hidung bergetar saat berbaring, sebab getaran mesin di lambung kapal merambat kemana-mana.
Merasa kunjungan ini penting dan menyejarah, meski tempat yang didatangi adalah pulau tak berpenghuni, bupati Majene mengenakan pakaian kebesarannya sebagai bupati: baju coklat dengan emblem sebagai seorang bupati. Hanya topi yang membedakan, soalnya di situ tertulis “Diadora”. Sepertinya pak bupati lupa membawa topi yang di situ ada tulisan “Bupati Majene”.
Yang lain pun demikian, khususnya beberapa anggota DPRD Kabupaten Majene dan seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
127Ekspedisi Bumi Mandar
Bapak Rusbi Hamid lengkap dengan tas punggung “Lemhanas-nya” yang penuh dengan barang bawaan dan celana warna khas tentara. Sedang Bapak Hajar Nuhun (Ketua DPRD Kabupaten Majene, Partai Demokrat), walau ini kunjungan ke pulau kecil, kostumnya tetap perlente. Bersama dengan Bapak Lukman (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene, Partai Golkar) mereka berdua mengenakan topi yang menandakan bahwa mereka wakil rakyat.
Walau tak semuda wakil-wakil rakyat dari Kabupaten Majene, Bapak Muhammad Darwis, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang juga mantan Bupati Majene, tak mau kalah begitu antusias untuk segera mendarat di Pulau Lerek-lerekang. Beberapa jam sebelum keberangkatan, beliau menelepon salah satu pejabat SKPD Majene, menanyakan apa saja peralatan dan pakaian yang harus dia bawa.
Beberapa kepala SKPD Kabupaten Majene pun demikian adanya. Tapi mereka lebih enjoy, sebab beberapa diantaranya sudah pernah ke Pulau Lere-lerekang, di ekspedisi sebelumnya yang sekaitan dengan penegasan bahwa pulau tersebut adalah milik Kabupaten Majene.
Semangat para penumpang KM Napoleon sepertinya tak diimbangi mesin perahu karet yang akan digunakan menyeberang ke pulau. Hampir setengah jam tak mau nyala. Seperti mesin yang bermasalah saluran bahan bakarnya dan pengapian di busi yang tak sempurna. Lama diutak-atik awak kapal, akhirnya mesin tempel bisa digunakan.
Yang pertama menyeberang adalah pejabat-pejabat teras eksekutif dan legislatif Kabupaten Majene beserta Kapolres Majene, Bapak AKBP Anwar Efendi. Jarak dari kapal ke pulau sekitar
128 Muhammad Ridwan Alimuddin
150 meter. Sekitar lima menit berjalan, akhirnya pejabat-pejabat tersebut, untuk pertama kalinya, menjejakkan kaki di pulau yang dalam 1-2 tahun terakhir diperjuangkan setengah mati. Pasir putih dan lidah ombak lembut menyambut sempurna.
Sedikit kilas balik, tahun lalu, beberapa pelayaran difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Majene ke Pulau Lere-lerekang. Kabarnya ada tiga pelayaran. Pelayaran pertama saya ikut serta, 30 November 2011. Misi utama adalah memasang plank nama bahwa berdasar Permendagri No. 43, Pulau Lere-lerekang (tertulis Pulau Lerek-lerekang) adalah milik Kabupaten Majene. Pelayaran kedua dan ketiga saya tak ikut serta, tapi kabarnya untuk menanam buah kelapa dan membangun rumah singgah bagi nelayan, dan yang keempat sekarang ini.
Juga pernah diadakan rapat akbar, di saat ribuan orang memenuhi jalan-jalan utama di kota Majene. Kegiatan dipimpin langsung bupati Majene tersebut menyeruakan agar Pulau Lere-lerekang dilepaskan dari wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
Bukan hanya itu, perjuangan-perjuangan di tingkat elit atau birokrasi di Jakarta pun dilakukan. Setelah sempat tak terdengar kabar beberapa bulan, akhir Mei lalu pihak Pemerintah Kabupaten Majene diundang Perusahaan Pearl Oil dan SKK Migas untuk datang ke Surabaya guna mengikuti pertemuan yang membahas pembangunan instalasi penambangan gas tak jauh dari Pulau Lerek-lerekang.
“Undangan tersebut suatu pertanda baik, sebab bisa diartikan Kabupaten Majene memiliki peranan penting dalam kegiatan penambangan gas di dekat Lerek-lerekang,” ungkap Bupati Majene.
129Ekspedisi Bumi Mandar
Sama halnya yang disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, Bapak Abdul Qadir Thahir, “Ada perkembangan baru dalam kasus Lerek-lerekang ini, ternyata titik pengeboran itu tak berada di barat Pulau Lerek-lerekang, melainkan di sebelah timurnya. Titik tersebut berada di antara Pulau Lerek-lerekang dengan Kabupaten Majene. Artinya apa, Kabupaten Majene memiliki posisi lebih menguntungkan dibanding daerah lain yang ingin merebut Pulau Lerek-lerekang. Jadi, pelayaran ini untuk membuktikan langsung informasi tersebut.”
Berdasar dari perkembangan dan informasi tersebut, kegiatan kunjungan bupati Majene dan beberapa anggota DPRD Majene dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilakukan. Selain sebagai bentuk penegasan bahwa Pulau Lerek-lerekang milik Kabupaten Majene, juga untuk memberi perhatian terhadap pulau tersebut. Dan yang lebih penting, jika memungkinkan, mengunjungi kegiatan pembangunan instalasi pembangunan kilang yang kabarnya sedang berlangsung tak jauh dari Pulau Lerek-lerekang.
Memperjuangkan Mempertahankan Lere-lerekang
Empat kali perahu karet bolak-balik dari KM Napoleon ke Pulau Lere-lerekang, guna menurunkan semua penumpang, kecuali beberapa awak yang tetap berada di kapal.
Ada rasa penasaran bukan hanya yang pertama kali menjejakkan kaki di pulau yang dibicarakan tiga tahun terakhir ini, tapi juga yang sering datang. Soalnya, dari kejauhan, sepertinya ada yang tidak beres di pulau. Nampaknya papan nama dirusak, dan rumah singgah yang “Koq berpindah dan berbeda gaya atapnya?”.
130 Muhammad Ridwan Alimuddin
Belum lagi, ada jejak kaki di pasir putih pulau. Guna mengantisapasi, siapa tahu, ada “musuh” di pulau, pihak kepolisian dan TNI ditunggu lengkap dan diharap tidak berombongan.
Setelah lengkap, mulailah rombongan berjalan ke arah timur pulau. Tak lama kemudian, rasa penasaran terjawab: papan nama yang dipasang November 2011 lalu yang di situ tanda bahwa Pulau Lerek-lerekang adalah milik Kabupaten Majene rusak. Papannya tidak ada, tinggal atap dan rangkanya. Beberapa meter didekatnya rumah singgah tak ada lagi. Itu yang paling membuat kecewa.
“Papan nama kita dirusak, demikian juga rumah singgah serta tanda yang dipasang pihak Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah salah satu hasil dari kunjungan kita. Ini sangat kita sesalkan, sebab selain rumah singgah itu kan kita peruntukan bagi nelayan. Jadi sebenarnya tidak perlu dirusak,” ucap Bupati Majene, Kalma Katta.
Bersama beberapa anggota DPRD Kabupaten Majene, DPRD Sulawesi Barat, pihak kepolisian dan TNI, dan kepala SKPD yang terkait dengan masalah Pulau Lere-lerekang, rombongan melanjutkan perjalanan keliling Pulau Lere-lerekang.
“Luas pulau sekitar enam hektar saja, tak sampai setengah jam untuk mengelilinginya,” demikian informasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene, Bapak Fadlil Rasyid, yang sudah tiga kali ke Pulau Lere-lerekang.
Pulau Lere-lerekang pulau tak perpenghuni, sebab kecil dan relatif terisolasi (baca: sangat jauh) dari pulau-pulau besar. Vegetasinya khas pulau kecil, berupa tumbuhan semak, beberapa pohon ketapang, pandan laut, salah satu jenis komunitas mangrove, formasi pes kapre, dan ilalang. Juga ada tanaman pohon kelapa yang ditanam di ekspedisi ketiga ke Pulau Lere-
131Ekspedisi Bumi Mandar
lerekang. Tak ada batu karang besar di atas pulau.
Sekeliling pulau adalah pasir putih, sangat pas sebagai sarang atau tempat menyimpan telur penyu. Sebagaimana dalam perjalanan yang menemukan dua lintasan jejak penyu. Beberapa anggota rombongan mencari-cari sarangnya. Katanya untuk obat kuat, tapi Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Majene mengingatkan untuk tidak mengambil. “Penyu itu binatang di lindungi, kita jangan ganggu sarangnya,” katanya.
Di tengah pulau ada galian berisi air tawar. Dibuat oleh nelayan yang sering datang ke Pulau Lere-lerekang. Kunjungan kali ini mendapati sumur sederhana tersebut berisi bangkai penyu. Penyu tersebut terjebak alias masuk lubang tapi tak bisa keluar. Sebab lama di situ, jadinya mati.
Sekitar seratus meter dari lokasi papan nama dan bekas rumah singgah, atau di sisi tenggara pulau, didapati dua bangunan permanen. Pertama “papan” (sebenarnya bukan papan sebab terbuat dari semen) nama yang, katanya, Pulau Lari-lariang (istilah lain dari Pulau Lere-lerekang) adalah milik Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, semacam pendopo yang lantainya marmer. Bangunan atapnya khas rumah Banjar. Inilah yang tadinya dianggap rumah singgah yang dibangun pihak Kabupaten Majene. Ternyata rumah singgah dirusak habis-habisan “diganti” dengan pendopo dan “dipindah” ke tempat lain (menghadap ke timur, di tenggara pulau).
Tidak seperti oknum yang merusak fasilitas Kabupaten Majene dan fasilitas negara (batas provinsi yang dipasang Kemendagri), pihak dari Majene sama sekali tidak merusak bangunan yang dibuat pihak Kabupaten Kotabaru. “Kita bukan pihak yang mengandalkan
132 Muhammad Ridwan Alimuddin
kekerasan, jadi tidak perlu dirusak. Kan kita beruntung, pulau kita dibuatkan bangunan. Apalagi itu papan nama yang mereka buat, kan kelihatan hurufnya rontok satu-satu, rusak sendiri,” tutur Bapak Rusbi Hamid, anggota DPRD Kabupaten Majene, salah satu motor penggerak perjuangan mempertahankan Pulau Lere-lerekang.
Selesai foto-foto bersama di fasilitas yang dibuatkan pihak Kabupaten Kotabaru “untuk” Kabupaten Majene, rombongan melanjutkan jalan kaki, ke sisi barat pulau. Yang menggembirakan, sekaligus bisa sebagai penanda bahwa pihak Kabupaten Kotabaru atau Provinsi Kalimantan Selatan tidak memahami atau tidak mengelilingi Pulau Lere-lerekang, papan nama yang dibuat Kabupaten Majene yang menghadap ke barat tetap berdiri kokoh. Dengan kata lain, apakah memang sengaja tidak dirusak atau memang tidak dilihat? Sebab bila melihat dua fasilitas lain yang dirusak, “seharusnya” papan nama tersebut juga ikut dirusak. Nyatanya baik-baik saja.
“Syukurlah, apa yang kita pasang hampir dua tahun lalu, salah satunya tetap dalam kondisi baik,” ucap Bapak Abdul Qadir Thahir, Kepala Disporabudpar, yang juga ikut serta memasang papan nama, di pelayaran pertama ke Pulau Lere-lerekang.
Beberapa anggota rombongan tidak hanya mengelilingi pulau, tapi lebih dari itu. Misalnya anggota rombongan paling senior, yakni Bapak Muhammad Darwis, mantan Bupati Majene yang sekarang ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Selain mencatat, antara lain apa yang dirusak dan tanda perbatasan yang ada di pulau, juga mengumpulkan kulit-kulit kerang serta batu-batu koral. “Pulau ini menarik, saya sangat terkesan ke pulau ini. Makanya saya banyak mencatat dan membawa oleh-oleh dari pulau. Semoga ke depan
133Ekspedisi Bumi Mandar
masalah yang kita hadapi segera selesai, dan Pulau Lere-lerekang tetap milik kita,” tanggap Bapak Muhammad Darwis walau capek tapi tetap penuh semangat.
“Bagaimana, kita pulang. Kan sudah keliling pulau,” pancing salah seorang anggota rombongan. Bapak Lukman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene menimpali, “Waduh, jangan dulu. Saya masih ingin lama di pulau.” Memang Bapak Lukman cukup antusias berada di pulau. Rasa penasarannya akan Pulau Lere-lerekang terjawab sudah. Sebagai wakil rakyat, beliau cukup paham bahwa apa yang diperjuangkan harus dipahami baik-baik.
Sesaat setelah keliling pulau, Bapak Bupati Majene dan jajaran muspida lainnya berkumpul di salah satu tempat lapang tapi terlindung, hampir di tengah pulau. Dilakukan diskusi informal mengenai hasil yang diperoleh dan langkah apa yang perlu dilakukan ke depan.
“Hasil yang kita peroleh dalam kunjungan ini akan memperkuat perjuangan kita mempertahankan Pulau Lere-lerekang. Saya optimis akan hal itu,” komentar Bapak Kalma Katta bersemangat.
Senada dengan komentar Kapolres Majene, Bapak AKBP Anwar Efendi, “Genap pengabdian saya di Kabupaten Majene, sebab sudah berkunjung ke Pulau Lere-lerekang. Sesuai hukum dan aturan yang berlaku, saya akan membantu semaksimal mungkin agar pulau ini tetap dalam wilayah Kabupaten Majene.”
Lautnya Sulbar Ternyata Terbagi-bagi
Dalam penentuan batas antar provinsi dengan menggunakan peta, diistilahkan “Survey and Delimitation”, peta yang digunakan adalah peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000.
134 Muhammad Ridwan Alimuddin
Khusus untuk pesisir barat Pulau Sulawesi atau Selat Makassar dari utara ke selatan (perbatasan dengan Malaysia/Filipina) hingga Laut Flores/Laut Jawa telah saya miliki beberapa tahun lalu, sejak masih mahasiswa.
Sewaktu kuliah di UGM, saya mengambil jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, program studi Manajemen Sumberdaya Perairan. Salah satu kajian penting adalah tentang pulau-pulau kecil, yang masa itu (awal 2000-an) mulai hangat dibicarakan (apalagi dengan adanya kasus Sipadan – Ligitan). Itu sebab sedikit banyak saya belajar dari pakar-pakar mengenai hal itu dan kenal dengan mereka, khususnya Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, pemberi pengantar buku pertama saya, Mengapa Kita Belum Cinta Laut?) dan Jacub Rais (mantan Kepala Bakosurtanal, ahli pemetaan). Syukurlah, ilmu pengetahuan akan hal itu bisa diterapkan saat ini.
Bila berdasar Permendagri No. 1/2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang mengacu kepada UU No 32/2004, sepertinya (masih menggunakan kata “sepertinya” sebab belum diperoleh hasil pengukuran resmi dari pihak berkompoten) wilayah laut Provinsi Sulawesi Barat itu tidak dalam satu kesatuan, tapi terpecah-pecah; terbagi-bagi.
Mengapa? Sebab kita memiliki beberapa pulau kecil yang jaraknya satu sama lain ada yang berada di atas 24 mil laut. Demikian juga jaraknya dari daratan utama (Pulau Sulawesi) yang juga lebih dari 24 mil laut.
Berdasar simulasi sederhana pengukuran batas laut yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat di peta LLN Lembar 20 Edisi 1992 (diterbitkan Bakosurtanal), bisa disimpulkan bahwa
135Ekspedisi Bumi Mandar
wilayah laut Sulawesi Barat terbagi atas empat, yaitu: 1) laut sepanjang pesisir daratan Pulau Sulawesi yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2) laut di sekitar gugusan Kepulauan Bala-balakang, 3) laut di sekitar Pulau Lumu-lumu, dan 4) laut di sekitar Pulau Lere-lerekang.
Untuk daratan utama, penentuan batasnya relatif gampang, sebab hanya menarik garis dari garis pasang terendah ke arah luar sejauh 12 mil laut. Agak rumit di bagian perbatasan, yaitu antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah (dengan Kabupaten Donggala) dan antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan (dengan Kabupaten Pinrang). Antar keduanya, dengan Sulawesi Selatan lebih rumit lagi sebab di wilayah situ ada beberapa pulau kecil (yang masuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar), yang penentuan titiknya lebih banyak dan berada di garis pantai yang melengkung (sudut Teluk Mandar).
Sebelum lanjut, sedikit disampaikan mengenai aturan hukam sekaitan penentuan batas suatu daerah di laut. UU No 32/2004 Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut pada provinsi paling jauh 12 mil laut diukur dari garis dasar ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sepertiganya untuk wilayah kewenangan laut kabupaten/kota.
Perlu ditekankan bahwa di situ tidak disebutkan tentang 4 mil laut untuk kewenangan laut kabupaten/kota mengingat tidak mungkin bagi kabupaten/kota mengklaim selebar 4 mil laut apabila provinsinya juga tidak bisa mengklaim wilayah laut secara penuh hingga 12 mil laut (makna Pasal 18 ayat (5). Jadi menggunakan istilah sepertiganya saja.
136 Muhammad Ridwan Alimuddin
Sebagai contoh selat di antara Jawa (Timur) dengan Bali. Sebab hanya, misalnya 6 mil), maka batasnya dibagi dua dengan menggunakan prinsip “median line” (garis tengah): 3 mil untuk Jawa Timur, 3 mil untuk Bali. Nah, karena tidak sampai 12 mil, maka “jatah laut” kabupaten adalah sepertinya, yaitu 1 mil saja dari garis pantai. Di atas 1 mil (2-3) mil bagiannya provinsi.
Untuk kasus seperti itu, di mana dua provinsi berhadap-hadapan (opposite) dan jaraknya tidak sampai 24 mil (12 mil dibagi dua), juga dialami Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju). Yaitu di perairan yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Pasir). Penentuan garis perbatasannya (delimitasi) cukup rumit sebab di situ ada beberapa pulau yang dari pulau tersebut ditarik garis dasar (baseline).
Secara teknis, untuk beberapa kasus memang rumit. Tapi aturan hukumnya sangat sederhana. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan petunjuk teknis yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 (Permendagri No.1/2006) tentang “Pedoman Penegasan Batas Daerah” yang mengacu kepada UU No 32/2004. Pedoman itulah yang akan dijadikan petunjuk teknis di dalam penetapan batas daerah di Indonesia.
Permendagri No. 1/2006 tentang “Pedoman Penegasan Batas Daerah” merupakan petunjuk teknis untuk penegasan batas yang mengacu pada UU No. 32/2004. Pasal-pasal pada Permendagri No. 1/2006 yang terkait tentang penegasan batas laut antara lain sebagai berikut
Pasal 1 ayat (6). Batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya
137Ekspedisi Bumi Mandar
merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut.
Pasal 15 ayat (2). Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten
dan daerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota kearah laut yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak;
2. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah;
3. Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah; 4. Batas wilayah laut pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut.
Bagian terakhir inilah yang harus dicamkan baik-baik. Sebab, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, aturan inilah yang “memecah” Provinsi Sulawesi Barat menjadi beberapa bagian. Alias tidak berada dalam satu kesatuan, sebagaimana bila ada garis imajiner di Tanjung Rangas di Majene - Pulau Lere-lerekang lalu - Pulau Lumu-lumu – Pulau Salissingang – Pulau Ambungi – muara Sungai Suremana di Mamuju Utara.
Artinya apa, aturan itu pula yang memungkinkan anjungan atau kilang gas yang dikunjungi Muspida Majene “tak memberi efek apa-
138 Muhammad Ridwan Alimuddin
apa” (tak ada “fee” pembagian hasil) ke Kabupaten Majene ataupun Provinsi Sulawesi Barat. Kenapa bisa? Sebab anjungan tersebut letaknya 16 – 18 mil laut dari Pulau Lere-lerekang (ke arah timur) atau berada di luar radius 12 mil (baca pembelasan ke-4 Pasal 15 ayat 2 di atas); sebab kilang tersebut letaknya lebih jauh lagi dari daratan utama yakni kurang lebih 80 mil.
Tapi apakah sesederhana itu? Apakah perjuangan selama ini akan sia-sia? Sepertinya tidak. Pihak pemerintah kita, khususnya Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat tidak akan tinggal diam. “Sepulang dari Pulau Lere-lerekang, kami akan melakukan langkah-langkah strategis,” ucap Bapak Kalma Katta, Bupati Majene, dengan mantap disaksikan ilalang Pulau Lere-lerekang.
Menuju Kilang yang “Diperebutkan”
Pelayaran pertama, kedua dan ketiga hanya bekas pondasi menara suar tak jauh dari pulau. Pelayaran keempat, sekitar 100 meter dari pulau, telah ada menara suar baru. Entah kapan dibangun, entah siapa yang bangun. Itulah perbedaan mencolok atau kondisi terbaru yang ada di sekitar Pulau Lere-lerekang dibanding dengan kunjungan sebelumnya.
Terlepas siapa pun yang membangunnya, bentuknya mirip menara seluler tapi lebih ringkih dan tak dicet warna merah – putih, menara suar setinggi kurang lebih 30 meter yang ada di dekat Pulau Lere-lerekang cukup penting. Sebagai rambu dalam melakukan pelayaran di laut lepas. Jika malam, lampu dari daratan, baik pulau kecil maupun pulau besar, amat berperan penting dalam membantu navigasi kapal ataupun nelayan kecil.
139Ekspedisi Bumi Mandar
Ada aturan penting yang berlaku di kalangan pelayar modern, jika mengetahui ada lampu suar tidak menyala, informasi tersebut dilaporkan ke pihak terkait, biasanya syahbandar. Pihak syahbandar kemudian melaporkan ke pembuat peta, dalam hal ini Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei Tanah dan Laut). Peta yang dikeluarkan akan diberi tanda bahwa lampu di titik tersebut tidak nyala, atau kalau sudah terlanjur cetak (edisi lama), biasanya diberi tanda khusus.
Peta adalah bagian dalam sebuah perang. Pihak yang tak memiliki peta merupakan penanda bahwa pihak tersebut tak memiliki unsur atau bekal dalam menyusun strategi perang. Sama halnya dalam urusan Pulau Lere-lerekang ini. Meski ini bukan sebuah perang sebagaimana jamaknya (angkat senjata, saling bunuh), apa yang dilakukan ada miripnya juga. Singkat kata, dengan peta, kita lebih tahu tentang wilayah kita dan apa yang harusnya dilakukan.
***
“Bagaimana kalau kita singgah ke kapal tugboat itu,” usul Pak Lukman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene sesaat setelah meninggalkan Pulau Lere-lerekang; sambil melihat ke arah kapal tugboat yang nampak “berlabuh”. Yang lain menimpali untuk tidak usah singgah soalnya itu bukan kapal utama yang melakukan pekerjaan pembuatan kilang.
“Tak apa-apa, ke sana saja. Kan dari sana mungkin bisa dapat informasi atau akses ke kapal utama,” tanggap Ketua DPRD Majene, Bapak Hajar Nuhun yang memiliki latar belakang bisnis minyak. Jadi tahu sedikit – banyak tentang urusan di atas kapal tugboat. Setelah mendapat lampu hijau dari Bupati Majene, KM
140 Muhammad Ridwan Alimuddin
Napoleon mendekat ke tugboat Vier Navigator. Beberapa awak nampak sedang memancing di sisi kiri kapal.
Agar tak dicurigai, pihak kepolisian dan TNI yang berseragam di atas KM Napoleon diminta ke arah haluan. Semakin mendekat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Majene dengan nada suara agak keras (agar terdengar) menyampaikan ke awak tugboat bahwa kami adalah rombongan dari Majene dan ikut serta Muspida Kabupaten Majene.
Laut yang tenang memudahkan dua kapal saling merapat. Setelah tali temali diikatkan, beberapa awak dari KM Napoleon termasuk bupati, anggota DPRD, Kapolres dan awak lain segera naik ke kapal tugboat. Agak repot sebab harus memanjat dinding atau semacam pagar besi tugboat.
Awak-awak tugboat mempersilahkan rombongan dari Majene memasuki ruang kabin kapal. Suasana di dalam cukup tenang dan bersih. Dapurnya mirip bar, ada meja santai-santai, kamar kecil dan perlengkapan ala kapal modern.
Singkat cerita, pihak Majene meminta kapten kapal tugboat untuk menyampaikan maksud mereka ke pihak kapal utama. Yakni berkunjungn ke kapal yang sedang membangun kilang. Dengan sigap, kapten kapal naik ke ruang kemudi yang juga ruang komunikasi. Sebab ada ‘speaker’ di ruang bawah, tempat Muspida Majene menunggu, komunikasi antara kapal Vier Navigator dengan kapal utama terdengar. “Mungkin bisa menunggu, kami komunikasikan dulu dengan pihak di Jakarta,” terdengar suara dari radio kapal utama.
Sambil menunggu tanggapan, kepada kapten kapal juga ditanyakan aktivitas apa saja yang telah dilakukan dan proses apa yang dilakukan saat ini.
141Ekspedisi Bumi Mandar
Beberapa lama kemudian, informasi dari kapal utama sudah ada. Kami diminta mendekat ke kapal tugboat yang lain, yang akan mengantar ke kapal utama. Mendengar hal itu, rombongan Majene turun ke KM Napoleon, nanti Vier Navigator yang memandu KM Napoleon ke arah kapal tugboat. Yang dari kejauhan, kapal tugboat tersebut bernama BNI Castor.
Mendekat ke BNI Castor, aktivitas pembangunan kilang juga semakin jelas. Yang tadinya hanya nampak kapal besar dengan “crane” raksasa, setelah memutarinya, ternyata sudah ada rangka kilang (platfom) yang terpasang. Beberapa bagian masih terbungkus plastik besar, laksana barang baru. Ada spanduk raksasa tertulis “PT Meindo Elang Indah” di bagian lain spanduk “PQP Tope Side Load Out P2 Module”.
Tugboat BNI Castor cukup besar, hampir dua kali lipat Vier Navigator. “Besar sekali ini kapal,” ucap Bapak Hajar Nuhun.
Menjelang merapat, awak-awak BNI Castor dengan seragam oranye, mengenakan helm, kacamata, pelindung dada dan sepatu boat bersiaga di sisi kapal. “Hanya yang tertentu saja bisa naik,” teriak kapten BNI Castor dari dek ruang kemudi, di bagian paling atas BNI Castor.
“Ayo pak, segera. Yang bisa naik harus mengenaka sepatu,” ucap awak BNI Castor. Mendengar hal itu, rombongan Majene yang sudah naik, termasuk Bupati dan Kapolres harus menunggu sebentar sepatu dari KM Napoleon. Bukan apa-apa, sejak dari Majene, ke Pulau Lere-lerekang hingga perjalanan pulang pakai sandal terus. Buat apa juga pakai sepatu. Beruntung beberapa orang, termasuk Kapolres yang membawa sepatu. Yang lain pinjam sepatu dari orang lain.
142 Muhammad Ridwan Alimuddin
“Bapak-bapak, sekarang Anda berada di kapal yang sedang melakukan kegiatan pembangunan kilang. Keselamatan diutamakan di sini. Untuk itu, yang bisa naik ke kapal Castoro Otto tertentu saja,” sambut kapten kapal Castoro otto yang belakangan diketahui berasal dari Toraja.
Sambil menunggu, rombongan dari Majene yang naik ke BNI Castor dilayani di ruang kemudi nan mewah. “Silahkan minum pak. Bisa merokok di sini, tapi kalau di kapal itu tidak boleh,” ucap kapten kapal dengan ramah.
Setelah ada komando dari kapal Castoro Otto, rombongan dari Majene siap-siap menyeberang. “Nanti kalau ke kapal bapak akan dimasukkan ke keranjang besar. Yang bisa naik empat orang saja. Kalau ada di atas, harus memeluk erat tali didepannya,” instruksi kapten Castoro Otto.
Singkat cerita, rombongan dari Majene naik ke kapal BNI Castor dengan menggunakan keranjang raksasa. Saya sendiri tidak ikut, mengalah. Banyaknya pihak yang mau naik kapal membuat kru kapal yang mengatur siapa saja yang bisa naik ngomel bukan main. Sebab dia mengatakan hal itu dalam Bahasa Inggris, dan saya ngerti, hanya saya saja yang mahfum. Teman-teman rombongan lain yang kebelet naik, seakan tak punya beban.
Sebab tak ikut naik, tak banyak yang bisa saya tuliskan. Kabarnya di atas mereka dilayani dengan baik, mendapat presentasi tentang pekerjaan pembangunan kilang yang sedang dilakukan. Turun dari BNI Castor, kami pun kembali ke kapal kayu untuk selanjutnya kembali ke Majene.
Diakui atau tidak, yang membuat Pulau Lere-lerekang diperebutkan adalah adanya sumber gas di sekitarnya, yang
143Ekspedisi Bumi Mandar
penyedotannya lewat kilang. Sebab fakta di lapangan kilang tersebut berada 16 mil laut dari Pulau Lere-lerekang atau di wilayah nasional, muncul pertanyaan: apakah pemerintah daerah di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan masih mati-matian memperebutkan pulau? Ataukah akan mengulang kesalahan masa lampau, yang tidak memperhatikan pulau kecil mereka jika tak ada potensi ekonomi di situ?
147Ekspedisi Bumi Mandar
Suasana di Pulau LerelerekangAnemon dan ikan badut banyak terdapat di perairan Pulau LerelerekangPulau LerelerekangKoordinat lokasi Pulau Lerelekang dalam GPSSalah satu jenis terumbu karang di perairan Pulau LerelerekangKarang rusak banyak ditemukan di perairan Pulau LerelerekangAparat keamanan berposes di depan plank nama sesaat setelah pemasangannyaPulau Lerelerekang. Tampak plank yang dipasang Pemerintah Kabupaten MajenePemancangan plank kepemelikan pulauPemasangan plank kepemilikan pulau oleh Pemerintah Kabupaten MajeneProses pembangunan platform sekitar Pulau LerelerekangKapal Castoro Otto dalam proses pengerjaan kilang gasPemerintah Kabupaten Majene membawa plank bahwa Pulau Lerelerekang masuk wilayah
Kabupaten Majene
148
GALUNG LOMBOK
“Panyapuang di Galung Lombok” dan Westerling
Secara nasional sebagai bagian Korban 40.000 Jiwa, spesifik di Mandar dikenal sebagai Peristiwa Galung Lombok. Tapi orang
Mandar menyebutnya “Panyapuang di Galung Lombok”.
Diistilahkan demikian sebab waktu itu untuk membunuh orang-orang Mandar yang dikumpul di Galung Lombok (sekarang Desa Galung Lombok, Kec. Tinambung, Kab. Polman), pasukan KNIL ‘menyapu’ (menembakan senjata mesin dengan membabi buta) kumpulan orang dengan senapan mesin.
Pembantaian massal dilakukan oleh Pasukan Westerling, sebab dipimpin Letnan Satu Raymond Pierre Westerling. Tapi apakah dia hadir langsung di Galung Lombok saat pembantaian? Menurut salah satu catatan sejarah, aksi di Galung Lombok dipimpin Stufkens dan Vermuelen. Orang Mandar yang ditembak membabi buta berasal dari Baruga, Tande, Simullu, Banggae dan sekitarnya (Kab. Majene), dan dari Tinambung, Kandeapi, Lawarang (Kab. Polman) dan sekitarnya.
Pasukan Westerling adalah pasukan elit, yaitu Pasukan berbaret merah yang dikenal dengan sebutan Detachement Speciale Troepen (DST) beranggotakan 123 prajurit. Organisasi ini
149Ekspedisi Bumi Mandar
ditiru perintis pasukan elit Indonesia yang belakangan bernama Kopassus.
DST sengaja dikirim pemerintah Belanda dari Batavia ke Sulawesi Selatan untuk membinasakan para pejuang untuk memadamkan semangat perjuangan. Menurut Belanda, kantong-kantong perjuangan rakyat Sulawesi Selatan berada di Afdeling Makassar, Pare-Pare, Bantaeng, dan Mandar. Sehingga korban sebagian besar dari kawasan tersebut.
Pembantaian berlangsung 1 Februari 1947, menewaskan rakyat dan para pejuang. Kurang lebih 300 orang, termasuk 32 orang tawanan anggota pejuang dari penjara Majene. Diantaranya Atjo Benja, Paqbicara Pangali-ali (Hadat Kerajaan Banggae, sebagai penghormatan kepadanya di Kota Majene ada nama Jalan Atjo Benja), M. Yusuf Paqbicara Baru Banggae, H. Ma’ruf Imam Baruga, Sulemana Kali Baruga, Daaming Kapala Segeri, H. Nuhun Imam Segeri, H. Sunusi, H. Jumdara, H. Hadang, H. Kanna I Paesa, M. Saleh, H. Yahya dan Sofyan.
Terjadinya Peristiwa Galung Lombok karena Belanda sama sekali tidak leluasa kembali berkuasa di daerah Mandar. Belanda mendapat perlawanan keras dari rakyat Mandar. Para pejuang yang tergabung dalam organisasi perjuangan KRIS-Muda bahu membahu dengan para pejuang yang membentuk Kelaskaran GAPRI 5.3.1 melakukan aksi mengganggu dan melawan Belanda. Belanda kewalahan.
Untuk itu, pada tanggal 11 Desember 1946 Letnan Gubernur General Dr. H. J. van Mook di Batavia mengumumkan keadaan darurat perang (SOB) untuk Afdeling Makassar, Pare-Pare, Bonthain, dan Mandar.
150 Muhammad Ridwan Alimuddin
Kurang dua bulan kemudian, pada 1 Februari 1947 pasukan Westerling mengepung kampung Baruga, Simullu, Segeri, Lembang, Tande (Kab. Majene) dan sekitarnya; dan dari Tinambung, Kandeapi, Lawarang (Kab. Polman) dan sekitarnya untuk menakut-nakuti rakyat pasukan Belanda membakar beberapa rumah rakyat.
Penduduk pada kampung-kampung tersebut dikumpulkan lalu digiring ke Kampung Galung Lombok. Entah kenapa Galung Lombok yang dipilih. Mungkin karena kampung ini terletak di tengah, antara Simullu, Tande, Baruga dengan Tinambung, Lawarang, Kandeapi.
Di tempat itu perempuan dan anak-anak dipisahkan dari laki-laki. Pasukan Westerling mengadakan “pengadilan singkat” untuk mengetahui siapa di antara mereka yang di mata Belanda dicap ektremis.
Untuk mengetahui secara pasti siapa anggota organisasi perjuangan GAPRI 5.3.1., KRIS Muda, TRIPS dan ALRI, Stufkens dan Vermuelen mendatangkan 32 orang tawanan anggota pejuang dari penjara Majene, sekitar 10 km dari Galung Lombok. Mereka dipaksa menunjuk siapa di antara massa yang hadir yang menjadi anggota pejuang atau simpatisan pejuang.
Mereka menutup mulut rapat-rapat. Karena tentara Belanda tidak berhasil memaksa mereka membuka rahasia, mereka dijejerkan dan ditembak satu persatu. Selanjutnya penembakan dan pembunuhan ditujukan kepada para pemuka masyarakat yang diduga membantu para pejuang. Kepala Distrik dan pemuka-pemuka masyarakat Baruga, Tande, Simullu, dan lain-lain satu persatu menemui ajal.
151Ekspedisi Bumi Mandar
Ada pendapat yang mengatakan bahwa korban yang tewas tidak akan banyak jika tidak terjadi Peristiwa Taloloq.
Hubungan Antara Peristiwa Taloloq dan “Panyapuang”
Peristiwa Taloloq adalah pertempuran di Taloloq (sekarang masuk Kel. Baruga, Kec. Banggae Kab. Majene) antara pejuang dengan pasukan Belanda yang sedang patroli. Latar belakangnya, seorang tentara Belanda hendak memperkosa seseorang wanita, dicegah oleh Harun dan Habi anggota pasukan pimpinan Basong.
Kejadian tersebut berlangsung pada saat pasukan Westerling menangkapi para pejuang dan digiring ke Galung dan Simullu bersama-sama rakyat yang lebih dahulu dikumpulkan di Galung.
Muhammad Saleh Banjar, Komandan Besar Laskar GAPRI 5.3.1 di Markas Pumbeke memerintahkan kepada sembilan orang Komandan Tempur: Yonggang, Basong, Hambo, Dose, Hammasa, Suleman Kume, Sukirno, Maryono dan Harun melaksanakan penghadangan dan penyergapan terhadap pasukan Westerling yang akan melalui jalanan ke Taloloq.
Pasukan Westerling yang ditunggu tiba di tempat penghadangan. Tanne bersama pasukannya datang untuk membantu kawan-kawannya. Tiba-tiba sebuah mobil pasukan Westerling datang. Pasukan Tande melempar mobil itu dengan granat. Mobil terbalik lalu masuk jurang.
Terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran tiga orang pasukan Belanda tewas, yaitu Sersan Mayor Van Euw, Prajurit Dickeon, dan seorang tidak diketahui namanya. Pihak GAPRI 5.3.1.
152 Muhammad Ridwan Alimuddin
Pejuang merampas satu pucuk senjata E.L. dan satu pucuk pistol otomatis Colt cap Kuda. Di pihak GAPRI 5.3.1., Yonggang dan Sukirno gugur. Pasukan Westerling membawa tiga orang kawannya yang tewas mengundurkan diri ke Galung Lombok, dan pasukan tempur GAPRI 5.3.1. Membawa Yonggang dan Sukirno ke Pumbeke.
Begitu Stufkens dan Vermuelen mendengar berita terbunuhnya tiga orang anak buahnya dan mobil pasukannya masuk jurang, keduanya naik darah. Maka terjadilah pembantaian rakyat di Galung Lombok yang tadinya hanya pengadilan massal mencari para pejuang, dan mungkin untuk membunuh beberapa orang saja.
Rakyat yang tidak berdosa banyak yang jatuh korban. Pembunuhan berlangsung dari sekitar pagi sampai sore. Di sore dan malam hari dilaksanakan penguburan seadanya oleh kerabat mereka yang masih hidup dan rakyat yang dipaksa oleh pasukan Westerling. Untuk membawa mayat ke rumah keluarganya tidak dilakukan sebab masyarakat masih dihinggapi ketakutan.
Monumen 40.000 Jiwa
Untuk mengenang dan sebagai penghormatan kepada mereka dibangun Monumen Korban 40.000 Jiwa Galung Lombok di Desa Galung Lombok, Kec. Tinambung, Kab. Polman.
Dalam areal TMP (Taman Makam Pahlawan) Korban 40.000 Jiwa Galung Lombok terdapat tugu berbentuk pilar. Bentuk dasarnya berupa/berbentuk segi empat dengan tinggi 0,5 meter, dan bagian atasnya lagi berbentuk segi delapan dengan tinggi 1 meter, pilarnya tiga buah. Masing-masing ketiga tugu/pilar berturut-turut tingginya sekitar 12, 9, dan 7 meter. Masing-masing
153Ekspedisi Bumi Mandar
tugu/pilar berukuran satu meter persegi. Pembangunannya dimulai 1983 atas prakarsa para Pejuang 45 dan Pemerintah daerah setempat. Biaya pembangunan dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Prov. Sulawesi Selatan.
Luas Taman Makam Pahlawan 7.700 meter bujur sangkar (panjang 110 meter dan lebar 70 meter). Jumlah makam di dalamnya 326 makam. Semua yang dimakamkan dalam Taman Makam Pahlawan beragama Islam. Setidaknya ada kelompok makam. Tak jauh dari tugu, ada kelompok makam bernisan putih, dari beton. Tak ada nama. Kelihatan lebih rapi.
Di belakang pohon rimbun, di balik dinding beton yang tertulisan 160-an nama yang gugur dalam “panyapuang”, ada juga makam. Ada satu lubang beberapa nisan atau “tindaq” dalam bahasa Mandar. Ada juga satu-satu. Tapi, tidak rapi. Mungkin karena alasan itu, setiap ada upacara atau pesiarah, yang diberi karangan bunga biasanya nisa yang rapi-rapi saja, yang putih.
Di luar areal taman terdapat beberapa makam pahlawan yang juga gugur dalam Peristiwa Galung Lombok, yaitu mayat yang dipindahkan belakangan, saat situasi aman. Ada juga korban dalam peristiwa itu tapi makamnya di pekuburan Cina, dekat Datoq.
Komponen fisiknya: pagar 300 m2, pintu gerbang 40 m2, monumen 40 m2, plaza upacara 500 m2, ruangan kantor 50 m2, tembok nama 10 m2, tembok abadi 30 m2, tiang bendera 1 buah, jalan utama 200 m2, gorong-gorong 275 m2, dan saluran air 100 m2.
Saat ini, TMP Galung Lombok cenderung tidak diperhatikan. Saluran air di depan pagar hancur berantakan, beberapa bagian tugu sudah retak-retak. Bila tak diperbaiki, tugu bisa rusak. Ruang kantor juga kayak gudang, tak ada isi. Saat ini (Ahad, 18
154 Muhammad Ridwan Alimuddin
Desember 2011), isinya karangan bunga saja. Tak ada isi layaknya ruang administrasi. Idealnya itu dimanfaatkan, misalnya musem kecil tentang Peristiwa Galung Lombok. Jadi, jika ada pelajar yang datang, mereka membawa pulang sejarah Mandar yang berdarah.
Kejadian lain
Tiga Februari 1947, dua hari sesudah sesudah Peristiwa Galung Lombok, Muhammad Saleh Banjar Komandan Besar Laskar GAPRI 5.3.1. memimpin pertempuran di daerah Baruga. Tiga orang kawannya gugur yaitu Sapaya, Dahlan, dan Suruni. Pada malam harinya memimpin lagi pertempuran di Simullu. Itulah pertempurannya yang terakhir, karena gugur bersama kawan-kawannya sesama pejuang yaitu Takung, Mariletung, Taaco’, Tamanynya, dan Sabarang. Dalam lanjutan pertempuran ketika para pejuang mundur ke Baruga, Lepu gugur.
Kemudian pada 5 Februari 1947 di Pamboang tentara KNIL menewaskan 35 orang pahlawan termasuk tawanan dari Majene. Di antara korban gugur ialah Kepala Distrik Pamboang, Kepala Desa, dan Polisi Kampung. Sebelum ditembak mati, ada yang disiksa sehebat-hebatnya. Telinga, hidung, dan kemaluannya dipotong.
Laporan Rahasia Belanda Tentang Peristiwa Galung Lombok
Belanda terkenal sebagai penjajah yang rajin mencatat apa saja selama mereka menjajah Nusantara (dan daerah jajahan lainnya). Bukan hanya mencatat, juga dalam bentuk dokumentasi foto. Sehingga bukan hal mengherankan, arsip atau foto-foto masa lampau dapat ditemukan, misalnya di beberapa museum di Belanda.
155Ekspedisi Bumi Mandar
Bukan hanya pandangan atas negeri jajahannya, kejahatan yang mereka lakukan pun dicatat. Termasuk kejadian di Galung Lombok. Laporan Rahasia Politik Belanda dari tanggal 1 Oktober 1946 sampai 31 Maret 1948, tepatnya Gaheim Politiek Verslag 1 – 15 Februari 1947, dapat ditemukan di Kantor Badan Arsip Nasional di Makassar.
Hanya saja isinya tidak rinci dalam menceritakan apa yang mereka lakukan. Kelihatan tidak seram, berbeda dengan cerita dari saksi mata atau keturunan dari saksi mata. Sedikit banyak, “Panyapuang” di Galung Lombok menjadi cerita yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk cerita versi lisan dari orang Mandar akan saya tuliskan belakangan. Di tulisan ini saya mengutip utuh (tapi terjemahan) Gaheim Politiek Verslag 1 – 15 Februari 1947.
Bersyukur Mandar memiliki (almarhum) Syaiful Sinrang, putra Majene. Beliau dikenal sebagai seniman pencipta dan penyanyi lagu-lagu Mandar, tapi beliau meninggalkan beberapa tulisan berkaitan sejarah dan kebudayaan Mandar. Dari bukunya, “Mengenal Mandar Sekilas Lintas”, saya menemukan terjemahan dan kopi catatan rahasia Belanda tersebut. Berikut isinya:
“Afdeling Mandar. Mulai dari 1 Februari 1947 di Onderafdeling Majene khususnya dalam wilayah Majene – Balanipa dilaksanakan aksi pembersihan besar-besaran. Dibentuklah Polisi Kampung. Polisi Kampung ini dan beberapa penduduk menyerahkan kira-kira 20 orang perampok kepada militer, antara lain seorang orang Banjar dan smokel senjata Mohammad Saleh. Pemimpin gerombolan yang terkenal bernama La Bora seorang pembantu Hamma Saleh, terbunuh.
Sisa dari gerombolan perampok dan pengacau itu diburu antara Tande dan Kota Majene dan dimusnahkan. Dua buah granat
156 Muhammad Ridwan Alimuddin
tangan dan administrasi dari GAPRI 5/3/1, organisasi dari Hamma Saleh jatuh ke tangan kita. Pemimpin gerombolan Pabarru tewas, sedang pemimpin Pabangga dan Pangali dapat tertangkap.
Pada pembersihan di Kampung Totolisi terbunuh 31 orang pemberontak, sedang di Kampung Simullu 4 orang perampok dimusnahkan. Di bahagian utara Majene 4 orang pengacau jatuh ke tangan militer, dan pada kesempatan itu beberapa barang kepunyaan Maraqdia Pamboang yang telah dirampok oleh gerombolan didapat kembali.
Maraqdia Matoa di Majene ditangkap, sedang 4 orang Kepala Distrik di Kerajaan Banggae harus diganti dengan orang lain. Penduduk menyerahkan kepada militer pemimpin pemberontak La Pangin pembunuh dari anggota militer Timor, dan tersangkut pada pembunuhan Controleur Monsees.
La Pangin tersebut mendarat pada tanggal 4 Februari yang lalu di Paria sekembalinya dari Jawa, yang pada bulan Agustus 1946 dikirim oleh Datu Suppa untuk membeli senjata. Pada waktu ditangkap kedapatan memiliki pistol. Di Kampung Rusung terbunuh 3 orang pengacau dan di dekat Limboro juga terbunuh 3 orang.
Pada aksi pembersihan yang dilancarkan oleh militer di Landschap Pamboang terbunuh Paqbicara Bonde dan Paqbicara Adolang. Juga di daerah ini penduduk pada akhirnya menyerahkan perampok dan pengacau kepada militer. Atas tindakan tiba-tiba dari penduduk dan pemburuan secara diam-diam oleh militer, rombongan ini dari Hamma Saleh melarikan diri ke bagian utara jurusan Rante.
Tindakan perburuan berjalan terus, dan bagaimana hasilnya saat penyusunan laporan ini belum diketahui. Keamanan dan ketentraman umum dalam Onderafdeling ini segera pulih kembali.
157Ekspedisi Bumi Mandar
Penduduk kembali berinisiatif dan memberi bantuan sepenuhnya mencari gerombolan yang tidak disukai. Kepercayaan rakyat menjadi pulih kembali.
Juga dalam Onderafdeling Polewali, yaitu di Landschap Balanipa, dalam saat laporan ini telah diadakan aksi-aksi pembersihan. Satu bagian dari Special Troeppen terhadang di Kampung Talolo. Kampung ini sudah dua kali diperiksa tetapi tidak ada hasilnya.
Pada pembersihan yang terakhir pada saat sementara istirahat, troep ini menghadang di antar bukit-bukit menyebabkan Sersan Ockerse dan dua orang militer luka berat. Pada permulaan dari periode ini, militer masih harus bekerja keras untuk memberantas perampokan. Aksi pembersihan masih berjalan terus”.
Atas laporan rahasia di atas, Syaiful Sinrang memberi penjelasan. Maraqdia Matoa Majene yang ditangkap Belanda ialah Andi Abdul Rajab dan empat kepala disrik (Paqbicara) di Kerajaan Banggae, yang mau diganti oleh Belanda. Mereka adalah Aco Benya (Paqbicara Pangaliali), Tambaru (Paqbicara Banggae), Yusuf (Paqbicara Baru), dan Kambo (Paqbicara Totoli).
Dalam pembunuhan Controleur Polewali Monsees, turut serta seorang putra Majene GAPRI 5/3/1 bernama I Bengga bekerjasama dengan La Pangin anak buah dari Datu Suppa Andi Abdullah Bau Massepe. Rante yang dimaksud Belanda sebagai tempat pelarian rombongan inti dari pasukan Hamma Saleh adalah kampung Ratte di Distrik Adolang.
Westerling, si Turki
“Semua keluarga menangis. Pikir kakekmu meninggal. Sewaktu 1 Februari 1947 itu, tembakan sayup-sayup terdengar sampai ke
158 Muhammad Ridwan Alimuddin
Tinambung. Ketakutan menghantui. Syukurlah, kakekmu datang. Dia berhasil lari saat tembakan diberondong. Tapi sayang, Tali’be, adik nenekmu tewas pada kejadian itu.”
Demikian cerita ibu saya tentang “Panyapuang” di Galung Lombok. Dia masih kecil waktu itu, tapi dia sudah bisa mengingat atau sadar akan kejadian paling suram di tanah Mandar di zaman kemerdekaan. Cerita demikian juga bisa didengar dari orang-orang tua di Tinambung, Lawarang hingga Baruga Majene.
Orang yang paling dianggap bertanggung jawab pada peristiwa Galung Lombok adalah Westerling. Hampir semua orang-orang tua di Tinambung pernah dengar nama itu. Tapi apakah Westerling secara fisik ada di Galung Lombok pas kejadian? “Westerling tidak ada, dia diwakili anak buahnya,” demikian pendapat Thalib Banru, mantan pegawai Badan Arsip Nasional di Makassar. Berikut riwayat singkat Westerling, sebagaimana dikutip dari ensiklopedia Wikipedia dan sumber-sumber lain.
Nama lengkapnya Raymond Pierre Paul Westerling. Lahir di Istanbul, Turki Utsmani, 31 Agustus 1919 dan meninggal (karena jantung) di Purmerend, Belanda, 26 November 1987 pada umur 68 tahun.
Westerling lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling (Belanda) dan Sophia Moutzou (Yunani). Orangtuanya adalah pasangan pedagang karpet. Ketika berusia 5 tahun, kedua orang tuanya meninggalkan Westerling. Anak tak bahagia itu lalu hidup di panti asuhan. Tempat itulah mungkin yang membentuk dirinya menjadi orang yang tidak bergantung dan terikat pada siapa pun.
Westerling, yang dijuluki “si Turki” (De Turk) karena lahir di Istanbul, Turki. Pasukannya juga disebut demikian, “si Turki”, tapi
159Ekspedisi Bumi Mandar
di Sulawesi Selatan menjadi “Pasukan Westerling”. Sebab memiliki darah Turki (negara yang banyak penduduk muslimnya), ia dapat leluasa mengaku sebagai orang Islam dan berpengaruh terhadap hubungannya dengan gerakan DI di Jawa Barat.
Westerling yang sudah tertarik pada buku-buku perang sejak masih belia menemukan kesempatan untuk jadi tentara ketika Perang Dunia pecah. Desember 1940, ia datang ke Konsulat Belanda di Istanbul. Westerling menawarkan diri menjadi sukarelawan. Ia diterima.
Tapi untuk itu, sebelumnya ia harus bergabung dengan pasukan Australia. Bersama kesatuannya, Westerling ikut angkat senjata di Mesir dan Palestina. Dua bulan kemudian ia dikirim ke Inggris dengan kapal. Ia menyelinap menuju Kanada, melaporkan diri ke Tangsi Ratu Juliana, di Sratford, Ontario. Di situlah ia belajar berbahasa Belanda.
Masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Commando Basic Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni.
Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Pelatihan di tempat tersebut merupakan neraka di dunia. Pelatihan dan pelajaran yang mereka peroleh antara lain perkelahian tangan kosong, penembakan tersembunyi, berkelahi dan membunuh tanpa senjata api, dan sebagainya.
Spesialisasi Westerling adalah sabotase dan peledakan. Ia pun mendapat baret merah dari SAS (The Special Air Service), pasukan
160 Muhammad Ridwan Alimuddin
khusus Inggris yang terkenal. Dan yang membanggakannya, ia pernah bekerja di dinas rahasia Belanda di London, pernah menjadi pengawal pribadi Lord Mountbatten, dan menjadi instruktur pasukan Belanda—untuk latihan bertempur tanpa senjata dan membunuh tanpa bersuara. Tapi ia pun pernah dipekerjakan di dapur sebagai pengupas kentang.
Setelah bertugas di Eastbourne sejak 31 Mei 1943, bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya pada 15 Desember 1943 Westerling ke India untuk betugas di bawah Laksamana Madya Mountbatten Panglima South East Asia Command (Komando Asia Tenggara). Tiba di India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan di Kedgaon, 60 km di utara kota Poona.
Tahun 1944, Inggris menerjunkannya ke Belgia. Dari situ ia bergerak ke Belanda Selatan. Menurut buku De Zuid-Celebes Affairs, di Belgia itulah ia kali pertama merasakan perang sesungguhnya. Tapi, menurut Westerling sendiri, dalam Westerling, ‘De Eenling’ (Westerling, Si Penyendiri), perkenalan pertamanya dengan perang terjadi di hutan-hutan Burma.
Berkilau agaknya prestasi militer Westerling. Tapi entah mengapa ia meninggalkan satuannya, pasukan elit Inggris, dan masuk menjadi anggota KNIL. Ia lalu terpilih masuk dalam pasukan gabungan Belanda-Inggris di Kolombo. Pada September 1945, bersama beberapa pasukan, Westerling diterjunkan ke Medan, Sumatera Utara. Tujuannya, menyerbu kamp konsentrasi Jepang Siringo-ringo di Deli, dan membebaskan pasukan pro- Belanda yang ditawan. Ia berhasil.
Sebulan kemudian tentara Inggris mendarat di Sumatera Utara, dan entah bagaimana Westerling bergabung dengan
161Ekspedisi Bumi Mandar
pasukan ini. Tugasnya, melakukan kontraspionase, demikian kata buku Westerling, De Eenling. Itu makanya di Medan ia mengkoordinir orang-orang Cina, membentuk pasukan teror Poh An Tui (PAT). Pertengahan tahun 1946, ia dikirim ke Jakarta.
Di KNIL, karier militer Westerling menanjak cepat. Mulanya, ia hanya seorang instruktur. Tak lama, pada usia 27 tahun, 20 Juli 1946, Letnan Satu Westerling diangkat sebagai Komandan Depot Speciale Troepen (DST), Pasukan Para Khusus Belanda. Pasukan inilah yang ditugaskan ke Makassar, untuk membantu Kolonel De Vries mempertahankan kekuasaan Belanda. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan.
Pada 9 November 1946, Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Dirk Cornelis Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara di Jakarta. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia.
Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Itulah sebabnya Westerling memiliki keleluasaan melakukan eksekusi di tempat, tanpa pengadilan resmi.
Dengan keberhasilan menumpas para ekstrimis, di kalangan Belanda baik militer mau pun sipil reputasi Pasukan Khusus DST
162 Muhammad Ridwan Alimuddin
dan komandannya, Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke Markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita: “Pasukan si Turki kembali.” Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947.
Kamp DST kemudian dipindahkan ke Kalibata, dan setelah itu, karena dianggap sudah terlalu sempit, selanjutnya dipindahkan ke Batujajar dekat Cimahi. Pada bulan Oktober 1947 dilakukan reorganisasi di tubuh DST dan komposisi Pasukan Khusus tersebut kemudian terdiri dari 2 perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL (Koninklijke Leger), 24 bintara KNIL, 13 bintara KL, 245 serdadu KNIL dan 59 serdadu KL. Pada tanggal 5 Januari 1948, nama DST dirubah menjadi Korps Speciale Troepen – KST (Korps Pasukan Khusus) dan kemudian juga memiliki unit parasutis. Westerling memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya menjadi Kapten.
Setelah Persetujuan Renville, anggota pasukan KST ditugaskan juga untuk melakukan patroli dan pembersihan, antara lain di Jawa Barat. Namun sama seperti di Sulawesi Selatan, banyak anak buah Westerling melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk di Jawa Barat. Perbuatan ini telah menimbulkan protes di kalangan tentara KL (Koninklijke Leger) dari Belanda, yang semuanya terdiri dari pemuda wajib militer dan sukarelawan Belanda.
Westerling Bersekongkol dengan Darul Islam
Pada 17 April 1948, Mayor KL R.F. Schill, komandan pasukan 1-11 RI di Tasikmalaya, membuat laporan kepada atasannya, Kolonel
163Ekspedisi Bumi Mandar
KL M.H.P.J. Paulissen di mana Schill mengadukan ulah pasukan elit KST (Korps Speciaale Troepen) yang dilakukan pada 13 dan 16 April 1948. Di dua tempat di Tasikmalaya dan Ciamis, pasukan KST telah membantai 10 orang penduduk tanpa alasan yang jelas, dan kemudian mayat mereka dibiarkan tergeletak di tengah jalan.
Pengaduan ini mengakibatkan dilakukannya penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Westerling. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian mencuat ke permukaan. Di samping pembunuhan sewenang-wenang, juga terjadi kemerosotan disiplin dan moral di tubuh pasukan elit KST. Kritik tajam mulai berdatangan dan pers menuding Westerling telah menggunakan metode Gestapo (Geheime Staatspolizei), polisi rahasia Jerman yang terkenal kekejamannya semasa Hitler, dan hal-hal ini membuat para petinggi tentara Belanda menjadi gerah.
Walaupun Jenderal Spoor sendiri sangat menyenangi Westerling, namun untuk menghindari pengusutan lebih lanjut serta kemungkinan tuntutan ke pangadilan militer, Spoor memilih untuk menon-aktifkan Westerling. Pada 16 November 1948, setelah duasetengah tahun memimpin pasukan khusus Depot Speciaale Troepen (DST) kemudian KST, Westerling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliteran. Penggantinya sebagai komandan KST adalah Letnan Kolonel KNIL W.C.A. van Beek. Setelah pemecatan atas dirinya, Westerling menikahi pacarnya dan menjadi pengusaha di Pacet, Jawa Barat.
Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan
164 Muhammad Ridwan Alimuddin
yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah “Ratu Adil Persatuan Indonesia” (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan “Angkatan Perang Ratu Adil” (APRA).
Westerling tetap aktif menjaga hubungan dengan bekas anak buahnya dan menjalin hubungan dengan kelompok Darul Islam di Jawa Barat. Secara diam-diam ia membangun basis kekuatan bersenjata akan digunakan untuk memukul Republik Indonesia, yang direalisasikannya pada 23 Januari 1950, dalam usaha yang dikenal sebagai “Kudeta 23 Januari”. Secara membabi buta Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, dan tak ada korban di pihak APRA.
Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, tentu menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional.
Sejak kegagalan tanggal 23 Januari, Westerling bersembunyi di Jakarta, dan mendatangkan istri dan anak-anaknya ke Jakarta. Dia selalu berpindah-pindah tempat, antara lain di Kebon Sirih 62A, pada keluarga De Nijs.
Pada 8 Februari 1950 istri Westerling menemui Mayor Jenderal Van Langen, yang menjabat sebagai Kepala Staf, di rumah kediamannya. Isteri Westerling menyampaikan kepada van Langen mengenai situasi yang dihadapi oleh suaminya. Hari itu
165Ekspedisi Bumi Mandar
juga van Langen menghubungi Jend. Dirk Cornelis Buurman van Vreeden, Hirschfeld dan Mr. W.H. Andreae Fockema, Sekretaris Negara Kabinet Belanda yang juga sedang berada di Jakarta. Pokok pembicaraan adalah masalah penyelamatan Westerling, yang di mata banyak orang Belanda adalah seorang pahlawan.
Dipertimbangkan antara lain untuk membawa Westerling ke Papua bagian barat. Namun sehari setelah itu, pada 9 Februari Hatta menyatakan, bahwa apabila pihak Belanda berhasil menangkap Westerling, pihak Republik akan mengajukan tuntutan agar Westerling diserahkan kepada pihak Indonesia. Hirschfeld melihat bahwa mereka tidak mungkin menolong Westerling karena apabila hal ini terungkap, akan sangat memalukan Pemerintah Belanda. Oleh karena itu ia menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda untuk mengurungkan rencana menyelamatkan Weterling.
Namun tanpa sepengetahuan Hirschfeld, pada 10 Februari Mayor Jenderal Van Langen memerintahkan Kepala Intelijen Staf Umum, Mayor F. van der Veen untuk menghubungi Westerling dan menyusun perencanaan untuk pelariannya dari Indonesia. Dengan bantuan LetKol. Johannes Josephus Franciscus Borghouts–pengganti Westerling sebagai komandan pasukan elit KST–pada 16 Februari di mess perwira tempat kediaman Ajudan KL H.J. van Bessem di Kebon Sirih 66 berlangsung pertemuan dengan Westerling, di mana Westerling saat itu bersembunyi. Borghouts melaporkan pertemuan tersebut kepada Letkol KNIL Pereira, perwira pada Staf Umum, yang kemudian meneruskan hasil pertemuan ini kepada MayJend. Van Langen.
Westerling pindah tempat persembunyian lagi dan menumpang selama beberapa hari di tempat Sersan Mayor KNIL
166 Muhammad Ridwan Alimuddin
L.A. Savalle, yang kemudian melaporkan kepada May. Van der Veen. Van der Veen sendiri kemudian melapor kepada Jenderal van Langen dan Jend. Buurman van Vreeden, Panglima tertinggi Tentara Belanda. Dan selanjutnya, Van Vreeden sendiri yang menyampaikan perkembangan ini kepada Sekretaris Negara Andreae Fockema. Dengan demikian, kecuali Hirschfeld, Komisaris Tinggi Belanda, seluruh jajaran tertinggi Belanda yang ada di Jakarta baik militer maupun sipil mengetahui dan ikut terlibat dalam konspirasi menyembunyikan Westerling dan rencana pelariannya dari Indonesia. Andreae Fockema menyatakan, bahwa dia akan mengambil alih seluruh tanggung jawab.
Pada 17 Februari Letkol Borghouts dan Mayor Van der Veen ditugaskan untuk menyusun rencana evakuasi. Disiapkan rencana untuk membawa Westerling keluar Indonesia dengan pesawat Catalina milik “Marineluchtvaartdienst - MLD” (Dinas Penerbangan Angkatan Laut) yang berada di bawah wewenang Vice Admiral J.W. Kist. Rencana ini disetujui oleh Van Langen dan hari itu juga Westerling diberitahu mengenai rencana ini.
Van der Veen membicarakan rincian lebih lanjut dengan Van Langen mengenai kebutuhan uang, perahu karet dan paspor palsu. Pada 18 Februari van Langen menyampaikan hal ini kepada Jenderal van Vreeden. Van der Veen menghubungi Kapten (Laut) P. Vroon, Kepala MLD dan menyampaikan rencana tersebut. Vroon menyampaikan kepada Admiral Kist, bahwa ada permintaan dari pihak KNIL untuk menggunakan Catalina untuk suatu tugas khusus.
Kist memberi persetujuannya, walau pun saat itu dia tidak diberi tahu penggunaan sesungguhnya. Jend. Van Langen dalam suratnya kepada Admiral Kist hanya menjelaskan, bahwa diperlukan
167Ekspedisi Bumi Mandar
satu pesawat Catalina untuk kunjungan seorang perwira tinggi ke kepulauan Riau. Tak sepatah kata pun mengenai Westerling. Selanjutnya dibuatkan paspor palsu di kantor Komisaris Tinggi (tanpa laporan resmi). Nama yang tertera dalam paspor adalah Willem Ruitenbeek, lahir di Manila.
Pada hari Rabu tanggal 22 Februari, satu bulan setelah “kudeta” yang gagal, Westerling yang mengenakan seragam Sersan KNIL, dijemput oleh Van der Veen dan dibawa dengan mobil ke pangkalan MLD di Pelabuhan Tanjung Priok. Pesawat Catalina hanya singgah di Tanjung Pinang dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Singapura. Mereka tiba di perairan Singapura menjelang petang hari. Kira-kira satu kilometer dari pantai Singapura pesawat mendarat di laut dan perahu karet diturunkan.
Dalam bukunya De Eenling, Westerling memaparkan, bahwa perahu karetnya ternyata bocor dan kemasukan air. Beruntung dia diselamatkan oleh satu kapal penangkap ikan Tiongkok yang membawanya ke Singapura. Setibanya di Singapura, dia segera menghubungi teman Tionghoanya Chia Piet Kay, yang pernah membantu ketika membeli persenjataan untuk Pao An Tui. Dia segera membuat perencanaan untuk kembali ke Indonesia.
Pada 24 Februari kantor berita Perancis Agence France Presse memberitakan bahwa Westerling telah dibawa oleh militer Belanda dengan pesawat Catalina dari MLD ke Singapura. Setelah itu pemberitaan mengenai pelarian Westerling ke Singapura muncul di majalah mingguan Amerika, Life.
Pada 26 Februari 1950 ketika berada di tempat Chia Piet Kay, Westerling digerebeg dan ditangkap oleh polisi Inggris kemudian
168 Muhammad Ridwan Alimuddin
dijebloskan ke penjara Changi. Sebelumnya, pada 20 Februari ketika Westerling masih di Jakarta, Laming, seorang wartawan dari Reuters, mengirim telegram ke London dan memberitakan bahwa Westerling dalam perjalanan menuju Singapura, untuk kemudian akan melanjutkan ke Eropa.
Westerling, Mati Karena Lalunya Diungkit-ungkit
Pemberitaan di media massa sangat memukul dan memalukan pimpinan sipil dan militer Belanda di Indonesia. Kabinet RIS membanjiri Komisaris Tinggi Belanda Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan. Hirschfeld sendiri semula tidak mempercayai berita media massa, sedangkan Jend. Buurman van Vreeden dan Jend. Van Langen menyangkal bahwa mereka mengetahui mengenai bantuan pimpinan militer Belanda kepada Westerling untuk melarikan diri ke Singapura.
25 Februari Hirschfeld menyadari bahwa semua pemberitaan itu betul dan ternyata hanya dia dan Admiral Kist yang tidak diberitahu oleh Van Vreeden, Van Langen dan Fockema mengenai adanya konspirasi Belanda untuk menyelamatkan Westerling dari penagkapan oleh pihak Indonesia.
Fockema segera menyatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab dan menyampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, bahwa Hirschfeld sama sekali tidak mengetahui mengenai hal ini. Menurut sinyalemen Moor, sejak skandal yang sangat memalukan Pemerintah Belanda tersebut terbongkar, hubungan antara Hirschfeld dengan pimpinan tertinggi militer Belanda di Indonesia mencapai titik nol.
169Ekspedisi Bumi Mandar
Setelah mendengar bahwa Westerling telah ditangkap oleh Polisi Inggris di Singapura, Pemerintah RIS mengajukan permintaan kepada otoritas di Singapura agar Westerling diekstradisi ke Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang Pengadilan Tinggi di Singapura, Hakim Evans memutuskan, bahwa Westerling sebagai warganegara Belanda tidak dapat diekstradisi ke Indonesia.
Sebelumnya, sidang kabinet Belanda pada 7 Agustus telah memutuskan, bahwa setibanya di Belanda, Westerling akan segera ditahan. Pada 21 Agustus, Westerling meninggalkan Singapura sebagai orang bebas dengan menumpang pesawat Australia Quantas dan ditemani oleh Konsul Jenderal Belanda untuk Singapura, Mr. R. van der Gaag, seorang pendukung Westerling.
Westerling sendiri ternyata tidak langsung dibawa ke Belanda, namun –dengan izin van der Gaag- dia turun di Brussel, Belgia. Dia segera dikunjungi oleh wakil-wakil orang Ambon dari Den Haag, yang mendirikan “Stichting Door de Eeuwen Trouw - DDET” (Yayasan Kesetiaan Abadi). Mereka merencanakan untuk kembali ke Maluku untuk menggerakkan pemberontakan di sana. Di negeri Belanda sendiri secara in absentia Westerling menjadi orang yang paling disanjung.
Awal April 1952, secara diam-diam Westerling masuk ke Belanda. Keberadaannya tidak dapat disembunyikan dan segera diketahui, dan pada 16 April Westerling ditangkap di rumah Graaf A.S.H. van Rechteren. Mendengar berita penangkapan Westerling di Belanda, pada 12 Mei 1952 Komisaris Tinggi Indonesia di Belanda Susanto meminta agar Westerling diekstradisi ke Indonesia, namun ditolak oleh Pemerintah Belanda, dan bahkan sehari setelah permintaan ekstradisi itu, pada 13 Mei Westerling dibebaskan dari
170 Muhammad Ridwan Alimuddin
tahanan. Putusan Mahkamah Agung Belanda pada 31 Oktober 1952, menyatakan bahwa Westerling adalah warganegara Belanda sehingga tidak akan diekstradisi ke Indonesia.
Setelah keluar dari tahanan, Westerling sering diminta untuk berbicara dalam berbagai pertemuan, yang selalu dipadati pemujanya. Dalam satu pertemuan dia ditanya, mengapa Sukarno tidak ditembak saja. Westerling menjawab, “Orang Belanda sangat perhitungan, satu peluru harganya 35 sen, Sukarno harganya tidak sampai 5 sen, berarti rugi 30 sen yang tak dapat dipertanggungjawabkan.” Beberapa hari kemudian, Komisaris Tinggi Indonesia memprotes kepada kabinet Belanda atas penghinaan tersebut.
Pada 17 Desember 1954 Westerling dipanggil menghadap pejabat kehakiman di Amsterdam di mana disampaikan kepadanya, bahwa pemeriksaan telah berakhir dan tidak terdapat alasan untuk pengusutan lebih lanjut. Pada 4 Januari 1955 Westerling menerima pernyataan tersebut secara tertulis.
Westerling kemudian menulis dua buku, yaitu otobiografinya Memoires yang terbit tahun 1952, dan De Eenling yang terbit tahun 1982. Buku Memoires diterjemahkan ke bahasa Prancis, Jerman dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Terror sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counter insurgency dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia dan Afrika.
Mati di tempat tidur
Nasibnya di luar medan perang bisa dibilang buruk. Ia mencoba bergerak di bidang percetakan, gagal. Pernah juga ia
171Ekspedisi Bumi Mandar
mencoba menjadi penyanyi opera, belajar menyanyi di Jerman, gagal lagi.
“Saya jual buku saja,” katanya suatu ketika. Dan akhirnya memang ia hidup sebagai pedagang buku bekas. Westerling nyaris terjun ke kancah perang lagi. Ia sempat membikin dua memorandum yang isinya mendorong agar Eropa (termasuk Belanda) berperang menghadapi Vietkong. Tak ada yang menanggapi. Menjelang perebutan Da Nang, Juli 1965, seseorang menghubunginya, menawarinya melatih pasukan Vietkong. Kabarnya, Westerling hampir berangkat bila tidak dicegah pemerintah Belanda.
Westerling memang khas tentara bayaran. Ia tampaknya tak pernah berpikir untuk siapa dan untuk apa dia menembak. Hingga saat-saat terakhirnya, sejauh diketahui, Westerling belum pernah mengaku bersalah atas terornya di Indonesia. Yang dilakukannya, katanya, adalah melindungi rakyat.
Si jagoan Kaptein de Turk (julukannya karena ia berdarah Turki) akhirnya ‘ditaklukkan’ bukan di medan perang, tapi di medan ilmu. Sejarawan De Jong melalui bukunya membuka kembali masa lalu De Turk, dan membuat penyakit jantungnya kambuh. Gara-gara masa lalunya diungkit-ungkit, Westerling meninggal dengan tenang tahun 1987.
174 Muhammad Ridwan Alimuddin
Makam korban Peristiwa Galung LombokGerbang masuk Taman Makam Pahlawan Korban 40000 Jiwa di Galung LombokTugu TMP Galung LombokDaftar nama-nama korban Peristiwa Galung LombokDaftar nama korban pembantaian di Galung Lombok dan tampak dari belakang monumenSalah satu saksi mata peristiwa Galung Lombok berdiri di depan daftar nama korbanBatara Hutagalung bersama saksi mata dan ahli waris peristiwa pembantaian di Galung LombokBatara Hutagalung memberi sambutanWesterlingSampul buku tentang Westerling
9
10 11
175
KEANGGUNAN BUNGGU
Tabuhan Musik Terpanjang Diiringi Ayunan Parang
Persis jam enam sore. Gendang, yang disebut “gimbal” dalam bahasa Kaili, berdiameter 30cm yang menjadi pusat ritual
sedang ditabuh-tabuh dua anak kecil. Umur tiga tahun. Pikir saya akan non-stop sampai tengah malam, ternyata tidak. Walau demikian, baru pertama kali saya menyaksikan pertunjukan musik terpanjang. Dari tengah hari, sekitar jam sebelas siang hingga petang. Lebih enam jam!
Menariknya, kalau tidak dikatakan membosankan, irama tabuhan itu-itu saja. Hampir tak ada irama. Jadi bayangkan saja mendengar musik irama monoton berjam-jam. Sekali lagi saya katakan, meski demikian, inilah “performance” pertama dalam musik dan tarian yang pernah saya saksikan betul-betul murni. Yaitu pertunjukan sebagai ritual, bukan “show” atau pementasan yang dibuat-buat. Amat mengesankan.
Ya, pertunjukan hanya di lapangan kecil, seluas lapangan bulutangkis di tanah kuning kering; berpusat pada “gimbal” kecil yang digantung di menara kecil setinggi satu meter tapi “panggung-nya” amat luas. Mencakup jalan, lorong (samping antar) rumah, dan bawah rimbun pohon.
176 Muhammad Ridwan Alimuddin
“Gimbal” dipukul bertalu-talu oleh dua orang, masing-masing satu sisi. Pemukul dikeliling beberapa penonton. Musil ritmik itu mengundang penari-penari yang tiba-tiba muncul. Entah dari mana datangnya. Satu persatu wanita mengayun-ayunkan sarung (selendang) atau “kain bali” melangkah sambil menari ke arah sumber bunyi.
Saat tiba, dengan tetap bergerak dengan gaya-gerak tarian yang “amat bersahaja” mengelilingi pemukul “gimbal” searah jarum jam. Beberapa wanita tua melakukan itu bermenit-menit. Ada sampai setengah jam. Tanpa lelah. Sama seperti irama musiknya, gerakan tariannya juga itu-itu saja.
Di satu sisi itu adalah daya tarik, sebab di luar arus utama (mainstream) gerakan tari kontemporer. Di sisi lain, di mata awam akan membosankan. Harus disadari, begitulah ciri tarian ritual. Seperti mantra yang kata-katanya berulang.
“Auuu ... Auuu ... Auuu”, tiba-tiba ada teriakan laksana lolongan jauh di sana. Diikuti teriakan penonton dengan bunyi sama. Beberapa orang mendongakkan kepala berlomba melihat asal suara itu. Sebagian penonton pada berlarian. Ada yang datang mengayun-ayunkan parang panjang dengan mata tajam. Seakan akan melibas siapa pun yang akan menghalanginya. Bukan satu orang, tapi beberapa, dari berbagai arah.
***
Senin, 4 Juni 2012, bersama teman wartawan Radar Sulbar di Pasangkayu, A Safrin Mahyuddin, saya menuju Ngovi. Saat saya tiba di Pasangkayu beberapa hari lalu, ada kabar akan ada upacara yang akan dilangsungkan masyarakat adat di pedalaman. Sebab acara tersebut langka dan memang saya mencitakan untuk
177Ekspedisi Bumi Mandar
“hunting” kebudayaan mereka, rencana kepulangan ke Mamuju ditunda. Saya harus menyaksikan acara tersebut.
Masalahnya, keberangkatan ke Pasangkayu tidak ada persiapan untuk riset atau liputan ke pedalaman. Untung masih ada waktu, saya meminta ke istriku di Pambusuang untuk menyiapkan paket yang isinya GPS, sepatu gunung, jaket, dan lembaran peta yang mencakup kawasan pedalaman Pasangkayu - Donggala. Permintaan itu bisa terpenuhi dan segera tiba di Pasangkayu keesokan harinya sebab dikirim lewat oto Radar Sulbar yang membawa koran dari percetakan.
Singkat cerita, permintaan tersebut tiba sehingga modal utama ke lapangan telah ada. Kamera dan perangkat lensa juga sudah ada. Saya bawa lebih awal sebab digunakan dalam acara pelatihan fotografi untuk awak humas di lingkungan SKPD Kabupaten Mamuju Utara.
Kami menggunakan motor Honda MegaPro rarna kuning. Platnya merah. Menurut teman, itu motor salah satu SKPD di Matra. Dalam hati saya berterima kasih pada SKPD tersebut. Saya tidak sebutkan juga di sini, nanti malah dimarahi bosnya sebab pinjamkan motor ke orang lain.
Berangkat dari Pasangkayu sekitar jam sepuluh siang. Untuk menuju pedalaman tempat upacara dilaksanakan, kami melalui Pasar Martajaya. Dari situ terus masuk, ke perkebunan sawit milik PT Pasangkayu - PT Astra. Sawitnya maha luas. Di beberapa tempat melewati kompleks perumahan pegawai perkebunan. Juga fasilitas untuk mereka, seperti TK dan SD serta fasilitas kesehatan.
Jalan beraspal hanya di awal-awal perjalanan. Di areal perkebunan sawit jalannya memang lebar, tapi hanya berupa
178 Muhammad Ridwan Alimuddin
sirtu (kerikil). Walau merupakan jalan sepi, tapi ada beberapa rambu lalu lintas serta papan-papan pengumuman supaya tidak membalap. Memang harus hati-hati menjalankan motor dengan kecepatan tinggi. Bisa-bisa terpeleset.
Beberapa kali motor stop untuk bertanya arah menuju Ngovi. Pusing juga mencari arah di perkebunan sawit. Jalannya seragam, banyak perempatan. Jalan bagai labirin. Membingungkan untuk menghafal jalan di areal perkebunan sawit. Untung saya membawa GPS, jadi rute terekam.
Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam, untuk jarak sekitar 33 km (berdasar data GPS) kami tiba di Ngovi. Saat tiba, Safrin agak sanksi apakah ini betul Ngovi, tempat pemukiman komunitas adat. Soalnya pemukimannya ada banyak bangunan atau rumah kayu. Ada pasar juga. Agar lebih pasti, kami bertanya ke pemilik warung yang kami singgahi. Betul, memang ini Ngovi. Betul akan ada upacara tahunan. Demikian info yang kami dapatkan.
Untuk lebih memastikan lagi, kami mencari rumah kepala desa. Letak rumah kepala desa tak jauh dari pasar. Hanya diantarai lapangan bola. Jauh di sana, sejauh mata memandang, hutan yang telah berubah menjadi kawasan perkebunan. Sawit masih kecil-kecil. Tampak bukit-bukit, yang jauh dibaliknya terdapat lembah Palu.
Rumah kepala desa rumah panggung. Bangunan dari papan dengan tiang dari batang kayu kecil. Bukan balok. Bentuk rumah agak membingunkan. Tidak tahu mana depan, mana teras. Ada tiga tangga yang kami lihat. Harus naik dari mana. Bagian utamanya bagai baruga, tapi letak lantainya jauh dari tanah. Dinding rumah setengah saja. Sepertinya rumah didesain terbuka. Bagus untuk sirkulasi udara.
179Ekspedisi Bumi Mandar
Perlahan kami naik di salah satu tangga yang terbuat dari batang-batang bambu. Di atas ada beberapa set kursi modern, memanjang di salah satu sisi rumah. Di atas, kami menanyakan keberadaan kepala desa. Anak muda yang menerima kami mengiyakan dan dia langsung masuk ke bagian rumah yang lain untuk memanggil kepala desa.
Sesaat kemudian, keluar sosok tua menghampiri kami. Dia mengenakan celana pendek coklat, tak mengenakan baju. Rambut tipis beruban. Bibir merah, gigi hitam, dan postur mata yang tajam.
Masyarakatnya Tak Primitif Lagi
Namanya Petrus Saliku. Kepala Desa Ngovi. “Saya menjabat kepala desa sudah lama, lebih 20 tahun,” kepala desa memperkenalkan diri. Ucapannya lancar, tapi tutur bahasa Indonesianya persis mirip orang asing yang berbahasa Indonesia.
“Dulu saya termasuk orang pertama dari saya yang bermukim di wilayah sini. Menuju ke tempat ini karena ini tanah nenek moyang. Waktu ke sini belum ada orang. Masih banyak monyet dan babi,” cerita pak Saliku kepada kami. Saya duduk di berseberangan dengannta (diantarai meja), sedang teman wartawan Radar Sulbar, Safrin duduk di samping kepala desa.
Kami ngobrol banyak dengan kepala desa, tapi saya belum melakukan wawancara khusus. Masih sebatas perkenalan dan untuk memastikan apakah betul akan ada upacara. Dia memastikan dan mengatakan upacara akan berlangsung beberapa hari. “Sebentar itu ada acara mattaro. Sekarang sedang dibuat gimba-nya. Ke sana saja nanti,” demikian informasi kepala desa, termasuk nama jenis alat musik yang digunakan.
180 Muhammad Ridwan Alimuddin
Betul apa yang disampaikan kepala desa. Saat kami masuk pusat desa, ada sekelompok pemuda sedang membangun menara kecil. Tak lama setelah pak desa menyampaikan informasi, sayup-sayup terdengar pukulan. Mirip gendang. Mungkin itu bunyi “gimba”.
Tak ingin awal-awal upacara terlewatkan, kami minta pamit dan berjanji untuk kembali menemuinya guna wawancara khusus.
Lokasi acara terletak di pinggir jalan. Ada lapangan kecil, lebih luas sedikit dari pada lapangan bulutangkis. Di lapangan kecil sudah ada bangunan konstruksi kecil nan sederhana, tepatnya tempat menggantung “gimba”. Di sudut atau puncak bangunan tersebut ada daun-daun. Mirip daun tanaman yang digunakan orang Mandar saat mengiringi rombongan calon mempelai di pernikahan. Yang digunakan “pa’ollong”. Kira-kira apa simbol penggunaan daun tersebut ya?
Sebab cuaca panas terik, saya dan penonton lain memilih menyaksikan acara di tempat yang terlindung dari panas. Ada di kolom rumah, bawah pohon, dan teras. Saya dan teman di warung, depan rumah penduduk. Kebetulan penjualnya orang Mandar dari Majene. Jadi bisa langsung akrab. Sama-sama perantau soalnya.
Dan mulailah saya mengamati dan mendokumentasikan ritual yang dilakukan komunitas adat Bunggu di Desa Ngovi. Menarik dan banyak hal baru yang saya saksikan.
***
Beberapa lelaki datang mengayunkan pedang. Saya yang tadinya sudah berada di dekat pemukul “gimba” untuk memotret jadi keder juga. Agak menjauh. Jangan sampai lelaki tersebut
181Ekspedisi Bumi Mandar
tiba-tiba mengayungkan parangnya kepada saya. Entah apa yang terjadi.
Bukan apa-apa. Sosok mata mereka sangat tajam, seperti orang marah. Melotot. Persis orang yang siap perang (berkelahi). Memang kepala desa mewanti-wanti kepada kami untuk tidak terlalu mendekat sebab jangan sampai para penari kerasukan.
Semakin lama semakin banyak lelaki datang mengayung-ayungkan parangnya. Dari berbagai arah. Penari wanita pun demikian halnya. Sarung batik atau kain bali mereka sebagai satu-satunya properti yang mereka gunakan dalam menari. Gerakannya itu-itu saja, tapi seakan tak bosan menyaksikannya.
Ada wanita dan lelaki tua yang sebelumnya saya lihat berjalan amat pelan begitu rentanya, saat menari menjadi kuat. Lincah, seperti wanita-wanita lain. Penonton juga semakin sering meneriakkan “Auuu … Auuu … Auuu”, apalagi kalau ada penari yang akan ikut bergabung. Ritual yang amat menarik, yang pertama kali saya lihat di Sulawesi Barat.
***
Mungkin upacara tahunan masyarakat Desa Ngovi dilaksanakan setiap tahun saat purnama. Dugaan itu muncul sebab semalam bulan purnama. Kecantikan purnama muncul kala akan tenggelam, di subuh hari. Agar pasti, dugaan tersebut harus dikonfirmasi pada tetua adat di sini.
Beberapa informan, pada pengumpulan informasi di hari pertama, mengatakan bahwa upacara digilir. Saat ini di Ngovi, nanti di tempat lain. Bulan depan. Jadi, sebagai tradisi tahunan agak lemah. Sekali lagi harus diricek.
182 Muhammad Ridwan Alimuddin
Sekarang hari kedua saya di Ngovi. Semalam tidur di warung dadakan yang dipasang oleh pedagang keturunan Majene. Mereke, dua keluarga, sudah lama tinggal di salah satu pemukiman dekat kebun sawit milik PT Pasangkayu. Sengaja datang ke Ngovi kemarin sebab ada upacara. Tapi itu agak mereka sesali sebab ternyata upacara tidak ramai; tidak banyak pembeli. Di hari-hari biasa, mereka hanya datang pada hari Selasa, sebagai hari pasar. Jadi kedatangan di hari Senin untuk kemudian bermalam adalah di luar kebiasaan.
Untung juga ada mereka, saya ada tempat bermalam. Bila bermalam di rumah penduduk di sini, kendala pertama adalah bahasa dan kedua makanan. Penduduk Ngovi mayoritas Kristen. Bila pun ada muslim, mereka pendatang khususnya orang Bugis. Beberapa toko kecil di sini milik orang Bugis. Untuk orang Mandar, hanya datang saat hari pasar. Juga ada rumah yang menandakan mereka orang Bali. Artinya ada juga Hindu di sini.
Seperti biasa, bila saya riset ke perkampungan yang di luar di kenal sebagai “suku terasing” atau suku yang “masih kuno”, harapan di benak untuk mendapati masyarakat yang sangat tradisional lebih dominan. Kekurangan berbenak begitu, ada kekecewaan bila realitas di lapangan tidaklah demikian.
Sebagaimana yang juga saya alami di Ngovi. Saat mendengar akan ada upacara untuk kemudian merencanakan menyaksikannya, saya membayangkan akan berada di tengah masyarakat yang masih “primitif”. Masih ada yang berbaju dari bahan kulit kayu, rumah-rumah unik, tak ada listrik, dan ciri kemoderenan lainnya. Apa yang saya imajikan itu ternyata beda.
183Ekspedisi Bumi Mandar
Bunggu Itu Suku Kaili?
Desa atau Kampung Ngovi hampir tak ada beda dengan kampung-kampung lain. Rumah panggung, rumah permanen, parabola, listrik (yang nyala saat malam, menggunakan gengset kecil), motor bersiliweran, mobil selalu ada, dan kostum mereka yang persis sama dengan masyarakat pantai.
Banyak yang punya “handphone” tapi untuk dengar musik saja. Signal bisa dikatakan tak ada walau di beberapa titik katanya ada. Hampir tak ada pembeda kecuali ada upacara/ritual yang kemarin terjadi.
Tapi sebagai peneliti, kekecewaan itu jangan dibawa-bawa terus. Tidak apa-apa di awal. Harus diakui, ini adalah realitas. Terlepas tak banyak kekunoan, apa yang dilihat, didengar, dirasakan itulah yang terjadi. Itulah ilmu, itulah pengetahuan. Setidaknya itu gambaran kondisi sosial masyarakat di pedalaman Pasangkayu - Donggala.
Sampai saat ini saya belum bisa mendefenisikan entitas (suku) masyarakat Ngovi. Apakah Suku Binggi atau Suku Kaili? Suku Kaili, salah satu suku yang cukup dikenal dalam kebudayaan (suku) Mandar. Malah ada lagu berbahasa Mandar yang syairnya, “Lambaq naung di Kaili” (Kuingin pergi ke Kaili).
Dalam benak orang Mandar, ada juga “stereotipe” (gambaran) bahwa wanita Kaili itu “bahaya”. Bahwa dengan melihat atau meliriknya saja, seorang lelaki akan langsung jatuh cinta. Entah betul atau tidak mitos tersebut. Yang jelas, saya tak mengalaminya di kampung ini.
Kesulitan utama sehingga tidak bisa mendefenisikan suku mereka adalah tidak-adanya pemahaman akan bahasa mereka.
184 Muhammad Ridwan Alimuddin
Tapi kendala ini tidak akan berjalan lama, saya optimis, bila wawancara 2-3 orang tetua di sini dan mencatat sampel kata/bahasa, mereka siapa bisa saya dapatkan.
Menurut hasil penelitian Charles E. Grimes, dalam publikasi ilmiahnya tentang bahasa-bahasa di Sulawesi, “Languanges of South Sulawesi”, bahasa Kaili digolongkan ke dalam Stok Sulawesi Tengah. Stok ini terbagi atas dua, yaitu Famili Kaili – Pamona (Topoiyo, Benggaulu, Bada, Bana [Uma, Pipikoro], Rampi atau Leboni, dan Pamona atau Bare’e yang terbagi atas Tomoni dan dialek lainnya di Sulawesi Tengah.
Kedua adalah Famili Bungku – Mori atau Bungku – Laki yang hanya mencakup satu yaitu Padoe (selatan Mori).
Khusus Kaili, ada subfamili-nya yang terbagi atas tiga yaitu Kaili (Ledo, Bunggu dan dialek lainnya), Baras, dan Sarudu.
Jelas masyarakat asli sini berbeda “ras” dengan masyarakat Sulawesi Barat yang di pantai. Masyarakat asli di sini perawakannya seperti orang Melanesia. Kulit hitam, rambut keriting-keriting kecil, perawakan tubuh kecil. Berbeda dengan Mongoloid. Dengan kata lain, saat saya berada di perkampung Ngovi, laksana saya berada di kampung-kampung tradisional di kawasan Nusa Tenggara Timur (saya pernah riset pulau-pulau kecil di NTT selama sebulan).
Tak salah bila saya menebak-nebak bahwa orang sini ada hubungan dengan orang-orang di kawasan timur Indonesia. Penelitian antropologi tentang masyarakat yang ada di pulau-pulau NTT dan selatan Maluku, yang juga ada dalam folklore setempat khususnya masyarakat Lamalera (pemburu paus), bahwa keturunan atau nenek moyang mereka berasal dari Sulawesi tepatnya Luwuk - Banggai (Pulau Sulawesi).
185Ekspedisi Bumi Mandar
Dengan kata lain, bahwa ada diaspora orang-orang yang pernah ada di Sulawesi, dalam hal ini kategori Melanesia. Untuk membuktikan hal tersebut harus dengan riset mendalam. Seperti menelusuri jalur migrasi di Pulau Sulawesi dari barat ke timur dan mencatat kode-kode DNA mereka (membandingkan DNA berkulit hitam, berambut keriting di Pulau Sulawesi dengan “kerabatnya” yang ada di pulau-pulau kawasan timur Indonesia).
***
Setengah empat sore. Hari kedua. “Gimba” masih talu-talu bunyinya, hampir empat jam. Seperti kemarin, tadi juga ada penari-penari. Kebanyakan wanita. Lelaki yang mengayungkan parang, kalau tidak salah ingat, hanya tiga orang.
Pikir tadi akan ada yang luar biasa, membedakannya dengan ritus kemarin. Soalnya ada api unggun dibakar di dekat lokasi “gimba”. Juga ada empat lembar daun pisang digelar di antara “gimba” dan api unggung. Wah, sepertinya akan ada ritual berjalan di atas bara api. Entah kenapa ritus itu tak jadi. Kabarnya akan dilakukan esok, menyambut pejabat-pejabat yang akan datang.
Yang menarik tadi, yang tidak ada kemarin, pemimpin upacara, saya lupa namanya, menyanyikan (mantra?) dekat “gimba” yang terus dipukul-pukul dua pemain. Sambil bernyanyi dalam bahasa Kaili, dia sesekali menyentuhkan tangannya ke kepala dua wanita tua yang jongkok di belakang pemukul “gimbal”. Saya tak mengerti apa yang dia ucapkan.
Selesai menyanyi, wanita yang jongkok tadi pindah dan tabuhan dihentikan beberapa lama. Pikir akan stop. Sekian menit kemudian, ada lagi yang melanjutkan tabuhan.
186 Muhammad Ridwan Alimuddin
Tetua atau pemimpin upacara posturnya renta. Bungkuk. Kumal. Bila di kota mungkin dianggap pengemis. Baju kaos kumal, celana pendek “celana pantainya” demikian juga. Tas kecil ada dipundaknya. Mengenakan topi. Wajah keriput dengan mata memerah tanda tua. Gigi hitam keropos karena efek sirih yang dia kunyah.
Kemarin, di hari pertama, saya melihatnya menari-nari. Awalnya tak mengaggap dia. Sesaat setelah dia menari, dia mendekati saya yang sedang duduk-duduk di warung. Mengamati saya. Saya senyum-senyum saja. Tak ada kata-kata. Lama kemudian, dia pindah. Beberapa kali saya menyaksikannya bolak-balik di jalan utama. Pelan sekali jalannya.
Perannya ternyata besar. Kemarin, saat ngobrol dengan seorang penduduk Ngovi, mengatakan bahwa orang tua itulah yang membuat “gimba”. Dia satu-satunya yang bisa. Kaget juga. Sesal sebab kemarin tidak menyapanya, saat mendekat ke saya. Dugaan saya, dia pasti dukun.
Dan tadi, saat kembali jalan bolak-balik, dengan langkah lemah, dia tersenyum ke saya. Saya membalasnya dan memanggil ke tenda warung tempat saya beristirahat. Saya tanya apakah dia bisa bahasa Indonesia. Jawabnya tidak. Hanya bisa Bahasa Bugis. Walau ditutur dalam bahasa Kaili, saya mengerti maksudnya.
Sayang, sebab saya tak bisa menggali banyak informasi darinya. Bukan apa-apa, saya tak mengerti dua bahasa (Kaili dan Bugis) tersebut. Saya pun menawarinya makanan dan minuman di warung tempat saya istirahat. Tapi dia ragu, katanya tak punya duit. Saya bilang nanti saya yang bayar. Dia gembira. Dia memilih minuman berwarna merah mirip Coca Cola. Minuman murahan yang dibuat lokal. Dia tambah gembira saat saya kasih rokok. Dia
187Ekspedisi Bumi Mandar
pun pulang, menuju rumah ketua adat. Membawa-bawa minuman ringannya. Tampak tangan ringkihnya kerepotan menusuk bagian atas gelas plastik. Itulah perkenalan saya dengannya, salah satu tokoh utama di komunitas adat Bunggu di Ngovi.
Ngovi, Daerah Kesekian yang Diabaikan Sulbar!
Menjelang jam enam sore, di hari kedua, buku “Meraba Indonesia”, ditulis Ahmad Yunus, diberikan oleh Ramon Y. Tungka ke saya, selesai dibaca. Jika tak ada perjalanan ini, ke kawasan ini, mungkin buku itu tak selesai-selesai dibaca. Dalihnya, sibuk beraktivitas.
Bukunya menarik dan penting bagi seorang traveler. Membacanya, seperti yang dikatakan Anis Baswedan di halaman awal buku tersebut, seakan kita berada di sana, di lokasi kejadian yang ditulis di dalam buku. Apalagi bila tempat tersebut pernah dikunjungi. Banyak tempat atau pengalaman yang dialami Ahmad Yunus dan Farid Gaban telah pernah saya kunjungi; datangi. Seperti pengalaman naik kapal Pelni, kapal perintis, berada di Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Tawau, Bira, Selayar, Kep. Taka Bonerate, berlayar ke Maumere hingga pulau-pulau kecil Nusantara yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, Kep. Togian dan Gorontalo.
Juga ada individu yang disinggung di dalam buku, mengenai sosok seorang pembuat perahu pinisi di Bira, juga saya kenal. Yakni H. Jafar. Ahmad Yunus tak menyebut namanya, tapi saya bisa pastikan yang dia maksud adalah H. Jafar sebab ciri-cirinya disebut: tangan kekar walau sudah tua, berkacamata, daun telinga yang besar tapi pendengaran sudah berkurang, dan bila berbicara agak keras.
188 Muhammad Ridwan Alimuddin
Beruntung buku traveling tersebut saya baca dikala saya sedang traveling juga. Bedanya, saya hanya beberapa hari, tapi Yunus Ahmad berbulan-bulan, hampir setahun. Saya katakan beruntung sebab beberapa kalimat atau kutipan yang dia tulis (dikutip dari buku lain) pas dengan apa yang saya alami.
Kesamaan sederhana apa yang dilakukan Ahmad Yunus (dan Farid Gaban) dengan saya adalah sama-sama melakukan perjalanan ke daerah perbatasan. Bila mereka berdua ke daerah Indonesia (negara) paling pinggir, maka saya ke daerah Sulawesi Barat (provinsi) yang juga di pinggiran. Hasilnya, kami sama-sama menyaksikan kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan.
***
Siapapun yang ada di Desa Ngovi, pikirnya akan berada di daerah administrasi Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukan apa-apa, papan nomor rumah, baliho pilkada, papan nama kantor desa semuanya ada tulisan Kabupaten Donggala atau Kecamatan Rio Pakava. Tapi apakah betul bahwa Desa Ngovi dan sekitarnya masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah?
Salah satu alat utama saya saat riset lapangan adalah peta rupabumi dan GPS (Global Positioning System). Dua sejoli alat tersebut amat sangat membantu. Ringkasnya begini. Bila saya ke lokasi tertentu, dalam kasus ini Desa Ngovi, maka secara otomatis GPS akan merekam titik koordinatnya. Setiap langkah, di mana saya berada akan dicatat oleh GPS. Rute perjalanan dari Pasangkayu ke Desa Ngovi secara akurat tercatat. Detik demi detik, meter demi meter.
Data koordinat tersebut saya masukan ke peta rupabumi, khususnya lembar peta nomor 2014-63, berjudul Gimpubia (salah
189Ekspedisi Bumi Mandar
satu nama tempat di dalam peta), skala 1 : 50.000. Angka koordinat yang diperoleh, dengan sampel lapangan bola Desa Ngovi yang dekat dengan rumah kepala desa, adalah 01 11 167” LS dan 119 32 399” BT. Titik koordinat tersebut, secara garis lurus, berjarak sekitar 20km dari kota Pasangkayu (barat ke timur).
Nah, yang mengagetkan, bila berdasar pada peta rupabumi di atas yang resmi dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional), terbit tahun 1991, titik tersebut masih berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (waktu itu; sekarang masuk wilayah Provinsi Sulawes Barat).
Mungkin tidak menjadi masalah besar bila “penyimpangannya” hanya beberapa meter, sebab mungkin saja itu kekurang-akuratan GPS. Tapi “penyimpangannya” sampai 5 km dari garis yang menunjukkan batas dua provinsi!
Artinya, Kabupaten Donggala “mengambil” daerah Sulawesi Barat beberapa puluh kilometer persegi. Sekedar catatan, saya mengandalkan angka atau koordinat GPS untuk merujuk tempat sebab di peta tidak ada tempat yang bernama Ngovi.
Untuk memastikan data koordinat yang diberikan oleh GPS tersebut benar, GPS saya kalibrasi dengan kamera saya yang mempunyai fasilitas GPS. Angka yang diberikan relatif sama. Penyimpangan tidak sampai puluhan meter. Untuk memastikan lagi, saya cek koordinat kediaman di Pambusuang dengan di peta, juga sesuai. Singkat kata, bukan GPS yang mengalami penyimpangan begitu besar, tapi sistem administrasi perbatasan dua provinsi, antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat. Tak beres.
Saat ini, bila berdasar situasi administrasi di lapangan, Desa Ngovi masuk wilayah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala,
190 Muhammad Ridwan Alimuddin
Provinsi Sulawesi Tengah. Nama kecamatan tersebut berdasar pada dua nama sungai yang berada di pedalaman, yaitu Sungai Rio dan Sungai Pakava. Yang mana gabungan dua sungai tersebut membentuk satu sungai besar, yakni Sungai Pasangkayu.
Kecamatan Rio Pakava setidaknya dibentuk setelah tahun 1999. Itu saya dasarkan atas adanya Surat Pernyataan Sikap Masyarakat “Ngowi/Bonemarava - Bambalamotu” terhadap pemerintah yang menginginkan menjadi kecamatan sendiri dan menjadi bagian dari Kabupaten Donggala.
Saya pribadi tak begitu menyalahkan Provinsi Sulawesi Tengah. Sengaja atau tidak disengaja, itu “sah-sah” saja sebagai teknik mengkooptasi wilayah lain. yang tidak beres adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara. Koq “dia” tidak tahu mana wilayahnya? Ketidaktahuan itu diwujudkan dalam ketidakpedulian. Baik itu penguatan batas-batas wilayahnya (dalam aturan tertulis) maupun perhatian terhadap daerah-daerah di perbatasan.
Kawasan Ngovi adalah kekayaan kita (Sulawesi Barat). Walau masyarakatnya masih amat tradisional dan cenderung tertinggal dari saudara-saudaranya di pesisir, bagaimana pun juga itu adalah rakyat Sulawesi Barat. Saat ini mereka seakan berada pada ketidakpastian. Misalnya untuk mengurus sertifikat tanah. Kabarnya, baik Pemkab Donggala maupun Pemkab Mamuju Utara sama-sama tak berani. Koq Pemkab Matra tak berani padahal amat jelas itu wilayahnya?
Untuk mengurus dokumen resmi pun masyarakat tahunya harus diurus di ibukota Kabupaten Donggala (sebab mereka pikir mereka masuk Donggala, sebagaimana tertulis di nomor rumah mereka). Ke Donggala jauhnya bukan main. Kalau ke Pasangkayu cuma 30an km, tapi ke Donggala lebih 100 km.
191Ekspedisi Bumi Mandar
Saya berandai-andai saja. Bila di Desa Ngovi ditemukan sumber tambang baik itu gas, minyak, emas atau apa saja yang bisa membuat orang kaya, maka serta merta pemerintah Sulawesi Barat baru akan panik. Untuk kemudian mengklaim itu wilayahnya. Sebagaimana kasus yang menimpa Pulau Lerelerekang. Parah memang kalau begini sikap pemerintah kita.
Mengenai keinginan atau sikap masyarakat Desa Ngovi tentang di mana mereka mau berada (apakah Sulawesi Tengah atau Sulawesi Barat), akan saya bahas di salah satu seri tulisan mendatang.
Mantap, Tari Dero Diiringi “House Music”
Malam kedua. Berbeda malam pertama. Malam ini, ada acara makan bersama di rumah adat. Hampir seratus orang duduk di bagian utama rumah adat. Anak-anak, wanita remaja, wanita tua, lelaki muda, lelaki tua. Mereka duduk berjejer membelakangi dinding rumah adat.
Di hadapan mereka; di tengah ruang utama, jejeran piring berisi banyak nasi. Juga mangkok berisi sayuran. Sesaat sebelum makan, ada petuah dari pastor. Mungkin kalau di tradisi Mandar, itu disebut acara “mambaca-baca” atau “makkuliwa”.
Saat saya mendokumentasikan, pak Amiruddin, aktivis LSM yang aktif membina kawasan ini berbisik kepada saya, “Puncak acara tadi digeser esok”. Bisikan itu menjawab pertanyaan saya di tulisan yang saya buat sebelumnya. Mengapa tak jadi dilaksanakan ritual berjalan di atas bara. Ternyata diundur esok agar disaksikan para pejabat.
Informasi itu mematahkan anggapan “tradisi asli” yang saya saksikan sejak kemarin. Dengan kata lain, adanya rencana kedatangan pejabat “mencemari” urutan upacara. Tapi tak apa.
192 Muhammad Ridwan Alimuddin
Mengingat kembali kutipan di dalam buku “Meraba Indonesia”, bahwa realitas adalah amunisi dan senjata adalah kata.
Maknanya, apa yang terjadi, walau itu tak sesuai harapan kita (penulis), itulah realitasnya. Dan itu harus kita jadikan sebagai peluru. Tidak sebaliknya. Karena tidak sesuai harapan malah kecewa dan membuat tak menulis. Lebih parah lagi bila memanipulasinya. Sekali lagi, realitas adalah amunisi, kata senjatanya.
Sebab tadi hujan, kalau tidak salah jam empat sore, acara pukul-pukul “gimba” terhenti. Tak seperti kemarin yang berlanjut sampai jam enam sore. Bila didengar saksama, ternyata tabuhan ada juga iramanya. Itu baru saya sadari tadi. Kesadaran itu tak sengaja juga. Itu gara-gara ada yang mau ikut menabuh. Sebab dia tak tahu, tabuhannya kacau, tak berirama. Artinya, bila memang sembarangan memukul-mukul, pasti bisa. Tapi ternyata tidak gampang memang.
Ada hikmah saya mengambil “base” di warung yang dekat dengan lokasi acara. Saat saya membaca buku “Meraba Indonesia”, di lokasi acara, di tengah rintik gerimis berlangsung ritual. Di atas tikar, beberapa piring nasi, dua “piring” (kulit batang pisang), dan daun sirih. Salah satu pemuka adat membaca mantra. Seakan berpidato. Berlangsung lima menit. Seakan ngerocos. Kalimatnya tak ada titik. Tak mengerti apa maknanya, sebab berbahasa Kaili.
Sesaat setelah aksinya tersebut, dia mengambil salah satu pelepah batang pisang yang berisi bahan ritual untuk kemudian membawanya ke sisi timur lokasi upacara. Ke jalan yang menuju kali kecil. Jarak dari lokasi pusat upacara sekitar 50 meter. Kulit batang pisang diaa letakkan, berjongkok, untuk kemudian berbicara kembali seperti tadi. Tapi ini tak lama. Sekitar satu menit saja.
193Ekspedisi Bumi Mandar
Walau saya belum tahu apa makna ritual tadi, saya beruntung bisa menyaksikannya. Bersyukur memiliki mata awas. Bila tidak, ritual tadi akan lolos dari amatan saya.
***
Pagi hari ketiga. Semalam tidur di dalam ruang tamu rumah kosong. Bagian depan rumah tersebut dijadikan tempat menjual penjual yang saya tumpangi. Ada dua penjual. Yang satunya sudah pulang kemarin, setelah hari pasar. Satunya tetap tinggal.
Jika kemarin saya tidur di bawah tenda biru (tenda penjual yang sudah pulang), maka semalam di bawah atap rumbia yang sebagian telah rusak. Sehingga semalam rembulan menemani tidur. Tembus pandangan ke angkasa. Untung tidak turun hujan.
Semalam saya bangun, sekitar jam 12 lewat. Lamat-lamat terdengar “house music”. Antara penasaran dan mau buang air kecil saya bangun. Keluar. Penjual bersama ponakannya tertidur lelap. Jualan tetap pada posisinya. Tak dirapikan. Di sini aman.
Kaget. Di lokasi acara ratusan orang kumpul. Muda-mudi. Saya mendekat, sebab dari kejauhan kurang begitu jelas. Lampu ndak begitu kuat menerangi. Rembulan pun kadang dihalangi awan.
Mereka menari-nari. Sambil berpegangan tangan, membentuk lingkaran besar (bayangkan kegiatan Pramuka). Hampir semua remaja laki-laki dan perempuan. Sebagian ABG. Tariannya sederhana saja. Gerakan kaki dihentak kecil-kecil. Dilakukan bersamaan sehingga lingkaran besar itu bergerak perlahan, mengelilingi pusat, yakni “gimba”. Inilah yang disebut “dero”. Tarian pergaulan yang dilakukan muda-mudi.
Tapi saya belum yakin betul apakah “dero” ini adalah tradisi masyarakat sini? Percaya atau tidak, musiknya bukan tabuhan khas-
194 Muhammad Ridwan Alimuddin
khas etnik. Tapi “house music”, musik diskotik yang bisa membuat kepala goyang-goyang. Hampir tak percaya. Di pedalaman sini ada aksi tarian massal, lebih seratus, yang musik pengiringnya musik disko. Di Mamuju atau di kota besar Sulbar yang lain tak ada seperti itu. Termasuk di Makassar. Ya, memang ada tapi itu di diskotik, bukan di area lapangan terbuka (outdoor).
Tarian “dero” gerakannya tak macam-macam. Kaki saja yang digoyang kecil-kecil sambil melangkah ke samping. Tangan kanan dan kiri memegang tangan orang di samping. Orang di samping bisa saja laki-laki atau perempuan. Yang pacaran pasti menikmati pegangan itu. Dan ternyata, tarian itu berlangsung beberapa jam. Sebab ternyata telah berlangsung sebelum jam sepuluh dan selesai menjelang jam dua dinihari.
Pasti membosankan gerakannya. Tapi itu tak jadi soal bagi yang pacaran atau baru mau cari pacar. Bila “house music” di kota identik dibarengi penggunaan ekstasi, di sini tidak. Penari “dero” biasa-biasa saja. Tak ada goyang kepala yang begituan, saat orang lagi “fly”. Yang mau bergabung bisa langsung masuk rantai lingkaran. Kadang si mata rantai, misalnya seorang gadis dan yang mau gabung laki-laki, melihat dulu siapa yang akan gabung. Bila tak dikenal atau mungkin dikenal tak laki-laki tersebut tak disukai, akan ditolak. Yang mau gabung pun tak memaksa. Dia bisa gabung di mata rantai lain. Tapi banyak juga yang langsung terima.
Banyak yang gabung membuat lingkaran semakin besar. Lingkarannya tak sempurna. Kadang gepeng di bagian lain, kadang benjol. Ada juga yang keluar. Mungkin capek. Sepasang muda-mudi yang keluar untuk kemudian cari tempat “aman” tak saya lihat. Tapi tak bisa saya jamin prilaku itu tak ada. Sangat memungkinkan
195Ekspedisi Bumi Mandar
untuk melakukannya. Di semak-semak pun bisa bila tak bisa tahan syahwat. Di sekitar kampung ada banyak area tersembunyi.
Tarian “dero”, pertama kali saya lihat di sini, di Ngovi, di kawasan yang saya anggap sebagai kawasan tradisional. Yang jauh dari modernisasi. Tapi kejadian semalam, persepsi itu terhapus. Sebab, selain “dero-nya” yang telah diiringi “house music”, keramaian tadi malam pun laksana pasar malam. Puluhan motor terparkir. Dari matic sampai motor ber-CC besar. Ramai bukan main. Entah darimana saja mereka.
“Dero” sebagai tarian pertama kali saya dengar dari salah satu pemuka adat di Kalumpang. Dia menyebut “dero” sebagai salah satu bentuk seni tari di tempat tersebut. Tapi katanya, “dero” itu pengaruh dari luar, dari Poso. Bukan budaya asli setempat. Saat mendengar info itu, saya belum terlalu seriusi apa itu “dero”. Soalnya hanya informasi saja, belum melihat langsung (sebab di Kalumpang sudah sangat jarang dilakukan).
Ternyata ratusan kilometer dari Kalumpang ke arah utara, yang juga pedalaman, juga ada “dero”. Wah, “dero-nya” mantap bukan main, pakai “house music”. Di kota-kota pasti laku begituan.
“The Rock” yang Kebal
Hari ketiga. Siang ini membosankan. Soalnya ada musik elekton persis depan warung yang saya jadikan “basecamp”. Hanya diseberangi jalan. Adanya elekton melengkapi suasana hati semalam, saat “dero” diiringi “house music”. Lucu campur ironi.
Saat bangun tadi pagi, selesai shalat, ngopi pakai kopi susu saset milik penjual. Syukur, ada tanda-tanda keinginan buang air. Seperti kemarin lusa, untuk BAB saya lebih memilih di kali kecil
196 Muhammad Ridwan Alimuddin
daripada semak-semak. Di kali jelas, “itu”-nya pindah dan bisa langsung cebok. Kalau disemak, pasti repot bukan main. Hal seperti itu pernah saya alami waktu riset di perkampungan adat Kajang di Bulukumba.
Selain adanya tempat tersedia buang air besar, yang membuat saya bisa bertahan di sini adalah adanya kamar mandi. Setidaknya saya bisa mandi sekali dalam sehari. Hari ini sepertinya tak bisa mandi. Dekat kamar mandi ada acara masak-masak daging. Baik ayam maupun babi. Saya lihat wanita-wanita yang urus rempah dan masak-memasak bolak balik kamar mandi untuk ambil air. Pasti aroma daging di dalam.
Semalam juga membuat trauma. Saat akan masuk kamar mandi untuk ambil air wudhu, tiba-tiba ada anjing keluar. Bukan kagetnya yang menurunkan “mood”, tapi ada pikiran si anjing tadi habis minum dari ember. Untung tempat saya nginap, di warung dadakan, ada stok air tawarnya. Begitulah suasana di sini, di ibukota Desa Ngovi.
***
Saya beruntung bisa melakukan liputan di Desa Ngovi. Bukan apa-apa, seperti yang pernah saya tuliskan sebelumnya, ada banyak hal baru yang saya lihat. Rencana ke sini pun tiba-tiba, tak ada perencanaan.
Meski informasi di luar mengatakan ada pesta adat di Desa Ngovi, jangan bayangkan kemegahan sebagaimana pesta adat di suku-suku lain. Misalnya Toraja atau upacara adat di Mandar. Di Ngovi, semua berlangsung bersahaja.
Misalnya “mattaro”. Dilihat sekilas persiapan utamanya hanya membuat tempat menggantung “gimba”. Tak ada hiasan-hiasan. Para peserta atau penari pun tampil amat bersahaja. Tak ada
197Ekspedisi Bumi Mandar
gladi-gladian. Pokoknya kalau mau, bisa langsung. Yang datang dari kebun pun bisa langsung menari-nari.
Ada hal menarik yang saya saksikan di Ngovi, di hari pertama dan hari ketiga. Salah seorang penari, lelaki tua, tampil memperlihatkan kesaktian dirinya. Yaitu kekebalan kulitnya terhadap benda-benda tajam. Tak seperti penari-nari lelaki lain yang hanya mengayung-ayungkan pedangnya, yang ini, si lelaki tua, dengan cueknya mengiris-iris tubuhnya. Perut, lengan, dan lehernya tak meninggalkan luka apalagi ceceran darah.
Menariknya, walau ini kebetulan saja atau tidak ada hubungan dengan penampilannya, si bapak tua ini mengenakan baju kaos “you can see” merah bertuliskan “The Rock”, group musik yang dibentuk oleh Ahmad Dhani, pentolan Dewa 19. Adapun celananya celana hijau pendek. Hari pertama dan kedua bajunya sama, hanya celana yang beda tapi masih sama-sama warna hijau.
Dengan mengelilingi “gimba” beserta penabuhnya, lelaki tua kekar tersebut menari-nari dan sesekali menari atau melompat di tempat sambil menyayat-nyayat tubuhnya. Baju merah “The Rock” kadang ditarik naik agar perutnya kelihatan, agar mudah memperlihatkan bahwa sayatan yang dia lakukan tak mampan ke kulit tubuhnya.
Ilmu kebal adalah salah satu tradisi yang menjadikan masyarakat Bunggu mempunyai tempat tersendiri dalam komunitas suku-suku di Sulawesi. Memang hampir semua suku memiliki kemampuan tersebut, tapi hanya beberapa komunitas yang biasa menampilkan kemampuan tersebut di muka umum.
Selain kebal terhadap benda tajam, beberapa lelaki Bunggu juga mempunyai kemampuan kebal terhadap benda panas. Sebagaimana
198 Muhammad Ridwan Alimuddin
yang sering mereka perlihatkan di even-even budaya, yaitu berjalan di atas bara. Penampilan atas kemampuan itu hampir saya saksikan di hari kedua. Hanya saja karena ada rencana kedatangan pejabat, bara yang sudah disiapkan tak jadi digunakan.
Tikam Babi Hingga Potong Gigi
Upacara siklus hidup hampir ada di semua suku. Seperti upacara menyambut kelahiran bayi (termasuk ritual saat hamil), menjelang remaja, perkawinan, hingga kematian. Begitu pun di komunitas adat Bunggu, khususnya yang tinggal di Desa Ngovi.
Walau tiga hari saja berada di tengah perkampungan komunitas Bunggu, saya merasa beruntung bisa menyaksikan salah satu upacara siklus hidup dalam komunitas tersebut. Yaitu upacara menyambut babakan kehidupan seorang anak. Ada dua kasus yang saya saksikan, pertama upacara yang dilakoni anak laki umur sekitar 5-6 tahun dan kasus kedua, anak gadis berumur 12 tahun.
Prosesi upacaranya hampir sama, yaitu mengenakan kostum adat Bunggu di atas rumah, melangkah turun melewati tangga sambil menginjak kapak yang dibungkus dedaunan, dan ketika tiba di tanah ada proses menikam babi.
Khusus perempuan, upacara menyambut kedewasaannya, ada prosesi unik, yakni keramas rambut dengan menggunakan “sampo” yang bahannya dicampur di dalam mulut bibinya. Unik. Setelah dikenakan seragam adat, anak gadis tersebut dibawa ke rumah ketua adat untuk menjalani upacara potong gigi (tidak dipotong betul, hanya menyentuhkan benda tajam ke giginya).
Upacara-upacara di atas sudah sangat jarang dilakoni oleh orang Mandar. Sejak saya mendalami dokumentasi kebudayaan
199Ekspedisi Bumi Mandar
Mandar, upacara potong gigi baru satu kali saya saksikan. Yakni di Rangas, Majene.
Walau sudah sangat jarang saat ini, tapi bisa dipastikan upacara tersebut, sebagian, pernah menjadi tradisi kuat di Mandar. Bapak saya pernah menjalaninya, tapi saya dan saudara lain tidak lagi. Menurut ibu saya, “Seorang tidak boleh disunat bila belum menjalani acara potong gigi”.
Dalam laporan yang ditulis orang Belanda pada tahun 1912, Noteboom, dalam “Nota van Toelichting Betreffende het Landschap Balangnipa”, ada deskripsi singkat tentang upacara tersebut di Balanipa.
Berikut terjemahannya (oleh H. A. M. Mappasanda dan Drs. M.Yunus Hafid), “Pada anak laki-laki upacara ini dilakukan bersama-sama. Pada anak-anak wanita berlangsung tanpa upacara. Anak cucu raja yang sudah cukup umur untuk disunat, kaum Hadat dipanggil lagi untuk berkumpul, dan Hadat memanggil para kepala kampung. Telah menjadi kebiasaan membangun bangsal tanpa lantai yang dinamai “battayang”. Berbagai-bagai permainan judi dilakukan siang dan malam, kadangkala selama selama 7 bulan. Wanita-wanita muda dipanggil lagi melakukan apa yang dinamai “mattuqduq”. Para budak arayang menjadi pelayan-pelayan pergi ke sana ke mari membawa payung keemasan dan lain-lain payung untuk menjemput tamu dan mengundang. Rangkaian upacara dilaksanakan 9 hari dan 8 malam tanpa berhenti. Pada malam pertama dilakukan nilattigi. Hari berikutnya dilakukan pengikiran gigi, dan sesudah itu disunat. Pada saat upacara berlangsung, bedil ditembakkan, wanita-wanita menari dan dimainkan berbagai macam alat musik.”
200 Muhammad Ridwan Alimuddin
***
Upacara potong gigi juga ada di suku lain. Sepertinya tradisi tersebut dipengaruhi oleh agama Hindu. Sebagaimana di Bali, upacara potong gigi adalah upacara wajib dijalani. Dan, upacara tersebut dilakukan besar-besaran dan massal. Dari eskavasi yang pernah dilakukan di Bali, di kawasan Gilimanuk, didapati fosil gigi manusia berumur 2000 tahun yang telah menjalani proses potong/meratakan gigi.
Di Bali, upacara potong gigi diistilahkan “mepandes” atau “metatah” atau “mesangih”. Makna upacara tersebut adalah simbol pengendalian diri terhadap musuh dalam diri manusia. Ritual ini dilakukan saat seorang anak menginjak dewasa atau di saat pertama akil baligh. Biasanya ditandai haid untuk anak perempuan dan perubahan suara pada anak laki-laki.
Komunitas yang relatif bertetangga dengan Suku Kaili (Bunggu) juga melakukan hal yang sama, yaitu suku di Pamona (Sulawesi Tengah, Poso). Upacara potong atau meratakan gigi disebut “maasa”. Tujuan upacara sama dengan yang ada di Bali, dan rata-rata dijalani anak yang beranjak dewasa. Populernya anak baru gede.
Pada upacara potong atau meratakan gigi yang betul-betul mempraktekan memotong (bukan simbolisasi saja), gigi yang dipotong adalah empat deretan gigi bagian atas dan dua gigi taring.
***
Upacara atau ritual yang dilangsungkan di Ngovi hanya diketahui oleh masyarakat atau keluarga yang akan melakukan upacara. Bagi orang luar, seperti saya, bila tak sigap, upacara-upacara akan lewat. Tak disaksikan. Untuk itulah, walau rasa bosan
201Ekspedisi Bumi Mandar
dang ngantuk menghinggap, mata saya tetap awas.
Saat sedang duduk-duduk di bawah warung, di kejauhan, tampak beberapa orang berkerumun di teras rumah. Lelaki tua, yang dikenal sebagai dukun komunitas Bunggu, yang sosoknya bak pengemis di perkotaan, ada di situ. Topi orens, sarung digantungkan di leher, baju kaos biru yang luntur warna serta celana ‘hawaii’ melekat di tubuhnya.
Sepertinya ada upacara. Saya bergegas di sana bersama kamera.Tiba, tampak seorang lelaki memegang tombak. Di atas teras, seorang wanita berbaju pink menggendong anaknya. Anaknya menggantung di dalam sarung, di pundak ibunya.
Ada kulit kayu melilit di kepala sang anak. Di lehernya, kain hitam, mirip buntalan kecil, tergantung. Ada jahitan di bibir atar sang anak. Sepertinya habis operasi bibir sumbing. Memang ada kabar, beberapa hari yang lalu ada aktivitas Dinas Kesehatan (apakah dari Donggala?) di Ngovi.
Sang ibu menggenggam daun kecil di tangan kanannya. Dia menunggu instruksi dari sang dukun yang berdiri di anak tangga yang terbuat dari batang-batang kayu. Anak tangga yang terbuat dari batang lebih kecil diikat dari kulit kayu. Tangan kanan dukun membawa kapak besar (“wase” dalam bahasa Mandar) yang dibungkus daun nangka. Tangan kirinya berpegang ke tangga, menahan tubuh ringkihnya. Agar tak jatuh.
Perlahan kapak tersebut diletakkan ke anak tangga untuk kemudian meminta sang wanita agar kaki anaknya, tapi kaki ibunya sebagai media, dijejakkan ke gagang kapak. Begitu terus di setiap anak tangga. Prosesi tersebut diawali pembacaan mantra dalam bahasa Kaili oleh sang dukun.
202 Muhammad Ridwan Alimuddin
Persis di depan anak tangga, seeokor babi hitam tergeletak tak berdaya. Masih hidup. Kakinya diikat satu sama lain. Nafasnya keras. Bunyi khas babi, mirip suara orang ngorok.
Menjelang tiba di tanah, anak kecil yang tetap digendong ibunya, diminta untuk melangkahi sang babi, untuk kemudian melakukan jejakan terakhir atas gagang kapak di samping tubuh babi.
Berikutnya adalah prosesi penikaman babi. Sebelum menikam, sang anak diminta untuk memegang gagang tombak. Mungkin sebagai simbol bahwa dialah yang akan melakukan penikaman. Sesaat kemudian, lelaki yang memegang tombak, perlahan menusukkan ujung tombak ke ketiak kaki kanan bagian depan babi.
Sedetik kemudian, darah mengecer. Erangan kesakitan sang babi tak membuat iba si penikam. Tombak yang menembus ke dalam tubuh diputar-putar, mengoyak-ngoyak hati (jantung?) babi. Agar teriakan tak begitu keras, rahang babi diinjak. Kasihan betul nasibmu babi. Sang anak yang menjalani upacara itu menyaksikan saja. Entah, apakah dia mengerti maksud upacara yang dia jalani itu.
Prosesi yang sama juga dialami seorang gadis kecil. Upacaranya berlangsung tidak lama setelah anak di atas. Rumah mereka berjarak sekitar 50 meter. Untung saya menyaksikan upacara pertama, jadi bisa mendapat info bahwa akan ada upacara yang lain juga, yang dilakoni gadis. Tentu upacara pertama ini amat sangat penting sebab bisa menjadi pembanding. Antara anak laki-laki kecil dengan anak perempuan beranjak dewasa.
Sebab mendapat info lebih dini, prosesi persiapan upacara untuk anak perempuan bisa saya saksikan.
203Ekspedisi Bumi Mandar
Persiapan upacara berlangsung di atas rumah, tepatnya ruangan di sebelah ruang dapur. Di rumah berdinding papan berlantai bilah-bilah kayu, terhampar tikar. Di atas tikar, ada dua “tappiang”. Yang pertama berisi pakaian dari kulit kayu, selendang dari kulit kayu, parang tradisional, dan beberapa dedaunan. Sedang yang kedua berisi kain tenunan khas Donggala berwarna merah, kain hitam, gelang dari kuningan, kotak untuk sirih yang terbuat dari kuningan, kalung manik-manik berwarna putih, dan pengikat kepala berbahan kulit kayu.
Sang gadis yang akan menjalani upacara ditemani nenek dan bibinya. Setelah bahan tersebut siap, upacara diawali pembacaan doa yang dipimpin seorang pastor.
Setelah pastor memanjatkan doa (dalam bahasa Indonesia), upacara dilanjutkan atau berpindah ke dapur. Giliran sang dukun tua yang memimpin.
Di salah satu sudut dapur, sang dukun melakukan komunikasi dengan arwah. Dia berdiri menghadap ke sudut dapur, menyampaikan beberapa kalimat berbahasa Kaili. Entah apa yang dia ucapkan.
Setelah itu, dia duduk di lantai. Di depannya terdapat niru (“tappiang”) yang berisi kain merah beserta pakaian dari kulit kayu. Dia melakukan koordinasi dengan kerabat sang gadis, membicarakan apa tahapan berikutnya.
Setelah membaca mantra atas benda-benda di atas niru, selendang dari kulit kayu diselempangkan ke tubuh sang gadis.
Sesaat kemudian mereka turun, mencari sumber air. Tiba di sumber air (baca: ledeng, air yang keluar dari selang plastik), parutan kelapa, bubuk kunyit dan entah apa lagi yang digenggam
204 Muhammad Ridwan Alimuddin
sang bibi gadis dimasukkan ke dalam mulut si bibi. Dikunyah.
Kaget, kunyahannya itu dikeluarkan, ditampung di telapak tangan si bibi. Sesaat kemudian, “sampo” tersebut dilumuri ke rambut sang gadis. Bila habis, dikeluarkan lagi dari mulut si bibi. Begitu terus sampai rambut betul-betul terolesi. Saya menahan diri agar tak muntah. Kemudian rambut dibilis, di bawah air mengalir dari ujung selang.
Untung prosesi tersebut tidak lama. Terus terang, saya jijik juga. Tapi begitulah realitasnya. Entah apa karena proses itu, rata-rata rambut wanita di Ngovi, sejauh yang saya lihat, lebat-lebat. Baik tua maupun gadis remajanya. Entahlah.
Selesai itu, gadis kembali dibawa ke rumah ketua adat. Di rumah yang disebut “battayang” tersebut, sang gadis dibaringkan, dipangku oleh bibinya. Ternyata, dia akan menjalani ritual potong/meratakan gigi. Menarik nih.
Upacara dipimpin si dukun tua, bukan oleh ketua adat. Dia tetap mengenakan “pet” oranyenya, sehingga kelihatannya bukan seperti dukun kebanyakan sebagaimana di film-film. Dia mendekat ke gadis yang sedang berbaring dengan mulutnya yang menggigit batang kayu kecil. Mirip kayu “lolong” (untuk memberi warna merah ke air minum). Di tangannya terdapat pisau (dapur) yang dililit daun. Seperti daun kelapa kering. Perlahan pisau mengarah ke mulut si gadis. Lalu.
Ternyata pemotongan atau perataan gigi tidak dilakukan. Hanya simbolisasi saja. Menurut salah seorang di antara mereka, pemotongan yang betul-betul dilakukan sudah tak dipraktekkan lagi.
Setelah simbolisasi pemotongan gigi dilakukan, si gadis meludah ke tempurung yang didalamnya terdapat “tai au” alias abu.
205Ekspedisi Bumi Mandar
Upacara pun selesai. Setelah itu si gadis dibawa kembali kerumahnya. Sepetinya si gadis telah suci. Agar tak “kotor”, saat dibawa kerumahnya, si gadis dipanggul kerabatnya yang lelaki. Si gadis dibawa kembali ke dapur.
Tiba, salah seorang kerabat perempuan si gadis memanaskan parang kecil di tungku. Sesat kemudian, dia menyentuhkan tangannya ke parang, menyentuh sesuatu (mirip lemak atau jejak asap dari kayu bakar) untuk kemudian jarinya tersebut disentuhkan ke gigi si gadis, kening, dan dahinya. Mirip proses “macco’bo” di Mandar.
Setelah itu, pakaian dari kulit kayu dikenakan kepada sang gadis. Tapi karena kekecilan (sempit), pakaian tersebut tidak melekat di tubuh, tapi disimpan di dalam kain merah tenun Donggala. Kain tersebut dijadikan sebagai tas, yang melintang di tubuh sang gadis. Sebagaimana kain hitam yang dikenakan anak lelaki di upacara sebelumnya.
Ke dalam kain tersebut juga dimasukkan kotak sirih. Adapun benda-benda lain dipasangkan sebagaimana mestinya, seperti ikat kepala, kalung, dan gelang kuningan. Di bagian belakang kepala sang gadis, di balik kulit kayu yang melilit kepalanya, disisipkan bunga. Kelihatan anggun.
Nah, berikutnya adalah acara turun melewati tangga, menginjak kapak, dan menikam babi. Sebagaimana prosesi yang saya lihat sebelumnya, tapi oleh anak laki-laki kecil.
Yang tak saya lihat yang dilakukan di upacara sebelumnya oleh anak lelaki, setelah menikam babi, adalah ritual di belakang rumah. Sekitar dua jam setelah sang gadis menikam babi, bersama sang dukun dan kerabat gadis, mereka melakukan ritual di belakang rumah.
206 Muhammad Ridwan Alimuddin
Mengelilingi satu titik, yang dipimpin pembacaan mantar si dukun. Tampak si gadis menenteng jantung babi bersama tiga ketupat.
Sesaat kemudian, dari dapur diturunkan niru (tappiang) lalu diletakkan ke tanah. Di atasnya terdapat beberapa kerat/potong daging babi dan beberapa genggam kecil nasi. Setelah berjalan keliling, jantung babi dan ketupat diletakkan ke dalam niru. Kemudian, dukun mengambil nasi dan daging untuk kemudian disuapkan ke mulut si gadis. “Tappiang” kemudian diangkat dan selanjutnya diputar-putar di atas kepala si gadis, yang dilakukan oleh bibinya. Upacara pun selesai.
Beristri Cantik, Jangan Cepat Tidur
Desa Ngovi, desa bersahaja. Periferal (pinggiran) Sulawesi Barat. Mungkin karena terlalu di pinggir, Sulawesi Barat hampir tak tahu bila wilayah itu dicaplok Sulawesi Tengah. Banyak yang tak sadar, bahwa kawasan Ngovi dan sekitarnya adalah wanita cantik.
Hari terakhir di Ngovi, saya kembali menemui Kepala Desa Ngovi, Petrus Saliku. Untuk menanyakan beberapa hal; mengkonfirmasi banyak hal. Khususnya kebudayaan komunitas adat Bunggu.
“Nenek saya dulu, sebelum dia meninggal, memberi saya tiga pesan. Pesan itu saya jadikan ilmu, yang saya bawa ke mana-mana,” tutur Pak Petrus dengan bahasa Indonesia yang tak lancar. Tapi enak didengar. Saya penasaran akan penyampainnya tersebut.
Sesaat kemudian dia memberitahukan pesan tersebut. Awalnya saya pikir itu rahasia, sehingga tak mendesak untuk memberitahukan segera. “Pertama, rejeki sedikit jangan ditolak,
207Ekspedisi Bumi Mandar
kedua rahasia orang jangan dibuka, dan ketiga kawin perempuan cantik jangan cepat tidur,” ungkapnya. Jelas, pesan yang ketiga itu yang membuat tambah saya penasaran.
Pesan pertama dan kedua mudah dimaknai artinya. Dalam penjelasan Pak Petrus, dia mengatakan bahwa kita jangan menolak pemberian orang lain walau itu sangat sedikit. Misalnya sebatang rokok. Sebab, itu bisa menjadi awal, menjadi pintu untuk rezeki yang lebih besar. Laksana bila ingin mendapatkan rezeki dari kelapa, pertama harus menanam satu buah kelapa dulu.
Yang kedua, kita harus menjadi sahabat atau tetangga yang baik. Caranya, jangan mambuka-buka atau menyebarluaskan aib orang lain. itu tidak baik.
Sedang yang ketiga, maknanya adalah, jika kita memiliki tanah yang subur, hendaknya kita jangan malas. Harus kita olah terus menerus agar bisa menghasilkan.
“Kawasan ini bagai isteri kami yang cantik. Bila tak diolah, kita tak akan dapat apa-apa, tak bisa dapat uang. Jadi, sebagai suami, kita jangan cepat tidur. Artinya, jangan mudah bermalas-malasan,” terang Pak Petrus Saliku akan makna pesan ketiganya.
Jujur, saya amat terkesan dengan petuah atau pesan tersebut. Memang kalau dipikir-pikir, fenomena kebanyakan di daerah kita, Sulawesi Barat, kita bagai memiliki isteri yang cantik tapi kita cepat tidur. Pada gilirannya, kesuburan yang dimilikinya tak memberi hasil maksimal.
Namun yang paling ironi adalah, kita sadar memiliki isteri cantik (baca: tanah subur) tapi kita malah menjual, menyewakan, memberikan “isteri” kita ke orang lain. Maka yang terjadi adalah, kecantikan “isteri” kita dinikmati habis-habisan orang lain. Lama
208 Muhammad Ridwan Alimuddin
kelamaan, kita sebagai “suami” sah akhirnya akan mendapatkan “isteri” kita kala dikembalikan, sudah tak cantik lagi, layu, dan mengenaskan.
Dengan kata lain, tanah-tanah subur kita malah dimanfaatkan investor, mulai dari perkebunan raksasa hingga pertambangan. Dan ketika kekayaan tersebut telah habis dikeruk, yang tertinggal adalah tanah-tanah yang rusak, lahan gundul, gersang, dan rusak.
***Komunitas adat Binggi, yang secara kultural menjadi bagian
dari Suku Kaili, sadar atau tidak, berada dalam pertarungan terhadap dunia luar. Diakui atau tidak, banyak kebudayaan atau gaya hidup mereka yang berubah.
Sebagai contoh, tarian “dero” yang tak lagi diiringi musik tradisional tapi dengan “house musik” adalah sesuatu yang mereka pilih. Ratusan orang melakukannya. Tak ada yang protes, meski ada rasa tak bahagia terpancar dari mimik tetua adat mereka, Pue Ponggo, saat saya pendapatnya akan fenomena tersebut. Jelas “house music” lebih praktis, lebih enak didengar. Tapi apakah hanya itu alasannya?
Paralel dengan erosi dalam kebudayaan mereka, adalah kerusakan lingkungan mereka. Wanita cantik yang selama ini menjadi isteri mereka sebagian besar dimanfaatkan “laki-laki” lain. Dalam hal ini perkebunan sawit. Menyaksikan dari udara lahan-lahan di Mamuju Utara, termasuk kawasan adat Bunggu, sebagian besar diisi perkebunan sawit. Kecantikan (kesuburan) tanah digerus habis-habisan. Entah sampai kapan.
Di sisi lain, kualitas masyarakat Bunggu, yang notabene bisa dikatakan pemilik awal lahan, berada pada taraf yang menyedihkan.
209Ekspedisi Bumi Mandar
Terus terang saja, ada beberapa individu yang meminta uang ke saya. Bukan memeras, tapi mereka sepertinya lapar, butuh rokok, dan ingin merasakan makanan dan minuman warna-warni yang ada di warung.
Dilema menghadapi sikap seperti itu. Bila memberi, jelas akan membuat mereka bahagia. Di sisi lain, sikap seperti itu bisa berbahaya. Jangan sampai ada pandangan bahwa orang luar identik dengan banyak uang; jangan sampai ketika ada mahasiswa yang datang penelitian atau KKN, mereka juga dimintai.
***Sepasang suami ister, umur hampir 70 tahun, badan bungkuk,
baju kumuh, dengan buntalan di pundak mereka, berdua di Pasar Ngovi. Melihat-lihat barang di salah satu penjual. Sesaat kemudian, mereka memilih barang yang ingin mereka beli. Garam, gula dan ikan “tuing-tuing” asap.
Si isteri, yang sehari sebelumnya membuat saya terkesan kala dia ikut menari di upacara, ternyata masih ada yang mau dia beli. “Mau beli apa lagi indoq?,” tanya si penjual. Dijawab si wanita tua, “Semmer”.
Si penjual pun memanggil temannya, sebab barang yang diminta si wanita tua tak ada dia jual. Jawabnya, “Ada. Harga sepuluh ribu”. Saat si wanita tua mendapat informasi harga, dia tampak murung. Uangnya tak cukup lagi.
Saya menanyakan ke penjual barang, “Apa yang dia ingin beli. Nanti saya yang bayar. “Ibunya mau beli semir rambut,” jawab si penjual. Sesaat kemudian, kotak kecil, oranye, ada tulisan Tancho dengan gambar wanita cantik berambut tebal berpindah tangan ke wanita tua. Ada kebahagiaan, pada dirinya, pada diriku.
211Ekspedisi Bumi Mandar
Penulis di perbatasan NgoviSeorang gadis Ngovi bersiap menjalani upacara siklus hidupGadis yang menjalani upacara siklus hidup menerima suapan dari dukunTarian yang dipertunjukkan dalam upacara setelah panen di Ngovi_02Dalam tarian yang diperankan oleh kaum lelaki Ngovi sering diperlihatkan kemampuan mereka
tidak luka oleh senjata tajamPenulis bersama tetua adat Ngovi (kedua dari kanan)Tarian yang dipertunjukkan dalam upacara setelah panen di Ngovi_01Sosok wanita tua di Ngovi
6
7 8
212
EKSPEDISI BUMI MANDAR
Ekspedisi Keliling Mandar Ala Jurnalis Radar Sulbar
Sejarah awal jurnalistik adalah laporan-laporan perjalanan dari para pengelana, khususnya para pelaut. Mengabarkan ke
masyarakat Eropa tentang ke-eksotikan dunia timur. Itulah sebab, akar kata jurnalistik adalah “journal”, semacam catatan harian. Dan, hingga saat ini, salah satu kewajiban nakhoda kapal adalah membuat jurnal.
Tak mengherankan bila tokoh-tokoh mashur waktu bahari (lampau) adalah para pengelana yang pergi berlayar. Siapa tak kenal Marco Polo, Ibnu Batuta dan Tome Pires? Catatan yang mereka bawa pulang untuk kemudian dipublikasi membuka mata Eropa betapa oriental (timur, benua Asia) begitu mengagumkan
Waktu berlalu, jurnal yang dilaporkan tidak sebatas para pelaut atau pengelana; bukan hanya catatan perjalanan yang dilaporkan, tapi kejadian-kejadian yang penting diketahui masyarakat. Itulah dunia jurnalisme.
Meski jurnalisme saat ini berbeda jauh dengan sejarah awalnya, wartawan atau jurnalis yang melakukan perjalanan untuk kemudian membuat tulisan lalu melaporkannya adalah keasyikan tersendiri. Sadar tidak sadar, itu adalah lakon jurnalisme
213Ekspedisi Bumi Mandar
paling tradisional. Hanya saja, melakukannya dewasa ini jauh lebih mudah, lebih gampang. Praktis. Dulu, sangat merepotkan.
Lampau, sebagaimana yang kita lihat di film-film, untuk menulis menggunakan bulu angsa, tintanya pun terpisah, berada di botol. Pun belum ada lampu benderang bila ingin menulis di waktu malam. Kira-kira bagaimana rasanya menulis dengan cara begitu di atas kapal? Tak usah di atas kapal, di darat pun pasti akan repot bila akan menulis berlembar-lembar. Dan ketika selesai, catatan lapangan tersebut diketik ulang (istilahnya manuskrip), dicetak dan dipublikasikan. Proses itu butuh beberapa tahun.
Sekarang, jauh memudahkan. Dalam hitungan detik – menit, tulisan bisa dibuat dan disebar “secepat kilat” ke seantero dunia. Bila pun akan dimuat di media cetak (koran), hanya berlangsung hitungan jam atau hari atau kalau dalam bentuk buku, bisa dalam hitungan bulan. Sebuah revolusi bila dibanding masa lalu.
Melakukan perjalanan (traveling), merupakan kesenangan tersendiri. Kebanggaan bila melakukan perjalanan jauh, apalagi kalau itu ke luar negeri. Melintasi beberapa negara. Ada banyak buku yang isinya catatan-catatan perjalanan para pelancong. Ada tentang “backpacker” keliling Eropa, Jepang, Amerika, Asia dan lain-lain. Misalnya karya Trinity (nama samaran), “The Naked Traveler: Catatan Seorang Backpacker Wanita Indonesia Keliling Dunia”.
Keliling Indonesia pun ada, yaitu buku “Meraba Indonesia: Ekspedisi “Gila” Keliling Nusantara” berisi kisah perjalanan penulisnya yang juga seorang jurnalis, Ahmad Yunus, bersama Farid Gaban keliling Indonesia dengan menggunakan motor.
Perjalanan jauh, ke negeri orang, baik dalam maupun luar negeri, terus terang menyenangkan. Di sisi lain, itu menjadi “tak
214 Muhammad Ridwan Alimuddin
berguna” ketika negeri atau daerah atau kampung sendiri tak dikenal; tak dijelajahi.
Saya pribadi telah melakukan beberapa ekspedisi pelayaran (lewat laut), ada yang ke ujung utara Indonesia, ke bagian paling tenggara Indonesia, dan ke bagian barat Indonesia. Pun kenal dan pernah membantu penjelajah dunia, yang pernah melakukan perjalanan non-mesin (jalan kaki, bersepeda, sampan, tenaga binatang) dari Afrika sampai ujung Amerika Selatan selama 12 tahun kala melakukan kegiatan di Mandar – Indonesia selama beberapa bulan. Tapi, hal itu rasanya belum berarti bila tak melakukan ekspedisi di daerah sendiri.
Ekspedisi adalah perjalanan, baik dalam bentuk kelompok maupun individu, biasanya dalam rangka penjelajahan, penelitian, maupun perang. Biasanya ekspedisi dilakukan pada daerah-daerah tertentu, misalnya yang belum atau jarang dikunjungi orang. Tapi dewasa ini, ketika nyaris tak ada wilayah di muka bumi yang pernah didatangi manusia, sifat ekspedisi mulai meluas.
Memang ekspedisi kebanyakan dilakukan organisasi pecinta alam, baik sipil, militer, maupun perguruan tinggi. Tapi kelompok masyarakat lain juga melakukannya, salah satunya kelompok jurnalistik. Beberapa stasiun televisi di Indonesia membuat acara bertema ekspedisi. Bedanya, ekspedisi dilakukan dalam rangka sebuah mata acara. Dan yang paling sering melakukan ekspedisi berkualitas untuk kemudian dimuat di media(nya) lalu dibukukan adalah Kelompok Kompas - Gramedia. Beberapa buku dihasilkan, diantaranya Ekspedisi Begawan Solo, Ekspedisi Tanah Papua, dan Ekspedisi Cincin Api.
Ekspedisi yang dilakukan oleh media atau kelompok atau perusahaan pers di Sulawesi Selatan dan atau Sulawesi Barat belum
215Ekspedisi Bumi Mandar
pernah saya baca/dengar/lihat. Baik itu di Pulau Sulawesi maupun di luar Pulau Sulawesi. Padahal, ekspedisi bisa menghasilkan liputan yang lain daripada yang lain (liputan hari-hari). Juga, bisa memberi warna lain akan sebuah kegiatan jurnalistik.
Walau masih jauh untuk dikatakan ekspedisi berkualitas, Ekspedisi Bumi Mandar digagas. Sebuah ekspedisi yang melakukan perjalanan “keliling” tanah Mandar atau Sulawesi Barat dengan menggunakan sepeda, berjalan kaki (bila sepeda tak bisa difungsikan), dan dengan perahu karet. Ekspedisi yang bertujuan mendokumentasikan atau meliput apa saja sejauh perjalanan untuk kemudian dilaporkan ke publik.
Untuk saat ini, kegiatan ekspedisi akan saya lakukan sendiri (bersepeda) dan didukung tim yang membantu perjalanan (menggunakan motor). Tapi untuk beberapa etape berikut, mungkin akan diikuti 1 – 2 orang teman.
Ekspedisi rencananya akan melalui beberapa tahap atau etape (tidak dalam satu kurun waktu non-stop), yaitu Etape I Paku – Suremana, Etape II Polewali – Mamasa – Mamuju (Tasiu), Etape III Mamuju (Tasiu) – Kalumpang – Sampaga (balik dengan menggunakan perahu, menyusuri Sungai Karama), Etape IV Mapilli – Tutar – Majene, dan Etape V Ulumandaq – Tinambung (menggunakan perahu karet).
Etape-etape tersebut di atas bisa saja tidak berurutan, sebab disesuaikan dengan kondisi tubuh, waktu dan kegiatan lain (pekerjaan rutin). Hal ini terjadi, sebab kegiatan ekspedisi, sampai saat ini tidak atau belum didukung oleh pihak yang memberi dukungan signifikan. Dalam arti, pelaku ekspedisi harus mengusahakan sendiri dana untuk membiayai perjalanan.
216 Muhammad Ridwan Alimuddin
Selama melakukan ekspedisi, laporan rutin akan saya kirimkan ke redaksi Radar Sulbar untuk kemudian dilaporkan ke pembaca keesokan harinya. Jadi, ekspedisi bisa juga dikatakan sebagai liputan. Untuk itu, dalam perjalanan dibawa serta perlengkapan yang memungkingkan penulisan dan pengiriman laporan mudah dilakukan.
Jam Tiga Sore Ekspedisi Dimulai
Rencananya berangkat Senin pagi, 13 Mei di perbatasan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat di ujung Kabupaten Pinrang. Berhubung hari sebelumnya hujan, mobilisasi peralatan ekspedisi (mengangkut sepeda dan tas menggunakan motor) ke perbatasan tertunda. Itu baru bisa dilakukan Senin siang. Walau demikian, memulai ekspedisi di hari yang direncanakan tetap bisa. Mudah-mudahan.
Tiba sekitar pukul 14.30. Setelah siapkan sepeda da peralatan lain, lewat jam tiga sore, Ekspedisi Bumi Mandar dimulai. Berdasar latihan yang dilakukan dua pekan sebelum hari H, masih ada waktu untuk bisa tiba di kota Polewali sebelum malam. Jaraknya sekitar 20 km, itu bisa ditempuh kurang dua jam.
Ekspedisi Bumi Mandar memilih moda transportasi sepeda dibanding kendaraan motor lainnya, baik mobil maupun mobil. Dengan bersepeda, urat nadi bumi Mandar tidak dilalui sekilas saja. Tapi dinikmati, walau harus capek. Tidak juga dengan berjalan kaki sebab akan kelamaan.
Menggunakan sepeda bukan juga barang baru. Sewaktu sekolah di MTsN Tinambung, kala era sepeda Mustang, ke sekolah pakai sepeda. Waktu SMA juga, tapi kalau kegiatan sore atau ke
217Ekspedisi Bumi Mandar
rumah guru belajar. Kalau dipakai pergi sekolah, tiba di sekolah keringatan. Bukan apa-apa, tanjakan Kandemeng – Layonga membuat lelah. Apalagi masa-masa itu masa “baler”.
Kuliah di Yogya, di kota pendidikan, tahun-tahun terakhir menggunakan sepeda dari asrama ke kampus. Di sana banyak mahasiswa yang menggunakan sepeda, beda di Makassar. Yang mahasiswanya malu menggunakan sepeda. Memang banyak mahasiswa yang bersepeda di Yogya, tapi di Universitas Kyoto, Jepang jauh lebih banyak. Waktu ke sana, cewek-cewek cantik berok mini juga menggunakan sepeda. Kalau di Indonesia, mana mungkin mau.
Balik ke Mandar, saya bawa serta sepeda yang dipakai kuliah di sana. Lama disimpan, rusak di tempat. Hingga kemudian niat ekspedisi memuncah. Sepeda berjasa tersebut saya perbaiki, setidaknya dipakai untuk latihan, hingga betul-betul ekspedisi berjalan. Masalahnya, sepeda gunung itu termasuk jadul kala ini. Beberapa alatnya tak ada lagi dijual. Terpaksa beli sepeda murah agar peralatannya bisa dikanibal. Syukurlah, sepeda bisa dipakai latihan dua pekan.
Dalam latihan dan pelaksaan Ekspedisi Bumi Mandar,bukan hanya mempersiapkan fisik tapi alat pendukung program atau aplikasi pendukung. Salah satunya aplikasi Runtastik di iPhone (yang juga ada di Android). Dengan aplikasi tersebut, data jarak, durasi, rute, elevasi, rata-rata kecepatan, dan informasi lain tercatat secara otomatis. Misalnya data dari latihan, statistiknya: 12 kegiatan, jarak 95,64 km (kurang lebih 100 km, sebab kadang saya lupa men-set aplikasi padahal sudah mengayuh beberapa kilometer), dan durasi total 7 jam.
218 Muhammad Ridwan Alimuddin
Dalam bersepeda jarak jauh, intinya adalah kesabaran. Sama dengan lari marathon. Beda dengan lari jarak pendek atau sprint. Dengan kata lain, jika mengayuh cepat, akan cepat capek atau lelah. Tapi kalau santai-santai, jarak puluhan – ratusan kilometer bisa ditempuh tanpa melelahkan.
Banyak juga yang salah paham bahwa ketika bersepeda, yang capek adalah betis. Sering ada yang bercanda “lippa’ai battis”. Padalah, yang bekerja keras dalam bersepeda adalah paha. Untuk itu, ketika pemanasan, paha-lah yang menerima porsi terbesar. Tetapi, bagian-bagian lain juga harus dipanasi. Selain betis dan pergelangan kaki, juga lengan. Sebab, lengan itu menumpu tubuh bagian atas.
Ekspedisi Bumi Mandar bukan jalan-jalan semata. Sebagaimana perjalanan yang banyak dilakukan, misal keliling Indonesia dengan sepeda. Ekspedisi ini juga adalah perjalanan ilmiah, bisa juga disebut liputan. Artinya, dalam perjalanan dibawa serta peralatan yang mendukung hal itu. Yang paling utama adalah bisa menulis, bisa memotret, dan alat komunikasi aktif terus. Bukan itu saja, rute haruslah tercatat detail. Dan alat yang paling memungkinkan untuk itu adalah menggunakan GPS (Global Positioning System).
Lebih lengkapnya, berikut sebagian besar peralatan yang dibawa dalam Ekspedisi Bumi Mandar: tas punggung dua set (besar dan kecil), helmet, tas pinggang bersama botol air minum, kaos tangan, kacamata, alat navigasi dan komunikasi berupa GPS Garmin 60CSx, kompas, alat pengukur suhu dan kecepatan angin digital, Blackberry dan iPhone 4 (sekaligus sebagai modem). Penerangan: senter anti air, lampu baca; solar panel atau tenaga surya beserta aki kering (terpasang bersama lampu) sebagai alat
219Ekspedisi Bumi Mandar
charge baterei dan alat komunikasi; netbook 320 GB Eee PC 10 inci dan alat tulis; alat masak kompor gas kecil dan tabung gas kecil, panci kecil dan piring plastik kecil; Gorilla pod (tripod elastis) dan mini monopod; kamera Nikon D300s dan lensa 35mm, pocket Nikon AW-100 (ada GPS dan kompas digital), kamera GoPro Hero 3 Black dan aksesorisnya; Powerbank 8500 A, beberapa baterei A2 isi ulang, baterei Wasabi dua unit (utk GoPro), batarei utk Nikon D300s 4 unit, baterei utk Nikon AW-100 2 unit, dan beberapa kabel USB. Semua alat di atas bisa masuk ke dalam dua tas, selain yang dipasang di sepeda (misal panel surya).
Adapun peralatan utama dan berukuran besar adalah tenda bulan dan satu unit sepeda “cross country” jenis “hardtail”. Awalnya, akan menggunakan sepeda yang pernah saya gunakan kuliah di Yogya dan dipakai latihan. Sampai pelaksanaan ekspedisi pun tetap mengharapkan menggunakan sepeda berjasa itu. Rencana berkata lain, ketika dibawa ke bengkel sepeda di Polewali (dalam perjalanan ke Paku), ternyata tak bisa juga diperbaiki. Khususnya leher sepeda yang goyang ketika direm. Tak ada lagi dijual alatnya. “Terpaksa” menggunakan sepeda lain untuk dipakai ekspedisi, yang lebih stabil dalam perjalanan jauh sampai ke Suremana dan etape lain.
Setelah menempuh perjalanan lebih satu jam dengan jarak 19 km, hari pertama Ekspedisi Bumi Mandar berhenti di Taman Bahari Polewali. Taman cocok untuk pasang tenda, untuk istirahat. Rencana esok pagi, 14 Mei, perjalanan akan dilanjutkan ke barat, ke arah Majene. Targetnya berhenti di Tanjung Ranga. Di atas tebing karang akan kembali pasang tenda. Semoga tetap bisa mengayuh, semoga tetap bisa menulis.
220 Muhammad Ridwan Alimuddin
Terima Kasih “Kambossolnya”
Baru selesai pasang tenda bulan di atas tebing karang di Tanjung Rangas. Suara ombak jelas menemani gesek sayap serangga memikat pasangannya. Suhu agak panas, sepertinya akan hujan sebentar. Titik air yang jatuh di tenda penanda kesekian.
Malam kedua Ekspedisi Bumi Mandar. Tempat bermalam saat ini berbanding terbalik dengan di Polewali, yang berada di taman. Di sana orang ramai dan ketika malam, beberapa pasang muda mudi asyik masyuk pacaran. Tak peduli orang-orang di sekitarnya. Di sini, di bukit karang Tanjung Rangas, sepi sekali. Tak ada orang. Rumah terdekat dari sini dua kilometer jaraknya. Mudah-mudahan tak terjadi apa-apa. Apalagi malam ini saya tak ditemani “tim darat”, si Suling Bambu nama Facebook-nya alias Sabri Hamid. Yang sedari start ikut serta. Kegiatan utamanya mendokumentasikan kegiatan ekspedisi. Tidak seperti saya yang naik sepeda, Sabri Hamid menggunakan motor saya. Dia tak ikut malam ini dan esok sebab harus selesaikan majalah Kominfo Polman, tempatnya kerja.
Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir tiba malam di tempat berkemah. Apalagi di lokasi yang medannya berat. Melintasi rumput kering beberapa puluh meter, di sisi bukit karang, di gelap gulita adalah kerepotan tersendiri. Belum lagi menenteng sepeda. Tapi, itumi juga yang bisa dicerita. Yang susah-susahnya.
Bila hari pertama hanya menempuh jarak 20an kilometer, hari kedua lebih 60 kilometer untk dua kali pemberangkatan. Pertama Polewali – Pambusuang, untuk jarak sekitar 41 kilo, ditempuh dua setengah jam. Sorenya, sekitar jam lima menuju Tanjung Rangas, jaraknya 22 kilometer. Seharusnya ditempuh sekitar satu jam saja.
221Ekspedisi Bumi Mandar
Tapi karena singgah-singgah, menjadi tiga jam dan dampaknya tiba malam di lokasi.
Walau sepi, terpencil, sengaja saya pasang tenda di sini karena ada beberapa alasan. Pertama, medannya sudah saya tahu. Sering ke sini motret. Pemandangannya bagus, khususnya “sunset”. Di pesisir Teluk Mandar, untuk dapat pemandangan matahari tenggelam tak bisa ke arah timur Harus ke ujung Tanjung Rangas sebab tak ada lagi daratan yang menghalangi. Nah, titik pertama untuk bisa lihat dan mendokumentasikan “sunset” itu di sini. Tempatnya agak tersembunyi, tapi kalau mau tahu tempat belokanya: kalau sudah dapat jalan rusak di antara Rangas dan Luwaor, di dekat lampu suar Rangas, dan di situ ada patok kilometer, beloklah ke arah laut. Di situ ada jalan setapak. Sebab saya tahu lokasinya, tiba malam tak apa-apa.
Alasan kedua, di masa mendatang lokasi ini bisa jadi tempat untuk berkemah atau “camping” bagi para “traveler”. Ingin merasakan sensasi di “alam liar” tapi tak mau jauh-jauh, di sini tempatnya. Dan yang ketiga, saya membayangkan jalan trans Sulawesi Barat dan jalan-jalan lain menjadi jalur wisata “cross country”, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ada banyak turis yang memiliki minat pada wisata demikian. Dan, alam di Sulawesi Barat layak untuk dinikmati dari atas sepeda. Belum lagi masyarakatnya yang penuh dengah harmoni.
Kaitannya dengan alasan ketiga di atas, apa yang dilakukan dalam Ekspedisi Bumi Mandar, yang memilih tinggal di alam dengan memasang tenda dibanding bermalam di rumah penduduk atau mesjid atau SPBU, ialah membuktikan bahwa Mandar atau Sulawesi Barat itu aman. Tapi pembuktian itu baru akan sah bila
222 Muhammad Ridwan Alimuddin
ekspdisi selesai dan kepada saya tak terjadi apa-apa oleh faktor gangguan dari pihak atau orang lain.
Artinya apa, kepada pihak luar dapat kita sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu aman. Bandingkan dengan daerah lain, yang malam-malam lewat, motor dirampas. Belum lagi ada yang diperkosa beramai-ramai dihadapan pacarnya, misalnya yang terjadi di Sumatera. Baru-baru ini juga terjadi, di Bali, perampok dan pemerkosa sudah berani sampai masuk hotel dan menjadikan turis asing sebagai korbannya. Di India, turis yang melakukan wisata bersepeda juga diperlakukan begitu. Jadi, dibanding tempat tersebut, daerah kita masih jauh lebih aman. Itu patut kita syukuri dan berharap di masa mendatang tak ada kejadian seperti itu.
Juga, sudah saatnya kita menghilangkan “imej” bahwa daerah kita itu angker, menyeramkan, dan orang-orang Mandar suka “mandoti-doti”. Banyak kepercayaan di masyarakat, yang kadang kita amini, di daerah kita banyak tempat-tempat menyeramkan. Katanya ada “pakkammi’na”, ada “pottianaq”, dan setan-setan ala Mandar lainnya. Ya, tidak apa-apa bila itu memang “wajar” dikeramatkan, misalnya makam atau kuburan. Tapi kalau tempat yang indah, yang bisa dinikmati, tidak perlu dikeramatkan. Bukan saya orang pemberani dan tak percaya pada hal-hal gaib, tapi untuk bermalam di sini, di bukit karang Tanjung Rangas seorang diri, masih “fain-fain aja”. Setidaknya saat laporan ini saya buat, menjelang jam sembilan malam. Entah sebentar, kala tengah malam.
Kalau memang ada setan di sini, mudah-mudahan saya tertidur lelap. Sebab memang capek bukan main. Apalagi paha yang pegalnya tak ketulungan. Wajar saja, sejauh pengalaman saya naik sepeda, terjauh itu terjadi tadi, 14 Mei.
223Ekspedisi Bumi Mandar
Tak sempat lagi masak malam ini. Tapi tak lapar juga. Saat meninggalkan rumah di Pambusuang, isteri memberi titipan “kambossol” (pisang masak yang dihancurkan, dicampur terigu sedikit, lalu digoreng; mungkin bisa disebut “brownis” ala Mandar sebab bentuknya tak karuan). Dan ketika singgah di rumah Tinambung, kebetulan atau tidak, ibu juga menitipkan “kambossol”. Jadi ingat salah satu film, judulnya “Badik Titip Ayah”, kalau kisah ini difilimkan, mungkin judulnya, “Kambossol Titipan Isteri dan Ibu”. Terima kasih atas “kambossolnya”, dari orang-orang tercinta dan makbul doanya.
Totolisi Selatan, Sentra “Gamacca” di Mandar
Melintas pantai barat Majene, Rabu, 15 Mei, merasakan kekhasan jalan trans ala Mandar: berada di pinggir pantai. Dibanding kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, sejauh yang pernah saya datangi, jalan utama di Majene sebagian besar berada di pinggir pantai.
Artinya apa, yang melintas dimanjakan matanya oleh keindahan pantai atau laut lepas. Nyiur pohon kelapa, sandeq yang nampak di kejauhan, rumah-rumah penduduk dan jejeran perahu. Berbicara tentang obyek wisata, keindahan di sepanjang jalan tersebut layak “jual”. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi jalan trans di Majene yang semakin bagus. Bersepeda di wilayah Majene dua hari terakhir memberi kesan bahwa pengendera sepeda makin enak. Jalan mulus dan lebar. Memang sih di beberapa titik masih ada perbaikan, tapi tak lama lagi akan ikut mulus.
Menikmati pemandangan di bukit karang Rangas (sekitar 5 km dari kota Majene) mendorong saya untuk tak segera berangkat.
224 Muhammad Ridwan Alimuddin
Jadinya baru bisa berangkat jam sembilan lewat. Saat matahari telah panas. Targetnya sih mau sampai Malunda. Tapi karena cuaca buruk bagi pengendara sepeda (hujan dan angin kencang), saya lama berhenti di salah satu warung kelapa muda, beberapa kilometer sebelum Somba. Kelapa mudanya enak bukan main, ada gula merah dan jeruk. Nikmatnya di atas level maknyos.
Hujan reda dan tak panas, sekitar jam tiga sore saya lanjutkan perjalanan. Menyempatkan diri singgah di rumah almarhum Muis Mandra, tapi karena anaknya yang ingin saya temui tidak ada, saya tak lama di situ. Lanjut ke utara, juga tak begitu jauh. Setelah menempuh 11 km dari warung kelapa muda, perjalanan hari ketiga dihentikan. Gerimis makin deras. Singgah di salah satu mesjid di Totolisi.
Selesai shalat, perhatian saya tertuju pada aktivitas beberapa ibu rumah tangga di kolom rumah. Mereka sedang membuat “gamacca”, semacam dinding atau plafon yang terbuat dari kulit pelepah batang sagu. Ketertarikan terhadap aktivitas mereka semakin meningkat tatkala salah satu jalan desa yang berada di sekitar mesjid atau perkampungan penduduk diberi nama Jl. Gamacca.
Apakah “gamacca” sesuatu yang spesial sehingga menjadi nama jalan? Sandeq saja yang begitu terkenal di Mandar, setahu saya, belum diabadikan sebagai nama jalan.
Sebagai bagian dari Ekspedisi Bumi Mandar, yakni membuat liputan hal-hal menarik di sepanjang rute, kegiatan pembuatan “gamacca”, apalagi dengan adanya nama Jl. Gamacca, tak saya lewatkan. Ternyata hujan ada hikmahnya. Jika tak hujan, jelas tak singgah, jelas tak menemukan pembuatan “gamacca”.
225Ekspedisi Bumi Mandar
“Kenapa diberi nama Jl. Gamacca jalan ini bu”? tanya saya ke salah satu wanita yang asyik menyelang-nyelingkan kulit “gamo”. Jawabnya, “Sebab di sini ada banyak pembuat gamacca, sampai dua puluh rumah.”
Ibu itu bernama Basse’ atau Amma’ Su’a. Telapak tangannya putih tapi agak kasar. Banyak bekas sayatan. “Ya, tangan sering luka. Itu sudah biasa kami alami saat membuat gamacca,” jawab Bu Basse’. Hal yang diiyakan tetangganya yang juga hadir di kolom rumah, Nurhayati.
Menurut Nurhayati, pembuatan “gamacca” adalah kegiatan utama wanita-wanita di Dusun Totolisi Selatan (Desa Totolisi, Sendana, Majene). “Di sini hampir semuanya wanita yang membuat, termasuk yang pergi mengambil bahannya di bukit, di Rura.” Tambahnya, “Bahannya diambil dari tanaman yang juga menghasilkan umba atau sagu dan daunnya bisa untuk atap rumbia”. “Umba juga dimakan di sini, bisa untuk jepa, bisa buat cendol, dan kue-kue,” tutur Bu Nurhayati, menjelaskan kegunaan sagu (umba dalam bahasa setempat).
“Gamacca” banyak ditemukan di rumah-rumah yang berada di pedesaan. Dulu, hampir semua rumah di Mandar menggunakan “gamacca”. Paling tidak sebagai plafon. “Gamacca” terkenal kuat bila dibanding tripleks atau serat kaca (yang dicampur semen). Bisa sampai puluhan tahun, asal tak kena air. Tapi dibanding dulu, sekarang sudah jarang. Orang lebih pilih yang praktis, semisal tripleks.
Meski jarang, masih ada pesanan satu dua. “Sekarang sudah sedikit, tapi hampir tiap hari ada saja yang datang beli. Ada dari Pamboang, Sendana dan Majene. Baru-baru ini ada yang dari Palu,
226 Muhammad Ridwan Alimuddin
pesan 35 lembar. Kabarnya dibuat sebagai dinding di warung,” jelas Bu Nurhayati.
“Rata-rata kami bisa kerja dua lembar dalam satu hari, kalau fokus di situ. Tapi kalau ada kegiatan lain, paling tidak bisa selesaikan satu lembar. Ukuran paling umum 2x2 meter, ada juga 2x1,” terang Bu Basse. Dia menambahkan, “Ada dua jenis gamacca, bila ada coraknya, itu disebut bunga, kalau tidak bercorak disebut sulajing. Bedanya sepuluh ribu. Yang bunga harganya 50 ribu, yang sulajing 40 ribu. Adapun ukuran kecil, harganya 25 ribu.”
Menurut Bu Basse, proses pembuatan diawali mengambil batang daun pohon sagu. Batang tersebut dikupas kulitnya. Setelah buang daging batang, kulit yang sudah menipis dikeringkang. Kalau sinar matahari bagus, dua hari bisa kering untuk selanjutnya dibuat “gamacca”. Menurut Bu Nurhayati, “Batang yang belum dikupas harganya seribu rupiah, panjang sekitar empat meter.”
Ternyata kegiatan membuat “gamacca” adalah kegiatan turun temurun. Bu Besse yang umurnya berkisar lebih lima puluh tahun menyampaikan bahwa sebelum dia lahir sudah ada proses pembuatan “gamacca”. “Dulu ibu dan nenek saya juga buat gamacca. Pembuatan gamacca membantu mendapatkan uang. Jika mengharap dari hasil pertanian, itu tak seberapa,” terang Bu Besse yang suaminya bekerja sebagai petani.
Ketika dikonfirmasi ke Kepala Dusun Totolisi Selatan, Bapak Saeri, “Pembuatan gamacca sangat bermanfaat di tempat kami. Tapi para pengerajin terkendala pada masalah dana. Mereka tak bisa membuat banyak gamacca, nanti ada yang pesan baru buat. Soalnya untuk pengadaan bahan mereka harus beli terlebih dahulu. Itu membuat pemesan menuggu lama sampai pesanan mereka selesai.”
227Ekspedisi Bumi Mandar
Kegiatan pembuatan “gamacca” patut diperhatikan pemerintah. Kegiatan tersebut terbukti membantu perekonomian masyarakat, selain melanjutkan tradisi pembuatan dinding tradisional. Majene patut bersyukur masih memiliki kelompok masyarakat yang membuat kerajinan “gamacca”. Memang ada juga pembuatan di tempat lain, tapi sepertinya tidak semasif di Totolisi Selatan. Semoga pembuatan “gamacca” masih tetap ada di masa mendatang dan pengerajin mereka memperoleh pendapatan yang layak.
Lama mencari tahu per-gamacca’ang di Totolisi Selatan, membuat saya untuk memutuskan bermalam di sini saja. Kalau lanjut untuk kejar lokasi yang layak untuk pasang kemah (rencana di dekat Palipi), tak akan sampai. Pengalaman sebelumnya, yang tiba di waktu malam, membuat saya agak kerepotan. Kebetulan halaman belakang mesjid, semacam teras yang teratapi, luas sekitar 5x10 meter, lumayan untuk dipasangi kemah. Setelah mendapat restu dari kepala dusun dan perangkat mesjid, selesai makan malam di rumah pak dusun, tenda bulan kembali saya dirikan. Beda dengan dua malam sebelumnya, tenda bulan kali ini tidak berada di bawah kolom langit. Tapi atap teras mesjid.
Majene, Negeri Seribu Teluk
Melintasi pesisir barat Pulau Sulawesi, antara Majene dengan Mamuju sudah puluhan kali. Mobil tak terhitung, dengan motor tiga kali, dengan sepeda baru akan satu kali. Lewat laut, beberapa kali. Tapi angkat jempol akan keindahan pantai Majene baru disadari ketika naik sepeda. Betul. Serius.
Meninggalkan Totolisi Selatan sekitar pukul delapan pagi. Tumben agak cepat berangkatnya, dibanding hari-hari sebelumnya.
228 Muhammad Ridwan Alimuddin
Cuaca cerah membuat saya berani pasang target untuk tiba di perbatasan Majene – Mamuju. Jaraknya hampir 70 km, karena cepat berangkat, bisa sampai dalam dua sesi. Sesi pertama sebelum tengah hari, sesi kedua setelah jam tiga. Rencana akhir sesi pertama di Baturoro.
Jalanan mulus, rata-rata datar, walau ada juga yang naik turun, membuat perjalanan ekspedisi terasa menyenangkan dan membahagiakan. Tepatnya di antara Ulidang dan Waigamo. Atau kawasan Tammerodo. Beberapa kilometer setelah berziarah di makam budayawan Mandar, Muis Mandra, teluk yang selama ini membuatku penasaran dengan tenang dan serius saya perhatikan.
Lekuk teluk kecilnya sangat indah, airnya jernih bagai kolam. Dan tenang. Cobanya saya membawa masker atau kacamata selam, saya akan singgah, turun ke laut, berenang dan menikmatinya. Saya berani bertaruh, teluk paling indah di Sulawesi Barat atau sepajang pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dari Jeneponto di selatan hingga pantai Suremana, “spot” ini paling cantik. Setidaknya saya sudah menyaksikan sepanjang pesisir itu, jadi ada dasar untuk membandingkan.
Hutan rimbung di garis pantainya, dihiasai beberapa pohon kelapa dan pisang. Tapi yang membuat amat-amat cantik adalah bebatuan di antara garis pantai dan bagian laut yang dalam. Saya belum tahu kondisi terumbu karangnya di bawah. Jika terumbu karangnya tak rusak oleh tangan-tangan jahil (pembom dan pembius ikan), sebagai pantai, kawasan yang tak begitu luas itu akan sempurna sebagai keping surga yang jatuh ke dunia. Tapi harapan bahwa karangnya bagus tidak begitu besar. Kawasan teluk cantik tersebut berada di tempat sepi. Artinya, para pembom
229Ekspedisi Bumi Mandar
dan pembius bebas beraksi di situ. Untuk memastikan, sekaligus melepas hasrat pada teluk cantik itu, suatu waktu saya akan kembali untuk menyelaminya. Mudah-mudahan.
Majene adalah negeri seribu teluk. Selain teluk di atas, Majene masih memiliki sekian banyak teluk yang cantik-cantik dengan kekhasan masing-masing. Keindahan teluk di Tammero’do dan sekitarnya jauh lebih tinggi kelasnya daripada Dato’ (Majene) dan Palippis (Polman). Apalagi Barane, tak ada apa-apanya. Seujung kuku.
Saya belum tahu dan belum melihat sejauh mana pemerintah Majene, khususnya dinas yang mengurusi sektor pariwisata, mengelola kecantikan pantai Majene di bagian “bawah” (Sendana hingga Malunda). Paling tidak saya belum melihat kampanye masif yang menawarkan keindahan tersebut.
Kira-kira apa bentuk “jualan” yang asetnya pantai – teluk tersebut? Idealnya sih pelayaran (cruise) ke spot tersebut dan mandi-mandi di laut, yaitu snorkling atau menyelam. Sebagaimana yang banyak dilakukan di Bali. Tapi itu belum bisa dilakukan bila tak diketahui kondisi karangnya di bawah. Apakah masih sehat atau tidak. Juga fasilitas – akomodasi disekitarnya yang belum memadai.
Yang paling berpotensi adalah pihak pemerintah Majene atau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan even tahunan, yaitu Tour de Majene (memimjam istilah Tour de France). Yaitu lomba sepeda yang rutenya di sepanjang jalan antara Majene dengan Malunda. Keindahan alam pantai Majene dan jalanannya nan mulus serta lebar amat mendukung. Anggaran 1 M (bandingkan Sandeq Race yang di atas 1 M dan Pawai Budaya Nusantara
230 Muhammad Ridwan Alimuddin
2013 yang 800 juta) untuk pelaksanaan lomba serta hadiah akan mengundang ratusan pesepeda baik di Sulawesi maupun dari tempat lain di Indonesia. Anggaran 1 M itu sangat kecil.
Bisa dibayangkan jika ada lomba sepeda yang diikuti ratuan orang, bisa dipastikan Majene akan memiliki kelebihan dibanding daerah lain di Sulawesi. Bukan itu saja, akan ada efek lain, hubungannya dengan perputaran ekonomi di daerah ini. Hotel, restoran, souvenir-souvenir, dan hal lain yang bisa menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat.
Melaksanakan lomba sepeda, baik yang diikuti atlet profesional maupun amatir, tak mustahil diwujudkan. Pemerintah atau legislatif tinggal melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan hal itu, baik di Jawa maupun di Sumatera. Salah satunya yang terkenal dan telah menjadi kalender rutin adalah Tour de Singkarak. Kabarnya beberapa tahun lalu pemerintah Polewali Mandar mengidekan lomba sepeda rute Mamuju – Polewali. Tapi urung dilaksanakan, salah satu alasannya karena waktu itu sedang marak-maraknya perbaikan jalan Trans Sulawesi. Alasan jalan rusak dan sedang diperbaiki tak berlaku saat ini.
Perjalanan dengan menggunakan sepeda di sepanjang Majene selama dua hari (mulai 17 Juni telah melintasi jalan trans di wilayah Mamuju), salah satu hasilnya adalah ide tersebut di atas. Dibanding kabupaten lain di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene harus memilih cara-cara kreatif untuk memajukan daerahnya. Baik dari segi pendidikan (sebagai Kota Pendidikan) maupun dari aspek wisata dan olahraga.
Jika pun keindahan tersebut tidak “diapa-apain” (dikelola sebagai aset wisata), setidaknya pengambil kebijakan menjaga keindahan
231Ekspedisi Bumi Mandar
tersebut. Hutan di garis pantai tidak malah ditebang, misalnya alasan pelebaran jalan; dilarang untuk sebagai daerah pemukiman apalagi untuk hotel; dan patroli untuk mengejar pembom dan pembius ikan juga sampai di kawasan ini. Atau, pihak terkait (dalam hal ini dinas yang mengurus pariwisata) memberi perhatian terhadap kawasan tersebut. Tidak hanya lewat sepintas lalu.
Pernah ada teman yang menyampaikan kepada saya, bahwa keindahan teluk-teluk Majene membuat takjub Dahlan Iskan. Sampai mengalahkan pantai-pantai di Eropa.
Menyisir Pesisir Barat Tappalang
Meninggalkan Maliaya’, kampung paling ujung utara Kecamatan Malunda, Majene sekitar pukul 7.30. Di seberang jembatan sudah masuk wilayah Kabupaten Mamuju. Jarak ke kota Mamuju tinggal 30 km, relatif dekat di atas kertas. Realitasnya, itu adalah rute paling berat. Lebih 20an km jalur berbukit. Membayangkannya saja sudah capek, bagaimana kalau melintasinya dengan sepeda.
Maliaya’ hingga Tappalang, di daerah yang terkena abrasi parah rutenya pemanasan saja. Datar, mulus, jalanan lebar. Dengan leluasa saya bersepeda sambil memotret bekas pemukiman penduduk di garis pantai dan kegiatan pembangunan tanggul. Bagi saya, tanggul itu buang-buang duit saja. Tak akan tahan menahan hempasan ombak. Jangka pendek memasang pemecah ombak di luar, berupa cakar-cakar beton. Hantampan ombak dinetralisir dengan memecahnya. Kalau tembok, akan frontal. Jangka panjang, pulihkan terumbu karang yang selama ini melindungi pantai Tappalang.
232 Muhammad Ridwan Alimuddin
Melewati perkampungan, jalanan mulai menanjak perlahan. Itu tanda bahwa jalur berbukit akan dimulai. Ketika melintas di persimpangan, yang ada plank arah jalan, terbersit ide untuk mengubah rute: langsung ke Mamuju dengan jalur standar atau melalui jalur Pasa’bu.
Jika lewat jalan trans, jalurnya jelas, aspalnya mulus, jaraknya dekat, hanya 30 km. Tapi bila memilih lintasan itu, siap-siap mengayuh mendaki sesering mungkin serta ada banyak kendaraan yang mengancam nyawa. Lewat jalur mudah itu, salah satu hasil utamanya capek saja. Beda dengan jalur alternatif.
Bila lewat Pasa’bu, rute tak jelas, kondisi jalan juga demikian, agak jauh sebab harus memutar yang selisihnya 20an kilometer dibanding jalur biasa, dan suasana jalan yang mungkin agak sepi. Hanya saja, bila berhasil lewat jalur Pasa’bu, selain capek, juga dapat pengalaman besar. Ya, itu sangat jelas sebab jalur itu jalur yang sangat langka dilalui kendaraan (jika pun bisa) dan kabarnya jalur trans Sulawesi akan digeser ke sana.
Di pertigaan berhenti sebentar, mengecek peta dan bertanya ke tukang ojek. Di atas peta ada simbol bahwa di situ ada jalan. Sedang jawaban tukang ojek, “Jalurnya susah, tidak bisa kendaraan.” Saya timpal, “Apa bisa sepeda, setidaknya jalan kaki?”. Mereka mengiyakan sambil memberi informasi bahwa ada beberapa bukit yang harus dilalui dan ada bagian jalan sekitar dua kilometer yang tidak bisa dilalui kalau air laut pasang. “Kalau siang airnya surut, bisa dilalui,” jelas mereka.
Mendengar informasi tersebut, saya pastikan tanpa ragu untuk melalui rute yang melalui Pasa’bu. Kegiatan bersepeda yang dilakukan kan bukan naik sepeda semata, tapi ekspedisi. Dan salah
233Ekspedisi Bumi Mandar
satu defenisi ekspedisi adalah melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jarang dikunjugi. Bukan itu saja, saya mau mengetes kemampuan melalui jalur bukan jalan raya. Kan selama ini (sejak Senin) lewat aspal butas terus. Dengan kata lain, ada beberapa hal yang bisa diperoleh jika menggunakan jalur berbeda.
Saya tak ragu sebab jaraknya sekitar 50 km. Jika bersepeda terus, itu bisa diselesaikan dalam satu hari. Paling tidak saya harus tiba di Sumareq sebelum malam. Saya pernah ke Sumareq beberapa tahun lalu (saat riset sandeq), jadi relatif aman di sana dibanding bagian lain (antara Pasa’bu dengan Sumareq) yang belum pernah saya datangi.
Menuju Pasa’bu kondisi jalan mantap. Pemandangan sekitar juga lumayan, ada sawah ada pantai. Salah satu yang membuat penasaran adalah Tanjung Ngaloq, tempat paling keramat di kalangan nelayan-nelayan Mandar.
Meninggalkan Pasa’bu kondisi jalan mulai tak baik. Kebanyakan sirtu (pasir batu) dan berbukit-bukit. Tapi bukitnya masih jauh lebih sedikit dibanding lewat jalur standar. Melitasi Tappalang Barat (yaitu dari Tappalang belok ke arah barat terus ke utara hingga sampai Simboro dan kembali belok ke timur menuju jalan trans), bagaikan melintasi atau menuju pedalaman. Ya, betul-betul seperti pedalaman. Saya langsung ingat ketika menuju Mosso atau Pallis di perbukitan Balanipa. Jalur berbukit dengan jalan sirtu. Uniknya, pedalaman yang ini berada di pesisir. Ombak jelas terdengar. Mirip-mirip suasana di pulau-pulau kecil terpencil.
Selain kondisi lingkungan atau jalan, kehidupan masyarakatnya pun sangat mirip suasana pedalaman. Rumah satu-satu dan tak begitu bagus dibanding rumah-rumah di perkotaan. Anak-
234 Muhammad Ridwan Alimuddin
anak yang bermain di halaman atau di jalan penasaran, kadang terheran-heran, ada sepeda ‘aneh’ melintasi kampung mereka.
Kecepatan kayuhan sepeda tak secepat di jalan raya. Jelas, kondisi jalan beda. Mendaki identik dengan capek, menurun penuh dengan was-was. Menurun di jalan aspal senang bukan main, bisa lepas tangan. Beda menurun di jalan berkerikil. Lepas tangan sedetik saja hasilnya celaka. Kadang ban belakang tak melengket, meluncur. Dibantu dengan rem depan juga agak bahaya, bisa-bisa terpelanting ke depan jika terlalu dalam direm depan. Bunyi kerikil tergilas menggenapkan risau. Jika terjatuh, kalau bukan “sa’dang” (sakit dada) atau “soyo” (susah menjelaskan defenisinya), pasti lecet parah.
Jika etape jalan aspal ucapan bismillah ketika memulai naik sepeda saja, yang ini bismillahnya banyak: saat meluncur turun dan karena sering stop (ngos-ngosan sehabis mendaki) maka sering juga mengangkat kaki untuk duduk di sadel. Belum lagi kalau turun jika saya tak kuat mengayuh di jalur berbukit. “Bismillah … bismillah ….”
Selama belum sampai atau melewati lintasan di pantai, saya tak lama istirahat. Takut air pasang sehingga tak bisa melintas. Jika di hari-hari sebelumnya saya istirahat saat jam 12 dan mulai lagi pada jam tiga, kali ini langsung-langsung. Artinya, istirahat tak lama-lama. Agar tak kelaparan atau kekurangan energi, saya bawa serta logistik yang mudah dimakan saat bersepeda. Yakni biskuit, kacang, dan permen. Serta dua botol air putih. Makan siang dengan nasi untuk kemudia bobo-bobo siang tak dijadwalkan.
Walau jalan rusak, motor bisa lewat dengan mudah. Beberapa mobil juga ada yang melintas, tapi satu dua. Ternyata,
235Ekspedisi Bumi Mandar
kendaraan mobil hanya bisa sampai Lebani. Saya tiba di Lebani sekitar pukul satu siang padahal jauhnya dari jalan trans Sulawesi sekitar 25 km saja. Itu ditempuh lebih lima jam, kalau di jalur aspal bisa dua kali lipat.
Melewati Lebani, jalannya bukan lagi sirtu tapi jalan setapak. Kadang melintasi kebun kelapa, kebun pohon jati, halaman rumah penduduk (pernah masuk kebun rumah sehingga saya harus keluar lewat pintu halaman), sungai-sungai kecil, dan pasir pantai. Walau telah berada di kondisi capek, jalur itu menyenangkan. Unik dan mengasyikkan. Saya sering berhenti untuk mengubah-ubah posisi kamera GoPro di sepeda guna mendapatkan sudut terbaik di rute unik.
Sebab jalurnya tak jelas, setiap ada orang saya selalu bertanya mengenai jalur ke arah Sumareq. Beberapa kilometer dari Lebani, yakni di daerah Tekke (Takke atau Tikkeq?) lintasan yang berupa pasir pantai mulai tampak. Syukurlah masih surut. Saya mencoba untuk tetap menggunakan sepeda tapi tak bisa. Ban terperosok. Ya, sebab pasirnya lembut. Mau tak mau menuntun sepeda di terik. Ada jejak ban motor, artinya jalur yang saya lalui betul.
Berjalan kurang lebih satu kilometer di pasir pantai, jejak ban motor terhenti di bukit karang setinggi 20an meter. Mana jalannya. Saya ambil nafas sambil melihat di sekeliling, mungkin ada jalan setapak di situ. Tak ada, yang ada hanya hutan rimbun. Beberapa menit kemudian, seorang bapak tua berjalan perlahan dengan hati-hati dari atas bukit karang. Oh, itu jalannya. Apakah saya harus memanggul sepeda sambil mendaki? Apakah ini yang disebut Batu Losa yang kabarnya pernah akan dipasangi dinamit oleh pihak militer agar Pasa’bu bisa tembus Sumare’?
236 Muhammad Ridwan Alimuddin
Jelas capek, setelah mengayuh sepeda puluhan kilometer dan berjalan satu kilometer di atas pasir pantai, dari Maliaya’ sampai Batu Losa (Jumat, 17/5). Asam laktat menumpuk di paha bagian depan. Itu penyebab pegal. Seakan belum cukup, harus mendaki lagi di atas bukit karang. Untung bukan karang kasar. Meski demikian, tanah yang mudah lepas tampak lebih berbahaya. Ya, mudah tergelincir. Jika jatuh sambil memanggul sepeda lalu jatuh ke jurang?
Tak mau berpikir negatif lama-lama, setelah cukup nafas, segera sepeda saya angkat di sisi kanan. Untung rangka sepeda terbuat dari aluminium, jadi agak ringan. Berjalan perlahan, hati-hati. Saya jauh lebih hati-hati daripada orang tua renta yang berjalan menurun, berlawanan arah dengan saya. Lekuk-lekuk tanah sedikit membantu sebagai tempat menumpu kaki. Perlahan tapi pasti, syukurlah bisa tiba di puncak. Paru-paru kembang kempis plus jantung berdetak keras dibuatnya. Itulah rintangan berat terakhir jika melakukan perjalanan dari Tapalang Barat menuju Mamuju (demikian juga sebaliknya).
Walau menempuh jarak lebih jauh dan berat, sengaja rute Ekspedisi Bumi Mandar memutar ke Pasa’bu lalu ke Sumare’ untuk kemudian ke Kota Mamuju agar kondisi jalan tersebut bisa disaksikan langsung. Dikatakan demikian, sebab pernah diberitakan bahwa Pemerintah Sulawesi Barat akan membuka akses jalan (baca: bisa dilalui mobil ataupun kendaraan lain dengan lancar).
“Pemprov Sulawesi Barat telah mengalokasikan anggaran Rp3,7 miliar untuk membangun jalan lingkar, tembus antara Kecamatan Tapalang Barat menuju Kota Mamuju,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar Ramli Hamid di Mamuju,
237Ekspedisi Bumi Mandar
Selasa (07/05). Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga digunakan untuk meledakkan salah satu bagian bukit Batu Losa, yaitu bagian yang harus saya daki sambil memanggul sepeda. Mengapa disebut Batu Losa? Mungkin karena di sisi bukit karang tersebut, yang persis berbatasan dengan pantai, semacam ada batu besar yang berlobang (tembus, atau “losa” dalam Bahasa Mandar).
Pada dasarnya, Pasa’bu bisa tembus ke Sumare’ dengan menggunakan motor. Tapi karena ada bukit Batu Losa yang menghalangi, hal itu sulit dilakukan (kecuali motor bisa diangkat melewati bukit, sebagaimana jika menggunakan sepeda; atau dilewatkan melalui laut dengan menggunakan perahu). Adapun mobil, jauh lebih sulit sebab masih ada beberapa bagian yang hanya berupa jalan setapak, melintas kebun kelapa, dan pasir pantai.
Kelihatannya memang berjalan memutar, tapi bila betul dibuka jalan mulus melewati Tapalang Barat, perjalanan menuju Mamuju atau sebaliknya, jauh lebih menyenangkan (tidak mabuk), aman, dan cepat. Dibanding jalur sekarang, memang tampak seperti potong kompas, tapi naik turun bukit, melalui jurang, dan bahaya lainnya.
Jadi wajar saja warga, baik yang “terisolir” di beberapa kampung di Tapalang Barat maupun warga yang sering bolak-balik ke Mamuju dari selatan, mengharapkan janji pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diwujudkan.
Dikatakan sebagai janji, sebab menurut arsip berita Radar Sulbar, yang dimuat pada 24 April 2012, masyarakat pernah menagih pemerintah akan janji-janji kampanye pada tahun 2007. Menurut Suhardi Duka pada 21 April 2012, “Sejak tahun 2007 dipidatokan
238 Muhammad Ridwan Alimuddin
bahwa akan dibangun jalan lingkar barat dari Tapalang Barat terus ke Simboro dan masuk ke Mamuju. Dulu disampaikan jalan itu untuk mengurangi tikungan dan seringnya longsor di jalur Botteng.”
Suhardi Duka juga menyampaikan bahwa jika janji pemprov pada mulanya sungguh menggembirakan masyarakat Mamuju. Makanya pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2011, masyarakat Tapalang Barat cukup apresiatif karena mengingat bahwa akan segera dibangunkan jalan lingkar hotmiks. Tapi kenyataannya, sampai April 2012 masyarakat masih dibuat menunggu kapan jalan lingkar tersebut dapat dinikmati oleh mereka. Sebagai Bupati, Suhardi prihatin dengan kondisi ini.
Masyarakat Tapalang Barat juga pernah berunjuk rasa di DPRD Sulbar pada 10 September 2012 lalu. Antara masyarakat dengan Kepala Dinas PU Sulbar dan DPRD Sulbar ada kesepakatan. Kesepakatan dalam pertemuan tersebut ialah: Pertama, kepala Dinas PU Sulbar akan memfasilitasi perubahan status jalan lingkar Tapalang Barat menjadi jalan strategis provinsi. Kedua, Kepala Dinas PU Sulbar akan menganggarkan dalam APBD Sulbar 2013 untuk pengerjaan jalan lingkar Tapalang Barat hingga Sumare’, khususnya pada tiga titik, yakni di Losa, pendakian SS, dan di Tapangkan sepanjang 15 kilometer. Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Dinas PU Sulbar Idham Hasib dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Muhammad Jayadi. Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan anggota DPRD Sulbar, Thamrin Endeng, Rakhmat AR, Andi Usman, dan H Abidin.
Ketika Ekspedisi Bumi Mandar melintas jalan yang dimaksud, setelah satu tahun berselang di mana Suhardi Duka menyampaikan hal di atas; setelah hampir sembilan bulan setelah ada kesepakatan
239Ekspedisi Bumi Mandar
antara masyarakat dengan legislatif dan eksekutif, jalan yang diperjuangkan agar diperbaiki, tampak belum diapa-apain, khususnya kawasan Batu Losa.
Setelah menuruni pendakian, perjalanan menuju utara relatif lancar. Maksudnya, bukan lagi jalan setapak. Jalanan sudah agak lebar, tapi masih berupa sirtu. Ada bangunan tanggul yang sudah rusak. Kampung yang dilintasi antara lain ialah Tapandullu, Malawa, hingga Sumareq. Nanti di Sumareq jalanan beton mulai mantap.
Sejak dari Pasa’bu sampai Tanjung Rangas, memang ada jalan berbukit, yang membuat saya harus turun dari sepeda (sebab tak kuat mengayuh). Tapi jaraknya tak beratus meter sebagaimana jalur kalau lewat Botteng atau “Jambatang Bolong”. Singkat kata, memang jarak jalan lingkar hampir dua kali lipat jauhnya dibanding jalan potong kompas (yang digunakan saat ini). Tapi kalau jalan lingkar itu mulus dengan aspal butas, kecepatan melintasinya jauh lebih cepat dan aman.
Menjelang jam lima sore, setelah meninggalkan Maliaya’ pukul 7.30 pagi, akhirnya saya tiba di titik nol kilometer Mamuju, persis di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Mudah-mudahan saja janji Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera membuat jalan layak pakai melalui pantai Tapalang Barat bisa segera diwujudkan oleh pemimpin kita yang berkantor di gedung mewah tersebut.
Pulau Karampuang, Sempurna untuk “Cross Country”
Menempuh kurang lebih 240 km selama lima hari, dari perbatasan Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan di Paku hingga
240 Muhammad Ridwan Alimuddin
Kota Mamuju, adalah tahap awal Ekspedisi Bumi Mandar. Bagi saya pribadi, itu pengalaman pertama naik sepeda terjauh yang dilakukan tiap hari. Bila dimasukkan jarak tempuh latihan, lebih 300 km. Jelas capek, jelas pegal.
Jarak dan durasi tempuh di atas masih di bawah dibanding yang pernah dilakukan sahabat saya dari Pa’giling, Mus Muliadi, naik sepeda dari Makassar sampai Tinambung (sekitar 290 km) dalam waktu dua hari saja. Berbeda soalnya Ekspedisi Bumi Mandar tidak mengutamakan kecepatan, tapi singgah-singgah meliput. Selain harus istirahat untuk menjaga kondisi. Kan perjalanan masih panjang.
Tak ingin kena dampak kegiatan fisik berlebih, setelah tiba di Mamuju, saya istirahat dua hari. Fisik harus dipulihkan. Namun tidak juga istirahat total, sesekali otot harus diregangkan. Tiba Jumat sore, Sabtu lebih banyak istirahat. Nanti pada hari Minggu, ekspedisi dilanjutkan. Tapi lokasinya bukan di Pulau Sulawesi, tapi Pulau Karampuang.
Telah lama dicitakan untuk mengelilingi pulau tersebut. Pernah sih jalan kaki memotong, tapi belum keliling. Menggunakan sepeda paling memungkinkan. Jalan kaki kelamaan, naik motor tidak mantap juga. Sekitar jam delapan pagi lewat, walau langit mendung tanda akan hujan, naik kapal kecil menuju Pulau Karampuang. Sepeda tentu dibawa serta.
Tak membuang waktu, khawatir hujan deras turun, sepeda langsung dikayuh. Saat mendarat di sisi timur pulau, langsung belok kanan, menyusuri jalan beton selebar lebih satu meter. Jalan sudah rusak, tapi pas sebagai rute bersepeda “cross country”. Sepedanya cocok dengan kondisi jalan, termasuk jalan setapak
241Ekspedisi Bumi Mandar
dari tanah, jalan becek, batu-batu karang, dan jalanan yang licin.
Jalan lingkar di Pulau Karampuang harus dimanfaatkan. Bukan hanya sebagai akses masyarakat setempat, tapi untuk wisatawan atau penggemar sepeda. Yang saya maksud, jalan-jalan tersebut sempurna sebagai rute bersepeda “cross country”. Sangat menarik, beberapa bagian menaikkan adrenalin. Walau begitu, rintangan atau rute jalan tersebut masih relatif aman untuk pesepeda “cross country” amatir.
Walau ada jalan keliling pulau, ada bagian yang, bagi saya, tidak bisa dilalui dengan menggunakan sepeda. Soalnya sangat miring dan berbentuk tangga. Apalagi kalau habis hujan, seperti kemarin, ban sepeda tak bisa lengket. Direm pun tetap tergelincir. Alias licin bukan main. Saya pun hati-hati menuntun sepeda. Jalur itu berada tak jauh dari Sumur Jodoh. Tapi kalau profesional “down hill”, itu tantangan tersendiri.
Melewati jalur tersebut “track-nya” lain lagi, jalan berlumpur. Melalui itu, sensasi ber-“cross country” betul-betul terasa. Saya sampai-sampai lupa bahwa saya sedang ber-ekspedisi, bukan lintas-melintas saja dengan sepeda.
Kesimpulannya, jalan lingkar di Pulau Karampuang, menurut GPS yang saya gunakan berjarak sekitar 10 km, adalah “track” bersepeda lintas alam yang sangat menarik. Membayangkan di masa mendatang pemerintah Kabupaten Mamuju atau pihak swasta mengadakan lomba sepeda “cross country” di Pulau Karampuang. Kan ada banyak peminat sepeda di Mamuju dan ada juga komunitas.
Masyarakat harus dididik untuk ikut kegiatan murni kompetisi. Tidak hanya sepeda santai yang, agar ramai, adakan saja “voucher”
242 Muhammad Ridwan Alimuddin
atau diimingi hadiah-hadiah setelah pengundian (kadang banyak juga yang nakal karena mengumpulkan kupon sebanyak mungkin). Selain itu tidak terlalu mendidik, juga keluarannya (output) tidak sebaik bila kompetisi atau lomba yang diadakan. Jika lomba, siapa tahu dari Mamuju muncul bibit pesepeda yang bisa mengharumkan nama daerah ini.
Masa’ bisa kalah dengan orang kota yang notabene tak ada areal “cross country” di tempat tinggal mereka. Maksud saya, kita di daerah dilimpahi kawasan atau daerah yang jika dimanfaatkan bisa menjadi arena latihan. Dan itu bisa didatangi dengan cepat dan gratis. Coba kalau di Jakarta, mau dapat “track” sebagaimana di Pulau Karampuang, harus ke Bogor atau Banten dulu. Demikian juga di Makassar. Dan, itu butuh biaya dan waktu lama. Kita di Mamuju, kurang satu jam sudah bisa tiba. Udaranya pun super segar.
Di daerah kita saat ini, meski sudah ada jalan aspal mulus, tapi untuk disebut betul-betul seperti kota, belum saatnya. Jalan-jalan setapak, berlumpur, sirtu masih lebih banyak. Di satu sisi memang itu kendala, di sisi lain itu yang dicari-cari pe-“cross country”. Jadi harus dimanfaatkan.
Kaitannya dengan sepeda, jika kita berada di kota-kota utama di Sulawesi Barat, yang banyak dimiliki masyarakat adalah sepeda jenis “cross country”. Ya, itu memang wajar sebab kondisi daerah kita lebih cocok menggunakan jenis sepeda tersebut. Tapi sepertinya bukan itu alasan utama, dugaan saya, jenis “cross country” lebih gagah kelihatan dibanding jenis sepeda lain.
Di sisi lain, walau banyak yang menggunakan sepeda jenis itu, tapi sepeda itu kebanyakan dipakai di jalan mulus. Di mana lebih cocok menggunakan sepeda jenis “city bike”. Malah, sepeda jenis
243Ekspedisi Bumi Mandar
“all mountain” hanya digunakan jalan-jalan mulus. Tidak dipakai di gunung-gunung. Kan mubazir.
Secara umum ada lima jenis sepeda, misalnya di salah satu merek yang marak digunakan di daerah kita. Oleh orang awam kadang hanya disebut “sepeda santai” dan atau “sepeda gunung”. Pertama adalah jenis “city bike”. Jenis ini ideal dipakai jalan mulus, di perkotaan. Tidak didesain terhadap benturan. Makanya tak ada “per” atau suspensi, baik di depan maupun di tengan (belakang).
Kedua jenis “cross country”. Dirancang untuk jalan mulus dan jalan pedesaan (tanah, kerikil, basah). Ciri khasnya adalah sudah menggunakan satu suspensidi garpu depan. Kadang juga disebut jenis “hard tail” (ekor keras) sebab di bagian tengah atau belakang belum ada peredam benturannya. Yang dipakai dalam Ekspedisi Bumi Mandar adalah jenis ini.
Berikut jenis “all mountain”. Dirancang cukup kuat sebab rute yang cocok adalah medan berat, naik turun gunung. Berbeda dengan “cross country”, jenis ini telah memiliki dua suspensi. Makanya disebut juga jenis “full suspension”. Walau kelihatan lebih gagah daripada jenis “cross country”, jika suspensi tengah tak bisa tidak diaktifkan, jenis “all suspension” kurang cocok digunakan di jalan mulus. Sebab suspensi tengahnya mempunyai pengaruh. Yaitu sepeda lebih berat untuk dikayuh. Anehnya, orang-orang kaya di daerah kita, yang bersepeda untuk santai-santai, lebih banyak yang menggunakan sepeda jenis “all mountain” atau “full suspension”.
Terakhir adalah jenis “down hill” (turun lembah) dan “dirt jump”. Jenis ini, hanya digunakan orang-orang profesional atau minat khusus. Yang pertama didesain untuk menuruni bukit. Konstruksinya didesain sedemikian rupa agar aman menuruni
244 Muhammad Ridwan Alimuddin
lembah yang curam dan kondisi jalan medan berat (berkerikil). Jenis ini, bila digunakan dalam waktu lama di jalan mulus, akan membuat cepat lelah. Sebab ukuran bidang kontak di ban lebih lebar.
Adapun jenis “”dirt jump” adalah sepeda yang biasa digunakan remaja atau pemuda yang hobi melakukan atraksi melompat (jumping) di jalan perkotaan atau arena khusus untuk itu. Orang awam biasa menyebutnya sepeda “bmx”, yang berasal dari kalimat “bicycle motocross” (kata “cross” disingkat menjadi huruf X).
Demikian sekilas tentang jenis “sepeda gunung”. Mana yang mau dimiliki, tergantung pada peruntukannya. Mau dipakai latihan jantung atau bersepeda santai, pakai jenis “city bike” saja. Untuk anak muda yang mau agak menantang, bisa “cross country” atau “mountain bike”. Harga berapa? Sepeda itu bertingkat-tingkat, kisarannya dari 1 juta sampai 100 juta. Yang dipakai dalam Ekspedisi Bumi Mandar harga sepedanya dua jutaan. Sudah lumayan untuk ekspedisi tahap pertama. Entahlah kalau melintasi daerah perbukitan yang “track-nya” sebagaimana di rute yang akan dilalui berikut.
Sungai Kalukku, Seperti Sungai di Amerika
“Mindaiq ai kaneneq,” pesan canda teman saat melihat foto profil di Blackberry saya; saat membaca “Berkemah di pinggir Sungai Kalukku”. Meski di pinggir sungai, sepertinya tak ada bahaya buaya (kaneneq dalam bahasa Mandar). Airnya dangkal dan deras. Beda kalau dalam dan diam.
Akhirnya saya bisa berkemah persis di pinggir sungai. Ada kenikmatan tersendiri memasang tenda tak jauh dari sungai. Apalagi kalau sungainya bersih dan suasana alam disekitarnya cantik,
245Ekspedisi Bumi Mandar
sebagaimana yang dimiliki Sungai Kalukku, tak jauh dari jembatan Tasiu’. Ada area berumput, yang sempurna untuk memasang tenda. Sesaat setelah tenda terpasang, saya memotretnya. Teman-teman yang melihat foto itu, baik di Blackberry maupun Facebook rata-rata sama komentarnya: indah, wow.
Ya, memang indah. Sebab memang Mandar atau Sulawesi Barat memiliki banyak keindahan. Hanya saja, kita tak sadar ada keindahan itu. Padahal kadang itu adanya di “belakang rumah” kita.
Lebih sepekan sejak dari perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Paku – Mamuju bisa dikatakan satu tahap tersendiri. Tapi saya belum merasa “sukku” sebagai satu tahap bila tidak sampai ke Suremana, sebagaimana yang direncanakan. Tapi rencana tersebut berubah setelah tiba di Mamuju. Maunya belok kanan, menuju pegunungan, menuju Mambi – Mamasa – Sumarorong terus turun ke Polewali. Yang levelnya bisa juga menjadi penyempurna tahap pertama Ekspedisi Bumi Mandar ini.
Ada beberapa pertimbangan mengapa rencana itu agak kuat belakangan. Pertama, di peta, jaraknya lebih dekat dibanding kalau ke Suremana. Tapi, itu di atas kertas. Realitasnya, jalurnya berat: berbukit, jalan tidak mulus, di beberapa bagian longsor, melalui hutan (kirai – kanan), dan asing bagi saya. Sebab memang belum pernah melalui jalur tersebut. Untuk sisi ini itu adalah tantangan sekaligus rintangan (berat).
Alasan kedua, lebih menarik kalau ke sana. Sebab saya akan bisa mendatangi semua wilayah-wilayah tujuh kerajaan di pegunungan alias Pitu Ulunna Salu. Terus terang saya belum pernah mendatangi sebagian besar anggota Pitu Ulunna Salu. Pasti ada hal baru bagi saya yang akan memperkaya ekspedisi ini. Antara lain,
246 Muhammad Ridwan Alimuddin
mencari tahu bagaimana Pitu Ulunna Salu berhubungan dengan Pitu Baqbana Binanga. Bagaimana mereka saling mengundang atau memenuhi undangan. Dengan kata lain, mereka itu lewat mana jalannya, misalnya, ada undangan dari Kerajaan Balanipa atau ketika deklasari Allawungan Batu di Luyo akan diadakan? Sebab sepertinya mereka tidak menggunakan jalur utama saat ini, yakni dari Polewali – Sumarorong – Mambi dan seterusnya. Pasti ada jalur lain.
Masih banyak alasan lain, antara lain, pola pemukiman penduduk, teknik pertanian, kondisi jalan, sekilas kehidupan masyarakat, dan sebagainya.
Tapi sepertinya pilihan tersebut ditunda atau dikembalikan pada rencana sebelumnya. Bahwa kali ini, di tahap awal ini rutenya adalah Paku – Suremana. Sekitar jam empat sore lewat, ketika berada di persimpangan: dari Mamuju ke Pasangkayu atau ke Kalumpang, ada pertimbangan untuk menunda. Faktor utama ialah cuaca. Hampir tiap hari, tampak dari kejauhan, pegunungan selalu hujan. Sebagaimana yang terjadi dalam perjalanan dari Mamuju ke Tasiu’. Bukan hanya di pantai, pegunungan juga. Sebab saya bersepeda, pasti itu rintangan berat. Apalagi harus melalui pegunungan. Lain halnya jika melintas di jalan raya.
Setelah memutuskan untuk tidak jadi ke arah Mambi, saya terus ke utara. Harus mencari tempat berkemah. Sudah jam lima. Tak lama lagi gelap. Ada teman sekolah dulu menawarkan rumah kerabatnya. Tapi saya lebih memilih untuk berkemah di sekitar pos Ekspedisi NKRI di Tasiu’. Beberapa bulan lalu saya pernah ke situ, di sebuah lapangan. Di situ aman dan layak untuk berkemah.
Sekitar seratus meter sebelum sampai di tempat belok ke arah pos Ekspedisi NKRI, ketika melintas di atas jembatan Sungai
247Ekspedisi Bumi Mandar
Kalukku (beberapa ratus meter dari Pasar Tasiu’), perhatian saya tertuju pada tempat lapang di pinggir Sungai Kalukku. Seperti orang yang melihat gadis, pandangan pertama, langsung jatuh cinta. “Saya harus berkemah di sana,” bisik dalam hati. “Bagaimana cara ke sana?” tanya saya ke pemuda yang kongkow-kongkow di trotoar jembatan. “Ke arah situ, nanti belok turun melewati kolom jembatan,” jawab mereka. Selesai menyampaikan terima kasih, saya segera meluncur turun. Ingin segera menjamah sang “gadis” alias memasang kemah dan menikmati sejuknya Sungai Kalukku.
Sungai Kalukku ber-hulu di sekitar Keang atau Sondoang. Sekita lima kilometer setelah Sondoang adalah Salubatu yang merupakan persimpangan: menuju Kalumpang dan atau menuju Mambi. Panjang Sungai Kalukku kurang lebih 30 km, termasuk sungai kecil.
Sungai Kalukku jelek-jelek begini ada miripnya dengan sungai-sungai di Amerika, sebagaimana yang biasa dilihat di siaran National Geographic. Arusnya deras-deras mungil. Membayangkan ada ikan salmon berlompatan di sela-sela batu. Begitu inginnya seorang sultan di Yaman di kerajaannya ada sungai beserta ikan salmonnya, dia membuat proyek raksasa. Membuat sungai di gurun dan mendatagkan ribuan ikan salmon dari Eropa ke daerahnya. Kisah ini ada di dalam film, “Salmon Fishin I Yaman”.
Artinya apa, keindahan yang dimiliki Sungai Kalukku adalah keindahan luar biasa. Sampai-sampai seorang sultan rela, mengeluarkan dana triliunan agar keindahan itu ada juga ditempatnya. Memang itu hanya ada di film, tapi bisa menjadi bahan renungan bahwa sungai dan segala kecantikan yang dimilikinya patut kita jaga dan kelola dengan baik.
248 Muhammad Ridwan Alimuddin
Ekspedisi Ini Merekam Perubahan
Kedua kalinya berkemah di bawah atap. Pertama di mesjid Syuhada Totolisi Selatan (15/5), kedua, malam ini (22/5) di Pololereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju. Bedanya, saat ini tenda berada di bawah atap balai desa. Baik balai desa dan kantor desanya sama-sama tak terawat. Untung juga, soalnya kalau terawat, mungkin saya pikir-pikir untuk pasang tenda di sini.
Perjalanan hari ini lumayan jauh, lebih 70 km. Dari Sungai Kalukku hingga Desa Pololereng. Sebenarnya saya masih bisa tambah jarak, sebab belum sampai jam lima sore. Tapi karena di daerah depan kurang saya hapal kondisinya, saya memilih untuk berhenti lebih cepat (jangan sampai dapat Tikke, yang kabarnya sering ada penghadang di situ). Apalagi balai desa, yang kelihatan dari atas jalan (balai desa dan kantor desa ada di bawah tebing kecil dari sisi kiri jalan jika menuju arah Pasangkayu), “memanggil” saya untuk pasang tenda di situ. Lumayanlah, walau di sekitar balai desa ada banyak rumah (artinya aman), tapi tak terlalu mencolok juga. Dan, jika pun hujan (saat tulisan ini dibuat, sedang hujan), tak mengganggu.
Sebagaimana tadi malam, sesaat setelah buat tulisan, gerimis mulai turun disertai kilat. Memang sih air tidak masuk, tapi membasahi tenda (tenda basah, tapi airnya tak jatuh) dan membuat khawatir sebab ada beberapa barang elektronik saya bawa. Menyadari hujannya tak akan deras, agar tak khawatir terus, saya memilih tidur. Syukurlah, saat bangun pagi, semua baik-baik saja.
Perjalanan dari Kalukku lumayan. Semua jalan mulus, lebih mulus daripada dari Majene ke Mamuju. Jalannya banyak
249Ekspedisi Bumi Mandar
yang datar, berbukit-bukit juga ada. Tapi tidak seperti di daerah Tappalang. Jika menanjak, harus turun. Tak kuat mengkayuh. Walau tetap capek, tiba di puncak, rasa itu perlahan hilang sebab terbayarkan jalan menurun yang relatif jauh dibanding saat mendaki.
Melakukan perjalanan dengan sepeda, membuat lebih banyak dan lama melakukan perenungan membawa memori ke masa lampau, saat pertama kali melakukan perjalanan ke arah utara Mamuju. Pada tahun 1993, jika liburan, saya ke daerah transmigran di Topoyo III. Waktu itu bapak dan beberapa kerabat ikut serta, sebagai peserta transmigran lokal mendampingi transmigran dari Bali dan Lombok.
Dulu jalannya sebagian besar baru dirintis. Makanya waktu ke Topoyo lewat laut alias naik kapal kayu. Naik di Mamuju turun di Babana. Sempat lama di Topoyo III menemani bapak. Tanam coklat, ubi jalar dan kacang. Pengalaman tak terlupakan. Pada masa itu jugalah sepeda menjadi bagian keseharian.
Setiap pagi dan sore pergi ke lorong lain untuk ambil air minum. Sebab jauh, pakai sepeda. Balok kayu dipasang melintang di atas boncengan lalu dua jerigeng dimasukkan ke masing-masing ujung balok tersebut. Kadang jerigen besar diikat dengan karet di atas boncengan. Berat bukan main, apalagi waktu itu tubuh saya masih kecil (sekarang juga kecil). Jenis sepeda yang digunakan dikenal dengan sebutan sepeda “singking” di daerah kita.
Kemungkinan besar kata “singking” berasal dari kata “jengki”. Kata “jengki” adalah juga penamaan sepeda tua di Jawa. Kata “jengki” berasal dari kata “Yangkee” atau orang-orang Amerika. Sebab dulu waktu tentara sekutu (Amerika dan Australia) ada di
250 Muhammad Ridwan Alimuddin
Indonesia, mereka banyak menggunakan jenis sepeda itu. Nama lain dari sepeda tua ialah “onthel”, itu berasal dari kata unta. Sebab memang sepeda tua itu mirip-mirip gaya unta.
Lama kelamaan, jalan trans Sulawesi antara Mamuju dengan tempat-tempat dibawahnya bisa dilalui dengan mobil. Tapi masih jauh beda dengan yang sekarang. Pernah pada tahun 2001 saya melakukan perjalanan dari Tinambung ke Palu menggunakan bis ukuran sedang. Berangkat jam delapan malam tiba 24 jam kemudian. Tidak hanya lama, melihat wajah, bagai pakai bedak. Soalnya jalan masih berupa tanah. Sehingga pada musim kemarau debu banyak bukan main. Sebaliknya pada musim hujan, becek tak ketulungan.
Seratus delapan puluh derajat saat ini. Mulus sekali. Menuju Pasangkayu atau Palu sudah sangat cepat. Berangkat pagi bisa tiba sore atau malam. Jika kondisi jalan masih sama waktu lampau, akan menderita bukan main. Masih banyak “allaq” (kawasan yang masih rawan, hutan kiri kanan, lama baru ketemu rumah penduduk) dan jalan yang rusak.
Meski berbeda, beberapa tempat, misalnya posisi warung, masih saya hapal. Tersenyum sendiri bila membayangkan kondisi beberapa tahun lalu. Sekaligus bersyukur bisa menyaksikan perubahan itu. Artinya adalah, harus jujur juga diakui, pembangunan di daerah kita sangat signifikan. Kesadaran itu akan muncul bila kita melihat sendiri kondisi masa lampau lalu membandingkannya dengan masa sekarang. Tinggal bagaimana kita mensyukuri dan memanfaatkan pembangunan yang ada di daerah kita.
Di sisi lain, pembangunan tersebut secara signifikan mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada di daerah kita.
251Ekspedisi Bumi Mandar
Khususnya kawasan utara Mamuju. Hutan gundul meningkat drastis. Yang dulunya rimba sekarang menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Kalau bukan coklat atau padi, pasti kelapa sawit.
Konversi lahan tersebut pasti memberi pendapatan bagi daerah kita. Sebagaimana yang disaksikan di jalan, hampir di semua halaman rumah penduduk (di sisi jalan) ada dijemur biji coklat. Banyak juga jagung dan hasil kebun lain. Adapun di jalan sering berpapasan dengan kendaraan yang memuat pisang (kemungkinan besar dibawa ke pelabuhan di Mamuju untuk selanjutnya dikapalkan ke Pulau Kalimantan) dan kelapa sawit.
Ya, pasti ada dampak bagi perekonomian. Tapi cepat atau lambat, konversi atau pengubahan tersebut akan menghasilkan efek yang negatif. Bukan hanya banjir, tapi secara umum akan mempercepat pemanasan global. Bila ingin tahu sejauh mana perubahan hutan menjadi lahan perkebunan, buka saja peta digital Google Earth di internet. Kawasan utara Mamuju hingga Pasangkayu itu amat jelas kelihatan kotak-kotak (tanda penataan perkebunan, khususnya sawit).
Salah satu tujuan Ekspedisi Bumi Mandar adalah merekam akan apa yang terjadi di daerah kita. Khususnya kawasan-kawasan yang dilalui. Merekam dalam arti, bisa menghasilkan perbandingan atau kesimpulan akan apa yang terjadi. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, saya pribadi telah bisa membandingkan apa yang terjadi 20 tahun lalu dengan saat ini. Dua dekade mendatang pasti ada perubahan yang lebih besar. Semoga saja perubahan itu (apakah perkembangan ke arah yang lebih baik atau mungkin juga kerusakan) masih bisa disaksikan.
252 Muhammad Ridwan Alimuddin
Topoyo, Riwayatmu Kini
Sejarah beberapa kampung atau pemukiman di Sulawesi Barat tak bisa lepas dari pengaruh para pendatang. Baik suku-suku di Pulau Sulawesi maupun yang dari Jawa, Bali dan Lombok. Yang paling berpengaruh dan terkenal adalah orang Jawa.
Pertama adalah Wonomulyo yang oleh orang Mandar disebut “Kappung Jawa” atau perkampungan orang Jawa. Sejarah Wonomluyo diawali dari proyek kolonisasi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1930-an. Belakangan, dengan alasan peyoratif (penghalusan kata), istilah tersebut diganti dengan nama transmigrasi.
Akhir tahun 80-an atau awal 90-an beberapa pemukiman transmigran dibuka di Mamuju. Hutan belantara diubah menjadi pemukiman penduduk atau daerah transmigran. Tommo, Topoyo, Tobadak, dan pemukiman lainnya yang banyak orang pendatang (khususnya Jawa, Bali dan Lombok) berasal dari kegiatan-kegiatan transmigran. Bisa dibayangkan jika dulu tak ada proyek transmigran, kemungkinan besar hutan-hutan Mamuju masih berupa hutan. Atau paling tidak kebun sawit saja.
Kebetulan atau tidak, setiap dibuka daerah transmigran, belakangan dibuka berhektar-hektar kebun sawit. Sepertinya para transmigran itu “diharapkan” jadi pekerja sawit. Tapi yang bisa dilakukan para transmigran, selain menanam tanaman holtikultura adalah menanam coklat. Sebagaimana yang saya lakukan bersama bapak saya dulu waktu bertransmigran di Topoyo III. Bibiti coklat didatangkan dari Karoke (Polewali Mandar), tempat yang termasuk daerah pertama yang dijadikan lahan penanaman coklat
253Ekspedisi Bumi Mandar
di era kepemimpinan S. Mengga di Kabupaten Polewali Mamasa (bibitnya dianggap bagus).
Coklat “dikeker”, disemai dan ketika berdaun, dibawa ke kebun. Pengalaman paling mengasikkan. Itu sebabnya jadi sedih sewaktu pekarangan atau tanah bapak di Topoyo III dijual. Soalnya di situ coklat yang saya tanam sudah besar-besar. Tapi mau diapa, harus dijual untuk membiayai kuliah saya di Jawa.
Pada catatan Ekspedisi Bumi Mandar kali ini saya menyinggung tentang transmigran, sebab di perjalanan dengan sepeda pada hari Rabu (23/05) sebagian besar rute yang dilalui melintasi pemukiman penduduk yang dulunya adalah daerah transmigran. Khususnya Topoyo. Dulu, Topoyo I dan II masih sangat sepi. Rumah-rumah penduduk atau pertokoan bisa dihitung jari. Setiap hari pasar di Wai Pute (belakangan dipindahkah ke pusat Topoyo saat ini) bersama teman pergi menjual korek gas.
Saat ini, Topoyo I ramainya bukan main. Rumah gedung, toko-toko dan lain sebagainya. Perkembangannya jauh mengalahkan kampung saya di Tinambung. Tinambung itu begitu-begitu saja, tapi Topoyo tidak begitu-begitu saja.
Dari pusat kota Topoyo, saya menuju Topoyo II dan Topoyo III. Rute ini menyimpang, sebab tak mengarah ke utara melainkan ke barat. Tapi tak apa, ekspedisi tidak hanya melalui jalan trans; tidak hanya “landur massapeda”.
Topoyo II juga berkembang, tapi jalannya masih tetap rusak. Meski ada rumah di kiri kanan, jejak sebagai daerah transmigran masih kelihatan jelas. Tidak sama dengan Topoyo I, yang hilang sama sekali ciri transmigrannya. Sudah banyak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Dulu, SMA paling dekat dengan Topoyo adalah
254 Muhammad Ridwan Alimuddin
SMA Budong-budong. Saya masih sangat ingat, pernah merengek-rengek untuk tidak sekolah di SMA Tinambung, sebab lebih ingin sekolah di SMA Budong-budong. Kan mau total bertransmigran, kira-kira seperti itu pikiran pendek saya waktu itu. Untung orangtau tidak ijinkan, jadi saya tetap lanjut di SMA Tinambung. Syukurlah, sebab jika tidak, mungkin sekarang saya jadi petani coklat atau sawit.
Masuk ke Topoyo III, membawa ke kenangan masa lampau. Membakar kayu-kayu besar, pergi mengambil jadub (jatah hidup), mengambil air minum, kebanjiran, dan suka duka lainnya. Sebagai daerah transmigran masih terlihat jelas. Petak-petak pekarangan masih terlihat jelas, demikian juga jalan atau lorong-lorongnya. Dulu masih berupa bekas hutan yang ditebang. Rumah-rumah transmigran kelihatan semua sebab belum ada tanaman besar. Sekarang, banyak belukar sebab tak terawat, menjadi kebun sawit, coklat atau bekas kebun jeruk. Rumah khas transmigran pun sudah pada hancur.
Jalan atau lorong masih berupa tanah. Jika hujan, becek atau genangan berwarna coklat di mana-mana. Yang membedakan hanyalah adanya rumah semi permanen di beberapa tempat dan sudah ada SMP, yaitu SMP II Topoyo.
Topoyo, dalam kurun waktu dua dekade, berkembang begitu cepat. Disadari atau tidak, peran Topoyo sebagai daerah pertumbuhan baru di Sulawesi Barat amat signifikan dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah baru-baru ini. Baik perputaran uang maupun pertambahan penduduk sangat drastis. Itu sebab, calon ibukotanya tak jauh-jauh dari Topoyo, yaitu di Polohu. Sekitar lima kilometer dari pusat kota Topoyo.
255Ekspedisi Bumi Mandar
Bandingkan saja dengan Tinambung. Ambil saja contoh sederhana. Di Tinambung itu baru satu ATM (Bank BRI saja), sedang di Topoyo dan sekitarnya paling tidak ada dua: BRI dan BNI. Apakah ketimpangan perkembangan ekonomi tersebut yang menjadi penyebab sehingga sampai saat ini Kabupaten Balanipa tak jadi-jadi?
Paku – Suremana Kampung Halamanku
“Memula mellamba dini di Paku // Naung di Suremana // Sanging maquwwa pirandi anna pole // Sitonganna sau dipau // Saemi dipanniaqi // Puangdi tia tammappasilolongang // Salamaq wattunna dipelei // Onncommi dipolei // … (tak terdengar jelas) // Litaq pembolongataq // ...”
Lagu legendaris Mandar di atas adalah salah satu pemberi inspirasi Ekspedisi Bumi Mandar. Itu juga salah satu sebab etape tahap awal ini adalah Paku – Suremana. Ada yang mengatakan judulnya “Litaq Pembolongang” yang berarti kampung halaman. Setidaknya sudah ada dua penyanyi yang mempopulerkan lagu tersebut. Pertama Syaiful Sinrang (duet dengan seorang wanita tapi saya belum tahu namanya) pada tahun 80-an dan Meiti Ba’an (salah tulis?) pada tahun 2000-an.
Bait pertama di atas persis menjiwai ekspedisi, “Memulai perjalanan dari Paku // Sampai di Suremana // Pada bertanya kapan akan datang // Sejujurnya // Sudah lama diniatkan // Hanya saja tuhanlah yang menentukan // Selamat sewaktu ditinggalkan // Demikian juga yang didatangi (bisa juga diartikan “Saat kembali) // … // Kampung halaman kita // …”
256 Muhammad Ridwan Alimuddin
Adapun bait kedua, yang belakangan meng-identikkan beberapa kampung pada komoditas tertentu, tak kalah menariknya: Duriang pole di Benuang // Pandenna to Pamboang // Dendenna tama golla kambunna to Palece // Kabeni pole di Malundaq // Lasseq bambanna to Tande // Iya nasammo mattambah saliliqu.
Terjemahannya: Durian dari Benuang (salah satu nama kerajaan dalam federasi Pitu Baqbana Binanga, yang sekarang ini nama kecamatan paling selatan/barat di Kabupaten Polewali Mandar) // Buah pandang orang Pamboang (juga nama kerajaan di federasi yang sama atau nama kecamatan di Kabupaten Majene) // Bungkuskan “golla kambu” orang Palece (nama desa di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar) // Buah kweni datang dari Malunda (nama kecamatan di Kabupaten Majene) // Buah langsat ranum orang Tande (nama desa di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene) // Itu semua yang menambah rinduku.
Dari lima nama tempat di atas, kaitannya dengan Ekspedisi Bumi Mandar, hanya tiga yang dilintasi di tahapan pertama ini. Sebab wilayahnya juga dilalui jalan trans Sulawesi. Yaitu Binuang, Pamboang dan Malunda. Sedangkan Palece agak “ke dalam” atau sekitar 6 km dari jalan poros (dari lampu merah di kota Tinambung). Adapun Tande, meski relatif dekat (3-4 km) tapi karena berada di perbukitan (bila masuk dari Jl. Nedan, pas samping Tasha Center) agak berat bila jalan kaki atau naik sepeda.
Bait kedua lagu di atas bisa jadi mencerminkan ciri khas tempat-tempat tertentu di Mandar sebelum tahun 80-an. Selain lima kalimat tersebut, yang juga terkenal adalah “Lipaq saqbena to Karama” (sarung sutra dari Karama, nama desa di Kecamatan Tinambung, pesisir Teluk Mandar) dan “Beruq-beruq to
257Ekspedisi Bumi Mandar
Kandemeng” (juga nama desa di Kecamatan Tinambung, menjadi bagian dari kota Tinambung). Hanya saja, kedua tempat tersebut tidak diidentikkan dengan buah atau makanan/kue (“golla kambu” nama sejenis kue di Mandar, terbuat dari kelapa, beras ketam dan gula merah yang dibungkus daun pisang kering), tapi hasil kerajinan (sarung sutra) dan bunga (dalam Bahasa Mandar, melati disebut “beruq-beruq”).
Lalu bagaimana dengan saat sekarang? Apakah tempat-tempat di atas masih identik dengan ciri khasnya?
Ada yang masih, ada juga yang tidak. Setidaknya ada perubahan atau persebaran. Misalnya buah durian. Salah satu sentra penghasil durian di Mandar atau Sulawesi Barat adalah daerah Kanang yang merupakan wilayah Binuang. Tapi bukan hanya Binuang penghasil utama durian di Mandar, juga beberapa tempat di Mamuju.
Adapun buah pandang dan kweni tak lagi identik dengan Pamboang dan Malunda. Meski kedua tempat itu mungkin masih menghasilkan komoditas tersebut, tapi tidak banyak. Dan yang paling berubah ialah Tande. Buah langsat yang ranum tak lagi milik tanah atau orang Tande. Itu sudah tersebar di banyak tempat. Mulai dari Mamuju hingga Binuang. Malah, buah langsat dari Tande (bambang atau tidak), sangat sedikit dibanding tempat lain di Mandar.
Demikian juga dengan sarung sutra. Wanita-wanita Karama sebagian besar beralih ke pembuatan tali dan di Kandemeng tak akan ditemukan lagi kebun melati.
Lagu “Litaq Pembolongang” adalah lagu masa lampau Mandar. Ke depan, idealnya ada lagu yang menggambarkan ke-Mandar-an
258 Muhammad Ridwan Alimuddin
saat ini, yang menggambarkan realitas atau kondisi kekinian. Yang mungkin juga bisa membuat lagu dengan ke-Mandar-an lebih kuat. Dengan kata lain, sebisa mungkin memasukkan unsur-unsur ke-Mandar-an atau mewakili tempat-tempat tertentu.
Misalnya unsur daerah pegunungan dan tempat-tempat di Mamuju. Bagaimana pun juga, tempat-tempat tersebut sekarang ini memiliki ciri khas tertentu. Seperi kelapa sawit dari Mamuju Tengah, “golla kambu” yang sekarang lebih banyak di Campalagiang (sentra oleh-oleh), buah coklat dari Mamuju, padi dari Wonomulyo, kopi dari Mambi atau Mamasa, “tarreang” atau jawawut dari Bala/Pambusuang, kelapa atau kopra dari Mamuju Utara, “tui-tuing” dari Somba, tali dari Lambe’, sandeq dari Pambusuang (sebab saat ini hanya Pambusuang yang memiliki banyak sandeq di Mandar), dan lain sebagainya.
Mengapa itu perlu dilakukan, sebab sebuah karya seni (lagu, film, puisi, cerpen) adalah juga perekam atau pendokumentasi akan apa yang ada di masa itu. Dan kadang itu lebih membumi dibanding dokumentasi biasa saja, seperti foto. Contoh paling gampang bisa dilihat dari lagu tersebut di atas “Litaq Pembolongang” tersebut di atas. Dengan mendengar lagunya saja, orang sudah bisa mengetahui komoditas unggulan atau aikon tempat tertentu; tak perlu baca buku, tak perlu dikampayekan.
Memang sih ada banyak lagu Mandar yang tercipta (banyak juga yang diterjemahkan mentah-mentah dari lirik lagu Indonesia) beberapa tahun terakhir. Tapi untuk menjadi legendaris sebagaimana lagu “Litaq Pembolongang”, yang hanya terdiri dari beberapa kalimat dan bukan lagu cinta-cinta, sepertinya belum ada.
259Ekspedisi Bumi Mandar
Diaspora Orang Mandar di Mandar
Diaspora dapat diartikan sebagai persebaran. Dalam istilah biologi, serbuk bunga yang tersebar kemana-mana, biasanya oleh hembusan angin, disebut diaspora. Sedang dalam antropologi, diaspora itu identi dengan merantau atau melakukan migrasi.
Ada banyak penelitian atau tulisan mengenai diaspora tentang orang Bugis di Nusantara, tapi tentang orang Mandar masih sangat sedikit. Persebaran orang Mandar ke luar Mandar memang menarik, tapi persebaran orang Mandar di Mandar (geografis) jauh lebih menarik.
Dalam Ekspedisi Bumi Mandar, semakin ke utara, khususnya Mamuju Tengah dan Mamuju Utara, mendapati orang Mandar lebih memberi kesan dibanding Mandar bagian selatan. Maksudnya, mendapati orang Mandar dari Polman hingga Mamuju wajar, tapi di Mandar utara ‘memunculkan rasa penasaran’.
Menuliskan hal ini mungkin akan menghasilkan polemik sebab sepertinya ada polarisasi bahwa orang Mandar itu asalnya dari tempat tertentu. Ya, mungkin akan jadi perdebatan bila realitas di lapangan tak demikian adanya. Alias, hal ini bukan saya karang-karang. Jika kita bertanya ke orang yang datang dari selatan ke utara, mereka akan menjawab, “Poleaq di kappung” atau “Poleaq di Mandar” (datang dari Mandar) atau “To Mandar nasang muaq indinie, llaiq ssao to Kaili” (Orang Mandar semua kalau di sini, di sana orang Kaili). Jawaban itu sekilas rancu. Bukankah mereka masih ada di tanah Mandar (Paku sampai Suremana)?
Inilah sumber perdebatan, bahwa kadang kita menyamakan antara orang Mandar (sebagai suku bangsa) dengan Mandar
260 Muhammad Ridwan Alimuddin
sebagai kesepakatan politik nenek moyang kita dulu atau juga Mandar sebagai geografis. Mandar sebagai geografis atau wilayah politik itu memang cukup luas, ujung pukul ujung selatan utara itu 500san kilometer, lebar puluhan kilometer. Tapi, di dalam wilayah yang luas itu ada suku bangsa. Suku bangsa tersebut ada yang banyak penduduknya, ada juga yang tidak. Dan kadang suku bangsa tersebut memiliki sub suku. Atau percabangan. Untuk memudahkan membedakan adalah dari bahasa.
Meski demikian, harus diakui juga, ada kesepakatan “Sipamandaq”. Bahwa dulu pemimpin-pemimpin 14 kerajaan, Pitu Ulunna Salu Pitu Baqbana Binanga bersepakat untuk “Missipaq Mandaq” atau bersifat seperti (sungai) Mandar. Yang mana Sungai Mandar itu menjadi besar sebab didukung atau berasal dari sungai-sungai kecil.
Sebagai pewaris, persatuan tersebut haruslah dijaga. Dengan catatan, pemahaman akan persatuan itu didasari pada pengetahuan bahwa memang kita itu bersatu sebab awalnya ada perbedaan; bahwa kita harus mengetahui kita di Mandar itu tidak seragam.
Dari dasar tersebut di atas, pembicaraan mengenai diaspora atau penyebaran orang Mandar di Mandar akan lebih mudah dipahami. Mandar sebagai suku itu ada di pesisir Teluk Mandar, khususnya sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan sebagian besar Kabupaten Majene. Nah, orang-orang dari sinilah yang saya maksud, yang melakukan penyebaran ke wilayah-wilayah lain yang bukan pemukiman “klasik” atau “tradisional” mereka.
Mereka melakukan penyebaran untuk kemudian bermukim umumnya terjadi baru-baru ini. Belum lama terjadi. Memang sih
261Ekspedisi Bumi Mandar
sudah ada penyebaran orang-orang dari tempat tersebut di waktu lampau, misalnya dalam muhibah kerajaan atau perang. Ketika orang Mandar sampai ke Kaili, sampai ke Gorontalo. Yang salah satu jejaknya adalah penamaan Teluk Tomini (Tomini itu berasal dari kata To Mene. To Mene adalah penyebutan orang-orang lokal di Sulawesi Tengah terhadap orang Mandar). Tapi sampai sejauh ini saya belum menemukan jejak pemukiman orang Mandar yang berasal dari kejadian ratusan tahun lampau.
Ada beberapa sebab hingga mengapa orang-orang dari Polewali Mandar dan Majene melakukan perpindahan ke utara. Dan sebagian dari faktor itu menarik untuk dikaji dalam penelitian khusus. Selain perang di masa kerajaan, faktor yang lain ialah mencari penghidupan lebih baik dan konflik atau perbedaan pandangan politik.
Yang pertama umumnya dilakukan oleh para nelayan. Di pesisir atau pantai Mamuju Tengah dan Mamuju Utara banyak sekali nelayan Mandar. Kedua, ketika marak pembukaan hutan untuk lahan transmigrasi (setidaknya ketika coklat mulai diperkenalkan), beberapa orang Mandar mencari peruntungan di utara. Sebab di bagian selatan, mungkin mereka tidak punya lahan. Tidak hanya untuk berkebun, tapi untuk berdagang dan membuka lahan tambak. Yang terakhir ini sepertinya lebih banyak dilakukan oleh orang Bugis. Jadi tak mengherankan banyak juga orang Bugis (Pinrang, Sidrap) di Mamuju Tengah dan Mamuju Utara.
Juga motif ekonomi tapi lain bentuknya ialah para birokrasi atau pencari lowongan sebagai birokrasi. Dulu, orang emoh ke wilayah utara. Sebab dianggap pembuangan; sebab terpencil. Sekarang lain ceritanya, berbondong-bondong datang sebab lebih
262 Muhammad Ridwan Alimuddin
mudah lolos masuk PNS, lebih mudah naik pangkat atau jabatan.
Faktor berikutnya adalah karena masalah politik. Yang saya maksud adalah dampak dari konflik di era DI/TII. Masa itu ada dua kelompok utama, tetap mendukung kepemimpinan Kahar Mudzakkar (dianggap pemberontak) atau pro pemerintah. Dalam konflik tersebut, ada komunitas yang cukup terkenal dan menjadi pendukung utama Kahar Mudzakkar di tanah Mandar, yaitu Pasukan Tande (masuk wilayah Kabupaten Majene saat ini).
Singkat kata, sebab dari peristiwa itu mereka “kalah perang”, sebagian orang Tande melakukan migrasi. Ada informasi yang saya dapatkan dari salah seorang wanita Tande di Desa Muhajir (beberapa kilometer setelah Topoyo), yang pindah dari Tande sejak dia masih berumur 10 tahun bersama orangtuanya, bahwa dulu mereka dimobilisasi tentara. Yang tidak jelas di situ, apakah militer yang dimaksud adalah pemerintah atau pengikut DI/TII. Tentara membantu mereka mencari dan membukakan lahan pertanian dan pemukiman.
Itu sebab ada banyak orang Tande di Desa Muhajir. Kata “muhajir” sendiri berasal dari bahasa Arab, pendatang. Atau merujuk sejarah yang terjadi masa Nabi Muhammad SAW. Yang dikenal ada kaum Anshar, ada kaum Muhajirin.
Bukan hanya di Muhajir banyak orang Tande, di beberapa tempat pun banyak, antara lain Totoli (Sulawesi Tengah) dan di Bambangloka. Saat saya tanya seorang orang Tomadia (Campalagiang) yang juga sudah lama di Bambangloka apakah ada orang Tande di sini, dia jawab, “Mereka banyak di dalam hutan berkebun.”
Dan sepertinya ada hubungan, ketika di situ ada banyak orang Tande, juga ada orang Palopo (Sulawesi Selatan). Koq banyak orang
263Ekspedisi Bumi Mandar
Palopo, padahal Palopo relatif jauh (sebab memutar)? Alasannya adalah, kekuatan utama pasukan DI/TII di Sulawesi Selatan adalah Palopo, sebab pemimpinnya (Kahar Mudzakkar) berasal dari sana.
Khusus untuk perpindahan orang Tande sangat menarik untuk dikaji, sebab itu berkaitan dengan salah satu peristiwa politik terbesar di Tanah Mandar. Bukan cuma itu, orang Tande juga sangat terkenal memiliki semangat dagang. Rata-rata pedagang besar orang Mandar itu berasal dari Tande dan mereka mempunyai hubungan emosional yang kuat sebagai sesama orang Tande.
Bukan hanya itu, sejarah tempat-tempat tertentu di Mamuju Tengah dan Mamuju Utara menarik untuk didalami. Paling tidak sejarah desa/dusun Majene dan Polewali di Kabupaten Mamuju Utara.
“Benu”, “Kaqdaro” dan “Bokaq”
Tiga kata di judul bila disingkat dalam satu kata maka menjadi “anjoro” atau kelapa. Sengaja menggunakan Bahasa Mandar sebab satu-satunya buah yang signifikan perannya dalam peradaban atau sejarah Mandar hanyalah kelapa. Tak ada yang lain.
Sepanjang perjalanan Ekspedisi Bumi Mandar di jalan trans Sulawesi yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, kabupaten yang padanya layak disematkan sebagai sentra kelapa adalah Mamuju Utara. Sebagian besar di sisi kiri kanan jalan adalah tanaman kelapa. Bukan hanya itu, industri rumah tangga yang berbahan baku kelapa juga banyak, khususnya “bokaq” atau kopra.
Meski demikian, tanaman kelapa di Mamuju Utara relatif “baru” bila dibandingkan dengan Mamuju, Majene dan Polewali
264 Muhammad Ridwan Alimuddin
Mandar. Malah bisa dikatakan, sebagaiman disinggung di awal, kelapa di tempat-tempat tersebut signifikan menentukan arah sejarah di Mandar. Hanya saja, di tiga kabupaten tersebut lahan kelapa sudah banyak dikonversi menjadi daerah pemukiman. Beda di Mamuju Tengah (tapi di sini mayoritas tanaman kerabat kelapa, yakni kelapa sawit) dan Mamuju Utara.
Kopralah yang berkontribusi penting dalam banyak hal kejadian di Mandar, termasuk dalam pengembangan beberapa wilayah dan kondisi sosial politik. Salah satu contoh kasus ialah ibukota baru Kerajaan Balanipa, yaitu Tinambung. Tinambung diperkirakan mulai berkembang pada tahun 1875.
Secara umum, terbentuknya kampung-kampung di sekitar kota Tinambung telah lama terjadi. Setidaknya pada abad ke-16, ketika masa akhir pemerintahan Todilaling (I Manyambungi), raja Balanipa ke-1. Yakni dari perbukitan (Napo) ke pesisir/pantai. Saat masa pemerintahan raja ke-4, yakni Daetta, diperkirakan pada tahun 1615, pelabuhan Para’ dan Ba’barura dikembangkan. Pada masa itu diangkat pengawas pelabuhan, yang disebut “sawannar” (syahbandar).
Sebagai kota kecil di pantai, Tinambung adalah kota dagang. Oleh sebab itu, pembentukan dan perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan, baik secara lokal, regional maupun internasional.Pada tahun 1819 salah satu pusat perdagangan dunia mulai mapan, yakni Singapura (sebelumnya disebut Tumasik, sehingga orang Mandar yang berlayar ke sana untuk berdagang disebut “Pattumasek”).
Pada masa itu dan setelahnya, salah satu komoditas perdagangan dunia yang juga banyak terdapat di Mandar marak
265Ekspedisi Bumi Mandar
diperdagangkan, yakni kopra. Dengan kata lain, Mandar terlibat dalam perdagangan internasional. Sebab pada tahun 1850, perdagangan antara orang pribumi dengan orang Eropa mulai marak.
Menurut catatan Belanda, pada tahun 1860, jumlah pohon kelapa di Sulawesi Selatan sekitar 407.279 pohon (Mandar 16.502 pohon). Dan berkembang pesat pada 1875, di saat pohon kelapa mencapai 755.500 pohon.Perdagangan dunia semakin marak semenjak dibukanya Terusan Suez di Mesir pada tahun 1869. Kemudian booming perdagangan kopi pada tahun 1870.
Pada tahun yang sama, para “maraqdia” di Mandar mengadakan perjanjian politik dengan Hindia-Belanda yang secara signifikan mempengaruhi kekuatan kepemimpinan di Mandar (menjadi melemahkan). Waktu itu, pihak Belanda membeli kopra dari pekebun Mandar dengan harga yang sangat rendah dan hanya orang Belanda-lah (VOC) yang boleh membeli kopra. Di pihak lain, para pedagang (umumnya dari kalangan bangsawan sendiri) mengetahui harga kopra sangat tinggi di Tumasik (Singapura). Pada masa itu, kopra adalah bahan baku utama untuk memproduksi mantega dan sabun.
Pedagang pribumi mengharapkan harga yang layak. Permintaan ini tak digubris Belanda. Maka terjadilah perlawanan. Paling terkenal oleh perlawanan Tokape (maraqdia ke-46). Saat tertangkap, dia dibuang ke Pacitan, Jawa Timur. Singkat kata, perang besar yang terjadi di Mandar “sebenarnya” gara-gara kelapa.
Bukan hanya pada masa itu, setelah kemerdekaan pun demikian. Apa sebab DI/TII harus menguasai Mandar? Kenapa
266 Muhammad Ridwan Alimuddin
gerangan Andi Selle mati-matian mempertahankan Mandar sebagai daerah kekuasaannya (yang belakangan ‘penindasan’ oknum-oknum orang Bugis terhadap orang Mandar melahirkan sentimen atau stereoripe tertentu terhadap orang Bugis oleh orang Mandar)?
Alasannya adalah karena kelapa! Ya, kelapa dalam hal ini “bokaq” alias kopra. Benda jelek dan beraroma khas tersebut bukan benda main-main. “Bokaq” adalah emas hijau. Sebagai komoditas penting, kopra mendatangkan banyak uang. Nah, itulah sebabnya Mandar harus dikuasi. Sebab dari perdagangan (dan penyelundupan) kopra, para pejuang, para pemberontak, dan oknum militer bisa mendapatkan uang. Uang untuk mendanai pertempuran, yaitu untuk membeli (biasa juga dibarter) senjata, dan untuk kepentingan pribadi.
Sehingga tak mengherankan pejabat-pejabat militer tempo dulu itu kaya-kaya. Salah satunya ada pendapatan atau komisi dari penjualan kopra. Sadar tidak sadar, beberapa bangunan sekolah dan mesjid yang dibangun di Mandar itu ada yang berasal dari perdagangan kopra atau “pencucian uang” dari penyelundupan kopra. Salah satu diantaranya ialah SMA 1 Majene, yang pembangunannya dibantu oleh Pasukan Andi Selle.
Efek dari perang atau penguasaan di atas, ketika terjadi kekacauan di Mandar, banyak orang Mandar mengungsi atau bermigrasi ke tempat lain. Baik ke wilayah lain di Mandar yang terpencil (baca tulisan sebelumnya: Diaspora Orang Mandar) maupun yang ke pulau-pulau di Selat Makassar, Laut Jawa dan Laut Bali. Itulah sebab di atas dikatakan bahwa kelapa itu memegang pengaruh penting dalam perjalanan sejarah Mandar.
267Ekspedisi Bumi Mandar
Saat ini komoditas kelapa tak sepenting dulu lagi. Ada saingannya, kelapa sawit. Untuk hal-hal tertentu, kelapa sawit jauh lebih efektif: tumbuh cepat, banyak minyaknya, kabarnya rendah kolestrol, mudah dibudidayakan dan gampang panennya. Beda dengan kelapa (asli).
Meski demikian, komoditas tersebut masih memberi sumbangsih perekonomian nusantara, khususnya di Sulawesi Barat. Selain sebagai bahan baku utama membuat minyak goreng lokal (“minnaq mandar” atau “minnaq anjoro”), juga dengan produk kopranya.
Bukan hanya kopra, “kaqdaro” atau tempurung dan “benu” atau sabutnya juga bisa menghasilkan uang. Hanya saja itu belum dimaksimalkan. Beberapa pengolahan kopra di sekitar wilayah Desa Majene, sabut kelapanya itu dibakar saja alias tak digunakan. Dekat Pasangkayu tampak ada pengolahan serat sabut kelapa, mudah-mudahan itu tetap berproduksi.
Adapun tempurungnya, hanya diolah sebagai bahan baku arang. Tapi di wilayah Mamuju Utara belum ada disaksikan industri pengolahan tempurung sebagaimana yang ada di sekitar Palippis (perbatasan Kecamatan Campalagiang dengan Kecamatan Balanipa) yang kabarnya dikelola oleh investor dari Korea Selatan.
Singkat kata, “anjoro” adalah bagian penting dalam sejarah kita, sejarah Mandar.
Berniat Menghentikan Ekspedisi
Walau jelas di sepedaku yang paling besar teks-nya adalah Pacific (jenis Mountain Bike Tranzline 500), tapi agak ragu apakah merek (ataupun merek lain, misalnya saya tidak menggunakan Pacific tapi
268 Muhammad Ridwan Alimuddin
menggunakan Polygon atau Specialized, atau merek lain) tersebut menjadi penentu lancar-lancarnya saja Ekspedisi Bumi Mandar.
Saya ajukan pertanyaan ini, sebab di sepeda yang saya gunakan (dan sepedaku yang lain yang ada di rumah), ada merek-merek lain yang mana perannya tak kalah penting. Sistem gir-nya bermerek Shimano (Altus), garpu depannya Zoom (sewaktu di Mamuju saya ganti dengan SR-Suntour 0-12 Series sebab butuh garpu yang lebih panjang), sistem rem-nya Shiman (pegangan) dan Zoom (cakram), ban-nya Kenda, tempat duduk Cionlli, dan pedal-nya Wellgo. Selain di batangan, teks Pacific juga ada di velg dan stang kemudi.
Bagian-bagian yang tak berhubungan langsung dengan sepeda juga macam-macam merek-nya: celana, kaos tangan dan tas yang dipasang di depan stang kemudi Eiger; dan helm, kacamata, botol air minum Polygon.
Jika salah satu benda atau bagian di atas tak ada atau menggunakan kualitas rendah (cepat rusak), bisa dipastikan perjalanan akan bermasalah. Ya, memang kekuatan sepeda itu bertumpu pada batangan, tapi jika ada bagian non-batangan yang rusak, efeknya pasti ada. Misalnya ban bocor, kan tak bisa jalan.
Sampai saat ini saya belum pernah menemukan satu merek yang semua bagiannya mereka produksi sendiri. Yang selalu ada, adalah sistem rem dan gir-nya, yaitu Shimano. Artinya apa, untuk fanatik (baca: menjelekkan merek lain) pada satu merek sepertinya bukan pilihan bijak. Sebab realitasnya adalah, sepeda yang kita gunakan/miliki itu terdiri dari beberapa unsur merek atau kerjasama beberapa merek atau didukung oleh sistem lain.
Ketika ada merek batangan berbeda, ternyata rem, garpu, ban dan bagian lainnya, persis sama atau juga digunakan di merek
269Ekspedisi Bumi Mandar
lain. Jadi? Lalu, ada juga kemungkinan, ini bisa saja terjadi, merek-merek tersebut beda sticker teks merek saja. Adapun desain dan materialnya sama saja. Yang penting adalah sepeda yang kita gunakan itu kuat dan penggunaannya sesuai.
Jadi, jika ada yang menanyakan mengenai merek perangkat penting yang digunakan dalam ekspedisi ini (sepeda) agak sulit untuk menjawabnya. Sebab sepeda itu adalah satu kesatuan sistem yang mana di situ ada banyak campur tangan merek. Sama seperti perangkat lain, misal kamera, laptop, handphone, dan lain, itu sangat dipengaruhi oleh pengguna. Alias, “man behind the gun” (orang di balik senjata). Dan kadang, “orang” itu bukan hanya kekuatan fisik semata, tapi semangat dan motivasi. Jujur saja, ada niatan untuk menghentikan ekspedisi ini di tengah jalan.
Pikirnya etape Pasa’bu – Mamuju paling berat, ternyata masih ada yang lebih berat: Topoyo – Korossa. Beberapa kilometer sebelum Korossa jalannya sempat menyurutkan nyali. Jalan berbukit, berbelok-belok, panas matahari. Mirip-mirip celah Khaiber di Afghanistan. Bedanya, yang di Sulawesi Barat ini masih banyak hijau-hijaunya (pohon, hutan) sedang di sana kering kerontang dan tebingnya bebatuan.
Sepertinya tidak apa-apa kalau jalannya menanjak sedemikian tinggi dan sisinya ada jurang, tapi itu jangan terlihat dari jauh. Soalnya pemandangan itu bagai gertakan. Tapi mau bagaimana lagi, perjalanan tinggal 1/3 lagi untuk sampai. Kalau mundur juga kan rugi. Atau, gimana bila numpang mobil?
Memang ada beberapa tawaran truk, tapi untuk numpang atau ditarik sepertinya tak mungkin. Perjalanan akan sia-sia. Bagaimana pun juga, ekspedisi ini adalah semacam latihan untuk
270 Muhammad Ridwan Alimuddin
tak membohongi, baik diri sendiri maupun orang lain. Sikap ini penting, baik saya sebagai ilmuwan maupun jurnalis.
Melintasi Topoyo – Korossa, bukan hanya berat dari segi medan tapi juga bagai klimaks perjalanan. Pada etape itu godaan untuk berhenti, dengan beragam macam dalih terpikirkan. Yang paling berpengaruh adalah isteri di rumah menghitung hari untuk melahirkan. Dari segi medis kelahiran itu bisa diperkirakan, tapi tak bisa memastikan kapan. Dokter memperkirakan akan lahir tengah Juni, tapi dari komunikasi dengan isteri, sepertinya sudah dekat. Kepala bayi sudah sering ada di bawah. Hasil pengecekan bidan juga mengiyakan, tak lama lagi.
Rugi bukan main bila tak menyaksikan anak lahir dengan alasan ekspedisi. Paling tidak susah menjelaskan ke keluarga. Sepertinya kegiatan ini membawa capek saja, sok-sokan, tujuannya apa, tak menghasilkan uang, dan sebagainya.
Mudah-mudahan ekspedisi bisa diselesaikan, setidaknya di tahap awal ini, Paku – Suremana. Jika pun itu terwujud, sama seperti kasus merek sepeda di awal tulisan ini, tidaklah bergantung pada satu orang atau pada diri saya sendiri yang bermerek “Muhammad Ridwan”. Ada banyak pengaruh “merek” (pihak) lain yang dukungannya juga sangat penting, sebagaiman pentingnya “reng”, “panggolingang”, pedal, “ratte”, “sipi-sipiq” pada sebuah “sapeda”.
Suremana, “Sureq” Orang “Mene”
Minggu, 26 Mei, Ekspedisi Bumi Mandar menempuh perjalanan dari Korossa ke Pasangkayu. Merupakan perjalanan terlama dan terjauh sepanjang ekspedisi, berangkat sekitar jam tujuh pagi, tiba menjelang jam lima sore. Dengan jarak tempuh lebih 100 km.
271Ekspedisi Bumi Mandar
Perjalanan yang cukup membuat otot lengan, paha dan betis dipenuhi asam laktat. Ketika diam beberapa lama, pegalnya terasa. Perjalan selama 11 hari sejauh 550 km telah dilalui. Sisa 50 km lagi untuk mencapai tujuan akhir Ekspedisi Bumi Mandar tahap pertama ini, yaitu rute Pasangkayu – Suremana. Secara psikologis, tahap terakhir ini paling berat.
Mengutip pendapat Arswendo, sastrawan – jurnalis yang pernah dipenjara, “Saat-saat paling menyiksa selama di penjara adalah ketika akan kebebasan tak lama lagi.” Itu diungkapkannya dalam buku yang dia tulis di penjara berjudul “Menghitung Hari”.
Jika Arswendo menghitung hari, saya menghitung kilometer di hari terakhir ekspedisi, Senin, 27 Mei. Bila di antara Mamuju sampai beberapa kilometer sebelum Pasangkayu tak ada tanda kilometernya (berupa tugu kecil yang dipasang di sisi jalan), dari Pasangkayu hingga Palu itu lengkap kilometernya. Tanda-tanda itu di satu sisi cukup informatif, di sisi lain amat menyiksa. Lagi 40 km, lagi 37 km, lagi 20 km, lagi 10 km, … semakin dekat semakin menyiksa perasaan.
Sekitar jam satu siang, akhirnya Ekspedisi Bumi Mandar etape Paku – Suremana bisa diselesaikan, ketika melintasi perbatasan Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Disaksikan dengan penuh tanya oleh petugas-petugas di perbatasan. Mungkin di dalam benak mereka, “Siapa ini orang aneh-aneh naik sepeda?”.
Walau secara formal tahapan ekspedisi telah selesai ketika melintas batas gerbang dan atau jembatan di atas Sungai Suremana, sepeda masih melaju beberapa ratus meter, guna memastikan bahwa ekspedisi mencapai wilayah Suremana.
272 Muhammad Ridwan Alimuddin
Dikatakan demikian, sebab dalam batas administrasi saat ini, Suremana itu tak masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tapi di wilayah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ekspedisi berhenti persis di kilometer 0 Suremana, yang berada di sisi kiri jalan. Kota Donggala masih 20an km, Palu masih 70an km.
Sepertinya masih banyak orang Mandar yang tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa ternyata Suremana (di jembatan tertulis Surumana) itu tidak ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat; tidak sesuai dengan kalimat bahwa Mandar itu dari Paku hingga Suremana. Belum diketahui mengapa hal itu bisa terjadi, apakah ada “pencaplokan” wilayah atau ada kesepakatan antara pemerintah Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah di masa lampau, ketika ada penentuan batas provinsi.
Ada juga kemungkinan, bahwa memang pada dasarnya Suremana itu tidak masuk wilayah Mandar, tapi hanya dijadikan sebagai penanda bahwa titik paling utara itu adalah Suremana. Kemungkinan hal ini ada sebab sampai saat ini saya belum pernah membaca referensi atau isi (terjemahan) lontar mengenai kesepakatan tertulis antara kerajaan di Pitu Baqbana Binanga (paling tidak Kerajaan Mamuju, sebab dia yang paling di utara) dengan kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah.
Mengapa Suremana dijadikan titik paling utara? Mengapa bukan kampung-kampung yang jelas masuk wilayah Mandar? Dugaan saya, itu disebabkan kampung (kuno) paling ramai di utara sebelum kota Donggala, yang terletak di pantai, tak jauh dari muara Sungai Suremana (sungai biasanya dijadikan batas alami antar suatu daerah) adalah Suremana Tua (ada dua tempat bernama Suremana, yang di pesisir bernama Suremana Tua, yang
273Ekspedisi Bumi Mandar
saat ini, yang dekat jalan raya adalah Suremana Baru).
Adapun perkampungan yang masuk di Mandar (Sulawesi Barat) yang letaknya paling dekat dengan perbatasan adalah Balabonda. Tapi bila dibandingkan jarak Suremana ke perbatasan dengan Balabonda ke perbatasan, Balabonda masih cukup jauh. Antara kurang 1 km dengan 3 km. Itu dulu, tapi sekarang beda. Di perbatasan saat ini, sudah ada pemukiman penduduk yang disebut Sarjo (kabarnya Sarjo itu adalah singkatan).
Ada juga yang mengatakan bahwa Mandar itu berada di antara Binanga Karaeng dengan Lalombi; antara Binanga Karaeng dengan Tana Mea. Bukan Paku – Suremana. Yang bila berdasar pada kisaran itu, maka wilayah Mandar bertambah beberapa kilometer. Bisa jadi hal tersebut ada benarnya, khususnya tentang Binanga Karaeng. Sebab ada ditulis dalam lontar mengenai muasal penentuan batas tersebut.
Namun yang perlu diperjelas di sini adalah tentang Lalombi. Ada yang beranggapan bahwa dengan menggunakan Lalombi sebagai batas utara, Mandar bisa lebih luas. Sebenarnya tidak, sebab bila berdasar garis koordinat bumi, Suremana itu masih lebih di atas dibanding dengan Lalombi.
Lain halnya dengan Tana Mea, yang jaraknya beberapa derajat/kilometer di atas Suremana. Hanya saja, tentang Tana Mea ini masih konon atau cerita-cerita. Bahwa disebut Tana Mea sebab dulunya di sana pernah terjadi pertumpahan darah (sehingga tanah menjadi warna merah) antara orang Mandar dengan orang di utara, memperebutkan wilayah. Kisah ini masih harus dikonfirmasi lebih lanjut untuk bisa digunakan sebagai salah satu dasar.
274 Muhammad Ridwan Alimuddin
Yang jelas, dari segi peristilahan, batas di utara itu masih lebih kuat bila menjadikan Suremana sebagai patokan. Alasan kesekian adalah bila berdasar pada kata Suremana. Kata tersebut sepertinya terdiri dari dua kata: “sure” dan “mana”. Kata “sure” kemungkinan besar berasal dari kata “sureq” atau corak/tanda, sedang “mana” itu penyebutan “mandar” oleh orang Kaili (sama seperti penamaan Teluk Tomini, yang mana kata itu berasal dari kata “to mene” atau orang Mandar).
Jika pun Suremana tidak masuk lagi wilayah Sulawesi Barat sekarang ini, itu bukan persoalan besar. Yang penting adalah, sebagai orang Mandar, kita terus mewariskan kesadaran sejarah bahwa Mandar itu merentang dari Paku (atau Binanga Karaeng) hingga Suremana.
280 Muhammad Ridwan Alimuddin
Sesaat sebelum memulai Ekspedisi Bumi MandarSebagian peralatan yang digunakan dalam ekspedisi
(netbook dalam tas merah Hello Kitty)Bekal perjalananMendokumentasikan dalam perjalananEkspedisi Bumi Mandar menempuh rute dari ujung
selatan Sulawesi Barat sampai ujung utara menggunakan sepeda
Berkemas di atas bukit karang di Tanjung Rangas Majene
Mendokumentasikan petani cengkeh di MajenePemecah batu di MajenePengerajin gamacca di Totolisi MajeneSalah satu teluk di pantai Kabupaten MajeneMelintasi tanjakan di KorossaPersiapan di perbatasan Sulawesi Selatan dengan
Sulawesi BaratSaat melintas sungai kecil di pesisir barat Tapalang
MamujuSituasi tempat berkemah di bukit karang di Tanjung
Rangas MajeneSetelah berkeliling di Pulau KarampuangPosisi kamera saat dipasang di sepeda
Suasana di dalam tendaPemandangan di pantai barat Tapalang MamujuBerziarah di makam budayawan Mandar Muis
MandraDi titik 0 km Suremana ujung utara MandarDi pelabuhan Belang belang MamujuMelintasi pantai barat Tapalang MamujuBersama kolega jurnalis Munawir (kiri) dan Farhan
(kanan) yang membantu Ekspedisi Bumi MandarBeristirahatBersama Asad Mana di kediamannya di Pasangkayu.
Beliau adalah pelaut Mandar yang pernah melayarkan sandeq di Prancis
Bersama siswa SMA Korossa yang baru lulus kuliah
24
26
25
27
281
PENULIS
Muhammad Ridwan Alimuddin (Iwan). Lahir 23 Desember 1978 di Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Menempuh pendidikan dasar sampai menengah di kampung halaman lalu lanjut kuliah di Manajemen Sumberdaya Perairan Jurusan Perikanan UGM Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai penulis, fotografer, peneliti, jurnalis, dan fixer. Kegiatan utama mendokumentasikan kebudayaan Mandar dan kebaharian Nusantara. Informasi lebih lanjut di www.ridwanmandar.com