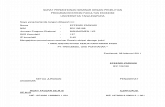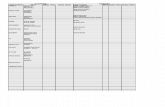E09lqo
-
Upload
leo-da-cruz -
Category
Documents
-
view
26 -
download
12
description
Transcript of E09lqo
-
PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
( STUDI KASUS BLOK RAJEGWESI SPTN I SARONGAN )
LAILATUL QOMARIAH
DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2009
-
PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
( STUDI KASUS BLOK RAJEGWESI SPTN I SARONGAN )
LAILATUL QOMARIAH E34104074
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kehutanan Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan
DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2009
-
RINGKASAN
Lailatul Qomariah. E34104074. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan). Di bawah bimbingan Tutut Sunarminto dan Eva Rachmawati. Taman Nasional Meru Betiri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Nomor: 277/Kpts-VI/1997 Tanggal 23 Mei 1997 seluas 58.000 Ha. Permasalahan yang dihadapi oleh TNMB berupa keberadaan perkebunan di dalam kawasan dan adanya buruh perkebunan dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah memberi peluang menjadi perambah/pelaku perusakan hutan (RKT TNMB 2008). Disisi lain TNMB kaya akan keanerakagaman hayati dan bentang alam yang bisa dijadikan daya tarik wisata, diantaranya Blok Rajegwesi yang menawarkan potensi daya tarik wisata alam maupun budaya karena Rajegwesi memiliki ciri khas dengan kehidupan masyarakat nelayannya. Tujuan utama penelitian adalah membuat suatu rancangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Blok Rajegwesi. Untuk itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara, yaitu mengetahui (a) potensi sumberdaya ekowisata yang terdapat di Blok Rajegwesi, (b) karakteristik masyarakat Blok Rajegwesi, (c) persepsi, motivasi, partisipasi dan minat masyarakat terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat serta (d) minat, persepsi dan motivasi pengunjung terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Pengambilan data responden masyarakat dan pengunjung dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner yang kemudian datanya diolah dengan menggunakan sistem tabulasi. Selanjutnya, data hasil tabulasi dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Sementara itu, rencana pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Rajegwesi dirumuskan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.
Sumberdaya ekowisata yang berada di Rajegwesi berupa Pantai Rajegwesi, Teluk Hijau, Teluk Damai, Stone Beach, Goa Jepang, dan habitat Rafflesia serta budaya masyarakatnya seperti kehidupan masyarakat nelayan, perayaan petik laut, dan petilasan Ki Ageng Wilis. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Rajegwesi didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu (1) potensi sumberdaya wisata yang terdapat di Rajegwesi, (2) persepsi dan motivasi masyarakat yang sangat mendukung sekali adanya pengembangan ekowisata di Rajegwesi, serta (3) minat pengunjung yang tinggi terhadap objek wisata alam di TNMB.
Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang dapat dilakukan di Rajegwesi yaitu bentuk ekowisata edukatif dengan program kegiatan yang ditawarkan adalah Adventure at Rajegwesi dan Rajegwesi Beach Tour. Peran masyarakat dalam program kegiatan tersebut terlihat dengan adanya bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pembagian keuntungan ekonomi. Proses pembagian keuntungan ekonomi dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan antara masyarakat dengan pengelola.
Kata Kunci: Rajegwesi, ekowisata, masyarakat.
-
ABSTRACT
Lailatul Qomariah. E34104074. Community Based Ecotourism Development in Meru Betiri National Park (Case Study Rajegwesi Block SPTN I Sarongan). Under Supervision of Tutut Sunarminto and Eva Rachmawati.
The area of Meru Betiri became national park based on Minister Forestry Decision about directing of Meru Betiri National Park No: 277/Kpts-VI/1997 on 23rd May 1997 with 58.000 Ha width. The problems faced by MBNP are the existence of plantation inside the area and the existence of plantation labour with very low income; which give them the opportunity to become invader / an agent of deforestation (RKT MBNP 2008). In the other side, MBNP have highly biodiversity richness and unique landscape that can be used as tourism object, like Block Rajegwesi that offers the potency of tourism attraction and culture also, because this area is unique in the way life of its fisherman society.
The main objective of this research is to create the design of ecotourism development based on community in Rajegwesi. There for, this research has spesific objectives, those are to know (a) the potency of ecotourism sources in Rajegwesi, (b) characteristics of Rajegwesi society, (c) perception, motivation, participation, and enthusiasm of Rajegwesi society about ecotourism development base on community also (d) enthusiasm, perception and motivation of visitor in ecotourism development base on community.
Data of responders society and visitors was collected by using interview and qutionnaire method. Then, data was processed and analyzed by using tabulation and descriptive analysis. Meanwhile, the planning of community based ecotourism development in Rajegwesi was formulated by using SWOT analyse approachment.
Ecotourism sources in Rajegwesi are Rajegwesi Beach, Green Bay, Peace Bay, Stone Beach, Japan Cave, and Rafflesia habitat also the culture are the fishery life, Petik Laut celebration, and Ki Ageng Wilis cemmetery. Community based ecotourism development in Rajegwesi relied on 3 (three) matters, those are (1) the potency of tourism sources in Rajegwesi (2) perception and motivation of i society which is very support the ecotourism development in Rajegwesi, also (3) high visitor enthusiasme to object of ecotourism in MBNP.
Community based ecotourism development which can be doing in Rajegwesi are education torism model based with activity program offered are Adventure at Rajegwesi dan Rajegwesi Beach Tour. The role of society in the activity program can be seen in model of participation where the society are involved in process of planning, decision making, implementation and sharing profit.). The process of profit sharing is conducted according to agreement which have been determined by among society with organizer.)
Key words: Rajegwesi, ecotourism, community.
-
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa Skripsi berjudul Pengembangan Ekowisata
Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok
Rajegwesi SPTN I Sarongan) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan
bimbingan komisi pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah
pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal dari
karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis, telah disebutkan
dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir laporan ini.
Bogor, Februari 2009
Lailatul Qomariah
NRP. E34104074
-
Judul Skripsi : Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan)
Nama : Lailatul Qomariah NRP : E34104074
Menyetujui: Komisi Pembimbing
Ketua, Anggota,
Ir.Tutut Sunarminto, M.Si Eva Rachmawati, S.Hut NIP. 131 878 494 NIP. 132 312 032
Mengetahui: Dekan Fakultas Kehutanan IPB,
Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr. NIP. 131 578 788
Tanggal Lulus :
-
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 1 bulan terhitung Tanggal 3 Juli
sampai 5 Agustus 2008. Lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah di
Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Banyuwangi.
Penyusunan skrispsi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh
gelar Sarjana Kehutanan di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan
Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Skripsi yang disusun
oleh penulis sebagai syarat wajib tersebut berjudul Pengembangan Ekowisata
Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok
Rajegwesi SPTN I Sarongan).
Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan
dan jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini tetap
dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.
Bogor, Februari 2009
Penulis
-
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam pelaksanaan penelitian skripsi, diantaranya:
1. Orang tuaku tercinta (Mudjiono dan Noerhajani) dan adik-adikku tersayang
(Ali Mukhtar dan Irmaniah) yang selalu memberikan semangat dan doa serta
dukungan materi.
2. Ir. Tutut Sunarminto, M.Si dan Eva Rachmawati, S.Hut selaku dosen
pembimbing yang telah memberikan nasehat, bantuan, bimbingan serta
perhatian sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
3. Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M. Sc selaku dosen pembimbing dan untuk kesabaran
serta arahan bagi penulis selama pembuatan proposal penelitian sebelum
digantikan oleh Eva Rachmawati, S.Hut.
4. Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.ScF.Trop selaku wakil dosen penguji Departemen
Manajemen Hutan dan Prof. Dr. Ir. Fauzi Febrianto, MS selaku wakil dosen
penguji Departemen Hasil Hutan untuk kesediaannya menjadi dosen penguji
dan untuk kesabaran serta arahan bagi penulis.
5. Ir. Herry Subagiadi, M.Sc selaku Kepala Balai TNMB beserta seluruh staff
dan pegawai TNMB yang telah banyak membantu selama penulis
melaksanakan penelitian di TNMB.
6. RM. Wied Widodo, S.Hut selaku Ketua SPTN I Sarongan beserta seluruh staff
kantor Sarongan (Pak Andik, Pak Didin, Pak Dzul, Pak Giyanto, Pak Saiful,
Pak Slamet, Mas Ali, Mas Beni, Mas Jumadi, Mas Alfian dan lainnya yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu). Terima kasih kesediannya
memberikan bimbingan dan arahan serta bantuannya selama penulis
melaksanakan penelitian di SPTN I Sarongan.
7. Seluruh mahasiswa KSH 41 yang pada umumnya telah banyak membantu dan
menjadi teman dalam suka maupun duka, khususnya mahasiswa satu
bimbingan (Heru Kurniawan, S.Hut dan Melincah U. Naibaho).
8. Sahabat-sahabat terbaik yang mewarnai hidupku (Puteri, Dita, Afin, Ade,
Linda, Kathy, Dede, Eko, Sulfan, Ucenk, Febi, Sefty, Diah, Melly). Terima
-
kasih untuk persahabatan, kepercayaan, dan pembelajaran penuh arti selama
ini.
9. Teman-temanku di kosan Pondok Iswara tercinta (Weni, Ratih, Enay, Rina,
Nona, Ismi, Uci) yang selalu memberikan dorongan semangat serta doanya.
10. Aaku Deni Ismanto yang selalu setia mendampingi baik dalam suka maupun
duka dan selalu memberikan semangat serta doanya.
11. Semua pihak yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi tetapi
namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
Bogor, Februari 2009
Penulis
-
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Penulis dilahirkan di Surabaya pada Tanggal 24 November 1986 dari
pasangan Mudjiono dan Noerhajani sebagai anak pertama dari tiga bersaudara.
Pada Tahun 1992, penulis memulai pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 11
Surabaya. Pada Tahun 1998, penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 3
Surabaya yang kemudian dilanjutkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi
lagi di SMA Negeri 2 Surabaya pada Tahun 2001.
Pada Tahun 2004 penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa Program
Studi Konservasi Sumberdaya Hutan, Institut Pertanian Bogor. Selama masa
perkuliahan, penulis aktif dalam beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan di
luar kampus seperti menjadi anggota HIMASURYA (Himpunan Mahasiswa
Surabaya) dan pengurus di HIMAKOVA (Himpunan Mahasiswa Konservasi).
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan, pada
Tahun 2008 penulis melaksanakan penelitian mengenai Pengembangan
Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus
Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan. Penelitian yang dilaksanakan selama 1
bulan tersebut dibimbing oleh Ir. Tutut Sunarminto, M.Si dan Eva Rachmawati,
S.Hut.
-
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Tujuan ................................................................................................. 2
C. Manfaat ............................................................................................... 3
D. Batasan Konsep................................................................................... 3
E. Kerangka Pemikiran........................................................................... . 4
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Taman Nasional.................................................................................... 6
B. Ekowisata ............................................................................................. 7
C. Ekowisata Berbasis Masyarakat........................................................... 9
D. Pengembangan Ekowisata .................................................................... 10
E. Penawaran dan Permintaan Pariwisata ................................................. 13
F. Motivasi ............................................................................................... 14
G. Minat .................................................................................................... 14
H. Persepsi ................................................................................................ 14
I. Masyarakat Lokal dan Partisipasinya................................................... 15
J. Analisis SWOT.................................................... ................................ 19
III. KONDISI UMUM LOKASI A. Sejarah .................................................................................................. 21
B. Luas dan Letak Kawasan ..................................................................... 21
C. Topografi .............................................................................................. 22
D. Iklim ..................................................................................................... 22
E. Tanah dan Geologi ............................................................................... 23
F. Flora dan Fauna..................................................................................... 23
G. Aksesibilitas.......................................................................................... 24
H. Demografi Masyarakat Blok Rajegwesi............................................... 25
-
I. Zonasi TNMB....................................................................................... 27
J. Kebijakan dan Peraturan Perundangan................................................. 30
IV. METODE TUGAS AKHIR A. Waktu dan Lokasi ................................................................................ 32
B. Alat ....................................................................................................... 33
C. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 33
D. Metode Penentuan Responden ............................................................. 34
E. Analisis Data ........................................................................................ 36
V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Potensi Sumberdaya Ekowisata di Rajegwesi ..................................... 38
1. Bentang Alam ................................................................................ 38
2. Keanekaragaman Hayati ................................................................ 40
3. Budaya Masyarakat ........................................................................ 41
B. Peta Penyebaran Potensi Sumberdaya Ekowisata di Rajegwesi.. 43
C. Masyarakat ........................................................................................... 44
1. Persepsi Masyarakat ....................................................................... 44
2. Partisipasi Masyarakat ................................................................... 46
3. Motivasi Masyarakat....................................................................... 47
4. Minat Masyarakat............................................................................ 47
D. Pengunjung ........................................................................................... 48
1. Karakteristik ................................................................................... 49
2. Motivasi dan Minat Pengunjung .................................................... 51
3. Persepsi Pengunjung ...................................................................... 51
E. Kapasitas Masyarakat Untuk Terlibat dalam Pengembangan
Ekowisata.............................................................................................. 52
F. Analisis dan Strategi Pengembangan dengan Analisis SWOT ............ 53
G. Konsep Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Rajegwesi 61
H. Program Kegiatan Ekowisata di Rajegwesi.................................... ..... 62
I. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata
Berbasis Masyarakat di Rajegwesi..................................................... 64
KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................... 67
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 69
-
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Matriks SWOT .................................................................................. 20
Tabel 2. Macam-Macam Alat untuk Penelitian .............................................. 32
Tabel 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Tugas Akhir ........................... 34
Tabel 4. Data Titik-Titik Koordinat Potensi Sumberdaya Ekowisata............. 43
Tabel 5. Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan........................................... 45
Tabel 6. Bentuk Partisipasi Masyarakat.......................................................... 46
Tabel 7. Motivasi Masyarakat ......................................................................... 47
Tabel 8. Minat Masyarakat.............................................................................. 48
Tabel 9. Data Jumlah Pengunjung Tahun 2003-2007 ..................................... 48
Tabel 10.Jumlah Pengunjung Berdasarkan Asal............................................ .. 49
Tabel 11. Jumlah Pengunjung Berdasarkan Umur........................................... 49
Tabel 12. Jumlah Pengunjung Berdasarkan Pendidikan.................................. 50
Tabel 13. Jumlah Pengunjung Berdasarkan Pekerjaan..................................... 51
Tabel 14. Motivasi dan Minat Pengunjung.. 51
Tabel 15. IFAS (Internal Factor Analysis Summary)........................................ 54
Tabel 16. EFAS (External Factors Analysis Summary). 54
Tabel 17. Alternatif Strategi dalam Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata
Berbasis Masyarakat di Rajegwesi 56
Tabel 18.Bentuk Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Rajegwesi 62
-
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 5
Gambar 2. Contoh Kegiatan Pengembangan Ekowisata di KTD-Sebangau ... 11
Gambar 3. Struktur Masyarakat Menurut Mata Pencaharian .......................... 26
Gambar 4. Struktur Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan ........................ 26
Gambar 5. Peta Zonasi di TNMB .................................................................... 29
Gambar 6. Peta Wilayah Kerja di TNMB........................................................ 32
Gambar 7. Pantai Rajegwesi ............................................................................ 38
Gambar 8. Teluk Hijau dan Teluk Damai ........................................................ 39
Gambar 9. Stone Beach .................................................................................. 39
Gambar 10. Goa Jepang ................................................................................... 40
Gambar 11. Rafflesia....................................................................................... . 41
Gambar 12. Kegiatan Nelayan Setelah Pulang Melaut .................................... 42
Gambar 13. Petilasan Ki Ageng Wilis ............................................................. 43
Gambar 14. Peta Potensi Sumberdaya Ekowisata di Rajegwesi.. 44
-
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Matriks Analisis SWOT .............................................................. 73
Lampiran 2. Kuesioner Masyarakat................................................................. 74
Lampiran 3. Kuesioner Pengunjung.................................................................. 77
Lampiran 4. Data Monografi Rajegwesi Tahun 2008.. 81
-
LAMPIRAN
-
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus sebagai hutan lindung
yang kemudian berubah menjadi Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pertanian Nomor: 276/Kpts./Um/6/1972 Tanggal 6 Juni 1972 dengan tujuan
utama perlindungan terhadap jenis Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica). Pada
perkembangan berikutnya status Meru Betiri berubah menjadi Taman Nasional
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan Taman
Nasional Meru Betiri (TNMB) Nomor: 277/Kpts-VI/1997 Tanggal 23 Mei 1997
seluas 58.000 Ha yang terletak pada dua wilayah kabupaten yaitu, Kabupaten Jember
seluas 37.585 Ha dan Kabupaten Banyuwangi seluas 20.415 Ha.
TNMB menghadapi beberapa permasalahan yang dapat mengganggu
keutuhan dan kelestarian kawasan berupa keberadaan perkebunan di dalam kawasan
TNMB karena orientasi perusahaan yang dominan mengarah kepada profit
(keuntungan) tanpa mempertimbangkan aspek ekologis kawasan serta adanya buruh
perkebunan dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah memberi peluang menjadi
perambah/pelaku perusakan hutan (RKT TNMB 2008). Aktivitas masyarakat sekitar
kawasan dalam memanfaatkan sumber daya alam di kawasan TNMB juga cenderung
mengarah pada tindakan merusak dan mengancam keberadaan kawasan TNMB sulit
dicegah dan dikendalikan, serta cenderung mengalami peningkatan baik kuantitas
maupun kualitasnya. Contoh dari beberapa kasus pelanggaran hutan yang melibatkan
masyarakat antara lain kasus pencurian kayu balok yang terjadi di STPN I Sarongan
pada tahun 2007 sebanyak 236 batang, pencurian bambu sebanyak 500 batang, dan
perambahan kawasan seluas 150 ha (Buku Statistik Balai TNMB 2007).
TNMB yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan salah satu
kawasan pelestarian alam yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan
alam yang menjadi daya tarik wisata. Potensi alam yang dikembangkan menjadi
obyek wisata di TNMB terdapat di dua lokasi (resort) yaitu Bandealit dan Sukamade.
Obyek wisata yang menyajikan keindahan panorama alam di dua lokasi tersebut
1
-
2
meliputi Pantai Rajegwesi, Pantai Sukamade, Teluk Hijau, Pantai Permisan, Teluk
Meru dan Teluk Bandealit.
Mackinnon (1990) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan banyak
bergantung pada kadar dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada kawasan
yang dilindungi oleh masyarakat disekitarnya. Sejalan dengan hal itu, untuk
mengurangi tekanan terhadap hutan oleh masyarakat, maka masyarakat lokal dapat
diberdayakan dalam kegiatan ekowisata yang berbasis masyarakat mengingat begitu
banyak pula potensi sumberdaya alam di TNMB yang berpotensi menjadi daya tarik
wisata. Selain dapat meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat lokal,
ekowisata ini juga memberikan keuntungan di bidang ekonomi bagi taman nasional.
Adanya hubungan yang bersifat ekonomi antara masyarakat sekitar Rajegwesi dengan
kawasan TNMB yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya yang
berada di kawasan TNMB untuk itulah penelitian pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat dilakukan di Resort Rajegwesi.
B. Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian adalah untuk membuat suatu rancangan
pengembangan ekowisata di TNMB, khususnya di Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan,
dengan melibatkan peran masyarakat lokal. Untuk itu, penelitian ini memiliki
beberapa tujuan antara, yaitu:
a. Mengetahui potensi sumberdaya ekowisata yang terdapat di Blok Rajegwesi
SPTN I Sarongan, meliputi bentang alam (topografi), keanekaragaman hayati
(keunikan/kekhasan flora dan fauna) dan adat istiadat/budaya masyarakat
Rajegwesi sebagai daya tarik wisata,
b. Mengetahui karakteristik masyarakat Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan
meliputi potensi sumber daya manusianya (mata pencaharian, tingkat
pendidikan, dsb),
c. Mengetahui persepsi, motivasi, partisipasi dan minat masyarakat Blok
Rajegwesi terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan
-
3
d. Mengetahui minat, persepsi dan motivasi pengunjung terhadap pengembangan
ekowisata berbasis masyarakat.
C. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak
pengelola untuk dijadikan acuan sebagai proses dalam pengembangan ekowisata di
TNMB khususnya di Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan. Selain itu juga diharapkan
dapat memberikan manfaat agar terjadi suatu peningkatan bagi kesejahteraan seluruh
komponen masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap
penyelenggaraan ekowisata di TNMB.
D. Batasan Konsep a. Ekowisata: Memiliki pengertian yang sama dengan ekoturisme atau wisata
ekologi, yang berarti wisatawan menikmati keanekaragaman hayati dengan
tanpa melakukan aktifitas yang menyebabkan perubahan pada alam, atau
hanya sebatas mengagumi, meneliti dan menikmati serta berinteraksi dengan
masyarakat lokal dan obyek wisata tersebut.
b. Ekowisata berbasis masyarakat: Ekowisata dapat menciptakan nilai
ekonomi untuk kawasan konservasi seperti taman nasional. Wisatawan
mengunjungi kawasan taman nasional untuk memahami dan menghargai
nilai-nilai dimana taman nasional tersebut didirikan dan wisatawan
mendapatkan keuntungan berupa pengetahuan dan pengalaman pribadi.
Adanya kunjungan dari wisatawan ke kawasan taman nasional tentu saja
memberikan keuntungan secara finansial bagi taman nasional yang dapat
dimanfaatkan taman nasional untuk biaya operasional.
Berbasis masyarakat berarti haruslah ada peranan dari masyarakat dalam
setiap kegiatan ekowisata dan masyarakat haruslah memperoleh manfaat dari
pengusahaan ekowisata, ada kendali atas pengembangan ekowisata dalam
rangka mengurangi dampak negatif terhadap kawasan, budaya dan kehidupan
sosial mereka serta terlibat dalam pengelolaan aktifitas ekowisata.
-
4
E. Kerangka Pemikiran Masyarakat Ekowisata (The Ecotourism Society, 1991 dalam Wood, 1996
dalam Lash, 1997) mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang
bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata dalam definisi ini dapat dilihat dari tiga
perspektif, yakni sebagai: (1) produk, merupakan semua atraksi yang berbasis pada
sumberdaya alam. (2) pasar, merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya
pelestarian lingkungan dan (3) pendekatan pengembangan, merupakan metode
pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan
(Damanik, 2006).
TNMB yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan salah satu
kawasan pelestarian alam yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan
alam yang menjadi daya tarik wisata. Salah satu obyek wisata di TNMB yang
berpotensi untuk dilakukan pengembangan ekowisata terdapat di Resort Rajegwesi
dengan pantainya yang menjadi daya tarik wisata. Rajegwesi berlokasi di desa
Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.
Data yang tercatat di Sarongan sampai Agustus 2007, pemukim Blok
Rajegwesi setiap tahunnya bertambah 8 kepala keluarga. Pertumbuhan pemukim
dusun Rajegwesi setiap tahunnya terus bertambah, apabila dibiarkan berlarut-larut
kemungkinan akan berubah menjadi perkampungan besar dan akan mengancam
keberadaan serta keutuhan kawasan TNMB. Untuk mengatasinya perlu dilakukan
sesegera mungkin upaya pengelolaan pemukim Blok Rajegwesi dengan menata
mereka sehingga menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan kawasan TNMB.
Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan adanya enclave di Rajegwesi
adalah adanya pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat, yaitu dengan
melibatkan peran masyarakat Rajegwesi keseluruhannya dalam pengelolaannya.
Harapan ke depan dengan adanya pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di
Blok Rajegwesi dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu
-
pihak TN dan masyarakat Rejegwesi itu sendiri. Adapun dampak positif tersebut
adalah:
a. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat
b. Terciptanya sumber pendapatan masyarakat yang beraneka ragam.
c. Tertatanya pemukim Rajegwesi dengan rapih
d. Terkendalinya ketergantungan masyarakat terhadap potensi sumber daya alam
yang berada di kawasan TNMB.
Motivasi dan persepsi pengunjung dapat menentukan keinginan dari
pengunjung untuk melakukan jenis wisata apa yang diiinginkan karena dapat
memberikan pengalaman berharga dan membuat pengunjung memiliki apresiasi
terhadap lingkungan. Masyarakat sebagai bagian dari kawasan memiliki peranan
penting dalam partisipasi dan interaksi terhadap kegiatan wisata sehingga manfaat
dari pelaksanaan kegiatan wisata dapat dirasakan oleh masyarakat
Kerangka penelitian yang secara garis besar menggambarkan keseluruhan kegiatan
penelitian yang dilakukan, disajikan pada Gambar 1.
Manajemen Sumberdaya wisata Masyarakat
Bentang alam Keunikan flora dan fauna
Karakte- ristik
Kebuda- yaan
Motivasi Persepsi
Minat Ekowisata
Pengembangan ekowisata berbasiskan masyarakat
Wisatawan
Taman Nasional Meru Betiri
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
5
-
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Taman Nasional
PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam menjelaskan bahwa Kawasan Taman Nasional adalah kawasan
pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi
yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Suatu kawasan ditunjuk sebagai
kawasan Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut
1) kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin
kelangsungan proses ekologis secara alami;
2) memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan
maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
3) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
4) memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai
pariwisata alam; dan
5) merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan,
zona rimba, dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi
kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka
mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.
Sesuai dengan batasan UU No. 5 Tahun 1990 bahwa taman nasional
dikelola dengan sistem zonasi, maka pemanfaatan potensi sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya di taman nasional dilakukan berdasarkan penataan
zonasi.
Pemanfaatan Taman Nasional untuk tujuan ilmu pengetahuan dan
penelitian dilakukan pada seluruh zona dengan izin Kepala Balai Taman Nasional.
Untuk tujuan pendidikan dilakukan pada zona rimba, zona pemanfaatan wisata
dan zona pemanfaatan lainnya. Sedangkan untuk tujuan pariwisata alam dilakukan
pada zona pemanfaatan intensif, dan secara terbatas pada zona rimba. Guna
mendukung kepentingan pemanfaatan oleh masyarakat setempat akan hasil hutan
non kayu dikembangkan adanya zona pemanfaatan tradisional dan zona
pemanfaatan khusus (Riyanto, 2005).
6
-
7
Taman Nasional merupakan salah satu kawasan konservasi yang
mengandung aspek pelestarian dan aspek pemanfaatan sehingga kawasan ini dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata dan minat khusus. Kedua bentuk
pariwisata tersebut yaitu ekowisata dan minat khusus, sangat prospektif dalam
penyelematan ekosistem hutan. Pengembangan kawasan yang demikian ini yang
menguntungkan bagi kelestarian hutan (Fandeli, 2005).
B. Ekowisata
Masyarakat Ekowisata Internasional (The Ecotourism Society) (1991)
mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab
dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal (responsible travel to natural areas that conserves the
environment and improves the well-being of local people) (Epler Wood, 1996
dalam Lash, 1997). Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif,
yakni sebagai (1) produk, (2) pasar, dan (3) pendekatan pengembangan. Sebagai
produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya
alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada
upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan
pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan
sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Di sini kegiatan wisata yang
bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian
lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang
berperan penting dalam ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku
wisata lain (tour operatour) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan
tanggungjawab tersebut (Damanik, 2006).
TIES (2000) dalam Damanik (2006), beberapa prinsip ekowisata yang
dapat diidentifikasi dari beberapa definisi ekowisata di atas, yakni sebagai berikut
1) mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan
dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata;
2) membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di
destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku
wisatawan lainnya;
-
8
3) menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun
masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama
dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW;
4) memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi
melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan;
5) memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal
dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal;
6) meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di
daerah tujuan wisata; dan
7) menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan
kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati aktraksi
wisata sebagai wujud hak asazi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan
disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.
The Ecotourism Society (dalam Fandeli 2002:115-116) terdapat delapan prinsip
yang bila dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan ecological
friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan
1) mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam
dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya
setempat;
2) pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan masyarakat
setempat akan pentingnya arti konservasi;
3) pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan
untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat
menerima langsung penghasilan atau pendapatan;
4) partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan;
5) keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat;
6) menjaga keharmonisan dengan alam;
7) pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah
dengan daya dukung kawasan buatan; dan
8) peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.
Semua pengertian di atas, mengarah kepada pemahaman terhadap aktifitas
berwisata atau mengunjungi kawasan alam dengan niat obyektif untuk melihat,
-
9
mempelajari, mengagumi keindahan alam, flora, fauna termasuk aspek-aspek
budaya baik di masa lampau maupun sekarang yang mungkin terdapat di kawasan
tersebut.
C. Ekowisata Berbasis Masyarakat
Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial ekowisata
adalah suatu langkah lebih lanjut dengan mengembangkan bentuk ekowisata
dimana masyarakat lokal yang mempunyai kendali penuh, dan keterlibatan di
dalamnya baik itu di manajemen dan pengembangannya, dan proporsi yang utama
menyangkut sisa manfaat di dalam masyarakat (WWF International, 2001).
Ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu memelihara penggunaan
sumberdaya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari itu,
memelihara kedua-duanya adalah tanggung jawab kolektif dan inisiatif individu di
dalam masyarakat tersebut. Selagi definisi dan penggunaan dari bentuk
terminologi CBT dan ekowisata berbasis masyarakat bisa berubah-ubah dari satu
negeri atau daerah [bagi/kepada] yang lain, tidaklah menjadi masalah yang berarti
tentang sebuah nana, tetapi hanyalah prinsip sosial dan tanggung jawab
lingkungan disetiap tindakan (The International Ecotourism Society, 2006)
WWF (World Wide Fund for Nature) Guidelines for Community-Based
Ecotourism Development (2001) menyebutkan syarat-syarat untuk memutuskan
pengembangan bisnis ekowisata sebagai berikut
a. kerangka ekonomi dan politik yang mendukung perdagangan yang efektif dan
investasi yang aman;
b. perundang-undangan di tingkat nasional yang tidak menghalangi pendapatan
dari wisata diperoleh dan berada di tingkat komunitas lokal;
c. tercukupinya hak-hak kepemilikan yang ada dalam komunitas lokal;
d. keamanan pengunjung terjamin;
e. resiko kesehatan yang relative rendah, akses yang cukup mudah ke pelayanan
medis dan persediaan air bersih yang cukup; dan
f. tersedianya fasilitas fisik dan telekomunikasi dari dan ke wilayah tersebut.
Adapun syarat-syarat dasar untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
seperti tercantum dalam buku tersebut adalah
-
10
a. lanskap atau flora fauna yang dianggap menarik bagi para pengunjung khusus
atau bagi pengunjung yang lebih umum;
b. ekosistem yang masih dapat menerima kedatangan jumlah pengunjung
tertentu tanpa menimbulkan kerusakan;
c. komunitas lokal yang sadar akan kesempatan-kesempatan potensial, resiko
dan perubahan yang akan terjadi, serta memiliki ketertarikan untuk menerima
kedatangan pengunjung;
d. adanya struktur yang potensial untuk pengambilan keputusan komunitas yang
efektif;
e. tidak adanya ancaman yang nyata-nyata dan tidak bisa dihindari atau dicegah
terhadap budaya dan tradisi lokal;
f. penaksiran pasar awal menunjukkan adanya permintaan yang potensial untuk
ekowisata, dan terdapat cara yang efektif untuk mengakses pasar tersebut.
Selain itu juga harus diketahui bahwa pasar potensial tersebut tidak terlalu
banyak menerima penawaran ekowisata.
Sesuai dengan yang tercantum dalam Guidelines for Community-Based
Ecotourism Development (2001) aspek dari komunitas untuk terlibat dalam
pengembangan ekowisata, adalah
a. kemampuan menjadi tuan rumah penginapan
b. keterampilan dasar bahasa inggris
c. keterampilan komputer
d. keterampilan pengelolaan keuangan
e. keterampilan pemasaran
f. keterbukaan terhadap pengunjung
D. Pengembangan Ekowisata
Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan
pengembangan obyek dan daya tarik wisata alamnya (ODTWA). Menurut
Departemen Kehutanan (2007) keseluruhan potensi ODTWA merupakan sumber
daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan
dan pelestarian lingkungan. Lebih rinci Departemen Kehutanan (2007)
menjelaskan pengembangan ODTWA sangat erat kaitannya dengan peningkatan
-
produktifitas sumber daya hutan dalam konteks pembangunan interaksi berbagai
kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, aspek
masyarakat, dan pihak swasta di dalamnya. Contoh kegiatan pengembangan
ekowisata di suatau kawasan dapat dilihat pada Gambar 2
.
Gambar 2. Contoh kegiatan pengembangan ekowisata di KTD-Sebangau
Suprana (1997), dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan
pelestarian alam memiliki strategi pengembangan dan program pengembangan
Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di kawasan hutan, antara lain
1. Strategi pengembangan ODTW
Pengembangan potensi ODTW untuk menunjang tujuan pembangunan
khususnya pengembangan pariwisata mencakup aspek-aspek perencanaan
pembangunan, kelembagaan, sarana prasarana dan infrastruktur, pengusahaan
pariwisata alam, promosi dan pemasaran, pengelolaan kawasan, sosial budaya dan
sosial ekonomi, penelitian pengembangan, dan pendanaan.
2. Program pengembangan ODTW
Pembangunan ODTW khususnya pengembangan ODTW dapat diwujudkan
dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan: (a) Inventarisasi potensi, pengembangan
dan pemetaan ODTW, (b) Evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan pengelola
ODTW, (c) Pengembangan dan pemantapan sistem pengelolaan ODTW, (d)
Pengembangan sistem perencanaan, (e) Penelitian dan pengembangan manfaat, (f)
Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur, (g) Perencanaan dan penataan,
(h) Pengembangan pengusahaan pariwisata alam dan (i) Pengembangan sumber
daya manusia.
Adanya pengembangan wisata di suatu tempat akan memberikan berbagai
keuntungan baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mackinnon et al
(1990) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di dalam dan disekitar
kawasan yang dilindungi merupakan salah satu cara terbaik untuk mendatangkan
11
-
12
keuntungan ekonomi kawasan terpencil, dengan cara menyediakan kesempatan
kerja masyarakat setempat, merangsang pasar setempat, memperbaiki sarana
angkutan, dan komunikasi. Muntasib et al. (2004) menyatakan beberapa prinsip
dasar pengembangan ekowisata, yaitu
1) berhubungan/kontak langsung dengan alam (Touch with nature);
2) bengalaman yang bermanfaat secara pribadi dan sosial;
3) bukan wisata massal;
4) program-programnya membuat tantangan fisik dan mental bagi wisatawan;
5) interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat;
6) adaptif (menyesuaikan) terhadap kondisi akomodasi pedesaan; dan
7) pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan.
Usman (1999) mengemukakan bahwa pengembangan ekowisata
Indonesia, hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah keikutsertaan
masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep
pengembangan wisata dengan melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta
masyarakat (community based ecotourism), pada dasarnya adalah memberikan
kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi
obyek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan.
Peran Pemerintah Kabupaten Jember dan Banyuwangi dalam membantu
pengelolaan kawasan ekowisata di Taman Nasional Meru Betiri sangat penting.
Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah khususnya PEMDA Jember telah
dituangkan dalam Peraturan Daerah. Seperti misalnya, Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2002 tentang pengawasan dan pengendalian
pengelolaan hutan. Dalam konsideran menimbang huruf b Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2002 tersirat adanya pengakuan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bahwa hutan saat ini telah mengalami
penurunan kualitas.
Kebijakan PEMDA Banyuwangi dalam kaitannya dengan kebijakan
perlindungan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan ekowisata termasuk taman
nasional hingga saat ini adalah nol karena belum ada produk hukum yang
diterbitkan PEMDA Kabupaten Banyuwangi maupun Keputusan Bupati
Banyuwangi (Riyanto, 2005).
-
13
E. Penawaran dan Permintaan Pariwisata (Supply and Demand)
Recreation demand atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan
permintaan rekreasi menurut Avenzora (2003) adalah tentang: (1) siapa yang
meminta; (2) apa dan berapa banyak yang diminta, dan (3) kapan diminta.
Sedangkan recreation supply atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan
penawaran rekreasi dapat dipahami melalui pengertian tentang : (1) apa dan
berapa banyak yang dapat diberikan, (2) kapan dapat diberikan, dan (3) kepada
siapa dapat diberikan.
Penawaran pariwisata yang berupa produk kepariwisataan terdiri atas tiga
komponen yaitu atraksi wisata, jasa wisata dan angkutan wisata (Soekadijo,
2000). Suatu daerah dapat dijadikan tempat tujuan wisata kalau kondisinya
mendukung sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata.
Segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut sebagai
modal atau sumberdaya kepariwisataan. Sumberdaya yang dapat menarik
kedatangan wisatawan ada tiga yaitu alam, kebudayaan, dan manusia itu sendiri.
Menurut Avenzora (2003), sumberdaya wisata dapat didefinisikan sebagai
suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang mengandung elemen-
elemen ruang tertentu yang dapat : (1) menarik minat orang untuk berekreasi, (2)
menampung kegiatan rekreasi, dan (3) memberikan kepuasan orang berekrasi.
Sumberdaya wisata juga identik dengan istilah ruang atau space. Space
merupakan suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang memiliki daya
tarik tertentu berupa air, udara, tanah dan sebagainya yang mampu menarik orang
untuk berekreasi atau berwisata dan menampung orang untuk melakukan kegiatan
wisata. Sudarto (1999) menyatakan unsur paling penting yang menjadi daya tarik
dari sebuah daerah tujuan wisata adalah:
1) kondisi alam, contoh hutan hujan tropis dan terumbu karang;
2) kondisi flora dan fauna yang unik, langka & endemik, seperti rafflesia, badak
jawa, komodo, orang utan;
3) kondisi fenomena alam seperti gunung Krakatau dan danau Kelimutu; dan
4) kondisi adat & budaya, seperti Baduy, Toraja, Bali dan Sumba.
-
14
F. Motivasi
Setiap tindakan manusia digerakkan dan dilatarbelakangi oleh motif
tertentu. Tanpa motivasi orang tidak akan berbuat apa-apa. Motivasi adalah suatu
bentuk dorongan minat dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang,
sesebuah keluarga atau organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan (Suhaidin,
2008).
Motif didefinisikan sebagai suatu alasan/dorongan yang menyebabkan
seseorang berbuat sesuatu/melakukan tindakan/bersikap tertentu. Suatu motif
umumnya terdapat dua unsur pokok yaitu unsur dorongan/kebutuhan dan unsur
tujuan. Proses timbal balik antara kedua unsur tersebut terjadi dalam diri manusia,
namun dapat dipengaruhi oleh hal-hal di luar dari manusia, misalnya keadaan
cuaca, kondisi lingkungan dan sebagianya. Oleh karena itu dapat saja terjadi
perubahan motivasi dalam waktu relatif singkat, jika ternyata motivasi yang
pertama mendapat hambatan atau tidak mungkin terpenuhi (Handoko, 1992)
dalam (Naibaho, 2002).
G. Minat
Minat mempunyai karakteristik pokok yaitu melakukan kegiatan yang
dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga dapat membentuk suatu kebiasaan
dalam diri seseorang. Minat dan motivasi memiliki hubungan dengan segi kognisi,
namun minat lebih dekat pada perilaku (Abadi, 2006).
H. Persepsi
Persepsi adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap obyek
tertentu yang dihasilkan oleh kemampuan mengorganisasi pengamatan.
Selanjutnya persepsi ditentukan oleh dua faktor dalam diri individu (faktor
internal) dan faktor luar individu (faktor eksternal). Faktor internal meliputi
kecerdasan, minat, emosi, pendidikan, pendapatan, kapasitas alat indera dan jenis
kelamin. Faktor eksternal meliputi pengaruh kelompok, pengalaman masa lalu dan
perbedaan latar belakang sosial budaya. Pandangan atau penilaian ini dipengaruhi
oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan (Kayam, 1985) dalam (Entebe,
2002).
-
15
I. Masyarakat Lokal dan Partisipasinya
Partisipasi menurut Ndraha (1987) meliputi tiga hal yaitu partisipasi dalam
memikul beban pembangunan (beban fisik dan non fisik), partisipasi dalam
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dan partisipasi dalam
menerima kembali hasil pembangunan. Ife (2005) mengemukakan beberapa
keadaan atau kondisi seseorang akan berpartisipasi yaitu
1) jika kegiatan tersebut penting bagi mereka;
2) mereka merasa bahwa tindakan mereka akan membuat suatu perubahan;
3) diakui dan dihargai adanya perbedaan-perbedaan partisipasi; dan
4) kemungkinan mereka untuk berpartisipasi
Anonim (2003) dalam Abikusno (2005) menyatakan bahwa prinsip
partisipasi masyarakat adalah dilibatkannya masyarakat setempat secara optimal
melalui musyawarah dan mufakat dalam kegiatan perencanaan dan
pengembangan. Adapun kriteria yang dimaksudkan dalam kegiatan pelibatan
masyarakat tersebut antara lain adalah
(1) melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses
perencanaan dan pengembangan ekowisata;
(2) membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk
mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata;
(3) membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk
melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang
ditimbulkan;
(4) meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang
berkaitan dan menunjang pengembangan wisata;
(5) mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran
pendapatan (leakage) serendah-rendahnya;
(6) meningkatkan pendapatan masyarakat.
Jain (2000) ada tujuh macam tipe partisipasi yang ada pada masyarakat,
antara lain
1) partisipasi pasif, tipe partisipasi yang tidak memperhitungkan tanggapan
partisipan dalam pertimbangan dan hasilnya telah terlebih dahulu ditetapkan.
Informasi hanya dibagikan pada external institusi;
-
16
2) partisipasi dalam pemberian informasi, orang memberikan jawaban atas
pertanyaan dimana mereka tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi
dalam konteks wawancara dan seringkali hal baru tidak dibagikan;
3) partisipasi dalam bentuk konsultasi, orang dikonsultankan dan pendapat
mereka termasuk ke dalam hitungan tetapi mereka tidak termasuk dalam
pembuatan keputusan;
4) partisipasi aktif, meliputi orang yang memberikan dorongan dalam materi
dan dorongan langsung untuk pelayanan yang disediakan. Dalam beberapa
contoh kasus, tidak adanya peraturan yang dimasukkan sekalipun dorongan
tersebut telah berakhir;
5) partisipasi fungsional, partisipasi terjadi dengan pembentukan dalam grup
dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti partisipasi pada
umumnya terjadi hanya setelah keputusan utama telah diambil;
6) partisipasi interaktif, orang berperan aktif dalam menghasilkan informasi
dan analisis berikutnya yang mengarah kepada rencana aksi dan
implementasinya. Hal itu melibatkan metodologi yang berbeda dalam mencari
bermacam-macam perspektif lokal. Dengan demikian melibatkan orang
dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan dan kualitas informasi;
dan
7) pergerakan pribadi, tipe partisipasi yang bebas dari campur tangan pihak
luar. Orang berpartisipasi dan mengambil inisiatif untuk mengganti sistem.
Mereka mengembangkan kontak untuk masukan dari luar tetapi tetap
menguasai kontrol atas sumberdaya.
Beberapa contoh bentuk partisipasi dalam wisata berbasis masyarakat (Jain, 2000)
1) partisipasi dalam perencanaan, partisipan memainkan peranan penting
dalam menyampaikan informasi, analisisnya dan pemanfaatan berikutnya
yakni dalam proses pembelajaran dan perencanaan. Aspek penting untuk
masyarakat berdasarkan kepariwisataan adalah partisipasi dalam menilai
pilihan dan ekonominya serta kemungkinan konservasinya;
2) partisipasi dalam pelaksanaan dan perjalanan prosesnya, wisata berbasis
masyarakat memerlukan pelaksanaan struktur dan penyusunan untuk
menjalankan aktifitas. Partisipan memegang peranan penting untuk
-
17
melaksanakan aktifitas, menyusun institusi dan dalam operasi
perusahaan; dan
3) partisipasi dalam pembuatan keputusan dan manajemen, partisipan
memainkan peran penting dalam pilihan, desain dan manajemen wisata
berbasis masyarakat, termasuk perusahaan wisata, aktifitas konservasi,
monitoring serta evaluasi; dan
4) partisipasi dalam pembagian keuntungan ekonomi, dalam hal ini
perbedaan yang dibuat mengenai tingkatan dalam pengambilan keputusan
dalam pemilihan aktifitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Perbedaan
awal antara tipe ini dan perbuatan awal...kepemilikan, bahwa partisipan
hanya mempunyai sedikit atau tidak dikatakan dalam aktifitas pilihan.
Pelaksanaan ekowisata harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap
perencanaan, pengelolaan dan pemantauan karena masyarakat lokal, terutama
penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain
kunci dalam pariwisata. Dengan demikian, kegiatan wisata alam diharapkan
mampu mengupayakan keuntungan finansial sekaligus sebagai alternatif
peningkatan taraf hidup masyarakat
Masyarakat harus diperlakukan sebagai subyek pembangunan karena
sesungguhnya merekalah yang akan meyediakan sebagian besar atraksi sekaligus
menentukan kualitas produk wisata. Selain itu masyarakat lokal merupakan
pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi
wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata
yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisatawan lainnya berada di tangan
mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir
sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di
kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.
Tidak jarang, masyarakat lokal sudah terlebih dahulu terlibat dalam
pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan dan
perencanaan. Oleh sebab itu peran mereka terutama tampak dalam bentuk
penyediaan akomodasi dan jasa guiding dan penyediaan tenaga kerja. Selain itu
masyarakat lokal biasanya juga mempunyai tradisi dan kearifan lokal dalam
pemeliharaan sumberdaya pariwisata yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata
-
18
lainnya (Damanik, 2006). Sedangkan menurut Rahardjo (2005) selain yang
disebutkan oleh Damanik, bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan oleh
masyarakat lokal antara lain
1) membentuk joint venture dengan tour operator dimana masyarakat
menyediakan lebih banyak service sedangkan pihak swasta hanya fokus pada
promosi dan pemasaran;
2) menyediakan layanan kepada tour operator;
3) menyewakan lahan kepada pihak tour operator. Dalam hal ini masyarakat
masih memungkinkan untuk melakukan monitoring atas dampak dari aktifitas
wisata;
4) mengembangkan program sendiri secara mandiri; dan
5) bekerja sebagai staf tour operator baik full time atau part time
Masyarakat sekitar kawasan taman nasional sebagai bagian integral dari
kawasan taman nasional dapat berperan serta baik secara langsung maupun tak
langsung. Masyarakat lokal tidak hanya sebagai host communities dalam
kegiatan ekowisata, tetapi sebagai pengelola yang juga memiliki kewenangan
dalam menentukan di setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekowisata tersebut.
Peran serta masyarakat tersebut dalam suatu kawasan konservasi akan terlihat
seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh masyarakat sekitar.
Pengembangan ekowisata dengan keterlibatan masyarakat lokal relatif
mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan
1) jumlah wisatawan berskala kecil sehingga lebih mudah dikoordinir dan
dampak yang akan ditimbulkan terhadap alam relative kecil dibanding
pariwisata massal;
2) ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam
mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil sehingga dapat
dikelola dan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal;
3) dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan
obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih
besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan;
dan
-
19
4) memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (cultural
sustainability) serta meningkatkan penghargaan wisatawan terhadap
kebudayaan lokal.
J. Analisis SWOT
SWOT adalah singkatan Strengths (kekuatan) dan Weaknesses
(kelemahan) yang merupakan lingkungan internal serta Opportunities (peluang)
dan Threats (ancaman) yang merupakan lingkungan eksternal. Rangkuti (2006)
menulis bahwa analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan Strengths dan Opportunities, namun secara bersamaan dapat
meminimalkan Weaknesses dan Threats
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi
sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain. Jadi kekuatan dan
kelemahan sumberdaya tersebut perlu ditegaskan sejak awal. Agak berbeda
dengan studi kelayakan, analisis sumberdaya ekowisata sudah harus menghasilkan
sintesis yang akan dijadikan basis proyek. Oleh sebab itu semua pihak, khususnya
masyarakat lokal, perlu mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
oleh kawasan dan objek ekowisata tersebut. Menurut Damanik (2006), agar hasil
analisis SWOT sebaiknya menggambarkan
1) perkembangan produk dan pasar ekowisata itu sendiri;
2) organisasi dan kelembagaan pariwisata;
3) peluang-peluang pengembangan inti kegiatan ekowisata (core activities) ; dan
4) jasa-jasa dan kegiatan lain yang mungkin dikembangkan.
Menurut Santoso dan Tangkilisan (tanpa tahun) menyebutkan bahwa ada beberapa
strategi yang diperoleh dari teknik analisa SWOT ini sebagai berikut
1) strategi SO (Strength Opportunity): memperoleh keuntungan dari peluang
yang tersedia di lingkungan eksternal ;
2) strategi WO (Weakness Opprtunity): memperbaiki kelemahan internal dengan
memanfaatkan peluang dari lingkungan luar ;
3) strategi ST (Strength Threat): menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk
menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar ; dan
-
20
4) strategi WT (Weakness Threat): memperkecil kelemahan internal dan
menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar
Adapun contoh pembuatan matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Matriks SWOT
Faktor Internal Faktor Eksternal
Kekuatan (Strengths) Menentukan faktor-faktor yang merupakan kekuatan internal
Kelemahan (Weakness) Menentukan faktor-faktor yang merupakan kelemahan internal
Peluang (Opportunity) Menentukan faktor-faktor yang merupakan peluang eksternal
Strategi S-O Menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Strategi W-O Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan kelemahan
Ancaman (Threat) Menentukan faktor-faktor yang merupakan ancaman eksternal
Strategi S-T Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Strategi T-W Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
-
III. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah
Taman Nasional Meru Betiri pada awal pembentukannya ditetapkan
sebagai hutan lindung yang merupakan keputusan dari Besluit van Den, Direktur
Landbouw Neveirheiden Handel, No. 7347/B pada Tanggal 29 Juli 1931 serta
Besluit Directur van Economische Zaken No. 5751 Tanggal 28 April 1938.
Tanggal 6 Juni 1972, Kawasan Meru Betiri ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa
dengan luas 50.000 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
267/Kpts/Um/6/1972, untuk perlindungan Harimau Jawa (Phantera tigris
sondaica). Statusnya kemudian berubah menjadi calon Taman Nasional pada
Tanggal 14 Oktober 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
736/Kpts/Mentan/X/82 dan resmi menjadi Taman Nasional melalui Surat
Keputusan No. 277/Kpts-VI/97 dengan luas 58.000 hektar.
B. Luas dan Letak Kawasan
Taman Nasional Meru Betiri seluas 58.000 Ha terdiri atas 57.155 Ha
daratan dan 845 ha perairan. Secara administrasi pemerintahan, Taman Nasional
Meru Betiri terletak di wilayah Kabupaten Jember (37.585 Ha) dan Kabupaten
Banyuwangi (20.415 Ha). Di dalam kawasan TNMB terdapat areal perkebunan
seluas 2.155 Ha yaitu Perkebunan Sukamade Baru dan Perkebunan Bandealit.
Secara geografis Taman Nasional Meru Betiri terletak diantara 8021-8034 LS
dan 113037-113058 BT. Batas administratifnya adalah
Sebelah Utara : PT. Perkebunan Treblasala dan PT. Perhutani RPH
Malangsari dan Curahtakir
Sebelah Timur : Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten
Banyuwangi, PTPN XII Sumberjambe, Perkebunan PT.
Sukamade
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
21
-
22
Sebelah Barat : Desa Curahnongko, Andongrejo, Sanenrejo Kecamatan
Tempurejo, Kabupaten Jember PTPN XII Kalisanen, PTPN
XII Kota Blater, PT. Perhutani RPH Sabrang Terate dan
Perkebunan PT. Bandealit
C. Topografi
Taman Nasional ini terletak pada ketinggian antara 0-1200 m dpl.
Keadaan topografi TNMB pada umumnya bergelombang, berbukit, dan
bergunung-gunung. Kawasan di bagian selatan berbukit-bukit dan makin kearah
pantai keadaan semakin bergelombang. Ketinggian tempat berkisar antara 900
hingga 1.223 m dpl. Gunung yang terdapat di kawasan ini antara lain Gunung
Permisan (587 m), Gunung Meru (343 m), dan Gunung Betiri (1.233 m).
Semuanya terletak di sebelah barat.
Taman Nasional Meru Betiri berbatasan dengan beberapa tempat yaitu di
sebelah selatan dengan Gunung Sumbudadung (520 m), Gunung Sukamade (363
m), Gunung Rajegwesi (181 m), dan Gunung Benteng (222 m), di bagian timur
dengan Gunung Gendeng (9893 m) dan Gunung Lumberpacet (760 m). Daerah
dengan topografi yang agak landai antara lain disekitar Teluk Rajegwesi seluas
1.316 ha yang sudah merupakan tanah desa, di isekitar Teluk Sukamade seluas 22
ha dan di bagian timur seluas 50 ha.
Pada umumnya keadaan topografi disepanjang pantai berbukit-bukit
sampai bergunung-gunung dengan tebing yang curam. Hanya sebagian kecil
pantai datar yang berpasir, yaitu dari timur ke barat; Pantai Rajegwesi, Pantai
Sukamade, Pantai Permisan, Pantai Meru, dan Pantai Bandealit. Pantai-pantai ini
merupakan kawasan yang mempunyai nilai ilmiah dan pariwisata yang tinggi.
D. Iklim
Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, kawasan TNMB
bagian utara dan timur termasuk tipe iklim B, sedangkan bagian lainnya termasuk
-
tipe iklim C. Curah hujan rata-rata antara 2.300 sampai dengan 4.000 mm/tahun
dengan rata-rata bulan kering 4 bulan dan bulan basah 7 bulan.
Kawasan TNMB banyak dipengaruhi oleh banyaknya angin munson,
dimana bulan November sampai bulan Maret angin bertiup dari arah barat yang
mengakibatkan turun hujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April
sampai bulan Oktober.
E. Tanah dan Geologi
Secara umum keadaan tanah di TNMB merupakan gabungan dari jenis
alluvial, regosol coklat, dan sebagian besar merupakan komplek latosol. Keadaan
tanah ini sangat erat hubungannya dengan proses geologis daerah yang
bersangkutan, yaitu tanah dengan bahan induk yang berasal dari batuan alluvial
vulkanik. Tanah di bagian selatan merupakan campuran tanah mediteran kuning
yang kurang subur, sedangkan di bagian utara tanahnya subur karena
mengandung batuan vulkanik. Tanah alluvial umumnya terdapat di daerah lembab
dan tempat-tempat rendah sampai daerah pantai. Sedangkan regosol dan latosol
umumnya terdapat pada lereng dan puncak gunung.
F. Flora dan Fauna
Taman Nasional Meru Betiri memiliki 5 formasi ekosistem yaitu formasi
hutan hujan tropis, formasi hutan mangrove, formasi hutan pantai, formasi hutan
rawa dan formasi hutan bambu. Keadaan ini menyebabkan tingginya
keanekaragaman flora dalam kawasan. Data statistik Balai TNMB tahun 2005
menunjukkan sejumlah 386 jenis tumbuhan yang telah teridentifikasi.
Taman nasional ini merupakan habitat flora fauna dalam kawasan.
Beberapa tumbuhan langka yaitu bunga Rafflesia (Rafflesia zollingeriana), dan
beberapa jenis tumbuhan lainnya seperti bakau (Rhizophora sp.), api-api
(Avicennia sp.), waru (Hibiscus tiliaceus), nyamplung (Calophyllum inophyllum),
rengas (Gluta renghas), bendo (Artocarpus elasticus), dan beberapa jenis
tumbuhan obat.
23
-
Dari segi keaneragaman fauna TNMB memiliki 202 jenis fauna yang telah
teridentifikasi yang meliputi kelas mamalia sebanyak 25 jenis, aves 170 jenis dan
reptilia sebanyak 7 jenis. Selain itu, TNMB memiliki potensi satwa dilindungi
yang terdiri dari 29 jenis mamalia, dan 180 jenis burung. Satwa tersebut
diantaranya Banteng (Bos javanicus javanicus), Monyet ekor panjang (Macaca
fascicularis), Macan tutul (Panthera pardus melas), Ajag (Cuon alpinus
javanicus), Kucing hutan (Prionailurus bengalensis javanensis), Rusa (Cervus
timorensis russa), Bajing terbang ekor merah (Iomys horsfieldii), Merak (Pavo
muticus), Penyu belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu sisik (Eretmochelys
imbricata), Penyu hijau (Chelonia mydas), dan Penyu ridel/lekang (Lepidochelys
olivacea). Sedangkan Rusa (Cervus timorensis) merupakan satwa eksotik TNMB
(Riyanto, 2005).
Resort Rajegwesi termasuk daerah yang memiliki beberapa tipe habitat
yaitu habitat hutan pantai, hutan pegunungan dataran rendah dan lahan-lahan
rehabilitasi yang digunakan masyarakat untuk tanaman pertanian serta areal hutan
mangrove yang tidak terlalu luas. Jenis-jenis tumbuhannya yaitu jenis bambu,
jenis Rotan, Bendo (Artocarpus elasticus), Timo (Kleinhovia hospita),
Bungur/Ketangi (Lagerstomia speciosa), Nyamplung (Callophylum inophylum),
Ketapang (Terminalia catappa), Ubi Laut (Ipomea pes-caprae) dan jenis jenis
mangrove Nipah (Nypah fructicans) dan jenis Bruguiera (data primer PKLP IPB
2008).
G. Aksesibilitas
Aksesibilitas untuk menuju resort Rajegwesi ini dapat dicapai melalui
jalan darat dari Jember dan Banyuwangi yaitu :
1. Jalur Jember-Glenmore-Trebesalak-Sarongan-Sukamade (Kawasan TNMB
bagian Timur) sepanjang 103 km dapat ditempuh dalam waktu 4-5 jam
dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Pemandangan sepanjang
perjalananan cukup menarik terutama pemandangan alam.
24
-
2. Jalur Jember-Genteng-Jajag-Pesanggaran-Sarongan-Sukamade (Kawasan
TNMB bagian timur) sepanjang 109 km dapat ditempuh dengan waktu 3,5
jam dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.
3. Jalur Banyuwangi-Jajag-Pesanggaran-Sarongan-Sukamade (Kawasan TNMB
bagian Timur) sepanjang 109 km ditempuh dalam waktu 3,5 jam dengan
kendaraan bermotor.
H. Demografi Masyarakat Blok Rajegwesi
Pemukim di Blok Rajegwesi dimulai sejak tahun 1938 yang semula
berjumlah 10 KK (kepala keluarga) seluas 28,5 Ha (informasi masyarakat
Rajegwesi). Pemukim tersebut hingga bulan Agustus 2007 jumlahnya terus
bertambah, tercatat berjumlah 247 KK seluas 41,8 Ha (data terlampir). Blok
Rajegwesi termasuk dalam sebuah Dusun dengan nama Dusun Krajan yang terdiri
dari 1 Rukun Warga (RW) dan 3 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif
pemerintahan Blok Rajegwesi termasuk Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran,
Kabupaten Banyuwangi.
Sarana prasarana yang telah ada di Blok Rajegwesi antara lain jaringan
listrik PLN, sarana ibadah (Masjid) dan mushalla, sarana pendidikan (SDN 5
Sarongan), jalan kendaraan roda empat kelas III dengan pengerasan aspal dan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bangunan rumah yang dimiliki pemukim sebagian
besar permanen dan sebagian kecil non permanen bahkan terdapat beberapa
bangunan rumah yang juga dilengkapi dengan bangunan toko kelontong.
1. Karakteristik Mayarakat Blok Rajegwesi
a. Matapencaharian
Mayoritas mata pencaharian masyarakat Rajegwesi adalah sebagai
nelayan. Adapun aktivitas masyarakat Rajegwesi yang mayoritas sebagai
nelayan tradisional merupakan modal utama untuk dijadikan suatu atraksi
ekowisata yang dapat menarik wisatawan. Persentase struktur masyarakat
menurut matapemcaharian utama dapat dilihat pada Gambar 3.
25
-
Gambar 3. Struktur masyarakat menurut mata pencaharian utama (data primer)
b. Pendidikan
Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat Rajegwesi masih tergolong
rendah. Sebanyak 72% masyarakat Rajegwesi hanya tamatan dari sekolah dasar
(SD), sedangkan untuk pendidikan tertinggi hanya sampai pada tingkat sekolah
menengah atas (SMA) sebanyak 4%. Persentase struktur masyarakat menurut
tingakat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.
52%
14%
6%
2%16%
10% NelayanPetaniWiraswastaPurn PNSNelayan+taniBuruh
Gambar 4. Struktur masyarakat menurut tingkat pendidikan (data primer)
c. Agama
72%
24%
4%
SD
SMP
SMA
Mayoritas penduduk di kawasan Blok Rajegwesi memeluk agama Islam.
Sesuai data yang terdapat dalam data monografi Kampung Rajegwesi Tahun
2008, masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 577 jiwa, agama Budha
sebanyak 41 jiwa, dan agama Kristen sebanyak 30 jiwa.
d. Bahasa Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa jawa Banyuwangian (Osing)
dan kadang-kadang memakai bahasa madura. Hal ini dapat diperhatikan dari
dialek dan logat masyarakat dalam pembicaraan kehidupan sehari-hari. Kondisi
ini dikarenakan mayoritas penduduk berasal dari Banyuwangi dan sekitarnya.
e. Budaya Masyarakat Rajegwesi mempunyai adat istiadat petik laut pada awal tahun
hijriah. Mereka mengadakan semacam syukuran di tepi laut sebagai ungkapan
rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang mereka peroleh. Mereka
26
-
juga berharap dengan mengadakan syukuran tersebut, semoga dikemudian hari
tetap menghasilkan panen dan semoga tidak ada aral melintang dalam bernelayan.
2. Kelembagaan Masyarakat di Rajegwesi
Adanya kelembagaan masyarakat di Rajegwesi merupakan suatu wadah
bagi masyarakat untuk menyampaikan beberapa aspirasinya atau sebagai macam
bentuk eksistensi masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Macam-macam
kelembagaan masyarakat yang terdapat di Rajegwesi antara lain kelompok
jamaah tahlil yang dilakukan tiap malam jumat, kelompok kesebelasan sepak
bola, kelompok rukun nelayan, POKMASWAS (Kelompok Masyarakat
Pengawas) kemudian untuk keperluan penanganan wisata di Rajegwesi akan
segera dibentuk suatu lembaga dalam waktu dekat (data primer hasil wawancara
dengan Ketua RT 3 di Blok Rajegwesi). Lembaga masyarakat yang menangani
wisata di Rajegwesi tersebut dibentuk oleh masyarakat yang beranggotakan dan
diketuai oleh masyarakat Rajegwesi itu sendiri sedangkan pihak TNMB berperan
sebagai pembina dan penanggung jawab.
I. Zonasi TNMB
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa taman nasional adalah sebuah
kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi ini
dimaksudkan untuk mengefektifkan pengelolaan taman nasional sehingga dapat
berfungsi secara optimal. Pada Tanggal 13 Desember 1999 melalui Surat
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor:
185/Kpts/DJ-V/1999, ditentukan zonasi TNMB.
Zona inti seluas 27.915 Ha (warna merah) terletak di bagian timur dan
sebagian bagian barat kawasan TNMB; dimana pada zona ini mutlak dilindungi,
di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun TNMB oleh aktivitas
manusia. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini hanya yang berhubungan
dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.
27
-
Zona rimba seluas 22.622 Ha (warna kuning) terletak di bagian barat dan
sebagian kecil bagian selatan kawasan. Pada zona ini dapat dilakukan kegiatan
sebagaimana kegiatan pada zona inti dan kegiatan wisata alam yang terbatas.
Zona pemanfaatan intensif seluas 1.285 Ha (warna hijau) terletak di Pantai
Bandealit, Pantai Sukamade, dan Pantai Rajegwesi kawasan TNMB. Pada zona
ini dapat dilakukan kegiatan sebagaimana pada zona inti dan zona rimba, dan
diperuntukkan bagi pusat pembangunan sarana/prasarana dalam rangka
pengembangan kepariwisataan alam dan rekreasi.
Zona rehabilitasi seluas 4.023 Ha (warna coklat) terletak di bagian utara
dan sebagian kecil bagian timur kawasan TNMB, dimana pada zona ini dapat
dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan yang sudah rusak akibat perambahan.
Zona penyangga seluas 2.155 Ha (warna biru) terletak di areal bekas
perkebunan PT. Bandealit Kabupaten Jember dan PT. Sukamade Baru Kabupaten
Banyuwangi. Zona ini adalah zona yang dikelola secara khusus dimana
merupakan bagian dari sistem pengelolaan taman nasional, bertujuan untuk
mengakomodir kepentingan perlindungan dan pelestarian taman nasional, wisata
alam dan wisata agro. Peta zonasi TNMB, disajikan pada Gambar 5.
28
-
Gambar 5. Peta Zonasi di TNMB Sumber : Balai Taman Nasional Meru Betiri
29
-
J. Kebijakan dan Peraturan Perundangan
Kebijakan dan peraturan perundangan pengelolaan TNMB berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan secara lestari
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan
pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) dengan tetap menjaga kelestarian
kawasan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan
kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa liar.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Pengusahaan pariwisata alam
berupa usaha sarana pariwisata dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk meningkatkan gejala keunikan
dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional.
Jenis usaha pariwisata alam berupa usaha akomodasi, makanan dan minuman,
sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, sarana wisata budaya. Usaha
pariwisata dilaksanakan dengan persyaratan luas kawasan yang dimanfaatkan
untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% dari
luas zona pemanfaatan taman nasional, bentuk bangunan bergaya arsitektur
budaya setempat dan tidak merubah bentang alam yang ada
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 167/Kpts-II/1994 tentang Sarana
dan Prasarana Pengusahaan Perusahaan Pariwisata Alam di kawasan Pelestarian
Alam. Sarana dan prasarana pengusahaan pariwisata alam dapat dibangun di
zona pemanfaatan taman nasional dengan dibebani ijin pengusahaan pariwisata
alam. Areal ijin pengusahaan pariwisata alam yang dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10%.
30
-
31
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1991 tentang
Kehutanan. Asas dan tujuan penyenggaraan kehutanan yaitu asas manfaat dan
lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan
dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka
fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi
untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang
dan lestari, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan
kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat
secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat
perubahan eksternal dan menjamin distribusi dan manfaat yang berkeadilan dan
berkelanjutan.
-
IV. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juli Agustus (30 hari) 2008.
Berlokasi di Resort Rajegwesi SPTN I Sarongan TNMB, khususnya di Blok
Rajegwesi pada bulan Juli 2008. Penentuan blok Rajegwesi sebagai lokasi
penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan letaknya terhadap kawasan,
yaitu daerah yang berada di dalam kawasan TNMB. Peta lokasi penelitian
disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6. Peta Wilayah Kerja di TNMB
Sumber : Balai Taman Nasional Meru Betiri
32
-
33
B. Alat
Alat yang digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Macam-macam alat untuk penelitian
No. Nama Alat Kegunaan
1. Kamera Untuk dokumentasi 2 Tape recorder Alat bantu wawancara 3. Geographic Position System (GPS) Untuk mengambil titik-titik koordinat dalam
pembuatan peta 4. Arc View Program di komputer untuk mengolah data hasil
pengambilan titik-titik koordinat dari GPS
C. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, verifikasi dan
pengamatan langsung di lapangan, wawancara serta penyebaran kuesioner. Studi
literatur dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai lokasi
penelitian yaitu di Resort Rajegwesi yang kemudian diverifikasi di lapangan.
Setelah mengetahui potensi-potensi ekowisata yang terdapat di resort Rajegwesi
yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur maka
dilakukan verifikasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada lokasi-lokasi
obyek wisata alam di Resort Rajegwesi yang kemudian dilakukan pengambilan
titik-titik koordinat pada masing-masing potensi obyek ekowisata yang berada di
sekitar Resort Rajegwesi dengan menggunakan alat GPS. Jenis dan teknik
pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 3.
-
34
Tabel 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Tugas Akhir
Jenis Data Data Teknik Pengumpulan
Data
Sumber Data
Primer
1. Potensi sumberdaya ekowisata meliputi bentang alam (topografi), keanekaragaman hayati (keunikan/kekhasan flora dan fauna), adat istiadat/budaya
2. Karakteristik masyarakat Rajegwesi meliputi potensi sumber daya manusianya (mata pencaharian, tingkat pendidikan,dsb)
3. Persepsi, partisipasi, dan keinginan masyarakat Rajegwesi terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
4. Minat, persepsi dan motivasi pengunjung terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
Studi literatur, Observasi Lapang, kuesioner dan wawancara.
Balai TNMB, masyarakat, dan pengunjung
Sekunder 1. Kondisi umum kawasan 2. Perkembangan wisata di Rajegwesi
3. Peta kawasan
Studi literatur dan wawancara.
Balai TNMB dan pengelola
D. Metode penentuan responden
D.1. Masyarakat
Penentuan responden untuk masyarakat dilakukan dengan menggunakan
dengan metode Snowball sampling dan sosiometri. Metode Snowball sampling
adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap
informan pangkal sampai dengan informan kunci. Wawancara akan dihentikan
ketika data yang terkumpul sudah mencapai titik jenuh, yaitu jawaban yang
diperolah menunjukkan kesamaan atau tidak ada informasi yang baru (Susiyanto,
2006). Sedangkan metode sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh
data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok, yang berukuran kecil sampai
sedang (10 - 50 orang), berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota
kelompok (WS. Winkel, 1985).
-
35
Metode snowball sampling dan sosiometri digunakan untuk mendapatkan
data tentang sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di desa tersebut.
Pengambilan datanya menggunakan panduan wawancara. Data tentang persepsi,
motivasi, partisipasi dan minat masyarakat diambil dengan menggunakan
kuesioner. Jumlah responden ditentukan berdasarkan heterogenitas dari populasi
Resort Rajegwesi itu sendiri yang dipilih secara acak berurutan dari data
penduduk baik wanita maupun pria. Jadi kita mengambil responden yang
sebelumnya sudah kita acak secara berurutan dari data penduduk yang tercatat di
kantor balai desa.
Wawancara menggunakan metode snowball dan sosiometri didapatkan
hasil 12 responden yang dianggap sebagai tokoh yang dituakan dan yang
mengetahui seluk beluk tentang sumber daya alam, cerita sejarah dan peninggalan
bersejarah di Rajegwesi. Mereka itu diantaranya adalah staf dan pegawai kantor
Balai Desa Sarongan, kepala Desa Sarongan, ketua dan anggota BPD, masing-
masing ketua RT di Rajegwesi, juragan ikan, dan sesepuh di Rajegwesi.
Penyebaran kuesioner untuk memperoleh data tentang partisipasi, persepsi,
motivasi, dan minat masyarakat didapatkan 50 responden yang tersebar di 3 (tiga)
RT di Rajegwesi.
D.2. Pengunjung
Pengambilan data tentang motivasi, persepsi dan minat pengunjung
menggunakan kuisioner. Penentuan responden terlebih dahulu ditentukan secara
stratifikasi, responden dikelompokkan menjadi tiga yaitu perorangan (1-2 orang),
grup kecil (3-10 orang), dan grup besar (lebih dari 10 orang). Pengelompokan ini
dimaksudkan agar memudahkan dalam pengambilan data tentang bentuk wisata
perorangan/tunggal ataukah kelompok. Kemudian di lapangan, penentuan
responden secara stratifikasi tersebut dilakukan secara accidental artinya
responden yang diperoleh secara kebetulan dikarenakan jumlah pengunjung tiap
hari tidak diketahui secara pasti. Penyebaran kuesioner untuk pengunjung
didapatkan 35 responden wisatawan asing dan 32 responden wisatawan domestik.
-
36
E. Analisis Data
Data yang didapat dari hasil wawancara, verifikasi, pengamatan lapang,
studi pustaka dan penyebaran kuesioner diolah dengan cara tabulasi data dan
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data titik-titik
koordinat pada lokasi obyek wisata alam di Rajegwesi diolah menggunakan
program Arc View di komputer, yang selanjutnya menghasilkan suatu peta
penyebaran potensi sumberdaya wisata alam di Resort Rajegwesi.
Hasil analisis deskriptif lalu dianalisis lebih dalam dengan pendekatan
SWOT (strength, weakness, opportunity, and threat) yang digunakan untuk
menyusun perencanaan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di
Rajegwesi. Analisis SWOT dimaksudkan untuk mengetahui gambaran mengenai
kekuatan dan kelemahan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Blok
Rajegwesi serta peluang dan ancaman yang dihadapi.
Sebelum dibuat matrik SWOT terlebih dahulu ditentukan faktor strategi
eksternal (EFAS) dan faktor strategi internal (IFAS) yang ditentukan dengan cara-
cara sebagai berikut (Rangkuti, 2006)
1. Menyusun 5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman serta kekuatan dan
kelemahan dalam kolom 1.
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot mulai dari 1,0 (sangat
penting) sampai dengan 0,00 (tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor-
faktor tersebut terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyara