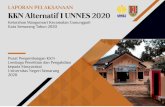Cover Laporan
-
Upload
vera-irawanda -
Category
Documents
-
view
39 -
download
1
Transcript of Cover Laporan

1. Tes Widal
Suatu jenis pemeriksaan serologi. Uji widal dilakukan untuk deteksi antibodi terhadap
kuman S.Thyphi. Pada uji Widal terjadi suatu reaksi aglutinasi antara antigen kuman
S.Thyphi dengan antibodi yang disebut aglutinin. Antigen yang digunakan pada uji
Widal adalah suspensi Salmonella yang sudah dimatikan dan diolah di laboratorium.
Maksud uji Widal adalah untuk menentukan adanya aglutinin dalam serum penderita
tersangka demam tifoid yaitu :
1. Aglutinin O (dari tubuh kuman)
2. Aglutinin H (flagela kuman)
3. Aglutinin Vi (Simpai kuman)
Dari ketiga aglutinin tersebut hanya aglutinin O dan H yang digunakan untuk
diagnosis demam tifoid. Semakin tinggi titernya semakin besar kemungkinan
terinfeksi kuman ini.
Titer widal biasanya angka kelipatan : 1/32 , 1/64 , 1/160 , 1/320 , 1/640.
Peningkatan titer uji Widal 4 x (selama 2-3 minggu) : dinyatakan (+).
Titer 1/160 : masih dilihat dulu dalam 1 minggu kedepan, apakah ada kenaikan
titer. Jika ada, maka dinyatakan (+).
Jika 1 x pemeriksaan langsung 1/320 atau 1/640, langsung dinyatakan (+) pada
pasiendengan gejala klinis khas.
2. Pemeriksaan Feses
Pemeriksaaan Makroskopik
Pemeriksaan makroskopik tinja meliputi pemeriksaan jumlah, warna, bau, darah,
lendir dan parasit (Gandasoebrata R, 1970).
a. Jumlah
Dalam keadaan normal jumlah tinja berkisar antara 100-250gram per hari.
Banyaknya tinja dipengaruhi jenis makanan bila banyak makan sayur jumlah tinja
meningkat (Hepler OE, 1956).
b. Konsistensi
Tinja normal mempunyai konsistensi agak lunak dan bebentuk. Pada diare
konsistensi menjadi sangat lunak atau cair, sedangkan sebaliknya tinja yang keras
1

atau skibala didapatkan pada konstipasi. Peragian karbohidrat dalam usus
menghasilkan tinja yang lunak dan bercampur gas (Hepler OE, 1956).
c. Warna
Tinja normal kuning coklat dan warna ini dapat berubah mejadi lebih tua dengan
terbentuknya urobilin lebih banyak. Selain urobilin warna tinja dipengaruhi oleh
berbagai jenis makanan, kelainan dalam saluran pencernaan dan obat yang
dimakan. Warna kuning dapat disebabkan karena susu,jagung, lemak dan obat
santonin. Tinja yang berwarna hijau dapat disebabkan oleh sayuran yang
mengandung khlorofil atau pada bayi yang baru lahir disebabkan oleh biliverdin
dan porphyrin dalam mekonium. Kelabu mungkin disebabkan karena tidak ada
urobilinogen dalam saluran pencernaan yang didapat pada ikterus obstruktif, tinja
tersebut disebut akholis. Keadaan tersebut mungkin didapat pada defisiensi enzim
pankreas seperti pada steatorrhoe yang menyebabkan makanan mengandung
banyak lemak yang tidak dapat dicerna dan juga setelah pemberian garam barium
setelah pemeriksaan radiologik. Tinja yang berwarna merah muda dapat
disebabkan oleh perdarahan yang segar dibagian distal, mungkin pula oleh
makanan seperti bit atau tomat. Warna coklat mungkin disebabkan adanya
perdarahan dibagian proksimal saluran pencernaan atau karena makanan seperti
coklat, kopi dan lain-lain. Warna coklat tua disebabkan urobilin yang berlebihan
seperti pada anemia hemolitik. Sedangkan warna hitam dapat disebabkan obat
yang yang mengandung besi, arang atau bismuth dan mungkin juga oleh melena
(Hepler OE, 1956).
d. Bau
Indol, skatol dan asam butirat menyebabkan bau normal pada tinja. Bau busuk
didapatkan jika dalam usus terjadi pembusukan protein yang tidak dicerna dan
dirombak oleh kuman. Reaksi tinja menjadi lindi oleh pembusukan semacam itu.
Tinja yang berbau tengik atau asam disebabkan oleh peragian gula yang tidak
dicerna seperti pada diare. Reaksi tinja pada keadaan itu menjadi asam (Hepler
OE, 1956).
e. Darah
Adanya darah dalam tinja dapat berwarna merah muda,coklat atau hitam. Darah
itu mungkin terdapat di bagian lua rtinja atau bercampur baur dengan tinja. Pada
perdarahan proksimal saluran pencernaan darah akan bercampur dengan tinja dan
2

warna menjadi hitam, ini disebut melena seperti pada tukak lambung atau varices
dalam oesophagus. Sedangkan pada perdarahan di bagian distal saluran
pencernaan darahterdapat di bagian luar tinja yang berwarna merah muda yang
dijumpai pada hemoroid atau karsinoma rektum (Hepler OE, 1956).
f. Lendir
Dalam keadaan normal didapatkan sedikit sekali lendir dalam tinja. Terdapatnya
lendir yang banyak berarti ada rangsangan atau radang pada dinding usus. Kalau
lendir itu hanya didapat di bagian luar tinja, lokalisasi iritasi itu mungkin terletak
pada usus besar. Sedangkan bila lendir bercampur baur dengan tinja mungkin
sekali iritasi terjadi pada usus halus. Pada disentri, intususepsi dan ileokolitis bisa
didapatkan lendir saja tanpa tinja (Hepler OE, 1956).
g. Parasit
Diperiksa pula adanya cacing ascaris, anylostoma dan lain-lain yang mungkin
didapatkan dalam tinja (Hepler OE, 1956).
Pemeriksaan Mikroskopis
Pemeriksaan mikroskopik meliputi pemeriksaan protozoa, telur cacing, leukosit,
eritosit, sel epitel, kristal dan sisa makanan. Dari semua pemeriksaan ini yang terpenting
adalah pemeriksaan terhadap protozoa dan telur cacing (Hyde TA, Mellor LD, Raphael
SS, 1976).
a. Protozoa
Biasanya didapati dalam bentuk kista, bila konsistensi tinja cair baru didapatkan
bentuk trofozoit (Hematest, Leaflet, 1956).
b. Telur cacing
Telur cacing yang mungkin didapat yaitu Ascaris lumbricoides, Necator americanus,
Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis dan sebagainya
(Hematest, Leaflet, 1956).
c. Leukosit
Dalam keadaan normal dapat terlihat beberapa leukosit dalam seluruh sediaan. Pada
disentri basiler, kolitis ulserosa dan peradangan didapatkan peningkatan jumlah
leukosit. Eosinofil mungkin ditemukan pada bagian tinja yang berlendir pada
penderita dengan alergi saluran pencenaan (Hematest, Leaflet, 1956).
3

d. Eritrosit
Eritrosi thanya terlihat bila terdapat lesi dalam kolon, rektum atau anus. Sedangkan
bila lokalisasi lebih proksimal eritrosit telah hancur. Adanya eritrosit dalam tinja
selalu berarti abnormal (Hematest, Leaflet, 1956).
e. Epitel
Dalam keadaan normal dapat ditemukan beberapa sel epite lyaitu yang berasal dari
dinding usus bagian distal. Sel epitelyang berasal dari bagian proksimal jarang
terlihat karena sel inibiasanya telah rusak. Jumlah sel epitel bertambah banyak kalau
ada perangsangan atau peradangan dinding usus bagian distal (Hematest, Leaflet,
1956).
f. Kristal
Kristal dalam tinja tidak banyak artinya. Dalam tinja normal mungkin terlihat kristal
tripel fosfat, kalsium oksalat dan asam lemak. Kristal tripel fosfat dan kalsium
oksalat didapatkan setelah memakan bayam atau strawberi, sedangkan kristal asam
lemak didapatkan setelah banyak makan lemak. Sebagai kelainan mungkin dijumpai
kristal Charcoat Leyden Tinja LUGOL Butir-butir amilum dan kristal hematoidin.
Kristal Charcoat Leyden didapat pada ulkus saluran pencernaan seperti yang
disebabkan amubiasis. Pada perdarahan saluran pencernaan mungkin didapatkan
kristal hematoidin (Hematest, Leaflet, 1956).
g. Sisa makanan
Hampir selalu dapat ditemukan juga pada keadaan normal, tetapi dalam keadaan
tertentu jumlahnya meningkat dan hal ini dihubungkan dengan keadaan abnormal.
Sisa makanan sebagian berasal dari makanan daun-daunan dan sebagian lagi berasal
dari hewan seperti serat otot, serat elastisdan lain-lain. Untuk identifikasi lebih lanjut
emulsi tinja dicampur dengan larutan lugol untuk menunjukkan adanya amilum yang
tidak sempurna dicerna. Larutan jenuh Sudan IIIatau IV dipakai untuk menunjukkan
adanya lemak netral seperti pada steatorrhoe. Sisa makanan ini akan meningkat
jumlahnya pada sindroma malabsorpsi. (Hematest, Leaflet, 1956).
4

3. Pembentukan bilirubin
Eritrosit secara fisiologis dapat bertahan/ berumur sekitar 120 hari, Sel-sel eritrosit tua
dikeluarkan dari sirkulasi dan dihancurkan oleh limpa. Proses penghancuran eritrosit
yang terjadi karena proses penuaan disebut proses senescence, sedangkan destruksi
patologik disebut hemolisis. Hemolisis dapat terjadi intravaskular dapat juga
ekstravaskuler, terutama dalam sistem RES, yaitu limfa dan hati.
Hemolisis eritrosit akan menyebabkan terurainya komponen-komponen hemoglobin
menjadi berikut :
1. Komponen protein yaitu globin yang akan dikembalikan ke pool protein dan dapat
dipakai kembali
2. Komponen heme akan pecah menjadi dua, yaitu :
a. Besi : yang akan dikambalikan ke pool besi dan dipakai ulang
b. Bilirubin : yang akan di sekresikan melalui hati dan empedu.
Di dalam limpa, sel darah merah yang tidak dipakai lagi terus menerus
dipecahkan menjadi pigmen berwarna kuning kehijauan yaitu bilirubin.
Bilirubin ini larut dalam lemak, tidak dalam air dan dapat masuk kedalam sel.
Dalam sel akan bersifat toksik. Bilirubin diangkut oleh vena lienalis kedalam
hati. Karena bilirubin bersifat sangat toksik terhadap sel-sel otak dan sel-sel
tubuh lainnya, makapengangkutan berlangsung dalam bentuk ikatan yang kuat
dengan albumin. Didalam hati bilirubin dilepaskan oleh hepatosit dari ikatan
albumin dan disalam sel hati dirobah menjadi bentuk yang tidak toksik
sehingga dapat di eksresi kedalam empedu. Didalam kolon bilirubin ini dirobah
lagi menjadi pigmen cokelat oleh bakteri usus yang menyebabkan tinja
berwarna cokelat. Pigmen ini tidak lagi merupakan bilirubin dan disebut
sterkobilin yang hampir identik dengan urobilin.
5

4. Pemeriksaan laboratorium fungsi hati
SGOT dan SGPT secara rutin diperiksa sebagai salah satu pemeriksaan untuk
mengetahui keadaan hati.
Fungsi hati adalah mengolah serta menyimpan bahan makanan. Karbohidrat yang
di absorbsi sebagai glukosa disimpan dalam hati sebagai glikogen. Glukosa dilepaskan
sesuai dengan kebutuhan. Protein yang diabsorbsi sebagai asam amino, tidak dapat
disimpan dalam hati. Setelah memakan protein, hampir semua asam amino mengalami
proses deaminasi dalam hati. Golongan asam amino dirubah dalam ureum yang di
eksresi melalui ginjal, rantai karbon yang tersisa mengalami oksidasi menjadi CO2 dan
air. Sebagian dari asam amino akan memasuki sirkulasi sistemik, tetapi perlu disadari
bahwa jumlahnya sangat kecil. Kadar asam amino yang tinggi dalam peredaran darah
6
Eritrosit hemolisis atau proses penuaan
Hemoglobin
Globin Protoporfirin
Asam amino
Pool protein
Disimpan/ digunakan lagi
Fe
Pool besi
Disimpan/ digunakan lagi
CO Bilirubin indirek
Bilirubin direk
HATI
Urine Urobilinogen
FesesSterkobilinogen
EMPEDU

dapat menjadi racun yang merusak fungsi otak. Asam amino yang berjumlah 22 macam
dipergunakan di dalam tubuh sebagai bahan-bahan dasar untuk membangun protein.
Beberapa macam dari ke 22 asam amino ini tidak dapat dibuat dalam tubuh
sehingga harus diperoleh dari makanan, yang disebut asam amino essensial. Asam
amino lainnya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain dengan bantuan enzim-
enzim khusus dalam sel-sel tubuh, terutama dalam sel hati. Enzim-enzim ini disebut
transaminase. Dua dari enzim ini yakni SGOT dan SGPT secara rutin dapat diperiksa.
5.Penatalaksanaan pada demam Tifoid
Tujuan penatalaksanaan:
1. Mengatasi gejala
2. Membasmi infeksi salmonella
3. Mencegah komplikasi yang mungkin timbul
4. Mencegah relaps
Prosedur penatalaksanaan
1. Rawat umum
a. Tirah baring selama demam masih ada
b. Diet ( boleh makan padat, namun rendah serat)
c. Demam sebaiknya cukup dengan kompres dingin saja
d. Jika pasien tampak toksik ,diberi hirokotison dosis 100 mg IV/ 8 jam
e. Dilakukan upaya mencegah dekubitus
2. Obat pilihan
a. Kloramfenikol 50-100 mg/KgBB selama ± 2 minggu. Kontrol jumlah
lekosit selama 5-7 hari.
b. Amoksisilin 2 dd 2000 mg atau Ampisillin 4 x sehari 1-2 gram (14 hari)
c. Kortimoksasol 2 x 2 tab ( 10-14 hari)
d. Fluoroquinolone generasi III 300mg-1 gr/hari (5-7 hari): Ciprofloxacin 2
x500 mg, prefloxacin1x 400 mg
e. Ceftriakson 20 mg/Kg/BB?hari (3-7hari)
f. Pada sepsis/DIC dapat ditambahkan Deksametason 3 mg/KgBB dosis
dalam 30 menit diikuti 1 mg/KgBB per 6 jam selama 24-48 jam
7

g. Jika sampai perforasi usus mungkin perlu pembedahaan.
Managemen Nutrisi
Penderita penyakit demam Tifoid selama menjalani perawatan haruslah
mengikuti petunjuk diet yang dianjurkan oleh dokter untuk di konsumsi, antara lain :
a. Makanan yang cukup cairan, kalori, vitamin & protein.
b. Tidak mengandung banyak serat.
c. Tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas.
d. Makanan lunak diberikan selama istirahat.
Makanan dengan rendah serat dan rendah sisa bertujuan untuk memberikan
makanan sesuai kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa sehingga
dapat membatasi volume feses, dan tidak merangsang saluran cerna. Pemberian bubur
saring, juga ditujukan untuk menghindari terjadinya komplikasi perdarahan saluran
cerna atau perforasi usus. Syarat-syarat diet sisa rendah adalah :
Energi cukup sesuai dengan umur, jenis kelamin dan aktivitas
Protein cukup, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total
Lemak sedang, yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total
Karbohidrat cukup, yaitu sisa kebutuhan energi total
Menghindari makanan berserat tinggi dan sedang sehingga asupan serat
maksimal 8 gr/hari. Pembatasan ini disesuaikan dengan toleransi perorangan
Menghindari susu, produk susu, daging berserat kasar (liat) sesuai dengan
toleransi perorangan.
Menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asam dan
berbumbu tajam.
Makanan dimasak hingga lunak dan dihidangkan pada suhu tidak terlalu panas
dan dingin
Makanan sering diberikan dalam porsi kecil
Bila diberikan untuk jangka waktu lama atau dalam keadaan khusus, diet perlu
disertai suplemen vitamin dan mineral, makanan formula, atau makanan
parenteral.
8

Diet sisa rendah terbagi dua , yaitu:
a. diet sisa rendah I
Diet sisa rendah I adalah makanan yang diberikan dalam bentuk disaring atau
diblender. Makanan ini menghindari makanan berserat tinggi dan sedang, bumbu
yang tajam, susu, daging berserat kasar (liat), dan membatasi penggunaan gula dan
lemak. Kandungan serat maksimal 4 gram. Diet ini rendah energi dan sebagian zat
gizi.
Tabel 1. Bahan Makanan yang Dianjurkan dan tidak Dianjurkan pada diet sisa rendah 1
Bahan makanan Dianjurkan Tidak Dianjurkan
Sumber karbohidrat Bubur saring, roti bakar,
kentang dipure, makaroni,
bihun rebus, biskuit,
krakers, tepung-tepungan
dipuding atau dibubur
Beras tumbuk, beras ketan,
roti whole wheat, jagung,
ubi, singkong, talas, cake,
tarcis, dodol, tepung-
tepungan yang dibuat kue
manis.
Sumber protein hewani Daging empuk, hati, ayam,
ikan giling halus, telur
direbus, ditim, diceplok air
atau sebagai campuran
dalam makanan dan
minuman
Daging berserat kasar,
ayam, dan ikan yang
diawet, di goreng kering,
telur diceplok, udang dan
kerang, susu dan produk
susu.
Sumber protein nabati Tahu ditim dan direbus,
susu kedelai
Kacang-kacangan seperti
kacang tanah, kacang
merah, kacang tolo, kacang
hijau, kacang kedelai,
tempe dan oncom.
Sayuran Sari sayuran Sayuran dalam keadaan
utuh
Buah-buahan Sari buah Buah dalam keadaan utuh
Minuman Teh, sirup, kopi encer Teh dan kopi kental,
9

minuman beralkohol dan
mengandung soda
Bumbu Garam, vetsin, gula Bawang, cabe, jahe, merica,
ketumbar, cuka dan bumbu
lain yang tajam
b. diet sisa rendah II
Diet sisa rendah II merupakan makanan peralihan dari diet sisa rendah I ke
Makanan biasa. Diet ini diberikan bila penyakit mulai membaik atau bila penyakit
bersifat kronis. Makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak. Makanan
berserat sedang diperbolehkan dalam jumlah terbatas, sedangkan makanan berserat
tinggi tidak diperebolehkan. Susu diberikan maksimal 2 gelas sehari. Lemak dan gula
diberikan dalam bentuk mudah cerna. Bumbu kecuali cabe, merica dan cuka, boleh
diberikan dalam jumlah terbatas. Kandungan serat diet ini adalah 4-8 gram.
Tabel 2. Bahan Makanan yang Dianjurkan dan tidak Dianjurkan pada diet sisa rendah II
Bahan makanan Dianjurkan Tidak Dianjurkan
Sumber karbohidrat Beras dibubur/ditim, roti
bakar, kentang rebus,
krakers, tepung-tepungan di
bubur atau dipuding
Beras tumbuk, beras ketan,
roti whole wheat, jagung,
ubi, singkong, talas, cake,
tarcis, dodol, tepung-
tepungan yang dibuat kue
manis.
Sumber protein hewani Daging empuk, hati, ayam,
ikan direbus, ditumis,
dikukus, diungkep dan di
panggang, telur direbus,
ditim, diceplok air atau
sebagai campuran dalam
makanan dan minuman,
susu maksimal 2 gelas
Daging berserat kasar,
ayam, dan ikan yang
diawet, telur diceplok dan
dadar, daging babi.
10

perhari.
Sumber protein nabati Tahu ditim direbus, ditumis,
pindakan, susu kedelai
Kacang-kacangan seperti
kacang tanah, kacang
merah, kacang tolo, kacang
hijau, kacang kedelai,
tempe dan oncom.
Sayuran Sayuran yang berserat
rendah dan sedang, seperti
kacang panjang, buncis
muda, bayam, labu siam,
tomat masak, wortel
direbus, dikukus dan
ditumis.
Sayuran yang berserat
tinggi seperti daun
singkong, daun katuk, daun
pepaya, daun dan buah
melinjo, oyong, pare serta
semua sayur yang dimakan
mentah
Buah-buahan Sari buah; buah segar yang
matang (tanpa kulit dan biji)
dan tidak banyak
menimbulkan gas seperti
pepaya, pisang, jeruk,
avokad, nenas
Buah yang dimakan dengan
kulit, seperti apel, jambu
biji, dan pir serta jeruk yang
dimakan dengan kulit ari;
buah yang menimbulkan
gas seperti durian dan
nangka.
Lemak Margaris, mentega dan
minyak dalam jumlah
terbatas untuk menumis,
mengoles dan setup
Minyak untuk menggoreng,
lemak hewani, kelapa dan
santan
Minuman Teh, kopi encer, sirup Teh dan kopi kental,
minuman beralkohol dan
mengandung soda
Bumbu Garam, vetsin, gula, cuka,
salam, laos, kunyit, kunci
cabe, merica
11

dalam jumlah terbatas.
Untuk kembali ke makanan "normal", lakukan secara bertahap bersamaan dengan
mobilisasi. Misalnya hari pertama dan kedua makanan lunak, hari ke-3 makanan biasa, dan
seterusnya.
6. Indikasi rawat inap pada pasien demam tifoid adalah:
Apabila demam tidak turun
Kondisi tidak membaik lebih dari 2 minggu
Apa bila demam tifoid berat atau terjadi komplikasi seperti toxic tphoid,sepsis
peritonitis atau perforasi
Sudah diberi obat selama 3 hari tidak ada perbaikan
7. Penyakit dengan demam lebih dari 2 minggu
1. Demam Tifoid
Demam tifoid disebut juga dengan Typus abdominalis atau typoid fever. Demam
tipoid ialah penyakit infeksi akut yang biasanya terdapat pada saluran pencernaan
(usus halus) dengan gejala demam satu minggu atau lebih disertai gangguan pada
saluran pencernaan dan dengan atau tanpa gangguan kesadaran.Masa Inkubasinya 10-
14 hari. Pada kasus-kasus yang khas, demam berlangsung 3 minggu. Bersifat febris
remiten dan suhu tidak berapa tinggi. Selama minggu pertama, suhu tubuh
berangsurangsur meningkat setiap hari, biasanya menurun pada pagi hari dan
meningkat lagi pada sore dan malam hari. Dalam minggu kedua, penderita terus
berada dalam keadaan demam. Dalam minggu ketiga suhu tubuh beraangsur-angsur
turun dan normal kembali pada akhir minggu ketiga.
2. Malaria
Masa inkubasi malaria biasanya berlangsung 8-37 hari tergantung spesies parasit
(terpendek untuk Plasmodium Falciparum dan terpanjang Plasmodium Malariae).
12

8. Efek samping obat demam tifoid
1. Kloramfenikol
Berikatan dengan %0s bacterial-ribosomal subunit dan menghambat sintesis protein
bakteri (bakteriostatik).
Efek samping : Mual, muntah, mencret, mulut kering, stomatitis, pruritus ani,
penghambatan eritropoiesis, Gray syndrom pada bayi baru lahir, anemia hemolitik,
exantema, urticaria, demam, gatal-gatal, anafilaksis, dan terkadang syndrom Stevens-
Jonson,
Kontraindikasi : Hipersensitivitas terhadap kloramfenikol
2. Tiamfenikol
Dosis dan keaktifan hampir sama dengan kloramfenikol, akan tetapi komplikasi
hematologi seperti kemungkinan terjadi anemia aplastik lebih rendah dibandingkan
dengan kloramfenikol.
Efek Samping : Mual, muntah, diare, depresisumsum tulang yang bersifat reversibel,
neuritis optis dan perifer, serta dapat menyebabkan Gray baby syndrom.
3. Kotrimoksazol
Menghambat sintesis dihydrofolic acid bakteri (bakteriostatik)
Efek samping : Thromboplebitis, mual, muntah, sakit perut, mencret, ulserasi
esofagus, leukopenia, trombopenia, anemia megaloblastik, peninggian kreatinin
serum, eksantema, urtikaria, gatal, demam.
9. Pemeriksaan Laboratorium penunjang
Pemeriksaan laboratorium untuk membantu menegakkan diagnosis demam
tifoid dibagi dalam empat kelompok, yaitu : (1) pemeriksaan darah tepi; (2)
pemeriksaan bakteriologis dengan isolasi dan biakan kuman; (3) uji serologis; dan
(4) pemeriksaan kuman secara molekuler.
1. Pemeriksaan darah tepi
13

Pada penderita demam tifoid bisa didapatkan anemia, jumlah leukosit
normal, bisa menurun atau meningkat, mungkin didapatkan trombositopenia dan
hitung jenis biasanya normal atau sedikit bergeser ke kiri, mungkin didapatkan
aneosinofilia dan limfositosis relatif, terutama pada fase lanjut. Penelitian oleh
beberapa ilmuwan mendapatkan bahwa hitung jumlah dan jenis leukosit serta
laju endap darah tidak mempunyai nilai sensitivitas, spesifisitas dan nilai ramal
yang cukup tinggi untuk dipakai dalam membedakan antara penderita demam
tifoid atau bukan, akan tetapi adanya leukopenia dan limfositosis relatif menjadi
dugaan kuat diagnosis demam tifoid.
a. Identifikasi kuman melalui isolasi/biakan
Diagnosis pasti demam tifoid dapat ditegakkan bila ditemukan bakteriS.
typhi dalam biakan dari darah, urine, feses, sumsum tulang, cairan duodenum
atau dari rose spots. Berkaitan dengan patogenesis penyakit, maka bakteri akan
lebih mudah ditemukan dalam darah dan sumsum tulang pada awal penyakit,
sedangkan pada stadium berikutnya di dalam urine dan feses.
Hasil biakan yang positif memastikan demam tifoid akan tetapi hasil
negatif tidak menyingkirkan demam tifoid, karena hasilnya tergantung pada
beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil biakan meliputi (1)
jumlah darah yang diambil; (2) perbandingan volume darah dari media empedu;
dan (3) waktu pengambilan darah.
Volume 10-15 mL dianjurkan untuk anak besar, sedangkan pada anak
kecil dibutuhkan 2-4 mL. Sedangkan volume sumsum tulang yang dibutuhkan
untuk kultur hanya sekitar 0.5-1 mL. Bakteri dalam sumsum tulang ini juga lebih
sedikit dipengaruhi oleh antibiotika daripada bakteri dalam darah. Hal ini dapat
menjelaskan teori bahwa kultur sumsum tulang lebih tinggi hasil positifnya bila
dibandingkan dengan darah walaupun dengan volume sampel yang lebih sedikit
dan sudah mendapatkan terapi antibiotika sebelumnya. Media pembiakan yang
direkomendasikan untuk S.typhi adalah media empedu (gall) dari sapi dimana
dikatakan media Gall ini dapat meningkatkan positivitas hasil karena hanya S.
typhi dan S. paratyphi yang dapat tumbuh pada media tersebut.
Biakan darah terhadap Salmonella juga tergantung dari saat pengambilan
pada perjalanan penyakit. Beberapa peneliti melaporkan biakan darah positif
14

40-80% atau 70-90% dari penderita pada minggu pertama sakit dan positif 10-
50% pada akhir minggu ketiga. Sensitivitasnya akan menurun pada sampel
penderita yang telah mendapatkan antibiotika dan meningkat sesuai dengan
volume darah dan rasio darah dengan media kultur yang dipakai. Bakteri dalam
feses ditemukan meningkat dari minggu pertama (10-15%) hingga minggu ketiga
(75%) dan turun secara perlahan. Biakan urine positif setelah minggu pertama.
Biakan sumsum tulang merupakan metode baku emas karena mempunyai
sensitivitas paling tinggi dengan hasil positif didapat pada 80-95% kasus dan
sering tetap positif selama perjalanan penyakit dan menghilang pada fase
penyembuhan. Metode ini terutama bermanfaat untuk penderita yang sudah
pernah mendapatkan terapi atau dengan kultur darah negatif sebelumnya.
Prosedur terakhir ini sangat invasif sehingga tidak dipakai dalam praktek sehari-
hari. Pada keadaan tertentu dapat dilakukan kultur pada spesimen empedu yang
diambil dari duodenum dan memberikan hasil yang cukup baik akan tetapi tidak
digunakan secara luas karena adanya risiko aspirasi terutama pada anak. Salah
satu penelitian pada anak menunjukkan bahwa sensitivitas kombinasi kultur darah
dan duodenum hampir sama dengan kultur sumsum tulang.
Kegagalan dalam isolasi/biakan dapat disebabkan oleh keterbatasan
media yang digunakan, adanya penggunaan antibiotika, jumlah bakteri yang
sangat minimal dalam darah, volume spesimen yang tidak mencukupi, dan
waktu pengambilan spesimen yang tidak tepat.
Walaupun spesifisitasnya tinggi, pemeriksaan kultur mempunyai
sensitivitas yang rendah dan adanya kendala berupa lamanya waktu yang
dibutuhkan (5-7 hari) serta peralatan yang lebih canggih untuk identifikasi bakteri
sehingga tidak praktis dan tidak tepat untuk dipakai sebagai metode diagnosis
baku dalam pelayanan penderita.
b. Identifikasi kuman melalui uji serologis
Uji serologis digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis demam
tifoid dengan mendeteksi antibodi spesifik terhadap komponen antigen S.
typhimaupun mendeteksi antigen itu sendiri. Volume darah yang diperlukan
untuk uji serologis ini adalah 1-3 mL yang diinokulasikan ke dalam tabung tanpa
antikoagulan. Beberapa uji serologis yang dapat digunakan pada demam tifoid ini
15

meliputi : (1) uji Widal; (2) tes TUBEX®; (3) metode enzyme immunoassay(EIA);
(4) metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA); dan (5) pemeriksaan
dipstik.
Metode pemeriksaan serologis imunologis ini dikatakan mempunyai nilai
penting dalam proses diagnostik demam tifoid. Akan tetapi masih didapatkan
adanya variasi yang luas dalam sensitivitas dan spesifisitas pada deteksi antigen
spesifik S. typhi oleh karena tergantung pada jenis antigen, jenis spesimen yang
diperiksa, teknik yang dipakai untuk melacak antigen tersebut, jenis antibodi yang
digunakan dalam uji (poliklonal atau monoklonal) dan waktu pengambilan
spesimen (stadium dini atau lanjut dalam perjalanan penyakit).
3.1 UJI WIDAL
Uji Widal merupakan suatu metode serologi baku dan rutin digunakan
sejak tahun 1896. Prinsip uji Widal adalah memeriksa reaksi antara antibodi
aglutinin dalam serum penderita yang telah mengalami pengenceran berbeda-
beda terhadap antigen somatik (O) dan flagela (H) yang ditambahkan dalam
jumlah yang sama sehingga terjadi aglutinasi. Pengenceran tertinggi yang masih
menimbulkan aglutinasi menunjukkan titer antibodi dalam serum.
Teknik aglutinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji hapusan
(slide test) atau uji tabung (tube test). Uji hapusan dapat dilakukan secara cepat
dan digunakan dalam prosedur penapisan sedangkan uji tabung membutuhkan
teknik yang lebih rumit tetapi dapat digunakan untuk konfirmasi hasil dari uji
hapusan.
Interpretasi dari uji Widal ini harus memperhatikan beberapa faktor antara
lain sensitivitas, spesifisitas, stadium penyakit; faktor penderita seperti status
imunitas dan status gizi yang dapat mempengaruhi pembentukan antibodi;
gambaran imunologis dari masyarakat setempat (daerah endemis atau non-
endemis); faktor antigen; teknik serta reagen yang digunakan.
Kelemahan uji Widal yaitu rendahnya sensitivitas dan spesifisitas serta
sulitnya melakukan interpretasi hasil membatasi penggunaannya dalam
penatalaksanaan penderita demam tifoid akan tetapi hasil uji Widal yang positif
akan memperkuat dugaan pada tersangka penderita demam tifoid (penanda
infeksi).3 Saat ini walaupun telah digunakan secara luas di seluruh dunia,
16

manfaatnya masih diperdebatkan dan sulit dijadikan pegangan karena belum ada
kesepakatan akan nilai standar aglutinasi (cut-off point). Untuk mencari standar
titer uji Widal seharusnya ditentukan titer dasar (baseline titer) pada anak sehat di
populasi dimana pada daerah endemis seperti Indonesia akan didapatkan
peningkatan titer antibodi O dan H pada anak-anak sehat.
3.2 TES TUBEX®
Tes TUBEX® merupakan tes aglutinasi kompetitif semi kuantitatif yang
sederhana dan cepat (kurang lebih 2 menit) dengan menggunakan partikel yang
berwarna untuk meningkatkan sensitivitas. Spesifisitas ditingkatkan dengan
menggunakan antigen O9 yang benar-benar spesifik yang hanya ditemukan pada
Salmonella serogrup D. Tes ini sangat akurat dalam diagnosis infeksi akut karena
hanya mendeteksi adanya antibodi IgM dan tidak mendeteksi antibodi IgG dalam
waktu beberapa menit
Walaupun belum banyak penelitian yang menggunakan tes TUBEX® ini,
beberapa penelitian pendahuluan menyimpulkan bahwa tes ini mempunyai
sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik daripada uji Widal.
3.3 METODE ENZYME IMMUNOASSAY (EIA) DOT
Uji serologi ini didasarkan pada metode untuk melacak antibodi spesifik
IgM dan IgG terhadap antigen OMP 50 kD S. typhi. Deteksi terhadap IgM
menunjukkan fase awal infeksi pada demam tifoid akut sedangkan deteksi
terhadap IgM dan IgG menunjukkan demam tifoid pada fase pertengahan infeksi.
Pada daerah endemis dimana didapatkan tingkat transmisi demam tifoid yang
tinggi akan terjadi peningkatan deteksi IgG spesifik akan tetapi tidak dapat
membedakan antara kasus akut, konvalesen dan reinfeksi. Pada metodeTyphidot-
M® yang merupakan modifikasi dari metode Typhidot® telah dilakukan inaktivasi
dari IgG total sehingga menghilangkan pengikatan kompetitif dan memungkinkan
pengikatan antigen terhadap Ig M spesifik.
Uji dot EIA tidak mengadakan reaksi silang dengan salmonellosis non-
tifoid bila dibandingkan dengan Widal. Dengan demikian bila dibandingkan
dengan uji Widal, sensitivitas uji dot EIA lebih tinggi oleh karena kultur positif
yang bermakna tidak selalu diikuti dengan uji Widal positif.2,8 Dikatakan 17

bahwaTyphidot-M® ini dapat menggantikan uji Widal bila digunakan bersama
dengan kultur untuk mendapatkan diagnosis demam tifoid akut yang cepat dan
akurat.
Beberapa keuntungan metode ini adalah memberikan sensitivitas dan
spesifisitas yang tinggi dengan kecil kemungkinan untuk terjadinya reaksi silang
dengan penyakit demam lain, murah (karena menggunakan antigen dan membran
nitroselulosa sedikit), tidak menggunakan alat yang khusus sehingga dapat
digunakan secara luas di tempat yang hanya mempunyai fasilitas kesehatan
sederhana dan belum tersedia sarana biakan kuman. Keuntungan lain adalah
bahwa antigen pada membran lempengan nitroselulosa yang belum ditandai dan
diblok dapat tetap stabil selama 6 bulan bila disimpan pada suhu 4°C dan bila
hasil didapatkan dalam waktu 3 jam setelah penerimaan serum pasien.
3.4 METODE ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)
Uji Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) dipakai untuk melacak
antibodi IgG, IgM dan IgA terhadap antigen LPS O9, antibodi IgG terhadap
antigen flagella d (Hd) dan antibodi terhadap antigen Vi S. typhi. Uji ELISA yang
sering dipakai untuk mendeteksi adanya antigen S. typhi dalam spesimen klinis
adalah double antibody sandwich ELISA. Chaicumpa dkk (1992) mendapatkan
sensitivitas uji ini sebesar 95% pada sampel darah, 73% pada sampel feses dan
40% pada sampel sumsum tulang. Pada penderita yang didapatkan S. typhi pada
darahnya, uji ELISA pada sampel urine didapatkan sensitivitas 65% pada satu
kali pemeriksaan dan 95% pada pemeriksaan serial serta spesifisitas
100%.18 Penelitian oleh Fadeel dkk (2004) terhadap sampel urine penderita
demam tifoid mendapatkan sensitivitas uji ini sebesar 100% pada deteksi antigen
Vi serta masing-masing 44% pada deteksi antigen O9 dan antigen Hd.
Pemeriksaan terhadap antigen Vi urine ini masih memerlukan penelitian lebih
lanjut akan tetapi tampaknya cukup menjanjikan, terutama bila dilakukan pada
minggu pertama sesudah panas timbul, namun juga perlu diperhitungkan adanya
nilai positif juga pada kasus dengan Brucellosis.
3.5 PEMERIKSAAN DIPSTIK
18

Uji serologis dengan pemeriksaan dipstik dikembangkan di Belanda
dimana dapat mendeteksi antibodi IgM spesifik terhadap antigen LPS S.
typhidengan menggunakan membran nitroselulosa yang mengandung antigen S.
typhisebagai pita pendeteksi dan antibodi IgM anti-human immobilized sebagai
reagen kontrol. Pemeriksaan ini menggunakan komponen yang sudah distabilkan,
tidak memerlukan alat yang spesifik dan dapat digunakan di tempat yang tidak
mempunyai fasilitas laboratorium yang lengkap.
4. Identifikasi kuman secara molekuler
Metode lain untuk identifikasi bakteri S. typhi yang akurat adalah mendeteksi
DNA (asam nukleat) gen flagellin bakteri S. typhi dalam darah dengan teknik
hibridisasi asam nukleat atau amplifikasi DNA dengan carapolymerase chain
reaction (PCR) melalui identifikasi antigen Vi yang spesifik untuk S. typhi. Kendala
yang sering dihadapi pada penggunaan metode PCR ini meliputi risiko kontaminasi
yang menyebabkan hasil positif palsu yang terjadi bila prosedur teknis tidak
dilakukan secara cermat, adanya bahan-bahan dalam spesimen yang bisa menghambat
proses PCR (hemoglobin dan heparin dalam spesimen darah serta bilirubin dan garam
empedu dalam spesimen feses), biaya yang cukup tinggi dan teknis yang relatif rumit.
Usaha untuk melacak DNA dari spesimen klinis masih belum memberikan hasil yang
memuaskan sehingga saat ini penggunaannya masih terbatas dalam laboratorium
penelitian.
19