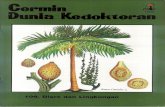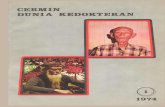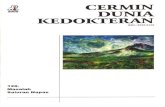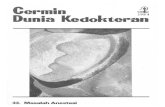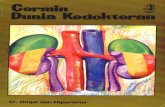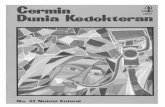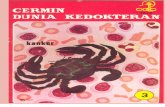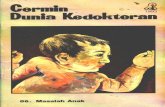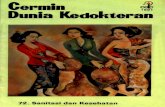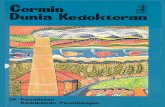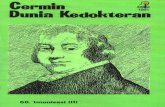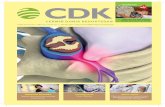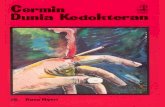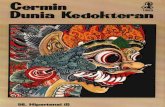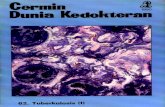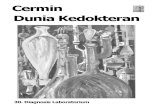Cdk 055 Malaria (II)
Transcript of Cdk 055 Malaria (II)


No. 55, 1989
Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian dan Pengembangan PT. Kalbe Farma
Daftar Isi : 2. Editorial Artikel:
3. Status Malaria di Indonesia 8. Situasi Kepekaan Plasmodium Falciparum terhadap Obat dan
Mobilitas Penduduk di Nunukan, Kalimantan Timur 12. Uji Coba Bacillus Thuringiensis H–14 untuk Pengendalian
Anopheles sundaicus 15. Efikasi Sabun Repelen Mengandung Deet dan Permethrin
untuk Perlindungan Gangguan Nyamuk 19. Hubungan Beratnya Penyakit Malaria Falciparum dengan
International Standard Serial Number: 0125 – 913X
Karya SriwidodoAlMaP.OPeDrPeDrDebaRaViReSeB.CProSaNotglPe
Kepadatan Parasit pada Penderita Dewasa 24. Keracunan Pestisida pada Petani di Berbagai Daerah di
Indonesia 27. Efek Karsinogenik beberapa Pestisida dan Zat Warna Ter-
tentu 32. Peningkatan Daya Tahan Tubuh oleh Kenaikan Suhu Tubuh
pada Mencit Terinfeksi dengan Plasm- odium berghei ANKA
38. Sebelum atau Sesudah Makan? Interaksi Obat dengan Makanan 44. Zat Kebal Bawaan Campak dan Pengaruhnya terhadap
Imunisasi Campak di Daerah Endemik Campak
49. Etika: Teknologi Kedokteran untuk Apa dan untuk Siapa?
54. Pengalaman Praktek: Berobat dart Pintu ke Pintu Malaria
56. Humor Ilmu Kedokteran 58. Abstrak-Abstrak 60. Ruang Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran
amat redaksi: jalah CERMIN DUNIA KEDOKTERAN . Box 3105 Jakarta 10002 Telp.4892808
nanggung jawab/Pimpinan umum: . Oen L.H. mimpin redaksi : Dr. Krismartha Gani, . Budi Riyanto W. wan redaksi : DR. B. Setiawan, Dr. Bam-ng Suharto, Drs. Oka Wangsaputra, DR. ntiatmodjo, DR. Arini Setiawati, Drs. ctor Siringoringo. daksi Kehormatan: Prof. DR. Kusumanto tyonegoro, Dr. R.P. Sidabutar, Prof. DR.
handra, Prof. DR. R. Budhi Darmojo, f. Dr. Sudarto Pringgoutomo, Drg. I.
drach. . Ijin : 151/SK/Dit Jen PPG/STT/1976, .3 Juli 1976. ncetak : PT. Temprint.
Tulisan dalam majalah ini merupakan pandang-an/pendapat masing-masing penulis dan tidak selalu merupakan pandangan atau kebijakan instansi/lembaga/bagian tempat kerja si penulis

Masih berkaitan dengan edisi terdahulu, kali ini Cermin Dunia Ke- dokteran melengkapi pembahasan tentang malaria dengan beberapa artikel mengenai aspek klinis dan hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggunaan insektisida. Dan ternyata demam yang timbul pada serangan malaria mungkin tidak sepenuhnya merugikan, seperti ditunjuk- kan oleh percobaan rekan Mohammad Sadikin dari bagian Biokimia FKUI. Dilengkapi dengan sebuah Pengalaman Praktek dan Abstrak me-ngenai Patogenesis Demam, mudah-mudahan dapat memuaskan para sejawat.
Selain itu, edisi ini diisi pula dengan beberapa artikel lain, diantara- nya mengenai pengaruh saat makan obat terhadap ketersediaan hayati- nya, sesuatu yang mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan, mungkin karena kekurang-fahaman para dokter akan mekanisme interaksinya. Ruang Etika akan membahas Teknologi Kedokteran – sesuatu yang banyak mendorong kemajuan, sekaligus membuka kemungkinan pen yalah-gunaan.
Akhir kata, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1409 H, segenap redaksi memohon maaf lahir dan batin, semoga untuk selanjutnya kami dapat lebih memuaskan para sejawat sekalian.
Redaksi
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 2

Artikel
Status Malaria di Indonesia
Cyrus H. Simanjuntak, P.R. Arbani** * Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI, Jakarta
**Dijen Pemberantasan Penyakit Menu/at- dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan RI Jakarta
PENDAHULUAN
Penyakit malaria hingga saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara-negara tropis yang biasanya merupakan negara yang sedang berkembang termasuk Indo-nesia1. Akibatnya, negara yang bersangkutan harus menyediakan dana yang cukup besar untuk memberantasnya apabila negara tersebut ingin membebaskan diri dari akibat yang sangat merugi kan dari penyakit ini.
Dalam kaftan ini perlu diingat bahwa sejak tahun 1959 yaitu sejak dicanangkannya dan dilaksanakannya usaha pem-basmian malaria oleh WHO, insidensi penyakit malaria telah banyak turun. Tapi akhir-akhir ini tanpa mengenyampingkan usaha yang disebut di atas, kenyataan memperlihatkan bahwa penularan malaria di daerah tropis mulai meningkat dan hampir kembali kepada keadaan saat sebelum usaha eradikasi malaria. Ternyata usaha eradikasi telah berhasil menurunkan atau meng-hilangkan malaria hanya di daerah dingin dan daerah sub tropis saja.
Timbulnya resistensi vektor malaria terhadap insektisida menyebabkan usaha eradikasi malaria gagal total, sehingga ke-giatan eradikasi yang banyak menyedot biaya dan tenaga tak mampu lagi dipertahankan. Sebagai gantinya diusahakan kegiat-an pemberantasan malaria (malaria kontrol) yang biayanya lebih ringan dengan masa kegiatan yang tidak terbatas. Indonesia merupakan pelopor yang menggantikan usaha eradikasi menjadi usaha pemberantasan, yang dimulai sejak tahun 1970.
Harus kita sadari bahwa timbulnya resistensi vektor malaria terhadap berbagai insektisida yang dianggap cukup aman dan timbulnya resistensi parasit P. fa/ciparum terhadap obat-obatan anti malaria seperti klorokuin dan Fansidar(R), menyebabkan pemberantasan malaria saat ini menjadi lebih remit. Kemajuan besar di bidang perhubungan dan komunikasi yang memper-mudah ruang gerak penduduk jelas memberi peluang besar bagi penyebaran penyakit ini dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga penularan akan meluas secara mudah. Dengan
demikian hampir seluruh tanah air merupakan daerah endemis terhadap malaria.
Endemisitas malaria bervariasi dari satu daerah ke daerah lain tergantung dari jenis vektor, keadaan alam (pegunungan, pantai, dataran dan lain-lain) dan faktor lainnya. Endemisitas tersebut berkisar antara hipo-, meso- dan hiper-endemi. Hingga saat ini, di Indonesia belum pemah diketemukan malaria dengan endemisitas holo-endemi seperti banyak diketemukan di Afrika. Selain itu, kecuali Jayapura, belum pernah diketemukan urban malaria di kota-kota besar di Indonesia. SEJARAH SINGKAT PEMBERANTASAN MALARIA DI INDONESIA
Kegiatan pemberantasan malaria di Indonesia hingga saat ini dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu : 1) Periode Sebelum Perang.
Usaha pemberantasan dilakukan sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena merupakan usaha setempat'. Usaha pem-berantasan ditujukan pada vektor penyebab dan pengobatan ter-hadap penderita, seperti : Metode mekanis, yaitu pengeringan atau penimbunan genangan air yang merupakan sarang jentik nyamuk vektor. Metode biologis, yaitu menanam ikan predator Haplodilus panchax di sarang jentik nyamuk, yaitu di air payau untuk me-makan jentik A. sundaicus dan di daerah persawahan untuk menghabiskan jentik A. aconitus. Pengobatan, yaitu mengobati penderita malaria dengan obat anti malaria dan memberikan obat pencegahan pada orang yang mempunyai risiko besar akan mendapat malaria. 2) Periode Sesudah Perang
Periode ini disebut periode pemberantasan malaria (MCP - Malaria Control Programme). Pada saat inilah ditemukan DDT (Dichloro-diphenyl-trichloretan) yang kemudian dianggap se-bagai insektisida penyelamat karena, murah, poten, dan stabil, suatu sifat yang ideal sebagai insektisida untuk dipergunakan
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 3

secara massal. Penemuan insektisida ini bersama-sama dengan penemuan obat malaria yang sangat ampuh yaitu 4-aminoqui-no/ine (misalnya klorokuin) dan 8-aminoquinoline (misalnya primakuin), memberi harapan besar. 3) Periode Pembasmian Malaria (MEP : Malaria Eradication Programme) 1959 - 1968
Timbulnya resistensi vektor malaria terhadap DDT dan dieldrin, menimbulkan kekhawatiran akan gagalnya program pemberantasan malaria. Pemakaian insektisida dalam jangka lama, menyebabkan semua populasi vektor akan menjadi resisten terhadap insektisida yang dipakai dalam jangka lama, walaupun disadari bahwa resistensi ini bersifat resesif. Oleh karena itu dipikirkan suatu program yang menyeluruh dan dilaksanakan secara serentak dan yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Oleh WHO, cara penanggulangan malaria diubah dari MCP(Malaria Control Programme) menjadi MEP(Malaria Eradi-cation Programme).
Pada tahun 1959 ditandatanganilah suatu persetujuan segi-tiga antara WHO, USAID dan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program MEP sesuai dengan penggarisan yang disusun oleh WHO.
Tiga fase pertama dari 4 fase yakni : fase Persiapan, Pe-nyemprotan, Konsolidasi dan Maintenance, akan dilaksanakan oleh KOPEM (Komando Operasi Pembasmian Malaria), suatu organisasi otonom yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden2. Secara simbolis penyemprotan rumah dengan DDT yang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 November 1959 di Kalasan, Yogyakarta oleh Presiden Sukarno sendiri; sejak itulah 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasio-nal.
Secara berangsur-angsur operasi penyemprotan dengan insektisida, DDT dan Dieldrin diperluas hingga 42 zona, yang meliputi Lampung, Jawa, Madura dan Bali. Pada mulanya, insidensi malaria turun dengan tajam dan mencapai titik terendah pada tahun 1965 dengan API(Annual Parasite Incidence) sebesar 0,12. Akan tetapi kemudian dengan keluarnya Indonesia dari WHO dan dihentikannya bantuan USAID, operasi pembasmian menjadi tertunda akibatnya API naik dan menjadi 0,15 pada tahun 1966; 0,21 pada tahun 1967; dan 0,27 pada tahun 1968. 4) Periode Pemberantasan Penyakit Malaria 1968–sekarang
Kekhawatiran akan timbulnya resistensi insektisida terutama DDT terhadap vektor malaria menjadi kenyataan. Akibatnya penanggulangan malaria tidak lagi tergantung pada satu-satunya senjata -DDT- tapi haruslah dibantu dengan usaha-usaha lain- nya. Selain itu keterbatasan dana menyebabkan usaha MEP yang menyedot terlalu banyak dana dan tenaga dalam waktu sangat singkat perlu segera diakhiri dan diganti dengan cara lain yang budget oriented. Maka pada akhir tahun 1968 organisasi KOPEM yang otonom, diintegrasikan . ke dalam Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (P2M&PLP) yang pada saat itu disebut Ditjen P4M (Pengawasan, Pemberantasan dan Pembasmian Penyakit Menular) dan menjadi Dinas Malaria. Integrasi ini terjadi di semua tingkatan yakni dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kkcamatan, dan seterusnya. TUJUAN PEMBERANTASAN MALARIA
Pemberantasan malaria saat ini dibagi dalam 2 tujuan, yakni
Tujuan Jangka Pendek dan Tujuan Jangka Panjang3. Tujuan Jangka Pendek ialah usaha untuk menurunkan jumlah kecamat-an yang insidensi malarianya tinggi (API di atas 0,75) dari 63 menjadi 37 kecamatan pada akhir Repelita IV dan memper-tahankan API menjadi kurang dari 0,1 untuk Jawa dan Bali. Bagi luar Jawa dan Bali Tujuan Jangka Pendek ialah menurun-kan prevalensi malaria menjadi kurang dari 5% di daerah prioritas dan menjadi 15 - 20% di daerah lain (bukan prioritas) pada akhir Repelita IV.
Tujuan Jangka Panjang pemberantasan penyakit malaria untuk Jawa dan Bali ialah untuk mengurangi jumlah kecamatan yang mempunyai insidensi tinggi menjadi hanya 20 kecamatan saja pada Repelita VI (1994/95 - 1998/99) dan mempertahankan API kurang dari 0,1. Untuk luar Jawa dan Bali, Tujuan Jangka Panjang ialah menurunkan prevalensi malaria hingga kurang dari 2% di daerah prioritas dan antara 5-100/o di daerah lainnya (non-prioritas) pada akhir Repelita VI. STRATEGI PEMBERANTASAN
Seperti disebutkan di atas, kegiatan pemberantasan malaria telah diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam Ditjen P2M&PLP di semua tingkatan.Hal ini dilakukan dengan maksud agar kegiatan ini merupakan pendekatan pemeliharaan kesehatan dengan melibatkan lebih banyak peran-serta masyarakat.
Secara strategi pemberantasan malaria di Jawa dan Bali sedikit berbeda dengan luar Jawa dan Bali (Tabel 1). Di Jawa dan Bali pemberantasan malaria meliputi seluruh propinsi dengan Desa merupakan unit terkecil, sedangkan di luar Jawa dan Bali kegiatan pemberantasan diprioritaskan di daerah proyek transmigrasi, daerah perbatasan (Malaysia dan Brunei Darussalam) dan daerah di mana ditemukan peningkatan sosio-ekonomi yang potensial. SITUASI MALARIA SAAT INI Insidensi Malaria
Di Jawa dan Bali, pengamatan penyakit malaria dilakukan dengan dua cara yakni ACD (Active Case Detection) dan PCD (Passive Case Detection). ACD dilakukan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah oleh petugas malaria desa (dulu PMD - Pembantu Malaria Desa), setiap 1 atau 2 bulan sebuah rumah harus dapat dikunjungi dan dari setiap penderita demam yang dikunjungi diambil darah tepi untuk pemeriksaan malaria secara mikroskopis. Sedangkan pada PCD, pengambilan darah dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik.
Tabel 2 memperlihatkan insidensi malaria di Jawa dan Bali pada dan tahun 1974 1985. Data ini cukup akurat karena ABER (Annual Blood Examination Rare) cukup konsisten antara 8 - 9%. Tampak penurunan insidensi malaria dari tahun ke tahun walaupun terlihat adanya fluktuasi API dan SPR (Slide Positivity Rate). Hal yang menarik ialah adanya peningkatan ratio P. falciparum dari 34,33 pada tahun 1974 menjadi 54,30 pada tahun 1982 dan sedikit menurun menjadi 38,39 pada tahun 1985. Ini merupakan suatu petunjuk akan adanya peningkatan resistensi P. falciparum terhadap obat anti malaria.
Dari insidensi penyakit malaria yang disajikan per propinsi (Tabel 3), tampak terus menerus tinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 1985, 79% dari kasus malaria di.Jawa dan Bali, terdapat
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 4

Tabel 1. Strategi Kegiatan Pemberantasan Malaria.
Luar Jawa dan Bali Jenis Kegiatan Jawa dan Bali
Prioritas Bukan Prioritas
Kontrol Vektor KegiatanAnti Larva Pengobatan Pengamatan
I R S Terbatas Presumptif, Radikal ACD, PCD
I R S Terbatas Supresif PCD, SM
– – Supresif PCD
IRS = Indoor Residua/ House Spraying ACD = Active Case Detection PCD = Passive Case Detection SMM = Survai Malariometrik Tabel 2. Situasi Malaria di Jawa dan Bali, tahun 1974 - 1985.
Tahun ABER Kasus API SPR Pf%
1974 8,93 229.711 2,73 3,05 34,33 1975 9,63 125.166 1,45 1,51 35,281976 8,96 96.999 1,11 1,23 40,94 1977 9,03 110.553 1,23 1,37 39,601978 8,91 127.590 1,39 1,56 34,39 1979 8,61 78.854 0,84 1,98 46,951980 9,52 176.733 1,85 1,95 46,60 1981 9,54 124.656 1,33 1,37 45,231982 9,42 84.266 0,86 0,92 54,301983 9,24 133.607 1,34 1,45 47,78 1984 8,44 86.088 0,85 1,00 42,76 1985 8,18 47.673 0,46 0,56 38,39
ABER – Annual Blood Examination Rate (%) API – Annual Parasite Incidence (1/100) SPR – Slide Positivity Rate Pf – Plasmodium falciparum ratio
Propinsi 1983 1984 1985
Kasus API Klaus API Kasus API
Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur B a l i Jogyakarta DKI Jakarta
10.035 108.626 13.375
71 1.166 353
0,34 4,08 0,44 0,01 0,41 0,14
3.336 67.258 14.407
69 731 287
0,11 2,48 0,47 0,02 0,25 0,11
1.982 37.788 7.085 181 575 62
0,06 1,37 0,23 0,07 0,20 0,01
Jumlah 133.636 1,34 86.088 0,85 47.673 0,46
API : Annual Parasite Incidence di Jawa Tengah. Walaupun di DKI masih ditemukan adanya kasus malaria (API a 0,01 pada tahun 1985), kasus-kasus tersebut merupakan kasus pendatang, karena penularan malaria di Jakarta tidak mungkin terjadi. Sejak tahun 1970 tidak pernah lagi diketemukan vektor malaria di Jakarta, kecuali di Pulau Seribu.
Dari 27 propinsi di Indonesia, 21 propinsi termasuk propinsi Luar Jawa dan Bali.Di luar Jawa dan Bali,SMM(Survai Malario-metrik) dilakukan di daerah prioritas guna menilai hasil dari operasi penyemprotan dan di daerah lain (non prioritas) untuk menentukan endemisitas malaria di daerah tersebut. Kegiatan PCD juga dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Poliklinik
seperti halnya di Jawa dan Bali. Dari SMM dan PCD penderita malaria tahun 1974 sd. 1985 terlihat inssidensi malaria di luar Jawa dan Bali terus menurun dengan sedikit fluktuasi (Tabel 4 dan 5). Tabel 4. Hasil Survai Malariometrik dad Luar Jawa dan Bali tahun 1974-1985.
Tahun Jumlah S.D. diperiksa Positif Parasite Rate
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
159.182 148.058 100.914 65.655 193.004 155.892 466.355 559.657 594.926 450.619 698.316 405.374
14.907 10.946 6.808 3.585 8.353 6.558 19.283 20.303 30.689 13.310 31.618 17.697
9,9 7,4 6,7 5,5 4,3 4,2 4,1 3,6 5,2 3,0 4,8 4,4
SD : Sediaan Darah Tabel 5. Klinis Malaria dan SPR dari Luar Jawa dan Bali tahun 1974 - 1985.
Tahun Klinis Malaria Jumlah S.D. diperiksa Positil SPR 1974 740.177 240.498 90.478 1975 774.602 318.641 78.234 24,5 1976 747.555 358.093 73.486 20,51977 635.676 217.858 52.805 24,21978 579.756 236.203 51.962 22,0 1979 1.075.658 358.427 87.105 24,3 1980 1.241.403 488.616 130.279 26,71981 756.771 353.788 90.730 25,6 1982 1.214.496 '410.946 104.814 25,51983 831.824 421.631 84.268 19,91984 1.395.389 456.290 105.416 23,11985 1.036.528 228.088 44.057 , 16,3
SPR : Slide Positivity Rate SD : Sediaan Darah Tabel 6. Penyebaran Vektor Malaria di Indonesia.
Tempat/Pulau Vektor Malaria
Jawa and Bali Sumatera Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Irian Jaya/Maluku
A. aconitus, A. sundaicus, A. subpictus, A. balabacensis. A. sundaicus, A. hyrcanus group, A. maculatus, A. letifer, A. aconitus.* A. balabacencts, A. umbrosus, A. hyrcanus group, A. letfer,A. sundaicus. A. barbirostris, A. sundaicus, A. subpictus, A. ludlowe, A. hyrcanus group, A. flavirostris, A. minimus; A. nigerimus*. A. subpictus, A. sundaicus, A. barbirostris, A. aconitus* A: farauti, A. holiensis, A. punctulatus, A. bancrofti, A. karwari.
* dicurigai sebagai vektor. Insidensi malaria per propinsi dapat dilihat pada gambar I,
insidensi malaria yang tinggi terdapat di Bengkulu, Kalbar, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Timor Timur dan Irian Jaya. Semua daerah yang disebut ini kebetulan adalah propinsi di luar Jawa dan Bali dengan SPR lebih dari 30%. SPR yang kurang dari 1% hanya terdapat di Sumatra Barat, Riau, DKI, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 5

Gambar I. Situasi Penyakit Malaria per Propinsi, tahun 1984.
Mortalitas Malaria
Pada saat ini, sangat sulit menentukan secara tepat jumlah penduduk yang meninggal karena malaria di Indonesia. SKRT (Survai Kesehatan Rumah Tangga) yang dilakukan pada 7 propinsi pada tahun 1986 menunjukkan bahwa CFR (Case Fatality Rate) malaria adalah 23,9 per 105 penduduk. Sebagian besar kematian ini terdapat pada anak umur 1 – 4 tahun. Vektor Malaria
Secara keseluruhan, telah ditemukan lebih dari 80 spesies Anopheles di Indonesia, 18 species di antaranya telah terbukti dan dipastikan sebagai vektor malaria6. Tabel memperlihatkan distribusi vektor malaria yang disajikan per pulau.
Vektor paling utama di Jawa dan Bali, yaitu daerah yang ditempati oleh lebih dari 70% penduduk Indonesia, adalah A. sundaicus dan A. aconitus. Vektor lain yang tidak kurang pentingnya oalah A. maculatus, A. subpictus, A. sinensis dan A. balabacensis. Masalah resistensi vektor malaria
Seperti diketahui, A. aconitus merupakan vektor utama di daerah persawahan di Jawa dan Bali. Pada tahun 1965, di Jawa Tengah telah dilaporkan adanya resistensi A. aconitus terhadap DDT, Dieldrin dan DDT bersama-sama7,8. Kemudian pada tahun 1982 tingkat resistensi ini mulai bertambah9. Belakangan ini dilaporkan pula timbulnya resistensi vektor ini terhadap DDT di Jawa Timur dan Yogyakarta6 A. sundaicus merupakan vektor utama malaria di daerah pantai di Jawa dan Bali. Baru-baru ini telah dilaporkan adanya resistensi A. sundaicus terhadap DDT di Jawa Timur, Lampung dan Cilacap10.A. subpictus (juga vektor malaria di daerah pantai), yang resisten terhadap DDT diduga telah mulai timbul di Jawa Timur, tapi hal ini belum ada konfirmasi yang pasti. Selain itu, juga telah dicurigai timbulnya resistensi A. farauti dan A. holiensi terhadap DDT. Masalah resistensi P. falciparum terhadap obat-obatan anti malaria.
Kasus pertama resistensi P. falciparum terhadap klorokuin di
Indonesia telah dilaporkan oleh Verdrager di Samarinda, Kali-mantan TimurlI. Kemudian menyusul laporan resistensi di daerah lainnya di Jayapura12 dan Kalimantan Timur13.
Kasus pertama P.falciparum yang rsisten terhadap klorokuin pada penduduk endogen Jawa ditemukan di Jepara tahun 198114. Dan pada tahun 1981 dilaporkan pula adanya resistensi P. falci-parum terhadap klorokuin di Sumatera Selatan dan Lampung. Pada saat ini, resistensi P. falciparum terhadap klorokuin telah menyebar dan tercatat pada 25 propinsi (gambar II).
KEPUSTAKAAN
1. Kondarshin AV. Malaria in South East Asia. SEA J Trop Med Pub Hlth 1986; 17 (4), 642-54.
2. Gandahusada S,Sumarlan. Malaria in Indonesia: A review of Literature. Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta, 24-27 April 1978.
3. Kumara Rai N, Arbani P R. Current status of Malaria in Indonesia. Problem of Malaria in the SEAMIC Countries. Proc 12th SEAMIC Work-shop pp 11-7. Eds. Chamlong Harinasuta and Denise C. Reynolds. SEAMIC, Tokyo. 1985.
4. Arbani PR, Jung RK Epidemiological Consideration for Planning Malaria Control in Indonesia. Official Report, 1986.
5. Budiarso RL. Pola Kematian. Presented at Seminar on Household Survey 1986. Jakarta 14-15 December 1987.
6. Santiyo Kirnowardoyo. Anopheles malaria vector in Indonesia. Problem of Malaria in the SEAMIC Countries. Proc 12th SEAMIC Workshop pp. 66-9. Eds. C Harinasuta and DC. Reynolds. SEAMIC Tokyo, 1985.
7. Surono M, Davidson G, Muir DA. The Development and Trend of Insec-ticide Resistance in An. aconitus Donitz and An. sundaicus Rodenwalt. Bull WHO'1965; 32, 161-8.
8. Surono M. Badawi AS, Muir DA, Soedono A dan Siran M. Observations on Doubly-Resistant An. aconitus Donitz in Java, Indonesia, and on its Amenability to Treatment with Malathion. Bull WHO 1965; 33, 453-9.
9. Bang YH, Arwati S, Gandahusada S. A Review of Insecticide Use for Malaria Control in Central Java, Indonesia. Malays Appl Bio 1982; 11(2), 85 - 96.
10. Kirnowardoyo S, Yoga GP. Entomological Investigation of an Outbreak of Malaria in Cilacap on South Eastern Central Java, Indonesia during 1985. J Corn Dis 1987; 19 (2), 121-7.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 6

Gambar II. Penyebaran P. Falciparum yang resisten terhadap klorokuin di Indonesia.
11. Verdrager J Alvah. Resistant Plasmodium falciparum infection from Sama-
rinda, Kalimantan. Bull Hlth Stud Indon II, 1974; 43-50. 12. Verdrager J, Arwati, Simanjuntak CH dan Suroso IS. Response of falciparum
malaria to a standard regimen of chloroquin in Jayapura, Irian Jaya. Bull Hlth Stud Indon IV 1976; 1&2, 19-25.
13. Verdrager J, Arwati, Simanjuntak CH dan Suroso JS. Chloroquine resistant falciparum malaria in East Kalimantan, Indonesia, J Trop Mid Hyg, 1976;
79, 58-60. 14. Simanjuntak CH, Arbani PR, Kumara Rai N. P. falciparum Resisten
terhadap choroquine di Kabupaten Jepara, Jaws Tengah. Bull H1th Stud Indon 1981; IX (2), 1-8.
15. Pribadi W, Dakung LS, Gandahusada S, Dalyono. Chloroquine Resistant P. falciparum infection from Lampung and South Sumatra, Indonesia. SEA J Trop Med Hlth 12 (1), 69-73.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 7

Situasi Kepekaan Plasmodium Falciparum terhadap Obat dan Mobilitas Penduduk
di Nunukan, Kalimantan Timur
Sahat Ompusunggu, Sekar Tuti Sulaksono, Harijani A. Marwoto, dan Rita Marleta Dewi
Pusat Penelitian Penyakit Menular, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I. , Jakarta
ABSTRAK
Suatu tes resistensi Plasmodium falciparum secara in vivo terhadap meflokuin dan secara in vitro terhadap klorokuin, kombinasi pirimetamin/sulfadoksin dan meflokuin telah dilakukan di Keeamatan Nunukan, Kabiipaten Bulungan, Kalimantan Timur pada tahun 1987. Tes in vivo terhadap meflokuin dan in vitro terhadap klorokuin dan meflokuin dilakukan sesuai dengan standar WHO sedangkan tes in vitro terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin merupakan modifikasi Eastham and Rieckmann dan Nguyen Dinh and Payne. Hasil tes resistensi ini dihubungkan dengan data sekunder tentang mobilitas penduduk di daerah tersebut.
Diperoleh basil bahwa dari 12 penderita yang berhasil dites belum ditemukan P: falciparum yang resisten terhadap meflokuin secara in vivo, sedangkan secara in vitro belum diketahui keadaan resistensi yang sebenarnya dari ketiga jenis obat. Selama tahun 1984 dan pertengahan pertama tahun 1985, sebagian besar (82%) pelintas batas pencari kerja yang resmi/terdaftar dari Indonesia ke Sabah (Malaysia) berasal dari Sulawesi Selatan dan hanya sebagian kecil (10% dan 8%) yang berasal masing-masing dari Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lainnya. Di samping itu ditemukan juga pelintas batas pencari kerja yang tidak resmi/tidak terdaftar yang diperkirakan jumlahnya lebih besar dan dengan komposisi asal yang kurang lebih sama, serta pelintas batas tradisional yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar lagi.
PENDAHULUAN
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur adalah daerah perbatasan antara Indonesia (Kalimantan Timur) dengan Malaysia (Sabah). Kedua suku bangsa yang men-diami daerah itu pada dasarnya berasal dari suku bangsa yang sama, sehingga banyak persamaan kebudayaan di antara kedua-nya. Sudah sejak dahulu kala terjadi perdagangan yang baik di kedua pihak dan saling kunjung mengunjungi merupakan hal yang biasa terjadi. Di samping itu juga perkembangan ekonomi yang tidak sama di kedua negara menyebabkan terjadinya ke-butuhan akin tenaga kerja dari pihak Malaysia terhadap Indo-nesiā. Keadaan ini menyebabkan banyak tenaga kerja dari Indo-nesia yang memasuki Malaysia baik secara resmi maupun tidak dan kelihatannya semakin meningkat akhir-akhir ini.
Malaria adalah salah satu penyakit menular endemis yang terdapat di daerah perbatasan tersebut, baik di Nunukan maupqn di Sabah. Adanya lalu lintas penduduk di kedua pihak menyebabkan masalah baru dalam pemberantasannya sebab strain-strain yang telah resisten terhadap obat-obat antimalaria di salah satu pihak akan dengan cepat menular ke pihak lainnya bila tidak diawasi dengan baik.
Di Kalimantan Tirnur telah ditemukan P. falciparum yang resisten terhadap klorokuin pada tahun 1979(1). Beberapa obat alternatif yang dipertimbangkan untuk penanggulangan strain yang resisten terhadap klorokuin ini antara lain adalah kombinasi pirimetamin/sulfadoksin, meflokuin, kina dan sebagainya. Namur. terhadap obat-obatan alternatif inipun sudah mulai ada strain yang resisten di beberapa tempat di Indonsia. Secara
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 8

in vitro telah ditemukan P. falciparum yang resisten terhadap meflokuin di Irian Jaya dan Jawa Tengah2.,. Secara in vivo juga telah ditemukan P. falciparum yang resisten terhadap kom-binasi pirimetamin/sulfadoksin di Irian Jaya3. Timor Timur;, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatans. Sedangkan di negara tetangga kita yang agak jauh (Thailand), P. falciparum telah resisten terhadap obat-obatan antimalaria bans pertama (klorokuin) dan bans kedua (kombinasi pirimetamin/sulfadoksin dan meflokuin) dan menunjukkan penurunan resistensi terhadap quinine). Dikhawatirkan strain-strain yang multiresisten ini dapat masuk ke Indonesia (Nunukan) baik melalui Malaysia (Sabah), maupun dan daerah lain di Indonesia sendiri.
Untuk mengetahui besarnya masalah resistensi P falciparum di Nunukan, Kalimantan Timur, pada tahun 1987 telah dilakukan suatu tes resistensi secara in vivo terhadap meflokuin dan secara in vitro terhadap klorokuin, kombinasi pirimetamin/ sulfadoksin dan meflokuin. Makalah ini melaporkan hasil tes resistensi tersebut dan dikaitkan dengan situasi mobilitas penduduk di daerah yang bersangkutan.
BAHAN DAN CARA Lokasi penelitian adalah di beberapa desa di Kecamatan
Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (gambar 1).
field test). Data-data mobilitas penduduk di sekitar perbatasan merupa-
kan data sekunder yang diperoleh dari laporan Kanwil/Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur7. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dan 792 orang penduduk yang diperiksa darah tepinya, di-peroleh hasil bahwa besarnya PR (Parasite Rate) adalah 12.4%. Dan penderita yang positif ini, 69,4% merupakan P. falciparum (termasuk campuran P. falciparutfi dan P vivax) dan 29,6% merupakan P. vivax. Angka ini menyerupai keadaan di daerah Luar Jawa - Bali pada umumnya. Nunukan memang termasuk daerah endemis malaria dan kelihatannya angka Parasite Rate-nya tidak berbeda jauh dengan angka rata-rata Parasite Rate malaria di daerah lainnya.
Hasil tes resistensi dapat dilihat pada tabel 1. Dari 22 penderita yang dites secara in vivo terhadap meflokuin, hanya 12 penderita yang berhasil dievaluasi dan semuanya masih sensitif. Dal= tes in vitro, dari•24 penderita yang dites terhadap masingmasing obat, hanya 3 penderita yang berhasil dievaluasi terhadap klorokuin dan 2 penderita di antaranya sudah resisten, sedangkan terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin hanya 2 penderita yang berhasil dievaluasi dan semuanya masih sensitif dan terhadap meflokuin hanya 3 penderita yang berhasil dievaluasi dan semuanya masih sensitif.
Meflokuin merupakan obat baru yang dikembangkan untuk menanggulangi P. falciparum yang resisten baik terhadap kloro-kuin maupun terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin. Secara eksperimental telah diketahui bahwa timbulnya resistensi terhadap meflokuin lebih mudahterjadi pada strain yang sudah resisten terhadap klorokuin daripada yang masih sensitif, dan resistensi terhadap meflokuin ini akan dipercepat bila strain yang bersangkutan sudah nlultiresisten8.. Dalam penelitian ini, secara in vitro belum ditemukan strain P. falciparum yang multiresisten (terhadap klorokuin dan kombinasi pirimetamin/sulfadoksin sekaligus).
Karena jumlah sampel yang berhasil dievaluasi sangat sedikit, maka basil tes secara in vitro ini belum dapat meng-
Tabel 1. Sensitivitas P. falciparum terhadap 3 macam obat di Nunukan, Kalimantan Timur.
Obat Jumlah
yang dites
Jlh yang berhasil
dievaluasiSensitivitas
Jumlah yang dites
Jlh yang berhasil
dievaluasi Sensitivitas
Meflokuin P/S
Klorokuin
22 – –
12 – –
semua S – –
24 24 24
3 2 3
semua S semua S 2 R, 1 S
R = Resisten; S = Sensitif; P/S = kombinasi pirimetamin/sulfadoksin.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 1987. Penderita yang memenuhi syarat untuk tes,diperoleh dengan cara screening dengan melakukan pemeriksaan darah tepi/jari pada penduduk. Syarat-syarat penderita dan cara tes in vivo terhadap meflokuin din tes in vitro terhadapklorokuin dan meflokuin sesuai dengan ketentuan WHO&, sedangkan cara tes in vitro terhadap kom-binasi pirimetamin/sulfadoksin merupakan modifikasi Eastham and Rieckmann dan Nguyen Dinh and Payne. Tes in vivo terhadap meflokuin yang dipakai adalah tes 7 hari (standard
gambarkan keadaan yang sebenarnya di daerah itu. Namun ber-dasarkan hasil penelitian terdahulu di propinsi Kalimantan Timur yang menemukan P. fakiparum yang resisten terhadap meflokuin, ini bukan berarti bahwa kehadiran strain yang resisten terhadap klorokuin belum berpengaruh terhadap pembentukan strain yang resisten terhadap meflokuin. Hal itu mungkin disebabkan karena jumlah sampel yang berhasil diamati dalam penelitian ini kurang banyak.
Walaupun strain yang resisten terhadap kombinasi pin-
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 9

metamin/sulfadoksin secara in vitro belum ditemukan karena ter-lalu sedikitnya sampel yang berhasil dievaluasi, bahaya masuknya strain yang resisten terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin ini masih tetap ada, misalnya dari Sulawesi Selatan. Dari laporan Kanwil/Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa Nunukan merupakan tempat transit sementara para pelintas batas, baik yang akan pergi maupun yang datang dari Tawau (kota terbesar di Sabah yang paling dekat dengan per-batasan). Pelintas batas ini dapat berupa pelintas batas tradisional (penduduk setempat yang berdagang atau kunjungan kekerabat-an) maupun pelintas batas pencari kerja. Data menunjukkan bahwa selama tahun 1984 sampai dengan pertengahan 1985, jumlah pelintas batas pencari kerja yang resmi (terdaftar pada pemerintah setempat) 943 orang, sebagian besar (82%) berasal dari Sulawesi Selatan dan sisanya (masing-masing 10% dan 8%) berasal dari Nusa Tenggara Timur dan daerah lainnya1. Peneliti-an pada tahun 1984–1985 telah menemukan satu kasus penderita. malaria falciparum yang sudah resisten terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin di Sulawesi Selatan5. Besarnya masalah resistensi P. falciparum terhadap kombinasi piri-metamin/sulfadoksin di Sulawesi Selatan saat ini belum di-ketahui secara tuntas, namun adanya kasus malaria falciparum yang sudah resisten terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin tersebut, perlu mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur sebab sewaktu-waktu dapat masuk ke daerah itu melalui para pelintas batas yang berasal dari Sulawesi Selatan atau dengan cara lain. Di samping pelintas batas pencari kerja yang resmi/terdaftar ini, juga terdapat pelintas batas pencari kerja tidak resmi/tidak terdaftar yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar, dan komposisi asalnyapun tidak berbeda jauh dengan pencari kerja yang resini/terdaftar. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelintas batas yang berasal dari Sulawesi Selatan, agar kemungkinan penyebaran strain-strain yang resisten terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin itu dapat dicegah. Tindakan pencegahan memang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan Nunukan, berupa pengobatan terhadap pelintas batas yang resmi sebelum dikirim ke agen-agen pemakai tenaga kerja tersebut di Malaysia. Namun sebelum mereka mendaftarkan diri secara resmi, mereka tinggal beberapa lama di Nunukan dan selama masa penantian ini, mereka sewaktu-waktu bisa menjadi sumber penularan ke penduduk di sekitarnya. Di samping itu, penularan yang lebih besar di-perkirakan bersumber dari pencari kerja tidak resmi yang jumlahnya lebih besar.
Sabah adalah daerah yang endemis malaria dan termasuk daerah malaria falciparum yang sudah resisten terhadap kloro-kuin. Dalam program pemberantasannya, pemerintah Malaysia telah menggunakan FansidarR (kombinasi pirimetamin/sulfa-doksin) dalam pengobatan P. fcalciparum9. Seperti diketahui, penggunaan pirimetamin yang berlangsung lama di suatu daerah dengan cepat akan menyebabkan timbulnya resistensi6. Ber-dasarkan hal ini maka tidak tertutup kemungkinan di Sabah juga sudah terdapat strain P. falciparum yang resisten terhadap kombinasi pirimetamin/sulfadoksin. Dikhawatirkan strain-strain yang resisten ini dapat terbawa oleh para pelintas batas tradisio-nal, sebab jenis pelintas batas ini tidak diawasi dengan ketat, baik oleh pihak pemerintah Malaysia maupun Indonesia. Jenis pelintas batas tradisional ini biasanya adalah penduduk
setempat yang pergi pada pagi hari dan pulang pada sore harinya dan kebanyakan mengadakan perjalanan dengan alasan untuk berdagang. Dalam hal inilah dibutuhkan perhatian yang lebih besar dari pihak dinas kesehatan setempat, agar pengawasan terhadap mereka dapat lebih ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Di samping itu juga diharapkan agar kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan para pelintas batas tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi di masamasa yang akan datang, sebab keuntungan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia narnun juga bagi Malaysia. KESIMPULAN 1) P. falciparum yang resisten terhadap meflokuin secara in vivo belum ditemukan, secara in vitro belum diketahui keadaan resistensi yang sebenarnya terhadap obat-obat lainnya. Betdasarkan basil penelitian terdahulu, dapat dikatakan daerah itu termasuk daerah malaria falciparum yang juga sudah resisten terhadap klorokuin. 2) Sebagian besar (82%) pelintas batas pencari kerja yang resmi/ terdaftar berasal dari Sulawesi Selatan dan hanya sebagian kecil (10% dan 8%) yang berasal masing-masing dari Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lainnya. Masih ada pelintas batas pencari kerja yang tidak resmi/tidak terdaftar yang jumlahnya diperkirakan lebih besar dan dengan komposisi asal yang kurang lebih sama dengan pelintas batas yang resmi, serta pelintas batas tradisional yang jumlahnya jauh lebih besar lagi. 3) Para pelintas batas ini dikhawatirkan mempermudah pe-masukan dan penyebaran strain-strain P. falciparum yang sudah resisten ke daerah tersebut, baik yang bersumber dari daerah lainnya di Indonesia maupun dari Sabah (Malaysia). SARAN
Pengawasan terhadap para pelintas batas di sekitar daerah perbatasan di Nunukan,.Kalimantan Timur agar lebih ditingkat-kan, baik oleh dnas kesehatan setempat maupun dengan kerja sama dengan pemerintah Malaysia.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 10

KEPUSTAKAAN
1. Rai NK Masalah P. falciparum yang resisten klorokuin di Indonesia. Kumpulan Naskah Lengkap Simposium dan Diskusi Panel Malaria, 9 Mei 1985, Semarang: 101–10.
2. Hoffman SL, Sjahrial Harun, Anthony J, H A. Marwoto. In Vitro Studies of Plasmodium falciparum to Mefloquine in Indonesia. Seminar Parasitologi Nasional Ke-III dan Kongres P4I Ke-II, Agustus 1983, Bandung.
3. Rumans LW. Dennis DT, S. Atmosoedjono. Fansidar–resistant falciparum malaria in Indonesia. Lancet 1980; 15 : 580.
4. Adjung, Sumami A, Legia S. Dakung, Wita Pribadi, Pramudya. Plasmodium falciparum dari Timor Timur yang in vivo resisten terhadap klorokuin dan Fansidar. Pertemuan teknis mengenai Plasmodium falciparum yang resisten terhadap klorokuin di Indonesia. Ditjen P3M, Depkes RI., Jakarta, 12 April 1982.
5. HA, Marwoto, Sakai Tuti E, S Ompusunggu, Susetyono dan Suwarni. Penelitian Resistensi P. falciparum terhadap Fansidar di Indonesia. Seminar-' Parasitologi Nasional Ke-IV dan Kongres P4I Ke-III, Yogyakarta, 12–14 Desember 1985.
6. Bruce-Chwatt, U. (Ed). Chemotherapy of Malaria. Second Ed., WHO Monograph Seri No. 27, WHO, Geneva. 1981.
7. Kanwil/Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Malaria–control acti-vities in East Kalimantan and Border Areas. Kanwil/Dinar Kesehatan Pro-pinsi Kalimantan Timur, Samarinda 1985.
8. UNDP/World Bank/WHO Update. Development of mefloquine as an anti-malaria drug. Bull WHO 1983; 61 (2) : 169–78.
9. Singh J. The Anti malaria Programme in Sabah, Malaysia. Dalam : Problems of Malaria in SEAMIC Countries. C. Harinasuta and D. Reynolds (eds.), SEAMIC, Tokyo 1985: 38-42.
UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Dr. Iskak Koiman, Kepala Pusat Penelitian Penyakit Menular, Badan Litbangkes Jakarta atas kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Juga kepada seluruh staf Puskesmas Nunukan dan staf Subdit Malaria Ditjen P2M & PLP Jakarta yang ikut membantu pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 11

Uji Coba Bacillus Thuringiensis H-14 untuk Pengendalban Anopheles Sundaicus
Santiyo Kirnowardoyo*, BambangPraswanto*,*Joharti Johor**, Yuwono***, I Made Rukta***
*Medical Entomologist, Pusat Penelitian Ekologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
**Medical Entomologist, Dit. Jen. PPM dan PLP, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta ***Assisten Entomologist, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Bali.
ABSTRACT
Evaluation of three kinds of formulation containing Bacillus thuringiensis H–14 against Anopheles sundaicus larvae was carried out at Banyuwangi/East Java and Jembrana/Bali. The application of granula formulation at 500 gr/10.000 m2 to the brackish water lagoon had no apparent effect on the target An. sundaicus population. A liquid formulation (Teknar) containing B. thuringiensis H–14 toxin, by weekly application at 100 ml/200 m2 gave good larval control of Anopheles sundaicus. A briquet formulation at 1 piece/9 m2 could reduce the number of larvae significantly, with very satisfactory effect of at least three weeks, but the operational aspect was not practical.
PENDAHULUAN
Anopheles sundaicus (Rodenwaldt), adalah vektor malaria utama daerah pantai Indonesia1. Nyamuk ini dikonfirmasi ulang sebagai vektor malaria di; Jawa Timur (1979). Nusa Tenggara Timur (1979), Sulawesi Selatan (1979), Lampung (1982), Riau (1982) dan Jawa Tengah (1985)2.
A sulic/aicus berkembang biak di genangan air payau, yaitu campuran antara air tawar dengan air asin dengan kadar garam optimum antara 12–18 g. per liter. Genangan yang baik untuk perkembangan An sundaicus adalah genangan air payau terbuka sehingga langsung menerima sinar matahari dan per mukaanr tertutup tanaman air (ganggang) yang terapung. Jarak terbang nyamuk mi hanya kira-kira tiga kilometer dan tempat berkembang biak3.
Meskipun pengendalian nyamuk mi telah dilakukan sejak tahun 50-an oleh pemerintah, tetapi letupan atau wabah malaria yang disebabkan An.sundaicus masih sering terjadi. Di antaranya terjadi di Kp. Laut/Ci1a yang termasuk wilayah Jawa Tengah selatan pada tahun 1984. Penyemprotan rumah penduduk dengan DDT sebagai upaya penanggulangan tidak dapat me mutuskan. penularan yang berlangsung Hal mi disebabkan karena An. sundaicus yang menjadi sasaran, kecuali telah kebal DDT, nyamuk tersebut tidak pemah hinggap di dinding rumah yang disemprot . Cara pengendalian lain dengan larvasida untak nyamuk mi, yang ditujukan kepada stadium jentik mem-. punyai banyak kelemahan, di antaranya resistensi vektor, pen cemaran lingkungan dan biaya yang besar Oleh karena itu di-
perlukan pengembangan alternatif cara pengendalian yang lebih baik.
Lebih dan sepuluh tahun yang lalu WHO telah mengem-bangkan beberapa cara pengendalian dengan menggunakan jasad hidup, di antaranya yang mendapat perhatian paling besar ialah penggunaan Bacillus thuringie 11–14. B. thuringie H–14 bekerja sebagai racun perut dan hanya efektip untuk stadium jentik Cara ini aman untuk serangga-bukan-sasaran termasuk ulat sutera dan serangga bermanfaat lain, serta aman pula untuk manusia dan binatang bertulang belakang . Meskipun ke mampuan membunuh jentik hanya antara dua atau tiga hari, tetapi aplikasinya cukup sekali per minggu, atau tiap dua minggu sekali tergantung dan kondisi tempat berkembang biak nyamuk sasaran6.
Di Indonesia, B. tliuri H-14 formulasi cair kental (Teknar™) dengan dosis 1.1–2.3kg/ha dengan aplikasi minggu-an, berhasil baik untuk mengendalikan An. sundaicus. Karena uji coba yang dilakukan oleh Schaeer dan kawan-kawan masih ter-batas, baik ditinjau dari besarnya contoh maupun metodologinya, maka uji coba B. r/:uringiensis H-14 untuk pengendalian An, sundaicus masih penlu dilanjutkan. Uji coba kali mi dilakukan di pantai Banyuwangi/Jawa T,mur dan Jembrana/Bali, dengan berbagai formulasi bahan mengandung B. tl,uri H-14 dengan metodologi berbeda-beda. Tujuan uji coba adalah untuk mengetahui efikasi yang diukür dan besamya reduksi rata-rata jumlah jentik stadium tiga dan empat per ciduk antara sebelum dan sesudab perlakuan. Kecuali çfikasinya, dalam uji coba ini

diamati pula banyaknya hari setelah perlakuan, di mana kepadat-an jentik dapat ditekan tetap rendah (batas tergolong rendah adalah rata-rata jumlah jentik kurang dari lima ekor per 10 ciduk). BAHAN DAN CARA KERJA
Bahan mengandung B. thuringiensis H–14 yang diuji terdiri dari tiga macam formulasi, yaitu : cair kental Teknar, Bactimos padat butiran kasar dan Bactimos padat bentuk gelang atau briket. Aplikasinya dapat dijelaskan sebagai beriktut : Teknar TM
Uji coba bahan ini dilakukan di pantai Banyuwangi. Di lapangan Teknar dicairkan dengan air, kemudian dengan alat semprot Hand Compression Sprayer larutan disemprotkan di permukaan tempat berkembang biak nyamuk. Bahan Teknar sebanyak 100 ml dicairkan menjadi 8 liter, kemudian disemprotkan di permukaan air dengan merata mencakup Was 200 m2. Perlakuan dilakukan mingguan selama 12 bulan. Penilaian efikasi diperhitungkan dengan menghitung besarnya reduksi rata-rata jumlah jentik stadium tiga dan empat per ciduk antara sebelum perlakuan dengan satu hari sesudahnya. Bactimos formulasi butiran kasar
Uji coba dilakukan di pantai Jembrana. Di lapangan butiran mengandung B. thuringiensis H-I4 langsung ditaburkan di permukaan tempat berkembang biak nyamuk. Bahan yang mengandung 500 g. bahan aktif ditaburkan untuk 10.000 m2 luas permukaan. Pengawasan kepadatan jentik untuk evaluasi dilakukan tiap tiga hari sekali, dengan dua kali survai sebelum perlakuan untuk mengumpulkan data dasar, dan dihentikati setelah kepadatan jentik menjadi tinggi kembali (rata-rata jumlah jentik lima ekor per 10 ciduk). Bactimos briquettes
Uji coba B. thuringiensis H-14 formulasi padat briquettes juga dilakukan di pantai Jembrana/Bali. Di tempat berkembang biak nyamuk ditancapkantonggak-tonggak bambu untuk meng-ikat bahan (briquettes) agar tetap terapung dan tidak dibawa arus. Jarak antara tonggak yang satu dengan lainnya kira-kira tiga meter, sehingga satu briquette, akan mempengaruhi kira-kira 9 m2 luas permukaan. Pengamatan kepadatan jentik untuk evaluasi dilakukan seperti evaluasi bahan Bactimos formulasi butiran kasar seperti tersebut di atas. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Tabel 1. terlihat bahwa Teknar 100 ml/8 liter air yang disemprotkan seluas 200 m2 permukaan, dengan aplikasi mingguan dapat memberikan penurunan rata-rata jumlah jentik per ciduk dengan bermakna. Pada tabel tersebut terlihat bahwa redulcsi paling kecil 76% hanya terjadi dua kali dari 50 kali survai, dengan reduksi rata-rata 92,52%.
label 2. menerangkan bahwa Bactimos formulasi butiran kasar ternyata tidak efektif. Reduksi bermakna hanyaterlihat pada satu hari setelah perlakuan. Enam hari setelah perlakuan kepadatan jentik telah kembali tinggi, yaitu rata-rata jumlah jentik per' 10 ciduk 5,40. Selanjutnya, hingga 24 hari setelah perlakuan kepadatannya selalu tinggi (di atas 29,30).
Sedangkan dengan Bactimos briquettes kejadiannya sangat berbeda. Pada Tabel 2. terlihat bahwa Bactimos briquettes ter-nyata efektif untuk pengendalian An. sundaicus. Sebelum per-
Tabel 1. Hasil Penangkapan Jentik Anopheles sundaicus di Tempat Berkembang Biak Disemprot dengan Teknar dengan Dosis 100 ml/200m2 Permukaan
Jumlah join stadium HI & IV (per ciduk)
No. Tanggal perlakuan Enam jam sebelum
perlakuan Sate hari sesudah
perlakuan
Reduksi I
(%)
1. 17-10-84 2,725 0,353 87,052. 24-10-84 0,953 0,004 99,58 3. 31-10-84 0,956 0,0r0 98,96 4. 7-11-84 2,297 0,036 98,45 5. 14-11-84 1,872 0,033 98,54 6. 21-11-84 1,825 0,019 98,96 7. 28-11-84 1,379 0,041 97,10 8. 5-12-84 2,244 0,026 98,85 9. 12-12-84 2,105 0,021 99,01 10. 19-12-84 0,165 0,000 100,00 11. 26-12-85 0,950 0,000 100,00 12. 2- 1-85 0,100 0,000 100,00' 13. 9- 1-85 0 573 0,000 100,00 14. 16- 1-85 0,113 0,000 100,00 15. 23- 1-85 0,825 0,000 100,00 16. 30- 1-85 1,125 0,000 100,00 17. 6- 2-85 3,037 0,042 98,63 18. 13- 2-85 0,450 0,024 94,94 19. 20- 2-85 0,255 0,061 80,69 20. 27- 2-85 0,098 0,030 76,56 21. 6- 3-85 1,128 0,000 100,00 22. 13- 3-85 0,093 0,004 95,87 23. 20-•3-85 0,363 0,000 100,00 24. 27- 3-85 0,611 0,092 86,91 25. 3-_ 4-85 0,359 0,071 83,58 26. 10- 4-85 0,815 0,000 i 100,00 27. 17- 4-85 0,765 0,080 90,53 28. 24- 4-85 0,544 0,109 83,30 29. 1- 5-85 0,208 0,065 76,21 30. 8- 5-85 0,600 0,000 100,00 31. 15- 5-85 0,247 0,008 96,86 32. 22- 5-85 0,054 0,000 100,00 33. 29-5-85 . 0,247 0,007 97,24 34. 5- 6-85 0,021 0,000 100,00 35. 42- 6-85 0,264 0,000 100,00 36. 18- 6-85 1,194 0,000 100,00 37. 26- 6-85 3,921 0,004 98,94 38. 3- 7-85 1;211 0,020 98,31 39. 10- 7-85 0,183 .0,000 100,00 40. 17- 7-85 0,960 0,000 100,00 41. 24- 7-85 1,387 0,000 100,00 42. 31- 7-85 0,350 0,000 100,00 43. 7- 8-85 0,388 0,000 100,00 44. 14- 8-85 0,008 0,000 100,00 45. 21- 8-85 0,004 0,000 100,00 46. 28- 8-85 0,053 0,005 91,38 47. 4- 9-85 1,980 0,011 99,45 48. 11- 9-85 0,510 0,021 96,08 49. 18- 9-85 0,530 0,000 100,00 50. 25- 9-85 1,810 0,000 100,00
lakuan rata-rata jumlah jentik stadium tiga dan empat per 10 ciduk adalah 13,10. Kepadatan jentik ini hingga 21 hari setelah perlakuan dapat ditekan tetap rendah. Baru pada hari ke 24 setelah perlakuan, kepadatannya kembali tinggi, yaitu rata-rata 5 ekor per 10 ciduk.
Hasil seperti tersebut di atas mungkin dapat diterangkan sebagai berikut : jentik An. sundaicus hidupnya di permukaan air. Jentik tersebut makan jasad apa saja_termasuk spora/kristal
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 13

Tabel 2. Hasil Penangkapan Jentik Anopheles sundaicus di Tempat Berkembang Biak Ditaburi Bactimos Butiran Kasar dan di Tempat Berkembang Biak Diberi Bactimos briquettes.
No. Tanggal Han sebelum/ sesudah perlakuan
Bactimos butiran lunar 500 gr/
Bactimos briquettes. Satu
10.000 m2 briquette /9 m2
1. 23-10-84 -6 14,30 6,50 2.
26-10-84
-3 Perlakuan
38,00 Perlakuan
19,70 Perlakuan
3. 30-10-84 +1 0,20 4,20 4. 1-11-84 +3 5,40 1,805. 5-11-84 +6 59,50 0,106. 7-11-84 +9 29,30 0,40 7. 10-11-84 +12 53,30 0,308. 16-11-84 +16 42,00 1,409. 19-11-84 +19 50,30 1,9010. 22-11-84 +22 56,00 1,1011. 24-11-84 +25 44,60 5,00
Keterangan : – Jumlah jentik yang dihitung hanya stadium III dan IV awal. – Jumlah jentik dinyatakan dengan rata-rata jumlah jentik per 10 ciduk. putih telur B. thuringiensis. Di dalam lambung jentik kristal putih telur tersebut akan dilarutkan menjadi molekul yang lebih kecil dan akan meracuni atau merusak jaringan lambung jentik. Medium Bactimos formulasi butiran kasar, karena berat, akan cepat membawa spora/kristal putih telur B. thuringiensis H-14 turun ke dasar tempat berkembang biak nyamuk, hingga tak termakan oleh jentik. Lain halnya dengan formulasi cair kental dari Teknar. Bahan Teknar yang dicairkan dengan air, bila di-semprotkan di tempat berkembang biak nyamuk, akan berada di permukaan selama dua hingga tiga hari. Jadi dalam waktu dua/tiga hari spora/kristal putih telur B. thuringiensis H-14 akan melayang-layang di permukaan air, sehingga ada kemungkinan besar termakan oleh jentik An. sundaicus. Meskipun daya bunuh-nya hanya dua/tiga hari, tetapi karena waktu diperlukan untuk perkembangan jentik kira-kira 8 hingga 10 hari, aplikasinya cukup dilakukan mingguan atau sekali dalam seminggu, karena dengan aplikasi yang berikut, jentik stadium tiga dan empat awal akan terbunuh (jentik stadium empat akhir akan tetap hidup). Meskipun cara penggunaannya tergolong sederhana, tetapi untuk mendapatkan dosis yang ditentukan ada kendalanya, yaitu kesulitan dalam penyemprotan. Penyemprot dapat berjalan cepat dengan mudah di tempat dangkal, tetapi agak sulit di tempat dalam dan sangat menyulitkan apabila dasar tempat perindukan (tempat berkembang biak) tanahnya letnbek atau berlumpur. Dalam operasi penyemprotan akan lebih baik apabila tersedia alat transport, sehingga kecuali memudahkan, penyemprotan dapat menyeluruh hingga di tempat yang dalam.
Dari segi lamanya daya bunuh, Bactimos briquettes adalah paling baik, karena cara ini dapat menekan kepadatan jentik tetap rendah selama 21 hari. Tetapi operasinya kurang praktis, karena kita harus memasang tonggak dan mengikat briquettes tersebut. Hal ini kecuali tidak praktis juga menarik perhatian angk-anak untuk merusaknya.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil uji coba di atas dapat disimpulkan bahwa:
bahan mengandung Bacillus thuringiensis H-14 yang sekarang telah diproduksi dan beredar di pasaran dengan berbagai formu-lasi (cair kental, padat butiran kasar dan padat briquettes), untuk pengendalian jenti k An. sundaicus yang tempat berkembang biaknya di genangan air payau, masih mempunyai banyak kelemahan yang perlu'diperbaiki. Perbaikan yang diharapkan untuk pengendalian jentik An. sundaicus ialah agar bahan yang mengandung B. thuringiensis H-14 mempunyai daya bunuh cukup lama dan dengan cara operasi yang sederhana.
Dari tiga formulasi bahan yang diuji hasilnya sebagaj berikut : 1) B. thuringiensis H-14 formulasi padat butiran kasar (granula) tidak efektif untuk pengendalian jentik Anopheles sundaicus. 2) B. thuringiensis H-14 formulasi cair kental (liquid) dapat di-gunakan dengan hasil baik, apabila aplikasinya mingguan (masih perlu diperbaiki, karena efisien balk biaya maupun tenaga). 3) B. thuringiensis H-14 formulasi padat briquettes cukup baik, tetapi tidak praktis.
KEPUSTAKAAN
1. Sundararaman S, RM Soeroto, M Siran. Vectors of Malaria in 'Mid Java. Indian Journal of Malariology. 1957, 11, 4.
2. Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Departemen Kesehatan, Vektor Malaria di Indonesia. 1985.
3. Soemarto, Santiyo, Zubaedah, Bambang Ristianto and Kadarusman. Penelitian Bionomik Anopheles sundaicus (Rodenwaldt) betina di Desa Cibalong (Mekarsari dan karyawamukti), Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Propinsi .jawa Barat kumpulan Makalah Seminar Parasitologi Nasional ke II, 24-27 Juni 1981, Jakarta.
4. Kirnowardoyo S, Gambiro PY. Entomological Investigation of an Outbreak of Malaria in Cilacap on South Coast of Central Java, Indonesia During 1985. J Communic. Dis. 1987, 19 (2): 121-7.
5. Rishikesh N, Planning and evaluation of large-scale field trials with microbial control agents. International Colloquium on Intertebrate Pathology, XVth Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 6-10 September 1982, University of Sussex, Brighton, United Kingdom.
6. WHO. Data sheet on the biological control agent Bacillus thuringiensis serotype H-14 (de Barjac 1978). WHO/VBC/79.750.VBC/BCDS/79.01. 1979.
7. Rishikesh N, Burgas HD, Vandekar M. Operational Use of Bacillus thuringiensis Serotype H-14 and Environmental Safety. WHO/VBC/83.871.
8. Schaefer CH, S. Kimowardoyo. An Operational Evaluation of Bacillus thuringiensis Serotype H-14 Against Anopheles sundaicus in West Java, Indonesia. WHO/VBC/84.896. 1984.
UCAPAN TERIMA KASIH Disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawt Timur dan Bali atas perkenannya sehingga uji coba ini dapat berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Bidang P3M beserta stiff dari kedua propinsi tersebut di atas, atas segala bantuannya untuk kelancaran jalannya uji coba. Tidak lupa kami ucapkan terima kaSih pula kepada semua staf dari Dinas Kesehatan kabupaten Banyuwangi dan Jembrana yang telah membantu kegiatan pelaksanaan uji coba hingga selesai.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 14

Efikasi Sabun Repelen Mengandung Deet dan Permethrin
untuk Perlindungan Gangguan Nyamuk
Santiyo Kirnowardoyo*, Pranoto Supardi**, Bambang Praswanto** *Medical Entomologist, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan R.I., Jakarta **Medical Entomologist,Dit. Jen. PPM dan PLP, Departemen Kesehatan R.I., Jakarta
Abstract
Field trial was conducted to test the efficacy of a repellent soap containing deet and permethrin. The soap's ability to repel Anopheles hyrcanus, Mansonia uniformis and Mansonia annulifera was evaluated. The field test, was done at Marunda/Cilincing, coastal area of Jakarta. The trial indicated that the repellent soap could reduce the occurence of mosquitoes landing and biting with an average of more than 90%, and with very satisfactory residual effect of a least eight hours.
PENDAHULUAN
Indonesia, yang terletak di daerah tropis sangat kaya dengan berbagai jenis serangga, baik yang bermanfaat atau yang merugikan manusia. Nyamuk adalah golongan serangga yang merugikan kehidupan manusia, baik karena peranan- nya dalam penularan beberapa penyakit maupun sebagai pengganggu kenyamanan. Di Indonsia, penyakit ditularkan nyamuk seperti malaria, demam berdarah dengue dan demam kaki gajah masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, yang pemberantasannya masih diprioritaskan oleh pemerintah. Meskipun telah banyak dilakukan upaya pemberantasan untuk melindungi masyarakat dari malaria; tetapi bagi masyarakat tertentu seperti anggota ABRI yang sedang tugas operasional, penebang kayu di hutan, penyadap pohon karet serta orang-orang yang karena tugasnya mempunyai risiko tertular malaria, uji coba perlindungan perorangan bagi mereka masih diperlukan.
Sejak akhir tahun 70-an, penelitian pengembangan cara perlindungan perorangan terhadap nyamuk dan serangga penghisap darah lain telah dimulai. Bahan kimia yang mungkin digunakan oleh sebagian besar masyarakat di masa depan ada-lah piretroidi . Kelambu yang dipoles (impregnated bed-net) dengan permethrin memberikan perlindungan yang lebih baik untuk pengendalian Anopheles daripada kelambu biasa2. Pakaian yang disemprot dengan permethrin dikombinasi dengan deet yang langsung disemprotkan di kulit, sangat efektif untuk melindungi pemakai terhadap gangguan Aedes
taeniorhynchūs Wiedemann3. Sedangkan sabun yang me-ngandung , deet dan permethrin, bila digosokkan di kulit, sangat efektif untuk melindungi pemakai dari gangguan berbagai nyamuk untuk paling tidak selama empat jam4.
Pada akhir tahun 1986, dilakukan uji efikasi sabun repelen yang mengandung deet dan permethrin di Jakarta. Uji efikasi di lapangan dapat berlangsung atas bantuan PADA (Program for Appropriate Technology in Health), suatu badan yang bergerak dalam uji bahan dan, alat yang berkaitan, dengan kesehatan. Penilaian efikasi selain ditinjau dari penurunan jumlah nyamuk yang hinggap atau menggigit subyek studi; dilihat pula dari lamanya perlindungan dari gangguan nyamuk setelah pemakaian sabun repelen.
BAHAN DAN CARA KERJA Uji coba lapangan dilakukan di Ds. Marunda, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara. Seperti daerah pantai Laut Jawa yang lain, Marunda adalah daerah datar dengan ketinggian kurang satu meter dari permukaan laut. Sebagian besar lahan diman-faatkan untuk tambak, sedang sebagian lainnya adalah sawah berawa. Perumahan terkumpul padat dalam kelompok dengan keadaan sanitasi yang belum dapat dikatakan baik.
Bahan yang diuji efikasinya adalah sabun repelen (bentuk seperti sabun mandi biasa) yang mengandung 20% deet (Diethyl toluamide) dan 0,5% permethrin (Simmons Nominees Pty. Ltd. Victoria, Australia).
Sebagai nyamuk sasaran adalah Anopheles dan Mansonia, yaitu genera yang dapat menularkan malaria dan demam kaki
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 15

gajah. Uji efikasi ini dilakukan untuk menjajaki kemungkinan penggunaannya oleh masyarakat.
Jumlah subyek studi 24 orang, dibagi menjadi dua ke-lompok, yaitu kelompok pemakai sabun (P) dan kelompok kontrol (K). Subyek studi bertindak sebagai penangkap nyamuk sekaligus sebagai umpan untuk menarik nyamuk. Ini berarti bahwa hanya nyamuk yang hinggap pada dirinya yang harus ditangkap. Penangkapan nyamuk hanya dilakukan di alam -luar (di luar rumah). Jarak antara subyek studi yang satu dengan lainnya kira-kira lima meter, kedudukannya berselang seling antara subyek pemakai sabun (P) dengan kontrol (K). Kedudukan subyek studi pada waktu melakukan penangkapan nyamuk dapat dilihat pada bagan di bawah :
P1 K1 P2 K2 P3 K3
K6 P6 K5 P5 K4 P4
P7 K7 P8 K8 P9 K9
K12 P12 K11 P11K10 P10
Pada waktu melakukan penangkapan nyamuk, subyek studi mengenakan baju lengan pendek dan menggulung celana-nya hingga lutut. Kelompok kontrol hanya membasahi tangan dan kakinya dengan air dan dibiarkan kering secara alami, sedang kelompok pemakai sabun setelah tangan dan kakinya dibasahi, dengan air, kemudian digosok dengan sabun hingga rata dan dibiarkan kering secara alami pula. Untuk menghindari bias yang disebabkan perbedaan daya tarik subyek terhadap nyamuk, maka tiap subyek pernah sebagai subyek pemakai sabun dan pernah pula sebagai kontrol. Besarnya penurunan rata-rata jumlah nyamuk hinggap atau menggigit (dalam persen) diperhitungkan dari perbandingan antara data data rata-rata basil penangkapan dengan data setelah subyek memakai sabun. Perbedaan hari penangkapan dikoreksi dengan hasil penangkapan subyek kontrol. Pada waktu penangkapan untuk mengumpulkan data dasar, semua subyek studi hanya membasahi tangan dan kakinya dengan air, tanpa menggosbknya dengan sabun. Survai (penangkapan nyamuk) untuk evaluasi dilakukan sebagai berikut :
Blok Subyek kontrol Subyek pemakai sabun
Data dasar Perlakuan kontrol Data dasar Perlakuan mema-
kai sabun A Hari I Hari II Hari I Hari II
12/X 12/X 12/Y 12/Y B Hari III Hari IV Hari III Hari IV 12/Y 12/Y 12/X 12/X
HASIL DAN PEMBAHASAN Pada label 1 terlihat bahwa rata-rata jumlah nyamuk
hinggap atau menggigit per orang antara data dasar dengan perlakuan kontrol dari subyek kontrol tidak ada beda nyata, sehingga data perlakuan memakai sabun dapat dibandingkan dengan data dasar subyek pemakai sabun (beda hari tak mem-pengaruhi hasil survai). Pada tabel ini terlihat bahwa ada pe-nurunan sangat bermakna antara data dasar dengan data per-lakuan dari subyek pemakai sabun. Untuk Spesies Anopheles hyrcanus dari rata-rata jumlah nyamuk .per subyek 3,14 (69/22) menjadi 0,14 (3/22), berarti ada penurtnan sebesar
95,54%. Mansonia uniformis dari rata-rata per subyek 13,23 (291/22) turun menjadi 0,41 (9/22) dengan penurunan 96,90%, sedang untuk Mansonia annulifera dari rata-rata 14,27 (314/22) menjadi 0,95 (21/22) berarti ada penurunan 93,34%.
Bila ditinjau dari data perlakuan memakai sabun dengan perlakuan kontrol, pada Tabel 1 juga terlihat adanya perbedaan yang menyolok. Pada tabel ini terlihat bahwa untuk Anopheles hyrcanus rata-rata jumlah nyamuk per subyek perlakuan memakai sabun 0,14 (3/22), sedang perlakuan kontrol 6,68 (147/22) dengan perbedaan 97,70%. Untuk Mansonia uniformis ada perbedaan sebesar 99,74%, sedang Mansonia annulifera perbedaannya 99,64%.
Dilihat dari lamanya perlindungan akibat memakai sabun, pada Tabel 2 terlihat, bahwa paling tidak pemakai sabun se-lama 8 jam dilindungi dari gangguan nyamuk. Untuk Ano-pheles hyrcanus, delapan jam setelah subyek memakai sabun, bila dibandingkan dengan kontrol ada perbedaan sebesar 95,24% (1/21), untuk Mansonia uniformis 50% (2/4), sedang Mansonia annulifera sebesar 68,43% (6/19).
Dari segi efikasi, sabun repelen yang mengandung deet dan permethrin sangat efektif untuk melindungi pemakai dari gangguan nyamuk. Cara perlindungan dengan mengguna-kan sabun repelen ini sangat praktis, karena mudah dibawa dan mudah digunakan di lapangan. Cara ini memberikan perlindungan lebih lama bila dibandingkan dengan cara yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan minyak kayu putih, minyak sereh, balsem dan lain sebagai- nya yang hanya memberikan perlindungan selama beberapa jam. Berdasarkan pengamatan selama uji coba dilakukan, tidak ada subyek studi yang menunjukkan tanda-tanda ke-racunan. Tetapi meskipun demikian, karena sabun ini me-ngandung jnsektisida (meskipun hanya permethrin dosis rendah) dan langsung digosokkan pada kulit, maka pemakaian-
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 16

Tabel 1. Jumlah Nyamuk Ditangkap Dalam Survai Penilaian Efikasi Sabun Repelen Mengandung Deet dan Permethrin di Marunda - Cilincing - Jakarta Tahun 1986.
Keterangan. A.h. = Anopheles hyrcanus M.u. = Mansonia uniformis M.a. = Mansonia annulifera nya masih perlu dibatasi. Sabun repelen ini bukan untuk konsumsi masyarakat umum, tetapi dapat digunakan oleh masyarakat khusus, seperti anggota ABRI yang sedang men-jalankan tugas operasional serta orang-orang yang berkaitan dengan tugasnya mengandung risiko mendapat gangguan nyamuk. KESIMPULAN
Sabun repelen yang mengandung 20% deet dan 0,5% permethrin sangat efektif ūntuk melindungi pemakai dari gangguan atau gigitan nyamuk. Setelah orang menggosok tangan dan kakinya dengan sabun rata-rata jumlah nyamuk hinggap/menggigit per orang turun sebesar lebih dari 90%. Lamanya perlindungan dari gangguan nyamuk paling tidak selama 8 jam, sehingga bagi mereka yang karena pekerjaan- nya mempunyai risiko digigit nyamuk selama satu malam
(satu hari), cukup satu kali menggosok tangarr dan kakirtya dengan sabun repelen. Sabun ini baik dan praktis digunakan oleh anggota1 ABRI yang sedang menjalankan tugas operasi-onal, penebang kayu di hutan, penyadap getah karet dan orang-orang yang dalam pekerjaannya mengandung risiko digigit nyamuk.
KEPUSTAKAAN
1. Elliot M, Janes NF, Patter. The future of pyrethroids in insect control. Ann. Rev. Entomol. 1979; 23 : 443-69.
2. Darriet F, Robert V, Vien NT, Garnevale P. Evaluation of the efficacy of permethrin impregnated intact and perforated mosquito nets against vectors of malaria WHO/VBC/84.899. 1984.
3. Schreck CE, Halle DG, Kline DI. The efectiveness of the permethrin and deet, alone or in combination for protection against Aedes taeniorhynchua Am J Trop Med Hyg. 1984; 33 : 725-30.
4. Yap HH. Efectiveness of soap formulation containing deet and permethrin as personal protection against outdoor mosquitoes in Malaysia. J Am Mosq Control Assoc 1986; 2 (1) : 63-7
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 17

Tabel 2. Jumlah Nyamuk Ditangkap Dipisahkan Jam Per Jam dalam Survai Penilaian Efikasi Sabun Repelen Mengandung Deet dan Permethrin di Marunda – Jakarta Tahun 1986.
Keterangan: A.h. = Anopheles hyrcanus. M.u. = Mansonia uniformis Ma. = Mansoniaannulifera.
UCAPAN TERIMA KASIH Terimakasih disampaikan kepada Sdr. Camat Cilincing serta para Pamong Desa Marunda atas perkenannya, sehingga uji coba lapangan ini dapat dilakasanakan. Terima kasih juga disampaikan kepada masya-
rakat dan aparat keamanan desa yang telah membantu kelancaran pelakasanaan uji coba ini. Akhirnya tidak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada PATH yang telah mengusahakan contoh sabun dan membiayai uji coba lapangan.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 18

Hubungan Beratnya Penyakit Malaria Falciparum dengan
Kepadatan Parasit pada Penderita Dewasa
Dr. Emiliana Tjitra MSc. Pusat Penelitian Penyakit Menular, Baden Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan R.I. Jakarta
ABSTRAK
Penelitian prospektif dari 49 penderita dewasa malaria falciparum telah dilakukan untuk mengetahui manifestasi klinis malaria dan mencari variabel-variabel yang berhubungan dengan beratnya penyakit berdasarkan kepadatan parasit aseksual. Dua di antara 8 penderita parasitemia tinggi (> 5%) manifestasi klinisnya ringan dan 9 dari 41 penderita parasitemia rendah (< 5%) bermanifestasi berat : 2 anemia berat, 1 jaundice nyata, 1 perdarahan, 1 shock, dan 4 malaria otak. SGOT pada ke-lompok parasitemia tinggi lebih besar dibandingkan kelompok parasitemia rendah ( p < 0,05 ). Variabel-variabel yang berhubungan langsung'atau tidak langsung terhadap berat-nya penyakit dan kepadatan parasit adalah pemeriksaan SGOT (berkorelasi positif dengan jumlah parasit, SGPT, dan bilirubin), SGPT (berkorerasi positif dengan bili-rubin), bilirubin (berkorelasi positif dengan kreatinin), kreatinin, dan bebas panas (berkorelasi positif dengan bebas parasit). Waktu yang dibutuhkan untuk bebas panas dan bebas parasit oleh penderita parasitemia tinggi lebih lama dibandingkan penderita dengan parasitemia rendah.
PENDAHULUAN
Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmo-dium. Di antara ke empat spesies plasmodium, Plasmodium falciparum mempunyai siklus hidup terpendek di dalam sel hati dan menyerang semua bentuk eritrosit sehingga multiplikasi di dalam darah cepat terjadi. Dalam darah tepi tampak bentuk ring (trofozoit muda) dan gametosit. Sedanglcan bentuk lain umumnya terlihat di pembuluh kapiler alat-alat dalam.
Infeksi ganda pada eritrosit dan infeksi berat sering terjadi, bahkan eritrosit yang terinfeksi dapat mencapai 50%1. Hampir semua penderita malaria falciparum berat mempunyai parasit dalam darah yang tinggi.l z, 4. Komplikasi malaria (malaria perniciosa) dapat terjadi jika > 5% eritrosit terinfeksi, 10% dari sel yang terinfeksi mengandung > 1 parasit, atau jika banyak bentuk sison di pembuluh darah parifers. Komplikasi daoat terjadi walaupun eritrosit yang terinfeksi kelihatannya ringan karena terdapatnya variasi biologi, sebagian penderita dengan kepadatan parasit darah rendah dapat menderita sakit berat seperti malaria otak3 .
Karena adanya variasi biologi tersebut maka dilakukan penelitian prospektif untuk mengetihui manifestasi klinis malaria dan mencari variabel-variabel yang berhubungan
* Dibacakan pada Pertemuan llmiah Penyakit Menular, Jakarta 21–24 Maret 1988.
dengan beratnya penyakit berdasarkan kepadatan parasit dalam darah. BAHAN DAN CARA
Penelitian prospektif pada penderita malaria falciparum dewasa telah dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 1984, di R.S. Chonburi, Thailand.
Subyek Kasus yang diteliti adalah penderita dewasa yang berumur
lebih dari 12 tahun dan mempunyai bentuk .parasit aseksual dalam darah, diperiksa oleh dokter yang bertugas di 'poliklinik rawat jalan atau di ruang gawat darurat .dan dirawat.
Pemeriksaan Dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut:
1) Riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik.. 2) Pemeriksaan parasitologik dengan sediaan hapus darah tipis dan tebal untuk mengetahui adanya parasit bentuk aseksual. Sediaan darah tebal diwarnai dengan cara Field dan sediaan darah tipis dengan cara Wright. Dihitung jumlah parasit asek-
sual per 1000 eritrosit dari sediaan darah tipis atau per 200 lekosit dari sediaan darah tebal. Jumlah parasit per mm3 di-
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 19

perkirakan dengan rumus (lihat annex). Pemeriksaan parasi-
tologik dilakukan setiap 12 jam yaitu pukul 7 pagi dan pukul 7 malam, sampai bentuk parasit aseksual tidak diketemukan, kemudian setiap hari pukul 7 pagi selama masa perawatan. 3) Pemeriksaan laboratorium rutin untuk hematokrit, jumlah lekosit, pemeriksaan urin dan faeces. 4) Kimia darah untuk fungsi hati dan fungsi ginjal: ,SGOT, SGPT, bilirubin, kreatinin, BUN, elektrolit, dan gula darah. 5) Pemeriksaan lain-lain pada keadaan penderita sebagai berikut : a) Kesadaran menurun, dilakukan pungsi lumbal untuk pe-ngukuran tekanan dan pemeriksaan cairan otak (jumlah sel, konsentrasi gula dan protein serta mikroorganismenya). b) diare, dilakukan pemeriksaan faeces secara mikroskopis. c) perdarahan, dilakukan pemeriksaan darah untuk trombosit dan koagulogram. d) anemia nyata (Ht < 20%), dilakukan pemeriksaan darah lengkap tērmasuk morfologi sel darah. e) jaundice nyata bilirubin > 8mg%), dilakukan pemeriksaan serologik untuk mengetahui adanya infeksi hepatitis virus. 6) Pemeriksaan suhu tubuh setiap empat jam (pukul 2, 6, 10, 14, 18 dan 22). 7) Semua penderita diobservasi secara klinis dan parasitologis untuk mengetahui waktu bebas panas dan bebas parasit aseksual.
Pengelompokan Penderita dikelompokkan berdasarkan kepadatan parasit
aseksual dalam darah tepi pada waktu masuk rumah sakit. 1) Kelompok parasitemia < 5%. 2) Kelompok parasitemia > 5%. Beratnya penyakit dilihat dari manifestasi klinis yang ada, dapat sebagai : 1) malaria ringan, dengan gejala klinis ringan. 2) muntah-muntah berat, dengan muntah-muntah berulang sehingga sulit untuk makan dan minunl. 3) malaria otak, dengan penurunan kesadaran tanpa adanya penyakit susunan saraf lain. 4) anemia berat, dengan nilai Ht 20% tanpa riwayat penyakit darah, tukak lambung atau infeksi cacing tambang. 5) jaundice nyata, dengan kadar bilirubin darah > 8 mg% tanpa penyakit hati lain. 6) shock, dengan tanda-tanda kulit tubuh dingin, berkeringat, denyut nadi lemah, cepat atau perbedaan tekanan sistole dan diastole < 20 mmHg. 7) perdarahan, inisalnya: epistaksis.
Pengobatan 1) Diberikan kina sulfat 600 mg, peroral, setiap 8 jam, se- lama 7 hari, pada penderita parasitemia < 5% dengan mani-festasi klinis ringan. 2) Diberikan kina dihidroklorida 600 mg. yang diencerkan dalam 100 ml dekstrosa 5%, secara intravena, selama 2 jam, setiap 8 jam sampai pengobatan peroral memungkinkan, yaitu dengan kina sulfat 600 mg, setiap 8 jam sampai total berjumlah 21 dosis.
Pengobatan ini untuk kelompok parasitemia > 5% dan penderita dengan manifestasi klinis berat walaupun parasitemia <5%, serta penderita dengan muntah-muntah berat.
Analisa data 1) Manifestasi klinis antara kelompok dibandingkan dengan menggunakan Fisher dan t–test. 2) Untuk mengetahui variabel-variabel yang berhubungan dengan beratnya penyakit dan kepadatan parasit, dilakukan test korelasi. HASIL
Dari 49 penderita (21 wanita dan 28 pria) dengan umur antara 14–62 tahun ( = 31 ± 4,1 th ), 41 kasus (84%) dengan parasitemia < 5% dan 8 kasus (16%) dengan parasitemia > 5%. Sedangkan karakteristik antara kedua kelompok tersebut tidak berbeda bermakna (tabel 1). Tabel 1. Karakteristik dari 49 penderita malaria falciparum dewasa.
Karakteristik Kelompok parasitemia <5%
Kelompok parasitemia > 5%
Jumlah penderita 41 8
Sex L:P 23 : 18 5 : 3 Umur (tahun) Riwayat pernah men-
* 29,9 ±3,2
* 26;1 ±5,3
derita malaria Penduduk daerah
24 (59%)
5 (63%)
endemis Lama demam sebelum
14 (34%)
2 (25%)
masuk R.S. (hari) 5,0 ± 0,6 3,9 ± 1,0
Keterangan : * mean Demam, nyeri kepala dan mual merupakan gejala klinis
yang paling sering dijumpai pada kedua kelompok tersebut ( > 75%) gejala klinis di antara kedua kelompok tersebut tidak berbeda bermakna (tabel 2). Walaupun demikian, muntah, dehidrasi, pucat, jaundice dan splenomegali lebih sering dijumpai pada penderita kelompok parasitemia > 5%, juga suhu tubuh kelompok parasitemia > 5% lebih panas dibandingkan kelompok parasitemia < 5%.
Pada tabel 3 dapat dilihat hasil pemeriksaan laboratorium kedua kelompok tersebut, hanya jumlah parasit serta SGOT yang berbeda bermakna (p < 0,05). Tiga penderita dari ke-. lompok parasitemia < 5% mempunyai nilai Ht < 21%, satu di antaranya menderita malaria otak (Ht = 19%) dan yang lainnya (dua penderita) dengan Ht = 16%. Dari hasil pemeriksaan bili-rubin, dua penderita mempunyai nilai > 8 mg%, satu pada ke-lompok parasitemia < 5% (bilirubin = 16,8 mg%), dan yang. lainnya pada kelompok parasitemia > 5% dengan bilirubin 14,4 mg% (tabel 4).
Cukup 'banyak penderita datang dengan muntah-muntah berat (13 pada kelompok parasitemia < 5%, 5 pada kelompok parasitemia > 5%). Penderita-penderita tersebut dikelompokkan tersendiri karena memerlukan penanganan khusus dengan pengobatan dan cairan intravena •untuk mencegah terjadinya shock karena telah didapat 1 kasus shock walaupun parasitemia < 5%. Perdarahan yang terjadi pada penderita parasitemia < 5% berupa epistakis, bukan disebabkan karena kelainan darah. Sedangkan penurunan kesadaran dari ke empat kasus malaria otak berupa somnolen sampai stupor.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 20

Tabel 2. Gejala klinis dari 49 penderita malaria falciparum dewasa pada waktu masuk R.S.
Gejala Kelompok parasitemia <5%
Kelompok parasitemia > 5%
Panas 41 (100)* 8 (100)
Sakit kepala 40 ( 98) 7 ( 88) Mual 35 ( 85) 6 ( 75) Muntah 29 ( 71) 6 ( 75) Diare 17 (42) 1 ( 13) Penurunan kesadaran 4 ( 10) 0 Suhu tubuh **38,5 t 0,3 38,7 ± 0,5 Dehidrasi 20 ( 49) 5 ( 63) Pucat 7 ( 17) 5 (63) Jaundice 7 (17) 5 ( 63) Hepatomegali 2. ( 51) 3 ( 38) Splenomegali 13 ( 32) 3 ( 38)
Keterangan: * persen ** mean ± SE Tabel 3. Hasil pemeriksaan laboratorium dari 49 penderita malaria
falciparum dewasa pada waktu masuk R.S.
Variabel Kelompok parasitemia <5%
Kelompok parasitemia >5%
Hematokrit (%) Lekosit / mm3** Jumlah parasit/mm3** SGOT (IU / L) SGPT (IU / L) Bilirubin (mg %) Kreatinin (mg %) BUN (mg %) Natriurn (mEq / >r) Kalium (mEq / L) Gula darah (mg %)
* 34,3 ± 1,9 3,8 ±0,05 4,5 ±0,1
33,3 ±4,8 32,3 ±4,9 2,1 ±0,7 1,1 ±0,1
20,4 ±2,9 131,3±1,5 3,5 ±0,2 110,5 ±8
35,6 ±2,5 3,9 ±0,06
5,5 ±0,1*** 64,1 ±12,6***
41,4 ±5,2 4,1 ± 1,6 1,2 ±0,2
22,0 ±4,2 131,9 ± 3,0
38± 0,1 98 t 6,7
Keterangan: * mean ± SE ** log *** p <0,05 Tabel 4. Manifestasi Minis dari 49 penderita malaria, falciparum dewasa
pada waktu masuk R.S.
Manifestasi klinis Kelompok parasitemia <5%
Kelompok parasitemia > 5%
Ringan 19 (46%) 2 (25%) Muntah-muntah berat 13 (32%) 5 (63%) Anemia berat 2 ( 5%) 0 Jaundice nyata 1 ( 2%) 1 (12%) Perdarahan 1 ( 2%) 0 Shock 1 (3%) 0 Malaria otak 4 (10%) 0
Total 41 (100%) 8 (100%)
Waktu yang dibutuhkan untuk 'bebas panas dan bebas
parasit dengan pengobatan kina lebih lama pada kelompok parasitemia > 5% dibandingkan kelompok parasitemia < 5%
walaupun tidak berbeda bermakna (tabel 5). Tabel 5. Hasil pengobatan dengan ldna sulfat atau kina dihidroklorida
dari 49 penderita malaria falciparum dewasa.
Variabel Kelompok parasitemia <5%
Kelompok parasitemia>5%
Bebas panas (jam) 53,0 ±8,2 71,1 ± 14,9
Bebas parasit (jam) 59,4 ±5,8 77,1 ±6,9
Keterangan: * mean ±SE Dari tabel 6 ternyata jumlah parasit berkorelasi positif
dengan SGOT (p < 0,05) dan bebas parasit (p <0,01), SGOT berkorelasi positif dengan SGPT (p < 0,01) dan bilirubin (p < 0,01), SGPT berkorelasi positif dengan bilirubin (p < 0.01), bilirubin berkorelasi positif dengan kreatinin (p < 0,05), serta bebas panas berkorelasi positif dengan bebas parasit (p < 0,05). Tabel 6. Analisa korelasi di antara bermacam-macam variabel dari 49
penderita malaria falciparum dewasa.
Variabel SCOT SGPT Biliru•- bin
Kreati- nin
Bebas panas
Bebas parasit
Jumlah
parasit 0,298* 0,101 0,214 0,021 0,211 0,424** SGOT 0,705** 0,631** 0,268 0,019 0,189 SGPT 0,617** 0,010 -0,005 0,147 Bilirubin 0,365* 0,207 0,183 Kreatinin Bebas 0,206 0,023
panas 0,306*
Keterangan: * = p < 0,05 ** = p < 0.01
Pada diagram 1 dapat dilihat distribusi dari 49 penderita
berdasarkan jumlah parasit dan nilai SGOT. Sedangkan pada diagram 2 berdasarkan jumlah parasit dan bebas parasit. PEMBAHASAN
Pada penelitian ini terdapat 2 kasus penderita parasitemia tinggi (> 5%) dengan manifestasi klinis rngan, ini mungkin disebabkan karena mempunyai toleransi klinis parasit yang tinggi. Seperti dtketahui, kekebalan malaria berhubungan dengan 2 komponen: toleransi klinis dan aktivitas parasitidal. Toleransi klinis terhadap parasitemia dapat sangat menakjub-kan, sediaan hapus darah dapat menunjukkan densitas parasit yang tinggi tetapi penderita tersebut masih dapat bekerja biasa. Pada kasus-kasus tersebut komponen klinis dari kekebalan telah jauh berkembang sedangkan komponen parasitisidal tidak berkembang6.
Muntah-muntah merupakan gejala yang sering ditemui dan kadang-kadang merupakan petunjuk beratnya keadaan klinis dari penyakit malaria falciparum akut. Tetapi muntah-muntah tersebut tidak dapat dihubungkan dengan beratnya atau lamanya sake. Dalam penelitian ini kasus muntah-
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 21

Diagram 1. Distribusi Bari 49 penderita dewas malaria falciparum ber-dasarkan jumlah parasit dan nilai SCOT.
Kepadatan parasit (log jumlah parasit / mm3) r = 0.298 (p <0.05) Diagram 2. Distribusi dari 49 penderita dewasa malaria falciparum ber-
dasarkan jumlah parasit dan lama bebas parasit. Kepadatan parasit (log jumlah parasit / mm3) r = 0.424 (p <0.01) muntah berat lebih banyak terdapat pada kelompok parasitemia > 5% (63%) dibandingkan kelompok parasitemia < 5% (32%). Jadi muntah-muntah berat dapat merupakan tanda peringatan akan adanya infeksi berat, dan juga merupakan salah satu penyebab dari dehidrasi dan shock selain karena pengeluaran keringat yang terlalu banyak dan berkurangnya cairan yang masuk.
Anemia lebih sering ditemukan pada penderita dengan
densitas parasit tinggi dan hematokrit berkorelasi negatif dengan densitas parasits . Ternyata dalam penelitian ini kasus anemia berat terdapat pada kelompok parasitemia < 5%. Hal ini disebabkan karena beratnya infeksi dan kelainan akibat infeksi tersebut tergantung dari status kekebalan penderita, faktor-faktor nutrisi, infeksi berulang, dan karakteristik genetik dari eritrosit penderita9.
Jaundice tanpa atau dengan hepatomegali, kelainan fungsi hati (SGOT, SGPT, bilirubin dan lain-lain) sering dijumpai pada'malaria falciparum. Pada penelitian ini terdapat penderita jaundice nyata pada kedua kelompok tersebut. Sedangkan SGOT pada kelompok parasitemia tinggi lebih besar dibandingkan kelompok parasitemia rendah (p < 0,05). Juga diketemukan korelasi positif antara jumah parasit dengan SGOT, SGOT dengan SGPT dan bilirubin, SGPT dengan bilirubin, bilirubin dengan kreatinin. Hal ini menunjukkan bahwa SGPT, SGPT, bilirubin dan kreatinin adalah variabel-variabel yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap beratnya infeksi malaria falciparum. Hall dick jugs menemukan korelasi positif antara bilirubin dengan SGPT, kreatinin dengan densitas parasit dan berpendapat bahwa jaundice lebih sering pada penderita sakit berat, sedangkan bilirubin merupakan indeks yang berguna untuk mengetahui fungsi hati dan beratnya penyakit malaria10
Perdarahan pada malaria dapat berbentuk petekiae, epistaksis, dan lain-lain tetapi perdarahan masif jarang terjadi. Pada penelitian ini terdapat satu kasus dengan epistaksis, koagulogram normal, parasitemia < 5% dan trombositopeni. Jadi penyebab epistaksis adalah trombositopeni, karena adanya mekanisme kekebalan yang kebanyakan dijumpai pada infeksi ringan P. falciparum.
Malaria otak adalah bentuk manifestasi klinis yang paling serius. Dalam penelitian ini terdapat 4 penderita malaria otak dengan parasitemia < 5%, satu dengan anemia berat dan se-muanya hidup. Malaria otak biasanya terjadi pada penderita-penderita dengan parasitemia tinggi meskipun kadang-kadang penderita parasitemia ringan datang dalam keadaan koma3. Hal ini mungkin disebabkan karena eritrosit yang terinfeksi parasit pada beberapa penderita lebih lekat dan cenderung menyumbat pembuluh darah kecil otak11
Dari hasil pengobatan dengan kina, terdapat korelasi positif antara bebas parasit dengan densitas parasit dan bebas panas. Hal ini sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk bebas panas dan bebas parasit penderita parasitemia tinggi vang lebih lama dibandingkan penderita parasitemia rendah.
Untuk mendapatkan data yang lebih baik perlu dilakukan penelitian dengan kasus yang lebih banyak disertai dengan aspek imunologi.
KESIMPULAN Malaria berat dapat terjadi pada penderita-penderita
dengan densitas parasit rendah, sebaliknya beberapa penderita dengan parasitemia tinggi dapat bermanifestasi klinis ringan.
SGOT, SGPT, bilirubin dan kreatinin adalah variabel-variabel yang berhubungan langsung atau tak langsung dengan beratnya penyakit berdasarkan kepadatan parasit.
Waktu untuk bebas panas dan bebas parasit lebih lama pada penderita parasitemia tinggi dibandingkan penderita parasitemia rendah.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 22

ANNEX Cara menghitung jumlah parasit aseksual per mm3 darah. A. Dari sediaan hapus tipis darah tepi. Diperkirakan MCV = 90 Jika X = jumlah parasit aseksual per 1000 eritrosit 1 mm3 darah mengandung parasit aseksual = X x Ht (%) x 1.000.000 9 x 1000 Jumlah parasit aseksual dalam 1 mm3 = X x Ht (%) x 1000 B. Dari sediaan hapus tebal darah tepi 9 Jika X = jumlah parasit aseksual per 200 lekosit Jumlah parasit aseksual dalam 1 mm3 = X x jumlah lekosit/mm3 200
KEPUSTAKAAN
1. Stone WJ, Hanchett JE, Knepshield JH. Acute renal insufficiency due to falciparum malaria. Arch Intern Med 1972; 129 : 620.
2. Punyagupta S, Srichailcul T, Nitiyanat P, Petchclai B. Acute pulmonary insufficiency in falciparum malaria: summary of 12 cases with evidence of DIC. Am J Trop Med & Hyg 1974; 23 (4) : 551-9.
3. Hall AP, Karnchanachetanee C, Sonkom P. The management of coma in falciparum malaria. Ann Rep. SEATO Medical-Research Lab 1975a: 224-5.
4. Sheehy TW. Disseminated intravascular coagulation and severe falciparum malaria. Lancet 1975: 516.
5. Macgraith BC. Malaria. In : Adams & Maegraith : Clinical Tropical Diseases, 7th ed. Oxford, London, Edinburgh, Melbourne: Black-well Scient Publ 1980 : 259.
6. Pampana E. The human recipient of the malaria infection. In: A textbook of malaria eradication. 2nd ed. London: Oxford University Press, 1969 : 56-71.
7. Olsson RA, Johnston EH. Histopathologic changes and small bowel absorption, in falciparum malaria. Am J Trop Med & Hyg 1969;18 (3) : 355-9.
8. Hall AP, Doberstyn EB, Sonkom P. Anemia in malaria and the role of blood transfusion. Ann Rep SEATO Medical Research Lab 1975b: 237-40.
9. Perrin LH, Mackey LJ, Miescher PA. The hematology of malaria in man. Seminars in hematology 1982; 19 (2) :70-82.
10. Hall AP, Schneider RJ, Nanakorn A, West HJ. Jaundice in falciparum malaria. Ann Rep. SEATO Medical Research Lab 1975c: 234–6.
11. Hall AP. The treatment of severe falciparum malaria. Trans Roy Soc Trop Med & Hyg 1977; 71 : 367–79.
UCAPAN TERIMA KASIH Disampaikan kepada : 1) Assoc. Prof. Pravan S. MD dan Dr. Tanawat. S atas saran dan petunjuknya. 2) Dr. Anchana. P dan seluruh teman kerja di R.S. Chonburi, Thailand, yang telah melancarkan dan membantu menterjemahkan bahasa Thai. 3) SEAMEO Trop–Med yang telah mensponsori fellowship ini. 4) Depkes RI, Kanwil Depkes NTT yang memberi kesempatan untuk belajar. 5) Badan Litbangkcs, Puslit Penyakit Menular yang memberi kesempatan untuk mengikuti seminar ini. 6) Ibu Dra Hariyani atas saran dan petunjuknya.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 23

Keracunan Pestisida pada Petani di berbagai Daerah di Indonesia
Kusnindar, SKM
Staf Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I., Jakarta PENDAHULUAN
Menurut penelitian, hasil produksi pertanian turun rata-rata sebesar 15% akibat serangan hama yang merusak pertanian) . Untuk mencegah hal tersebut, telah dilakukan berbagai pe-nelitian sampai ditemukannya pestisida. Pestisida merupakan salah satu hasil teknologi modern yang terbukti berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui' peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan sangat berguna untuk memberantas berbagai binatang pengganggu rumah tangga.
Penggunaan pestisida di masa mendatang diperkirakan akan selalu meningkat, yaitu dalam usaha meningkatkan produksi di bidang pertanian, perkelunan dan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, peningkatan ekspor non migas dan pendapatan masyarakat. Juga dalam usaha memberantas penyakit menular, khususnya penyakit yang ditularkan melalui vektor/serangga. Dengan meningkatnya penggunaan pestisida ini, maka akibat yang ditimbulkan juga makin meningkat.
Pestisida organik sintetis terutama golongan organofosfat dan karbamat merupakan bahan kimia yang terutama di-gunakan oleh para petani sejak tahun 1973. Pestisida golongan organoklorin (misal: DDT dan Dieldrin) telah lama di-tinggalkan, mengingat sifatnya yang persisten di lingkumgan. Senyawa pestisida golongan organofosfat dan karbamat lebih toksis daripada golongan organoklorin, tetapi kurang persisten di lingkungan dan mengalami dekomposisi alami yang pendek, sehingga kemungkinan keracunan lebih kecil. PERMASALAHAN
Salah satu masalah kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan di pedesaan di Indonsia dewasa ini .adalah akibat penggunaan bahan kimia pertanian pestisida yang dapat menimbulkan, keracunan akut, sedang atau ringan.
Masalah penggunaan pestisida di Indonsia menyangkut dua hal pokok, yaitu secara kuantitatif: jumlah petard yang sangat banyak, dan secara kualitatif: petani pengguna insektisida
tidak/kurang mengikuti prosedur penggunaan pestisida. Berbagai faktor dapat memperburuk efek samping atau ke-racunan akibat pekerjaan, misalnya rendahnya tingkat pen-didikan petani, disiplin yang kurang, keadaan gizi yang kurang dan pengelolaan yang kurang baik. Penelitian Titi Sari Reno-wati2 mendapatkan bahwa 82% petani penyemprot tidal( pernah mendapatkan petunjuk kerja pada saat `mereka akan menyemprot untuk pertama kalinya.
Dengan melihat besarnya bahaya efek samping penggunaan pestisida, masalah keracunan pestisida pada petani perlu mendapatkan perhatian agar tujuan penggunaan pestisida mencapai sasarannya yakni untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya menjadi malapetaka, khususnya bagi masyarakat petani. PENELITIAN-PENELITIAN YANG DILAKUKAN
I Ketut Winasa meneliti pemanfaatan alat pelindung pada 102 petani bawang merah, ternyata hanya 18 (17,65%) yang memanfaatkannya dengan baik. Secara lebih terperinci ia me-ngemukakan bahwa hanya 2 (1,96%) responden yang me-manfaatkan Kacamata pelindung, 12 (11,76%) memanfaatkan sepatu boot, 18 (17,65%) memanfaatkan sarung tangan, 27 (26,46%) menggunakan masker. Baju lengan panjang diguna-kan oleh 57 (55,88%) responden, celana panjang pada 85 (83,33%) dan topi pelindung pada 99 (97,06%) responden.
Umumnya mereka kurang menyadari perlunya alat-alat pelindung tersebut, karena ternyata hanya 19 (25,53%) di antara 75 petani yang tidak menggunakan masker/pelindung pernafasan yang mengetahui kegunaannya. Sedangkan di kalangan yang tidak menggunakan sarung tangan hanya 20 (23,80%) saja yang benar-banar tahu manfaatnya. Secara keseluruhan, hanya 18 (17,65%) responden yang dinilai baik menggunakan alat pelindung, sedangkan 84 (82,35%) sisanya masih perlu ditingkatkan pengetahuannya. (Tabel 1)
Sugeng Budiono (1985/86)3 telah melakukan pengukuran aktivitas kolinesterase terhadap 105 pekerja pertanian di Brebes dan 173 pekerja perkebunan di Klaten yang terpapar pestisida, didapatkan hasil sebagai berikut : (Tabel 2)
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 24

Tabel 1. Alasan tdak dimanfaatkannya alat pelindung Kecamatan Kubutambahan 1986.
Tidak Perlu Perlu tapi mahal Tidak Tabu Lain-lain Jumlah
n % n % n % n % n % Topi 1 33,33 - - - - - - 1 3 , 100Masker 39 52,00 19 25,53 11 14,67 6 +8,00 75 100 Sarung . tangan 38 45,24 20 23,81 23 27,38 3 3,57 84 100 Baju lengan panjang
76 57,78 3 6,67 5 11,11 11 74,74 45 100
Celana panjang 7 41,18 7 41,18 1 5,88 2 11,76 17 100
Kacama- ta pelin- dung
49 49,00 27 27,00 23 23,00 1 1,00 100 100
Sepatu boot 49 48,89 27
130,00 18 1 20,00 1 , 1,11 90 100
Tabel 2. Aktivitas kolinesterase pada petani dan pekerja perkebunan
(1986) Aktivitas Kolinesterase
Sektor fi 100%-75% normal
75%-50% 150%.25% keracun- an ringan
keracun- an sedang
25%-0% kceracun-
lan berat _
Pertanian (Brebes) . 105 (100%) 15 (14,3%) 41(39,0%) 38 (36,2%) 11 (10,5%)
Perkebunan (Kiaten) 173 (100%) 78 (45,9%) 68 (39,3%) 26 (15,0%) 1 ( 0,6%)-
Orang.orang yang menderita keracunan ringan seharusnya istirahat bekerja selama dua minggu, sedangkan bila keracunan sedang; tidak boleti lagi bekerja dengan pestisida dan bila perlu di bawah pengawasan dokter. Orang dengan keracunan berat harus istirahat dan diobati oleh dokter.
Suma'mur dkk. (1983)6 melakukan penelitian atas 5671 penduduk desa Bangunharjo, Yogyakarta. 1261 (22,2%) di antaranya petani. Di kalangan petani tersebut, 469 (37%) orang menggunakan atau berhubungan dengan pestisida, dan 18 (3,8%) pernah mengalami keracunan. Hanya 147 •(31,3%) dari para petani tersebut yang mengetahui cara masuknya pestisida ke dalam tubuh, sedangkan yang mengetahui gejala dini keracunan hanya 29 (6,2%) orang saja.
Selain itu juga dilakukan pengukuran kadar kōlinesterase darah atas 100 petani yang dipilih secarā acak, ternyata hasil-nya sebagai berikut :
Tabel 3. Kadar kolinesterase pada petani desa Bangunharjo, Yogyakarta.
Kadar kolinesterase (%) Jumlah
62,5 – 75 75 – 87,5
87,5 – 100,0
17 64 19
Pengukuran kadar kolinesterase yang dilakukan di desa
Sendangtirto segera setelah selesai penyemprotan menunjukkan hasil sebagai berikut :
Tabel 4. Kadar kolinesterase pada petani desa Sendangtirto.
Kadar kolinesterase(%) Jumlah
37,5 – 50,0 50,0 – 62,5 62,5 – 75,0
11 1 7
Sedangkan pengukuran yang dilakukan satu minggu
setelah penyemprotan di desa PotoronQ menghasilkan data sebagai berikut: Tabel 5. Kadar kolinesterase pada petani desa Potorono.
Kadar kolinesterase (%) Jumlah
50,0 – 62,5 62,5 – 75,0 75,0 – 87,5 87,5 – 100,0
4 7 38 3
Mustamin (1987)6 mengemukakan kasus keracunan ringan
dan sedang yang terjadi pada petani pemakai pestisida di Tulungagung, Karo Sumatera Utara, Malang dan Banyuwangi seperti tersebut dalam tabel berikut : Tabel 6. Tingkat keracunan pestisida pada petani di beberapa tempat.
Jenis petani, Jumlah orang Tingkat Keracunan
Tempat, Waktu diperiksa Berat Sedang Ringan Normal Petani padi Tulungagung (Januari 1986)
59 - - 18 41 (69%)
(September 1985) 60 - - 1 59 (98%) Petani hortikul- tural Karo, Sumatera Utara (Januari 86)
59 - 7 36 94 (62%)
Malang, Jatim (Mara 1986) 128 - 5 11 113 (89%)
Pekerja perkebun- nan coklat Banyuwangi, Jatim (Oktober 1986)/
60 - 1 2 56 (95%)
XXVI Ltd (Oktober 1986) 67 - 10 27 30 (45%)
Glenmore Ltd
Penelitian tentang pengetahuan, sikap dan praktek pengelolaan pestisida di Tulungagung menunjukkan bahwa 63% pe-ngetahuan mereka tidak baik, 73% sikap mereka tidak baik dan 82% dari mereka tidak baik dalam menggunakan alat- alat pelindung, 69% tidak bail( dalam personal hygiene dan 87% tidak balk dalam membuang limbah dan mencuci spray-can.
Penelitian A. Syazali S Muhibat (1985)6 pada perkebunan PTP XIII di Bandung menunjukkan keracunan pada pekerja penyemprot sebesar 12,3%.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 25

PEMBAHASAN Berbagai penelitian dalam tahun 1985/1986 menunjukkan
telah terjadi keracunan di kalangan petani pemakai pestisida, antara lain di Brebes 85,7% dan di Klaten 54,8%3, di Yogya-karta 17,0%4, di Tulungagung/Jatim 31%, di Karo Sumatera Utara 38%, di Malang 11%, di Banyuwangi/Jatim 30%5 , dan di Bandung 12,3%6.
Meskipun survai secara nasional belum pernah ailakukan, namun demikian data tersebut dapat memberikan gambaran dan diperkirakan ± 35,0% penyemprotan di Indonsia telah keracunan, baik ringan, sedang maupun berat.
Jumlah penduduk di Indōnesia tahun 1988 diperkirakan berjumlah 175 juta7, dan ± 63% adalah petanis, jadi jumlah petani ± 110.200.000 jiwa. Dengan perkiraan jumlah petani penyemprot adalah 37,1%4 , maka jumlah petani yang terpapar pestisida meliputi 40.792.500 orang. Bila ± 35% petani ter-papar pestisida mengalami keracunan, maka jumlah petani yang mengalami keracunan kira-kira 14.277.375 orang.
Terjadinya keracunan pestisida pada petani dimungkinlcn karena pelaksanaan pengelolaan pestisida yang tidak baikl'2'4 5 antara lain. tidak dimanfaatkan alat pelindung. Alasan tidak dimanfaatkannya alat pelindung menurut penelitian di Kubu-tambahan Bali' 46,7% menganggapnya tidak perlu, 26,6% karena mahal, 17% karena tidak tahu dan 10% karena lain hal.
KESIMPULAN DAN SARAN Upaya pencegahan keracunan pestisida pada petani pe-
nyemprot perlu ditingkatkan, mengingat ± 35% petani pe-nyemprot mengalami keracunan yang diperkirakan meliputi 14 juta orang.
Pengetahuan, sikap dan praktek pengelolaan pestisida dalam rangka meningkatkan produksi di bidang pertanian, rata-rata tidak baik.
Penyululian dan pengawasan terhadap petani penyemprot, tentang pengelolaan pestisida masih perlu ditingkatkan dan kerjasama lintas sektoral lebih dimantapkan.
KEPUSTAKAAN
1. I Ketut Winasa. Pemanfaatan slat pelindung petani hortikultural bawang merah sebagai upaya pengamanan penggunaan pestisida di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, FKM–UI Jakarta, 1986.
2. Titi Sari Renowati. Kadar cholinesterase darah pada penyemprot apel dan kobis di desa Bulukerto dan Torongrejo Kecamatan Batu Kabupaten Malang, Fakultas Kedokteran Airlangga Surabaya, 1988. hat. 1–8.
3. A.M. Sugeng Budiono. Pengukuran aktivitas cholinesterase pengamatan kasus pestisida. Maj Hiperkes dan Keselamatan Kerja, 1986/1987; XIX, 4; 1987; XX, 1.
4. Suma'mur PK, Bunandir, Sudirman, Widarto. Penelitian tentang keracunan pestisida pada petani di Yogyakarta, Maj Hiperkes dan Keselamatan Kerja 1985/1986; XVIII, 4; 1986; XIX, 1 hal. 56–85.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 2 Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 26

Efek Karsinogenik beberapa Pestisida dan Zat Warna Tertentu
Dr. H. Sardjono O. Santoso Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
PENDAHULUAN
Karsinogenesis kimiawi merupakan suatu proses multi-tahap. Sebagian besar karsinogen sebenarnya tidak reaktif (prokarsinogen atau karsinogen proximate), namun di dalam tubuh diubah menjadi karsinogen awal (primary) atau menjadi karsinogen akhir (ultimate). Sitokrom–P450 – suatu mono-oksidase dependen retikulum endoplasmik sering mengubah karsinogen proximate menjadi intermediate–defisien–elektron yang reaktif (electrophils). Intermediate (zat perantara) yang reaktif ini dapat berinteraksi dengan pusat-pusat di DNA yang kaya elektron (nucleophilic) untuk menimbulkan mutasi. Interaksi antara karsinogen akhir dengan DNA semacam ini dalam suatu sel diduga merupakan tahap awal terjadinya karsinogenesis kimiawi. DNA sel dapat pulih kembali bila mekanisme perbaikannya normal, namun bila tidak sel yang mengalami perubahan dapat tumbuh menjadi tumor yang akhirnya nampak secara klinis. Ko-karsinogen (promoter) sendiri bukan karsinogen. Promoter berperan mempermudah pertumbuhan dan perkembangan sel tumor dormant atau latent. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya tumor dari fase awal tergantung pada adanya promoter tersebut dan untuk kebanyakan tumor pada manusia periode laten berkisar dari 15 sampai 45 tahun. PROSES KARSINOGENESIS
Interaksi awal antara suatu karsinogen dengan sel tujuan mungkin berlangsung singkat dan irreversibel. Tahap ini di-sebut tahap inisiasi, sedangkan tahap-tahap berikutnya belum jelas, hanya ada dua buah hipotesa yang menerangkannya sebagai berikut Hipotesa I
Hipotesa pertama ini menerangkan bahwa tahap inisiasi yang menimbulkan suatu sel kanker dan tahap-tahap berikutnya tergantung dari kemampuan pertumbuhan spesies seluler tersebut. Hal ini berarti bahwa proses karsinogenesis merupa-
Disajikan pada Penataran Pengamanan Bahan Berbahaya, 3 s/d 8 No- vember 1986, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
kan proses perkembangan atau evolusi dari suatu sel kanker. (Bagan 1).
Bagan 1. Proses evolusi suatu sel kanker yang ditimbulkan oleh suatu karsinogen.
Rangsangan Karsinogen + Sel Tujuan Sel Neoplastik Kanker
Keterangan: Sel neoplastik adalah kumpulan sel abnormal yang terbenthk oleh selsel yang tumbuh terus menerus secara tidak terbatas, tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya dan tidak berguna bagi tubuh.
Hipotesa II Hipotesa kedua ini menerangkan bahwa tahap inisiasi
menyebabkan suatu perubahan pada sel nonneoplastik se-hingga bersifat dapat mengalami evolusi menjadi suatu sel kanker. Hal ini berarti bahwa proses karsinogenesis merupakan proses perkembangan atau evolusi menjadi suatu sel kanker (Bagan 2).
Bagan 2. Proses evolusi suatu sel nonneoplastdc menjadi suatu sel kanker yang ditimbulkan oleh suatu karsinogen. Rangsangan Karsinogenik + Sel Tujuan Populasi Sel Baru
Pertumbuhan
Neoplasia Jinak
Kanker < ––––––––– atau
Neoplasia Tetap
Pestisida yang dinilai positif menimbulkan tumor atas dasar test pada hewan percobaan, satu spesies atau lebih,
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 27

dengan tingkat kemaknaan p < 0.01 ialah : aldrin, aramit, klorbenzilat, p,p' –DDT, dieldrin, mirex, strobane dan heptakior (semuanya terdaftar untuk penggunaan food crops) dan āmitrol, avadex, bis (2–kloroetil) eter, N–12–hidroksietil)–hidrazin, dan PCNB.
Oleh karena itu Panitia Keamanan Pestisida di Amerika Serikat (Durham dan William, 1972) menyatakan sebagai berikut: Pemaparan manusia terhadap pestisida harus di-pertimbangkan semata-mata karena adanya keuntungan yang jelas bagi kesehatan. Evaluasi Zat-zat Kimia yang Bersifat Karsinogen oleh Inter-national Agency For Research On Cancer (IARC) Pada Tahun 1971–1977.
Pada tahun 1971–1977, International Agency for Research on Cancer (IARC) mengambil inisiatif untuk mengevaluasi zat-zat kimia yang bersifat karsinogen. Sejumlah 368 jenis zat-zat kimia telah dievaluasi dan dari jumlah ini 26 jenis zat kimia yang didapat dari proses industri atau obat-obatan yang masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan atau mulut ternyata positif bersifat karsinogen terhadap manusia, 221 jenis zat kimia positif bersifat karsinogen terhadap binatang percobaan dan 121 jenis zat kimia lainnya mungkin bersifat karsinogen terhadap manusia atau binatang percobaan.
Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan data bidang peng-gunaan utama 368 jenis zat-zat kimia yang dievaluasi. Tabel 1. Data bidang penggunaan utama 368 jenis zat-zat kimia yang
dievaluasi dalam 16 volume monograf IARC.
Bidang penggunaan utama Jurnlah zat kimia
Zat-zat kimia untuk industri 173 Obat-obatan 84Pestisida 34Zat-zat yang terdapat di alam 32Additives makanan atau kosmetika 31Macam-macam zat kimia dan analognya 7Proses industri 5Hasil sampingan industri 2 Jumlah 368
Tabel 2 memperlihatkan 26 jenis zat kimia yang positif bersifat karsinogen terhadap manusia, sedangkan sejumlah 342 jenis zat kimia lainnya mungkin bersifat karsinogen terhadap manusia atau binatang percobaan (Lampiran 1 dan 2). Tabel 2. 26 jenis zat kimia yang positif bersifat karsinogen terhadap
manusia.
No. Zat-zat kimia atau proses
Bidang pengunaan utama
Organ tubuh tujuan
Can masuk ke tubuh
1. Aflatoksin Lingkungan Hati Tertelan, ter- industri hirup.
2. 4-aminobi- Industri Kandung- Terhirup, ter-
fenil. kemih scrap kulit, tertelan.
3. $enyawa- senyawa
Industri, obat- obatan, lingkung-
Kulit, hati, paru-paru.
Terhirup, ter- telan, terse-
arsenat. an rap kulit.
4. Asbestos. Industri.
Paru-paru, rongga, pleura, saluran pencer- naan.
Terhirup, ter- telan.
5. Auramina. Industri Kandung kemih.
Terhirup, ter- telan, terse- rap kulit.
6. Benzena. Industri. Sistim pem- bentukan darah.
Terhirup, ter- wrap kulit.
7. Benzidina. Industri. Kandung– kemih
Terhirup, ter- telan, terse- rap kulit.
8. Bis (kloro- metil) - eter. Industri. Paru-paru. Terhirup.
9. Industri yang Industri Paru-paru, Terhirup.mengguna- kelenjar pros- tertelan.
kan kadmi- um (mung- kin kadmi- um oksida).
tat.
10. Kloramfeni- Obat-obatan Sistem pem- Tertelan, kol. bentukan
darah. suntikan.
11.
Klorometil metil eter (mungkin terasosiasi dengan bis (klorometil)- eter.
Industri. Paru-paru. Terhirup.
12. Kromium Industri Paru-paru, Terhirup.
(industri- indu§tri penghasll kromat).
rongga hidung. -
13. Siklofosfa- Obat-obatan Kandung– Tertelan, sun-mida. kemih. tilcan.
14. Dietilstil- bestrol. Obat-obatan Vagina, rahim. Tertelan.
15.Pertambang- an hematit (radon)
Industri Paru-paru. Terhirup.
16. Minyak iso- Industri Rongga hidung, Terhirup.propil. tenggorokan.
17. Melfalan Obat-obatan Sistim pemben-tukan darah.
Tertelan, sun- tikan.
18. Gas mustard Industri Paru-paru, tenggorokan Terhirup.
19. 2-naftilamina Industri Kandung – kemih.
Terhirup, ter- scrap kulit, tertelan.
20. Nikel (pa- Industri Rongga hidung, Terhirup.
murnian nrkel) paru-paru.
21. N, N–bis Obat-obatan Kandung – Tertelan. (2-kloroetil)-
2-naftilamina. kemih.
22. Oksimetolona Obat-obatan Hati Tertelan.23. Fenasetin Obat-obatan Ginjal Tertelan.24: Fenitoin Obat-obatan Kelenjar getah
bening. Tertelan, sun- tilcan.
25. Jelaga bar- minyak
Industri, lingkung-
Paru-paru, kulit (scretum)
Terhirup, ter- scrap kulit.
26. Vinil klorida Industri Hati, otak, pazu-paru
Terhirup, ter- wrap k alit.
Dari ribuan senyawa yang disintesis sebagai zat pewarna, karena sifat toksiknya hanya beberapa saja yang dapat di-terima dan digunakan dalam pewarna makanan, kosmetik dan
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 28

obat. Yang populer digunakan dalam pewarna makanan ada-lah: Tartrazin C.I. Food Yellow 4/19140 Sunset Yellow C.I. Food Yellow 3/15985 Cochineal Red C.I. Food Red 7/16255 Amaranth I C.I. Food Red 9/16185 Blue FCE C.I. Food Blue 2/42090 Indigocarmin C.I. Food Blue 1/73015 Pure Black B.N. C.I. Food Black 1128440
Zat warna sintetik tersebut di atas tidak toksik, kemurniannya tinggi, dan tidak mengandung komponen toksik, isomer dan logam berat.
Zat warna sintetik yang bukan khusus untuk makanan berbahaya karena meskipun penggunaannya sedikit, efek yang tidak diingini akan timbul sesudah jangka waktu yang lama, bahkan sampai beberapa tahun kemudian. Sebagai contoh misalnya benzidin yang digunakan sebagai zat perantara (intemediate) sintesis zat pewarna, ternyata dapat menyebabkan kanker setelah penggunaan selama 10 tahun atau lebih. Efek toksik yang timbul akibat penggunaan zat warna biasanya menyangkut kelainan lambung, ginjal dan kandung kemih, efek alergi dan yang paling berbahaya adalah kanker.
Zat-zat pewarna di bawah ini yang biasanya dipakai untuk mewarnai makanan dan minuman seyogyanya dilarang, yakni: 1) Pewarna langsung, terutama yang mengandung benzidin, misalnya : Congo Red C.I. Direct Red 28/22120 Direct Brown C.I. Direct Brown 2/22311 Direct Black C.I. Direct Black 38/30235.
Zat-zat pewarna ini mewarnai makanan sangat kuat, relatif murah sehihgga populer di pasaran. 2) Pewarna asam biasa. Zat-zat ini kurang toksik dibanding dengan yang pertama, namun seyogyanya dilarang untuk mewarnai makanan. Masyarakat yang tidak mengerti meng-gunakān zat warna ini oleh karena murahnya.
Contoh : Metanil Yellow C.I. Acid Yellow 36/13065
Acid Orange II C.I. Acid Orange 7/15510 Acid Orange Egg C.I. Acid Orange 10/16230 Nigrosine C.I. Acid Black 2/54420
Biasanya zat pewarna ini digunakan untuk mewarnai kertas, kulit dan tekstil. 3) Zat pewarna basa, populer digunakan dalam industri kertas. Zat warna ini mempunyai warna yang baik, cemerlang dan tampak menarik dalam larutan air.
Masyarakat yang tidak mengerti menggunakan zat pe-warna basa seperti : Auramin C.I. Basic Yellow 2 Rhodamin C.I. Basic Violet 10 Brilliant Green C.I. Basic Green 1 untuk mewarnai kerupuk, minuman, pisang goreng, dan se-bagainya. 4) Pembersih kaca optik (Optical bleaching agents).
Zat ini digunakan untuk memperbaiki penampakan bihun, sehingga kelihatan lebih putih bersih, cemerlang. Inipun seyogyanya harus dilarang, karena kita tidak mengetahui efek apa yang kita harus pikul di masa yang akan datang setelah penggunaan sekian lama.
Walaupun masih terdapat kontroversi mengenai peng-gunaan zat warna ini kiranya kita harus waspada akan ke-mungkinan efek yang merugikan di masa yang akan datang. Kita harus pertimbangkan untung-ruginya mengingat begitu banyaknya zat kimia yang mungkin dapat menimbulkan kanker, termasuk diantaranya zat pewarna dan pestisida (lihat lampiran).
KEPUSTAKAAN
1. Goodman & Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics. 7th ed Mc. Milian, New York, 1985. p. 1595
2. Casarett Li, Doull J. Toxicology, The Basic Science of Poisons, McMillan, New York, 1975.
3. Cyelak, zat pewarna tekstil/kertas/kulit yang sering dipakai untuk warna makanan. Temukarya Pengamanan Teknis Bahan Berbahaya Dit. Jen. POM, 1984.
4. Sardjono O. Santoso. Efek karsinomagenric, mutagenik, teratogenik beberapa obat serta upaya pencegahannya. Temukarya Pengamanan Teknis Bahan Berbahaya, Dir. Jen. POM, 1984.
LAMPIRAN 1
Daftar 342 jenis zat-zat kimia yang mungkin bersifat karsinogen terhadap manusia atau binatang percobaan.
1. Acetamide 18. Aramite* 36. Beryllium oxide* 50. Cadmium acetate 2. Acridine orange 19 Arsenic trioxide 37. Beryllium phosphate* 51. Cadmium chloride*3. Acrillavnium chloride 20. Aurothioglucose! 38. Beryllium sulfate* 52. Cadmium powder*4. Actinomycins* 21. Azaserine* 39. Beryl ore* 53. Cadmium sulfate*5. Adriamycin 22. Aciridine* 40. hHC (technical grades)* 54. Cadmium sulfide*6. Aldrin 23.2-(1-Aziridinyl)-ethanol* 41. Bis(1-aziridinyl)-morpholino- 55. Calcium arsenate7. Amaranth 24. Aziridylbenzoquinone* phosphine sulfide* 56. Calcium chromate*8. 5-Aminoacanaphthene 25. Azobenzene* 42. Bis(chloroethyl) ether* 57. Cantharidin*9. p--Aminoazobenzene* 26. Barium chromate 43. 1, 2-Bis(chloromethoxy) 58. Carbaryl 10. O-Aminoazotoluene* 27. Benz(a)acridine* ethane* 59. Carbon tetrachloride*11. p-Aminobenzoic acid 28. Benz(c)acridine* 44. 1; 4-Bis(chloromethoxy- 60. Carmoisine12. 2-Amino-5-(nitro-2-furyl)- 29. Benzo(b)fluoranthene* methyl)-benzene* 61. Catechol 1, 3, 4-thiadiazole* 30. Benzo(/)fluoranthene* 45. Blue VRS* 62. Chlorambucil*13. 4-Amino-2-nitrophenol 31. Benzo(a)pyrene* 46. Brilliant blue FCF* 63. Chlorinated dibenzodioxins .14. Amitrole* 32. Benzo(e)pyrene* 47. 1, 4,Butanediol dimethane- 64. Chlormadione acetate*15. Aniline 33. Benzyl chloride* sulfonata (Myleran)* 65. Chlorobenzilate*,16. Anthranilic acid 34. Benzyl violet 4B* 48. (3-Butyrolactone* 66. Chloroform17. Apholate 35. Beryllium* 49. y-Butyrolactone 67. Chloropropham
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 29


Keterangan: Tanda (*) menunjukkan bahwa zat-zat kimia tersebut terbukti positif bersifat karsinogen hanya terhadap binatang percobaan.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 31

Peningkatan Daya Tahan Tubuh oleh Kenaikan Suhu Tubuh pada
Mencit Terinfeksi dengan Plasmodium berghei ANKA
Mohamad Sadikin
Bagian Biokimla, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta PENGANTAR
Kenaikan suhu tubuh hampir selalu terjadi pada peradangan dan merupakan salah satu dari lima tanda inflamasi yang sudah dikenal sejak zaman Galenus. Kenaikan suhu tubuh (kalor) ataupun demam (pireksia) adalah gejala peradangan yang dirasakan secara subyektif olehpenderita dan di samping itu dapat pula diamati secara obyektif dengan perabaan pengamat, atau dengan menggunakan alat pengukur sederhana yaitu termometer. Dengan cara yang terakhir ini, yang maslh tetap sangat sederhana,, pengamat memperoleh gambaran tentang derajat berat atau ringannya gejala peradangan tadi dalam bentuk data kuantitatif.
Penyakit malaria yang disebabkan oleh hemoparasit dari genus Plasmodium merupakan penyakit yang tersebar di ber b.agai daerah tropis di dunia. Indonesia, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia, merupakan daerah holoendemik malaria. Penyakit ini menyerang dan membunuh puluhan juta orang per tahun d'i'seluruh dunia, sebagian besar dari korban adalah anak-anak dan usia dewasa muda. Salah satu gejala yang sangat menonjol pada penyakit ini ialah adanya demam yang tinggi, yang terjadi bersamaan dengan timbulnya parasitemia. Gejala demam ini demikian kuat asosiasinya dengan malaria, sehingga pada daerah-daerah yang hiperendemik malaria, adanya demam., apalagi demam yang tinggi, sering dihubungkan dengan penyakit ini. Pemeriksaan fisik, laboratorium dan kebijaksanaan pengobatan diarahkan untuk memastikan dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh hemoprotozoa ini. Bahkan di kalangan orang banyak sendiri timbul kecenderung-an untuk melakukan pengobatan sendiri, bailc dalam bentuk usaha pertama maupun sebagai pengobatan definitif, yang didasari oleh gagasan tentang asosiasi yang sangat erat antara demam dengan malaria.
Berikut ini dilaporkan akibat kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh suhu lingkungan yang tinggi terhadap morta-litas, derajat parasitemia dan derajat anemia pada mencit-
*) Penelitian ini dilakukan di Laboratoire d'Immunologie et Biologie Parasitaire, Universite de Bordeaux II, 146 Rue de Leo Saignat, 33000 Bordeaux, France, di bawah pengawasan Prof. DR. R. PautrizeL
mencit yang sengaja diinfeksi dengan Plasmodium berghei ANKA, suatu hemoprotozoa yang menyebabkan penyakit malaria pada rodensia, terutama rodensia kecil. Tujuan pe-nelitian ini ialah untuk melihat, apakah suhu tubuh berpengaruh dalam,penyembuhan penyakit infeksi, dengan menggunakan Plasmodium berghei ANKA sebagai penyebab infeksi.
BAHAN DAN CARA: Binatang percobaan: Mencit-mencit putih Swiss betina,
umur 6 mihggu pada saat percobaan dimulai, berat badan 25 g. Sebelum percobaan dimulai, semua mencit ini disesuaikan dulu dengan keadaan laboratorium selama dua minggu. Makanan dan minuman diberikan secara ad libitum.
Parasit: Plasmodium berghei ANKA, dipelihara di laborato-rium dengan dua cara. Pertama, ialah dengan memelihara parasit ini dalam makhluk hidup, yaitu mencit. Untuk tujuan ini, tiap minggu dua ekor mencit sehat diinokulasi dengan darah yang berasal dari mencit yang sudah diinokulasi minggu sebelumnya. Pemindahan parasit dengan cara ini perlu, oleh karena mencit yang telah terinfeksi akan mati dalam jangka waktu lima sampai sepuluh hari sesudah inokulasi bila tidak diobati. Pemeliharaan yang kedua ialah dengan menyimpan darah yang berasal dari mencit terinfeksi dalam tabung- tabung kapiler plastik dan diletakkan dalam bejana tertutup berisi nitrogen cair (suhu –l800C). Plasmodium berghei ANKA diperoleh dari Institut de Medecine Tropicale du Prince Leopold, Antwerpen, Belgia. Parasit ini diisolasi untuk pertama kali dari seekor tikus'hutan di Katanga, Zaire (ANKA: ANtwerpen – KAtanga).
Ruang panas: Sebuah kamar tembok berukuran 2 x 2 x 2,5 m, yang suhunya diatur konstan 35°C dan kelembaban antara 90 – 95%. Ruangan ini juga dilengkapi dengan alat pengatur lamanya pencahayaan, sehingga diperoleh lamanya pencahayaan 12 jam dan lama gelap 12 jam pula.
Peralatan laboratorium: Kaca obyek, milcroskop optik, larutan pewarna May Grunwald dan larutan pewarna Giemsa,
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 32

minyak imersi, mikrokapiler yang dinding dalamnya telah dilapisi heparin (DADE) dan alat pemusing untuk mikrokapiler tadi, untuk memperoleh nilai hematokrit.
Inokulasi mencit, baik untuk tujuan pemeliharaan sumber parasit maupun untuk tujuan percobaan, dilakukan dengan menyuntikkan sel darah merah yang mengandung parasit (SDMP) yang telah disuspensikan dalam larutan PBS (phos-phate buffer saline) pH 7,2 – 7,4 atau dalam larutan Alsever. SDMP tadi disuntikkan secara intraperitoneal sebanyak 0,5 ml dengan konsentrasi 105 SDMP/0,5 ml suspensi. Selama pe-nyiapan suspensi, tabung yang berisi larutan PBS atau Alsever, begitu juga tabung berisi darah yang berasal dari mencit telah terinfeksi, diletakkan dalam bejana es yang mempunyai suhu 0°–4°C. Penyuntikan dilakukan dengan menggunakan semperit tuberkulin plastik sekali pakai yang baru.
Untuk tujuan percobaan, sejumlah besar mencit yang se-belumnya telah mengalami penyesuaian dengan suasana laboratorium selama dua minggu, diinokulasi dengan cara yang telah disebutkan tadi. Kemudian mencit-mencit itu dibagi secara acak menjadi dua kelompok yang masing-masing terdiri dari sejumlah mencit yang sama. Satu kelompok diletakkan dalam ruang panas dengan suhu 35°C, sedangkan kelompok lain diletakkan dalam ruang degan suhu biasa, 22°–25°C. Selain itu, sejumlah yang sama dari mencit, yang tidak diinokulasi, diletakkan pula dalam ruang panas bersuhu 35°C tadi. Pengamatan mortalitas dari tiap kelompok dilakukan tiap hari, demikian pula pengukuran temperatur rektum pada 5 ekor mencit dari tiap kelompok. Penilaian parasitemia dan mikrohemātokrit dilakukan tiap tiga hari.
Penilaian parasitemia: Dilakukan dengan membuat sediaan darah tipis (sediaan hapus) yang diwarnai berturut-turut dengan larutan pewarna May-Grunwald selama 5 menit, kemudian dengan larutan pewarna Giemsa selama 15 menit. Setelah dicuci dengan air dan dikeringkan, dilihat dengan mikroskop biasa dengan menggunakan minyak imersi. Untuk menilai tingkat parasitemia, seluruhnya diperiksa 1000 eritrosit, baik yang mengandung parasit (SDMP) maupun tidak (SDM). Tingkat parasitemia dinyatakan dalam % SDMP dari keseluruhan eritrosit yang dihitung. Jelasnya, bila ditemukan sejumlah n SDMP dan m (dalam hal ini 1000) keseluruhan eritro sit yang dihitung (SDMP + SDM), maka tingkat para-sitemia dihitung sebagai berikut :
%100xmn
Penilaian mikrohematokrit: Dilakukan dengan mengguna-kan mikrokapiler yang dinding dalamnya tēlah dilapisi heparin. Sesudah tabung-tabung mikrokapiler ini terisi darah, salah satu ujungnya ditutup denganmemanaskannya sebentar pada nyala Bunsen yang kecil, selanjutnya dipūsing pada alat pemusing dengan rotor khusus untuk mikrokapiler,.pada kecepatan 6000 putaran tiap menit, selama 5 menit. Pembacaan nilai hematokrit dilakukan dengan menggunakan skala. Plasma yang terpisah di bagian atas tumpukan sel-sel, dipisahkan dengan memotong tabung tadi tepat pada perbatasan cairan dengan tumpukan sel. Plasma tadi disimpan dalam alat pendingin bersuhu -20°C, untuk pemeriksaan kadar protein, imunoglubulin dan pengukuran titer antibodi anti-plasmodium.
Pengukuran suhu rektum dilakukan tiap hari pada saat yang sama, antara pukul 9 – 10 pagi. HASIL:
Mortalitas: Hasil pengamatan pada kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri atas 25 ekor mencit disajikan dalam gambar 1. Pada kelompok mencit terinfeksi dan ditempatkan dalam ruangan biasa, dalam minggu pertama belum ada yang mati. Tetapi pada minggu ke tiga, 82% dari mencit-mencit ini sudah mati dan pada minggu ke empat tidak ada lagi yang hidup. Kematian terbanyak terjadi pada minggu ke tiga.
Gambar 1. Mortalitas kumulatif seisms peroobaan pada mencit-
mencit yang diinokulasi dengan Plasmodium berghei ANKA pada suhu 35°C dan suhu ruang bias (20 C).
Bila mencit terinfeksi dipelihara dalam ruangan bersuhu 35°C, 4% dad mencit tadi mati pada. minggu pertama. Se-
lanjutnya pada minggu.ke dua, persentase kematian total 12% dan 33% pada minggu ke tiga. Setelah enam minggu berada dalam ruang panas, separuh dari jumlah mencit bertahan hidup dan sembuh. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suhu lingkungan 35°C ini sangat mengurangi angka kematian mencit; bahkan separuh di antaranya sembuh.
Derajat parasitemia: Pada mencit-mencit yang dipelihara pada suhu ruangan biasa, jumlah parasit naik dengan cepat. Tiga hari sesūdah inokulasi, parasitemia sudah mencapai 5%, yang terus naik dengan tajam pada hari-hari berikutnya. Pada akhir minggu ke dua, tingkat parasitemia sudah mencapai 60% lebm dan mencit-mencit sudah tampak sakit berat, kurus, daun telinga, ekor dan moncong terasa dingin dan tampak pucat dan kadang-kadang kekuningan; bulu-bulu berdiri dan binatang tersebut menggigil. Parasitemia tertinggi ialah 66%, yaitu pada minggu ke tiga.
Sebaliknya, mencit-mencit terinfeksi yang dipelihara pada ruangan dengan suhu 35°C menunjukkan perilaku pertumbuh-an parasitemia yang berbeda. Pertumbuhan parasit menjadi sangat terhambat. Pada hari ke tiga sesudah inokulasi, sangat sukar untuk menemukan parasit dalam sediaan darah tipis. Pada akhir, minggu ke dua, tingkat parasitemia tidak lebih
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 33

dari 10%. Tingkat parasitemia tertinggi tidak lebih dari 15% dan sesudah itu turun kembali dan sembuh pada minggu ke enam. Dari semuanya ini dapat dikatakan bahwa suhu ling-kungan yang panas (35°C) sangat mengurangi tingkat parasi-temia (gambar 2). Gambar 2. Pertumbuhan parasit pada mencit-mencit yang diinokulasi
dawn Plasmodium bergh°ei ANKA pada suhu 35 C dan temperatur ruang biasa (20 C)
Tingkat anemia: Tingkat anemia atau berat ringannya
derajat kehilangan darah diukur sebagai berikut :
anemiatingkat %100xHt
HtHt
O
nO =−
HtO : Nilai hematokrit sebelum inokulasi
Htn : Nilai hematokrit n hari sesudah inokulasi.
Pada mencit-mencit yang tidak diinokulasi dan ditempat-kan dalam ruang panas, sesudah tiga hari memperlihatkan kenaikan nilai hematokrit yang ringan. Pada hari ke tujuh, nilai tersebut kembali lagi ke keadaan semula, yaitu 45% (data tidak dicantumkan). Ini berarti mencit-mencit tersebut mengalami gangguan keseimbangan cairan yang menjurus kepada dehidrasi pada hari-hari pertama berada di ruang bersuhu 35°C tadi. Perubahan yang tiba-tiba ini dapat diatasi dan keseimbangan cairan kembali normal sesudah beberapa hari menyesuatican diri di lingkungan yang baru yang bersuhu lebih panas tadi. Pada mencit-mencit yang terinfeksi dan di-letakkan dalam suhu lingkungan biasa, tiga hari sesudah inokulasi sudah memperlihatkan kehilangan darah. Pada hari-hari berikutnya, kehilangan darah ini berlangsung terus se-hingga Makin berat. Pada akhir minggu pertama, mencit-mencit kelompok ini sudah kehilangan 20% dari sel darah merahnya semula; di akhir minggu ke dua, kehilangan tersebut mencapai 70%. Pada akhir minggu ke tiga, mencit yang ber-tahan hidup sudah kehilangan sebagian besar sel darah merah, yaitu mencapai 85%. Saat puncak anemia ini terjadi ber-samaan dengan saat mortalitas kumulatif yang tertinggi.. Se-baliknya, pada mencit-mencit yang diinokulasi dan dipelihara pada ruang bersuhu panas, derajat anemia jauh lebih rendah;
berbeda dengan mencit-mencit terinfeksi yang dipelihara pada ruang dengan suhu biasa, tiga had sesudah inokulasi tidak dijumpai adanya anemia; malahan yang tampak ialah sebaliknya, terjadi kenaikan nilai hematokrit seperti halnya pada mencit-mencit kontrol yang tidak terinfeksi dan. di-pelihara dalam ruang panas tadi. Kehilangan ,darah baru tampak pada akhir minggu pertama dengan tingkat yang sangat rendah. Peningkatan derajat kehilangan darah terjadi dengan lambat. Nilai tertinggi ialah 30%. Secara umum dapat dikatakan bahwa suhu lingkungan yang relatif tinggi (35°C), yang sangat mengurangi derajat• parasitemia dan mortalitas, juga sangat memperkecil kehilangan darah (gambar 3).
Gambar 3. Pertumbuhan anemia pada mencit-mencit yang diinokulasi
dengan Plasmodium berghei ANKA pada suhu 35 C dan suhu ruang biasa (20°C).
Perubahan suhu rektum: Suhu rektum diukur pada 5 ekor
mencit yang sama pada tiap kelompok. Suhu rektum pada mencit yang tidak diinokulasi dan dipelihara pada ruang dengan suhu biasa ialah 36,8°C. Pada mencit-mencit yang di-tempatkan pada ruang 35°C, diinokulasi ataupun tidak, tampak kenaikan suhu rektum sejak hari pertama sesudah ditempatkan dalam ruangan tersebut. Namun demikian, kenaikan ini lebih besar pada mencit yang diinokulasi dibandingkan dengan mencit yang tidak diinokulasi. Sesudah berada selama 48 jam di ruang bersuhu 35°C tadi, suhu rektum mencapai 39,4°C pada mencit-mencit.yang diinokulasi. Pengamatan selama seminggu memperlihatkan variasi yang ringan di sekitar nilai Mi. Pada mencit-mencit yang tidak diinokulasi dan ditempatkan di ruang panas yang sama, suhu rektum naik mencapai 38,2°C ,dan bertahan di sekitar nilai ini selama pengamatan seminggu itu.
Pada mencit-mencit yang diinokulasi dan dipelihara pada ruangan dengan suhu lingkungan biasa, tidak terjadi kenaikan suhu rektum. Yang dijumpai malahan `sebaliknya, yaitu pe-nurunan suhu rektum sampai 36,5°C. Ini sudah terlihat pada hari ke dua. Penurunān suhu rektum pada kelompok ini berlangsung terus; pack hari ke empat mencapai 36°C, kemudian 35,6°C. Pada hari ke tujuh sudah mencapai 34,8°C
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 34

(gambar 4). Secara umum dapat dikatakan, bahwa pada mencit-mencit yang terinfeksi dan diletakkan pada suhu biasa, terjadi penurunan suhu rektum secara progresif. Suhu lingkungan yang tinggi (35°C) menaikkan suhu rektum, dan kenaikan ini lebih tinggi lagi bila mencit-mencit yang diletak-kan di ruang panas tersebut terinfeksi, dalam hal ini dengan PL berghei ANKA.
Gambar 4. Variasi suhu rektum pada mencit-mencit yang diinokulasi
dengan Plasmodium begkei ANKA dan yang tidak di-inokulasi dan ditempatkan pada suhu 35°C dan suhu ruang biasa (20°C).
PEMBICARAAN
Pada penelitian ini, pengaruh suhu lingkungan yang relatif tinggi, sebesar 35°C, terhadap perjalanan penyakit yang di-sebabkan oleh Plasmodium berghei ANKA sudah tampak pada hari-hari pertama. Pengaruh itu tampak jelas pada ber- bagai parameter yang diamati, yaitu saat munculnya para-sitemia serta derajatnya, konsekuensi dari parasitemia terhadap jumlah sel darah merah yang dinilai dalam bentuk hematokrit maupun temperatur rektum. Perubahan berbagai parameter ini berlangsung selama percobaan dan memberi hasil berupa turunnya angka kematian secara tajam dan muncul serta bertambahnya jumlah kesembuhan, yang tidak akan terjadi secara spontan dalam keadaan biasa.
Pengaruh suhu lingkungan yang tinggi terhadap perjalanan penyakit yang biasanya fatal telah dilaporkan oleh berbagai peneliti. Mereka mengamati bahwa suhu lingkungan yang tinggi menguntungkan binatang percobaan yang sengaja di-inokulasi dengan berbagai macam mikroorganisme. Hal ini tampak pada mencit-mencit yang sengaja diinokulasi dengan Try panosoma equiperdumr pada mencit-mencit yang di-inokulasi dengan Trypanosoma brucei2 dan pada mencit yang diinokulasi dengan Schistosoma mansoni. Pada ber- bagai eksperimen ini, terbukti bahwa perjalanan penyakit berubah dengan tajam. Trypanosoma equiperdum selalu fatal bagi mencit. Binatang tersebutakan mati dalam waktu 48 jam
sesudah inokulasi bila tidak diberi pengobatan. Dengan mem-berikan perlakuan panas, Pautrizel dkk. berhasil mengubah pola perjalanan penyakit; mencit-mencit bertahan hidup sampai 96 jam, bahkanada yang lebih dari itu. Tingkat para-sitemia menjadi jauh lebih rendah,.tertama pada 48 jam per-tama. Trypanosoma brucei juga protozoa darah yang me-nyebabkan penyakit yang fatal bagi mencit. Suhu lingkungan yang panas mengubah perjalanan penyakit sehingga menjadi kronis dengan tingkat parasitemia yang rendah. Demikian pula halnya dengan Schistosoma mansoni; penyakit fatal pada mencit berubah menjadi penyakit ringan, dengan tingkat parasit yang rendah.
Pengaruh suhu lingkungan yang tinggi dalam menurunkan mortalitas tidak hanya tampak pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit saja. Gejala ini juga tampak pada penyakit-penyakit virus. Mencit-mencit yang diinfeksi dengan virus herpes simpleks mengalami penurunan mortalitas bila dipelihara dalam ruangan dengan suhu tinggi4, seperti halnya mencit-mencit yang diinokulasi dengan virus coxsackies, virus dengue6 dan virus rabies7. Seperti halnya berbagai parasit tadi, virus-virus ini selalu menyebabkan kematian pada mencit. Akan tetapi perlakuan dengan memelihara mencit-mencit ini dalam ruang bersuhu panas mengubah perjalanan penyakit dengan drastis. Bila ,pada berbagai penyakit yang disebabkan oleh parasit tadi, masih terjadi perubahan ke arah kronis dengan tingkat parasitemia yang rendah, maka. pada penyakit-penyakit virus ini suhu lingkungan setinggi 35°C menyebabkan kesembuhan. Bahan-bahan yang berasal dari mencit-mencit yang sembuh ini, bila dibiakkan in vitro pada biakan jaringan, atau in vivo pada mencit baru yang sehat, tidak akan menginfeksi biakan jaringan atau mencit baru tadi.
Pada percobaan yang dilakukan ini, didapatkan penurunan suhu tubuh dari mencit-mencit yang diinokulasi dengan PL berghei ANKA dan ditempatkan dalam ruangan dengan suhu biasa. Ini sesuatu yang di luar perkiraan. Lazimnya pada penyakit malaria yang dijumpai pada manusia selalu ada demam, bahkan ini merupakan salah satu gejala yang mencolok. Demam ini demikian erat dihubungkan dengan malaria sehingga sering disamakan dengan penyakit itu sendiri. Pada mencit-mencit dalam percobaan ini, kenaikan suhu tubuh di atas yang biasa atau demam baru tampak bila mencit ter-infeksi tadi ditempatkan dalam ruang panas. Bahwa kenaikan suhu tubuh ini tidaklah semata-mata kenaikan pasif yang disebabkan oleh meningkatnya suhu lingkungan, tampak bila dibandingkan dengan mencit-mencit tidak terinfeksi yang ditempatkan di dalam ruang panas. Kenaikan srlhu rektum pada mencit-mencit kontrol ini tidaklah setinggi kenaikan yang dijumpai pada mencit terinfeksi. Ini berarti, pada mencitmencit terinfeksi, selain terjadi kenarlcan suhu tubuh secara pasif, terjadi pula kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh adanya infeksi. Dilihat sekilas, hal ini bertentangan dengan fakta terjadinya penurunan suhu tubuh dari mencit terinfeksi yang dipelihara pada suhu ruang biasa.
Ini dapat diterangkan sebagai berikut: bila mencit ter-infeksi diletakkan dalam ruang dengan suhu biasa,. produksi panas yang terjadi akibat infeksi tidak dapat menaikkan suhu tubuh. Ada dua kemungkinan untuk menerangkan hal tersebut. Pertama, pusat pengaturan suhu (termoregulator)
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 35

pada mencit, terutama yang terinfeksi dan dipelihara pada suhu ruangan biasa, tidak berjalan dengan baik. Kemungkinan kedua, panas yang terbentuk akibat peradangan. lebih banyak terbuang daripada menaikkan suhu tubuh. Dalam suatu pengamatan pada mencit, tikus dan marmut yang diletakkan dalam ruangan dengan berbagai suhu lingkungan, Hervington8 menemukan fakta yang menarik. Ternyata, suhu rektum paling rendah dalam beberapa suhu lingkungan ditemukan pada mencit, sedangkan yang tertinggi padā marmut. Pada tiap hewan ini ada suhu kritis. Di atas suhu kritis ini, suhu tubuh naik lebih tinggi. Suhu lingkungan kritis ini ialah 35°C. Hervington menerangkannya dalam hubungan dengan perbandingan luas permukaan badan dengan berat badan. Oleh karena produksi panas adalah fungsi dari massa tubuh, nilai ini ternyata paling besar bagi mencit. Dengan perkataan lain, untuk 1 gram berat badan, tersedia luas permukaan tubuh yang lebih besar pada mencit dibandingkan dengan kedua rodensia lainnya, sehingga peluang kehilangan panas pada mencit menjadi lebih besar. Akan tetapi hal ini juga tergantung kepada gradien suhu tubuh – suhu lingkungan. Makin besar perbedaan ini, kehilangan panas juga makin besar; sebaliknya bila perbedaan ini kecil atau tidak ada, maka kehilangan panas tidak terjadi.
Dalam percobaan ini tampak pula bahwa kenaikan suhu tubuh dalam keadaan terinfeksi, dalam hal ini dengan me-naikkan suhu lingkungan, mampu mengubah perjalanan penyakit, sangat mengurangi mortalitas dan menyebabkan kesembuhan. Ini berarti bahwa demam yang tidak terlalu tinggi mungkin sekali membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berbagai pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti lain menjurus ke arah yang sama. Anjing-anjing baru lahir ternyata belum mampu mengatur suhu tubuhnya dengan balk. Inokulasi dengan virus herpes anjing menyebabkan kematian. Di samping itu juga suhu tubuh turun. Tetapi bila anak anjing baru lahir dan diinokulasi dipelihara dalam ruang panas, akan terjadi kesembuhan9. Hal yang sama diamati pula oleh Furuchi dan Shimizu pada babi baru lahir yang diinfeksi dengan virus gastroenteritis10. Pemeliharaan pada ruang dengan suhu 35°C – 37°C menyebabkan hewan-hewan tersebut babas dari virus dan gejala-gejala yang diakibatkannya, sementara pada hewan yang ditempatkan pada ruang dengan suhu 20°C – 25°C terjadi gejala-gejala gastroenteritis. Pengamatan yang dilakukan Weinstein dkk.. pada -manusia mengingatkan kita pāda hal yang samall . Dalam suatu kajian retrospektif terhadap sejumlah kasus peritonitis, mereka menyimpulkan antara lain bahw,a bila suhu tubuh 38°C atau lebih, maka mortalitas sangat rendah. Bila sebaliknya, maka kematian 100%. Upaya untuk menurunkan suhu tubuh dengan sengaja pada makhluk terinfeksi yang disertai demam, ternyata menyebabkan makhluk tersebut tidak mampu melenyapkan penyebab infeksi. Ini dijumpai Husseini dkk (1982) pada binatang ferret yang diinokulasi dengan, virus influenza12. Bila tanggap demam binatang tersebut dihilangkan dengan mencukur bulunya atau dengan memberi salisilat, maka daya eliminasi virus pada hewan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan hewan terinfeksi yang tanggap demamnya tidak dilenyapkan.
Tampaknya kecenderungan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada suhu tubuh yang tinggi tidak hanya tampak secara ontogenesis. Hal ini juga dijumpai secara filogenesis.
Vertebrata yang bukan mamalia dan burung mempunyai suhu tubuh yang sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan (poi-kilotermi). Pada binatang-binatang ini juga tampak pula bahwa kenailcan suhu tubuh pada keadaan infeksi sangat mengurangi kematian dan jumlah mikroorganisme yang dapat diasingkan dari berbagai organ tubuh, setelah sebelumnya diinokulasikan.
Pada jenis ikan hiu, Ginglymostoma cirratum, yang di-inokulasi dengan bakteriofag. Bakteriofag yang disuntikkan ini lenyap jauh lebih cepat dari berbagai organ ikan tadi, bila ia dipelihara pada suhu 30°C dibandingkan dengan suhu 21°C13. Gejala yang lebih mencolok lagi diamati oleh Covert dan Reynold (1.977) pada ikan Carasius auratus yang diinokulasi dengan bakteri patogen Aeromonas hydrophila, dan dipelihara dalam air dengan empat macam suhu: yang tertinggi 32°C, yang terendah 25°C. Ternyata ikan-ikan yang dipelihara pada suhu tertinggi bertahan hidup dan sembuh seluruhnya, sedangkan ikan-ikan yang ada dalam air dengan suhu terendah hanya bertahan hidup sebanyak 40%14. Fakta yang sama juga ditemukan pada reptil. Kadal gurun Dipsosaurus dorsalis yang disuntik dengan bakteri patogen Aeromonas hydrophila dipelihara pada berbagai macam suhu. Kadal-kadal ini sembuh dari infeksi bila dipelihara pada suhu tertinggi dari percobaan ini, yaitu 40°C'. Bila kadalkadal terinfeksi ini dibebaskan untuk memilih ruangan dengan berbagai macam suhu, maka semuanya memilih ruangan( dengan suhu tertinggi (40°C).
Ternyata, kecenderungan untuk menaikkan suhu badan dengan berbagai macam cara pada keadaan terinfeksi ini tidaklah terbatas pada vertebrata saja. ia dijumpai juga pada artropoda, dalam hal ini crustacea' . Para peneliti ini meng-inokulasi udang Cambarus bartoni dengan bakteri patogen Aeromonas hydrophila.Kemudian udang-udang itu dipelihara dalam bejana yang berisi air yang dilengkapi dengan termo-regulator ' sehingga menghasilkan gradien suhu. Ternyata binatang itu memilih bagian dari bejana dengan suhu tertinggi, yaitu 22,1°C, sedangkan suhu tubuh udang-udang itu naik hampir 2°C dan sembuh dari infeksi. Akan tetapi, bila udang udang terinfeksi sengaja diletakkan dalam air dengan suhu rendah, maka semua binatang ini mati.
Kesemuanya ini menunjukkan bahwa balk pada makhluk hemeotermi maupun pada makhluk poikilotermi, adanya infeksi akan mendorong makhluk-makhluk tadi untuk me-naikkan suhu badannya, balk dengan cara pengaturan meta-bolisme secara sentral melalui pusat pengaturan suhu di hipo-talamus (pada makhluk homeotermi) maupun melalui tingkah laku, yaitu dengan sengaja mencari tempat dengan suhu ling-kungan yang tinggi. Kenaikan suhu tubuh dalam keadaan infeksi ini, yang tidak lain adalah demam, dan yang dicapai dengan berbagai cara ini, ternyata sangat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Dari pengamatan yang di-lakukan dalam penelitian ini dan juga dari berbagai penyelidfican yang telah dilakukan orang dengan menggunakan berbagai binatang percobaan dan penyebab penyakit, didapat kesimpulan yang tidak konvensional dan bertentangan dengan anggapan umum: kenaikan suhu tubuh, yaitu demam, dalam batasbatas yang dapat ditoleransi tubuh, tampaknya diperlukan oleh tubuh untuk meningkatkan daya tahan terhadap infeksi. Walaupun kesimpulan ini tampaknya tidak sesuai dengan anggapan umum, beberapa fakta empiris pada manusia secara
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 36

tidak disadari mendukung kesimpulan ini. Misalnya, telah lama dipratekkan secara empiris pengobatan sifilis stadium lanjut dengan membangkitkan demam pada penderita, dengan cara menyuntikkan darah malaria atau suspensi Salmonella typhosa. Meskipun pengobatan ini dilakukan sebelum kurun antibiotika dan kini dianggap telah masuk perbendaharaan sejarah kedokteran belaka, ia tetap menunjukkan peran demam dalam menyembuhkan penyakit infeksi. Fakta lain ialah sehubungan dengan lepra. Mycobacterium leprae pada penderita ditemukan terutama di daerah permukaan, seperti kulit, telinga, testis, yang umumnyamempunyai suhu relatif lebih rendah dibandingkan dengan alat-alat dalam. Salah satu kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir ini ialah bahwa kuman lepra manusia berhasil dikembang-biakkan dalam jumlah besar pada armadillo, sejenis mamalia ber- sisik yang mirip dengan trenggiling. Pada hewan ini, kuman lepra tidak hanya ditemukan di permukaan badan, tetapi juga pada berbagai macam alat-alat dalam jumlah besar. Dengan demikian terbukalah sumber kuman lepra dalam jumlah besar, yang memungkinkan berbagai penyelidtican untuk penyakit ini, bahkan untuk mengembangkan vaksin. Penyelidikan Purtilo dkk memperlihatkan bahwa hal itu dimungkinkan, karena suhu tubuh armadillo yang relatif rendah, yaitu antara 300C (di kulit) dan 350C (pada alatalat dalam)17. Akhirnya, patut disebutkan pula bahwa dewasa ini di berbagai pusat penelitian kanker sedang dipelajari dan dikembangkan secara intensif pengobatan penyakit keganasan ini dengan hipertermia; yaitu dengan sengaja menaikkan suhu tubuh penderita dengan mengubah suhu lingkungan selama beberapa saatla. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kenaikan suhu tubuh mungkin mengandung berbagai manfaat yang selama ini tidak disadari.
KEPUSTAKAAN
1. Pautrizel AN, Mattern P, Capbern A dkk. Influence d'une ambi- ance thermique elevee sur revolution de la trypanosomiase experi- mentale de la souris. CR Acad Sci Paris 1977; 284 : 2187–90.
2. Otieno LH. Influence of ambient temperature on the course of
experimental typanosomiasis in mice. Ann Trop Med Parasitol. 1972; 66:15–24.
3. Tribouley J, Tribouley–Duret J, Appriou M dkk. Influence de la temperature ambiante sur revolution de Schistosoma mansoni chez la souris. Annales de Parasitologie Paris, 1977; 52 : 629–36.
4. Lycke E, Hermodsson S, Kristensson K dkk. The herpes simplex virus encephalitis in mice in different environmental temperature. Acta Path Micro Scand. Sect. B, 1974; 79 : 502–10.
5. Walner, D.L. dan Boring, W.D: "Factors influencing host-virus interaction. III. Further studies on the alteration of coxsackie virus infection in adult mice by environmental temperature", J. ImmunoL 1958; 86 : 39–43.
6. Cole GA, Wisseman CL. The effects of hyperthermia on dengue virus infection of mice. Proc Soc Exp BioL (N.Y) 1969; 130 : 359–63.
7. Bell JF, Moore GJ. Effects of high ambient temperature on various stage of rabies virus infection in mice. Inf Immun. 1974; 10 : 510–4.
8. Herrington LP. The heat regulation of small laboratory animal at various experimental temperature. Am J Physiol. 1940; 129 : 123–39.
9. Carmichel LE, Barnes FD, Percy DH. Temperature as a factor in resistance of young puppies to canine herpesvirus. J Inf Dis 1960; 120 : 669–78.
10. Furuchi S, Shimizu J. Effect of ambient temperature on multiplication of attenuated transmissible gastroenteritis virus in the bodies of newborn piglets. Inf Immun. 1976; 13 : 990–2.
11. Weinstein MP, lannini PB, Stratton CW. Spontaneous bacterial peritonitis. A review of 28 cases with emphasis on improved survival and factor influencing prognosis", Am. J. Med. 1978; 64 : 592–594.
12. Husseini RH, Sweet C, Collie MH dkk. Elevation of nasal viral levels by suppression of fever in ferrets infected with influenza virus of difference virulence. J Infect. Dis. 1982; 145 : 520–4.
13. Russell WJ, Taylor SA, Sigel MM. Clearance of bacteriophage in poikilothermic vertebrates and the effect of temperature. J Reticuloendoth Soc. 1976;19 : 91–6.
14. Covert JB, Reynold WW. Survival value of fever in fish. Nature 1977; 267 : 43–5.
15. Kluger MJ, Ringler DH, Anver MR. Fever and survival. Science 1975; 188 : 166–8.
16. Casterlin, ME, Reynolds WW. Behavioral fever in crayfish. Hydrobiologia 1977; 56 : 99–101.
17. Purtilo DT, Walsh GP, Storrs EE dkk. Impact of cool temperature on transformation of human and armadillo (Dasypus noveminctus Linn) as related to leprosy. Nature 1974; 248 : 450-2.
18. Dickson JA, Shah SA. Hyperthermia: the immune response and tumor metastasis. Natl Cancer Inst Monogr. 1982; 61 : 183–92.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 37

Sebelum atau Sesudah Makan ? Interaksi Obat dengan Makanan
DR Mathilda B. Widianto Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Dept. Farmasi Institut Teknologi Bandung, Bandung
PENDAHULUAN
Obat A harus diminum dengan sedikit air (tanpa digigit) setelah makan; obat B sebaiknya diminum setengah jam setelah makan. Seringkali pasien menjadi bingung dan menanyakan kepada dokternya pada kunjungan berikutnya, atau me-nanyakan kepada petugas di apotek. Untuk dapat memberikan nasehat yang tepat tentu saja kita barns mengetahui dasar yang menentukan peraturan tersebut.
Dasar yang menentukan apakah obat diminum sebelum, selama atau setelah makan tentunya adalah karena absorpsi, ketersediaan hayati serta efek terapeutik obat bersangkutan, yang amat tergantung dari waktu penggunaan obat tersebut serta adanya kemungkinan interaksi obat dengan makanan itu sendiri. Cukup banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelidiki hal ini.
Kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan dapat terjadinya interaksi obat dengan makanan adalah : • Perubahan motilitas lambung dan usus, terutama kecepatan pengosongan lambung dari saat masuknya makanan; • Perubahan pH, sekresi asam serta pro duksi empedu; • Perubahan suplai darah di daerah splanchnicus dan di mu-kosa saluran cerna; • Dipengaruhinya absorpsi obat oleh proses adsorpsi dan pembentukan kompleks; • Dipengaruhinya proses transport aktif obat oleh makanan; • Perubahan biotransformasi dan eliminasi.
Dari semua pengaruh ini, pengaruh yang terbesar pada interaksi obat dan makanan adalah laju pengosongan lambung. FAKTOR YANG MENENTUKAN LAJU PENGOSONGAN LAMBUNG
Walaupun sering dianggap bahwa sebagian besar obat di-absorpsi di lambung, sesungguhnya ususlah yang amat ber-peran pada absorpsi obat karena luasnya 1000 kali lebih
besar daripada lambung. Bahkan senyawa asam lemah seperti asetosal di mana'persyaratan untuk terjadinya absorpsi optimal terdapat di lambung, absorpsi di sini hanya sekitar 10% nya. Selebihnya, sisa yang 90%' sebagian besar diabsorpsi di usus halus. Pada kasus-kasus tertentu misalnya setelah. pemberian laksansia atau penggunaan preparat retard, maka di usus besarpun dapat terjadi absorpsi obat yang cukup besar. Karena besarnya peranan usus halus dalam hal ini, tentu saja cepatnya makanan ,masuk ke dalam usus akan amat mempengaruhi ke-cepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi.
Peranan jenis makanan juga berpengaruh besar di sini.Jika makanan yang dimakan mengandung komposisi 40% karbo-hidrat, 40% lemak dan 20% protein maka walaupun pe-ngosongan lambung akan mulai terjadi setelah sekitar 10 menit, proses pengosongan ini baru berakhir setelah 3 sampai 4 jam. Dengan ini selama 1 sampai 1,5 jam volume •lambung tetap konstan karena adanya proses-proses sekresi. Dengan kondisi semacam ini separuh dari jumlah makanan yang dimakan telah meninggalkan lambung dalam waktu 2-3. jam. Jika makanan yang dimakan lebih ringan, maka waktu paruhnya sekitar 0,5 sampai 1 jam, dan jika yang masuk hanya air maka waktu paruhnya hanya sekitar 15 menit.
Tidak saja komposisi makanan, suhu makanan yang di-makanpun berpengaruh pada kecepatan pengosongan lambung ini. Sebagai contoh makanan yang amat hangat atau amat dingin akan memperlambat pengosongan lambung.
Ada pula peneliti yang menyatakan pasien.yang gemuk akan mempunyai laju pengosongan lambung yang lebm lambat daripada pasien normal. Nyeri yang hebat misalnya migren atau rasa takut, juga obat-obat seperti antikolinergika (misal atropin, propantelin), antidepresiva trisiklik (misal amitriptilin, imipramin) dan opioida (misal petidin, morfin) akan memperlambat pengosongan lambung. Sedangkan percepatan pengosongan lambung diamati setelah minum cairan dalam jumlah besar, jika tidur pada sisi kanan (berbaning pada sisi
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 38

kiri akan mempunyai efek sebaliknya,) atau pada penggunaan obat seperti metokiopramida atau khinidin.
Jelaslah di sini bahwa makanan mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung, maka adanya gangguan pada absorpsi obat karenanya tidak dapat diabaikan. Yang patut diper-timbangkan hanyalah apakah interaksi tersebut berarti secara klinis atau tidak. GANGGUAN ABSOPRSI – ARTI KLINIS
Absorpsi parasetamol pada kondisi perut kosong akan lebih besar jika dibandingkan dengan setelah makan. Kadar plasma maksimum yang pada keadaan perut kosong dicapai setelah 40 menit, baru akan dicapai dalam 2,2 jam jika di-lakukan setelah makan, dan kadar yang dicapai juga lebih rendah. Akan tetapi ketersediaan hayati absolut (jumlah parasetamol yang masuk dalam darah dibandingkan jika di-berikan secara iv) tetap. Jika misalnya obat ini dimaksudkan untuk mengobati nyeri akut, tentu saja perlambatan absorpsi ini tidak diingini karena sangat berarti secara terapeutik. Jika mengenai antibiotika, maka pertanyaan apakah akan berarti secara klinis atau tidak, agak sulit dijawab. Misalnya sefaleksin jika digunakan dalam keadaan lambung kosong akan diabsorpsi lebih cepat dibandingkan jika digunakan
Gambar 1. Kadar plasma sefaleksin 500 mg yang digunakan dalam lambung kosong dibandingkan pemberian setelah makan.
setelah makan (Gambar 1). Walaupun ketersediaan hayatinya sama, adanya perbedaan laju absorpsi ini mungkin berguna, apalagi kadar optimal yang dapat dicapai pun berbeda. Se-baliknya jika digunakan setelah makan, dalam waktu 2,6 jam kadar yang cukup tinggi akan dipertahankan, yang lebih lama dibandingkan penggunaan pada lamb ung kosong (1,8 jam). Pada penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme tertentu, waktu kontak yang lama ini tentu lebih menguntungkan. Sedangkan pada mikroba yang tidak begitu mudah diatasi dengan selafeksin tentu kadar plasma yang tinggi lebih bermanfaat. Perbedaan Cara Pemberian
Yang lebih kompleks tentunya adalah pengaruh berbagai
makanan pada kadar serum dan otomatis terhadap efek terapeutik obat jika bentuk sediaan berbeda-beda, seperti sirup, tablet retard, tablet salut yang resisten terhadap getah lambung dan sebagainya.
Asam valproat misalnya, yang digunakan untuk menangani epilepsi, jika digunakan dalam bentuk sirup setelah makan, seperti terlihat juga pada parasetamol dan sefaleksin, akan diperlambat absorpsinya; kadar serum maksimal pun akan lebih kecil (Gambar 2). Absorpsi akan diperlambat pula jika
Gambar 2. Kadar serum Valproat Na 600 mg dalam sediaan sirup, preparat retard yang larut dalam asam lambung dan preparat yang baru larut dalam cairan usus, pada lambung kosong dan setelah makan.
digunakan bentuk tablet retard yang larut dalam getah lam-bung, meskipun kadar maksimum serum tetap. Sebaliknya bila diberikan bentuk sediaan yang resisten terhadap getah lambung, maka jika digunakan setelah makan, absorpsi akan amat 'diperlambat (lag-time). Pada keadaan lambung kosong lag time ini berkisar sekitar 2,1 jam dan jika digunakan setelah makan bergeser menjadi sekitar 7,6 jam. Jika dilihat pula bahwa pada obat-obat antiepilepsi kepekaan tiap individu bervariasi maka harga ini akan dapat berkisar menjadi antara 3 sampai 13 jam. Sedangkan pada keadaan lambung kosong, mula kerja obat ini kurang lebih seragam yaitu 1,8 sampai 2,7 jam. Karena itu jika dipilih preparat asam valproat yang baru dapat larut dalam usus dan digunakan setelah makan, dapat menghasilkan perbedaan, kadar serum yang cukup
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 39

besar sehingga mungkin terjadi dosis berlebih atau terlalu sedikit. Perbedaan komposisi makanan
Wallusch dkk melihat pengaruh berbagai komposisi ma-kanan pada absorpsi indometasin (Gambar 3). Seperti juga -obat-obat lain yang sudah dibahas, absorpsi indometasin jika digunakan sesudah makan juga akan diperlambat, perlambatan ini paling besar jika makanan banyak mengandung karbohidrat. AUC tidak dipengaruhi baik oleh perbedaan komposisi makanan maupun akibat penggunaan setelah makan. Akan tetapi di.sini -- walaupun ada perlambatan absorpsi dan dengan demikian juga perlambatan timbulnya efek -- arti klinisnya hampir tidak ada. Jadi untuk antiflogistika ini yang barangkali lebih berperan adalah waktu makan sedangkan susunan makanan tidak begitu penting. BERKURANGNYA KETERSEDIAAN HAYATI
Penggunaan obat bersama makanan tidak hanya dapat menyebabkan perlambatan absorpsi tetapi dapat pula mem-pengaruhi jumlah yang diabsorpsi (ketersediaan hayati obat bersangkutan).
Penisilamin yang digunakan sebagai basis terapeutika dalam menangani reumatik, jika digunakan segen. setelah makan, ketersediaan hayatinya jauh lebih kecil dibanding- kan jika tablet tersebut digunakan dalam keadaan lambung kosong (Gambar 4). Ini akibat adanya pengaruh laju pe-ngosongan lambung terhadap absorpsi obat. Akibat lain yang ikut berperan adalah pH, ketidakstabilan penisilamin, pem-bentukan kompleks dan proses oksidatif yang terjadi. Pengaruh pH
Jika kita lihat pH lambung dan usus dua belas jari setelah makan, maka di lambung (sebagai akibat netralisasi lambung oleh makanan) dalam waktu satu jam pH akan bergeser ke pH yang lebih tinggi, maksimum sekitar pH 5. Sebaliknya di usus dua belas jari pH akan turun dan dalam waktu 0,5 sampai 3 jam setelah makan, rata-rata pH sekitar 5,5.
Jika obat diminum setelah makan tentu saja di samping
Gambar 4. Kadar plasma tablet penisilamin 500 mg yang digunakan sebelum atau setelah makan.
memperlambat absorpsi obat, perubahan pH ikut berpengaruh. Pada antibiotika seperti penisilin, eritromisin, rifampisin, tetrasiklin, ketersediaan hayatinya lebih kecil karena se- bagian senyawa ini tidak stabil dalam suasana asam, atau seperti pada tetrasiklin dan rifampisin pada pH di atas 3 kelarutannya akan berkurang. Kurangnya kelarutan pada Ph di atas 3 ini juga berlaku untuk kētokonazol dan diazepam. Pada digoksin dan turunannya Q--asetildigoksin atau metil-
Gambar 3. Pengaruh komposisi makanan pada kadar plasma kapsul
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 40

digoksin pH di bawah 3 akan menyebabkan hidrolisis sehingga akan mengurangi absorpsinya. Pembentukan kompleks
Pembentukan kompleks atau khelat dapat pula memper-kecil ketersediaan hayati obat-obat yang diminum setelah makan. Contoh yang paling dikenal adalah berkurangnya absorpsi tetrasiklin jika diminum bersama atau setelah makan-an yang kaya kalsium, seperti susu atau produk-produk susu. Juga dengan antasida misalnya gel aluminium hidroksida, kerja tetrasiklin akan amat berkurang karena terhambatnya absorpsi. Kekecualian terlihat hanya pada doksisiklin (Vibramycin®) yang ketersediaan hayatinya hanya sedikit dipengaruhi oleh susu. Kadar serum maksimum praktis tidak berubah, hanya eliminasinya terlihat jauh lebih cepat. Karena interaksinya dengan logam-logam bervalensi 2 atau 3 maka harus diperhatikan juga penggunaan tetrasiklin dengan berbagai tonika yang mengandung senyawa besi. Terganggunya transport
Contoh lain berkurangnya ketersediaan hayati jika di-minum setelah makan, adalah obat anti parkinson levodopa. .
Mekanisme kerjanya agak berbeda dari contoh di atas. Berbeda dengan kebanyakan obat yang diabsorpsi secara pasif, levodopa diabsorpsi secara aktif (pembawa asam amino). Pembawa ini juga digunakan oleh asam amino lain, sehingga jika banyak asam amino dalam makanan akan terjadi kompetisi dengan pembawa ini. Jadi makanan kaya protein, akan menuwkan kadar serum dan akibatnya akan terjadi apa yang kita namakan fenomena on–off PERBAIKAN ABSORPSI MEMPERTINGGI KETERSEDIA-AN HAYATI
Fenitoin juga diduga mempunyai transport aktif. Karena sistem transport ini diaktifkan oleh transport glukosa maka dengan makanan yang kaya karbohidrat absorpsi fenitoin akan diperbesar.
Meningkatnya absorpsi obat jika diberikan setelah makan
juga terjadi pada beberapa obat lain. Contoh yang sering dikemukakan adalah antimikotikum oral griseofulvin (misal Fulcin®. Karena sifat lipofilnya, senyawa ini sukar larut dalam air, sehingga ketersediaan hayatinya bervariasi (30–70%), konsentrasi efektif tidak. akan dicapai. Tetapi jika griseofulvin diberikan bersama makanan yang kaya lemak misalnya susu maka absorpsi akan meningkat dengan nyata.
Obat yang juga meningkat ketersediaan hayatinya pada pemberian setelah makan adalah etretinat yang digunakan pada penanganan psoriasis (Gambar 5). Di sini dengan pemberian bersama makanan yang kaya lemak, misalnya susu akan dicapai kadar serum yang lebih tinggi daripada pada keadaan lambung kosong. Ini disebabkan karena lipofilitas obat yang tinggi, kelarutan obat dalam getah lambung menjadi kurang baik sehingga absorpsi dalam keadaan lambung kosong sedikit.
Pemblok reseptor beta propranolol akan diabsorpsi lebih baik jika digunakan setelah makan walau komposisi makanan tidak begitu berpengaruh (Gambar 6). Walaupun demikian pada keadaan lambung kosong absorpsi propranolol juga hampir sempurna. Peningkatan ketersediaan hayati obat pemblok reseptor beta dipengaruhi juga oleh besarnya first-pass effect nya. Karena itu sampai saat ini diduga bahwa interaksi obat-obat ini dengan makanan akan mengurangi first-pass effect obat. Sebagaimana diketahui pemasukan makanan akan meningkatkan suplai darah di daerah spanchni-cus serta .di mukosa lambung dan usus. Selain itu besarnya pe-nguraian pemblok beta• yang first-pass effectnya tinggi misal-nya propranolol tergantung langsung dari suplai darah di hati dan dengan demikian tergantung dari proses pengangkut-an farmakon tersebut. Pendapat ini mungkin benar dan dapat dibuktikan dalam contoh kombinasi propranolol dan hidra-lazin. Pada penggunaan kombinasi ini terlihat dengan jelas kadar plasma propranolol yang jauh lebih tinggi daripada pada pemberian tunggal. Ini disebabkan karena pemberian hidralazin meningkatkan suplai darah pada organ peng- absorpsi dan hati sehingga pada kombinasi ini first pass effect
Gambar 5. Kadar plasma kapsul etretinat 100 mg pada lambung kosong, dengan susu 0,5 liter atau makanan yang banyak mengandung lemak.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 41

Gambar 6. Kadar plasma propranolol (1 mg/kg) pada lambung kosong dan setelah makanan yang banyak mengandung protein atau karbohidrat.
propranolol juga berkurang.
PERUBAHAN METABOLISME OBAT AKIBAT MAKANAN Makanan dapat juga mempengaruhi metabolisme obat.
Interaksi yang akan dibahas di sini bukan interaksi akut seperti yang sudah dibahas tetapi merupakan interaksi akibat kebiasaan makan seseorang. Daging bakar
Seperti kita. ketahui pembakaran daging dengan arang menghasilkan hidrokarbon polisiklik seperti benzpiren. Se-nyawa ini merupakan penginduksi enzim yang poten, karena itu telah diteliti pengaruh konsumsi makanan demikian ter-hadap metabolisme obat. Sebagai model digunakan fenasetin yang diberikan dalam dosis 900 mg. Hasil yang diperoleh cukup mencengangkan: pemberian daging bakar pada setiap periode makan selama 4 hari berturut-turut akan menurunkan kadar serum fenasetin dengan drastis. Yang menarik adalah bahwa waktu paruh eliminasi fenasetin pada diet semacam ini tidak berubah. Ini tentunya memperkuat dugaan bahwa terjadi peningkatan metabolisme fenasetin terutama dalam saluran cerna atau pada saat melewati hati pertama kali. Rokok
Asap rokok juga mengandung hidrokarbon polisiklik. Tidaklah mengherankan bahwa pada berbagai penelitian di-temukan adanya induksi enzim yang menyebabkan peningkatan metabolisme serta peningkatan bersihan (clearance) bercagai obat.
Ekskresi teofilin pada perokok jauh lebih tinggi daripada pada bukan perokok. Dibandingkan dengan bukan perokok, dosis teofilin yang dibutuhkan 'perokok sekitar 25% lebih tinggi. Lagipula variasi individu pada perokok cukup besar sehingga keamanan penggunaan obat juga relatif rendah. Ternyata induksi enzim yang disebabkan rokok akan sulit kernbali ke normal lagi. Untuk ini dibutuhkan paling sedikit
6 bulan setelah rokok dihentikan untuk mendapatkan harga bersihan yang tetap.
Senyawa lain yang dieliminasi dengan cepat pada perokok adalah nikotin, kofein, lidokain, propranolol, imipramin, oksazepam, fenasetin, pentazosin. Yang agak ditinggikan antara lain alkohol. Sedangkan bersihan yang tidak berubah adalah antara lain kodein, petidin, diazepam, klordiazepoksida (walaupun pada penggunaan obat ini efek sedasi yang terjadi pada perokok lebih kecil daripada bukan perokok), nortriptilin, prednison, prednisolon. Alkohol
Pada umumnya pemasukan akut alkohol akan menginhibisi enzim sehingga eliminasi obat diperlambat, sedangkan peng-gunaan kronis akan berakibat sebaliknya. Tiramin dalam makanan
Interaksi yang juga amat penting adalah antara tiramin (simpatomimetik tak langsung) yang ada dalam makanan dengan obat-obat inhibitor monoaminoksidase yang digunakan sebagai antidepresiva. Interaksi yang terjadi menyebabkan timbulnya krisis hipertensi yang kadang-kadang disertai perdarahan intrakranial yang dapat berakhir dengan kematian.
Tiramin ada dalam jumlah besar dalam makanan seperti keju, tempe, hati, ekstrak ragi atau ekstrak daging. Inhibitor monoaminoksidase ini menghambat penguraian noradrenalin endogen dan dengan ini meningkatkan kadar noradrenalin di sistem saraf pusat dan di perifer. Simpatomimetika tak lang-sung seperti tirarnin membebaskan juga noradrenalin. Dengan demikian jelaslah mengapa dapat timbul gangguan kardio-vaskular seperti diterangkan di atas. Apalagi tiramin ini juga dihambat penguraiannya oleh IMAO tersebut. Karena itu pada penggunaan tranilsipromin atau simpatomimetika lain bahaya ini perlu diperingatkan. Berbeda misalnya dengan selegilin, senyawa ini pada dosis harian di bawah 10 mg hanya menghambat MAO-B yang berperan pada penguraian dopamin di sel glia.
KESIMPULAN Dilihat dari semua interaksi yang mungkin timbul pada
penggunaan mananan bersama obat-obatan terlihat bahwa yang terutama adalah interaksi pada tahap absorpsi. Umumnya penggunaan obat bersama makanan akan memperlambat absorpsi. Sebagai contoh adalah aspirin, parasetamol, indo-metasin, tenoksikam, amoksisilin, sefaleksin, kaptopril, pen-toksifilin, asam valproat. Jika obat digunakan bukan untuk keadaan akut, maka perlambatan absorpsi ini tidak berarti secara terapeutik karena pada penggunaan selanjutnya kadar serum juga akan naik.
Yang berarti adalah perubahan ketersediaan absolitt atau-pun relatif dari obat. Ketersediaan yang lebih kecil misalnya terjadi pada ampisilin, sefaleksin, tetrasiklin, kotokonazol, levodopa, teofilin. Peningkatan abssorpsi yang mengakibatkan peningkatan ketersediaan hayati terjadi misalnya pada griseo-fulvin, nitrofurantoin, propranolol, metoprolol, fenitoin, karbamazepin, senyawa litium, etretinat. Bagi senyawasenyawa ini saat penggunaan obat amat menentukan.
Belum lagi berbagai bentuk sediaan retard yang pengaruh dan interaksinya dengan makanan bervariasi, misalnya teofilin. Bahkan teofilin yang diproduksi berbagai pabrik, ketersediaan hayatinya amat berbeda satu sama lain (Gambar 7). Ada preparat teofilin yang jika digunakan bersama makanan akan mempunyai ketersediaan hayati separuh dari ketersedaan
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 42

Gambar 7. Kadar serum 2 preparat retard teofiin yang digunakan dalam keadaan lambung kosong atau setelah makan.
hayati dalam keadaan lambung kosong, dan ada preparat yang justru dengan penggunaān bersama makanan ketersedia- an hayatinya meningkat duakali daripada keadaan lambung kosong. Jelaslah bahwa penggunaan obat harus dsesuaikan dengan sifat obat dan interaksi yang mungkin terjadi.
Bagi preparat analgetika dan antiflogistika yang pada pang gunaan dalam keadaan lambung kosong senantiasa menyebab-kan keluhan gastrointestinal, penggunaan bersama makanan adalah usaha yang terbaik.
Antasida misalnya sebaiknya diberikan sekitar 1 – 1,5-jam setelah makan (segera setelah pH 2., d'icapai kembali), supaya dapat terjadi pendaparan asam lambung dengan efektif di antara kedua waktu makan. Atas dasar yang sama yaitu untuk menurunkan sekresi asam pada malam hari, pemblok reseptor H2 seperti simetidin, ranitidin dan famotidin diberikan se-belum tidur. Beberapa antibiotika seperti penisilin, sefalosporin atau eritromisin – jika pasien tahan – sebaiknya diberikan dalam keadaan lambung kosong bersama,banyak air untuk
meningkatkan kadar obat dalam serum. Jelaslah bahwa anjuran umum untuk mengatakan bahwa
obat diminum setelah makan atau sebaliknya sebelum makan tidaklah mungkin diberlakukan bagi semua jenis obat. Untuk kondisi-kondisi akut, hendaknya ikut dipertimbangkan pula cara pemberian obat ini agar pengobatan dapat dilakukan dengan efektif.
KEPUSTAKAAN
1. Nimmo WS et al. Br J Clin Pharmacoi. 1975; 2, 509-13. 2. Alpsten M et aL Eur J Clin PharmacoL 1982;-22, 57-61. 3. Wallusch WW et aI. 1nt J Clin Pharmacol. 1978;16, 40-4. 4. Osman MA. Clin Pharmacol Thar. 1983; 33 : 465-70. 5. Colburn WA. J Clin PharmacoL 1985; 25 : 583-9. 6. Fricke U. Med. Mo. Pharm., 1988;11 (5), 169-80. 7. McLean AJ. et aL Clin. PharmacoL Ther. 1981; 30 : 31-4. 8. Karim A. et al. Clin. PharmacoL Ther. 1985; 38 : 77-83.

Zat Kebal Bawaan Campak dan Pengaruhnya terhadap Imunisasi Campak
di Daerah Endemik Campak
Bambang Heriyanto, Djoko Yuwono Pusat Penelitian Penyakit Menular, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan R.I., Jakarta
SUMMARY
A trial of measles vaccination was done in an endemic area of measles virus infection, in Sukoharjo regency, Central Java province. The study involving 293 healthy children from 6–24 months of age. A further live-attenuated-measles vaccine, Schwarz strain, produced by Perum Bio Farma was used in the study. The virus titer of vaccine was 101'5 /0.1 ml at the time of prevaccination, while postvaccination virus titer was 102.8/0.1 ml, the vaccine was administered through subcutaneous injection. The hemaglutination inhibition test was performed to detect measles antibody in the serum which was collected by filter paper strip from finger prick, at the time of prevaccination and 3 months after vaccination. The result of the study revealed that measles vaccination among children 6 – 8 months of age with positive maternal measles antibody, caused no GMT antibody increase, with GMT: 4 (in log 2). However the optimal seroconversion reate (100%) after measles vaccination was reached among children 9–14 months of age with no detectable measles antibody initially. The antibody increase was from < 3.0 to 5.3 (in log 2). The study also indicated that based upon serological finding, immunization among children below 9 months of age in measles virus endemic area is quite unnecessary.
PENDAHULUAN
Imunisasi campak di Indonsia diberikan sejak umur 9–14 bulan dengan dosis tunggal secara suntikan subkutan, sedangkan imunisasi campak di negara 'maju diberikan pada anak setelah usia 12 bulan1,2. Di negara berkembang imunisasi campak dianjurkan untuk diberikan lebih awal dengan maksud memberikan kekebalan campak sedini mungkin, sebelum ter-kena infeksi virus campak secara alami3'4 . Pemberian irnunisasi lebih awal rupanya terbentur oleh adanya zat kebal bawaan campak yang berasal dari ibu yang ternyata dapat menghambat terbentuknya zat-kebal-campak dalam tubuh anak secara sempurna, sehingga imunisasi campak ulangan masih harus diberikan 4–6 bulan kemudian3,5,6
Hasil penelitian survai serologi di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa berdasarkan penyebaran virus
campak ada dua daerah yang berbeda secara serologik, yakni daerah endemik dan non endemik campak7. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa imunisasi campak yang di Indonsia diberikan pada usia 9–14 bulan, pada kenyataannya inengalami hal yang bertentangan. Per- tama di daerah endemik campak ternyata imunisasi campak yang diberikan pada usia 9–14 bulan diterima juga oleh anak-anak yang telah memiliki zat kebal campak yang di- dapat akibat infeksi alamiah. Kedua, sebaliknya di daerah non endemik ternyata sampai usia 2 tahun masih banyak anak-anak yang rentan terhadap infeksi virus campak, se- hingga imunisasi campak pada daerah non endemik tetap diperlukan7,8.
Untuk mengetahui pengaruh zat-kebal-campak baik yang berasal dari ibu ataupun yang diperoleh secara alamiah
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 44

terhadap imunisasi campak, maka telah dilakukan suatu penelitian ujicoba vaksin campak di suatu daerah endemik campak ,di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.
Dari penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan dalam program imunisasi campak di Indonesia. BAHAN DAN CARA KERJA
Sampel dan daerah penelitian. Penelitian dilakukan di kabupaten Sukoharjo,JawaTengah. Sejumlah 293 anak sehat umur antara 6-24 bulan yang
belum pernah mendapat imunisasi campak diikut sertakan dalam penelitian ini. Imunisasi dilakukan oleh juru imunisasi dan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh seorang dokter dari Puskesmas setempat. Sampel berupa darah yang diambil dari ujung jari ditampung pada lempengan kertas saring berukuran 4 x 25 mm2, setiap sampel memerlukan dua lempengan kertas saring. Pengambilan sampel dilakukan sebelum imunisasi dan 3 bulan setelah imunisasi. Vaksin campak.
Vaksin campak yang dipakai adalah vaksin campak yang mengandung virus hidup yang telah dilemphkan, berasal dari galur Schwarz, yang dikemas oleh.Pērum Bio Farma. Vaksin dibeiikan secara suntikan subkutan dengan dosis 0,5 ml. Pemeriksaan potensi vaksin pravaksinasi dan pascavaksinasi dilakukan dengan menghitung infektivitas (TCID50) pada biakan sel Vero secara mikroteknik. Titer virus vaksin pra vaksinasi sebesar 103,5/0,i ml, setelah imunisasi ternyata titer virus vaksin turun mencapai 102,3/0,1 ml. Pemeriksaan zat kebal campak.
Untuk mendapatkan cairan serum, lempengan kertas saring yang telah berisi darah kering dilarutkan ke dalam larutan 12,5% kaolin dalam larutan garam fosfat, sehingga konsentrasi serum menjadi 1 : 8; yang merupakan konsentrasi serum -awal yang dipakai dalam pemeriksaan serologi. Untuk menghilangkan zat penghambat non spesifik di dalam serum, perlu dilakukan adsorpsi dengan darah kera yang telah diuji sensitivitasnya terhadap virus campak, sebanyak 50 ul 50% darah kera ditambahkan ke dalam ekstrak serum jernih dan ditempatkan pada suhu 4°C semalam suntuk. Ekstraksi serum dipisahkan dengan memutar pada kecepatan 2000 ppm selama 10 menit, selanjutnya cairan serum slap untuk diperiksa.
Pemeriksaan zat-kebal-campak dilakukan dengan uji hambatan hemaglutinasi cara Rosen L. (1961). Antigen campak yang dipakai galur Toyoshima, dengan kadar 4 HA unit. Pengenceran serum dari 1 : 8 sampai 1 : 512. Reaksi antigen antibodi selama 1 jam pada suhu kamar. Reaksi hemaglutinasi darah kera selama I jam pada suhu 37°C, sedangkan pembaca-an basil dilakukan dengan mengamati terbentuknya hemaglu-tinasi darah kera oleh virus campak. Terbentuknya hemaglu-tinasi berarti tidak adanya zat kebal campak dalam darah (seronegatif). HASIL
Pemeriksaan serologi pada populasi anak sebelum imunisasi. campak memperlihatkan bahw 74,1% (n=293) anak di
daerah penelitian telah memiliki kekebalan terhadap campak, dengan perincian 56,1%; 84,8% dan 75,2% masing-masing pada usia 6-8 bulan, 9-14 bulan dan 15-24 bulan. (Tabel 1). Pemeriksaan zat-kebal-campak pra imunisasi dan pasca imunisasi, pada anak-anak usia 6-8 bulan yang telah memiliki kekebalan campak pada saat pra imunisasi memperlihatkan tidak adanya kenaikan titer virus rata-rata (GMT), yaitu dari 4 menjadi 4 (log 2), sedangkan pada kelompok usia 9-14 bulan dan 15-24 bulan terjadi kenaikan masing-masing dari 3,9 menjadi 5,2 (log 2) dan 3,9 menjadi 5,6 (log 2) (Tabel 2). Tabel 1. Status kekebalan anak-anak terhadap virus campak di daerah
endemik campak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, se-
belum imunisasi campak tahun 1985.
Kelompok usia Kumulatif seropositif (%)
Jumlah sampel
6-8 bulan 9-14 bulan 15-24 bulan
32 (56,1) 67 (84,8) 118 (75,2)
57 79
157
Jumlah 217 (74,1) 293
Tabel 2. Hasil pemeriksaan titer zat-kebal-campak pada berbagai ke-
lompok usia sink pra dan pasca imunisasi, dengan zat-kebal- campak pada saat praimunisasi.
Kelompok usia (bulan)
6 - 8 9 - 14 15 - 24 Titer
zat kebal (uji Hl)
Pra Pasca Pra Pasca I Pra Pasca<8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 11 1 16 8 3 12 0 38 8 32 0 3 1 11 7 33 64 0 1 0 4 0 7
128 0 1 0 0 0 6 256 0 0 0 0 0 1 512 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 8 15 15 56 56
GMT (log 2) 4 4 3,9 5,2 3,9 5,6
Serokonversi (%) 25,0 13,3 42,9
GMT : liter rata-rata zat-kebal-campak (logaritma 2)
Pemeriksaan kadar zat-kebal-campak pada anak-anak yang pada saat pra imunisasi belum memiliki zat-kebal-campak ter-nyata memperlihatkan . adanya kenaikan kadar zat-kebal-campak sebesar 5,0 (log 2); 5,3 (log 2) dan 4,8 (log 2), masing-masing pada kelompok usia 6-8 bulan, 9-14 bulan dan 15-24 bulan. Selanjutnya penghitungan rasio serokonversi setelah imunisasi campak memperlihatkan adanya serokonversi optimal 100% pada kelompok usia 9-14 bulan, sedangkan rasio-serokonversi sebesar 93,3% dan 94,4% dicapai pada kelompok usia 6-8 bulan dan 15-24 bulan (Tabel 3).
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 45

Tabel 3. Hasil pemeriksaan titer zat-kebal-campak pada berbagai ke-lompok usia anak pra dan pasca imunisasi, yang tidak memiliki zat kebal pada saat praimunisasi.
Kelompok usia (bulan)
6 – 8 9 – 14 15 – 24
Titer zat kebal (uji HI)
Pra Pasca Pra Pasca Pra Pasca
<8 11 1 9 0 21 1
8 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 4 32 0 6 0 6 0 13 64 0 1 0 3 0 0
128 0 1 0 0 0 3 256 0 1 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0
Jumlah 11 11 9 9 21 21
GMT (log 2) <3 5,0 <3 5,3 <3 4,8
Serokonversi
(%) 93,3 100 94,4
Pemeriksaan zat-kebal-campak pada anak-anak yang tidak
mendapat imunisasi campak memperlihatkan adanya selisih titer rata-rata zat-kebal-campak yang paling tinggi pada kelompok usia 9–14 bulan, hal ini membuktikan bahwa kelompok usia 9–14 bulan dapat memberikan tanggap kebal yang optimal secara alamiah. Sedangkan titer rata-rata zat,-kebal-campak pada . kelompok usia 6–8 bulan mencapai titer sebesar 5,5 (log 2), hal ini menunjukkan bahwa infeksi virus campak tertinggi ada pada kelompok usia 6–8 bulan (Tabel4). Tabel 4. Titer zat-kebal-campak pada anak-anak yang tidak mendapat
imunisasi campak, selang pengambilan darah pertama dan ke-dua selama 3 bulan.
Kelompok usia (bulan)
6–8 .9–14 15–24 Titer
zat kebal (ujiHI)
Pra Pasca Pra Pasca Pra Pasca
<8 4 0 2 0 15 1 8 0 0 1 0 9 0
16 2 1 2 0 9 9 32 1 2 0 4 2 19 64 0 3 0 0 0 4 128 0 1 0 1 0 1 256 0 0 0 0 0 1 512 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 7 5 5 35 35
GMT (log 2) 4,3 5,5 3,6 5,4 3,6 5,0
Serokonversi (%) 42,9 80 57,1
Penghitungan rasio serokonversi' terhadap anak-anak
yang tidak memiliki zat-kebal-campak pada saat praimunisasi
Tabel 5. Hubungan antara titer zat-kebal-campak dan rasio serokon-versi pada berbagai kelompok usia anak dengan dan tanpa zat-kebal-campak pada saat praimunisasi terhadap kelompok anak pembanding.
Praimunisasi dengan zat kebal
Praimunisasi tanpa zat kebal
Kelompok pembanding
Kelompok usia
(bulan) Titer Serokonv. Titer Serokonv. Titer Serokonv.
6 – 8 9 – 14
15 – 24
0,0* 2,4* 3,2*
25,0 13,3 42,9
31,6** 38,9** 27,5**
93,3 100,0 94,4
2,3* 3,5* 2,6*
42,9 80,0 57,1
Titer : Selisih titer zat-kebal-campak sesudah dan sebelum imuni- sasi campak.
Rasio serokonversi: Perbandingan antara jumlah seronegatif menjadi seropositif campak terhadap jumlah sampel pada masingmasing kelompok usia, atau adanya perubahan titer zatkebal-campak sebesar 4 kali kelipatan pada sampel yang telah memiliki zat-kebal-campak pada saat praimunisasi.
* : lidak berbeda bermakna secara statistik (p > 0,05). ** : Berbeda bermakna secara statistik (p <0,01 ). dilakukan dengan membandingkan jumlah seronegatif yang menjadi seropositif terhadap jumlah keseluruhan sampel pada masing-masing kelompok usia, sedangkan rasio serokonversi terhadap anak-anak yang telah memiliki zat-kebal-campak pada saat praimunisasi dilakukan dengan membandingkan jumlah kenaikan kadar zat-kebal-campak kelihatan terhadap jūmlah sampel pada masing-masing kelompok usia. PEMBAHASAN
Penelitian tentang ujicoba vaksin campak di beberapa negara berkembang telah memperlihatkan adanya beberapa faktor yang menentukan agar imunisasi campak dapat berhasil, salah satu di antaranya adalah umur optimal anak-anak pada saat memperoleh imunisasi campak yang erat kaitannya
dengan kematangan sistem imunitas tubuh anak terhadap vaksin campak3,5,9,10. Akibatnya tidak terdapat keseragaman
dalam menentukan saat pemberian imunisasi campak, rasio serokonversi setelah imunisasi campak yang dihasilkan pada penelitian di masing-masing negara tidak sama.
WHO telah menentukan pemberian imunisasi campak di negara berkembang pada usia 9–14. bulan. Akan tetapi pe-nelitian lebih lanjut ternyata memperlihatkan perlunya pem-berian imunisasi campāk lebih awal dengan maksud memberi-kan kekebalari campak sedini mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi virus campak secara alamiah3,6,10. Hal ini perlu mendapat perhatian khususnya di negara ber-kembang seperti Indonesia, di mana angka kematian tertinggi akibat campak terjadi pada anak-anak di bawah 12 bulan.
Dari penelitian dapat diketahui bahwa imunisasi campak yang telah djlakukan di daerah endemik campak di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada anak-anak usia 6–24 bulan ternyata juga memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan di daerah Jawa Barāt9 yang memperlihatkan hasil rasio sero-konversi optimal 100% apabila imunisasi diberikan pada anak-anak antara usia 9–14 bulan yang pada saat imunisasi tidak memperli1 atkan adanya zat kebal campak di dalam
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 46

Gambar 1. Kurva titer rata-rata zat-kebal-campak setelah imunisasi campak pada anak-anak yang telah memiliki zat-kebal campak saat preimunisasi.
Gambar 2. Kurva titer rata-rata zat-kebal-campak setelah imunisasi dan
rasio serokonversi pada anak-anak yang tidak memiliki zat kebal bawaan campak saat praimunisasi.
serum mereka. Pada penelitian ini selain dicapai rasio sero-konversi optimal pada usia antara 9-14 bulan, titer zat kebal yang dicapai tertinggi juga pada usia tersebut sebesar 5,3 (log 2), sedangkan imunisasi pada usia 6-8 bulan ternyata masih memberikan rasio serokonversi yang cukup tinggi sebesar 93,3% dan titer rata-rata zat kebal sebesar 5,0 (log 2). Jika dibandingkan dengan kelompok anak yang pada saat pra imunisasi telah memiliki zat-kebal-campak dengan titer 4,0 (log 2) pada saat pasca imunisasi, maka secara statistik terdapat perbedaan bermakna (p < 0,01).
Selanjutnya imunisasi pada kelompok usia 9-14 bulan
Gambar 3. Kurva titer rata-rata zat-kebal-campak yang diperoleh se- cara alamiah pada kelompok anak yang tidak mendapat imunisasi campak (kontrol).
meningkatkan kadar zat-kebal dari 3,9 menjadi 5,2 (log 2) dan rasio serokonversi sebesar 13,3%, nilai tersebut meningkat dengan makin bertambahnya usia anak, yaitu dari 3,9 menjadi 5,6 (log 2) dan rasio serokonversi 42,9% pada kelompok umur 15-24 bulan (Tabel 2). Perbandingan antara kelompok anak yang pada saat praimunisasi telah memiliki zat-kebai-campak dengan kelompok yang tidak memiliki zat-kebai-campak. ter-hadap kelompok pembanding ternyata memperlihatkan hasil berbeda bermakna secara statistik, yaitu antara kelompok anak yang pada saat praimunisasi telah memiliki zat kebal campak dengan kelompok yang tidak memiliki zat kebal campak (p < 0,01), sedangkan perbedaan kelompok yang pada saat pra imunisasi telah memiliki zat kebal campak dengan kelompok pembanding, tidak bermakna (p > 0,05), (Tabel 5).
Oleh karena itu imunisasi campak di daerah endemik campak, di mana sebagian besar anak (74,1%) telah memiliki zat-kebal-campak ternyata secara serologik tidak cukup efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa imunisasi.campak di darah endemik campak tidak efektif pada anak-anak di bawah usia 9 bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan serologik. Hasil penelitian serupa inilah yang menggugah para ahli u'ntuk mengembangkan vaksln campak jenis baru yang lebih poten dengan memilih galur virus campak yang telah dimodifikasi, seperti penelitian Dr. Sabin di Meksiko yang menggunakan vaksin campak aerosol, galur Schwarz-Edmonston, yang dapat memberikan titer zat kebal 27 kali lipat, yaitu mencapai 1300 dan 3800 pada anak-anak berusia 4-6 bulan dan 12-24 bulan4,10.
KESIMPULAN DAN SARAN Berpedoman pada hasil serologi dapat diketahui bahwa
tampaknya pemberian imunisasi campak sedini mungkin di daerah endemik campak dengan maksud memberikan ke-kebalan terhadap serangan virus campak di alam ternyata kurang efektif.
Pemberian imunisasi campak pada anak-anak yang tidak memiliki zat-kebal-campak ternyata dapat memberikan zat-
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 47

kebal yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,3 (log 2) dan rasio serokonversi mencapai 100%, apabila diberikan pada usia 9–14 bulan.
Infeksi virus campak secara alami di daerah endemik campak ternyata dapat memberikan zat-kebal-campak yang cukup tinggi.
KEPUSTAKAAN
1. Krugman S. Present Status of Measles and Rubella Immunization in the United States. A Medical Progress Report. I J Pediatr. 1977; 90 (1).
2. Weibel RE, Buynak EB., McLean AA., Hillmen MR. Persistence of Antibody After Administering of Monovalent and Combined Live Attenuated Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccines. Pediatrics, 1978; 61 : 5–11.
3. Ministry of Kenya and World Health Organization. Measles Immunity in the First Year after Birth and the Optimum Age for Vaccination in Kenyan Children. Bull WHO, 1977; 55 : 21–30.
4. Sabin AB., Albrecht P. Takeda AK. Ribeiro BM. Veronesi R. High Effectiveness of Aerosolized Chick Embryo Fibroblast Measles Vaccine in Seven-months-old and Older Infants. J Inf ect. Dis 1985; 152 (6) : 1231–7.
5. King B. Measles Vaccination in a Rural Tanzanian Community. East African Med J 1978; 55 : 252–5.
6. Wu Shaoyuan, Xue Xinqing, Zang Yihan et al. An Investigation of the Causes of Failures in Measles Vaccination in Early Infancy. J Biol Standard, 1982; 10 : 197–203.
7. B Heriyanto, D Yuwono. Status Kekebalan Anak terhadap Virus Morbilli pada Beberapa Daerah Pedesaan di Indonesia. Maj Kesehatan Masyarakat, 1985; XIV : 34, 18–21.
8. Voorhoeve AM, Muller AS, Sculpen TWJ, Germet W, Valkemburg HA, Ensering HE. Agents Affecting Health of Mother and Child in a Rural Area of Kenya. III. The Epidemiology of Measles. Trop. Geogr. Med, 1977; 29 : 428–40.
9. Cukasah U, Rahman O. Kekebalan Bawaan Campak 0–12 bulan dan Serokonversi setelah Imunisasi Campak dari Pengunjung Klink Bayi Sehat RS. Hasan Sadikin. Bandung: Maj Kedokt. 1984; XVII : 1–4.
10. Sabin AB., Arechiga AF., de Castro JF et al. Successful. Immunization of Children With and Without Maternal Antibody by Aerosolized Measles Vaccine. I. Different 'Result With Undiluted Human Diploid Cell and Chick Embryo Fibroblast Vaccines. JAMA 1983; 249 : 2651–62.
11. La Forece FM., Henderson RH., Keja J. The Expanded Programme in Immunization. World Health Forum, 1987; 8 : 2, 208–14.
12. Makino S. Development and Characteristics of Live AIK–C Measles Virus Vaccine, A Brief Report. Rev. Infect. Dis, 1983; 5 (3) : 504–5

ETIKA
Dr. Drs. Rahmatsjah Said S.S. DAJ Psikiater di Rumah Saki/ Jiwa Bogor, Bogor
ETIKA: Teknologi Kedokteran,
untuk Apa dan untuk Siapa ?
Setiap dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi pasal 2 KODEKI 1981.
"Bila perlu, nanti kita scanning kepalanya, kalau dengan obat yang saya berikan ini keluhan bapak belum hilang", demikian kāta seorang doker kepada pasiennya yang datang dengan keluhan nyeri kepala dan nyeri tengkuk yang sudah beberapa bulan terakhir dideritanya. "Mungkin ada kelainan di otak, yang dapat kita periksa dengan CT-Scan", sambung dokter itu menjelaskan kepada pasiennya, seorang pegawai perusahaan asing. Setelah melakukan pemeriksaan rutin dan tidak menemukan kelainan, langsung , saja dokter tersebut menganjurkan pemeriksaan scanning dengan komputer, salah satu teknologi kedokteran mutakhir, apabila obat-obat pe-nenang yang diberikannya tidak memberikan reaksi penyem-buhan. Sejawat itu tidak berusaha menelusuri lebih lanjut riwayat penyakit pasiennya.
Ternyata pasien tersebut mengeluh sakit kepala yang makin berat sejak beberapa bulan terakhir, yang makin terasa jika ia pulang ke rumah. Sekitar waktu itu ia mendapat jabatan yang lebih tinggi di perusahaannya, ini berarti beban kerja yang lebih banyak dan menuntut tanggung jawab yang lebil4 tinggi. Pada saat yang hampir bersamaan ada masalah di rumah yang dihadapinya. Istrinya merasa "tersisih" karena suami sibuk dengan pekerjaan kantor, padahal sang nyonya ini seharihari sibuk mengasuh tiga orang anaknya, yang salah satu di antaranya mempunyai kelainan bawaan. Sementara itu, ia menerima berita dari kampung bahwa orang tuanya terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit yang cukup berat. Menghadapi semua masalah ini, ia tidak mempunyai teman untuk bertukar pikiran atau untuk mencurahkan keluhan-keluhannya. Jika ia sampaikan kepada atasan di kantor, ia khawatir jabatan yang baru didudukinya itu akan ditarik kembali karena bisa saja ia dianggap tidak mampu oleh atasan-nya. Sedangkan di rumah, istrinya pun sudah membuat posisi yang menyudutkannya ke posisi yang tidak mengenakkan. Ditambah masalah orangtuanya nun jauh di kampung halaman. Semua masalah-masalah tersebut dicobanya untuk ditahan sendiri. Ternyata kemudian timbul keluhan-celuhan nyeri kepala dan nyeri tengkuk, yang mendorongnya untuk ber-
obat ke seorarig dokter. Sayangnya sejawat tersebut hanya terpaku kepada keluhan yang disampaikannya saja, tanpa ber-usaha untuk mencari atau menelusuri riwayat penyakitnya lebih lanjut.
Jika kita lihat, setelah dokter tersebut melakukan pe-meriksaan rutin dengan alat-alat yang sederhana, seperti stetoskop dan tensimeter, dan tidak menemukan kelainan, langsung ia memberikan obat penenang ditambah dengan sebuah anjuran untuk melakukan pemeriksaan dengan alat mutakhir dan canggih, tanpa berusaha untuk mencoba me-nelusuri masalah yang melatarbelakangi keluhannya itu. Terkesan adanya suatu kelalaian atau kelemahan dalam anjuran pemeriksaan dengan CT-Scan itu.
Padahal, setiap tindakan dalam dunia kedokteran harus ada dasarnya; setiap intervensi medis harus mempunyai indikasi yang kuat, untuk apa tindakan itu dilakukan dan siapa yang mendapatkan tindakan itu. "Untuk apa" pertanyaan yang menunjukkan perlunya pengetahuan klinis yang cukup untuk menentukan tindakan itu, dan "untuk siapa" pertanyaan yang menunjukkan perlunya sikap etis yang tepat untuk pengambilan keputusan dalam intervensi medis itu. TEKNOLOGI
Tekne adalah peralatan yang dipergunakan sebagai per-panjangan tangan manusia untuk mengerjakan dunianya. Oleh karena itu kemajuan teknik sebagai cara kerja yang di-ilmiahkan, merupakan pencerminan perkembangari kebudaya-an manusia. Manusia disebut juga sebagai a tool-making animal, karena manusia akan menunjukkan martabatnya se-bagai manusia, seja'uh ia mampu menciptakan alat untuk di-pergunakan dalam mengkaryakan dunianya.
Biologi modern pun mendukung pendapat, bahwa teknik hendaklah dipandang sebagai suatu lanjutan dari badan ma-nusia. Dalam alam binatang, alat-alat merupakan sebagian dari badannya sendiri. Organ-organ badannya sendiri sebagai sen-jata (cakar, taring, tanduk rusa), slat penggerak (sayap, telapak kuku), perisai' (duri-duri, kulit kerang), mantel untuk menahan
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 49

udara dingin (kulit berbulu), dan seterusnya. Jarang sekali binatang memakai alat-alat selain yang ada pada tubuhnya, mereka tidak menghasilkan alat-alat secara sistematis, apalagi usaha-usaha untuk penyempurnaan alat-alat itu. Dari banyak segi, organ-organ manusia lebih lemah daripada organ-organ binatang; indra pendengaran, penglihatan dan penciumannya, kekuatan fisik dan kecepatan bergerak, giginya dan peng-amanan kulitnya – dalam semua bidang ini manusia lebih terbelakang daripada binatang. Tetapi manusia mempunyai suatu perlengkapan sehingga badannya mempunyai siiatu lingkup gerak yang amat jauh, yaitu alat-alat yang diperguna-kannya beserta teknik. Organ-organ badannya dapat dilengkapi alat-alat, jarak spasial dan jarak waktu dapat dijembatani dengan alat-alat observasi dan alat-alat ukur, bahkan sambil beristirahat alat-alat itu dapat disuruhnya bekerja. Apalagi, alat-alat itu dapat digantikan, diperbaiki dan dijajarkan, sehingga menjadi mesin-mesin raksasa. Dengan demikian, lingkup gerak badannya dapat diperluas sampai hampir tidak ada batasnya.
Dengan menyebut teknik atau teknologi sering kita mem-bayangkan adanya mesin. Dunia manusia adalah dunia-mesin. Gambaran seperti itu terbayang karena mesin adalah bentuk teknik. yang paling jelas, masif dan mengesankan manusia. Dalam sejarah kemajuan bangsa-bangsa, teknik bermula dengan mesin. Tetapi dewasa ini teknik bukan lagi tampil sebagai alat, melainkan sebagai "sikap". Martin Heidegger telah mempertanyakan fenomen teknologi sebagai masalah filsafat. Ia mengartikan teknologi sebagai suatu bentuk ke-beradaan di dunia, yang mencerminkan manusia tercelcam dalam keinginannya untuk selalu memperbesar kelengkapan serta kemudahan baginya terhadap alam, dalam rangka men-jamin eksistensinya. Dengan demikian teknologi menimbulkan suatu relasi yang ditandai dengan hasrat meng-eksploitasi alam sejauh dan seefisien mungkin. Ini berarti perubahan hubungan antara manusia dengan alamnya yang semula ditentukan oleh nilai kualitatif, menjadi hubungan produksi dan komoditi yang dikuantifikasikan. Dengan penyorotan ini maka tampaklah bahwa teknologi tidak netral lagi, tidak lagi begitu saja tergantung kepada siapa yang memakainya, karena dalam dirinya sudah menentukan sikap serta kecenderungan-kecenderungannya sendiri.
Ilmu dan teknologi telah menunjukkan peranan dan jasa-nya dalam kehidupan manusia. Berkat teknologi, banyak aspek realitas telah diperdekat untuk penyelidikan akal budi manusia dan pengelolaan tangkas manusia. Kedekatan ini memperlihatkan kemungkinan akses yang lebih besar terhadap realitas dan proses realitas. Bahkan melalui teknologi, ke-pandaian manusia seakan-akan menyatu dengan realitas itu sendiri, seperti terlihat dalam penguasaan manusia dalam mengendalikan proses-proses alamiah. Namun patut diingat, bahwa ' kedekatan yang disebabkan oleh .teknologi adalah kedekatan spasial dan kuantitatif. Kedekatan semacam ini tidak dapat menggantikan kadar kedekatan makna manusiawi sebagai tetangga, keluarga dan bangsa. Teknologi adalah efisien dan membawa efisiensi dalam segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia. Tetapi, teknologi juga dapat menimbulkan dampak lain, seperti manipulasi, fragmentasi dan individuasi. KEMAMPUAN ATAU "KEKUASAAN" MEDIK
Berdasarkan kekuasaan atau kemampuan medik, J.H. van
den Berg membagi sejarah kedokteran dalam tiga masa. Masa pertama, masa tanpa kekuatan medik, ini berlangsung sampai 1870. Masa ke dua, masa transisi dari tanpa kekuatan teknik-medik menuju adanya kekuatan atau kemampuan teknik. Ini berlangsung sejak 1870 sampai beberapa tahun yang lalu. Masa ke tiga, masa kekuasaan teknik-medik. Ini baru berlangsung beberapa tahun terakhir, yang sekarang makin berkembang.
Untuk menunjukkan secara lebih terinci, pada masa ke dua ada sejumlah penemuan dan inovasi yang dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori.
Perjuangan melawan infeksi.
Beberapa waktu setelah Pasteur menemukan mikroorga-nisme yang menyebabkan infeksi, maka kemudian berbagai organisme . penyebab bermacam penyakit infeksi dapat di-temukan. Seperti, pada 1882 Robert Koch menemukan bacillus tuberculosis. Sudah jelas bahwa penemuan-penemuan tersebut adalah sangat penting; ditemukannya organisme penyebab penyakit infeksi merupakan langkah pertama dalam usaha berjuang melawan penyakit. Tujuannya adalah untuk menghancurkan organisme tersebut.
Pada dasarnya, para dokter berusaha agar dapat mem-bunuh: organisme yang dapat membahayakan pasien. Pada 1907, Ehrlich menemukan salvarsan yang dapat meracuni kuman trypanosoma syphilis, yang pertama-tama diidentifikasi pada 1905. Pada 1935 sulfonamid dapat disintesis, dan ini menimbullcan suatu perubahan dalam hal melawan infeksi-infeksi yang "biasa" dan gonorrhoe. Setelah 1940 mulailah pemakaian penicillin secara luas, yang sebelumnya ditemukan oleh Fleming pada 1928. Para pasien sekarang mungkin tidak pernah membayangkan bagaimana sengsaranya mereka se-belum ditemukannya hal-hal tersebut; mungkin para dokter pada masa yang akan datang juga sedikit yang menyadari hal tersebut. Pencegahan infeksi.
Setelah publikasi karya Pasteur tentang proses fermentasi, maka Lister, seorang dokter Inggris, pada 1865, mulai men-sucihamakan udara ruangan untuk tindakan operasi. Meskipun, sebenarnya profilaksis terhadap infeksi operasi bukan ber-dasarkan metode Lister, tetapi berdasarkan teknik aseptik Pasteur. Yaitu, bahwa usaha atau tindakan yang dilakukan sebelum melakukan operasi adalah dengan menyingkirkan organisme yang menyebabkan penyakit dari alat-alat yang akan dipergunakan, dan juga dari tangan ahli bedah serta pada bagian badan pasien yang akan dioperasi. Pada saat ini orang sudah terbiasa dengan pikiran bahwa sebelum tindakan operasi maka alat-alatnya harus disterilkan dulu dan ahli bedahnya juga harus memakai pakaian yang steril serta sarung tangan steril pada tangan , yang sudah dicuci dengan baik. Perlu kita ingat bahwa tindakan-tindakan tersebut baru dimulai sekitar satu abad yang lalu. Perkembangan ilmu bedah.
Untuk itu harus kita tambahkan dua hal yang berkaitan dengan darah. Yaitu masalah mencegah trombosis dan cara transfusi darah, hal ini dapat dikembangkan setelah Land-steiner menemukan sistem golongan darah pada 1900. Me-lawan infek'si, mencegah infeksi, dan cara pemberian darah adalah sangat penting untuk suatu tindakan operasi, yang
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 50

sekarang berkembang dengan pesat. Di samping bahwa kemampuan melakukan operasi akan
menimbulkan kebanggaan tertentu, maka operasi yang paling menantang adalah operasi terhadap organ vital atau sistem organ, seperti susunan saraf pusat, jantung dan ginjal.
Bedahsaraf. Pada 1890, untuk pertama kali dokter me-nusukkan jarum berongga (hollow needle) di antara dua buah vertebra untuk dapat mengambil liquor cerebrospinalis untuk melengkapi pemeriksaan subjek tersebut. Prosedūr bedah yang sederhana ini sekarang sudah menjadi prosedur rutin yang di-lakukan oleh para neurolog di setiap klinik. Sebaiknya ia juga tahu apa-apa yang dilakukan oleh sejawatnya satu abad yang lalu dalam menata pekerjaannya, yang pada waktu itu belum diketahui bagaimana caranya merangsang refleks. Pada waktu itu profesi neurologi belum terdengar. Bedahsaraf berkembang lebih awal. Tidak ada operasi bedahsaraf yang pernah dilakukan sebelum 1900, tetapi dalam waktu yang singkat ternyata bedahsaraf telah berkembang dengan pesat.
Bedahjantung. Operasi jantung juga belum lama dilaksana-kan. Pada 1925, seorang dokter membuka katup aurikulo-ventrikular dengan sarung tangannya. Empat puluh tahun kemudian, pada 1967, operasi jantung pertama dilakukan. Nama Christian Barnard, dokter bedahjantungnya, Vanshansky dan Bleiberg menjadi terkenal ke seluruh dunia setelah operasi itu.
Bedahginjal. Operasi ginjal juga belum lama berkembang. Operasi transplantasi ginjal pertama dilaksanakan pada 1954. Sejak itu, beberapa ribu orang' mendapatkan transplantasi ginjal. Harapan hidup rata-rata pada pasien transplantasi ginjal sampai beberapa tahun yang lalu sekitar satu tahun; sekarang harapan hidup itu menjadi beberapa tahun, dan diperkirakan dengan perkembangan masalah imunologi maka harapan hidup pasien ini juga akan diperpanjang. "Bayi tabung".
Bayi tabung menjadi terkenal sejak 1978, ketika Louise Brown lahir. Bayi tersebut "dirakit" di klinik Bourn Hall di Cambridgeshire, Inggris oleh tim dokter Patrick Steptoe dan Robert Edward. Kini sudah banyak "adik" Louise Brown yang dirakit di berbagai klinik IVF (In Vitro Fertilization) di seluruh dunia, termasuk di Indonsia. Dan cara ini kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Bank Organ.
Dengan makin bertambahnya para ahli, dan makin ber-kembangnya teknik medis, maka potensi pelayananpun meningkat juga. Misalnya, sehubungan dengan transplantasi ginjal yang pertama kali dilakukan pada 1954, sekarang ribuan orang di seluruh dunia dapat ditolong dengan teknik tersebut. Demikian juga dengan operasi organ lainnya. Kita belum dapat memperkirakan organ apa selanjutnya yang dapat ditransplantasi, setelah ginjal dan jantung. Ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya yang diperukan. Di samping itu timbul masalah lain, dari mana organ-organ itu didapatkan dan di mana harus diletakkan agar dapat di-pergunakan dalam keadaan baik pada saat transplantasi di-laksanakan. Ada pemikiran yang melihat, bahwa hampir selalu ada sejumlah korban kecelakaan lalu lintas dan ini mungkin dapat merupakan sumber untuk memenuhi ke-butuhan organ-organ tersebut. Setelah disimpan di bank organ, pada saat diperukan dapat diambil dari bank ter-
sebut. Mungkin, di samping patroli lalu lintas, patroli organ harus disiapkan untuk siaga di jalan, pada satu saat kelak. Patroli ini akan selalu siap untuk mengambil organ pada setiap kecelakaan lalu lintas dari mayat yang masih segar dan kemudian menyerahkannya kepada helikopter yang siap diparkir di simpang jalan dan kemudian segera membawanya ke bank organ tersebut. Juga, setiap subjek harus membawa kartu indentitas tentang organ tubuhnya yang akan segera diambil jika memang dibutuhkan pada saat ia meninggal.
Tetapi, untuk ini perlu perencanaan dan pemikiran yang betul-betul matang, karena selain aspek klinis, etis, juga aspek hukum sangat menentukan untuk kemungkinan melaksanakan program seperti itu. Tampak, bahwa ini adalah urusan yang mungkin mencengangkan kita; kemampūan atau kekuatan teknik-medik secara keseluruhan dapat menimbulkan kekhawatiran, kalau tidak hati-hati dikelola. Manifestasi kemampuan medik lainnya.
Beberapa jenis kemampuan atau kekuatan medik telah kita uraikan, dan ini menunjukkan perkembangan yang selalu terjadi dengan cepat.
Reanimasi atau resusitasi. Pengertian ini mencakup semua usaha yang dilaksanakan untuk membangkitkan atau mem-bangunkan seseorang yang tampaknya akan mati. Pada prak-
teknya, usaha reanimasi terdiri dari membangkitkan kembali sirkulasi yang terhambat, yaitu dengan memberikan oksigen kepada pasien, dengan pernafasan dari mulut ke mulut, dengan menyuntikkan stimulansia, atau dengan merangsang jantung. Biasanya massage jantung selalu dilakukan dan berhasil setelah usaha lain gagal. Kalau memang perlu, massage jantung lang-sung kepada organnya setelah membuka rongga thorax. Jika jantung berhenti berdenyut selama 6 sampai 8 menit, maka kerusakan otak akibat kekurangan oksigen tidak akan di-perbaiki kembali, jika kemudian dilakukan resusitasi, maka pasien akan bangun dengan disertai gangguan mental.
Respirasi artifisial. "Senjata" baru lainnya dalam "jajaran" usaha medis adalah respirasi artifisial secara mekanis. Teknik ini makin dikenal masyarakat, terutama -setelah media massa mengungkapkan korban-korban kecelakaan lalu lintas yang path awalnya dibantu dengan respirator ini, kemudian tidak dapat lepas lagi dari alat ini. Bentuk resusitasi ini dipakai pada pasien-pasien yang otot pernafasannya tidak dapat ber- fungsi lagi. Pada waktu yang lalu, pasien-pasien itu biasanya tidak tertolong dan meninggal karena asfiksi, tetapi sēkarang mereka dapat tetap hidup dengan bantuan respirator itu. Obat-obatan
Pemakaian obat-obatan demikian luasnya dan bervariasi-nya, sehingga para pakar sekalipun tidak dapat menyebutkan semua medikasi yang beredar itu. Kalau kita lihat perkembang-annya – Aspirin, salah satu obat modern pertama, pertama kali dipasarkan pada 1899. Hasil ekstraksi organ, seperti yang terkenal – insulin, yang dapat dipakai untuk mengontrol diabetes, pertama kali dipersiapkan pada 1920. Pada obatobat gangguan jiwa, obat psikotropik pertama yang penting dikeluarkan pada 1952, yaitu chlorpromazine atau largactil.
Pada saat ini jenis obat-obatan dan peredarannya sudah sangat sulit, dikontrol, terutama di negara-negara berkembang. Karena di luar faktor medis, banyak sekali yang berperanan dalam usaha ini, yang akhirnya menjadi beban konsumen.
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 51

Human Genome. Dalam TIME 20 Maret 1989 dikemukakan, para ahli dari
NIH (National Institute of Health) mencanangkan proyek 3 milyar dollar untuk membuat peta kromosom dan untuk "membaca" instruksi yang lengkap dalam pembentukan manusia.
Genome manusia adalah satu perangkat lengkap instruksi untuk pembentukan manusia. Akan jadi apakah bayi ini nanti? Bintang sepak bola? Sarjana? Pemusik? Meskipun masa depan anak akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi sebagian dari nasibnya sudah ditentukan sebelumnya. Encode pada genome, DNA pada 46 kromosom anak-anak, adalah instruksi yang tidak hanya tentang struktur, ukuran, warna dan atribut fisik saja, tetapi juga tentang intelegensi, kerentanan terhadap penyakit, kemungkinan hidup serta beberapa aspek tingkah laku. Tujuan akhir dari Pro yek Human Genome adalah untuk "membaca" dan mengerti instruksi-instruksi tersebut, sehingga potensi manusia yang lebih baik dapat kita kembangkan, dan potensi yang tidak baik dapat dicegah sedini mungkin.
Setelah melihat perkembangan yang terjadi dalam dunia kedokteran, walau belum lengkap, ada gambaran bahwa sedang berkembang dengan cepat kemampuan atau.kekuatan teknik medik yang modern. Setiap orang, cepat atau lambat, akan berhubungan dengan "kekuasaan" ini. Pada satu sisi kita mengucapkan syukur karena perkembangan ini sudah dapat banyak membantu masalah-masalah atau keluhankeluhan yang selama ini tidak dapat tertolong. Tetapi, pada sisi lain, bukan mustahil kemajuan ini malahan membawa malapetaka, apabila kekuatan atau kemampuan teknik-medik itu tidak dipergunakan dengan tepat.
Agar dapat memanfaatkan kemampuan atau "kekuasaan" teknik-medik ini dengan tepat, perlu diketahui indikasinya dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi dengan tindakan tersebut.
INDIKASI DAN MANIPULASI*)
Setiap tindakan atau intervensi medik terhadap pasien harus selalu mempunyai dasar bertindak atau indikasi. Setiap tindakan dengan alat atau memakai teknik-medik tertentu harus jelas, pertama, untuk apa tindakan itu dilakukan. Untuk keadaan klinis atau penyakit.•apa saja tindakan itu dapat di-lakukan dan apa kemungkinan akibat dari tindakan itu. Ini lebih menyangkut aspek pengetahuan atau keterampilan dokter tersebut. Kedua, untuk siapa tindakan itu dilakukan. Ini bukan berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomi pasien, tetapi yang dimaksud, apakah kondisi pasien dengan keadaan atau penyakit yang dideritanya itu masih tepat diberikan tindakan atau intervensi dengan teknik-medis tersebut?
Dengan mengetahui keadaan pasien dengan tepat, dan pengetahuan tentang indikasi setiap tindakan dengan tepat, maka akan dapat dibeuikan pelayanan untuk pasien dengan
*Manipulasi bisa berarti, menangani sesuatu atau seseorang dengan kepandaian yang dimiliki, demi maksud tertentu (manus=tangan, bhs. Latin). Kata manipulasi ini mulanya hanya dipakai di bidang teknologi, terutama dalam lapangan pertambangan. Tetapi kemudian pemakaiannya meluas ke bidang-bidang lain, seperti psikologi dan kedokteran. Walaupun pemakaian kata meluas dari dunk teknilc sampai ke bidang kehidupan manusia, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa ada perbedaan kualitatif yang besar dari dua bidang yang dicakup dalam satu kata ini.
tepat juga. Mungkin, tindakan teknis-medis yang sederhana sudah cukup untuk dipakai dalam membantu atau menyelesai-kan masalah pasien tertentu, seperti pada kasus pembuka tulisan ini. Seandainya sejawat tersebut mau melakukan wawancara lebih lanjut, dengan mendengarkan keluhankeluhan pasien, kemudian memberikan beberapa saran yang sederhana, keluhān pasien itu dapat berkurang dan diselesaikan, sehingga ia dapat menata kembali suasana emosionalnya, baik di rumah ataupun di tempat kerjanya. Jadi, tanpa melakukan pemeriksaan dengan alat mutakhir yang canggih, seperti CT-Scan, melainkan hanya dengan pemeriksaan memakai stetoskop dan tensimeter diteruskan dengan wawancara lebih lanjut, keluhan-keluhan pasien itu dapat dibantu.
Agar setiap dokter dapat mengetahui indikasi yang tepat untuk setiap intervensi medis, diperuukan pengetahuan dan ketrampilan. Untuk itulah setiap dokter harus dapat menjaga dan menyegarkan dan meningkatkan ilmunya. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang selalu berkembang sesuai dengan per-kembangan kehidupan manusia. Apalagi belakangan ini, kemajuanteknologi berkembang dengan pesat, termasuk teknologi-kedokteran, Karena itu, mereka yang tidak berusaha menyegarkan pengetaltuannya dan tidak berusaha meningkat-kan ketrampilannya akan mudah tertinggal di belakang, serta diragukan kemampuannya untuk dapat menjalankan profesinya menurut ukuran yang tertinggi. Ini sesuai dengan motto medicine is life-long study, yang selalu disampaikan pada setiap insan kedokteran.
Penyegaran dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tidak selalu harus ditempuh dalam pendidikan formal saja, seperti jalur spesialisasi. Jalnr lain, seperti paket latihan singkat, simposium, malahan belakangan secara tertulis pun sudah banyak dikembangkan, di samping tulisan-tulisaft hasil penelitian atau perkembangan barn yang banyak diuraikan dalam media kedokteran. Sehinggasebenarnya, sudah banyak kemudahan atau kesempatan yang dapat dikembangkan oleh setiap dokter pada saat ini, jika dibandingkan dengan para dokter beberapa generasi yang la1u,, asal ada kemauan dari yang bersangkutan.
Agar dapat mengetahui indikasi yang tepat, maka setiap dokter selalu menyegarkan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Ini menyangkut aspek klinis. Sedangkan aspek etis, adalah apakah tindakan itu sudah tepat dilakukan pada pasien tertentu? Apakah usaha itu memang didorong motivasi "demi kemanusiaan", bukan motif lainnya yang tersembunyi dl batik tindakan itu.
Ada yang melihat, bahwa perkembangan ilmu dan teknik yang mengagumkarn sejak abad yang lalu itu adalah suatu rangkaian proses evolusi dalam rangka kemajuan dan mengem-
bangkan suatu proses humanisasi. Dan ini menimbulkān ke-yakinan bahwa kemajuan ilmu dan teknik adalah merupakan puncak evolusi, sehingga apapun yang dapat dicapai oleh ilmu dan teknik adalah selalu baik. Di sinilah titik kelemahannya, yaitu ' tidak dibedakan dengan tegas antara kemajuan teknologi dan kemajuan demi kemanusiaan. Kemajuan dalam ilmu dan teknologi adalah sangat baik jika.di bawah pengaruh kebijaksanaan demi kemanusiaan. Kekuatan penyembuh dan pembebasan yang paling kuat terdapat dalam hubungan yang sejati antar manusia, sedangkan kekuatan penghancur yang terkuat terdapat dalam objektivasi tanpa adanya perasaan. Jika hubungan personal mengarah kepada sistem komunikasi
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 52

yang bersifat impersonal, maka akan terbuka semua jalan untuk manipulasi, dan kemampuan untuk melindungi diri pun menjadi menurun.
Dalam etika kedokteran, yang paling diutamakan adalah hubungan dokter dengan pasien. Dokter terutama harus mem-perhatikan masālah martabat manusia, baik martabat dirinya sendiri, maupun martabat pasiennya juga. Dalam menghadapi pasiennya, dokter harus memandangnya sebagai manusia dengan suatu kesatuan yang utuh. Dalam proseS terapi mung-kin dokter perlu memakai sedikit kekerasan, tetapi yang lebih penting yaitu bagaimana pasien merasakan bahwa dokter itu menghargai dan mempercayainya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, sehingga dapat bekerja sama sebagai partner. Hampir setiap tindakan terapeutik mengandung elemenelemen manipulasi, yang mengganggu atau membatasi fungsi biologis atau fungsi psikologis tertentu. Tetapi sambil menekan beberapa fungsi tersebut, terapi selalu diarahkan kepada per-baikan, dan ini yang lebih panting bagi seseorang. Jadi tidak harus berarti memanipulasi manusia.
Sambil mengobati fungsi tertentu dari pasiennya, sang dokter tidak boleh melepaskan pandangannya dari konsep kesehatan yang menyeluruh dan otonomi maksimum sebagai tujuan akhir terapi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, maka dokter dan pasien berhubungan sebagai partner yang saling mentaati dan saling menghargai. Tidak satu pun berusaha memanipulasi yang lain. Pasien tidak boleh meminta kepada dokter tentang sesuatu hal yang dia ketahui tidak dapat di-penuhi sehubungan dengan kata-hati sang dokter. Dan juga dokter sebaiknya tidak membuat keputusan untuk pasiennya, pada saat di mana pasien itu sendiri dapat membuat keputusan tersebut. Dokter seharusnya memberikan informasi kepada pasien atau kepada keluarganya sesuai dengan keperluannya, ini dalam rangka kerja sama sebagai partner.
Dalam abad teknologi, kita semua tergoda untuk meng-andalkan terlalu banyak kepada cara-cara manipulasi dalam
rangka mencari bantuan tertentu, sehingga kita dapat me-ngembangkan tenaga kita. Mungkin godaan yang paling besar untuk melampaui garis batas manipulasi adalah sikap reduksio-nisme yang khas pada bidang-bidang tertentu dalam kedokter-an. Dengan reduksionisme maka aspek-aspek khusus diabsolut-kan, sehingga ini sering mengarah kepada teknologi manusia, di mana dalam mengobati maka manusia hanya dipandang sebagai objek saja. Sikap reduksionisme dan kecenderungan untuk mengabsolutkan satu bidang spesialisasi ini akan meng-hadapkan masing-masing spesialisasi itu kepada bahaya mani-pulasi yang akan menurunkan derajat kemanusiaan. Tidak usah diragukan lagi, bahwa cara dokter menangani terapi dari satu sisi ini, akan membahayakan manusia dan akan membentuk hubungan manipulatif terhadap pasiennya.
Hanya pandangan yang melihat pasien sebagai manusia seutuhnya dan berhubungan dengan dokter dalam rangka hubungan eksistensinya inilah yang .dapat menghindarkan suatu tindakan terapi dari usaha manipulasi. Sehingga per-kembangan teknik-medik dapat menjadi kekuatan yang memberikan manfaat bagi manusia, bukan menimbulkan malapetaka.
KEPUSTAKAAN
1. Berg JH vd. Medical Power and Medical Ethics, WW Norton & Co New York. 1978. hal. 19–33.
2. Haring. Manipulation, Ethical Boundaries of Medical, Behavioural & Genetic Manipulation. St. Publ. London 1975. hal . 87–100
3. Jaroff L. The Gene Hunt. TIME. March 20, 1989. hal. 38-45. 4. Peursen CA v. Strategi Kebudayaan. Di Indonesiakan oleh Dick
Hartoko. BPK Gunung Mulia. Jakarta. 1976. hal. 118-30. 5. Poespowardojo S. Refleksi Budaya Mengenai Pembangunan Nasional.
Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Indonesia ke 35, 2 Februari 1984 di Jakarta.
6. Sigerist HE. Civilization and Disease. The University of Chicago Press. Chicago & London. 1970. hal. 164-79.

Pengalaman Praktek
Berobat dari PinPara pasien kini tampaknya c
usaha menyembuhkan penyakitnytebal atau istilah kerennya disebut toh mereka lebih suka ke doktePuskesmas. "Demi gengsi", katanymerupakan hak setiap orang. Namekonomi kurang mampu lantas semata-mata untuk memenuhi hasrsebetulnya tidak memerlukan penpasien itu kemudian berganti-ganti
Kala itu hari Minggu siang, samasih menyusu. Si ibu menderita terserang demam dan batuk-batubeberapa dokter spesialis di KotaPuskesmas. Yang membuat hati saitu pasien telah melelang barang-Alhasil harta bendanya ludes, peny
Kisahnya bermula ketika pasipraktek dokter tersebut, pasien tiddiladeni oleh seorang pembantu ySetelah menunggu sekian lama, pasJelasnya, pasien sama sekali tidasentuhan tangan Pak Dokter yang tidak mengajukan protes, bahkan dberharga mahal itu ke sebuah Apohingga habis. Namun penyakitnya t
Merasa tidak cocok dengan dokota yang sama. Di sini pun'nasibmemeriksakan darah, kencing, tinjTotal jendral biayanya kira-kira sebiaya obat. Kendati pasien memdiperolehnya dengan susah payaAkibatnya semakin parah, sebabseparuhnya untuk mengirit ongkos.
Dalam keadaan pikiran kalut dberobat ke dokter ahli lainnya. Dadia menuju ke tempat'praktek dokkosong. Pasien diterima oleh sependaftaran Rp 5.000,- kemudianmenunggu. Tetapi apa lacur, sudbahkan hingga menjelang tengah mbantu itu seenaknya menyuruh passiang. Untuk kesekian kalinya pasidiperbuatnya kecuali pasrah meneri
Entah apa yang mendorongnyaterdampar di rumah saya. Hati saselesai memberikan pelayanan, pamenyodorkan kepada saya. Tentu terus terang saya katakan bahwa
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 54
tu ke Pinta enderung memilih pelayanan dokter spesialis dalam a. Pelakunya tentu saja mereka yang berkantong "kaum elite". Meskipun hanya flu atau pusing ringan r spesialis daripada ke dokter umum apalagi ke
a. Memang kita tidak bisa menyalahkannya, sebab itu un, apa jadinya bila seorang pasien dengan keadaan memaksakan diri menjual perhiasan dan miliknya, atnya berobat ke dokter spesialis, padahal penyakitnya anganan spesialistik. Ironis sekali! Lebih tragis bila dokter. ya kedatangan seorang ibu dengan seorang anak yang radang pada kedua payudaranya, sedangkan si anak k. Menurut pengakuannya, dia sudah berobat ke X. Padahal, di desa tempat tinggalnya sudah ada ya trenyuhjustru untuk biaya pengobatan "istimewa" barang perhiasan, ternak, basil bumi, dan lain-lain. akitnya tidak kunjung sembuh. en berobat pada dokter ahli A di Kota X. Di tempat ak sempat melihat muka Pak Dokter. Pasien hanya ang menanyakan identitas dan keluhan alakadarnya. ien langsung diberi resep tanpa diperiksa oleh dokter.
k mendapat sapaan barang sepatah katapun apalagi amat didambakannya itu. Walaupun demikian, pasien engan keyakinan tebal pasien membawa secarik kertas tek. Dengan patuh pasien meminum semua obatnya
iada berubah alias belum sembuh. . kter ahli A, pasien pindah berobat ke dokter ahli B di pasien tidak jauh berbeda. Bahkan pasien disuruh a . . . dan segala tetek bengek pemeriksaan lainnya. harga dua ekor kambing dewasa jantan. Belum lagi bawa uang cukup banyak, namun karena duit itu h maka beban yang dideritanya pun kian berat. resep yang diberikan oleh dokter cuma ditebus an kantong kian menipis, pasien bertekad meneruskan sar pasien lugu, dengan wajah kuyu dan langkah lesu ter ahli C. Ketika pasien tiba, ruang tunggu masih orang pembantu. Anehnya, pasien dimintai uang diberi sebuah kartu bernomor 100, dan disuruh ah berpuluh-puluh pasien lainnya selesai diperiksa alam,dia belum juga dipanggil. Sadisnya lagi, pem-
ien pulang dengan pesan agar besok datang lagi lebih en yang malang itu menelan kegetiran. Yah, apa mau ma nasib. , pasien yang merana dan terlunta-lunta itu akhirimya ya terharu mendengar ceritanya, apalagi ketika saya sien segera membuka gelang emas di tangannya lalu saja saya tidak mau menerima pemberian itu. Secara obat yang saya berikan itu adalah obat sampel

(contoh) yang saya peroleh secara gratis. Lebih jauh, saya memberikan ceramah singkat dengan bahasa yang mudah tentang masalah kesehatan, manfaat Puskesmas dan Posyandu bagi masyarakat pedesaan.
Sebulan kemudian, mantan pasien saya itu datang membawa oleh-oleh seekor ayam gemuk. Saat itu hati saya berbunga-bunga dan bangga. Bukan lantaran oleholehnya, melainkan karena perubahan sikap dan pola pikir si pasien terhadap masalah kesehatan. Dia kini betul-betul sudah mengerti akan makna keberadaan Puskesmas dan Posyandu yang telah menyebar hingga ke pelosok-pelosok. Selain itu, dia juga menjaai tenaga andalan Posyandu di desanya.
Dr Ketut Ngurah Lab Parasitologi FK-Unud, Denpasar
Malaria infeksi yang sudah jarang dijumpai di kota besar seperti Jakarta, tetapi yang masih harus dipikirkan kemungkinannya.
Kasus ini terjadi lebih kurang setengah tahun yang lalu. Pada suatu hari seorang wanita, berumur 45 tahun, datang dengan keluhan: sejak beberapa hari terserang panas dingin serta menggigil, disusul dengan menjadi kuningnya seluruh tubuh. Urine juga berwarna kuning tua. Rasa mual dan lemas sekali juga ada. O.rang sakit dikirim ke rumah sakit untuk dirawat dengan dugaan suatu kasus hepatitis. Di R.S. oleh dokter yang merawatnya diperiksadarah lengkap (termasuk malaria) dan tes-tes fungsi hepar. Hasil: memang terdapat kelainan-kelainan fungsi hepar. Darah tepi : Malaria (–).
Setelah beberapa hari pengobatan untuk hepatitis tidak memberi perbaikan maka darah malaria diperiksa lagi. Hasilnya tetap negatif. Dapat difahami bila dokter tersebut kemudian memikirkan suatu hepatitis akut (oleh virus) yang fulminan dan pada umumnya berakhir fatal. Padawaktu itu keadaan pasien sudah buruk; soporous dengan ikterus: yang hebat. Keluarga orang sakit minta konsul ke dokter lain untuk mendapat pendapat kedua (=second opinion).
Dokter ini mengulangi sendiri pemeriksaan darah tepi atas malaria. Hasilnya: malaria tropika(+). Terapi; malaria langsung diberikan dan dalam waktu kurang dari 1 minggu pasien sudah dapat dikatakan sembuh.
Nah, di mana pasien mendapat infeksi parasit plasmodium itu? Ternyata dua minggu sebelum sakit, pasien telah berkunjung ke Bangka, di tempat tersebut ia masuk hutan dan merasa telah diserang dan digigit oleh nyamuk-nyamuk.
Pelajaran yang dapat ditarik dari kasus ini: irifeksi malaria memang sudah jarang sekali dijumpai dalam praktek sehari-hari di kota besar seperti Jakarta. Akan tetapi bila dalarim anamnesis terdapat riwayat berkunjurig ke daerah di mana malaria masih prevalen, jangan lupa untuk memikirkan infeksi malaria.
OLH
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 55

HUMOR
ILMU KEDOKTERAN POLUSI UDARA
Kafena sudah merasa kewalahan dalam usaha mengatasi polusi udara, pemerintah .daerah suatu kota meng-adakan sayembara tentang cara terbaik mengatasi polusi udara. dengan cara yang cepat dan murah.
Maka para ahli dari berbagai disiplin ilmu segera mengirimkan/mengajukan berbagai usul, lengkap dengan per-hitungan teknologi yang canggih. Te-tapi ketika hasil sayembara diumum-kan, semuanya menjadi terperangah dan heran.
Pemenangnya ialah seorang dukun Indian ahli mendatangkan hujan!
Hk KALAU ISTRI DOKTER SAKIT
Seorang istri ngomel karena tidak diperiksa oleh suaminya seorang dok-ter. "Setiap bilang sakit kepala atau sakit perut; tanpa diperiksa langsung diberi obat. Memangnya pasien gratis, tidak bayar atau sudah bosan ya" H. Sambil mengancam si istri meneruskan omelannya: "Kalau perlu aku akan periksa ke dokter lain" !.
Dengan. tenang dan senyum manis suaminya menjelaskan: "Aku sudah tahu penyakitmu Ma. Hampir Setiap malam kamu buka semua bajumu dan kuremas-remas; apa itu tidak periksa namanya"!
Dr. Putu Sumantra. Denpasar Bali.
LANGSING Suatu ketika di Posyandu, seorang ibu kurus dan kecil dengan menggendong
anaknya mendatangi petugas untuk diperiksa. Petugas : "Demi kesehatan ibu dan anak ini alangkah baiknya jika ibu makan empat sehat lima sempurna, yaitu daging, telur, sayuran, buah-buahan dan susu supaya tetap sehat." Ibu : "Wah!! Sulit bu, sebab kondisi saya biasa langsing." Petugas : "Langsing boleh tetapi kesehatan harus tetap dijaga." (menasihatkan). Ibu : "Maaf bu, ehm . . . Maksud saya langsing itu adalah LANGganan SING- kong" (memelas). Petugas : "Oooooo…………. (manggut-manggut maklum).
Arry S.O.S. Jakarta
KE BAWAH SEDIKIT
Pada suatu seminar Ilmiah Internasional berkumpullah para pakar ilmu pengetahu-an dari berbagai negara dan disiplin ilmu di antaranya dari Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Indonesia sendiri. Pada suatu ketika berbincanglah mereka. AS : "Negara kami telah berhasil menghitung jari jari atom yang sebenarnya
dengan mikroskop perbesaran 1015 kali ukuran normal". US : "Mana mungkin! Pasti ada juga salahnya". AS : "Kalau terjadi kesalahan, paling hanya kurang sedikitlah". US : "Soviet bahkan telah mengirim pesawat ruang angkasanya dengan tepat
menuju pusat Mars !" AS : "Belum pernah terjadi itu dan pasti tidak begitu tepat." US : "Kalau terjadi kesalahan paling kurang sedikit ke bawah!"
Mendengar kesombongan para ahli tersebut, ahli Indohesia yang kebetulan seorang dokter tidak mau kalah set. Indonesia : "Di negara saya orang sudah berhasil mendapatkan anak dengan menetes-(kalem) kan sperma pada lubang puser seorang wanita". AS & US : "Nonsense, bohong, tidak ilmiah!!" Indonesia : "Yah, kalau salah sedikit paling-paling hanya kurang ke bawah sedikit,
deh." (tersenyum bangga). Arry SOS
Jakarta
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 56

RESEP Dokter Lestari : "Anda yang terma
suk baru buka prak tek, ternyata banyak juga pasien yang da tang dan bahkan bisa mengungguli praktek lain, apa sih resep- nya ?"
Dokter Heri : "Ah nggak ada resep- nya kog. Cuma pa- sien yang kemari saya gratisi."
Dokter Lestari : "Oh .... ???" Suharsono Pekalongan
KONTES BUGIL A : Apa kau sudah mendengar, baru
baru ini ada pengumuman tentang kontes yang salah satu syaratnya ialah pengiriman foto seluruh ba- dan tanpa busana ?
B : Gila ! Kontes apaan tuh ? A : Kontes bayi sehat !!
Hk Jakarta
TARIF LISTRIK A : Wah, kelihatannya banyak yang
keberatan atas kenaikan tarif listrik yang baru saja diumumkan, ya?
B : Ya, tapi ada juga malah harap- harap cemas, lho!
A : Ah, masakan begitu, siapa sih? B : Ahli kebidanan !
Hk Jakarta
BOLEH KAN?
Sepasang suami istri sedang me-ngendarai mobil. Tiba-tiba di tikungan istrinya mengatakan pada suaminya: "Lihat itu mas, tanda lalu-lintas: 'Hati-hati banyak anak!' "
Suaminya menjawab kalem: "Nggak usah risau kita…………kan sudah ikut KB !"
"Heee ??????" Juvelin Jakarta
AMPUTASI Seorang homosex yang telah berkali-kali berobat mengeluh pada dokter yang me-memeriksanya. Homo : "Tolonglah saya dokter, setiap kali habis main anu saya nyeri dan serasa
melepuh." Dokter : "Saya telah berusaha mengobati tetapi anda tetap bandel. Kini saya hanya
dapat menasihati hentikanlah perbuatan itu." Homo : "Waduh, tidak bisa, dokter. Kalau dihentikan terasa badan ini sakit, linu,
dan pegal, Dok !" Dokter : "Yah, apa boleh buat. Pengobatan yang paling manjur adalah……………. amputasi !!!" Homo : "Haaa ???? !.!! !"
Arry SOS Jakarta
SUNTIK KESEHATAN
Bertugas sebagai Dokter Puskesmas di pedalaman memang banyak suka dukanya. Kejadian sehari-hari yang kadang-kadang menggelikan timbul karena kesederhanaan pola berpikir masyarakat.
Suatu sore datang seorang pāsien ke tempat praktek saya.Ia minta "suntik ke-sehatan" karena badannya pegal-pegal sehabis bekerja di ladang. Hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan suatu penyakit. Akhirnya saya berikan injeksi vitamin ditambah obat analgētik peroral. Selesai suntik ia menyodorkan uang selembar lima ribuan sambil berkata: "Dok, uangnya tidak usah kembali, tapi saya minta tambahan suntik sekali lagi." Astaga, saya jadi terkejut. "Pak, suntik itu tidak sama dengan jajan bakso kalau enak rasanya kita bisa minta tambah lagi".
ATK Salatiga
MANTAN Seorang pejabat mendatangi sebuah praktek dokter ternama. Sang pejabat : "Bila isteriku berobat kemari dokter nggak menarik bayaran, apa
karena isteri pejabat ataukah nggak butuh uang sih ?" Dokter : "Bukan itu pak, cuman karena dia mantan pacar saya." Sang pejabat : (dengan mata membelalak) "Hah ???"
Suharsono Pekalongan
SUDAH BIASA Suatu petang. saya sedang memeriksa seorang pasien wanita muda berparas lu-
mayan, yang memeriksakan kesehatan karena 'profesi'nya. Tapi tiba-tiba lampu di kamar praktek padam. Dengan agak bingung karena kegelapan saya katakan: "Maaf bu, silahkan menunggu di ruang tunggu, sampai lampunya nyala lagi." Jawabnya tanpa ragu-ragu: "Tidak apa-apa dok, saya sudah biasa'diperiksa'di tempat remang-remang kok, teruskan saja………..kepalang tanggung."?????????????
Juvelin Jakarta
APANYA ? Tidak semua pasien yang menderita sakit dapat mengemukakan sakit yang di-
deritanya dengan leluasa di hadapan dokter yang memeriksanya, apalagi kalau pasien-nya sangat pemalu atau takut menyinggung perasaan.
Suatu ketika, seperti yang pernah saya alami pada pasien saya seorang wanita muda, waktu saya tanya: "Sakit apa, bu?"
Dengan suara lirih : "Anu dok,………..kacang saya sakit,………….gatal-gatal." "Heee ????????????, ooooooooooooooooooo………………"
Juvelin Jakarta

ABSTRAK - ABSTRAK
PATOGENESIS DEMAM Demam yang menyertai infeksi dan penyakit lain berhubungan dengan resetting dari
termostat yang terletak di hipotalamus. Banyak mekanisme patogenik yang kompleks, yang dihubungkan dengan sebab terjadinya demam.
Faktor yang umum ditemukan adalah, sebagai reaksi terhadap berbagai rangsang infeksi, imunologik dan inflamatorik, sel-sel seperti makrofag dan monosit mengeluarkan beberapa jenis polipeptid yang disebut monokines. Monokines ini mempengaruhi metabolisme, dan dua di antaranya – interleukin–1 (IL-1) dan tumor necrosis factor (TNF) diketahui berperan sebagai pirogen endogen. Selain itu, alpha-interferon (IFN-a) yang diproduksi sel sebagai respons terhadap infeksi virus, juga bersifat pirogenik. Zat mana yang secara langsung menyebabkan demam masih belum dapat dipastikan, tetapi kurang/tidak adanya respons demam pada fase akut beberapa infeksi viral mungkin menunjukkan bahwa IFN-a lebih berperan.
IL–1 berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh karena antara lain menstimulasi limfosit T dan B, mengaktivasi netrofil, merangsang sekresi reaktan (C–reactive protein, haptoglobin, fibrinogen) dari hepar, mempengaruhi kadar besi dan seng plasma dan meningkatkan katabolisme otot. IL–1 bereaksi sebagai pirogen dengan merangsang sintesis PG E2 di hipptalamus, yang kemudian bekerja pada pusat vasomotor sehingga meningkatkan produksi panas sekaligus menahan pelepasan panas, sehingga menyebabkan demam.
TNF (cachectin) juga mempunyai efek metabolisme dan mungkin berperan pada penurunan berat badan yang kadang-kadang diderita setelah seseorang menderita infeksi. TNF bersifat pirogen melalui dua cara - efek langsung melepaskan PG E2 dari hipotalamus dan merangsang penglepasan IL–1.
Medicine International (Quarterly Ed). 1988; 3 : 2081
Hk. DEMAM PASCAVAKSINASI
Penelitian atas 282 anak yang menerima vaksinasi DPT menunjukkan bahwa pem-berian asetaminofen (parasetamol) secara profilaktik dapat mencegah timbulnya demam, nyeri dan kegelisahan pascavaksinasi secara bermakna.
AJDC 1988; 142: 62–5 brw
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 58

ABSTRAK - ABSTRAK
PENGAKTIVASI KANAL POTASIUM: CARA BARU PENGOBATAN ANGINA, HIPERTENSI, DAN ASMA.
Pengobatan angina pektoris, asma bronkial, dan hipertensi ensensial dapat dilakukan dengan cara relaksasi otot polos melalui berbagai mekanisme termasuk antagonisme kalsium, pengaktipan guanilatsiklase, dan penghambatan fosfodiesterase. Penemuati terakhir menunjukkan bahwa relaksasi otot polos dapat terjadi pula melalui pembukaan kanal potasium. Tiga jenis obat yang bekerja melalui mekanisme kerja pembukaan kanal potasium ini adalah pinacidil, cromokalim, dan nicorandil. Disamping membuka kanal potasium, nicorandil juga mempunyai efek pengaktipan guanilatsiklase.
Eksperimen pada hewan menunjukkan bahwa comokalim dan pinacidil bekerja sebagai vasodilator arteri perifer, menurunkan tekanan darah yang besarnya tergantung pada dosis dengan refleks takikardi. Cromokalim 3–10 kali lebih poten dibandingkan pinacidil dan mempunyai lama kerja yang lebih panjang. Sedangkan nicorandil mem-,punyai efēk sistemik yang sebanding dengan nitro gliserin. Penurunan tekanan darah sepintas dapat pula terjadi yang diikuti dengan peningkatan aliran darah koroner.
Studi elektrofisiologik menunjukkan bahwa ke tiga obat ini mengaktipkan kanal potasium, yang disertai dengan penurunan tahanan membran dan hiperpolarisasi sal. Pada saat membran sel terhiperpoldrisasi, kanal kalsium menutup, kadar Ca* intraseluler menurun dan sel otot relaksasi. Hiperpolarisasi sel berikutnya akan mencegah influks 'Ca* dan memacu pertukaran Na+/Ca* dan selanjutnya menurunkan Ca* intraseluler.
Nicorandil yang mempunyai aktivitas meningkatkan guanilatsiklase dan pembukaan kanal potasium, menurunkan preload dan afterload melalui dilatasi pembuluh darah koroner pada kadar yang rendah. Pada angina variant dan angina pektoris, efek anti-angina yang maksimal terjadi setelah 1 jam pemberian oral dan berakhir ietelah 4–6 jam. pinacidil menurunkan tekanan darah melalui penurunan afterload. Cromokalim pada pemberian per oral,mempunyai waktu paruh hayati yang panjang yaitu 24 jam.
Efek samping utama dari ke tiga ōbat ini adalah sakit kepala. Edema, takikardi, hipertrikosis pernah dilaporkan pada pengobatan dengan pinacidil.
Nicorandil diperkirakan akan sangat bermanfaat pada pengobatan angina, sedang pinacidil pada pemberian bersama diuretik tiazid merupakan antihipertensi yang poten. Cromokalim yang mempunyai waktu paruh hayati yang panjang akan sangat bermanf*at untuk pengobatan asma noktumal.
INPHARMA 5 NOV. 1988 p 4 VSR
VITAMIN A DAN KEHAMILAN Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemakaian vitamin A menjelang dan selama
kehamilan adalah sebagai berikut : – Wanita-wanita pada usia reproduktifharustahu bahwa kelebihan vitamin A sebelum
dan selama kehamilan dapat membahayakan fetus yang dikandungnya. – Suplemen vitamin A (sebagai rational atau ester retinil) maksimum tiap hari yang
diperbolehkan sebelum dan selama kehamilan yaitu 8000 IU. – Produsen sebaiknya menurunkan jumlah vitamin A dalam sediaan-sediaan vitamin
menjadi 5–8000 IU per unit dosis dan menyebutkan sumber vitaminnya. Vitamin A sebagai retional/ester retinil dalam dosis tinggi, misalnya 25000 IU atau lebih tidak diperlukan sebagai suplemen nutrisi dan bahkan kemungkinan.dapat mengakibatkan teratogenik. (3–karoten seharusnya menjadi sumber utama vitamin A bagi wanita usia produktif, mengingat /3–karoten tidak -toksis terhadap embrio.
– Produk yang mengandung retinol/ester retinil seharusnya diberi label peringatan bahwa pemakaian yang berlebihan dapat membahayakan embrio/fetus.
Oleh karena itu megadosis vitamin A hendaknya dihindari menjelang atau selama kehamilan.
TPO
Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 59

Cermin Dunia Kedokteran No. 55, 1989 60
Ruang Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran
Dapatkah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini? 1. Di Indonesia, urban malaria dijumpai di :
a) Jakarta b) Ujungpandang c) Biak d) Jayapura e) Kupang
2. Nyamuk vektor malaria yang dijumpai di Jawa dan Bali ialah nyamuk di bawah ini, kecuali : a) A. aconitus b) A. sundaicus c) A. barbiro stris d) A. balabacensis e) A subpictus
3. Sifat A. sundaicus adalah seperti di bawah ini, kecuali: a) Berkembang biak di air payau b) Lebih menyukai permukaan air terbuka yang
terlindung dari sinar matahari c) Ada strain yang telah resisten terhadap DDT d) Merupakan vektor utama di daerah persawahan e) Semua benar.
4. Slide positivity rate lebih dari 30% ditemukan di propinsi: a) Kalimantan Barat b) Kalimantan Timur c) Kalimantan Selatan d) Kalimantan Tengah e) Sulawesi Selatan
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karsi-nogen ialah : a) Prokarsinogen b) Kokarsinogen c) Sitokrom d) Sel tujuan e) Semua benar
6. Zat-zat di bawah ini dapat bersifat karsinogen, kecuali: a) Aflatoksin b) Benzidin c) Fenasetin d) Fenobarbital e) Kloramfenikol
7. Hal-hal yang mempengaruhi interaksi obat dengan makanan ialah:
a) Kecepatan pengosongan lambung b) Perubahan aliran darah lambung c) pH lambung d) Sekresi dan produksi empedu e) Semua benar
8. Antibiotika di bawah ini absorpsinya akan berkurang pada suasana asam, kecuali : a) Pensilin b) Amoksisilin c) Eritromisin d) Tetrasiklin e) Rifampisin