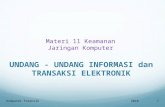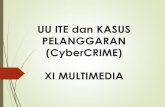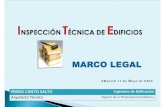Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITE
-
Upload
internetsehat -
Category
Internet
-
view
594 -
download
0
Transcript of Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITE

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 1
Catatan Kritis Terhadap Rancangan Undang‐Undang
Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik
A. Pengantar
Di era modern seperti sekarang ini, teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam
aktivitas kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan semakin
canggihnya fitur‐fitur yang ditawarkan teknologi digital untuk membantu aktivitas manusia
memiliki andil yang sangat signifikan dalam mendigitalisasi perilaku manusia di ruang publik.
Aktivitas yang dulu dilakukan secara offline telah bermigrasi ke ruang‐ruang online.
Perkembangan ini harus direspon dengan seperangkat regulasi yang dapat mengakomodasi
kebutuhan teknologi untuk beraktualisasi dalam kehidupan manusia tanpa mengurangi esensi
kemanusiaan itu sendiri. Kebebasan yang secara hakiki diperoleh ketika manusia beraktivitas
secara offline harus dipertahankan ketika online.
Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dengan membentuk Undang‐Undang No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konsiderans UU ITE secara jelas
mengakui bahwa UU ITE ditujukan untuk mengatur kegiatan yang muncul sebagai konsekuensi
dari perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah infrastruktur
hukum berupa regulasi untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka
melakukan pencegahan penyalahgunaan yang mengacu pada nilai sosial budaya masyarakat
Indonesia.
Pada dasarnya, semangat pembentukan UU ITE pada masa itu bertujuan untuk mengatur posisi
dokumen elektronik, informasi elektronik dan tanda tanda tangan elektronik dalam hukum dan
kaitannya dengan aktivitas pemanfataannya; pelembagaan sistem elektronik dan
penyelenggaraan sertifikasi elektronik; aspek‐aspek transaksi elektronik, nama domain, HAKI,
dan perlindungan hak pribadi; serta pengaturan mengenai peran masyarakat dan pemerintah.
Pembentukan UU ITE, jika dilihat dari materi muatannya, sebenarnya diniatkan untuk
mengatur pemanfaatan teknologi dalam transaksi perdagangan. Salah satu teknologi yang
dimanfaatkan, terutama sekali, adalah internet. UU ITE ditujukan untuk mengatur setiap ekses
yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi informasi global bagi dunia perekonomian
dan perdagangan.1
1 Lebih lanjut diuraikan dalam: Wahyudi Djafar, Kebijakan Kontrol versus Kebebasan Berinternet, (Jakarta: ELSAM, 2014), hal. 23.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 2
UU ITE memiliki pengaturan yang terlampau luas jika sejak awal diniatkan hanya untuk
mengatur kegiatan perekonomian secara elektronik. Kendati seluruh pasal di dalam UU ITE
mengatur hubungan ekonomi, beberapa pasal di dalamnya justru digunakan untuk hal‐hal yang
melampaui niat awalnya. Secara garis besar, selain mengatur ihwal transaksi elektronik, tanda‐
tangan elektronik, bukti elektronik, UU ITE juga mengatur ihwal perlindungan data pribadi,
yurisdiksi, intelectual property, pencemaran nama baik, ujaran kebencian bahkan kesusilaan
dalam konteks digital. Sayangnya, model pengaturan semacam ini justru melahirkan masalah
baru perihal penikmatan kebebasan berekspresi dan berpendapat akibat penegakan Pasal 27,
Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE yang ancaman pidananya lebih lima tahun. Selain secara
konstitusionil melanggar, model pengaturan tindak pidana internet yang diatur hanya dengan
tiga pasal minim penjelasan merupakan sebuah kekeliruan besar dalam prinsip tata kelola
internet. Mengingat luasnya dimensi internet (bukan hanya menyangkut ihwal perekonomian
digital semata), UU ITE merupakan ancaman tidak hanya pada durabilitas (daya tahan) aktivitas
perekonomian modern melainkan juga pada komitmen pemajuan dan penegakan hak atas
kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mengikat Pemerintah Indonesia dalam hukum
HAM internasional.
Kasus‐kasus yang bermunculan sepanjang 2008‐2015 menunjukkan bahwa penggunaan pasal‐
pasal pidana terutama Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 UU ITE dilatar‐
belakangi oleh motif yang memanfaatkan relasi kuasa untuk membungkam kritik terhadap
kinerja pejabat negara dan politisi. Dengan pola yang sama pula, UU ITE menjadi legitimasi bagi
pemilik kapital untuk mengkriminalisasi konsumen yang menyampaikan keluhan terhadap
pelayanan komersil yang dinikmatinya. Dalam waktu kurang dari delapan tahun, UU ITE justru
berperan secara kontradiktif dalam merespon perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.
UU ITE, di sisi lain, justru menjauh dari diskursus teknologi informasi yang semakin kompleks
seperti hak atas privasi. Kemajuan teknologi informasi memampukan teknologi untuk
menyimpan data‐data pribadi individu secara massal yang dapat disalahgunakan oleh pihak
lain. Diskursus lain yang berkembang adalah adanya tren untuk menggunakan internet sebagai
medium penyebarluasan atau propaganda kebencian terhadap ras, agama dan etnik yang secara
signifikan akan berimplikasi pada eksistensi konten‐konten di internet. Regulasi internet
semestinya mampu menjangkau area yang sangat kompleks dari kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi sebagai bagian dari penyediaan medium untuk berekspresi dan berpendapat.
Indonesia sudah memiliki basis konstitusionalnya bahwa setiap orang memiliki kebebasan
untuk mengeluarkan pendapat, gagasan dan ekspresi di ruang publik. Undang‐Undang Dasar
1945 juga menjamin setiap orang untuk bebas mengakses dan menyebarluaskan informasi tanpa
membiarkan hak atas privasi orang lain terganggu. Isu pemanfaatan teknologi informasi,
khususnya internet, pada dasarnya merupakan isu yang belum terlalu lama dan tengah
mengalami perkembangan diskursus yang signifikan. Model penyelesaian sengketa kasus‐kasus
internet, sebagai elemen penting dalam diskursus tata kelola internet, merupakan hal yang
terus‐menerus didorong agar diwujudkan karena kekhasan internet itu sendiri. Berdasarkan
hal‐hal di atas, UU ITE ternyata telah jauh tertinggal dari apa yang selama ini dibayangkan.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 3
B. Gambaran Umum Implementasi UU ITE
Alih‐alih dapat mengatasi persoalan teknologi informasi secara baik, penegakan UU ITE justru
memicu penolakan dari publik. Undang‐undang yang semula ditujukan untuk mengatur
penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang, justru mengandung beberapa
muatan pasal yang melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat. Persoalannya adalah
penegakan hukum UU ITE yang diharapkan memberikan keadilan dan kepastian hukum justru
tak pernah mencapai tujuan itu sama sekali. Mulai dari model pengaturan yang tidak sesuai
dengan mandat hak asasi manusia dalam Undang‐Undang Dasar 1945 hingga putusan hakim
yang menunjukkan beragamnya interpretasi terhadap pasal‐pasal pemidanaan di dalam UU
ITE. Di antara pasal‐pasal pemidanaan yang ada, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran
nama baik adalah yang paling problematik.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safe Net) Indonesia mencatat bahwa UU ITE
telah digunakan untuk mengkriminalisasi sebanyak 127 netizen sejak disahkan pada 2008. Di
samping itu, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun mulai dari hanya 4 kasus
selama dua tahun pertama UU ITE disahkan dan meningkat hingga 62 kasus untuk tahun 2015
saja. Hal ini menunjukkan UU ITE semakin menjadi tren pemidanaan dan trennya diperkirakan
akan jauh melampaui jumlah saat ini jika UU ITE masih dipertahankan sampai tahun‐tahun
mendatang. Perlu diingat bahwa 127 kasus ini hanyalah kasus‐kasus yang diancam dengan
pelanggaran terhadap Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE serta Pasal 31 UU ITE tentang penyadapan
ilegal.
Sumber: Rincian kasus UU ITE sejak 2008 hingga 2015 oleh Safe Net.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Psl 31 0 0 0 0 0 0 0 1
Psl 29 0 0 0 0 0 1 0 1
Psl 28 (2) 0 0 0 0 1 1 2 5
Psl 27 (3) 2 2 1 3 6 18 38 48
Psl 27 (1) 0 0 0 0 0 0 0 2
Somasi 0 0 0 0 0 1 1 3
0
10
20
30
40
50
60
70
Jumlah

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 4
Berdasarkan data yang diolah Safe Net di atas, pola pemidanaan menunjukkan adanya
penggunaan kekuasaan dalam memanfaatkan kehadiran pasal‐pasal karet dalam UU ITE di atas.
Adanya tren penuntutan yang tidak menggunakan pidana maksimal plus putusan hakim yang
selalu di bawah tuntunan menunjukkan keberadaan UU ITE sendiri diragukan secara hukum
oleh penegak hukum. Interpretasi hakim terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam beberapa
kasus misalnya, menunjukkan keberagaman yang menghilangkan asas kepastian hukum UU
ITE. Dalam beberapa putusan, misalnya, hakim selalu menautkan Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal
310 dan/atau Pasal 311 KUHP sehingga tujuan UU ITE sebagai lex specialis dari ketentuan KUHP
tidak tercapai. Meskipun demikian, ada juga putusan hakim yang hanya menggunakan pasal‐
pasal UU ITE tanpa pasal‐pasal KUHP yang justru menunjukkan betapa fleksibelnya penafsiran
terhadap UU ITE.
Dari seluruh kasus yang pernah terjadi, mayoritas pelapor adalah orang‐orang yang memiliki
posisi strategis di pemerintahan, politisi atau pemilik kapital. Sementara yang dilaporkan adalah
orang‐orang yang punya akses kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan pelapor seperti
wartawan, tukang sate, pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga, mahasiswa, penulis, sastrawan
dan perawat. Meskipun ada juga kasus di mana posisi terlapor dan pelapor setara, penggunaan
UU ITE lebih sekedar sebagai upaya balas dendam pelapor terhadap terlapor. Berikut adalah
kategori para pelapor, seperti yang dicatat Safe Net, disusun secara berurutan menurut
persentase:
1. Pejabat publik (kepala daerah, kepala instansi/departemen).
2. Kalangan profesi (dokter, jaksa, polisi).
3. Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pimpinan/manajer perusahaan).
4. Sesama warga (statusnya setara).
Dalam laporan situasi kebebasan berekspresi tahun 2014, Lembaga Studi dan Advokasi
masyarakat (Elsam) mencatat bahwa medium elektronik yang dapat dijangkau UU ITE bahkan
lebih luas dari apa yang dibayangkan. Facebook, media online, youtube, twitter memang masih
mendominasi sebagai medium yang terjangkau UU ITE. Namun di sisi lain, UU ITE ternyata
juga menjangkau televisi sebagai medium berpendapat yang dapat dijerat dengan UU ITE.
Prinsipnya, sepanjang setiap peralatan informasi dan komunikasi dapat ditafsirkan sebagai
benda elektronik, maka UU ITE dapat menjangkaunya.
Sumber: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia 2014, ELSAM.
Facebook, 46%
Twitter, 12%Youtube, 7%
Path, 5%
Line, 3%
BBM, 3%
SMS, 5%
Email 2%
Televisi, 2% Media Online, 15%

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 5
Salah satu kasus kriminalisasi atas ekpresi yang sah yang terkenal adalah kasus Florence yang
menuliskan status dalam akun media sosialnya dengan konten yang dianggap menghina kota
Yogyakarta tempatnya menempuh jenjang strata‐2. Atas perbuatannya tersebut, Florence
diancam 6 tahun penjara.2 Selain Florance terdapat kasus Furqan Ermansyah pemilik akun
Facebook ‘Rudy Lombok’ dijerat dengan pasal serupa karena dianggap telah mencemarkan
nama baik Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat (BPPD NTB). Selain itu
kenyataannya masih banyak sederet nama yang harus menjalani proses hukum akibat
menyalurkan ekspresi yang sah melalui internet seperti Prita Multasari, Benny Handoko, dan
sejumlah nama lainnya.
UU ITE juga menerapkan sanksi pidana penjara yang sangat tinggi hingga enam tahun. Namun
pada faktanya, penuntut umum jarang melakukan penuntutan dengan tuntutan maksimal dan
hakim selalu memutus dengan vonis penjara di bawah dakwaan. Dalam catatan Safe Net
setidaknya hakim selalu memutus pidana di bawah dua tahun penjara. Hal ini membuktikan
bahwa penetapan tingginya sanksi pidana tidak memiliki makna yang esensial (apalagi
proporsional) dengan tindak pidana yang dilakukan. Apa rasionalitasnya? Kenapa jumlah yang
ditetapkan sedemikian rupa? Tidak ada penjelasan.
Dilihat dari tingginya penggunaan pasal pencemaran nama baik ini maka terlihat bahwa
pelaksanaan UU ITE sudah tidak sesuai dengan koridor sebagaimana tujuan awal dibentuknya
undang‐undang ini. Terutama delik pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi
yang menimbulkan rasa permusuhan yang diancam lebih berat dari KUHP. Dalam konteks
pencemaran nama baik, pengaturan ini merupakan salah satu bentuk represi terhadap hak
untuk menyatakan pendapat dan ekspresi. Karena dapat mengancam pihak‐pihak, baik secara
individu dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun pekerjaan jurnalistik.
Selain itu juga kekosongan hukum terkait pengaturan konten internet yang menyebabkan
tindakan semena‐mena dalam pemblokiran dan penapisan atas konten internet. Hal ini
disebabkan karena Indonesia belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan
akuntabel dalam hal melakukan pemblokiran konten internet. Padahal UU ITE sebagai salah
satu payung hukum kebijakan terkait internet dapat menjadi rujukan dalam pembentukan
kebijakan pemblokiran dan penyaringan. Akibat kekosongan hukum tersebut dan ketiadaan
pengaturan yang jelas setingkat undang‐undang maka pembatasan hak atas tindakan
pemblokiran dilakukan secara semena‐mena. Pada akhirnya masyarakat secara perlahan
kehilangan hak atas informasi yang merupakan bagian dari pembatasan terhadap hak asasi
manusia.
Meningkatnya kriminalisasi atas ekspresi yang sah dan pemblokiran konten internet yang
semena‐mena menyebabkan sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU
ITE. Hal ini disebabkan karena jelang tujuh tahun berlakunya peraturan tersebut, UU ITE tidak
sesuai dengan naskah awal dibentuknya terdahulu. Pengaturan yang seharusnya meletakkan
prinsip‐prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak‐hak pengguna,
2 Lihat http://news.liputan6.com/read/2154890/status‐di‐media‐sosial‐yang‐berujung‐bui‐sepanjang‐2014?p=1, diakses pada 28 Agustus 2015.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 6
serta perumusan tanggungjawab dari pemangku kepentingannya.3 Namun demikian, muatan
konten revisi tersebut juga perlu diawasi guna menciptakan harmonisasi peraturan dan menjaga
pengaturan dalam rangka melindungi pemanfaatan teknologi internet.
C. Prinsip Pengaturan Hukum Teknologi Informasi
Dalam waktu yang relatif singkat teknologi internet menjadi salah satu instrumen penting
dalam kehidupan manusia. Pasalnya pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana informasi
dan teknologi telah hadir dalam ruang‐ruang pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti
kesehatan, pendidikan, dan menciptakan revolusi dalam transaksi ekonomi. Fenomena tersebut
turut mempengaruhi perkembangan dalam dunia hukum yang kenyataannya memiliki proses
dinamika yang lambat dan tidak secepat perkembangan teknologi itu sendiri. Di sisi lain,
penyalahgunaan dari teknologi tersebut membutuhkan peran hukum dalam mengembalikan
tujuan dari perkembangan teknologi. Dengan demikian seiring dengan perkembangannya,
dibutuhkan pula peran hukum yang responsif atas perkembangan teknologi yang semakin
canggih.
Karakteristik teknologi internet yang memiliki skala global dan tanpa batas membutuhkan
suatu regulasi dan tata kelola internet yang diharapkan mampu melindungi dan sesuai dengan
harapan masyarakat internasional. Dengan demikian terdapat jaminan untuk memanfaatkan
teknologi tersebut secara berkelanjutan dalam konteks jaringan global. Meskipun demikian,
perlindungan tersebut secara utama ditujukan pada pemerintahan suatu negara. Negara sebagai
entitas kekuasaan, memiliki yurisdiksi atas orang, benda, dan peristiwa yang terjadi dalam
wilayahnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anggota
masyarakat dari segala macam ancaman dan atau bahaya. Adapun pengaturan upaya
perlindungan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kerangka referensi hukum. Yang
kemudian hukum tersebut mengimplementasikan nilai dan pemahaman akan pemanfaatan
teknologi internet.
Kerangka referensi hukum dalam pengaturan pemanfaatan teknologi internet merupakan
bentuk multidisipliner ilmu hukum yang harus direintegrasi dengan berbagai ilmu. Sehingga
segi teknis teknologi internet harus dipadukan dengan segi yuridis sehingga menciptakan
regulasi internet. Regulasi mengenai tata kelola internet tidak lain bertujuan untuk melindungi
kepentingan umum yang ada dalam setiap pemanfaatannya. Berdasarkan klasifikasi yang
dijelaskan Roscoe Pound, kepentingan hukum terbagi menjadi tiga kategori yaitu kepentingan
publik (public interest), kepentingan masyarakat (social interest), dan kepentingan pribadi
(private interest).4 Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan negara
sebagai badan hukum dan sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Sedangkan kepentingan
masyarakat adalah kepentingan sosial akan keamanan umum seperti kedamaian dan ketertiban,
kesehatan dan keamanan. Kepentingan sosial ini turut berperan dalam memelihara sumber
daya sosial yang juga termasuk dalam kemajuannya. Kepentingan pribadi adalah kepentingan
individu, keluarga, dan hak milik yang termasuk protecticon of physical integrity, freedom of
will, reputation, privacy, freedom of belief and opinion. Dengan demikian regulasi internet
3 Lihat Joanna Kulesza, Internasional Internet Law, (London: Routlegde, 2012) 4 Wolfgang Friedmann, Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1993), hal. 131.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 7
memiliki konsekuensi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan‐kepentingan
tersebut secara seimbang.5
Dalam rangka menjaga kepentingan‐kepentingan umum tersebut, inisiatif dalam regulasi
bidang tata kelola internet yang berlandaskan hukum dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yang
terdiri dari 1)Regulasi yang mengatur khusus mengenai prosedur internet; 2) Regulasi terhadap
penyesuaian atas pemanfaatan internet (misalnya perlindungan merk dagang); 3) Regulasi
mengenai pemanfaatan internet yang tidak membutuhkan penyesuaian secara signifikan dan
melindungi kepentingan umum. (Misalnya perlindungan hak). Pengaturan internet yang
demikian diharapkan menjamin stabilitas dan mengurangi kompleksitas dalam tata kelola
internet yang pada dasarnya memiliki satu tujuan yaitu mempertahankan fungsi internet serta
turut serta dalam dinamika pembangunan internet. Dengan demikian regulasi tersebut menjadi
fleksibel terhadap perubahan perkembangan teknologi, sekaligus menciptakan mekanisme
yang efisien dalam tata kelola internet.
D. Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia
Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat tahun 2009,
menyatakan bahwa selama bertahun‐tahun internet telah digunakan oleh masyarakat global
untuk mengakses dan menyebarkan informasi serta menyampaikan gagasannya. Internet telah
menjadi ruang publik di mana warga negara memiliki hak untuk mengaktualisasikan
ekspresinya atas nama hak asasi manusia. Tidak mengherankan hingga akhirnya La Rue
menegaskan bahwa kehadiran undang‐undang nasional yang komprehensif mutlak diperlukan
sebagai bagian dari penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan
berpendapat di internet.
Ide tersebut selaras dengan bunyi konstitusi Indonesia yaitu Undang‐Undang Dasar 1945.
Sebagai negara demokrasi, Pasal 28 F UUD 1945 menuliskan bahwa Indonesia berkewajiban
untuk melindungi warga negara dalam hal berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.6 Pula berdasarkan resolusi 20/8 Dewan
HAM Perserikatan Bangsa‐Bangsa menegaskan bahwa perlindungan hak yang dimiliki setiap
orang secara tradisional atau pada saat offline, juga secara otomatis melekat pada saat mereka
online. Perlindungan ini khususnya terkait dengan hak atas kemerdekaan berekspresi, yang
berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang digunakan. Sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik,
yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU no. 12 Tahun 2003. Sehingga Indonesia secara
hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi memiliki konsekuensi untuk
memberikan perlindungan atas hak informasi warga negaranya.
Berdasarkan konsensus internasional, pada dasarnya pembatasan kebebasan ekspresi dapat
dilakukan. Hal tersebut tertulis dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional Hak‐hak
Sipil dan Politik (Sipil) mengatur sejumlah jaminan kebebasan berekspresi. Yang kemudian
dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang memperbolehkan pembatasan dalam hal‐hal
tertentu dan dengan syarat‐syarat tertentu. Menurut ketentuan ini pembatasan yang
5 Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 2. 6 Lihat Pasal 28F UUD 1945.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 8
diperkenankan dalam hukum internasional harus diuji dalam metode yang disebut uji tiga
rangkai yaitu:
1. Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang‐undang;
2. Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan
dalam pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol;
3. Pembatasan tersebut benar‐benar diperlukan dan sepadan (proporsional) untuk
menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut .
Adapun penjelasan mengenai pembatasan hak atas kebebasan ekspresi tersebut dijelaskan lebih
rinci dalam Komentar Umum No. 34 tentang kebebasan berekspresi. Dalam pembahasan
tersebut dijelaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan produk hukum yang
berbentuk undang‐undang yang disesuaikan pada kebutuhan yang telah dibatasi yaitu untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak pribadi dan hak atas
reputasi orang lain, dan untuk memenuhi syarat‐syarat yang adil dalam hal kesusilaan,
ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pada dasarnya Komentar Umum No. 34 disebutkan bahwa pembatasan tersebut bukan
merupakan sebuah paksaan dari negara, karena apabila pembatasan dalam bentuk undang‐
undang itu merupakan sebuah pemaksaan dari negara maka dapat disimpulkan pembatasan itu
tidak lagi didasarkan pada suatu keadaan “bahaya” atau suatu kebutuhan negara tersebut.7
Melainkan peraturan tersebut sebatas menjadi kekuasaan pemerintah yang bertindak sebagai
penguasa.
Selain itu, Komentar Umum No. 34 juga menyebutkan bahwa pembatasan tidak hanya harus
sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 19 ayat (3), namun harus sesuai dengan ketentuan
dan tujuan dari Kovenan Hak Sipol itu sendiri. Sehingga Undang‐Undang tersebut tidak boleh
melanggar ketentuan non‐diskriminatif dari kovenan. Salah satu poin penting adalah
keberadaan undang‐undang tersebut tidak boleh memberikan hukuman‐hukuman yang tidak
sesuai dengan Kovenan seperti hukuman fisik.
E. Catatan Kritis Terhadap Rancangan UU Perubahan UU ITE
1. Pasal 27 ayat (3): (Masih) Melanggar Hak atas Kebebasan Ekspresi
Masifnya penggunaan pasal 27 ayat (3) oleh penegak hukum atas sejumlah pengaduan atas
ekspresi yang sah merupakan salah satu alasan penting untuk merevisi UU ITE. Rumusan pasal
tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan; penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik, dan materi yang mengandung materi SARA, serta tingginya ancaman
hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun denda, meski
menuai banyak kontroversi kenyataannya tidak diubah. Bentuk perubahan hanya berkutat pada
pengurangan ancaman pidana penjara yang semula enam (6) tahun menjadi empat tahun, tanpa
melihat kembali rumusan ancaman pidana tersebut.
7 Lihat Komentar Umum No. 34 Kovenan Internasional Hak‐Hak Sipil dan Politik.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 9
Padahal rumusan dalam RUU ITE memberikan definisi baru atas perbuatan pencemaran nama
baik. Meskipun penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam ayat ini mengacu
pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP, tetapi dengan rumusan perbuatan yang tertulis dalam pasal
27 ayat (3) maka unsur‐unsur yang terkandung di dalamnya memiliki konsekuensi yang
berbeda. Penjelasan tersebut tidak detail menguraikan sejauh mana pencemaran nama baik
dalam RUU ITE mengadopsi unsur‐unsur dalam KUHP. Selain itu ancaman hukuman dalam
RUU ITE jauh lebih berat dibandingkan dengan ancaman yang tertulis dalam KUHP, sehingga
berpengaruh pada hukum acara pidana dan sangat kental pembatasan atas kebebasan ekspresi
dalam peraturan tersebut.
Pada dasarnya rumusan pasal Pencemaran Nama Baik yang terkandung dalam pasal 27 ayat (3)
RUU ITE masih dapat diakomodir oleh rumusan dalam KUHP. Hal ini dapat dilihat dari
perbandingan unsur‐unsur yang terkandung dalam rumusannya.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Pasal 310 KUHP Pasal 311 KUHP
Rumusan Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama‐lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak‐banyaknya Rp. 4.500,‐“ (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama‐lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak‐banyaknya Rp. 4.500,‐
Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama‐lamanya empat tahun.
Unsur a. Setiap orang b. Dengan sengaja atau
tanpa hak :
a. Barang siapa a. Seseorang

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 10
mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya
c. Informasi Elektronik dan/atau Dokuem Elektronik
d. Yang memiliki muatan: penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
b. Merusak kehormatan atau nama baik
c. Menuduh melakukan sesuatu
d. Menyebarkan berita tersebut pada khalayak umum
b. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan
c. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar
Dalam rumusan pasal‐pasal tersebut dapat melihat perbandingan yang akan berakibat pada
akibat hukumnya, yang bisa didetailkan berikut ini:
a. Frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses”
Kenyataannya frasa ini tidak menunjukkan unsur objektif sebagaimana layaknya sebuah delik
pidana. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan mengenai tindakan apa yang dapat dikategorikan
sebagai “membuat dapat diakses”. Dalam konteks pemanfaatan internet, pada dasarnya
aktivitas internet membuka kesempatan bagi pihak lain untuk mengakses atau mengetahui
persebaran informasi. Sehingga pada dasarnya definisi ini menjadi sangat kabur apakah
perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan pelaku internet yang mengunggah,
ataukah pihak penyelenggara sistem internet? Pada dasarnya frasa tersebut dapat menjadi
‘perluasan’ dari unsur ‘menyebarkan pada khalayak publik’ dalam pidana pencemaran nama
baik KUHP.
b. Frasa ‘memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
Rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) tidak mengatur secara jelas unsur‐unsur sebuah informasi
elektronik yang seperti apa yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
Jika mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP, maka KUHP memberikan penjelasan yang lebih
detail mengenai penistaan yang diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud untuk merusak
nama baik atau kehormatan seseorang. Selain itu terdapat unsur yang harus dipenuhi adalah
bahwa berita yang disebarkan tersebut adalah tidak benar atau tidak dapat dibuktikan, maka
pihak yang menyebarkan dapat dihukum. Sehingga terdapat pengujian atas konten pencemaran
nama baik itu terlebih dahulu.
Sedangkan pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam RUU ITE tidak menjelaskan lebih
lanjut mengenai frasa “muatan penghinaan” atau “pencemaran nama baik”. Padahal kejelasan
terhadap bentuk perbuatan tersebut mempertegas batasan terhadap suatu pernyataan yang
dianggap sebagai penghinaan. Dengan kata lain Pasal 27 ayat (3) tidak memenuhi prinsip‐
prinsip perumusan delik dalam doktrin hukum pidana. Secara umum tindak pidana ini adalah
tindak pidana formal yang tidak memerlukan implikasi atau akibat, jadi walaupun tidak
diuraikan secara jelas mengenai kerugian yang diderita atau mengakibatkan hal‐hal tertentu
maka dapat dijerat dengan pasal ini. Hal ini dapat berakibat memberikan ketidakpastian hukum

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 11
dan keadilan karena penggunaan pasal ini cenderung bersifat subjektif dan kabur.8 Tanpa
adanya pengujian akan unsur ‘penghinaan’ atau ‘pencemaran nama baik’ dalam RUU ITE maka
setiap tindakan mendistribusikan informasi ke dalam internet akan sangat membatasi ruang
ekspresi masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena undang‐undang menyebabkan timbulnya
ketakutan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas (berekspresi) di dunia maya yang tidak
lain adalah bentuk pelanggaran akan hak kebebasan ekspresi masyarakat.
2. Kemunduran Dalam Hukum Acara Pidana Khususnya Dalam Proses Penahanan
Ancaman pidana pasal 27 ayat (3) RUU ITE dituliskan dalam pasal 45 ayat (3). Bentuk revisi
terkait pasal pencemaran nama baik ini hanya sebatas pengurangan pidana penjara yaitu yang
semula dari enam (6) tahun menjadi empat (4) tahun dan denda Rp 750.000.000,‐. Meskipun
sudah direvisi, besarnya ancaman tersebut tetap lebih berat dibandingkan ancaman pidana
dalam KUHP. Ancaman pidana untuk penghinaan dalam KUHP relatif ringan karena berkisar
pada penjara 4 bulan, 9 bulan, hingga 4 tahun bagi pembuat memfitnah. Hal ini menjadi kental
sebagai kebijakan yang represif karena tujuan awal UU ITE dibentuk untuk mengatur mengenai
transaksi elektronik dan bukan mengenai tindak pidana.
Beratnya ancaman pidana penghinaan nama baik dalam RUU ITE memiliki konsekuensi dalam
proses peradilan khususnya dalam proses penahanan. Meskipun ancaman penjara tidak lebih
dari 5 tahun tetapi pada prosesnya, RUU ITE tidak mewajibkan adanya penetapan yang
dikeluarkan ketua pengadilan negeri setempat sebagaiaman diatur dalam UU ITE. Hal ini
merupakan salah satu kemunduran dalam proses pidana dalam konteks UU ITE.
3. Izin Hakim Dalam Penangkapan dan Penahanan Telah Sesuai dengan Prinsip
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Salah satu hal yang paling mengherankan dari perubahan UU ITE adalah pemerintah berusaha
merubah pengaturan yang pada dasarnya sangat baik. Yaitu merubah adanya penetapan dari
Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila ingin melakukan penahanan dan penangkapan.
Perlu untuk digarisbawahi bahwa ICCPR telah mengatur agar setiap orang yang dicabut dari
kebebasannya ‘berhak untuk diajukan ke pengadilan, agar pengadilan tanpa penundaan
memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila
penahanan tersebut tidak sah.9 Oleh karena itu setiap orang yang ditangkap atau ditahan karena
tuntutan pidana harus segera dibawa ke depan hakim atau petugas lain yang diberi kuasa
hukum untuk menggunakan kekuasaan yudisialnya.10
Dalam konteks ini, harus diakui bahwa UU ITE telah mengatur setidaknya lebih memumpuni
bahkan dari pada pengaturan yang dilakukan dalam KUHAP yang saat ini berlaku. Ketentuan
yang terdapat dalam ICCPR harus menjadi pertimbangan dan dasar utama pengaturan
penangkapan dan penahanan dalam RUU ITE sebab Indonesia merupakan negara pihak dalam
ICCPR.
8 Lebih lanjut diuraikan dalam: Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Pasal Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya, (Jakarta: ELSAM, 2015), hal. 18. 9 Pasal 9 ayat (4) ICCPR. 10 Pasal 9 ayat (3) ICCPR.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 12
Keinginan Pemerintah untuk kembali mencabut ketentuan dalam Pasal 43 ayat (6) dengan
mengatur penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, juga
merupakan bentuk ketidaktelitian perumus dalam melihat arah kebijakan hukum acara pidana
Indonesia yang saat ini ada dalam RKUHAP. Konsep KUHAP yang telah direvisi
memperkenalkan pos (institusi‐lembaga) baru tentang Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP),
yang pada prinsipnya berkeja untuk melihat legitimasi penangkapan dan penahanan dengan
waktu singkat setelah seseorang ditangkap atau ditahan.
Dengan begitu, maka sudah tepat apabila dalam hal penangkapan dan penahanan, haruslah
mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, selain sebagai bentuk kontrol, juga
merupakan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, terlebih Indonesia harus juga
menyesuikan dengan kewajiban internasional nya terhadap ICCPR yang telah diratifikasi.
4. Ketentuan Mengenai Prosedur Penyadapan/Intersepsi Komunikasi Harus
Diatur Dengan Undang‐Undang
Pengaturan mengenai penyadapan terhadap informasi pribadi diatur dalam Pasal 31 ayat (1)
sampai (4) UU ITE yang kemudian dalam rancangan revisi UU ITE Pasal 31 ayat (4) dihapus.
Rancangan perubahan pasal intersepsi dalam UU ITE sama sekali mengabaikan fakta bahwa
diskursus intersepsi terhadap data privasi merupakan sebuah komponen perlindungan hak
asasi manusia yang sangat khas dan tidak bisa serta‐merta diintegrasikan dengan pengaturan
internet secara umum. Majelis Umum PBB bahkan mengeluarkan resolusi khusus untuk
perlindungan hak atas privasi melalui Resolusi 69/166 Tentang Hak Atas Privasi di Era Digital
yang pada intinya meminta seluruh negara pihak Kovenan mengevaluasi seluruh regulasi terkait
dengan hak atas privasi dan mengutamakan perlindungan hak atas privasi dalam setiap
pengambilan kebijakan berbasis pemanfaatan teknologi digital.
Di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas privasi dijamin oleh Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945
yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi manusia.” Jaminan terhadap hak atas privasi bahkan dinyatakan dalam UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup dimensi perlindungan diri pribadi,
martabat dan keluarga (Pasal 29 ayat (1)), bebas dari rasa aman dan tentram (Pasal 30), bebas
dari gangguan (Pasal 31 ayat (1)), larangan memasuki pekarangan rumah orang lain (Pasal 31
ayat (2)) dan kemerdekaan dalam hubungan surat‐menyurat (Pasal 32).
Dalam Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, hak atas privasi dilindungi dalam Pasal 17 ICCPR
yang perlindungannya mencakup (1) perlindungan dari interferensi yang sewenang‐wenang dan
tidak sah dan (2) hak untuk dilindungi dari interferensi dan serangan. Kovenan mengakui
bahwa hak atas privasi dapat dibatasi sehingga secara hukum seseorang dapat diakses data
pribadinya untuk kepentingan yang sangat terbatas. Frank La Rue menyatakan bahwa ada enam
syarat yang harus dipenuhi dalam hal pembatasan terhadap hak atas privasi yaitu (1) segala
bentuk pembatasan harus diatur dengan undang‐undang; (2) pembatasan tidak boleh
melanggar esensi perlindungan hak asasi manusia; (3) pembatasan dilakukan dalam masyarakat

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 13
yang demokratis; (4) pembatasan tidak boleh mengekang penikmatan atas hak asasi manusia
lainnya; (5) pembatasan merupakan tindakan yang memang benar‐benar dibutuhkan untuk
mencapai tujuan (prinsip nesesitas); dan (6) pembatasan harus sesuai dengan prinsip
proporsionalitas yaitu tindakan pembatasan harus sepadan dengan kepentingan yang ingin
dilindungi.11
Pernyataan La Rue sangat sejalan dengan mandat Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang‐undang dengan maksud semata‐mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai‐
nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Prinsip kembali ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU‐VIII/2010
tentang pengujian UU ITE yang menyatakan bahwa mekanisme penyadapan harus diatur dalam
undang‐undang tersendiri dengan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi. Lebih
lanjut, MK menguraikan elemen apa saja yang perlu diatur dalam pengaturan mengenai
penyadapan yaitu:
‐ Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam UU untuk memberikan izin penyadapan.
‐ Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan.
‐ Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan.
‐ Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.
Sedangkan, MK menegaskan bahwa unsur‐unsur penyadapan harus didasarkan pada:
‐ Wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penydapan.
‐ Tujuan penyadapan secara spesifik.
‐ Kategori subyek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan.
‐ Adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan.
‐ Tata cara penydapan.
‐ Pengawasan terhadap penyadapan.
‐ Penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting.
‐ Mekanisme komplain.
Indonesia saat ini memiliki 20 jenis peraturan perundang‐undangan yang mengatur mekanisme
penyadapan yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan satu dari tiga fungsi yaitu fungsi
penegakan, fungsi intelijen negara dan fungsi penegakan kode etik hakim. Fungsi‐fungsi itu
dapat dijalankan masing‐masing oleh lembaga intelijen, lembaga penegak hukum hingga
lembaga penegak kode etik hakim yang jumlahnya lebih dari tujuh lembaga pemerintahan.
Durasi penyadapan yang diatur dalam peraturan perundang‐undangan juga bervariasi berkisar
antara 3 bulan sampai waktu yang tak terhingga sedangkan sektor yang dapat menjadi target
penyadapan termasuk intelijen, narkotika, pencucian uang, korupsi, dan perdagangan orang.
11 Lihat Frank La Rue, Laporan Pelapor Khusus untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Nomor A/HRC/23/40, 17 April 2013, paragraf ke‐29.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 14
Mempertimbangkan luasnya muatan pengatura penyadapan, sangat tidak tepat meletakkan
pengaturan penyadapan di dalam UU ITE. Penyadapan merupakan tindakan yang membatasi
hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturannya harus dilakukan dengan undang‐undang
sebagaimana mandat UUD 1945.
5. RUU ITE Harus Memberi Ruang Ihwal Prosedur Pemblokiran/Penapisan
Internet Atau Tata Kelola Konten Internet Secara Umum
Sebagai salah satu regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi internet, RUU
Perubahan UU ITE belum memberikan ruang khusus untuk membahas pemblokiran situs atau
konten internet. Akibat kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut maka tindakan
pemblokiran dan penapisan dilakukan dengan semena‐mena tanpa prosedur dan dasar hukum
yang jelas. Padahal di era globalisasi ini, akses peredaran informasi di kalangan masyarakat
sebagian besar sudah berada di dunia internet. Sedangkan berdasarkan prinsip hak asasi
manusia yang dituliskan dalam konsensus internasional, hak atas informasi masyarakat dalam
cara tradisional juga berlaku secara online dalam artian dunia internet. Maka pemblokiran dan
penapisan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai salah satu
bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas informasi.
Perihal pengaturan pemblokiran internet dalam RUU Perubahan UU ITE ini ditemukan pada
pasal 43 ayat 5 poin h yang berbunyi : “membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang
terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat
diakses.” Dari rumusan pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik
memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran atas situs yang diduga sebagai barang bukti
pidana bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam RUU Perubahan UU ITE
menganggap bahwa tindakan pemblokiran adalah salah satu bentuk penahanan dalam hukum
acara pidana agar pelaku tidak menghilangkan barang bukti. Pemahaman tersebut adalah
sangat keliru mengingat berdasarkan konsensus internasional hak asasi manusia yang juga
sudah di ratifikasi Indonesia, tindakan pemblokiran harus berdasarkan pada aturan hukum
yang jelas. Sedangkan di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum akan peraturan mengenai
pemblokiran.
Adapun rencana pemerintah mengenai peraturan atas pemblokiran situs internet diatur dalam
bentuk Peraturan Mentri. Peraturan Menteri sebagai peraturan yang mengatur tindakan
pemblokiran internet tidak sesuai dengan rumusan cakupan peraturan Menteri untuk
melakukan pembatasan hak. Hal ini disebabkan karena tindakan pemblokiran situs internet
merupakan salah satu pembatasan hak yang harus dilakukan berdasarkan ketertiban umum,
moral publik dan kemanan negara sehingga kewenangan akan pembatasan tersebut tidak dapat
dipergunakan secara sewenang‐wenang. Oleh sebab itu pemblokiran internet harus
dirumuskan dalam Undang‐Undang dengan penjelasan secara rigid, batasan dan cakupannya
serta limitatif.
Dengan demikian, secara khusus RUU Perubahan UU ITE harus membatasi wewenang penyidik
dalam hal melakukan pemblokiran karena sejauh ini belum memiliki dasar hukum yang sesuai
dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu RUU Perubahan UU ITE harus menyediakan ruang

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 15
pengaturan konten yang memperhatikan tiga elemen pengujian ini (i)tindakan pemblokiran
konten harus diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan
prinsip‐prinsip prediktibilitas dan transparansi; (ii) tindakan tersebut harus memenuhi salah
satu tujuan yang diatur pada pasal 19 ayat (3) ICCPR, yaitu untuk melindungi hak‐hak dan
reputasi orang lain; keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral
publik sesuai dengan prinsip legitimasi; dan (iii) tindakan itu harus dapat dibuktikan
urgensinya dan seminimal mungkin dilakukan sebagai mekanisme terakhir untuk mencapai
tujuan utama sesuai dengan prinsip‐prinsip kepentingan dan proporsionalitas. Selain itu secara
jelas juga harus mengatur mengenai kewenangan untuk melakukan seluruh tindakan tersebut
harus diberikan pada badan yang independen dari pengaruh politik, komersial atau pihak yang
tidak berwenang, tidak secara semena‐mena ataupun diskriminatif. Hal tersebut tidak lain
untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia khususnya hak kebebasan ekspresi.
F. Penutup dan Rekomendasi
Undang‐Undang ITE dikenal sebagai instrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sanksi pidana dan sanksi adminsitratif, serta banyak aspek‐aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, pengaturan yang termaktub dalam UU ITE nampak sangat dipaksakan karena memadukan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrumen hukum yang terpisah. Konsekuensinya, aspek‐aspek pengaturan dalam UU ITE nampak kurang koheren antara satu dengan yang lainnya. terlepas dari itu, banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman norma hukumnya menjadi dangkal dan berkutat pada tataran permukaannya saja. Oleh karena itu, proses revisi UU ITE ini harus mengakomodasi setidaknya hal‐hal berikut ini:
a. Pengaturan Tata Kelola Konten Internet
Lahirnya UU ITE sebagai salah satu produk hukum yang menangkap fenomena dunia internet dan media elektronik, menjadikan undang‐undang ini sebagai salah satu pedoman dalam pengaturan tata kelola konten internet, termasuk pengaturan mengenai praktik pemblokiran konten internet. Namun kenyataannya UU ITE hanya mengatur mengenai tindakan yang dilarang dan yang dimaknai sebagai pengaturan tentang jenis‐jenis konten dilarang yang termuat dalam Pasal 27,28, 29 UU ITE. Ketidakjelasan dan kekosongan hukum mengenai mekanisme pemblokiran dan jenis konten yang dilarang berdampak pada praktik pemblokiran konten internet terlampau lebih luas dari sasaran yang hendak dituju (over blocking). Dengan demikian, sesuai dengan semangat kelahiran UU ITE sebagai landasan hukum pengaturan intrusi teknologi internet sudah seharusnya menyediakan ruang pengaturan konten internet yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Di samping itu pengaturan tersebut juga dibutuhkan untuk mengharmonisasi sejumlah peraturan terkait pembatasan konten internet. Pengaturan tentang hal ini disisipkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 mengenai pengertian situs internet yang bermuatan negatif, kemudian materi pengaturannya disisipkan antara Pasal 29 dan Pasal 30, dalam bentuk bab baru yang berjudul “Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”, yang muatannya antara lain mengatur sebagai berikut:

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 16
1. Jenis‐jenis konten internet yang bermuatan negatif dapat dilakukan tindakan
pemblokiran konten internet; 2. Prosedur/mekanisme di dalam melakukan tindakan pemblokiran; 3. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pemblokiran; 4. Pemulihan (remedy) yang disediakan.
b. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi
Berdasarkan Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa setiap informasi melalui media eletronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas peretujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang‐undangan. Terkait dengan perlindungan data pribadi seseorang dalam konteks media elektronik yang sangat cepat distribusi informasinya, maka diperlukan sebuah pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang‐Undang. Perubahan Pasal 26 UU ITE selengkapnya sebagai berikut: Pasal 26: (1) Penggunaan setiap data dan informasi melalui sarana elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; (2) Perlindungan data pribadi dalam sarana elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut berdasarkan Undang‐Undang.
c. Pengaturan Lebih Lanjut Terkait Tindakan Intersepsi atau Penyadapan Pengaturan intersepsi atau penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) memerlukan pengaturan dengan ketentuan lebih detil. Adapun ketentuan lanjutan mengenai tata cara intersepsi dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat (4) harus diubah dengan mendasarkan peraturan tersebut kepada Undang‐Undang. Hal ini disebabkan karena materi muatan terkait praktik surveilans erat kaitannya dengan pembatasan akan hak kebebasan warga negara sehingga memerlukan produk hukum setingkat Undang‐Undang untuk mengaturnya. Tujuannya tidak lain untuk meminimalisir pelanggaran terhadap privasi dalam praktik surveilans. Hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU‐VIII/2010 yang mengatakan bahwa praktik penyadapan atau intersepsi komunikasi merupakan bagian dari surveilans, sehingga untuk masuk kategori sebagai lawfull interception diperlukan pengaturan dalam bentuk undang‐undang khusus. Adapun Undang‐Undang tersebut bertujuan mengharmonisasi sejumlah peraturan perundang‐undangan yang mengandung konten surveilans.12 Selain itu demi melindungi hak atas privasi warga negara diperlukan pengaturan yang mengatur pra‐syarat izin melakukan tindakan surveilans tersebut. 12 Setidaknya terdapat 20 peraturan perundang‐undangan yang mengandung konten surveilans : Bab XXVII KUHP Tentang
Kejahatan Jabatan Pasal 430 sampai dengan Pasal 434; UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaUU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 17
Perubahan Pasal 31 UU ITE selengkapnya sebagai berikut:
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang‐undang.
(4) Dihapus, diganti dengan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang‐undang.
d. Penghapusan Pasal Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik,
Kesusilaan, dan Penyebaran Kebencian Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rumusan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE tidak memenuhi prinsip Lex Certa dalam hukum pidana dan merupakan bentuk duplikasi tindak pidana dalam KUHP yang justru mengarah pada overkriminalisasi. Sehingga penerapan dari pasal tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu untuk menghindari permasalahan dari implikasi pengaturan tersebut, pengaturan mengenai pencemaran nama baik, kesusilaan dan penyebaran kebencian dalam UU ITE harus dihapuskan. Sedangkan terhadap tindakan tersebut pengaturannya masih dapat diakomodasi oleh KUHP.
***
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi; Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi No. 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi Untuk Pertahanan dan Keamanan Negara; Peraturan Kapolri tentang Prosedur Intersepsi di Pusat Monitoring Kepolisian.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016
pg. 18
Profil ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak‐hak sipil dan politik serta hak‐hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa‐Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). Kegiatan utama ELSAM adalah: (1) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (2) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (3) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (4) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia. Program kerja ELSAM yaitu: (1) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; (2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan (3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia; Alamat: Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta‐INDONESIA 12510 Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519 Surel: [email protected], laman: www.elsam.or.id, Twitter: @elsamnews ‐ @ElsamLibrary