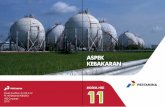Bab Viii Hse, Csr, & Asr
-
Upload
cicungcimong -
Category
Documents
-
view
57 -
download
8
description
Transcript of Bab Viii Hse, Csr, & Asr
80
BAB VIIIHEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT &CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
8.1 PendahuluanDalam melakukan kegiatan MIGAS perlu dilakukan upaya untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan dalam bekerja. Segala peraturan tentang keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan diterapkan dalam HSE (Health Safety and Environment). Penerapan HSE bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, nihil kecelakaan, bebas penyakit dan ramah lingkungan. Adanya bahaya dan resiko pada kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) yang akan berdampak pada pekerja, perlengkapan/peralatan, material, dan lingkungan hidup di sekitar area operasi.Pembahasan materi HSE pada POD di lapangan TMA & TMB ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah kondisi wilayah, study lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggap darurat, medical evacuation, serta Corporate Social Responsibility (CSR). Pembahasan ini didasarkan pada sekenario yang akan dilaksanakan di lapangan TMA & TMB yaitu sekenario penambahan sumur baru. Dengan adanya penambahan sumur baru, berarti akan ada kegiatan pemboran yang dilakukan. Berdasarkan skenario ini aspek HSE yang penting untuk diperhatikan yaitu pada proses pemboran dan juga proses produksi.8.1.2 Landasan Hukum Dasar hokum berupa peraturan-peraturan dan perundang - undangan yang menjadi acuan serta penerapan dalam bidang HSE antara lain :PP No 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang;PP No.35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;UU No.22 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Minyak dan gas Bumi;PP No.42 Tahun 2001 tentang badan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan;UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;PP No.29 Tahun 1997 tentang analisis mengenai dampak lingkungan;UU No.1 Tahun 1970 tentangkeselamatankerja;Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1981);Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14); Keputusan Presiden RI Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan,dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
8.2 Kondisi WilayahLapangan TMA & TMB terletak di perairan selat madura. Untuk kondisi wilayah dapat dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain : secara geografis, secara topografi, dan kondisi dari wilayah tersebut.8.2.1 GeografisWilayah blok TMA & TMB secara geografis blok ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya terletak di wilayah perairan selat Madura dengan koordinat diantara 072313.1 lintang selatan dan 1130203.2 Bujur Timur. Batas wilayah dalam peta regional adalah sebagai berikut : Sebelah Barat : Sidoarjo Sebelah Utara : Pulau Madura Sebelah Selatan: Pasuruan8.2.2 IklimWilayah Jawa Timur Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21-34 C .
8.3 Study LingkunganUntuk menyelenggarakan kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar lokasi lapangan eksplorasi gas field TMA & TMB perlu dilakukan kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan tersebut. Hal ini disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disingkat AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Sebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No.27/ 1999 yang di dukung oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dan keputusan kepala BAPEDAL tentang pedoman penentuan dampak besar dan penting. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usah dan / atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatip dan memaksimalkan dampak positip terhadap lingkungan hidup. AMDAL ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para kontraktor untuk mendapatkan izin melakukan usaha.Di lapanganTMA & TMB ini, untuk mendapatkan izin agar dapat dilaksanakannya proyek pengembangan, maka studi AMDAL mutlak harus dilaksanakan.Dalam studi AMDAL terdapat kriteria - kriteria yang harus dipenuhi agar memenuhi syarat dari kelengkapan AMDAL berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No.56 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting, di antaranya :a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak,b. Luas wilayah persebaran dampak,c. Lamanya dampak berlangsung,d. Intensitas dampak,e. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak,f. Sifat kumulatif dampak,g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.Industri minyak dan gas bumi termasuk ke dalam jenis rencana kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Akan tetapi untuk dapat mewajibkan dilaksanakannya AMDAL terdapat skala/besaran di mana skala/besaran ini digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan ini perlu untuk dilaksanakan AMDAL atau tidak.Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka untuk Lapangan TMA & TMB yang merupakan lapangan gas yang terletak di offshore harus melengkapi dokumen AMDAL apabila memproduksikan minyak 15000 BOPD dan gas 90 MMSCFD serta memiliki transmisi MIGAS dengan panjang 100 km dengan tekanan 16 bar. Berdasarkan hasil simulasi untuk produksi dari skenario pengembangan semua sumur di Lapangan TMA & TMB nilai kumulatif produksi gas melebihi batas minimum wajib dilaksanakannya AMDAL. Berikut field peak production rate dari masing-masing sumur serta kumulatifnya:Tabel 8.1Oil & Gas Production RateWELLOIL RATE, BOPDGAS RATE, MMSCFD
CUMMULATIF
Sehingga berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk lapangan TMA & TMB diwajibkan untuk dilakukannya analisis mengenai dampak lingkungan terhadap kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, serta menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ( RKL & RPL ).
8.4 Study Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan HidupRencana pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan yang di timbulkan akibat dari rencana usaha dan kegiatan pemboran dan produksi migas. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat kelompok aktivitas :8.4.1 Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup(a) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negative lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek;(b) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya: rehabilitasi lokasi proyek);(c) Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakrsa maupun pihak lain terutama rnasyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut;(d) Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan.8.4.2 Kedalaman rencana pengelolaan Lingkungan hidupMengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip , kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/ penanggulangan/ pengendalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang basic design untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena:(a) Pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/ atau kegiatan (proyek) relatif masih umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomi; sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Keterbatasan data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan ini sudah barang tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan dalam dokumen RKL; (b) Pokok- pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa; Disamping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil dokumen ANDAL. dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan oleh dokumen ANDAL.8.4.3 Rencana pengelolaan lingkungan hidupRencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistimatis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut:(a) Rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak besar dan penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis; dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dimaksud;(b) Rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa, dan dasar kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;(c) Rencana Pengelolaan lingkungan mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah serta kualifikasi yang akan dilatih;(d) Rencana pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL. Aspek- aspek yang perlu diutarakan sehubungan/dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang, unit serta jumlah kualifikasi personalnya.8.4.4 Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini kita kenal seperti teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.(a) Pendekatan teknologiPendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup;(b) Pendekatan sosial ekonomi Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah.c) Pendekatan institusiPendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup.
8.5 Lingkup Rencana Pemantauan Lingkungan HidupPemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tindakan mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional tergantung pada skala keacuhan terhadap masalah yang dihadapi. Disamping skala keacuhan, ada 2 (dua) kata kunci yang membedakan pemantauan dengan pengamatan secara acak atau sesaat, yakni merupakan kegiatan yang bersifat berorientasi pada data sistematik, berulang dan terencana.2.2 Kedalaman rencana pemantauan lingkungan hidupAda beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup, yakni :(a) Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak besar, dan penting. Dengan demikian tidak seluruh komponen lingkungan hidup yang harus dipantau. Hal-hal yang dipandang tidak penting atau tidak relevan tidak perlu di pantau;(b) Keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak besar dan penting yang dinyatakan dalam ANDAL dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL;c) Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinlLai/diuji efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan;(d) Pemantauan lingkungan harus layak secara ekonomi. Walau aspek-aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal-hal yang penting saja (seperti diuraikan pada butir (a) sampai (c ), namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan;(e) Rancangan pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup :1) Jenis data yang dikumpulkan;2) Lokasi pemantauan;3) Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;4) Metode data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);5) Metode analisis data.f) Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud adalah institusi yang bertanggung jawab sebagai penyandang dana pemantauan, pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan. dan pengawas kegiatan pemantauan. Koordinasi dan kerjasama antar institusi ini dipandang penting untuk digalang agar data dan informasi yang diperoleh, dan selanjutnya disebarkan kepada berbagai penggunanya. dapat bersifat tepat guna tepat waktu dan dapat dipercaya.
8.6 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL)Kegiatan pemboran dan produksi yang dilakukan pada lapangan TMA & TMB ini adalah pemboran pada sumur infill. Akan dilakukan pemboran 3 sumur infill dalam lapangan TMA & TMB. Pada tahap kegiatan pemboran pasti akan memberikan dampak kepada lingkungan sekitar maupun pekerja. Untuk mencegah dampak seminimal mungkin yang akan terjadi akibat pemboran dan eksploitasi pengembangan lapangan, perlu disusun rencana pengelolaan lingkungan. Ada beberapa materi dampak yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan pemboran dan eksploitasi tersebut, yaitu :1. Kualitas UdaraPada tahap pemboran dan eksploitasi pengembangan lapangan perlu diperhatikan, kualitas udara di wilayah sekitar agar tidak terkena dampak dari pemboran yang menyebabkan kualitas udara di wilayah sekitar menjadi buruk. Pada tahap pemboran penyebab kemungkinan pembuat polusi udara adalah emisi gas yang dikeluarkan oleh genset, H2S, CO2, CO yang mungkin reales saat pemboran berlangsung. Tolak ukur dampak terhadap kualitas udara ini adalah bersumber dari Permen LH No.13 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi serta PP No.41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengontrol kualitas genset, memasang instalasi peralatan untuk memisahkan H2S dengan pengolahan ulang sulfur sistem claus, dan mentritmen gas CO2 menjadi powder yang nantinya dapat digunakan untuk bahan APPAR,dan melakukan proses pengecekkan secara berkala. Proses pengecekan ini dinamakan Continuos Emission Measurement System (CEMS).
2. Tingkat KebisinganPada proses pemboran pastilah banyak fasilitas yang memiliki kapasitas suara yang menimbulkan kebisingan yang berdampak pada lingkungan sekitar dan para pekerja yang bekerja dilapangan pemboran tersebut. Pada proses pemboran tingkat kebisingan dari genset yang digunakan harus diteliti secara fisika berapa kapasitas suara yang dikeluarkan dan berapa frekuensi yang dihasilkan. Tolak ukur dampak terhadap kualitas udara bersumber dari Kep-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, serta Kep-Menteri Tenaga Kerja No.51 tahun 1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja. Upaya untuk meminimalisasi dampak terhadap para pekerja adalah dengan memberikan hearing protection, a dan mengecek kualitas genset secara berkala agar tidak menimbulkan dampak kebisingan yang cukup besar.3. Tingkat Pencemaran AirPada pemboran pastilah akan menggunakan lumpur pemboran, menurut peraturan menteri ESDM No. 45 tahun 2006 tentang pengelolaan lumpur pemboran, limbah lumpur dan serbuk bor pada kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, lumpur pemboran yang akan digunakan adalah lumpur yang bebahan dasar air akan tetapi ada bahan aditif yang digunakan pada campuran lumpur perlu dilakukan uji TCPL. Menurut Permen LH No. 1 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air. Limbah yang dihasilkan dari lumpur pemboran ini adalah limbah lumpur yang mungkin mengandung unsur-unsur berbahaya dan beracun seperti mercury, limbah lain adalah limbah B3 yang sangat berbahaya. Untuk mengurangi dampak pencemaran air yang disebabkan oleh lumpur pemboran pertama kita perlu membuat tempat penampungan di darat untuk menampung limbah lumpur lalu melakukan pengelolaan pada limbah yang ada pada tempat penampungan barulah setelah itu dilakukan proses pemisahan limbah cair dengan padatan, untuk limbah cair dapat dibuang keperairan jika sudah dilakukan proses terlebih dahulu, untuk limbah padat dapat ditimbun jika kadar hidrocarbon yg terkandung kurang dari atau sama dengan 1%, untuk menanggulangi limbah B3 adalah dapat menggunakan tiga cara, yaitu reuse, recycle, dan recovery.4. KemasyarakatanPembukaan lokasi pemboran baru adalah faktor yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Dampak yang akan timbul terhadap masyarakat yang mungkin besar adalah dampak kesenjangan sosial, dampak fisika, juga berkurangnya produktifitas tangkapan hasil laut para nelayan di pesisir pantai sekitar wilayah pemboran dan produksi gas. Menurut Permen No. 17 tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisa dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Untuk menanggulangi dampak yang akan timbul terhadap masyarakat sekitar haruslah dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan pemboran dan eksploitasi pengembangan, juga mengganti rugi apabila terjadi penurunan produktifitas tangkapan hasil laut nelayan di sekitar wilayah eksploitasi yang di sebabkan oleh kegiatan eksplorasi migas.5. Tenaga KerjaDampak dari pemboran dan produksi juga bisa memberi akibat kepada para pekerja yang bekerja dan berada di sekitar wilayah kerja MIGAS. Dampak yang mungkin terjadi kepada para pekerja kemungkinan adalah sampai timbulnya korban meninggal atau korban luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Tolak ukur yang dapat dilihat adalah ada atau tidaknya korban selama kegiata pemboran dan eksploitasi pengembangan berlangsung. Berdasarkan peraturan UU No. 1 tahun 1970 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningktkan produksi serta produktivitas nasional. Dampak yang akan terjadi dapat dicegah dan diminimanlkan dengan memberikan perlengkapan safety dalam setiap pekerjaan, mengawasi para pekerja dalam melaksanakan SOP (Standard operating procedure), memberikan rambu-rambu disetiap daerah atau wilayah yang memerlukan alat safety.
8.7 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) selama kegiatan pemboran diperlukan untuk mengetahui/memantau keadaan lingkungan sekitar dari dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan pemboran tersebut. Ada beberapa komponen yang dipantau selama kegiatan pemboran tersebut.Komponen-komponen tersebut adalah :1. Kualitas Udara dan Tingkat KebisinganDampak yang ditimbulkan terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan selama pemboran adalah penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Dampak ini akibat dari emisi gas buang, flare dan kebisingan dari peralatan pemboran. Tolak ukurnya adalah Permen LH No.13 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi dan PP No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PerMen LH No.13 tahun 2009, Kep MenLH No.13/MENLH/III/1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan Kep-48/MENLH/11/1999. Metode yang digunakan untuk memantau kualitas udara dan tingkat kebisingan adalah melakukan pengukuran kualitas udara ambient disekitar lokasi kegiatan dan pengukuran emisi gas pada flare stack serta genset, menginvetarisasi aktifitas dan kesiapan petugas SATGAS dan melakukan pendataan kasus penyakit yang terjadi disekitar area kegiatan. Lokasi pemantauan kualitas udara dan tingkat kebisingan dilakukan disekitar area pemboran dan lingkungan sekitar lokasi Lapangan TMA & TMB. Pemantauan terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan dilakukan setiap enam (6) bulan sekali.2. Kualitas Air Pembangunan fasilitas pemboran, kebocoran pipa penyalur gas hingga mencemari perairan sekitar merupakan sumber masalah dari penurunan kualitas air laut dan penurunan keragaman jenis ikan disekitar laut. Tolok ukur dampak tersebut adalah Permen LH No 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Untuk memantau kualitas air dan biota aquatis dilakukan pemantauan dengan metode pengambilan sampel air laut untuk dianalisa, menginventarisasi berbagai jenis ikan yang terdapat pada laut disekitar lokasi kegiatan pemboran dan eksploitasi pengembangan. Periode pemantauan dilakukan setiap enam (6) bulan sekali.3. KemasyarakatanPerubahan-perubahan yang terjadi tentang keadaan sosial masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan merupakan dampak yang dapat timbul akibat kegiatan pemboran. Hasil wawancara (kuisioner) kepada masyarakat sekitar dapat dijadikan tolak ukur mengenai perubahan-perubahan tersebut. Metode yang digunakan untuk memantau keadaan masyarakat adalah dengan melakukan wawancara dan survey yang dilakukan pihak independen. Periode untuk melakukan survey ini adalah tiap satu (1) tahun sekali.4. Tenaga KerjaDampak kegiatan pemboran terhadap para pekerja adalah luka-luka, baik ringan maupun berat atau malah mungkin kecelakaan fatal yang dapat menyebabkan kematian. Metode yang dilakukan untuk pemantauan mengenai para pekerja adalah observasi langsung dilokasi, daily report, monthly report, STOP Card, pengawasan menjalankan Standart Operaing Procedure (SOP) selama proses pemboran. Periode pemantauan adalah setiap saat kegiatan berlangsung.66