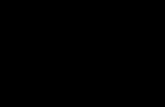Bab VI. ESP
-
Upload
m-auzan-pramadhan -
Category
Documents
-
view
98 -
download
10
description
Transcript of Bab VI. ESP

BAB VI
POMPA ESP
A. Pendahuluan
Pompa ESP(Electric Submersible Pump) yang dikenal sebagai
pompa reda adalah pompa sentrifugal yang bekerja dengan
memanfaatkan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh putaran
impeller terhadap cairan yang akan dialirkan. Cairan tersebut akan
masuk ke tengah impeller (baling-baling), dimana impeller ini akan
melemparkannya dengan kekuatan/tekanan tertentu, sesuai yang
diinginkan. Pompa ESP ini terendam di dalam fluida dan digerakkan
dengan tenaga listrik.
Menurut Centrilift dalam handbook for electrical submersible
pumping system, ESP adalah pompa sentrifugal dengan multistage
(tingkat banyak) yang setiap tingkat dari pompa benam listrik ini
terdiri dari bagian yang bergerak atau impeller dan bagian yang
diam atau diffuser.
Setiap tingkat ESP (stages) terdiri dari satu impeller dan satu
diffuser yang terbuat dari nikel. Sedangkan poros pompa terbuat
dari monel. Impeller dipasang pada poros tegak dari pompa yang
berputar pada bushing. Hubungan antara poros pompa dan poros
protektor dilakukan dengan perantara coupling. Jumlah tingkat
pompa tergantung pada head pengangkatan. Kapasitas pompa selain
VI-1

ditentukan oleh RPM-nya juga dipengaruhi oleh besar diameter
impeller dan hal ini terbatas oleh casing, maka diperlukan tingkat
pompa yang banyak.
ESP ini dapat memproduksikan fluida dari 200 - 100.000 BPD
dan kedalaman yang dapat dicapai adalah 15.000 ft. Ukuran
motornya mencapai 700 horse power dan ini lebih besar dari pompa
manapun. Metoda pengangkatan fluida dengan electrical submersible
pump (ESP) digunakan untuk industri migas, baik untuk sumur
produksi maupun sumur injeksi (secondary recovery) dan untuk saat
ini banyak dipakai terutama pada sumur-sumur produksi di lepas
pantai. Hal ini dikarenakan ESP dianggap sebagai metoda yang
efisien dan efektif untuk sumur yang mempunyai indeks
produktifitas (PI) yang besar, sumur yang dalam, serta sumur-sumur
miring (measured well).
B. Prinsip kerja Pompa ESP
Prinsip kerja pompa ESP ini adalah mengubah kerja poros
menjadi energi mekanik (energi kinetik dan energi tekanan),
sehingga menimbulkan tekanan yang tinggi pada sisi keluarnya
(discharge). Untuk melakukan hal tersebut maka pompa
memerlukan suatu penggerak mula agar energi mekanik yang
diterima diteruskan ke fluida.
Pada dasarnya prinsip kerja Electric Submersible Pump ini
adalah berdasarkan prinsip kerja pompa sentrifugal banyak tingkat
yaitu berdasarkan adanya kenaikkan tekanan di dalam impeller yang
diakibatkan oleh gaya sentrifugal dari impeller yang diputar oleh
VI-2

motor listrik. Pompa sentrifugal terdiri dari bagian yang bergerak
(impeller) dan bagian yang diam (diffuser).
Impeller dipasang pada poros yang dikopel dengan motor
sehingga berputar sesuai dengan putaran poros, sedangkan diffuser
dipasang pada housing dan dibatasi dari pergerakkan (kondisi statis).
Setiap satu pasang impeller dan diffuser disebut dengan tingkat
(stages). Impeller menghasilkan gaya sentrifugal pada fluida (head
kecepatan), dan diffuser yang diam di sekeliling impeller (rumah
impeller) mengubah sebagian head tekanan secara efektif sekaligus,
sehingga pengaruh aliran fluida ke pusat impeller pada tingkat
berikutnya, sehingga head yang dihasilkan menjadi tinggi. Impeller
berfungsi untuk mengalirkan/mengumpan secara sentrifugal fluida
dengan arah horizontal dari poros. Diffuser berfungsi untuk
membalikkan arah fluida dan mengalirkan kembali secara horizontal
ke arah poros dan naik ke impeller di atasnya. Proses ini terulang
beberapa kali sesuai dengan jumlah tingkat (stages) yang dimiliki
pompa tersebut.
Tiap tingkat yang digunakan akan sangat menentukan
besarnya kapasitas yang akan dipindahkan, yang disesuaikan dengan
produksi yang diinginkan. Jika pompa bekerja melebihi
kapasitasnya, maka akan menimbulkan pengikisan pada bagian atas
(up trust), dan sebaliknya jika pompa dioperasikan ke bawah
kapasitanya akan menimbulkan pengikisan pada bagian bawah
(down trust).
VI-3

Gambar 6.1
Prinsip Kerja Pompa ESP
VI-4

Gambar 6.2
Unit Pompa ESP
C. Kelebihan dan Kekurangan Pompa ESP
Kelebihan pompa ESP :
1. Dapat dipergunakan pada sumur-sumur miring.
2. Perencanaan serta pemilihan instalasi sederhana dan fleksibel.
3. Efisiensi pompa praktis konstan selama waktu pemakaian.
VI-5

4. Umur pengoperasian pompa relatif panjang dengan biaya
maintenance yang kecil
Kelemahan pompa ESP :
1. Putaran mesin yang tinggi dalam pompa dapat menimbulkan
masalah terbentuknya emulsi yang relatif sulit untuk
ditanggulangi.
2. Tidak cocok untuk kondisi sumur (well) yang banyak pasir.
3. Efisiensi pompa yang rendah untuk sumur dengan gas oil ratio
yang tinggi.
D. Peralatan Pompa ESP
1. Peralatan Diatas Permukaan Tanah
a. Wellhead
Wellhead atau tubing support merupakan bagian teratas dari
peralatan pompa yang berfungsi untuk menahan tubing dan pompa
di dalam sumur (Gambar 6.3).
VI-6

Gambar 6.3
Wellhead
b. Junction Box
Alat ini berfungsi sebagai tempat melepaskan gas yang ikut
merambat naik melalui kabel ke permukaan danker dalam
switchboard. Biasanya diletakkan 15 feet dari wellhead dan dipasang
kira-kira 2-3 feet di atas permukaan tanah. Sedangkan kabel
switchboard berfungsi sebagai penghubung atau penyambung kabel
di atas permukaan tanah dengan kabel yang ada di dalam tanah.
Fungsi dari junction box antara lain :
1. Sebagai ventilasi terhadap adanya gas yang mungkin bermigrasi
ke permukaan melalui kabel agar terbuang ke atmosfer.
2. Sebagai terminal penyambung kabel dari dalam sumur dengan
kabel dari switchboard.
c. Switchboard
Alat ini merupakan pusat pengendali, memonitor arus motor,
memberikan perlindungan terhadap kelebihan beban yaitu pada saat
terjadinya hubungan singkat jika motor terpaksa bekerja melampaui
kapasitasnya. Dapat juga melakukan perlindungan terhadap
kekurangan beban misalnya gas lock pada pompa atau sumur yang
dioperasikan. Switchboard biasanya mempunyai tegangan antara
400-4.800 volt.
Fungsi utama dari switchboard adalah :
1. Untuk mengontrol kemungkinan terjadinya downhole problem
seperti: overload atau underload current
2. Auto restart setelah underload pada kondisi intermittent well
VI-7

3. Mendeteksi unbalance voltage
Pada switchboard biasanya dilengkapi dengan ammeter chart
yang berfungsi untuk mencatat arus motor versus waktu ketika
motor bekerja.
Gambar 6.4
Switchboard
d. Transformator
Merupakan alat untuk mengubah tegangan listrik, bisa untuk
menaikkan atau menurunkan tegangan. Alat ini terdiri dari core
(inti) yang dikelilingi oleh coil dari lilitan kawat tembaga. Keduanya,
baik core maupun coil direndam dengan minyak trafo sebagai
pendingin dan isolasi. Perubahan tegangan akan sebanding dengan
jumlah lilitan kawatnya. Biasanya tegangan input transformer
diberikan tegangan tinggi agar didapat ampere yang rendah pada
VI-8

jalur transmisi, sehingga tidak dibutuhkan kabel (penghantar) yang
besar. Tegangan input yang tinggi akan diturunkan dengan
menggunakan step-down transformer sampai dengan tegangan yang
dibutuhkan oleh motor.
2. Peralatan Dibawah Permukaan Tanah
a. Electric Motor
Jenis electric submersible pump adalah motor listrik induksi
dua kutub tiga fasa yang diisi dengan minyak pelumas khusus yang
mempunyai tahanan listrik (dielectric strength). Dipasang paling
bawah dari rangkaian dan motor tersebut digerakkan oleh arus
listrik yang dikirim melalui kabel dari permukaan. Motor berfungsi
untuk menggerakkan pompa dengan mengubah tegangan listrik
menjadi tegangan mekanik.
Fungsi dari minyak tersebut adalah sebagai :
1. pelumas
2. tahanan
3. media penghantar panas motor yang ditimbulkan oleh perputaran
rotor ketika motor tersebut sedang bekerja.
Jadi minyak tersebut harus mempunyai spesifikasi tertentu
yang biasanya sudah ditentukan oleh pabrik, yaitu berwarna jernih,
tidak mengandung bahan kimia, dielectric strength tinggi, lubricant
dan tahan panas. Minyak yang diisikan akan mengisi semua celah-
celah yang ada dalam motor, yaitu antara rotor dan stator.
Motor berfungsi sebagai tenaga penggerak pompa (prime
mover), yang mempunyai 2 (dua) bagian pokok, yaitu :
VI-9

1. Rotor (gulungan kabel halus yang berputar)
2. Stator (gulungan kabel halus yang stasioner dan menempel pada
badan motor). Stator menginduksi aliran listrik dan mengubah
menjadi tenaga putaran pada rotor, dengan berputarnya rotor
maka poros (shaft) yang berada ditengahnya akan ikut berputar,
sehingga poros yang saling berhubungan akan ikut berputar pula
(poros pompa, intake dan protector).
Gambar 6.5
VI-10

Electric Motor2)
b. Protector
Protector sering juga disebut dengan seal section (centrilift)
atau Equalizer (ODI). Secara prinsip protector mempunyai 4 (empat)
fungsi utama, yaitu :
1. Untuk melindungi tekanan dalam motor dan tekanan di annulus.
2. Menyekat masuknya fluida sumur ke dalam motor.
3. Tempat duduknya thrust bearing (yang mempunyai bantalan axial
dari jenis marine type) untuk merendam gaya axial yang
ditimbulkan oleh pompa.
4. Memberikan ruang untuk pengembangan dan penyusutan minyak
motor sebagai akibat dari perubahan temperatur dari motor pada
saat bekerja dan saat dimatikan.
Secara umum protector mempunyai 2 (dua) macam tipe, yaitu :
1. Positive Seal atau Modular Type Protector
2. Labyrinth Type Protector
Untuk sumur-sumur miring dengan temperatur > 300oF
disarankan menggunakan protector dari jenis positive seal atau
modular type protector.
VI-11

Gambar 6. 6
Protector2)
c. Intake
Intake dipasang di bawah pompa dengan cara
menyambungkan sumbunya (shaft) memakai coupling. Intake
merupakan saluran masuknya fluida dari dasar sumur ke pompa
menuju permukaan. Untuk jenis-jenis tertentu, intake ada yang
dipasang menjadi satu dengan housing pompa (Intregrated), tetapi
ada juga yang berdiri sendiri.
VI-12

Ada beberapa jenis intake yang sering dipakai yaitu :
1. Standart Intake, dipakai untuk sumur dengan GLR rendah.
Jumlah gas yang masuk pada intake harus kurang dari 10%
sampai dengan 15% dari total volume fluida. Intake mempunyai
lubang untuk masuknya fluida ke pompa, dan dibagian luar
dipasang selubung (screen) yang gunanya untuk menyaring
partikel masuk ke intake sebelum masuk ke dalam pompa.
2. Rotary Gas Separator dapat memisahkan gas sampai dengan 90%
dan biasanya dipasang untuk sumur-sumur dengan GLR tinggi.
Gas Separator jenis ini tidak direkomendasikan untuk dipasang
pada sumur-sumur yang abrasive.
3. Static Gas Separator atau sering disebut reverse gas separator yang
dipakai untuk memisahkan gas hingga 20% dari fluidanya.
Gambar 6.7VI-13

Intake atau Gas Separator3)
d. Pump Unit
Unit pompa merupakan Multistages Centrifugal Pump yang
terdiri dari impeller, diffuser, shaft (tangkai) dan housing (rumah
pompa). Di dalam housing pompa terdapat sejumlah stage, dimana
tiap stage terdiri dari satu impeller dan satu diffuser. Jumlah stage
yang dipasang pada setiap pompa akan dikorelasi langsung dengan
head capacity dari pompa tersebut. Dalam pemasangannya bisa
menggunakan lebih dari satu (tandem) tergantung dari head capacity
yang dibutuhkan untuk menaikkan fluida dari lubang sumur ke
permukaan. Impeller merupakan bagian yang bergerak, sedangkan
diffuser adalah bagian yang diam. Seluruh stage disusun secara
vertikal, dimana masing-masing stage dipasang tegak lurus pada
poros pompa yang berputar pada housing.
Prinsip kerja pompa ini, yaitu fluida yang masuk ke dalam
pompa melalui intake akan diterima oleh stage paling bawah dari
pompa, impeller akan mendorongnya masuk, sebagai akibat proses
centrifugal maka fluida tersebut akan terlempar keluar dan diterima
oleh diffuser.
Oleh diffuser, tenaga kinetis (velocity) fluida akan diubah
menjadi tenaga potensial (tekanan) dan diarahkan ke stage
selanjutnya. Pada proses tersebut fluida memiliki energi yang
semakin besar dibandingkan pada saat masuknya. Kejadian tersebut
terjadi terus menerus sehingga tekanan head pompa berbanding
linier dengan jumlah stages, artinya semakin banyak stage yang
VI-14

dipasangkan, maka semakin besar kemampuan pompa untuk
mengangkat fluida.
Gambar 6.8
Pump Unit3)
e. Electric Cable
Kabel yang dipakai adalah jenis tiga konduktor. Fungsi utama
dari kabel tersebut adalah sebagai media penghantar arus listrik dari
switchboard sampai ke motor di dalam sumur. Kabel harus tahan
terhadap tegangan tinggi, temperatur, tekanan migrasi gas dan tahan
terhadap resapan cairan dari sumur. Untuk itu maka kabel harus
mempunyai isolasi dan sarung yang baik.
VI-15

Bagian dari kabel biasanya terdiri dari konduktor, isolasi, sarung
dan jaket.
Gambar 6.9
Electric Cable3)
Ada dua jenis kabel yang biasa dipakai yaitu : round dan flat
kabel. Pada jenis round kabel dibagian luar sarungnya dibungkus
lagi dengan karet (rubber jacket). Biasanya kabel jenis round ini
memiliki ketahanan yang lebih lama dari pada jenis flat kabel, tetapi
memerlukan ruang penempatan yang lebih besar.
Secara umum ada dua jenis kabel yang biasa dipakai dilapangan,
yaitu :
1. Low Temperatur : disarankan untuk pemasangan pada sumur
dengan temperature maksimum 200°F.
VI-16

2. High Temperatur : disarankan untuk pemasangan pada sumur-sumur dengan temperatur yang cukup tinggi sampai mencapai 400 oF.
f. Check Valve
Check valve biasanya dipasang pada tubing (2-3 joint) di atas
pompa. Bertujuan untuk menjaga fluida tetap berada di atas pompa.
Jika check valve tidak dipasang maka kebocoran fluida dari tubing
(kehilangan fluida) akan melalui pompa yang dapat menyebabkan
aliran balik dari fluida yang naik ke atas, sebab aliran balik (back
flow) tersebut membuat putaran impeller berbalik arah dan dapat
menyebabkan motor terbakar atau rusak.
Jadi umumnya check valve digunakan agar tubing tetap terisi penuh
dengan fluida sewaktu pompa mati dan mencegah supaya fluida
tidak turun ke bawah.
g. Bleeder Valve
Bleeder valve dipasang satu joint di atas check valve,
mempunyai fungsi mencegah minyak keluar pada saat tubing
dicabut. Fluida akan keluar melalui bleeder valve.
h. Centalizer
Berfungsi untuk menjaga kedudukan pompa agar tidak
bergeser atau selalu ditengah-tengah pada saat sumur dioperasikan.
E. Kelakuan Kinerja Pompa (Pump Performance)
VI-17

Kelakuan kerja atau sifat karakteristik kerja pompa
ditentukan berdasarkan test pabrik dengan menggunakan air tawar.
Penyajian secara grafis dari hasil test tersebut dibuatkan dalam
bentuk pump performance curve seperti yang diperlihatkan pada
Gambar 6.10. Kelakuan kinerja pompa ESP ini adalah tentang
head capacity curve, pump efficiency dan brake horse power terhadap
rate . Pump performance curve ini dapat dicari dari katalog atau fihak
distributor jasa pompa ESP. Untuk Gambar 6.10 adalah jenis pompa
ESP IND1300/50HZ/2917 RPM, dimana lebih cocok digunakan
untuk ukuran casing minimal 5,5 in (OD) dengan optimum range
produksi 800 bpd – 1360 bpd.
VI-18

Gambar 6.10
Contoh Pump Performance Curve
1. Head Capacity Curve
Kurva ini menunjukkan hubungan antara total dynamic head
(TDH) dengan laju produksi pada kecepatan (RPM) konstan. Dengan
naiknya total dynamic head (TDH) maka rate akan turun dan begitu
pula sebaliknya. Pompa baru atau yang masih baik daya kerjanya
akan berkarakteristik kerja sepanjang kurva ini. Penyimpangan dari
VI-19

kurva ini dapat dikarenakan oleh rusaknya pompa, besarnya volume
gas yang masuk ke dalam pompa atau disebabkan tubing bocor.
Kurva head suatu ESP akan mendekati laju nol apabila terjadi
shut off head atau head bilamana ESP bekerja dan flowline valve
(klep produksi) ditutup. Dalam mencari shut off head ini, maka
impeller akan berputar pada cairan yang perputarannya didaerah
itu-itu saja dan daya yang diperlukan untuk melawan friksi di cairan
dan bearing akan berubah menjadi panas (karena itu menutup tidak
boleh lebih dari satu menit). Besarnya shut off head tergantung dari
besarnya diameter impeller dan kecepatannya, dimana untuk pompa
bertingkat banyak (multistages) ditentukan dengan menggunakan
persamaan :
H = shut off head fluida yang dipompakan (ft)
D = diameter impeller (inch)
N = kecepatan impeller (RPM)
S = jumlah stage (tingkat)
Shut off head yang sebenarnya tergantung dari aliran fluida
dalam pompa dan dari kemungkinan adanya peralatan yang bocor.
Perbedaan antara rumus ini dengan keadaan sebenarnya pada kerja
pompa bisa mencapai 20%. Bentuk kurva head tergantung dari lebar
impeller, jumlah sudu-sudu impeller, bentuk dan friksi pada pompa
itu sendiri. Head capacity suatu pompa digunakan untuk menghitung
jumlah stage pompa dengan rationya terhadap total dynamic head
(TDH). Pompa dengan head yang lebih curam lebih disukai karena
VI-20

bisa lebih toleran terhadap kesalahan data-data sumur (API, GOR,
SG, dan lain-lainnya).
Dari Gambar 6.10 untuk target produksi sebesar 1000 bpd
akan didapatkan head capacity sebesar 15 ft.
2. Brake Horse Power Curve
Kurva brake horse power pada Gambar 6.11 menunjukkan
brake horse power (BHP) input yang diperlukan oleh setiap stage
pompa. Kurva ini mula-mula naik sedikit dengan naiknya laju
produksi, kemudian turun. Hal ini dikarenakan efek laju produksi
lebih besar dari turunnya head dan pada laju produksi besar
turunnya head yang lebih berpengaruh, karena bentuknya lebih
curam. Test pabrik dilakukan dengan air tawar yang viskositasnya 1
cp (32 SSU) dan SG=1.
Berdasarkan Gambar 6.10 untuk target produksi sebesar 1000
bpd akan didapatkan brake horse power (BHP) sebesar 0,18 HP/stage.
3. Pump Efficiency Curve
Efisiensi pompa ESP bukanlah efisiensi volume pompanya,
melainkan ratio dari output horse power (HP) pompa dibagi dengan
input brake horse power.
VI-21

qt = laju produksi total fluida (BPFD)
TDH = total dynamic head (ft)
P1 = input brake (HP)
SG = specific gravity cairan (SG air = 1)
Efisiensi pompa ini sebenarnya adalah gabungan antara gaya
hidrolis, volumetris dan mekanis. Seperti terlihat pada Gambar 6.10,
efisiensi naik dari nol pada laju produksi nol ke maksimum lalu
turun kembali pada laju produksi maksimum.
Di sebelah kiri daerah maksimum ini akan terlihat, kehilangan
karena kebocoran, friksi pada bearing (leher) dikarenakan
terjadinya down thrust (gerak impeller menggesek ke bawah) dan
friksi antara impeller dan fluida produksi terjadi.
Di sebelah kanan daerah maksimum tersebut akan terjadi
friksi dalam fluida itu sendiri, dinding impeller, dan juga upthrust
(gerak impeller menggesek keatas). Untuk menerangkan adanya
upthrust dan downthrust dapat dilihat pada Gambar 6.11. Pada
gambar tersebut, impeller akan menekan ke atas (upthrust) pada laju
produksi tinggi (rpm tinggi) dan akan menekan ke bawah
(downthrust) pada laju produksi rendah (rpm rendah). Pada daerah
effisiensi tertinggi, impeller seakan-akan melayang bebas (floating).
ESP didesain agar bekerja pada daerah mendekati effisiensi
maksimal untuk mengurangi kerusakan bearing dan washer (tatakan)
pompa akibat terjadinya upthrust atau downthrust. Pada prakteknya
di lapangan ternyata upthrust lebih merusak daripada downthrust,
karena washer di bagian atas lebih kecil luas bidang kontaknya
VI-22

daripada di bagian bawah. Walaupun demikian, perlu dipertahankan
agar pompa tetap bekerja pada effisiensi maksimum, agar
pemakaian pompa dapat bertahan lama. Harga effisiensi maksimum
ini biasanya sekitar 55% sampai dengan 75%.
GAMBAR 6.11
POSISI UP THRUST DAN DOWN THRUST PADA POMPA10)
G. Data Perencanaan Pompa ESP
VI-23

No Nama Data Simbol Satuan Nilai
1. Laju produksi Q bfpd
2. Water cut WC fraksi
3. Gas Oil Ratio GOR scf/stb
4. Specific gravity oil SGo -
5. Specific gravity water SGw -
6. Specific gravity gas SGg -
7. Bottom hole temperature T °F
8. Top perforation TP ft
9. Bottom perforation BP ft
10. Tekanan statik sumur Ps psia
11. Tekanan alir dasar sumur Pwf psia
12. Tekanan kepala sumur Pwh psia
13. Ukuran casing Dc in (ID)
14. Ukuran tubing Dt in (OD)
15. Faktor kompresibilitas gas Z -
H. Langkah Kerja Perencanaan Pompa ESP
VI-24

H.1. Menentukan Kemampuan Berproduksi Sumur
1. Menentukan laju produksi maksimal (Qmax) dengan persamaan
Vogel.
, (bfpd)
2. Menentukan laju produksi optimal (Qopt)
Qopt = 0,8 x Qmax , (bfpd)
H.2. Menentukan Gradient Fluida (GF)
1. Oil phase specific gravity = (1 – WC) x SGo
2. Water phase specific gravity = WC x SGw
3. Specific gravity fluid (SGf)
SGf = (1 – WC)SGo + WC x SGw
4. GF = 0,433 x SGf , (psi/ft)
H.3. Menentukan Pump Intake Pressure (PIP)
1. Mid Perforation (MP)
MP = (TP + BP)/2 , (ft)
2. Pump setting depth (PSD)
PSD = TP – 100, (ft)
3. Tekanan aliran dasar sumur pada kondisi PIP (Pwf*)
, (psia)
4. PIP = Pwf* - (MP – PSD)GF , (psia)
H.4. Menentukan kebutuhan gas separator
1. Kelarutan gas (Rs) dengan persamaan Standing
VI-25

a. °API = (141,5/SGo) – 131,5
b. Yg = 0,00091 x T – 0,0125 x °API
c. , (scf/stb)
2. Faktor volume formasi minyak (Bo)
a. F = Rs x (SGg/SGo)0,5 + 1,25 x T
b. Bo = 0,972 + 0,000147 x F1,175 , (bbl/stb)
3. Faktor formasi gas (Bg)
Bg = 5,04 (Z x T)/PIP, (bbl/Mscf)
4. Menentukan laju produksi minyak pada PIP (Qo*)
Qo* = (1 – WC) x Qopt , (bopd)
5. Menentukan laju produksi gas pada PIP (Qg*)
Qg* = Qo* x GOR , (scfd)
6. Menentukan laju produksi gas terlarut (Qgrs)
Qgrs = Qo* x Rs , (scfd)
7. Menentukan laju produksi gas bebas (Qgf)
Qgf = Qg* - Qgrs , (scfd)
8. Menentukan volume minyak pada PIP (Vo)
Vo = Qo* x Bo , (bpd)
9. Menentukan volume air pada PIP (Vw)
Vw = Wc x Qopt x Bw , (bpd)
10. Menentukan volume gas bebas pada PIP (Vg)
Vg = Qgf x Bg x 1000 , (bpd)
11.Menentukan volume total fluida pada PIP (Vt)
Vt = Vo + Vw + Vg , (bpd)
12. Hitung persen gas bebas (% Vg)
VI-26

% Vg = (Vg/Vt) x 100 %
Jika : Vg > 10 % butuh gas separator
Jika : Vg < 10 % tidak butuh gas separator
H.5. Menentukan kebutuhan advance gas handler (AGH)
1. Hitung volume gas bebas yang tidak dapat dipisahkan oleh gas
separator (Vg*)
Vg* = 0,1 x Vg
2. Hitung % Vg* = (Vg*/Vt) x 100 %
Jika : % Vg* > 20 % , butuh advanced gas handler (AGH)
H.6. Composite specivic gravity pada PIP (SGf*)
1. Hitung volume gas bebas dalam tubing (Vgt)
Vgt = Qgrs + (Vg*/Bg) x 1000 , (scfd)
2. Hitung GOR dalam tubing (GOR*)
GOR* = Vgt/Qo* , (scf/bbl)
3. Hitung massa minyak (Mo)
Mo = Qo* x SGo x 62,4 x 5,6146 , (lb/day)
4. Hitung massa air (Mw)
Mw = WC x Qopt x SGw x 62,4 x 5,6146 , (lb/day)
5. Hitung massa gas (Mg)
Mg = GOR* x Qo* x SGg x 0,0752 , (lb/day)
6. Hitung Total Mass Produced Fluid (TMPF)
TMPF = Mo + Mw + Mg , (lb/day)
7. Hitung : SGf* = (TMPF/Vt)/(62,4 x 5,6146)
VI-27

H.7. Menentukan Total Dynamic Head (TDH)
1. Hitung Fluid Over Pump (FOP)
FOP = (PIP/SGf*) x 2,31 , (ft)
2. Hitung Vertical Lift (HD)
HD = PSD – FOP , (ft)
3. Hitung Friction Loss (FL)
, (/1000 ft)
4. Hitung head friction loss (HF)
HF = PSD x (FL /1000) , (ft)
5. Hitung Tubing Head (HT)
HT = 2,31 (Pwh/SGf*) , (ft)
6. Hitung : TDH = HD + HF + HT , (ft)
H.8. Pemilihan Jenis Pompa ESP
1. Tentukan jenis pompa ESP dari catalog yang sesuai dengan range
Qopt dan ukuran casing yang digunakan.
2. Dari jenis pump performance curve tentukan :
a. Head capacity per stage (HC) , ft/stage
b. Brake Horse power per stage (BHP), HP/stage
3. Tentukan jumlah stage yang dibutuhkan (S)
S = TDH/HC , (stage)
4. Maximum head in operating range (MHOR)
MPOR = HC x S , (ft)
VI-28

5. Hitung Maximum pressure in operating range (MPOR)
MPOR = 0,433 x MHOR , (psia)
H.9. Perencanaan Motor
1. Hitung Brake Horse Power Motor (HPmotor)
HPmotor = S x BHP x SGf* , (HP)
2. Pemilihan Jenis Motor (Gunakan Lampiran A)
a. Tentukan seri jenis motor yang sesuai dengan HPmotor
b. Tegangan listrik motor (Vmotor) , (HP)
c. Arus listrik (I) , (ampere)
d. OD motor , (in)
3. Uji Kesesuaian Motor
a. Menentukan kecepatan aliran di annulus motor (FV)
, (ft/sec)
b. Jika FV > 1, jenis motor sesuai
c. Jika FV < 1, jenis motor tidak sesuai dan diganti
H.10. Perencanaan Kabel
1. Tentukan jenis kabel untuk arus listrik yang digunakan (I) dimana
voltage drop dibawah 30 volt.
2. Tentukan kehilangan tegangan kabel per 1000 ft (ΔV/1000) dari
Lampiran B untuk arus listrik (I)
3. Hitung total kehilangan tegangan kabel (ΔVK)
ΔVK = (TP – 50) x (ΔV/1000) , (Volt)
VI-29

H.11. Perencanaan Transformator dan Switchboard
1. Tentukan tegangan untuk motor dan kabel (Vtot)
Vtot = Vmotor + ΔVK , (Volt)
2. Hitung : KVA = 1,73 x Vtot x I/1000 , (KVA)
3. Tentukan jenis transformator dan switchboard dari Lampiran C
4. Uji transformator & switchboard
a. Hitung tegangan start (VS)
VS = 0,35 x Vmotor , (volt)
b. Kehilangan tegangan selama start (ΔVS)
ΔVS = 3 x ΔVK , (volt)
c. Total tegangan pada waktu start (VStot)
VStot = VS + ΔVS
Jika : Vtot > VStot , bekerja baik
Jika : Vtot < VStot , tidak bekerja
VI-30

VI-31