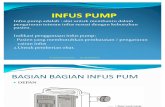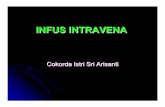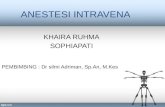BAB II TINJAUAN PUSTAKA Intravena / Infus · TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengetahuan Perawat Tentang...
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA Intravena / Infus · TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengetahuan Perawat Tentang...
-
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengetahuan Perawat Tentang Pemasangan Terapi
Intravena / Infus
Perawat profesional adalah perawat yang bertanggung
jawab dan berwewenang memberikan pelayanan keperawatan
secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga
kesehatan lain sesuai dengan kewenanganya (Depkes RI,
2002). Menurut PerMenKes No HK.02.02/Menkes/148/1/2010,
perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat
baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Menurut PP No. 32 th 1996 tentang
tenaga kesehatan, perawat adalah seseorang yang telah lulus
dan mendapatkan ijazah dari pendidikan kesehatan yang diakui
pemerintah. Definisi perawat menurut ICN (international council
of nursing) tahun 1965, perawat adalah seseorang yang telah
menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat
serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan
pelayanan keperawatan yan bertanggung jawab untuk
meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan
penderita sakit. Dari beberapa pengertian diatas pendidikan dan
tingkat pengetahuan sangat penting untuk mencetak perawat
-
11
yang profesional. Tingkat pengetahuan yang tinggi diperlukan
untuk profesi keperawatan untuk dapat memberikan pelayanan
keperawatan secara mandiri dengan baik dan dapat mampu
berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain.
Pengetahuan didapat dari proses pembelajaran baik secara
formal maupun informal. Pembelajaran formal seperti Program
Diploma 3 Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan
(PSIK), S2, maupun S3. Pembelajaran informal didapat dari
pendidikan informal, seperti pembelajaran klinik, pelatihan
khusus, seminar dan di dalam dunia kerja itu sendiri. Melalui
pembelajaran tersebut baik formal maupun informal perawat
seharusnya mempunyai dasar yang kuat dari segi pengetahuan
sehingga dapat mampu bekerja berdampingan dan sepadan
dengan tenaga kesehatan lainnya. Dengan pengetahuan yang
didapat tersebut perawat dituntut untuk dapat melakukan segala
bentuk tindakan keperawatan berdasar pada pengetahuan yang
didapatkan, termasuk dalam tindakan tindakan invasif seperti
pemasangan terapi intravena. Dalam pemasangan terapi
intravena perawat dituntut tidak hanya terampil, tetapi juga
harus mampu mengetahui, memahami, mengaplikasikan,
menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi dari setiap tahap-
tahap tindakan terapi intravena.
-
12
Menurut Notoatmodjo (2003), yang dimaksud dengan
pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh
individu dimana pengetahuan ini akan menimbulkan suatu atau
pemahaman terhadap suatu objek. Pengindraan terjadi melalui
panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran,
penciuman, raba, dan rasa. Sebagian besar domain yang
sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.
Bloom dalam Hurlock (1999), menyatakan bahwa
pengetahuan yang tercakup dalam kognitif mempunyai enam
aspek, yaitu :
a. Tahu (know) ialah mengingat suatu materi yang yang telah
dipelajari sebelumnya.
b. Memahami (comprehension) ialah sebagai suatu
kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek
yang diketahui dan dapat menginterprretasikan materi
secara benar
c. Aplikasi (aplication) ialah mampu menggunakan rumus-
rumus, metode, dan lain sebaginya dalam situasi yang lain.
d. Analisis (analysis) suatu kemampuan untuk menjabarkan
materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen,
tetati masih didalam suatu struktur organisasi sikap tersebut
dan masih ada kaitannya satu dengan yang lain.
-
13
e. Sintesis (syntesis) ialah menunjukkan kepada suatu
kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam
suatu bentuk keseluruhan yang baru
f. Evaluasi (evaluation) ialah berkaitan dengan kemampuan
untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pengetahuan
perawat tentang terapi intravena dapat dijabarkan dari
bagaimana seorang perawat mengetahui, memahami,
mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi dari setiap
tahap-tahap tindakan terapi intravena. Dapat dijabarkan sebagai
berikut :
2.1.1. Mengetahui.
Perawat dituntut untuk dapat mengingat materi baik
berupa urutan prosedur, persiapan alat, jenis komplikasi,
dan lain-lain tentang terapi intravena yang yang telah
dipelajari sebelumnya di dalam proses pendidikan formal
maupun informal yang telah ditempuh.
2.1.2. Memahami
Perawat harus mampu untuk menjelaskan secara
benar tentang tentang tujuan pemberian terapi intravena,
memahami tipe dari cairan yang akan digunakan,
memahami pemilihan akses dan cara pemberian terapi
intravena, dan memahami perawatan terapi intravena,
-
14
sehingga dapat menginterprretasikan materi secara
benar. Dapat dijabarkan sebagai berikut:
2.1.2.1. Memahami tujuan terapi intravena
Memahami tujuan pemberian terapi intravena:
1. Untuk menyediakan air, elektrolit, dan nutrient untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Untuk menggantikan air dan memperbaiki
kekurangan elektrolit.
3. Untuk menyediakan suatu medium untuk pemberian
obat secara intravena (Smeltzer, 2002).
2.1.2.2. Memahami tipe dari cairan
Dalam Perry & Potter (2005), Cairan intravena dibagi
dalam beberapa kategori seperti cairan isotonik,
hipotonik, dan hipertonik. Larutan elektrolit dianggap
isotonik jika kandungan elektrolit totalnya (anion
ditambah kation) kira-kira 310 mEq/L. Larutan elektrolit
dianggap hipotonik jika kandungan elektrolit totalnya
kurang dari 250 mEq/L. Larutan elektrolit dianggap hi
pertonik jika kandungan elektrolit totalnya melebihi 375
mEq/L. Perawat juga harus mempertimbangkan
osmolalitas suatu larutan, tetap mengingat bahwa
osmolalitas plasma adalah kira-kira 300 mOsm/L (SI :
300 mmol/L).
-
15
1. Cairan isotonik
Cairan yang diklasifikasikan isotonik mempunyai
osmolalitas total yang mendekati cairan ekstraseluler
dan tidak menyebabkan sel darah merah mengkerut
atau membengkak. Komposisi dari cairan isotonik
meningkatkan volume cairan ekstraseluler. Satu liter
cairan isotonik meningkatkan cairan ekstraseluler
sebesar 1 liter. Meskipun demikian cairan ini
meningkatkan plasma hanya sebesar ¼ liter karena
cairan isotonic merupakan cairan kristaloid dan
berdifusi dengan cepat kedalam kompartemen cairan
ekstraseluler. Untuk alas an yang sama, 3 liter cairan
isotonik dibutuhkan untuk menggantikan 1 liter darah
yang hilang (Smeltzer, 2002).
Larutan dekstrosa 5% dalam air mempunyai
osmolalitas serum sebesar 252 mOsm/L. Sekali
diberikan, glukosa dapat langsung cepat
dimetabolisme dan larutan yang pada awalnya
merupakan isotonis kemudian berubah menjadi
cairan hipotonis, sepertiga ekstraseluler, dan 2/3
intraseluler. Karena itu, dekstrosa 5% dalam air
terutama dipergunakan untuk mensuplai air dan
untuk memperbaiki osmolalitas serum yang
-
16
meningkat. Satu liter dekstrosa 5% dalam air
memberikan kurang dari 200 kkal dan merupakan
sumber kecil kalori untuk kebutuhan sehari-hari
tubuh (Smeltzer, 2002).
Normal saline (0,9 % Natrium klorida)
mempunyai osmolalitas total sebesar 308 mOsm/L.
Karena osmolalitasnya secara keseluruhan ditunjang
oleh elektrolit, larutan ini tetap dalam kompartemen
ekstraseluler. Untuk alasan ini, normal salin sering
digunakan untuk mengatasi kekurangan volume
ekstraseluler. Meskipun disebut sebagai “normal”,
cairan normal salin ini hanya mengandung natrium
dan klorida dan tidak merangsang CES secara nyata
(Smeltzer, 2002).
Larutan Ringer mengandung kalium dan kalsium
selain natrium klorida. Larutan Ringer Laktat juga
mengandung prekusor bikarbonat (Smeltzer, 2002).
2. Cairan hipotonik
Salah satu tujuan dari larutan hipotonik adalah
untuk menggantikan cairan seluler, karena larutan ini
bersifat hipotonis dibandingkan dengan plasma.
Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan air bebas
untuk ekskresi sampah tubuh. Pada saat tertentu,
-
17
larutan natrium hipotonik digunakan untuk mengatasi
hipernatremia dan kondisi hiperosmolar yang lain.
Larutan salin berkekuatan menengah (natrium
klorida 0,45%) sering digunakan. Infus larutan
hipotonik yang berlebihan dapat menyebabkan
terjadinya deplesi cairan intravascular, penurunan
tekanan darah, edema seluler, dan kerusakan sel.
Larutan ini menghasilkan tekanan osmotik yang
kurang dari cairan ekstraseluler (Smeltzer, 2002).
3. Cairan hipertonik
Dekstrosa 5% ditambahkan pada normal salin
atau larutan ringer, osmolalitas totalnya melebihi
osmolalitas ekstraseluler. Meskipun demikian,
dekstrosa dengan cepat dimetabolisme dan hanya
tersisa larutan isotonik. Oleh karena itu, efek
kompartemen intraseluler sifatnya hanya sementara.
Sama halnya dengan cairan dekstrosa yang
ditambahkan larutan elektrolit multiple hipotonik.
Dekstrosa 40% dalam air diberikan untuk membantu
memenuhi kebutuhan kalori. Larutan ini sangat
hipertonis dan harus diberikan pada vena sentral
(Smeltzer, 2002).
-
18
Larutan salin juga tersedia dalam konsentrasi
osmolar yang lebih tinggi dari ekstraseluler. Larutan
ini menarik cairan dari intraseluler ke ekstraseluler
dan menyebabkan sel-sel mengkerut. Jika diberikan
dengan cepat atau dalam jumlah yang besar, dapat
menyebabkan kelebihan volume ekstraseluler,
kelebihan cairan sirkulatori dan dehidrasi. Larutan
hipertonik menghasilkan tekanan osmotik lebih tinggi
dari cairan ekstraseluler (Smeltzer, 2002).
2.1.2.3. Memahami pemilihan akses dan cara
pemberian terapi intravena
1. Akses pemberian terapi intra vena
Banyak tempat yang dapat digunakan untuk
terapi intravena. Vena di daerah ekstermitas dipilih
sebagai lokasi perifer dan pada mulanya merupakan
tempat satu-satunya yang digunakan oleh perawat.
Terdapat beberapa jalur penusukan yang biasa
dilakukan oleh perawat yaitu : lengan, punggung
tangan dan punggung kaki. Penggunaan vena
didaerah kaki biasanya digunakan pada pasien anak-
anak, tetapi pada orang dewasa juga dapat
digunakan pada kasus-kasus tertentu seperti resiko
-
19
tromboemboli. Vena-vena yang biasanya dihindari
adalah vena dibawah infiltrasi vena sebelumnya atau
dibawah area flebitis, vena yang sklerotik atau
bertrombus, lengan dengan pirai arteriovena atau
vistula, lengan yang mengalami edema, infeksi,
bekuan darah, atau kerusakan kulit, lengan yang
mengalami mastektomi.
Idealnya, kedua lengan dan tangan harus di
inspeksi dengan cermat sebelum melakukan pungsi
vena. Lokasi di pilih dimana tidak menggangu
mobilisasi fisik. Lokasi yang dipilih adalah yang
paling distal dari lengan dan tangan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan
tempat penusukan vena :
1. Kondisi vena
2. Jenis cairan atau obat yang akan diberikan
3. Lama terapi
4. Usia pasien
5. Riwayat kesehatan dan status kesehatan pasien
sekarang
6. Ketrampilan tenaga kesehatan (Smeltzer, 2002).
-
20
Vena-vena yang dapat dijadikan sebagai tempat
penusukan :
1. Jalur akses Peripherally Inserted Central
Catheter (PICC or PIC line) dan Midline Catheter
(MLC)
Adalah terapi yang menggunakan kateter
sentral yang terpasang secara perifer (PICC)
atau katerer midline (MLC). PICC digunakan
pada pasien yang membutuhkan rawat jalan
dalam jangka waktu menengah sampai jangka
panjang. Tempat pemasangan PICC pada vena
fosa antekubital, diatas atau dibawah vena
basilica, sefalika, atau aksilaris. Vena basilica
merupakan vena yang lazim digunakan.
Sedangkan MLC digunakan pada pasien yang
tidak mempunyai akses perifer tetapi
membutuhkan antibiotika IV, darah dan nutrisi
parenteral. Tampat pemasangan MLC dilakukan
selebar 2-3 jari diatas fosa antekubital atau
selebar 1 jari dibawah fosa antekubital kedalam
vena sefalika, basilica atau kubital mediana.
2. Lengan : basilic vein (vena basilika), cephalic
vein (vena sefalika), median cubital vein (vena
-
21
kubital mediana), median vein of fore arm (vena
antebrakialis mediana), radial vein (vena
radialis), vena sefalika asesorius,
3. Punggung tangan : superficial dorsal veins (vena
metakarpal), dorsal vein arch (vena dorsalis),
vena digitalis
4. Punggung kaki : great saphenous vein, dorsal
plexus, dorsal arch (Perry & Potter, 2005).
2. Cara pemberian terapi intravena / Pungsi Vena
Kemampuan untuk memilih vena yang akan
digunakan untuk memberikan cairan dan obat
merupakan ketrampilan keperawatan yang
diharapkan. Termasuk dalam memilih tempat pungsi
yang sesuai dan jenis kanula, dan mahir/terampil
dalam teknik penusukan vena.
Vena harus dikaji dengan palpasi dan inspeksi.
Vena harus teraba kuat, elastic, besar, bulat, tidak
keras, datar, dan tidak bergelombang. Pedoman
umum untuk memilih kanul sebagai berikut :
a. Panjang kanul 1,8 cm – 3 cm
b. Kateter dengan diameter yang kecil untuk
memenuhi ruang minimal dalam vena
-
22
c. Ukuran 20-22 untuk kebanyakan cairan IV,
ukuran yang lebih besar digunakan pada larutan
yang mengiritasi atau kental. Ukuran 18 biasanya
digunakan untuk transfusi darah (Smeltzer,
2002). Ukuran kateter nomor 16 biasanya
digunakan untuk bedah mayor atau trauma,
ukuran kateter nomor 18 untuk produk darah,
ukuran kateter nomor 20-22 biasanya digunakan
pada kebanyakan pasien namun ukuran kateter
nomor 22 terutama digunakan pada anak-anak
dan orang tua, dan ukuran kateter nomor 24
biasanya digunakan pada pasien pediatrik dan
neonatus (Rocca, 1998).
2.1.2.4. Memahami Perawatan terapi intravena.
Mempertahankan terapi intravena yang sudah
terpasang merupakan tanggung jawab keperawatan
yang menuntut pengetahuan tentang larutan yang
sedang diberikan dan prinsip-prinsip aliran. Selain itu,
pasien harus dikaji dengan teliti dari komplikasi local
maupun sistemik (Smeltzer, 2002). Perawat setelah
selesai memasang harus selalu mengontrol dan
-
23
merawat infus yang sudah terpasang. Yang harus
diperhatikan oleh perawat adalah :
1. Mengganti cairan jika sudah habis
2. Mendampingi aktivitas pasien agar tidak terganggu
dengan pemasangan infus (Perry & Potter, 2005).
3. Menjaga agar tetap steril
Penggunaan cairan antiseptik yang benar dibutuhkan
agar tetap menjaga terapi intravena/infus yang
terpasang maupun saat memasang infus tetap dalam
keadaan steril.
a. Cairan Anti septik
Antiseptik terutama digunakan untuk mencegah
dan mengobati infeksi pada luka. Sediaan antiseptik
dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka
iris, luka lecet dan luka bakar ringan. Penerapan
antiseptik pada luka mungkin perlu diikuti tindakan
lain seperti pembersihan dan penutupan luka dengan
pembalut agar tetap bersih dan terjaga.
b. Jenis-jenis antiseptik
Ada banyak sekali agen kimia yang dapat
digunakan sebagai antiseptik. Beberapa antiseptik
yang umum digunakan adalah etakridin laktat
(rivanol), alkohol, yodium, dan hidrogen peroksida.
-
24
Sebagian besar produk antiseptik di pasar
mengandung satu atau lebih campuran zat tersebut.
1. Etakridin laktat (rivanol)
Etakridin laktat adalah senyawa organik
berkristal kuning orange yang berbau
menyengat. Penggunaannya sebagai
antiseptik dalam larutan 0,1% lebih dikenal
dengan merk dagang rivanol. Tindakan
bakteriostatik rivanol dilakukan dengan
mengganggu proses vital pada asam nukleat sel
mikroba. Efektivitas rivanol cenderung lebih kuat
pada bakteri gram positif daripada gram negatif.
Meskipun fungsi antiseptiknya tidak sekuat jenis
lain, rivanol memiliki keunggulan tidak mengiritasi
jaringan, sehingga banyak digunakan untuk
mengompres luka, bisul, atau borok bernanah.
2. Alkohol
Alkohol adalah antiseptik yang kuat. Alkohol
membunuh kuman dengan cara menggumpalkan
protein dalam selnya. Kuman dari jenis bakteri,
jamur, protozoa dan virus dapat terbunuh oleh
alkohol. Alkohol (yang biasanya dicampur
yodium) sangat umum digunakan untuk
-
25
mensterilkan kulit sebelum dan sesudah
pemberian suntikan dan tindakan medis lain.
Alkohol kurang cocok untuk diterapkan pada luka
terbuka karena menimbulkan rasa terbakar.
Jenis alkohol yang digunakan sebagai
antiseptik adalah etanol (60-90%), propanol (60-
70%) dan isopropanol (70-80%) atau campuran
dari ketiganya. Metil alkohol (metanol) tidak boleh
digunakan sebagai antiseptik karena dalam
kadar rendah pun dapat menyebabkan gangguan
saraf dan masalah penglihatan.
3. Yodium
Yodium atau iodine biasanya digunakan
dalam larutan beralkohol (disebut yodium tinktur)
untuk sterilisasi kulit sebelum dan sesudah
tindakan medis. Larutan ini tidak lagi
direkomendasikan untuk mendisinfeksi luka
ringan karena mendorong pembentukan jaringan
parut dan menambah waktu penyembuhan.
Generasi baru yang disebut iodine
povidone (iodophore), sebuah polimer larut air
yang mengandung sekitar 10% yodium aktif, jauh
lebih ditoleransi kulit, tidak memperlambat
-
26
penyembuhan luka, dan meninggalkan deposit
yodium aktif yang dapat menciptakan efek
berkelanjutan.
Keuntungan antiseptik berbasis yodium
adalah cakupan luas aktivitas antimikrobanya.
Yodium membunuh semua patogen utama
berikut spora-sporanya, yang sulit diatasi oleh
disinfektan dan antiseptik lain. Beberapa orang
alergi terhadap yodium. Tanda alergi
yodium adalah ruam kulit kemerahan, panas,
bengkak dan terasa gatal.
4. Hidrogen peroksida
Larutan hidrogen peroksida 6% digunakan
untuk membersihkan luka dan borok. Larutan 3%
lebih umum digunakan untuk pertolongan
pertama luka gores atau iris ringan di rumah.
Hidrogen peroksida sangat efektif memberantas
jenis kuman anaerob yang tidak membutuhkan
oksigen. Namun, oksidasi kuat yang
ditimbulkannya merangsang pembentukan parut
dan menambah waktu penyembuhan. (Majalah
kesehatan.com, 2011).
-
27
2.1.3. Mengaplikasi
Perawat diharap mampu untuk memahami dan
mengaplikasi Standar Operasional Prosedur Tindakan
Terapi Intravena sesuai dengan standard yang berlaku
di rumah sakit.
Ketampilan perawat dalam pemasangan terapi dapat
diukur dari bagaimana perawat tersebut melakukan
pemasangan infus sesuai dengan SOP yang berlaku.
Ketampilan tersebut meliputi ketrampilan dalam tahap
pre interaksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap
terminasi. Kemampuan untuk memilih vena yang akan
digunakan untuk memberikan cairan dan obat
merupakan ketrampilan keperawatan yang diharapkan.
Termasuk dalam memilih tempat pungsi yang sesuai
dan jenis kanula, dan mahir/terampil dalam teknik
penusukan vena.
1. Pengertian Terapi Intravena
Terapi intra vena adalah terapi yang bertujuan
untuk mensuplai cairan ketika pasien tidak mampu
mendapatkan cairan lewat mulut, untuk menyediakan
kebutuhan garam untuk menjaga keseimbangan
cairan, untuk menyediakan kebutuhan gula
(glukosa/dekstrosa) sebagai bahan bakar untuk
-
28
metabolisme, dan untuk menyediakan beberapa
jenis vitamin yang mudah larut melalui intravena
(Kozier, 1983).
2. Tujuan Terapi
Pemberian obat melalui terapi intravena memiliki
keuntungan dimana dalam situasi darurat ketika
obat-obat yang dapat bekerja cepat bias diberikan
melalui intravena. Sehingga efektifitas kerja obat bisa
langsung ke tujuan pengobatan (Perry & Potter,
2005). Sedangkan menurut Smeltzer 2002, tujuan
terapi intravena adalah untuk menyediakan air,
elektrolit, dan nutrient untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, untuk menggantikan air dan memperbaiki
kekurangan elektrolit, dan untuk menyediakan suatu
medium untuk pemberian obat secara intravena.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terapi
Intravena
Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk jenis
larutan yang akan diberikan, lamanya terapi
intravena yang diharapkan, keadaan umum pasien.
Pertimbangan memilih tempat penusukan vena
sebaiknya melihat kondisi vena, jenis cairan atau
obat yang digunakan, lama terapi, usia/ukuran
-
29
pasien, riwayat kesehatan/status kesehatan pasien
sekarang, dan ketrampilan dan pengetahuan tenaga
kesehatan (smeltzer, 2002).
4. Tahap-Tahap Terapi Intravena
Tahap-tahap terapi intravena yang digunakan
diambil dari buku Fundamental Of Nursing Potter and
Perry dan mengambil SOP dari Rumah Sakit Citarum
Semarang, yang nanti akan menjadi bahan
perbandingan tentang prosedur terapi intravena.
-
30
2.1.4. Memahami, mengevaluasi, menganalisis dan
mengidentifikasi komplikasi terapi intravena
Terapi intravena menimbulkan kecenderungan
menimbulkan berbagai bahaya seperti trombosis dan
emboli kateter. Selain itu juga dapat menyebabkan
komplikasi lokal maupun sistemik. Komplikasi sistemik
seperti kelebihan beban cairan, emboli udara,
septicemia, infeksi, lebih jarang terjadi tetapi seringkali
lebih serius dibanding komplikasi lokal seperti infiltrasi,
flebitis, tromboflebitis, dan hematoma.
1. Komplikasi terapi intravena
Komplikasi menurut smeltzer (2002) adalah :
A. Komplikasi lokal
Komplikasi lokal yang mungkin terjadi adalah:
a. Infeksi lokal
Infeksi lokal yang berhubungan dengan
terapi intravena dikarenakan terjadinya
kontaminasi pada saat persiapan,
pemasangan, pemberian obat intravena,
penggantian balutan, atau penggantian cairan
infus. Tanda dan gejala meliputi nyeri,
sumbatan aliran darah, bengkak, merah,
-
31
pengerasan dan panas pada tempat
penusukan.
b. Hematoma
Hematoma adalah darah yang
mengumpul dalam jaringan atau dibawah kulit
yang biasanya diakibatkan oleh pecahnya
pembuluh darah pada tempat penusukan
terapi intravena. Ditandai dengan perubahan
warna kulit, bengkak, dan nyeri.
c. Infiltrasi
Infiltrasi adalah masuknya cairan kedalam
jaringan sekitar (bukan pembuluh vena) yang
biasanya terjadi karena jarum melewati
pembuluh vena. Ditandai dengan edema,
ketidaknyamanan, dan rasa dingin didaerah
infiltrasi, tidak terdapat aliran darah dan
penurunan kecepatan aliran yang signifikan.
Jika larutan bersifat iritatif maka dapat
menyebabkan kerusakan jaringan. Tindakan
perawatannya dengan menghentikan terapi
dan mengganti jalur penusukan, kompres
dengan air hangat, dan meninggikan
ekstermitas agar cepat diserap oleh tubuh.
-
32
d. Flebitis
Flebitis adalah suatu reaksi lokal yang
berupa peradangan pada pembuluh darah
vena di tunika intima yang ditandai dengan
panas, nyeri, bengkak, dan kemerahan
(Rubor, Dolor, Kalor, Tumor, Fungsi laesa)
dengan atau tanpa pus pada daerah
penusukan yang timbul 3 x 24 jam atau
kurang dari waktu tersebut bila infus masih
terpasang (Depkes RI, 2001).
e. Tromboflebitis
Tromboflebitis adalah adanya
peradangan pada pembuluh darah dan
adanya bekuan darah. Biasanya merupakan
gejala sisa dari kejadian flebitis. Ditandai
dengan nyeri yang terlokalisasi, kemerahan,
rasa hangat, bengkak, aliran melambat,
sianosis pada ekstermitas, imobilisasi
ekstermitas karena bengkak, demam,
malaise, dan lekositosis. Tindakan perawatan
dengan menghentikan terapi intravena,
memberikan kompres hangat, meninggikan
ekstermitas, mengganti jalur penusukan.
-
33
f. Bekuan pada jarum
Bekuan ini desebabkan karena selang IV
yang tertekuk, kecepatan aliran yang terlalu
lambat, kantong IV yang kosong/habis, atau
tidak memberikan aliran setelah pemberian
obat atau larutan intermiten. Tanda dan
gejalanya adalah penurunan kecepatan aliran
dan darah kembali ke selang IV.
Jika terjadi bekuan, jalur IV harus
dihentikan, perawat harus segera mengganti
infus yang lama dengan yang baru. Perawat
tidak boleh mengirigasi atau melakukan
pemijatan pada selang, tidak mengembalikan
aliran dengan meningkatkan kecepatan atau
menggantungkan cairan lebih tinggi, dan
tidak boleh melakukan aspirasi bekuan dari
kanul.
g. Ekstravasasi
Ekstravasasi adalah keluarnya cairan dari
pembuluh darah vena ke jaringan sekitar.
Ditandai dengan nyeri, rasa terbakar, kaku,
teraba dingin, aliran melambat / terhenti, dan
merembes/balutan basah.
-
34
h. Trombosis
Thrombosis adalah adanya trauma pada
sel endothelial dinding vena yang
menyebabkan menempelnya fibrin dan sel
darah merah pada dinding tersebut yang
menyebabkan penyumbatan aliran darah
(smeltzer, 2002).
B. Komplikasi sistemik
a. Kelebihan beban cairan
Menyebabkan peningkatan tekanan darah
dan tekanan vena sentral, dipsnea berat, dan
sianosis. Tanda dan gejala tambahan
termasuk batuk dan kelopak mata yang
membengkak, berat badan meningkat, sakit
kepala. Penyebabnya kemungkinan karena
infus yang terlalu cepat, penyakit jantung,
hati, dan ginjal.
b. Emboli
Emboli adalah penyumbatan secara tiba-
tiba dari pembuluh darah vena oleh benda
asing seperti bekuan darah, maupun udara
ke aliran darah. Dapat ditandai dengan
dipsnea, sianosis, hipotensi, nadi lemah
-
35
cepat, hilangnya kesadaran, nyeri dada,
bahu, dan punggung bawah
c. Pulmonary edema
Dapat terjadi karena kelebihan cairan
yang diakibatkan oleh terlalu cepatnya cairan
infus yang menyebabkan tekanan ke vena
sentral meningkat dan menyebabkan edema
paru.
d. Septisemia
Septisemia adalah infeksi sistemik yang
disebabkan oleh adanya mikroorganisme
yang masuk kedalam tubuh. Ditandai dengan
kenaikan suhu tubuh mendadak, sakit
punggung, sakit kepala, peningkatan nadi
(takikardi), peningkatan frekuensi nafas,
mual, muntah, diare, demam, menggigil,
tremor, malaise umum, kolaps vascular (jika
parah), hipotensi.
-
36
2.2. Infeksi Flebitis
2.2.1. Infeksi Nosokomial
Infeksi Flebitis merupakan satu dari infeksi
nosokomial. Menurut Bennet & Brachman (dalam Gould
D & Brooker C, 2003), infeksi yang di dapat di rumah
sakit (infeksi nosokomial) adalah infeksi yang tidak ada
atau berinkubasi pada saat masuk rumah sakit. Dengan
kata lain, Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang
terjadi di rumah sakit atau infeksi oleh kuman yang
didapat selama berada di rumah sakit. Infeksi
nosokomial tidak saja menyangkut penderita tetapi juga
yang kontak dengan rumah sakit termasuk staf rumah
sakit, sukarelawan, pengunjung dan pengantar.
Suatu Infeksi dikatakan di dapat rumah sakit apabila:
1. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit
tidak didapatkan tanda-tanda klinik dari infeksi
tersebut.
2. Pada waktu penderita dirawat di rumah sakit tidak
sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut.
3. Tanda-tanda klinik tersesut baru timbul sekurang-
kurangnya setelah 3 x 24 jam sejak dimulainya
perawatan.
-
37
4. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa dari infeksi
sebelumnya.
5. Bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah terdapat
tanda-tanda infeksi dan dapat dibuktikan infeksi
tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah
sakit yang sama pada waktu lalu, serta belum pernah
dilaporkan sebagai infeksi nosokomial. (Parhusip,
2005)
2.2.2. Flebitis
2.2.2.1. Pengertian flebitis
Flebitis adalah suatu reaksi lokal yang berupa
peradangan pada pembuluh darah vena di tunika
intima yang ditandai dengan panas, nyeri,
bengkak, dan kemerahan (Rubor, Dolor, Kalor,
Tumor, Fungsi laesa) dengan atau tanpa pus
pada daerah penusukan yang timbul 3 x 24 jam
atau kurang dari waktu tersebut bila infus masih
terpasang (Depkes RI, 2001).
Flebitis di definisikan sebagai inflamasi vena
yang disebabkan baik oleh iritasi kimia maupun
mekanik. Hal ini dikarakteristikan dengan adanya
daerah yang memerah dan hangat di sekitar
-
38
daerah penusukan atau sepanjang vena, nyeri
atau rasa lunak di daerah penusukan atau
sepanjang vena, dan pembengkakan. Insiden
flebitis meningkat sesuai dengan lamanya
pemasangan jalur intravena, komposisi cairan,
atau obat yang diinfuskan (terutama pH dan
tonisitas), ukuran dan tempat kanula
dimasukkan, pemasangan jalur IV yang tidak
sesuai, dan masuknya mikroorganisme pada
saat penusukan.
Flebitis dapat dicegah dengan menggunakan
teknik aseptik selama pemasangan,
menggunakan ukuran kateter dan jarum yang
sesuai untuk vena, mempertimbangkan
komposisi cairan dan medikasi ketika memilih
daerah penusukan, mengobservasi tempat
penusukan akan adanya komplikasi apapun
setiap jam, dan menempatkan kateter atau jarum
dengan baik (Smeltzer, 2002).
-
39
2.2.2.2. Penyebab Flebitis
a. Flebitis Kimia
1. pH dan osmolaritas cairan
pH dan osmolaritas cairan infus yang
ekstrem selalu diikuti risiko flebitis tinggi.
pH larutan dekstrosa berkisar antara 3 –
5, di mana keasaman diperlukan untuk
mencegah karamelisasi dekstrosa selama
proses sterilisasi autoklaf, jadi larutan
yang mengandung glukosa, asam amino
dan lipid yang digunakan dalam nutrisi
parenteral bersifat lebih flebitogenik
dibandingkan normal saline. Obat suntik
yang bisa menyebabkan peradangan
vena yang hebat, antara lain kalium
klorida, vancomycin, amphotrecin B,
cephalosporins, diazepam, midazolam
dan banyak obat khemoterapi. Larutan
infus dengan osmolaritas > 900 mOsm/L
harus diberikan melalui vena sentral.
2. Obat-obatan
Mikropartikel yang terbentuk bila
partikel obat tidak larut sempurna selama
-
40
pencampuran juga merupakan faktor
kontribusi terhadap flebitis.
3. Kateter yang terbuat dari silikon dan
poliuretan kurang bersifat iritasi dibanding
politetrafluoroetilen (teflon) karena
permukaan lebih halus, lebih
thermoplastik dan lentur. Risiko tertinggi
untuk flebitis dimiliki kateter yang terbuat
dari polivinil klorida atau polietilen.
b. Flebitis Mekanis
Flebitis mekanis dikaitkan dengan
penempatan kanula. Kanula yang
dimasukkan ada daerah lekukan sering
menghasilkan flebitis mekanis. Ukuran kanula
harus dipilih sesuai dengan ukuran vena dan
difiksasi dengan baik (Smeltzer, 2002).
c. Flebitis Bakterial
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap
flebitis bakteri meliputi :
1. Teknik pencucian tangan yang buruk.
2. Kegagalan memeriksa peralatan yang
rusak atau tidak steril.
3. Teknik aseptik tidak baik
-
41
4. Teknik pemasangan kanula yang buruk
5. Kanula dipasang terlalu lama
6. Tempat suntik jarang diinspeksi visual
(Smeltzer, 2002).
2.2.2.3. Tanda dan Gejala Flebitis
Tanda dan gejala flebitis adalah :
a. Rubor (Kemerah-merahan)
Kulit kemerahan timbul dengan cepat di
atas vena.
b. Dolor (Nyeri)
Nyeri yang terlokalisasi.
c. Kalor (Panas)
panas tubuh cukup tinggi, pada saat
diraba terasa hangat
d. Tumor (Bengkak)
Pembengkakan / oedema dengan kulit
pucat, panas, dan keras.
e. Fungsi laesa (Perubahan fungsi).
-
42
2.3. Kerangka Konseptual
Bagan 1.1 Kerangka Konseptual
2.4. Hipotesis
Ha: Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan
perawat tentang pemasangan terapi intravena dengan angka
kejadian flebitis.
H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan
perawat tentang pemasangan terapi intravena dengan angka
kejadian flebitis.
Pemberian Terapi Intravena
Pengetahuan Perawat
Terjadi flebitis
Tidak terjadi flebitis