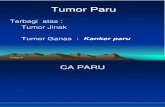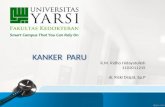BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Kanker Paru · PDF file2.2 Klasifikasi dan Epidemiologi...
-
Upload
vuongthien -
Category
Documents
-
view
237 -
download
2
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Kanker Paru · PDF file2.2 Klasifikasi dan Epidemiologi...

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Kanker Paru
Kanker paru merupakan kanker yang onsetnya dimulai dari paru-paru dimana
terjadi pertumbuhan sel abnormal yang sangat cepat dan tidak terkendali.
Pertumbuhan sel yang tidak normal tersebut dipicu oleh kerusakan DNA diantaranya
adanya delesi pada bagian DNA, inaktivasi gen supresor tumor, aktivasi proto-
onkogen menjadi onkogen, tidak terjadinya apoptosis dan aktivitas dari enzim
telomerase.(Yu, dkk, 2014; Yolder dkk,2010)
2.2 Klasifikasi dan Epidemiologi Kanker Paru
Di Indonesia, kanker paru termasuk dalam 3 besar kanker terbanyak bersama
dengan kanker payudara dan kanker serviks. Kanker paru merupakan kanker dengan
prevalensi terbanyak yang diderita oleh pria. Berdasarkan data dari RS Kanker
Dharmais Jakarta, prevalensi dari kanker paru dari tahun 2010 hingga 2013 selalu
meningkat, dimana pada tahun 2010 terdapat 117 kasus dengan 38 kematian, tahun
2011 terdapat 163 kasus dengan 39 kematian, tahun 2012 terdapat 165 kasus dengan
62 kematian, dan pada tahun 2013 terdapat 173 kasus dengan 65 jumlah kematian.
(Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan RS Kanker Dharmais, 2010-2013).
Berdasarkan data RISKESDAS pada tahun 2013, terdapat 347.792 orang yang
menderita kanker dengan 8.729 orang merupakan penduduk Bali dan kebanyakan
penderita berumur diatas 75 tahun, akan tetapi masih belum ada data spesifik
mengenai kanker paru baik di Bali.(Pusdatin Kemenkes RI,2015) Berdasarkan data
Register pada Poli Paru RSUP Sanglah pada tahun 2014 dan 2015, Kanker paru
merupakan salah satu kasus penyakit paru terbanyak dengan total kasus 583 pada
tahun 2014 dan 968 pada tahun 2015
Secara umum, kanker paru dibagi kedalam dua jenis yaitu NSCLC dan SCLC.
Perbedaan diantara keduanya adalah SCLC memiliki agresivitas yang lebih tinggi
dibandingkan dengan NSCLC. Namun secara epidemiologi, NSCLC lebih sering

dijumpai, yakni sekitar 85% dari total kasus kanker paru. Menurut klasifikasi WHO,
kanker paru terdiri dari 4 tipe major sel yaitu SCLC, NSCLC yang termasuk
adenokarsinoma, SCC dan LCC. Secara histologi, tumor dapat terjadi baik berupa
tipe tunggal maupun campuran. (WHO,2012)
SCC merupakan jenis terbanyak dari NSCLC yang terdiagnosis. Morfologi SCC
menyerupai tumor ekstrapulmonal yang nampak seperti sarang tumor yang
terinflitrasi yang tidak memiliki jembatan intraselular. Keratin seringkali nampak
pada morfologi jaringan SCC. Terjadinya SCC ini diduga dipengaruhi oleh merokok,
seiring menurunnya jumlah perokok, maka SCC tergantikan oleh adenokarsinoma
sebagai jenis NSCLC yang paling sering terdiagnosis. Adenokarsinoma paling sering
mengenai wanita berumur di bawah 60 tahun. Adenokarsinoma memiliki kelenjar,
struktur papilari, pola branchioalveolar, musin sel atau pola solid yang terdiferensiasi
buruk. Adenokarsinoma memiliki tipe signet ring, clear cell and mucinous serta fetal
adenocarcinoma. BAC merupakan subtype dari adenokarsinoma yang tumbuh
bersama alveolus tanpa menginvasi dan dapat dilihat sebagai masa tunggal
multinoduler difus pada X-ray, dan “ground glass” opacity pada CT-
Scan.(Harrison,2012)
SCLC merupakan tumor neuroendokrin yang cenderung muncul sebagai masa
sentral dengan pertumbuhan endobrakial dan sangat berhubungan dengan merokok.
SCLC memiliki sel dengan sitoplasma yang sedikit, nucleus hiperkromatik kecil
dengan pola kromatin seperti “Salt and Pepper” serta nucleolus yang prominen.
SCLC sering memproduksi hormone spesifik seperti ACTH, AVP, ANF dan GRP
yang berhubungan dengan distinctive paraneoplastic syndrome.(Harrison,2012)
LCC cenderung muncul pada bagian perifer dan nampak sebagai karsinoma yang
berdeferensiasi buruk dari komposisi paru tanpa adanya bukti squamous, diferensiasi
grandular atau SCLC pada mikroskop cahaya. Tumor ini terdiri dari lapisan sel
malignant besar yang berkaitan dengan nekrosis. Varian dari LCC termasuk basaloid
karsinoma yang muncul sebagai lesi endobrakial yang menyerupai tumor
neuroendokrin stadium tinggi dan lymphoepithelioma-like carcinoma yang berkaitan
dengan infeksi EBV. (Harrison, 2012)

Gambar 2.1. Klasifikasi kanker paru berdasarkan morfologi jaringannya
(Harrison,2012)
2.3 Staging Kanker Paru
Penderajatan untuk KPKBSK ditentukan menurut International System For
Lung Cancer, berdasarkan sistem TNM. Pengertian T adalah tumor yang
dikategorikan atas Tx, To s/d T4, N untuk keterlibatan kelenjar getah bening(KGB)
yang dikategorikan atas Nx, No s/d N3,sedangkan M adalah menunjukkan ada atau
tidaknya metastasis jauh.(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia,2003)
Tabel 2.1. Penderajatan kanker paru berdasarkan sistem TNM
Derajat TNM
Occult Ca Tx N0 M0
0 Tis N0 M0
IA T1 N0 M0
IB T2 N0 M0
IIA T1 N0 M0

IIB T2 N1 M0
IIIA T3 N1 M0
T3 N2 M0
IIIB Sebarang T N3 M0
T4 Sebarang N M0
IV T4 Sebarang N Sebarang M
Keterangan :
T :Tumor Primer
To :Tidak ada bukti ada tumor primer. Tumor primer sulit dinilai, atau tumor primer
terbukti dari penemuan sel tumor ganas pada sekret bronkopulmoner tetapi tidak
tampak secara radilogis atau bronkoskopik.
Tx :Tumor primer sulit dinilai, atau tumor primer terbukti dari penemuan sel tumor
ganas pada sekret bronkopulmoner tetapi tidak tampak secara radilogis atau
bronkoskopik.
Tis :Karsinoma in situ
T1 :Tumor dengan garis tengah terbesar tidak melebihi 3 cm, dikelilingi oleh jaringan
paru atau pleura viseral dan secara bronkoskopik invasi tidak lebih proksimal dari
bronkus lobus (belum sampai ke bronkus lobus (belum sampai ke bronkus utama).
Tumor superfisial sebarang ukuran dengan komponen invasif terbatas pada dinding
bronkus yang meluas ke proksimal bronkus utama
T2 :Setiap tumor dengan ukuran atau perluasan sebagai berikut :
- Garis tengah terbesar lebih dari 3 cm
- Mengenai bronkus utama sejauh 2 cm atau lebih distal dari karina
mengenai pleura viseral
- Berhubungan dengan atelektasis atau pneumonitis obstruktif yang meluas ke
daerah hilus, tetapi belum mengenai seluruh paru.
T3 :Tumor sebarang ukuran, dengan perluasan langsung pada dinding dada (termasuk
tumor sulkus superior), diafragma, pleura mediastinum atau tumor dalam bronkus

utama yang jaraknya kurang dari 2 cm sebelah distal karina atau tumor yang
berhubungan dengan atelektasis atau pneumositis seluruh paru
T4 :Tumor sebarang ukuran yang mengenai mediastinum atau jantung, pembuluh
besar, trakea, esofagus, korpus vertebra, karina, tumor yang disertai dengan efusi
pleura ganas atau satelittumor nodul ipsilateral pada lobus yang sama dengan tumor
primer.
N : Metastasis KGB regional
Nx : KGB tak dapat dinilai
No: Tak terbukti keterlibatan KGB
N1:Metastasis pada kelenjar getah bening peribronkial dan/atau hilus ipsilateral,
termasuk perluasan tumor secara langsung
N2:Metastasis pada kelenjar getah bening mediatinum ipsilateral dan/atau KGB
subkarina
N3:Metastasis pada hilus atau mediastinum kontralateral atau KGB skalenus/
supraklavila ipsilateral /kontralateral
M Metastasis jauh.
Mx :Metastasis tak dapat dinilai
Mo :Tak ditemukan metastasis jauh
M1:Ditemukan metastasis jauh. “Metastastic tumor nodule”(s) ipsilateral di luar
lobus tumor primer dianggap sebagai M1
2.4 Faktor Risiko Terjadinya Kanker Paru
2.4.1 Jenis Kelamin
Jenis kelamin diduga berkaitan dengan kejadian kanker paru. Hal ini dapat
dilihat dari data epidemiologi bahwa pasien kanker paru pria lebih banyak dari wanita
begitu juga dengan jumlah kematiannya. Laki-laki memiliki tingkat metilasi pada gen
Ras Association domain Family 1A (RASSF1A) yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perempuan yaitu 7,5% dibandingkan dengan 17,9% dengan nilai
P<0,01.(Vaissiere dkk, 2015) dimana gen RASSF1A merupakan salah satu tumor
supresor yang mengkode protein menyerupai RAS efektor protein, sehingga apabila

terjadi metilasi yang menginduksi inaktivasi dari ekspresi gen tersebut maka akan
menimbulkan hilangnya inhibisi pada Cyclin D1 sehingga cell cycle arrest tidak
terjadi. Hal ini tentunya menyebabkan sel membelah secara tidak terkendali dan
menjadi kanker. (Song dkk, 2008) Tingginya kejadian kanker paru pada laki-laki juga
dapat dikaitkan dengan kebiasaan merokok laki-laki yang lebih besar dibandingkan
perempuan yaitu 63,38% dibandingkan dengan 31,62% dengan nilai P<0,01.(Gupta
dkk,2014)
2.4.2 Umur
Menurut data epidemiologi, kebanyakan penderita kanker paru merupakan
orang yang sudah berumur. Kecenderungan data memperlihatkan bahwa semakin
tuanya umur maka akan semakin tinggi risikonya untuk terkena kanker. Sebuah
penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2014 menyebutkan bahwa adanya
kecenderungan pola merokok sesuai umur turut mempengaruhi terjadinya kanker
paru. Populasi yang berumur 50-75 tahun, 77%nya merupakan perokok aktif
(p<0,0003) sedangkan pada orang yang berumur diatas 75 tahun, hanya 23% yang
merupakan perokok. (Gupta dkk,2014). Populasi yang berumur 45-49 tahun
menunjukkan inaktivasi gen MTHFR paling tinggi dibandingkan kelompok umur
lainnya yaitu 18,5% (P<0,01) yang dikaitkan erat dengan kebiasaan merokok.
Golongan umur 50-64 tahun memiliki inaktivasi gen tertinggi pada gen CDH1 dan
GSTP1 sedangkan golongan umur >70tahun memiliki kecenderungan inaktivasi gen
GTSP1 dan RASSF1A yang paling tinggi diantara kelompok umur lainnya. Hal ini
menyebabkan golongan umur diatas 45 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk
menderita kanker paru dibandingkan populasi yang berumur dibawah 45 tahun.
(Vaissere 2015) Sebuah penelitian insiden kanker di Korea juga membuktikan bahwa
kecenderungan kanker paru terjadi pada pria dan wanita diatas 65 tahun.(Kyu dkk,
2011)

2.1.3 Berat Badan
2.4.3 Riwayat Merokok
Merokok memiliki kaitan yang erat dengan kejadian kanker paru. Rokok
memiliki 73 jenis zat pemicu kanker dan 16 diantaranya diakui sebagai karsinogen.
Karsinogen yang erat kaitannya dengan kanker paru adalah NKK, NNN dan PAH.
NNK dengan dosis 1,8mg/kg dapat menginduksi kanker paru pada mencit, estimasi
dosis terendah dari NNK pada perokok dengan lama merokok 40 tahun adalah sekitar
1,1mg/kg sehingga risiko kanker paru akan semakin tinggi apabila lama merokok
semakin panjang.(Yuan dkk,2015) Perokok memiliki kadar metilasi yang tinggi
terhadap gen SULF-2 (P<0,05) yaitu sebuah gen yang memproduksi enzim
ekstraseluler yang mengkatalis reaksi hidrolisis 6-O-Sulfo dari polisakarida heparan
sulfat. Heparan sulfat proteoglikan tersebar pada membran sel dan ECM dan
berfungsi sebagai koreseptor untuk berbagai macam faktor pertumbuhan dan sitokin.
Inaktivasi dari SULF-2 mencegah pelepasan gugus sulfat dari ikatan dengan IFN
yang akan meningkatkan transkripsi dari IFN sehingga menghasilkan metaplasia sel
mucus yang diakibatkan dari disregulasi cell death yang terlibat dalam signaling IFN
Gambar 2.2. Grafik hubungan antara umur dan kejadian kanker paru. (A) kejadian pada
laki-laki (B) pada perempuan. Dapat dilihat bahwa kejadian kanker paru memiliki
hubungan yang berbanding lurus dengan umur pasien. Dapat dilihat juga bahwa kejadian
tertinggi terdapat pada kelompok umur diatas 65 tahun yaitu puncaknya pada umur 80-84
tahun untuk pria dan diatas 85 tahun untuk wanita.(Kyu dkk, 2011)

yang akan menyebabkan terjadinya kanker paru. (Bruse dkk, 2014; Tessema
dkk,2012)
Merokok juga mempengaruhi metilasi gen MTHFR, tingkat metilasi gen
MTHFR pada orang yang merokok lebih tinggi secara signifikan yaitu 72,1%
(P<0,01) dibandingkan dengan mantan perokok (63,8%) dan yang tidak merokok
(31,6%). MTHFR merupakan produk gen yang memainkan peran sebagai methionine
pool serta memastikan bahwa kadar homosistein dalam tubuh tidak mencapai level
toksik. Enzim MTHFR mengkatalis sintesis metionin yang dibutuhkan dalam
metabolism S-adenosilmetionin yang memiliki peran penting pada proses metilasi
DNA dan ekspresinya dapat mengubah metilasi DNA yang bersangkutan, Inaktivasi
MTHFR menyebabkan penurunan signifikan 5-metilsitosin yang akan menginduksi
hipometilasi DNA yang nantinya akan mengganggu program cell death yang memicu
perkembangan tumor.(Vassiere dkk,2015)
Gambar 2.3. Pengaruh rokok terhadap
metilasi gen MTHFR
Peningkatan metilasi MTHFR terjadi
akibat kandungan benzopyrene pada
rokok mempengaruhi metilasi CpG sites
yaitu ditemukan bahwa dari 6 CpG
MTHFR, setidaknya 1-4nya mengalami
metilasi yang lebih besar secara
signifikan pada perokok. Kandungan
lain dalam rokok juga dapat
memindahkan cis-acting element yang
menghalangi penyebaran metilasi dari
pusat metilasi, serta mengganggu pola
modifikasi histon dari CpG.(Vassiere
dkk,2015)

Merokok juga memiliki kaitan yang erat dengan kejadian PPOK dimana PPOK juga
berkaitan dengan kejadian kanker paru. Sebuah penelitian telah mengidentifikasi 5
gen yang terganggu akibat merokok yang berpengeruh terhadap kanker paru yang di
induksi PPOK, gen tersebut adalah WIPF1 yang meregulasi formasi sinapsis
imunologikal dan aktivasi sel T, BCL2I yang meregulasi tumor supresor p53, SGK1
yang kenaikan regulasinya mempengaruhi pertumbuhan tumor, ZNF397 yang
memiliki peran dalam formasi sentromer dan transkripsi gen serta CLK1 yang
merupakan faktor pemotongan DNA alternatif yang di induksi oleh keadaan
hipoksia.(Faner dkk,2014). Pengaruh merokok terhadap kejadian kanker paru juga
dapat dibuktikan melalui efek dari berhenti merokok. Orang yang berhenti merokok
terbukti mengalami perubahan hasil skrining dari tahun sebelumnya disaat ia masih
merokok. Orang yang sebelumnya terskrining positif berisiko besar terhadap kanker
paru akan menjadi negative atau setidaknya risikonya berkurang saat ia berhenti
merokok setidaknya satu tahun P<0,05. (Tamemmagi dkk,2014; Slatore dkk,2014)
2.4.4 Berat Badan
Berat badan memiliki kaitan dengan berbagai jenis kanker. Indeks Masa Tubuh
(IMT) yang tinggi merupakan salah satu predisposisi dari berbagai jenis kanker, akan
tetapi kanker paru memiliki kecenderungan yang berbeda dengan kanker lainnya.
Kenaikan IMT justru memberikan efek negative terhadap risiko kanker paru.
.(Bashkaran dkk,2014)
Gambar 2.4. Grafik perbandingan IMT dan 95%CI terhadap kejadian kanker
paru. Dapat dilihat bahwa kejadian kanker paru meningkat pada IMT dibawah
25kg/m2 baik pada pria maupun wanita, yang berarti bahwa pasien kanker paru
cenderung memiliki IMT yang kecil.(Song dkk,2014)

IMT yang rendah pada pasien kanker paru diduga juga terkait dengan kecenderungan
orang dengan IMT rendah untuk merokok. Perokok pria cenderung memiliki IMT
lebih rendah dibandingkan dengan mantan perokok maupun bukan perokok
(P<0,001) sedangkan pada wanita tidak terdapat perbedaan yang begitu signifikan
antara IMT mantan perokok dibandingkan dengan bukan perokok, akan tetapi
perokok wanita memiliki kecenderungan memiliki IMT lebih rendah (<25,57kg/m2)
dibandingkan dengan dua grup pembandingnya (>26,8kg/m2) dengan nilai P<0,013
.(Gupta dkk,2014; Song dkk,2014).
2.4.5 Riwayat Penyakit Paru Lainnya
Salah satu penyakit paru yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker
paru adalah PPOK yang merupakan penyakit fatal dan progressive pada paru ditandai
dengan hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak sepenuhnya reversible.
Hambatan aliran ini bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi paru
terhadap partikel beracun. Baik PPOK maupun kanker paru sama-sama memiliki
kaitan erat dengan merokok seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab merokok
diatas(Durham&Adcock, 2015; Faner et,al,2014.) PPOK juga diyakini sebagai faktor
independent yang menyebabkan terjadinya kanker paru. RNOS yang merupakan
pencetus kanker akibat inflamasi kadarnya sangat meningkat pada PPOK, selain itu
fungsi mitokondria pada pasien PPOK sangat menurun sehingga sel endotel paru
tidak mampu untuk berapoptosis. Sitokin terutama IFNγ dan M-CSF yang dihasilkan
Tabel 2. Perbandingan IMT pada perokok pria dan wanita. Dapat dilihat pada
perokok aktif, rata-rata IMTnya lebih rendah dibandingkan dengan mantan
perokok maupun yang tidak pernah merokok (Song dkk,2014)

dari inflamasi PPOK dapat memberikan sinyal untuk diferensiasi dan pembelahan sel
serta dapat memanggil sel imun lain untuk berinfiltrasi dan membentuk tumor.
Inflamasi kronik juga mengakibatkan adanya overekspresi dari NFkB yang dapat
menginhibisi gen supresi tumor p53. Jalur PI3K yang berperan penting pada
proliferasi dan supresi apoptosis sel juga teraktivasi pada penderita PPOK, selain itu
peningkatan aktivasi protein Wnt dan B-catenin pada PPOK memiliki asosiasi dengan
pertumbuhan kanker yang cepat pada percobaan mencit. (Durham&Adcock, 2015;
Wauters dkk,2014)
2.4.6 Riwayat Penyakit Ekstrapulmonal
Komorbiditas pada pasien kanker paru memiliki efek positif terhadap
perkembangan kanker dan efek negative terhadap kemampuan survival pasien.
Komorbiditas juga dapat menutupi gejala kanker paru sehingga menyebabkan
diagnosis kanker yang tertunda. Komorbiditas juga mempengaruhi proses
penyembuhan kanker paru dikarenakan kebanyakan komorbiditas menjadi salah satu
kontra indikasi dari tindakan operasi. Beberapa penyakit ekstrapulmonal yang dapat
memicu terjadinya kanker paru sekaligus memperparah perjalan kanker paru adalah
kondisi-kondisi yang menurunkan sistem imunitas seperti infeksi HIV, penggunaan
obat imunosupresan pada pasien autoimun maupun pasien dengan riwayat
transplantasi organ. Adapun penyakit metabolik seperti diabetes juga dapat
meningkatkan risiko terjadinya kanker paru.(Lachina, Green & Jakobsen, 2014)
Berdasarkan ICD 10, komorbiditas penyerta dari kanker paru dibagi menjadi kelas
yaitu kelas pertama seperti infark miokard, gagal jantung kongestif, penyakit vascular
perifer, PPOK, penyakit liver dan diabetes. Sedangkan kelompok 2 adalah hemiplegi,
penyakit ginjal, diabetes dengan kerusakan organ, tumor lain di luar paru, leukemia
dan limfoma. Kelompok 3 adalah penyakit liver moderat atau parah dan kelompok 4
adalah metatstasis dari tumor solid atau AIDS. Komorbiditas terbanyak selain PPOK
adalah metastasis tumor solid 24,8%, diabetes tanpa komplikasi 10,3% dan penyakit
vascular perifer 8,7%.(Marcus dkk, 2014) Penelitian Kong dkk pada tahun 2014
menyatakan bahwa pasien dengan penyakit terkait defisiensi vitamin D memiliki

risiko yang lebih besar untuk terkena kanker paru. Vitamin D memiliki fungsi sebagai
anti proliferative, anti angiogenik, anti metastasis dan efek pro apoptosis terhadap sel.
Orang yang kekurangan vitamin D memiliki risiko 5 kali lebih besar untuk menderita
kanker paru dengan OR=5,8 dan 95%CI=2,84-11,84.(Kong dkk,2014)
2.4.7 Pekerjaan
Berbagai pekerjaan memiliki risikonya masing-masing. Beberapa pekerjaan
memiliki asosiasi dengan meningkatkan risiko seseorang untuk menderita kanker
paru dikarenakan lingkungan yang dapat mengganggu fungsi paru. Eksposur dalam
pekerjaan yang paling sering adalah eksposur dari debu serbuk kayu. Pekerjaan yang
terpapar dengan debu serbuk kayu ini diantaranya tukang gergaji, tukang kayu,
pengrajin kayu dan pekerja furnitur. Paparan dari debu kayu diyakini sebagai salah
satu faktor risiko kanker paru terbukti dalam penelitian pasien kanker paru yang
bukan perokok memiliki kecenderungan bekerja dengan paparan dari debu kayu
(OR=1,4 ; 95%CI= 1-2).(Vallieres dkk,2015) Pekerjaan lain yang dianggap berisiko
terhadap kejadian kanker paru adalah penambang batu bara, penambang bijih besi
dan pemecah batu. Penambang yang bekerja di bawah tanah memiliki tingkat
eksposur yang tinggi terhadap bahan karsinogenik bagi paru seperti arsenik, asbestos,
kromium, nikel, PAH, silika dan buangan mesin diesel sedangkan pemecah batu
paling sering berkontak dengan silika. Kelompok pekerja ini memiliki risiko yang
tinggi terhadap kanker paru apabila sudah terpapar zat karsinogenik selama lebih dari
10 tahun.(Taeger dkk,2015) Pekerja manual (pekerja yang bekerja dengan tangan
tanpa bantuan mesin) diduga memiliki risiko tinggi terhadap kontak dengan bahan
karsinogenik. Pekerjaan yang termasuk di dalam pekerja manual adalah pekerja
terampil seperti petani, tukang las dan tukang ledeng, lalu pekerja pemrosesan dan
operator mesin seperti pemecah batu dan perakit, serta pekerja dasar seperti tukang
bersih-bersih. Risiko kanker paru lebih tinggi pada pekerja manual dibandingkan
dengan manager atau pekerjaan professional lainnya dengan OR 2,5 dan 95%CI 1.2-
5.05, 71,35% pekerja tersebut mendapatkan ekpaparan karsinogenik dari lingkungan
tempat bekerja mereka.(Nordin dkk,2014)

2.4.8 Riwayat Keluarga
Keluarga diduga memiliki peranan penting dalam kejadian kanker paru.
Keluarga diduga memiliki peran penting dalam menurunkan polimorfisme pada gen
seseorang. Keluarga juga diduga berperan dalam menurunkan kebiasaan merokok
pada seseorang. Studi meta analisis yang dibuat oleh Makidou dkk menunjukkan
bahwa dari 31 case control 27 diantaranya menunjukkan riwayat kanker paru pada
keluarga berkaitan dengan peningkatan risiko kanker paru (95%CI : 1,58-2.10) dan
11 dari studi tersebut menujukkan peningkatan risiko signifikan pada pasien yang
tidak pernah merokok yang menandakan keluarga berperan besar pada pewarisan
genetik kanker (95%Ci : 1,1-2,06). Sedangkan dari 17 studi cohort semuanya
menunjukkan peningkatan risiko kanker paru yang signifikan pada pasien dengan
riwayat keluarga (95%CI: 2,57-40,41). (Matakidou dkk, 2006) Penelitian dari Anna
dkk menunjukkan bahwa riwayat penyakit kanker paru dalam keluarga dapat
meningkatkan risiko seseorang menderita kanker paru, selain itu apabila keluarga
yang memiliki riwayat kanker paru adalah ibu dan saudara perempuan maka risiko
akan jauh lebih meningkat dengan OR 2,74 dan 3,58 seperti ditunjukkan pada tabel di
bawah.(Anna dkk, 2009)
Tabel 2.3. Data pasien kanker paru dengan riwayat keluarga penderita kanker paru

Beberapa gen yang diwariskan keluarga diduga mempengaruhi meningkatnya risiko
kanker paru. Gen pada kromosom 5p15.33 yang memiliki pengaruh besar pada
wanita yang tidak pernah merokok, diduga menaikan risiko melalui mediasi
peningkatan TERT yang mengakibatkan overekspresi mRNA yang menyebabkan
kanker paru. Gen pada kromosom 6p21-6p22 juga memiliki keterkaitan dengan
meningkatnya risiko kanker paru dengan mengakibatkan adanya DNA mismatch
repair pada gen M5H5. Gen pada kromosom 9p21.3 yang merupakan pengkode
tumor suppressor gene yang dapat menghambat CDK dan apoptosis terinduksi
stressor pada sel paru yang dapat meningkatkan risiko kanker paru serta gen pada
kromosom 12p13.33 yang juga dapat mempengaruhi DNA repair mechanism pada
sel kanker paru.(Timofeeva dkk,2012)
2.5 Penatalaksanaan Kanker Paru di Indonesia
Berdasarkan pedoman dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, penatalaksanaan
penyakit kanker paru terdiri dari radioterapi, kemoterapi dan pembedahan. Adapun
algoritma penatalaksanaan kanker paru di Indonesia adalah sebagai berikut :

Gambar 5. Alur penatalaksanaan kanker paru di Indonesia (PDPI,2003)
2.6 Keluaran Yang Dihasilkan Dari Upaya Pengobatan
Setiap jenis penatalaksanaan yang digunakan untuk mengobati kanker paru memiliki
keluaran yang berbeda-beda. Tiga modalitas utama dalam penatalaksanaan kanker di
Indonesia merupakan kemoterapi, radioterapi dan pembedahan yang masing-masing
memiliki hasil keluaran yang berbeda-beda. Berikut penulis akan menjelaskan satu-
persatu keluaran dari modalitas berdasarkan literatur terdahulu.
2.6.1 Kemoterapi
Kemoterapi untuk pasien kanker merupakan modalitas yang cenderung paling
sering digunakan pada penderita kanker paru. Kemoterapi kerap kali dianggap
sebagai modalitas yang tidak efektif serta memiliki toksik yang tinggi terhadap
penggunanya, akan tetapi beberapa studi menyatakan bahwa kemoterapi merupakan
modalitas yang dapat meningkatkan survival pasien, menurunkan gejala serta
meningkatkan kualitas hidup pasien kanker.(Brown dkk,2013; Bonferroni dkk, 2012;
Brimingham dkk, 2009) Studi yang dikerjakan oleh Schiller dkk yang
membandingkan keefektivitasan pada beberapa kemoterapi yang digunakan pada
pasien kanker paru menunjukkan bahwa terapi dengan menggunakan ciplastin dan
gemcitabin memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan survival selama 2 tahun.
(Schiller dkk, 2012)
Table 2.4. Perbedaan keluaran pada beberapa regimen kemoterapi untuk kanker
paru. Dapat dilihat respon komplet maupun partial tertinggi dicapai oleh
gemcitabine, kestabilan kanker dicapai tertinggi oleh docetaxel dan survival terbaik
dihasilkan oleh gemcitabine (Schiller dkk, 2012)

2.6.2 Radioterapi
Pengobatan kanker paru stadium awal biasanya tidak memungkinkan untuk
dilakukan pembedahan dikarenakan ukuran kanker yang masih terlalu kecil.
Kebanyakan penatalaksanaan pada penyakit kanker paru stadium awal adalah dengan
menggunakan radioterapi. Salah satu jenis radioterapi yang dapat digunakan sebagai
modalitas adalah stereotactic body radiotheraphy (SBRT) yang sekarang lebih
dikenal dengan stereotactic ablative radiotherapy (SABR) yang merupakan teknologi
noninvasive dengan ketepatan yang tinggi sehingga dapat mentarget tumor dengan
lebih baik tanpa meningkatkan kadar toksik pada tubuh pasien. (Solda dkk, 2013 ;
Palma dkk,2012) Penelitian dari palma dkk juga menunjukkan bahwa radioterapi
yang digunakan dalam mengobati kanker paru merupakan terapi dengan tingkat
toleransi tinggi dan hanya menghasilkan efek samping minor pada pasien seperti yang
akan dijelaskan pada tabel 2.5. (Palma dkk,2012)
SABR biasa digunakan untuk pasien kanker paru yang memiliki kontra indikasi
untuk pembedahan. Penelitian dari Verstegen dkk pada tahun 2013 juga
membuktikan bahwa SARBP tidak memberikan toksisitas yang lebih rendah secara
Tabel 2.5. Perbandingan 30-day mortality pada pasien dengan kanker paru
stadium awal yang diberikan tindakan bedah dibandingkan dengan radioterapi.
Dapat dilihat bahwa pasien yang mendapatkan tindakan radioterapi tidak ada
yang meninggal setelah 30 hari dibandingkan dengan pembedahan yang
menghasilkan 8% pasien meninggal, 25% meninggal setelah lobektomi dan 7%
setelah segmentektomi. Komplikasi yang terjadi pada radioterapi 69%nya
merupakan toksisitas tingkat 1 dan 2 yaitu berupa kelelahan, batuk, sesak, mual
dan berkurangnya nafsu makan. (Palma dkk,2012)

signifikan pada 90-day mortality pada pasien kanker paru stadium 1 dan 2
dibandingkan dengan pembedahan dan video assist thoracoscopy surgery
(VATS).(Verstegen dkk, 2013)
2.6.3 Pembedahan
Pembedahan merupakan penatalaksanaan kanker paru yang cukup umum
dilakukan di Indonesia. Beberapa teknik pembedahan dilakukan untuk
mengeradikasi sel kanker pada paru-paru pasien mulai dari pembedahan terbuka
maupun pembedahan melalui endoskopi. Pembedahan biasanya dilakukan untuk
kanker paru stadium lanjut akan tetapi pembedahan juga memiliki keuntungan untuk
pengobatan kanker paru stadium awal (1&2) yaitu kemampuannya untuk melihat
getah bening secara invasive sehingga dapat memutuskan untuk memulai kemoterapi
adjuvant apabila terdeteksi dimulainya metastasis melalui getah bening. Selain itu,
pembedahan juga memberikan keuntungan untuk mendapatkan diagnosis
histopatologi pasti.(Verstegen dkk,2013; Zhang dkk, 2013) Studi meta analisis yang
dilakukan oleh Taioli et al menunjukkan bahwa prosedur pembedahan dengan VATS
lebih menguntungkan dibandingkan dengan torakostomi dengan 5 years survival 62-
97% dan 5 years mortality yang lebih rendah (95%CI : 3-6). Studi Taioli et al
menyarankan lobektomi dengan VATS dijadikan sebagai terapi pengganti
torakostomi dikarenakan lobektomi VATS memiliki komplikasi yang lebih sedikit,
durasi penggunaan chest tube yang lebih pendek dan durasi opname yang lebih
pendek. (Taioli dkk, 2013). Lobektomi VATS dilakukan dengan menggunakan teknik
three-port-non-rib-spreading dengan peralatan torakoskopik standar, insisi untuk
akses masuk dibuat sebsar 4cm di antara interkosta 3 dan 4 pada garis anterior aksila.
Port kamera sebesar 1cm diletakkan diantara interkosta 7 dan 8 pada garis anterior
aksila dan dibuat lubang 1cm pada posterior untuk retraksi dan insersi stapler.(Taioli
dkk,2013 ; Zhang dkk,2013; Lee dkk,2013) Perbandingan keluaran jangka panjang
antara beberapa teknik pembedahan tidak memberikan perbedaan yang bermakna
secara statistic (p:0,767) dimana pasien yang mampu bertahan selama 3 dan 5 tahun
pada pasien open thoracostomy sebesar 87,2% dan 74,9% sedangkan VATS sebesar

80,9% dan 76,6% akantetapi pada pasien kanker dengan stadium 2 dan 3 keluaran
jangka panjang bermakna secara signifikan (p=0,363) dimana pasien dengan OS yang
mampu bertahan selama 3 tahunnya sebesar 58,4% (95%CI:33,3-83,5), VATS
sebesar 61,3% (95%CI: 48,6-74,0). (Lee dkk, 2013)
2.7 Prognosis Kanker Paru
Seperti yang telah dibahas pada bagian pendahuluan, kanker paru merupakan
salah satu kanker yang fatal dengan tingkat kematian paling tinggi jika dibandingkan
dengan kanker lainnya. Prognosis kanker paru dikelompokkan berdasarkan
stadiumnya dimana semakin tinggi tingkatan kankernya maka angka 5 years survival-
nya akan semakin rendah. (American Cancer Society, 2016)
STAGE 5 YEARS SURVIVAL
I A 49%
I B 45%
II A 30%
II B 31%
III A 14%
III B 5%
IV 1%
‘
Tabel 2.6. Persentase pasien yang mampu bertahan hidup setelah diagnosis kanker paru
selama 5 tahun berdasarkan derajatnya. Dapat dilihat bahwa pasien kanker paru
memiliki prognosis yang buruk dimana pada stage I A saja persentase pasien yang
mampu bertahan sampai 5 tahun tidak sampai setengahnya dan pada stage akhir hanya
1% pasien yang mampu bertahan sampai 5 tahun.