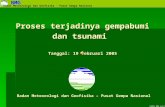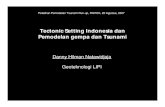BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. 1. Studi Pustaka Telah dilakukan penelitian terkait mekanisme sumber...
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. 1. Studi Pustaka Telah dilakukan penelitian terkait mekanisme sumber...

7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2. 1. Studi Pustaka
Telah dilakukan penelitian terkait mekanisme sumber gempabumi di
Selatan Jawa. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan:
Table 2.1. Penelitian yang relevan mengenai analisa jenis sesar di Selatan Jawa menggunakan
metode Mekanisme Fokus
No Peneliti Judul Publikasi Hasil
1 Emile
A. Okal
The South of
Java
Earthquake of
1921
September 11:
a negative
search for a
large
interplate
thrust event at
the Java
Trench
Geophysical
Journal
International
(2012) 190,
1657-1672
Berdasarkan teknik relokasi modern,
kompilasi tegangan mekanisme
fokus dari rekaman seismogram,
kuantifikasi gelombang permukaan
mantel dan simulasi numerik dari
tsunami biasa (hanya 10 cm di
Cilacap), disimpulkan bahwa
gempabumi 1921 terjadi pada
kedalaman 30 km, merupakan gempa
dangkal dan menampilkan
mekanisme strike-slip dominan,
dengan momen 5 x 1027 dyn cm.
2 Iktri M.,
dkk
Studi
Mekanisme
Fokus Gempa
Mikro Sekitar
Cekungan
Bandung
Jurnal
Geofisika
Vol. 14 No.
1/2013
(ITB)
Hasil yang diperoleh menunjukkan
antara lain gempa dengan
mekanisme fokus dip-slip (sesar
naik dan turun) di sekitar wilayah
gunung api dan gempa dengan
mekanisme fokus strike-slip (sesar
geser) di wilayah sekitar sesar aktif.

8
Table 2.1. (Lanjutan)
No Peneliti Judul Publikasi Hasil
3 Ngoc
Nguyen
dkk
Indonesia’s
Historical
Earthquakes:
Modelled
examples for
improving the
national
hazard map
Geoscience
Australia:
Record
2015/23
Sekenario guncangan tanah pada tiap
kejadian dimodelkan dengan
software OpenQuake dan
menghasilkan pergerakan tanah dan
pada software InaSAFE digunakan
untuk menghitung potensi bencana.
Catatan historis menunjukkan bahwa
Jawa sangat aktif di masa lalu, dan
akan terus menjadi pulau dengan
seismisitas aktif yang mungkin ada
sumber patahan yang merusak dan
belum dikenal saat ini.
4 S.
Hidayati
dkk
Mekanisme
Fokus dan
Parameter
Sumber
Gempa
Vulkano-
Tektonik di
Gunung
Guntur, Jawa
Barat
Jurnal
Geologi
Indonesia,
Vol. 6 No. 1
Maret 2011:
1-11
(PVMBG)
Sebaran hiposentrum gempa VT
pada periode Juli – Oktober 2009
secara umum menunjukkan berada di
bagian lereng barat di bawah kawah
Guntur-Gandapura pada kedalaman
kurang dari 5 km. Pola sebaran
kedalamannya semakin dalam ke
arah barat laut. Mekanisme fokus
gempa VT adalah sesar turun
oblique, sesar geser, dan sesar naik
oblique. Mekanisme gempa yang
tidak unik ini kemungkinan
disebabkan oleh struktur yang cukup
rumit di area kompleks Gunung
Guntur, yang berarah barat laut –
tenggara.

9
Telah dilakukan penelitian terkait mekanisme sumber gempa yang
terdapat pada Tabel 2.1, pada penelitian pertama dengan objek kajian
gempabumi di Selatan Jawa. Penelitian tersebut membahas kejadian
gempabumi yang berpotensi tsunami dengan menggunakan metode
mekanisme fokus dari gerak awal gelombang-P dan menghitung momen
tensornya. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan data polaritas
gerak awal gelombang-P dari serangkaian kejadian gempabumi terasa di
Selatan Jawa.
Penelitian kedua mengenai gempa mikro di sekitar Cekungan
Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah data
polaritas gerak awal gelombang-P. Menggunakan metode yang sama,
perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Dalam
penelitian ini mengambil objek yang lebih luas, yaitu gempabumi terasa di
Selatan Jawa.
Penelitian ketiga mengenai kejadian-kejadian gempabumi yang
digunakan untuk melihat potensi bencana yang dapat ditimbulkan serta
perhitungan tentang mitigasi yang dapat dilakukan. Sedangkan pada
penelitian ini lebih terfokus pada tiap kejadian gempabumi terasa dengan
mengidentifikasi pola sesar pada serangkaian kejadian gempabumi di Selatan
Jawa pada periode Oktober 2016 s.d. Maret 2017.
Studi mengenai sesar kejadian gempabumi menggunakan metode
mekanisme fokus juga pernah dilakukan seperti pada penelitian keempat.

10
Objek kajian pada penelitian tersebut adalah gempa VT (vulkano-tektonik) di
Gunung Guntur, Jawa Barat. Sedangkan pada penelitian ini objek yang
digunakan adalah gempabumi di Selatan Jawa.
Secara garis besar terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian terkait sebagaimana tercantum pada tabel 2.1. Perbedaan
dengan nomor 1 dan 3 terletak pada metode yang digunakan, sedangkan pada
nomor 2 dan 4 terdapat perbedaan pada beberapa metode dan objek kajiannya.
2. 2. Landasan Teori
2. 2. 1. Gempabumi
Sebelum memasuki pembahasan mengenai gempabumi, lebih dulu
kita mengenal Teori Apungan Benua (Continental Drift). Teori ini
dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener (1912). Benua-benua yang ada
saat ini dahulunya bersatu yang dikenal sebagai super-kontinen yang bernama
Pangea. Super-kontinen Pangea ini diduga terbentuk pada 200 juta tahun yang
lalu yang kemudian terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil
yang kemudian bermigrasi (drifted) ke posisi seperti saat ini (McGuire, 2005).
Gempabumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan
energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan
batuan pada kerak bumi. Akumulasi penyebab terjadinya gempabumi
dihasilkan dari pergerakan lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan

11
dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempabumi sehingga efeknya
dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi (BMKG, 2014).
Gambar 2.1. Super-kontinen Pangaea (USGS, diakses pada 17 Maret 2017)
A. Parameter gempabumi (Sudibyakto, 2000)
1. Waktu terjadinya gempabumi (Origin Time – OT)
2. Lokasi pusat gempabumi (Episenter)
3. Kedalaman pusat gempabumi (Depth)
4. Kekuatan gempabumi (Magnitudo)

12
B. Karakteristik gempabumi (Sudibyakto, 2000)
1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat.
2. Lokasi kejadian tertentu.
3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana.
4. Berpotensi terulang lagi.
5. Belum dapat diprediksi.
6. Tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi.
C. Istilah-istilah yang digunakan dalam gempabumi
Peristiwa gempabumi memiliki beberapa istilah yang sering
digunakan. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
gempabumi:
Tabel 2.2. Istilah-istilah yang digunakan dalam gempabumi
No. Istilah Definisi
1 Seismologi Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang
gempabumi
2 Seismograf Seismograf adalah alat pencatat getaran gempabumi
yang terjadi di permukaan bumi. Prinsip yang
digunakan seismograf adalah pada saat terjadi
gempabumi, harus diusahakan penggantungan
sedemikian rupa sehingga massa yang digantungkan
tidak ikut bergerak ketika terjadi gempa.

13
Tabel 2.2. (Lanjutan)
No. Istilah Definisi
3 Makroseista Makroseista adalah wilayah yang mengalami kerusakan
terbesar.
4 Homoseista Homoseista adalah garis yang menghubungkan tempat-
tempat yang mengalami getaran gempa pada waktu
yang sama.
5 Isoseista Isoseista adalah garis yang menghubungkan tempat-
tempat yang mempunyai intensitas yang sama.
6 Pleistoseista Pleistoseista adalah garis yang melingkari daerah yang
mengalami kerusakan terbesar akibat gempa.
7 Hiposenter Hiposenter adalah pusat gempabumi yang terletak di
dalam bumi
8 Episenter Episenter adalah pusat gempabumi yang letaknya di
permukaan bumi.
9 Skala Richter Skala Richter adalah kekuatan gempa diukur dengan
Skala Richter atau SR, yang didefinisikan sebagai
logaritma (basis 10) dari amplitudo maksimum, yang
diukur dalam satuan mikrometer, dari rekaman gempa
oleh instrumen pengukur gempa (seismometer) Wood-
Anderson, pada jarak 100 km dari pusat gempanya.
Skala ini diusulkan oleh fisikawan Charles Richter.
Sumber: McGraw-Hill, 2003

14
D. Klasifikasi gempabumi
1. Berdasarkan peristiwa yang menyebabkannya:
a. Gempa Tektonik
Gempa tektonik merupakan gempa yang mengiringi gerakan
tektonik suatu atau beberapa lempeng yang menghasilkan suatu
patahan (fault). Jenis gempa ini merupakan jenis gempa terkuat dan
meliputi area yang luas. Gempabumi tektonik disebabkan oleh
pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat
tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan
tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antar batuan dikenal
sebagai kecacatan tektonik (HMGF-UGM, 2016). Gempa jenis ini
merupakan gempa yang banyak terjadi di daerah-daerah pertemuan
lempeng tektonik seperti di Selatan Jawa.
b. Gempa Vulkanik
Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi saat sebelum
dan sedang terjadi letusan gunung api. Jenis gempa ini kurang kuat
jika dibandingkan dengan jenis gempa tektonik dan hanya terasa di
daerah sekitar gunung tersebut (Rafferty, 2012).
Gempabumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang
biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya
semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang

15
juga akan menimbulkan terjadinya gempabumi. Gempa tersebut
hanya terasa di sekitar gunung api.
c. Gempa Runtuhan (Terban)
Gempa runtuhan merupakan gempa yang terjadi akibat
runtuhnya atap goa yang terdapat dalam litosfer, seperti goa kapur
dan terowongan tambang. Jenis gempa ini relatif lemah dan hanya
terasa di sekitar tempat runtuh itu terjadi.
2. Berdasarkan letak kedalaman hiposenter:
a. Gempa Dalam
Gempa dalam di mana letak hiposenter pada kedalaman lebih
dari 300 kilometer di bawah permukaan bumi. Gempabumi dalam
pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Tempat yang pernah
mengalami gempa dalam adalah di bawah Laut Jawa, Laut Sulawesi
dan Laut Flores.
b. Gempa Menengah (Intermediate)
Gempa menengah di mana letak hiposenter pada kedalaman
antara 60 s.d. 300 kilometer di bawah permukaan bumi. Gempabumi
menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan
getarannya lebih terasa. Tempat yang pernah terkena antara lain
sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa bagian selatan, sepanjang
Teluk Tomini, Laut Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara.

16
c. Gempa Dangkal
Gempa dangkal di mana letak hiposenter pada kedalaman
kurang dari 60 kilometer di bawah permukaan bumi. Gempabumi
ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Tempat yang
pernah terkena antara lain Pulau Bali, Pulau Flores, Yogyakarta dan
Jawa Tengah.
E. Intensitas gempabumi (BMKG, diakses pada 17 Maret 2017)
Intensitas gempabumi adalah ukuran kerusakan akibat gempabumi
berdasarkan hasil pengamatan dari efek gempabumi terhadap manusia,
struktur bangunan dan lingkungan pada tempat tertentu.
1. Skala Intensitas Gempabumi (SIG) BMKG
SIG adalah Skala Intensitas Gempabumi. Skala ini menyatakan
dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gempabumi. Skala
Intensitas Gempabumi (SIG-BMKG) digagas dan disusun dengan
mengakomodir keterangan dampak gempabumi berdasarkan tipikal
budaya atau bangunan di Indonesia. Skala ini disusun lebih sederhana
dengan hanya memiliki lima tingkatan yaitu I s.d. V.

17
Tabel 2.3. Skala Intensitas Gempabumi BMKG
Skala
SIG
BMKG
Warna Deskripsi
Sederhana Deskrispsi Rinci
Skala
MMI
PGA
(gal)
I Putih
TIDAK
DIRASAKAN
(Not Felt)
Tidak dirasakan atau dirasakan hanya
oleh beberapa orang tetapi terekam
oleh alat.
I-II < 2.9
II Hijau DIRASAKAN
(Felt)
Dirasakan oleh orang banyak tetapi
tidak menimbulkan kerusakan.
Benda-benda ringan yang digantung
bergoyang dan jendela kaca bergetar.
III-V 2.9-
88
III Kuning
KERUSAKAN
RINGAN
(Slight Damage)
Bagian non struktur bangunan
mengalami kerusakan ringan, seperti
retak rambut pada dinding, genteng
bergeser ke bawah dan sebagian
berjatuhan.
VI 89-
167
IV Jingga
KERUSAKAN
SEDANG
(Moderate
Damage)
Banyak Retakan terjadi pada dinding
bangunan sederhana, sebagian roboh,
kaca pecah. Sebagian plester dinding
lepas. Hampir sebagian besar genteng
bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur
bangunan mengalami kerusakan
ringan sampai sedang.
VII-
VIII
168-
564
V Merah
KERUSAKAN
BERAT
(Heavy Damage)
Sebagian besar dinding bangunan
permanen roboh. Struktur bangunan
mengalami kerusakan berat. Rel
kereta api melengkung.
IX-
XII
>
564
2. Skala MMI (Modified Mercalli Intensity)
Skala Mercalli adalah satuan untuk mengukur kekuatan
gempabumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari Italia
yang bernama Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Skala Mercalli
terbagi menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang
yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta
membandingkan tingkat kerusakan akibat gempabumi tersebut. Oleh itu

18
skala Mercalli adalah sangat subjektif dan kurang tepat dibanding
dengan perhitungan magnitudo gempa yang lain. Oleh karena itu, saat
ini penggunaan Skala Richter lebih luas digunakan untuk mengukur
kekuatan gempabumi. Tetapi skala Mercalli yang dimodifikasi, pada
tahun 1931 oleh ahli seismologi Harry Wood dan Frank Neumann masih
sering digunakan terutama apabila tidak terdapat peralatan seismometer
yang dapat mengukur kekuatan gempabumi di tempat kejadian.
Tabel 2.4. Skala Mercalli
Skala
Intensitas Klasifikasi Secara Umum
I MMI Getaran tidak dirasakan, kecuali dalam keadaan hening oleh
beberapa orang.
II MMI Getaran dirasakan oleh beberapa orang.
III MMI Getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan-
akan ada truk lewat. Benda-benda yang bergantung bergoyang.
IV MMI Pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, di luar
oleh beberapa orang, sebagian piring dan gelas berbunyi, jendela dan
pintu bergetar, dinding berbunyi.
V MMI Getaran dirasakan oleh hampir semua orang, banyak yang terbangun.
Jendela kaca pecah, barang-barang di atas meja berjatuhan. Pohon-
pohon, tiang-tiang dan barang-barang besar lain tampak bergoyang.
Bandul lonceng dapat berbunyi.

19
Tabel 2.4. (Lanjutan)
Skala
Intensitas Klasifikasi Secara Umum
VI MMI Getaran dirasakan oleh semua orang, kebanyakan terkejut dan lari
keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pabrik rusak.
VII MMI Hampir semua orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah
dan bangunan dengan kontruksi yang baik, cerobong asap pecah dan
retak-retak. Goncangan terasa oleh orang yang naik kendaraan.
VIII MMI Kerusakan ringan pada bangunan yang kuat. Retak-retak pada
bangunan yang kuat. Dinding dapat lepas dari rangka rumah. Pabrik-
pabrik dan monumen roboh. Air menjadi keruh.
IX MMI Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi
tidak lurus, retak-retak pada bangunan yang kuat. Rumah tampak
bergeser dari pondasinya. Pipa-pipa tanah putus.
X MMI Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka-rangka rumah lepas dari
pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung. Tanah longsor di sekitar
sungai dan di tanah-tanah yang curam, air bah.
XI MMI Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan
rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama
sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali.
XII MMI Hancur sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah.
Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara.

20
2. 2. 2. Gelombang Seismik
Mekanisme gempabumi dikontrol oleh pola penjalaran gelombang
seismik di dalam bumi. Pola mekanisme ini bergantung pada medium
penjalaran atau keadaan struktur kulit bumi serta distribusi gaya atau stress
yang terjadi. Gelombang seismik adalah gelombang elastis yang menjalar di
dalam bumi. Gelombang seismik dapat diklasifikasikan menjadi dua
kelompok yaitu gelombang badan (body wave) dan gelombang permukaan
(surface wave) (McGuire, 2005).
A. Gelombang badan (body wave)
Gelombang badan (body wave) adalah gelombang yang merambat
melalui lapisan dalam bumi. Gelombang ini terdiri dari dua macam
gelombang, yaitu:
a. Gelombang longitudinal (P)
Gelombang longitudinal (P) yaitu gelombang yang arah
rambatnya searah dengan arah gerak partikel medium yang
dilewatinya. Gelombang ini memiliki kecepatan rambat paling cepat
dibandingkan dengan gelombang-S, dan dapat merambat melalui
medium padat, cair dan gas.

21
Gambar 2.2. Gelombang-P (Elnashai, 2008)
b. Gelombang transversal (S)
Gelombang transversal (S) adalah gelombang yang arah
rambatnya tegak lurus terhadap arah gerak partikel medium yang
dilewatinya. Gelombang Sekunder (Gelombang-S) disebut juga
gelombang shear atau gelombang transversal. Gelombang ini
memiliki cepat rambat yang lebih lambat bila dibandingkan dengan
gelombang-P dan hanya dapat merambat pada medium padat saja.
Gambar 2.3. Gelombang-S (Elnashai, 2008)
Berikut ini merupakan contoh ilustrasi gelombang primer (P) dan
gelombang sekunder (S) di dalam bumi:
Medium tidak terganggu
Kompresi
Dilatasi
Medium tidak terganggu
Panjang gelombang

22
Gambar 2.4. Contoh ilustrasi fase gelombang badan menggunakan nomenklatur
(Stein, 2005)
Kecepatan gelombang seismik bertambah dengan kedalaman,
maka lintasan gelombang seismik akan berbentuk lengkungan cekung
ke permukaan bumi. Kecepatan gelombang-P (Vp) bergantung pada
konstanta panjang gelombang (𝜆), rigiditas (𝜇) dan densitas (𝜌)
medium yang dilalui dan secara matematis dirumuskan sebagai
berikut (dijelaskan lebih rinci pada lampiran 1):
𝑉𝑝 = √𝜆+2𝜇
𝜌 (2.1)
Gelombang-P mempunyai kecepatan paling tinggi dibanding
dengan kecepatan gelombang yang lain sehingga tercatat paling awal
di seismogram. Gelombang-S mempunyai gerakan partikel tegak
lurus terhadap arah penjalaran dan mempunyai kecepatan (Vs):
𝑉𝑠 = √𝜇
𝜌 (2.2)

23
B. Gelombang permukaan (surface wave)
Gelombang permukaan yaitu gelombang yang menjalar sepanjang
permukaan atau pada suatu lapisan dalam bumi. Gelombang ini terdiri
dari Gelombang Love (LQ) dan Gelombang Rayleigh (LR).
Gelombang Love (LQ) dan gelombang Rayleigh (LR) yaitu
gelombang yang menjalar melalui permukaan yang bebas daripada
bumi. Gelombang Love merupakan gelombang permukaan yang
menjalar dalam bentuk gelombang transversal yang merupakan
gelombang S horizontal yang penjalarannya paralel dengan
permukaannya, dan gelombang ini tidak bisa merambat dalam
medium cair (Elnashai, 2008).
Gambar 2.5. Gelombang Love (Elnashai, 2008)
Gelombang Rayleigh merupakan gelombang permukaan yang
orbit gerakannya elips tegak lurus dengan permukaan dan arah
penjalarannya. Gelombang jenis ini adalah gelombang permukaan
yang terjadi akibat adanya interferensi antara gelombang tekan dengan
gelombang geser secara konstruktif (Elnashai, 2008).
Medium tidak terganggu

24
Gambar 2.6. Gelombang Rayleigh (Elnashai, 2008)
2. 2. 3. Sesar
Sesar atau patahan adalah struktur retakan yang telah mengalami
pergeseran. Umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan, rekahan
dan sebagainya. Adapun di lapangan indikasi suatu sesar dapat dikenal
melalui: gawir sesar atau bidang sesar; breksiasi, gouge, milonit; deretan mata
air; sumber air panas; penyimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan;
gejala-gejala struktur minor seperti: cermin sesar, gores garis, lipatan dan
sebagainya (Noor, 2012).
A. Terminologi sesar
Sesar biasanya dipresentasikan secara geometri seperti pada
gambar 2.7. Bidang sesar (fault plane) adalah sebuah bidang yang
merupakan bidang tektonik antara dua blok tektonik. Sudut
kemiringan sesar (dip angel) adalah sudut yang dibentuk antara bidang
sesar dengan bidang horizontal. Vektor kemiringan (dip vector) adalah
vektor yang searah dengan kemiringan bidang sesar, sedangkan vektor
strike (strike vector) adalah vektor yang sejajar dengan arah strike
sesar.
Medium tidak terganggu

25
Arah pergerakan sesar secara umum dapat dibedakan menjadi 3
jenis, yaitu:
1. Dip Slip Movement: Pergerakan sesar terjadi dalam arah sejajar
dengan sudut kemiringan sesar. Pergerakan yang dominan adalah
arah vertikal.
2. Strike Slip Movement: pergerakan dasar terjadi dalam arah sejajar
dengan sudut strike sesar. Pergerakan yang dominan adalah arah
horizontal.
3. Dip and Slip Movement Combination: kombinasi antara yang
pertama dan kedua.
Gambar 2.7. Terminologi Sesar (HMGF-UGM, 2016)
Orientasi sesar ditentukan oleh parameter bidang sesar yang
terdiri dari:
1. Strike (𝜑): adalah sudut yang dibentuk oleh jurus sesar dengan
arah utara. Strike diukur dari arah utara ke arah timur searah
dengan jarum jam hingga jurus patahan (0⁰ ≤ 𝜑 ≤ 360⁰).
u
𝜑
𝛼 = dip
𝛽 = hade = 90˚ - dip
𝛾 = rake
𝜑 = strike
ab = net slip
ae = strike slip
cb/ad = dip slip
ae = vertical slip = throw
de = horizontal slip = heave

26
2. Dip (𝛼): adalah sudut yang dibentuk oleh bidang sesar dengan
bidang horizontal dan diukur pada bidang vertikal dengan arah
tegak lurus terhadap jurus patahan (0⁰ ≤ 𝛼 ≤ 90⁰).
3. Rake (𝛾): adalah sudut yang dibentuk arah slip dan jurus patahan.
Rake berharga positif pada patahan naik (thrust fault) dan negatif
pada patahan turun (normal fault) (-180⁰ ≤ 𝛾 ≤ 180⁰).
B. Jenis-jenis sesar (Noor, 2012)
1. Sesar turun (normal fault)
Patahan dikatakan masuk ke dalam normal fault jika patahan
tersebut memungkinkan satu blok misalnya bagian foot wall
memiliki lapisan yang bergerak searah namun relatif naik terhadap
blok lainnya yaitu hanging wall. Ciri yang sangat mudah
ditemukan pada jenis normal fault adalah tingkat kemiringannya
yang hampir 90⁰.
Gambar 2.8. Sesar turun yang disebabkan oleh gaya tegasan tensional
horizontal, di mana hanging-wall bergerak ke bagian bawah foot-wall
Blok Hanging-Wall
Blok Foot-Wall

27
2. Sesar naik (reverse fault)
Kebalikan dari normal fault, untuk jenis reverse fault ini
merupakan patahan yang terjadi dengan arah foot wall yang relatif
turun dibandingkan dengan hanging wall. Ciri yang mudah
ditemukan pada jenis patahan ini adalah tingkat kemiringannya
yang relatif kecil yaitu sekitar 45˚ saja atau setengah dari
kemiringan normal fault.
Gambar 2.9. Sesar naik sebagai hasil dari gaya tegasan kompresional, di
mana bagian hanging-wall bergerak relatif ke bagian atas dibandingkan foot-
wall
3. Sesar mendatar
Untuk jenis strike fault ini merupakan patahan yang memiliki
arah relatif mendatar baik itu ke kiri maupun ke kanan. Arah
patahan ini memang tidak seluruhnya bergerak dengan arah
mendatar namun juga bisa dengan arah vertikal. Patahan jenis ini
yang bergerak ke arah kiri disebut dengan dekstral sedangkan
untuk patahan yang bergerak ke kanan disebut dengan sinistral.
Blok Hanging-Wall
Blok Foot-Wall

28
Gambar 2.10. Sesar mendatar adalah patahan yang pergerakan relatifnya
berarah horizontal mengikuti arah patahan
2. 2. 4. Mekanisme Sumber Gempabumi
Sekarang kita tinjau bagaimana proses terjadinya sebuah gempabumi.
Seorang ahli seismologi Amerika yang bernama Reid pada tahun 1906
mengadakan penelitian untuk membahas tentang proses pemecahan di sebuah
sumber gempabumi pada gempa San Fransisco yang terjadi di sesar San
Andreas. Displacement dari sesar San Andreas ini kebanyakan horizontal, di
mana pada bagian timur yang menghadap ke daratan Amerika bergerak ke
selatan terhadap yang di sebelah barat (Ibrahim, 2005).
A. Momen tensor
Sebelum masuk pada pembahasan mengenai momen tensor, mari
kita lebih dulu mengenal mengenai gaya tunggal, kopel tunggal dan
kopel ganda.

29
Gambar 2.11. Deskripsi gaya tunggal, kopel tunggal dan kopel ganda (Stein, 2005)
Gaya tunggal didefinisikan sebagai gaya yang memiliki momen
tensor hanya pada satu arah saja. Contoh dari gaya tunggal ini adalah
gelombang seismik itu sendiri, seperti pada bentuk dan arah
gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Sedangkan gaya kopel
(kopel tunggal) didefinisikan sebagai gaya yang memiliki dua buah
gaya yang bekerja secara bersamaan.
Gambar 2.11 mengilustrasikan hubungan antara geometri patahan
gempabumi dengan kopel ganda. Pada contoh ini, strike-slip samping
kiri berada pada arah ± y pada patahan di bidang y-z, gaya badan Mxy
+ Myx menjadikannya sumber kopel ganda.
Gaya tunggal
Gaya kopel
Kopel ganda

30
Gambar 2.12. Sembilan kopel tunggal yang merupakan komponen dari momen tensor seismik
(Stein, 2005)
Sebagaimana kita lihat, kesebandingan untuk sumber seismik pada
beberapa geometri direpresentasikan oleh momen tensor seismik, M,
di mana komponennya merupakan sembilan gaya kopel
𝑴 = (
𝑀𝑥𝑥 𝑀𝑥𝑦 𝑀𝑥𝑧
𝑀𝑦𝑥 𝑀𝑦𝑦 𝑀𝑦𝑧
𝑀𝑧𝑥 𝑀𝑧𝑦 𝑀𝑧𝑧
) (2.3)
Komponen momen tensor diberikan oleh momen skalar dan
komponen dari ��, unit vektor normal terhadap bidang sesar, dan ��,
unit vektor slip,
𝑀𝑖𝑗 = 𝑀0 (𝑛𝑖𝑑𝑗 + 𝑛𝑗𝑑𝑖) (2.4)
Jika persamaan di atas disubtitusikan ke tiap komponen pers. (2.3),

31
𝑀𝑥𝑥 = 𝑀0 (𝑛𝑥𝑑𝑥 + 𝑛𝑥𝑑𝑥) = 2 𝑀0 𝑛𝑥𝑑𝑥
𝑀𝑥𝑦 = 𝑀0 (𝑛𝑥𝑑𝑦 + 𝑛𝑦𝑑𝑥)
𝑀𝑥𝑧 = 𝑀0 (𝑛𝑥𝑑𝑧 + 𝑛𝑧𝑑𝑥)
𝑀𝑦𝑥 = 𝑀0 (𝑛𝑦𝑑𝑥 + 𝑛𝑥𝑑𝑦)
𝑀𝑦𝑦 = 𝑀0 (𝑛𝑦𝑑𝑦 + 𝑛𝑦𝑑𝑦) = 2 𝑀0 𝑛𝑦𝑑𝑦
𝑀𝑦𝑧 = 𝑀0 (𝑛𝑦𝑑𝑧 + 𝑛𝑧𝑑𝑦)
𝑀𝑧𝑥 = 𝑀0 (𝑛𝑧𝑑𝑥 + 𝑛𝑥𝑑𝑧)
𝑀𝑧𝑦 = 𝑀0 (𝑛𝑧𝑑𝑦 + 𝑛𝑦𝑑𝑧)
𝑀𝑧𝑧 = 𝑀0 (𝑛𝑧𝑑𝑧 + 𝑛𝑧𝑑𝑧) = 2 𝑀0 𝑛𝑧𝑑𝑧 (2.5)
Sehingga pers. (2.3) menjadi
𝑴 = 𝑀0 (
2 𝑛𝑥𝑑𝑥 𝑛𝑥𝑑𝑦 + 𝑛𝑦𝑑𝑥 𝑛𝑥𝑑𝑧 + 𝑛𝑧𝑑𝑥
𝑛𝑦𝑑𝑥 + 𝑛𝑥𝑑𝑦 2 𝑛𝑦𝑑𝑦 𝑛𝑦𝑑𝑧 + 𝑛𝑧𝑑𝑦
𝑛𝑧𝑑𝑥 + 𝑛𝑥𝑑𝑧 𝑛𝑧𝑑𝑦 + 𝑛𝑦𝑑𝑧 2 𝑛𝑧𝑑𝑧
) (2.6)
Formulasi ini menunjukkan bahwa
1. Simpangan �� dan �� menjadikan tensor simetris 𝑀𝑖𝑗 = 𝑀𝑗𝑖. Secara
fisis, hal ini menunjukkan bahwa bidang gelincir (slip) pada
masing-masing bidang sesar atau bidang bantu mempunyai pola
radiasi seismik yang sama.
2. Jejak (jumlah komponen diagonal) dari tensor adalah nol

32
∑ 𝑀𝑖𝑖
𝑖
= 𝑀𝑗𝑗 = 2 𝑀0 𝑛𝑖𝑑𝑖 = 2 𝑀0 �� ∙ �� = 0
karena vektor slip berada pada bidang sesar dan tegak lurus terhadap
vektor normal.
Pada notasi ini, gempabumi di gambar 2.11. direpresentasikan
sebagai
𝑴 = (0 𝑀0 0
𝑀0 0 00 0 0
) = 𝑀0 (0 1 01 0 00 0 0
) (2.7)
di mana M0 didefinisikan sebagai momen seismik skalar yang
diberikan oleh
𝑀0 = 𝜇��𝐴 (2.8)
dengan 𝜇 adalah koefisien geser (shear modulus), �� adalah
perpindahan patahan rata-rata, dan A adalah area dari patahan. Momen
seismik merupakan pengukuran paling dasar dan terkenal dari
kekuatan gempabumi. Satuan dari M0 adalah Nm (1N = 105 dyne, dan
demikian 1Nm = 107 dyne-cm) (Shearer, 2009). M0 didefinisikan
dengan momen tensor M yang memiliki nilai eigen m1 ≥ m3 ≥ m2. Jika
M merupakan kopel ganda, maka M0 = m1 = -m2, dan m3 = 0 (Aki,
2002). Menggunakan teknik inversi centroid moment tensor (CMT),
Dziewonski dan Woodhouse mendefinisikan momen CMT kopel

33
ganda sebagai "nilai mutlak dari rata-rata nilai eigen dominan".
Demikian (Bowers, 1999):
𝑀0 = |𝑚1|+ |𝑚2|
2 (2.9)
Sehingga momen totalnya adalah
𝑀0 = 1
√2 (∑ 𝑀𝑖𝑗
2𝑖𝑗 )
1
2 (2.10)
Gambar 2.13. Momen tensor pilihan dan mekanisme fokus terkait (Stein, 2005)
Untuk membangun momen tensor yang tidak berupa kopel ganda
sederhana seperti di atas, dimisalkan (Jost, 1989)
Momen Tensor Beachball Momen Tensor Beachball

34
𝑴𝟏 = 1 (1 0 00 1 00 0 1
) (2.11)
𝑴𝟐 = 6 (0 1 01 0 00 0 0
) (2.12)
𝑴𝟑 = 3 (0 0 00 −1 00 0 1
) (2.13)
𝑴𝟒 = 1 (0 0 00 0 −10 −1 0
) (2.14)
Keempat momen tensor tersebut ditumpangkan untuk menjelaskan
sumber kompleks yang didominasi oleh mekanisme sesar naik.
Hasilnya adalah
𝑴 = (1 6 06 −2 −10 −1 4
) (2.15)
Tabel 2.5 menunjukkan nilai eigen dan vektor eigen dari pers. (2.15),
dimana sumbu pusatnya adalah M.
Tabel 2.5. Tensor sesar campur
Nilai Eigen Vektor eigen
3.8523 (-0.2938, -0.1397, -0.9456)
5.8904 (0.7352, 0.5592, -0.3170)
-6.7427 (0.6109, -0.7883, -0,0734)
Total nilai eigen adalah 3, yang merupakan nilai yang diharapkan dari
pers. (2.11).

35
Gambar 2.14. Mekanisme fokus kopel ganda dari kopel mayor pers. (2.15)
B. Polaritas gerak awal gelombang-P (Stein, 2005)
Ide dasarnya adalah polaritas (arah) yang pertama dari kedatangan
gelombang-P bervariasi antara stasiun seismik pada arah yang berbeda
dari gempabumi. Gambar 2.15 mengilustrasikan konsep tentang
gempabumi pada sesar geser. Masing-masing gerak awalnya adalah
kompresi, untuk stasiun yang berada di sekitar patahan yang
materialnya bergerak “menuju” stasiun, atau dilatasi, ketika bergerak
“menjauhi” stasiun. Demikian ketika gelombang-P tiba di
seismometer, komponen vertikal seismogram merekam gerak awal
naik atau turun, sehubungan dengan kompresi atau dilatasi.
Gambar 2.15. Gerak awal gelombang-P teramati oleh seismometer yang berada
di sekeliling gempabumi memberikan informasi tentang orientasi sesar
Episenter
Kompresi
Kompresi
Dilatasi
Dilatasi
Bidang bantu
Bidang sesar Naik
Turun

36
Gerak awal terbagi empat kuadran, dua kompresi dan dua dilatasi.
Pembagian antar kuadran terdapat di sepanjang bidang sesar dan
bidang yang tegak lurus terhadap bidang sesar. Pada arah ini, karena
gerak awal berubah dari dilatasi ke kompresi, seismogram
menunjukkan gerak awal yang kecil atau nol. Bidang tegak lurus ini
disebut bidang nodal, memisahkan kuadran kompresi dan dilatasi. Jika
bidang ini dapat ditemukan, maka geometri sesar dapat diketahui.
Masalahnya adalah bahwa gerak awal dari pergeseran pada bidang
sesar sebenarnya dan dari pergeseran pada bidang tegak lurus, bidang
bantu, mungkin saja sama. Sehingga gerak awal sendiri tidak bisa
memisahkan mana yang merupakan bidang sesar yang sebenarnya.
Bagaimanapun, informasi tambahan sering kali dapat menjawab
pertanyaan ini. Terkadang informasi geologi atau geodesi cenderung
lebih memahami sesar atau observasi dari pergerakan tanah yang
mengindikasikan bidang sesar.
Gambar 2.16. Sistem koordinat orientasi-sesar untuk menjelaskan bentuk radiasi
sebuah kejadian gempabumi: (a) bidang sesar, (b) bidang bantu, merupakan bidang
yang tegak lurus terhadap bidang sesar, (c) kopel ganda, merupakan gabungan dari
bidang sesar dan bidang bantu
Bidang
sesar
Bidang
bantu
Kopel
ganda
(a)
(b)
(c)

37
C. Proyeksi diagram mekanisme fokus
Mekanisme fokus atau lebih dikenal sebagai focal mechanism dari
gempabumi adalah penggambaran dari deformasi inelastis (inelastic
deformation) di kawasan sumber yang menghasilkan gelombang
seismik. Dalam banyak kasus, hal ini berhubungan dengan peristiwa
patahan yang mengacu pada orientasi bidang sesar yang bergeser dan
slip vectornya, hal ini dikenal juga sebagai solusi bidang patahan.
Mekanisme fokus berasal dari solusi momen tensor gempabumi, yang
dapat diperkirakan dari analisis gelombang seismik teramati.
Saat terjadi gempabumi, terjadi pelepasan energi yang menyebar
keseluruh bagian bumi. Mekanisme fokus dapat diturunkan dengan
mengamati pola gerakan pertama (first motion) gempabumi. Yaitu,
apakah gelombang-P yang tiba tercatat pertama kali pada
seismometer berupa puncak atau lembah. Dalam hal ini, energi yang
tersebar oleh gempa akibat sesar membagi bumi menjadi empat bagian
(Butler, diakses 14 Mei 2017). Perbedaan first motion ini disebabkan
karena posisi stasiun terhadap sumber gempabumi.
Dalam pembuatan mekanisme fokus, Gelombang-P yang tercatat
dari berbagai stasiun di dunia dikumpulkan. Lalu gelombang-P
dibedakan berdasarkan pola first motion-nya. Dalam contoh ini,
gelombang-P yang tiba di stasiun sebagai puncak disimbolkan dengan
bulatan hitam. Sedangkan gelombang-P yang tiba pada stasiun sebagai

38
lembah disimbolkan dengan bulatan putih. Sedangkan pada kasus
bentuk gelombang tiba yang diragukan disimbolkan dengan (x).
Solusi mekanisme fokus biasanya ditampilkan secara grafis
menggunakan diagram beachball. Pola energi radiasi selama
gempabumi dengan satu arah gerakan pada satu bidang patahan dapat
dimodelkan sebagai kopel ganda, yang digambarkan secara matematis
sebagai kasus khusus dari sebuah tensor urutan kedua (sama dengan
tegangan dan regangan) yang dikenal sebagai momen tensor.
Berikut ini adalah cara sangat sederhana membuat diagram
beachball
Gambar 2.17. Cara pembuatan mekanisme fokus (Cronin, 2004)
Intinya, jika lingkaran tersebut dibagi 4 kuadran, maka bagian
paling atas adalah utara. Kalaupun tidak dibagi menjadi 4 kuadran,
maka bagian atas adalah utara. Biasanya, tensor selalu berwarna gelap.
Jadi jika ada 4 kuadran dengan warna gelap terang selang seling maka
itu adalah sesar geser. Jika lingkaran tersebut dibagi menjadi tiga
bagian, dan di tengah berwarna gelap, maka itu adalah sesar naik.
Sta gel-P Simbol Sta gel-P Simbol Sta gel-P Simbol

39
Begitu juga sebaliknya, jika di tengah warna terang, maka itu adalah
sesar turun.
Gambar 2.18. Mekanisme Fokus untuk gempabumi dengan jenis sesar (dari kiri):
sesar geser, sesar naik dan sesar normal/turun (Stein, 2005)

40
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian : 27 Maret 2017 s.d. 31 Agustus 2017
Tempat penelitian : Stasiun Geofisika Kelas 1 Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta.
3.2. Alat dan Bahan
A. Alat Penelitian
a. Komputer
b. Seperangkat SeisComP3
c. Buku catatan
Gambar 3.1. Alat Penelitian: (a) lokasi sensor, (b) rekaman gelombang oleh sensor,
(c) pengolahan data kejadian gempabumi, (d) rekaman data kejadian gempabumi
(a) (b) (c) (d)

41
B. Bahan Penelitian
a. Tanggal terjadi gempa f. Longitude
b. Bulan terjadi gempa g. Latitude
c. Tahun terjadi gempa h. Magnitudo
d. Original time i. Stasiun pencatat gempa
e. Kedalaman j. Polarisasi gelombang-P
3.3. Prosedur Penelitian
Pada penulisan data ini yang digunakan adalah fase awal gelombang-
P yang tercatat di stasiun BMKG dari gempabumi terasa yang terjadi di
Selatan Jawa periode Oktober 2016 s.d. Maret 2017 dengan 31 kejadian
(Inatews BMKG, diakses 15 April 2017).
1. Kejadian Gempabumi 11 Oktober 2016, Pusat gempa berada di laut 79
km Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Dirasakan di Pacitan III MMI,
Bantul II MMI, Nganjuk II MMI.
Tabel 3.1. Data gempabumi kejadian 1
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
7:34:01 8.52' S 111.18' E 25 4.7
Stasiun
PWJI epc KRK epc SMRI epc
TBJI epc JAGI epc KMMI epc

42
2. Kejadian Gempabumi 11 Oktober 2016, Pusat gempa berada di laut 64
km Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Dirasakan di Pacitan II MMI.
Tabel 3.2. Data gempabumi kejadian 2
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
11:52:44 8.44' S 111.21' E 36 4.3
Stasiun
PWJI epc UGM epc NGJI epc SMRI epc
TBJI epc JAGI epd KMMI epd
3. Kejadian Gempabumi 23 Oktober 2016, Pusat gempa berada di laut 67
km Baratdaya Garut, Jawa Barat. Dirasakan di Bandung II MMI.
Tabel 3.3. Data gempabumi kejadian 3
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
5:44:49 8.05' S 107.35' E 67 4.9
Stasiun
CNJI epd LEM epc SKJI epd CBJI epc SMRI epd
BLSI epc PCJI epd KASI epc TBJI epd
4. Kejadian Gempabumi 23 Oktober 2016, Pusat gempa berada di laut 81
km Baratdaya Garut, Jawa Barat. Dirasakan di Bandung, Garut,
Sukabumi, Tasikmalaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan Soreang II–
III MMI.

43
Tabel 3.4. Data gempabumi kejadian 4
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
12:45:46 7.54' S 107.04' E 35 4.8
Stasiun
SKJI epc CBJI epc LEM epc JCJI epc SBJI epc
UGM epc KASI epc PCJI epc LWLI epc
5. Kejadian Gempabumi 4 November 2016, Pusat gempa berada di darat
45 km Baratlaut Madiun, Jawa Timur. Dirasakan di Madiun,
Trenggalek, Yogyakarta, Magetan dan Ngawi III MMI.
Tabel 3.5. Data gempabumi kejadian 5
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
12:08:07 7.33' S 111.18' E 19 4.9
Stasiun
NGJI epd UGM epc SMRI epc YOGI epc KRK epd
GMJI epd KMMI epd ABJI epd JAGI epd PBKI epd
6. Kejadian Gempabumi 6 November 2016, Pusat gempa berada di darat
15 km Baratdaya Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dirasakan di Jakarta
II MMI.

44
Tabel 3.6. Data gempabumi kejadian 6
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
6:44:14 7.15' S 107.32' E 10 4.2
Stasiun
CNJI epc CBJI epd JCJI epc
SKJI epd SBJI epd SMRI epd
7. Kejadian Gempabumi 8 November 2016, Pusat gempa berada di laut
271 km Baratdaya Lebak, Banten. Dirasakan di Pangalengan III MMI.
Tabel 3.7. Data gempabumi kejadian 7
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
4:31:23 8.21' S 104.35' E 10 6
Stasiun
SKJI epc SBJI epd CNJI epc KASI epd BLSI epd
LWLI epd KLI epd JCJI epc PMBI epd YOGI epc
UGM epd SMRI epd PPBI epd JMBI epd TBJI epc
KRK epc DSRI epd PBKI epc TPRI epd KMMI epc
JAGI epd MNSI epd IGBI epc DNP epd BBKI epc
8. Kejadian Gempabumi 11 November 2016, Pusat gempa berada di laut
83 km Baratdaya Lebak, Banten. Dirasakan di Pelabuhan Ratu II MMI.

45
Tabel 3.8. Data gempabumi kejadian 8
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
11:05:39 7.19' S 106.11' E 29 4.5
Stasiun
SKJI epd SBJI epc BLSI epc KASI epc
KLI epc LWLI epc KSI epc PPBI epc
9. Kejadian Gempabumi 11 November 2016, Pusat gempa berada di laut
89 km Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Dirasakan di Yogyakarta III
MMI, Pacitan II-III MMI.
Tabel 3.9. Data gempabumi kejadian 9
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
15:15:31 8.58' S 111.19' E 10 5.1
Stasiun
PCJI epd PWJI epd UGM epc KRK epc
YOGI epc SMRI epc TBJI epc JAGI epc
KMMI epc IGBI epc JCJI epc CNJI epc
CBJI epc PBKI epc BBKI epc KSI epc
10. Kejadian Gempabumi 11 November 2016, Pusat gempa berada di laut
96 km Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Dirasakan di Yogyakarta, Bantul,
Tulung Agung, Magelang dan Pacitan III MMI.

46
Tabel 3.10. Data gempabumi kejadian 10
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
7:26:44 9.02' S 111.17' E 10 5.2
Stasiun
PCJI epd KRK epc UGM epc SMRI epc GRJI epc
JAGI epc KMMI epc PWJI epc IGBI epc
CBJI epc SKJI epc KASI epc PPBI epc
11. Kejadian Gempabumi 15 November 2016, Pusat gempa berada di laut
74 km Tenggara Cilacap, Jawa Tengah. Dirasakan di Yogyakarta dan
Bantul II MMI.
Tabel 3.11. Data gempabumi kejadian 11
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
19:41:10 8.22' S 109.12' E 10 4.7
Stasiun
YOGI epd UGM epc SMRI epd PCJI epc CNJI epc
NGJI epd GRJI epc GMJI epd JAGI epc
12. Kejadian Gempabumi 18 November 2016, Pusat gempa berada di laut
93 km Baratdaya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dirasakan di Yogyakarta, Klaten, Bantul, Sleman dan Gunung Kidul I-
II MMI.

47
Tabel 3.12. Data gempabumi kejadian 12
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
9:19:29 8.52' S 110.34' E 10 5.3
Stasiun
PCJI epd UGM epc YOGI epc SWJI epd NGJI epd
SMRI epc KRK epd GRJI epd GMJI epc
JCJI epc LEM epc JAGI epd BWJI epd
CNJI epc KMMI epd ABJI epd SBJI epc
13. Kejadian Gempabumi 15 Desember 2016, Pusat gempa berada di laut
64 km Baratdaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirasakan di
Tasikmalaya II-III MMI.
Tabel 3.13. Data gempabumi kejadian 13
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
23:58:31 8.11' S 107.54' E 22 4.8
Stasiun
CNJI epc LEM epd JCJI epd CBJI epc
UGM epc SMRI epd PCJI epc UWJI epd
SWJI epd PWJI epc GWJI epd

48
14. Kejadian Gempabumi 3 Januari 2017, Pusat gempa berada di laut 133
km Tenggara Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dirasakan di
Kebumen II-III MMI.
Tabel 3.14. Data gempabumi kejadian 14
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
4:02:25 8.53' S 108.43' E 10 5.1
Stasiun
KPJI epc YOGI epc UGM epc JCJI epd CNJI epc
LEM epd SMRI epc NGJI epd PWJI epc SWJI epc
UWJI epc GRJI epc GMJI epc JAGI epc KASI epc
ABJI epc BYJI epc LWLI epc MDSI epd PPBI epd
15. Kejadian Gempabumi 4 Januari 2017, Pusat gempa berada di laut 62 km
Tenggara Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirasakan di
Tasikmalaya II-III MMI, Monanjaya I-II MMI.
Tabel 3.15. Data gempabumi kejadian 15
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
16:08:41 8.12' S 108.18' E 31 4.2
Stasiun
KPJI epd CNJI epd JCJI epd YOGI epc CBJI epd
SKJI epd UGM epc SMRI epd PWJI epc

49
16. Kejadian Gempabumi 13 Januari 2017, Pusat gempa berada di laut 74
km Tenggara Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dirasakan di Sukabumi II-III
MMI.
Tabel 3.16. Data gempabumi kejadian 16
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
2:45:00 7.36' S 106.57' E 18 4.6
Stasiun
CNJI epc SKJI epc CBJI epc SBJI epd KASI epd
SMRI epd LWLI epd MDSI epd ABJI epd DSRI epd
17. Kejadian Gempabumi 13 Januari 2017, Pusat gempa berada di darat 14
km Tenggara Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirasakan di Bantul
III MMI, Yogyakarta II MMI.
Tabel 3.17. Data gempabumi kejadian 17
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
21:24:59 7.60' S 110.25' E 10 3.6
Stasiun
UGM epd YOGI epc SMRI epd NGJI epc
UWJI epd KRK epc BCJI epc CNJI epd

50
18. Kejadian Gempabumi 23 Januari 2017, Pusat gempa berada di laut 210
km Baratdaya Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dirasakan di Sukabumi II
MMI.
Tabel 3.18. Data gempabumi kejadian 18
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
13:12:15 8.30' S 105.52' E 10 5.1
Stasiun
SKJI epc CNJI epd SBJI epc LEM epd
KASI epc KPJI epd MDSI epc UGM epc
SMRI epd UWJI epd GMJI epc JAGI epc
19. Kejadian Gempabumi 27 Januari 2017, Pusat gempa berada di laut 117
km Selatan Sukabumi, Jawa Barat. Dirasakan di Pangandaran II-III
MMI.
Tabel 3.19. Data gempabumi kejadian 19
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
0:50:10 7.58' S 107.01' E 14 4.9
Stasiun
CNJI epd SKJI epc JCJI epd KPJI epc SBJI epc
BLSI epc KASI epd SMRI epc KLI epd
MDSI epd SWJI epc PWJI epc PPBI epc

51
20. Kejadian Gempabumi 29 Januari 2017, Pusat gempa berada di laut 166
km Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dirasakan di Malang II
MMI.
Tabel 3.20. Data gempabumi kejadian 20
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
18:57:24 9.44' S 112.52' E 10 4.9
Stasiun
GMJI epc KRK epc JAGI epd PWJI epd BLJI epc
BYJI epc SWJI epd ABJI epc DNP epc NGJI epd
GRJI epc UGM epd SMRI epd KPJI epd
21. Kejadian Gempabumi 8 Februari 2017, Pusat gempa berada di laut 126
km Baratdaya Lumajang, Jawa Timur. Dirasakan di Malang, Jember,
Blitar, Trenggalek, Nusa Dua dan Tabanan III MMI, Kuta II MMI.
Tabel 3.21. Data gempabumi kejadian 21
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
0:21:49 8.31' S 113.07' E 10 4.9
Stasiun
GMJI epd JAGI epc BYJI epc PWJI epd
SWJI epd BRJI epd NGJI epd DNP epc
BWJI epd UWJI epd SMRI epd KPJI epd

52
22. Kejadian Gempabumi 8 Februari 2017, Pusat gempa berada di laut 79
km Baratdaya Sukabumi, Jawa Barat. Dirasakan di Cianjur III-IV MMI,
Bandung III MMI, Lembang III MMI, Sukabumi III MMI, Bogor I-II
MMI.
Tabel 3.22. Data gempabumi kejadian 22
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
15:34:16 7.38' S 106.54' E 25 5.2
Stasiun
CNJI epc LEM epc JCJI epc SBJI epd KASI epd
SMRI epc LWLI epd MDSI epd SWJI epc JAGI epd
23. Kejadian Gempabumi 13 Februari 2017, Pusat gempa berada di laut 33
km Tenggara Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirasakan di
Tasikmalaya II MMI.
Tabel 3.23. Data gempabumi kejadian 23
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
15:12:47 7.56' S 108.14' E 49 5.2
Stasiun
KPJI epc JCJI epc CNJI epd YOGI epd UGM epd
SMRI epc UWJI epc NGJI epd SWJI epd PWJI epd
BLSI epd GRJI epc KASI epd KLI epd GMJI epd

53
24. Kejadian Gempabumi 16 Februari 2017, Pusat gempa berada di laut 66
km Baratdaya Garut, Jawa Barat. Dirasakan di Bandung, Pengalengan,
Pelabuhan Ratu, Ciamis, Pangandaran dan Tasikmalaya II-III MMI.
Tabel 3.24. Data gempabumi kejadian 24
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
1:53:35 7.50' S 107.16' E 19 5.1
Stasiun
CNJI epd JCJI epd KPJI epc SBJI epc
BLSI epc SMRI epc SWJI epc
25. Kejadian Gempabumi 19 Februari 2017, Pusat gempa berada di laut 49
km Baratdaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirasakan di
Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran dan Garut III-IV MMI.
Tabel 3.25. Data gempabumi kejadian 25
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
22:39:41 8.05' S 108.01' E 10 4.8
Stasiun
CNJI epd KPJI epd JCJI epd YOGI epc UGM epd
SMRI epd UWJI epd NGJI epc SWJI epc
KASI epc MDSI epc PPBI epc ABJI epc

54
26. Kejadian Gempabumi 10 Maret 2017, Pusat gempa berada di laut 132
km Barat Pelabuhan Ratu, Banten. Dirasakan di Panimbang II-III MMI,
Cibaliung II-III MMI, Pandeglang I-II MMI.
Tabel 3.26. Data gempabumi kejadian 26
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
23:33:14 7.08' S 105.22' E 10 4.7
Stasiun
SBJI epc CBJI epc CNJI epd BLSI epd
KASI epc LWLI epc JCJI epc MDSI epc
PMBI epd PPBI epc PWJI epd
27. Kejadian Gempabumi 14 Maret 2017, Pusat gempa berada di laut 68 km
Selatan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Dirasakan di Pelabuhan Ratu,
Cicurug, Bogor dan Sukabumi III-IV MMI.
Tabel 3.27. Data gempabumi kejadian 27
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
9:51:08 7.35' S 106.41' E 29 4.9
Stasiun
CNJI epd CBJI epd SBJI epd JCJI epd KPJI epc
BLSI epc KASI epc KLI epd MDSI epc
PMBI epd PWJI epc GMJI epd ABJI epc

55
28. Kejadian Gempabumi 15 Maret 2017, Pusat gempa berada di laut 56 km
Baratdaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirasakan di
Pangandaran, Garut dan Pelabuhan Ratu II-III MMI.
Tabel 3.28. Data gempabumi kejadian 28
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
9:26:54 8.06' S 107.55' E 24 4.9
Stasiun
CNJI epc JCJI epd CBJI epc UGM epc SMRI epd
SWJI epc TBJI epc KASI epc GRJI epc
MDSI epc BLJI epd PPBI epd DSRI epd
29. Kejadian Gempabumi 18 Maret 2017, Pusat gempa berada di laut 61 km
Baratdaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirasakan di Sukabumi
dan Pelabuhan Ratu II-III MMI, Bandung Barat I-II MMI.
Tabel 3.29. Data gempabumi kejadian 29
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
23:56:39 8.08' S 107.52' E 10 5
Stasiun
CNJI epd JCJI epd CBJI epc UGM epc SMRI epd
SWJI epc TBJI epc KASI epc GRJI epc
MDSI epc BLJI epd PPBI epd DSRI epd

56
30. Kejadian Gempabumi 23 Maret 2017, Pusat gempa berada di laut 48 km
Baratdaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirasakan di
Tasikmalaya, Soreang, Pangalengan dan Garut II-III MMI, Banjar II
MMI.
Tabel 3.30. Data gempabumi kejadian 30
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
21:35:35 8.01' S 107.55' E 10 5
Stasiun
CNJI epd KPJI epd JCJI epd YOGI epc
UGM epc SBJI epd SMRI epd SWJI epc
PWJI epc KASI epd LWLI epd
31. Kejadian Gempabumi 26 Maret 2017, Pusat gempa berada di laut 51 km
Baratdaya Kabupaten Tasimalaya, Jawa Barat. Dirasakan di
Tasikmalaya I-II MMI.
Tabel 3.31. Data gempabumi kejadian 31
Jam (WIB) Lintang Bujur H (km) M (SR)
9:00:16 8.03' S 107.55' E 20 4.4
Stasiun
CNJI epd KPJI epd JCJI epd CBJI epd SKJI epc
SMRI epd NGJI epc SWJI epc PWJI epc

57
Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam proses pengolahan data
gempabumi menggunakan perangkat lunak SeisComP3, yaitu:
a. Pada tampilan layar (d), pilih tab Events (e). Kemudian atur
rentang waktu penelitian pada pojok kanan bawah (f), lalu pilih
Read (g). Kemudian akan muncul data gempabumi pada periode
waktu yang telah ditentukan tersebut (Gambar 3.2).
Gambar 3.2. Menentukan periode penelitian: (e) tab event, (f) rentang waktu rekaman,
(g) menampilkan data kejadian gempabumi
b. Memilih kejadian gempa yang akan dianalisa, klik kiri sehingga
muncul titik data gempabumi pada tab Summary (h). Pilih Show
Details (i) untuk membuka data gempabumi pada kejadian
tersebut (Gambar 3.3).
c. Pada layar (c) akan muncul data gempabumi dari kejadian terpilih.
Pada tab First Motion (j), pilih Picker (k) untuk menentukan jenis
gelombang-P yang diterima oleh tiap stasiun (Gambar 3.4).
(e)
(f) (g)

58
Gambar 3.3. Menampilkan data kejadian gempabumi: (h) tab summary, (i) menampilkan detail
Gambar 3.4. Memulai Picker: (j) tab first motion, (k) memulai picking gerak awal gelombang-P
d. Pada tampilan berikutnya pilih 'P' kemudian menentukan jenis
gelombang-P pada tiap-tiap stasiun. Klik kiri dua kali pada gerak
awal gelombang-P, kemudian klik kanan dan tentukan jenis
gelombang-P tersebut. Lakukan pada setiap stasiun pencatat
gempa (Gambar 3.5).
(h)
(i)
(j)
(k)

59
Gambar 3.5. Analisa jenis gelombang-P pada tiap stasiun pencatat kejadian gempabumi
e. Setelah menentukan jenis gelombang-P pada setiap stasiun, pilih
Apply (ikon bulat merah) untuk memasukkan data hasil
pengolahan di atas.
Gambar 3.6. Relokasi jenis golambang P pada beachball serta hasil mekanisme fokus kejadian
gempabumi: (l) tab first motion, (m) relokasi posisi stasiun terhadap pusat gempabumi, (n) hasil
mekanisme focus, (o) data bidang nodal dari beachball
f. Tampilan akan kembali ke layar sebelumnya. Masih pada tab First
Motion (l), klik Relocate (m) di pojok kiri bawah, lalu analisa
(l)
(m)
(n)
(o)

60
bentuk Mekanisme Fokus pada beachball (n) sesuai dengan hasil
Picking sebelumnya (Gambar 3.6).
g. Hasil beachball (n) tersebut (Gambar 3.6), dianalisa bentuk
mekanisme fokus pada kejadian gempa dipilih. Selain itu, di pojok
kanan atas (o) terdapat data nodal plane (NP1 dan NP2). Bidang
nodal tertulis secara berturut-turut NP1: Sudut Strike/ Dip/ Rake.
3.4. Diagram Alir
Gambar 3.7. Diagram alir pengolahan data gempabumi
Menentukan jenis gelombang-P (Picking)
Bentuk diagram
beachball
Tidak
MULAI
Data Gempabumi
Load data
Relocate
Ya
Analisa
SELESAI

61
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Studi mengenai sesar gempabumi terasa di Selatan Jawa ini
menggunakan metode mekanisme fokus pada kejadian-kejadian gempabumi
periode Oktober 2016 s.d. Maret 2017. Data yang digunakan adalah data
kejadian gempabumi terasa yang tercatat di Stasiun Geofisika Kelas I
Yogyakarta, diolah dengan perangkat SeisComP3. Parameter yang digunakan
meliputi waktu kejadian (origin time), lokasi kejadian (lintang dan bujur),
kedalaman, kekuatan gempa (magnitudo) serta polaritas gelombang-P yang
terekam pada tiap stasiun seismik. Gempabumi terasa di Selatan Jawa
sepanjang periode penelitian tercatat ada 31 kejadian. Kisaran magnitudo
kejadian-kejadian gempabumi tersebut berada pada rentang 3.5 SR s.d. 6 SR.
Gambar 4.1. Peta persebaran gempabumi terasa di Selatan Jawa

62
Berdasarkan data yang diperoleh dari pusat data BMKG, 31 kejadian
gempabumi terasa di Selatan Jawa memiliki intensitas antara 2 s.d. 4 MMI.
Tabel 4.1. Data gempabumi terasa di Selatan Jawa periode Oktober 2016 s.d. Maret 2017
WAKTU
(WIB) LOKASI
M
(SR)
H
(km)
BIDANG NODAL
(strike/dip/rake) DIAGRAM
2016-10-11
7:34:01
8.87 LS,
111.30 BT
4.7 25 NP1: 83/61/89
NP2: 266/29/93
2016-10-11
11:52:44
8.73 LS,
111.35 BT
4.3 36 NP1: 130/85/3
NP2: 40/87/175
2016-10-23
5:44:49
8.08 LS,
107.59 BT
4.9 67 NP1: 177/29/88
NP2: 359/61/91
2016-10-23
12:45:46
7.90 LS,
107.06 BT
4.8 35 NP1: 143/62/88
NP2:326/28/93
2016-11-04
12:08:07
7.55 LS,
111.30 BT
4.9 19 NP1: 150/53/-88
NP2: 326/37/-93
2016-11-06
6:44:14
7.25 LS,
107.54 BT
4.2 10 NP1: 352/89/1
NP2: 262/89/179
2016-11-08
4:31:23
8.35 LS,
104.59 BT
6.0 10 NP1: 93/41/91
NP2: 272/49/89
2016-11-09
11:05:39
7.31 LS,
106.19 BT
4.5 29 NP1: 111/45/46
NP2: 344/59/124
2016-11-10
15:15:31
8.96 LS,
111.31 BT
5.1 10 NP1: 105/58/90
NP2: 285/32/90
2016-11-11
7:26:44
9.03 LS,
111.29 BT
5.2 10 NP1: 132/57/91
NP2: 311/33/89

63
Tabel 4.1. (Lanjutan)
WAKTU
(WIB) LOKASI
M
(SR)
H
(km)
BIDANG NODAL
(strike/dip/rake) DIAGRAM
2016-11-15
19:41:10
8.36 LS,
109.22 BT
4.7 10 NP1: 86/40/78
NP2: 282/51/100
2016-11-18
9:19:29
8.87 LS,
110.57 BT
5.3 10 NP1: 108/88/1
NP2: 18/89/178
2016-12-15
23:58:31
8.18 LS,
107.90 BT
4.8 22 NP1: 274/78/26
NP2: 178/64/167
2017-01-03
4:02:25
8.88 LS,
108.72 BT
5.1 10 NP1: 196/48/-48
NP2: 323/56/-127
2017-01-04
4:02:25
8.19 LS,
108.30 BT
4.2 31 NP1: 84/16/92
NP2: 261/74/89
2017-01-13
2:45:00
7.60 LS,
106.94 BT
4.6 18 NP1: 113/55/-90
NP2: 294/35/-89
2017-01-13
21:24:59
7.99 LS,
110.41 BT
3.6 10 NP1: 174/34/-140
NP2: 50/69/63
2017-01-23
13:12:15
8.50 LS,
105.87 BT
5.1 10 NP1: 142/45/90
NP2: 32245/90
2017-01-27
0:50:10
7.97 LS,
107.01 BT
4.9 14 NP1: 177/58/123
NP2: 306/45/49
2017-01-29
18:57:24
9.73 LS,
112.87 BT
4.9 10 NP1: 88/42/-111
NP2: 296/51/-72
2017-02-08
0:21:49
8.52 LS,
113.11 BT
4.9 10 NP1: 77/80/90
NP2: 256/10/90

64
Tabel 4.1. (Lanjutan)
WAKTU
(WIB) LOKASI
M
(SR)
H
(km)
BIDANG NODAL
(strike/dip/rake) DIAGRAM
2017-02-08
15:34:16
7.64 LS,
106.90 BT
5.2 25 NP1: 91/89/-179
NP2: 1/89/-1
2017-02-13
15:12:47
7.94 LS,
108.24 BT
5.2 49 NP1: 350/90/0
NP2: 80/90/-180
2017-02-16
1:53:35
7.83 LS,
107.26 BT
5.1 19 NP1: 110/47/90
NP2: 290/43/90
2017-02-19
22:39:41
8.08 LS,
108.01 BT
4.8 10 NP1: 158/46/120
NP2: 298/51/62
2017-03-10
23:33:14
7.13 LS,
105.36 BT
4.7 10 NP1: 303/56/-154
NP2: 198/69/-37
2017-03-14
9:51:08
7.59 LS,
106.69 BT
4.9 29 NP1: 276/70/27
NP2: 176/65/157
2017-03-15
9:26:54
8.10 LS,
107.91 BT
4.9 24 NP1: 150/68/-157
NP2: 51/69/-23
2017-03-18
23:56:39
8.13 LS,
107.86 BT
5.0 10 NP1: 110/36/90
NP2: 290/54/90
2017-03-23
21:35:35
8.02 LS,
107.91 BT
5.0 10 NP1: 58/77/-89
NP2: 235/13/-93
2017-03-26
9:00:16
8.05 LS,
107.91 BT
4.4 20 NP1: 107/29/91
NP2: 286/61/90
Sumber: BMKG

65
4.2. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola sesar di Selatan
Jawa. Pola sesar pada kejadian gempabumi dapat digambarkan menggunakan
mekanisme fokus. Penentuan jenis bidang sesar dapat dilakukan
menggunakan 2 cara, yaitu menghitung momen tensor dari kejadian
gempabumi dan mengamati gerak awal gelombang-P. Momen tensor
digunakan untuk menggambarkan arah gaya penyebab gempabumi, sehingga
dari inversi momen tensor dapat diketahui mekanisme fokus suatu kejadian
gempabumi (Madrinovella, 2013). Gerak awal gelombang-P yang tercatat
oleh seismometer dapat berupa puncak atau lembah. Posisi stasiun dan jenis
gerak awal gelombang-P terekam dapat digunakan untuk menggambarkan
mekanisme fokus gempabumi dengan membuat garis bidang nodal (bidang
bantu) sehingga terbentuk diagram beachball (Butler, diakses 14 Mei 2017).
Hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak SeisComP3
menampilkan bentuk sesar pada gempabumi terasa di Selatan Jawa yang
sangat variatif. Hal ini di sebabkan oleh tatanan geologi Pulau Jawa yang unik.
Bentuk patahan pada kejadian gempabumi di Selatan Jawa berupa sesar naik,
sesar turun dan beberapa sesar geser.
Pulau Jawa di dominasi oleh zona subduksi yang disebabkan oleh
batas lempeng konvergen. Gempabumi di Selatan Jawa sendiri merupakan
gempabumi yang disebabkan oleh penunjaman lempeng Australia yang

66
merupakan lempeng samudera terhadap lempeng Eurasia yang merupakan
lempeng benua.
Gempabumi terasa di Selatan Jawa pada periode Oktober 2016 s.d.
Maret 2017 memiliki kekuatan yang beragam mulai dari 3 SR s.d. 6 SR.
BMKG mencatat bahwa kejadian-kejadian gempabumi pada periode
penelitian ini memiliki intensitas mulai dari II s.d. IV MMI. Jumlah kejadian
gempabumi pada penelitian ini adalah 31 kejadian dengan 3 kejadian berupa
gempa daratan dan sisanya merupakan gempa lautan. Gempabumi terasa di
Selatan Jawa di dominasi oleh gempa dangkal, yaitu gempabumi dengan
kedalaman kurang dari 60 km. Keseluruhan dari gempabumi tersebut
merupakan gempa tektonik, yaitu gempa yang mengiringi gerakan tektonik
lempeng yang menghasilkan suatu patahan (fault).
Penelitian ini membagi daerah gempabumi Selatan Jawa menjadi 4
zona. Zona 1 merupakan zona palung laut di mana sumber gempabumi berada
di daerah palung laut yang ada di Selatan Jawa. Zona 2 merupakan zona
subduksi barat di mana gempabumi terjadi di zona subduksi Pulau Jawa
sebelah barat. Daerah ini adalah daerah yang memiliki seismisitas paling aktif
dibanding zona lain. Zona 3 merupakan daerah subduksi Pulau Jawa sebelah
timur. Sedangkan zona 4 adalah daerah daratan Pulau Jawa.
Pola bidang sesar pada kejadian gempabumi terasa di daerah palung
laut Selatan Jawa ditunjukkan oleh gambar 4.2, di mana pada sisi barat
terdapat bidang sesar dengan jenis sesar naik, dengan arah tegak lurus

67
terhadap arah palung laut. Sedangkan pada sisi timur bidang sesar berupa
sesar normal dominan dengan sedikit sesar geser. Kedalaman gempa di zona
ini merata pada kedalaman 10 km.
Gambar 4.2. Pola sesar pada area palung laut Selatan Jawa
Zona subduksi Selatan Jawa bagian barat merupakan daerah dengan
seismisitas paling aktif dibanding daerah lain di Selatan Jawa. Hal ini
ditunjukkan oleh dominasi gempabumi yang terlokalisasi di area tersebut.
Pola bidang sesar yang terbentuk pada kedalaman kurang dari 20 km
didominasi oleh sesar naik dengan arah patahan tegak lurus terhadap
bentangan subduksi Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan oleh adanya 4 kejadian
gempabumi yang memiliki patahan berupa sesar turun dengan arah tegak
lurus terhadap bentang subduksi Pulau Jawa. Namun demikian ada juga
gempabumi dengan jenis patahan berupa sesar turun dominan terhadap sesar
geser pada kejadian 26, serta sesar turun pada kejadian 16 dan 30.

68
Gambar 4.3. Pola sesar di zona subduksi Selatan Jawa bagian barat. Ο: kedalaman 10-20 km.
Ο: kedalaman 21-40 km. Ο: kedalaman 41-70 km.
Patahan berupa sesar geser dominan terjadi pada kedalaman 21 s.d. 40
km. Arah dari pergeseran patahan tegak lurus terhadap bentangan subduksi
Pulau Jawa. Gempabumi pada kedalaman 41-70 km terdapat pada 2 kejadian,
yaitu gempabumi yang berpusat di Baratdaya Garut dan Tenggara
Tasikmalaya. Jenis patahan pada kedua kejadian tersebut berupa sesar naik
yang berupa lempeng barat menunjam ke lempeng timur, dan sesar geser yang
disebabkan oleh lempeng utara bergeser terhadap lempeng selatan.
Zona 3 merupakan daerah gempabumi yang berada di area subduksi
Pulau Jawa bagian timur. Gempabumi di area ini memiliki kekuatan kurang
lebih 5 SR dengan kedalaman 10 km s.d. 36 km. Area gempabumi pada
subduksi Pulau Jawa bagian timur didominasi oleh jenis patahan berupa sesar
naik. Pada periode Oktober 2016 s.d. Maret 2017 terdapat 8 kejadian
gempabumi terasa di zona 3. Dominasi sesar naik terlihat jelas dengan adanya

69
6 dari 8 kejadian gempabumi terasa di semua kedalaman. Dua kejadian lain
berupa sesar geser yang ada pada kejadian 2 dan kejadian 12. Arah patahan
pada semua kejadian gempabumi terasa di zona ini mengikuti bentang
subduksi Pulai Jawa, yaitu tegak lurus terhadap bentangan subduksi Pulau
Jawa.
Gambar 4.4. Pola sesar di zona subduksi Selatan Jawa bagian timur. Ο: kedalaman 10-20 km.
Ο: kedalaman 21-40 km.
Zona 4 merupakan daerah daratan Jawa. Gempabumi terasa di daratan
jawa pada periode penelitian ini hanya terdapat 3 kejadian. Tiga kejadian
tersebut memiliki kedalaman di bawah 20 km. Pola bidang sesar yang
terbentuk berupa sesar naik pada kejadian gempabumi terasa di Baratlaut
Madiun, sesar turun dominan terhadap sesar geser pada gempabumi terasa di
Bantul dan sesar geser pada kejadian gempabumi di Kabupaten Bandung.
Kegempaan di daratan Jawa diidentifikasi sebagai sesar turun dan geser.

70
Gambar 4.5. Pola sesar pada zona daratan Pulau Jawa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sesar di Selatan Jawa
bergantung pada letak dan kedalamannya. Gempabumi di area palung laut
Selatan Jawa yang memiliki kedalaman seragam juga memiliki pola patahan
yang seragam, di mana pada bagian luar palung membentuk patahan naik dan
di bagian dalam palung membentuk patahan turun.
Bentangan subduksi yang memiliki kedalaman kurang dari 20 km
membentuk pola patahan yang didominasi oleh patahan naik. Hal ini
disebabkan oleh adanya tumbukan lempeng konvergen di area tersebut.
Gempabumi dengan kedalaman lebih dari 20 km menunjukkan pola patahan
yang berupa sesar geser. Arah dari patahan-patahan di area subduksi
cenderung tegak lurus terhadap bentangan subduksi. Zona subduksi Pulau
Jawa membentang dari barat ke timur (atau sebaliknya), sedangkan pola

71
patahan-patahan yang ada memiliki arah yang tegak lurus terhadap bentangan
subduksi Pulau Jawa, yaitu dari arah utara-selatan.
Gempabumi terasa di daratan Jawa hanya terdapat 3 kejadian. Tentu
saja data ini tidak cukup untuk menjelaskan pola kegempaan di daratan Jawa.
Namun dari data yang ada, tiga kejadian tersebut memiliki pola patahan
berupa sesar geser di Jawa Barat, sesar geser dengan dominan sesar turun di
Yogyakarta, serta sesar turun di Jawa Timur.
Menurut Omer Aydan gap seismik di Indonesia berjumlah 8 titik.
Lokasi gap seismik di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.2. Berdasarkan
peta tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Selatan Jawa memiliki dua titik
gap seismik, yaitu daerah Selat Sunda dan Yogyakarta. Tidak seperti Aceh
yang telah melepaskan seluruh energinya pada tahun 2004 silam, gempabumi
di Yogyakarta 11 tahun yang lalu belum mencapai batas maksimal energi
yang dapat dikeluarkan oleh lempeng aktif di selatan Yogyakarta. Artinya
bahwa gempa berkekuatan besar masih mungkin terjadi di Yogyakatarta.
Data gempabumi terasa di Selatan Jawa periode Oktober 2016 s.d.
Maret 2017 juga menunjukkan bahwa tidak ada kejadian gempabumi di area
gap seismik selatan Yogyakarta. Dua kejadian gempabumi terasa terekam
pada lokasi gap seismik Selat Sunda dengan kekuatan 5.1 SR dan 6 SR,
merupakan gempabumi paling kuat di antara kejadian-kejadian lain di dalam
penelitian ini. Gempabumi di selatan Selat Sunda pada 8 November 2016 juga
belum mencapai batas maksimal energi yang dapat dikeluarkan oleh lempeng

72
aktif di Selatan Jawa. Hal ini menjadi kekhawatiran karena gempabumi
berkekuatan besar masih mungkin terjadi di Selatan Jawa.
Kejadian-kejadian gempabumi terasa di Selatan Jawa yang merupakan
gempa tektonik, yaitu gempabumi yang mengiringi gerakan tektonik lempeng
yang menghasilkan suatu patahan, memiliki pola berbeda pada kedalaman
berbeda. Hal ini menunjukkan pola pergerakan lempeng di daerah penelitian
berbeda pada tiap lapisan. Korelasi pergerakan tiap lapisan ini serupa dengan
pergerakan awan di langit, di mana pada ketinggian berbeda memiliki arah
dan kecepatan berbeda.
Terkait gempabumi tektonik, Al-Qur’an meralat dugaan kita tentang
diamnya gunung dengan menyatakan gunung itu bergerak (Purwanto, 2012).
Dalam sebuah ayat yaitu:
سبها ال جبال وترى صن ع الس حاب مر تمر وهي جامدة تح كل أت قن ال ذي للا
ء تف علون بما خبير إن ه شي
Dan engkau melihat gunung-gunung, kau sangka ia tetap di
tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) berjalannya awan. (Begitulah) ciptaan
Allah yang mencipta dengan kokoh segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha
Mengetahui apa yang kau perbuat (QS. An-Naml [27]: 88) (Agama, 2010).
Ayat di atas memberitahukan bahwa gunung-gunung tidaklah diam
sebagaimana kelihatannya, tetapi mereka terus bergerak. Gerakan gunung-
gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi (Yahya, 2004). Thanthawi

73
Jauhari berpendapat sesungguhnya bumi mengelilingi matahari dan gunung
yang membuat berjalan bersamanya. Sekilas kita melihat gunung seakan-akan
gunung itu tidak berjalan, tetapi sesunguhnya gunung itu berjalan seperti
jalannya awan.
Thanthawi Jauhari memahami ayat di atas berbicara tentang keadaan
gunung pada hari sekarang maupun pada hari kemudian, hal ini dijelaskan
ketika Thanthawi Jauhari mengutip kisah Syaikh Junaidi, yaitu ketika salah
satu murid bertanya kepada beliau: '‘apakah tuan tidak mempunyai keinginan
untuk mendengarkan?’ beliau menjawab: ‘dan kamu melihat gunung-gunung
itu kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana
jalannya awan. Dan pada waktunya bumi akan rata karena besarnya letusan
gunung’.
Sepintas membaca cerita tersebut apa yang dilakukan Allah itu adalah
penghancuran dunia pada hari akhir, tetapi di sisi lain Allah memberikan
peringatan dan pelajaran supaya manusia tetap berpikir untuk mengungkap
rahasia yang sangat menajubkan tentang keadaan alam ini. Beliau juaga
mengatakan (Jauhari, 1933):
مستمررة كله حركة العالم أن. ادج سريعا ريا جا جارية الحقيقة فى هي و
Dan gunung pada hakikatnya berjalan sangat cepat. Sesungguhnya
alam seisinya terus bergerak. Hal ini menjelaskan bahwa pada hari akhir
gunung tidak akan lagi berjalan sebagaimana fungsinya, melainkan gunung
akan berjalan sangat cepat sehingga mengakibatkan rotasi bumi tidak

74
beraturan. Thanthawi Jauhari juga menjelaskan bahwa seluruh alam
hakikatnya bergerak di antaranya gunung. Karena pada hakikatnya gunung
berjalan sangat lamban. Pendapat beliau ini sama dengan pendapat Hisham
Thalbah bahwa lempengan-lempengan bumi bergerak secara terus menerus.
Gerakannya lambat, sehingga mata tidak bisa memantaunya secara langsung.
Namun gerakan tersebut dapat dirasakan saat terjadinya gempa bumi,
sebagaimana hal itu dapat diukur melalui alat laser. Dengan alat ini, rata-rata
gerakan bagian dari lempengan-lempengan bumi tersebut dapat dideteksi
yaitu 1 mm/ tahun dan ada yang berpendapat 1 s.d. 12 cm/tahun (Thalbah,
2008).
Sementara itu Tim Badan Geologi juga mengatakan dalam keseharian,
kita merasakan sepertinya bumi diam, tidak bergerak. Pada hakikatnya bumi
yang tersusun dari lempeng benua dan lempeng samudera saling berjalan,
bertumbukan, saling menjauh, atau saling berpapasan. Dan gerakannya
Litosfer untuk memperbaiki ekosistemnya, karena bumi ini dalam orde jutaan
tahun selalu berganti kulit agar harmonisasi kehidupan ini berjalan dengan
baik. Tiap hari gerakannya diwujudkan dengan gempa-gempa yang tak terasa
karena keterbatasan indera manusia, namun bisa direkam dengan alat
seismograf (Geologi, 2002).
Dr. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa dari hasil rekaman satelit
membuktikan Jazirah Arab beserta gunung-gunungnya bergerak mendekati
Iran beberapa sentimeter setiap tahunnya. Jauh sebelum masa kini sekitar lima

75
juta tahun yang lalu Jazirah Arab bergerak memisahkan diri dari Afrika dan
membentuk laut Merah. Di sekitar daerah Somalia sepanjang Pantai Timur ke
Selatan saat ini sedang dalam proses pemisahan yang lamban dan telah
membentuk "Lembah Belah" yang membujur ke Selatan melalui deretan
danau Afrika (Shihab, 2002). Inilah yang dimaksud dengan Thanthawi
Jauhari dalam kisah tentang Junaidi, Sesungguhnya diamnya Syaikh Junaidi
menyerupai gunung yang mana dia sebenarnya bergerak, tetapi manusia
menyangka dia diam, karena manusia melihat dari segi dhahirnya, tetapi
hatinya bergerak dari barat sampai timur.