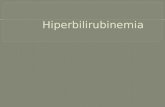BAB I Hiperbilirubinemia
-
Upload
rahmabasri -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
description
Transcript of BAB I Hiperbilirubinemia

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penulisan
1

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Defenisi Hiperbilirubinemia
Merupakan suatu kondisi bayi baru lahir dengan kadar bilirubin serum total lebih dari 10
mg% pada minggu pertama yang ditandai dengan ikterus, yang dikenal dengan ikterus
neonatorum patologis. Hiperbilirubinemia yang merupakan suatu keadaan meningkatnya
kadar bilirubin di dalam jaringan ekstravaskular, sehingga konjungtiva, kulit dan mukosa
akan berwarna kuning. Keadaan tersebut juga berpotensi besar terjadi ikterus, yaitu
kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirek pada otak. Bayi yang mengalami
hiperbilirubinemia memiliki ciri sebagai berikut: adanya ikterus terjadi pada 24 jam pertama,
peningkatan konsentrasi bilirubinserum 10 mg% atau lebih setiap 24 jam, konsentrasi
bilirubin serum 10 mg% pada neonatus yang cukup bulan dan 12.5mg% pada neonatus yang
kurang bulan, ikterus disertai dengan proses hemolisis kemudian ikterus yang disertai dengan
keadaan berat badan lahir kurang dari 2000 gram, masa gestasi kurang dari 36 minggu,
asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan dan lain-lain (A. Aziz Alimun Hidayat;
2011).
2

2.2. Metabolisme Bilirubin
Bilirubin merupakan produk bersifat toksisk yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Sebagian
besar bilirubin tersebut berasal dari degradasi hemoglobin darah dan sebagian lagi dari hem
bebas atau proses eritropoesis yang tidak efektif (
Penumpukan bilirubin merupakan penyebab teradinya kuning pada bayi baru lahir.
Bilirubin meerupakan uraian dari produk protein yang mengandung heme pada sistem
retikuloendotelial. 75% protein yang mengandung heme ada dalam sel darah merah
(hemoglobin) sementara 25% berasal dari mioglobin, sitokrom dan tidak efektifnya
eritropoesis pada sumsum tuang (Indrasanto et al, 2008).
Bilirubin adalah hasil pemecahan sel darah merah. Hemoglobin (Hb) yang berada di
dalam sel darah merah akan dipecah menjadi bilirubin. Satu gram Hb akan menghasilkan 34
mg bilirubin. Bilirubin ini dinamakan bilirubin indirek yang larut dalam lemak, terikat oleh
albumin dan diangkut kedalam hati.di dalam hati biirubin indirek akan dikonjugasi oleh
enzim glukoronil transferase menjadi bilirubin direk yang larut dalam air untuk kemudian
disalurkan melalui saluran empedu ke usus.
Biirubin direk di dalam usus akan terikat oleh makanan dan di keluarkan sebagai
sterkobilin bersama tinja. Apabila tidak ada makanan di dalam usus, bilirubin direk ini akan
diubah oleh enzim di dalam usus yang juga terdapat di dalam ASI yaitu enzim beta-
glukoronidase menjadi bilirubin indirek yang akan diserap kembali dari dalam usus dan
masuk aliran darah. Bilirubin indirek ini akan diikat oleh albumin dan kembali ke dalam hati.
Rangkaian ini disebut siklus enterohepatik (Suradi dalam Hegar, 2008).
Sebagian besar neonatus mengalami peningkatan kadar bilirubin indirek pada hari
pertama kelahiran. Hal ini terjadi karena terdaatnya proses fisiologik tertentu pada neonatus.
Proses tersebut antara lain karena tingginya kadar eritrosit neonatus, masa hidup eritrosit
yang lebih pendek (80-90 hari) dan belum matangnya fungsi hepar. Peningkatan kadar
bilirubin ini teradi pada hari ke 2-3 dan mencapai puncaknya pada hari ke 5-7, kemudian
akan menuun kembali pada hari ke 10-14. Kadar bilirubin biasanya tidak melebihi 10 mg/dl
pada bayi cukup bulan dan kurang dari 12 mg/dl pada bayi kurang bulan. Pada keadaan
tersebut peningkatan biirubin masih dianggap normal karenanya disebut ikterus fisiologik (A.
H. Markum, 1991).
2.3. Etiologi Hiperbilirubinemia
Hiperbilirubinemia bisa disebabkan oleh bermacam- macam keadaan. Penyebab yang
paling sering adalah:
3

a. Produksi yang berlebihan
Hal ini melebihi kemampuan bayiuntuk mengeluarkannya, misalnya pada hemolisis
yang timbul akibat inkompatibilitas golongan darah ABO atau defesiensi enzim
Glucose-6-phospate dehydrogenase (G6PD) (Iskandar Wahidiyat, 1985).
b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar
Gangguan ini disebabkan oleh imaturasi hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi
bilirubin, gangguan fungsi hepar, akibat asidosis, hipoksia dan infeksi atau tidak
terdapatnya enzim glukoronil transferase (sindrom Criggler-Najjar). Penyebab lain
adalah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin
ke sel hepar (Iskandar Wahidiyat, 1985).
c. Gangguan transportasi
Bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut ke hepar. Ikatan
bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat misalnya salisilat,
sulfafurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapat bilirubin
indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak (Iskandar Wahidiyat,
1985).
d. Gangguan dalam ekskresi
e. Gangguan ini dapat terjadi akibat obsttruksi dalam hepar atau diluar hepar. Kelainan
di luar hepar biasanya disebabkanoleh kelainan bawaan. Obstruksi dalam hepar
biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain (Iskandar Wahidiyat,
1985).
2.4. Klasifikasi Hiperbilirubinemia
2.4.1. Hiperbilirubinemia tidak terkonugasi/ Indirek
Hiperbilirubinemia tidak terkonjugasi adalah peningkatan bilirubin serum tidak
terkonyugasi. Beberapa penyebab terjadinya hiperbilirubinemia tidak terkonyugasi
non fisiologis adalah: Inkompibilitas ABO, Hiperbilirubinemia ASI/ Breast milk
jaundice, Rh isoimmunization, infeksi, hematom subdural atau sefalohematom, memar
yang luas, bayi yang lahir dari ibu dengan diabetes melitus, polisitemia atau
hiperviskositas, defisiensi enzim G6PD, defisiensi pyrufat kinase, congenital
spherocytosis, Lucey Driscoll syndrome, Crigler- Najar disease, hipotiroid dan
hemoglobinopati (Gomella, 1999).
Defisiensi G6PD merupakan penyakit X-Linked resesiv yang menyebankan
anemia hemolitik dapat terjadi akut atau kronis yang beresiko terjadinya
4

hiperbilirubinemia berat. Klien yang menderita defisiensi G6PD biasanya
asimptomatik, walaupun pada beberapa kasus ditemukan karena terpapar zat-zat
kimia seperti naphthalene (kapur barus/ kamper) dan obat-obatan seperti sulfamides,
antipiretik, nitrofurane, primaquine dan chloroquine (Gurrola et al, 2008).
Hiperbilirubinemia tidak terkonyugasi (Indirek) terdiri dari hiperbilirubinemia
fisiologis dan Hiperbilirubinemia non fisiologis (Indrasanto et al, 2008).
Hiperbilirubinemia fisiologis
Hiperbilirubinemia fisiologis terjadi hampir pada setiap bayi. Peningkatan
bilirubin serum tidak terkonyugasi (Indirek) terjadi selama minggu pertama
kehidupan dan terpecahkan dengan sendirinya. Hiperbilirubinemia pada bayi sehat
dan cukup bulan akan terlihat pada hari ke 2-3 dan biasanya hilang pada hari ke 6-
8 tetapi mungkin tetap ada sampai hari ke 14 dengan maksimal total kadar
bilirubin serum kurang dari 12 mg/dl. Pada bayi kurang bulan sehat,
hiperbilirubinemia akan terlihat pada hari ke 3-4 dan hilang pada hari ke 10-20
degan kadar serummaksimal kurang 15 mg/dl (Indrasanto et al, 2008).
Hiperbilirubinemia nonfisiologis
Hiperbilirubinemia non fisiologis dicurigai jika kriteria hiperbilirubinemia
fisiologis tidak terpenuhi. Kriteria hiperbilirubinemia non fisiologis adalah:
hiperbilirubinemia terjadi sebelum bayi berumur 36 jam, peningkatan kadar
bilirubin serum lebih dari 0.5 mg/dl/ jam, total bilirubin serum lebih dari 15 mg/dl
pada bayi cukup bulan dan diberi susu formula, total bilirubin serum lebih dari 17
mg/dl pada bayi cukup bulan dan diberi ASI, hiperbilirubinemia klinis lebih dari 8
hari pada bayi cukup bulan dan lebih dari 14 hari pada bayi kurang bulan
(Indrasanto et al, 2008).
Bentuk lain dari hiperbilirubinemia yag jarang terjadi adalah hiperbilirubinemia
karena ASI atau Breast Milk Jaundice. Hiperbilirubinemia karena ASI ini tidak
jelas apakah merupakan hiperbilirubinemia terkonyugasi atau tidak, tetapi hal ini
jarang mengancam jiwa. Karakteristik hiperbilirubinemia karena ASI adalah
kadar bilirubin indirek yang masih meningkat setelah 4-7 hari pertama,
berlangsung lebih lama dari hiperbilirubinemia fisiologis yaitu sampai 3-12
minggu dan tidak ada penyebab lainnya. Hiperbilirubinemia karena ASI juga
bergantung kepada kemampuan bayi mengkonyugasi bilirubin indirek (misalnya
bayi prematur akan lebih besar kemungkinan terjadi hiperbilirubinemia).
5

Penyebab hiperbilirubinemia karena ASI belum jelas tetapi ada beberapa faktor
yang diperkirakan memegang peranan yaitu: 1) Terdapat hasil metabolisme
hormon progesteon yaitu pregnane3-a 20 betadiol di dalam ASI yang
menghambat uridine diphosphoglucoronic acid (UDPGA), 2) Peningkatan
konsentrasi asam lemak bebas yang nonesterified yang menghambat fungsi
glukoronid transferase di hati, 3) peningkatan sirklasi enterohepatik karena adanya
peningkatan aktivitas β glukoronidase di dalam ASI saat berada dalam usus bayi
dan 3) Defek pada aktivitas uridine diphosphate-glucoronyl transferase (UGTIAI)
pada bayi homozigot atau heterozigot untuk varian sindro Gilbert (Suradi dalam
Hegar, 2008).
2.4.2. Hiperbilirubinemia terkonyugasi/ direk
Hiperbilirubinemia terkonyugasi/ direk merupakan tanda disfungsi hepatobiliaris
yang ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin direk lebih dari 20% dari total
bilirubin serum (Indrasanto et al, 2008). Penyebab hiperbilirubinemia terkonyugasi
adalah obstruksi ekstra hepatik biliaaris (atresia biliaris dan kista koledokal),
kolestasis intrahepatik dengan duktus biliaris normal, infeksi dan inborn error of
metabolism.
6

2.5. Patofisiologi Hiperbilirubinemia
7
ERITROSITHEMOGLOBIN
HEM GLOBIN
Fe/ Besi Biliverdin
Bilirubin indirek
berikatan dengan albumin
hati
bilirubin berikatan dengan protein Y
konjugasi dengan enzim glukoronil transferase
ekskresi bilirubin ke usus
urobilinogen↑ glukoronidase
sterkobilin
feses/ urine
↑ hidrasi bilirubin
reabsorpsi bilirubin
↑ siklus entero hepatis
imaturitas hati
↑ bilirubin indirek dalam darah
↓ enzim glukoronil transferase
defisiensi protei Y
bilirubin indirek ↑
konjugasi bilirubin terganggu
obstruksi hepar
eritrosit bayi masuk ke peredaran darah ibu
reaksi antigen- antibodi
bayi lahir
antibodi ibu ↑ terhadap antigen
bayi(kehamilan ke II)
hemolisis
inkompatibilitas Rh
defesiensi albumin
bilirubin yang berikatan dengan
albumin ↓
ikterus
HIPERBILIRUBINEMIA
gangguan integritas kulitTERAPI
FOTOTERAPI TERAPI TUKAR
spemaparan sinar dengan intensitas tinggi
↑ suhu tubuh↑ infisible water loss
peningkatan suhu tubuh (hipertermi) kurang volume cairan
prosedure pemasangan
kateter tali pusat
resiko tinggi trauma

2.6. Manifestasi Klinis Hiperbilirubinemia
2.7. Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia
Tanpa memperdulikan etiologinya, tujuan pengobatan hiperbilirubinemia adalah
mencegah agar konsentrasi bilirubin indirek dalam darah tidak mencapai kadar yang
menimbulkan neurotoksisitas, dianjurkan transfusi tukar atau fototerapi untuk
mempertahankan total maksimum serum kurang dari kadar yang ditentukan(Nelson,)
Apabila terjadi resiko tinggi cedera karena dampak peningkatan kadar bilirubin, maka
intervensi yang dapat dilakukan adalah mekaji dan mengawasi dampak perubahan kadar
bilirubin, seperti adanya jaundice, konsentrasi urine, letargi, kesulitn makan, refleks moro,
adanya tremor, iritabilitas, memantau hemoglobin dan hematokrit, serta pencatatan
penuturan; melakukan fototerapi dengan mengatur waktu sesuai dengan prosedure dan
menyiapkan untuk melakukan transfusi tukar. Dengan mempertimbangkan resiko cedera
karena efek dari transfusi tukar, maka intervensi yang dapat dilakukan adalah:
Memantau kadar bilirubin, hemoglobin, hematrokit sebelum dan sesudah transfusi
tukar setiap 4-6 jam selama 24 jampasca transfusi tukar, memantau tekanan darah,
nadi dan temperatur.
Mempertahankan sistem kardiovaskular dan pernapasan.
Mengkaji kulit pada abdomen, ketegangan, muntah dan sianosis
Mempertahankan kalori, kebutuhan cairan sampai dengan pasca transfusi tukar
Melakukan kolaborasi pemberian obat untuk meningkatkantransportasi dan
konjugasi, seperti pemberian albumin atau pemberian plasma dengan dosis 15-20
ml/kgBB (A. Aziz Alimun Hidayat; 2011).
a. Fototerapi
Merupakan tindakan dengan memberikan terapi melalui sinar yang menggunakan
lampu. Lampu yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 500 jam untuk menghindari
turunya energi yang dihasilkan oleh lampu (A. Aziz Alimun Hidayat; 2011).
Peralatan yang digunakan dalam terapi sinar terdiri dari 10 buah lampu neon yang
diletakkan secara paralel dan dipasang dalam kotak yang berventilasi. Agar bayi
mendapatkan energi cahaya yang optimal (350-470 nanometer), lampu diletakkan
pada jarak tertentu dan bagian bawah kotak lampu dipasang pleksi glas biru yang
berfungsi untuk menahan sinar ultraviolet yag tidak bermanfaat untk penyinaran
(Sofyan Ismael, 1991).
8

Terapi sinar menyebabkan terjadinya isomerisasi bilirubin. Energi sinar mengubah
senyawa yang berbentuk 4Z, 15Z-biirubin menjadi senyawa berbentuk 4Z, 15E-
bilirubin yang merupakan bentuk isomernya. Bentuk isomer tersebut mudah larut
dalam plasma dan lebih mudah di ekskresikan oleh hati ke dalam saluran empedu.
Peningkatan bilirubin isomer dalam empedu menyebabkan bertambahnya pengeluaran
cairan empedu ke dalam usus sehingga peristaltik usus meningkat dan bilirubin akan
lebih cepat meninggalkan usus halus. Terapi sinar dilakukan pada semua penderita
hiperbilirubinemia dengan kadar bilirubin indirek lebih dari 10mg/dl dan pada bayi
dengan proses hemolisis yang ditandai oleh adanya ikterus pada hari pertama
kelahiran (Sofyan Ismael, 1991).
Cara melakukan fototerapi adalah sebagai berikut:
Pakaian bayi dibuka agar seluruh bagian tubuh bayi terkena sinar.
Kedua mata dan gonad di tutup dengan penutup yang memantulkan cahaya.
Jarak bayi dengan lampu 40 cm.
Posisi bayi sebaiknya diubah setiap 6 jam sekali.
Lakukan pengukuran suhu setiap 4-6 jam.
Periksa kadar bilirubin setiap 8 jam atau sekurang-kurangnnya sekali dalam 24
jam.
Lakukan pemeriksaan hemoglobin secara berkala terutama pada pasien yang
mengalami hemolisis.
Lakukan observvasi dan catat lamanyaterapi sinar.
Breikan atau sediakan lampu masing-masing 20 wat sebanyak 8-10 buah yang
disusun secara paralel.
Berikan ASI yang cukup. Pada saat memberikan ASI, bayi dikeluarkan dari
tempat terapi dan dipangku (posisi menyusui), penutup mata dibuka, serta
diobservasi ada tidaknya iritasi (A. Aziz Alimun Hidayat; 2011).
b. Transfusi Tukar
Merupakan cara yang dilakukan dengan tujuan mencegah peningkatan kadar
bilirubin dalam darah. Pemberian transfusi tukar dilakukan apabila kadar bilirubin
indirek 20mg/dl, kenaikan kadar bilirubin yang cepat yaitu 0.3-1 mg/ jam, anemia
berat dengan gejala gagal jantung dan kadar hemoglobin tali pusat 14 mg% dan uji
coombs direk positif (A. Aziz Alimun Hidayat; 2011).
9

Dalam melakukan transfusi tukar perlu diperhatikan golongan darah yang
diberikan dan teknik serta penatalaksanaan pemberian. Apabila hiperbilirubinemia
yang terjadi dissebabkan oleh inkompatabilitas golongan darah Rhesus makatransfusi
tukar dilakukan dengan menggunakan darah golongan O Rhesus negatif. Pada
inkompatabilitas golongan darah ABO, darah yang dipakai adalah darah golongan O
Rhesus positif. Pada keadaan lain yang tidak berkaitan dengan proses aloimunisasi,
sebainya dipergunakan darah yang bergolongan sama dengan bayi. Bila keadaan ini
tidak memungkinkan, dapat dipakai darah golongan O yang kompatibel dengan
serum ibu. Apabila ha tersebut juga tidak ada maka dapat dimintakan darah O dengan
titer anti A atau anti B yang rendah (kurang dari1/256) jumlah darah yang dipakai
untuk transfui tukar berkisar antara 140-180ml/kg BB (Sofyan Ismael, 1991).
Cara pelaksanaan transfusi tukar adalah sebagai berikut:
Pasien disiapkan di kamar yang aseptik yang dilengkapi dengan peralatan
yang dapat memantau tanda-tanda vital bayi
Persiapkan alat-alat seperti kateter tali pusat, kran 3 cabang dan jarum semprit.
Mengambil 10-20 ml darah bayi untuk dilakukan pemeriksaan sebelum
transfusi.
Pasang kateter transfusi pada pembuluh darah umbilikus.
Transfusi dilakukan dengan menyuntikkan darah secara perlahan sebanyak
darah yang dikluarkan
Pengeluaran dan penyuntikan darah dilakukan secara bergantian sebanyak 10-
20 ml setiap kali, dan berulang-ulang sampai darah yang disediakan habis..
Untuk menghindari bekuan darah, setiap 100 ml transfusi dilakukan pula
pembilasan dengan larutan NaCl-heparin dan pemberian 1ml kalsium
glukonat.
Lakukan observasi kemungkinan terjadinya komplikasi transfusi tukar seperti
asidosis, bradikardi, aritmia ataupun henti jantung (Sofyan Ismael, 1991).
Lakukan observasi umum keadaan pasien
Periksa kadar hemoglobin dan bilirubin setiap 12 jam (A. Aziz Alimun
Hidayat; 2011).
10

11